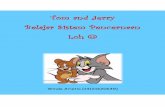Tugas Besar Perwil
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Tugas Besar Perwil
Tugas IV Perencanaan Wilayah
Pengembangan Wilayah DenganMempertimbangkan Konsep MitigasiBencana (Studi Kasus: Gempa dan
Tsunami Di Aceh Tahun 2004)
Oleh
Rofiqoh Etika Amalin 3612100003Ahmad Ikhfan Efendi 3612100013Hera Windy W 3612100023Bilqis Nur Chulaimi 3612100038
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAFAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAANINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan YME, karena
dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan
judul “Pegembangan Wilayah Dengan Mempertimbangkan Konsep
Mitigasi Bencana (Studi Kasus: Gempa Dan Tsunami Di Aceh
Tahun 2004)”. Meskipun banyak hambatan yang kami alami dalam
proses pengerjaannya, tapi kami berhasil menyelesaikan
makalah ini tepat pada waktunya.
Kami juga menyampaikan terimakasih kepada dosen
pembimbing yang telah membantu dan membimbing kami dalam
mengerjakan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini
masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna
sempurnanya makalah ini. Penulis berharap semoga karya tulis
ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca
pada umumnya.
Surabaya, 19 Mei 2015
Penulis
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................iiDAFTAR ISI...............................................iiiBAB I PENDAHULUAN..........................................11.1 Latar Belakang.......................................11.2 Rumusan masalah......................................31.3 Tujuan...............................................41.4 Sistematika Penulisan................................4
BAB II REVIEW LITERATUR....................................62.1 Pengertian Bencana...................................62.2 Jenis dan Karakteristik Bencana Alam.................72.3 Pengertian Bencana Tsunami...........................72.4 Penyebab dan Dampak Tsunami..........................82.5 Upaya Penanganan Tsunami yang sudah ada..............9
BAB III GAMBARAN UMUM.....................................123.1 Kondisi geografis...................................123.2 Bencana Tsunami di Provinsi Aceh....................123.3 Dampak dari Bencana Tsunami.........................13
BAB IV ANALISIS...........................................144.1 Alat Analisis.......................................144.2 Hasil Analisis......................................17
BAB V KONSEP PENANGANAN...................................185.1 Macam Konsep Penanganan.............................185.2 Konsep Penanganan Provinsi Aceh......................20
BAB VI PENUTUP............................................216.1 Kesimpulan..........................................216.2 Lesson Learned......................................21
DAFTAR PUSTAKA............................................22
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Definisi Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun
2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah suatu peristiwa
atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. Bencana yang disebabkan oleh factor alam biasanya
disebut dengan bencana alam. Definisi bencana alam itu sendiri
yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam dapat berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang disebabkan
oleh factor nonalam disebut dengan bencana nonalam. Bencana
non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam. Bencana nonalam dapat berupa
gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah
penyakit. Dan yang terakhir adalah bencana yang disebabkan
oleh factor social yang disebut dengan bencana sosial. Bencana
social yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat,
dan teror. Dari ketiga penyebab bencana, bencana alam
merupakan bencana yang kejadiannya tidak dapat dicegah.
1
Bencana alam memiliki dampak negatif yang merugikan
masyarakat pada lokasi bencana tersebut. Adapun dampak
negative dari terjadinya bencana alam yakni, timbulnya korban
jiwa, merusak fasilitas umum, sawah, dan rumah masyarakat,
serta membunuh ternak-ternak yang dimiliki masyarakat.
(Tugino, 2015)
Indonesia merupakan sebuah wilayah kepulauan yang berada
di atas pertemuan tiga lempeng raksasa yaitu Lempeng Benua
Eurasia, Lempeng Samudera Pasifik dan Lempeng Samudera Indo-
Australia. Lempeng benua ini saling berinteraksi satu sama
lain. Dengan adanya interaksi antar lempeng tersebut dapat
menimbulkan kerentanan terjadinya gempa bumi.
Gambar 1 Letak Tiga Lempeng di Indonesia
Sumber : arsildangeograf.blogspot.com
2
Gambar 2 Persebaran pusat gempa bumi
Sumber : Selamat Dari Bencana Tsunami
Pada gambar diatas, titik coklat merupakan pusat-pusat gempa
bumi yang pernah terjadi. Pada wilayah yang sering terjadi
gempa biasa disebut subduksi. Subduksi merupakan proses yang
berlangsung terus sejak jutaan tahun lalu dan akan terus
berlangsung. Hasil dari subduksi ini menyebabkan Indonesia
menjadi wilayah yang memiliki beribu-ribu pulau dengan ratusan
gunung berapi nan indah, yang abunya menyuburkan tanah
sehingga menghijau daratannya karena dipenuhi ribuan jenis
tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia yang
ditakdirkan tinggal di di dalamnya. Selain itu juga terdapat
kekayaan alam berbagai mineral, minyak bumi, batubara di bumi
Indonesia. Namun subduksi tersebut juga menimbulkan beberapa
bencana seperti tsunami dan gempa bumi. (Yulianto, Kusmayanto,
Supriyatna, & Dirhamsyah, 2007)
Tsunami adalah suatu peristiwa rangkaian gelombang laut
yang menjalar dengan kecepatan kurang lebih sebesar 900 km per
jam. Gelombang ini biasanya ditimbulkan akibat dari adanya
3
gempabumi yang terjadi di dasar laut. Untuk kecepatannya
sendiri tergantung dari kedalaman laut itu sendiri. Namun
gelombang ini tidak akan trasa oleh kapal yang ada di samudra,
karena gelombang ini ketika dilaut tidak tinggi.Bencana
tsunami dan gempa bumi rentan terjadi di kawasan subduksi ini.
Wilayah Indonesia yang rentan yakni barat Sumatra, bagian
selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Halmahera, Sulawesi Utara,
sampai dengan Papua bagian utara. Tsunami pernah terjadi di
Indonesia, lebih tepatnya pada wilayah Aceh. (Yulianto,Kusmayanto, Supriyatna, & Dirhamsyah, 2007)
Dari peristiwa tsunami tersebut, menimbulkan dampak yang
sangat banyak bagi kehidupan masyarakat di tempat yang terkena
bencana tersebut. Dampak Buruk Bagi Ekosistem yakni kehidupan
yang dinamis dari suatu ekologi akan terputus mata rantainya
sebab manusia, tumbuhan dan hewan yang tersapu gelombang
tersebut akan terganggu kehidupannya bahkan tak sedikit yang
kehilangan nyawa. Rusaknya berbagai mata rantai ekosistem ini
tentu akan berpengaruh banyak pada kehidupan manusia dari
berbagai aspek, baik itu ekonomi, sosial maupun budaya. Dampak
Buruk Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat dapat dirasakan pada
sendi-sendi ekonomi masyarakat akan lumpuh. Hal ini
ditimbulkan dampak tsunami dalam lingkup ekonomi ini cukup
sulit dipulihkan meskipun bangunan fisik sebagai infrastruktur
kegiatan masyarakat sudah pulih.
Bencana tsunami tidak dapat di cegah kejadiannya, namun
dampak yang dihasikan dapat diminimalisir dengan menggunakan
4
perencanaan yang baik dan pola ruang yang baik untuk membuat
zona buffer bencana yang ada di sana
1.2 Rumusan masalah
Dalam penulisan makalah ini, adapun rumusan masalah yang
mendasari yakni :
1. Bagaimana pengembangan wilayah yang berbasis
penanggulangan bencana yang selama ini sudah dilakukan?
2. Apa saja factor penyebab timbulnya permasalahan
pengembangan wilayah dalam hal kebencanaan?
3. Upaya dan rekomendasi apa yang sesuai dengan masalah
bencana tersebut?
4. Lesson learned apa yang dapat kita ambil dari pembahasan
tersebut?
1.3 Tujuan
Dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka
tujuan dari penulisan makalah ini yakni :
1. Mereview beberapa referensi mengenai faktor penyebab
timbulnya permasalahan resiko bencana, dampak dan
implikasinya, serta upaya dan rekomendasi penanganan
persoalan penanggulangan risiko bencana.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya permasalahan
pengembangan wilayah dan mampu menilai dampak/ implikasi
permasalahan risiko bencana.
5
3. Menyusun upaya dan rekomendasi untuk mengatasi persoalan
resiko bencana yang telah diidentifikasi.
4. Mampu menyususn lesson learned terkait dengan upaya untuk
mengatasi permasalahan penanggulangan risiko bencana yang
telah dijabarkan
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan makalah ini adalah sebagai
berikut :
Bab I Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang berisi
tentang latar belakang,, rumusan masalah, tujuan dan
sistematika penulisan makalah.
Bab II Tinjauan Pustaka bab yang berisi penjelasan tentang
pengembangan kawasan berbasis penanganan resiko bencana.
Bab III Gambaran Umum merupakan bagian bab yang menjelaskan
lebih rinci gambaran dari kasus yang dibahas pada makalah ini.
Bab IV Analisis adalah bagian dari makalah yang akan membahas
mengenai analisis yang untuk mengidentifikasi maslah tersebut.
Bab V Konsep Penanganan dimana pada bab ini membahas tentang
kriteria penanganan yang akan ditawarkan untuk masalah yang
dibahas. Penanganan ini disusun dengan melihat hasil dari
analisis kasus.
Bab VI Penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan lesson
learned dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya.
6
BAB II
REVIEW LITERATUR
2.1 Pengertian Bencana
Bencana merupakan suatu periatiwa di alam atau di
lingkungan buatan manusia yang berpotensial merugikan
kehidupan manusia, harta, benda atau aktivitas manusia (Sri
Harta, 2009). Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (menurut
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana). Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa
istilah terkait dengan bencana.
a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.
8
c. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit.
d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok
atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
Secara keseluruhan karakteristik bencana di Indonesia
dipengaruhi oleh posisi geologis, posisi astronomis, dan
perilaku manusianya yang menghasilkan berbagai bencana, yaitu
banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan,
angin badai, gelombang badai/pasang, gempa bumi, letusan
gunung api, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit. (Sholeh,2012)
2.2 Jenis dan Karakteristik Bencana Alam
Jenis dan karakteristik bencana alam yang terjadi
tentunya berbeda antar satu jenis bencana dengan bencana alam
lainnya. Terkadang terdapat beberapa bencana alam yang terjadi
dalam satu kejadian seperti misalanya angin badai/ angin
topan/ puting beliung disertai dengan banjir, atau banjir
disertai dengan tanah longsor dan lainnya.Klasifikasi bencana
alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi tiga jenis,
yaitu :
a. Bencana Alam Geologis
9
Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal
dari dalam bumi (gaya endogen). Yang termasuk dalam
bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung
berapi, dan tsunami.
b. Bencana Alam Klimatologis
Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang
disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Contoh bencana
alam klimatologis adalah banjir, badai, banjir bandang,
angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran alami
hutan (bukan oleh manusia). Gerakan tanah (longsor)
termasuk juga bencana alam, walaupun pemicu utamanya
adalah faktor klimatologis (hujan), tetapi gejala awalnya
dimulai dari kondisi geologis (jenis dan karakteristik
tanah serta batuan dan sebagainya).
c. Bencana Alam Ekstra-Terestrial
Bencana alam Ekstra-Terestrial adalah bencana alam yang
terjadi di luar angkasa, contoh: hantaman/impact meteor.
Bila hantaman benda-benda langit mengenai permukaan bumi
maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi
penduduk bumi.Konsep Pengembangan Wilayah dengan
mempertimbangan Mengurangi Resiko bencana banjir dan
bencana geologis.
2.3 Pengertian Bencana Tsunami
Terdapat berbagai pengertian mengenai tsunami menurut
banyak penulis, pengertian tsunami tersebut, yakni:
10
Abdillah Rikito, Tsunami adalah gelombang air yang
sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan
di dasar samudra.
Noname, Tsunami adalah gelombang transien yang
disebabkan oleh gempa tektonik ataupun oleh letusan
gunung berapi. Tsunami juga berasal kata dari bahasa
Jepang dimana artinya gelombang yang sering terjadi di
daerah-daerah pelabuhan di pantai Jepang (Tsu =
Pelabuhan dan Nami = gelombang).
Ali Nurjaya, Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Tsu
berarti "pelabuhan", dan namiberarti "gelombang",
sehingga tsunami dapat diartikan sebagai "gelombang
pelabuhan".
Dari berbagai pengertian dari pakar-pakar tersebut, dapat
ditarik kesimpulan bahwa penegrtian dari tsunami tersebut
yakni gelombang air laut yang menggulung tinggi dengan
kecepatan yang sangat tinggi menuju daratan. Hal ini di Jepang
disebut dengan “Gelombang Pelabuhan” dimana juga berarti sama
bahwa gelombang yang menuju daratan.
2.4 Penyebab dan Dampak Tsunami
Tsunami terjadi karena adanya gangguan implusif terhadap
air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara
tiba-tiba. Ini terjadi karena tiga sebab, yaitu: gempa bumi,
letusan gunung api dan longsoran (land slide) yang terjadi
didasar laut. Dari ketiga penyebab tsunami, gempa bumi
merupakan penyebab utama. Besar kecilnya gelombang tsunami
11
sangat ditentukan oleh karakteristik gempa bumi yang
menyebabkannya. Bagian terbesar sumber gangguan implusif yang
menimbulkan tsunami dahsyat adalah gempa bumi yang terjadi di
dasar laut. Walaupun erupsi vulkanik juga dapat menimbulkan
tsunami dahsyat, seperti letusan gunung Krakatau pada tahun
1883. (Harytami, 2009)
Gempa bumi di dasar laut ini menimbulkan gangguan air
laut, yang disebabkan berubahnya profil dasar laut. Profil
dasar laut iniumumnya disebabkan karena adanya gempa bumi
tektonik yang bisa menyebabkan gerakan tanah tegak lurus
dengan permukaan air laut atau permukaan bumi. Apabila gerakan
tanah horizontal dengan permukaan laut, maka tidak akan
terjadi tsunami.Apabila gempa terjadi didasar laut, walaupun
gerakan tanah akibat gempa ini horizontal, tetapi karena
energi gempa besar, maka dapat meruntuhkan tebing-tebing
(bukit-bukit) di laut, yang dengan sendirinya gerakan dari
runtuhan in adalah tegak lurus dengan permukaan laut. Sehingga
walaupun tidak terjadi gempa bumi tetapi karena keadaan
bukit/tebing laut sudah labil, maka gaya gravitasi dan arus
laut sudah bisa menimbulkan tanah longsor dan akhirnya terjadi
tsunami. Hal ini pernah terjadi di Larantuka tahun 1976 dan di
Padang tahun 1980.
Gempa-gempa yang paling mungkin dapat menimbulkan tsunami
adalah :
a. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut.
b. Kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km.
12
c. Magnitudo gempa lebih besar dari 6,0 Skala Richter.
d. Jenis pensesaran gempa tergolong sesar naik atau sesar
turun. Gaya-gaya semacam ini biasanya terjadi pada zona
bukaan dan zona sesar.
Berikut merupakan dampak yang diakibatkan oleh bencana Tsunami
:
Korban Jiwa
Kerusakan Infrastruktur
Rusaknya mata pencaharian
Pemerintah akan kewalahan dalam pelaksaan pembangunan
pasca bencana karna faktor dana yang besar
2.5 Upaya Penanganan Tsunami yang sudah ada
Menurut Dwi Jokowinarno (2009) upaya meminimalisir dampak
dari bencana tsunami yakni dengan cara mitigasi. Dimana
mitigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau
meminimalkan potensi dampak negatif dari suatu bencana.
Terdapat 6 (enam) langkah yang bisa diupayakan dalam melakukan
mitigasi bencana tsunami
1. Melakukan upaya-upaya perlindungan kepada kehidupan,
infrastruktur dan lingkungan pesisir.
2. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat pesisir
terhadap kegiatan mitigasi bencana gelombang pasang.
3. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
13
4. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan
mitigasi bencana.
5. Menyusun payung hukum yang efektif dalam upaya mewujudkan
upaya-upaya mitigasi bencana yaitu dengan jalan
penyusunan produk hukum yang mengatur pelaksanaan upaya
mitigasi, pengembangan peraturan dan pedoman perencanaan
dan pelaksanaan bangunan penahan bencana, serta
pelaksanaan peraturan dan penegakan hukum terkait
mitigasi.
6. Mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat pesisir melalui melakukan
kegiatan mitigasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi
kawasan, meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan
pesisir untuk kegiatan perekonomian.
Sedangkan mitigasi menurut Danny (2007) adalah dengan
melakukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Mengupayakan pengetahuan yang” up to date” tentang
potensi sumber bencana alam, baik pengetahuan dasar
ataupun peta potensi bencana dan detil teknis yang
efektif dan efisien untuk pelaksanaan mitigasinya
2. Membuat program nasional jangka panjang untuk menggalakan
riset dibidang kebencanaan, terus menerus meng-update
database potensi sumber bencana dan juga peta-peta
kebencanaan.
14
3. Melaksanakan pemantauan (sumber) bencana alam yang
berbasis pengetahuan kebencanaan yang memadai.
4. Melakukan pemantauan ini mencakup: jaringan seismometer &
GPS pemantau proses gempabumi, jaringan pemantau cuaca,
jaringan sensor pemantau gunung api, jaringan sensor
pemantau gerakan tanah, jaringan sensor pemantau banjir.
5. Menambahkan pendidikan dan pengetahuan untuk para pejabat
pemerintahan dan petugas pelaksana penanggulangan bencana
dan juga untuk masyarakat umum untuk membangun kesiapan
masyarakat dan sarana-fasilitasnya dalam mengurangi efek
bencana di masa datang dan menyiapkan pelaksanaan kondisi
darurat apabila bencana terjadi, usaha rehabilitasi, dan
rekonstruksi.
6. Meningkatkan kesiapan manajemen dan infrastruktur apabila
bencana terjadi, yaitu untuk membantu pelaksanaan
evakuasi, tindak tanggap darurat, rehabilitasi,dan
rekonstruksi. Usaha ini meliputi misalnya: pelebaran atau
pembuatan jalan-jalan untuk membantu evakuasi, membuat
bangunan khusus untuk tempat berlindung bagi masyarakat
dari tsunami, menyiapkan sarana-fasilitas untuk membantu
korban dalam situasi tanggap darurat, menyiapkan bahan
makanan ditempat yang aman dan strategis untuk para
korban, dsb.
7. Melakukan rencana pembangunan dan pengembangan wilayah
yang aman bencana alam. Dalam hal ini berarti
mengantisipasi dimana saja daerah yang padat penduduk dan
15
infrastruktur yang sudah kadung berada di daerah rawan
bencana. Kemudian untuk selanjutnya tidak lagi
mengembangkan suatu daerah tanpa memperhitungkan resiko
bencana alam.
8. Good governance dalam sistem manajemen penanggulangan
bencana
16
BAB III
GAMBARAN UMUM
3.1 Kondisi geografis
Secara geografis daerah Aceh adalah Provinsi Aceh
terletak di bagian barat Indonesia tepatnya di bagian ujung
Pulau Sumatera. Provinsi Aceh terletak antara 2°- 6° lintang
utara dan 95°– 98° lintang selatan, dengan ketinggian rata-
rata 125 meter diatas permukaan laut dengan Ibukota berada di
Banda Aceh. Provinsi ini memiliki luas wilayah 56.758,85 km2
atau 5.675.850 Ha dengan wilayah lautan sejauh 12 mil seluas
7.479.802 Ha. Secara administrative, Provinsi Aceh memiliki 18
kabupaten dan 5 kota. Keberadaan Provinsi Aceh memiliki lokasi
yang menjadi pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional
dan Internasional. Provinsi Aceh memiliki batas-batas wilayah,
sebagai berikut :
- Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara
3.2 Bencana Tsunami di Provinsi Aceh
Bencana tsunami di Aceh terjadi pada 26 Desember 2004.
Tsunami yang terjadi ditimbulkan oleh gempa bumi berkekuatan
9,3 SR yang berpusat di 3,3 LU - 95,98 BT. Gempa bumi tersebut
tidak hanya menyebabkan tsunami, namun juga menimbulkan
17
getaran kuat sehingga membuat patahan sepanjang ± 1200 km yang
membentang dari Aceh sampai ke Andaman India. (BMKG, 2010)
Tragedi tsunami akhir tahun 2004 ini, merujuk pada data
dari BNPB terdapat 173.741 jiwa yang meninggal dan 116.368
orang dinyatakan hilang, sedangkan di Provinsi Sumatera Utara
terdapat korban meninggal sebanyak 240 jiwa. (BMKG, 2010) Dan
menurut PBB, tsunami Samudra Hindia menjadi gempa dan Tsunami
terburuk 10 tahun terakhir.
3.3 Dampak dari Bencana Tsunami
Setelah terjadi gelombang tsunami, hal ini menimbulkan
berbagai dampak pada Provinsi Aceh. Pada gambar dibawah ini
merupakan penampang yang diambil dengan cita satelit pada saat
Aceh belum terkena tsunami dan setelah terkena tsunami.
Gambar 3 Sebelah kiri Aceh sebelum Tsunami Aceh, sebelah kanan
Sesudah Tsunami Aceh
Sumber : BMKG, 2004
Bencana tsunami menimbulkan berbagai dampak yang negative
terhadap berbagai aspek, seperti lingkungan, ekonomi, dan lain
sebagainya. Wilayah pesisir Aceh mengalami kerusakan dan
perubahan garis pantai dan lahan serta kerusakan berbagai
18
ekosistem mangrove dan terumbu karang. Selain lingkungan juga
banyak fasilitas umum yang hilang dan rusak akibat sapuan dari
tsunami itu sendiri. Kota di Provinsi Aceh yang diperkirakan
mengalami kerusakan terparah adalah kota Meulaboh. (BRR, 2006)
Kerugian yang dihasilkan dapat mencapai sekitar Rp 13,4
triliun. Dengan bencana ini juga menimbulkan konflik mengenai
kepemilikan lahan karena hilangnya batas kepemilikan lahan.
Selain batas lahan, jaringan jalan juga terputus. Sekitar 3000
km jaringan jalan rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi
untuk sarana transportasi. Sekitar 120 jembatan besar serta
1500 jembatan kecil juga telah hanyut dan tidak dapat lagi
digunakan. Serta terdapat 4000 sambungan telepon yang rusak.
(BRR, 2006)
19
BAB IV
ANALISIS
4.1 Alat Analisis
Proses patahan bumi yang pecah dan bergerak tiba-tiba
pada waktu gempa besar menimbulkan goncangan yang sangat keras
di daerah sumber dan sekitarnya. Goncangan ini tentunya dapat
menimbulkan kurasakan pada lingkungan hidup manusia. Apabila
gempa bumi terjadi di bawah laut maka pengangkatan dasar laut
yang terjadi menyebabkan terjadinya tsunami. Tsunami berbeda
dengan gelombang laut biasa. Gelombang laut biasa terjadi
karena tenaga arus angin di atas sehingga hanya bagian atas
dari badan air saja yang bergerak.
Gelombang tsunami menggerakan seluruh badan air dan
dengankecepatan yang sangat tinggi. Dilaut dalam kecpatan
gelombang tsunami mencapai 700 km/jam. Makin mendekat ke
pantai, laut makin dangkal sehingga kecepatannya berkurang,
namun hal ini membuat amplitudo gelombang semakin besar. Oleh
karena itu tsunami bisa sangat berbahaya, walaupun dengan
tingi gelombang yang hanya 1-3 meter sama seperti gelombang
badai biasa tapi daya momentumnya jauh lebih besar. Efek
terjangan tsunami dapat menimbulkan kerusakan hebat pada
lingkungan alam dan lingkungan hidup manusia seperti yang
terjadi tsunami Aceh tahun 2004. Berdasarkan katalog gempa
(1629 – 2002) di Indonesia pernah terjadi tsunami sebanyak 109
kali, yakni 1 kali akibat longsoran (landslides), 9 kali
akibat gunung berapi dan 98 kali akibat gempa bumi tektonik.
Gempa yang menimbulkan tsunami sebagian besar berupa gempa
20
yang mempunyai mekanisme fokus dengan komponen dip-slip, yang
terbanyak adalah tipe thrust (Flores, 1992) dan sebagian kecil
tipe normal (Sumba, 1977). Gempa dengan mekanisme fokus strike
slip kecil sekali kemungkinan untuk menimbulkan tsunami.
Berdasarkan pengamatan dan survai lapangan yang telah
dilakukan, gelombang tsunami telah masuk sejauh tidak kurang
dari dua kilometer di banyak bagian yang morfologinya relatif
datar seperti kota~kota Banda Aceh dan Meulaboh. Aspek
morofologi yang relatif datar ini akan menjadi bagian penting
bagi pertimbangan pembangunan kembali Aceh pasca bencana gempa
dan tsunami.
Gambar 4 Sumber Gempa Bumi di Lepas Pantai Barat Sumatera
Bencana di Aceh memberikan pelajaran beberapa aspek
penting yang perlu dipelajari dan diperhatikan dalam
pembangunan kembali Aceh pasca bencana tsunami. Aspek penting
tersebut adalah didasarkan atas:
21
Kajian tingkat kerusakan, pemetaan daerah terkena tsunami
dan kondisi fisik dan ekologis kawasan pesisir pasca
bencana tsunami.
Pemetaan kembali wilayah pesisir terutama akibat adanya
penurunan daratan kawasan pesisir
Pembuatan zonasi kerentanan multibencana (gempa, tsunami,
banjir, longsor dan lain-lain).
Aspek pendidikan bencana
Dalam penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan
perencanaan dan pemanfaatan ruang, tetapi juga pengendalian
pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian terhadap kemungkinan
terjadinya bencana, sehingga mampu berkontribusi dalam
pengurangan resiko bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui
pengakomodasian kajian dan pemetaan zona kebencanaan sebagai
salah satu dasar dalam merumuskan struktur dan pola ruang
dalam RTRW. Tidak sekedar menempatkan kawasan rawan bencana
sebagai salah satu zona, tetapi juga menempatkan kawasan
budidaya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya
bencana pada kawasan tersebut.
Dalam penentuan pola dapat juga dilakukan dengan melihat
daya dukung dan daya tampung dari lingkungan tersebut. Dalam
analisis mengenai hal ini dapat dilakukan dengan
mengklasifikasikan berbagai lahan yang terdapat disana sesuai
dengan klasisfikasi kemampuan lahan.
22
Pada dasarnya kebencanaan merupakan suatu aspek yang
tidak dapat terpisahkan dengan ilmu perencanaan wilayah dan
kota sendiri. Bencana yang terjadi karena adanya pertemuan
antara Hazard dan Vulnerability, bukanlah sesuatu hal yang
sama sekali tidak dapat dihindari atau paling tidak
diminalisir dampaknya. Resiko dari terjadinya bencana pun akan
semakin meningkat ketika tidak adanya kapasitas yang dimiliki
oleh masyarakat di daerah tersebut.
Risk=Hazard×VunerabilityCapacity
Ket :
Risk : Indeks resiko bencana
Hazard : Bahaya
Vulnerability : Kerentanan
Capacity : Kemampuan
Upaya menempatkan pengurangan resiko bencana sebagai
investasi pembangunan dalam kerangka yang lebih luas, taat
azas, mengikat dan berkelanjutan adalah menempatkan substansi
pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW). Penataan Ruang Berbasis Bencana
dimaksudkan sebagai penataan ruang yang memuat pengurangan
resiko bencana sebagai dasar dalam alokasi pemanfaatan ruang
bagi pembangunan. Dalam hal ini, dapat diintegrasikan dengan
gagasan Penataan Ruang Istimewa. Jadi penataan ruang istimewa
bukan sekedar penataan ruang wilayah yang mengakomodasi ruang-
23
ruang keistimewaan, tetapi juga berbasis pada pengurangan
resiko bencana.
4.2 Hasil Analisis
Dalam kasus Aceh sendiri, untuk pengembangan wilayahnya
sendiri diperlukan untuk mengetahui lokasi mana saja yang
merupakan kawasan yang memiliki resiko bencana tsunami tinggi,
sedang, maupun rendah. Dalam hal ini untuk Provinsi Aceh
menurut resiko terjadinya tsunami akan dijelaskan pada gambar
Gambar 5 Peta Zona Rawan Bencana Provinsi Aceh
Ket :
Warna merah : resiko tinggi
Warna kuning : resiko sedang
Warna hijau : resiko rendah
24
Sehingga dapa disimpulkan bahwa abupaten yang memiliki resiko tinggi yakni Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. Sedangkan untuk yang beresiko sedang yakni kabupaten Calang, Aceh Barat, Sumeulue, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Bireuen, Langsa Kota, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Untuk kabupaten yang memiliki resiko bencana rendah yakni kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
25
BAB V
KONSEP PENANGANAN
5.1 Macam Konsep Penanganan
Pengurangan resiko bencana, atau lebih populer dengan
mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengurangan resiko
bencana bersifat preventif dan harus diletakkan pada aktivitas
yang berkelanjutan melalui instrumen yang mengikat bagi pelaku
pembangunan. Instrumen ini berperan sebagai guidence
pembangunan sekaligus memastikan bahwa secara substansial
memuat rekomendasi pemanfaatan ruang yang mampu mengurangi
resiko bencana. Hal ini menunjukkan bahwa investasi
pengurangan resiko bencana dapat diletakkan melalui penataan
ruang.
Hingga kini terdapat berbagai kesulitan untuk
mengintegrasikan aspek kebencanaan didalam perencanaan tata
ruang. Tanpa kita sadari permukiman sudah banyak terbangun di
perbukitan yang rawan longsor ataupun banjir. Seperti bangun
dari tidur, pada akhirnya muncul berbagai program atau
kegiatan mitigasi baik struktural maupun non-struktural untuk
menghadapi permasalahan tersebut. Karena bukanlah hal yang
mudah untuk merelokasi permukiman yang sudah terbangun di
suatu tempat ke area lain yang dianggap relatif lebih aman
terhadap bencana. Berbagai program atau kegiatan mitigasi
bencana tersebut menjadi suatu pengungkit tersendiri yang
26
diharapkan mampu mengurangi kerentanan ataupun meningkatkan
kapasitas.
Ada beberapa mitigasi bencana yang dapat di lakukan dalam
mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana gempabumi
dan tsunami, yaitu :
a. Hazard Assessment (Mengadakan analisis bahaya yang akan
ditimbulkan)
Gempa bumi berakibat langsung dan tak langsung. Akibat
langsung adalah getaran, bangunan rusak/roboh, gerakan
tanah (tanah terbelah, bergeser), longsor, liquification
(berubah sifat menjadi cairan), tsunami dan lain-lain.
Sedangkan akibat tidak langsung adalah gejolak sosial,
kelumpuhan ekonomi, wabah penyakit, gangguan ekonomi,
kebakaran dan lain-lain. Sebenarnya akibat gempa ini
tergantung dari kekuatan gempa dan lokasi kejadian.
Lokasi kejadian apakah di kota, di desa atau di hutan,
tentunya tingkat bahaya akan lebih tinggi bila terjadi di
kota.
b. Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia
Untuk melaksanakan mitigasi bencana , salah satu tindakan
adalah membuat suatu sistem peringatan dini. Seperti kita
ketahui bahwa gempabumi dan tsunami yang terjadi di Aceh
yang lalu telah menalan banyak korban dan keruskan di
berbagai negara dan Indonesia mengalami dampak paling
parah.
27
Prinsip dasar pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami
adalah bahwa ada selang/jeda waktu antara terjadinya
gempabumi dengan tsunami. Jeda waktu antara kejadian
gempabumi dengan tsunami yang tiba dipantai terjadi
karena dalam pembentukan tsunami perlu proses dan adanya
perbedaan kecepataan antara gelombang gempaumi dengan
tsunami. Kecepatan gelombang gempabumi jauh lebih cepat
dibandingkan dengan gelombang tsunami. Sehingga gelombang
gempabumi akan lebih dahulu sampai di pantai dibandingkan
gelombang tsunami.
Saat ini BMG telah mengoperasikan system TREMORS (Tsunami
Risk Evaluation Through Seismic Moment from a Real-time
System) untuk mendeteksi gempa bumi yang menimbulkan
tsunami . Namun belum efektif, karena informasi yang
keluar lebih dari 30 menit setelah gempabumi terjadi. Hal
ini karena TREMORS bekerja berdasarkan pembacaan waktu
tiba gelombang primer, gelombang sekunder, gelombang
permukaan dan amplitudo. Hal ini menyebabkan sistem ini
tidak efektif sebagai peringatan dini tsunami lokal
c. Educational Program (Program Pendidikan)
Pengetahuan dan pemahaman mengenai bencana alam sangat
penting untuk semua lapisan masyarakat, sehingga perlu
dimasukan dalam program pendidikan sejak usia dini atau
sejak pendidikan dasar. Sebelum resmi masuk di dalam
kurikulum pendidikan maka BMG Wilayah I telah melakuakn
sosialisasi tentang peningkatan pemahaman masyarakat ini
ke sekolah-sekolah di Sumatera Utara, tujuannya adalah
28
agar siswa paham bahwa di wilayah Indonesia khususnya
Sumatera Utara ini merupakan daerah yang rawan bencana
alam. Sejak dini para siswa diharapakan mampu
mengantisipasi bila bencana datang agar dampak bencana
dapat diminimalkan.
d. Land Use Manajemen
Dalam penggunaan lahan juga sangat perlu diperhatikan
kemungkinan terjadi bencana. Misalnya: untuk mengurangi
laju arus tsunami di pinggir pantai perlu
dipelihara/ditanam tanaman yang mampu mengurangi laju
gelombanga tsunami, mislanya mangrove harus tetap
dipertahankan, menanam pohon-pohon dengan skala luas di
sekitar pantai dsb.
e. Building Code
Building Code pada prinsipnya membangun bangunan tahan
gempa, berdasarkan zonasi tingkat kerawanan gempa atau
percepatan tanah. Dari zona-zona kerawanan gempa tersebut
bangunan akan dirancang bangunan bagaimana yang harus
tahan gempa.
5.2 Konsep Penanganan Provinsi Aceh
Dengan demikian, dapat diberikan konsep untuk penanganan
resiko bancana di Provinsi Aceh dengan membedakan pembangunan
berdasarkan pemetaan resiko yang ada di Provinsi Aceh yang
telah dibahas pada bab sebelumnya. Kabupaten yang beresiko
tinggi yakni Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie dapat
29
dikembangkan untukmenjadi kawasan yang dimonan akan kegiatan
konservasi, seperti mangrove. Untuk bangunan dapat juga
dibentuk dengan menggunakan rumah cde, sehingga lebih aman dan
nyaman. Sedangkan untuk yang beresiko sedang yakni kabupaten
Calang, Aceh Barat, Sumeulue, Nagan Raya, Aceh Barat Daya,
Aceh Selatan, Singkil, Bireuen, Langsa Kota, Aceh Utara, dan
Aceh Timur dapaat dikembangkan untuk menjadi wilayah
pariwisata dan permukiman. Namun untuk menjaga wilayah
tersebut untuk tetap aman, pembangunan juga harus selalu
meninjau kembali zona sempadan pantai yang layak untuk diberi
bangunan permanen.. Untuk kabupaten yang memiliki resiko
bencana rendah yakni kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan
Gayo Lues. Untuk wilayah kabupaten ini merupakan kabupaten
yang tidak bersebalah secara langsung dengan laut. Sehingga
untuk pembangunan sebaiknya dipusatkan untuk berada disini
karena resiko terkenqa bencana yang rendah.
30
BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Dari berbagai pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :
1. Terdapat tiga (3) penyebab bencana, social, alam,
nonalam. Bencana alam tidak dapat di cegah
untukterjadinya namun resiko yang dihasilkan dapat
diminimalisir.
2. Untuk memperkecil resiko dari bencana alam itu sendiri
dapat dilakukan dengan pembangunan wilayah yang meninjau
kerawanan terhadap bencana.
3. Provinsi Aceh sendiri merupakan provinsi yang pernah
terkena bencana tsunami.
4. telah ada peta resiko bencana yang membagi kota-kota di
Provinsi Aceh yang merupakan kawasan resiko tinggi,
sedang, dan rendah.
5. Untuk pembangunan kembali Provinsi Aceh harusnya
dilandasi dengan melakukan analisis kerawanan bencana.
6.2 Lesson Learned
Hal yang dapat dipelajari dari penjelasan makalah ini
adalah bencana alam tidak harus menjadi musuh bagi manusia.
Bencana alam memang tidak dapat dicegah namun dapat
meminimalisir reaiko yang didapatkan dengan pembangunan
31
DAFTAR PUSTAKA
Akbar, A., & Ma'rif, S. (2014). Arah Perkembangan Kawasan Perumahan Pasca Bencana Tsunami di Kota Banda Aceh. Jurnal Teknik PWK , 274-284.
BMKG. (2010). Gempabumi & Tsunami 26 Desember 2004. Retrieved Mei 24, 2015, from Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: https://inatews.bmkg.go.id/new/about_inatews.php?urt=2
BRR. (2006). Aceh and Nias Two Years After the Tsunami. New York: Progress Report.
Harytami. (2009, Maret 5). TSUNAMI, PENYEBAB DAN AKIBATNYA. Retrieved Mei 25, 2015, from Harytami3’s Blog: https://harytami3.wordpress.com/2009/03/05/tsunami-penyebab-dan-akibatnya/
Rosyidie, A. (2006). Dampak Bencana Terhadap Wilayah Pesisir Belajardari Tsunami Aceh. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota , 63-81.
Sholeh, M. (2012, Januari 21). KARAKTERISTIK BENCANA DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN WAWASAN KEBENCANAAN DI SEKOLAH. Retrieved Mei 25, 2015, from Muh. Sholeh: http://muhsholeh.blogspot.com/2012/01/karakteristik-bencana-di-indonesia-dan.html
Tugino. (2015). Peristiwa Alam Beserta Dampaknya. Retrieved Mei 23, 2015, from Media Belajar: http://mastugino.blogspot.com/2012/11/peristiwa-alam-beserta-dampaknya.html
Yulianto, E., Kusmayanto, F., Supriyatna, N., & Dirhamsyah. (2007). Pembelajaran dari Tsunami Aceh dan Pangandaran. Retrieved Mei 18, 2015, fromSelamat Dari Bencana Tsunami: http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E5/sumber_lainnya/Selamat%20dari%20bencana%20tsunami.pdf
33