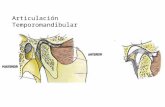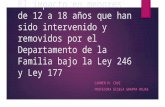Propolis: Alternative Medicine for the Treatment of Oral ...
RESUS ORAL MEDICINE
Transcript of RESUS ORAL MEDICINE
I. DESKRIPSI KASUS
A. Kunjungan I
Pemeriksaan Subyektif :
Seorang pasien wanita usia 20 tahun datang ke RSGMP
mengeluhkan gusinya sering berdarah saat sikat. Keluhan
tersebut dirasakan pasien sejak 6 bulan yang lalu. pasien
juga merasakan mulutnya terasa kotor dan tidak hilang
degan menyikat gigi. Pasien biasa menyikat gigi 2 kali
sehari saat mandi pagi dan sore, Pasien belum pernah
memeriksakan keadaannya tersebut ke dokter gigi dan belum
pernah membersihkan karang gigi. Pasien merasa kurang
nyaman dengan keadaan tersebut dan terkadang merasa bau
mulut jika berbicara.
Pemeriksaan Obyektif :
1. Terdapat pembulatan papilla interdental hampir
diseluruh regio, berwarna kemerahan, tidak sakit,
tekstur licin, konsistensi kenyal dan mudah berdarah.
Debris dan kalkulus tampak hampir diseluruh regio. Pada
bagian posterior rahang atas dan bawah kalkulus
mencapai bagian oklusal gigi dan beberapa bagian
mencapai daerah subgingiva.
OHI = 9,3 (buruk)
PI = 78%
BOP : +
PD : 3 mm (mesial 11)
1
Halitosis +
Dx. Gingivitis disertai halitosis
Treatment Planning :
a. KIE
b. Scaling USS
c. Kontrol
Penampakan klinis:
2. Terdapat kavitas pada prokimal sisi mesial gigi 46
dengan kedalaman pulpa disertai dengan nodul pada kavitas
berwarna kemerahan, konsistensi kenyal, tekstur halus dan
licin, palpasi pada nodul negative.
Sondasi : -
Perkusi : +
Palpasi : -
CE : -
2
Dd. Nekrosis pulpa disertai periodontitis
Nekrosis pulpa disertai abses periapikal
Penampakan klinis dan foto rontgen:
3
TINDAKAN
1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
a. Memberi edukasi pada pasien untuk menjaga kebersihan
mulutnya dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari
yaitu setelah makan pagi dan malam sebelum tidur.
b. Mengajarkan pada pasien cara menyikat gigi yang baik
dan benar.
c. Menginformasikan pada pasien mengenai perawatan yang
perlu dilakukan, seperti pembersihan karang gigi
minimal 6 bulan sekali, pencabutan sisa akar dan
gigi yang sudah tidak dapat dipertahankan, serta
penumpatan gigi-gigi yang berlubang.
2. Scalling USS pada seluruh regio baik supragingiva
maupun subgingiva
3. Premedikasi gigi 46 sebelum dilakukan ekstraksi
R/ Amoxicillin tab 500 mg No XV
S 3 dd tab I
R/ Kalium diklofenak tab 50 mg No X
S 2 dd tab I
B. Kunjungan II (Kontrol)
Pemeriksaan subyektif :
Pasien datang untuk mengontrolkan giginya yang telah
dilakukan pembersihan karang gigi 2 minggu yang lalu dan
4
pasien merasakan bau mulut yang sudah mulai berkurang
dibandingkan sebelum membersihkan karng gigi.
Pemeriksaan Obyektif :
1. Tampak gingiva yang mulai membaik, warna merah muda,
tekstur stipling dan konsistensi kenyal. Sudah tidak
tampak karang gigi, hanya terdapat debris yang menumpuk
pada bagian posterior.
OHI = 3,5 (sedang)
PI = 39,2%
BOP : -
PI = 2 mm (mesial 11)
Halitosis : -
Dx. Gingiva sehat
2. Tampak nodul pada kavitas gigi 46 yang mulai mengecil,
berwarna merah muda sama seperti mukosa disekitarnya,
konsistensi kenyal, tekstur halus dan licin, palpasi pada
nodul negative.
Sondasi : -
Perkusi : -
Palpasi : -
CE : -
Dx. Nekrosis pulpa disertai dengan disertai gingiva
polip
5
Penampakan klinis:
II. Pertanyaan Kritis
1. Apa saja etilogi dari halitosis dikaitkan dengan
kasus di atas?
2. Apasajakah klasifikasi dari halitosis?
3. Adakah hubungan antara periodontal disease dengan
halitosis?
4. Bagaimana patofisiologi dari halitosis yang
berhubungan dengan intraoral?
5. Bagaimana metode untuk mendiagnosis halitosis yang
benar?
6. Bagaimana penatalaksanaan/treatment untuk pasien
halitosis?
III. LANDASAN TEORI
1. Etiologi dari halitosis antara lain
a. Etiologi intraoral:
6
1. Tongue biofilm coating
Malodour berhubungan dengan kumpulan
mikroba (biofilm) yang terdapat pada
dorsum lidah. Hal ini bia disebabkan
karena oral hygiene yang buruk, dan
kebiasaan buruk seperti merokok.
2. Plak (berhubungan dengan gingival dan
periodontal disease)
Hal ini dapat dilihat dari gingivitis,
periodontitis, acute necrotizing
ulcerative gingivitis, pericoronitis, dan
abses.
3. Ulceration
Adanya lesi-lesi di mulut juga dapat
menjadi factor etiologi dariterjadinya
halitosis, misalnya lesi karena penyakit
sisemik (gastrointestinal dan
haematological disease)
4. Hiposalivasi
Hiposaliva bia disebabkan oleh karena
konsumsi obat, Sjogren syndrome, dan
terapi kanker (kemoterapi)
5. Penggunaan alat orthodontic atau gigi
tiruan
Penggunaan alat yang terus menerus dengan
tidak diimbangi dengan menjaga kebersihan
mulut maka dapat menyebabkan kebersihan
mulut yang buruk dan candidiasis sehingga
7
menimbulkan halitosis (malodour)
6. Bone disease
Beberapa contohnya yaitu dry socket,
osteomyelitis, osteonecrosis dan
malignancy.
b. Etiologi ekstra oral:
1. Respiratory system (microbial
etiology)
Contoh: Bronchitis, lung malignancy, nasal
malignancy, sinusitis, tonsillitis,
pharyngeal malignancy
2. Gastrointerstinal tract
Contoh: gastro-esophageal reflux disease,
malignancy
3. Metabolic disorder
Contoh: diabetes, liver disease, renal
failure
4. Drugs
Contohnya adalah obat-obatan chemotherapy,
phenothiazines, solvent abuse.
5. Psychogenic
Contoh: depression, obsessive compulsive
disorder
2. Klasifikasi dari halitosis:
a. Halitosis Fisiologis
Halitosis jenis ini biasa dirasakan pasien
ketika bangun tidur di pagi hari. Hal ini
8
merupakan normal nocturnal hiposalivasi. Pada
beberapa penelitian dijelaskan bahwa terjadi
peningkatan aktivitas microbial metabolic ketika
tidur. Halitosis fisiologis ini biasanya dapat
segera hilang dengan makan, menyikat gigi,
menyikat lidah, serta membilas mulut dengan air
segar.
c. Halitosis Gaya Hidup (lifestyle of halitosis)
Halitosis jenis ini berkaitan dengan gaya hidup
seperti minum-minuman berlkohol, merokok, makan-
makanan yang memiliki aroma seperti bawang dan
durian). Tembakau yang terkandung pada rokok
merupakan factor predisposisi dari terjadinya
hiposalivasi dan penyakit periodontal yang
merupakan etiologi dari halitosis.
d. Halitosis Patologis
Pada sebagian besar pasien dengan keluhan
halitosis, bau yang ditimbulkan berasal dari
aktivitas bakteri anaerob yang menghasilkan
produk seperti volatile sulfur compounds (VSC).
Halitosis patologis bias disebabkan oleh factor-
faktor yang berasal dari intra oral maupun
ekstra oral..
e. Pseudohalitosis
Halitosis jenis ini biasanya dikeluhkan oleh
pasien, namun orang-orang disekitarya tidak
mencium bau dari mulutnya.
f. Halitophobia
9
Pasien dengan halitophobia merupakan pasien yang
telah mendapatkan perawatan pada kasus halitosis
patologis maupun pseudohalitosis namun masih
terus merasakan bahwa dirinya masih memiliki bau
mulut.
3. Hubungan gingivitis dengan halitosis yaitu dikaitkan
dengan aktivitas dari bakteri proteolitik dan
putrefaktive (Scully and Greeman, 2008). Aktivitas
bakteri pada periodontal disease tersebut berkaitan
dengan produk volatile sulfur compounds (VSC) yang
dhasilkan dan dapat menyebabkan bau mulut. VSC
dihasilkan dari aktivitas bakteri putrefactive yang
ada pada saliva, krevikular gingiva, serta
permukaan dorsum lidah. Substratnya yang berupa
sulfur dengan kandungan asam amino (missal:
cysteine, cysteine, dan methionine) dapat ditemukan
pada saliva, cairan krevikular gingiva, dan produk
proteolysis dari protein substrat. Dijelaskan pada
penelitian Yaegaki dan Sanada (1992), bahwa
terkadang pada pasien dengan poket periodontal yang
dalam, tongue coating pun juga tebal. Tongue coating
inilah yang menjadi tempat berkumpulnya bakteri
hingga dapat menyebabkan halitosis. Selain itu,
poket periodontal yang dalam merupakan tempat yang
sangat disukai oleh bakteri anaerob da menjadi suatu
penyebab dari timbulnya halitosis. Pada penelitian
lain dijelaskan bahwa bleeding on probing lebih
berhubungan dengan halitosis dibandingkan dengan
10
hanya melihat kedalaman poket periodontal. Proses
inflamasi yang aktif merupakan penghubung utam
antara penyakit gingiva dan periodontal dengan
halitosis. Tanda utama berupa bleeding on probing
pada gingivitis atau periodontitis aktif selalu
disertai dengan aktivitas bakteri, peningkatan
cairan sulkus gingiva, dan peningkatan aliran darah
inilah yang berkaitan dengan timbulnya halitosis.
Proses inflames yang berjalan juga dapat lebih
diperburuk oleh senyawa-senyawa penyebab halitosis
karena senyawa tersebut bersifat toxic dan dapat
meningkatkan kerusakan jaringan periodontal.
4. Halitosis yang berkaitan dengan intra oral
disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menghasilkan
produk berupa volatile sulfur compounds. Halitosis
disebabkan karena adanya gas odor dalam udara yang
berasal dari rongga mulut.
Populasi bakteri pada mulut, terutama pada posterior
lidah merupakan factor utama penyebab halitosis
(Rosenberg, 1997). Terdapat hubungan yang kuat
antara tongue coating dengan halitosis.
5. Cara mendiagnosis halitosis dapat dilakukan dengan
beberapa metode penilaian, diantaranya:
a. Organoleptic measurement
Penilaian dilakukan berdasarkan persepsi dari
pemeriksa terhadap halitosis yang terdapat
pada pasien.
11
b. Gas Chromatography (GC)
Penilaian ini merupakan gold standard untuk
menilai halitosis yang spesifik dengan
memberi penilaian terhadap VSC, yang
merupakan penyebab utama halitosis. Peralatan
untuk GC mahal dan membutuhkan skill dari
operator. Penilaian ini ditujukan untuk
penelitian, bukan untuk pemeriksaan klinis.
c. Sulfide monitoring
Sulfide monitor digunakan untuk menganalisa
total kandungan sulfur yang terdapat pada
udara yang keluar dari rongga mulut.
d. Ammonia detector
Alat yang digunakan untuk mendeteksi
substansi penyebab halitosis yang tidak
mengandung sulfide.
Pemeriksaan yang perlu dilakukan pada pasien
dengan keluhan halitosis diantaranya
a. Dorsum lidah, meliputi pemeriksaan
kedalaman fissure dan sulcus pada permukaan
lidah, adanya tongue coating (warna dan
ketebalan), adanya ulcer, erosi. Scraping
lidah dengan sendok juga dapat dilakukan
untuk mencium adakah bau yang dtimbulkan dari
hasil scraping tersebut.
b. Sulkus gingiva dan poket periodontal
12
beberapa bakteri pathogen pada jaringan
periodontal dapat memproduksi VSC yang
menyebabkan halitosis.
c. Keadaan klinis dari rongga mulut yang
lain, sperti palatum, mukosa bukal, dan dasar
mulut.
6. Treatment untuk pasien halitosis yang dapat
dilakukan adalah instruksi untuk memperbaiki
kebersihan mulutnya. Selain itu, operator juga harus
mencari tahu penyebab dari halitosis pada pasien.
Dijelaskan oleh Krespi (2006), penggunaan dental
floss dan pembersihan area interdental dapat efektif
mengurangi produk bakteri yang dapat menimbulkan
halitosis. Selain itu, metode pembersihan lidah
dengan menyikat lidah, scraping lidah, dan mengunyah
permen karet juga dianjurkan untuk mengurangi
resiko penumpukan bakteri pada dorsum lidah.
Selain itu, pembersihan karang gigi juga dapat
dilakukan untuk mengurangi resiko terbentuknya poket
periodontal dan perdarahan pada gingiva yang
merupakan salah satu factor etiologi dari halitosis.
Keadaan klinis oral seperti gigi nekrosis, sisa
radix, dan karies dilakukan perawatan untuk
mengurangi resiko penumpukan bakteri dan menimbulkan
halitosis.
IV. REFLEKSI KASUS
13
Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa
halitosis pada kasus ini termasuk dalam halitosis
patologis dengan etiologi utamanya adalah kebersihan
mulut pasien yang buruk, ditemukan banyak karies dan
terdapat coating tongue pada lidah pasien.
Penatalaksanaan untuk pasien halitosis pada kasus
ini adalah dengan memberikan instruksi untuk perbaikan
kebersihan mulutnya seperti penggunaan dental floss dan
pembersihan area interdental, pembersihan bagian dorsum
lidah, pembersihan karang gigi rutin minimal 6 bulan
sekali dan penyikatan gigi minimal 2 kali sehari setelah
makan pagi dan malam sebelum tidur. Selain itu,
menghilangkan resiko lain yang dapat menjadi factor
pemicu halitosis seperti pencabutan sisa radix, perawatan
pada gigi-gigi yang karies dan juga perawatan lesi-lesi
oral yang ada juga penting untuk dilakukan.
V. KESIMPULAN
Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, dapat
disimpulkan bahwa kebersihan mulut sangat berpengaruh
terhadap timbulnya keluhan halitosis. Pembersihan karang
gigi menjadi salah satu langkah yang baik untuk mengatasi
halitosis yang ditimbulkan dari intra oral.
14
II. Daftar Pustaka
1. Anonim. Types Of Enamel Finish Line (Bevel)
2. Krespi M.D, Shrime, Kacker. 2006. The Relationship Between
Oral Malodor and Volatile Sulfur Compound-Producing Bacteria.
Otolaryngology-Head and Neck Surgery.
3. Washio J, Sato Takuichi, Koseki T. 2005. Hydrogen Sulfide-
Producing Bacteria in Tongue Biofilm and Their Relationship with Oral
Malodor. Journal of Medical Microbiology,54, 889-895
4. Silveira Elcia MV, Piccinin Flavia, Gomes Sbrina. 2012.
Effect of Gingivitis Treatment on the Breath of Chronic Periodontitis
Patients. Oral Health Preventive Dentistry 2012, 10; 93-
100.
15