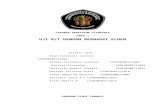Profil Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Tanaman Obat di Sulawesi Tenggara terhadap Bakteri...
Transcript of Profil Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Tanaman Obat di Sulawesi Tenggara terhadap Bakteri...
SKRIPSI
PROFIL FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIBAKTERI
TANAMAN OBAT DI SULAWESI TENGGARA
TERHADAP BAKTERI Salmonella typhi YCTC
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana (S-1)
Oleh :
MUHAMMAD JEFRIYANTO BUDIKAFA
F1F1 10 054
PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
OKTOBER 2014
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi
Profil Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Tanaman Obat di Sulawesi
Tenggara Terhadap Bakteri Salmonella typhi YCTC
Diajukan oleh:
Muhammad Jefriyanto BudikafaF1F1 10 054
Telah disetujui oleh:
Pembimbing I,
Prof. Dr. Sahidin, S.Pd., M.Si.NIP. 19690420 199403 1 004
Pembimbing II,
Rini Hamsidi,S.Farm.,M.Farm.,Apt.NIP. 19810705 200812 2 002
Mengetahui,Ketua Jurusan Farmasi UHO,
Nur Illiyyin Akib, S.Si.,M.Si.,Apt.NIP. 19810319 200801 2 006
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yangpernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yangpernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacudalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Kendari, Oktober 2014
Muh. Jefriyanto B.
F1F1 10 054
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi
dengan judul “Profil Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Tanaman Obat di
Sulawesi Tenggara Terhadap Bakteri Salmonella typhi YCTC” dapat
terselesaikan.
Melalui kesempatan ini secara khusus dan tulus penulis sampaikan
penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Drs.
Budikafa dan Ibunda Dra. Aifa atas segala doa, restu, semangat, bimbingan,
arahan, nasehat yang memberikan kedamaian hati serta ketabahan dalam
mendidik, membesarkan dan menitipkan harapan besar kepada penulis. Semoga
Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada Ayah dan
Ibunda tersayang.
Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada Bapak Prof. Dr. Sahidin, S.Pd., M.Si. selaku penasehat akademik,
pembimbing pertama sekaligus Dekan Fakultas Farmasi dan ibu Rini Hamsidi,
S.Farm., M.Farm., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan
waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama
mengikuti perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
v
Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S., selaku Rektor Universitas Halu Oleo,
2. Ibu Nur Illiyyin Akib, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi
Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo.
3. Ibu Henny Kasmawati, S.Farm., M.Si., Apt., selaku Kepala Laboratorium
Farmasi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Dr. Muzuni, S.Si., M.Si, Bapak Adryan Fristiohady, S.Farm., M.Sc.,
Apt. dan Ibu Wa Ode Sitti Zubaydah, S.Si., M.Sc. selaku Dewan Penguji yang
telah banyak memberikan ide dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan
tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi, serta seluruh staf di lingkungan
Fakultas Farmasi UHO atas segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan
selama penulis dalam menuntut ilmu.
6. Kakak penulis Fandi Ardiansyah, S.Pd. dan Adik Penulis Muh. Ridwan
Apriansyah dan Siti Fatimah Apriyani terima kasih untuk segalanya.
7. Saudari Sri Rahayu Ningsi, terima kasih untuk dukungan dan motivasi yang
selalu diberikan kepada penulis.
8. Kakanda Agung Wibawa Mahatva Yodha, S.Si., terima kasih untuk bantuan
dan arahannya selama ini.
9. Agriawan Al Hikmah, S. Ked., Ld. Surazal., Thomas Alfaidin Arnol, S. Pd.,
Refly Julian Praditya, Didit Zulfikar, S.H., dan Ridho Rosadi yang merupakan
vi
sahabat penulis terima kasih atas semangat dan dukungan yang selalu
diberikan untuk penulis.
10. Rekan-rekan organisasi EFD : Edi, Ipank, Aja, Azhar, Endra, Harry, Noe, Adi,
Erman, Leo, Aco, Rudi, Ical, Agil, Anzul, Arly, Ipul semoga kompak selalu.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 terima kasih telah membawa
keceriaan dan semangat baik di dalam maupun di luar laboratorium. Semoga
Allah SWT memberikan dan memudahkan jalan bagi kita semua tanpa
terkecuali.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya
membangun dari semua pihak sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan
skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan. Insya Allah.
Kendari, Oktober 2014
Penulis
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................................i
HALAMAN PERSETUJUAN................................................................................ ii
PERNYATAAN..................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv
DAFTAR ISI......................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL.................................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x
DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................... xi
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN .............................................................. xii
ABSTRAK ........................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian...................................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian.................................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA............................................................................. 6
A. Tanaman Obat .......................................................................................... 6
B. Metode Ekstraksi .................................................................................... 16
C. Metode Kromatografi Lapis Tipis .......................................................... 17
D. Bakteri S. typhi ....................................................................................... 18
E. Antibiotik Pembanding........................................................................... 19
F. Uji Profil Fitokimia................................................................................ 21
G. Uji Aktivitas Antibakteri ........................................................................ 25
H. Kerangka Konsep ................................................................................... 27
BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 28
A. Waktu dan Tempat Penelitian ................................................................ 28
viii
B. Jenis Penelitian ....................................................................................... 28
C. Bahan Penelitian..................................................................................... 28
D. Alat Penelitian ........................................................................................ 29
E. Prosedur Penelitian................................................................................. 29
F. Pengolahan Data .................................................................................... 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 34
A. Preparasi Sampel .................................................................................... 34
B. Uji Profil Fitokimia ................................................................................ 36
C. Uji Aktivitas Antibakteri ........................................................................ 42
BAB V PENUTUP................................................................................................ 52
A. Simpulan................................................................................................. 52
B. Saran ....................................................................................................... 54
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 55
LAMPIRAN.......................................................................................................... 61
ix
DAFTAR TABEL
Nomor Teks Halaman
1.2.3.
Perhitungan Rendamen EkstrakHasil uji golongan senyawa metabolit sekunderHasil uji aktivitas antibakteri
354146
x
DAFTAR GAMBAR
Nomor Teks Halaman
1.2.3.4.5.6.
Tanaman Pecah Beling (S. crispus)Tanaman Belimbing (A. bilimbi)Tanaman Kangkung (I. aquatica)Tanaman Secang (C. sappan)Tanaman Jarak Pagar (J. curcas)Struktur molekul kloramfenikol
7911131520
7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
17.18.
Kerangka konsep penelitianPlat KLT setelah dielusiUji golongan senyawa alkaloidUji golongan senyawa flavonoidUji golongan senyawa taninUji golongan senyawa saponinUji golongan senyawa triterpenHasil uji aktivitas tanaman Keji beling (S. crispus)Hasil uji aktivitas tanaman Belimbing (A. bilimbi)(a) Hasil uji aktivitas tanaman Kangkung (I. aquatica) (b)Hasil uji aktivitas tanaman Jarak pagar (J. curcas)Hasil uji aktivitas tanaman Secang (C. sappan)(a) Struktur kloramfenikol (b) Struktur alkaloid (c)Struktur flavonoid (d) Struktur tanin (e) Struktur saponin(f) Struktur triterpen
27373838394041434444
4548
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Teks Halaman1.2.3.4.5.6.
Penyiapan Ekstrak TanamanPembuatan ReagenPenapisan FitokimiaPembuatan Standar Kekeruhan McFarlandBagan Alir Uji Aktivitas AntibakteriDokumentasi
616263656769
xii
ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN
Lambang/Singkatan Arti Lambang dan Keterangan
YCTC
atm
cm
KLT
ppm
NaCl
nm
NA
tRNA
mRNA
dkk
µm
S
ml0C
HCl
Cm
UV
λ
mm
FeCl3
CFU
Yogyakarta culture type collection
Atmosphere
Centimeter
Kromatografi Lapis Tipis
part per milion
Natrium Klorida
Nanometer
Nutrient Agar
Transfer RNA
Messanger RNA
dan kawan-kawan
Mikrometer
Svedberg
Mililiter
Derajat Celcius
Hydrochlorida
Centimeter
Ultra Violet
Lamda (Panjang Gelombang)
Milimeter
Besi (III) Klorida
Colony Forming Unit
xiii
ABSTRAK
Uji profil fitokimia dan aktivitas antibakteri dilakukan terhadap beberapatanaman obat yaitu ekstrak metanol tanaman Keji beling (Strobilanthes crispusBI), Belimbing (Averrhoa bilimbi Linn.), Kangkung (Ipomoea aquatica), Secang(Caesalpinia sappan Linn.) dan Jarak pagar (Jatropha curcas Linn.) yang ada diSulawesi Tenggara. Uji profil fitokimia dilakukan dengan metode KLT untukmengidentifikasi golongan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid,flavonoid, tanin, saponin dan triterpenoid, sedangkan uji aktivitas antibakteriterhadap bakteri Salmonella typhi YCTC menggunakan metode difusi agardengan kloramfenikol sebagai kontrol positif. Hasil diperoleh menunjukkanbahwa ekstrak bagian akar dan daun tanaman S. crispus menghasilkan diameterzona bening sebesar 9 mm dan 5 mm, ekstrak bagian daun tanaman A. bilimbimenghasilkan diameter zona bening sebesar 9 mm, sedangkan ekstrak bagianbatang dan bunga tanaman C. sappan menghasilkan diameter zona bening sebesar3,5 mm dan 6 mm terhadap bakteri S. typhi YCTC.
Kata kunci : Fitokimia, Antibakteri, Salmonella typhi YCTC, Zona bening,S. crispus, A. bilimbi, C. sappan.
xiv
ABSTRACT
Phytochemical profile and antibacterial activity test performed on severalmedicinal plants methanol extracts of plants Keji beling (Strobilanthes crispusBI), Starfruit (Averrhoa bilimbi Linn.), Water spinach (Ipomoea aquatica),Secang (Caesalpinia sappan Linn.) and Jathropa (Jatropha curcas Linn.) existingin the Southeast Sulawesi. Phytochemical screening carried out by TLC method toidentify classes of secondary metabolic compounds like alkaloids, flavonoids,tannins, saponins and triterpenoids, while the antibacterial activity test against thebacteria Salmonella typhi YCTC using the agar diffusion method withchloramphenicol as a positive control. The results obtained show that the extractof the roots and leaves of plants of S. crispus yield a diameter of 9 mm and 5 mmclear zone, the extract of the leaves of plants A. bilimbi yield a diameter of 9 mmclear zone, while the extract of the trunks and flowers of C. sappan. plantsproduce a clear zone diameter of 3,5 mm and 6 mm against the bacteria.
Keywords : Phytochemical, Antibacterial, Salmonella typhi YCTC, Clear zone,S. crispus, A. bilimbi, C. sappan.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyakit infeksi selalu menempati urutan teratas penyebab kesakitan dan
kematian di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Infeksi yang terjadi
dipengaruhi oleh mikroorganisme penyebab yang masuk, derajat virulensi serta
kekebalan tubuh sehingga penderita infeksi biasanya minum obat yang
mengandung antibiotik (Wahyono, 2012). Penggunaan antibiotik dalam
mengobati penyakit infeksi saat ini mengalami kendala dengan munculnya
organisme yang resisten terhadap antibiotik. Keadaan resisten ini disebabkan dari
berbagai macam faktor mulai dari faktor penderita, faktor obat dan faktor
mikroorganisme itu sendiri (Pratiwi, 2008). Sebagian besar penyakit infeksi yang
merugikan bagi manusia disebabkan oleh mikroorganisme, salah satunya adalah
bakteri Salmonella typhi penyebab penyakit infeksi akut yaitu demam tifoid
(Pelczar dan Chan, 2007).
Demam tifoid pada masyarakat dengan standar hidup dan kebersihan
rendah, cenderung meningkat dan terjadi secara endemis. Sumber penularan
penyakit demam tifoid adalah penderita yang aktif, penderita dalam fase
penyembuhan dan kronik karier. Demam tifoid juga dikenali dengan nama lain
yaitu Typhus abdominalis, Typhoid fever atau Enteric fever. Demam tifoid adalah
penyakit sistemik yang akut yang mempunyai karakteristik demam, sakit kepala
dan ketidakenakan abdomen berlangsung lebih kurang 3 minggu yang juga
disertai gejala-gejala perut pembesaran limpa dan erupsi kulit (Supriyono, 2011).
2
Antibakteri yang segera diberikan dengan diagnosis klinis demam tifoid
yaitu kelompok antibakteri lini pertama. Berdasarkan efikasi dan harga, saat ini
kloramfenikol masih menjadi pilihan pertama, tetapi kekurangannya adalah
pemberian dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan resistensi. Faktor-
faktor penyebab resistensi ini adalah pemakaian antibakteri tanpa resep atau tanpa
pedoman dan kontrol dokter, pilihan antibakteri, dosis, serta lama pemberian
antibakteri yang kurang tepat (Kemenkes, 2006).
Penelitian zat yang berkhasiat sebagai antibakteri perlu dilakukan untuk
menemukan senyawa antibakteri baru yang berpotensi untuk menghambat atau
membunuh bakteri yang resisten terhadap antibiotik dengan harga yang
terjangkau. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah memanfaatkan zat
aktif yang terkandung dalam tanaman (Khunaifi, 2011).
Tanaman obat telah lama menjadi sasaran pencarian obat baru.
Perkembangan penggunaan obat khususnya dari tumbuh-tumbuhan untuk
membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah cukup meluas.
Salah satu manfaat penggunaan obat dari tanaman-tanaman tersebut pada manusia
adalah sebagai antibakteri (Awoyinka dkk., 2007).
Kegunaan tumbuhan obat secara umum sebenarnya disebabkan oleh
kandungan kimia yang dimiliki. Namun, tidak semua kandungan kimia diketahui
secara lengkap karena pemeriksaan bahan kimia dari suatu tanaman memerlukan
biaya yang mahal (Hariana, 2006).
Sulawesi Tenggara terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dan tiap suku
mempunyai banyak keluarga. Hal ini akan memberikan kontribusi penting
3
terhadap keragaman etnobotani (Ruslin dan Sahidin, 2008). Keragaman ini juga
memberikan perbedaan dalam cara pemanfaatan tanaman untuk pengobatan
penyakit, termasuk dalam pengobatan penyakit infeksi dimana masih terdapat
sebagian masyarakat yang menggunakan pengetahuan empiris dalam pemanfaatan
tanaman sebagai obat antibakteri, beberapa diantaranya telah dikenal dan biasa
digunakan oleh masyarakat secara turun temurun sebagai tanaman yang berkhasiat
sebagai obat seperti tanaman Keji beling (Strobilanthes crispus BI), Belimbing
(Averrhoa bilimbi Linn.), Kangkung (Ipomoea aquatica), Secang (Caesalpinia
sappan Linn.) dan Jarak pagar (Jatropha curcas Linn.). Oleh karena itu
masyarakat perlu diberi informasi mengenai tanaman-tanaman yang berpotensi
sebagai antibakteri agar pengetahuan masyarakat tentang tanaman obat tradisional
semakin meningkat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan dari
masyarakat tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian
lanjutan eksperimental untuk menggali potensi antibakteri dari tanaman Keji
beling (Strobilanthes crispus BI.), Belimbing (Averrhoa bilimbi), Kangkung
(Ipomoea aquatica), Secang (Caesalpinia sappan L.) dan Jarak pagar (Jatropha
curcas) sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri S. typhi untuk alternatif
terapi yang mudah dan aman bagi masyarakat serta memberikan informasi
mengenai kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada melalui skrining
fitokimia dari tanaman.
4
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu :
1. Metabolit sekunder golongan apa saja yang terdapat yang terdapat dalam
ekstrak metanol tanaman Keji beling (S. crispus) (akar, batang dan daun),
Belimbing (A. bilimbi) (akar, batang dan daun), Kangkung (I. aquatica)
(batang dan daun), Secang (C. sappan) (bunga, biji, batang dan daun), Jarak
pagar (J. Curcas) (akar, batang dan daun)?
2. Bagaimana potensi dari ekstrak metanol tanaman Keji beling (S. crispus) (akar,
batang dan daun), Belimbing (A. bilimbi) (akar, batang dan daun), Kangkung
(I. aquatica) (batang dan daun), Secang (C. sappan) (bunga, biji, batang dan
daun), Jarak pagar (J. Curcas) (akar, batang dan daun) sebagai antibakteri
terhadap pertumbuhan bakteri S. typhi YCTC?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui golongan metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak
metanol tanaman Keji beling (S. crispus) (akar, batang dan daun), Belimbing
(A. bilimbi) (akar, batang dan daun), Kangkung (I. aquatica) (batang dan
daun), Secang (C. sappan) (bunga, biji, batang dan daun), Jarak pagar (J.
Curcas) (akar, batang dan daun).
2. Untuk mengetahui potensi dari ekstrak metanol Keji beling (S. crispus) (akar,
batang dan daun), Belimbing (A. bilimbi) (akar, batang dan daun), Kangkung
(I. aquatica) (batang dan daun), Secang (C. sappan) (bunga, biji, batang dan
5
daun), Jarak pagar (J. Curcas) (akar, batang dan daun) sebagai antibakteri
terhadap pertumbuhan bakteri S. typhi YCTC.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini yaitu :
1. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan skrining fitokimia dan uji
aktivitas antibakteri dari tanaman.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kandungan senyawa
metabolit sekunder dan potensi tanaman Keji beling (S. crispus), Belimbing (A.
bilimbi), Kangkung (I. aquatica), Secang (C. sappan) dan Jarak pagar (J.
curcas) sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri S. typhi YCTC.
3. Sebagai sumber informasi prospek pemanfaatan tanaman Keji beling (S.
crispus), Belimbing (A. bilimbi), Kangkung (I. aquatica), Secang (C. sappan)
dan Jarak pagar (J. curcas) sebagai bahan baku untuk untuk pengembangan
obat di masa mendatang.
4. Memberikan informasi dan tambahan pustaka bagi mahasiswa Fakultas
Farmasi Universitas Halu Oleo sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas
akhir.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tanaman Obat
1. Tanaman Keji Beling (Strobilanthes crispus BI.)
Tumbuhan Keji beling adalah jenis tumbuhan yang biasa ditanam
masyarakat sebagai tumbuhan pagar, dapat tumbuh hampir diseluruh wilayah
Indonesia. Tumbuhan ini juga sebagai tumbuhan herbal liar hidup menahun yang
banyak manfaatnya bagi kesehatan dalam penyembuhan beberapa penyakit.
Dalam bahasa lokal Keji beling dikenal dengan sebutan keci beling di Jawa dan
picah beling di Sunda (Hariana, 2003 dalam Gunawan, 2011).
Klasifikasi tumbuhan keji beling adalah sebagai berikut:
Regnum : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Dicotyledonae
Bangsa : Scrophulariales
Suku : Acanthaceae
Genus : Strobilanthes
Spesies : Strobilanthes crispus BI
Keji Beling merupakan tumbuhan tergolong tumbuhan semak, biasanya
hidup menggerombol, tinggi 1-2 meter pada tumbuhan dewasa. Morfologi dari
tumbuhan Keji beling yaitu memiliki batang beruas, bentuk batangnya bulat
dengan diameter antara 0,12 - 0,7 cm, berbulu kasar, percabangan monopodial.
7
Kulit batang berwarna ungu dengan bintik-bintik hijau pada waktu muda dan
berubah jadi coklat setelah tua. Tergolong jenis daun tunggal, berhadapan, bentuk
daunnya bulat telur sampai lonjong, permukaan daunnya memiliki bulu halus, tepi
daunnya beringgit, ujung daun meruncing, pangkal daun runcing, panjang helaian
daun berkisar ± 5-8 cm, lebar ± 2-5 cm, bertangkai pendek, tulang daun menyirip,
dan warna permukaan daun bagian atas hijau tua sedangkan bagian bawah hijau
muda (Hariana, 2003 dalam Gunawan, 2011). Tumbuhan Keji beling ditunjukkan
pada Gambar 1.
Gambar 1. Keji Beling (S. crispus)
Tumbuhan Keji beling mengandung beberapa zat gizi yang berkhasiat
dalam mengobati beberapa penyakit, seperti batu ginjal, diabetes melitus, maag
dan sebagai laksatif. Keji beling mengandung zat-zat kimia antara lain: kalium,
natrium, kalsium, asam silikat, alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol. Kalium
berfungsi melancarkan air seni serta menghancurkan batu dalam empedu, ginjal
dan kandung kemih. Natrium berfungsi meningkatkan cairan ekstraseluler yang
menyebabkan peningkatan volume darah. Kalsium berfungsi membantu proses
pembekuan darah, juga sebagai katalisator berbagai proses biologi dalam tubuh
8
dan mempertahankan fungsi membran sel. Sedangkan asam silikat berfungsi
mengikat air, minyak, dan senyawa-senyawa non-polar lainnya (Soewito, 1989
dalam Gunawan, 2011).
2. Tanaman Belimbing (Averrhoa bilimbi Linn.)
Tanaman belimbing merupakan tanaman yang biasa ditanam sebagai pohon
buah, kadang tumbuh liar dan ditemukan dari dataran rendah sampai 500 m.
Tanaman ini memiliki banyak nama daerah, diantaranya Sumatera: Asom
belimbing, balimbieng, balimbingan, balimbing ; Jawa: belimbing wuluh,
calincing wulet, bhalingbhing bulu ; Bali: blimbing buloh ; Sulawesi: limbi,
balimbeng, lumpias, lembetue, bainang, calene, takurela ; Papua: uteke. Dalam
bahasa Inggris dikela sebagai cucumber tree atau bilimbi, sedangkan dalam
bahasa latin disebut Averrhoa bilimbi (Gunawan dan Mulyani, 2004).
Menurut Tjitrosoepomo (2000), sistematika tumbuhan buah belimbing
wuluh diklasifikasikan sebagai berikut :
Regnum : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Kelas : Dicotyledoneae
Bangsa : Oxalidales
Suku : Oxalidaceae
Genus : Averrhoa
Spesies : Averrhoa bilimbi Linn.
9
Belimbing wuluh merupakan tanaman berbentuk pohon kecil, tinggi
mencapai 10 m dengan batang yang tidak begitu besar dan mempunyai garis
tengah hanya sekitar 30 cm. Daun majemuk menyirip ganjil dengan 21-45 pasang
anak daun. Anak daun bertangkai pendek, bentuknya bulat telur, ujung runcing,
pangkal membundar, tepi rata, panjang 2-10 cm, lebar 1-3 cm, warnanya hijau,
permukaan bawah warnanya lebih muda. Ciri buah belimbing wuluh yaitu
buahnya berbentuk bulat lonjong bersegi hingga seperti torpedo, panjangnya 4-10
cm. Warna buah ketika muda hijau dengan sisa kelopak bunga menempel pada
ujungnya. Apabila buah sudah masak, maka buah berwarna kuning atau kuning
pucat. Daging buahnya mengandung banyak air dan rasanya asam.Kulit buahnya
berkilap dan tipis. Biji bentuknya bulat telur, gepeng (Wijayakusuma dan
Dalimartha, 2006). Tanaman belimbing ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Belimbing (A. bilimbi)
Khasiat dari buah belimbing wuluh ini adalah sebagai obat batuk, gusi
berdarah, sariawan, jerawat, panu dan bisul (Gunawan dan Mulyani, 2004),
dimana tanaman ini mengandung senyawa flavonoid, steroid/triterpenoid,
10
glikosida, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B1, dan C
(Wijayakusuma dan Dalimartha, 2006).
3. Tanaman Kangkung (Ipomoea aquatica Poir.)
Tanaman kangkung adalah salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat karena selain dapat diolah menjadi berbagai macam masakan,
tanaman ini juga dapat menyembuhkan. Tanaman kangkung memiliki klasifikasi
sebagai berikut (Maryani, 2003).
Regnum : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Dicotyledoneae
Bangsa : Solanales
Suku : Convolvulaceae
Genus : Ipomea
Spesies : Ipomea aquatiqa Poir.
Secara alamiah, kangkung ini dapat ditemukan di kolam, rawa, sawa, dan
tegalan. Tumbuhnya menjalar dengan banyak percabangan. Sistem perakarannya
tunggang dengan cabang-cabang akar yang menyebar ke berbagai penjuru.
Tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan bentuk helaiannya seperti hati.
Bunganya menyerupai terompet. Bentuk buahnya bulat telur dan di dalamnya
berisi 3 butir biji (Santosa, 2008). Tanaman kangkung ditunjukkan pada
Gambar 3.
11
Gambar 3. Kangkung (I. aquatica)
Kandungan gizi dalam 100 gram kangkung darat diantaranya adalah 458,00
gram kalium dan 49,00 gram natrium. Kalium dan natrium dalam tanaman ini
merupakan persenyawaan garam bromida. Senyawa-senyawa ini bekerja sebagai
obat tidur berdasarkan sifatnya yang menekan susunan saraf pusat. Selain
mengandung kalium dan natrium, daun kangkung juga mengandung zat kimia
seperti karoten dan sitosterol. Oleh karena itu, tanaman kangkung berkhasiat
sebagai antiinflamasi, diuretik dan hemostatik (Maryani, 2003)
.4. Tanaman Secang (Caesalpinia sappan Linn.)
Kayu secang sangat dikenal terutama di Sulawesi secara empiris sebagai
pemberi warna pada air minum yang dikenal sebagai teh secang. Kayu secang
juga merupakan salah satu ramuan yang digunakan dalam pembuatan minuman
tradisional Betawi bir pletok yaitu sebagai pemberi warna (Winarti dan
Nurdjanah, 2005). Kayu secang memiliki rasa sedikit manis dan hampir tidak
berbau dan sering juga digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit.
Kayu secang mengandung komponen yang memiliki aktivitas antioksidan dan
antimikroba (Sundari dkk., 1998).
12
Menurut Tjitrosoepomo (2000), sistematika tumbuhan secang
diklasifikasikan sebagai berikut :
Regnum : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Kelas : Dicotyledoneae
Bangsa : Rosales
Suku : Caesalpiniaceae
Genus : Caesalpinia
Spesies : Caesalpinia sappan Linn.
Tumbuhan secang merupakan perdu dengan tinggi 5-10 m, batang dan
percabangannya berduri tempel yang bentuknya bengkok dan letaknya tersebar,
batang berbentuk bulat, warnanya hijau kecoklatan. Secang tumbuh liar dan
kadang ditanam sebagai tanaman pagar atau pembatas kebun. Daun tumbuhan ini
bertipe majemuk menyirip ganda, bunganya bertipe majemuk berbentuk malai
dengan mahkota bentuk tabung dan berwarna kuning, buahnya menyerupai buah
polong yang berisi 3-4 biji berbentuk bulat memanjang dan berwarna kuning
kecoklatan. Panenan kayu dapat dilakukan mulai umur 1-2 tahun dan kayunya bila
digodok memberi warna merah gading muda, dapat digunakan untuk pengecatan,
memberi warna pada bahan anyaman, kue, minuman atau sebagai tinta (Dianasari,
2009). Tanaman secang ditunjukkan pada Gambar 4.
13
Gambar 4. Secang (C. sappan)
Menurut Winarti dan Nurdjanah (2005), secara empiris kayu secang dipakai
sebagai obat luka, batuk berdarah, berak darah, darah kotor, penawar racun,
sipilis, menghentikan pendarahan, pengobatan pasca persalinan, desinfektan,
antidiare dan astringent. Berbagai penelitian juga telah dilakukan untuk menguji
manfaat kayu secang, seperti khasiatnya sebagai antibakteri. Dituliskan oleh
Indriani (2003), bahwa kayu secang juga mempunyai aktivitas sebagai antibakteri
dan bakteriostatik sehingga sering digunakan sebagai obat muntah darah, diare
dan disentri.
5. Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas Linn.)
Jarak pagar telah lama dikenal masyarakat di berbagai daerah Indonesia,
yaitu sejak diperkenalkan oleh bangsa Jepang pada tahun 1942. Saat ini
masyarakat manaman jarak sebagai pagar di pekarangan. Beberapa nama daerah
(nama lokal) yang diberikan kepada tanaman jarak pagar ini yaitu Sunda : jarak
kosta, jarak budeg, Jawa : jarak gundul, jarak pager, Madura : kalekhe paghar,
Bali : jarak pager, Nusa Tenggara : lulu mau, paku kase, jarak pageh, Alor :
14
kuman nema, Sulawesi : jarak kosta, jarak wolanda, bindalo, bintalo, tondo
utomene, Maluku : ai huwa kamala, balacai, kadoto (Hariyadi, 2005).
Klasifikasi tanaman jarak pagar adalah sebagai berikut (Alamsyah, 2006).
Regnum : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
kelas : Dicotyledoneae
Bangsa : Euphorbiales
Suku : Euphorbiaceae
Genus : Jatropha
Spesies : Jatropha curcas Linn.
Tanaman jarak pagar mudah beradaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya,
menghendaki lingkungan tumbuh yang optimal bagi pertumbuhannya, yaitu pada
ketinggian 0 – 2000 m di atas permukaan laut, suhu berkisar antara 18º–30ºC.
Pada daerah dengan suhu rendah (<18ºC) jarak pagar mengalami hambatan
pertumbuhan, sedangkan pada suhu tinggi (>35ºC) menyebabkan gugur daun dan
bunga, buah kering sehingga produksi menurun. Jarak pagar dapat tumbuh pada
tanah yang kurang subur, tetapi memiliki drainase baik, tidak tergenang, dan pH
tanah 5.0 – 6.5 (Hariyadi, 2005).
Daun jarak pagar berwarna hijau kekuningan berukuran 6 x 15 cm dengan
tepi berlekuk. Daun jarak pagar mengandung flavanoid, apigenin, vitexin, dan
isovitexin. Daun jarak pagar juga mengandung dimer dari triterpene alkohol
(C63H117O) dan dua flavonoid glikosida (Alamsyah, 2006).
15
Batang jarak pagar mengandung β-sitosterol dan β-D-glukosida, marmesin,
propacin, curculathrine A dan B, diterpenoid jatropol, jatropholone A dan B,
coumarin tomentin, dan coumarino jatrophin. Batang jarak pagar mengeluarkan
getah bening dan tidak menggumpal. Getah jarak pagar dapat digunakan untuk
mempercepat penyembuhan luka yang sulit disembuhkan, infeksi pada gusi, dan
anti pendarahan pada luka yang terpotong atau tergores (Alamsyah, 2006).
Tanaman jarak pagar ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Jarak Pagar (J. curcas)
Buah jarak pagar berbentuk kapsul dan berukuran kecil dengan diameter
2,5– 4 cm. Buah yang belum masak berwarna hijau, sedangkan jika sudah masak
buah berwarna hitam dengan ukuran 2 cm. Daging biji berwarna putih dan
mengandung minyak (Kingsbury, 1964). Biji jarak pagar rata-rata berukuran 18 x
11 x 9 mm, berat 0,62 gram, dan terdiri atas 58,1 % biji inti berupa daging
(kernel) dan 41,9 % kulit. Kulit hanya mengandung 0,8 % ekstrak eter. Kadar
minyak trigliserida dalam inti biji sama dengan 55% atau 33% dari berat total biji.
Asam lemak penyusun minyak jarak pagar terdiri atas 22,7% asam jenuh dan
77,3% asam tak jenuh. Kadar asam lemak minyak terdiri dari 17,0% asam
16
palmiat, 5,6 % asam stearat, 37,1 % asam oleat, dan 40,2 % asam linoleat (Stegar
dan van Loon, 1941 dalam Brodjonegoro dkk., 2006).
B. Metode Ekstraksi
Ekstraksi merupakan salah satu metode pemisahan berdasarkan perbedaan
kelarutan. Secara umum ekstraksi dapat didefinisikan sebagai proses pemisahan
dan isolasi zat dari suatu zat dengan penambahan pelarut tertentu untuk
mengeluarkan komponen campuran dari zat padat atau zat cair. Dalam hal ini
fraksi padat yang diinginkan bersifat larut dalam pelarut (solvent), sedangkan
fraksi padat lainnya tidak dapat larut. Proses tersebut akan menjadi sempurna jika
solute dipisahkan dari pelarutnya, misalnya dengan cara distilasi/penguapan
(Wahyuni dkk., 2004).
Ekstraksi adalah pemisahan yang menggunakan bantuan pelarut. Beberapa
hal yang harus diperhatikan untuk tercapainya kondisi optimum ekstraksi antara
lain: senyawa dapat terlarut dalam pelarut dengan waktu yang singkat, pelarut
harus selektif melarutkan senyawa yang dikehendaki, senyawa analit memiliki
konsentrasi yang tinggi untuk memudahkan ekstraksi, serta tersedia metode
memisahkan kembali senyawa analit dari pelarut pengekstraksi (Fajriati dkk.,
2011).
Maserasi merupakan cara ekstraksi yang sederhana. Maserasi merupakan
proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada
temperatur ruangan pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam
rongga sel yang mengandung zat aktif sehingga zat aktif akan larut, karena adanya
17
perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel, maka larutan yang
terpekat didesak keluar. Pelarut yang digunakan dapat berupa air, etanol, metanol,
atau pelarut lain. Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan
efektifitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam
pelarut tersebut (Christina. 2008).
C. Metode Kromatografi Lapis Tipis
Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang berdasarkan
kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Uraian mengenai
kromatografi pertama kali dijelaskan oleh Michael Tswett, seorang ahli biotani
Rusia yang bekerja di Universitas Warsawa (Sudarmadji dkk., 2007).
Kromatografi dapat dibedakan atas berbagai macam tergantung pada
pengelompokannya. Berdasarkan pada mekanisme pemisahannya, kromatografi
dibedakan menjadi kromatografi adsorpsi, kromatografi partisi, kromatografi
pasangan ion, kromatografi penukar ion, kromatografi eksklusi ukuran dan
kromatografi afinitas. Berdasarkan pada alat yang digunakan, kromatografi dapat
dibagi atas kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis (KLT), kromatografi cair
kinerja tinggi (KCKT), dan kromatografi gas (KG) (Gandjar dan Rohman, 2007).
Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan
yang memisahkan, yang terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan
pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran
yang akan dipisah berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita (awal),
setelah plat atau lapisan ditaruh di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan
18
pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama rambatan kapiler
(pengembangan). Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus dideteksi
(Dumont, 1985).
Teknik KLT hingga saat ini masih digunakan untuk mengidentifikasi
senyawa-senyawa kimia, karena murah, sederhana, serta dapat menganalisis
beberapa komponen secara serempak. Teknik standar dalam melaksanakan
pemisahan dengan KLT diawali dengan pembuatan lapisan tipis adsorben pada
permukaan plat kaca. Tebal lapisan bervariasi, bergantung pada analisis yang akan
dilakukan (kualitatif atau kuantitatif) (Hayani dan Sukmasari, 2005).
D. Bakteri S. typhi
Bakteri S. typhi merupakan bakteri Gram negatif dan termasuk
enterobacteriaceae (bakteri enterik batang gram negatif) yang bersifat fakultatif
anaerob atau aerob, tidak berspora dan intraseluler fakultatif (Madjid, 2003).
Bakteri ini tidak berkapsul, mempunyai flagela dan tidak membentuk spora, akan
mati pada pemanasan 57 ˚C selama beberapa menit. S. typhi memiliki tiga antigen
yang penting untuk pemeriksaan laboratorium yaitu antigen O (somatik), antigen
H (flagela), dan antigen K (selaput) (Widoyono, 2011).
Bakteri ini memiliki panjang sekitar 3-5 μm dengan lebar 1 μm (Madigan
dkk, 2012). Karena merupakan Gram negatif, maka struktur dinding selnya tipis
(10-15 nm) dan berlapis tiga (multi). Komposisi dinding selnya mengandung lipid
tinggi (11-22%) yang termasuk membran luar (7-8 nm terdiri dari lipid, protein
dan lipopolisakarida), peptidoglikan (2-7 nm) berada di lapisan kaku sebelah
19
dalam antara membran dalam dan luar serta jumlahnya sedikit (sekitar 10% berat
kering), dan tidak memiliki asam tekoat (Pelczar dan Chan, 2007).
Bakteri ini merupakan bakteri patogen yang mempunyai kemampuan
transmisi, perlekatan pada sel inang, invasi sel dan jaringan inang, toksigenisitas
dan kemampuan menghindari sistem imun inang, sehingga sekali masuk ke dalam
tubuh, bakteri harus menempel atau melekat pada sel inang, biasanya pada sel
epitel (Madjid, 2003).
Demam tifoid adalah infeksi akut pada saluran pencernaan yang 96%
disebabkan oleh S. typhi, sisanya disebabkan oleh S. paratyphi. Bakteri masuk
melalui makanan/minuman, setelah melewati lambung bakteri mencapai usus
halus dan setelah menembus dinding usus akan mencapai folikel limfoid usus
halus (plaque Peyeri). Bakteri akan mengikuti aliran limfe mesenterial ke dalam
sirkulasi darah lalu mencapai jaringan RES untuk bermultiplikasi (hepar, lien,
sumsum tulang). Setelah itu bakteri mencapai sirkulasi darah untuk menyerang
organ lain, baik intra dan ekstra intestinal (Pudjiaji dkk., 2009).
E. Antibiotik Pembanding
Antibiotik yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini adalah
kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan kristal putih yang sukar larut dalam air
(1:400), rasanya sangat pahit (Setiabudy, 2009) dan merupakan salah satu jenis
antibiotika turunan amfenikol (Susanti dkk., 2009). Senyawa dengan rumus
molekul C11H12Cl2N2O5 dan nama kimia D (-) treo-2-dikloroasetamido-1-p-
20
notrofenilpropana-1,3-diol, memiliki struktur molekul sebagai berikut (USP
XXXI, 2008)
HOO
HN
Cl
ClOH
N+O
O-
Gambar 6. Struktur molekul kloramfenikol
Kloramfenikol memiliki mekanisme kerja sebagai antibakteri yang bersifat
stereospesifik, karena hanya satu stereoisomer yang memiliki aktivitas antibakteri
yaitu D (-) treo-isomer. Bekerja pada spektrum luas yaitu efektif terhadap Gram
positif dan Gram negatif. Mekanisme kerja kloramfenikol menghambat sintesis
protein pada bakteri dan dalam jumlah terbatas pada sel eukariot. Obat ini segera
berpenetrasi ke sel bakteri, kemungkinan melalui difusi terfasilitasi.
Kloramfenikol terutama bekerja dengan mengikat subunit ribosom 50 S secara
reversibel (di dekat tempat kerja antibiotik makrolida dan klindamisin, yang
dihambat secara kompetitif oleh obat ini). Walaupun pengikatan tRNA pada
bagian pengenalan kodon ini ternyata menghalangi pengikatan ujung tRNA
aminosil yang mengandung asam amino ke tempat akseptor pada subunit ribosom
50 S. Interaksi antara peptidiltranferase dengan substrat asam aminonya tidak
dapat terjadi, sehingga pembentukan ikatan peptide terhambat (Mardjono, 1995).
Konsentrasi kloramfenikol yang tinggi dapat bersifat bakterisid terhadap
bakteri tertentu, namun umumnya kloramfenikol bersifat bakteriostatik
(Ganiswara, 2007). Selain menghambat sintesis protein, kloramfenikol juga
mencegah ujung aminoasil tRNA bergabung dengan peptidil transferase (enzim
21
yang menghubungkan asam amino dengan rantai peptid selama proses sintesis
protein). Kloramfenikol bersifat larut dalam lemak sehingga menembus sel bakteri
(Olson, 2004).
F. Uji Profil Fitokimia
Fitokimia merupakan zat kimia alami yang terdapat di dalam tumbuhan dan
dapat memberikan rasa, aroma atau warna pada tumbuhan (Daris, 2010).
Penapisan fitokimia adalah pemeriksaan kandungan kimia secara kualitatif untuk
mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam suatu tumbuhan.
Tumbuhan sebagai makhluk hidup akan menghasilkan senyawa metabolit
sekunder sebagai bentuk adaptasinya dengan lingkungan sekitar. Senyawa ini
memiliki fungsi sebagai alat pertahanan diri dan reproduksi. Metabolit sekunder
juga dikatakan memiliki sifat adaptif agar tumbuhan dapat bertahan hidup atau
tidak musnah (Ruslin dan Sahidin, 2008).
Penapisan fitokimia dilakukan menurut metode Cuiley (1984). Penapisan
fitokimia dilakukan untuk mengetahui komponen kimia pada tumbuhan tersebut
secara kualitatif. Misalnya: identifikasi tanin dilakukan dengan menambahkan
1-2 ml besi (III) klorida pada sari alkohol. Terjadinya warna biru kehitaman
menunjukkan adanya tanin galat sedang warna hijau kehitaman menunjukkan
adanya tanin katekol (Praptiwi dkk., 2006). Senyawa metabolit sekunder yang
terdapat antara tanaman pada daerah yang satu dan daerah yang lainnya berbeda-
beda walaupun dengan jenis tanaman yang sama. Senyawa metabolit sekunder
22
yang dihasilkan oleh tumbuhan terbagi ke dalam beberapa golongan utama antara
lain flavonoid, alkaloid, triterpen, steroid, saponin, dan tanin (Saleh, 2007).
1. Flavonoid
Kandungan flavonoid yang merupakan senyawa fenol dapat menyebabkan
penghambatan terhadap sintesis dinding sel bakteri. Oleh karena itu flavonoid
merupakan komponen antibakteri yang potensial (Liana, 2010). Flavonoid dapat
menghambat perakitan dinding sel bakteri. Penghambatan tersebut mengakibatkan
penggabungan rantai glikan tidak terhubung silang ke dalam peptidoglikan
dinding sel menuju suatu struktur yang lemah dan menyebabkan kerusakan pada
dinding sel bakteri. Kerusakan pada dinding sel bakteri atau hambatan pada
pembentukannya dapat berakibat lisis pada sel bakteri (Jawetz dkk., 2007).
Lisisnya sel bakteri tersebut dikarenakan tidak berfungsinya lagi dinding sel yang
mempertahankan bentuk dan melindungi bakteri yang pada akhirnya
menyebabkan kematian bakteri (Liana, 2010).
Senyawa flavonoid dapat juga berefek antibakteri melalui kemampuan
untuk membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan protein yang dapat
larut serta dinding sel bakteri (Dwidjoseputro, 2010). Ikatan kompleks senyawa
flavonoid dengan protein sel bakteri melalui ikatan hidrogen menjadikan sel
bakteri tidak stabil karena struktur protein sel bakteri menjadi rusak karena
adanya ikatan hidrogen dengan flavonoid, sehingga protein sel bakteri menjadi
kehilangan aktivitas biologinya, akibatnya fungsi permeabilitas sel bakteri
terganggu dan sel bakteri akan mengalami lisis yang berakibat pada kematian sel
bakteri (Harbone, 2003).
23
2. Alkaloid
Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak ditemukan
di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloida berasal dari tumbuh-tumbuhan dan
tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Hampir semua alkaloida yang
ditemukan di alam mempunyai keaktifan biologis tertentu. Alkaloid memiliki
kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga adalah dengan cara
mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga
lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel
tersebut. Senyawa alkaloida mempunyai struktur heterosiklik yang mengandung
atom N didalam intinya dan bersifat basa, karena itu dapat larut dalam asam-asam
serta membentuk garamnya, dan umumnya mempunyai aktifitas fisiologis baik
terhadap manusia ataupun hewan (Robinson, 2005).
3. Triterpen
Triterpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan
oleh tumbuhan terutama terkandung pada getah dan vakuola selnya. Pada
tumbuhan senyawa-senyawa golongan terpen dan turunanannya merupakan hasil
metabolisme sekunder. Triterpen atau isoprenoid ini merupakan salah satu
senyawa organik yang banyak tersebar di alam, yang terbentuk dari satuan isopren
(CH3=C(CH3)-CH=CH2) dan kerangka karbonnya dibangun oleh penyambungan
dua atau lebih satuan isopren. Sebagian besar triterpen mempunyai kerangka
karbon yang dibangun oleh dua atau lebih unit C-5 yang disebut unit isopren
(Lenny, 2006).
24
Triterpen mempunyai manfaat sebagai obat tradisional, antibakteri dan
antijamur. Senyawa terpenoid ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan
cara mengganggu proses pembentukan membran sel atau dinding sel bakteri
sehingga dinding sel atau membran sel bakteri tidak terbentuk atau terbentuk tapi
tidak sempurna (Lenny, 2006).
4. Saponin
Senyawa saponin dari tumbuhan adalah glikosida dari triterpen dan steroid
yang larut dalam air dan tersebar luas pada tumbuhan tingkat tinggi. Keberadaan
saponin sangat mudah yaitu ditandai dengan pembentukan larutan koloidal
dengan air yang apabila dikocok menimbulkan buih, sehingga senyawa saponin
bisa berperan sebagai senyawa penurun tegangan permukaan yang kuat (Cheeke,
2004). Manfaat lain dari saponin adalah sebagai spermisida (obat kontrasepsi laki-
laki), antimikrobia, anti-infalmasi, dan aktivitas sitotoksik (Purnobasuki, 2004).
Senyawa saponin memiliki banyak khasiat antara lain, dapat menghambat
bakteri dengan cara merusak membran sel pada bakteri. Kerusakan membran sel
bakteri ini menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam bakteri
yaitu protein, nukleotida dan lain-lain yang akan menyebabkan bakteri mati
(Jaya, 2010).
5. Tanin
Tanin merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenol.
Secara kimia terdapat dua jenis tanin yang tersebar tidak merata dalam dunia
tumbuhan, yaitu tanin terkondensasi atau tanin katekin dan tanin terhidrolisis
(Robinson, 2005). Tanin yang terdapat dalam tumbuhan diduga dapat
25
mengkerutkan dinding sel atau membran sel bakteri sehingga dapat mengganggu
permeabilitas sel dari bakteri. Akibat terganggunya permeabilitas, sel bakteri tidak
dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau
bahkan mati (Ajizah, 2004).
G. Uji Aktivitas Antibakteri
Uji antibakteri dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas
suatu bakteri terhadap antibakteri. Terdapat 3 metode yang umum digunakan
dalam uji antibakteri, yaitu metode dilusi kaldu, metode dilusi agar, dan metode
difusi cakram. Prinsip dari metode difusi cakram adalah senyawa antibakteri
dijenuhkan ke dalam kertas saring (kertas cakram). Kertas cakram yang
mengandung senyawa antibakteri tertentu ditanam pada media pembenihan agar
padat yang telah dicampur dengan bakteri yang diuji, kemudian diinkubasi pada
suhu dan waktu tertentu. Selanjutnya diamati adanya area (zona) bening di sekitar
cakram kertas yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri (Brock dan
Madigan, 1991).
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran zona penghambatan dan
harus dikontrol adalah (Pratama, 2005) :
1. Konsentrasi bakteri pada permukaan medium. Semakin tinggi konsentrasi
bakteri maka zona penghambatan akan semakin kecil.
2. Kedalaman medium pada cawan petri. Semakin tebal medium pada cawan petri
maka zona penghambatan akan semakin kecil.
26
3. Nilai pH dari medium. Beberapa antibiotika bekerja dengan baik pada kondisi
asam dan beberapa kondisi alkali/basa.
4. Kondisi aerob/anaerob. Beberapa antibakterial kerja terbaiknya pada kondisi
aerob dan yang lainnya pada kondisi anaerob.
27
H. Kerangka Konsep
Gambar 7. Kerangka Konsep Penelitian
Infeksi olehbakteri S. typhi
Demam Tifoid
Pemberian antibiotik dalam jangka waktuyang panjang menyebabkan resistensi bakteri
Kandungan kimia, khasiat dan efek samping yangbelum terbukti secara ilmiah
Uji profil fitokimia denganmetode KLT
Uji aktivitas antibakteriterhadap S. typhi YCTC
Luas zona hambat
Profil fitokimia dan AktivitasAntibakteri terhadap pertumbuhan
S. typhi YCTC
Penggunaan tanaman sebagaiobat tradisional
28
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-September 2014 yang bertempat
di Laboratorium Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari,
Sulawesi Tenggara.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental ekplorasi yaitu pengujian
profil fitokimia dan aktivitas ekstrak metanol daun, buah, bunga, batang, dan akar
dari beberapa tanaman terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella typhi YCTC.
C. Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanaman Keji beling
(S. crispus) (akar, batang dan daun), Belimbing (A. bilimbi) (akar, batang dan
daun), Kangkung (I. aquatica) (batang dan daun), Secang (C. sappan) (bunga,
biji, batang dan daun), Jarak pagar (J. Curcas) (akar, batang dan daun), metanol,
medium NA, alkohol 70%, bakteri S. typhi YCTC, kloramfenikol, akuades,
larutan NaCl steril, kloroform, metanol, HCl pekat, asam asetat, FeCl3 1%,
H2SO4, benzene, n-heksan, etil asetat, pereaksi Lieberman-burchard dan amoniak.
29
D. Alat Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aluminium foil, autoklaf
(WiseClave), batang pengaduk, blender (Philips), cawan petri, chamber, corong,
erlenmeyer (Pyrex), gelas kimia, gelas ukur (Pyrex), hot plate, inkubator, jarum
ose, kertas saring, labu takar, laminar air flow, lampu UV (Srahlen Germany),
neraca analitik, oven (Gallenkamp Civilab-Australia), penotol/pipa kapiler, pinset,
pipet mikro, pipet tetes, pisau, plat KLT, rotary vacuum evaporator (IKA-Werke
RV 05 Germany), spatula, spektronik 20D, wadah plastik (jerigen dan botol
plastik) dan vial.
E. Prosedur Penelitian
1. Pengambilan dan Penyiapan Sampel
Sampel pada penelitian ini yaitu tanaman Keji beling (S. crispus),
Belimbing (A. bilimbi) dan Kangkung (I. aquatica) diperoleh dari kebun warga
Desa Monapa Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan sedangkan
tanaman Secang (C. sappan) dan Jarak pagar (J. curcas) diperoleh di daerah
sekitar Kota Kendari. Preparasi sampel dilakukan dengan membersihkan sampel
terlebih dahulu kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan sebelum
dipotong-potong menjadi kecil kemudian diblender sampai menjadi serbuk.
Semua serbuk tersebut kemudian ditimbang 50 - 100 gram dari tiap-tiap bagian
tanaman dan disimpan dalam wadah plastik (botol plastik) untuk pengerjaan
selanjutnya.
30
2. Tahap Ekstraksi
Ekstraksi maserasi serbuk tanaman dilakukan dalam wadah tertutup selama
3 x 24 jam menggunakan pelarut metanol. Pemisahan residu dan filtrat
dilakukan setiap 1 x 24 jam diiringi penggantian pelarut yang sama. Maserat
dipisahkan dari ampas dengan penyaringan menggunakan corong dan kertas
saring kemudian diuapkan dengan Rotary Vacuum Evaporator pada suhu 56o C
hingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak tersebut kemudian ditimbang dan
didapatkan bobot yang berbeda-beda.
3. Metode Pengenceran
Konsentrasi ekstrak 10.000 ppm yang digunakan pada metode ini ditentukan
melalui uji pendahuluan dengan mengacu pada metode sebelumnya. Konsentrasi
tersebut dibuat dengan melarutkan ekstrak dalam metanol.
4. Skrining Fitokimia
Uji fitokimia dengan KLT dilakukan dengan menggunakan plat silika gel
GF254. Ekstrak dari masing-masing tanaman ditotolkan pada jarak ± 1 cm dari tepi
bawah plat dengan pipa kapiler kemudian dikeringkan dan dielusi dengan fase
gerak kloroform-metanol (9:1). Setelah gerakan fase gerak sampai pada garis
batas, elusi dihentikan. Noda-noda pada permukaan plat diperiksa di bawah sinar
UV pada panjang gelombang 254 nm, 366 nm dan sinar tampak, kemudian
diberikan reagen penguji untuk masing-masing golongan senyawa. Reagen
penguji masing-masing golongan senyawa adalah sebagai berikut:
31
a. Golongan senyawa alkaloid digunakan pereaksi Dragendorff untuk mendeteksi
yang menunjukkan bercak coklat jingga (Lutfillah, 2008).
b. Golongan senyawa flavonoid diuapi uap amoniak akan menghasilkan warna
kuning kehijauan (Kusnaeni, 2008).
c. Golongan senyawa tanin digunakan penyemprot FeCl3 1% menghasilkan
warna lambayung (biru kehitaman) (Harborne, 2003).
d. Golongan senyawa saponin ketika ditambah H2SO4 menimbulkan warna ungu-
ungu gelap (Kristianingsih, 2005).
e. Golongan senyawa triterpenoid digunakan pereaksi Lieberman-burchard
menghasilkan warna merah ungu (violet).
5. Uji Aktivitas Antibakteri
a. Sterilisasi alat dan bahan
Cawan petri, erlenmeyer, tabung reaksi, spatula, kertas saring, Nutrient
Agar (NA), dan seluruh alat dan bahan (kecuali metanol dan ekstrak tanaman)
yang akan digunakan disterilisasi di dalam autoklaf pada suhu 121oC dan tekanan
15 Psi selama 15 – 20 menit setelah sebelumnya dicuci bersih, dikeringkan, dan
dibungkus dengan kertas (Pelczar dan Chan, 2005).
b. Penyiapan media
Media untuk pertumbuhan bakteri digunakan nutrient agar (NA). Media
disiapkan dengan cara menimbang media NA sebanyak 20 gram, dilarutkan dalam
1.000 ml air suling dalam erlenmeyer dan dipanaskan menggunakan hot plate
32
sampai mendidih dan larut sempurna kemudian disterilkan dalam autoklaf pada
suhu 121 oC selama 15 menit.
c. Penyiapan kultur bakteri
Bakteri uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu bakteri S. typhi YCTC
yang berasal dari koleksi pribadi Prof. Sahidin. Bakteri yang digunakan
diremajakan dengan cara memindahkan 1 atau 2 ose yang ditanam pada media
NA, kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi dan diinkubasi selama 24 jam
pada suhu 37 ± 2oC.
d. Pembuatan suspensi mikroba
Suspensi standar 0,5 Mc. Farland
Sebanyak 0,05 mL BaCl2 dicampurkan dengan 9,95 mL H2SO4 1% dalam
tabung reaksi setelah itu dihomogenkan dimana suspensi 0,5 Mc. Farland adalah
suspensi standar yang menunjukkan kekeruhan jamur sama dengan 108 CFU/mL.
Cara pembuatan :
Bakteri yang akan diuji disuspensikan dengan cara menumbuhkan
mikroba dalam media cair NaCl steril. Kekeruhan bakteri diukur hingga sesuai
dengan standar Mc. Farland 0,5 menggunakan spektronik 20D pada λ 625 nm
(Khan dkk, 2006).
e. Pengujian aktivitas antibakteri
Aktivitas antibakteri diuji dengan metode difusi agar menggunakan kertas
cakram. Metode ini dilakukan dengan cara mencampur sebanyak 50 μl suspensi
bakteri ke dalam 15 ml media agar yang telah di cairkan dalam cawan petri steril
dan kemudian dibiarkan menjadi padat. Kertas cakram dengan diameter 6 mm
33
yang telah diteteskan 20 μl masing-masing zat uji (Adyana dkk., 2004), kontrol
pelarut dan ditambahkan pula antibiotik standar (kloramfenikol) diletakkan pada
permukaan media selanjutnya diinkubasi. Hasil uji daya antibakteri didasarkan
pada pengukuran diameter daerah hambat (DDH) pertumbuhan bakteri yang
terbentuk di sekeliling kertas cakram (Noor dkk., 2006).
F. Pengolahan Data
Data yang telah dihasilkan dianalisis dengan cara membandingkan karakter
perubahan visual yang terjadi pada pengujian yang dilakukan. Untuk pengujian
aktivitas antibakteri dapat dilihat dengan mengukur zona bening yang terbentuk
pada media pertumbuhan bakteri yang digunakan lalu membandingkan antara
zona bening yang terbentuk pada kontrol positif dan sampel penelitian. Luas zona
hambat setiap ekstrak tanaman dan kontrol positif diplotkan dalam bentuk
diagram batang untuk melihat perbandingan keefektifan dalam menghambat
pertumbuhan bakteri S. typhi YCTC. Diagram batang tersebut akan memberikan
gambaran ekstrak tanaman apakah yang mempunyai potensi paling baik dalam
menghambat pertumbuhan bakteri.
Data yang diperoleh pada uji profil fitokimia dengan metode KLT dapat
dianalisis dengan melihat noda yang tampak pada plat KLT setelah diberi reagen
penguji untuk menentukan golongan senyawa yang terdapat pada masing-masing
ekstrak tanaman.
34
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Preparasi Sampel
Sampel pada penelitian ini yaitu tanaman Keji beling (S. crispus),
Belimbing (A. bilimbi) dan Kangkung (I. aquatica) diperoleh dari kebun warga
Desa Monapa Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan sedangkan
tanaman Secang (C. sappan) dan Jarak pagar (J. curcas) diperoleh di daerah
sekitar Kota Kendari. Preparasi sampel dimulai dengan melakukan sortasi basah
dengan air mengalir yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor yang terdapat
pada sampel. kemudian dikeringkan terlebih dahulu sebelum dipotong-potong
menjadi kecil. Pemotongan sampel bertujuan untuk memudahkan proses
pengolahan menjadi serbuk, selanjutnya dilakukan proses sortasi kering untuk
memisahkan kotoran, bahan organik asing dan simplisia yang rusak karena proses
sebelumnya. Sampel kemudian diblender sampai menjadi serbuk dimana semakin
kecil ukuran dari suatu partikel akan memperbesar luas permukaan dari sampel
sehingga interaksi antara sampel dan pelarut akan lebih maksimal. Semua serbuk
tersebut kemudian ditimbang 50 - 100 gram dari tiap-tiap bagian tanaman dan
disimpan dalam wadah plastik (botol plastik) untuk pengerjaan selanjutnya.
Pada pembuatan ekstrak dari masing-masing tanaman cara penyarian yang
dipilih adalah metode maserasi. Metode ini dipilih karena memiliki beberapa
keuntungan antara lain tidak adanya proses pemanasan sehingga senyawa-
senyawa yang bersifat labil tidak menjadi rusak atau hilang oleh adanya panas,
cara pengerjaannya mudah, peralatannya sederhana dan mudah diusahakan
35
(Anonim, 1986). Maserasi dilakukan dalam wadah tertutup selama 3 x 24 jam
menggunakan pelarut metanol. Pemisahan residu dan filtrat dilakukan setiap
1 x 24 jam diiringi penggantian pelarut yang sama. Tujuan perendaman selama
24 jam adalah untuk mengendapkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan
yang ikut tersari dalam pelarut. Maserat dipisahkan dari ampas dengan
penyaringan menggunakan corong dan kertas saring kemudian diuapkan dengan
Rotary Vacum Evaporator pada suhu 56o C hingga diperoleh ekstrak kental. Hasil
ekstraksi serbuk tiap bagian tanaman dengan menggunakan pelarut metanol dan
setelah diuapkan dengan menggunakan alat Rotary Vacum Evaporator dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perhitungan Rendamen Ekstrak
Sampel Serbuk (g) Ekstrak(g)
Rendamen(Ekstrak/Serbuk x
100 %) (%)
Keji Beling(Strobilanthescrispus)
Akar (A1) 44,32 1,52 3, 42
Batang (A2) 50,31 2,35 4,67
Daun (A3) 59,66 2,16 3,62
Belimbing(Averrhoabilimbi)
Akar (B1) 60,25 3,44 5,70
Batang (B2) 72,47 2,54 3,50
Daun (B3) 53,42 2,04 3,81
Kangkung(Ipomoeaaquatica)
Batang (C1) 40,55 1,40 3,45
Daun (C2) 48,24 1,31 2,71
Jarak Pagar(Jatropha curcas)
Akar (D1) 55,21 2,04 3,69
Batang (D2) 63,48 2,11 3,32
Daun (D3) 48,50 2,27 4,68
Secang(Caesalpiniasappan)
Batang (E1) 52,66 2,15 4,08
Daun (E2) 45,75 1,86 4,06
Biji (E3) 40.58 1,05 2,58
Bunga (E4) 45,20 1,63 3,60
36
B. Uji Profil Fitokimia
Uji profil fitokimia pada penelitian ini dilakukan dengan metode KLT.
Metode KLT dilakukan karena metode ini sederhana, murah, serta dapat
menganalisis beberapa komponen secara serempak. Pengujian dilakukan untuk
mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada masing-
masing ekstrak metanol tanaman. Golongan senyawa metabolit sekunder yang
diuji pada penelitian ini yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, saponin dan triterpen.
Uji fitokimia dengan KLT dilakukan dengan menggunakan plat silika gel
GF254. Ekstrak dari masing-masing tanaman ditotolkan pada jarak ± 1 cm dari tepi
bawah plat dengan pipa kapiler kemudian dikeringkan, tujuan dikeringkannya
totolan pada plat sebelum dielusi adalah untuk menguapkan pelarut yang
digunakan sehingga yang terdapat pada plat nantinya hanya senyawa-senyawa
yang ada dalam ekstrak tersebut. Eluen yang dipakai sebagai fase gerak pada
penelitian ini adalah kloroform-metanol (9:1), digunakan eluen yang sama untuk
semua golongan senyawa dikarenakan fokus pada penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi golongan senyawa metabolit sekunder apa saja yang terdapat
pada masing-masing ekstrak tanaman. Setelah gerakan fase gerak sampai pada
garis batas, elusi dihentikan. Kemudian dilihat pada sinar UV 254 nm, 366 nm
dan sinar tsmpak sebelum ditambahkan reagen penguji untuk masing-masing
golongan senyawa. Gambar 8 menunjukkan plat KLT setelah dielusi pada panjang
gelombang 254 nm, 366 nm dan sebelum diberi penampak noda.
37
` (a) Lampu UV 254 nm (b) Lampu UV 366 nm
(c) Plat KLT sebelum diberi penampak noda
Gambar 8. Plat KLT setelah dielusi
1. Alkaloid
Hasil uji golongan senyawa alkaloid diperoleh berdasarkan noda yang
tampak pada plat KLT setelah masing-masing ekstrak ditotolkan pada lempeng
dan dielusi dengan fase gerak kemudian ditambahkan pereaksi Dragendorff
sebagai penampak noda. Ekstrak dengan kandungan senyawa alkaloid akan
menghasilkan warna coklat jingga yang merupakan reaksi antara bismut dan
merkuri nitrat dengan senyawa alkaloid.
38
Gambar 9. Uji Golongan Senyawa Alkaloid
Hasil uji golongan senyawa alkaloid menunjukkan hasil positif kandungan
senyawa pada akar dan daun tanaman keji beling (S. crispus), batang dan daun
tanaman belimbing (A. bilimbi), daun tanaman jarak pagar (J. curcas) dan batang
tanaman secang (C. sappan).
2. Flavonoid
Hasil uji golongan senyawa flavonoid diperoleh berdasarkan noda yang
tampak pada plat KLT setelah masing-masing ekstrak ditotolkan pada lempeng
dan dielusi dengan fase gerak kemudian diuapi dengan uap amoniak. Hasil uji
positif akan menampakkan warna kuning kehijauan.
Gambar 10. Uji Golongan Senyawa Flavonoid
39
Hasil uji golongan senyawa flavonoid seperti pada Gambar 10 menunjukkan
hasil positif kandungan senyawa pada daun tanaman keji beling (S. crispus),
batang tanaman kangkung (A. bilimbi) dan batang tanaman jarak pagar (J. curcas).
3. Tanin
Hasil uji golongan senyawa tanin diperoleh berdasarkan noda yang tampak
pada plat KLT setelah masing-masing ekstrak ditotolkan pada lempeng dan dielusi
dengan fase gerak kemudian ditambahkan FeCl3 1% sebagai penampak noda.
Hasil uji positif akan menghasilkan warna lembayung (biru kehitaman).
Gambar 11. Uji Golongan Senyawa Tanin
Hasil uji golongan senyawa tanin seperti pada Gambar 11 menunjukkan
hasil positif kandungan senyawa pada daun tanaman keji beling (S. crispus),
batang tanaman belimbing (A. bilimbi), daun tanaman kangkung (I. aquatica) dan
batang, daun dan bunga tanaman secang (C. sappan).
40
4. Saponin
Hasil uji golongan senyawa saponin diperoleh berdasarkan noda yang
tampak pada plat KLT setelah masing-masing ekstrak ditotolkan pada lempeng
dan dielusi dengan fase gerak kemudian ditambahkan H2SO4. Hasil uji positif
akan menghasilkan warna ungu-ungu gelap.
Gambar 12. Uji Golongan Senyawa Saponin
Hasil uji golongan senyawa tanin seperti pada Gambar 12 menunjukkan
hasil positif kandungan senyawa pada akar dan batang tanaman keji beling (S.
crispus), semua bagian tanaman belimbing (A. bilimbi), semua bagian tanaman
kangkung (I. aquatica), semua bagian tanaman jarak pagar (J. curcas) dan bagian
batang, biji dan bunga tanaman secang (C. sappan).
5. Triterpen
Hasil uji golongan senyawa triterpen diperoleh berdasarkan noda yang
tampak pada plat KLT setelah masing-masing ekstrak ditotolkan pada lempeng
dan dielusi dengan fase gerak kemudian ditambahkan pereaksi Lieberman-
burchard. Hasil uji positif akan menghasilkan warna merah-ungu (violet).
41
Gambar 13. Uji Golongan Senyawa Triterpen
Hasil uji golongan senyawa tanin seperti pada Gambar 13 menunjukkan
hasil positif kandungan senyawa pada bagian akar tanaman jarak pagar (J. curcas)
dan bagian batang dan bunga tanaman secang (C. sappan).
Hasil uji profil fitokimia untuk menentukan kandungan golongan senyawa
metabolit sekunder dari masing-masing ekstrak metanol tanaman dapat dilihat
pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil uji golongan senyawa metabolit sekunder
Sampel A F Ta S Tr
Keji Beling(Strobilanthescrispus)
Akar (A1) 1 - - 2 -
Batang (A2) - - - 1 -
Daun (A3) 1 1 1 - -
Belimbing(Averrhoa bilimbi)
Akar (B1) - - - 2 -
Batang (B2) 1 - 1 1 -
Daun (B3) 1 - - 2 -
Kangkung(Ipomoea aquatica)
Batang (C1) - 1 - 3 -
Daun (C2) - - 1 2 -
Jarak Pagar(Jatropha curcas)
Akar (D1) - - - 2 1
Batang (D2) - 1 - 3 -
Daun (D3) 1 - - 2 -
Secang(Caesalpinia
Batang (E1) 1 - 1 3 2
Daun (E2) - - 1 - -
42
sappan) Biji (E3) - - - 2 -
Bunga (E4) - - 1 3 3
Keterangan :
A : Alkaloid Tr : Triterpen
F : Flavonoid 1,2,3 : Jumlah kandungan senyawa
Ta : Tanin - : Tidak mengandung
S : Saponin
C. Uji Aktivitas Antibakteri
Uji aktivitas antibakteri pada penelitian ini dilakukan terhadap bakteri S.
typhi YCTC. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui daya hambat ekstrak
metanol dari masing-masing ekstrak tanaman dan kloramfenikol terhadap bakteri
S. typhi YCTC. sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanaman Keji
beling (S. crispus), Belimbing (A. bilimbi), Kangkung (I. aquatica), Secang (C.
sappan), Jarak pagar (J. Curcas). Masing-masing ekstrak diencerkan dengan
konsentrasi 10.000 ppm kemudian diuji pada bakteri uji untuk melihat aktivitas
tanaman tersebut dalam menghambat pertumbuhan pada bakteri uji.
Hasil pengukuran diameter zona hambat terhadap pertumbuhan S. typhi
YCTC didapatkan dari hasil pengukuran diameter zona bening yang terbentuk di
sekitar kertas cakram, kemudian nilai disesuaikan dengan indikator diameter zona
hambat, dengan interpretasi apabila didapatkan nilai ˂ 3 mm pada pengukuran
diameter zona bening bermakna respon hambatan lemah, 3-6 mm bermakna
respon hambatan sedang dan jika bernilai > 6 mm respon hambatan kuat (Pan
dkk., 2009).
Hasil pengujian aktivitas antibakteri dari masing-masing ekstrak metanol
sampel tanaman terhadap bakteri S. typhi YCTC memberikan hasil yang berbeda-
43
beda. Pada tanaman Keji beling (S. crispus), diperoleh interpretasi respon
hambatan yang berbeda-beda pada masing-masing bagian tanaman. Bagian akar
tanaman menunjukkan interpretasi respon hambatan yang kuat terhadap bakteri
dengan nilai 9 mm, bagian batang tidak menunjukkan respon hambatan terhadap
bakteri uji dengan nilai 0 mm, sedangkan pada bagian daun menunjukkan respon
hambatan yang sedang dengan nilai 5 mm sehingga bagian akar dan daun dari
tanaman Keji beling (S. crispus) dapat dikatakan memiliki potensi sebagai
antibakteri terhadap bakteri S. typhi YCTC berdasarkan respon hambatan berupa
zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram seperti ditunjukkan pada
Gambar 14.
Gambar 14. Hasil uji aktivitas tanaman Keji beling (S. crispus)
Hasil uji pada tanaman Belimbing (A. bilimbi) menunjukkan hanya pada
bagian daun yang berpotensi sebagai antibakteri S. typhi YCTC dengan
interpretasi respon hambatan kuat dengan nilai 9 mm, sedangkan pada bagian akar
dan batang tanaman tidak berpotensi sebagai antibakteri terhadap S. typhi YCTC
karena tidak adanya zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Gambar
15 menunjukkan hasil uji aktivtas dari tanaman belimbing (A. bilimbi).
44
Gambar 15. Hasil uji aktivitas tanaman Belimbing (A. bilimbi)
Hasil uji pada tanaman Kangkung (I. aquatica) dan Jarak pagar (J. Curcas)
menunjukkan tidak adanya respon hambatan dari keseluruhan bagian tanaman
karena tidak terbentuk zona bening di sekitar kertas cakram pada cawan petri
seperti ditunjukkan pada Gambar 16, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua
tanaman tersebut belum berpotensi sebagai antibakteri terhadap S. typhi YCTC.
(a) (b)
Gambar 16. (a) Hasil uji aktivitas tanaman Kangkung (I. aquatica) (b) Hasil ujiaktivitas tanaman Jarak pagar (J. curcas)
Hasil uji aktivitas pada tanaman Secang (C. sappan) menunjukkan adanya
respon hambatan terhadap bakteri S. typhi YCTC pada bagian batang dan bunga
44
Gambar 15. Hasil uji aktivitas tanaman Belimbing (A. bilimbi)
Hasil uji pada tanaman Kangkung (I. aquatica) dan Jarak pagar (J. Curcas)
menunjukkan tidak adanya respon hambatan dari keseluruhan bagian tanaman
karena tidak terbentuk zona bening di sekitar kertas cakram pada cawan petri
seperti ditunjukkan pada Gambar 16, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua
tanaman tersebut belum berpotensi sebagai antibakteri terhadap S. typhi YCTC.
(a) (b)
Gambar 16. (a) Hasil uji aktivitas tanaman Kangkung (I. aquatica) (b) Hasil ujiaktivitas tanaman Jarak pagar (J. curcas)
Hasil uji aktivitas pada tanaman Secang (C. sappan) menunjukkan adanya
respon hambatan terhadap bakteri S. typhi YCTC pada bagian batang dan bunga
44
Gambar 15. Hasil uji aktivitas tanaman Belimbing (A. bilimbi)
Hasil uji pada tanaman Kangkung (I. aquatica) dan Jarak pagar (J. Curcas)
menunjukkan tidak adanya respon hambatan dari keseluruhan bagian tanaman
karena tidak terbentuk zona bening di sekitar kertas cakram pada cawan petri
seperti ditunjukkan pada Gambar 16, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua
tanaman tersebut belum berpotensi sebagai antibakteri terhadap S. typhi YCTC.
(a) (b)
Gambar 16. (a) Hasil uji aktivitas tanaman Kangkung (I. aquatica) (b) Hasil ujiaktivitas tanaman Jarak pagar (J. curcas)
Hasil uji aktivitas pada tanaman Secang (C. sappan) menunjukkan adanya
respon hambatan terhadap bakteri S. typhi YCTC pada bagian batang dan bunga
45
dengan adanya zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Bagian
batang dari tanaman menunjukkan interpretasi sedang dengan nilai 3,5 mm, pada
bagian bunga juga menunjukkan interpretasi sedang dengan nilai 6 mm,
sedangkan bagian daun dan biji dari tanaman tidak menunjukkan adanya respon
hambatan terhadap bakteri S. typhi YCTC. Gambar 17 menunjukkan hasil uji
aktivitas antibakteri tanaman secang (C. sappan).
Gambar 17. Hasil uji aktivitas tanaman Secang (C. sappan)
Perbedaan respon hambat yang dilihat dengan terbentuknya diameter zona
bening di sekitar kertas cakram yang telah dijenuhkan dengan ekstrak dari bagian
yang berbeda-beda masing-masing tanaman terhadap S. typhi YCTC diduga
karena terdapat perbedaan kandungan senyawa aktif yang dimiliki oleh masing-
masing ekstrak walaupun pada prinsipnya semua tanaman memiliki senyawa
metabolik sekunder yang aktif. Senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan
biasanya tersebar merata ke seluruh bagian tanaman tetap dalam kadar yang
berbeda-beda (Robinson, 2005).
Hasil uji aktivitas antibakteri dari masing-masing ekstrak metanol tanaman
dapat dilihat pada Tabel 3.
46
Tabel 3. Hasil uji aktivitas antibakteri
SampelDiameter
Daerah hambat(mm)
Interpretasi
Keji Beling(Strobilanthescrispus)
Akar (A1) 9 Kuat
Batang (A2) 0 Tidak ada aktivitas
Daun (A3) 5 Sedang
Belimbing(Averrhoa bilimbi)
Akar (B1) 0 Tidak ada aktivitas
Batang (B2) 0 Tidak ada aktivitas
Daun (B3) 9 Kuat
Kangkung(Ipomoea aquatica)
Batang (C1) 0 Tidak ada aktivitas
Daun (C2) 0 Tidak ada aktivitas
Jarak Pagar(Jatropha curcas)
Akar (D1) 0 Tidak ada aktivitas
Batang (D2) 0 Tidak ada aktivitas
Daun (D3) 0 Tidak ada aktivitas
Secang(Caesalpiniasappan)
Batang (E1) 3,5 Sedang
Daun (E2) 0 Tidak ada aktivitas
Biji (E3) 0 Tidak ada aktivitas
Bunga (E4) 6 Sedang
Data hasil penelitian di atas menunjukkan ada beberapa ekstrak yang tidak
menunjukkan aktifitas daya hambat sebagai antibakteri terhadap S. typhi YCTC
sedangkan pada hasil profil fitokimianya memiliki kandungan golongan metabolit
sekunder yang kemungkinan aktif sebagai antibakteri. Ada beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi hal tersebut. Setiap senyawa memiliki konfigurasi yang
berbeda-beda sehingga efek biologi pada setiap senyawa juga berbeda meskipun
dalam golongan senyawa metabolit yang sama dan banyaknya kandungan
senyawa aktif dalam ekstrak menyebabkan senyawa aktif akan lebih mudah untuk
merusak sel bakteri, tidak terbentuknya zona hambat pada beberapa ekstrak
disebabkan oleh rendahnya senyawa aktif yang dapat menyebabkan
penghambatan pertumbuhan bakteri uji (terjadi pada sebagian kecil dari jumlah
47
total sel bakteri) sehingga bakteri yang tidak terganggu oleh senyawa aktif yang
kadarnya rendah dapat terus tumbuh.
Faktor lain yang mempengaruhi hasil penelitian ini adalah adanya unsur-
unsur pada ekstrak yang merupakan nutrien yang dibutuhkan mikroorganisme
dalam jumlah yang relatif besar, yakni sebagai penyusun protein, sebagai kofaktor
enzim dan kation seluler (Prescott dkk., 2005). Setiap tumbuhan juga memiliki
perbedaan akumulasi, jenis, dan kadar metabolit sekunder yang kemungkinan
dapat menyebabkan perbedaan aktivitas antibakteri (Irmalia, 2011). Hasil uji
aktivitas antibakteri dari tanaman jarak pagar (J. curcas) menunjukkan tidak
adanya respon hambatan pada bakteri S. typhi. Hal ini tidak sesuai dengan
beberapa literatur dan pengetahuan empiris masyarakat yang menjelaskan bahwa
tanaman ini berpotensi sebagai antibakteri, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor
lingkungan tempat tumbuh dari tanaman dimana lokasi tanaman yang berbeda
akan menghasilkan kandungan senyawa metabolit sekunder yang berbeda pula
sehingga aktivitas yang dimiliki juga akan berbeda, selain itu tanaman ini
kemungkinan aktif pada jenis bakteri yang lain seperti E. coli dan S. aureus.
Senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan triterpen merupakan
senyawa yang memiliki kesamaan struktur dengan kontrol positif yang digunakan
yaitu kloramfenikol dimana pada senyawa-senyawa tersebut terdapat cincin
aromatik yang juga terdapat pada kloramfenikol sehingga dapat dikatakan bahwa
cincin aromatik tersebut yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri oleh karena
itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan aktivitas dari masing-
masing golongan senyawa berkaitan dengan struktur yang dimilikinya. Gambar 18
48
OH
N
O
O-
OH
HN
O
Cl
Cl
menunjukkan perbandingan struktur dari kloramfenikol dengan masing-masing
golongan senyawa metabolit sekunder.
(a) (b)
(c) (d)
(e) (f)
Gambar 18. (a) Struktur kloramfenikol (b) Struktur alkaloid (c) Strukturflavonoid (d) Struktur tanin (e) Struktur saponin(f) Struktur triterpen
N
O
O
OH
OH
49
Kloramfenikol sebagai kontrol positif merupakan senyawa dengan rumus
molekul C11H12Cl2N2O5 yang digunakan sebagai antibiotik bersifat bakteriostatik
dan berspektrum luas. Kloramfenikol bertindak dengan jalan menghambat sintesis
protein yaitu mengikat sub unit 50 S pada ribosom sel bakteri dan menghambat
aktifitas enzim peptidil transferase dengan cepat tanpa mengganggu sintesis DNA
dan RNA. Kerja kloramfenikol dengan melihat kerangka molekul senyawa
terdapatnya atom klor dan cincin aromatik, dengan subtituen gugus nitro dengan
posisi para dan 2 gugus hidroksil. Adanya struktur tersebut memungkinkan
terjadinya interaksi dengan enzim peptidil transferase di ribosom bakteri sehingga
terjadi penghambatan kerja enzim tersebut (Mardjono, 1995).
Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri melalui penghambatan sintesis
dinding sel yang akan menyebabkan lisis pada sel sehingga sel akan mati
(Lamothe, 2009). Senyawa alkaloid memilki gugus basa yang mengandung
nitrogen yang akan bereaksi dengan senyawa asam amino yang menyusun dinding
sel bakteri dan DNA bakteri. Reaksi ini mengakibatkan terjadinya perubahan
struktur dan susunan asam amino, sehingga akan menimbulkan perubahan
keseimbangan genetik pada rantai DNA mengakibatkan kerusakan dan
mendorong terjadinya lisis sel bakteri yang akan menyebabkan kematian sel pada
bakteri (Tanaka dkk., 2006).
Mekanisme golongan senyawa flavonoid sebagai antibakteri melalui
kemampuan untuk membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan protein
yang dapat larut serta dinding sel bakteri (Dwidjoseputro, 2010). Ikatan kompleks
senyawa flavonoid dengan protein sel bakteri melalui ikatan hidrogen menjadikan
50
sel bakteri tidak stabil karena struktur protein sel bakteri menjadi rusak karena
adanya ikatan hidrogen dengan flavonoid, sehingga protein sel bakteri menjadi
kehilangan aktivitas biologinya, akibatnya fungsi permeabilitas sel bakteri
terganggu dan sel bakteri akan mengalami lisis yang berakibat pada kematian sel
bakteri (Harbone, 2003).
Mekanisme kerja tanin, dapat mengerutkan dinding sel atau membran sel
bakteri sehingga dapat mengganggu permeabilitas sel. Akibat terganggunya
permeabilitas, sel bakteri tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga
pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati (Ajizah, 2004 dalam Rahmadani,
2013).
Mekanisme kerja dari golongan senyawa saponin, akan mengubah tegangan
muka dan mengikat lipid pada sel bakteri yang menyebabkan lipid terekskresi dari
dinding sel sehingga permeabilitas membran bakteri terganggu (Wardhani dan
Nanik, 2012). Senyawa saponin dapat bersifat antibakteri dengan merusak
membran sel. Rusaknya membran menyebabkan substansi penting keluar sel dan
juga dapat mencegah masuknya bahan-bahan penting ke dalam sel. Jika fungsi
membran sel dirusak maka akan mengakibatkan kematian sel (Monalisa dkk.,
2011).
Mekanisme terpenoid sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan porin
(protein transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan
polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin yang
merupakan pintu keluar masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas
51
dinding sel bakteri yang akan mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan nutrisi
sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau mati (Cowan, 1999).
Dalam hal ini belum dapat ditentukan secara pasti satu golongan senyawa
aktif yang berfungsi sebagai antibakteri. Untuk mengetahui dengan pasti golongan
senyawa yang aktif sebagai antibakteri maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih
lanjut terhadap masing-masing golongan senyawa tersebut. Selain dari golongan
senyawa yang teridentifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT), tidak
tertutup kemungkinan terdapatnya metabolit/golongan senyawa aktif lain dalam
ekstrak metanol dari masing-masing tanaman yang belum teridentifikasi dan
berpotensi sebagai antibakteri terhadap S. typhi YCTC.
52
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Metabolit sekunder golongan senyawa alkaloid terdapat pada ekstrak metanol
akar dan daun tanaman keji beling (S. crispus), batang dan daun tanaman
belimbing (A. bilimbi), daun tanaman jarak pagar (J. curcas) dan batang
tanaman secang (C. sappan).
2. Metabolit sekunder golongan senyawa flavonoid terdapat pada ekstrak
metanol daun tanaman keji beling (S. crispus), batang tanaman kangkung
(I. aquatica) dan batang tanaman jarak pagar (J. curcas).
3. Metabolit sekunder golongan senyawa tanin terdapat pada ekstrak metanol
daun tanaman keji beling (S. crispus), batang tanaman belimbing (A. bilimbi),
daun tanaman kangkung (I. aquatica) dan batang, daun dan bunga tanaman
secang (C. sappan).
4. Metabolit sekunder golongan senyawa saponin terdapat pada ekstrak metanol
akar dan batang tanaman keji beling (S. crispus), semua bagian tanaman
belimbing (A. bilimbi), semua bagian tanaman kangkung (I. aquatica), semua
bagian tanaman jarak pagar (J. curcas) dan bagian batang, biji dan bunga
tanaman secang (C. sappan).
5. Metabolit sekunder golongan senyawa triterpen terdapat pada ekstrak metanol
akar tanaman jarak pagar (J. curcas) dan batang dan bunga tanaman secang
(C. sappan).
53
6. Ekstrak metanol bagian akar dan daun tanaman Keji beling (S. crispus)
menunjukkan adanya respon hambat terhadap pertumbuhan S. typhi YCTC
dengan nilai 9 mm (interpretasi kuat) dan 5 mm (interpretasi sedang),
sedangkan bagian batang tidak menunjukkan respon hambatan terhadap
bakteri S. typhi YCTC.
7. Ekstrak metanol bagian daun tanaman Belimbing (A. bilimbi) menunjukkan
adanya respon hambatan terhadap pertumbuhan S. typhi YCTC dengan nilai
9 mm (interpretasi kuat), sedangkan bagian akar dan batang tidak
menunjukkan respon hambatan terhadap bakteri S. typhi YCTC.
8. Ekstrak metanol bagian batang dan daun tanaman Kangkung (I. aquatica)
tidak menunjukkan adanya respon hambatan terhadap pertumbuhan S. typhi
YCTC.
9. Ekstrak metanol bagian batang dan bunga tanaman Secang (C. sappan)
menunjukkan adanya respon hambatan terhadap pertumbuhan S. typhi YCTC
dengan nilai 3,5 mm (interpretasi sedang) dan 6 mm (interpretasi sedang),
sedangkan bagian daun dan biji tidak menunjukkan respon hambatan
terhadap bakteri S. typhi YCTC.
10. Ekstrak metanol bagian akar, batang dan daun tanaman Jarak pagar
(J. curcas) tidak menunjukkan adanya respon hambatan terhadap
pertumbuhan S. typhi YCTC.
54
B. Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas adalah :
1. Perlu dilakukan isolasi terhadap ekstrak tanaman yang memiliki aktivitas
antibakteri agar diketahui kandungan senyawa yang terdapat didalamnya.
2. Perlu dilakukan pengujian dengan metode biautografi untuk mengetahui
golongan senyawa metabolit sekunder yang memberikan aktivitas antibakteri.
3. Ekstrak metanol beberapa bagian tanaman Keji beling (S. crispus), Belimbing
(A. bilimbi) dan Secang (C. sappan) memiliki potensi sebagai antibakteri
terhadap S. typhi YCTC sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai
literatur untuk penelitian selanjutnya dengan metode lain (in vivo).
4. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai potensi dan profil
fitokimia tanaman obat ini, dapat dilakukan publikasi melalui media internet
maupun sosialisasi kepada masyarakat.
55
DAFTAR PUSTAKA
Adyana, I, K., Yulinah. E., Sigit J. I. K Fisheri N., dan Insanu M., 2004, EfekEkstrak Daun Jambu Biji Daging Buah Putih dan Jambu Biji Daging BuahMerah sebagai Antidiare, Acta Pharmaceutica Indonesia, (1).
Ajizah, A.. 2004. Sensitivitas Salmonella Typhimurium terhadap Ekstrak DaunPsidium Guajava L. Bioscientiae. 1 (1).
Alamsyah, A, N., 2006, Biodisel Jarak Pagar: Bahan Bakar Alternatif YangRamah Lingkungan, Agromedia Pustaka, Jakarta.
Amelia, 2008, Saponin Fitokimia Ajaib, http/209.85.175.104/search?q=cache;XqOe419Ap-sJ: Diakses pada 23 Mei 2014.
Anonim, 1986, Sediaan Galenik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia,Jakarta.
Aripin, S., 2007, Identifikasi Senyawa Flavonoid dari Bunga Angsret (Spathodacampanulata Beauv) dan Uji Aktivitasnya Sebagai Antioksidan, Skripsi,Universitas Brawijaya, Malang.
Awoyinka, O.A., Balogun, I.O., dan Ogunnowo, A.A.. 2007. PhytochemicalScreening and In Vitro Bioactivity Cnidoscolus aconitifolius(Euphorbiaceae). Journal of Medicinal Plants Research. 1 (3).
Brodjonegoro, T, P., Rekksowardjojo, I, K., dan Soerawidjaja, T, H., 2006, JarakPagar, Sang Primadona, Departemen Teknik Kimia, LaboratoriumTermofluida dan System Utilitas, Kelompok Riset Biodiesel ITB, Bandung.
Cheeke, R, P., 2004, Saponins : Surprising Benefits Of Desert Plants, LinusPailing Institute, USA.
Christina, 2008, Formulasi Gel Antioksidan Ekstrak Buah Buncis (Phaseolusvulgaris L) dengan Menggunakan Basis Aqupec 505 hv., UniversitasPadjajaran, Bandung.
Cowan, M., 1999, Plant Product as Antimicrobial Agent, Clinical MicrobiologyReviews, 12 (4)
Dalimartha, S., dan Wijayakusuma, H., 2006. Ramuan Tradisional untukPengobatan Hepatitis, Penebar Swadaya, Jakarta.
Daris, A., 2010, Fitokimia Mencegah Penyakit Degeneratif. IndonesianPharmacists Association, Diakses 27 Juni 2014.
56
Dianasari, N., 2009, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kayu Secang (Caesalpiniasappan L.) terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella dysentriae sertaBioautografinya, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
Dumont, 1985, Analisis Obat secara Kromatografi dan Mikroskopi, ITB,Bandung.
Dwidjoseputro, D., 2010, Dasar-Dasar Mikrobiologi, Djambatan, Jakarta.
Fajriati, I., Malawati, R., dan Muzakky, 2011, Studi Ekstraksi Padat CairMenggunakan Pelarut Logam Cr dan Cu dalam Sampel Sedimen Sungai diSekitar Calon PLTN Muria, Jurnal Ilmu Dasar, 12 (1).
Gandjar, I. G., dan Abdul, R., 2007, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
Ganiswara, G, G., 2007, Farmakologi dan Terapi. Edisi 5, Fakultas KedokteranUniversitas Indonesia, Jakarta.
Gunawan, D., dan Mulyani, S., 2004, Ilmu Obat Alam (Farmakognosi) Edisi 1,Penebar Swadaya, Jakarta.
Gunawan, I., 2011, Efek Keji Beling (Sericocalyx Crispus L) terhadap PenurunanTekanan Darah Pria Dewasa, Skripsi, Fakultas kedokteran UniversitasKristen Maranatha, Bandung.
Harborne, J, B., 2003, Metode Fitokimia : Penuntun Cara Modern MenganalisaTumbuhan. Edisi II, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
Hariyadi, 2005, Budidaya Tanaman Jarak (Jatropha curcas ) sebagai SumberBahan Alternatif Biofuel, Departemen Budidaya Pertanian, FakultasPertanian IPB, Bogor.
Hariana, A.. 2006. Tumbuhan Obat dan Khasiatnya Seri Pertama. PenerbitPenebar Swadaya : Jakarta.
Hayani, E., dan Sukmasari, M., 2005, Teknik Pemisahan Komponen EkstrakPurwoceng Secara Kromatografi Lapis Tipis, Buletin Teknik Pertanian, 10(2).
Indriani H., 2003, Stabilitas Pigmen Alami Kayu Secang (Caesalpinia sappanLinn) dalam Model Minuman Ringan, Skripsi, Institut Pertanian Bogor,Bogor.
57
Irmalia, W.R.. 2011. Daya Antibakteri Ekstrak Biji Coklat (Theobroma cacao)Varietas Farastero terhadap Streptococus mutans. Skripsi. FakultasKedokteran Gigi, Universitas Airlangga.
Jawetz, E., J, L, Melnick, dan E, A, Adelberg, 2007, Mikrobiologi untuk ProfesiKesehatan (Review of Medical Microbiology) : Diterjemahkan oleh H.Tomang, Penerbit EGC, Jakarta.
Jaya, A, M., 2010, Isolasi dan Uji Efektivitas Antibakteri Senyawa Saponin dariAkar Putri Malu (Mimosa pudica), Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas Sainsdan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Kemenkes, 2006, Pedoman Pengendalian Demam Tifoid, Kementerian KesehatanRepublik Indonesia, Jakarta.
Khunaifi, M., 2010, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong (Anrederacordifolia (Ten.) Steenis) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus danPseudomonas aeruginosa, Skripsi, Fakultas Sains dan Teknologi,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Kingsbury, J, M., 1964, Poisonous Plants of the United States and Canada.Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
Kristianingsih, 2005, Isolasi dan Identifikasi Senyawa Triterpenoid dari AkarTanaman Kedondong Laut (Polyscias fruticosa), Skripsi, UniversitasBrawijaya, Malang.
Kusnaeni, V., 2008, Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Fraksi n-Heksana dariekstrak kulit batang Angsret (Spathoda campanulata Beauv), Skripsi,Universitas Brawijaya, Malang.
Lenny, S. 2006. Senyawa Flavonoida, Fenilpropanoida dan Alkaloida, KaryaIlmiah, Departemen Kimia FMIPA Universita Sumatera Utara, Medan.
Liana, I., 2010, Aktivitas Antimikroba Fraksi dari Ekstrak Metanol DaunSenggani (Melastoma candidum D. Don) terhadap Staphylococcus aureusdan Salmonella typhimurium serta Profil Kromatografi Lapis Tipis FraksiTeraktif, Skripsi, Jurusan Biologi F-MIPA. Universitas Sebelas Maret,Surakarta.
Lutfillah, M., 2008, Karakterisasi Senyawa Alkaloid Hasil Isolasi dari KulitBatang Angsret (Spathoda campanulata Beauv) Serta Uji AktivitasnyaSebagai Antibakteri secara In Vitro, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
Madigan, M, T., Martinko, J, M., Stahl, D, A., dan Clark, D, P., 2012, Brock :Biology of Microorganism 13th Edition.
58
Madjid, B., 2003, Mikrobiologi Medik 2, Fakultas Kedokteran UniversitasHasanuddin, Makassar.
Mardjono, M., 1995, Farmakologi dan Terapi, Gaya Baru, Jakarta.
Maryani, H., 2003, Tanaman Obat untuk Mengatasi Penyakit pada Usia Lanjut,Agromedia Pustaka, Jakarta.
Noor, M. S. Poeloengan., dkk, 2007, Uji Daya Antibakteri Ekstrak Etanol KulitBatang Bungur (Largerstoremia speciosa Pers) terhadap Staphylococcusaureus dan Escherichia coli secara in vitro, Seminar Nasional TeknologiPeternakan dan Veteriner, Universitas Pancasila Jakarta.
Olson, J., 2004, Belajar Mudah Farmakologi, Cetakan 1, EGC, Penerbit BukuKedokteran, Jakarta.
Pan, X., Chen, F., Wu, T., Tang, H., dan Zhao, Z. 2009. The Acid, Bile Toleranceand Antimicrobial Property of Lactobacillus acidophilus NIT. J. FoodControl. 20
Pelczar, M J., dan Chan, E, C, S., 2005, Dasar-dasar Mikrobiologi Edisi 1, UIPress, Jakarta.
____________, 2007, Dasar-Dasar Mikrobiologi Edisi 2, UI Press, Jakarta.
Praptiwi, Puspa Dewi, dan Mindarti Harapini, Nilai Peroksida Dan Aktivitas AntiRadikal Bebas Diphenyl Picril Hydrazil Hydrate (Dpph) Ekstrak MetanolKnema laurina, Majalah farmasi indonesia, 17(1).
Pratiwi, S,T., 2008, Mikrobiologi Farmasi, Erlangga, Jakarta.
Prescott L.M., Harley, J.P., dan Klein, D.A., 2005. Microbiology, Sixth Edition.McGraw-Hill, New York.
Pudjiaji, A, H., Hegar, B., Handryastuti, S., Idris, N, S., Gandaputra, E, P., danHarmoniati, E, D., 2009, Ikatan Dokter Anak Indonesia. PedomanPelayanan Medis.
Purnobasuki, H., 2004, Potensi Mangrove sebagai Tanaman Obat. JurusanBiologi FMIPA Unair, Surabaya.
Rahmadani, S. S., 2013, Uji Daya Hambat Ekstrak Tanaman Komba – Komba(Chromolaena odorata) terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureusATCC 25923, Streptococcus sp, Salmonella typhi YCTC, dan Escherechia
59
coli ATCC 35218. Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo,Kendari.
Robinson, 2005, Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi, ITB, Bandung.
Ruslin dan Sahidin, I., 2008, Identifikasi dan Determinasi Tanaman ObatTradisional Masyarakat Sulawesi Tenggara pada Arboretum Prof. MahmudHamundu, Majalah Farmasi Indonesia. 19 (2).
Santosa, H., 2008 Ragam dan Khasiat Tanaman Obat. Agromedia Pustaka,Jakarta.
Setiabudy, R., 2009, Farmakologi dan Terapi, Balai Penerbit FKUI, Jakarta.
Sudarmadji, S., Haryono, B., dan Suhardi, 2007, Analisa Bahan Makanan danPertanian, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
Sumaryanto, A., 2009, Isolasi Karakterisasi Senyawa Alkaloid dari Kulit BatangTanaman Angsret (Spathoda campanulata Beauv) Serta Uji AktivitasBiologisnya dengan Metode Uji Brine Shrimp, Skripsi, UniversitasBrawijaya, Malang.
Sundari, D, L., Widowati, dan M, W, Winarno., 1998, Informasi Khasiat,Keamanan dan Fitokimia Tanaman Secang (Caesalpinia sappan L.). WartaTumbuhan Obat Indonesia. 4 (3).
Supriyono, 2011, Demam Tifoid, Departemen Kesehatan Republik Indonesia,Jakarta.
Susanti, M., Isnaeni, dan Poedjiarti, S., 2009, Validasi Metode Bioautografi untukDeterminasi Kloramfenikol, Jurnal Kedokteran Indonesia, 1 (1).
Tanaka, J.C.A., C.C. da Silva, A.J.B. de Oliveira, C.V. Nakamura dan B.P. DiasFilho, 2006, Antibacterial activity of indole alkaloids from Aspidospermaramiflorum, Braz J Med Biol Res, 39.
The United States Pharmacopeial Convention, 1999, The United StatesPharmacopeia. Ed. 31th, Vol. 2nd, The United States PharmacopeialConvention, Inc., Philadelphia.
Tjitrosoepomo, G., 2000, Morfologi Tumbuhan, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.
Wahyono, H., 2010, Resistensi Antibiotik, Pidato pengukuhan guru besarMikrobiologi FK UNDIP, Semarang.
60
Wahyuni, A., Hardjono dan P, H, Yamrewav., 2004, Ekstraksi Kurkumin dariKunyit, Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Kimia.
Wardhani, K, L., dan Nanik, S., 2012, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak EtilAsetat Daun Binahong (Anredera scandens (L.) Moq.) terhadap Shigellaflexneri Beserta Profil Kromatografi Lapis Tipis. Jurnal Ilmiah Kefarmasian2 (1)
Widoyono, 2011, Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, danPemberantasannya. Edisi II, Erlangga, Jakarta.
Winarti, C., dan Nurdjanah, N., 2005, Peluang Tanaman Rempah dan ObatSebagai Sumber Pangan Fungsional, Jurnal Litbang Pertanian. 24 (2).
Yodha, Agung W, M., 2012, Isolasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Kimia DariKulit Batang Mangkokan (Nothopanax Scutellarium Merr) Serta UjiAktivitasnya Terhadap Bakteri, Fungi Dan Radikal Bebas, Skripsi,Universitas Haluoleo, Kendari.
61
Lampiran 1. Penyiapan Ekstrak Tanaman
a. Pembuatan ekstrak kental
b. Pembuatan larutan ekstrak 10.000 ppm
Sampel Tanaman
- Dikumpulkan- Dibersihkan dengan air mengalir- Dikeringkan- Dipotong kecil-kecil- Diblender hingga menjadi serbuk
Serbuk tanaman
- Ditimbang 50-100 gram- Dimasukkan dalam wadah
plastik- Direndam dengan metanol
selama 3x24 jam- Dipisahkan filtrat dan residunya
Filtrat Residu
- Dikumpulkan- Dipekatkan dengan vacuum rotary
evaporatorpada suhu 56oC- Disimpan pada wadah vial
Ekstrak kental
Ekstrak kental
- Ditimbang 0,5 gram- Dimasukkan dalam labu takar 50
ml- Dilarutkan dengan metanol hingga
tanda tera- Dimasukkan dalam wadah kaca
Larutan ekstrak 10.000 ppm
62
Lampiran 2. Pembuatan Reagen
a. Pembuatan Dragendrof (alkaloid) noda coklat jingga
1. 0,6 g bismutsubnitrat dalam 2 mL HCl pekat dan 10 mL H2O.
2. 6 g KI dalam 10 mL H2O.
Kedua larutan tersebut dicampur dengan 7 mL HCl pekat dan 15
mL H2O (Harborne, 1987).
b. Pembuatan FeCl3 1%
1% = x100 %
1% = x100 %
gram = 1
Jadi, untuk membuat larutan FeCl3 1% diambil sebanyak 1 gram serbuk
FeCl3dan dilarutkan dalam labu ukur 100 ml
c. Pembuatan H2SO4 0,1 M
M1 x V1 = M2 x V2
18 x V1 = 0,1 x 50
V1 = 0,277 ml
Jadi, untuk membuat H2SO4 0,1 M dipipet 0,277 ml H2SO4 18 M dan
dilarutkan dalam labu ukur 50 ml.
d. Pembuatan reagen Lieberman-Burchard
5mlasam asetat anhidrat dan 5 mL asam sulfat konsentrate ditambahkan
secara hati-hati melalui dindingnya ke dalam 50 mL etanol dalam
keadaan dingin (Wagner, 2001).
63
Lampiran 3. Penapisan Fitokimia
a. Alkaloid
b. Flavonoid
c. Tanin
Ekstrak tanaman
- Diditotolkan pada jarak ± 1 cm daritepi bawah plat KLT
- Dielusi dengan kloroform-metanol(9:1)
- Disemprotkan pereaksi Dragendorff- Diamati perubahan yang terjadi- Positif mengandung alkaloid jika
muncul noda coklat-jingga
Hasil
- Diditotolkan pada jarak ± 1 cm daritepi bawah plat KLT
- Dielusi dengan kloroform-metanol(9:1)
- Diuapi dengan amoniak- Diamati perubahan yang terjadi- Positif mengandung flavonoid jika
menghasilkan warna kuning-kuningkehijauan
Hasil
Ekstrak tanaman
- Diditotolkan pada jarak ± 1 cm daritepi bawah plat KLT
- Dielusi dengan kloroform-metanol(9:1)
- Disemprotkan FeCl3 1%- Diamati perubahan yang terjadi- Positif mengandung tanin jika
menghasilkan warna lembayung(biru kehitaman)
Hasil
Ekstrak tanaman
64
d. Saponin
e. Triterpenoid
- Diditotolkan pada jarak ± 1 cm daritepi bawah plat KLT
- Dielusi dengan kloroform-metanol(9:1)
- DitambahkanH2SO4
- Diamati perubahan yang terjadi- Positif mengandung saponin jika
menimbulkan warna ungu-ungugelap
Hasil
Ekstrak tanaman
- Diditotolkan pada jarak ± 1 cm daritepi bawah plat KLT
- Dielusi dengan kloroform-metanol(9:1)
- Disemprotkan pereaksi Lieberman-burchard
- Diamati perubahan yang terjadi- Positif mengandung saponin jika
menimbulkan warna merah ungu(violet)
Hasil
Ekstrak tanaman
65
Lampiran 4. Pembuatan Standar Kekeruhan McFarland
Standar McFarland berada dalam bentuk skala yang bernomor dari 0,5
sampai 10, yang menjelaskan konsentrasi spesifik dari bakteri per mL.
Jumlah bakteri sesuai dengan skala Mc. Farland (Smile, 2009)Skala
McFarlandJumlah Bakteri
(x 106/mL)0,5 1501 3002 6003 9004 1.2005 1.5006 1.8007 2.1008 2.4009 2.70010 3.000
Bahan-bahan yang digunakan dalam standar Mc. Farland antara lain yaitu :
Larutan 1 : 1% Barium Klorida encer (1% b/v BaCl2)Larutan 2 : 1% Asam Sulfat encer (1% b/v H2SO4)
Komposisi bahan standar McFarlandStandar McFarland
No. 0,5 0,05 mL BaCl2 dalam 9,95 mL H2SO4
No. 1 0,1 mL BaCl2 dalam 9,9 mL H2SO4
No. 2 0,2 mL BaCl2 dalam 9,8 mL H2SO4
No. 3 0,3 mL BaCl2 dalam 9,7 mL H2SO4
No. 4 0,4 mL BaCl2 dalam 9,6 mL H2SO4
No. 5 0,5 mL BaCl2 dalam 9,5 mL H2SO4
No. 6 0,6 mL BaCl2 dalam 9,4 mL H2SO4
No. 7 0,7 mL BaCl2 dalam 9,3 mL H2SO4
No. 8 0,8 mL BaCl2 dalam 9,2 mL H2SO4
No. 9 0,9 mL BaCl2 dalam 9,1 mL H2SO4
No.10 1,0 mL BaCl2 dalam 9,0 mL H2SO4
Standar McFarland tersedia di pasaran (Smile, 2009).
66
Pembuatan Larutan Standar McFarland 0,5
- diambil 9,95 ml- diambil 0,05 ml
BaCl2 1,175 % H2SO4 1 %
- Dicampur- Dikocok dengan vortex
Larutan standar McFarland 0,5
- Diukur dengan spektrofotometer padaλ 625 nm
Absorbansi larutan standar
67
Lampiran 5. Bagan Alir Uji Aktivitas Antibakteri
a. Sterilisasi
b. Pembuatan Media
c. Pembuatan Suspensi Mikroba
Larutan NaCl Steril
- Ditambahkan kultur mikroba yang akandiujikan sedikit demi sedikit- Dikocok dengan vortex- Diukur kekeruhannya dengan
spektrofotometer pada λ 625 nm hinggaabsorbansinya sama dengan absorbansilarutan standar McFarland0,5
Suspensi mikroba
- Ditimbang sebanyak 20 gram- Dilarutkan sampai 1.000 ml dengan
akuades dalam erlenmeyer- Dipanaskan sampai mendidih- Dimasukkan dalam autoklaf pada suhu
121oC dan tekanan 15 Psi selama 15 – 20menit
Media bakteri (NA)
Nutrient Agar (NA)
- Dicuci sampai bersih- Dikeringkan- Dibungkus dengan kertas- Dimasukkan dalam autoklaf pada
suhu 121oC dan tekanan 15 Psiselama 15 – 20 menit
Alat dan Bahan Steril
Alat dan Bahan
68
d. Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Tanaman
Ekstrak kental
- Dibuat dalam konsentrasi 10.000 ppm- Diteteskan sedikit demi sedikit pada
kertas cakram steril (diameter 6 mm)hingga 20 µl
Kertas cakram yang mengandung 20 µl
ekstrak tanaman
- Diletakkan diatas kultur mikroba ujidalam cawan petri- Diinkubasi selama 18-24 jam
Kultur bakteri yang telah diinkubasi
- diukur zona bening jika ada yangterbentuk di sekitar kertas cakram
Diameter zona hambat
69
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian
Preparasi Sampel Maserasi
Evaporasi Ekstrak kental
Larutan Ekstrak 10.000 ppm
69
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian
Preparasi Sampel Maserasi
Evaporasi Ekstrak kental
Larutan Ekstrak 10.000 ppm
69
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian
Preparasi Sampel Maserasi
Evaporasi Ekstrak kental
Larutan Ekstrak 10.000 ppm