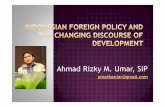politik luar negeri tiongkok terhadap upaya
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of politik luar negeri tiongkok terhadap upaya
POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP UPAYAKEMERDEKAAN TAIWAN PADA MASA PRESIDEN HU JINTAO
(2003-2013)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Putri Anastasya Wulandari
1110113000034
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2016
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul:
POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP UPAYAKEMERDEKAAN TAIWAN PADA MASA PRESIDEN HU JINTAO
(2003-2013)
1. Merupakan karya hasil saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil asli karya
saya atau merupakan hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 29 Februari 2016
Putri Anastasya Wulandari
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Mahasiswa:
Nama : Putri Anastasya WulandariNIM : 1110113000034Program Studi : Hubungan Internasional
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP UPAYAKEMERDEKAAN TAIWAN PADA MASA PRESIDEN HU JINTAO (2003-2013)
Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.
Jakarta, 29 Februari 2016
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi Pembimbing
Dr. Badrus Sholeh, MA. Teguh Santosa, MANIP. 19710211 199903 1 002
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP UPAYAKEMERDEKAAN TAIWAN PADA MASA PRESIDEN HU JINTAO
(2003-2013)
Oleh
Putri Anastasya Wulandari1110113000034
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 29Februari 2016. Skripsi ini teah diterima sebagai salah satu syarat memperolehgelar Sarjana Sosial (S.sos) pada program Studi Hubungan Internasional
Jakarta, 29 Februari 2016
Ketua, Sekretaris,
Dr. Badrus Sholeh, MA. Eva Mushoffa, MHSPS.NIP. 19710211 199903 1 002
Penguji 1 Penguji 2
M. Adian Firnas, M.Si. Febri Dirgantara H, S.E., M.M
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada 29 Februari 2016.Ketua Program Sudi
Dr. Badrus Sholeh, M.ANIP. 19710211 199903 1 002
iv
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang politik luar negeri Tiongkok terhadap upayakemerdekaan Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao periode 2003-2013. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis politik luar negeriTiongkok terhadap Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao (2003-2013), menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeriTiongkok terhadap Taiwan kemudian mengetahui bentuk kepentingan Tiongkokterhadap Taiwan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan carastudi pustaka.
Pembahasan skripsi ini menggunakan konsep kepentingan nasional yangdigunakan untuk melihat bentuk kepentingan Tiongkok dalam politik luarnegerinya terhadap Taiwan. Selain itu, skripsi ini menggunakan konsep kebijakanluar negeri untuk menggambarkan bentuk dan proses kebijakan luar negeri yangdikeluarkan oleh Tiongkok terhadap Taiwan. Penulis juga menambahkanbeberapa konsep seperti faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhipolitik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan. Berdasarkan analisa konsep dandata yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa pemerintahanPresiden Hu Jintao Tiongkok cenderung menggunakan soft power terhadapTaiwan. Tiongkok juga lebih menekankan kepada pendekatan ekonomi danmembuka perundingan bilateral bagi kedua negara tersebut.
Sejak berdirinya Tiongkok pada tahun 1949, politik luar negeri tidakterlepas dari adanya pengaruh sejarah Tiongkok itu sendiri seperti Perang Dunia,Perang Saudara hingga munculnya abad penghinaan (century of humiliation).Sejak saat itu, masalah kedaulatan dan integritas nasional menjadi fokus setiappemimpin Tiongkok dalam politik luar negeri terhadap Taiwan. Taiwanmerupakan wilayah yang terletak di Samudera Pasifik, terpisah dengan CinaDaratan oleh Selat Taiwan. Status Quo yang masih dipertahankan oleh Tiongkokterhadap Taiwan terjadi setelah Kuomintang memisahkan diri dari Tiongkokkarena mengalami kekalahan dalam Perang Sipil dan menganggap bahwa Taiwansebagai pemerintahan yang sah untuk mewakili Cina.
Kata Kunci: Politik Luar Negeri Tiongkok, Taiwan, Presiden Hu Jintao,ECFA, Anti Secession Law (ASL), Presiden Chen Shui-bian, Presiden Ma Ying-jeou.
v
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala
limpahan karunia dan rahmat yang tidak terhingga kepada penulis yang akhirnya
mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “POLITIK LUAR NEGERI
TIONGKOK TERHADAP UPAYA KEMERDEKAAN TAIWAN PADA MASA
PRESIDEN HU JINTAO (2003-2013)” dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta
salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutan terbaik
beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Penulis mendedikasikan skripsi ini sebagai sumbangsih untuk Negara
tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, almamater serta keluarga. Terima
kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Andi Inding,
satu-satunya sosok laki-laki hebat dalam keluarga sekaligus panutanku untuk
senantiasa menjadi anak yang berbakti serta dibalik sifat kerasnya tersimpan kasih
sayang untukku. Kepada ibunda Sri Herlina sosok wanita hebat dalam keluarga
yang selalu berjuang demi anaknya. Beliau merupakan panutanku untuk menjadi
seorang wanita yang sabar, tegar dan mandiri. Kepada adik tersayang Vania
Utami F yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa bagi penulis.
Kepada sanak saudara A Febi Nugraha, A Dadang Hidayat dan Ananda Nur
Fauziyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril maupun materil
bagi penulis.
Penulis sangat menyadari bahwa selama menempuh masa studi jenjang S1
hingga skripsi ini selesai tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai orang-orang
hebat yang berada di sekeliling penulis. Oleh karena itu penulis ingin
menyampaian terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berjasa
memberikan bantuan moril maupun materil selama masa studi S1 hingga skripsi
ini selesai.
Terima kasih kepada Bapak Teguh Santosa selaku dosen pembimbing
skripsi yang telah meluangkan waktu di sela kesibukannya yang sangat padat serta
banyaknya mahasiswa yang dibimbing. Terima kasih banyak atas waktu untuk
vi
memberikan arahan, motivasi, saran, bimbingan sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini.
Seluruh dosen dan staff FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima
kasih atas bantuan selama penulis berada di jenjang perkuliahan. Terima kasih
kepada jajaran dosen Program Studi Hubungan Internasional, rasa terima kasih
mungkin tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa syukur penulis atas
ilmu yang telah diberikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M.
Adian Firnas, M. Si selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan
bimbingan serta arahan selama masa studi berlangsung.
Kawan-kawan terbaik HI A 2010 yang telah menjadi bagian terpenting
selama masa kuliah yaitu Yuri, Dini, Zakiah, Aulia, Viqry, Navis, Ahmad, Bagus,
Edo, Ode, Emir, Dimas, Uda, Adriean, Adam, Banu, Dea, Nindy, Isti, Oya, Peni,
Isti, Rosa, Tisa, Hana, Meri, Clara, Anggi, Dhani, Syafiq, Nabila, Pipit, Yoga,
Uun, Retno. Khususnya kepada Diffitriana Rahmawati, Hegia Melatira, Siti
Kholillah dan Elhumairoh yang selalu menjadi sahabat terbaik baik di setiap
kehidupan perkuliahan maupun di kehidupan nyata serta bersedia meluangkan
waktu untuk bertukar fikiran di sela-sela kesibukan masing-masing.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abi Dzar Alghiffari sahabat
serta teman hidup yang selalu bersama sejak awal perkuliahan. Terima kasih telah
menjadi partner terbaik penulis di berbagai situasi baik senang maupun susah.
Terima kasih banyak atas waktunya untuk menjadi tempat penulis berkeluh kesah.
Kepada Keluarga Beke yaitu Nidaul, Nurbaiti, Irma, Lala, Naura, Intan, Qoqo,
dan Hana terima kasih atas dukungan dan motivasinya, yang selalu menjadi
penyemangat bagi penulis. Kepada KKN Semut yaitu Deti, Chika, Ridwan, Eko,
Adil, Ayu, Tia, Ennur, Khaidar, Lusi, Rofi, Rani, Muzy, dan Fathin terima kasih
atas dukungan dan motivasinya serta selalu menghibur penulis dikala lelah dalam
mengerjakan skripsi.
Kepada seluruh staff dan karyawan Kementrian Luar Negeri Republik
Indonesia, Direktorat Asia Selatan dan Tengah, PT. Chevron Pacific Indonesia,
vii
PT. Tripatra Engineering and Constructor dan Litbang Harian Kompas, terima
kasih yang sebesar-besarnya atas pengalaman dan ilmu terkait dunia kerja.
Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,
terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama proses penyelesaian skripsi
ini. Semoga Allah membalas kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan
bantuan dengan limpahan kebaikan. Pada akhirnya penulis berharap semoga
skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis pun sangat menyadari bahwa
skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu penulis sangat terbuka atas
segala kritik dan saran demi penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi untuk
kedepannya.
Jakarta, 29 Februari 2016
Putri Anastasya W.
viii
DAFTAR ISI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME............................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI........................................................... ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI........................................................ iii
ABSTRAK ............................................................................................................. iv
KATA PENGANTAR ............................................................................................ v
DAFTAR ISI........................................................................................................ viii
DAFTAR TABEL................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x
DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah................................................................................ 1
B. Pertanyaan Penelitian ............................................................................. 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..................................................................... 9
D. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 10
E. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 14
1. Politik Luar Negeri............................................................................. 14
2. Kebijakan Luar Negeri ....................................................................... 17
3. Kepentingan Nasional ........................................................................ 19
F. Metode Penelitian ................................................................................. 22
G. Sistematika Penulisan........................................................................... 23
BAB II DINAMIKA HUBUNGAN TIONGKOK DAN TAIWAN SEBELUMMASA PEMERINTAHAN PRESIDEN HU JINTAO (1946-2002)
A. Sejarah Hubungan Tiongkok dan Taiwan pada Tahun 1946-2002 ....... 25
1. Perang Sipil antara Partai Nasionalis (KMT) dan Partai KomunisTiongkok (PKT) pada tahun 1946-1949.............................................25
B. Politik Luar Negeri Tiongkok terhadap Taiwan sebelum MasaPemerintahan Presiden Hu Jintao pada Tahun 1949-2002 ...................... 27
1. Politik Luar Negerti Tiongkok Terhadap Taiwan pada Masa PresidenMao Zedong (1949-1976)...................................................................30
2. Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Taiwan Pada Masa PresidenDeng Xiaoping (1978-1997) .................................................................... 34
ix
3. Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Taiwan Pada Masa PresidenJiang Zemin (1995-2002) ......................................................................... 39
BAB III ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLITIKLUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP TAIWAN PADA MASAPRESIDEN HU JINTAO (2003-2013)
A. Faktor Internal ...................................................................................... 46
1. Perubahan Sistem Politik Domestik Tiongkok ...................................... 46
2. Kepentingan Ekonomi Tiongkok terhadap Taiwan .............................. 51
3. Faktor Ideosinkretik ........................................................................... 58
B. Faktor Eksternal.................................................................................... 65
1. Munculnya dukungan Amerika Serikat Terhadap Taiwan................... 65
2. Keanggotaan Taiwan dalam World Trade Organization (WTO) .....70
BAB IV POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP UPAYAKEMERDEKAAN TAIWAN PADA MASA PRESIDEN HU JINTAO(2003-2013)
A. Kebijakan Tiongkok Terhadap Upaya Kemerdekaan Taiwan Pada MasaPresiden Hu Jintao (2003-2013).................................................................. 75
1. Anti-Secession Law (Undang-Undang Anti Pemisahan) ...................... 77
2. Enam Proposal Hu Jintao Terhadap Taiwan .......................................... 81
3. Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) ..................... 85
B. Respon Taiwan Terhadap Kebijakan Tiongkok Pada Masa Presiden HuJintao (2003-2013) ........................................................................................ 92
1. Kebijakan Taiwan Terhadap Tiongkok Pada Masa Presiden ChenShui-Bian (2000-2008) ............................................................................. 93
2. Kebijakan Taiwan Terhadap Tiongkok Pada Masa Presiden Ma Ying-Jeou (2008-2012)....................................................................................... 98
BAB V PENUTUP
Kesimpulan.......................................................................................... 102
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 106
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Kondisi Untung dan Rugi yang dimiliki oleh Tiongkok dan Taiwandalam Perekonomian............................................................................... 53
Tabel 2. Rangkuman Bab, Pasal, dan Lampiran yang tercantum dalam EconomicCooperation Framework Agreement (ECFA) ........................................ 88
Tabel 3. Data Statistik Perdagangan Antara Taiwan dan Tiongkok dari Tahun2003-2013 ............................................................................................... 90
Tabel 4. Rangkuman Kebijakan Taiwan Terhadap Tiongkok pada masa PresidenChen Shui-bian (2000-2008)................................................................... 97
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Peta Taiwan .......................................................................................... 3
xi
DAFTAR SINGKATAN
ADB Asian Development Bank
ARATS Association for Relations Across the Taiwan Straits
CC Central Committee
CEPA Closer Economic Partnership Arrangement
CMC Central Military Commission
CPC Communist Party of China
CSIS Central Strategic and International Studies
CYL Communist Youth League of China
DPP Democratic Progressive Party
ECFA Economic Cooperation Framework Agreement
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
HKI Hak Kekayan Intelektual
ICAO International Civil Aviation Organization
KMT Kuomintang
MFN Most Favoured Nation
NPC National People’s Congress
NP New Party
OCTS One Country Two System
PBB Persatuan Bangsa-Bangsa
PFP People First Party
PKT Partai Komunis Tiongkok
PLA People Liberations Army
RRT Republik Rakyat Tiongkok
SEF Straits Exchange Foundation
TAIP Taiwanese Independence Party
TETO The Taipei Economic and Trade Office
xii
TPR Tentara Pembebasan Rakyat
TRA Taiwan Relations Act
TSU Taiwan Solidarity Union
UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WHO World Health Organization
WTO World Trade Organization
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Politik luar negeri merupakan “action theory” dimana
kebijaksanaan suatu negara ditujukan kepada negara lain untuk mencapai
suatu kepentingan tertentu. Menurut Plano, kepentingan nasional tersebut
dapat dijangkau melalui kebijakan luar negeri.1 Singkatnya politik luar
negeri memiliki hubungan antara kontrol dan kekuasaan wilayah suatu
negara kepada negara lain yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan luar
negeri untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.
Konsep politik luar negeri tersebut didukung dengan adanya
berbagai penelitian yang melihat politik luar negeri Tiongkok dari
berbagai karakteristik yaitu pertama, melindungi kedaulatan dan integritas
teritorial. Kedua, mempromosikan pembangunan dan modernisasi
ekonomi sebagai wujud pencapaian kekuatan nasional yang komprehensif.
Ketiga, mendapatkan rasa hormat di dunia internasional serta
memaksimalkan atau setidaknya mengkonsolidasikan status Tiongkok
sebagai negara yang berkekuatan besar.2
Politik luar negeri yang yang ditujukan untuk mencapai
kepentingan nasional memiliki kategori sesuai dengan tingkatannya
1 Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin. Hal. 6.2 Chai Winberg (ed). 1999. Relations Between the Chinese Mainland and Taiwan. Asian Affairs
26, 2. Hal. 59.
2
masing-masing yaitu core/basic/vital interest; kepentingan yang sangat
tinggi nilainya sehingga negara bersedia untuk berperang dalam
mencapainya. Termasuk melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga
dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut oleh negara tersebut.3
Salah satu tujuan politik luar negeri Tiongkok adalah wilayah dan
kedaulatan. Sejak tahun 1980-an, dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping,
Tiongkok telah memiliki tujuan politik luar negeri yang masih
dipertahankan hingga saat ini yaitu pertama, untuk mempertahankan
kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Tiongkok. Kedua, untuk
menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk reformasi,
keterbukaan dan modernisasi bagi Tiongkok.4
Dalam hubungannya, hingga saat ini Tiongkok dan Taiwan masih
mempertahankan status quo. Hal ini terjadi setelah Taiwan memisahkan
diri dari daratan Tiongkok sejak tahun 1949 setelah mengalami kekalahan
dalam Perang Sipil dan menduduki sebuah pulau yaitu Formosa yang saat
ini disebut Taiwan.5 Partai Nasionalis atau disebut juga Kuomintang
(KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek menganggap sebagai
pemerintahan yang sah atas Tiongkok.
3 James N. Rosenau. 1969. International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research andTheory. New York: The Free Press. Hal. 167.
4 Center for Strategic and International Studies (CSIS). Chinese Foreign Policy: What Are theMain Tenets of China’s Foreign Policy. Diakses dari (www.csis.org/CHINABALANCESHEET) pada Senin, 20 Oktober 2014.
5 Michael Roberge dan Youkyoung Lee. 2009. China-Taiwan Relations. Diakses darihttp://www.cfr.org/china/china-taiwan-relations/p9223 pada Rabu, 15 Oktober 2014.
3
Gambar 1. Peta Taiwan6
Alasan bagi Taiwan melawan pengaruh Tiongkok adalah tidak
disetujuinya status legal dari pemerintahan di Taiwan . Hal ini dikarenakan
Tiongkok menganggap bahwa isu Taiwan sebagai suatu gerakan separatis
yang menuntut kedaulatan dan akan memicu gerakan separatis di wilayah
lain yang berada disekitar Tiongkok seperti Hongkong, Macau dan Tibet.
Isu Taiwan mempengaruhi politik luar negeri Tiongkok pada
empat level yaitu pertama di tingkat domestik menyangkut legitimasi
suatu negara pada pemerintahan di Tiongkok. Kedua, di tingkat lintas selat
isu Taiwan menyangkut sengketa sejarah atas reunifikasi yang ingin
dilakukan oleh Tiongkok. Ketiga, pada tingkat regional isu Taiwan
mempengaruhi politik kekuasaan di antara kekuatan besar seperti
6 Executive Yuan, Republic of China (Taiwan). The Republic of China Year Book. 2013. Diaksesdari http://www.ey.gov.tw/Upload/UserFiles/YB%202013%20all%20100dpi.pdf Pada Jumat, 8Januari 2016.
4
Tiongkok dan Amerika Serikat. Keempat, tingkat internasional
menyangkut ancaman diplomasi yang dilakukan untuk mengupayakan
status Taiwan di organisasi-organisasi internasional.7
Secara hukum internasional, Taiwan tidak dianggap sebagai
negara yang berdaulat oleh sebagian besar negara atau organisasi
internasional termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan saat ini
Taiwan hanya memiliki hubungan diplomatik dengan 22 negara seperti
Kiribati, Nauru, Kepulauan Solomon, Republik Kepulauan Marshall,
Republik Palau, Tuvalu, Burkina Faso, Swaziland, Republik Demokratik
Sao Tome and Principe, Takhta Suci Vatikan, Belize, El Salvador, Haiti,
Nicaragua, Paraguay St. Lucia, Republik Dominika, Republik Guatemala,
Republik Honduras, Republik Panama, Saint Vincent dan Grenadines,
Saint Christopher (Saint Kitts) dan Nevis.8
Diluar hubungan diplomatik dengan 22 negara tersebut, Taiwan
pun hanya diberi kesempatan membuka kantor perwakilan di beberapa
negara. Hal ini ditandai dengan adanya kerjasama dalam bidang
perdagangan, investasi, budaya dan kerjasama non-politik. Taiwan
memiliki lebih dari 100 kantor perwakilan di lebih dari 70 negara,
termasuk kantor perwakilan di Indonesia yang diberi nama “The Taipei
Economic and Trade Office” (TETO). Kantor ekonomi dan perdagangan
Taipei tersebut merupakan perwakilan dari pemerintah Republik Cina
7 Xu Xin. “The Dynamics of the Taiwan Question in Chinese Foreign Policy: Dialectics of National Identityand International Constraint”. Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies Vol.7. Hal. 1.
8 Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan). Diplomatic Allies. Diakses darihttp://www.mofa.gov.tw/en/AlliesIndex.aspx?n=DF6F8F246049F8D6&sms=A76B7230ADF29736 pada Selasa, 5 Mei 2015.
5
(Taiwan) di Indonesia. TETO memiliki misi untuk mengurus kepentingan
Taiwan dan mempromosikan hubungan bilateral antara Taiwan dan
Indonesia.9
Bagi Tiongkok, pentingnya penyatuan wilayah Taiwan adalah
untuk mengatasi penghinaan yang terjadi dalam sejarah Tiongkok dan
mempertahankan rasa hormat maupun posisi yang telah diraih Tiongkok.10
Kembalinya Hongkong ke dalam wilayah Tiongkok merupakan
kesuksesan pemerintahan Tiongkok dalam penyatuan wilayah dan
kedaulatan di Tiongkok. Namun, keberhasilan Tiongkok sebelumnya
dalam mengembalikan wilayah Hongkong tidak lengkap sampai
Taiwan berada di bawah kekuasan pemerintahan Tiongkok pula.
Proses unifikasi tersebut terhambat oleh munculnya kelompok-
kelompok oposisi di Taiwan seperti Partai Progresif Demokrat (DPP),
sistem politik Taiwan dan bangkitnya dua kekuatan seimbang antara dua
partai di Taiwan yaitu DPP dan KMT. Mempengaruhi perubahan cara
pandang kebijakan Tiongkok bergantung pada partai apa yang
memenangkan pemilu di Taiwan. Kuomintang (KMT) merupakan partai
yang berevolusi dari partai nasionalis berbasis pemerintahan militer. Basis
dukungan KMT adalah di bagian utara Taiwan dekat dengan ibukota baru
9 The Taipei Economic and Trade Office (TETO). Diakses dari http://www.roc-taiwan.org/id/mp.asp?mp=292 pada Rabu, 29 April 2015.
10 Jia Qingguo. 2005. “Disrespect and Distrust: the external origins of contemporary ChineseNationalism”. Journal of Contemporary China 14, no. 42. Hal. 20.
6
mereka yaitu Taipei.11 KMT merupakan partai yang mendukung
reunifikasi dengan Tiongkok.
Gerakan pro-demokrasi pada tahun 1970-an dan 1980-an
memunculkan Partai Progresif Demokrat (DPP). DPP berkuasa sekitar
tahun 2000-2008 di bawah Presiden Chen Sui Bian. Agenda dari DPP
mendukung kemerdekaan Taiwan secara de jure sehingga meningkatkan
ketegangan dengan Tiongkok.12 Ketegangan tersebut berlanjut selama
Taiwan berupaya untuk meraih statusnya sebagai negara yang merdeka
serta menjadi anggota organisasi internasional khususnya PBB.13
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat
diketahui bahwa politik luar negeri suatu negara ditujukan untuk mencapai
kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun
kepentingan nasional suatu bangsa ditentukan oleh siapa yang berkuasa
pada waktu itu.14 Hal ini sejalan dengan dinamika hubungan Tiongkok dan
Taiwan tidak terlepas dari peran pemerintahan yang menguasai Tiongkok-
Taiwan pada waktu itu. Tiongok merupakan negara sebagai aktor yang
melakukan politik luar negeri, meskipun aktor-aktor lain dalam
pemerintahan seperti partai berperan penting dalam membuat keputusan
dari kebijakan luar negeri Tiongkok.
11 Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Political Development. Diakses darihttp://dfat.gov.au/geo/taiwan/pages/taiwan-country-brief.aspx pada Sabtu, 30 Mei 2015.
12 Ibid.13 Awani Irewati. 2015. Pemilu Taiwan, Kemenangan Partai Kuomintang. Diakses dari
http://www.p2p-lipi.go.id/menu/columns.aspx?id=40&lang=en pada Rabu 11 Februari 2015.14 Mochtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta:
LP3ES. Hal. 184.
7
Pemimpin suatu negara memiliki peran penting dalam perumusan
kebijakan luar negeri. Terdapat batasan yang tidak jelas antara politik
domestik dan internasional, hal ini semakin didukung dengan adanya
globalisasi. Seringkali isu yang berada pada level domestik dapat dengan
mudah mempengaruhi ke lingkungan internasional. Korelasi antara level
domestik dan internasional memberikan kesempatan bagi pemimpin suatu
negara untuk mendukung agenda mereka.15 Kepemimpinan mampu
menegaskan kapabilitas dari individu untuk menggerakan, memobilisasi,
dan menginspirasi negara atau rakyatnya untuk mencapai kepentingan
nasional beserta tujuan negara tersebut
Tahun 2003 merupakan masa pemerintahan Presiden Hu Jintao.16
Ketika para pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) bertemu pada
bulan November 2002, nama Hu Jintao disinggung akan menjadi calon
pengganti Jiang Zemin. Sejak kepemimpinanya, Presiden Hu telah
menorehkan banyak kesuksesan di bandingkan pendahulunya yaitu
Presiden Jiang Zemin. Menurut Chien-min dan Chang, Hu Jintao telah
mengubah kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan secara radikal. Hu Jintao
merupakan pemimpin Tiongkok yang paling pragmatis dalam menangani
masalah Taiwan.17
15 Andrea Grove. 2007. Political Leadership in Foreign Policy, Manipulating Support AcrossBorder. Palgrave Macmillan. Hal. 1.
16 Arthur S. Ding. 2013. The Hu Jintao Decade in China’s Foreign and Security Policy (2002–12):Assessments and Implications. SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Hal. 1.
17 Mathieu Duchâtel dan François Godement. 2009. China’s Politics under Hu Jintao . Journal ofCurrent Chinese Affairs 3: German Institute of Global and Area Studies (GIGA).
8
Jiang Zemin dianggap gagal dalam mewujudkan tujuan nasional
Tiongkok untuk mengembalikan Taiwan ke dalam wilayah Tiongkok.
Tindakan keras Jiang Zemin dalam menyelesaikan permasalahan Taiwan
mulai mendatangkan protes untuk menuntut kemerdekaan yang lebih besar
kepada pemerintahan Tiongkok. Terjadinya krisis di Selat Taiwan pada
tahun 1995-1996 dan sulitnya memperbaiki hubungan diplomatik dengan
Amerika Serikat terkait krisis di Selat Taiwan tersebut sehingga pada masa
pemerintahan Jiang Zemin upaya reunifikasi cenderung terhambat dan
akan meningkatkan resiko angkatan bersenjata untuk menyerang Taiwan.18
Hu Jintao yang merupakan Presiden Tiongkok setelah Jiang Zemin
cenderung menggunakan soft power terhadap Taiwan. Kebijakan Taiwan
lebih menekankan kepada pendekatan ekonomi, agar dapat memberikan
keuntungan langsung bagi penduduk Taiwan. Tiongkok juga lebih terbuka
dan terlibat langsung dalam perundingan bilateral dengan pejabat Taiwan.
Pendekatan ini dianggap sebagai permulaan Tiongkok sebelum melakukan
reunifikasi dengan Taiwan.
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan politik luar negeri suatu negara yaitu Tiongkok dengan
Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao. Sebagai negara,
Tiongkok untuk memenuhi kepentingan nasionalnya melakukan berbagai
interaksi dengan negara lain termasuk kerjasama maupun konflik. Politik
luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan mengalami perubahan pada masa
18 Ibid.
9
Presiden Hu Jintao (2003-2013), Tiongkok memasuki dinamika hubungan
yang bersifat kooperatif dengan Taiwan setelah melalui proses konflik
yang cukup panjang. Kondisi stabil yang cenderung diharapkan dari dua
negara ini berkaitan erat dengan stabilitas hubungan antar selat.
B. Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini akan berfokus untuk menjawab pertanyaan mengenai “
Bagaimana Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Upaya Kemerdekaan
Taiwan pada Masa Pemerintahan Presiden Hu Jintao (2003-2013)?”
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menganalisis proses politik luar negeri Tiongok terhadap Upaya
Kemerdekaan Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao
(2003-2013).
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri
Tiongkok terhadap upaya kemerdekaan Taiwan pada masa
pemerintahan Presiden Hu Jintao (2003-2013).
3. Mengetahui kepentingan Tiongkok terhadap pencegahan
kemerdekaan Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao.
Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :
1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap
perkembangan ilmu-ilmu sosial dan politik. Khususnya Ilmu
Hubungan Internasional, Studi Kawasan Asia Timur dan Kajian
10
Strategis dari suatu formulasi politik luar negeri dan proses
perumusan kebijakan luar negeri.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-
penelitian sejenis agar dapat dikembangkan ke tahap selanjutnya.
Dapat pula dijadikan sebagai bahan literatur bagi para akademisi
yang memiliki ketertarikan terhadap isu politik luar negeri
Tiongkok dan Taiwan.
3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini berguna mengaplikasikan
konsep dari suatu kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pembuat
keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit yang
ada dalam politik internasional serta pengendaliannya untuk
mencapai tujuan nasional yang spesifik, seperti tujuan nasional
yang ingin dicapai oleh Tiongkok.
D. Tinjauan Pustaka
Terdapat beberapa penelitian terkait dengan “Politik Luar Negeri
Tiongkok Terhadap Upaya Kemerdekaan Taiwan Pada Masa
Pemerintahan Presiden Hu Jintao (2003-2013)” yang sebelumnya pernah
dilakukan. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Azmi Muharom pada tahun
2014 untuk memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Azmi Muharom dalam skripsinya menganalisis kebijakan luar
negeri Tiongkok terhadap Taiwan dalam negosiasi Economic Cooperation
Framework Agreement (ECFA) tahun 2010. Tulisan ini berfokus kepada
kerjasama ekonomi yang digunakan Tiongkok sebagai soft power terhadap
11
Taiwan. Azmi menemukan bahwa negosiasi pada bidang ekonomi antara
Tiongkok dengan Taiwan ini menggunakan prinsip integrative strategy
yaitu tindakan yang menciptakan keuntungan bersama melalui negosiasi
dengan orang lain yang tujuannya tidak bertentangan. Dengan konflik
politik yang telah berlangsung antara Tiongkok dan Taiwan selama lebih
dari enam dekade, langkah negosiasi ini mensyaratkan Tiongkok bersedia
menurunkan tarif bagi 539 produk impor dari Taiwan, sementara Taiwan
hanya bersedia menurunkan tarif bagi 267 produk impor Tiongkok.
Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah
kepentingan nasional, framework mengenai kebijakan luar negeri dari
Holsti dan Rosenau serta framework diplomasi ekonomi. Dari hasil analisa
dengan menggunakan ketiga teori tesebut Azmi menyimpulkan bahwa
Tiongkok menyetujui negosiasi ECFA didasari faktor internal dan
eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi negosiasi ECFA
antara Tiongkok dan Taiwan adalah peran kepemimpinan politik dan
militer Tiongkok yang mengalami perubahan diikuti dengan perubahan
kepentingan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi
adalah kebijakan Taiwan terhadap Tiongkok yang berubah setelah
pemilihan presiden Taiwan pada tahun 2008 dan partisipasi Tiongkok
dalam World Trade Organization (WTO).
Analisis data dilakukan melalui analisis data primer dan sekunder
dari pertanyaan-pertanyaan resmi pemerintah Tiongkok dan Taiwan,
press release dan beberapa dokumen lainnya serta melakukan wawancara
12
mendalam terhadap narasumber yang kompeten di bidangnya. Data
sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa pencarian data
melalui informasi berupa buku rujukan, jurnal, skripsi, hasil penelitian dan
penerbitan-penerbitan lainnya yang berkaitan dengan tema yang diusung
oleh penulis.
Secara umum, skripsi Azmi memiliki persamaan pembahasan
dengan skripsi ini yaitu terkait dengan isu politik luar negeri Tiongkok
terhadap Taiwan pada tahun 2010 dimana tahun tersebut masih berada di
bawah kepemimpinan Presiden Hu Jintao. Namun disamping itu, terdapat
perbedaan antara skripsi Azmi dengan penelitian ini yang terletak pada
fokus pembahasan. Azmi lebih fokus terhadap soft diplomacy Tiongkok
terhadap Taiwan melalui sudut pandang ekonomi pada tahun tertentu.
Sedangkan penulis membahas politik negeri Tiongkok terhadap Taiwan
yang berfokus pada masa pemerintahan tertentu yaitu Presiden Hu Jintao.
Kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Xulio Rios pada tahun 2012
yang berjudul “The Development of the Relations between Mainland
China and Taiwan during Hu Jintao’s Term of Office: From the Anti-
Secession Law to the Enforcement of the ECFA”. Rios dalam
penelitiannya membuat analisis mendalam mengenai perkembangan
hubungan Tiongkok-Taiwan selama masa pemerintahan Presiden Hu
Jintao sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan
Presiden Tiongkok. Hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan
merupakan tema yang umum bagi stabilitas di Asia-Pasifik dan merupakan
13
salah satu tantangan besar bagi stabilitas keamanan di kawasan tersebut.
Kebangkitan Tiongkok dan kembalinya fokus Amerika Serikat terhadap
kawasan ini menunjukan pola yang berbeda dari integrasi, kerjasama atau
konflik yang dapat terjadi di masa mendatang.
Rios menganalisis selama dua periode masa pemerintahan Presiden
Hu banyak terjadi perubahan dalam hubungan bilateral antara Beijing dan
Taipei. Perubahan ini merupakan langkah yang diambil oleh Tiongkok
sebagai cara utama untuk menyelesaikan modernisasi dan penyatuan
kembali Cina daratan dengan Taiwan. Rios juga menggambarkan secara
rinci fase utama dan perkembangan dari setiap proses perbaikan hubungan
antara Tiongkok dan Taiwan. Hal ini juga memperhitungkan peran aktor
eksternal yang paling determinan dan menggambarkan dengan contoh
dari dua hal yang menjadi kecenderungan utama dalam pengembangan
hubungan bilateral seperti Anti-Secession Law dan ECFA.
Rios melihat hal utama yang menjadi masalah antara Tiongkok dan
Taiwan adalah pertama, pencapaian reunifikasi adalah suatu hal yang
mutlak bagi Tiongkok. Tiongkok dapat mengubah hal ini tergantung pada
keadaan. Kedua, bagi Taiwan penegasan sebagai negara de facto yang
berarti konstruksi permanen identitas baru dan penegasan kedaulatan
negara. Hal ini memungkinkan Taiwan dipahami dalam konteks propinsi-
negara yang dapat melemahkan Tiongkok untuk menuntut status Taiwan
sebagai negara secara hukum. Ketiga, meningkatnya saling
14
ketergantungan ekonomi antar selat dengan perkembangan yang sangat
potensial merupakan dasar penyatuan kedua negara ini.
Rios lebih memfokuskan analisisnya dengan menggunakan empat
dimensi yang berbeda untuk melihat sejauh mana perkembangan
Tiongkok-Taiwan yaitu pertama ekonomi dan perdagangan. Kedua,
pengakuan di dalam dunia internasional. Ketiga, turis dan kebudayaan.
Keempat, keamanan. Terkait dengan hubungan Tiongkok dan Taiwan,
Rios juga menganalisa peran dari negara Jepang dan Amerika Serikat
sebagai pendukung penting dari perkembangan konflik Tiongkok dan
Taiwan. Taiwan mengandalkan kedua negara ini untuk mempertahankan
kedaulatannya. Sedangkan penelitian ini hanya membahas dua hal yang
dapat dijadikan acuan untuk melihat perkembangan hubungan Tiongkok
dan Taiwan yaitu ECFA dan Anti-Secession Law. Penelitian ini berfokus
pada kedua negara yaitu Tiongkok dan Taiwan serta adanya keterlibatan
dari negara yang berada di luar kawasan seperti Amerika Serikat.
E. Kerangka Pemikiran
1. Politik Luar Negeri
Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, secara
garis besar penelitian ini berpusat pada analisis politik luar negeri suatu
negara pada masa pemerintahan tertentu. Adanya interaksi antar negara
merupakan suatu bentuk usaha dari negara untuk memenuhi kepentingan
nasionalnya.
15
Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan suatu
negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Juga merupakan bagian
dari kebijaksanaan nasional, semata-mata dimaksudkan mengabdi pada
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk kurun waktu
yang telah dihadapi, lazimnya disebutkan sebagai kepentingan nasional”.19
Dalam buku yang ditulis Miriam Budiarjo, terdapat definisi politik
luar negeri sebagai “Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan yang
diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan,
kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya”.20
Berarti bahwa politik luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya.
Dalam hal ini, terdapat Teori Pengambilan Keputusan menurut
Graham Allison dan Morton Harperin yang mengarahkan perhatian
teorinya secara langsung bukan hanya kepada negara atau kalangan
eksekutif dalam negara tetapi juga pada perilaku manusia khususnya
pembuat keputusan yang sesungguhnya membuat kebijakan pemerintah
yaitu mereka yang tindakannya otoritatifnya baik maksud dan tujuannya
adalah tindakan negara.21 Tindakan negara yang dimaksudkan adalah
tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara.
Dalam Teori Pembuatan Keputusan, politik luar negeri dapat
dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yaitu kondisi dalam
19 Sumpena Prawirasaputra.1984. Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Bandung: RemajaKarya. Hal. 7
20 Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Hal 1221 Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe. 1981. Introduction to International Relation:
Power and Justice. Prentice. Hal. 128.
16
negeri suatu negara, kemampuan ekonomi dan militer, konteks
internasional, yaitu posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya
dengan negara lain dalam sistem internasional.22
Politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari
lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi
politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat
keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi
yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu
pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan
eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin
dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.23
Sumber-sumber dalam politik luar negeri berkaitan erat dengan
pola interaksi diantara aktor-aktor dalam politik luar negeri tersebut.
Sebagai contoh pola hubungan antara Tiongkok dan Taiwan. Dalam
membahas pola hubungan kedua negara tersebut, dapat menggunakan
Konsep Situasi sebagai suatu alat analisis (analytical tool) yang dapat
memberikan alat untuk menentukan lingkungan eksternal yang relevan
bagi para pembuat keputusan (decison makers).24
22 Anna Yulia Hartati. 2004. Diplomasi Indonesia Pasca Perang Dingin. Jurnal Spektrum Vol. 1No. 1. Hal 41.
23 James N. Rosenau. 1980. The scientific Study of Foreign Policy. New York: The Free Press.Hal. 171-173.
24 Howard Lentner. 1974. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach.Ohio: Bill and Howell Co. Hal. 105-171.
17
2. Kebijakan Luar Negeri
Sejauh ini, untuk memahami suatu kebijakan luar negeri
difokuskan kepada pemimpin dan pengambilan keputusan itu sendiri, akan
tetapi kebijakan luar negeri lebih melibatkan beberapa hal penting.
Kebijakan luar negeri adalah keinginan untuk memahami tindakan dan
perilaku negara terhadap negara-negara lain dan lingkungan internasional
pada umumnya.
Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai totalitas suatu negara
terhadap dan interaksi dengan lingkungan di luar perbatasannya.25 Definisi
mencakup berbagai wilayah masalah, yang didefinisikan sebagai satu
kekhawatiran yang saling terkait dalam pembuatan kebijakan luar negeri.
Secara tradisional, kebijakan luar negeri telah difokuskan untuk upaya
mempertahankan dan meningkatkan kekuatan dan keamanan suatu negara.
Proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup: Pertama,
menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan
dan sasaran yang spesifik. Kedua, menetapkan faktor situasional di
lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan
kebijakan luar negeri. Ketiga, menganalisis kapabilitas nasional untuk
menjangkau hasil yang dikehendaki. Keempat, mengembangkan
perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam
menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kelima, melaksanakan tindakan yang diperlukan. Keenam
25 Marijke Breuning. 2007.”Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction”. New York:Palgrave MacMillan. Hal. 5.
18
secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang
telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.26
Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi
semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya
dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau
akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan-
tindakan tersebut.27 Menurut Coloumbis dan Wolfe yang mengacu pada
James N. Rosenau menyatakan bahwa terdapat lima kategori variabel
yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri yaitu: variabel
ideosinkretik, birokratik, nasional dan sistemik.28
Variabel ideosinkretik, variabel ini berfokus pada persepsi, citra
dan karakteristik pribadi dari para pembuat keputusan. Meskpiun variabel
ini sulit untuk diukur seberapa besar pengaruhnya terhadap kebijakan luar
negeri suatu negara tetapi keberadaan variabel ini dirasakan lebih besar
pengaruhnya kepada keputusan penting yang akan diambil oleh negara
tersebut. Selain itu variabel ini memiliki pengaruh yang kuat pada negara
dengan sistem pemerintahan totaliter dan otoriter dibandingkan negara
dengan sistem pemerintahan demokrasi. Kuatnya pengaruh tersebut
dikarenakan kurangnya partisipasi dan pengawasan publik terhadap
pemerintahan.
26 Op. Cit. Plano dan Olton. Hal. 5.27 K.J. Holsti. 1992. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Bandung: Bina Cipta. Hal 21.28 Theodore Columbis dan James H.Wolfe. 1990. Introduction to International Relation: Power
and Justice.New Jersey: Prentice Hall. Hal. 117-126.
19
Variabel birokratik, variabel ini berfokus pada struktur dan proses
pemerintahan serta sejauh mana dampaknya terhadap proses pembuatan
kebijakan luar negeri. Variabel ini lebih dirasakan pada negara demokrasi
karena memiliki sistem birokrasi yang besar dan kompleks.
Variabel nasional, variabel ini meliputi atribut-atribut nasional
yang akan mempengaruhi output dari kebijakan luar negeri. Seperti,
lingkungan (luas territorial, kondisi geografis, tipe daerah, iklim dan
sumber daya alam), populasi (jumlah penduduk, tingkat kepadatan
penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan), ekonomi (pertumbuhan
ekonomi, produktivitas industri dan pertanian beserta GNP), politik
(sistem politik), sosial (struktur kelas, distribusi pendapatan, budaya,
agama, tingkat homogenitas atau heteregonitas).
Variabel sistemik, merupakan variabel eksternal yang
mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara, antara lain
seperti struktur dan proses dari sistem internasional, hukum internasional,
organisasi internasional, organisasi internasional. Variabel ini juga
berkaitan erat dengan aksi atau tindakan dan kebijakan-kebijakan dari
negara lain, khususnya negara yang memiliki pengaruh besar dalam sistem
internasional, pada akhirnya dapat mempengaruhi dan merangsang
kebijakan luar negeri suatu negara.
3. Kepentingan Nasional
Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan
perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional dapat dijelaskan
20
sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang akan
mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam
merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara
secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara
yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan
ekonomi.29
Teori kepentingan nasional, menurut Daniel S. Papp mencakup
beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan
militer, moralitas dan legalitas .30 Meskipun masih terdapat beberapa
perbedaan pandangan, konsep ini cukup memberi gambaran umum
mengenai hal-hal yang termasuk dalam national interest.
National interest atau kepentingan nasional merupakan istilah yang
wajib dikaji dalam fenomena-fenomena hubungan internasional oleh
kalangan penstudi hubungan internasional secara luas. Kepentingan
nasional digunakan untuk menggambarkan dan mendukung kebijakan-
kebijakan tertentu.31 Kepentingan nasional ini sering disebut sebagai
konsepsi umum yang merupakan unsur vital bagi negara karena tujuan
mendasar serta faktor yang paling menentukan bagi para pembuat
keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah inti dari
29 Op. Cit. Plano dan Olton, Hal.11.30 Daniel S. Papp. 1988. Contemporary International Relation: A Framework for Understanding.
New York: MacMillan Publishing Company. Hal. 2931 Griffiths Martin, dan Terry O’Callaghan. 2002. International Relations: The Key Concepts. New
York : Routledge. Hal. 203.
21
kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat juga diartikan sebagai
kepentingan negara untuk melindungi teritorial dan kedaulatan negaranya.
Kepentingan nasional sebagai kebutuhan materi dan kebutuhan
spriritual dalam suatu negara bangsa. Secara materi, bangsa membutuhkan
keamanan dan pembangunan. Secara sprititual, suatu negara bangsa
memerlukan kehormatan dan pengakuan dari masyarakat internasional.32
Dalam studi kasus Tiongkok, definisi “kepentingan nasional”
menjadi lebih bermasalah karena terjadi tumpang tindih antara aparatur
negara Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Yan Xuetong
dalam analisisnya membedakan antara kepentingan negara (dalam ranah
domestik) dan kepentingan nasional. Menurut Yan, kepentingan negara
sering bertentangan dengan kelompok-kelompok lain dari kelas penguasa.
Negara dalam konteks domestik adalah alat dari kelas penguasa dan
mewakili kepentingan elit penguasa dalam menghadapi konflik dengan
kelompok lain.
Terdapat tiga karakteristik kepentingan nasional yang telah
diidentifikasi oleh ilmuwan di Tiongkok. Pertama, kepentingan nasional
dipandang sebagi sesuatu yang dibentuk oleh faktor budaya nasional,
pengalaman sejarah dan identitas nasional. Kedua, kepentingan nasional
dipandang sebagai prinsip-prinsip yang relatif stabil dalam memandu
kebijakan Tiongkok secara jangka panjang. Ketiga, meskipun kepentingan
nasional mewakili kepentingan dan aspirasi bangsa secara kolektif, hal ini
32 Yan Xuetong. 1993. Zhongguo guojia liyi fenxi (Analysis of China’s National Interests).Tianjin: Tianjin People’s Press.
22
tidak menghalangi kemungkinan adanya ketidaksepakatan dalam berbagai
kelompok pada prioritas kepentingan tersebut.33
F. Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan bersifat penelitian kualitatif.
Menurut Bagong Suyanto dan Sutinah yang dikutip dari Taylor dan
Bogdan, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang
menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan
tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti.34 Peneliti
menggunakan metode kualitatif karena dalam skripsi ini berusaha
menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi
munculnya politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan pada masa
pemerintahan Presiden Hu (2003-2013).
Penelitian kualitatif juga mengandalkan data dari sumber sekunder
yang diperoleh melalui buku, skripsi, jurnal, makalah, dokumen
pemerintah, media elektronik dan surat kabar. Peneliti berupaya untuk
mencari data sekunder tersebut melalui beberapa sumber seperti
Perpustakaan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Perpustakaan
Universitas Indonesia, American Corner di Perpustakaan Umum UIN
Syarif Hidayatulah dan Perpustakaan Central Strategic and International
Studies (CSIS).
33 Qin Yaqing. 2003. “Guojia Shenfen, zhanlue wenhua he anquan liyi – guanyu zhongguo yuguoji shehui guanxi de sang jiashe (Nation Identity, Strategic Culture and Security Interests:Three Hypotheses on the Interaction between China and International Society)”. Shijie Jingjiyu Zhengzhi. Hal.11-16.
34 Bagong Suyanto dan Sutinah. 2009. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal.166.
23
Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya
yang dilakukan adalah menganalisis data. Peneliti menganalisa data yang
telah didapat melalui klasifikasi dan pembuatan kategori data. Lebih
lanjut, peneliti juga melakukan penelitian secara sistematis, data mentah
yang diperoleh dalam sebuah deskripsi kemudian dipahami tanpa harus
kehilangan kompleksitas permasalahan yang diteliti. Setelah data yang
diperoleh peneliti diklasifikasi menjadi data yang dibutuhkan, peneliti
mulai memahami, memaknai dan kemudian menampilkan data tersebut.
Data tersebut yang pada akhirnya berguna untuk menjelaskan
permasalahan yang diteliti dengan menggunakan konsep-konsep yang
terkait dengan penelitian ini.
G. Sistematika PenulisanPenulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sub-bab
masing-masing di setiap bab:
BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah
tentang topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dilanjutkan
dengan pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II Dinamika Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Taiwan
sebelum Masa Pemerintahan Presiden Hu Jintao. Bab ini membahas
mengenai awal mula konflik Tiongkok-Taiwan. Kemudian dilanjutkan
dengan membahas masing-masing politik luar negeri dari setiap Presiden
di Tiongkok sebelum masa pemerintahan Presiden Hu Jintao.
24
BAB III Faktor-faktor yang Mempengaruhi Politik Luar Negeri
Tiongkok Terhadap Taiwan pada Masa Presiden Hu Jintao. Pembahasan
dalam bab ini dimulai dengan menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan pada masa
Presiden Hu Jintao. Faktor-faktor yang akan dibahas terdiri dari faktor
internal dan eksternal.
BAB IV Analisa Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Taiwan
pada Masa Presiden Hu Jintao. Bab ini menganalisa kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan Tiongkok terhadap Taiwan pada masa Presiden Hu
Jintao, mulai dari Anti- Secession Law atau Undang-Undang Anti
Pemisahan untuk mencegah kemerdekaan Taiwan, Economic Cooperation
Framework Agreement (ECFA) untuk memperkuat kerjasama dalam
bidang ekonomi dan Enam Proposal Hu Jintao dalam pengelolaan
hubungan yang damai dengan Taiwan. Kemudian dilanjutkan dengan
menganalisa respon Taiwan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan
Tiongkok pada masa Pemerintahan Hu Jintao.
BAB V Kesimpulan. Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh
pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.
25
BAB II
DINAMIKA HUBUNGAN TIONGKOK DAN TAIWAN
SEBELUM MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN HU JINTAO
(1946-2002)
A. Sejarah Hubungan Tiongkok dan Taiwan pada Tahun 1946-2002
1. Perang Sipil antara Partai Nasionalis (KMT) dan Partai Komunis
Tiongkok (PKT) pada Tahun 1946-1949
Berbagai peristiwa penting telah berkontribusi dalam
pembentukan hubungan antara Tiongkok dan Taiwan. Berawal dari Perang
Sipil pada tahun 1949 mengakibatkan keduabelah pihak benar-benar
terpisah secara sistem politik dan ekonomi karena Perang Sipil tersebut
dimenangkan oleh pihak komunis. Meskipun keduanya terpisah dalam
sistem politik dan ekonomi namun hubungan keduanya tetap terjaga melalui
hubungan ekonomi serta status quo pada masing-masing pihak. Tiongkok
tetap menjadi negara dengan sistem pemerintahan otoriter yang berbasis
partai tunggal sedangkan Taiwan saat ini diakui oleh sebagian negara
sebagai negara yang memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dengan
berbasis multipartai.
Konflik Perang Sipil pada tahun 1949 merupakan bentuk
perjuangan antar kedua partai untuk menguasai daratan Tiongkok secara
keseluruhan. Adapun Perang Sipil dari tahun 1946-1949 merupakan akibat
26
dari konflik antara Partai Komunis dan Nasionalis yang telah ada sejak
tahun 1927 yang menandai puncak dari ketidakstabilan politik di daratan
Tiongkok. Sebelum tahun 1927, pemerintahan di Tiongkok telah mengalami
kemunduran yang diperparah oleh peningkatan intervensi asing dan
eksploitasi seperti Perang Opium I (1839-1842), pemberontakan, dan
penjajahan Jepang.35
Perang Saudara tersebut mengakibatkan adanya polarisasi pada
konteks politik internasional melalui pengembangan Perang Dingin. Perang
antara Partai Nasionalis dan Komunis di Tiongkok telah menjadi bagian dari
usaha Soviet dan Amerika untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan
pasca Perang Dingin. Setelah kemenangan yang diraih oleh pihak Partai
Komunis, pada bulan Oktober 1949 Mao Zedong memproklamasikan
berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kemudian para pengikut
Chiang Kai-shek yang kalah menduduki Pulau Formosa atau yang sekarang
disebut Taiwan. Chiang Kai-shek membawa sekitar dua juta orang
pengikutnya yang menentang haluan Komunis. Sejak saat itu Chiang Kai-
shek mendeklarasikan Taiwan sebagai negara yang terpisah dari
Tiongkok.36
Setelah Perang Saudara selesai, PKT mengkonsolidasikan kontrolnya atas
Tiongkok. Pengalaman akan perang yang panjang dijadikan pedoman oleh
35 The Civil War. Diakses dari http://share.nanjing-school.com/dphistory/files/2014/09/Civil-War-1946-9-2i0pi2f.pdf Pada Minggu, 22 Juni 2015.
36 Angga Nurdin. 2010. Taiwan, Dilema Diantara Dua Super Power. Jurnal Multiversa, Vol. 2 No.1. Yogyakarta: Institute of Internasional Studies (IIS) Jurusan Hubungan InternasionalUniversitas Gadjah Mada (UGM).
27
partai komunis dalam mengembangkan rezim komunis di Tiongkok. Bagi
PKT hal ini merupakan lanjutan bagi pemerintahan yang otoriter bagi
Tiongkok. Tiongkok pun tetap menjadi negara dengan sistem satu partai.37
Konflik yang masih terjadi antara Tiongkok-Taiwan hingga saat ini
semakin kompleks, konflik tersebut meliputi isu kedaulatan wilayah,
identitas nasional, dan keamanan nasional. Hubungan kedua negara ini
mengalami pasang surut baik dalam hal politik, ekonomi, maupun
keamanan. Pada sub-bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai
perkembangan hubungan politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan
yang dibagi ke dalam tiga masa pemerintahan sebelum Presiden Hu Jintao
yaitu masa pemeritahan Presiden Mao Zedong, Deng Xiaoping dan Jiang
Zemin.
B. Politik Luar Negeri Tiongkok terhadap Taiwan sebelum Masa
Pemerintahan Presiden Hu Jintao pada Tahun 1949-2002
Pendekatan Tiongkok terhadap kedaulatan wilayah dalam politik luar
negerinya cukup signifikan. Tiongkok memiliki sejarah yang berasal dari
peradaban yang berkembang pesat dimana Tiongkok mencapai kemajuan
dari sisi ekonomi, politik dan militer dan sejarah yang menyakitkan dari
invasi asing yang dimulai dari Perang Opium hingga agresi Jepang. Hal ini
memberikan kontribusi terhadap perkembangan rasa nasionalis yang kuat.
37 Op. Cit. Civil War Case Study 2: The Chinese Civil War (1927-37 and 1946-49).
28
Menjaga kedaulatan teritorial telah menjadi salah satu prinsip dari kebijakan
luar negeri Tiongkok.38
Politik luar negeri Tiongkok pasca perang dingin secara garis besar
terdiri dari tiga kepentingan utama yaitu pembangunan, kedaulatan dan
tanggung jawab.39 Kepentingan kedaulatan tersebut merupakan tanggung
jawab Tiongkok dalam menjaga stabilitas baik secara internal maupun
eksternal dari konflik yang menyangkut kedaulatan nasional. Menjaga
integritas wilayah Tiongkok dengan mempertahankan kebijakan yang menuju
ke arah reunfikasi dengan wilayah Taiwan.
Elemen kunci dari politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan
muncul pada akhir tahun tujuh puluhan. Kebijakan ini berisi sembilan
elemen dasar yaitu pertama, hanya ada ‘satu Cina’, Taiwan merupakan bagian
dari Tiongkok serta tidak akan menjadi negara yang merdeka. Kedua,
reunifikasi Taiwan dengan Tiongkok adalah hal mutlak, semakin cepat
prinsip ‘Satu Cina’ tercapai akan lebih baik. Ketiga, reunifikasi harus terjadi
dalam formula satu negara dua sistem dimana Taiwan diizinkan untuk
mempertahankan sistem politik, ekonomi, dan militer dengan syarat adanya
pengakuan dari Taipei bahwa pemerintah Tiongkok sebagai pemerintah
tunggal.40
38 Qingguo Jia. From Self-imposed Isolation to Global Cooperation: The Evolution of ChineseForeign Policy Since the 1980s. Hal. 170. Diakses dari http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-1999-2/artjia.pdf pada Selasa,11 November 2014.
39 Wang Yizhou. 2003. Quanqiu zhengzhi he zhongguo wai jiao (Global politics and Chineseforeign policy). Beijing: World Knowledge Press. Hal. 51-52.
40 Ralph N. Clough. 1993. Reaching Across the Taiwan Strait: People to People Diplomacy.Colorado: Westview Press. Hal. 126.
29
Keempat, perundingan reunifikasi harus dimulai sesegera mungkin.
Kelima, perundingan reunifikasi dapat dilakukan dengan perwakilan dari
Partai Nasionalis (KMT) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT), tetapi tidak
boleh menggunakan perwakilan dari Beijing dan Taipei sebagai dua
pemerintahan yang sama karena bagi Tiongkok, Taiwan hanyalah pihak yang
berwenang yang mengelola suatu provinsi.41
Keenam, kedua belah pihak harus mempromosikan interaksi people to
people untuk mempersiapkan proses reunifikasi secara halus. Ketujuh,
kebijakan three link diperlukan untuk memfasilitasi interkasi kedua belah
pihak secara langsung. Kedelapan, meskipun Tiongkok melaksanakan proses
reunfikasi secara damai tetap memiliki kewenangan untuk menggunakan
kekuatan mlilter terhadap Taiwan jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk
mencegah Taiwan memisahkan diri secara permanen dari Tiongkok.
Kesembilan, hanya Tiongkok yang berhak mewakili Tiongkok dalam dunia
internasional sehingga Taiwan hanya dapat memiliki hubungan budaya dan
ekonomi dengan negara-negara asing bukan hubungan sebuah hubungan
diplomatik.42
Elemen kunci dari politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan dapat
disimpulkan meliputi keamanan nasional, menjaga kedaulatan nasional dan
integritas wilayah, menjamin adanya kelanjutan dalam pembangunan
ekonomi dan sosial. Hal ini menekankan bahwa inti kepentingan nasional
41 Ibid.42 Ibid.
30
Tiongkok mirip dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai setiap
negara berdaulat yang ingin menjaga keutuhan wilayahnya.
1. Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Taiwan Pada Masa Presiden
Mao Zedong (1949-1976)
Politik luar negeri Tiongkok pada masa pemerintahan Mao Zedong
tidak lepas dari adanya pengaruh sejarah modern Tiongkok. Hal ini
bermula pasca runtuhnya Dinasti Manchu (Qing) dan berakhirnya Perang
Sipil. Berdirinya RRT diproklamirkan oleh Mao Zedong pada 1 Oktober
1949 setelah kemenangan Partai Komunis Tiongkok (PKT) melawan
Kuomintang (KMT). PKT yang telah berhasil menguasai seluruh daratan
Tiongkok, sedangkan KMT kalah dan menduduki pulau Formosa atau
Taiwan.43 Sejak saat itu, masalah kedaulatan dan integritas nasional
Tiongkok dalam menghadapi Taiwan menjadi fokus perhatian Mao
dalam masa kepemimpinannya.
Pada Era Mao Zedong, perumusan kebijakan Tiongkok terhadap
Taiwan disesuaikan dengan situasi politik baik didalam maupun diluar
Tiongkok saat itu. Konflik yang berakar dari Perang Sipil pada tahun
1946-1949 membuat hubungan Tiongkok dan Taiwan semakin menegang.
Ketegangan tersebut ditambah dengan munculnya Amerika Serikat dalam
konflik ini, membuat Tiongkok mengupayakan adanya reunifikasi dengan
Taiwan untuk menjaga integritas wilayah Tiongkok dan menggunakan
People Liberations Army (PLA) sebagai ancaman perang terhadap
43 Umar Suryadi Bakri. 1997. China Quo Vadis?: Pasca Deng Xiaoping. Jakarta: Pustaka SinarHarapan. Hal 1.
31
Taiwan.44 Hal ini menjelaskan politik luar negeri Tiongkok terhadap
Taiwan hingga tahun 1966 dimana bentrokan bersenjata dalam skala kecil
sering terjadi.
Setelah Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengalahkan
Kuomintang (KMT) dalam Perang Sipil, keduanya terikat dalam hubungan
lintas selat yang kontroversional. PKT menggunakan PLA untuk
membersihkan Tiongkok dari sisa pasukan KMT yang mengalami
kekalahan dalam Perang Sipil. PKT beserta Pemimpin Tiongkok mulai
menyiapkan kebijakan pembebasan Taiwan45 sehingga Tiongkok dan
Taiwan dapat mewujudkan unifikasi dibawah rezim PKT.
Untuk mendukung kebijakannya dalam merebut wilayah Taiwan,
Mao memberikan perhatian khusus terhadap bantuan dari negara sekutu
Komunisnya yaitu Uni Soviet (Rusia). Hal ini didukung dengan adanya
kunjungan rahasia yang dilakukan oleh Liu Shaoqi (Chairman of the
National People’s Congress Standing Committee) ke Moskow.46 Pihak
Tiongkok dan Uni Soviet membuat kesepakatan, setelah Uni Soviet
memberikan bantuan militer udara dan laut maka Uni Soviet memberikan
dukungan kepada PKT dalam kampanye dukungan untuk PLA dalam
mengatasi masalah dengan Taiwan.
Selain Rusia, campur tangan Amerika Serikat membuat Mao juga
menetapkan prinsip dua arah dalam politik luar negeri Tiongkok dalam
44 Chen Jian. 2001. Mao’s China and The Cold War. London: The University of North CarolinaPress. Hal 165.
45 Ibid.46 Ibid.
32
menangani masalah Taiwan. Hal itu dilakukan Mao untuk menjawab
tuntutan Amerika Serikat bahwa permasalahan Taiwan harus diselesaikan
secara damai. Mao mencegah agar tidak terjadi perang dengan Amerika
Serikat. Adapun urusan Taiwan dianggap sebagai urusan internal.
Negosiasi dapat dilakukan tetapi menurut Mao cara militer dapat menjadi
inti dari kebijakan Tiongkok terhadap Beijing. Visi Mao terhadap Taiwan
tidak terbatas pada pengaturan geografis Selat Taiwan. Perhatian utamanya
bagaimana memainkan peran Tiongkok pada kekuatan Perang Dingin,
tidak hanya sekedar reunifikasi melalui kebijakan militer. 47
Usaha Mao dalam melawan pengaruh Amerika di Taiwan
memiliki tujuan untuk mengurangi kesempatan bagi Taiwan untuk
bekerjasama dengan Amerika serikat.48 Meskipun Mao gagal dalam
mewujudkan tujuan nasional Tiongkok dalam bentuk penyatuan wilayah
dengan Taiwan tetapi rencana Mao untuk melemahkan pengaruh Amerika
Serikat di Kawasan Asia Timur cukup berhasil.
Pada tahun 1971 Majelis Umum PBB mengakui Tiongkok untuk
mewakili Cina di PBB. Selama dua puluh tahun (1950-1970) Taiwan telah
mengupayakan hubungan diplomatik yang intensif untuk tetap
mempertahankan posisinya dalam PBB. Tujuan Taiwan memasuki PBB
sebelumnya adalah untuk memperluas hubungan diplomatik dan
47 Ibid48 Joseph Y. S. Cheng. 1998. China in the Post-Deng Era. Hongkong: The Chinese University
Press. Hal. 255-230.
33
memperluas pengaruh Taiwan terhadap negara-negara di dalam organisasi
tersebut.49
Bagi Mao, strategi militer yang baik adalah selalu melihat
kesempatan menguntungkan dan mengambil inisiatif untuk melawan
musuh.50 Tiongkok menyadari bahwa Taiwan tidak mampu melawan
militer Tiongkok tanpa adanya bantuan dari militer Amerika Serikat.
Sehingga Tiongkok ikut serta dalam Perang Korea yang memungkinkan
Mao berkerja sama dengan Komunis di Korea dan memiliki bantuan
perlindungan Komunis dari Rusia.
Terdapat tiga tujuan dari politik luar negeri Tiongkok terhadap
Taiwan pada masa pemerintahan Mao Zedong yang dirangkum secara
keseluruhan. Pertama, untuk menjaga keamanan nasional yang diraih oleh
Tiongkok pasca Perang Sipil. Kedua, untuk menjamin kedaulatan negara.
Ketiga untuk meningkatkan status internasional Tiongkok.51 Dapat
disimpulkan kebijakan Mao adalah untuk state survival atau pertahanan
suatu negara dan lebih berorientasi pada keamanan. Politik luar negeri
Tiongkok dibawah Mao Zedong berpusat pada tujuan sebagai berikut
pertama, untuk menjaga keamanan nasional. Kedua untuk menjamin
kedaulatan Tiongkok dan integritas teritorial. Ketiga untuk meningkatkan
status Tiongkok dalam politik internasional.
49 Yu San Wang, (ed). 1990. Foreign Policy of the Republic of China on Taiwan: An UnorthodoxApproach. New York. Praeger Publishers. Hal. 8.
50 Ibid. Hal. 250.51 Harish Kapur (ed.). 1985. The End of and Isolation: China After Mao. Dordrecht: Martinus
Nijhoff Publishers. Hal. 167-201.
34
2. Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Taiwan Pada Masa Presiden
Deng Xiaoping (1978-1997)
Berakhirnya masa pemerintahan Mao Zedong pada akhir tahun
1970an, PKT membuat pergantian kebijakan yang cukup signifikan.
Sebelumnya masa pemerintahan Mao Zedong memiliki kebijakan
pembebasan Taiwan yang secara keseluruhan menggunakan cara yang
keras dan tegas pada pelaksanaannya. Untuk masa pemerintahan Deng
Xiaoping, pemerintahan Tiongkok memberikan perhatian pada kebijakan
baru yaitu reunifikasi secara damai.52
Tujuan kebijakan Deng terhadap Taiwan tidak berubah namun
pendekatan kebijakannya sangat jauh berbeda dari Mao Zedong. Mao lebih
berorientasi dengan cara militer sedangkan Deng menjadikan ekonomi dan
perdagangan sebagai alat untuk mencapai unifikasi dengan Taiwan.53
Dengan kebijakan terbuka, Deng memberikan lingkungan usaha yang
komprehensif dan kompetitif bagi Hongkong, Makau dan Taiwan.
Secara keseluruhan Deng cukup berhasil dalam menggunakan
kebijakan terbuka untuk menarik Taiwan. Kebijakan ini lebih
mengedepankan pada kerjasama ekonomi daripada konfrontasi militer dan
mengutamakan integrasi kekuatan pada pasar. Kelemahan kebijakan
terbuka terletak pada paham Leninisme yang dipegang oleh Deng
52 Sean Coney. 1997. Why Taiwan is Not Hongkong: A Review of The PRC’s “One Country TwoSystems” Model for Reunification with Taiwan. Pacific Rim Law & Policy Journal Vol. 6.No. 3.Hal 503.
53 Op. Cit. Cheng.
35
Xiaoping. Dalam konstitusi Tiongkok, tidak diijinkan adanya liberalisme
dan kelonggaran dalam kontrol politik.54
Menurut Partai Komunis Tiongkok (PKT), Hongkong, dan
Taiwan adalah wilayah Tiongkok yang harus dikembalikan. Dalam pidato
majelis kader partai, Deng Xiaoping mengidentifikasikan tiga tujuan
utama politik luar negeri Tiongkok yaitu penangkalan hegemonisme,
unifikasi dan modernisasi ekonomi. Tiga tujuan tersebut juga dianggap
sebagai tiga prioritas nasional Tiongkok pada tahun 1980an.55 Oleh karena
itu, setiap pemimpin Tiongkok mengupayakan untuk tercapainya tiga
tujuan tersebut dimana salah satunya adalah unifikasi dengan Taiwan.
Upaya yang dilakukan oleh pemimpin Tiongkok agar dapat
mewujudkan unifikasi damai dengan Taiwan salah satunya dengan
menggunakan kebijakan One Country Two Sytem (OCTS) atau satu
negara dengan dua sistem merupakan dasar kebijakan Tiongkok yang
dirumuskan oleh Deng Xiaoping untuk mencapai mencapai unifikasi
dengan damai dan memecahkan masalah kedaulatan Hongkong, Macau
dan Taiwan yang ditimbulkan oleh latar belakang sejarah.
Kebijakan ini berawal dari sidang paripurna ketiga komite sentral
kesebelas PKC yang diselenggarakan di Beijing pada tanggal 18 Desember
tahun 1978. Sidang tersebut mengusung tiga misi penting dalam politik
luar negeri Tiongkok yaitu pertama membangun perdamaian dunia, kedua
54 Ibid.55 Parris H. Chang. 2014. Beijing’s Unification Strategy toward taiwan and Cross-Strait Relations.
The Korean Journal of Defense Analysis Vol. 26 No. 3. Hal. 300. Penulis mengutip dari DengXiaoping’s Selected Works 1975–1982. 1983. Beijing: People’s Publishing House. Hal. 203.
36
mencapai reunifikasi nasional, ketiga mempercepat modernisasi di empat
bidang yaitu industri, pertanian, pertahanan, ilmu pengetahuan dan
teknologi. Pada tanggal 11 Januari 1982, Deng Xiaoping pertamakali
mengajukan gagasan untuk pemecahan masalah Taiwan dengan sebuah
konsep satu negara dua sistem.56
Posisi pemerintah Tiongkok pada kebijakan One Country Two
System (OCTS) ini didukung dengan kemunculan buku putih Tiongkok
tentang pertanyaan Taiwan dan unifikasi. Pada bagian tiga buku putih
tersebut menegaskan posisi Tiongkok pada kebijakan reunifikasi secara
damai; one country two systems (OCTS). Pertama, hanya ada satu Cina.
Dimana Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Pusat pemerintahan
Tiongkok berada di Beijing dan otoritas di Taipei bukanlah legitimasi dari
pemerintah Tiongkok. PRC menentang adanya model “Two China’s”
(Daratan sebagai Tiongkok sedangkan Taiwan adalah wilayah yang
terpisah dari Tiongkok); OCTS merupakan satu Cina dengan satu
pemerintahan di Beijing dan pemerintahan yang terpisah di Taiwan kedua
meskipun hanya ada satu Tiongkok sangat memungkinkan bagi
masyarakat sosialis dan kapitalis untuk hidup berdampingan di dalamnya
ketiga setelah reunifikasi, Taiwan akan menikmati otonomi tingkat tinggi
sebagai daerah administratif khusus. Hal tersebut memiliki kekuatan baik
dari segi administratif maupun legislatif yang terdiri dari peradilan yang
56 Drafting and Promulgation of the Basic Law and Hongkong’s Reunification with theMotherland. Diakses darihttp://www.basiclaw.gov.hk/en/publications/book/15anniversary_reunification_ch1_1.pdf padaSenin, 23 Februari 2015.
37
independen dan dapat menjalankan urusan partai, politik,militer, ekonomi
dan keuangannya sendiri. Akan tetapi daerah administrasi khusus ini akan
terbatas pada hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Jika hal
tersebut terjadi pemerintah Taiwan harus membicarakan kepada
pemerintah pusat di Beijing keempat hubungan ekonomi dan lainnya
antara Tiongkok harus dengan cepat memperluas menjadi negosiasi
terhadap proses reunifikasi.57
Sejak Deng Xiaoping menetapkan kebijakan reformasi dan
keterbukaan pada era 1970an, Tiongkok sedang menuju ke arah politik
luar negeri yang berbeda dengan masa pemerintahan Mao Zedong. Dengan
kebijakan ini Deng Xiaoping telah memberikan kontribusi besar bagi
perkembangan politik luar negeri Tiongkok. Setelah kebijakan ekonomi
tahun 1989, Deng Xiaoping mengeluarkan kebijakan keep a low profile
yang berfokus pada upaya mengakhiri campur tangan asing dalam politik
luar negeri Tiongkok seperti campur tangan Amerika dalam masalah
Taiwan.58 Hal ini dilakukan Deng untuk mengamankan situasi Tiongkok
dalam lingkungan internasional.
Dalam politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan pada masa
pemerintahan Deng Xiaoping terdapat dua prioritas, pertama untuk
mempertahankan situasi internasional yang damai dengan mewujudkan
“empat modernisasi”, kedua untuk mendorong terwujudnya tatanan politik
57 Op. Cit. Coney. Hal. 504.58 Chen Zimin. International Responsibility and China’s Foreign Policy. Diakses dari
www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series3/pdf/3-1.pdf pada Kamis 26 Februari2015.
38
dan ekonomi internasional yang baru.59 Dalam dua prioritas tersebut, Deng
juga menekankan pada penyatuan kembali Taiwan ke dalam wilayah
Tiongkok. Dalam pidato pembukaan di Kongres Nasional Ke-12
Communist Party of China (CPC) pada tahun 1982, Deng menyatakan
untuk meningkatkan modernisasi sosialis, berjuang untuk penyatuan
Tiongkok terutama pengembalian Taiwan ke Tiongkok, menentang
hegemonisme, bekerja untuk menjaga perdamian dunia. Hal ini merupakan
tiga tugas utama yang dilakukan di tahun 1980an. Konstruksi ekonomi
merupakan inti dari tugas-tugas ini yang menjadi dasar untuk solusi atas
permasalahan internal dan eksternal kami.60
Dalam hal ini strategi politik luar negeri Tiongkok pada masa
pemerintahan Deng Xiaoping berorientasi pada modernisasi Tiongkok.
Modernisasi yang dilakukan oleh Deng juga bertujuan untuk mengisolasi
Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional. Tiongkok
dibawah kekuasaan Deng merupakan negara yang berusaha untuk
mengembangkan kekuatannya secara pragmatis, menyeimbangkan
keinginan, mendorong usaha dan inisiatif untuk diarahkan pada
pencapaian tujuan nasional secara cepat dan semulus mungkin.61
59 Joseph Y. S. Cheng. 1989. The Evolution of China Foreign Policy in the Post-Mao Era: FromAnti-Hegemony to Modernization Diplomacy, in China: Modernization in the 1980’s “Zhongguode ‘Xiandaihua’ Wiajiao Zhengce”. Hongkong: Chinese University Press. Hal. 3-66.
60 Robert Maxwell (ed). 1984. Deng Xiaoping: Speeches and Writings. New York: Pergamon. Hal.87.
61 Paul Kennedy. 1987. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and MilitaryConflict from 1500 to 2000. New York: Random House. Hal. 447.
39
3. Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Taiwan Pada Masa Presiden
Jiang Zemin (1995-2002)
Jiang Zemin terpilih menjadi Presiden Tiongkok generasi ketiga
pada Maret 1993 dan sebagai Ketua Komisi Militer Pusat atau Central
Military Commission (CMC). Terpilihnya Jiang Zemin karena prestasi
yang luar biasa, kemampuan, dan dukungan dari pendahulunya yaitu Deng
Xiaoping. Lahir pada 17 Agustus 1926 di Yangzhou, sebuah kota budaya
yang terkenal di Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Jiang melanjutkan
pendidikannya hingga berkuliah di Shanghai Jiaotong University.62
Jiang Zemin lahir dari keluarga intelektual dan lulus insinyur
kelistrikan di Shanghai Jiaotong University. Sebelumnya Jiang pernah
bekerja di sebuah pabrik mobil di Uni Soviet dan sebagai diplomat di
Rumania pada tahun 1950an. Jiang pernah menjabat sebagai menteri yang
bertanggungjawab atas industri elektronik, walikota dan ketua partai di
Shanghai.63
Dengan latar belakang karir politik tersebut, pergantian politik
pada masa Jiang telah dikelola oleh institusi. Kurangnya kontribusi
kebijakan yang revolusioner dan pengalaman militer, membuat Jiang
harus beralih ke faktor institusional untuk pergantian politik di Tiongkok.
Tidak seperti Mao Zedong dan Deng Xiaoping, Jiang memiliki waktu
62 People’s Daily Online. Jiang Zemin Biography. Diakses darihttp://en.people.cn/leaders/jzm/biography.htm pada Minggu, 22 Maret 2015.
63 British Broadcasting Corporation (BBC). Jiang Zemin’s Profile. Diakses darihttp://www.bbc.com/news/world-asia-China-20038774 pada Minggu, 29 Maret 2015.
40
yang lebih singkat dan mudah saat pergantian politik.64 Jiang Zemin
hampir tidak memiliki hambatan sebagai penerus baru setelah Deng
Xiaoping.
Kemudahan Jiang dalam menangani proses pergantian politik di
Tiongkok dikarenakan adanya sejumlah kelonggaran pada institusi yang
mengatur pergantian politik tersebut seperti pertama, para anggota dalam
Politburo dan posisi atas pada institusi di Tiongkok akan pensiun pada
umur 70 tahun. Kedua, terdapat dua pembagian kekuasaan besar di
Tiongkok yaitu partai dan posisi kenegaraan seperti presiden, sekretaris
jenderal. Ketiga, kriteria untuk memasuki institusi yang bias, jika anggota
muda dan berpendidikan akan langsung dibawa ke Politburo pada setiap
kongres dan akan dipertimbangkan untuk menjadi generasi penerus dari
kepemimpinan di Tiongkok.65
Dari kekurangan latar belakang Jiang sebagai pemimpin, terlihat
pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jiang termasuk kebijakan
dalam mengelola hubungan dengan Taiwan. Pada tahun 1995, Jiang Zemin
mengeluarkan sebuah formula untuk melanjutkan strategi Deng Xiaoping
dalam mewujudkan reunifikasi yang damai dengan Taiwan yaitu Jiang
Zemin Eight Point atau delapan poin Jiang Zemin. Kebijakan ini menjadi
pedoman dasar untuk hubungan lintas-selat pasca pemerintahan Deng
Xiaoping. Meskipun kebijakan ini didasari oleh ide Deng Xiaoping, tetapi
64 Jhon Wong dan Yongnian Zheng (ed). 2002. Post Jiang Leadership Succession: Problems andPerspective. Singapore: Singapore University Press. Hal. 5-6.
65 Ibid.
41
pada era Jiang Zemin, kebijakan ini lebih mengedepankan bagaimana
menuntun diskusi lintas-selat menuju reunifikasi.66
Kebijakan delapan poin Jiang Zemin dapat dijelaskan sebagai
berikut pertama, menggunakan prinsip ‘Satu Cina’ merupakan dasar dan
prasyarat reunifikasi secara damai. Kedua, Tiongkok tidak keberatan
terhadap perkembangan hubungan non-pemerintah dalam bidang ekonomi
dan budaya antara Taiwan dengan negara-negara lain. Ketiga, konsistensi
bagi pihak Tiongkok untuk mengadakan negosiasi dengan otoritas Taiwan
pada dalam hal reunifikasi. Keempat, pihak Tiongkok akan
mengupayakan pencapaian reunifikasi secara damai, dan berjanji tidak
akan menggunakan kekuatan atau kekerasan, jika kekerasan tersebut
terpaksa digunakan, semata untuk diarahkan untuk melawan pasukan asing
yang ikut campur dalam reunifikasi Tiongkok dan untuk ‘kemerdekaan
Taiwan’.67
Kelima, tertantang dengan pembangunan ekonomi di abad 21,
konflik antara Tiongkok dan Taiwan tidak akan mempengaruhi pertukaran
ekonomi dan kerjasama lintas selat. Keenam, menjaga budaya yang telah
ada selama 5.000 tahun dari semua etnis dan kelompok yang berada di
Tiongkok dan Taiwan. Ketujuh, menjaga, melindungi sekaligus
menghormati hak dan kepentingan 21 juta orang Taiwan baik yang lahir
disana maupun di provinsi lain. Kedelapan, Tiongkok menyambut
66 David Lampton (ed). 2001. The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era ofReform, 1978-2000. Standford: Standford University Press. Hal. 313.
67 People’s Daily Online. Jiang Zemin’s Eight Proposal. Diakses darihttp://en.people.cn/90002/92080/92129/6271625.html pada Rabu, 1 Juli 2015.
42
kunjungan dari pihak Taiwan dalam statusnya yang tepat begitupun
sebaliknya baik untuk mendiskusikan urusan negara atau diskusi mengenai
isu-isu tertentu maupun kunjungan sederhana.68
Terdapat beberapa pertimbangan yang signifikan terkait kebijakan
delapan poin Jiang Zemin yaitu pertama, kebijakan tersebut mendapat
persetujuan resmi dari politburo, sehingga proposal tersebut mendapat
dukungan politik yang kuat. Kedua proposal tersebut telah memiliki
penyesuaian strategis terhadap pendekatan Beijing dengan Taiwan.
Meskipun mempertahankan rumus satu negara dua sistem dari Deng
Xiaoping, proposal ini telah menekankan pada usulan yang konkrit seperti
KTT lintas selat. Ketiga, proposal tersebut menyarankan bahwa Jiang siap
untuk melakukan tawar-menawar politik. Keempat, proposal tersebut
mencerminkan pola baru bagi Tiongkok dalam mengatasi politik domestik
di Taiwan.69
Pada tahun setelahnya, Tiongkok dikejutkan dengan kebijakan tak
terduga dari Amerika Serikat untuk memberikan Presiden Taiwan Lee
Teng-hui visa yang memungkinkan dirinya untuk melakukan kunjungan
pribadi ke Universitas Cornell pada bulan Juni 1995. Jiang Zemin
mengubah kebijakan reunifikasi dengan Tiongkok yang didukung oleh
partai dan PLA. Kebijakan militer pun digunakan oleh Tiongkok guna
meredam dukungan pro-kemerdekaan dari Taiwan ataupun Amerika
68 Ibid.69 Hung-mao Tien dan Yun-han Chu (ed). 2000. China Under Jiang Zemin. United States of
America: Lynne Rienner Publisher. Hal. 207.
43
Serikat. Manuver militer dan tiga kali uji coba rudal ini ditujukan untuk
mengintimidasi dan mempengaruhi hasil pemilihan presiden Taiwan.
Serangan militer sejauh 30 mil pada awal bulan Maret 1996 menargetkan
Keelung dan Kaohsiung yang merupakan pelabuhan utama di Taiwan.70
Kesimpulan dari penjelasan diatas, pada masa pemerintahan
Jiang Zemin, kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan cenderung lebih tegas
dan keras, seperti ancaman militer (wengong wuhe) yang menimbulkan
krisis lintas selat. Sedangkan pada periode selanjutnya Tiongkok
memberikan penekanan lebih besar pada kebijakan yang terkait pada
hubungan kekuatan besar guna memberikan pengaruh dan tekanan kepada
pihak Amerika. Selain dua strategi ini, Jiang Zemin juga mengambil
kebijakan lain untuk memperkuat pertukaran dagang yaitu kebijakan
untuk menggunakan orang, individu atau bisnis untuk menekan dan
membatasi pemerintah Taiwan. Dari keseluruhan kebijakan yang
dikeluarkan oleh Presiden Jiang Zemin tersebut dinilai kurang efektif
untuk mencapai unifikasi. Sebaliknya penerapan militer dan kekerasan
dalam kebijakan Tiongkok meningkatkan kesenjangan hubungan antara
Tiongkok-Taiwan.
Adanya studi yang mempelajari kebijakan yang dikeluarkan
Tiongkok pada masa krisis dengan beriorientasi pada kebijakan militer,
terutama pada masa pemerintahan Presiden Jiang Zemin. Krisis di Selat
Taiwan yang terjadi pada tahun 1995-1996 menunjukkan adanya orientasi
70 Jean Pierre Cabestan. 1995. “Mainland Missileand the Future of Taiwan and Lee Teng-hui”.China Perpective. Hal. 43.
44
militer sebagi respon terhadap kebijakan dari pemerintah Taiwan.
Mengamati bahaya dari kepemimpinan Tiongkok yang memuja pertahanan
demi keamanan negara atau yang disebut konsep “cult defense”.71
Penggunaan militer dalam kebijakan Tiongkok tersebut karena
munculnya sebuah rasa tidak aman yang berasal dari sejarah negara
Tiongkok salah satunya adalah abad penghinaan atau century of
humiliation. Rasa ketidakamanan tersebut memicu pemimpin Tiongkok
untuk merespon lingkungan internasional secara berlebihan dan negatif
dan menyebabkan pemimpin tersebut merasionalisasi penggunaan
kekuatan militer sebagai pertahanan negara.72
71 Vincent Wei-Cheng Wang. 2007. The Chinese Military and the Taiwan Issue: How ChinaAssesses Its Security Environment. Southeast Review of Asian Studies Vol. 29. University ofRichmond. Hal. 125
72 Ibid.
45
BAB III
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP
UPAYA KEMERDEKAAN TAIWAN PADA
MASA PRESIDEN HU JINTAO (2003-2013)
Dalam politik luar negeri terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
proses pengambilan keputusan. Howard Lentner mengklasifikasikan faktor-faktor
tersebut menjadi dua kelompok yaitu faktor domestik atau internal dan faktor luar
negeri atau eksternal.73 Sementara James Rosenau menyarankan para penstudi
kebijakan luar negeri untuk menggunakan metode cluster of input dengan memilih
dan menggabungkan faktor mana yang paling penting serta patut diberi perhatian
dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara.74
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa faktor internal dan
faktor eksternal yang paling dominan untuk menjelaskan latar belakang politik
luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Hu
Jintao periode 2003-2013. Faktor internal tersebut diantaranya politik domestik
Tiongkok, faktor ekonomi Tiongkok terhadap Taiwan, dan idiosinkretik
pemimpin Tiongkok yaitu Presiden Hu Jintao. Sedangkan faktor eksternal
diantaranya adalah dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan serta masuknya
Taiwan sebagai anggota WTO.
73 Howard Lentner. 1974. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach.Ohio: Bill and Howell Co. Hal. 105-171.
74 James N. Rosenau, Gavin Boyd dan Kenneth W. Thompson. 1976. World Politics: AnIntroduction. New York: The Free Press. Hal. 18.
46
A. Faktor Internal
1. Perubahan Sistem Politik Domestik Tiongkok
Politik domestik memiliki pengaruh bagi kepentingan nasional
yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Dalam hal
ini, politik domestik Tiongkok meliputi berbagai elemen seperti, sistem
pemerintahan, lembaga-lembaga dan kelompok elit yang terdapat dalam
negara tersebut.75 Elemen-elemen yang terdapat dalam politik domestik
tersebut yang kemudian menentukan ruang lingkup dalam pengambilan
keputusan kebijakan luar negeri.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah menjadi partai tunggal yang
memiliki kekuasaan politik di Tiongkok sejak 1949. Untuk menjaga
kekuasaan partai atas negara dan masyarakat, Tiongkok merancang sistem
politik dimana partai sangat dilibatkan dengan urusan negara. Hal tersebut
dibuktikan dengan adanya dewan negara yang merupakan anggota dari
partai sehingga setiap anggota partai yang terpilih diberikan posisi-posisi
penting pula dalam struktur pemerintahan.
Ketentuan utama dalam sistem politik Tiongkok sesuai konstitusi
bahwa PKT adalah satu-satunya partai politik yang memiliki kekuasaan
tertinggi. Dengan menggunakan sistem sosialis, semua hak-hak rakyat
berada dibawah kekuasaan negara yang dijalankan melalui kongres rakyat
75 Jeremy Patiel. 2010. Structure and Process in Chinese Foreign Policy: Implications for Canada.China Papers No.8. Canadian International Council (CIC).
47
nasional. Prinsip partai adalah sentralisme demokrat yang berarti
pembentukan aspirasi dari atas (partai) ke bawah (masyarakat).76
Situasi politik dalam kepemimpinan PKT juga mampu menentukan
evolusi kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan. Dalam konsep politik
domestik Tiongkok yang berkaitan dengan partai, figur kepemimpinan
dalam partai memiliki tingkat pengaruh yang lebih dominan. Hal ini
dikarenakan pimpinan partai memiliki peran sebagai pemimpin negara
sekaligus militer yang memberikan dasar pada stabilitas politik dan
keamanan luar negerinya.77
Gambaran politik domestik Tiongkok dimulai dengan adanya
lembaga-lembaga politik seperti Partai Komunis Tiongkok (PKT), Central
Military Comission (CMC) atau Komisi Dewan Pusat, Dewan Negara
yang merupakan perwakilan dari PKT dan Kongres Rakyat Nasional
sebagai badan legislatif unikameral.78 Lembaga-lembaga tersebut turut
berperan dalam proses pengambilan keputusan seperti penyusunan serta
pelaksanaan kebijakan-kebijakan di Tiongkok.
Tiongkok memiliki sistem unikameral, dimana kekuasaan tertinggi
lainnya berada pada National People’s Congress (NPC) atau kongres
rakyat nasional yang sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dari PKT.
Menurut pasal 57 konstitusi Tiongkok, “kongres rakyat nasional adalah
76 The Constitutional System. Diakses dari http://www.china.org.cn/english/Political/26143.htmpada Sabtu, 17 Oktober 2015.
77 Michael D. Swaine. 1995. China Domestic Change and Foreign Policy. National DefenceResearch Institute (RAND). Hal.3
78 Susan V. Lawrence dan Michael F. Martin. 2013. Understanding China’s Political System.Congressional Research Service (CRS). Hal.1.
48
organ tertinggi kekuasaan negara”.79 Pada setiap kongresnya, para delegasi
yang mengikuti NPC memilih anggota komite sentral yang baru. Pada
pertemuan komite sentral yang disebut “plenum”, mereka memilih 25
anggota dari politbiro. Dari 25 anggota tersebut terdapat 7 anggota elit dari
komisi tetap politbiro. Selanjutnya dari 7 anggota tersebut terdapat
sekretaris jenderal sebagai pemimpin tertinggi partai dan negara.80 Struktur
yang ada di dalam partai tersebut memiliki peran yang sama dalam
pemerintahan. Karena Tiongkok memiliki sistem politik yang
menggabungkan peran partai dengan negara.
Fungsi dari kongres adalah pertama, untuk mendengar dan
memeriksa laporan dari komisi pusat. Kedua, untuk mendengar dan
memeriksa laporan dari Central Comission for Discipline Inspection atau
komisi pusat untuk inspeksi kedisplinan. Ketiga, untuk membahas dan
memutuskan isu-isu utama dari partai. Keempat, untuk merevisi konstitusi
partai. Kelima, untuk memilih Komisi Pusat. Keenam, untuk memiliki
Komisi Pusat Untuk Inspeksi Kedisplinan.81
Selain itu NPC juga memilih anggota Komisi Pusat, Komisi Pusat
Untuk Inspeksi Kedisplinan. Setelah itu, Komite Pusat memilih anggota
Politburo, Komite Tetap, CMC dan juga sekretaris jenderal dimana posisi
tersebut merupakan posisi tertinggi di PKT. Secara praktek, proses dalam
79 Kerry Dumbaugh dan Michael F. Martin. 2009. Understanding China’s Political System.Congressional Research Service (CRS). Hal. 2.
80 Susan V. Lawrence. 2013. China’s Political Institutions and Leaders in Charts. CongressionalResearch Service (CRS). Hal. 4.
81 China Internet Information Center. China Political System. Diakses darihttp://www.china.org.cn/english/Political/26151.htm pada Kamis, 28 Januari 2016.
49
sistem ini memiliki arah dari atas ke bawah bukan dengan arah bawah ke
atas. Arah tersebut menjelaskan bahwa posisi tertinggi dari partai dipilih
oleh NPC yang berada di bawah alur dari posisi sekretaris jenderal.82
Selain NPC, Politburo Standing Committee (PSC) atau Komisi
Tetap Politbiro merupakan pusat pengambilan keputusan PKT pada semua
isu dan terkait kebijakan utama. Anggot PSC terdiri dari sembilan orang
yaitu Hu Jintao (CCP General Secretary, PRC President, CMC
Chairman), Wu Bangguo (Chairman of NPC), Wen Jiaobao (Premiere,
State Council), Jiang Qinglin (Chairman, Chinese People’s Political
Consultative Conference), Zeng Qinghong (Executive Secretary, CC
Secretariat, Central Party School), Huang Ju (Executive Vice Premiere,
State Council), Wu Guangzheng (Chairman, Central Discipline Inspection
Commision), Li Changchun, Luo Gan.83 Anggota PSC termasuk
didalamnya Hu Jintao yang memiliki posisi sekretaris jenderal, Presiden
Tiongkok sekaligus pemimpin militer sehingga dapat mempengaruhi
perumusan kebijakan luar negeri.
Penjelasan diatas mendukung adanya struktur partai yang sejajar
dengan negara dan proses pembuatan keputusan yang terpusat pada
pemimpin tertinggi partai serta mengikat kepada anggota partai. Tiap
anggota partai wajib untuk melaksanakan kebijakan serta orientasi partai.
82 William A. Joseph. 2014. Politics In China: An Introduction. New York: Oxford UniversityPress. Hal 196.
83 Alice Miller. The Politburo Standing Committee Under Hu Jintao. China Leadership MonitorNo. 35. Hal. 3. Diakses darihttp://media.hoover.org/sites/default/files/documents/CLM35AM.pdf pada Kamis, 28 Januari2016.
50
Hal ini telah dijelaskana dalam konstitusi Tiongkok bahwa “partai
merupakan pusat dari kepemimpinan di seluruh Tiongkok”.84 Melalui
sistem ini dijelaskan bahwa institusi pemerintahan di Tiongkok berfungsi
untuk menjalankan kebijakan partai. PKT yang berfungsi untuk
mengawasi dan mengarahkan jalannya pemerintahan melalui sistem
tersebut.
Perubahan sistem politik domestik tersebut dipengaruhi dengan
adanya perkembangan reformasi ekonomi yang telah lebih dahulu
dilakukan oleh Deng Xiaoping yaitu kebijakan pintu terbuka (open door
policy). Seiring dengan perkembangan ekonomi tersebut perlahan
Tiongkok melakukan reformasi politik yang lebih mengarah pada
keterbukaan. Hal ini didukung dengan adanya penerapan dari democratic
centralism dimana Tiongkok mulai terbuka dengan badan organisasi partai
lainnya dalam pembuatan keputusan dan menggabungkan sistem
kepemimpinan kolektif dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.
Perubahan sistem dalam PKT juga didukung dengan adanya
sipilisasi dan spesialisasi yaitu perubahan pada kepemimpinan partai. Hal
tersebut, didukung dengan adanya gelombang perubahan pada generasi di
Tiongkok yang dibagi menjadi tiga yaitu pertama generasi tahun 1980an
yang aktif melakukan pertukaran ilmu dengan barat. Gelombang kedua,
generasi setelah tahun 1980an yang dipengaruhi oleh rasa nasionalisme
84 Ita Melati. 2013. Upaya Cina dalam Mempertahankan Komunisme Pasca Runtuhnya Uni Soviet.Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Diakses dari http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/11/Jurnal-HI-Ita%20Melati%20%2811-15-13-04-42-36%29.pdf padaJumat, 16 Oktober 205.
51
dan patriotik. Gelombang ketiga generasi akhir 1980an yang lebih
berfokus pada kekuatan publik dan pemerintahan Tiongkok. Generasi ini
menggantikan generasi sebelumnya dengan memiliki spesialisasi yang
lebih terdidik untuk menjadi birokrat. Perkembangan generasi ketiga
dianggap mampu untuk mengembangkan kebijakan yang damai dan
mengutamakan perkembangan ekonomi.
2. Kepentingan Ekonomi Tiongkok terhadap Taiwan
Pergeseran dari kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan dari
pembebasan terhadap penggunaan senjata menuju kepada kebijakan yang
rekonsiliatif bertujuan agar Tiongkok lebih fokus mengembangkan
hubungan sosial dan ekonomi. Tiongkok telah berusaha untuk
mempromosikan integrasi ekonomi terhadap dunia internasional dan
Taiwan sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping. Integrasi ekonomi
tersebut akan memberikan dampak yang saling menguntungkan antara
Tiongkok dengan Taiwan.85 Faktor yang mempengaruhi asumsi ini
dikarenakan adanya sifat untuk saling melengkapi sumber daya atau faktor
pendukung lainnya pada integrasi ekonomi yang terjadi antara Taiwan dan
Tiongkok.
Para analis mengungkapkan bahwa langkah politik yang ingin
dilakukan oleh suatu negara harus didahului langkah perdamaian seperti
mempromosikan hubungan sosial disertai saling ketergantungan ekonomi.
85 Chris Baker. 2013. Deepening Socio-Economic Relations Across Taiwan Strait. Diakses darihttp://www.e-ir.info/2013/10/20/deepening-socio-economic-relations-across-taiwan-straits/ padaSelasa, 27 Oktober 2015.
52
Langkah ini dilakukan agar dapat mendukung upaya menuju perdamaian
politik. Hubungan antara saling ketergantungan ekonomi dan politik
merupakan hubungan timbal balik. Jika ada peningkatan dalam salah satu
hal tersebut maka akan mempengaruhi perbaikan dalam hal lain seperti
peningkatan hubungan politik.86 Perjanjian serta interaksi
dalam ekonomi maupun sosial dalam tingkat yang rendah pun
mampu menyebabkan hubungan politik yang meningkat.
Keadaan yang saling mempengaruhi dikarenakan Tiongkok dapat
menawarkan tenaga kerja murah dan tanah yang akan menjadi pasar
terbesar di dunia bagi Taiwan. Sedangkan Taiwan disisi lain mampu
menawarkan keunggulan dalam bidang manufaktur berteknologi tinggi,
manajemen perusahaan serta modal. Sifat yang saling melengkapi ini akan
menghasilkan perdagangan dan investasi sehingga berdampak pada adanya
ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua belah
pihak.87
Pada Tabel 1 dijelaskan bahwa Tiongkok dan Taiwan saling
memiliki kondisi untung dan rugi sehingga akan saling melengkapi dalam
hubungan ekonomi. Aktifitas perekonomian yang besar antara Tiongkok
dan Taiwan juga sangat memungkinkan terjadinya pertukaran dalam
perdagangan. Tiongkok merupakan negara yang memiliki sumber daya
manusia yang cukup banyak namun memiliki kekurangan dalam hal
86 Charles A. Kupchan. 2010. How Enemies Become Friends. Princeton: Princeton UniversityPress. Hal. 3.
87 Ibid.
53
modal, tanah yang subur dan teknologi. Kondisi yang saling melengkapi
ini mendukung peralihan ekonomi Tiongkok dari negara agraris menuju
negara industri.
Tabel 1. Kondisi Untung dan Rugi yang dimiliki Oleh Tiongkok danTaiwan dalam Perekonomian88
Pada kasus ini, dengan memperdalam hubungan ekonomi antara
Tiongkok dan Taiwan dapat memungkinkan terjadinya rekonsiliasi politik.
Kerjasama ekonomi tersebut dapat menjadi alat yang dapat meredam
keinginan Taiwan untuk memisahkan diri dari wilayah Tiongkok. Dengan
adanya kerjasama tersebut kedua belah pihak dapat mengembangkan rasa
kebersamaan melalui manfaat peningkatan dari sektor ekonomi sehingga
Taiwan dapat kehilangan dukungan masyarakat yang ingin memisahkan
88 Chatam House, The Royal Institution of International Affairs. Program Report. Kerry Brown, et.al. 2010. Investment Across the Taiwan Strait. Diakses darihttp://www.chatamhouse.org/publications/papers/view/109512# pada Kamis, 28 Januari 2016.
Taiwan TiongkokKeuntungan Keuntungan
1. Tenaga kerja yang berpendidikandiserati pengalaman yang besar
2. Memiliki investasi yang baik dalamteknologi dan penelitian
3. Perekonomian yang terintegrasibertaraf internasional dengan AS
4. Memiliki standar pemerintahan danhukum yang baik
5. Perlindungan terhadap hakkekayaan intelektual
1. Memiliki tenaga kerja yang besar2. Memiliki lahan yang berlimpah3. Memiliki kebijakan pemerintah yang
mendukung pertumbuhan ekonomi4. Memiliki pasar konsumen yang besar
Kerugian Kerugian1. Bergerak sesuai dengan kebijakan
Tiongkok2. Kekhawatiran status politik yang
tidak teratur3. Status diplomatik
1. Tidak seimbangnya reformasiekonomi dan reformasi politik yangmungkin akan bersifat kaku dalamproses negosiasi.
2. Memiliki tantangan demografi
54
diri dengan Tiongkok.89 Singkatnya dengan mencapai kerjasama ekonomi
diharapkan Taiwan dapat lebih kooperatif dengan Tiongkok.
Kemajuan hubungan lintas-selat tersebut dikarenakan sebelumnya
Tiongkok mengalami kegagalan dalam penggunaan kebijakan militer dan
kekerasan pada masa Presiden Jiang Zemin, kebijakan Tiongkok terhadap
Taiwan lebih bergantung pada pengaruh kekuatan ekonomi. Perekonomian
Tiongkok telah menunjukkan perkembangan cukup signifikan pada
pertengahan tahun 1990 sementara tingkat perekonomian Taiwan mulai
menurun karena menderita resesi ekonomi dan guncangan dari harga
minyak. Pemerintah Tiongkok pun cukup percaya diri dengan
pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang cukup signifikan tersebut.90 Dari
perspektif tersebut kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan saat ini dapat
dirangkum sebagai bentuk promosi unifikasi melalui keterlibatan ekonomi.
Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa dengan adanya
peningkatan interaksi pada sektor ekonomi dimaksudkan untuk
mempromosikan unifikasi dengan Taiwan. Tiongkok mulai membuka
perdagangan internasional pada tahun 1979 mengimplementasikan
kebijakan ekonomi pintu terbuka (open door policy). Kebijakan ini
menyatakan bahwa peraturan sementara mengenai perdagangan terbuka
dengan Taiwan adalah untuk menegaskan bahwa perdagangan tersebut
merupakan bentuk khusus dari masa transisi sebelum Taiwan kembali ke
89 Op. Cit. Chris baker.90 Yasuhiro Matsuda. 2004. PRC-Taiwan Relations under Chen Shui-bian’s Government:
Continuity and Change between the First and Second terms. Senior Research in NationalInstitute for Defence Studies. Hal. 5.
55
wilayah Tiongkok serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi
reunifikasi.91
Dari sudut pandang Tiongkok, penyatuan kembali wilayah Taiwan
kepada Tiongkok didukung oleh dua alasan yaitu secara politik dan
ekonomi. Alasan politik bahwa secara historis, kesatuan suatu negara
dikaitkan secara erat dengan kekuatan nasional dan pemisahan wilayah
akan memberikan kelemahan bagi negara itu sendiri. Kedua alasan
ekonomi melalui kebijakan unifikasi dengan Taiwan akan memberikan
kontribusi besar dalam kemajuan ekonomi kedua negara. 92
Hal tersebut merupakan strategi Tiongkok dalam mempromosikan
pertukaran ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan nasional.
Pertukaran ekonomi ini dilakukan untuk menarik Taiwan agar dapat
menerima unifikasi politik dengan konsep Tiongkok. Hal ini didasari oleh
dua asumsi yaitu pertama kerjasama ekonomi membutuhkan tingkat
integrasi yang akan memperluas integrasi secara politik. Kedua pemerintah
Taiwan pada awalnya menolak untuk mengorbankan kedaulatan negaranya
tetapi pada akhirnya bersedia untuk melakukan kegiatan ekonomi agar
dapat melintasi batas-batas politik yang menghalangi hubungan Tiongkok
dan Taiwan. 93
Strategi Tiongkok tesebut menyebabkan hubungan ekonomi
keduanya meningkat. Pada tahun 2007, Tiongkok mengupayakan
91 Denny Roy. 2004. Cross-Strait Economic Relations: opportunities Outweigh Risks. Paper SeriesAsia Pasific Center for Security Studies. Hal. 1.
92 Ibid.93 Ibid.
56
peningkatan kerjasama dan memperkuat hubungan perdagangan lintas-
selat. Didukung dengan adanya penghapusan beberapa tarif atas produk
pertanian Taiwan. Pada tahun 2008, Tiongkok menegaskan akan
mendorong perdagangan langsung dengan Taiwan dan membangun
mekanisme kerjasama dalam perdagangan berdasarkan kebijakan ‘Satu
Cina’.94 Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut dapat
menyebabkan dampak dari integrasi ekonomi seperti memberikan
kesempatan dan kemajuan bagi bisnis di Tiongkok maupun Taiwan.
Selain itu, Taiwan juga memiliki investasi yang besar di Tiongkok.
Pada tahun 2006, perusahaan Taiwan menginvestasikan sekitar US$55
milyar dolar pada Tiongkok. Surat kabar resmi di Tiongkok melaporkan
adanya peningkatan dari 1.474 kasus investasi baru oleh perusahaan
Taiwan di Tiongkok. Laju investasi secara langsung yang dilakukan
Taiwan meningkat sebesar 21 persen dari tahun sebelumnya.95
Faktor ekonomi dalam kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan
menunjukkan era baru hubungan yang damai di lintas-selat. Memperdalam
hubungan ekonomi dengan Taiwan mampu melemahkan batas negara yang
menghambat hubungan keduanya. Semakin meningkatnya hubungan
ekonomi Tiongkok dan Taiwan, semakin besar pula kemungkinan adanya
pendekatan menuju kebijakan politik yang ingin dicapai oleh Tiongkok.
94 Xinhua News Agency. 2008. Mainland to further direct trade with Taiwan. Diakses darihttp://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2008-01/20/content_6406756.htm pada Selasa, 5Januari 2016.
95 Eric Von Kesler. 2008. Taiwan’s Dilemma: China, The United States, and Reunification. NavalPostgraduate School. Monterey: California. Hal. 14.
57
Kepentingan ekonomi Tiongkok terhadap Taiwan juga merupakan bentuk
state survival.
Dalam instrumen politik luar negeri terdapat faktor ekonomi yang
menjadi saluran penting untuk mencapai kepentingan negara. Faktor
ekonomi tersebut memiliki dampak ketergantungan sehingga
mengharuskan adanya suatu kerjasama ekonomi dalam kerangka
hubungan bilateral. Dari penjelasan tersebut hubungan antara politik dan
ekonomi dapat dilihat dalam kebijakan ekonomi yang mampu
mempengaruhi interaksi politik maupun sebaliknya. Poin penting dalam
faktor ekonomi bagi politik luar negeri yaitu pertama, mampu
mengeksploitasi kebutuhan dan ketergantungan ekonomi serta membantu
menciptakan ruang untuk membentuk kebijakan yang dapat melemahkan
politik negara tersebut.
Menurut Baldwin, baik perang maupun ekonomi tidak dapat
dipisahkan dari politik. Keduanya dapat dilihat sebagai instrumen yang
digunakan untuk mencapai tujuan dalam politik.96 Tidak semua kebijakan
ekonomi yang dikeluarkan oleh suatu negara bertujuan untuk mencapai
tujuan ekonomi pula. Menurut Papp, negara merupakan entitas yang
mampu mendefinisikan sendiri apa kepentingannya dan menentukan
upaya-upaya untuk mencapainya.97 Hal ini sejalan dengan kepentingan
96 David Baldwin. 1985. Economic Statecraft. New Jersey: Princeton University Press. Hal. 40.97 Daniel S. Papp. 1997. Contemporary International Relations: Framework for Understanding.
USA: Allyn and Bacon. Hal. 38.
58
ekonomi Tiongkok sebagai bentuk state survival untuk mendapatkan
keuntungan politik dan tetap eksis dalam tren integrasi ekonomi.
3. Faktor Ideosinkretik
Dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri
terdapat faktor psikologis atau faktor idiosinkretik yang mempengaruhi
keputusan atau kebijakan yang dapat diambil oleh para pengambil
kebijakan. Sumber idiosinkratik tersebut merupakan nilai (value),
pengalaman (experience), bakat (talent), kepribadian elit politik
(personality of leaders), serta belief dan belief system yang mempengaruhi
persepsi, kalkulasi, dan perilaku terhadap kebijakan luar negeri. Dalam hal
ini juga termasuk persepsi dari elit politik tentang keadaan alami dari arena
internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.98 Profil Hu Jintao
akan dijelaskan sebagai berikut agar dapat mengetahui kepribadian,
pengalaman, nilai serta bakat dari elit politik yang berpengaruh membuat
dalam pengambilan keputusan.
Hu Jintao lahir di Shanghai pada Desember 1942, Hu berasal dari
keluarga berpendidikan dan pedagang teh. Hu merupakan anak pertama
dari tiga bersaudara. Keluarganya sempat berpindah tempat tinggal karena
penjajahan Jepang di Shanghai. Hu muda dibesarkan di daerah Taizhou di
provinsi Jiangsu. Pada tahun 1959 Hu masuk ke Universitas Tsinghua di
98 Anak Agung B. Perwita dan yani Yanyan M. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 57-58.
59
departemen teknik hidrolik dengan jurusan pembangkit listrik tenaga air
dan Hu merupakan mahasiswa termuda di kelasnya.99
Organisasi sekolah partai telah mengidentifikasikan Hu sebagai
calon anggota partai. Hal ini disebabkan Hu memiliki potensi
kepemimpinan dan tertarik dengan ideologi Komunis. Kepribadian Hu
membuat Presiden Universitas Tsinghua tertarik, Presiden Universitas
tersebut memiliki hubungan dekat dengan Komite Pusat Partai Komunis
Cina dan para petinggi di Beijing.100
Pada tahun 1964, Hu Jintao diterima sebagai anggota partai
dengan masa percobaan. Lalu Hu diangkat sebagai peneliti di Universitas
Tsinghua dan instruktur politik untuk organisasi sekolah partai. Pada tahun
1965 Hu resmi diangkat menjadi anggota partai. Setelah lulus dari
Universitas Qinghua, Hu melanjutkan sebagai peneliti dan instruktur
politik disana samapai awal revolusi budaya dari tahun 1966-1976. Pada
tahun 1968, Hu dikirim ke Gansu yang merupakan salah satu provinsi
termiskin di Tiongkok. Setelah satu tahun bekerja di tim pembangunan
perumahan, Hu menjabat berturut-turut sebagai teknisi, sekretaris kantor
dan wakil sekretaris partai di biro teknik kementerian sumber daya air dan
listrik. Hal ini menandai awal karir Hu jintao di Partai Komunis.101
99 Jhon J. Tkcacik, et. al. 2002. Who’s Hu? Assessing China’s Heir Apparent, Hu Jintao. Diaksesdari http://www.heritage.org/research/lecture/whos-hu#pgfId=1010081 pada 29 Maret 2015.
100 State Council Information Office and the China International Publishing Group (CIPG). HuJintao State President. Diakses dari http://en.people.cn/leaders/vpresident.html pada Sabtu, 17Oktober 2015.
101 Ibid.
60
Pada tahun 1974, Hu dipindahkan ke komite pembangunan
provinsi Gansu dan menjabat sebagai sekretaris. Pada tahun 1975 sampai
1980, Hu menjabat sebagai wakil kepala komite divisi manajemen
perencanaan. Setelah itu, Hu mendapatkan promosi sebagai wakil direktur
komite pada tahun 1980 dan kemudian diangkat menjadi sekretaris komite
provinsi Gansu dari Liga Pemuda Komunis Cina atau Communist Youth
League (CYL). Selama kongres rakyat nasional kesebelas dari CYL yang
diselenggarakan pada tahun 1982, Hu terpilih menjadi anggota sekretariat
komite sentral CYL dan presiden dari federasi pemuda Tiongkok. Pada
November 1984, Hu menjadi sekretaris pertama dari sekretariat komite
pusat liga pemuda, dimana Hu menjadi pemimpin pada puncak organisasi
pemuda terbesar.102
Pada tahun 1985, ketika Hu berumur 42 tahun, Hu diangkat
menjadi sekretaris komite provinsi Guizhou selama tiga tahun. Pada akhir
tahun 1988, Hu menjadi sekretaris partai untuk Komite Otonomi Regional
Tibet. Selama Kongres Rakyat Nasional ke-14 pada Oktober 1992, Hu
terpilih menjadi anggota Komite Tetap Politbiro dari Komite Sentral PKT.
Selanjutnya Hu menjadi Presiden sekolah partai Komite Sentral PKT. Hu
juga menjabat sebagai komite tetap pada kongres rakyat nasional ke-16
dari konsultatif politik rakyat Tiongkok.103
Dari ringkasan karir politik Hu Jintao, pengalaman Hu Jintao yang
dimulai dari organisasi pemuda memungkinkan Hu untuk memiliki
102 Ibid.103 Ibid.
61
pemahaman yang baik dari generasi muda Tiongkok. Hu Jintao juga
memiliki asosiasi politik yang luas. Sepanjang karir politiknya, Hu telah
berafiliasi dengan tiga sumber utama perekrutan elit di Tiongkok yaitu
Universitas Qinghua, Chinese Communist Youth League and Central Party
School. Perkembangan karir politik ini menunjukkan pandangan opitimis
bahwa saat ini sangat penting untuk membangun koalisi dan jaringan
dalam berpolitik. Afiliasi ini menjadi aset yang cukup besar bagi Hu
Jintao.104
Dari penjelasan karir politik, Hu Jintao berasal dari faksi yang
disebut “populis”. Faksi tersebut berhubungan dengan Liga Komunis
Muda, dimana organisasi ini mendidik para generasi muda yang memiliki
bakat untuk menjadi pemimpin nasional. Organisasi ini juga diberi julukan
“Faksi Tuanpai”. Organisasi ini sering dikaitkan dengan Hu Jintao karena
pernah menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut.105
Prinsip yang dipegang teguh oleh tuanpai adalah memperkuat dan
mengkonsolidasikan kepemimpinan pusat, mempertahankan stabilitas
sosial, mendistribusikan hasil pembangunan guna memberantas
kemiskinan, melenyapkan kesenjangan antara daerah maju dan
berkembang serta melenyapkan berbagai penyakit sosial yang timbul dari
104 Op. Cit. Jhon J. Tkcacik, Joseph Fewsmith dan Maryanne Kivlehan.105 Dahana, Guru Besar Studi Cina Universitas Indonesia. 2010. Faksionalisme Menjelang
Peralihan Generasi. Diakses darihttps://kabartiongkok.wordpress.com/2010/11/02/faksionalisme-menjelang-peralihan-generasi/pada Sabtu, 17 Oktober 2015.
62
pembangunan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Hu Jintao
menjadi konsep masyarakat yang harmonis dalam kepemimpinannya.106
Terdapat poin-poin penting yang dapat dilihat mengenai sifat-sifat
Hu dalam berpolitik yaitu Hu memiliki kepercayaan kuat dalam
Marxisme, Hu memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap partai. Hu
memiliki gambaran besar dari kesejahteraan bangsa, memiliki gaya kerja
yang demokratis dan bersedia untuk mendengarkan pandangan dari
berbagai sektor. bersih dan tidak korup, Hu memiliki gaya hidup yang
sederhana dan rasa tanggungjawab. Hu memiliki pribadi yang lebih tenang
dan tertutup. Hu memiliki pengalaman lebih dari lima belas tahun bekerja
di daerah termiskin di Tiongkok sehingga Hu memiliki pemahaman
mengenai daerah-daerah yang belum berkembang di Tiongkok. 107
Hal ini sejalan dengan pengalaman Hu Jintao. Hu Jintao
sebelumnya pernah menempati beberapa posisi sebelumnya di provinsi
termiskin di Tiongkok seperti Guizhou dan Tibet. Pengalaman ini akan
membantu Hu Jintao dalam menghadapi beberapa tantangan besar yang
akan dihadapi Tiongkok di tahun-tahun mendatang terkait masalah
kemiskinan, kesenjangan ekonomi, isu-isu minoritas.108
Kondisi nyata dalam politik luar negeri dan domestik dapat
dicerminkan melalui pembuatan kebijakan luar negeri. Belief
106 Ibid.107 Willy Wo and Lap Lam. 2006. Chinese Politics in the Hu Jintao Era: New Leaders, New
Challenges. New York: An East Gate Book. Hal. 11.108 Op. Cit. Jhon J. Tkcacik, Joseph Fewsmith dan Maryanne Kivlehan.
63
109memberikan peta jalan bagi seorang individu pembuat kebijakan untuk
lebih memahami tujuan dan maksud dari suatu realita. Pembuatan
kebijakan didasari pada pandangan subjektif pembuat keputusan terhadap
realita politik dunia. Kemudian dari adanya pemahaman tersebut muncul
strategi yang juga sebagai respon dari realita politik tersebut.
Kecenderungan yang dimiliki oleh pembuat keputusan adalah
memilih strategi mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan atau
kepetingan nasional. Informasi dan realita yang ada akan sesuai atau tidak
dengan belief yang dimiliki oleh pembuat kebijakan. Hal tersebut akan
menyebabkan respon yang berbeda realita yang terlihat oleh pembuat
keputusan sehingga pilihan rasional yang terjadi adalah pemimpin tersebut
akan bertindak guna memaksimalkan tujuan dan meminimalisir
kerugian.110
Sedangkan beliefs system merupakan mekanisme yang menjadi
penyebab dari pilihan politis yang diambil. Belief menjadi suatu
keterkaitan dimana prinsip seorang pembuat kebijakan mau meneruskan
atau merubah kebijakan yang sudah ada sebelumnya atau membuat
kebijakan baru. Hal itu terjadi jika informasi yang dibutuhkan oleh
109 Belief adalah gagasan yang diyakini oleh individu sebagai suatu kebenaran.110 Defa Arimasera. 2014. Pengaruh Belief Hu Jintao Terhadap Persiapan China-ASEAN Free
Trade Area (CAFTA) Tahun 2003-2010. Diakses darihttps://www.academia.edu/9870688/Pengaruh_Belief_Hu_Jintao_Terhadap_Persiapan_CAFTA_Tahun_2003-2010 pada Sabtu, 17 Oktober 2015.
64
pembuat kebijakan tidak sesuai dengan belief yang telah dimiliki
sebelumnya.111
Hu Jintao adalah seorang pemimpin dengan tipe konfusian
sehingga memiliki penekanan kebijakan secara damai. Sebelumnya
konfusianisme merupakan salah satu filsafat yang dominan di Tiongkok.
Konfusianisme menjadi dasar belief yang diyakini oleh individu.112
Artinya, negara yang berdasarkan konfusianisme dipandang anggotanya
sebagai perbedaan namun dalam satu kesatuan. Individu mencapai tujuan
dan harmoni kehidupan dalam konteks sosialnya sendiri. Kualitas
kebenaran, keindahan, keharmonisan dan tatanan masyarakat tertanam
pada hubungan antara keluarga dan negara, dimana penguasa juga dituntut
berperilaku bijak.
Filsafat tentang konfusianisme muncul dalam konsep Masyarakat
Harmonis untuk kebijakan luar negeri Tiongkok. Dalam konsep tersebut
Hu menggabungkan unsur-unsur yang ada dalam Konfusianisme. Istilah
harmoni sendiri membangkitkan nilai-nilai sosial dalam pemerintahan
berdasarkan etika dari konfusianisme yaitu individu yang disiplin serta
kontribusi terhadap tatanan sosial dan stabilitas domestik maupun
internasional.
111 Ibid.112 Ibid.
65
B. Faktor Eksternal
1. Munculnya Dukungan Amerika Serikat Terhadap Taiwan
Amerika Serikat dan Taiwan telah memiliki kemitraan yang kuat
sejak tahun 1949. Mengingat pentingnya Taiwan bagi Amerika Serikat,
kedua negara menandatangani Sino-American Mutual Defense Treaty pada
tahun 1954 untuk membuat sebuah aliansi militer. Sebagai respon dari
normalisasi hubungan Amerika Serikat-Tiongkok, pada tanggal 10 April
1979 Presiden Carter meresmikan Taiwan Relations Act (TRA) yang
menjadi poin penting dalam hubungan Taiwan-Amerika Serikat.113
Meningkatnya dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan membuat
kemajuan besar dalam interaksi bilateral seperti keamanan, perdagangan,
investasi, pertukaran budaya, dan pendidikan.
Selain TRA, Amerika Serikat melalui Presiden Ronald Reagan
menawarkan “six assurances” ke Taiwan pada tahun 1982. Kebijakan
tersebut memastikan bahwa Amerika Serikat: pertama belum sepakat
untuk mengakhiri penjualan senjata ke Taiwan. Kedua belum menyepakati
untuk mengadakan konsultasi dengan Tiongkok terkait penjualan senjata
ke Taiwan. Ketiga tidak akan mengupayakan mediasi hubungan Taiwan
dan Tiongkok. Keempat belum sepakat merevisi Undang-Undang
Hubungan AS-Tiongkok. Kelima tidak mengubah posisi atas kedaulatan
113 Taipei Economic and Cultural Representative Office in the U.S. (TECRO). 2012. Taiwan-U.S.Relations. Diakses darihttp://www.taiwanembassy.org/US/ct.asp?xItem=266456&CtNode=2297&mp=12&xp1=12pada Kamis 11 Maret 2015.
66
Taiwan. Keenam tidak akan menekan Taiwan untuk bernegosiasi dengan
Tiongkok.114
Amerika Serikat menyadari bahwa Taiwan akan menjadi target
agresi berikutnya oleh Uni Soviet. Amerika memerlukan adanya
penambahan kekuatan di kawasan Asia Timur untuk membendung agresi
dari Uni Soviet. Namun, Amerika Serikat menyadari bahwa Selat Taiwan
memiliki sensivitas konflik antara Tiongkok dan Taiwan. Keberpihakan
Amerika Serikat terhadap Tiongkok atau Taiwan akan meningkatkan
kemungkinan berperang. Untuk menghindari hal tersebut Amerika Serikat
menggunakan strategi pendekatan yang netral terhadap hubungan
Amerika-Tiongkok dan Taiwan atau neutralization approach.115
Pendekatan tersebut dilakukan Amerika dikarenakan Amerika tetap ingin
mendukung Taiwan tanpa menimbulkan konflik dengan Tiongkok.
Untuk mencegah Tiongkok melakukan perebutan Taiwan ke Cina
daratan dengan kekerasan, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan
strategic ambiguity dibawah Taiwan Relations Act (TRA) pada tahun
1979.116 TRA memungkinkan Amerika Serikat untuk memberikan
pengakuan secara de facto terhadap Taiwan bukan pengakuan de jure.
Strategic Ambiguity merupakan kebijakan luar negeri Amerika
Serikat terhadap Tiongkok dan Taiwan, kebijakan tersebut memiliki pola
114 Ibid.115 Robert Lincoln Hines. 2013. Change and Continuity in Chinese Strategic Culture-Chinese
Decision Making in The Taiwan Strait. American University. Hal. 33. Penulis megutip dari ShuGuang Zhang. 1992. Deterrence and Strategic Culture: Chinese-American Confrontations,1949-1958. Ithaca: Cornell University Press.
116 Ibid.
67
hubungan antara negara yang bersifat ambigu. Pada satu sisi Amerika
Serikat tengah membangun hubungan baik dengan Tiongkok, hal ini
didukung dengan adanya penerimaan prinsip “Satu Cina” oleh Amerika
Serikat. Akan tetapi di sisi lain Amerika Serikat tetap mempertahankan
hubungan baik dengan Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan
politik dan militer sebagai bentuk kepentingan AS dalam menjadikan
Taiwan sebagai mitranya.117
Kebijakan tersebut memiliki tujuan sebagai penyeimbang dalam
bentuk kemitraan ekonomi dengan Tiongkok sebagai negara dengan
pertumbuhan ekonomi paling besar di dunia sedangkan Taiwan merupakan
bentuk penyeimbang atas penahanan militer terhadap kekuatan Tiongkok
di Asia Timur, bersama sama dengan Taiwan, Jepang, Korea Selatan,
Filipina.118
Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam strategic
ambiguity tersebut didorong oleh faktor ekonomi. Taiwan merupakan
salah satu pembeli terbesar senjata Amerika Serikat di dunia dan
merupakan yang terbesar di Asia. Hal ini dibuktikan oleh penjualan senjata
Amerika Serikat terhadap Taiwan sejak tahun 2010 senilai lebih 120
milyar dolar AS. Penjualan tersebut termasuk akuisisi senjata senilai 5,85
milyar dolar AS yang disepakati oleh pemerintahan Obama pada
117 Muhammad Ciptadi Mamonto. 2010. Analisa Kebijakan Luar Negeri Strategic AmbiguityAmerika Serikat: The US Interest towards the Two China. Malang: Universitas Brawijaya. Hal.2-3.
118 Ibid.
68
September 2011.119 Pada bulan Agustus 2013, Presiden Ma mengatakan
bahwa Taiwan masih belum memiliki kesiapan tempur dan senjata
sehingga akan terus membeli senjata dari Amerika Serikat.120
Amerika Serikat telah menjalin hubungan non-diplomatik dengan
Taiwan sejak tahun 1979. Hubungan non-diplomatik antara AS dan
Taiwan salah satunya adalah dengan terbentuknya TRA (Taiwan
Relations Act) pada April 1979. TRA menyediakan peran bantuan
keamanan yang diperlukan untuk memertahankan Taiwan dari ancaman
Tiongkok.121 Melihat dari sejarah berdirinya, TRA telah memiliki
dukungan kebijakan yang kuat dan kerangka kerja yang fleksibel untuk
pemeliharaan kerjasama dalam bidang pertahanan antara Amerika Serikat
dan Taiwan.
Amerika Serikat turut mendukung masuknya Taiwan ke dalam
organisasi-organisasi internasional. Dengan dukungan Amerika Serikat,
Taiwan dapat terus berpartisipasi dalam beberapa organisasi internasional
seperti World Health Assembly (WHA) sebagai observer pada tahun 2009.
Amerika Serikat juga membantu Taiwan sebagai observer dalam
International Civil Aviation Organization (ICAO). Pada September tahun
2008, Amerika Serikat memiliki misi di PBB untuk membuat pernyataan
akan mendukung Taiwan berpartisipasi dalam badan-badan khusus
119 Grace Kuo. 2013. MND Reaffirms Strong Taiwan-US Defense Ties. Diakses dar ihttp://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=204910&ctNode=445 . pada Sabtu 21 Februari 2015.
120 Taipei Mission in the Republic of Latvia. 2013. Press Release. Diakses dari http://www.roc-taiwan.org/LV/ct.asp?xItem=414777&ctNode=7925&mp=507 pada Sabtu 21 Februari 2015.
121 Shirley A. Kan dan Wayne M. Morrison. 2014. U.S-Taiwan Relationship: Overview of PolicyIssues. Congressional Ressearch Service (CRS). Hal. 4.
69
PBB.122 Amerika Serikat dan Taiwan memiliki kesamaan dalam
keanggotaan di beberapa organisasi internasional seperti World Trade
Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation forum, dan
Asian Development Bank (ADB).123
Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok dan Taiwan
menimbulkan keseimbangan kekuasaan di kawasan Asia Timur. Amerika
Serikat merupakan negara yang berkuasa pasca Perang Dingin berupaya
mempertahankan posisinya di kawasan tersebut, salah satunya melalui
upaya balancing dengan Taiwan dari kekuatan Tiongkok namun, di satu
sisi muncul Tiongkok sebagai kekuatan baru di dalam dinamika sistem
internasional yang akan menghambat kekuatan Amerika Serikat di
kawasan Asia Timur.
Munculnya dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan dalam
bentuk dukungan militer dan politik sebagai penyeimbang dari kekuatan
Tiongkok di Asia Timur. Tiongkok memiliki peran besar dalam
perkembangan ekonomi dan politik sehingga mengancam kekuatan
Amerika Serikat di kawasan tersebut. Selain hal tersebut, Amerika juga
menganggap Taiwan sebagai mitra dalam perdagangan senjata sekaligus
negara yang memerlukan dukungan internasional untuk mengembangkan
demokratisasi dalam negaranya, sehingga sikap proaktif dari Amerika
122 Op. Cit. Taipei Economic and Cultural Representative Office in the U.S. (TECRO).123 U.S. Department of State, Bureau of East Asian and Pacific Affairs Fact Sheet. 2015. U.S.-
Taiwan Relations. Diakses dari http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35855.htm pada Rabu 11Maret 2015.
70
Serikat sebagai negara demokrasi akan membantu perluasan dukungan
terhadap Taiwan.
2. Keanggotaan Taiwan dalam World Trade Organization (WTO)
Organisasi ini didirikan pada tahun 1995, sebelumnya bernama
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang bertujuan
membantu untuk membantu menciptakan sistem perdagangan
internasional yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, WTO juga merupakan organisasi
internasional yang di dalamnya menegosiasikan kesepakatan serta
menyediakan forum untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan.
Mekanisme perdagangan dalam WTO memberikan kerangka hukum dan
kelembagaan untuk pelaksanaan segala bentuk perjanjian dalam
perdagangan.124
Taiwan bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada
tanggal 1 Januari 2002 dengan nama resmi “separate custom territory of
Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu” atau “Chinese Taipei”.125 Pemberian
status keanggotaan ini menyusul diterimanya Tiongkok sebagai anggota
WTO pada tahun 2001. Keanggotaan Taiwan memiliki tujuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas perdagangan dan investasi
dengan anggota WTO lainnya, termasuk dengan Tiongkok. Selain itu
124 WTO. WTO Overview. Diakses darihttps://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm pada Senin, 16 November2015.
125 WTO (World Trade Organization). 2001. WTO successfully concludes negotiations on entry ofthe Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu. 2001. Diakses darihttps://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr244_e.htm Diakses pada Rabu, 30 Desember2015.
71
masuknya Tiongkok dan Taiwan ke dalam WTO diharapkan mampu
memperluas hubungan bilateral dan mengurangi konflik diantara
keduanya.
Sebagai organisasi WTO memiliki tiga pokok prinsip utama yang
mengatur hubungan antar anggotanya yaitu, pertama hubungan pergangan
internasional yang dilakukan antar negara didasarkan atas prinsip
resiproksitas dimana perdagangan tersebut bersifat timbal balik. Kedua
adalah prinsip non-diskriminasi atau disebut juga most favoured nation
(MFN), tidak mengistimewakan suatu Negara saja dan tidak melakukan
diskriminasi terhadap negara lain sesama anggota WTO. Ketiga,
transparansi dimana perlakuan dan kebijakan yang dilaksanakan suatu
negara dapat diketahui oleh mitra dagangnya. negara anggota WTO
diharuskan memberi pengumuman terkait perubahan kebijakan atau aturan
yang berkaitan dengan seluruh perjanjian WTO kepada negara anggota
WTO lainnya.126
Selain prinsip tersebut, yang membedakan WTO dengan organisasi
internasional lainnya yaitu, organisasi ini tidak memerlukan syarat
mengenai status kenegaraan anggotanya. Adanya syarat tersebut
memudahkan Taiwan untuk bergabung ke dalam WTO bersama Tiongkok.
Oleh karena itu, WTO merupakan tempat dimana Taiwan dapat
perpartisipasi penuh dalam suatu organisasi internasional.127 Keanggotaan
Tiongkok dan Taiwan secara bersamaan tersebut memungkinkan adanya
126 Yoan Panjaitan . 2012. Faktor-Faktor yang Menjadikan Cina sebagai Kekuatan Ekonomi Barudi WTO (2001-2009). Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Hal. 3.
127 Steve Charnovitz. 2006. Taiwan WTO Membership and Its International Implications. GeorgeWashington University Law School.
72
suatu forum internasional secara netral bagi kedua pemerintahan tersebut
untuk bertemu, bernegosiasi serta berdiskusi jika diperlukan dalam status
negara yang setara.
Penjelasan di atas didukung oleh adanya syarat keanggotaan WTO
yang diatur dalam perjanjian Marakesh pada pasal XII ayat 1 yaitu128 :
“Any State or separate customs territory possessing full autonomy in the
conduct of its external commercial relations and of the other matters
provided for in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements may
accede to this Agreement, on terms to be agreed between it and the WTO.
Such accession shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade
Agreements annexed there to”. Decisions on accession shall be taken by
the Ministerial Conference. The Ministerial Conference shall approve the
agreement on the terms of accession by a two-thirds majority of the
Members of the WTO.
Terdapat beberapa hal penting yang dapat kita garisbawahi
mengenai keanggotaan dalam WTO, pertama tidak terdapat syarat
mengenai status negara, sebagian dari wilayah kedaulatan suatu negara
dapat memiliki keanggotaan WTO yang terpisah dimana negara tersebut
memiliki otoritas penuh dalam perdagangan luar negeri yang telah diatur
dalam perjanjian WTO. Kedua, seluruh anggota WTO memiliki suara
untuk menerima anggota baru dalam WTO.129
128 World Trade Organization (WTO). Marrakesh Agreement Establishing the World TradeOrganization. Diakses dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm padaJumat, 8 Januari 2016.
129 Op. Cit. Panjaitan. Hal. 86.
73
Karena pasal-pasal terdapat didalam WTO memberi kewajiban
kepada Tiongkok untuk memperlakukan Taiwan dan bagaimana Taiwan
memperlakukan Tiongkok sebagai negara yang setara satu sama lain.
Masuknya Taiwan ke dalam WTO dapat meningkatkan hubungan
ekonomi bahkan politik secara bilateral. Selain itu WTO beserta anggota
lainnya mengakui bahwa Taiwan adalah suatu wilayah pabean yang
terpisah sehingga Taiwan memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan
ekonominya secara internal maupun eksternal dalam kerangka WTO.
Masuknya Taiwan ke dalam WTO akan menunjang pengaruh
politik dan ekonomi untuk memperluas peran Taiwan dalam dunia
internasional. Taiwan memerlukan dukungan internasional untuk
membangun lingkungan kerjasama ekonomi tidak hanya dengan Tiongkok
melainkan dengan negara-negara lainnya. Sebelumnya Taiwan telah
tertinggal jauh dengan Tiongkok yang sudah memulai integrasi ekonomi
dengan negara-negara lainnya seperti ASEAN+3, APEC, dan beberapa
perdagangan bebas dengan 22 negara.130
Kenggotaan Tiongkok dan Taiwan memiliki dampak kepada
perkembangan hubungan yang lebih luas dan terbuka bagi kedua belah
pihak. Perkembangan ini terjadi pada Taiwan dimana terdapat peningkatan
dukungan perdagangan dengan Tiongkok dapat mengubah hubungam
politik. Meskipun kondisi politik antara Tiongkok dengan Taiwan masih
belum memiliki kepastian namun Tiongkok akan menerima adanya
130 The Asia Regional Integration Center (ARIC). Free Trade Agreeements by Country. Diaksesdari https://aric.adb.org/fta-country# pada Jumat, 8 Januari 2016.
74
peningkatan perdagangan dan peluang investasi dalam rangka penguatan
ekonomi serta hubungan dengan Taiwan sehingga Tiongkok dapat
mengarahkan kepada agenda unifikasi.131
Selain Tiongkok harus mematuhi peraturan yang ada dalam WTO,
dampak dari keanggotaan Tiongkok dalam WTO mengarah pada
kesetaraan Taiwan yang juga sebagai negara anggota WTO. Kesetaraan
yang dimaksud adalah jika antar dua anggota WTO memiliki sengketa,
anggota yang berasal dari negara lain dapat bergabung untuk
menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan demikian negara seperti
Amerika Serikat atau Jepang dapat masuk dalam diskusi penyelesaian
sengketa tersebut.132 Hal ini membuktikan bahwa keanggotaan WTO
merupakan perkembangan besar bagi peran Tiongkok dalam dunia
internasional.
131 Ardhy Dinata Sitepu. 2013. Dampak Penandatanganan Economic Cooperation FrameworkAgreement terhadap Economic Security Taiwan pada tahun 2011-2013. Skripsi Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
132 WTO. Understanding WTO. Diakses darihttps://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/tif_e.htm pada Rabu, 30 Desember 2015.
75
BAB IV
POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP UPAYA
KEMERDEKAAN TAIWAN PADA MASA PRESIDEN HU JINTAO
(2003-2013)
A. Kebijakan Tiongkok Terhadap Upaya Kemerdekaan Taiwan Pada
Masa Presiden Hu Jintao (2003-2013)
Kepemimpinan dapat membentuk arah politik suatu negara. Hal ini
sejalan dengan tujuan politik luar negeri dimana pemerintah melalui para
perumus kebijaksanaan nasional seperti pemimpin negara mampu meluaskan
pengaruhnya dengan mengubah atau mempertahankan tindakan dengan
negara lain untuk meningkatkan citra dan kondisi negaranya di masa depan.
Sejalan dengan kebijakan luar negeri yang berupa rencana dan komitmen
membutuhkan pengembangan oleh para pembuat keputusan seperti pemimpin
untuk membina dan mempertahankan situasi internal dan eksternal yang
sejalan dengan orientasi kebijakan luar negeri.133 Sulit untuk menjelaskan
keputusan dari kebijakan luar negeri tanpa mengacu pada sosok pemimpin
serta kesuksesan diplomasi suatu negara dapat bergantung pada keterampilan
dari sosok individu seperti presiden.
Dalam sistem politik domestik Tiongkok, sosok pemimpin negara seperti
Sun Yat-sen, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin dan Hu Jintao
memiliki pengaruh yang dominan dibandingkan dengan lembaga-lembaga
negara yang ada di Tiongkok. Hal ini disebabkan sosok pemimpin tersebut
133 Yanyan M. Yani. Politik Luar Negeri. Diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/politik_luar_negeri.pdf pada Kamis, 2 Juli 2015.
76
sebagai pemimpin partai dan pemimpin suatu negara termasuk di dalamnya
kepemimpinan militer yang menjadi dasar pada stabilitas politik dan
keamanan negara tersebut.134
Pergantian kepemimpinan oleh ‘generasi keempat’ yaitu Presiden
sekaligus sekretaris jenderal PKC Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen
Jiabao. Pergantian kepemimpinan tersebut disertai dengan perubahan
hubungan lintas selat. Politik luar negeri Tiongkok terhadap Taiwan dalam
bentuk undang-undang dan proposal tersebut dilakukan sebagai kemajuan
yang besar karena menawarkan bentuk negosiasi dan kerjasama bagi
Tiongkok dan Taiwan.
Alasan Tiongkok menggunakan politik luar negeri tersebut karena
keduanya telah memiliki kontrol atas masing-masing wilayah. Baik Tiongkok
maupun Taiwan memiliki pemerintahan, militer dan populasi. Keduanya pun
telah bertindak secara independen dalam menangani isu domestik dan
internasional dengan demikian keduanya telah terpecah menjadi entitas
politik yang berbeda. Untuk alasan tersebut Tiongkok dan Taiwan dua aktor
independen dan Tiongkok mengupayakan unifikasi terhadap Taiwan agar
menjadi bagian dari wilayahnya.
Berikut akan dibahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan
Tiongkok untuk mencegah upaya kemerdekaan Taiwan pada masa Presiden
Hu Jintao seperti Undang-Undang Anti Pemisahan, Enam Proposal Hu Jintao
dan Kerjasama Ekonomi dalam kerangka ECFA. Selain itu juga akan dibahas
134Op. Cit. Swaine. Hal. 3.
77
mengenai respon Taiwan mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
oleh Tiongkok pada masa Presiden Chen Shui-bian pada tahun 2002-2008
dan Presiden Ma Ying-jeou pada tahun 2008-2012.
1. Anti-Secession Law (Undang-Undang Anti Pemisahan)
Undang-undang anti pemisahan dapat dipahami sebagai puncak
kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan dalam mendapatkan dukungan
internasional masa Presiden Chen Shui-bian. Kemenangan Presiden Chen
Shui Bian pada tanggal 18 Maret 2000 dengan suara sebanyak 39,3 persen
mengubah pola politik domestik Taiwan dan hubungan antara Tiongkok
dengan Taiwan. Kemenangan ini juga menandai berakhirnya pemerintahan
Kuomintang atas Taiwan selama 50 tahun.135
Chen Shui-bian berasal dari Partai Progresif Demokrat yang
cenderung mendukung kemerdekaan Taiwan. Kemenangan Presiden Chen
menjadi tantangan bagi hubungan Tiongkok-Taiwan. Tiongkok merasa
terancam oleh kemenangan partai yang mendukung demokratisasi serta
kemerdekaan bagi Taiwan.136 Perkembangan demokratisasi tersebut akan
mengubah pandangan penduduk Taiwan terhadap hubungan lintas selat
dan meningkatkan rasa nasionalisme.
DPP telah menjelaskan sikapnya dalam mengelola hubungan
dengan Tiongkok sejak piagam partai pada tahun 1991 yaitu kinerja
partai bertujuan untuk meraih kemerdekaan Taiwan. Pada tanggal 20
135 Gerrit W. Gong. China-Taiwan Relations: Cross-Strait Cross-Fire. Center for Strategic andInternational Studies (CSIS). Diakses darihttp://csis.org/files/media/csis/pubs/0001qchina_taiwan.pdf Pada Minggu, 5 Juli 2015.
136 Vincent Wei. 2002. "The Chen Shui-Bian Administrations Mainland Policy: Toward a ModusVivendi or Continued Stalemate?". American Asian Review Vol. 20, no. 3. Hal . 91-124.
78
Oktober 2001, kongres partai DPP memutuskan untuk mengangkat
resolusi (Taiwan Qiantu Jueywiyen) untuk mengelola kebijakan terhadap
Tiongkok.137 Resolusi tersebut menjelaskan bahwa DPP menganggap
Taiwan sebagai negara independen yang berdaulat dan tidak perlu
menyatakan kemerdekaan.
Sebelumnya Taiwan berada dibawah pemerintahan Kuomintang
yang mendukung kebijakan ‘Satu Cina’ serta mendukung adanya
reunifikasi dengan Tiongkok. Kuomintang atau Partai Nasionalis Cina
merupakan partai politik di Taiwan bersama dengan “People First Party
(PFP) dan Chinese New Party” (CNP) membentuk koalisi Pan-Blue yang
mendukung unifikasi dengan Tiongkok serta menerima prinsip satu
Tiongkok.138 Namun DPP yang merupakan pihak oposisi memunculkan
pandangan berbeda mengenai kemerdekaan Taiwan. Pandangan ini sesuai
dengan tiga prinsip DPP yaitu demokrasi, perdamaian dan kemakmuran.
Prinsip pertama mengenai demokrasi, bahwa status Taiwan sebagai negara
yang berdaulat hanya dapat diubah melalui proses demokrasi dengan
persetujuan Taiwan tanpa ada ketentuan dari negara lain.139
Dalam rangka menanggapi situasi baru yang terjadi, DPP terus
mendorong reformasi secara struktural di lembaga-lembaga negara agar
dapat menindaklanjuti status Taiwan. DPP pun menentukan serangkaian
137 Mikael Mattlin. 2004. Same Content, Different Wrapping: Cross-Strait Policy Under DPPRule. Diakses dari http://chinaperspectives.revues.org/436 Pada Rabu, 14 Oktober 2015.
138 Kuomintang Official Website. Introduction of the Party. Diakses darihttp://www1.kmt.org.tw/english/page.aspx?type=para&mnum=105 pada Kamis 15 Oktober2015.
139 Chen Yuan Tung. 2005. The Evolution and Prospects of Cross-Strait Relations in the ChenShui-Bian Administration. Diakses dari http://www3.nccu.edu.tw/~ctung/Documents/W-B-a-17.doc Pada Rabu, 14 Oktober 2015.
79
resolusi bagi masa depan Taiwan yang disebut sebagai proklamasi yaitu
pertama, Taiwan merupakan negara berdaulat dan independen. Setiap
perubahan terhadap status Taiwan harus ditentukan oleh pemungutan
suara. Kedua Taiwan bukan bagian dari Tiongkok. Ketiga, Taiwan harus
memperluas perannya dalam dunia internasional serta mencari pengakuan
internasional. Keempat, Taiwan dan Tiongkok harus terlibat dalam dialog
yang komprehesif guna mencari solusi dan mengembangkan kerjasama
ekonomi jangka panjang menuju perdamaian.140
Kemenangan Presiden Chen Shui Bian dapat memicu konflik
antara Tiongkok dan Taiwan kembali setelah pemilu tahun 1988 yang
dimenangkan oleh Lee Teng-hui sehingga Tiongkok mengeluarkan
undang-undang anti pemisahan yang telah dirumuskan sejak akhir
desember 2004. Lalu pada tanggal 14 Maret 2005 undang-undang tersebut
resmi disahkan lewat Kongres Rakyat Nasional. Alasan undang-undang
tersebut disahkan karena pertimbangan Tiongkok atas berlanjutnya proses
yang mendukung kemerdekaan Taiwan sejak masa pemerintahan Presiden
Chen Shui-bian.
Undang-undang anti pemisahan ini terdiri dari 10 artikel, setiap
artikel berisikan rangkuman kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan. UU ini
dirancang mempromosikan unifikasi secara damai, menjaga perdamaian
dan stabilitas Selat Taiwan serta menjaga kedaulatan Tiongkok.141
140 Taiwandc.org, DPP Resolution for Taiwan Future. Diakses dari http://www.taiwandc.org/nws-9920.htm pada Rabu, 28 Oktober 2015.
141 Zou Keyuan. 2005. Governing the Taiwan Issue in Accordance with Law: An Essay on China’sAnti-Secession Law. Chinese Journal of International Law Vol. 4 No. 2. Hal. 456.
80
Beberapa isi undang-undang tersebut memiliki tema ganda
mengenai pengelolaan Tiongkok untuk membawa Taiwan menuju
reunifikasi secara damai. Sebagian lagi menjelaskan prinsip yang diambil
Tiongkok dalam bentuk dialog dan komunikasi antar selat. Pasal pertama
menjelaskan tujuan Tiongkok dalam pengesahan undang-undang tersebut
adalah untuk menentang dan membela kepentingan nasional, kedaulatan
serta keutuhan wilayah Tiongkok. Pasal kedua mendefinisikan status quo
lintas selat. Pasal ketiga menjelaskan bahwa Taiwan merupakan warisan
Perang Saudara.
Pasal keempat mengajak semua kalangan di Tiongkok dan Taiwan
untuk berjuang menuju persatuan nasional. Pasal kelima menyatakan
bahwa prinsip satu Tiongkok merupakan dasar untuk reunifikasi secara
damai. Pasal keenam memberikan perincian langkah-langkah Tiongkok
dalam mengelola hubungan yang damai dengan Taiwan seperti
memfasilitasi pertukaran ekonomi, sosial, ilmu dan budaya. Pasal ketujuh
menjelaskan tentang adanya negosiasi dengan Taiwan untuk topik-topik
yang mencakup penyelesaian konflik lintas selat, partisipasi Taiwan
dalam dunia internasional dan pembangunan institusi yang akan
memfasilitasi unifikasi.142
Legitimasi dalam undang-undang ini dikarenakan prinsip satu
Tiongkok yang tetap dipertahankan oleh Tiongkok dalam setiap
kebijakannya terhadap Taiwan. Tingkatan undang-undang ini setara
dengan undang-undang yang pernah dikeluarkan Tiongkok terhadap
142 Chunjuan N. Wei. China’s Anti Secession Law and Hu Jintao’s Taiwan Policy. Yale Journal ofInternational Affairs. Hal. 16.
81
wilayah Hongkong dan Makau. Undang-undang ini bukan bersifat seperti
hukum yang melegalkan perang seperti yang diketahui oleh Taiwan.143
Undang-undang ini akan bersifat damai jika Taiwan tetap mempertahan
status quo dan menghindari batas-batas yang telah ditetapkan Tiongkok.
Tiongkok pun mendapatkan dukungan dari dunia internasional
dalam pengesahan undang-undang tersebut. Dukungan yang datang dari
berbagai belahan dunia meliputi Uni Afrika yang menegaskan dukungan
dan prinsipnya pada kebijakan satu Tiongkok.144 Uni Eropa dan
Luxemburg mendukung undang-undang anti pemisahan ini dengan
harapan konflik dengan Taiwan dapat diselesaikan secara damai. Rusia,
Belarus, Pakistan, Suriah, Macedonia, dan Venezuela menyuarakan hal
yang sama untuk mendukung pengesahan undang-undang anti pemisahan
terhadap Taiwan. Undang-undang ini dianggap penting untuk menjaga
kedaulatan dan integritas teritorial serta mempromosikan masa depan
pembangunan Tiongkok.
2. Enam Proposal Hu Jintao Terhadap Taiwan
Enam proposal yang diajukan oleh Hu Jintao dalam
pengembangan hubungan lintas selat merupakan kelanjutan dari empat
proposal sebelumnya yang dijadikan pedoman pula untuk mengelola
hubungan dengan pihak Taiwan. Empat proposal tersebut ditetapkan saat
Presiden Hu menghadiri diskusi panel bersama anggota badan penasehat
143Anti-secession Law Not a 'War Mobilization Order'http://www.china.org.cn/english/government/121749.htm Diakses pada Sabtu, 10 Oktober 2015.
144 International Community Supports China’s Anti Seccesion Law. 2005 diakes darihttp://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-03/16/content_425454.htm pada Minggu, 11Oktober 2015.
82
Tiongkok mewakili wilayah Taiwan pada bulan Maret 2005. Empat
proposal yang diajukan oleh Hu Jintao adalah sebagai berikut:
Pertama, tetap berpegang pada prinsip satu Cina. Prinsip ini
merupakan landasan utama dalam mengembangkan hubungan lintas selat
dan unifikasi secara damai. Tiongkok menerima perundingan serta dialog
selama Taiwan tidak mengabaikan prinsip satu Cina baik secara
perorangan maupun partai politik. Dialog tersebut dapat melebar pada
topik seputar kerjasama militer, status politik Taiwan, kerangka hubungan
damai serta stabilitas lintas selat.145
Kedua, tidak akan menyerah untuk mencari upaya unifikasi secara
damai. Sejumlah 1,3 miliar masyarakat Tiongkok termasuk pula Taiwan
sangat mengharapkan perdamaian serta penyelesaian masalah atas konflik
lintas selat. Unifikasi tidak berarti bahwa satu sisi akan mengambil
wilayah yang lain secara paksa tetapi kedua belah pihak mengupayakan
berunding secara damai menuju tujuan tersebut. Ketiga, tidak akan
mengubah prinsip dan menggantikan harapan orang-orang Taiwan. Orang-
orang di Taiwan adalah saudara sedarah dan mereka juga memiliki peran
penting dalam mengembangkan hubungan lintas selat.
Keempat, tidak akan memberikan kompromi terhadap kegiatan
separatis seperti Taidu (kemerdekaan Taiwan). Menjaga kedaulatan serta
keutuhan wilayah merupakan kepentingan inti dari Tiongkok. Pihak
Tiongkok berharap otoritas di Taiwan dapat memenuhi kebijakan “five no”
serta memenuhi komitmennya untuk tidak mencari legalisasi bagi
145 Four-point Guidelines on Cross-Straits Relations Set Forth by President Hu. 2005. Diaksesdari http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm pada sabtu, 17 Oktober 2015.
83
kemerdekaan Taiwan baik melalui reformasi maupun konstitusi. Presiden
Hu menggunakan kesempatannya untuk memberikan pandangan seorang
pemimpin bagi masa depan hubungan lintas selat. Pandangan atau prinsip
Tiongkok yang dituangkan dalam empat proposal sebagai tanggapan atas
tantangan separatis di bawah Presiden Chen Shui-bian. Proposal ini
menggambarkan wujud ketulusan Tiongkok dan keinginan baik dalam
menjaga perdamaian lintas selat.146
Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2008, Presiden Hu Jintao
menyampaikan pidato yang berjudul “promosi pengembangan hubungan
damai lintas selat dan pencapaian revitalisasi untuk bangsa Tiongkok”.147
Dalam pidato tersebut Presiden Hu meringkas enam poin pendekatan
kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan yaitu :
Pertama, penegasan prinsip satu Tiongkok dan meningkatkan
kepercayaan politik lintas selat. Meski Taiwan dan Tiongkok belum
bersatu kembali sejak tahun 1949, keadaan tersebut didukung dengan
adanya “antagonisme politik”. 148 Untuk dapat menyatukan kedua wilayah
tersebut, baik Tiongkok maupun Taiwan harus mengembangkan
146 President Hu's "four-point" speech shows utmost sincerity toward Taiwan. Diakses darihttp://en.people.cn/200503/08/eng20050308_176059.html pada Sabtu, 17 Oktober 2015.
147 Yang Kai-huang. 2009. “Hu Six Points amid the Interaction between KMT and CCP”.Diakses dari http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/04115463073.pdf pada Kamis, 28Januari 2016.
148 Taiwan Affairs Office of the State Council PRC. 2008. Let Us Join Hands to Promote thePeaceful Development of Cross-Strait Relations and Strive with a United Resolve for the GreatRejuvenation of the Chinese Nation. Speech at the Forum Marking the 30th Anniversary of theIssuance of the Message to Compatriots in Taiwan. Diakses darihttp://www.gwytb.gov.cn/en/Special/Hu/201103/t20110322_1794707.htm pada Sabtu, 17Oktober 2015.
84
pemahaman prinsip satu Tiongkok agar dapat membangun kembali
kepercayaan politik satu sama lain.
Kedua, memajukan kerjasama ekonomi dan mempromosikan
pembangunan. Kedua sisi selat harus terlibat dalam kerjasama ekonomi
yang luas, memperluas tiga hubungan langsung, meningkatkan
kepentingan bersama, membentuk hubungan dekat untuk mencapai situasi
yang saling menguntungkan. Pihak Tiongkok akan terus menyambut dan
mendukung investasi dari perusahaan Taiwan untuk mengembangkan
bisnis mereka.
Ketiga, untuk mempromosikan budaya Tiongkok dan memperkuat
ikatan spiritual. Budaya Tiongkok memiliki sejarah panjang yang dapat
menjadi aset bagi masyarakat di kedua sisi selat. Budaya dan sejarah dapat
menjadi ikatan emosional yang kuat bagi masyarakat. Keempat,
memperkuat kunjungan dan pertukaran dua arah antara Tiongkok maupun
Taiwan. Kunjungan tersebut dapat berupa pariwisata, dialog, budaya, atau
pendidikan. Kelima, untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengadakan
konsultasi tentang urusan eksternal. Pihak Tiongkok secara konsisten
berkomitmen untuk menjaga hak-hak hukum dan kepentingan rekan-rekan
Taiwan yang ada diluar negeri. Keenam, untuk mengakhiri permusuhan
dan mencapai kesepakatan damai.
Beberapa proposal yang diajukan oleh Hu Jintao berfungsi sebagai
cetak biru untuk mengarahkan pembangunan damai di lintas selat.
Proposal tersebut juga sebagai bentuk normalisasi hubungan lintas selat
pada pemerintahan Hu Jintao tanpa dibatasi oleh isu politik dan militer.
85
Beberapa poin penting dalam proposal yang diajukan oleh Hu Jintao yaitu,
pertama memperkuat kepercayaan politik antara Tiongkok dan Taiwan.
Kedua, membahas mekanisme kerjasama ekonomi lintas selat. Ketiga
memperluas pertukaran budaya dan pendidikan. Keempat, penyelesaian
damai tentang partisipasi Taiwan dalam dunia internasional.
3. Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)
Globalisasi ekonomi memainkan peran penting dalam
mempromosikan hubungan lintas selat sampai pada penandatanganan
ECFA. Tujuan dari penandatanganan ECFA adalah untuk menikmati
kerjasama ekonomi dan pembangunan tanpa harus dibatasi oleh kedaulatan
politik. Selain melewati kerangka ekonomi dalam ECFA, Tiongkok dan
Taiwan memiliki organisasi non-pemerintah untuk melakukan
perundingan lintas selat. Dari pihak Taiwan adalah Straits Exchange
Foundation (SEF) yang didirikan pada tahun 1991. Sedangkan di pihak
Tiongkok terdapat Association for Relations Across the Taiwan Straits
(ARATS) yang bertindak sebagai wakil untuk perundingan lintas selat.
Perjanjian ECFA antara Tiongkok dan Taiwan merupakan hasil
dari 37 kali pertemuan antara SEF dan ARATS yang dimulai dari tahun
1991. Hambatan yang muncul dari proses negosiasi tersebut dikaitkan
dengan isu politik dan keamanan nasional kedua negara. Sebelumnya
perjanjian perdagangan perdagangan antara Tiongkok dan Taiwan
menyerupai model Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA),
model perjanjian perdagangan yang digunakan antara Tiongkok dengan
Hongkong dan Macau. Model ini bertentangan dengan Taiwan karena
86
Tiongkok akan menganggap Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok sama
seperti Hongkong dan Macau.
ECFA merupakan suatu bentuk perjanjian perdagangan bebas
sementara antara Tiongkok dan Taiwan. Meskipun Tiongkok dan Taiwan
telah menjadi anggota WTO, keduanya masih memiliki kendala dalam
menantangani suatu perjanjian perdagangan karena konflik politik yang
terjadi antara keduanya. Dengan adanya ECFA tersebut dapat
memungkinkan keduanya untuk bekerjasama dari segi ekonomi sehingga
memberi kemudahan dalam mengatur agenda diskusi dan negosiasi di
masa depan.149 Karena masalah politik antara keduanya, ECFA diharapkan
mampu menjadi suatu tahap untuk mewujudkan perdagangan bebas yang
lebih komprehensif sehingga dapat mewujudkan hubungan lintas selat
secara damai.
ECFA secara resmi ditandatangani di Chongqing pada 29 Juni
2010. Kerjasama ekonomi tersebut akan menawarkan potensi yang lebih
besar bagi hubungan Tiongkok dan Taiwan. Potensi tersebut terlihat dari
adanya pengurangan hambatan dalam perdagangan secara bertahap.
Mekanisme dan Konten ECFA dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari
pendahuluan, prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam kerjasama
ECFA, aturan perdgangan dan investasi, kerjasama ekonomi, daftar Early
149 Chi-An Chou. 2010. A Two-Edged Word: Economic Cooperation Framework AgrementBetween The Republic of China and The People’s Republic of China. International Law &Management Review Vol.6. Diakses darihttp://www.law2.byu.edu/ilmr/articles/spring_2010/BYU_ILMR_spring_2010_1_A%20Two-Edged%20Sword.pdf pada Senin, 4 Januari 2016.
87
Harvest dan aturan tambahan lainnya. Naskah ECFA memiliki lima
lampiran yang mencakup daftar produk serta pengaturan pengurangan
biaya yang disepakati dalam program Early Harvest untuk perdagangan
barang, aturan-aturan untuk produk barang yang termasuk dalam program
Early Harvest, mekanisme perlindungan antara kedua belah pihak yang
berlaku bagi perdagangan barang yang termasuk dalam program Early
Harvest, sektor dan langkah bagi liberalisasi dibawah program Early
Harvest untuk perdagangan jasa, definisi penyedia jasa untuk masuk ke
sektor yang telah diliberalisasi melalui program Early Harvest.
Pertama, ketentuan umum yang menjelaskan tentang dasar dan
tujuan ECFA serta mekanisme kerjasama ekonomi serta liberalisasi
perdagangan. Kedua perdagangan dan liberalisasi investasi yang
menjelaskan tentang rangkaian dan jadwal negosiasi perdagangan yang
meliputi barang, jasa, serta investasi. Ketiga, memasukkan kerjasama
industri, kepabeanan, fasilitas perdagangan, ijin impor dan keamanan
pangan. Keempat, Early Harvest mengidentifikasi barang dan jasa yang
akan memenuhi persyaratan untuk penurunan tarif awal dan akses pasar.
Kelima, langkah-langkah untuk mendukung keamanan pangan,
mekanisme penyelesaian konflik dan pembentukan badan eksekutif.150
150 Op. Cit. Brown. Hal. 44.
88
Tabel 2. Rangkuman Bab, Pasal, dan Lampiran yang tercantum dalamEconomic Cooperation Framework Agreement (ECFA)151
Chapter ClausePreambleChapter 1 General Principles Article 1. Objectives
Article 2. Cooperation MeasuresChapter 2 Trade and Investment Article 3. Trade in food
Article 4. Trade in businessArticle 5. Investment
Chapter 3 Economic Cooperation Article 6. Economic cooperationChapter 4 Early Harvest Article 7. Early harvest trade in food
Article 8. Early harvest trade in serviceChapter 5 Other Article 9. Exceptions
Article 10. Dispute settlementArticle 11. Institution arrangementArticle 12. Document FormatsArticle 13. Annexes and Subsequent AgreementsArticle 14. AmendmentsArticle 15. Entry into forceArticle 16. Termination
Lampiran dalam ECFAAnnex 1 Product list and tariff reduction arrangements under
the early harvest for trade in goodsAnnex II Provisional rules of origin applicable to products
under the early harvest for trade in goodsAnnex III Safeguard Measures between the two parties
applicable to products under the early harvest fortrade in goods
Annex IV Sectors and liberalization measures under the earlyharvest for trade in services
Annex V Definitions of service suppliers applicable to sectorsand liberalization measures under the early harvestfor trade in services
Berdasarkan tabel 2, konten ECFA berisi kesepakatan bagi
keduabelah pihak untuk menguatkan hubungan ekonomi serta
perdagangan lintas selat menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam
WTO yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi antara Tiongkok
Taiwan. Prinsip-prinsip meliputi aspek kesetaraan dan timbal balik. Selain
151 Tzu-Chun Sheng dan Shu-Hui Lan. 2014. Is Economic Cooperation Framework Agreement theThreshold of Sustainable Development for Taiwan’s Industries?. International Journal ofEconomics and Finance Vol. 6. Canadian Center of Science and Education. Hal. 44.
89
itu juga ECFA juga bertujuan untuk memperomosikan liberalisasi barang,
jasa dan investasi beserta mekanismenya. Pada bab tiga bahkan ECFA
meluaskan kerjasamanya pada perlindungan hak kekayan intelektual
(HKI), kerjasama pada sektor keuangan, bea cukai, industry, e-commerce,
kerjasama level usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).152
Pada bab empat menjelaskan tentang program early harvest (panen
awal), pada program ini keduabelah pihak sepakat untuk mengutamakan
pengurangan tarif pada produk yang telah ditentukan. Dalam program
tersebut Tiongkok akan menurunkan tarif pada 539 item yang akan di
ekspor ke Taiwan sedangkan Taiwan akan menurukan tarif pada 267 item
yang akan di ekspor ke Tiongkok. Item yang sudah disepakati dalam
program early harvest meliputi sektor pertanian, manufaktur, tekstil,
petrokimia, transportasi.153 Pada bab lima menjelaskan mengenai aturan-
aturan lain diluar konteks perdagangan seperti langkah-langkah pendukung
dalam mengontrol keamanan pangan, mekanisme penyelesaian sengketa,
badan eksekutif, amandemen, tanggal berlaku, dan sebagainya.
Hasil dari keikutsertaan Tiongkok dalam integrasi ekonomi dunia,
perdagangan antara Tiongkok dan Taiwan pun ikut berkembang dari US$
44,67 milyar dolar pada tahun 2002 menjadi US$129,22 miliar dolar pada
tahun 2008.154 Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2009 akibat
dari krisis keuangan global, keduanya berusaha mempertahankan
152 Disadur oleh penulis dari Economic Cooperation Framework Agreement. Diakses darihttp://www.mac.gov.tw/public/data/051116322071.pdf pada kamis, 7 Januari 2016.
153 Annex I Product List and Tariff Reduction Arrangementshttp://www.ecfa.org.tw/EcfaAttachment/ECFADoc/Annex%20I%20Product%20List%20and%20Tariff%20Reduction%20Arrangements.pdf
154 Op. Cit. Sheng dan Lan. Hal. 39-40.
90
pedagangan bilateralnya. Hasilnya dari tahun 2010-2012 keduanya tetap
mempertahankan peningkatan perdagangan sehingga tetap memberikan
lingkungan kerjasama ekonomi yang stabil semenjak penandatanganan
ECFA.
Tabel 3. Data Statistik Perdagangan Antara Taiwan dan Tiongkok dariTahun 2002-2012155
Tahun Ekspor Tiongkok denganTaiwan (dalam milyarUSD)
Impor Tiongkok denganTaiwan (dalam milyarUSD)
TotalPerdagangan(dalam milyarUSD)
2002 6.59 38.08 44.672003 9.00 49.36 58.362004 13.55 64.78 78.322005 16.55 74.68 91.232006 20.74 87.11 107.842007 23.46 101.02 124.482008 25.88 103.34 129.222009 20.51 85.72 106.232010 29.68 115.69 145.372011 35.11 124.92 160.032012 36.78 132.18 168.96
Hasil dari data tersebut menjelaskan bahwa perdagangan antara
Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2003-2013 yaitu pada masa
pemerintahan Hu Jintao mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dilihat
dari data diatas terjadi penurunan jumlah perdagangan Tiongkok dengan
Taiwan sebesar USD 22,99 milyar. Penurunan tersebut terjadi karena
adanya krisis ekonomi global yang disebabkan oleh krisis finansial di
Amerika Serikat. Krisis finansial secara global tersebut membuat
155 Tzu-Chun Sheng dan Shu-Hui Lan. 2014. Is Economic Cooperation Framework Agreement theThreshold of Sustainable Development for Taiwan’s Industries?. International Journal ofEconomics and Finance Vol. 6. Canadian Center of Science and Education. Hal. 39.
91
pertumbuhan Tiongkok turun sebesar 20% atau senilai 11.7 milyar US
Dolar.156
Dari penjelasan diatas, walaupun Tiongkok tidak mendapat
keuntungan sebesar Taiwan dalam penandatanganan ECFA Tiongkok
memiliki beberapa kepentingan terhadap ECFA selain motif ekonomi
yaitu, sebagai bentuk dari strategi soft power Tiongkok dalam memperluas
pengaruhnya secara bilateral dan internasional. Soft power tersebut
meliputi menggabungkan perjanjian perdagangan dengan rencana
pembangunan antara Tiongkok dengan Taiwan. Selain itu juga ECFA
merupakan salah satu usaha Tiongkok untuk mencapai tujuan unifikasi
dengan Taiwan secara damai. Hal ini sejalan dengan politik luar negeri
Tiongkok yang disebut peaceful development atau pembangunan secara
damai serta harmonius world.
Kedua konsep politik luar negeri Tiongkok tersebut didasari oleh
lima prinsip yang disebut peaceful coexistance atau koeksistensi damai
yang pernah dilakukan oleh perdana menteri Zhou Enlai pada tahun
1950an. Lima koeksistensi dama tersebut mencakup penghormatan atas
kedaulatan, prinsip non-agresi dan intervensi, persamaan derajat serta
memberlakukan koeksistensi damai dengan negara-negara yang berbeda
sistem sosial. Pembangunan damai yang dulu telah dilakukan oleh
Tiongkok akan tetap berlanjut hingga pemerintahan Hu Jintao. Kebijakan
156 Kompas. 2009. Volume Perdagangan Indonesia-China Terimbas Krisis. Diakses darihttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/08/24/11435164/volume.perdagangan.indonesia-china.terimbas.krisis pada Senin, 4 Januari 2016.
92
tersebut termasuk upaya pengembangan Tiongkok melalui pertumbuhan
ekonomi serta mencapai perdamaian dunia. Sedangkan harmonious world
adalah bagian dari strategi Presiden Hu untuk pembangunan Tiongkok
yang lebih harmonis dengan menekankan bagaimana menangani
perbedaan dalam suatu masalah bagi dengan sesama negara tetangga
maupun msyarakat internasional. Meninggalkan cara-cara peperangan dan
menunjukkan toleransi yang tinggi.
Kebijakan yang telah dijelaskan diatas dianggap efektif untuk
mengurangi konflik dengan Taiwan terkecuali dalam hal ini Taiwan
memancing Tiongkok untuk menggunakan cara-cara yang tegas dalam
meredam upaya kemerdekan Taiwan. Pada awal masa pemerintahan Hu
Jintao, Tiongkok telah dihadapkan pada kondisi yang cukup sulit karena
Taiwan semakin bertindak agresif dengan mengadakan pemilihan umum
kedua kalinya setelah sebelumnya dilakukan oleh Presiden Lee Teng-hui
sehingga Tiongkok mengeluarkan kebijakan ASL untuk meredam Taiwan.
Selain itu juga Tiongkok juga bersikap kooperatif dengan mengajukan
enam proposal damai dan menandatangani kerjasama ekonomi dalam
bentuk ECFA guna mewujudkan reunifikasi damai dengan Taiwan.
B. Respon Taiwan Terhadap Kebijakan Tiongkok Pada Masa Presiden Hu
Jintao (2003-2013)
Sejak tahun 2003, pada masa kepemimpinan Hu Jintao, pandangan
Tiongkok mengenai isu Taiwan mengalami perubahan dibandingkan dengan
kepemimpinan Jiang Zemin. Perubahan tersebut memberikan kontribusi yang
relatif stabil dan damai dalam hubungan lintas selat selama tahun 2003-2013.
93
Walaupun sempat mengalami sedikit ketegangan pada tahun 2000 yaitu
ketika Taiwan dipimpin oleh Chen Shui-bian dari partai DPP sehingga
menyebabkan kebuntuan dalam bidang politik, tetapi pertukaran ekonomi,
budaya dan lainnya terus berkembang dengan pesat.
Selama masa pemerintahan Hu Jintao dari tahun 2003-2013, terdapat
dua masa pemerintahan di Taiwan yaitu Chen Shui-bian dan Ma Ying-jeou.
Masing-masing pemimpin tersebut memberikan respon yang berbeda
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Selama periode 2000-
2008 Taiwan dipimpin oleh Chen Shui-bian yang berasal dari partai DPP,
Taiwan menekan Tiongkok dengan mengadakan pemilihan umum.
Ketegangan politik ini dapat diatasi sementara dengan adanya kebijakan Five
No’s, Three mini Links sehingga resiko terjadinya perang dengan Tiongkok
dapat dihindari.
Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Ma Ying-Jeou, Taiwan
memiliki konsistensi pengembangan hubungan lintas-selat yang damai.
Perkembangan hubungan lintas-selat yang damai ini ditandai dengan adanya
promosi kerjasama ekonomi dalam kerangka ECFA dan peningkatan
hubungan politik dalam kerangka kebijakan flexible diplomacy.
1. Kebijakan Taiwan Terhadap Tiongkok Pada Masa Presiden Chen
Shui-Bian (2000-2008)
Respon Taiwan terhadap politik luar negeri Tiongkok dapat
dipengaruhi dengan perkembangan politik domestik Taiwan.
Perkembangan tersebut ditandai oleh adanya perubahan kebijakan sebagai
94
respon dalam menanggapi konflik dengan Tiongkok. Terkait kebijakan
Taiwan tersebut bergantung pada partai yang memenangkan pemilihan
presiden. Keseimbangan politik dalam negeri Taiwan memiliki dampak
terhadap respon yang dikeluarkan terhadap Tiongkok.
Setiap Presiden memainkan peran penting dalam menangani konflik
dengan Tiongkok. Masing-masing presiden memiliki karakteristik serta
latar belakang dalam pembuatan suatu kebijakan. Latar belakang Presiden
Chen yang memenangkan pemilihan umum pada tanggal 17 Maret 2000,
berasal dari Partai Demokratik Progresif (DPP). Partai DPP memiliki
acuan serta rancangan yang disahkan dalam kongres nasional pertama
pada tahun 1986 untuk menetapkan bahwa pembentukan Taiwan sebagai
negara yang berdaulat dan independen sebagai tujuan partai.157
Sebagian besar anggota DPP memiliki identitas dan rasa
nasionalisme yang kuat dibandingkan dengan partai Kuomintang
(KMT).158 Kemenangan Chen Shui-bian membawa tantangan baru bagi
hubungan lintas selat. Kemenangan Chen Shui-bian didukung oleh latar
belakangnya yang merupakan penduduk asli Taiwan kedua yang menjadi
Presiden Taiwan setelah Presiden Lee Teng-hui sehingga presiden Chen
memberikan semangat baru bagi masyarakat Taiwan yang mendukung
kemerdekaan.
Kemunculan Partai DPP dimulai pada tahun 1990 merupakan salah
satu faktor yang memisahkan dua partai politik yang ada di Taiwan yaitu
157 Mumin Chen. 2005. Prosperity vs. Security: National Security of Taiwan 2000-2004. TaiwanInternational Studies Quarterly, Vol. 1, No. 2, Hal. 126.
158 Hung-Chin Wei. 1999. Taiwan’s Democratic Progressive Party and its Mainland China Policy.Durham Theses. Durham University.
95
Kuomintang (Pan Blue) yang bergabung dengan New Party (NP), People
First Party (PFP) yang mendukung adanya unifikasi dengan Tiongkok
sedangkan Democratic Progressive Party (Pan Green) yang bergabung
dengan Taiwanese Independence Party (TAIP) dan Taiwan Solidarity
Union (TSU) yang mendukung kemerdekaan Taiwan.159
Chen Shui-bian yang didukung oleh partai DPP tersebut membuat
hubungan Tiongkok dan Taiwan menjadi rawan konflik. Hal ini terjadi
setelah Presiden Chen memenangkan pemilihan presiden kedua pada tahun
2004. Chen Shui-bian tetap gencar untuk mempromosikan kemerdekaan
Taiwan. Pemerintahan Chen diharapkan lebih menyesuaikan kebijakannya
dengan Tiongkok, jika Presiden Chen terus melanjutkan kebijakannya
tersebut maka pihak Taiwan akan sulit untuk membawa Tiongkok ke
dalam proses negosiasi di masa yang akan datang.
Melihat latar belakang Presiden Chen Shui-bian, gambaran umum
kebijakan yang dikeluarkan dalam merespon kebijakan Tiongkok pada
masa Hu Jintao bertujuan untuk mendukung kemerdekaan Taiwan dan
memperoleh dukungan untuk Taiwan dalam dunia internasional. Agenda
politik DPP meliputi pembangunan identitas nasional Taiwan yang
terpisah dari Tiongkok. Selama masa pemerintahan Chen Shui-bian,
kebijakan yang dikeluarkan berupa penguatan identitas nasional Taiwan di
mata internasional.
159 Fuh Sheng Hsieh. 2005. Etnicity, National Identity, and Domestic Politics in Taiwan. Journal ofAsian and African Studies. London: Sage Publication. Hal 14-15. Diakses darihttp://jas.sagepub.com/content/40/1-2/13.full.pdf pada Rabu, 26 Maret 2015.
96
Untuk itu pihak Taiwan memberikan kebijakan penahan untuk
mengurangi ketegangan dengan Tiongkok. Kebijakan yang berbentuk
penahanan tersebut seperti kebijakan Five No’s dimana Taiwan tidak akan
memproklamirkan kemerdekaan, mencabut nama resmi Negara yang
sudah ditetapkan sebelumnya, mengulang kembali pandangan lintas selat
seperti Lee Teng-hui (State to State Theory), mengadakan referendum
masalah kemerdekaan, mencabut pedoman unifikasi nasional atau
menghilangkan Dewan Unifikasi Nasional.160
Pada tahun 2004 Chen Shui-bian memberikan perhatian besar pada
hubungan lintas selat setelah terpilih kembali pada pemilihan Presiden.
Untuk mengurangi ketegangan hubungan antara Tiongkok dan Taiwan,
Presiden Chen membuka tiga hubungan langsung antara Tiongkok dan
Taiwan melalui transportasi, layanan pos, dan perdagangan yang meliputi
Kinmen, Matsu dan Penghu. Setelah itu Taiwan berusaha memperluas
hubungan dengan Tiongkok lewat pariwisata atau kunjungan turis dari
Taiwan ke Tiongkok dan sebaliknya.161
160 Chien Min-chao. One Step Forward, One Step Backward: Chen Shui-bian Mainland Policy.Diakses dari http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/29500/1/4.pdf pada Kamis, 31Desember 2015.
161 David G. Brown. China-Taiwan Relations: Chen Muddies Cross-Strait Waters. Center forStrategic and International Studies (CSIS). Yang diakses darihttp://csis.org/files/media/csis/pubs/0203qchina_taiwan.pdf pada Sabtu, 9 Januari 2016.
97
Tabel 4. Rangkuman Kebijakan Taiwan Terhadap Tiongkok pada masaPresiden Chen Shui-bian (2000-2008)162 163
No. Tahun Kebijakan yang diambil1. 2000 Chen Shui-bian memenangkan pemilihan
Presiden. Chen Shui-bian merupakan calonkandidat yang berasal dari Partai DPP yangmengalahkan kekuasaan KMT selama 55 tahun.
Pada pidato pelantikannya, Presiden Chenmengeluarkan kebijakan Five No’s untukmencegah Tiongkok menggunakan militerterhadap Taiwan.
2. 2001 Taiwan membuka tiga hubungan langsungdengan Tiongkok.
Presiden Chen mengumumkan pandangannyadalam mengelola hubungan lintas selat yaituOne Country Each Side.
Taiwan menjadi anggota WTO3. 2004 Presiden Chen kembali terpilih dalam pemilihan
umum presiden untuk periode 2004-2008. Three mini links (tiga hubungan langsung
Taiwan-Tiongkok melalui transportasi, layananpos, dan perdagangan)
4. 2006 Presiden Chen menyatakan bahwa PedomanNasional Unifikasi telah berhenti untukditerapkan serta dihapusnya Dewan UnifikasiNasional.
Respon Taiwan terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Chen
Shui-bian merupakan hasil pengaruh dari perkembangan politik dalam
negeri Taiwan yang didukung oleh kemenangan partai DPP. Dengan latar
belakang tersebut, terdapat pola hubungan antara politik domestik Taiwan
dengan lintas selat, jika seorang politisi dengan identitas pro-Taiwan
memenangkan pemilihan presiden, ancaman terhadap hubungan Tiongkok
dan Taiwan akan meningkat. Sebaliknya jika politisi tersebut memiliki
identitas pro-Tiongkok maka tingkat ancaman bagi hubungan Tiongkok
162 Edgardo E. Dagdag. 2004. Chen Shu-bian and Taiwan- China (Cross-strait) Relations AnInitial Assessment. Diakses dari www.asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-39-1-2-2003/dagdag.pdf pada Senin, 5 Januari 2016.
163 Op. Cit. Vincent Wei-cheng Wang. Hal. 102-104.
98
dan Taiwan akan menurun. Oleh karena itu sebagian besar kebijakan yang
dikeluarkan oleh Presiden Chen dapat memicu konflik dengan Tiongkok.
2. Kebijakan Taiwan Terhadap Tiongkok Pada Masa Presiden Ma Ying-
Jeou (2008-2016)
Setelah hubungan Tiongkok dan Taiwan menegang pada masa
pemerintahan Chen shui-bian, hubungan keduanya mengalami fase baru
setelah terpilihnya Ma Ying-jeou dan Vincent Siew dari partai
Kuomintang (KMT) dalam pemilihan presiden tahun 2008. Ma Ying-jeou
memenangkan suara sebanyak 58,45% dibandingkan dengan calon
kandidat dari partai DPP Frank Hsieh dan Su Tseng-chang yang hanya
mendapatkan suara sebanyak 41,55%.164 Sejak pelantikannya Presiden Ma
secara aktif mengejar pembentukan kembali hubungan lintas selat dengan
mengupayakan pembangunan keamanan yang stabil untuk menunjang
kerjasama ekonomi baik dengan Tiongkok maupun dengan Negara
lainnya.
Dalam kebijakan luar negerinya Presiden Ma menekankan
komitmen untuk memperdalam partisipasi Taiwan dalam proses integrasi
ekonomi secara regional dan internasional dan hubungan antara Tiongkok
dan Taiwan pasca Presiden Chen Shui-bian. Untuk peningkatan hubungan
secara damai tersebut Presiden Ma mengeluarkan kebijakan three no’s
dengan Tiongkok. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa Taiwan akan
164 Mo Yan-chih. 2008. Decisive Victory for Ma-Ying-jeou. Diakses darihttp://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2008/03/23/2003406711 pada Selasa, 5Januari 2016.
99
mengadopsi tiga sikap yaitu tidak ada unifikasi, tidak ada deklarasi
kemerdekaan dan tidak ada penggunaan kekuatan.165
Penekanan komitmen Presiden Ma untuk memperbaiki hubungan
dengan Tiongkok setelah mengadopsi konsensus 1992 adalah terbukanya
kembali pertemuan antara Strait Exchange Foundation (SEF) dengan
Associaion for Relation Across the Taiwan Strait (ARATS). Pertemuan
tersebut termasuk dalam langkah Presiden Ma untuk memperdalam
hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Pertemuan antara pihak yang
mewakili Taiwan dengan Tiongkok tersebut berujung pada tercapainya
penandatanganan ECFA pada tahun 2010.
ECFA merupakan suatu bentuk kerangka kerjasama antara
Tiongkok dan Taiwan yang memberi aturan yang jelas antara keduabelah
pihak. Beberapa keuntungan yang akan didapat oleh Taiwan dengan
adanya penandatanganan ECFA yaitu, Taiwan tidak akan terkena dampak
buruk dari adanya perdagangan bebas dari yang telah Tiongkok lakukan
dengan negara-negara lain termasuk ASEAN. Selain itu dengan
penandatanganan ECFA akan membuat investor Taiwan lebih mudah
masuk ke Tiongkok.
Setelah penandatanganan ECFA, selama masa pemerintahan Ma
Ying-jeou pemerintahannya menggunakan flexible diplomacy dalam
mengelola hubungan dengan Tiongkok. Inti dari kebijakan ini adalah
mengarahkan kebijakan luar negeri Taiwan untuk mengurangi konflik
165 Ralph Cossa. 2008. Looking Ma’s three noes. Diakses darihttp://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/01/21/2003398185 pada Selasa, 5Januari 2016.
100
dengan Tiongkok dan menerima konsensus 1992 yang menjadi dasar bagi
pengelolaan hubungan Tiongkok dengan Taiwan. Diplomasi ini digunakan
agar pemerintah Taiwan dapat meningkatkan peran Taiwan dalam dunia
internasional tanpa halangan dari Tiongkok.166
Flexible diplomacy ini memiliki manfaat bagi Taiwan di tiga level
yaitu, pertama ditingkat internasional Taiwan akan mendapat pengakuan
serta memulihkan kepercayaan dari masyarakat internasional setelah
kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Chen sebelumnya. Hal positif
tersebut akan menciptakan peluang baru bagi hubungan diplomasi Taiwan
dengan Negara-negara lain di masa yang akan datang. Sedangkan pada
tingkat lintas selat, diplomasi ini membantu Taiwan untuk meredakan
konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan serta menambah
dukungan dari Tiongkok agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam World
Health Organization (WHO).167
Poin yang membedakan antara kebijakan Ma Ying-jeou dengan
Chen Shui-bian adalah kebijakan Ma-Ying-jeou tetap menjaga status quo
dengan Tiongkok dan menerapkan kebijakan yang lebih pragmatis,
pengurangan konflik serta provokasi. Kebijakan three no’s, kerjasama
ECFA serta flexible diplomacy merupakan pendekatan kebijakan Ma
dalam mengembangkan hubungan dengan Tiongkok.168 Kebijakan Ma
166 Taiwan Today. Chiayi Ho. 2010. Taiwan Academics Laud Ma’s Flexible Diplomacy. Diaksesdari http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=100359&ctNode=2357 pada Sabtu, 8 Januari 2016.
167 Kaocheng Wang. Taiwan Diplomatic Policy under Ma Ying-jeou Administration. Diakses darihttp://fsi.stanford.edu/sites/default/files/evnts/media//Taiwan%27s_diplomatic_policies.pdfpada Sabtu, 8 Januari 2016.
168 Jorg Thiele. 2014. The Operational Code of Chen Shui-bian and Ma Ying-jeou: A NewApproach in the Analysis of Cross-strait Relations. European Consortium for PoliticalResearch. University of Vienna. Hal. 13.
101
tersebut sebagai langkah gencatan senjata dengan Tiongkok dan untuk
memperluas posisi Taiwan di dunia internasional.
Baik pada masa Chen Shui-bian maupun Ma Ying-Jeou, Tiongkok
dan Taiwan masih mempertahankan status quo. Kedua presiden Taiwan
tersebut hanya menunda usaha Tiongkok dalam mewujudkan unifikasi.
Namun, kedua presiden tersebut memiliki cara yang berbeda dalam
menunda kebijakan reunifikasi yang dilakukan Tiongkok. Presiden Chen
Shui-bian cenderung merespon kebijakan Tiongkok dengan tindakan yang
akan memicu konflik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemenangan Chen
Shui-bian dalam pemilihan umum, latar belakang Presiden Chen yang
berasal dari partai DPP, pandangan mengenai teori One Country Each Side
serta menghapus Dewan Unifikasi Nasional. Tindakan tersebut akan
menyulitkan proses negosiasi bagi kedua belah pihak di masa depan.
Sedangkan pada masa pemerintahan Ma Ying-jeou menunda
negosiasi untuk mencapai reunifikasi dengan menggunakan cara-cara
damai dan menguntungkan bagi Taiwan. Cara-cara tersebut lebih
menciptakan suasana yang kooperatif antara Tiongkok dan Taiwan serta
lebih mengedepankan kerjasama ekonomi seperti adanya penandatanganan
Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA).
102
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Isu lintas-selat merupakan isu yang menarik untuk dibahas dalam
politik luar negeri Tiongkok. Hingga saat ini Tiongkok belum mampu
melakukan kebijakan unifikasi terhadap wilayah Taiwan. Hubungan
Tiongkok dan Taiwan saat ini masih menggunakan status quo dimana
keduanya saling mempertahankan prinsip yang dipegang baik oleh
Tiongkok maupun oleh Taiwan. Taiwan terus melakukan upaya untuk
mendapatkan pengakuan sebagai pemerintahan yang sah baik dimata
Tiongkok maupun di mata internasional.
Terkait isu Taiwan, dalam hal ini kedaulatan merupakan salah satu
dari dua isu yang paling penting dalam sengketa politik selain isu keamanan
antara Tiongkok dan Taiwan. Di era globalisasi isu kedaulatan tidak lagi
menjadi penghambat antara hubungan lintas Selat. Tiongkok lebih
mengedepankan aspek ekonomi daripada berlarut dalam konflik politik
dengan Taiwan. Interaksi ekonomi dan sosial di lintas selat secara intensif
dapat menumbuhkan interaksi antar pemerintahan yang berguna bagi
kepentingan keduabelah pihak.
Adanya perubahan pola dalam politik luar negeri Tiongkok
terhadap upaya kemerdekaan pada masa pemerintahan Hu Jintao membuat
103
respon Taiwan dan dunia internasional menjadi positif terhadap Tiongkok.
Hal tersebut menjadikan Taiwan lebih kooperatif, mengurangi konflik serta
menciptakan banyaknya dukungan terhadap kebijakan satu Cina.
Dari sudut pandang Tiongkok penyatuan politik tetap menjadi
tujuan jangka panjang daripada penyatuaan ekonomi. Strategi yang realistik
untuk dijalankan saat ini adalah dengan mempromosikan hubungan lintas
selat yang damai setelah masuknya Tiongkok dalam WTO dan
mengembangkan kerjasama melalui integrasi ekonomi sehingga
memungkinkan Tiongkok untuk bernegosiasi masalah unifikasi di masa
depan.
Politik luar negeri yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap upaya
kemerdekaan Taiwan pada masa pemerintahan Hu Jintao tidak terlepas dari
faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang
mempengaruhi politik luar negeri Tiongkok yaitu pertama, sistem politik
domestik Tiongkok. Pergantian pemerintahan dari Jiang Zemin ke Hu Jintao
sekaligus mengubah arah politik luar negeri Tiongkok, Hu Jintao memiliki
pandangan yang terbuka, fokus pada pengembangan cara-cara damai lewat
kerjasama ekonomi. Selain itu politik domestik banyak melibatkan aktor-
aktor yang mempengaruhi pembuatan suatu keputusan. Pengaruh aktor-
aktor tersebut tidak akan melebihi kekuasaaan tertinggi dari Hu Jintao.
Kedua, kepentingan ekonomi yang ditunjukkan oleh Tiongkok
dengan adanya perubahan kebijakan dari penggunaan militer menuju pada
kebijakan yang lebih rekonsiliatif guna mengembangkan hubungan sosial
104
dan ekonomi. Faktor ekonomi ini juga digunakan untuk melengkapi sumber
daya antara Tiongkok dan Taiwan sekaligus bentuk state survival. Jika suatu
Negara ingin melakukan langkah politik maka harus didahului oleh langkah
perdamaian seperti adanya integrasi ekonomi.
Ketiga, faktor ideosinkretik yang mempengaruhi keputusan atau
kebijakan yang diambil oleh Hu Jintao dipengaruhi oleh nilai, pengalaman,
bakat, kepribadian elit politik serta belief. Hu Jintao yang memiliki latar
belakang konfusianisme memiliki penekanan pada kebijakan luar negeri
yang damai. Filsafat tentang konfusianisme tersebut muncul dalam politik
luar negerinya seperti peaceful development dan harmonious world.
Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri
Tiongkok terhadap Taiwan pada masa Hu Jintao yang pertama yaitu, adanya
dukungan dari Amerika Serikat dalam bentuk militer dan politik. Dukungan
militer yaitu adanya Taiwan relations Act (TRA), kerjasama militer dalam
hal pembelian senjata. Sedangkan dukungan politik tersebut berbentuk
kebijakan strategic ambiguity dimana AS dapat mempertahankan hubungan
kerjasama dengan Taiwan walaupun AS sudah terikat kebijakan satu Cina
dengan Tiongkok. AS juga memberika dukungannya kepada Taiwan agar
dapat berpartisipasi dalam organisasi internasional. Kedua adalah
keanggotaan Taiwan dalam WTO yang akan memperluas pengaruh politik
dan ekonomi Taiwan dalam dunia internasional.
Dampak globalisasi juga mempengaruhi hubungan lintas selat,
selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan
105
Taiwan semakin berkembang dan terintegrasi dengan Negara-negara lain.
Hal ini didukung dengan meluasnya pengaruh Tiongkok dan Taiwan pasca
memasuki WTO dan adanya penandatanganan kerjasama ECFA. Kerjasama
ekonomi tersebut tidak mungkin terjadi jika kedua pemerintahan tersebut
tidak mengesampingkan masalah keamanan dan politik yang selama ini
menjadi sumber konflik antara Tiongkok dan Taiwan. Terdapat beberapa
teori yang mengatakan bahwa Taiwan akan mengutamakan peningkatan
hubungan ekonomi di lintas selat daripada politik. Bagi Tiongkok, untuk
saat ini kerjasama ekonomi akan meningkatkan perdamaian dan stablilitas.
Terkait respon Taiwan terhadap politik luar negeri Tiongkok
sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik Taiwan. Dari
perkembangan politik domestik dari masa Presiden Chen Shui-bian sampai
Ma Ying-jeou dapat disimpulkan suatu pola antara Tiongkok dan Taiwan,
jika seorang politisi dengan identitas pro-Taiwan memenangkan pemilihan
presiden, ancaman terhadap hubungan Tiongkok dan Taiwan akan
meningkat. Sebaliknya jika politisi tersebut memiliki identitas pro-Tiongkok
maka tingkat ancaman bagi hubungan Tiongkok dan Taiwan akan menurun.
106
Daftar Pustaka
Buku
Bae, Jung-Ho dan Jae H. Ku (ed). 2012. China’s Domestic Politis and Foreign
Policies and Major Countries’ Strategies toward China. Seoul: Korea
Institute for National Unification (KINU).
Bakri, Umar Suryadi. 1997. China Quo Vadis?: Pasca Deng Xiaoping. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
Baldwin, David. 1985. Economic Statecraft. New Jersey: Princeton University
Press.
Breuning, Marijke. 2007. Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction.
New York: Palgrave MacMillan.
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Chang, Parris H. 2014. Beijing’s Unification Strategy toward taiwan and Cross-
Strait Relations. The Korean Journal of Defense Analysis Vol. 26 No. 3.
Hal. 300. Penulis mengutip dari Deng Xiaoping’s Selected Works 1975–
1982. 1983. Beijing: People’s Publishing House.
Cheng, Joseph Y. S. 1998. China in the Post-Deng Era. Hongkong: The Chinese
University Press.
Cheng, Joseph Y. S. 1989. The Evolution of China Foreign Policy in the Post-
Mao Era: From Anti-Hegemony to Modernization Diplomacy, in China:
Modernization in the 1980’s “Zhongguo de ‘Xiandaihua’ Wiajiao
Zhengce”. Hongkong: Chinese University Press.
Clough, Ralph N. 1993. Reaching Across the Taiwan Strait: People to People
Diplomacy. Colorado: Westview Press.
Coulumbis, Theodore A. dan James H. Wolfe. 1981. Introduction to International
Relation: Power and Justice. Prentice.
Griffiths, Martin dan Terry O’Callaghan. 2002. International Relations: The Key
Concepts. New York : Routledge.
107
Grove, Andrea. 2007. Political Leadership in Foreign Policy, Manipulating
Support Across Border. Palgrave Macmillan.
Holsti, K.J. 1992. Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (terj.).
Bandung: Bina Cipta.
Hu, Weixing (ed). 2013. New Dynamics in Cross-Taiwan Strait Relations. New
York: Routledge
Jian, Chen. 2001. Mao’s China and The Cold War. London: The University of
North Carolina Press.
Joseph, William A. 2014. Politics In China: An Introduction. New York: Oxford
University Press
Kennedy, Paul. 1987. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change
and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House.
Kesler, Eric Von. 2008. Taiwan’s Dilemma: China, The United States, and
Reunification. Naval Postgraduate School. Monterey: California.
Kupchan, Charles A. 2010. How Enemies Become Friends. Princeton: Princeton
University Press.
Lampton, David (ed). 2001. The Making of Chinese Foreign and Security Policy
in the Era of Reform, 1978-2000. Standford: Standford University Press.
Lentner, Howard. 1974. Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual
Approach. Ohio: Bill and Howell Co.
Mamonto, Muhammad Ciptadi. 2010. Analisa Kebijakan Luar Negeri Strategic
Ambiguity Amerika Serikat: The US Interest towards the Two China.
Malang: Universitas Brawijaya.
Mas’oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.
Jakarta: LP3ES.
Maxwell, Robert (ed). 1984. Deng Xiaoping: Speeches and Writings. New York:
Pergamon.
Papp, Daniel S. 1988. Contemporary International Relation: A Framework for
Understanding. New York: MacMillan Publishing Company.
Perwita, Anak Agung B. dan yani Yanyan M. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
108
Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung:
Abardin.
Prawirasaputra, Sumpena.1984. Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
Bandung: Remaja Karya.
Rosenau, James N. 1969. International Politics and Foreign Policy: A Reader in
Research and Theory. New York: The Free Press.
Rosenau, James N. 1980. The scientific Study of Foreign Policy. New York: The
Free Press.
Rosenau, James N., Gavin Boyd dan Kenneth W. Thompson. 1976. World
Politics: An Introduction. New York: The Free Press.
Stuart, Douglas T dan Harish Kapur (ed.). 1985. The End of and Isolation: China
After Mao. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2009. Metode Penelitian Sosial: Berbagai
Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Tien, Hung-mao dan Yun-han Chu (ed). 2000. China Under Jiang Zemin. United
States of America: Lynne Rienner Publisher.
Wang, Yu San (ed). 1990. “Foreign Policy of the Republic of China on Taiwan:
An Unorthodox Approach”. New York. Praeger Publishers.
Wong, Jhon dan Yongnian Zheng (ed). 2002. Post Jiang Leadership Succession:
Problems and Perspective. Singapore: Singapore University Press.
Wo, Willy and Lap Lam. 2006. Chinese Politics in the Hu Jintao Era: New
Leaders, New Challenges. New York: An East Gate Book.
Xuetong, Yan. 1993. Zhongguo guojia liyi fenxi (Analysis of China’s National
Interests). Tianjin: Tianjin People’s Press.
Yizhou, Wang. 2003. Quanqiu zhengzhi he zhongguo wai jiao (Global politics
and Chinese foreign policy). Beijing: World Knowledge Press.
Zhang, Shu Guang. 1992. Deterrence and Strategic Culture: Chinese-American
Confrontations, 1949-1958. Ithaca: Cornell University Press.
109
Skripsi dan Tesis
Hines, Robert Lincoln. 2013. Change and Continuity in Chinese Strategic
Culture-Chinese Decision Making in The Taiwan Strait. American
University.
Muharom, Azmi. 2014. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terhadap Taiwan dalam
negosiasi Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) pada
tahun 2010. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Panjaitan, Yoan. 2012. “Faktor-Faktor yang Menjadikan Cina sebagai Kekuatan
Ekonomi Baru di WTO (2001-2009)”. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Indonesia.
Sitepu, Ardhy Dinata. 2013. Dampak Penandatanganan Economic Cooperation
Framework Agreement terhadap Economic Security Taiwan pada tahun
2011-2013. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Wei, Hung-Chin. 1999. Taiwan’s Democratic Progressive Party and its Mainland
China Policy. Thesis. Durham University.
Widarsa, Avina Nadhila. 2011. Kepentingan Cina dalam Penandatanganan Cross
Strait Economic Cooperation Framework Agreement dengan Taiwan
pada tahun 2010. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia.
Jurnal dan Publikasi
Brown, Kerry, Justin Hempson-Jones dan Jessica Pennisi. 2010. “How Taiwan’s
Relationship with China Affects its Position in the Global Economy”.
The Royal Institute of International Affairs.
Cabestan, Jean Pierre. 1995. “Mainland Missileand the Future of Taiwan and Lee
Teng-hui”. China Perspective.
Charnovitz, Steve. 2006. “Taiwan WTO Membership and Its International
Implications”. George Washington University Law School.
Chou, Chi-An. 2010. “A Two-Edged Word: Economic Cooperation Framework
Agrement Between The Republic of China and The People’s Republic of
110
China”. International Law & Management Review Vol.6. Diakses dari
http://www.law2.byu.edu/ilmr/articles/spring_2010/BYU_ILMR_spring_
2010_1_A%20Two-Edged%20Sword.pdf pada Senin, 4 Januari 2016.
Coney, Sean. 1997. “Why Taiwan is Not Hongkong: A Review of The PRC’s “One
Country Two Systems” Model for Reunification with Taiwan”. Pacific
Rim Law & Policy Journal Vol. 6.No. 3.
Ding, Arthur S. 2013. “The Hu Jintao Decade in China’s Foreign and Security
Policy (2002–12): Assessments and Implications”. Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI).
_______. “Drafting and Promulgation of the Basic Law and Hongkong’s
Reunification with the Motherland”. Diakses dari
http://www.basiclaw.gov.hk/en/publications/book/15anniversary_reunific
ation_ch1_1.pdf pada Senin, 23 Februari 2015.
Duchâtel, Mathieu dan François Godement. 2009. “China’s Politics under Hu
Jintao”. Journal of Current Chinese Affairs 3: German Institute of
Global and Area Studies (GIGA).
Dumbaugh, Kerry dan Michael F. Martin. 2009. “Understanding China’s
Political System”. Congressional Research Service (CRS).
Gong, Gerrit W. “China-Taiwan Relations: Cross-Strait Cross-Fire”. Center for
Strategic and International Studies (CSIS). Diakses dari
http://csis.org/files/media/csis/pubs/0001qchina_taiwan.pdf Pada
Minggu, 5 Juli 2015.
Hairen, Zong. 2002. “The low-profile Hu Jintao”. Hong Kong Economic Journal.
Hartati, Anna Yulia. 2004. “Diplomasi Indonesia Pasca Perang Dingin”. Jurnal
Spektrum Vol. 1 No. 1.
Holbig, Heike. 2009. “Remaking CCP’s Ideology: Determinant, Progress and
Limits under Hu Jintao”. German Institute of Global and Area Studies
(GIGA).
Hsieh, Fuh Sheng. 2005. “Etnicity, National Identity, and Domestic Politics in
Taiwan”. Journal of Asian and African Studies. London: Sage
Publication. Hal 14-15. Diakses dari http://jas.sagepub.com/content/40/1-
2/13.full.pdf pada Rabu, 26 Maret 2015.
111
Jia, Qingguo. “From Self-imposed Isolation to Global Cooperation: The
Evolution of Chinese Foreign Policy Since the 1980s”. Diakses dari
http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-1999-2/artjia.pdf pada Selasa,11
November 2014.
Kai-huang, Yang. 2009. “Hu Six Points amid the Interaction between KMT and
CCP”. Diakses dari
http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/04115463073.pdf
Kan, Shirley A. dan Wayne M. Morrison. 2014. “U.S-Taiwan Relationship:
Overview of Policy Issues”. Congressional Ressearch Service (CRS).
Kastner, Scott. 2006. “Does Economic Integration Across the Taiwan Strait Make
Military Conflict Less Likely?”. Journal of East Asian Studies Vol. 6.
Keyuan, Zou. 2005. Governing the Taiwan Issue in Accordance with Law: An
Essay on China’s Anti-Secession Law. Chinese Journal of International
Law Vol. 4 No. 2.
Lawrence, Susan V. dan Michael F. Martin. 2013. Understanding China’s
Political System. Congressional Research Service (CRS).
Matsuda, Yasuhiro. 2004. PRC-Taiwan Relations under Chen Shui-bian’s
Government: Continuity and Change between the First and Second
terms. Senior Research in National Institute for Defence Studies.
Melati, Ita. 2013. “Upaya Cina dalam Mempertahankan Komunisme Pasca
Runtuhnya Uni Soviet”. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Diakses
dari http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2013/11/Jurnal-HI-Ita%20Melati%20%2811-15-13-04-
42-36%29.pdf pada Jumat, 16 Oktober 205.
Miller, Alice. The Politburo Standing Committee Under Hu Jintao. China
Leadership Monitor No. 35. Diakses dari
http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/CLM35AM.pdf.
pada Kamis, 28 Januari 2016.
Min-chao, Chien. “One Step Forward, One Step Backward: Chen Shui-bian
Mainland Policy”. Diakses dari
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/29500/1/4.pdf pada
Kamis, 31 Desember 2015.
112
Mumin, Chen. 2005. “Prosperity vs. Security: National Security of Taiwan 2000-
2004”. Taiwan International Studies Quarterly, Vol. 1, No. 2.
Nanjing School. “The Civil War”. Diakses dari http://share.nanjing-
school.com/dphistory/files/2014/09/Civil-War-1946-9-2i0pi2f.pdf Pada
Minggu, 22 Juni 2015.
Nurdin, Angga. 2010. “Taiwan, Dilema Diantara Dua Super Power”. Jurnal
Multiversa, Vol. 2 No. 1. Yogyakarta: Institute of Internasional Studies
(IIS) Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).
Patiel, Jeremy. 2010. Structure and Process in Chinese Foreign Policy:
Implications for Canada. China Papers No.8. Canadian International
Council (CIC).
Qingguo, Jia. 2005. “Disrespect and Distrust: the external origins of
contemporary Chinese Nationalism”. Journal of Contemporary China 14,
no. 42.
Roy, Denny. 2004. Cross-Strait Economic Relations: opportunities Outweigh
Risks. Paper Series Asia Pasific Center for Security Studies.
Sheng, Tzu-Chun dan Shu-Hui Lan. 2014. “Is Economic Cooperation Framework
Agreement the Threshold of Sustainable Development for Taiwan’s
Industries?”. International Journal of Economics and Finance Vol. 6.
Canadian Center of Science and Education.
Swaine, Michael D. 1995. China Domestic Change and Foreign Policy.
California: RAND’s National Defence Research Institute.
Tung, Chen Yuan. 2005. “The Evolution and Prospects of Cross-Strait Relations
in the Chen Shui-Bian Administration.” Diakses dari
http://www3.nccu.edu.tw/~ctung/Documents/W-B-a-17.doc Pada Rabu,
14 Oktober 2015.
Wang, Vincent Wei-cheng. 2002. The Chen Shui-bian Administration Mainland
Policy: Toward a Modus Vivendi or Continued Stalemate?. American
Asian Review Vol 20.
Wang, Vincent Wei-Cheng. 2007. The Chinese Military and the Taiwan Issue:
How China Assesses Its Security Environment. Southeast Review of
Asian Studies Vol. 29. University of Richmond.
113
Wei, Chunjuan N.. China’s Anti Secession Law and Hu Jintao’s Taiwan Policy.
Yale Journal of International Affairs.
Wei, Vincent. 2002. "The Chen Shui-Bian Administrations Mainland Policy:
Toward a Modus Vivendi or Continued Stalemate?". American Asian
Review Vol. 20, no. 3.
Winberg, Chai (ed). 1999. “Relations Between the Chinese Mainland and
Taiwan”. Asian Affairs 26, no. 2.
Xin, Xu. “The Dynamics of the Taiwan Question in Chinese Foreign Policy:
Dialectics of National Identity and International Constraint”.
Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies Vol.7.
Yani, Yanyan M. “Politik Luar Negeri”. Diakses dari
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2010/01/politik_luar_negeri.pdf pada Kamis, 2 Juli
2015.
Yaqing, Qin. 2003. “Guojia Shenfen, zhanlue wenhua he anquan liyi – guanyu
zhongguo yu guoji shehui guanxi de sang jiashe (Nation Identity,
Strategic Culture and Security Interests: Three Hypotheses on the
Interaction between China and International Society)”. Shijie Jingji yu
Zhengzhi.
Zimin, Chen. “International Responsibility and China’s Foreign Policy”. Diakses
dari www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series3/pdf/3-
1.pdf pada Kamis 26 Februari 2015.
Internet
Arimasera, Defa. “2014. Pengaruh Belief Hu Jintao Terhadap Persiapan China-
ASEAN Free Trade Area (CAFTA) Tahun 2003-2010”. Diakses dari
https://www.academia.edu/9870688/Pengaruh_Belief_Hu_Jintao_Terhad
ap_Persiapan_CAFTA_Tahun_2003-2010 pada Sabtu, 17 Oktober 2015.
Baker, Chris. 2013. “Deepening Socio-Economic Relations Across Taiwan
Strait”. Diakses dari http://www.e-ir.info/2013/10/20/deepening-socio-
economic-relations-across-taiwan-straits/ pada Selasa, 27 Oktober 2015.
114
BBC. “Jiang Zemin’s Profile”. Diakses dari http://www.bbc.com/news/world-
asia-China-20038774 pada Minggu, 29 Maret 2015.
Center for Strategic and International Studies (CSIS). “Chinese Foreign Policy:
What Are the Main Tenets of China’s Foreign Policy”. Diakses dari
www.csis.org/CHINABALANCESHEET pada Senin, 20 Oktober 2014.
China Daily. “Anti-Secession Law adopted by NPC”. Diakses dari
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-
03/14/content_424643.htm pada Rabu, 28 Oktober 2015.
China Daily. “International Community Supports China’s Anti Seccesion Law”.
2005 diakes dari http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-
03/16/content_425454.htm pada Minggu, 11 Oktober 2015.
China Daily. “Mainland to further direct trade with Taiwan,” diakses dari
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2008-
01/20/content_6406756.htm pada Selasa, 27 Oktober 2015.
China Internet Information Center. “The Constitutional System”. Diakses dari
http://www.china.org.cn/english/Political/26143.htm pada Sabtu, 17
Oktober 2015.
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). “Political Development”.
Diakses dari http://dfat.gov.au/geo/taiwan/pages/taiwan-country-
brief.aspx pada Sabtu, 30 Mei 2015.
Irewati, Awani. 2015. “Pemilu Taiwan, Kemenangan Partai Kuomintang”.
Diakses dari http://www.p2p-
lipi.go.id/menu/columns.aspx?id=40&lang=en pada Rabu 11 Februari
2015.
Kompas. 2009. “Volume Perdagangan Indonesia-China Terimbas Krisis”. Diakses
dari
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/08/24/11435164/volume.pe
rdagangan.indonesia-china.terimbas.krisis pada Senin, 4 Januari 2016.
Kuo, Grace. 2013. “MND Reaffirms Strong Taiwan-US Defense Ties”. Diakses
dar i http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=204910&ctNode=445 .
pada Sabtu 21 Februari 2015.
115
Kuomintang (KMT). “Introduction to the party”. Dari
http://www1.kmt.org.tw/english/page.aspx?type=para&mnum=105 pada
Kamis 15 Oktober 2015.
Mattlin, Mikael. 2004. Same Content, Different Wrapping: Cross-Strait Policy
Under DPP Rule. Diakses dari http://chinaperspectives.revues.org/436
Pada Rabu, 14 Oktober 2015.
Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan). “Diplomatic Allies”.
Diakses dari
http://www.mofa.gov.tw/en/AlliesIndex.aspx?n=DF6F8F246049F8D6&s
ms=A76B7230ADF29736 pada Selasa, 5 Mei 2015.
People’s Daily Online. “Hu Jintao State President”. Diakses dari
http://en.people.cn/leaders/vpresident.html pada Sabtu, 17 Oktober 2015.
People’s Daily Online. “Jiang Zemin Biography”. Diakses dari
http://en.people.cn/leaders/jzm/biography.htm pada Minggu, 22 Maret
2015.
People’s Daily Online. “Jiang Zemin’s Eight Proposal”. Diakses dari
http://en.people.cn/90002/92080/92129/6271625.html pada Rabu, 1 Juli
2015.
People's Daily Oline. “President Hu's ‘four-point’ speech shows utmost sincerity
toward Taiwan. Diakses dari
http://en.people.cn/200503/08/eng20050308_176059.html pada Sabtu, 17
Oktober 2015.
Roberge, Michael dan Youkyoung Lee. 2009. China-Taiwan Relations. Diakses
dari http://www.cfr.org/china/china-taiwan-relations/p9223 pada Rabu,
15 Oktober 2014.
Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO). 2012. “Taiwan-
U.S. Relations”. Diakses dari
http://www.taiwanembassy.org/US/ct.asp?xItem=266456&CtNode=2297
&mp=12&xp1=12 pada Kamis 11 Maret 2015.
Taipei Mission in the Republic of Latvia. 2013. “Taiwan will continue to
purchase U.S. arms: President Ma”. Diakses dari http://www.roc-
116
taiwan.org/LV/ct.asp?xItem=414777&ctNode=7925&mp=507 pada
Sabtu 21 Februari 2015.
Taiwan Affairs Office of the State Council PRC. 2008. “Let Us Join Hands to
Promote the Peaceful Development of Cross-Strait Relations and Strive
with a United Resolve for the Great Rejuvenation of the Chinese Nation.”
Diakses dari
http://www.gwytb.gov.cn/en/Special/Hu/201103/t20110322_1794707.ht
m pada Sabtu, 17 Oktober 2015.
Taiwan DC. “DPP Resolution for Taiwan Future”. Diakses dari
http://www.taiwandc.org/nws-9920.htm pada Rabu, 28 Oktober 2015.
Tempo. 2010. “Faksionalisme Menjelang Peralihan Generasi”. Diakses dari
http://koran.tempo.co/konten/2010/11/03/216799/Faksionalisme-
Menjelang-Peralihan-Generasi pada Sabtu, 17 Oktober 2015.
The Taipei Economic and Trade Office (TETO). Diakses dari http://www.roc-
taiwan.org/id/mp.asp?mp=292 pada Rabu, 29 April 2015.
Tkcacik, Jhon J., Joseph Fewsmith dan Maryanne Kivlehan. 2002. “Who’s Hu?
Assessing China’s Heir Apparent, Hu Jintao”. Diakses dari
http://www.heritage.org/research/lecture/whos-hu#pgfId=1010081 pada
29 Maret 2015.
U.S. Department of State. 2015. “U.S.-Taiwan Relations”. Diakses dari
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35855.htm pada Rabu 11 Maret 2015.
World Trade Organization (WTO). “Understanding WTO”. Diakses dari
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/tif_e.htm pada
Rabu, 30 Desember 2015.
WTO. “WTO Overview”. Diakses dari
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm pada
Senin, 16 November 2015.
WTO. 2001. “WTO successfully concludes negotiations on entry of the Separate
Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu.” 2001.
Diakses dari https://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr244_e.htm
Diakses pada Rabu, 30 Desember 2015.
117
Xiang, Zhang. 2010. “Chinese Mainland, Taiwan Sign Landmark Economic
Pact”. Diakses dari http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2010-
06/29/c_13375203.htm pada Senin, 4 Januari 2016
Xinhua News Agency. “Anti-secession Law Not a 'War Mobilization Order' “.
Dari http://www.china.org.cn/english/government/121749.htm Diakses
pada Sabtu, 10 Oktober 2015.
Xinhua News Agency. “Four-point Guidelines on Cross-Straits Relations Set
Forth by President Hu”. Diakses dari
http://www.china.org.cn/english/2005lh/121825.htm pada sabtu, 17
Oktober 2015.