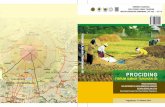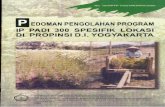Pertumbuhan Generatif dan Komponen Hasil Padi Gogo Varietas Lokal dengan Perlakuan Mutagen Sodium...
Transcript of Pertumbuhan Generatif dan Komponen Hasil Padi Gogo Varietas Lokal dengan Perlakuan Mutagen Sodium...
USULAN PENELITIAN
PERTUMBUHAN GENERATIF DAN KOMPONEN HASILGENERASI M-1 PADI GOGO (Oryza sativa L.)
VARIETAS LOKAL DENGAN PERLAKUAN MUTAGEN SODIUMAZIDA (SA)
Oleh:
JAVIERI PRATAMANIM. 1006114042
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
JURUSAN AGROTEKNOLOGIFAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU2014
USULAN PENELITIAN
PERTUMBUHAN GENERATIF DAN KOMPONEN HASILGENERASI M-1 PADI GOGO (Oryza sativa L.)
VARIETAS LOKAL DENGAN PERLAKUAN MUTAGEN SODIUMAZIDA (SA)
Oleh:
JAVIERI PRATAMANIM. 1006114042
Diajukan sebagai salah satu syaratuntuk melaksanakan penelitian
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGIJURUSAN AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAUPEKANBARU
2014LEMBAR PENGESAHAN
PERTUMBUHAN GENERATIF DAN KOMPONEN HASILGENERASI M-1 PADI GOGO (Oryza sativa L.)
VARIETAS LOKAL DENGAN PERLAKUAN MUTAGEN SODIUMAZIDA (SA)
Oleh:
JAVIERI PRATAMANIM. 1006114042
Menyetujui
Dosen Pembimbing I
Dr. agr. Ir. Tengku
Dosen Pembimbing II
Ir. Muhammad Ali, MSc
Nurhidayah.NIP. 196201211988032003
NIP.196110031986031003
Mengetahui
Ketua Program Studi Agroteknologi
Ir. Fifi Puspita, MPNIP. 196612121991032003
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kesehatan dan keselamatan kepada penulis
sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan
judul “Pertumbuhan Generatif dan Komponen Hasil
Generasi M-1 Padi Gogo (Oryza Sativa L.) Varietas Lokal
dengan Perlakuan Mutagen Sodium Azide (SA)”.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. agr.
Ir. Tengku Nurhidayah sebagai dosen pembimbing I dan
Ir. Muhammad Ali, MSc sebagai dosen pembimbing II yang
telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan
motivasi sampai selesainya usulan penelitian ini.
Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada
seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis
di dalam penyelesaian usulan penelitian ini.
Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca
untuk perbaikan usulan penelitian ini sehingga
bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga mengharapkan
agar usulan penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi
acuan dalam pelaksanaan penelitian.
v
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.................................. iii
DAFTAR ISI...................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN................................. vii
I. PENDAHULUAN................................. 1
I.1......................................... Latar
Belakang................................. 1
I.2.........................................
Tujuan Penelitian........................ 4
I.3.........................................
Hipotesis................................ 5
II. TINJAUAN PUSTAKA ........................... 6
II.1........................................
Tanaman Padi (Oryza sativa L.)................ 6
II.2........................................
Pemuliaan Mutasi......................... 8
II.3........................................
Mutagen Kimia Sodium Azide (SA).......... 12
vi
III.............................................BAHAN
DAN METODE.................................. 14
III.1.......................................
Tempat dan Waktu......................... 14
III.2....................................... Bahan
dan Alat................................. 14
III.3.......................................
Metode Penelitian........................ 14
III.4.......................................
Pelaksanaan Penelitian................... 16
III.5.......................................
Pengamatan............................... 19
DAFTAR PUSTAKA.................................. 21
LAMPIRAN........................................ 23
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Jadwal rencana kegiatan penelitian........... 23
2. Denah penelitian yang disusun berdasarkan
Rancangan Acak Kelompok (RAK)................ 24
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kebutuhan padi sebagai bahan makanan pokok
sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di Riau
dimasa yang akan datang semakin meningkat sejalan
dengan meningkatnya jumlah penduduk. Meningkatnya
populasi penduduk sebesar 230 juta jiwa dengan tingkat
pertumbuhan penduduk sebesar 1.4 %/tahun menyebabkan
pasokan beras pada saat ini telah mencapai tingkat
terendah dalam kurun waktu 30 tahun (ACIAR-SADI, 2009).
Menurut BPS (2013), produksi tanaman padi di Riau
pada tahun 2013 adalah 440.131 ton dengan luas areal
panen 120.833 ha dan produktivitas 36,42 ku/ha. Menurut
BPPN et al. (2013), jumlah penduduk di provinsi Riau pada
tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 6,34 juta jiwa,
dengan perhitungan konsumsi beras 139 kg/kapita/tahun
maka kebutuhan beras di provinsi Riau untuk tahun 2015
adalah 881.260 ton/tahun. Kondisi ini sangat
memperihatinkan karena produksi padi tidak memenuhi
kebutuhan masyarakat.
2
Selain padi varietas unggul, petani padi di
Indonesia banyak juga menanam padi varietas lokal
dengan berbagai kekhasan yang dikembangkan secara turun
temurun oleh masyarakat setempat. Di daerah kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau masih banyak petani yang
menanam padi varietas lokal, diantaranya adalah
varietas Korea, Cekur, Cekur Putih, Karetik Putih dan
Lembuk Sawah. Varietas Korea dan Lembuk Sawah merupakan
padi yang disukai dengan lebih pulen dan banyak ditanam
oleh masyarakat setempat. Padi varietas lokal umumnya
berproduksi lebih rendah, mempunyai batang lebih tinggi
yang rentan terhadap kerebahan dan berumur relatif
panjang (6-7 bulan) dibandingkan dengan padi jenis
unggul.
Rendahnya upaya dalam peningkatan produktivitas
padi antara lain disebabkan terbatasnya penerapan
teknologi dan terjadinya penurunan kapasitas produksi
(Mugiono dan Dwimahyani, 2008). Di Riau, penurunan
produksi padi pada tahun 2013 terjadi karena adanya
penurunan luas panen yang cukup siginifikan, yaitu
sebesar 25.497 ha atau 17,70 %. Hal ini disebabkan
3
karena sebagian besar masyarakat Riau banyak melakukan
konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan kelapa
sawit (Gunawan, 2014). Selain itu, penurunan
produktivitas padi di Riau lebih dipengaruhi oleh
kondisi cuaca yang ekstrim dan curah hujan tinggi yang
mengakibatkan permasalahan pada padi dan lahan sering
tergenang banjir (Riau Terkini, 2012).
Beberapa upaya perlu dilakukan untuk mengatasi
beberapa permasalahan yang menjadi kendala tanaman padi
antara lain dengan meningkatkan produktivitas lahan dan
sistem produksi, mengembangkan varietas unggul yang
spesifik lokasi pada berbagai jenis lahan, membuka
lahan baru, serta menyediakan teknologi dan prasarana
produksi tepat guna. Upaya tersebut dapat dilakukan
dengan melaksanakan sistem yang terpadu guna mencapai
tujuan yang diinginkan (Mugiono dan Dwimahyani, 2008).
Penggunaan varietas unggul merupakan teknologi
yang handal dalam meningkatkan produksi pangan.
Teknologi ini lebih aman dan lebih ramah terhadap
lingkungan serta lebih efektif digunakan bagi petani
(Mugiono dan Dwimahyani, 2008).
4
Pemuliaan tanaman dengan bantuan mutasi merupakan
teknik yang banyak digunakan untuk menghasilkan
variasi-variasi sifat baru (Anonim, 2013). Mutasi
adalah suatu proses dimana suatu gen mengalami
perubahan struktur yang mengakibatkan perubahan
fenotipe yang diwariskan dari satu generasi ke generasi
berikutnya (Mugiono dan Dwimahyani, 2008).
Induksi mutasi dapat dilakukan dengan mutagen
fisik ataupun kimia. Beberapa di antara mutagen kimia
yang banyak digunakan adalah Ethyl Methane Sulphonate (EMS)
dan Sodium Azide (SA). Beberapa penelitian melaporkan
bahwa mutagen SA efektif digunakan untuk menghasilkan
mutan pada beberapa tanaman, seperti gandum, padi,
kedelai, lupin, sayuran dan tanaman hias. Sebagian
besar aplikasi SA memberikan pengaruh mutasi positif
terhadap hasil, ketahanan rebah, ketahanan penyakit,
umur panen dan tinggi tanaman (Fehr, 1987).
Aplikasi mutagen kimia dilakukan pada konsentrasi,
pH dan durasi perendaman yang tepat. Penggunaan mutagen
kimia dianjurkan aplikasinya pada pH 6 - 8 dengan
durasi perendaman 6 - 18 jam. Pemberian perlakuan
5
mutagen bervariasi menurut jenis tanaman dan lamanya
perendaman dengan konsentrasi berkisar antara 0,01 -
1,0 %. Konsentrasi mutagen SA yang dapat digunakan pada
tanaman padi adalah 0,5 – 2,0 mM dengan lama waktu
aplikasi 3 – 5 jam (Anonim, 2011)
Penelitian Rao dan Reddi (1986) memperlihatkan
pengaruh mutagen SA yang beragam pada tanaman padi.
Perlakuan SA pada konsentrasi 0,001 – 0,005 M dalam
buffer phosfat pH 3,0 dengan durasi 4 jam dan
praperlakuan 24 jam perendaman pada padi kultivar Viz
Jaya, IET-5656 dan Fujinimori memperlihatkan bahwa
persentase perkecambahan, kelulusan hidup, tinggi bibit
dan jumlah daun menurun pada populasi yang mendapat
perlakuan mutagen SA. Tinggi tanaman, jumlah cabang
malai, jumlah gabah per malai dan berat gabah per malai
menurun akibat perlakuan SA, sedangkan jumlah anakan
meningkat pada kultivar Viz Jaya dan Fujiminori. Jumlah
mutasi klorofil banyak ditemukan pada kultivar Viz Jaya
dibandingkan IET-5656 dan paling sedikit pada
Fujiminori. Selain itu ditemukan pula mutasi terhadap
morfologi seperti tinggi, setengah kerdil, kerdil,
6
cepat dan lambat berbunga, kaya protein dan bentuk biji
yang berbeda antara kultivar lainnya.
Berdasarkan dari penjelasan dan uraian di atas,
maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul
“Pertumbuhan Generatif dan Komponen Hasil Generasi M-1
Padi Gogo (Oryza sativa L.) Varietas Lokal dengan
Perlakuan Mutagen Sodium Azide (SA)”.
1.2. Tujuan Penelitian
Mengamati pengaruh konsentrasi mutagen SA dan
mendapatkan konsentrasi yang baik untuk meningkatkan
pertumbuhan generatif dan komponen hasil generasi M-1
pada dua varietas padi gogo.
1.3. Hipotesis
Terdapat perbedaan pertumbuhan generatif dan
komponen hasil generasi M-1 padi gogo varietas lokal
dengan perlakuan mutagen SA pada konsentrasi yang
berbeda.
7
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tanaman Padi (Oryza sativa L.)
Padi merupakan tanaman pangan yang bernilai
ekonomis tinggi bagi perekonomian Indonesia, yang
merupakan bahan makanan dalam menghasilkan beras.
Berdasarkan klasifikasinya padi termasuk ke dalam
kingdom: Plantae, divisio: Spermatophyta, klas:
Angiospermae, subklas :Monocotyledonae, ordo: Graminae, genus:
Oryza, dan spesies: Sativa (Surowinoto, 1982).
Morfologi padi terdiri dari dua bagian utama,
yaitu bagian vegetatif yang meliputi akar, batang dan
daun. Sedangkan bagian kedua adalah bagian generatif
yang meliputi malai yang terdiri dari bunga dan bulir-
bulir/buah padi (surowinoto, 1982).
Daun tanaman padi tumbuh pada batang dalam susunan
yang berselang-seling, pada setiap buku terdapat satu
daun. Tiap daun terdiri dari helaian daun, pelepah daun
yang membungkus ruas, telinga dan lidah daun. Daun yang
terakhir muncul adalah daun bendera (daun yang berada
di atas sekali), yang merupakan daun terpendek dan
8
terlebar dari daun yang lainnya. Anakan (tunas) mulai
tumbuh setelah memiliki 4 atau 5 daun dan tumbuh pada
dasar batang.
Anakan primer merupakan anakan yang tumbuh pada
kedua ketiak daun pada batang utama, sedangkan anakan
sekuder adalah anakan yang tumbuh pada ketiak anakan
primer dan seterusnya yang biasanya bertambah kecil
(Manurung dan Ismunadji, 1988).
Bunga padi berbuku dan berongga, dari buku batang
ini tumbuh anakan atau daun. Bunga atau malai muncul
dari buku terakhir pada setiap anakan produktif. Akar
padi adalah akar serabut yang sangat efektif dalam
penyerapan unsur hara, tetapi peka terhadap kekeringan.
Akar tanaman padi terkonsentrasipada kedalaman antara
10-20 cm kedalam tanah (Purwono dan Purnamawati, 2010).
Bagian generatif tanaman padi terdiri dari malai
dan buah padi. Malai adalah sekumpulan bunga padi
(spikelet) yang keluar dari buku paling atas. Pada malai
terdapat cabang-cabang bunga, jumlah cabang
mempengaruhi besar rendemen tanaman padi suatu
varietas. Bunga padi merupakan bunga telanjang dan
9
menyerbuk sendiri dengan mempunyai satu bakal buah,
benang sari dan tangkai putik. Benih padi merupakan
benih ortodok (dapat disimpan tahan lama) yang ditutupi
oleh palea dan lemma (Manurung dan Ismunadji, 1988).
Malai padi terdiri dari bulir-bulir yang timbul
dari buku paling atas dan pada tiap bulir terdapat satu
bunga padi. Ruas buku terakhir dari batang merupakan
sumbu utama dari malai. Pada waktu malai berbunga,
malai berdiri tegak kemudian terkulai bila bulir telah
berisi dan matang. Panjang malai dapat mencapai 20-30
cm. Bunga padi adalah bunga telanjang yang artinya
tidak memiliki perhiasan bunga. Berkelamin dua dengan
bakal buah berada di atas yang terdiri dari 6
benangsari, kepala sari besar dan mempunyai 2 buah
kepala putik yang tertutup oleh lemma, palea dan nerver
atau kulit gabah (Surowinoto, 1982).
Pertumbuhan tanaman padi dibagi tiga fase yaitu
vegetatif (awal pertumbuhan sampai pembentukan bakal
malai/primordia), reproduktif (primordia sampai
pembungaan), dan pematangan (pembungaan sampai gabah
matang). Tahap vegetatif dimulai dari stadia bibit yang
10
selanjutnya akan membentuk anakan padi yang jumlahnya
terus bertambah. Tahap produksi dimulai saat awal
pembentukan malai dan berakhir pada saat pembungaan,
yang berlangsung kira-kira 30 hari (Prasetyo, 2003).
Secara umum padi dibedakan dalam tiga jenis yaitu
varietas padi hibrida, varietas padi unggul dan
varietas padi lokal. Padi gogo sebagian besar masih
dalam jenis varietas lokal. Padi gogo adalah tanaman
pangan yang ditanam di lahan kering pada daerah yang
bercurah hujan rendah atau di dataran tinggi pada suatu
daerah yang kurang mampu dalam menampung air. Padi gogo
umumnya ditanam sekali setahun pada awal musim hujan
(Prasetyo, 2003).
Padi gogo memerlukan air sepanjang pertumbuhannya
dan kebutuhan air tersebut hanya mengandalkan pada
curah hujan. Padi gogo dapat tumbuh mulai dari dataran
rendah sampai dataran tinggi, daerah tropis/subtropis
pada 45° LU sampai 45° LS dengan cuaca panas dan
kelembaban tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Rata-rata
curah hujan yang baik adalah 200 mm/bulan selama 3
bulan berturut-turut atau 1500-2000 mm/tahun. Padi
11
dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Di dataran
rendah, padi gogo dapat tumbuh pada ketinggian 0-650 m
dari permukaan laut (dpl) dengan temperatur 22-27 °C
sedangkan di dataran tinggi 650-1.500 m dpl dengan suhu
19-23 °C (AAK, 1990).
Teknik budidaya tanaman padi gogo meliputi
persiapan benih, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan,
pemeliharaan dan pemanenan. Menurut Prasetyo (2003),
kebutuhan benih padi gogo adalah 40 kg/ha dengan
menggunakan jarak tanam 20 x 20 cm. Benih padi gogo
dapat ditanam dalam lubang yang dibuat dengan
menggunakan alat tugal pada kedalaman 2,5 cm. Penanaman
benih terlalu dalam dapat mengganggu perkecambahan dan
pertumbuhan tanaman muda (Partohardjono dan Makmur,
1989).
Kebutuhan hara bagi tanaman dapat dipenuhi dengan
melakukan pemupukan. Pupuk dasar yang diberikan untuk
tanaman padi gogo adalah Urea, TSP dan KCl dengan dosis
masing-masing pupuk 150 kg/ha, 135 kg/ha dan 60 kg/ha
dan (Prasetyo, 2003). Pemberian pupuk TSP dan KCl
dilakukan pada awal penanaman atau pada saat penugalan,
12
sedangkan pupuk Urea diberikan 3 kali dengan dosis 1/6
pada 14 hari setelah tanam, 1/2 dosis pada 42 hari
setelah tanam dan 1/3 dosis pada 55 hari setelah tanam
(Hantoro, 2007).
Upaya peningkatan produksi padi dapat dilakukan
melalui perbaikan varietas dengan teknik pemuliaan
mutasi atau perakitan varitas unggul yang telah ada
melalui persilangan dan bioteknologi. Kegiatan
penelitian tanaman padi sawah dengan teknik mutasi
telah banyak dilakukan, institusi BATAN telah berhasil
menciptakan varietas baru melalui pemuliaan dengan
teknik mutasi. Beberapa varietas padi yang telah
dilepas diantaranya adalah; Atomita 1, Atomita 2,
Atomita 3, Atomita 4, Situgintung, Cilosari, Woyla,
Meraoke, Kahayan, Winongo, Diah Suci, Yuwono dan
Mayang.
2.2. Pemuliaan Mutasi
Mutasi adalah perubahan genetik, baik perubahan
pada gen tunggal, sejumlah gen maupun susunan kromosom
yang merupakan sumber pokok dari semua keragaman
13
genetik dan merupakan bagian dari fenomena alam.
Perubahan dapat terjadi pada setiap bagian tanaman,
khususnya bagian sel yang aktif membelah (Yunita,
2009).
Teknik mutasi bertujuan untuk meningkatkan
keragaman genetik tanaman. Berdasarkan proses
terjadinya, perubahan genetik melalui mutasi terbagi
menjadi mutasi alami dan mutasi buatan (Agusrial,
2009). Mutasi alami adalah perubahan materi genetik
secara spontan di alam, sedangkan mutasi buatan terjadi
akibat pemberian mutagen secara sengaja untuk tujuan
pemuliaan tanaman (Soeranto, 2003).
Perbaikan sifat genetik dan agronomik tanaman
dapat dilakukan melalui pemuliaan secara konvensional
yaitu melalui persilangan, namun untuk tanaman yang
tidak dapat diperbaiki melalui persilangan ddiperbaiki
melalui mutasi induksi yang disebut mutasi buatan
(Soedjono, 2003). Mutasi induksi dapat dilakukan pada
tanaman dengan perlakuan bahan mutagen tertentu
terhadap organ reproduksi tanaman seperti biji, stek
batang, serbuk sari dan akar (Anonim, 2011). Mutasi
14
pada tanaman dapat menyebabkan perubahan pada bagian-
bagian tanaman, bentuk maupun warna dan perubahan pada
sifat-sifat lainnya. Tanaman hasil mutasi dinamakan
mutan, sedangkan generasi pertamanya biasa dinyatakan
dengan M-1 (Herawati dan Setiamihardja, 2000).
Hasil induksi mutasi dapat dilihat secara tidak
langsung. Hal ini disebabkan perlakuan mutagen akan
mengubah genotip alela dalam pola acak. Frekuensi
perubahan gen–gen terinduksi tergantung pada
konsentrasi mutagen.
Menurut Yanti et al, (2009), keberhasilan induksi
mutasi pada tiap-tiap jenis tanaman tergantung pada
jenis mutagen, kosentrasi mutagen, lama perlakuan dan
organ tanaman yang diperlakukan. Welsh (1991)
menyatakan bahwa kecepatan mutasi bervariasi sesuai
dengan konsentrasi mutagen, semakin tinggi konsentrasi
mutagen maka semakin sering terjadi mutasi, pemunculan
kromosom, kematian gen yang tidak diharapkan serta
kerusakan fisiologis pada tanaman.
Kerusakan fisiologis dapat disebabkan karena
kerusakan kromosom dan kerusakan sel di luar kromosom.
15
Pemisahan penyebab tersebut sulit dilakukan karena
keduanya terjadi pada generasi M-1 sebagai akibat dari
perlakuan mutagen. Kerusakan tersebut merupakan
gangguan fisiologis bagi pertumbuhan tanaman. Besarnya
kerusakan fisiologis tergantung pada besarnya
konsentrasi yang digunakan dan semakin tinggi
konsentrasi yang digunakan maka semakin tinggi
kerusakan fisiologis yang timbul. Molekul atau sel
tersebut akan rusak atau mati jika kerusakan terjadi
pada bagian molekul atau sel yang peka, namun apabila
kerusakan yang terjadi pada molekul atau sel yang tidak
peka, maka molekul atau sel tersebut tidak mati
(Mugiono, 2001).
Menurut Soeranto (2011), perubahan yang terjadi
pada materi genetik pada umumnya diekspresikan pada
fenotipe tanaman dan diturunkan pada generasi
berikutnya. Secara umum ekspresi mutasi pada fenotipe
tanaman dapat menuju ke arah positif maupun negatif dan
mutasi bahkan dapat kembali ke normal. Mutasi ke arah
negatif dapat menimbulkan kematian, ketidaknormalan,
sterilitas bahkan kerusakan fisiologis. Mutasi yang
16
terjadi kearah sifat positif dan terwariskan
kegenerasi-generasi berikutnya merupakan mutasi yang
dikehendaki oleh pemulia tanaman pada umumnya.
Kerusakan tanaman pada generasi M-1 dapat diukur
dengan beberapa cara seperti tinggi bibit atau
panjang akar pada umur tertentu, viabilitas,
kemungkinan dapat hidup di lapangan, kemampuan hidup
lama dan fertilitas (kesuburan). Kerusakan dapat pula
dihitung berdasarkan jumlah bunga per malai, jumlah
biji per malai, jumlah biji per tanaman, dan kemampuan
berbiak. Pengurangan kemampuan berbiak yang diakibatkan
oleh mutagen mempunyai bermacam-macam fenomena,
diantaranya adalah hambatan pertumbuhan yang
menghalangi pembungaan, bunga terbentuk namun kurang
memenuhi bentuk reproduksi yang diperlukan, bentuk
reproduksinya terjadi namun tepung sarinya mandul serta
biji terbentuk namun tidak mampu berkecambah (Herawati
dan Setiamihardja, 2000).
Dalam pemuliaan tanaman, penggunaan induksi mutasi
buatan tergantung pada jumlah variabilitas alami yang
ada. Apabila di alam telah tersedia alela yang
17
diinginkan, para pemulia memilih untuk menggunakan
alela tersebut daripada mengubah komposisi genetik dan
kromosom melalui mutagen. Induksi mutasi buatan relatif
lebih baik dilakukan pada tanaman yang menyerbuk
sendiri dibandingkan pada tanaman yang menyerbuk
silang. Pada tanaman yang menyerbuk sendiri, sebagian
besar alela dengan nilai adaptasi tinggi biasanya akan
cepat hilang karena sifat homozigositasnya sehingga
memperkecil variabilitas genetik. Dengan demikian
peluang memperoleh mutan dan variabilitas genetik yang
diinginkan melalui cara-cara buatan pada tanaman yang
menyerbuk sendiri secara teoritis lebih tinggi (Welsh,
1991).
Bahan mutagen yang sering digunakan dalam
penelitian pemuliaan tanaman dapat digolongkan menjadi
dua kelompok, yaitu mutagen kimia (chemical mutagen) dan
mutagen fisika (physical mutagen). Mutagen fisika bersifat
sebagai radiasi pengion (ionizing radiation) dan termasuk
di antaranya sinar-X, radiasi gamma, radiasi beta,
neutron dan partikel akselerator (Anonim, 2011).
Mutagen kimia umumnya berasal dari senyawa alkil
18
(alkylating agents) misalnya Ethyl Methane Sulfonate (EMS),
Hydrosilamine, Asam Nitrat, Acridine dan Sodium Azide (SA).
2.3. Mutagen Sodium Azide (SA)
Sodium Azida (NaN3) umumnya digunakan sebagai
pestisida dan dalam industri generator gas nitrogen
dapat memberi efek mutagen yang tinggi terhadap
sebagian besar organisme termasuk tanaman dan hewan.
Sodium Azida merupakan mutagen yang sangat efisien
terhadap tanaman gandum dan tanaman lainnya, namun
tidak terlalu berpengaruh terhadap hewan mamalia dan
tidak bisa memberi efek mutasi terhadap Neurospora,
Drosophila, dan Arabidopsis thaliana. Mutagenisitas Sodium
Azida dimediasi melalui produksi metabolit organik
azida dan sangat berpengaruh pada pH. Sodium Azida juga
dikenal sebagai logam berat yang berfungsi sebagai
penghambat enzim sehingga mempengaruhi metabolisme dan
respirasi sel hidup (Gruszka, 2005).
19
Rao dan Reddi (1986) melakukan penelitian tentang
SA pada konsentrasi 0,001 – 0,005 M dalam buffer pH 3,0
dengan lama perendaman 4 jam pada padi kultivar Viz
Jaya, IET-5656 dan Fujiminori dengan praperlakuan 24
jam perendaman dalam air. Mereka melaporkan bahwa
persentase perkecambahan, kelulusan hidup, tinggi bibit
dan jumlah daun menurun pada populasi yang mendapatkan
perlakuan mutagen SA.
Ando dan Montalvan (2001) mengaplikasikan mutagen
SA dengan pelarut buffer phosphat pH 3,0 dan Sinar
Gamma pada benih padi Brazillian rice kultivar IAC-
1246. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efisiensi
mutagen SA lebih tinggi dari sinar gamma pada
konsentrasi 1,0 mM dan 5,0 mM dan lebih rendah pada 0,5
mM dibandingkan sinar gamma 10, 15, 20 dan 30 Kr dengan
sumber Co60.
20
III. BAHAN DAN METODE
3.1. Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan di lahan Unit Pelayanan
Teknis (UPT) Fakultas Pertanian Universitas Riau, Jalan
Bina Widya Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan,
Kota madya Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan selama 4
bulan yang dimulai dari bulan April sampai Juli 2014.
3.2. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
benih padi yang berumur 1 bulan yang terdiri dari 2
varietas lokal dari Kabupaten Pelalawan (Korea dan
Lembuk Sawah), aquades, tanah, pupuk Urea, TSP dan KCl
serta pestisida Curaterr 3G, Delsene 200 MX dan
Dharmabas 500 EC. Alat yang digunakan dalam penelitian
terdiri dari cangkul, garu, parang, mistar ukur, sprayer,
label, tongkat sampel dan alat tulis.
3.3. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen yang
disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang
21
terdiri dari 2 faktor (faktorial), yakni 2 varietas
padi lokal (2 varietas) dan konsentrasi mutagen Sodium
Azide (5 taraf), sehingga terdapat 10 kombinasi
perlakuan. Masing-masing kombinasi perlakuan dilakukan
pengulangan sebanyak 4 kali, sehingga didapat 40 unit
percobaan. Setiap unit terdiri dari 30 bibit padi yang
telah mendapat perlakuan mutagen. Sampel ditetapkan
secara sengaja pada 10 individu yang dianggap mengalami
perubahan morfologi dan diduga mutan dari setiap unit
percobaan.
Adapun faktor perlakuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Faktor I : Varietas padi lokal (V), terdiri dari:
V1 : Varietas Korea
V2 : Varietas Lembuk Sawah
Faktor II: Konsentrasi Mutagen SA (S), terdiri dari:
S1 : 0 mM
S2 : 0,5 mM
S3 : 1,0 mM
22
S4 : 1,5 mM
S5 : 2,0 mM
Data hasil pengamatan dianalisis secara Analysis of
Variance (ANOVA). Uji lanjut yang digunakan adalah
Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5%.
Analisis ragam dilakukan dengan model linear berikut:
Yijk = µ + Ri + Gj + Nk + (GN)jk + εijk
Keterangan:
Yijk : Hasil pengamatan pada faktor varietas
padi taraf ke-j yang diberi
mutagen ke-k pada ulangan ke-i.
µ : Rata-rata.
Ri : Pengaruh ulangan.
Gj : Pengaruh varietas padi pada taraf ke-j.
Nk : Pengaruh konsentrasi mutagen pada taraf
ke-k.
(GN)jk : Interaksi antara varietas padi pada
taraf ke-j dengan konsentrasi
mutagen pada taraf ke-k.
ε : Efek error kedua faktor.
3.4. Pelaksanaan Penelitian
23
3.4.1. Persiapan Benih Padi
Benih padi yang digunakan dalam penelitian adalah
benih padi varietas lokal Kabupaten Pelalawan, yakni
varietas Korea dan Lembuk Sawah. Benih yang digunakan
berasal dari gabah bernas yang dipanen pada musim panen
2013.
3.4.2. Persiapan Medium Pembibitan
Tanah bagian atas dan pupuk kandang sapi
dikeringanginkan, kemudian diayak dengan ayakan pasir
yang memiliki diameter lubang ayak 0,5 cm2. Tanah dan
pupuk kandang dicampur dengan perbandingan 3:1 dan
diberi Furadan 3G dengan dosis 17 kg/ha dan diaduk
rata. Campuran medium selanjutnya dimasukkan kedalam
baki kecambah hingga lubangnya terisi penuh. Media
dalam baki kecambah disiram dengan air dan
diinkubasikan selama 1 minggu.
3.4.3. Pembuatan Sungkup Pembibitan
Sungkup dibuat untuk melindungi benih dan bibit
yang akan tumbuh dari terik cahaya matahari dan
serangan hama, terutama tikus. Rangka sungkup terbuat
24
dari kayu setinggi 40 cm berbentuk segi empat dengan
ukuran 3 m × 1,2 m dan atapnya terdiri dari kawat kasa
baja berwarna hitam.
3.4.4. Induksi Mutagen SA
Benih padi direndam dalam aquades selama 5 menit
untuk memisahkan gabah bernas dan hampa. Gabah bernas
dihitung sebanyak 200 benih dan ditambah 10 % benih
cadangan untuk setiap perlakuan, selanjutnya benih
diberi praperlakuan dengan perendaman dalam aquades
selama 48. Mutagen SA dilarutkan dalam 0,1 M buffer
phosfat pH 6,0 dengan konsentrasi yang sesuai untuk
masing-masing perlakuan yakni: 0 mM, 0,5 mM, 1 mM, 1,5
mM dan 2 mM. Benih padi yang telah mendapat
praperlakuan direndam dalam larutan mutagen selama 8
jam di dalam botol kaca sesuai dengan konsentrasi
masing-masing perlakuan sambil dilakukan pengadukan
dengan shaker. Setelah pengadukan, benih dicuci dalam
tiga tahap yaitu perendaman benih ke dalam aquades
sebanyak 5 kali 4 menit dan dilanjutkan dengan
perendaman dalam aquades sebanyak 4 kali 15 menit. Pada
25
tahap terakhir, benih dicuci dengan air sebanyak 6 kali
30 menit. Setelah pencucian, benih segera ditanam pada
medium semai di dalam baki kecambah.
3.4.5. Persiapan Bibit Padi
Bibit padi yang digunakan dalam penelitian adalah
bibit padi varietas lokal dari Kabupaten Pelalawan
yaitu varietas Korea dan Lembuk Sawah. Bibit yang
digunakan berasal dari gabah bernas yang dipanen pada
musim panen tahun 2013 yang telah disemai dan berumur 1
bulan setelah tanam.
3.4.6. Persiapan Lahan dan Bedengan
Penanaman bibit padi dilakukan di kebun percobaan
pada bedengan penelitian. Bedengan dibentuk dengan
ukuran 1 m x 1,2 m sebanyak 40 buah. Pengolahan tanah
dilakukan dengan cara pembalikan tanah dan dilanjutkan
dengan penghalusan tanah dan perataan tanah dengan
menggunakan cangkuldan garu. Pembuatan bedengan
dilakukan dengan penempatan yang sesuai dengan denah
(layout) percobaan.
26
3.4.7. Pemupukan
Pemupukan dilakukan dengan cara ditaburkan di
antara larikan tanaman dan kemudian ditutup kembali
dengan tanah. Pupuk dasar yang diberikan untuk tanaman
padi gogo adalah Urea, TSP dan KCl dengan dosis masing-
masing pupuk 18 g/plot, 16,2 g/plot dan 7,2 g/plot.
Pemberian pupuk TSP dan KCl dilakukan pada awal
penanaman atau pada saat penugalan, sedangkan pupuk
Urea diberikan 3 kali, dengan dosis 1/6 pada 14 hari
setelah tanam, 1/2 dosis pada 42 hari setelah tanam dan
1/3 dosis pada 55 hari setelah tanam.
3.4.8. Penanaman Bibit
Penanaman bibit dilakukan dengan memindahkan bibit
yang sudah berumur 30 hari dari pembibitan ke bedengan
percobaan yang telah dipersiapkan di kebun percobaan.
Pada setiap bedengan, lubang tanam disiapkan terlebih
dahulu dengan kedalaman 5 cm dan diameter 5 cm pada
jarak 20 cm dalam baris dan 20 cm antar baris sebelum
penanaman. Pengambilan bibit dilakukan dengan mendorong
27
bagian bawah daerah perakaran bibit ke atas hingga
bibit tersebut keluar dari lubang baki kecambah. Bibit
ditanam pada bedengan dengan meletakkan 1 batang per
lubang tanam. Jumlah bibit yang ditanam pada bedengan
disesuaikan dengan jumlah bibit yang ada pada baki
kecambah saat pembibitan.
3.4.9. Pemeliharaan
3.4.9.1. Penyiraman
Penyiraman dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi
dan sore hari atau disesuaikan dengan kondisi tanah di
bedengan percobaan.Penyiraman dilakukan dengan
menggunakan sprinkler yang telah terdapat di kebun
percobaan. Penyiraman dihentikan setelah tanah tampak
basah merata selama 5-10 menit.
3.4.9.2. Penyiangan
Penyiangan dilakukan terhadap gulma yang tumbuh di
sekitar tanaman pada bedengan percobaan dengan cara
dicabut dengan tangan.
3.4.9.3. Pengendalian Hama dan Penyakit
28
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan
menggunakan Curater 3G yang diberikan pada media tanam
di dalam bedengan 1 minggu sebelum tanam. Penyemprotan
Winder 2g/l air dilakukan untuk mengendalikan hama
penggerek batang dan walang sangit, selanjutnya
dilakukan penyemprotan Dithane M-45 80 WP 2 g/l air
dilakukan 2 minggu setelah bibit ditanam di bedengan
dan diulangi pada minggu ke 4, 6, dan 8 setelah bibit
ditanam.
3.5. Pengamatan
Pengamatan parameter pertumbuhan generatif tanaman
dilakukan pada semua tanaman sampel. Parameter yang
diamati dalam kegiatan penelitian ini adalah:
3.5.1. Umur Keluar Malai (hari)
Pengamatan umur keluar malai dilakukan dengan
menghitung jumlah hari yang dibutuhkan tanaman sejak
tanaman disemai setelah empat minggu hingga salah satu
anakan mengeluarkan malai pada satu tanaman.
3.5.2. Jumlah Anakan Produktif (batang)
29
Pengamatan dilakukan dengan menghitung seluruh
jumlah anakan yang mengeluarkan malai yang ada dalam
satu rumpun tanaman padi gogo. Pengamatan jumlah anakan
dilakukan setelah tanaman memasuki masa primordial
bunga.
3.5.3. Umur Panen (hari)
Pengamatan umur panen dilakukan dengan cara
menghitung jumlah hari yang dibutuhkan tanaman sejak
mulai tanaman disemai hingga salah satu malai yang
telah masak siap untuk dipanen.
3.5.4. Panjang Malai (cm)
Pengamatan dilakukan dengan mengukur panjang
malai, mulai dari pangkal sampai ujung malai.
3.5.5. Jumlah Cabang Primer Malai (buah)
Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah
cabang primer yang terdapat dalam satu malai sampel.
3.5.6. Jumlah Bulir Gabah per Malai (bulir)
30
Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah
semua semua gabah yang terdapat dalam satu malai
tanaman sampel.
3.5.7. Persentase Gabah Bernas (%)
Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah
gabah yang bernas, lalu dibagi dengan jumlah seluruh
gabah dalam satu malai dan dikalikan 100%.
3.5.8. Berat Gabah Bernas per Malai (g)
Pengamatan dilakukan dengan menimbang semua gabah
bernas yang terdapat dalam malai tanaman sampel.
3.5.9. Berat 100 Gabah Bernas per Rumpun (g)
Pengamatan dilakukan dengan mengambil gabah yang
bernas sebanyak 100 biji secara acak dari tiap rumpun
tanaman sampel, kemudian dilakukan penimbangan.
3.5.10. Berat Gabah Bernas per Rumpun (g)
Pengamatan dilakukan dengan menimbang semua bulir
gabah bernas yang tedapat dalam satu rumpun tanaman
sampel.
31
DAFTAR PUSTAKA
AAK (Aksi Agri Kanisius). 1990, Budidaya Tanaman Padi.Kanisius. Yogyakarta.
ACIAR-SADI. 2009. Peningkatan Hasil Panen Padi untukKebutuhan Pangan Nasional. Lembar Fakta ProgramACIAR. Agustus. Halaman 1. Makassar.
Agusrial. 2009. Teknik mutasi.http://www.infonuklir.com. Diakses tanggal 11Januari 2012.
Ando, A. and R. Montavan. 2001. Gamma-Ray Radiation andSodium Azide (NaN3) Mutagenic Efficiency in Rice.Crop Breeding and Applied Biotechnology. P. 339-346
Anonim. 2011. Mutasi dalam Pemuliaan Tanaman.http://solarmusik.blogspot.com/2011/12/mutasi-dalam-pemuliaan-tanaman.html. Diakses tanggal 26January 2013.
Anonim. 2013. Pemuliaan Tanaman.http://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_ tanaman. 4Maret 2014 (20:01)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), BadanPusat Statistik (BPS) dan United NationsPopulation Fund (UNFPA). 2013. Proyeksi PendudukIndonesia 2010-2035. BPS. Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Data Produksi PadiNasional. Jakarta.
Fehr, W.R. 1987. Mutation Breeding. In: Fehr, W.R.Principles of Cultivar Development. MacmillanPublishing, New York. P. 287-297
Gunawan, A. 2014. Produksi Padi Riau Menurun AkibatKonversi Lahan Sawah ke Sawit. Riaubisnis.com. 3Maret 2014. Pekanbaru.
32
Hantoro, F.R.P. 2007. Teknologi Budidaya Padi Gogo.Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa TengahBadan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Herawati, T dan R. Setiamihardja. 2000. PemuliaanTanaman Lanjutan. Program Pengembangan KemampuanPeneliti Tingkat S1 Non Pemuliaan Dalam Ilmu DanTeknologi Pemuliaan. Universitas Padjadjaran,Bandung.
Manurung dan Ismunadji, 1988. Morfologi dan FisiologiPadi. Padi Buku I. Pusat Penelitian danPengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
Mugiono dan Dwimahyani, I. 2008. Perbaikan VarietasPadi dengan Teknik Mutasi di Indonesia. SeminarNasional Padi. Juli: 139-151.
Mugiono. 2001. Pemuliaan Tanaman Dengan Teknik Mutasi.Puslitbang Teknologi Isotop dan Radiasi, Jakarta.
Partohardjono, S dan A, Makmur. 1989. PeningkatanProduksi Padi Gogo. Balai Penelitian TanamanPangan Bogor. Institut Pertanian Bogor.
Prasetyo, Y. T. 2003. Bertanam Padi Gogo Tanpa OlahTanah. Penebar Swadaya. Jakarta.
Purwono dan Purnamawati, H. 2010. Budidaya 8 JenisTanaman Pangan Unggul. Penebar Swadaya. Jakarta.
Rao, D.R.M and T.V.V.S. Reddi. 1986. Azide Mutagenesisin Rice. Proceedings Plant Science. P. 205-215.
Riau Terkini.com. 2012. 2011 Produksi Padi Riau Turun 4Persen. 3 Februari. Pekanbaru.
Soedjono, S. 2003. Aplikasi Mutasi Induksi dan VariasiSomaklonal dalam Pemuliaan Tanaman. Jurnal LitbangPertanian. 70-78
Soeranto. 2003, Peran IPTEK Nuklir dalam PemuliaanTanaman untuk Mendukung Industri Pertanian,
33
Prosiding Pertemuan dan Presentasi IlmiahPenelitian Dasar Ilmu Pengetahuan dan TeknologiNuklir P3TM-BATAN,Yogyakarta, 08 juli 2003.
Soeranto. 2011. Aplikasi Iptek Nuklir dalam PemuliaanTanaman. Pusat aplikasi teknologi isotop danradiasi, badan tenaga nuklir nasional (BATAN)Jakarta.
Surowinoto, S. 1982. Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo.Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Welsh, J. R. 1991. Dasar-dasar Genetika dan PemuliaanTanaman (Terjemahan). I. Penerbit Erlangga.Jakarta. 224 hal.
Yanti, Y., T. Habazar, Mardinus dan Mansyurdin. 2009.Perubahan Bentuk Planlet Pisang Raja Sereh HasilMutasi dengan Ethyl Methane Sulphonate (EMS)secara invitro. 104-108
Yunita, R. 2009. Pemanfaatan Variasi SomaklonalDanseleksi In Vitro Dalam Perakitan TanamanToleran Cekaman Abiotik. Balai Besar Penelitiandan Pengembangan Bioteknologi dan SumberdayaGenetik Pertanian. Bogor.
KegiatanBulan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
Pemberian PerlakuanPersemaian danPemeliharaaan BibitPengolahan TanahPenanamanPemupukan anorganik setengah dosisanjuranPengamatan TanamanPenyiramanPenyiangan GulmaPengendalian Hama
V1S1 V1S2 V1S3 V1S1
V1S4 V1S4
V1S2
V1S4
V1S5
V1S1
V1S5V1S5
V1S3 V1S3 V1S4
V1S5
V2S5
V2S2
V1S1
V2S1
V1S3
V1S2
V2S1
V1S2
V2S2
V2S4 V2S5
V2S4 V2S5 V2S3
V2S1
V2S1
V2S3
V2S2 V2S2 V2S3
V2S3 V2S4 V2S5 V2S4
Lampiran 2. Denah penelitian yang disusun berdasarkan
rancangan acak kelompok (RAK)
IV II I III
Ketarangan:
1. S1, S2, S3, S4, dan S5 : Mutagen SA
2. V1 dan V2 : Varietas padi gogo
3. I, II, III, dan IV : Ulangan
U
a
a