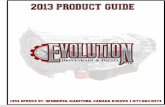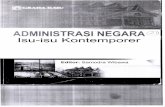Media Massa dan Isu Radikalisme Islam
Transcript of Media Massa dan Isu Radikalisme Islam
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 i
Diterbitkan Oleh:Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sebelas Maret
Surakarta
KomunikasiKomunikasi MassaMassaJurnal
Vol. 7 No. 2, Juli 2014 ISSN: 1411-268X
ii Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Jurnal Komunikasi MassaTerbit dua kali setahun
Hak cipta dilindungi Undang-undang.Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi dalam pelbagai bentuk mediumbaik cetakan, elektronik, maupun mekanik.ISSN: 1411-268
Diterbitkan Oleh:Program Studi Ilmu KomunikasiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sebelas MaretSurakarta
Desain dan tata letak oleh Sri Hastjarjo
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 iii
Dewan RedaksiPemimpin RedaksiDra. Prahastiwi Utari, M.Si, PhD.
Redaktur PelaksanaTanti Hermawati, S.Sos., M.SiDra. Sofi ah, M.SiSri Herwindya Baskara Wijaya, S.Sos, M.SiEka Nada Shofa Alkhajar, S.Sos., M.Si
Redaktur AhliProf. Drs. Pawito, PhD.Drs. Mursito BM, SUDr. Sri Hastjarjo
Mitra BestariProf. Sasa Djuarsa Senjaya, PhD. (Universitas Indonesia)Prof. Dr. Dedi Mulyana(Univeritas Padjadjaran Bandung)Prof. Pamela Nilam, PhD.(University of Newcastle, Australia)
Alamat Redaksi:Program Studi Ilmu KomunikasiFISIP Universitas Sebelas MaretJl. Ir. Sutami 36-A, Kenthingan, Jebres Surakarta, 57126Tlp./Fax: (0271) 632478E-mail: [email protected]
Pemasar/sirkulasiBudi Aryanto, Tlp. (0271) 632478
Jurnal Komunikasi Massa terbit dua kali dalam setahun, diterbitkan oleh Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai media wacana intelektualitas bagi pengembangan Ilmu Komunikasi. Dewan Redaksi mengundang para pelajar, peneliti, dan praktisi bidang komunikasi dan media massa untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel ilmiah, maupun hasil penelitian. Syarat penulisan artikel tercantum di halaman sampul belakang. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit naskah tanpa mengurangi esensi isi.
Vol. 7 No. 2, Juli 2014ISSN: 1411-268X
Daftar IsiStrategi Komunikasi Pemasaran Rumah Sakit Sebagai Upaya Peningkatan Publisitas (Pengembangan Model Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Tiga Rumah Sakit Swasta)Tanti Hermawati, dkk ................................................ 111
Watergate Scandal Reassessed: Mass Media’s Watchdog Role and Its Impact on American Political SystemSalieg Luki Munestri ................................................. 121
Film dan Konstruksi Citra Politik (Analisis Wacana Politik Pencitraan dalam Film Jokowi)Erwin Kartinawati ..................................................... 133
Wacana Revitalisasi Pancasila di Media (Studi Analisis Framing Pemberitaan tentang Revitalisasi Pancasila di Harian Kompas Tahun 2013)Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk ......................... 147
Media Massa dan Isu Radikalisme IslamLeni Winarni .............................................................. 159
Media Komunitas, Kredibilitas dan Relasi Sosial: Framing Komunikator dalam Citizen JournalismMahfud Anshori......................................................... 167
Peran Komunikator dalam Ritual Hajatan (Studi Kasus Peran Tokoh Terop dalam Hajatan Etnis Madura di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)Adi Inggit Handoko ................................................... 177
Pemikiran Harold Innis terhadap Pengembangan Ilmu KomunikasiA. Eko Setyanto, dkk .................................................. 191
Film, Feminisme, dan Budaya: Kajian Feminisme Pada Karakter M dalam Serial James BondDewanto Putra Fajar ................................................. 203
Perempuan di Media Online: Representasi Perempuan dalam Website www.kompas.comMonika Sri Yuliarti ................................................... 215
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 111
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 111-120
Strategi Komunikasi Pemasaran Rumah Sakit Sebagai Upaya Peningkatan Publisitas
(Pengembangan Model Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Tiga Rumah Sakit Swasta)
Tanti HermawatiPrahastiwi Utari
Hamid Arifi nProgram Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
AbstrakPrivate hospital in Surakarta although have implemented these types of marketing communications, but the packaging is still not well ordered. So this problem is more focused on how the existing marketing communications in three private hospitals made a model of the communication strategy, so that health messages and existing services delivered in an integrated manner. The method used in this research is descriptive qualitative in-depth observations on society. Data obtained by interviewing informants. Selection of research informants with purposive sampling to obtain information on the characteristic of the target community as a hospital.Of the research will be able to generate a model of integrated marketing communication strategy, with the identifi cation of marketing communication applied in hospitals. Model of integrated marketing communication strategies can be used as inputs hospital as a basis for policy-making institution of delivering a message to the community hospital is packaged in an integrated manner so as to increase publicity.Keywords: Models, Strategies, Integrated Marketing Communications
Pendahuluan
Rumah sakit merupakan salah satu perusahaan yang awalnya merupakan perusahaan non profi t. Rumah sakit atau sarana kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan sebagai kesatuan sosio-ekonomi mengandung unsur norma moral dan norma etika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam perkembangannya, rumah sakit
tidak lagi hanya merupakan perusahaan non profi t yang bergerak di bidang sosial saja, namun sudah menuju profi t oriented. Walaupun ada orientasi ke arah profi t, namun tetap ada etika dan moral tertentu yang harus dipatuhi oleh semua rumah sakit di Indonesia.
Organisasi atau perusahaan harus mengetahui siapa target pasarnya dan dengan cara apa harus mengkomunikasikan
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
112 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
tentang perusahaannya. Apabila salah dalam menentukan strategi, maka target yang dituju tidak akan tercapai, sebagaimana yang dikemukakan Henley ( 2001 :180) : Organizations can fail to reach their objectives because they miss the mark when it comes to communicating messages to members, potential donors or other important constituencies such as leader and government offi cials.
Dengan strategi komunikasi yang terencana dengan baik dimana dengan penggunaan jenis komunikasi pemasaran yang telah diterapkan di beberapa perusahaan seperti, periklanan, personal selling, sales promotions, public relations dan direct marketing akan membawa dampak yang baik pada peningkatan publisitas sebuah perusahaan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa tiga rumah sakit yang menjadi obyek penelitian telah melakukan lima jenis komunikasi pemasaran (periklanan, personal selling, sales promotions, public relations dan direct marketing) namun dari focus group discussion dengan para tim manajemen menunjukkan bahwa masing-masing jenis komunikasi pemasaran masih dijalankan sesuai dengan kebutuhan sesaat. Padahal kalau ingin memposisikan sebagai rumah sakit dengan brand tertentu, tentunya masyarakat perlu mengenali seperti apa rumah sakit tersebut.
Membangun image perusahaan supaya terkenal di masyarakat memang tidak bisa diwujudkan dalam waktu sesaat, namun diperlukan adanya perencanaan yang matang dan strategi khusus. Tiga rumah sakit (RS PKU Muhammadiyah Surakarta, RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu) dipilih sebagai obyek riset dan makalah ini mencoba membahas temuan dari riset terkait tentang strategi pemasaran terpadu yang diterapkan.
Tinjauan Pustaka1). Komunikasi
Komunikasi berasal dari kata communication (bahasa Latin) yang berarti pemberitahuan, pemberian bagian (dalam sesuatu), pertukaran, dimana si pembicara meng harapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Kata sifatnya adalah communis artinya bersifat umum atau bersama-sama. Kata kerjanya adalah communicare, artinya berdialog, berunding atau bermusyawarah. (Daryanto, 2010:63). Komunikasi dapat dianggap proses penciptaan suatu kesamaan atau suatu kesatuan pemikiran antara pengirim dan penerima (Shimp, 2003:163). Kunci utama dari defi nisi ini adalah diperlukan kesamaan pikiran yang dikembangkan antara pengirim dan penerima jika terjadi komunikasi. Kesamaan pemikiran ini membutuhkan adanya hubungan saling berbagi (sharing) antara pengirim (seperti pengiklan) dengan penerima (konsumen).
Mencermati pada defi nisi komunikasi tersebut, dapat diketahui bahwa di dalam komunikasi terkandung unsur-unsur pemberi pesan/sumber, isi pesan, proses pemberitahuan, penerima pesan dan umpan balik. Secara iengkapnya, semua aktifi tas komunikasi melibatkan delapan elemen berikut : Sumber, Penerjemah, Pesan, Saluran, Penerima, Interpretasi, Gangguan dan Umpan balik.
Sumber atau source adalah orang atau kelompok orang, misalnya sebuah perusahaan, yang memiliki pemikiran (ide, rencana pelayanan, dan lain-lain) untuk disampaikan kepada orang atau kelompok orang lain. Dari sumber ini kemudiaan ada penerjemah (encoding) pesan untuk mencapai pemikiran ke dalam bentuk-bentuk simbolis.
Sumber tersebut memilih tanda-tanda spesifi k dari berbagai kata, struktur kalimat, symbol dan unsur non
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 113
verbal yang amat luas pilihannya, untuk menerjemahkan sebuah pesan hingga dapat dikomunikasikan dengan efektif kepada khalayak sasaran. Message atau pesan adalah suatu ekspresi simbolis dari pemikiran sang pengirim. Saluran adalah yang dilalui pesan dari pengirim kepada penerima. Sedangkan penerima adalah orang yang dengan mereka, pihak pengirim berusaha untuk menyampaikan ide-idenya. Noise merupakan gangguan yang kadang terjadi dalam proses komunikasi. Unsur yang terakhir adalah feedback atau umpan balik, memungkinkan sumber pesan memonitor seberapa akurat pesan yang disampaikan dapat diterima.
Dalam penelitian strategi komunikasi, fi hak yang paling berperan dalam hal ini adalah komunikator atau sumber. Terkait dengan sebuah institusi, maka komunikasi yang terjadi adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi di dalam organisasi ataupun antar organisasi, baik bersifat formal maupun informal. Komunikasi informal adalah yang terjadi di luar struktur organisasi. (Daryanto,2010: 37).
Fiske dan Hartley (1983:79) menjelas-kan beberapa faktor yang menjembatani pengaruh komunikasi :a) Semakin besar monopoli sumber
komunikasi yang diterima, maka semakin besar pula perubahan dan pengaruh dalam selera.
b) Pengaruh komunikasi akan lebih besar bila pesan tadi dilandasi dengan opini, kepercayaan dan disposisi dari penerima.
c) Komunikasi dapat menghasilkan pergeseran yang efektif pada suara-suara yang asing, suara yang lembut, piranti peripheral yang tidak ada pada system syaraf penerima.
d) Komunikaasi akan lebih efektif bila sumber itu benar-benar dipercaya akan
memberikan ketrampilan, status yang tinggi, obyektivitas atau kemampuan, dan bila sumber tadi secara khusus mempunyai kekuatan daan dapat diidentifi kasikan.
Berkaitan pesan yang disampaikan pihak rumah sakit dalam komunikasi pemasarannya, pesan itu sendiri pada dasarnya bersifat abstrak. Untuk membuatnya konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh komunikan, maka diciptakan sejumlah lambang.
Lambang komunikasi disebut juga bentuk pesan, yakni wujud konkret dari pesan. Pesan inilah yang harus dikemas dengan baik apabila mempunyai tujuan agar dapat dimengerti, difahami dan diterima sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penyampai pesan.
2. StrategiDalam kerangka berpikir strategis
(strategic thinking), ketika orientasi berfi kir hanya sebatas company (berpikir mikro), maka hanya akan memperoleh result yang bersifat short term. Yang dimaksud strategi disini adalah kemampuan pemimpin dalam membangun sebuah visi yang akan mengarahkan organisasi di masa depan atau membangun model bisnis yang menjadi acuan bagi organisasi dalam mengalokasi sumber daya yang dimiliki. Visi sebuah perusahaan ibarat kapal besar organisasi berlayar ke arah yang benar. Dalam mengarahkan organisasi melalui visi yang menjangkau jauh ke depan inilah yang dimaksud strategy dalam konsep The Leadership Philosophy (Arif Yahya, 2013 : 108).
Pada awalnya konsep strategi (strategy) didefi nisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan (ways to Achieve ends). (Ismail Sholihin, 2012:24). Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen, strategi tidak hanya didefi nisikan hanya semata-
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
114 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
mata sebagai cara untuk mencapai tujuan karena strategi dalam konsep manajemen strategic mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri melalui berbagai keputusan strategis. Yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Hal ini diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan.
Melihat strategi merupakan salah satu bagian dari rencana (plan), ternyata tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap berbagai fenomena strategis dalam dunia bisnis.. Terdapat dua karakteristik stratrgi yang sangat penting, yang pertama adalah, strategi direncanakan terlebih dahulu secara sadar dan sengaja mendahului berbagai tindakan yang akan dilakukan berdasarkan strategi yang dibuat tersebut. Kedua, strategi kemudian dikembangkan dan diimplementasikan agar mencapai suatu tujuan.
Strategi sebagai sebuah “plan” me-rupakan suatu rencana yang terpadu, komprehensif dan terintregasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pokok perusahaan dapat dicapai. Sedangkan apabila strategi dikatakan sebagai manuver merupakan sesuatu yang spesifi k untuk member isyarat mengancam kepada pesaing perusahaan.
Selain itu strategi juga menunjukkan perspektif dari para pembuat keputusan strategis di dalam memandang dunianya. Strategi merupakan pemikiran yang hidup di dalam benak pembuat keputusan strategis dan seperti halnya ideology atau budaya kemudian berusaha untuk dijadikan nilai bersama di dalam organisasi.
Dari uraian di atas, menurut Mintzberg dalam Sholihin (2012:25) mendefi nisikan strategi dengan memperhatikan berbagai dimensi dari konsep strategi yang dinamakan “5P’s of Strategy” yaitu : Strategy as a Plan, Strategy
as a Ploy, Strategy as a Pattern, Strategy as a Position dan Strategy of Perspective.
Rencana pada tingkat korporat (corporate-level plan) mencakup di dalamnya penetapan visi, misi dan tujuan-tujuan korporasi, strategi yang dikembangkan dan sruktur korporasi yang dipilih oleh perusahaan. Misi dan tujuan korporasi selanjutnya akan menjadi pedoman untuk menentukan tujuan divisi/unit bisnis dan tujuan berbagai fungsi organisasi. Untuk mencapai tujuan korporasi, maka dibuatlah strategi pada tingkat korporat (corporate level strategy), strategi ini akan memberikan arah dalam industry dan pasar mana perusahaan akan bersaing. Strategi pada tingkat korporasi akan merumuskan dengan spesifi k berbagai tindakan yang akan diambil untuk memperoleh keunggulan kompetitif/keunggulan bersaing dengan memilih dan mengelola sejumlah bisnis yang berbeda (Sholohin, 2012: 10).
3. Komunikasi PemasaranPersaingan dalam dunia usaha
merupakan hal yang tak terelakkan dalam sistem ekonomi pasar, seiring dengan tumbuhnya perekonomian. Persaingan memaksa perusahaan menerapkan konsep pemasaran yang berbeda dengan perusahaan lain untuk terus memajukan perusahaan. Boyd (2000) mendefi nisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial yang melibatkan kegiataan-kegiaataan penting yang memungkinkan individu dan perusaahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran ( Boyd, 2000: 4).
Konsep inti dari pemasaran adalah pertukaran atau exchange. Alasaan yang mendasari bahwa konsep inti dari pemasaran adalah pertukaran yaitu bahwa
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 115
seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lainnya merupakan pertukaraan. Tak ada seorang individu pun yang mendapatkan sesuatu (barang atau jasa) tanpa memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung. Alasan terjadinya pertukaran adalah untuk memuaskan kebutuhan (Sutisna, 2002: 264).
Shimp (2003: 106) menyebutkan usaha komunikasi pemasaran diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan di bawah ini :a) Membangkitkan keinginan akan suatu
kategori produkb) Menciptakan kesadaran akan merk c) Mendorong sikap positif terhadap
produk dan mempengaruhi niatd) Memfasilitasi pembelian
Dalam proses penerimaan suatu produk, konsumen akan terfokus pada proses mental yang dilalui, mulai dari mendengar informasinya sampai memutus-kan menggunakan produk tertentu. Dengan informasi yang dikomunikasikan dengan baik, mendorong konsumen untuk mencari informasi mengenai suatu produk yang kurang diketahuinya.
Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah pakar mengenai defi nisi komunikasi pemasaran terpadu (IMC). Shimp (2001: 24) menyebutkan bahwa IMC adalah proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan IMC adalah mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya. IMC menganggap, seluruh sumber yang dapat menghubungkan pelanggan atau calon pelanggan dengan produk atau jasa dari suatu merek atau perusahaan, adalah jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan di masa datang.
Defi nisi serupa juga dikemukakan oleh Kotler, et al ( 2004: 220) yang merumuskan IMC sebagai konsep yang melandasi upaya perusahaan untuk mengintegrasikan dalam rangka menyampaikan pesan yang jelas, konsisten dan persuasif mengenai organisasi dan produknya. Dalam bukunya Service Management and Marketing, Gronroos (2000: 221) mendefi nisikan IMC sebagai strategi yang mengintegrasikan media marketing tradisional, direct marketing, public relations dan media komunikasi pemasaran lainnya, serta aspek-aspek komunikasi dalam penyampaian dan konsumsi barang dan jasa, layanan pelanggan dan customer encounters lainnya.
Jadi IMC adalah integrasi untuk menangani secara proporsional dan tidak lagi terfokus hanya pada pelanggan semata, tetapi perusahaan perlu mendengar masukan dari semua pihak (stakeholder) termasuk konsumen dan setiap titik kontak dengan public menyebarkan pesan komunikasi mulai dari produk, logo perusahaan, pengalaman menggunakan produk, iklan, layanan pelanggan, berita di media massa sampai rumor yang mampu menyebar secara berantai.
Komunikasi pemasaran selalu melalui proses dimana perusahaan menyampaikan pesan kepada stakeholder dalam mencapai tujuan perusahaan, untuk menginformasikan, mempengaruhi, mengingatkan atau membangun citra perusahaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chen, Chien Wei dalam Journal of Global Marketing : “ Marketing communication is a process through which a fi rm conveys a series of messages to stakeholders in pursuit of the fi rm’s goals-to inform, persuade, remind or build images to delineate product ar service” (2011: 40).
Dalam penerapan komunikasi pemasaran yang terpenting adalah pesan
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
116 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
yang disampaikan harus dikemas secara terpadu dari berbagai jenis komunikasi pemasaran yang ada. Produk atau pelayanan baru, seperti halnya pelayanan yang ada di rumah sakit, apabila akan dikenalkan kepada masyarakat perlu dikomunikasikan dengan pesan yang tepat. Misalnya akan menggunakan kelima jenis komunikasi pemasaran secara menyeluruh, maka semuanya harus menyampaikan pesan yang sama.
Dalam Journal of Global Marketing dikatakan :
“New product performance will be enhanced to the extent that the fi rm undertakes programs to generate communication visibility and simultaneously maintain a reasonably level of consistency in messages. Such fi ndings are in accordance with the integrated marketing communication principle that aims to ensure consistency of message and the complementary use of media” (Chen, Chien Wei, 2011: 411)
Dalam penelitian ini, komunikasi pemasaran yang akan ditekankan adalah periklanan, personal selling, sales promotions, public relations dan direct marketing. Kelima komponen inilah yang akan diterapkan oleh rumah sakit secara terintegrasi. Pesan dari masing-masing jenis komunikasi pemasaran akan dibuat dengan bercirikan emphaty pada masyarakat dan keterpaduan pesan. Dengan demikian brand image sebuah rumah sakit akan terbentuk sesuai dengan visi dan misi rumah sakit tersebut.
Model Integrated Marketing Communication, menurut A. Adji Watono dan Maya C. Watono menyebutkan Model tersusun dari tiga lingkaran (circle) yang disebut sebagai Discovery Circle , Intent Circle dan Strategy Circle. (2011:79) Discovery Circle memuat elemen-elemen yang diarahkan untuk mengeksplorasi lingkungan eksternal (pasar, konsumen, pesaing) maupun lingkungan internal (di dalam produk/merek/nama perusahaan)
dalam rangka menemukan insight-insight untuk pengembangan brand.
Intent Circle akan ditemukan masalah (problem) dan keuntungan (advantage) yang muncul setelah dilakukan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal. Berdasarkan identifi kasi masalh dan peluang akan ditentukan tujuan dan arah (intent) dari pengembangan komunikasi pemasaran yang akan dilakukan terhadap sebuah brand.
Strategy Circle berisi langkah-langkah penyusunan strategi dan taktik brand dalam memenangkan persaingan pasar setelah tujuan dan arah pengembangan dirumuskan, maka penyusunan strategi, taktik dan program dilakukan untuk bisa merealisasikan tujuan dan arah tersebut. Setelah dirumuskan, strategi, taktik dan program akan dieksekusi di lapangan dan akan dievaluasi secara terus menerus sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat diwujudkan.
Dalam Journal Health Marketing Quarterly disebutkan :
The three models work seguentially as a guide to generating out-standing communication results that marketers can use to guide their effort to generate effective communication programs : 1) Identifi cation of storage communication elements. The fi rst model helps marketing communicators think through their strategic message, audiences and actions sought. 2) The business communication model provides a tactical overview of how to deliver marketing communication. 3) Communication Management Process depict the operational day to day process of executing all the communication activities. (Wlliam R. Gombeski et.al, 2007: 97)
Metodologi
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Lokasi penelitian RS PKU Muhammadiyah Surakarta, RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu. Data
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 117
primer dari para informan yang berada di tiga wilayah lokasi penelitian (Surakarta, Karanganyar dan Klaten). Sedangkan data sekunder diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.
Pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, Focus Group Disscusion (FGD) dan dokumentasi. Validitas data adalah dengan teknik triangulasi data (sumber). Analisis data yakni model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sutopo (2002: 94). Dalam model analisis interaktif ini terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dengan verifi kasinya.
Sajian dan Analisis Data
1. RS PKU Muhammadiyah SurakartaRS PKU Muhammadiyah Surakarta
memilih periklanan, personal selling, sales promotions, public relations dan direct marketing secarang lengkap. Dari hasil wawancara dengan manajemen sebagai informan internal rumah sakit dikatakan bahwa rumah sakit telah menggunakan semua jenis komunikasi pemasaran sebagai upaya meningkatkan publisitas.
Periklanan sebagai salah satu komunikasi pemasaran dipilih rumah sakit digunakan dengan beriklan tidak secara vulgar. Karena ada aturan sebuah rumah sakit apabila ingin beriklan. Sehingga iklan yang dilakukan biasanya dengan cara men-support pada acara-acara tertentu, misalnya seminar atau ikut mensponsori kegiatan tertentu, kemudian rumah sakit memasang spanduk disitu. Personal selling dilakukan rumah sakit dengan cara mengajak kerjasama dengan berbagai instansi lain, misalnya agar sebuah perusahaan mengansuransikan karyawannya yang bekerjasama dengan rumah sakit. Atau menawarkan kepada rumah sakit yang
lebih kecil atau bidan yang menerima persalinan dengan rawat inap agar merujuk pasiennya apabila ada pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sales Promotions yang dilakukan rumah sakit ini dengan cara memberikan discount pada pasien yang mempunyai kartu anggota Muhammadiyah, memberikan keringanan biaya pada pasien yang kurang mampu dan menawarkan beberapa kemudahan untuk mengurus keringanan biaya. Public Relations telah banyak dilakukan oleh rumah sakit ini, diantaranya menyelenggarakan pengobatan gratis, khitanan massal, ikut terlibat memeriahkan car free day di Solo dengan menggunakan costum medis. Direct marketing dilakukan diantaranya dengan membuat website rumah sakit yang bisa diakses secara umum.
Sedangkan dari pihak eksternal (pasien, keluarga pasien, masyarakat sekitar), ternyata apa yang dilakukan oleh rumah sakit, ada sebagian yang diketahui oleh pihak eksternal, tetapi ada pula sebagian yang tidak diketahui oleh masyarakat. Mengenai iklan rumah sakit, hanya mereka yang lewat saja yang pernah membaca spanduk yang dipasang oleh PKU. Namun ada juga masyarakat/pelnggan rumah sakit yang menyatakan pernah melihatnya. Personal selling yang pernah dilakukan rumah sakit di mata pasien atau masyarakat kurang tersampaikan kepada mereka.
Pasien yang datang biasanya tidak mengetahui tentang kerjasama yang dilakukan rumah sakit dengan instansi tertentu yang dijalinnya. Mereka datang berobat ada yang membayar sendiri, ada pula yang menggunakan jaminan kesehatan. Namun, konsumen menyatakan bhwa mereka mengetahui dari kepala desa yang memberi tahu atau ada juga tetangganya. Sales promotions juga belum semuanya memahami. Memang ada
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
118 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
yang menggunakan fasilitas masyarakat miskin. Namun ada pila masyarakat yang merasa keberatan mengenai biaya rumah sakit, tetapi tidak mendapatkan keringanan. Direct marketing yang diujudkan dalam bentuk website ternyata belum sepenuhnya diakses oleh pasien/ masyarakat. Namun ada pula yang pernah membacanya sekilas.
Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa rumah sakit perlu mengetahui karakteristik masyarakat, khususnya pengguna jasa layanan rumah sakit. Sehingga apabila akan menentukan komunikasi apa yang dipilih, pesan akan tersampaikan sesuai kepada target yang menjadi sasarannya. Hal ini sangat diperlukan survei oleh pihak rumah sakit baru membuat perencanaan komunikasi pemasaran terpadunya.
2. RS PKU Muhammadiyah KaranganyarHasil penelitian di rumah sakit ini tidak
berbeda jauh dengan rumah sakit yang pertama. Dari pihak internal rumah sakit, ketika diwawancarai, menyebutkan bahwa RS PKU Muhammadiyah Karanganyar telah melakukan kelima jenis komunikasi pemasaran ( periklanan, personal selling, sales promotion dan direct marketing). Namun ketika di cross check kepada masyarakat, khususnya pasien yang menggunakan jasa layanan, belum semua komunikasi pemasaran yang dipilih oleh tumah sakit dimengerti dan difahami. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa periklanan pernah dilakukan di TA TV dalam kegiatan tertentu.
Selain itu juga menggunakan leafl et yang isinya hal-hal mengenai PKU Karanganyar. Personal selling juga telah dilakukan dengan mendatangi bidan untuk merujuk ibu yang akan melahirkan membutuhkan penanganan dokter kandungan. Sales promotions dilakukan dengan cara memberikan keringanan
biaya pada pasien kurang mampu, memberi kartu discont pada anggota Muhammadiyah yang memiliki KTA. Public Relations dilakukan dengan pernah mengadakan seminar, sedangkan direct marketing masih dalam proses.
Namun demikian pesan yang disampaikan kepada masyarakat belum terintegrasi dengan baik. Masing-masing komunikasi pemasaran berjalan sendiri0sendiri . Ketika di cross check kepada masyarakat, ternyata sebagian pasien tidak mengetahui kalau rumah sakit pernah beriklan melalui televisi. Namun ada yang pernah membaca leafl et.
Kartu discount juga belum sepenuhnya diketahui pasien. Hal ini memang dibutuhkan strategi khusus, agar pesan yang ingin disampaikan rumah sakit ke;ada masyarakat tidak sia-sia.
3. RSU PKU Muhammadiyah DelangguRSU PKU Muhammadiyah Delanggu
juga telah menggunakan kelima jenis komunikasi pemasaran (periklanan, personal selling, sales promotions, public relations dan direct marketing). Data yang diperoleh dari internal rumah sakit (tim manajemen) menyebutkan bahwa rumah sakit pernah melakukan iklan di berbagai media. Kemudian mengenai personal selling, rumah sakit juga selalu mengadakan kunjungan ke beberapa kalurahan, ke bidan, kefi hak yang menjalin kerjasama dan lain-lainnya. Sedangkan sales promotions dengan memberikan keringanan biaya, menggunakan jamkesmas, jampersal yang sekarang berubah menjadi BPJS.
Public Relations dilakukan dengan mengadakan pengobatan gratis, khitanan massal, seminar dan kegiatan lainnya. Direct marketing dengan memili website yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan layanan PKU. Ketika data di cross check dengan informal eksternal, ternyata tidak semua komunikasi pemasaran
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 119
yang dilakukan PKU diketahui oleh masyarakat. Ada sebagian yang tidak pernah melihat TV lokal. Namun ada beberapa yang mengatakan pernah melihatnya. Sedangkan untuk personal selling, sebagian besar informan menyakan mengetahuinya. Sales promotion, para informan juga sering mendengar, walaupun itu hanya dikhususkan untuk warga Muhammadiyah.
Masyarakat yang tidak tergabung dalam organisasi Muhammadiyah tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Public Relations yang paling banyak diketahui oleh masyarakat, karena sosialisasinya secara merata ke beberapa tempat. Direct marketing, banyak yang sudah mengetahui, namun ada sebagian yang tidak pernah membuka website PKU.
Dari hasil yang diperoleh di lapangan, baik dari internal maupun eksternal, bisa dianalisis bahwa strategi komunikasi pemasaran rumah sakit perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk menghindara agar target yang dikehendaki rumah sakit tidak salah sasaran. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam kelima jenis komunikasi pemasaran tersbut harus benaer-benar diintegrasikan, sehingga masyarakat bis tahu tentang rumah sakit sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rumah sakit.
Diskusi
Dari paparan hasil penelitian di tiga rumah sakit (RS PKU Muhammadiyah Surakarta, RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu) perlu adanya tindak lanjut dan diskusi untuk membuat formulasi agar pihak rumah sakit mampu menyampaikan pesan layanan rumah sakit dan diterima sama oleh masyarakat. Integrated Marketing Communications merupakan dasar pijakan yang bisa dijadikan dasar bahwa rumah sakit
perlu membuat rencan strategi komunikasi pemasaran secara terpadu.
Oleh Kotler, et al (2004: 220) merumuskan Integrated Marketing Communications sebagai konsep yang melandasi upaya perusahaan untuk mengintegrasikan dalam rangka menyampaikan pesan yang jelas, konsisten dan persuasif mengenai organisasi dan produknya. Dari defi nisi Kotler tersebut jelas bahwa pesan yang disampaikan oleh rumah sakit harus jelas, konsisten dan persuasif. Jelas dalam arti kata, apa yang ingin disampaika rumah sakit seharusnya bermuara dari visi dan misi rumah sakit, sehingga pesan tidak melenceng dari tujuan rumah sakit. Konsisten dalam arti semua pesa yang disampaikan melalui berbagai jenis komunikasi pemasaran tidak boleh berbeda-beda. Sedangkan persuasif , mampu mempengaruhi masyarakat untuk mau menggunakan layanan jasa yang ditawarkan oleh rumah sakit.
Selain itu, Gronroos (2000: 221) dalam bukunya Service Manajement and Marketing mendefi nisikan Integrated Marketing Communications sebagai strategi yang mengintegrasikan media marketing tradisional, direct marketing, public relations dan media komunikasi pemasaran lainnya, serta aspek-aspek komunikasi dalam penyampaian dan konsumsi barang dan jasa, layanan pelanggan dan customer encounters lainya. Dengan demikian rumah sakit perlu memikirkan bagaimana membuat model strategi komunikasi pemasaran secara terintegrasi.
Berkaitan dengan model strategi komunikasi pemasaran rumah sakit, peneliti merancang sebuah model yang bisa digunakan tim manajemen rumah sakit sebagai acuan dalam merencanakan strategi komunikasi pemasaran yang akan dilaksanakan di rumah sakit. Model ini dibuat guna memberikan arahan bahwa setiap akan memilih komunikasi pemasaran
Tanti Hermawati, dkk. Strategi Komunikasi Pemasaran ...
120 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
selalu harus mengingat apa tujuan utama dari rumah sakit. Melihat visi dan misi perusahaan dalam hal ini rumah sakit. Selain itu juga harus melihat karakteristik masyarakat di sekitar rumah sakit.
Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Rumah Sakit Muhammadiyah yang
ada di wilayah eks karesidenan Surakarta, khususnya yang menjadi subyek penelitian ( RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu) memanfaatkan berbagai jenis komunikasi pemasaran.
2. Komunikasi Pemasaran dilakukan belum konsisten dan pengguna jasa layanan masih belum mengetahui seluruhnya dari komunikasi pemasaran yang dilakukan rumah sakit.
3. Dihasilkan pengembangan model strategi komunikasi pemasaran yang bisa dijadikan pijakan rumah sakit ketika hendak menentukan komunikasi pemasaran yang akan dipilih.
Daftar PustakaA.Adji Watono dan Maya C.Watono,
(2011). IMC Integrated Marketing Communication that Sells. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Arief Yahya, (2012). Great Spirit Grand Strategy. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Boyd, Walker & Larreche. (2000). Manajemen Pemasaran Jilid 2. Jakarta: Erlangga
Chen, Chen Wei, (2011), Integrated Marketing Communication and New Product Performance in International Market, Journal of Global Marketing, Nov/Dec 2011, Vol 24, Issue 5 p 397-416
Daryanto, (2010). Ilmu Komunikasi. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
Fiske, John & Hartley, John. (1983). Reading Television. London: Routledge.
Gronroos,C. (2000). Service Management and Marketing, A Marketing Relationship Management Approach. Second Edition. West Sussex: Chicheste.
Henley, Teri Kline, 2001. Integrated Marketing Communications for Local Nonprofi t Organizations : Messages in Nonprofi t Communications. Journal of Nonprofi t & Public Sector Marketing. Vol 9 Issues ½ p 179. 6p. 1 chart, New Orleans.
Iskandar.(2009), Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Gaung Persanda
Ismail Sholihin. (2012). Manajemen Strategik. Jakarta : Penerbit Erlangga
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 2011. Pedoman Etika Promosi Rumah Sakit, Jakarta
Philip Kotler. (2004). Manajemen Pemasaran. Jakarta : Penerbit Erlangga
Shimp, Terence. A. (2003). Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: Erlangga
Sutisna.2002. Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Sotopo HB, 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta : UNS Press.
William R. Gombeski, Jr et al, (2007). Effectively Executing a Comprehenshive Marketing Communication Strategy. Journal of Health Marketing Quarterly (The Howarth Press). Vol 24 No. 3/4 pp 97-115
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 121
Watergate Scandal Reassessed: Mass Media’s Watchdog Role and Its Impact on American Political System
Salieg Luki MunestriInternational Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences,
Sebelas Maret University Surakarta
AbstractHaving successful fi rst term, President Nixon and his advisers worried about reelection. They organized strategy to win the 1972 reelection. The tactics he constructed brought him to get involved in the one of the biggest US constitutional crises, the Watergate Scandal. Bob Woodward and Carl Bernstein performed media muckraking concerning the issue. This led to the fi nal judgment, his presidential impeachment in 1974. Forty years after President Nixon’s resignation, there remain questions on how important was the role of journalism in bringing him down and how have journalism and politics changed after the scandal. Undeniably the case has brought signifi cant impacts on journalism and how journalists work today. This paper aims to reassess the scandal and provide the impacts on media and journalism and public’s perception of American government which play part in defi ning the U.S. political system. Finally the author calls for the United Nation to encourage initiatives to strengthen the capacity building of investigative journalism throughout the world. Keywords: President Nixon, the Watergate Scandal, impeachment, journalism, Bob
Woodward and Carl Bernstein, media muckraking, the U.S. political system, investigative journalism
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 121-132
Introduction
On June 17, 1972, fi ve men; Bernard Barker, Virgillo Gonzalez, Eugenio Martinez, James McCord, and Frank Sturgis, were arrested at 2:30 A.M. in a burglary at Democratic headquarters, carrying photographic equipment and electronic gear. The burglars had not broken into the small local Democratic Party offi ce but the headquarters of the Democratic National Committee in the Watergate offi ce-apartment-hotel complex.
The case, as so called Watergate Case, interested Washington Post to have
investigative reports on the case since although there were still too many unknown factors about the break-in to make it a story. There was no immediate explanation to why the fi ve suspects would want to bug the democratic National Committee offi ces, and whether or not they were working for any other individuals or organizations. Some questions aroused among American society. Two reporters of Washington Post, Bob Woodward and Carl Bernstein, took the challenge to conduct investigative reports concerning Watergate. They started to collect the puzzles from James McCord
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
122 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
whom on June 18, 1972 the Associated Press made it embarrassingly clear that James McCord was the security coordinator of the Committee for the Re-Election of the President (CREEP). They found that John Mitchel, the campaign director of the CREEP, was an individual behind the case, and this led to the next very complicated investigation as the Watergate involved almost all President Nixon’s men. The two reporters tried to get any single information, indication, and clue from all the members of the Committee, many of whom refused to give comment but nervousness. They get many clues leading to the spot of the problem by a secret man called Deep Throat, whom Bob Woodward often met in a basement parking area secretly at 2 A.M. Only Woodward and Bernstein know precisely Deep Throat’s identity.
Woodward and Bernstein got puzzled with the incomplete information. They collected any single part of it and arranged it, thus, resulted in a shocking fact that led their investigation to some political scandals such as purchasing voters which was called “rat fucking”, corruptions, and other conspiracy behind President’s Nixon reelection on November 11, 1972. Felt challenged for further answer, they continued their investigative journalism and the fi nal answer was the House of Judiciary Committee voted to offi cially charge Nixon with misconduct and to impeach him. The Committee charged him with hindering the process of the court by cover-up, misusing federal agencies to violate the citizen’s rights, and refusing to comply with the Congress demand to deliver the tapes and other materials related to the break-in. President Nixon announced his resignation in 1974; “I have never been a quitter. To leave offi ce before my term is completed is opposed to every instinct in my body. But as president I must put the interests of America fi rst. Therefore,
I shall resign the Presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as President at that hour in this offi ce.” 1 Vice President Gerald R. Ford took the oath as the new President the following day to complete the remaining two and a half years of Nixon’s administration.
The following part of the paper respectively brings understanding concerning Nixon, his administration and his interconnection with Watergate. It elaborates the case and how it could force Nixon to end his administration. The next part investigates the media muckraking and the impact of the scandal on today’s journalism and its relations with politics, particularly in the United States.
Nixon and Watergate Scandal
Watergate scandal began when President Richard Nixon and his people in his administration tried to cover up his involvement in the break-in Democratic National Committee headquarters. Although the scandal began with burglary, many believed that the case was rooted from the atmosphere Nixon and his advisers had built in the White House. President Nixon worked so hard to become the president of the United States. His winning brought him so defensive, secretive, and even offended against any critics. He was often recognized for his paranoia. He trusted no one and believed that everyone was attempting to bring him down. He was always so suspicious of those around him that he created a secret intelligence team to investigate any daily activities he thought untrustworthy. He was always worried that his abuse of power was revealed.
1 President Nixon Resignation Address, in ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/historicspeeches/nixon/resignation.html, retrieved on August 27, 2014
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 123
Moreover, Nixon started his presidency when the condition of the American society was in turmoil. Riots, chaos and protests over the Vietnam War were escalating, consuming the country. These protesters and other radicals were believed to endanger his administration and were always trying to topple him down. Moreover, the Vietnam War played a role in shaping the public negative feeling about the government. His paranoia made him form the “plumbers”2 to prevent information about the war from leaking to the press. His secret bombing campaign in Cambodia, Operation Breakfast,3 unavoidably helped shape the public perception that his administration did not represent the best interests of the public. Nixon’s interwoven crimes redoubled his paranoia, thus, he ordered a cover-up. He, even, compiled an ‘enemies list’, consisting of his political opponents and any people he considered potential threat to his presidency.
In 1972 President Nixon began his re-election campaign, organized by a special committee, the Committee to Re-Elect the President (CREEP).4 His reelection was uncertain. His sole challenger, South Dakota Senator George McGovern was seen too liberal. Nevertheless, anti-war
2 “White House Plumbers” was a secret unit tasked with digging up dirt on Pentagon Papers leaker Daniel Ellsberg. The Plumbers went on to commit crimes for the Committee for the Re-Election of the President, including the Watergate burglaries. http://content.t i m e . c o m / t i m e / s p e c i a l s / p a c k a g e s /article/0,28804,2071839_2071844_2071846,00.html, retrieved on September 15, 2014
3 “Operation Breakfast” was the fi rst course in a four-year bombing campaign that drew Cambodia headlong into the Vietnam War. The Nixon Administration kept the bombings secret from Congress for several months. http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/cambodia/tl02.html, retrieved on September 10, 2014
4 CREEP was a fund-raising organization for President Nixon’s 1972 election campaign. Many of its members were later indicted with criminal charges relating to their actions within the CRP.
movement still raged, bringing negativity to his reelection. Ambitioned to be re-elected at all cost, Nixon and his people started to investigate and gather information concerning their Democratic opponents. Furthermore, they began spying, digging information and spreading rumors and false reports of the opponent to gain more public support. As an effort to support the president, fi ve persons were instructed to break into the Democratic Party headquarters at the Watergate complex and to steal any campaign-related fi le. They also placed wiretaps on the offi ce telephones to get as many campaign information as possible. One of the burglars was uncovered to be an ex-CIA and also a member of CREEP. Some reports revealed that the burglars were secretly paid by CREEP fund controlled by the White House.
During the investigation process, the President ordered a cover-up, though he might not have ordered the break-in. As the investigation of the fund paid to the burglars was leading to the White House’s involvement, he had the CIA stop the FBI from conducting the investigation, pronouncing that the investigation threatened national security. Countering the efforts to stop the FBI inspection, the FBI’s deputy director, W. Mark Felt, leaked information about the Watergate to the Washington Post secretly. The case was blown up by the Post against the White House’s version since then, bringing two-sided puzzle for the public. The White House announced that the President and people in the White House have connections with the burglary. Most Americans believed the White House version. This was proven by Nixon’s winning for the 1972 reelection. Nixon gained nearly 61 percent of the popular vote, compared to 37.5 percent for George McGovern.5
5 http://teampride.yolasite.com/resources/
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
124 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
The investigation done by the two reporters, FBI and other corporations came to an investigation of the President. Woodward and Bernstein in the Washington Post portrayed in simple language Nixon vast abuse of power during the 1972 election as follow:
Following members of Democratic candidates’ families and assembling dossiers on their personal lives; forging letters and distributing them under the candidates’ letterheads; leaking false and manufactured items to the press; throwing campaign schedules into disarray; seizing confi dential campaign fi les; and investigating the lives of dozens of Democratic campaign workers.6
However, the President had built his legal defense before the investigators. Henry Kissinger, the Assistant to the President for National Security Affairs, had tried to disavow his former aides publicly and to accept a measure of responsibility for Watergate. However, the suggestion was angrily rejected by saying “contrition is bullshit”. On January 30, 1974, the President delivered his annual State of the Union Message to a joint session of the house and Senate, the justices of the Supreme Court and the members of the Cabinet, as well as to other guests and national TV audience. “One year of Watergate is enough,” he declared at the conclusion and then implored the country and the Congress to turn to other, more urgent matters.7
Through a series of judicial trial, all the House of Representatives, the Senate, the Chief of Justice of the United States, gained
Ch21.2.pdf6 Carl Bernstein and Bob Woodward, “FBI
Finds Nixon Aides Sabotaged Democrats,” Washington Post 10 October 1972,http://www.washingtonpost.com/wpdyn/ content/article/2002/06/03/AR2005111001232.html,, retrieved on 5 March 2012
7 h t t p : / / w w w . p r e s i d e n c y . u c s b . e d u /ws/?pid=4327, retrieved on September 1, 2014
the same conclusion about the president that he was the man who would sit in judgment at a trial of impeachment. However, the president refused to accept as he said, “I want you to know that I have no intention whatever of ever walking away from the job that the American people elected me to do for the people of the United States.”8 The Constitution, however, gives the House of Representatives power to conduct an impeachment through Article II, Section 4, saying “the President’ Vice President and all civil Offi cers of the United States, shall be removed from Offi ce on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.”9 The articles of impeachment against him were written as follow:
On June 17, 1972, and prior thereto, agents of the Committee for the Re-election of the President committed unlawful entry of the headquarters of the Democratic National Committee in Washington, District of Columbia, for the purpose of securing political intelligence. Subsequent thereto, Richard M. Nixon, using the powers of his high offi ce, engaged personally and through his close subordinates and agents, in a course of conduct or plan designed to delay, impede, and obstruct the investigation of such illegal entry; to cover up, conceal and protect those responsible; and to conceal the existence and scope of other unlawful covert activities.10
Moreover the Congressional Impeachment Articles accused Nixon of:
Approving, condoning, acquiescing in, and counseling witnesses with respect to the giving of false or
8 h t t p : / / w w w . p r e s i d e n c y . u c s b . e d u /ws/?pid=4327, retrieved on September 1, 2014
9 Article II, Section 4 of the Constitution10 U.S. Congress, “Articles of Impeachment
Adopted by the House of Representatives Committee on the Judiciary,” 27 July 27 1974, Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=76082, (retrieved on 2 August 2014).
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 125
misleading statements to lawfully authorized investigative offi cers and employees of the United States and false or misleading testimony in duly instituted judicial and congressional proceedings.11
The presidential position, then, was given to the vice president, Gerald Ford on August 9, 1974. In his Resignation speech, President Nixon praised Vice President Ford, “the leadership of America will be in good hands,”12 ensuring that Ford would be the right person to continue his position as the President of the United States.
Media’s Watchdog Role
The episode of revealing the scandal fi nalized in Richard Nixon’s resignation has so far been considered as a heroic media role. Some schools of journalism often teach the lesson of Watergate issue and the media muckraking Woodward and Bernstein did as an example of courageous press coverage. Nevertheless, some best remember the media muckraking played at best a modest role in ousting Nixon from offi ce. Yet, how important was the media muckraking in exposing and bringing down the president? Some scholars argue Woodward and Bernstein’s investigative journalism did not play signifi cant role. They merely uncovered several elements of the misdeeds, a few days before it came out anyway. Indeed, even if media coverage had been passive, Nixon would have been forced out of offi ce.
Television and newspapers publicized stories and news in every single second,
11 U.S. Congress, “Articles of Impeachment Adopted by the House of Representatives Committee on the Judiciary,” 27 July 27 1974, Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=76082, (retrieved on 2 August 2014)
12 ht tp ://www.pres ident ia l rhetor ic .com/historicspeeches/nixon/resignation.html, retrieved on September 6, 2014
and the investigative authorities play their part in revealing truth. With the burglars arrested, the investigative authorities had collected the information to uncover the scandal. Without the media muckraking, the FBI linked the burglars to the White House and traced the case. Woodward and Bernstein were not the only persons successfully did the investigation. They systematically marginalized the work of law enforcement offi cials to play their parts.
Conversely, Bernstein counters “You can’t write ‘if’ history; history is what happened. What happened is that the press coverage played a very big role in making information available that the Watergate break-in was part of something vast and criminal and directed from or near the Oval Offi ce against President Nixon’s opponents.” He acknowledges that the “role of Bob [Woodward] and myself has been mythologized” because “in great events people look for villains and heroes” and oversimplify what happened. “At the same time, we were in the right place at the right time and did the right thing.”13
Washington Post reporters, Woodward and Bernstein, produced “the single most spectacular act of serious journalism [of the 20th] century,” said media critic Ben Bagdikian.14 Another scholar asserted what they did put American political history and journalism on the same line, equally important. Marvin Kalb, a senior fellow at Harvard’s Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy, believes that the Post’s reporting was “absolutely critical” to “creating an atmosphere in Washington and within the government that Nixon was in serious trouble and
13 Carl Bernstein in http://ajrarchive.org/article.asp?id=3735, retrieved on August 28, 2014
14 Mark Feldstein, “Watergate Revisited,” in American Journalism Review, August-September 2004 in http://ajrarchive.org/article.asp?id=3735, retrieved on September 10, 2014
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
126 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
that the White House was engaged in a cover-up. I believe that the reporting of Woodward and Bernstein represents a milestone of American journalism.”15
The endless media coverage and televised congressional hearings made the scandal always be in mind and fostered the prevalent negative picture about government that changed American political system forever. Gladys Lang and Kurt Lang suggested that television was the most effective and essential medium to rally public reaction against Nixon and his administration. Television, furthermore, made the scandal more widespread among Americans, breaking Nixon strategists’ optimism that most of the public would not read the transcripts of the hearings. According to the Gallup Poll, 42 percent of Americans had less favorable opinion of Nixon after watching the hearings while only 17 percent had more favorable opinion about him. More than 60 percent of the public supported the congressional decision to demand direct access to Watergate tapes. Even though many people did not watch the hearings, they probably read the news reports through printed and other media.16
Undeniably, journalism gave great contribution to infl uence public opinion. Media televised so many struggles between Nixon and his opponents. The more television played out the news, the more public ready for the president’s removal. Thomas Kazee expressed that television helped shift perceptions of Nixon among people who were not interested in politics.17 Thus, journalism
15 Mark Feldstein, “Watergate Revisited,” in American Journalism Review, August-September 2004 in http://ajrarchive.org/article.asp?id=3735, retrieved on September 10, 2014
16 Lang and Lang, “Polling on Watergate: The Battle for Public Opinion,” 534-535.
17 Thomas Kazee, “Television Exposure and
may help the public prepare for Nixon’s removal, but it was not media that forced the president to end his presidency. Instead, it was Congress. Shortly to say, media did not play a leading role, but it did play a role. Besides, the impeachment of President Nixon reminded public that no one is above the law, even the president of the United States.
Impacts on Journalism
What impact, then, have the Watergate investigative reports had on journalism? The case triggered more and more journalists to explore deep concerning any issues related to the White House. Since the Watergate, the relationship between the White House and the press has changed forever. Many journalists are obsessed with rooting out evidence of government corruption or public offi cial failures, though they might be small or insignifi cant ones. These journalists dream of Pulitzers and want to be seen as another fi gure of Woodward and Bernstein. This has been a booming trend since then. Reporters not only seek and present information, but also do “gotcha” investigation.
The number of investigative journalist has grown signifi cantly since the Watergate. The increasing interest in journalism was proven by the signifi cantly increasing enrollment at the MU School of Journalism, said Daryl Moen.18 “It certainly attracted hundreds, if not thousands,” Moen said of the growth of all journalism schools in the post-Watergate era.19 This observable
Attitude Change: The Impact of Political Interest,” in The Public Opinion Quarterly ( Oxford University Press, 1981) 516.
18 Daryl Moen was an MU journalism professor who was executive editor of the Columbia Missourian from 1974 to 1984
19 http://www.columbiamissourian.com/a/84628/watergate-gave-journalism-a-boost/, retrieved on September 5, 2014
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 127
fact occurred at other Journalism school’s enrollment, too. Though the interest has decreased recently, there has been an increase in the enrollment of journalism schools and journalism in general.
Investigative reporting mushroomed and became a sexy trend. Woodward and Bernstein attractively inspired young people to be investigative journalists to make changes. Both wrote All the President’s Men, telling the coverage of the scandal and The Final Days, which illustrated the last days of Nixon’s administration. What the two journalists did brought a new image on journalism, from merely reporting news to investigating scandals, which is more challenging. Many journalists intentionally search for Watergate-like story even when there is none. This led to media’s negativity which disenfranchised many people.
Today, it is common to see journalists have their investigative team to analyze their reports, inspired by what Woodward and Bernstein did. Besides, the changes included the beginning of celebrity journalism in which the reporters become the story and unanimous sources are more acceptable. “Woodstein” has launched the era of the journalists as celebrity. In the era, journalists compete to gain fame and recognition through the news they report. The same as the book Woodward and Bernstein wrote, All the President’s Men movie tells story about the scandal, which boosted the two journalists’ popularity. They themselves became the news for other journalists to report. This phenomenon brought out an attractive side of journalism.
Another perfect prove of the trending journalism is the establishment of Investigative Reporters and Editors, Inc. (IRE) in 1975. It is a grassroots nonprofi t organization dedicated to improving the quality of investigative reporting by providing a forum in which
journalists throughout the world could help each other by sharing story ideas, newsgathering techniques and news sources. The incorporation has mission to foster excellence in investigative journalism, which is essential to a free society. This can be achieved through some steps such as providing training, resources and a community of support to investigative journalists, promoting high professional standards, protecting the rights of investigative journalists, and ensuring the future of IRE.20
Moreover, the constitutional protection that journalists enjoy justifi es investigative journalism or media muckraking. The First Amendment of US Constitution stated that “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”21 Moreover, Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights stated “everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”22 These articles boost the overwhelming growth of media muckraking today, disregarding the media accountability and ethical standards.
Watergate Legacy to Public
To show how infl uential was the Watergate scandal, there are many scandals
20 http://www.ire.org/about/, retrieved on September 3, 2014
21 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/208044/First-Amendment, retrieved on September 2, 2014
22 http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a18, retrieved on September 2, 2014
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
128 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
being labeled with a “gate” suffi x recently to make them attention-grabbing. Almost every scandal has suffi x “gate” attached to it. This phenomenon does not happen only in the USA, but also in some other region. Besides, the suffi x has not been attached only to political scandal, but also to any scandals attractive enough to report. Some of the scandals with “gate” suffi x attached are Nipplegate (Janet Jackson and Justin Timberlake), Monicagate (affair between Monica Lewinsky and Bill Clinton), Spygate (New England Patriots), Tunagate in Canada, Dianagate/Squidgygate and Thatchergate in the UK, Pemexgate, Toallagate in Mexico, Winegate in Franch (a scandal involving chemicals being used to turn vinegar wine into table quality) and many more. To American Journalism Review, Sam Dash, who served as chief counsel to the Senate Watergate Committee all those years ago stated “When people hear this proliferation of ‘gates,’ they feel the press is telling them this is the same as Watergate, and whatever Watergate has stood for has lost its meaning.”23
Nixon and the Watergate have left mixed legacy to public. What media exposed widened the gap among the public and political elite. Skepticism of the government lived for some time and there were no signs of abating any time soon. Though cynicism of the federal government and public offi cials did not start from Watergate, the scandal has left long lasting impact on the public confi dence in the government. Garry Wills states that Americans have always viewed their government with suspicion. He states that public distrust of government has infl uenced the US political system since the early days of the republic.24
23 http://www.usatoday.com/story/money/columnist/r ieder/2014/01/15/t ime-to-jettison-the-gate-suffi x/4490115/, retrieved on September 14, 2014
24 Garry Wills, A Necessary Evil: A History of
Stephanie Slocum-Schaffer points out that Watergate had a signifi cant impact on the 1970s and the rest of the century. She argues that Watergate caused the public to see the government as dishonorable.25 According to a Gallup Poll, in 1972, before Watergate became the scandal of the decade, more than 50% of American adults said they trust the government “all or most of the time”, while 45% opted for the “only some of the time” alternative. By 1974, high trust had dropped to 36% and has remained below 50% since then, demonstrating the signifi cant impact that the Watergate scandal has had on public confi dence in the U.S. government.26 While according to Darrel West, Ph.D., of Brown University, for most people who came of age during the 1970s, Watergate was the crucial political event. Before Watergate two-thirds of Americans trusted Washington but then after Watergate two-thirds of Americans mistrusted Washington.27
The disbelief in the government as an impact of the Watergate challenged the presidents after Nixon to restore and regain public’s confi dence in government.28 President Ford and Carter failed to do this task. President Ronald Reagan was able to address this challenge through anti-government rhetoric and an emphasis on reduction of government’s hand in every way possible. This tapped into the decline in confi dence by rejecting the very idea that an active government was a positive
American Distrust of Government (New York : Simon and Schuster , 1999) 1-10.
25 Slocum-Schaffer, America in the Seventies, (Syrcause: Syracuse University Press, 2003) 207, 210-211.
26 Gallup Poll in http://www.gallup.com/poll/4378/americans-faith-government-shaken-shattered-watergate.aspx, retrieved on September 3, 2014
27 Quoted in Journalism Education Association, in http://jea.org/wp-content/uploads/2012/02/specialreport.pdf, retrieved on September 6, 2014
28 Richard Harris, “The Era of Big Government Lives.”
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 129
thing.29 He embraced an idea that an active government was unfavorable and that the American people without government interference were best suited to cope with their own problems. Trust in the Executive branch of government sank from 73% in May of 1972 to 40% in April of 1974 at the height of the Watergate scandal. However, that trust rebounded to 58% under Gerald Ford in June of 1976 and is currently at 62% under Bill Clinton.30
Another poll commissioned by the Senate subcommittee on intergovernmental affairs in September 1973 found that public support for all major government institutions and public offi cials was below thirty fi ve percent.31 The myth portraying president as always great, reliable, trustful and defender or the people’s life was broken. Such a condition shifted the youth and job seekers’ interest to work in any government institutions. Many potential candidates for public offi cials and staffs for federal offi ces hesitated to register for the government image was ruined by Watergate. There was a moment when it was diffi cult to fi nd federal offi cers.
On the other side, the Watergate scandal has left positive legacies, too. The media and publics are more aware of the people seeking for power. The uncovering journalism drove a change on the transparency of the government and the people within. The governments meetings and records are more accessible to public. The case aroused a demand to change the entire political atmosphere to prevent such a crisis from happening again. A series of political reform
29 Richard Harris, “The Era of Big Government Lives.”
30 Gallup Poll in http://www.gallup.com/poll/4378/americans-faith-government-shaken-shattered-watergate.aspx, retrieved on September 3, 2014
31 The Associated Press, “Confi dence in Government Sags,” in Daytona Beach Morning Journal, 3 December 1973.
were made since the scandal was exposed in 1974. They are the Freedom of Information Act (FOIA) in 1974, National Emergencies Act in 1976, Government in Sunshine Act in 1976, and the Ethics in Government and Presidential Records Acts, both in 1978. Another important post-Watergate reform was the passage of amendments to the Federal Elections Campaign Act (FECA) in 1974, 1976, and 1979.
The Freedom of Information Act allows for the full or partial expose of previously unreleased documents and information controlled by the United States Government. The National Emergencies Act was to stop open-ended states of national emergency and formalize the power of Congress to provide certain checks and balances on the emergency powers of the President. The act imposes certain “procedural formalities” on the President when invoking such powers. The Sunshine Act required government agencies, with exceptions, to conduct all meetings open to the public. The Ethics in Government Act required public offi cials to disclose their (and their immediate family) fi nancial and employment history and create restrictions on lobbying efforts by public offi cials for a set period after leaving public offi ce. The Presidential Records Act required preservation of all presidential records and documents. They are all to halt any potential Watergate-like cases.
Nevertheless, the reforms failed to restore the public’s trust in the government and were not strong enough to prevent such event like Watergate scandal from happening. The government always has its own way to prevent its secret from the publics’ ears and media coverage. Ted Sorensen, a former Kennedy speechwriter and advisor, stated that Watergate has affected signifi cantly every subsequent presidential administration, though the case may not be a strong deterrent of similar misdeeds.
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
130 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Removing the perpetrators of Watergate, even without altering the environment in which they operate, should teach some future White House occupants the necessity of not trying something similar. But it may only teach others the necessity of not being caught. History has never proven to be a strong deterrent.32
Somehow, corruption like what Nixon did seems more diffi cult to do since the distrust caused by the scandal has made the safeguard more aware of any government abuse of power.
Conclusion
Today, the Watergate scandal is still remembered as one of the U.S. terrible constitutional crisis. On the other side, it represented a victory for democracy in America and is seen as a perfect example of why freedom of the press is such an important part of preserving democratic community and halting the government abuses of power. Though history may not have been a good deterrent of any government misdeeds, the scandal has left important lesson for American political system and how journalism works today. Mass media play a crucial role as a watchdog of government and public offi cers. This is undeniably indispensable for democracy. Further, the freedom of press seems to have been “exported” together with the spread of democracy.
Watergate signaled the birth of a more aggressive journalism. Considering the impacts of Watergate on the development of journalism and American politics today, which possibly extend across the border, it is imperative that the United Nations foster initiatives to strengthen the capacity building of investigative journalism throughout the
32 Theodore Sorensen, Watchmen in the Night: Presidential Accountability after Watergate (Cambridge : MIT University Press , 1975) 7.
world. There should be debates or discussions concerning the media accountability and ethical standards, providing journalists with guiding principles on how to best perform their profession. This, hopefully, will lead journalists to give more professional journalistic works in the future.
Refferences:Bernstein, Carl and Bob Woodward. 1972. FBI
Finds Nixon Aides Sabotaged Democrats. Washington Post 10 October 1972, in http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2002/06/03/AR2005111001232.html, retrieved on 5 March 2012
Feldstein, Mark. 2004. Watergate Revisited, article in American Journalism Review, August -September 2004 in http://ajrarchive.org/article.asp? id=3735, retrieved on September 10, 2014
Gallup Poll in http://www.gallup.com/poll/4378/americans-faith-government-shaken-shat tered-watergate.aspx, retrieved on September 3, 2014
Harris, Richard. 1997. The Era of Big Government Lives. Polity: Palgrave Macmillan Journals.
http://ajrarchive.org/article.asp?id=3735, retrieved on August 28, 2014
http://content.time.com/time/specials/packages/article /0,28804,2071839_2071844_2071846,00.html, retrieved on September 15, 2014
h t t p : / / t e a m p r i d e . y o l a s i t e . c o m /resources/Ch21.2.pdf, retrieved on August 25, 2014
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/208044/First-Amendment, retrieved on September 2, 2014
ht tp ://www.columbiamissour ian .com/a/84628/watergate-gave-journalism-a-boost/, retrieved on
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 131
September 5, 2014
http://www.ire.org/about/, retrieved on September 3, 2014
http://www.pbs.org/frontlineworld/s t o r i e s / c a m b o d i a / t l 0 2 . h t m l , retrieved on September 10, 2014
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=4327, retrieved on September 1, 2014
http://www.presidentialrhetoric.com/historicspeeches/nixon/resignation.html, retrieved on September 6, 2014
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a18, retrieved on September 2, 2014
h t t p : / / w w w . u s a t o d a y . c o m /s t o r y / m o n e y / c o l u m n i s t /rieder/2014/01/15/time-to-jettison-the-gate-suffi x/4490115/, retrieved on September 14, 2014
Journalism Education Association, in http://jea.org/wp-content/uploads/ 2012/02/specialreport.pdf, retrieved on September 6, 2014
Kazee, Thomas A. 1981.Television Exposure and Attitude Change: The Impact of Political Interest. In The Public Opinion Quarterly. Oxford: Oxford University Press
Lang, Gladys Engel, and Kurt Lang. 1980. Polling on Watergate: The Battle for Public Opinion. In The Public Opinion Quarterly. Oxford: Oxford University Press.
President Nixon Resignation Address, in http://www.presidentialrhetoric.com/historic.com/historisspeeches/nixon/resignation.htmlretrieved on August 27, 2014
Slocum-Schaffer, Stephanie. 2003. America in the Seventies. Syracuse : Syracuse University Press
Sorensen, Theodore. 1975. Watchmen in the Night: Presidential Accountability
after Watergate. Cambridge: MIT University Press.
The Associated Press. 1973.Confi dence in Government Sags, in Daytona Beach Morning Journal, 3 December 1973.
U.S. Congress. 1974. Articles of Impeachment Adopted by the House of Representative Committee on the Judiciary, 27 July 1974, by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project, in http://www.presidency.ucsb.edu /ws/?pid=76082, retrieved on 2 August 2014.
Wills, Garry. 1999. A Necessary Evil: A History of American Distrust of Government. New York: Simon and Schuster
Salieg Luki Munestri. Watergate Scandal Reassessed ...:
132 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 133
Film dan Konstruksi Citra Politik(Analisis Wacana Politik Pencitraan dalam Film Jokowi)
Erwin KartinawatiAlumnus Program Pascasarjana S2 Ilmu Komunikasi
Universitas Sebelas Maret Surakarta
AbstractFilm can be used as a mean to introduce a public fi gure. Jokowi, one of it. Analysis of Teun Van Dijk model revealsdiscourse that carried in the fi lm, namely Jokowi as someone who really deserves to be a leader. Everything that in Jokowi arelike requirements that must have been by a leader. This discourse is constructed through political image as an interesting and positive personality, that are smart and intelligent; appreciates pluralism; religious; honestly, doesn’t tempt to bribe, brave; family and fi lial affection towards parents; philanthropist; humble, humanizing fellow; leadership talent; hard worker, love the culture; faithful, and not involved in banned organizations. Philosophy of Java leadership, especially related to politic and power is source of image construction seen byusing of symbols, phrases and terms in the fi lm. This paper reinforces the view thatsoft campaign can be an effective mean of gaining more public attention besides open or direct campaign (hard campaign).Key words: Jokowi, Soft Power Campaign, Analysis of Teun Van Dijk model
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 133-146
Pendahuluan
Peluncuran fi lm tak sekadar pertimbangan ekonomis namun bisa pula memuat unsur politis. Sebagai bentuk komunikasi massa, fi lm dapat menjadi wahana untuk menyampaikan pesan ke khalayak. Melalui fi lm, komunikator memasukkan hal-hal yang ingin disampaikan ke khalayak. Film masih dianggap sebagai media yang memiliki kekuatan besar menanamkan pengaruh di benak masyarakat. Kemampuan menyajikan realitas secara audio-visual, dramatisasi lewat efek suara dan atau gambar, karakter tokoh dan jalan cerita, mampu mengajak
khalayak terlibat secara lebih.1 Meski begitu, aspek kontrol dalam fi lm tidak sekuat koran atau televisi yang menyajikan berita berdasar fakta terjadi. Fakta dalam fi lm tidak ditampilkan layaknya berita yang harus apa adanya namun abstrak. Karenanya, cerita fi lm dibuat imajinatif meski berdasar fenomena terjadidi masyarakat.2 Kisah hidup tokoh atau orang terkenal adalah salah satu hal yang dapat diangkat sebagai tema fi lm.
1 Jay Black, Frederick C. Whitney, Introduction to Mass Communication, Brown Publishers, USA, 1998, hal.348-349.
2 Marfi Amir, Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam, Jakarta, Logos, 1999, hal. 27.
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
134 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Citra diri tentang tokoh banyak digambarkan dalam bentuk fi lm-fi lm semacam ini seperti pekerja keras, bijaksana, teguh pendirian, dsb. Jokowi adalah salah satu fi lm yang mengambil kisah hidup seorang tokoh sebagai tema utama cerita, Joko Widodo (Jokowi). Tulisan ini akan membahas wacana diangkat dalam fi lm Jokowi serta bagaimana wacana dikonstruksikan. Film ini dipilih karena Jokowi selaku tokoh sentral, sebelumnya menyatakan jika kemunculan kisahnya di layar lebar ini tidak bernuansa politis.3 Namun belakangan fi lm ini diakui sebagai salah satu sarana kampanye dalam pencalonannya sebagai presiden RI, pada Pilpres 2014.4 Film Jokowi secara tidak langsung telah menginformasikan kepada publik tentang siapa dan seperti apa sosok Jokowi. Dalam konteks ini, fi lm sebagai media massa dapat dipilih sebagai saluran komunikasi politik ke masyarakat. Tak hanya pada Pilpres namun juga pada Pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah, media massa khususnya fi lm, dapat menjadi saluran komunikasi utama untukkampanye.
Film dapat digunakan untuk menimbulkan citra tertentu tentang tokoh maupun suatu hal. Melalui citra dibangun akan tumbuh persepsi atau kesan tentang diri atau sesuatu. Kesan atau citra inilah yang dibangun terhadap tokoh melalui fi lm. Dalam komunikasi politik, kesan menjadi penting karena membentuk dasar bagi sejumlah keputusan.5 Dalam konteks Pemilu, fi lm dapat digunakan sebagai alat untuk menimbulkan kesan baik di mata masyarakat sehingga dapat
3 kompas.com, “Tak ada Izin, Jokowi Keberatan fi lm Jokowi”, Rabu 22 Mei 2013 pkl 16.37 wib.
4 merdeka.com, “Film Jokowi jadi Media Kampanye Pilpres”, Senin 9 Juni 2014 Pkl 18.57 wib.
5 Steward L. Tubbs, Sylvia Moss, Human Communication, edisi terj.Deddy Mulyana dan Gembirasari, Rosdakarya, Bandung, 2001, hal.34.
mempengaruhi keputusan publik. Film juga dapat digunakan sebagai ajang sosialisasi sekaligus mobilisasi. Dengan menggunakan media, elit politik tidak hanya merefl eksikan tetapi juga membantu menciptakan pengharapan massa dan mitos yang dapat diterima secara luas.6
Politik pencitraan melalui fi lm khususnya di Indonesia bukan hal baru. Jauh sebelum erareformasi, ada fi lm wajib tonton Janur Kuningdan Serangan Fajar. Pascatumbangnya orde barufi lm itu dinyatakan tak lagi wajib tonton, karena disebut sebagai alat untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus terhadap Soeharto. Janur Kuning menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan di balik Serangan Umum 1 Maret 1949, sementara Serangan Fajarmemposisikannya sebagai pahlawan utama Revolusi Indonesia.7Berdekatan dengan masa pemilihan umum, selain Jokowi, muncul Sepatu Dahlan. Kehadiran fi lm-fi lm bertemakan biografi yang sebelumnya diawali sukses kisah mantan Presiden RI Ainun Habibie, bisa menjadi salah satu dasar jika fi lm yang notabene sebagai media lama masih dianggap sebagai upaya efektif untuk membentuk atau menggambarkan citra diri, di tengah boom media baru.
Film Jokowi dirilis Juni 2013 menceritakan bagian hidup Jokowi berikut kisah cintanya dengan Iriana. Produser fi lm Jokowi mengatakan fi lm ini digunakan sebagai ajang mengenalkan sosok Jokowi ke masyarakat. Karenanya, selama masa kampanye pihaknya ikut road show di berbagai tempat, memutar fi lm Jokowi di tengah-tengah masyarakat.8 Dari sini dapat dikata jika fi lm sebagai media massa telah digunakan sebagai alat
6 Dan Nimmo, Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek, Rosdakarya, Bandung, 2000, hal.30.
7 Wikipedia, akses 1 April 2014.8 www.merdeka.com, Op.Cit.
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 135
komunikasi politik yakni sebagai saluran sekaligus sumber informasi mengenai para kontestan Pemilu serta sarana pembentukan citra tertentubagi kandidat untuk menggiring pembentukan opini publik di masyarakat mengenai citra diri kandidat. Citra diri yang baik darikandidat akan berpengaruh besar bagi para pemilih dalam memutuskan pemberian suara.9
Politik pencitraan berkenaan erat bagaimana strategi pencitraan dibangun. Pencitraan bahkan dinilai hal wajib dilakukan politikus layaknya di dunia bisnis. Para politikus atau pemimpin politik sangat berkepentingan dalam pembentukan citra melalui komunikasi politik dalam usaha menciptakan stabilitas sosial dan memenuhi tuntutan rakyat. Karenanya, politikus harus menciptakan dan mempertahankan tindakan politiknya yang membangkitkan citra memuaskan, supaya dukungan opini publik dapat diperoleh dari rakyat sebagai khalayak komunikasi politik.10Pencitraan dianggap penting bahkan disebut sebagai satu kekuatan politik tersendiri. Keberhasilan dalam melakukan komunikasi politik tergantung pada cara media mengkonstruksi kekuatan politik tersebut. Media memiliki kekuatan signifi kan dalam komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak. Dari sini terlihat jika pencitraan merupayakan upaya konstruktif dari sumber pesan. Sumber memiliki peran besar dalam melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana dibangun. Setiap pernyataan adalah tindakan penciptaan makna yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan diri serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara.11
9 Wahyu Prasetyawan, “Image Construction in Politics : Political Adverstiment in 2009 Indonesian Election”, Journal of Issaes in Asia vol 27 no 2, 2012, hal 310.
10 Ahmad Arifi n, Pencitraan dalam Politik, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006, hal 145.
11 AS Hikam, Bahasa dan Politik (Yudi Latif dan
Analisis Wacana
Guna mengetahui wacana dibangun serta bagaimana wacana dibangun dalam fi lm Jokowi digunakan analisis model Teun A. Van Dijk. Perangkat analisis digunakan berupa kata, kalimat, potongan scene, latar, simbol-simbol dalam fi lm. Analisis Wacana dimaksudkan untuk membongkar hal tersembunyi dari sumber/subyek yang mengemukakan pernyataan.12 Dalam bidang politik, wacana dikaitkan dengan politik bahasa.13 Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, entah mempengaruhi, membujuk, menyanggah, bereaksi dan sebagainya sehingga wacana dipahami sebagai sesuatu yang terkontrol dan diekspresikan secara sadar, bukan sesuatu di luar kendali.14
Setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung kepentingan, apalagi melalui media massa maka setiap tindakan komunikasi adalah suatu wacana. Dalam pandangan ini, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan “kenyataan lain” atau “kenyataan kedua” dalam bentuk wacana (discourse) dari “kenyataan pertama”. Cara ditempuh dalam pembentukan wacana (realitas kedua) itu adalah sebuah proses disebut konstruksi realitas. Untuk melakukan konstruksi realitas, digunakan strategi yang mencakup pilihan bahasa mulai dari kata hingga paragraf;pilihan fakta. Hasil dari proses ini berupa wacana (discourse) atau realitas yang dikonstruksi berujud tulisan (text), ucapan (talk), tindakan (act) atau peninggalan (artifact). Oleh karena discourse yang terbentuk ini telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, bahwa
Idy Subandy Ibrahim, ed), Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orba, Bandung, Mizan, 1996, hal 80.
12 Eriyanto, Analisis wacana : Pengantar Analisis Teks Media, Jakarta, Prenada Kencana, 2011, hal 5.
13 Ibid, hal 6. 14 Ibid, hal 8.
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
136 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan.15Di media, bahasa tak sekadar alat penggambar realitas namun dapat menentukan atau menciptakan citra di benak kalayak. Penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas berupa citra sebab bahasa mengandung makna.16Wacana berperan dalam mendefi nisikan individu dan menempatkan seseorang dalam posisi tertentu.17 Media memiliki peran besar dalam hal itu melalui proses pendefi nisian dan penandaan sehingga representasi dihadirkan tampak wajar, alami sesuai kenyataan.18
Analisis model Teun Van Dijk melihat wacana dari tiga dimensi yakni teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Dimensi teks meneliti bagaimana struktur teks dan strategi wacana dipakai menegaskan tema tertentu, kognisi sosial mempelajari produksi teks yang melibatkan kognisi individu komunikator, dan konteks sosial mempelajari bangunan wacana berkembang di masyarakat akan suatu masalah.19 Meski terdiri 3 elemen, ketiganya saling terkait, mendukung satu sama lain. Analisis dalam tulisan ini hanya menyertakan dimensi teks dan konteks sosial, tidak menyertakan kognisi atau pemikiran dari pembuat fi lm sebagai latar produksi.
Konstruksi Citra Politik
Film ini mewacanakan Jokowi sebagai sosok yang benar-benar layak menjadi
15 Ibnu Hamad, “Perkembangan Analisis Wacana dalam Ilmu Komunikasi: Sebuah Telaah Ringkas”, http://syariat-tharikat-hakikat.blogspot.com/2008/04/perkembangan-analisis-wacana-dalam-ilmu.html, akses I Juli 2014.
16 Melvin DeFleur, Theories of Mass Communication, 5th ed, Longman, London, 1989, h.265-269.
17 Eriyanto, Op.Cit, hal.19.18 Ibid, hal 27. 19 Eriyanto, Op.Cit, hal.224.
seorang pemimpin. Hal itu konstruksi melalui citra sebagai pribadi ideal. Semua yang ada pada diri Jokowi merupakan kepribadian yang dibutuhkan pada setiap pemimpin. Jokowi adalah “paket” lengkap sehingga tak ada alasan untuk tidak menghendaki atau memilihnya sebagai seorang pemimpin. Analisis menunjukkan, wacana dibangun melalui konstruksi citra pribadi yang positif. Mengapa Jokowi dengan pribadi yang unggul merupakan sesuatu yang ditawarkan ke publik sebagai tema utama cerita? Tulisan Gregg Thompson dalam bukunya The Power to Lead diantaranyabisa menjawab hal ini.
Thompson mengatakan kepribadian merupakan satu hal penting bagi seorang pemimpin. Kepribadian dapat menjadi senjata ampuh bagi seorang pemimpin. Untuk mencapai tujuannya, seorang pemimpin dapat menggunakan dua kekuatan berupa soft power dan hard power.20Soft power selain seperti budaya, nilai-nilai dan kekuasaan moral,serta kepribadian yang menarik. Mereka adalah kekuatan yang dapat digunakan untuk menaklukkan hati orang tanpa harus menggunakan rangsangan material. Sedangkan hard power adalah kekuatan berupa reward, punishment atau alat lainnya yang bersifat material, digunakan untuk mendapatkan dukungan publik. Rupanya, soft power inilah yang dikembangkan komunikator fi lm Jokowi dengan menyajikan kepribadian Jokowi yang menarik, sebagai bentuk strategi politik untuk menarik dukungan publik. Komunikator tampaknya sadar tentang apa dilakukan. Ini didasarkan pada beberapa riset yang menyimpulkan bahwa kandidat atau politisi perlu memperhatikan kepribadiannya. Kepribadian politisi yang menarik dapat mempengaruhi peningkatan
20 Gregg Thompson, The Power to Lead, SelectBooks, New York, 2009.
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 137
perolehan suara.21 Mengapa kepribadian penting? Politisi yang memiliki visi ke depan, nasionalis, integritas, dedikasi, cerdas, arif, aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, berani, memiliki jiwa kepimpinan, memiliki track records yang signifi kan dalam peran-peran stategis, adalah orang yang memiliki kriteria sangat baik sebagai politisi.22
Kriteria sangat baik sebagai politisi sebagaimana tersebut di atas, dibangun pula pada sosok Jokowi dalam fi lm. Pemimpin adalah orang yang menjadi tempat bergantung orang lain23. Karenanya untuk dapat menjadi pemimpin, harus memiliki kekuatan, keunggulan dan kemampuan lebih dibanding lainnya, agar mendapat kepercayaan publik. Asumsinya, dia yang memiliki kemampuan lebih akan mampu mengatasi suatu hal dengan lebih baik dibanding lainnya.
1. Pintar dan CerdasSeorang pemimpin sudah seharusnya
memiliki kemampuan berpikir lebih dibanding yang lain. Itu ada pada Jokowi. Konstruksi bahwa Jokowi layak menjadi pemimpin karena pintar dan cerdas dikonstruksikan lewat scene-scene yang menggambarkan bahwa ia selalu menjadi siswa terbaik, mulai SD hingga perguruan tinggi, seperti scene 00.34.40-00.35.17 saat ia SD, saat SMA (00.53.00-00.53.15), dan scenemasa kuliah 01.11.12-01.11.40, lulus (01.32.25-01.32.37).
Semuascenesaling mendukung dan memperkuat konstruksi sub tema tentang sosok Jokowi yang pintar dan cerdas. Pemilihan kalimat sebagai pendefi nisi, komentar dalam narasi serta detil-detil
21 Silih Agung Wasesa, Political Branding and Public Relations, Gramedia, Jakarta, 2011, hal.290.
22 Ibid. 23 Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari
Orang Jawa, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1984, hal 70.
yang digunakan semuanya menguatkan/menonjolkan sosok Jokowi dengan citra positif dengan cara melemahkan sosok lain yakni Jokowi yang selamat dari becak terigu karena ia menggunakan otaknya sementara teman-teman SD-nya yang sebelumnya mengejek Jokowi kena imbasnya, juga digunakan metafora sebagai dasar pembenar bahwa Jokowi orang pintar dengan penggunaan kalimat “kata Simbahku”, “orang pintar itu”, “pake otak”, dst. Perintah guru SMA untuk tepuk tangan atas keberhasilan Jokowi memecahkan soal sementara semua temannya tidak mampu, menampilkan bagaimana Jokowi lebih unggul serta melemahkan yang lain, dapat pula dilihat dalam scene Jokowi saat kuliah. Hanya ia yang mampu memberikan penjelasan atas tema dari dosen dan menjawab pertanyaan dari mahasiswa lain. Konstruksi citra Jokowi sebagai sosok pintar dan cerdas dilakukan dengan memberikan detil-detil, metafora dan koherensi pembeda sehingga memunculkan maksud adanya hal bertentangan antar tokoh, yang pada akhirnya menampakkan Jokowi pada posisi yang lebih unggul.
Selain pada skema, hal itu dapat dilihat pada elemen detil sekaligus koherensi pembeda seperti tepuk tangan, menunjukkan bahwa Jokowi aktif yang lain tidak, Anto yang membersihkan tepung di rambut dan menyikut temannya, gelak tawa bernada ejekan terhadap Anto, yang tadinya mengejek Jokowi. Pemilihan kalimat diucap para guru, baik secara eksplisit maupun implisit mengungkapkan maksud komunikator. Penggunaan kata “pinter, pakai otak” secara leksikon memperjelas maksud dan tema dikonstruksikan terhadap sosok Jokowi. Makna itu dikuatkan dengan kalimat “kata simbahku” yang secara retoris menunjukkan adanya dasar penguat bahwa dalam melakukan semua hal itu harus ada dasar atau dipikir sebelumnya. “Simbah” dalam bahasa
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
138 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Jawa24 berarti nenek atau kakek. Masyarakat Jawa juga menggunakan sebutan itu untuk orang yang dituakan karena kemampuan lebih dimiliki, sekalipun usianya masih muda. Pemilihan kata “simbah” menegaskan arti bahwa apa yang dilakukan Jokowi ada dasar yakni dari orang yang dianggap memiliki pengetahuan/pengalaman lebih sehingga apa yang dikatakannya adalah benar, patut jadi rujukan. Secara sintaksis, kalimat kata “simbah” menyampaikan maksud komunikator, menunjukkan Jokowi orang yang penuh perhitungan, melakukan sesuatu dengan dasar, tidak asal.
2. Menghargai pluralisme.
Jokowi dikonstruksikan sebagai sosok yang mampu menghargai pluralisme atau perbedaan. Pengalaman hidup tinggal dengan orang-orang berbeda latar belakang agama, suku, dan sosial menjadi dasar konstruksi bahwa ia tak akan terpicu dan akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan berbungkus suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Konstruksi itu terlihat dari analisis tematik terhadap scene-scene ditampilkan, sintaksis, dan stilistik serta elemen detil yang semuanya memposisikan sosok Jokowi di posisi lebih serta melemahkan sosok lainnya.
Jokowi dan keluarganya tinggal, bergaul dan bersahabat dengan keluarga beda agama. Jokowi lahir dengan agama Islam namun ia dan keluarganya tinggal di rumah sewa yang pemiliknya beragama Katholik. Di dalam rumah terpajang representasi Yesus Kristus di atas kayu salib (scene 00.23.47-00.24.14). Secara semantik, scene ini menampilkan pesan/maksud bahwa bagi Jokowi, perbedaan tidak harus dan bukan menjadi masalah. Hal itu diskemakan dengan adegan dimana Jokowi mampu bergaul dan
24 Nursam Windarti, Kamus Basa Jawa, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2012, hal 199.
bersahabat baik dengan anak pemilik rumah meski beda agama, diungkapkan lewat scene Jokowi yang sering diantar ke tempat mengaji, oleh anak pemilik rumah. Sub tema ini diperkuat dengan penggunaan latar berupa adegan Jokowi kecil diberi penjelasan ayahnya bahwa manusia harus saling menghormati dan berbuat baik sekalipun beda keyakinan (scene 00.24.38-00.25.00).Mihardjo : “Bu Harjo dan keluarganya itu le, punya keyakinan berbeda dengan kita. Rak popo to?” (Jokowi mengangguk). “Tuhan juga menciptakan manusia yang berbeda-beda tapi tetap satu keturunan, ya Nabi Adam. Tapi biarpun kita berbeda, tetap harus saling menghormati dan berbuat baik, ya!.” (Jokowi mengangguk lagi tanda mengerti perkataan bapaknya).
Nasehat di atas, secara semantik sekaligus menjadi latar atau penjelas maksud ingin disampaikan komunikator mengenai pandangannya terhadap perbedaan dalam hidup. Pemilihan kata dan kalimat makin memperjelas pemaknaan. Tehnik pengambilan gambar secara dekat (close-up) terhadap Jokowi kecil yang mengangguk-angguk mendengarkan penjelasannya bapaknya, merupakan elemen grafi s untuk menonjolkan betapa pentingnya bagian ini. Jokowi yang masih kecilpun, sudah paham cara menyikapi perbedaan.
Jokowi yang mampu menghargai pluralisme juga dikonstruksikan lewat scene ia tinggal di lingkungan sosial kurang baik, masyarakat judi sabung ayam. Jokowi dan keluarganya tidak terpengaruh. Ia tetap rajin mengaji, bapaknya tidak ikut-ikutan berjudi, dan ibunya terus menasehatinya untuk rajin beribadah (scene 00.25.00-00.25.30). Sub tema dalam scene ini dapat dilihat dari aspek semantik dan penggunaan detil. Kalimat-kalimat dalam dialog menggunakan koherensi pembeda yang semuanya menonjolkan
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 139
sosok Jokowi pada citra positif dengan melemahkan sosok/pemeran lainnya.
Scene mengkonstruksikan Jokowi dan keluarganya taat terhadap agama sementara lainnya tidak, sebab melakukan perbuatan dilarang agama. Scene menonjolkan sosok Jokowi dalam citra positif dengan cara melemahkan sosok lainnya seperti Jokowi berwudhu, mengenaikan peci, teriakan suara ibunya, “Joko, jangan lupa mengaji!,” dan bagaimana ia lari menerobos kerumunan sabung ayam menonjolkan sosok Jokowi yang taat di tengah kurang kuatnya kontrol agama di lingkungan sekitar ia hidup. Koherensi pembeda pembeda ini dikuatkan dengan adegan riak riuh para peserta sabung ayam “Ayo..ayo..ayo”, menimbulkan makna kontras dengan apa dilakukan Jokowi sehingga menimbulkan efek positif bagi Jokowi dan negatif bagi lingkungan di sekelilingnya. Islam melarang umatnya berjudi termuat dalam QS Al-Maidah : 90.
Konstruksi citra ini ditampilkan pula dalam scene Jokowi kuliah di Yogyakarta, hidup di tengah masyarakat dari berbagai latar belakang berbeda. Selama tinggal di kos, ia berbagi kamar dengan seorang warga keturunan Batak (ditampilkan lewat logat bicara (scene 01.09.10). Sub tema ini mewacanakan sosok Jokowi yang bakal mampu menjaga kerukunan di tengah-tengah banyaknya perbedaan di masyarakat.
Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial, tak hanya dalam keluarga namun juga masyarakat, dimana semua pihak dalam keadaan damai satu sama lain, saling menerima, saling kerjasama dalam suanasa tenang dan sepakat.25
25 Frans Magnis Suseno, Etika Jawa : Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 39.
Rukun adalah salah satu kaidah dasar kehidupan orang Jawa yang selalu dijaga agar tidak terjadi konfl ik. Dengan bertindak rukun, orang Jawa dikatakan tidak egois. Mampu berbaur dengan orang lain termasuk salah satu upaya menjaga kerukunan. Dalam Jawa dikenal istilah “durung jawani, ora njawani” menujuk arti tidak paham sehingga berlaku layaknya orang tidak dewasa. Orang yang demikian dalam sebutan ekstrim bisa disebut “durung dadi uwong” (belum jadi manusia) atau “kaya kewan” (seperti hewan).26 Istilah itu juga dapat digunakan untuk menyebut orang Jawa yang tidak mampu menyelaraskan hidupnya dengan orang lain.
Masyarakat Jawa adalah orang-orang yang mengutamakan kebersamaan dan keselarasan. Dari sini jelas bahwa mereka yang tidak mampu menyelaraskan diri dengan lingkungannya, tidak akan mungkin mendapatkan simpati sehingga tidak akan mungkin dipilih menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu mengampu masalah perbedaan hingga tercipta ketertiban. Pemimpin yang demikian dinilai mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya. Namun tidak semua pemimin mampu melakukan hal itu. Idiologi kepemimpinan Jawa menyebarkan mitos bahwa hanya pemimpin yang memiliki wahyulah yang mampu menciptakan perlindungan dan ketertiban bagi masyarakatnya. Niels Mulder menjelaskan keterkaitan wahyu dengan keyakinan di Jawa.27
Bahwa kemampuan dalam melindungi masyarakat merupakan turunan perlindungan dari atas, perlindung yang lebih tinggi, sumber yang dianggap memegang perlindungan paling akhir
26 Ibid, hal 158. 27 Niels Mulder, Op.Cit, hal.46.
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
140 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
(Tuhan). Pemimpin, keselarasan, ketertib-an adalah satu paket. Dari sini kita dapat membaca maksud komunikator meng-konstruksikan Jokowi sebagai sosok yang mampu menghargai perbedaan. Dengan adanya rasa saling menghormati, ketertiban maupun kerukunan hidup dapat tercipta. Kemampuan ini, tak hanya datang begitu saja kepada Jokowi namun berkat terpilih sebagai penerima “wahyu”. Bahwa tanda-tanda kekuasaan, sudah ia miliki.
3. Penganut agama yang baik
Konstruksi Jokowi adalah sosok dengan ibadah baik, dilakukan dengan menyodorkan scene Jokowi pandai mengaji, melakukan sholat malam. Analisis pada struktur mikro dan makro teks menunjukkan penonjolan-penonjolan pada karakter Jokowi dan pelemahan pada karakter lain.
Scene 00.27.02 menampilkan kemampu-an Jokowi membaca kitab suci disusul pemilihan dialog, “Bagaimana tadi? Bisa, mengajinya?” tanya salah satu teman. “He eh, bisa ngaji, gampang”. Jawab Jokowi. Gampang dalam bahasa Jawa berarti mudah. Secara leksikon, kata ini digunakan untuk memperkuat makna Jokowi adalah pintar juga taat agama. Membaca kitab suci adalah salah satu kewajibanorang Islamdantaranya diperintahkan dalam QS Al-Alaq :1- 4 dan QS Al A’rof : 157.
Selain mampu mengaji, seorang muslim yang baik juga dikonstruksikan lewat scene dimana Jokowi juga melakukan sholat malam, meskipun hanya ada satu adegan, yakni saat ia tinggal di kos saat masih kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (scene 01.11.42). Sembahyang adalah hal wajib termuat dalam QS 4 An Nisaa’ : 103. Islam juga mengajarkan umatnya untuk menuaikan sholat sunat sebagai ibadah tambahan sebagaimana termuat dalam QS Al Baqarah : 153.
Sementara sholat sunah sebagai ibadah tambahan ada banyak macamnya namun yang umum dilakukan adalah sholat tahajud sebagaimana termuat dalam QS Al Isro’ : 79. Sebagai sosok yang taat agama, Jokowi juga dikonstruksikan tidak minum-minuman keras dan bergaul dengan orang baik (scene 01.00.00-01.00.36) :“Aku ndak mabuk-mabukan buk, aku ndak bergaul dengan orang-orang nggak genah. Aku nggak mau ngecewain ibuk,” kata Jokowi kepada ibunya yang menangis karena berpikir Jokowi telah salah pergaulan.
Scene-scene di atas mengangkat tema jokowi sebagai sosok yang menjalankan syariat agama Islam dengan baik. Mempelajari Al-quran, sembahyang, tidak berjudi dan minum-minuman keras adalah perintah sebagaimana tercantum dalam kitab suci orang Islam, Al-Quran, khususnya Al Maidah ayat 90. Ibadah yang dilakukan Jokowi sebagaimana ditunjukkan dalam scene-scene di atas mencitrakan karakter orang beriman. Berbicara soal Islam selalu akan dikaitkan dengan masalah iman. Hitam putih keislaman seseorang selalu diukur dari kadar keimanannya, yaitu sejauh mana orang tersebut mematuhi segenap perintah Tuhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.28 Sepak terjang seseorang yang mencerminkan kesempurnaan iman adalah bila ia mampu mempraktikkan seluruh cabang iman dalam kehidupannya. Iman adalah percaya yangmana dalam ajaran Islam, merujuk kepercayaan terhadap enam hal. Cabang Iman merujuk pada hadits, ada 60 diantaranya memuliakan Al-Quran, mendirikan sholat, memelihara diri dari makan dan minum yang diharamkan, berbakti kepada orangtua, dan dermawan.29 Rujukan di atas mengungkap maksud komunikator tentang bagaimana Jokowi dicitrakan dari sudut pandang agama.
28 Syamsul Rijal Hamid, ibid., hal.36.29 Ibid, hal.40-52.
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 141
4. Jujur, tidak tergiur suap, dan pemberaniJokowi sosok yang jujur, tidak tergiur
suap dikonstruksikan dalam scene 00.27.15-00.28.26. Jokowi dihadang di jalan dan diminta tutup mulut agar tidak melapor ke guru bilaada anak bolos mengaji. Untuk tutup mulut, Jokowi diberi uang namun menolak. Jumlah uang ditambah, Jokowi tetap menolak. Jokowi lebih memilih menerima dihajar akibat menolak suap serta menerima amarah dari ayahnya karena dianggap berkelahi.“Ini.” Kata seorang anak lelaki berbalut kain sarung layaknya kostum ninja, menyodorkan satu koin uang logam ke Jokowi. “Buat apa itu?” tanya Jokowi. “Jangan bilang ke pak ustad kalau kami kabur!”. “Maaf kalau seperti ini aku ndak bisa terima”. Timpal Jokowi. “Kurang?” “Huh sudah miskin sombong.” Kata temannya yang lain. “Nih aku tambahin buat jajan” kata anak pemberi uang tadi. “Maaf tapi aku tetap ndak bisa nerima” jawab Jokowi lagi. Sesaat kemudian Jokowi dihajar karena menolak.
Scene ini baik secara tematik, skematik, maupun stilistik, mengkonstruksikan citra Jokowi sebagai sosok pemberani dengan melemahkan sosok yang lain. Ditampilkan, ia dihadang anak berkostum ala ninja, saat itu sejumlah temannya membalikkan langkah pertanda takut namun tidak bagi Jokowi. Ia menghadapi masalah di depan matanya. Analisis semantik menunjukkan maksud yang jelas atau tersurat, penggambaran Jokowi yang anti suap dan pemberani. Secara sintaksis kalimat dipilih menunjukkan Jokowi sosok antisuap. Scene ini juga menggunakan koherensi pembeda dengan menunjukkan makna berkebalikan antara keputusan dipilih Jokowi dengan apa dilakukan temannya yakni membolos, menyuap, dan takut menghadapi musuh.
Tema pemberani dikonstruksikan juga lewat scene Jokowi menceburkan diri ke dalam arus sungai, mengambilkan baju
hanyut salah seorang nenek yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai (scene 00.38.00-00.38.20). Secara sintaksis, scene ini menggunakan koherensi pembeda dengan melemahkan sosok lain disertai detil berupa tidak adanya orang lain yang peduli terhadap teriakan simbok pemilik baju hanyut. Scene 00.39.03-00.39.25 juga mencitrakan sosok pemberani. Jokowi kecil berteriak lantang, melawan petugas Satpol PP yang tengah menggusur rumahnya. Semua scene saling menguatkan satu sama lain, mendukung dengan cara memperkuat karakter positif pada diri Jokowi.
5. Sayang, peduli keluarga, berbakti kepada orangtua, suka menolong, dermawan, rendah hati, memanusiakan sesama, bakat, takdir pemimpin
Jokowi sepertinya memang sudah lahir dengan takdir sebagai pemimpin. Tema ini dikonstruksikan melalui banyaknya penggunaan praanggapan yang dipakai komunikator untuk memperjelas maksud diutarakan. Kalimat-kalimat dalam setiap scene mengutarakan tema secara jelas yangmana didukung pula oleh penggunaan latar dan elemen retoris sebagai penegas. Sub tema ini digambarkan secara jelas lewat skema cerita dijalankan yang dari awal dari akhir, hampir semuanya menggunakan asumsi-asumsi berupa keyakinan maupun ungkapan yang menunjukkan bahwa ia memang ada bakat (takdir) menjadi seorang pemimpin. Cerita dibangun dengan cara menggiring asumsi bahwa ia nantinya bakal menjadi orang besar.
Scene awal bagian dari pembuka fi lm 00.05.45-00.00.06.28 : Mihardjo menimang anaknya yang baru lahir. Mihardjo : “Tak ting tung ting tung. Anak bapak besok gedhe jadi apa? Tukang kayu kayak bapak.”Kakek : “Wo..ra maju”. Mihardjo : Lha mau jadi apa to pak? Bapaknya saja tukang kayu, yo le
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
142 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
yo?,”Kakek : Kalau kamu mendoakan anakmu itu jangan asal-asalan. Besok besar jadi petinggi. Jadi orang yang bikin dunia makmur, jadi panutan orang banyak, gitu.”
Ucapan kakek Joko yang menanggapi omongan Mihardjo di atas setidaknya menggambarkan bahwa Jokowi tidak hanya diinginkan hidup sebagai orang biasa namun orang besar, seorang petinggi, dalam hal ini menjadi top leader. Analisis pada tataran mikro berupa pemilihan kata dan kalimat dipakai dalam narasi fi lm juga menguatkan hal itu seperti elemen sintaksis dan stilistik yang ditunjukkan dalam pemilihan kata “petinggi”, “jadi orang yang bikin dunia makmur”, serta “panutan orang banyak.” Kata “jadi orang yang bikin dunia makmur” mengindikasikan bahwa Jokowi tak hanya cukup diharapkan menjadi pemimpin yang menjadi panutan orang banyak namun juga memenuhi aspirasi, keinginan dan kebutuhan warga dipimpinnya. Pemilihan kata “dunia” menunjukkan bahwa Jokowi diharapkan tak hanya menjadi petinggi di tataran rendah atau sedang namun menjadi top leader atau pemimpin dengan karir tertinggi, semisal di tingkatan pemerintah kota, tentu tak hanya menjadi lurah namun walikota, dalam tataran tingkatan lebih tinggi tentunya menjadi gubernur hingga dan berakhir menjadi seorang presiden.
Adanya asumsi atau praanggapan bahwa Jokowi akan menjadi orang besar juga dapat dilihat pada scene 32.15-34.36. Jokowi dinasehati kakeknya. Sambil memegang wayang : Le ini sapa? Raden Werkudara dia ini satria yang gagah besar lurus hatinya. . Nah itu le kamu sudah belajar dari pengalaman (Joko mengangguk tanda paham)…Le kamu besok bisa jadi orang besar. Simbah bisa merasakan itu.”
Scene 01.07.07-01.09.07 : Mihardjo dan Jokowi makan soto. Mihardjo: “Kamu harus nirun tukang soto itu. Yang datang ke sini
macem macem permintaannya. Dari permintaan yang buanyak dan bermacem macem itu, tukang soto tetap melayani. Nanti kalau kamu di tengah-tengah masyarakat, ketemu orang dari berbagai jenis mereka juga akan punya keinginan dan permintaan yang muacem macem. Banyak permintaan, banyak keinginan tapi kamu tetap harus melayani. Tapi sebenarnya le, kamu yang menjadi panutan mereka. Ada peribahasa ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Bagaimana memenangkan sesuatu tanpa membuat musuh yang dikalahkan itu merasa kalah ataupun direndahkan.”
Scene-scene di atas, ucapan Mihardjo kepada anaknya menunjukkan ada pesan bagaimana bila Jokowi nantinya menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Skema ini didukung dengan pemilihan kata yakni “melayani”, “panutan”, “orang besar”. Elemen leksikon ini begitu jelas menunjukkan maksud dari komunikator tentang bagaimana Jokowi seolah sudah dipersiapkan dengan sangat matang berbekal pesan-pesan baik dari orangtuanya bila nanti menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Bahwa pemimpin selain sebagai panutan juga seorang pelayan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penggunaan metafora dalam istilah Jawa “ ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake”. Sebuah peribahasa Jawa yang selalu erat kaitannya dengan cara orang Jawa menghadapi atau menundukkan lawan dengan cara-cara persuasif, dengan memberikan contoh sebagai sosok kesatria, bertanggung jawab dan tidak menghinakan lawan.30 Elemen praanggapan “Nanti kalau kamu di tengah-tengah masyarakat” makin memperjelas makna teks mengenai kepemimpinan. Skema cerita pada bagian akhir makin menunjukkan dengan jelas mengenai tema bahwa Jokowi adalah sosok yang layak menjadi seorang pemimpin. Scene 01.44.00
30 RMP Sosrokartono, Ilmu dan Laku, Citra Jaya Murti, Surabaya, 1988, hal. 91.
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 143
-01.45.10 menampilkan latar berupa fl ashback di masa lalu Jokowi bersama sang ayah, setelah bapaknya meninggal. Tergiang ucapan bapaknya “Setiap orang lahir dengan takdirnya sendiri. Dengan sebisanya bapak dan ibu membesarkan kamu. Tapi takdir itu ada di tangan kamu sendiri. Waktu bapak memberimu nama Joko Widodo, bapak berharapkamu akan jadi lelaki yang selamat dunia dan akhirat. Itu hanya nama sederhana, kamu sendiri yang bisa membuat nama sederhana itu menjadi berharga.”.
Film ini banyak menggunakan kata bijak sebagai latar atau penjelas yang membentuk pribadi Jokowi. Latar disusul dengan skema cerita pelantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai klimaks atau puncak cerita dimana pelantikan itu disaksikan seluruh pedagang Pasar Gede Solo. Tak hanya tua dan dewasa, anak-anak pun sangat antusias menyaksikan prosesi ini. Scene ini juga diperlihatkan dengan sangat detil untuk menunjukkan maksud dan makna dari komunikator tentang sosok Jokowi yang begitu berharga di mata masyarakat, dielu-elukan, diimpi dan didamba masyarakat. Bahwa kemenangannya adalah kemenangan rakyat. Elemen detil dimulai dari seorang anak laki-laki kecil sekitar usia enam tahun berlari menuju pasar dengan sangat tergesa. Seluruh lorong pasar diperlihatkan “mati”. Barang-barang dagangan ditinggalkan begitu saja oleh pedagang seolah tak lagi penting bagi mereka. Kemanakah mereka? Ternyata mereka semua berkumpul di salah satu sudut pasar, bersama menyaksikan pelantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI melalui televisi tabung kecil. Tua, muda, anak-anak bersama menyaksikan prosesi ini. Begitu pelantikan selesai semua bertepuk tangan, tertawa dan menangis. Tak hanya orang dewasa yang menangis tanda bahagia akan keberhasilan Jokowi dalam pemilihan Gubernur DKI, anak
kecil yang melihat dari perawakan belum ada usia 6 tahun tadi juga turut menangis tanda lega bahagia. Adegan menghadirkan anak kecil dalam moment ini secara detil sebenarnya sangat berlebihan sebab tak ada relevansinya dengan kemenangan Jokowi sebagai Gubernur. Secara logika, anak-anak belum memiliki keterkaitan emosi maupun referensi tentang pemimpin idola, kecuali memang ada keterkaitan keluarga. Namun adegan ini dimasukkan untuk menguatkan maksud komunikator bahwa Jokowi adalah pemimpin yang sangat didamba dan dinanti, impian rakyat bahwa hingga seorang anak kecil yang biasanya belum paham apa-apa, turut sangat menginginkan kemenangannya.
Maksud ini diperkuat dengan situasi seluruh pasar yang “mati” demi menonton prosesi pelantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI. Bagaimana para pedagang meninggalkan seluruh dagangan tanpa ada pengamanan sama sekali seperti menutupi dengan lembar plastik atau upaya lainnya, demi untuk menonton acara pelantikan Jokowi di televisi, menunjukkan bahwa momen itu jauh lebih penting dari apapun. Kehilangan barang dagangan tidak ada artinya dibanding tidak dapat menyaksikan walikota mereka yang dulu, kini berhasil di karir politik yang lebih tinggi. Shot-shot wanita tua bakul pasar, aktivitas kerokan sambil nonton TV menunjukkan maksud komunikator bahwa Jokowi adalah representasi rakyat kecil sehingga otomatis akan memperhatikan nasib mereka. Detil diberikan sangat banyak yakni model siaran televisi yang dibuat dua layar memperlihatkan pelantikan Jokowi dan kerumunan warga di luar gedung pelantikan, menandakan antusias dan kebahagiaan mereka. Seperti sorak sorai, poster-poster tulisan “Jakarta Bersatu” dan masyarakat membawa berbagai simbol kebahagiaan seperti simbol cinta berbentuk hati (love) (scene 01.45.11-01.46.35). Lambang cinta,
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
144 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
air mata, tawa, tepuk tangan, kerumunan massa, menunjukkan betapa Jokowi adalah pemimpin idaman yang dapat menyatukan seluruh masyarakat.
6. Berkeinginan maju, pekerja keras, tak mudah menyerah, mencintai budaya asli, setia, idak terlibat organisasi terlarang.
Jokowi pantas menjadi seorang pemimpin di negeri ini salah satunya dikonstruksi lewat citra politiknya yang bersih, tidak terlibat organisasi terlarang terutama Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini dapat dilihat pada scene00.20.00-00.20.47. Jokowi dan bapaknya tidak ditangkap aparat karena tidak tercatat dalam jaringan partai bersimbol palu arit itu. Meski hanya disajikan dalam hitungan kurang dari satu menit, sekilas, tidak ada keterkaitan dengan jalannya cerita secara keseluruhan, scene yang menyatakan jika Jokowi dan seluruh keluarganya tidak terlibat partai komunis ini sangat penting untuk dihadirkan sebagai bukti atau jaminan bahwa Jokowi tidak pernah memiliki persoalan hukum dan politik. Citra tidak terlibat PKI penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan sosial serta politik yang luas.
Daftar PustakaAgung Wasesa, Silih. 2011. Political
Branding and Public Relations. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Amir, Marfi . 1999. Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam. Jakarta : Logos.
Antlov, Hans; Cederroth, Sven. 2001. Kepemimpinan Jawa : Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Arifi n, Ahmad. 2006. Pencitraan dalam Politik. Jakarta : Pustaka Indonesia.
AW, Suranto. 2010. Komunikasi Sosial Budaya. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Black, Jay; Whitney, Frederick C., 1998. Introduction to Mass Communication. USA : Brown Publishers.
Budi Suseno, Dharmawan. 2009. Wayang Kebatinan Islam. Bantul : Kreasi Kencana.
De Fleur, Melvin. 1989. Theories of Mass Communication, 5th edition, London : Longman
Eriyanto. 2011. Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Fachruddin, Andi. 2012. Produksi Televisi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Garret, Peter; Bell, Allan. 1998. Media Discourse : A Critical Overview . Oxford: Blackwell Publishers.
Hamid, Syamsul Rijal. 2008. Buku Pintar Agama Islam. Bogor : Cahaya Salam.
Hikam AS. 1996. Bahasa dan Politik (Yudi Latif dan Idy Subandy Ibrahim, ed), Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orba. Bandung: Mizan.
Magnis Suseno, Frans. 1996. Etika Jawa : Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta : Gramedia Pustaka.
----------. 2001. Etika Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Mufti, Muslim. 2012.Teori-Teori Politik. Bandung : Pustaka Setia.
Mc Quail, Denis. 2011. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Salemba Humanika.Ed. 6.
Niels Mulder. 1984. Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
----------.1996. Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional.Yogyakarta : UGM Press.
Nimmo, Dan. 2000. Komunikasi Politik : Khalayak dan Efek. Bandung : Rosdakarya.
Erwin Kartinawati. Film dan Konstruksi ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 145
Pawito. 2009. Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta : Jalasutra.
Prasetyawan, Wahyu, “Image Construction in Politics : Political Adverstiment in 2009 Indonesian Election”, Journal of Issaes in Asia vol 27 no 2, 2012, hal 310.
Sobur, Alex. Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framing. Bandung: Rosdakarya.
Sosrokartono, RMP.1988. Ilmu dan Laku. Surabaya : Citra Jaya Murti.
Tubbs, Steward L.; Moss, Sylvia. 2001. Human Communication (edisi terj. Deddy Mulyana dan Gembirasari). Bandung : Rosdakarya.
Windarti, Nursam. 2012. Kamus Basa Jawa. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
Hamad, Ibnu. “Perkembangan Analisis Wacana dalam Ilmu Komunikasi: Sebuah Telaah Ringkas”, http://syariat-tharikat-hakikat.blogspot.com/2008/04/perkembangan-analisis-wacana-dalam-ilmu.html, akses 1 Juli 2014.
www.mpr.go.id, tentang Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003 tentang Pembubaran dan Pelarangan Komunis, akses 10 Juli 2014, pkl 16.15 wib.
www.mahkamahkonstitusi.go.id., akses 10 Juli 2014 pkl 16.15 wib.
www.kompas.com, “Tak ada Izin, Jokowi Keberatan Film Jokowi”, Rabu 22 Mei 2013 pkl 16.37 wib.
www.merdeka.com, “Film Jokowi jadi Media Kampanye Pilpres”, Senin 9 Juni 2014 Pkl 18.57 wib.
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 147
Wacana Revitalisasi Pancasila di Media(Studi Analisis Framing Pemberitaan tentang
Revitalisasi Pancasila di Harian Kompas Tahun 2013)
Sri Herwindya Baskara Wijaya Mursito BM
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sebelas Maret Surakarta
AbstractThis research attempts to examine more deeply about the revitalization of Pancasila discourse in the media. The mass media were selected as the study sample was Compass. Compass chosen, as well as national level newspapers, also considering the related daily known as the largest newspaper in Indonesia, even in Southeast Asia and intense in publishing views about the Indonesian nationality. Chosen period of the year 2013 in view of the many prominent discourse about the revitalization of Pancasila. This research is qualitative communication research. Qualitative communication research. This study used the method of framing analysis Entman models.This paper fi nd as many as 20 news related to the revitalization of Pancasila discourse in the media (newspaper Kompas) during the year 2013. A total of 17 news live news manifold (straight news) and 3 manifold news news story (news feature). Almost all objects always mempertautkan news discourse discourse Pancasila Pancasila Four Pillars Nationality, 1945, the Republic of Indonesia (NKRI) and Unity in Diversity. This means framing Compass assume that Pancasila with Four Pillars of Nationality as a separate entity not.Compass looked Pancasila as an ideal value system for Indonesia. Indonesia has a diversity of cultures, customs, religion, creed, tribe, nation, and tradition, so it requires an order of values that can overshadow all that diversity. Pancasila is also regarded as the order derived from the Indonesian character, so that its implementation would be easy. All you need do now is to demonstrate that the values of Pancasila now starting to decline from the discovery of evidence of abuse. And promote the importance of the implementation of Pancasila in the life of the state.In addition to socializing, studying history is also an important part in understanding the importance of the implementation of Pancasila for Indonesia. Pancasila were born from the womb of mother earth to be a factor why the values contained in Pancasila so down to earth. So, not an impossible thing that Pancasila can be implemented in the country of Indonesia.Key words: revitalization of Pancasila, framing analysis, mass media
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 147-158
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
148 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Pendahuluan
Bangsa Indonesia sejak terbentuknya tahun 1945 bisa dikatakan belum sesuai harapan dan cita-cita para pendiri bangsa ini yaitu tercapainya Indonesia yang bermartabat, adil dan makmur. Malah yang terjadi saat ini Indonesia justru terpuruk dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak pihak menilai ragam permasalahan yang merundung Indonesia saat ini dikarenakan bangsa Indonesia telah meninggalkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Jati diri itu sebenarnya tercermin dari ideologi bangsa ini yaitu Pancasila. Pancasila digali oleh Ir Soekarno dari karakter-karakter dasar bangsa Indonesia sendiri seperti berketuhanan, gotong royong, ramah, saling menghormati, toleransi, dan lain-lain.
Sebagaimana disampaikan Rikard Bagun bahwa sampai sekarang belum terlihat jelas upaya mewujudkan nilai sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh. Tidak pernah sepenuh hati dilaksanakan secara konkret. Upaya perwujudan nilai-nilai Pancasila selama ini terkesan setengah hati. Tidak banyak yang peduli jika Pancasila diganggu oleh ideologi lain. Lemahnya dukungan juga terlihat pada wacana tentang Pancasila yang cenderung melemah.
Dalam kerangka itulah, penggalian kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempertimbangkan rasionalitas dan aktualisasinya dalam mengatasi masalah kekinian adalah cara tepat untuk mentransformasikan ketakutan menjadi harapan.1 Sebagaimana dikatakan Frans Magnis Suseno bahwa Pancasila sebagai janji dan komitmen tegas seluruh bangsa kepada segenap warganya bahwa tak ada diskriminasi dan pembedaan apapun atas nama suku, agama, ras, kedudukan sosial
1 Yudi Latif, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: 2011), hal. 614.
dan nuansa budaya mereka. Pancasila sebagai perjanjian solidaritas bangsa Indonesia lintas kelompok, golongan dan umat.2
Penelitian ini menelaah lebih dalam soal wacana revitalisasi Pancasila di media massa. Adapun media massa yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah Kompas dan Republika tahun 2013. Dipilihnya Kompas dan Republika, selain sebagai koran level nasional, juga mengingat harian terkait dikenal sebagai koran yang intens menyuarakan pandangan soal kebangsaan. Dipilihnya periode tahun 2013 mengingat tahun tersebut banyak mengemuka wacana soal revitalisasi Pancasila terutama saat program empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara digeliatkan kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Isu tentang revitalisasi Pancasila adalah bagian dari isu program Empat Pilar Kebangsaan yang dipopulerkan oleh mantan Ketua MPR, Taufi k Kiemas. Empat Pilar Kebangsaan meliputi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Peneliti sendiri pernah meriset soal nilai-nilai Pancasila seperti pada novel “Habibie dan Ainun” tahun 2012. Hasil penelitian dirinya menunjukkan bahwa terdapat sejumlah nilai-nilai Pancasila sebagai implementasi dari pendidikan karakter bangsa yang diwacanakan mantan Presiden BJ. Habibie lewat novel tersebut yakni religius, disiplin, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, bertanggung jawab.3 Peneliti juga
2 Frans Magnis Suseno, John Rawls, Keadilan dan Pancasila, dalam “Berebut Jiwa Bangsa Dialog, Perdamaian dan Jiwa Bangsa”, (Jakarta: 2007), hal. 76-77.
3 Sri Herwindya Baskara Wijaya, (2012). Pendidikan Karakter Bangsa dalam Novel ( Studi tentang
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 149
melakukan riset tentang nilai-nilai Pancasila terkait wacana intoleransi beragama di Indonesia pada media lokal di Kota Solo tahun 2012. Ditemukan bahwa sepanjang tahun 2012 terjadi penyimpangan atas nilai-nilai Pancasila melalui terjadinya kekerasan atas nama agama yakni kasus Syiah, kasus Ahmadiyah dan kasus Gereja Yasmin. 4
Peneliti melihat belum ada penelitian yang khusus membahas mengenai revitalisasi Pancasila sebagai sebuah wacana publik di media massa berskala nasional. Padahal Pancasila diyakini sebagai ideologi terbaik bangsa di tengah kemerosotan di berbagai bidang kehidupan pada bangsa Indonesia dewasa ini. Terlebih lagi jika wacana revitalisasi Pancasila digaungkan oleh media massa berskala nasional sehingga diharapkan efek positifnya juga bersifat massif dan menyeluruh.
Rumusan Masalah
Bagaimana framing pemberitaan tentang revitalisasi Pancasila itu di Harian Kompas tahun 2013?
Tinjauan Pustaka
1. Revitalisasi PancasilaRevitalisasi menurut kamus besar
Bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara dan perbuatan yang menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenernya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti
Pesan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa Menggunakan Pendekatan Semiologi Komunikasi dalam Novel Nonfi ksi “Habibie dan Ainun” karya B.J. Habibie dan “Belahan Jiwa” karya Rosihan Anwar ). (Surakarta: Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS).
4 Ibid., (2013). Media Massa dan Intoleransi Beragama (Studi Kasus tentang Wacana Intoleransi Beragama pada Surat Kabar lokal di Kota Surakarta Tahun 2012). Surakarta: Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS.
sangat penting atau perlu sekali. Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, revitalisasi secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.5
Revitalisasi Pancasila dapat diartikan sebagai usaha mengembalikan Pancasila kepada subjeknya yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan. Untuk merevitalisasi, maka Pancasila perlu diajarkan dalam kaitannya dengan pembuatan atau evaluasi atas kebijakan publik selain dibicarakan sebagai dasar negara. Pancasila dapat dihidupkan kembali sebagai nilai-nilai dasar yang memberi orientasi dalam pembuatan kebijakan publik yang pro terhadap aspek-aspek agama, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila.6
Dalam proses revitalisasi tercakup pengertian Pancasila sebagai ideologi merupakan pangkal atau dasar berpikir, lalu ada prinsip-prinsip, kemudian ada institusi-institusi yang menggerakkannya, dan terakhir ada ukuran-ukuran untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip itu terwujud atau tidak. Prinsip-prinsip adalah bagaimana sebagai ideologi Pancasila meningkatkan harkat dan martabat manusia, bagaimana meningkatkan persatuan nasional dan bagaimana menciptakan kesejahteraan dalam keadilan sosial. Institusi-institusi apa saja yang diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip itu.7
Mempertimbangkan posisi krusial Pancasila di atas, maka perlu dilakukan revitalisasi makna, peran, dan posisi Pancasila bagi masa depan Indonesia
5 Triwardana Mokoagow, dalam http://fi lsafat.kompasiana.com/2013/12/18/revitalisasi-pancasila-617631.html
6 Ibid.7 Midian Sirait, dalam http://socio-politica.
com/2013/07/29/revitalisasi-pancasila-7/
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
150 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
sebagai negara modern. Perlunya revitalisasi Pancasila karena didasari keyakinan bahwa Pancasila merupakan simpul nasional yang paling tepat bagi Indonesia yang majemuk. Rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral kepemimpinan nasional. Empat pemimpin nasional pasca Soeharto sejak dari Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum berhasil membawa Pancasila ke dalam wacana dan kesadaran publik. Ada kesan traumatik untuk kembali membicarakan Pancasila. Kini, sudah waktunya para elite dan pemimpin nasional memberikan perhatian khusus kepada ideologi pemersatu ini jika kita betul-betul peduli pada nation and character building dan integrasi bangsa Indonesia.8
Revitalisasi Pancasila semakin terasa penting kalau diingat kita tengah gigih menerapkan prinsip-prinsip “good governance”, dimana tiga aktor yaitu pemerintah (state), swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) harus bersinergi secara konstruktif mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Antara lain terwujud dalam bentuk pelayanan publik (public services) yang optimal. Dalam kaitannya dengan ancaman atau pengaruh globalisasi harus dihadapi dengan sikap mental dan karakter yang kuat sebagai jatidiri bangsa Indonesia. Akhirnya revitalisasi Pancasila menjadi penting karena kita masih menghadapi ancaman disintegrasi nasional dengan semangat separatisme dari Daerah yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Pemerintah Pusat.9
8 Kristiawan Hadisusanto, dalam http://dhd45jateng.wordpress.com/2012/06/25/revitalisasi-pancasila-sebagai-jati-diri-bangsa-indonesia/
9 Ibid.
2. Surat KabarMedia massa dalam era global
telah berhasil tidak saja kemampuannya menyatukan berbagai wilayah yang terpisah tergabung dalam sebuah desa raksasa bernama desa global melainkan juga membangun citra hidup global dengan keberhasilan membangun ekonomi global. 10 Media massa menjadi medium yang strategis dalam berbagai proses sosial, ekonomi dan politik bangsa.11
Media massa memainkan peran signifi kan di era global dewasa ini baik sebagai penyebar informasi, pembentuk opini publik, penghibur masyarakat hingga pengawas jalannya kekuasaan (watchdog). Surat kabar adalah salah satu jenis media massa yang ada saat ini. Dilihat dari jenisnya, surat kabar termasuk jenis media massa cetak. Selain surat kabar juga terdapat majalah, tabloid dan buletin. Selain media massa cetak juga terdapat media massa elektronik yaitu televisi, radio dan internet. Peranan surat kabar atau koran sebagai media informasi tidak diragukan lagi dalam konteks dewasa ini. Surat kabar bersama televisi dan internet saat ini menjadi media massa utama dalam memasifkan distribusi informasi ke berbagai penjuru dunia. Setiap negara memiliki industri-industri penerbitan koran dengan jutaan jurnalis bekerja di dalamnya.
Dilihat dari bentuk fi siknya surat kabar merupakan media analog (media cetak). Pada bentuk standar Koran memiliki ukuran 8 dan 9 kolom ke samping. Sedangkan pada bentuk baru, memiliki ukuran 6 dan 7 kolom. Surat kabar merupakan teknologi dan media
10 Andrik Purwasito, 2002 dalam Mahrus M. Mahsun, Komodifi kasi Global, dalam “Komodifi kasi Budaya dalam Media Massa”, (Surakarta: 2005), hal. 186.
11 McQuail, 2000, dalam Widodo Muktiyo, Dinamika Media Lokal dalam Mengkonstruksi Realitas Budaya Lokal sebagai Sebuah Komoditas, (Surakarta: 2011), hal. 28.
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 151
yang sangat aktual. Surat kabar juga menyajikan berita dan informasi yang singkat, padat dan jelas. Surat kabar hanya dapat dinikmati secara visual, yaitu menggunakan satu indera, penglihatan. Ini menjadikan surat kabar sebagai hot media dan tidak multitafsir. Surat kabar pun merupakan media yang praktis dan portabel.12
Era reformasi adalah era kebebasan pers. Presiden ketiga Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, membubarkan Departemen Penerangan, biang pembatasan pers pada orde baru yang dipimpin Harmoko. Surat kabar dan majalah kemudian dibiarkan tumbuh dan menjamur, begitu juga media-media lainnya: televisi dan radio. Tanpa tekanan; tanpa batasan. “Informasi adalah urusan masyarakat,” kata Gus Dur. Kebebasan ini kemudian melahirkan raksasa-raksasa media. Disebut raksasa karena hampir semua lini media digeluti: surat kabar, majalah, televisi, radio, dan website (surat kabar digital). Mereka adalah Kompas (Jacoeb Oetama), Jawa Pos (Dahlan Iskan), Media Indonesia (Surya Paloh), Media Nusantara Citra (Hary Tanusoedibjo), dan Tempo (Goenawan Mohamad). Luar biasanya, media mereka sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.13
Metodologi Penelitian
Penelitian ini memakai metode analisis framing model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki karena memiliki dua kelebihan dibanding analisis framing yang lain. Pertama, karena memberikan ruang lebih luas terhadap unit analisis seperti struktur berita, gaya bahasa, idiom, gambar, foto
12 http://lutviah.net/2011/01/14/media-massa-surat-kabar/, diakses 25 Desember 2012.
13 http://sejarah.kompasiana.com/2011/01/04/surat-kabar-di-indonesia/, diakses 25 Desember 2012.
dan juga grafi k. Kedua, terdapat empat bagian besar dengan bagian analisis masing-masing sehingga lebih lengkap dan sangat membentuk mulai dari proses pembentukan kategorisasi sampai tahap analisis.14
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan interactive model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.15 Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian komunikasi kualitatif. Penelitian komunikasi kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai gejala-gejala atau realitas-realitas agar dapat memberikan pemahaman (understanding, verstehen) mengenai gejala atau realita.16 Dipilihnya jenis penelitian ini mengingat riset yang dilakukan adalah riset wacana dimana termasuk dalam studi kualitatif.
Sumber data penelitian ini adalah berita-berita tentang wacana revitalisasi Pancasila pada Harian Kompas selama tahun 2013. Untuk melengkapi kesempurnaan data, peneliti juga akan menggunakan metode wawancara dengan sejumlah responden yang ahli soal Pancasila, kebangsaan dan media massa. Dipilihnya Kompas, selain sebagai koran level nasional, juga mengingat harian terkait dikenal sebagai koran terbesar
14 Eriyanto, 2002, Analisis Framing, (Yogyakarta: LKiS), hal. 257, dalam Ibid.
15 Punch, 2008, hal. 202, dalam Op.Cit.16 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif,
(Yogyakarta: LKiS), hal.36, dalam Adam Maulana Yusuf, 2014, Pemberitaan Mundurnya Calon Peserta Konvensi Partai Demokrat dalam Media Online (Studi Analisis Framing Pemberitaan Media Online metrotvnews.com dan VIVAnews tentang Mundurnya Calon Peserta Konvensi Partai Demokrat untuk Menentukan Calon Presiden pada Pemilu 2014), (Surakarta: Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS), hal 29.
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
152 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara dan intens dalam mempublikasikan pandangan soal kebangsaan Indonesia. Dipilihnya periode tahun 2013 mengingat tahun tersebut paling banyak mengemuka wacana soal revitalisasi Pancasila. Hal ini terutama sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) aktif mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk melengkapi kesempurnaan data, peneliti juga akan menggunakan metode wawancara dengan sejumlah responden yang ahli soal Pancasila, kebangsaan dan media massa. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai literatur yang mendukung penyelesaian penelitian ini terutama literatur-literatur yang terkait soal Pancasila, kebangsaan dan media massa.
Obyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan internal sampling yakni teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dimana sampel diambil untuk mewakili informasinya, bukan populasinya.17 Obyek penelitian ini adalah berita-berita tentang wacana revitalisasi Pancasila yang muncul di Harian Kompas selama setahun penuh yakni periode tahun 2013.
Sementara validitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengujian dependability (reliabilitas). Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat menglangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut melalui sejumlah proses ilmiah yakni penentuan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data hingga membuat
17 Sutopo, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: UNS Press), hal. 63, dalam Ibid., hal. 38.
kesimpulan.18 Untuk menguatkan validitas data, maka setiap sajian data akan dianalisis secara detail melalui analisis data. Uji analisis data akan dilakukan melalui interpretasi sahih melalui penguatan pada interteks dan intersubyektifi tas (komparasi data dari berbagai referensi dan wawancara mendalam).
Sajian dan Analisis Data
A. Analisis Model EntmanRobert N. Entman adalah salah
seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep mengenai framing ditulis dalam sebuah artikel untuk Journal of Political Communication dan tulisan lain yang mempraktikkan konsep itu dalam suatu studi kasus pemberitaan media. Entman (Sobur, 2009:163) melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas.
Kedua fakor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Dibalik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi berita.
Entman mengemukakan empat perangkat untuk melakukan analisis framing. Pertama, Problem Identifi cation yaitu bagaimana media mengidentifi kasi masalah. Kedua, Causal Interpretation, yaitu bagaimana media mengidentifi kasi penyebab masalah. Ketiga, Moral Evaluation, yaitu bagaimana media melakukan penilaian atas penyebab suatu
18 Ibid.
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 153
masalah. Dan Treatment Recommendation, yaitu bagaimana media menawarkan dan merekomendasikan suatu cara penanganan masalah dan bahkan memprediksi hasilnya. Analisis berita-berita tersebut akan didasarkan pada empat struktur besar, yaitu sebagai berikut :
1. Defi ne Problems atau Problem Identifi cation
Defi ne Problems atau Problem Identifi cation, adalah elemen yang pertama kali dilihat mengenai framing. Elemen ini merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dilihat dan dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama akan dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda pula (Eriyanto, 2008:190).
Harian Kompas memandang Pancasila sebagai suatu tatanan nilai ideal yang cocok diterapkan di Indonesia. Dalam substansinya Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan cita-cita dan karakter bangsa Indonesia karena Pancasila disarikan berdasarkan budaya dan sosial bangsa Indonesia. Dalam berjalannya waktu, nilai-nilai Pancasila mengalami benturan dengan ideologi asing yang justru melemahkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, pertama, harian Kompas berdasarkan pemberitaannya berupaya untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, munculnya hambatan dan tantangan yang mesti dihadapi dalam melestarikan Pancasila diantaranya gempuran ideologi asing, ketiga, gambaran mentalitas elit politik dan tokoh-tokoh yang menjadi
fi gur bangsa dalam bernegara, keempat, kondisi sosial, politik, bangsa Indonesia dalam penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari.
2. Diagnose Causes atau Causal interpretation
Diagnose Causes atau Causal interpretation (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor atas suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa apa (what), tetapi bisa juga siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah pun secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.
Dalam keseluruhan berita Kompas, Pancasila dipandang sebagai bagian penting bangsa Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pancasila menjadi bagian sejarah bangsa yang mesti dikenang. Maka Pancasila menjadi suatu bagian mutlak yang harus ada di Indonesia. Namun, dalam penerapannya tidak berjalan dengan mulus. Peerapan nilai-nilai Pancasila masih menjadi utopia karena masih ditemukan beberapa perilaku yang tidak cocok dengan nilai luhur Pancasila diantaranya adalah bobroknya mentalitas elit politik dalam menjalankan tugasnya. Beberapa diantara mereka menerapkan praktik korupsi, hingga mencitrakan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Selain korupsi juga masih ada, kekerasan yang berlatarbelakang agama dan keyakinan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemahaman Pancasila sebagai nilai luhur bangsa belum diterapkan dengan baik.
3. Make Moral Judgement atau Moral Evaluation
Make Moral Judgement atau Moral
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
154 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Evaluation (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefi nisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefi nisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar atau dikenal oleh khalayak.
Melihat kondisi bangsa yang pasang surut menghadapi gempuran ancaman internal dan ekternal negara, perlu ada upaya antisipasi untuk tetap menjaga eksistensi Pancasila. Harian Kompas dalam pemberitaannya menginformasikan beberapa akibat yang terjadi dari adanya ancaman terhadap Pancasila. Diantaranya munculnya keresahan dari tokoh senior dalam memandang kondisi bangsa yang terpuruk dan akhirnya melahirkan perkumpulan-perkumpulan dengan cita-cita untuk memperjuangkan Pancasila. Selain itu, penting pula adanya diskusi-diskusi yang membahas tentang Pancasila dan pematangan pemahaman lainnya dengan bertukar ide dan gagasan dalam menjaga esistensi Pancasila. Kompas memandang bahwa munculnya gerakan-gerakan tersebut disebabkan oleh keresahan dari tiap individu yang masih peduli terhadap bangsa. Mereka yang tergerak ini akhirnya berusaha untuk mengumpulkan semangat melalui aktivitas-aktivitas literasi, diskusi, sosial, dan lain sebagainya. Aksi nyata pemerintah dalam menjaga eksistensi diantaranya dengan melakukan revitalisasi situs-situs bersejarah yang menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia.
4. Treatment RecommendationTreatment Recommendation (menekan-
kan penyelesaian) adalah elemen yang dipakai untuk menilai apa yang di-kehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang
dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat bergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2008:191).
Kompas memandang perlu adanya kesadaran sosial dalam menyakini Pancasila sebagai landasan fundamental bernegara. Kesadaran sosial tersebut dapat dibentuk seiring berjalannya waktu. Meskipun banyak sekali ancaman yang dapat melemahkan Pancasila, bukan suatu hal yang mustahil bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu akan dapat terwujud. Diantaranya dalam mewujudkan implementasi kesadaran nilai-nilai berPancasila, pertama, negara memerlukan tokoh atau fi gur yang dapat menjadi contoh nyata dalam mensosialisasikan Pancasila. Dari fi gur tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mencontoh sikap dan perilaku penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara lebih mudah. Kedua, dibentuknya beberapa badan organisasi yang bergerak di bidang penyadaran nilai-nilai Pancasila juga akan memudahkan masyarakat dalam memahami Pancasila. Ketiga, mengadakan napak tilas perjalanan perjuangan pahlawan bangsa diantara adalah tokoh-tokoh yang melahirkan Pancasila, sehingga masyarakat menjadi lebih memahami nilai-nilai perjuangan dan maksud yang ada dari setiap nilai Pancasila.
Kesimpulan
Harian Kompas memandang Pancasila sebagai suatu tatanan nilai ideal yang cocok diterapkan di Indonesia. Dalam substansinya Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan cita-cita dan karakter bangsa Indonesia karena Pancasila disarikan berdasarkan budaya dan sosial bangsa Indonesia. Dalam berjalannya waktu, nilai-nilai Pancasila
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 155
mengalami benturan dengan ideologi asing yang justru melemahkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, Harian Kompas berdasarkan pemberitaannya berupaya untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, munculnya hambatan dan tantangan yang mesti dihadapi dalam melestarikan Pancasila diantaranya gempuran ideologi asing, ketiga, gambaran mentalitas elit politik dan tokoh-tokoh yang menjadi fi gur bangsa dalam bernegara, keempat, kondisi sosial, politik, bangsa Indonesia dalam penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari.
Dalam keseluruhan berita Kompas, Pancasila dipandang sebagai bagian penting bangsa Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pancasila menjadi bagian sejarah bangsa yang mesti dikenang. Maka Pancasila menjadi suatu bagian mutlak yang harus ada di Indonesia. Namun, dalam penerapannya tidak berjalan dengan mulus. Penerapan nilai-nilai Pancasila masih menjadi utopia karena masih ditemukan beberapa perilaku yang tidak cocok dengan nilai luhur Pancasila diantaranya adalah bobroknya mentalitas elit politik dalam menjalankan tugasnya.
Beberapa diantara mereka menerap-kan praktik korupsi, hingga mencitrakan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Selain korupsi juga masih ada, kekerasan yang berlatarbelakang agama dan keyakinan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemahaman Pancasila sebagai nilai luhur bangsa belum diterapkan dengan baik.
Melihat kondisi bangsa yang pasang surut menghadapi gempuran ancaman internal dan ekternal negara, perlu ada upaya antisipasi untuk tetap menjaga
eksistensi Pancasila. Harian Kompas dalam pemberitaannya menginformasikan beberapa akibat yang terjadi dari adanya ancaman terhadap Pancasila. Diantaranya munculnya keresahan dari tokoh senior dalam memandang kondisi bangsa yang terpuruk dan akhirnya melahirkan perkumpulan-perkumpulan dengan cita-cita untuk memperjuangkan Pancasila.
Selain itu, penting pula adanya diskusi-diskusi yang membahas tentang Pancasila dan pematangan pemahaman lainnya dengan bertukar ide dan gagasan dalam menjaga eksistensi Pancasila. Kompas memandang bahwa munculnya gerakan-gerakan tersebut disebabkan oleh keresahan dari tiap individu yang masih peduli terhadap bangsa. Mereka yang tergerak ini akhirnya berusaha untuk mengumpulkan semangat melalui aktivitas-aktivitas literasi, diskusi, sosial, dan lain sebagainya. Aksi nyata pemerintah dalam menjaga eksistensi diantaranya dengan melakukan revitalisasi situs-situs bersejarah yang menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia.
Kompas memandang perlu adanya kesadaran sosial dalam menyakini Pancasila sebagai landasan fundamental bernegara. Kesadaran sosial tersebut dapat dibentuk seiring berjalannya waktu. Meskipun banyak sekali ancaman yang dapat melemahkan Pancasila, bukan suatu hal yang mustahil bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu akan dapat terwujud.
Diantaranya dalam mewujudkan implementasi kesadaran nilai-nilai ber-Pancasila, pertama, negara memerlukan tokoh atau fi gur yang dapat menjadi contoh nyata dalam mensosialisasikan Pancasila. Dari fi gur tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mencontoh sikap dan perilaku penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara lebih
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
156 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
mudah. Kedua, dibentuknya beberapa badan organisasi yang bergerak di bidang penyadaran nilai-nilai Pancasila juga akan memudahkan masyarakat dalam memahami Pancasila. Ketiga, mengadakan napak tilas perjalanan perjuangan pahlawan bangsa diantara adalah tokoh-tokoh yang melahirkan Pancasila, sehingga masyarakat menjadi lebih memahami nilai-nilai perjuangan dan maksud yang ada dari setiap nilai Pancasila.
Saran
a) Bagi PenelitiDisarankan kepada para peneliti
untuk terus mengembangkan riset-riset mereka seputar tema Pancasila, empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika), media massa dan analisis framing. Pengembangan riset-riset ini sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta masukan berharga bagi negara, masyarakat serta kalangan media massa.
b) Bagi MahasiswaDisarankan bagi mahasiswa untuk
memperdalam kajian-kajian tentang Pancasila atau empat pilar berbangsa sehingga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mengingat mahasiswa sebagai bagian dari generasi emas yang bakal melanjutkan estafet perjalanan bangsa. Selain itu, disarankan mahasiswa memperdalam kajian tentang media massa serta analisis framing baik untuk kepentingan riset maupun penambahan khazanah keilmuan sehingga bisa menjadi mahasiswa yang kompeten.
c) Bagi NegaraDisarankan kepada pemangku negara
khususnya eksekutif, legislatif dan yudikatif agar lebih gencar mensosialisasikan tentang
ideologi Pancasila atau empat pilar berbangsa agar cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa dapat terwujud. Sosialisasi hendaknya menggandeng berbagai pihak terutama simpul-simpul kultural seperti kalangan pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Lebih penting lagi adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila dan empat pilar berbangsa oleh pemangku negara mengingat mereka adalah wakil-wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan.
d) Bagi MasyarakatDisarankan kepada masyarakat
agar berupaya memperdalam kembali dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Empat Pilar Kebangsaan agar tugas, pokok dan fungsi mereka sebagai warga negara dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, hendaknya masyarakat tidak terpengaruh ideologi-ideologi asing lain di luar Pancasila yang justru bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4) Bagi Kalangan Media MassaDisarankan agar kalangan media
massa termasuk Harian Kompas agar lebih intensif lagi mempublikasikan soal nilai-nilai Pancasila melalui media massa masing-masing. Hal ini agar negara tetap dalam rel kebangsaannya sesuai amanat para pendiri bangsa. Publikasi tentang Pancasila dan juga Empat Pilar Kebangsan tidak hanya soal nilai-nilainya, melainkan juga pelaksanaannya oleh negara dan masyarakat baik yang benar maupun salah agar menjadi pengingat bagi kebaikan bersama sebagai sebuah bangsa.
Daftar PustakaAndrik Purwasito, (2002), dalam Mahrus
M. Mahsun, Komodifi kasi Global, dalam “Komodifi kasi Budaya dalam Media Massa”, Surakarta: Litera.
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 157
Eriyanto, 2002, Analisis Framing. Yogyakarta: LKiS.
Frans Magnis Suseno. (2007). John Rawls, Keadilan dan Pancasila, dalam “Berebut Jiwa Bangsa Dialog, Perdamaian dan Jiwa Bangsa”, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
McQuail, (2000), dalam Widodo Muktiyo, Dinamika Media Lokal dalam Mengkonstruksi Realitas Budaya Lokal sebagai Sebuah Komoditas, Surakarta: UNS Press.
Kristiawan Hadisusanto, dalam http://dhd45jateng.wordpress.com/2012/06/25/ revitalisasi-pancasila-sebagai-jati-diri-bangsa-indonesia/, akses Maret 2014.
Midian Sirait, dalam http://socio-politica.com/2013/07/29/rev i ta l i sas i -pancasila-7/, akses Maret 2014.
Pawito, (2007), Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: LKiS).
Sri Herwindya Baskara Wijaya, (2012). Pendidikan Karakter Bangsa dalam Novel (Studi tentang Pesan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa Menggunakan Pendekatan Semiologi Komunikasi dalam Novel Nonfi ksi “Habibie dan Ainun” karya B.J. Habibie dan “Belahan Jiwa” karya Rosihan Anwar ). Surakarta: Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS.
_____. (2013). Media Massa dan Intoleransi Beragama (Studi Kasus tentang Wacana Intoleransi Beragama pada Surat Kabar lokal di Kota Surakarta Tahun 2012). Surakarta: Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS.
Sutopo. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Triwardana Mokoagow, dalam h t t p : / / f i l s a f a t . k o m p a s i a n a .com/2013/12/18/ revitalisasi-pancasila 617631.html, akses Maret 2014.
http://lutviah.net/2011/01/14/media-massa-surat-kabar/, diakses Maret 2014.
h t t p : / / s e j a r a h . k o m p a s i a n a .com/2011/01/04/surat-kabar-di-indonesia/, diakses Maret 2014.
Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
Sri Herwindya Baskara Wijaya, dkk. Wacana Revitalisasi Pancasila ...
158 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 159
Media Massa dan Isu Radikalisme Islam
Leni WinarniProgram Studi Ilmu Hubungan Intenasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sebelas Maret Surakarta
AbstractIslam radicalism no longer became international issues after black September 2001. This tragedy has evoked a misperception about Islam; meanwhile it forces a new wave of hate crime in USA and the West countries. This paper is objective to argue about the mass media as an effective propaganda by radical movements, and also analyzing how the mass media’s effectiveness as a one of main player to counterterrorism and prevent radicalism spread and other violence that happen in the last several decades. Media should have a social responsibility to prevent radicalism or terrorism and give the proportion information about the Moslem’s world. Key words: mass media, internet, Islam radicalism, propaganda.
Pendahuluan
Ketika Perang Dunia I berkecamuk, lalu berturut-turut Perang Dunia II hingga Perang Dingin, media massa ikut sibuk dalam hiruk pikuk peperangan. Tak terkadang para jurnalis harus terjun langsung ke medan pertempuran. Kini Perang Dunia telah usai, Perang Dingin pun telah berlalu saat Kremlin tidak lagi menjadi pusat kekuasaan Uni Soviet, yang kemudian tergantikan dengan satu kekuatan dunia, Amerika Serikat dengan kapitalisme sebagai simbolnya dan peperangan dalam skala kecil “intra-state” di lima benua. Namun gaung media massa mengendap dalam historis kemenangan, kekalahan, dan kekejaman peperangan global. Sejarah mendeskripsikan bahwa media massa memiliki kekuatan dan memberikan pengaruh persuasif yang
masif pada publik sebab meskipun masih bersifat anekdot, media massa terbukti berpengaruh telah melakukan brainwash selama Perang Dunia berlangsung dan menjadi mesin efektif bagi penyebaran ideologi fasisme di Eropa selama masa perang (Curran, Gurevitch, 2005). Sehingga tidak mengherankan jika media massa disebut-sebut ikut andil dalam menyebarkan paham atau ideologi yang berpengaruh signifi kan terhadap konstruksi dunia di masa itu.
Makalah ini hendak mendiskusikan bagaimana peranan media massa dalam mengkounter fenomena radikalisme yang mengatasnamakan agama, yang kembali marak belakangan ini dengan kemunculan ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah), yang dengan cepat menjadi perbincangan dunia setelah al-Qaeda, khususnya di
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 159-166
Leni Winarni, Media Massa dan Isu...
160 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Indonesia. Bagaimana pula efektifi tas peranan media massa dalam memberikan penjelasan publik mengenai hal ini? Selain itu paper ini juga akan memperdebatkan mengapa gerakan radikal menggunakan media massa, terutama internet, bukankah mereka adalah gerakan anti modernisasi ataukah sebaliknya, merupakan produk dari modernisasi itu sendiri? Dengan menggunakan kajian teoritis dalam perspektif ilmu-ilmu politik dan sosial, radikalisme menjadi bagian dari dinamika sosial itu sendiri sebagai aksi dan reaksi dari anti kemapanan, anti globalisasi, dan simbol kekuatan baru yang anti Barat.
Radikalisme dan Fenomena Sosial
Jika menelisik lebih jauh, sebenarnya apa yang mendasari radikalisme Islam agaknya memerlukan kajian tersendiri. Sebab konteks radikal atau militan tidak selalu berkaitan dengan kekerasan. Radikalisme merupakan konteks pemikiran yang menginginkan adanya pemurnian ajaran Islam secara total. Bisa jadi pemikiran ini sebagai akibat dan reaksi dari semakin derasnya arus kapitalisme yang diusung oleh Barat sehingga memarginalkan orang-orang Islam sendiri terhadap ajaran Islam. Karena tidak selamanya pemikiran radikalisme diwujudkan dalam kekerasan. Hanya saja fakta bermunculannya gerakan-gerakan radikal yang mengarah pada tindakan kekerasan justru menjadi pemberitaan yang di blowup secara masif sehingga berimbas pada pelabelan bahwa gerakan radikal pastilah teroris. Namun untuk memudahkan penulisan dalam paper ini, penulis tetap menggunakan istilah radikalisme dalam artian yang negatif. Meskipun bukan lah hal baru dalam ranah historis, radikalisme kembali mengemuka paska runtuhnya gedung kembar WTC (World Trade Center) di New York pada tahun 2001 lalu,
dan isu radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama, khususnya Islam. Padahal, radikalisme telah lahir berabad-abad lampau, radikalisme bahkan muncul dalam agama lain seperti Kristen dan Yahudi (Simut, 2010).
Meskipun masih dalam perdebatan dan penelitian yang komprehensif baik dari perspektif teologi dan sejarah, tiga agama samawi ini masing-masing memiliki doktrin mengenai konteks perjuangan yang sering diasumsikan secara negatif dan memunculkan tindakan atau sikap radikal. Konteks yang demikian sangat tergantung dengan tingkat pemahaman dan penafsiran serta kemampuan mengartikan ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing individu akan perang suci. S e h i n g g a dibutuhkan pemahaman dari para ahli tafsir dan agama dalam menerjemahkan ayat-ayat dalam kitab suci. Seringkali gerakan-gerakan radikal dikaitkan dengan fenomena gerakan sosial, padahal gerakan sosial dan radikalisme agama adalah konteks yang berbeda. Pada abad ke-19, gerakan sosial disinonimkan dengan perubahan sosial yang didasarkan pada perubahan material dan relasi sosial mayoritas masyarakat (Calhoun, 2012).
Ia juga mengatakan bahwa gerakan sosial menekankan aksi kolektif sebagai reaksi atas dibatasinya ruang gerak sosial publik akibat kekuasaan oligarki para elit pemerintah yang mengontrol negara secara sentralistik yang kemudian berimbas pada berevolusinya gerakan sosial menjadi gerakan sosialis atau jika gerakan sosialis terdengar begitu sektarian, gerakan sosial ini terasosiasi dalam perkumpulan dewan buruh atau mobilisasi demokrasi. Dominasi mengenai arti gerakan sosial tersebut kemudian memberikan banyak penilaian yang sama terhadap gerakan-gerakan yang lain, seperti agama, politik, regional, nasional, anti perbudakan, anti kemapanan-dimana juga ikut berkontribusi terhadap gerakan
Leni Winarni, Media Massa dan Isu...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 161
sosial dan perubahan sosial (Calhoun, 2012). Apakah radikalisme Islam merupakan
bagian dari gerakan sosial ? Hal itu masih mengundang sejumlah analisis dan kajian empriris, namun beberapa fakta aktivitas muslim radikal menunjukkan kecenderungan tersebut.
Aktivitas Islam dapat diperspektifkan sebagai aksi kolektif atau tindakan bersama sehingga hal ini bisa diartikan sebagai gerakan sosial. Teori ini memperdebatkan bahwa kesuksesan rekruitmen anggota gerakan sosial dikarenakan adanya proses selektif yang ketat serta social network dan hubungan sosial yang kuat (Wiktorowicz, 2004).
Selanjutnya masih dalam Wiktorowicz (2004), memaparkan bahwa rekruitmen anggota gerakan sosial, khusus nya tertariknya kalangan akademik yang rasional ke dalam aktivitas tersebut, dikarenakan gerakan sosial memiliki kemampuan untuk membingkai aktivitas mereka sebagai kewajiban moral, terutama pada aktivitas yang beresiko tinggi. Kewajiban moral inilah yang sebenarnya membuat mereka berani mengambil resiko, termasuk kalangan akademik, untuk ikut andil dalam aktivisme radikal dan menyakini ideologi tersebut dengan mempraktekannya sebagai tugas yang mulia. Walaupun para aktivis radikal mengungkapkan bahwa tindakan mereka adalah berjihad dan bertujuan demi kebaikan, namun cara-cara yang mereka lakukan tentu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan itu sendiri.
Mengapa Mereka Menggunakan Media Massa?
Jika di era 90-an, penyebaran ideologi radikal masih dapat dikontrol oleh pemerintah, namun di era digital saat ini, sangat sulit untuk menekan penyebaran masif radikalisme melalui internet.
Terlebih lagi di era itu banyak negara masih dikuasai oleh rejim otoriter dan memang teknologi internet belumlah berkembang pesat seperti saat ini, sehingga media massa seperti media cetak dan televisi, justru menjadi alat propaganda efektif bagi penguasa dan pemberitaan masih dikendalikan oleh pemerintah.
Di Indonesia, bahkan hampir semua media di masa Soeharto tidak luput dari sensor pemerintah. Di satu sisi media massa tidak bersifat independen, netral dan obyektif dalam mengungkap fakta di lapangan, namun disisi lain minimnya berita-berita negatif di media membuat kondisi keamanan lebih stabil. Meskipun setelah era Soeharto berakhir, permasalahan negeri ini tiba-tiba mencuat begitu banyak dan menghasilkan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah era reformasi hingga saat ini. Namun, bergantinya jaman, juga memberikan perubahan yang sangat signifi kan pada teknologi informasi, terutama internet di akhir satu dekade ini.
Setiap orang bahkan dapat menjadi ahli propaganda libertan hanya dengan membuat blog pribadi dengan identitas palsu. Begitu mudahnya internet dan akses yang murah bahkan terkadang tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun, maka internet menjadi alternatif pilihan yang paling efektif dalam melakukan propaganda radikal. Pemanfaatan media internet di abad ini bahkan mampu melampau media massa lainnya dalam hal kecepatan penyampaian berita pada publik. Sayangnya internet juga digunakan oleh gerakan-gerakan radikal untuk mempengaruhi massa, terutama para pemuda yang relatif masih labil emosinya sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi. Gerakan-gerakan radikal ini dapat dengan mudah memainkan rasa keingintahuan atau ketidaktahuan
Leni Winarni, Media Massa dan Isu...
162 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
mereka akan pemahaman dan wawasan mengenai ideologi-ideologi radikal untuk menjadi bagian dari aktivitas gerakan mereka.
Coleman dan McCahill (2010) dalam Jewkes (2011) mengatakan bahwa gerakan Muslim radikal mengklaim bahwa lebih dari setengah pemuda Saudi yang menjadi anggota mereka direkrut melalui internet. Ia juga mengemukakan bahwa hal serupa juga terjadi dalam sistem perekrutan beberapa kelompok berhaluan kiri di Eropa, seperti neo-Nazis, skinheads dan kelompok yang terafi liasi dengan Ku Klux Klan-yang menargetkan pemuda sebagai sasaran propaganda melalui internet dengan mengesankan rasis, anti-semit dan propaganda homophobia tanpa mengkhawatirkan bahwa publikasi mereka akan mendapatkan sanksi hukum.
Tambahnya pula, meskipun negara seperti Jerman dan negara-negara Eropa lainnya telah mengkriminalkan pelaku publikasi dan penyebar hate propaganda, namun tidak mudah memberlakukan undang-undang pelanggaran penggunaan internet, sehingga para aparat penegak hukum tidak dapat berbuat banyak meskipun telah ada pelaporan mengenai tindakan kriminal yang spesifi k melalui internet. Hal yang sama pun terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Media massa dinilai sebagai alat propaganda yang efektif, sebab secara tepat propaganda dapat mencapai sasaran yang dituju secara sistemastis, prosedural, dan disertai dengan perencanaan yang matang (Nurudin, 2001).
Propaganda memang tidak selalu diasumsikan negatif, ia adalah ibarat dua sisi mata uang, bisa saja bermakna negatif atau positif, sangat tergantung pada peran pihak-pihak yang melakukan propaganda. Demikian pula dengan media massa, sebagai bagian yang hampir tak
terpisahkan dari propaganda itu sendiri. Media massa dapat saja menjadi alat propaganda penyebar paham menyesatkan dan sebaliknya dapat pula menjadi alat propaganda positif guna melawan usaha-usaha propaganda bersifat negatif.
Penggunaan media massa oleh gerakan-gerakan radikal sebenarnya memang bukanlah fenomena baru, namun peristiwa 11 september 2001 lalu memunculkan kembali isu radikalisme atau terrorism based on religion dan gaungnya masih menjadi isu kontroversial dan sentral dalam bidang keamanan dunia. Kontroversi al-Qaeda dan gerakan-gerakan Islam radikal lainnya yang menyuarakan simbol-simbol Islam yang mereka bawa secara langsung berdampak pada kaum muslim global dan mempengaruhi peta konfl ik dunia.
Bahkan belakangan ini isu-isu radikalisme Islam kembali mencuat dengan lahirnya ISIS yang dengan cepat mendunia dan menjadi topik global paska mereka meng-upload video sadis pembunuhan wartawan AS di you tube. Pesan kengerian tersampaikan dengan cepat dan sekaligus menunjukkan eksistensi gerakan mereka. ISIS, sama halnya dengan gerakan-gerakan yang dinilai ekstrim dan terror lainnya, ikut menggunakan media massa untuk menarik minat para anggota mereka yang tidak hanya datang dari sekitar Irak dan Suriah saja, tapi berhasil menarik simpati dunia. Di Indonesia, gerakan ini telah ditetapkan sebagai gerakan terlarang oleh pemerintah, para ulama, bahkan masyarakat sendiri melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya ISIS.
Media massa terutama internet memang memberikan peluang lebih besar untuk seseorang berkreatifi tas, mendapatkan informasi dari banyak hal, serta mengaktualisasikan diri mereka, namun tidak terkadang pula media internet
Leni Winarni, Media Massa dan Isu...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 163
justru memberikan informasi yang salah dan diyakini sebagai kebenaran sebab kurangnya pengetahuan dan wawasan pengguna internet. Apapun jamannya, efektifi tas propaganda media massa bahkan telah teruji melalui kajian historis, misalnya seperti di massa Perang Dunia II.
Peranan Media Massa dalam Meng-kounter Radikalisme
Secara teoritis, media massa haruslah memiliki tanggung jawab sosial, yaitu memberikan penerangan kepada publik sehingga dapat memperoleh informasi yang tepat dan dapat mengambil keputusan terbaik demi kepentingan publik atau masyarakat luas (Budiharso, 2003). Pelurusan informasi kebenaran oleh media massa menjadi tuntutan publik yang kritis dalam menyikapi perubahan dinamis dunia dalam berbagai aspek. Terlebih lagi di era abad ini, media massa bukanlah sesuatu yang tercetak saja di atas kertas, tapi ia melewati batas ruang dan waktu, sebab internet telah menciptakan komunitas global yang menyatukan dunia, menghilangkan batas-batas imajiner. Peristiwa yang terjadi di belahan bumi timur dapat dengan segera diketahui oleh masyarakat yang tinggal di belahan bumi barat dan sebaliknya. Dengan cepat, informasi tersebar luas dan menjangkau seluruh dunia.
Ketika seluruh dunia dikejutkan dengan peristiwa black September, yang tidak lama kemudian diakui oleh Osama bin Laden dan organisasinya al-Qaeda bahwa mereka adalah dalang peristiwa tersebut dan diberitakan secara bombastis oleh media internasional maupun lokal, sebenarnya mereka sangat menikmati hal tersebut sebagai propaganda cuma-cuma (Nacos, 2007).
Dalam bukunya yang berjudul “Mass-Mediated Terrorism, The Central Role of The Media in Terrorism and Counterterrorism”,
Nacos (2007), mengatakan bahwa selama satu dekade ini jaringan televisi global melakukan pemberitaan mengenai terorisme internasional, yang di sisi lain justru dinikmati pula oleh kelompok-kelompok teroris sebagai bentuk pengakuan dunia internasional akan eksistensi mereka dan kesempatan untuk menyebarkan propaganda ke seluruh dunia. Jaringan satelit Arab al-Jazeera khususnya menjadi salah satu pemeran internasional dalam media massa setelah liputan mereka mengenai Afghanistan dan keterlibatan AS dan koalisinya ketika mendesak Taliban dan al-Qaeda untuk keluar dari negara itu. Beberapa media televisi dari Timur Tengah seperti al-Arabiya dan the Lebanese Hizbollah’s al-Manar, menjadi sangat fenomenal paska kebangkitan radikalisme Islam dan dengan sangat cepat meroket menjadi salah satu stasiun televisi lokal yang diperhitungkan secara global.
Paska peristiwa 11 September 2001, saat runtuhnya gedung World Trade Center, terorisme memunculkan ketakutan, fanatisme, isu radikalisme, Islam phobia, hingga upaya-upaya memperkenalkan Islam yang lebih moderat melalui media massa. Walaupun banyak juga pemberitaan dimasa itu yang justru menyudutkan ummat Islam dan memunculkan fenomena hate-crime atau kejahatan berdasarkan kebencian. Fenomena tersebut meningkat terutama di Amerika Serikat yang memposisikan diri mereka terhadap korban dari terorisme dan di sisi lain juga menampilkan negara adi daya tersebut sebagai promotor utama dalam menentang radikalisme dan terorisme internasional.
Hal yang mencengangkan dunia paska black September, adalah peristiwa bom Bali pada tahun 2002. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar
Leni Winarni, Media Massa dan Isu...
164 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
di dunia menjadi sorotan internasional, lalu alih-alih mendapatkan label sebagai negara sarang teroris. Indonesia yang dikenal sebagai Islam moderat kemudian menarik perhatian dunia dengan peristiwa bom bunuh diri yang menggemparkan itu. Pada akhirnya kemudian tidak hanya meramaikan perbincangan seputar terorisme global, namun juga mendorong dan menuntut media massa lokal untuk dapat memberikan informasi ke publik mengenai isu-isu perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Peranan media massa, cetak dan elektronik (televisi dan radio), khususnya di Indonesia, dalam mengkonter gerakan-gerakan radikal yang merugikan ummat Muslim sangat diperlukan. Publik berhak mendapatkan informasi yang tidak hanya memberitakan sisi-sisi negatif, tapi diharapkan mampu memberikan kesejukan terhadap masyarakat dengan memberikan berita-berita yang positif seputar Islam sebab sebuah agama diturunkan ke muka bumi tentunya untuk keselamatan ummat manusia sendiri dan bukan agama pedang. Media massa pada akhirnya dituntut lebih proaktif dan obyektif dalam melakukan pemberitaan, sehingga tidak lagi menjadi alat propaganda.
Namun, tantangan terberat dalam pemberitaan media massa datang dari media internet. Sebab tidak semua pemberitaan di internet dimiliki oleh perusahaan-perusahaan surat kabar yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi hukum apabila melanggar kode etik jurnalistik, informasi datang bahkan dari media antah-berantah yang tidak jelas rekam jejak dan kepemilikannya. Untuk menangkal radikalisme baik itu datang dari agama, politik, ideologi radikal lainnya yang memicu ketidakstabilan keamanan, tidak hanya menjadi tugas media massa semata,
namun menjadi tanggung jawab sosial bersama. Jika mengibaratkan internet adalah sebuah pasar yang menjual apapun, maka seorang pembeli yang cerdas tentu mampu memilah-milah barang dagangan mana yang bagus, bermutu atau tidak. Dan keberhasilan media massa bukan dari informasi yang mereka sampaikan saja, tapi juga bagaimana kelanjutan paska mereka memberikan informasi tersebut ke publik, sudahkah informasi tersebut efektif dalam mengkounter ide-ide radikal atau terorisme atau tidak?
Kesimpulan
Radikalisme abad ini menarik agama, khususnya Islam dalam situasi dan kondisi yang tak terelakkan dan memunculkan konektivitas antara Islam dan kekerasan, sehingga merugikan dunia Islam padahal ia adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kelahiran Islam ribuan abad silam bahkan tidak diwarnai dengan pedang, melainkan Islam membawa pesan-pesan perdamaian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Disatu sisi juga melabelkan bahwa radikalisme sebagai pemahaman yang sangat negatif.
Ada dua hal utama yang dapat disimpulkan dalam paper ini, pertama, bahwa media internet mengambil porsi dan peranan yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada publik, terutama kaum muda akan ideologi radikal. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa perekrutan kaum muda dalam organisasi-organisasi radikal banyak dilakukan dengan menggunakan media internet. Fakta bahwa organisasi teroris dan yang terafi liasi dengannya telah memanfaatkan teknologi yang dapat memudahkan mereka menyebarkan propaganda dan merekrut anggota potensialnya melalui internet adalah hal yang sangat miris dari kemajuan media massa itu sendiri.
Leni Winarni, Media Massa dan Isu...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 165
Kedua, media massa memegang peran kunci dalam menangkal dan memberi-kan informasi ke publik terhadap isu-isu radikalisme sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan ber-kembang nya gerakan-gerakan ekstrimis dimulai dari lingkungannya sendiri. Meskipun pada dasarnya, Indonesia adalah negara Islam moderat dan radikalisme sulit berkembang di negeri ini, namun bukan berarti Indonesia tidak luput sebagai target bagi mereka, terutama generasi muda. Apapun itu, media massa memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap publik, meskipun disisi lain pemberitaan-pemberitaan itu memang menguntungkan gerakan-gerakan tersebut sebagai bentuk dari propaganda cuma-cuma, namun ia juga memunculkan gerakan massa dari masyarakat sendiri untuk aktif berperan serta menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum tanpa hanya bergantung pada pemerintah.
Daftar PustakaBudiharso, Suyuti S. (2003). Politik
Komunikasi. Grasindo.
Calhoun, Craig. (2012). The Roots of Radicalism: Tradition, the Public Sphere and Early Nineteenth-Century Social Movements. University of Chigago Press
Crelinsten, Ronald. (2009). Counterterrorism. Polity
Gurevitch, Michael & Curran, James. (Eds.). (2005). Mass Media and Soceity. USA: Bloomsbury.
Hoffman, Bruce. (2006). Inside Terrorism. University of Columbia Press.
Jewkes, Yvonne. (2011). Media & Crime (2th ed.). Sage Publication Ltd.
Koentjoro & Rubianto, Beben. (2009). Radikalisme Islam dan Perilaku Orang
Kalah dalam Perspektif Psikologi Sosial. Psikobuana, 1(1). 64-70
Nacos, Brigitte L. (2007) Mass-Mediated Terrorism, The Central Role of The Media in Terrorism and Counterterrorism. Rowman & Littlefi eld Publisher, Inc.
Miles, M.B & Hubermen, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. London: Sage Publications, in Punch. (2005). Introduction to Social Research, Quantitative, and Qualitative Approaches. Sage Publication Ltd.
Simut, Corneliu C. (2010). Traditionalism and Radicalism in the History of Christian Thought. Palgrave Macmillan.
Timmerman, Christian. (Ed.) (2009). Faith-based Radicalism: Christianity, Islam, and Judaism Between Constructive Activism and Destructive Fanaticism. Peter Lang International Academic Publisher, 2009
Wiktorowicz, Quintan. (Ed.). (2003). Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach (Indiana Series in Middle East Studies). USA: Indiana University Press.
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 167
Media Komunitas, Kredibilitas dan Relasi Sosial: Framing Komunikator dalam Citizen Journalism
Mahfud AnshoriProgram Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
AbstractCitizen Journalism is new phenomenon in Production-Consumption of News. Infl uenced by internet technology, Citizen Journalism widely spreads in in all country as counterpart to Conventional Journalism. It also raised new issues in mass communication approach, particularly in social relation and credibility issues.This study examined the articles are written in kompasiana, Citizen Journalism site maintained by Kompas.com ranging from July to September 2014. Using a purposive sampling technique, this research obtained seven articles that deserve to be studied according to researchers in accordance with the formulation of the problem to be addressed. This study used the constructionist approach as framing analysis method introduced by Van Dijk.The research concluded that the ideological structures in the realm of consciousness of each author beyond the written text and superstructure and social cognition is more infl uenced than any principles in conventional journalism such as credibility, honesty and impartiality.
Keywords: Citizen Journalism, Framing, Kompasiana, Credibility and Social Relations.
Pendahuluan
Pemanfaatan media komunitas bagi khalayak adalah sebuah fenomena baru di tengah perkembangan new media yang difasilitasi oleh internet. Facebook, Youtube, Twitter, Tumblr dan lain sebagainya adalah media sosial yang acap kali dipilih oleh sebagian banyak orang untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Media online yang dianggap sebagai bentuk media baru (new media) yang sarat teknologi dan mengalami perkembangan luar biasa ternyata juga memiliki masalah
yang hampir sama, yakni masalah kualitas, kredibilitas serta krisis keuangan. Pada sisi kualitas dan kredibilitas, tradisi jurnalistik di media online dikritik tidak mempunyai basis praksis yang kuat, sehingga kredibilitas dan kualitas lembaga informasi siber acap kali masih dipandang sebelah mata. Bagi lembaga yang sudah mendapat tempat di publik, permasalahan datang dari mekanisme organisasi dan sifat adaptif yang sulit dirumuskan secara holistik.
Perubahan perilaku konsumen juga berasal dari kencenderungan untuk
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 167-176
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
168 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
mencari berita diluar mainstream dari media besar, dimana mereka lebih tertarik pada ‘berita-berita kecil dan remeh-temeh’ dalam konteks jurnalistik konvensioal dibandingkan dengan berita-berita politik, keuangan, atau berita-berita internasional lainnya. Seperti kasus terakhir dimana menjadi trending informasi yang cukup kuat dari seseorang yang memutilasi seekor binatang di dunia maya, namun tidak banyak berita-berita terkait di media massa konvensional.
Disisi lain, fenomena jurnalistik warga (citizen journalism) memungkinkan audien menjadi produser. Khalayak dapat mempublikasikan informasi, opini dan data dengan mudah melalui weblog atau website mereka sendiri. Fenomena media komunitas juga mengalihkan ruang publik pada praktik ruang publik maya, seseorang dapat menyebarkan beragam informasi, mengkonsolidasi jaringan sosial dan membentuk kelompok-kelompok sosial lintas batas.
Pembaca sebagai komunikator, hal ini merupakan ciri dari keberadaan media komunitas di era internet. Sebagai komunikator, permasalahan yang pertama dihadapi oleh para pembaca ini adalah meraih kredibilitas dan membangun relasi sosial.
Penelitian ini berusaha untuk mengkaji bagaimana cara komunikator-komunikator dalam media komunitas membingkai tulisannya guna meraih kredibilitas dan membangun relasi sosial diantara pembaca dan penulis lainnya.
Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah kajian model pembingkaian informasi dari para penulis non profesional di media komunitas di situs jejaring kompasiana. Kajian ini diharapkan mampu memberikan khazanah pengembangan keilmuan di bidang komunikasi terutama yang terkait
dengan kajian tentang fenomena new media di Indonesia.
Tinjauan Pustaka
Kajian tentang kredibilitas media komunitas online lebih sulit dilaksanakan dibanding dengan media sosial/komunitas konvensional oleh karena kemampuan “melekatkan” berbagai sumber dan keberagaman lapisan dalam menyebarluaskan isi (Sundar, 2008). Satu isi blog dapat dirujuk berberbagi sumber, dan kemampuan hyperlink media online adalah salah satu contoh tingkat kesulitan dalam mengkaji kredibilitas media online.
Dalam kajian komunikasi, kredibilitas dapat dilihat dalam tiga prespektif yakni kredibilitas media, kredibilitas isi/pesan dan kredibilitas sumber/komunikatornya. Kredibilitas media dapat dilihat dari bagaimana pengguna menggunakan berbagai ragam media mulai dari radio, koran, televisi, internet dan lain sebagainya, sementara kredibilitas pesan/isi adalah terkait dengan kualitas isi media, akurasi dan update dari informasi yang ditulis tersebut. (Metzger, 2003).
Banning and Sweetser (2007) menggunakan alat ukur umum untuk melihat unsur kredibilitas dari sebuah blog berupa: unsur faktualitas yang tersaji, terkait dengan profi t oriented; menghargai privasi orang lain, menekankan pada kebutuhan komunitas dan dapat dipercaya. Sementara itu pada tahun 2009, Johnson and Kaye (2009) juga menggunakan alat ukur kredibilitas media tradisional untuk mengkaji blog berupa tingkat kepercayaan, kejujuran akurasi dan kedalaman. Sementara Thorson dkk (2010) mengkaji kredibilitas media blog dapat dilihat pada tingkat kejujuran/ketidakjujuran, bias/tidak bias, akurat/tidak akurat dan penyampian fakta sesungguhnya/ tidak menyampaikan fakta sesungguhnya,
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 169
keseimbangan/ketidakseimbangan dan dapat dipercaya/tidak dipercaya.
Terkait dengan kredibilitas sumber terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yang and Lim (2009) yang memberikan impresi bahwa pengguna individu cenderung percaya pada organisasi ketika mereka memperoleh level yang lebih besar dari interaktivitas dalam media sosial. Kredibitas media sosial menjadi kritis ketika berhadapan dengan bentuk interaktivitas media. Interaktivitas sangat kuat berasosisasi dengan kredibilitas. Yang menjadi temuan penelitian tersebut adalah tidak terdapat signifi kasi yang kuat antara kredibilitas penulis blog dengan pengguna.
Mahfud Anshori dkk (2010) juga menemukan kesimpulan bahwa, interaktivitas dalam fi tur berita online mendorong pengguna untuk lebih banyak memilih membaca artikel dalam berita tersebut, dibanding dengan berita di portal yang tanpa disertai dengan fi tur interaktivitas.
Minjeong Kang (Kang, 2010) dalam artikel ilmiah berjudul Measuring Social Media Credibility: A Study on a Measure of Blog Credibility melakukan kajian terkait dengan kredibilitas media sosial dengan membatasi kajian pada kredibiltas pada isi dan penulis blog. Hasil kajian tersebut menghasilkan dan menvalidasi 14 alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kredibilitas blog dengan menggunakan metode FGD dan survey. FGD digunakan untuk mencari kriteria kredibilitas yang diinginkan dengan melibatkan 5 kelompok FGD yang terdiri dari 7 sampai dengan 10 partisipan. Selanjutnya penelitian tersebut menggunakan uji statistik untuk mencari kriteria model yang bagus untuk mengukur alat uji tentang reliabilitas blog dalam dua dimensi yakni kredibilitas isi blog dan kredibilitas penulis blog (blogger).
Desain dan Metode
Penelitian ini menggunakan pen-dekatan Framing yang sebagaimana yang dipopulerkan oleh Van Dijk. Van Dijk (1991: 108) menyatakan seperti halnya dalam proses berargumentasi atau menyusun topik pembicaraan, berita juga mengikuti skema yang berbentuk hirearkis yang terdiri dari beberapa komponen seperti a). Summary yang terdiri dari headline dan lead, b). Background yang terdiri dari Main Events, Context dan History, c). Verbal Reactions serta d). Comment (Dijk, 1991, hal. 115). Wartawan menggunakan komponen-komponen frame tersebut untuk menyusun sebuah berita. Skema berita tidak saja berhubungan dengan skema naratif (cara berkisah) yang umum tetapi juga berhubungan dengan rutinitas produksi berita yang ditujukan oleh cara dari kategori-kategori tersebut muncul dalam skema berita.
Sementara untuk artikel non jurnalistik seperti editorial atau opini, Van Dijk menyarankan pendekatan yang sedikit berbeda. Oleh karena sifat artikel editorial atau opini bersifat informal dan merupakan buah karya pemikiran yang tidak memiliki skema yang tetap maka menganalisis framing dua jenis artikel tersebut menggunakan pendekatan skema berita akan menjadi sulit. Van Dijk ( 1989) menyarankan suatu metode analisis yang lebih ekletis, dimana artikel dibedah berdasarkan beberapa kaidah kategori yakni : a) Defi ning Situation b) Explanation, c) Moral d) The actors dan e). The ideological value structure.
Defi ning Situation; dalam rangka mem berikan gambaran tetang pokok per-masalahan, penulis artikel opini/editorial pada awalnya akan membuat ringkasan atas pokok permasalahan yang hendak dibahas. Meski demikian, dalam konteks menjelaskan dan mengevaluasi pokok permasalahan tersebut, penulis biasanya
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
170 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
meringkas dan mengihtisarkan peristiwa, memilih dimensi-dimensi yang relevan dan fokus pada peristiwa atau aktor tertentu. Peringkasan, pemilihan dan fokus dimensi-dimensi tertentu ini mencerminkan kerangka idiologis dari sang penulis.
Explanation; penjelasan atas peristiwa/topik yang dibahas. Cara penulis artikel menjelaskan peristiwa/topik yang dibahas, sudut pandang dan pemilihan-pemilihan fakta tertentu merupakan latar idologi penulis.
Moral; saran atau prediksi dari berbagai defi nisi situasi dan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini menunjukan keberpihakan dan cara pandang mendepan dari sang penulis artikel.
The actors; pemilihan pelaku-pelaku dan peristiwa-peristiwa dalam artikel yang tulis merupakan seleksi yang dilakukan oleh penulis opini/editorial. Guna memahami susunan argumentasi dari editoral/penulis artikel, siapa yang pro atau yang kontra serta latar idiologi yang ada dibelakang media, peneliti perlu untuk memahami para pelaku yang dibahas dalam artikel tersebut.
The ideological value structure. Penyusunan sebuah artikel opini/editorial merefl eksikan cara pandang penulis artikel/editorial atau yang lebih fundamental mencerminkan stuktur idiologis, nilai dan norma yang dimiliki oleh penulis artikel/editorial atau media tersebut.
Penelitian ini meneliti artikel-artikel yang ditulis di kompasiana, situs Citizen Journalism yang dikelola oleh Kompas.com mulai dari bulan Juli sampai dengan September 2014. Menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh tujuh artikel yang menurut peneliti layak untuk diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dijawab.
Hasil
1) Yusril Ihza Mahendra vs Mawalu: Konstruksi dan Framing Penulis
Terdapat dua artikel yang terkait dengan kajian konstuksi dan Framing dari Penulis. Artikel pertama adalah artikel dengan judul “OMG! Diam-diam Ternyata Jokowi Minta Tolong Yusril Jadi Pengacaranya Gugat Hasil Pilpres 2014 di MK, Tapi ditolak Yusril Mentah-mentah” (Mawalu, 2014). Dalam artikelnya tersebut, Mawalu mengulas tentang bagaimana Yusril Ihza Mahendara menolak tawaran dari Tim Sukses Jokowi JK guna menjadi penasehat hukum, jikalau hasil Pilpres 2014 harus diselesaikan di tingkat Mahkamah Konstitusi.
Mawalu sendiri adalah seorang penulis di Kompasiana yang cukup aktif menulis dan mengulas tetang Pilpres 2014 dengan sudut pandang sebagai seorang pendukung Prabowo. Meski demikian, sang penulis menuturkan dalam artikelnya bahwa sebelum mendukung Prabowo menjadi Calon Presiden Pada pemilu 2014, ia adalah seorang pendukung Jokowi. (Mawalu, 2014).
Mengutip kicauan twitter dari Yusril Ihza Mahendra di @yusrilihza_Mhd, Mawalu menyusun argumentasi tentang tanda-tanda kekalahan Jokowi-JK pasca Pilpres 2014. Artikel tanggal 12 Juli 2014 dibuka dengan kutipan screen-shoot dari twitter Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan tidak memihak kepada salah satu dari kubu Capres 2014. Sikap ini diapresiasi oleh penulis artikel sebagai suatu sikap yang baik dan mencerminkan ke-negarawan-an.
Merasa bahwa pernyataannya perlu diklarifi kasi lebih lanjut, supaya tidak disalahartikan, Yusril Ihza Mahendra merasa perlu menulis artikel klarifi kasi yang berjudul “Pemihakan Saya Hanya kepada Bangsa dan Negara” (Mahendra, 2014).
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 171
a) Defi ning Situation Artikel “OMG! Diam-diam Ternyata
Jokowi Minta Tolong Yusril Jadi Pengacaranya Gugat Hasil Pilpres 2014 di MK, Tapi ditolak Yusril Mentah-mentah” yang ditulis oleh Mawalu dilatarbelakangi oleh kicauan seorang tokoh nasional di bidang hukum dan mantan menteri, Yusril Ihza Mahendra yang menolak untuk menjadi konsultan hukum jikalau ada sengketa hasil Pilpres 2014 dari pihak Jokowi JK.
Mawalu mendefi nisikan suatu situasi dari looser psycology yang melanda tim Jokowi JK, dimana sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan, tim tersebut telah berupaya mencari bantuan hukum. Hal ini didefi nsikan oleh Mawalu sebagai suatu kekalahan kubu Jokowi JK, dengan menyatakan bahwa Yusril menolak mentah-mentah permohonan mereka.
Situasi ini sebenarnya dipicu oleh karena perbedaan penghitungan Quick Count dari berbagai lembaga survey pasca pencoblosan Pilpres 2014, dimana ada lembaga survey yang memenangkan pihak Prabowo Hatta dan sebagian yain memenangkan Jokowi JK. Perbedaan penghitungan Quick Count ini yang menyebabkan euforia pemenang Pilpres 2014 menjadi tertunda.
Rupanya indikasi aura kekalahan perolehan suara Jokowi pada pilpres 2014 ini sudah disadari oleh Jokowi sejak dini. Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa lembaga-lembaga Quick Count yang memenangkan suara baginya hanya akal-akalan saja alias ansor (angin sorga) karena Jokowi sadar hasil perhitungan real count suara terbanyak memang diperoleh Prabowo-Hatta.
Lead artikel tersebut secara langsung mendefi nisikan situasi yang hendak disampaikan, dimana Jokowi JK telah menyadari sepenuhnya bahwa hasil Quick
Count yang dirilis di berbagai media yang menyatakan pasangan tersebut sebagai pemenang pemilu adalah tidak benar. Secara eksplisit pula Mawalu menyatakan bahwa pemenang sebenarnya adalah Prabowo Hatta.
Sementara itu Yusril Ihza Mahendra memiliki cara pandang yang berbeda dan merasa untuk mengklarifi kasi atas tulisan Mawalu tersebut. (Mahendra, 2014). Dalam paragraf leadnya Yusril menyebut bahwa ada sebagian besar tulisan dari Mawalu tersebut hanya berdasarkan pendapatnya pribadi dan cenderung bias.
i. Kemarin, Sabtu (12/07/2014), Saudara Mawalu menulis artikel di laman Kompasiana.com tentang sikap saya terhadap Pilpres, dengan judul yang provokatif, “OMG! Diam-diam Ternyata Jokowi Minta Tolong Yusril Jadi Pengacaranya Gugat Hasil Pilpres 2014 di MK, Tapi ditolak Yusril Mentah-mentah”. [http://komp.as/A4kpo].
ii. Beberapa materi yang diungkapkan dalam artikel itu, merupakan opini Mawalu sendiri yang mendasarkan atas beberapa tuits yang saya publikasi pada akun twitter saya,https://twitter.com/Yusrilihza_Mhd, dan mengganggu bahkan cenderung untuk disalahpahami oleh pembaca. Untuk meluruskan beberapa poin dalam artikel yang cenderung bias itu, berikut saya tampilkan utuh pendapat yang saya tulis pada Rabu (09/Juli/2014) malam itu. Mudah-mudahan menjadi informasi yang utuh.
Pertama kali, Yusril menyebut bahwa judul artikel yang ditulis oleh Mawalu adalah provokatif dan dianggap sarat dengan opini pribadi dari Mawalu. Yusril merasa bahwa judul dan artikel Mawalu tersebut menggangu dirinya dan cenderung untuk terjadi salah tafsir dari pembaca Kompasiana. Salah tafsir yang dimaksud adalah bahwa Yusril Ihza Mahendra memiliki tendesi khusus dalam
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
172 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
kasus penolakan permintaan dari tim sukses Jokowi JK.
b) ExplanationMawalu menulis bahwa Yusril Ihza
Mahendra menolak permohonan tim sukses Jokowi JK untuk menjadi penasehat hukumnya dengan alasan-alasan tertentu.
1) Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menteri Kehakiman itu menolak mentah-mentah per-mohonan Jokowi yang meminta-nya dengan sangat agar ia jadi Pengacaranya. Penolakan itu terpaksa dilakukan Yusril karena ia mengendus niat kurang baik dari pasangan capres dan cawapres nomor dua itu.
Mawalu menyebutkan bahwa penolakan dari Yusril Ihza Mahendra berdasarkan adanya iktikad yang tidak baik dari pasangan Jokowi-JK. Namun Mawalu tidak menyertakan penjelasan lebih lanjut tentang maksud iktikad tidak baik tersebut.
Mawalu justru menjelaskan alasan normatif yang dikemukakan oleh Yusril ketika menolak permohonan Tim Jokowi JK, bahwa dengan pertimbangan tidak enak hati, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa ia netral dalam Pilpres 2014.
2) Yusril menuturkan di akun Twitternya pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014, setelah usai Pilpres kubu Jokowi malam itu langsung menelepon dirinya minta agar ia bela mereka. Karena tak enak hati sama Jokowi dan JK, Yusril pun beralasan bahwa ia hanya ingin netral saja dalam Pilpres 2014 ini tak mau bela siapa-siapa.
Pertimbangan Yusril yang ingin netral dalam Pilpres 2014 dan tidak mau membela siapa-siapa ini dipuji oleh Mawalu sebagai sikap negarawan yang baik, dimana kepentingan pribadi dan golongan dibawah kepentingan negara dan bangsa.
3) Salut aku kepada bang Yusril yang
tetap komitmen dalam koridor kebenaran. Kita patut bersyukur kepada Tuhan YME bahwasannya di negara ini masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran demi kepentingan nusa dan bangsa, bukan untuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi semata.
Sebagai pendukung Prabowo Hatta, secara eksplisit Mawalu juga menegas-kan bahawa sikap Prabowo yang siap menerima setiap keputusan KPU atas hasil Pilpres 2014 tanpa ada rencana menggungatnya di Mahkamah Konstitusi, adalah jiwa besar serang pemimpin.
4) Menilik dari manuver yang memalukkan ini, Jokowi sejatinya harus belajar kepada Prabowo yang telah berbesar hati siap menerima kekalahan kalau memang pada saat real count pada tanggal 22 Juli 2014 nantinya ia kalah perolehan suara.
5) Prabowo saja tak pernah berniat akan melakukan gugatan hasil pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi, tapi kok bisa-bisanya kubu Jokowi nego Yusril untuk gugat hasil pilpres ke Mahkamah Institusi. Indikasi ini sudah jelas, artinya mereka sudah tahu bahwasanya perolehan suara Jokowi memang di bawah Prabowo. Buktinya Prabowo tenang-tenang saja, tapi kubu Jokowi sudah kalang kabut duluan. Tanya kenapa?
Struktur retoris yang disusun oleh Mawalu meneguhkan kembali posisinya sebagai seorang pendukung Prabowo Hatta, seraya mengajak pembaca berfi kir tentang apa yang terjadi sebenarnya atas permintaaan tersebut. Penolakan Yusril menjadi pengacara Jokowi JK dinarasikan sebagai titik point sudut pandangnya dalam pembahasan di artikelnya tersebut.
Disisi lain, Yusril menegaskan arti netralitas dalam Pilpres 2014 dalam arti konsisteni sikap. Hal itu yang dinyatakan sebagai berikut:
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 173
i. Sampai malam ini dan Insya Allah seterusnya, saya tetap mempertahankan sikap netral saya dalam Pilpres 2014 ini. Malam ini tvone mengundang saya, katanya ada acara dialog menghadirkan saya dan Mahfud MD. Saya diposisikan sebagai pengamat dalam acara ini.
ii. Saya sudah datang ke gedung Bidakara, tapi saya minta maaf kepada crew tvone, saya tidak bisa ikut dalam acara tersebut. Saya katakan, kehadiran saya dalam acara Presiden Pilihan Rakyat di tvone, bisa menimbulkan anggapan saya memihak kubu Prabowo. Saya ingin tetap netral, tidak mendukung apalagi memihak kepada salah satu pasangan, tidak Prabowo-Hatta, tidak juga Jokowi-JK.
iii. Dari zaman Presiden Suharto sikap saya selalu seperti itu dan sampai sekarang tidak berubah. Saya rela diberhentikan dari suatu jabatan, karena saya berbeda pendapat dengan Presiden, apalagi jika saya anggap Presiden melanggar UUD 1945.
Yusril menyatakan bahwa netralitas yang ia maksud adalah tidak memihak kepada salah satu kubu Capres dan Cawapres, baik Prabowo Hatta maupun Jokowi JK. Yusril menekankan bahwa ia menolak setiap acara atau permintaan dari masing-masing kandidat Presiden-Wakil Presiden, jika sekiranya hal tersebut akan menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa ia mendukung salah satu kandidat. Dengan menyebutkan penolakannya sebagai pengamat di acara TV One, Yusril hendak menyatakan bahwa dirinya bersikap adil. Bahwa yang ditolak bukan saya permintaan dari pihak Jokowi JK namun juga dari pihak Prabowo Hatta.
Yusril juga menyatakan bahwa ia memiliki sikap konsisten atas pilihannya tersebut, bukan saja pada Pilpres 2014 saja, namun jauh sebelumnya.Penegasan ini dibuat Yusril, bahwa dirinya adalah sosok yang memegang teguh atas prinsip, konsisten dan berani.
c) Moral Saran dari Mawalu dalam artikelnya
adalah bahwa Jokowi JK beserta timnya untuk memiliki jiwa besar sebagaimana ditunjukan oleh Prabowo. Siap menerima hasil keputusan KPU. Perbedaan penghitungan Quick Count tidaklah menjadi dasar keabsahan hukum atas pemenang Pilpres 2014.
Jika KPU telah memutuskan pemenang dalam Pilpres 2014, semua pihak harus menerimanya dengan baik dan legowo. Menempuh jalur hukum untuk menggungat hasil Pilpres 2014 adalah suatu tindakan yang tidak terpuji.
Terkait dengan penolakan Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat hukum, Mawalu secara sarkasme menulis:
6) Kembali lagi ke permohonan Jokowi ke Yusril yang ditolak mentah-mentah itu, saran aku buat Jokowi dan JK, sebaiknya kalian sewa Pengacara Farhat Abbas saja. Siapa tahu bisa menang.
Mawalu mengandaikan pembaca kompasiana mengetahui siapa yang disebut dengan Farhat Abbas. Seorang pengacara yang sering membuat kontroversi dan bagi sebagian orang dianggap aneh.
Sementara moral yang hendak disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra adalah bahwa persoalan nilai uregensi dari netralitas dalam pilpres 2014, bahwa pilpres 2014 sarat dengan kepentingan kelompok dan golongan, sementara kepentingan nusa dan bangsa terlupakan.
d) The actorsMawalu mendeskripsikan para pelaku
dalam artikelnya Mawalu, Prabowo Hata dan Yusril Ihza Mahendra sebagai bagian dari kami, sementara Jokowi JK dan Farhat Abbas sebagai bagian dari mereka.Salah satunya adalah dengan menggunakan kata ganti “aku” dan “bung Yusril” Mawalu
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
174 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
berusaha untuk mendekatan identitas dirinya dengan Yusril Ihza Mahendra. Kata ganti “aku” juga mencerminkan Mawalu sebagai sosok muda yang kritis, seperti halnya pengunaan sebutan “aku”yang populer pada gerakan mahasiswa diantara para aktivitis 1998.
Semantara Yusril memanggil Mawalu dengan sebutan “saudara Mawalu”, sebagai bentuk komunikasi berjarak, bahwa Yusril tidak mengenal dekat dengan Mawalu. Yusril secara konsten menyebut dirinya sebagai “saya” frasa yang lebih sopan, rendah hati, dimana hal ini Yusril hendak mengkomunikasikan dirinya sebagai sosok dan fi gur yang telah matang pengalaman.
Yusril menempatkan dirinya berada dalam posisi bersama kepentingan bangsa dan negara, sementara kepentingan masing-masing kandidat presiden dan kelompok pendukungnya berada pada posisi berseberangan. Posisi ini sama dengan posisinya dulu yang berseberangan dengan posisi Soeharto di tahun 1998.
e) The ideological value structureStruktur nilai idiologis dari dua artikel
ini pada hakikatnya sama, yakni bahwa masing-masing kandidat Presiden/Wakil Presiden harus taat azas, menghormati hukum atas keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2014.
Hal ini berangkat pada pemikiran idiologi “law and order”, hukum dan ketertiban umum, bahwa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan mengikuti segenap hasil keputusan yang sah di mata hukum terkait dengan Pilpres 2014.
Yang berbeda dalam dua artikel ini adalah cara pengemasan dari struktur idiologis tersebut. Mawalu mengemas idiologi taat azas dan menghormati hukum tersebut dalam kerangka mengecilkan
posisi satu pihak dan memberi peran lebih besar pada pihak lain, sementara Yusril Ihza Mahendra mengemas idiologi taat azas dan menghormati hukum tersebut sebagai suatu bentuk menjunjung tinggi kepentingan nusa dan bangsa.
Di sisi lain, Mawalu menyusun artikelnya dalam posisi sebagai seorang pendukung Prabowo Hatta sementara Yusril Ihza Mahendra hendak memposisikan diri sebagai bapak bangsa, national heroes, yang akan turun tangan jika keadaan dan kepentingan nusa dan bangsa terganggu.
Dari dua artikel tersebut tampak bahwa struktur idiologis yang ada di alam kesadaran masing-masing penulis artikel jauh melampaui dari narasi teks yang ditulis. Cara mengemas idiologi dalam narasi teks berbeda, Mawalu yang secara terang-terangan, provokatif dan sedikit sakrastik, sementara Yusril Ihza Mahendra menggunakan bahasa-bahasa implisit, euforis-romantis dan halus.
Kesimpulan dan Saran
1. Dalam konteks penulisan artikel opini, cara berfi kir dan mengkonstruksi wacana mencerminkan sikap, kepribadian dan orientasi politik dari komunikator. Narasi teks mencerminkan bagaimana framing penulisan digunakan untuk mempertegas posisi penulis dalam suatu sikap dan wacana tertentu. Dalam hal ini struktur idiologis yang ada di alam kesadaran masing-masing penulis artikel jauh melampaui dari narasi teks yang ditulis.
2. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas penulis artikel di Kompasiana adalah dengan dua teknik yakni: Pertama, menframe tulisan gaya dengan mengutip sumber berita dengan gaya personal style. Hal ini
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 175
dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas penulis artikel. Teknik ini jarang digunakan dalam penulisan artikel berita dalam kaidah jurnalistik konvensional. Meskipun demikian, dalam konteks komunikasi, percakapan interpersonal yang bersifat privat ini akan lemah untuk dijadikan dasar argumentasi jika tidak disertai bukti otentik, seperti transkrips rekaman suara. Lokus sites dan lokus konteks menjadi sangat ahistoris, jika seorang penulis artikel menulis pengalaman pribadinya sebagai dasar argumentasi karena hal tersebut sulit untuk dilakukan verifi kasi. Teknik kedua adalah dengan menggunakan hiperlink dari sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses langsung oleh pembaca artikel. Teknik ini sangat populer dalam Citizen Journalism dan dianggap sebagai salah satu moda interaktivitas yang khas untuk penulisan artikel di internet..
Namun permasalahan kredibilitas penulis artikel dan sumber informasi yang dirujuk menjadi krusial ketika dihadapkan kepada persoalan kebenaran informasi yang disampaikan. Kredibilitas penulis artikel adalah terkait dengan kejujuran identitas penulis. Oleh karena sifat dari media intenet yang sangat terbuka dan fl eksibel yang menyebabkan siapapun tanpa harus memiliki identitas yang jelas dapat menyusun fakta dan informasi dan disajikan di media internet. Di sisi lain, banjir informasi (information fl oods) dapat menyebabkan orang mengambil kesimpulan yang berbeda dari sebuah fakta/peristiwa yang sama. Perbedaan kesimpulan ini dipicu oleh pengunaan informasi sekunder yang tingkat keabsahannya diragukan.
3. Artikel dalam bentuk reportase (liputan/padangan mata) dalam praktek jurnalistik warga (citizen journalism) belum memiliki kredibilitas yang kuat karena sangat kuat unsur manipulatif dan subjektivitas dari peliput berita. Kemampuan pembaca dalam menelaah artikel berita menjadi sangat penting untuk memilih dan memilah informasi yang diperoleh.
Daftar PustakaAnshori, M. (2010). Jurnalistik Online;
Kajian Empat Portal Berita Online di Indonesia. Komunikasi Massa, 22-25.
Banning, S. A., & Sweetser, K. D. (2007). How Much Do They Think It Affects Them and Whom Do They Believe?: Comparing the Third-Person Effect and Credibility of Blogs and Traditional Media. Communication Quarterly, 55(4) , 451-466.
Borupaung, R. (2014, Juli 17). Surat Terbuka untuk Luhut B Pandjaitan. Dipetik Juli 22, 2014, dari kompasiana: h t t p : / / p o l i t i k . k o m p a s i a n a .com/2014/07/17/surat-terbuka-untuk-luhut-b-panjaitan-664770.html
Dijk, T. V. ( 1989). Race, riots and the press An analysis of editorials in the British press about the 1985 disorders. Gazette 43, 229-253.
Dijk, T. V. (1991). Media contents The Interdisciplinary study of news as discourse. Dalam K. B. Jensen, & N. W. Jankowski, A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research (hal. 108-120). New York: Routledge.
Jack, S. (2014, April 13). Tanggapan Tulisan Hazmi Srondol Mengenai Prabowo. Dipetik Juli 17, 2014, dari kompasiana: h t t p : / / p o l i t i k . k o m p a s i a n a .c o m / 2 0 1 4 / 0 4 / 1 3 / t a n g g a p a n -tulisan-hazmi-srondol-mengenai-prabowo-648712.html
Mahfud Anshori. Media Komunitas, Kredibilitas ...
176 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Johnson, T. J., & Kaye, B. K. (2009). In blog we trust? Deciphering credibility of components of the internet among politically interested internet users. Computers in Human Behavior, 25, 175-182.
Kang, M. (2010). Measuring Social Media Credibility – A Study on a Measure of Blog Credibility. Institute for Public Relations, 2-22.
M. A. (2014, Juni 15). Jokowi and Sacred Images. Dipetik Juli 22, 2014, dari kompasiana: http://politik.kompasiana.com/2014/06/15/jokowi-and-sacred-images-658734.html
Mahendra, Y. I. (2014, Juli 13). Pemihakan Saya Hanya kepada Bangsa dan Negara. Dipetik Juli 14, 2014, dari Kompasiana/hukum: http://hukum.kompasiana.com/2014/07/13/pemihakan-saya-hanya-kepada-bangsa-dan-negara-668119.html
Mawalu. (2014, Juli 05). Ini Sebab Mawalu Pindah ke Lain Hati Dukung Prabowo, Tanya Kenapa? Dipetik Juli 17, 2014, dari 05: http://politik.kompasiana.com/2014/07/05/ini-sebab-mawalu-p i n d a h - k e - l a i n - h a t i - d u k u n g -prabowo-betanya-kenapa-671684.html
Mawalu. (2014, Juli 12). OMG! Diam-diam Ternyata Jokowi Minta Tolong Yusril Jadi Pengacaranya Gugat Hasil Pilpres 2014 di MK, Tapi ditolak Yusril Mentah-mentah. Dipetik 07 14, 2014, dari politik kompasiana: http://politik.kompasiana.com/2014/07/12/omg-secara-siluman-ternyata-jokowi-minta-yusril-jadi-pengacaranya-b i l a m a n a - h a s i l - p i l p r e s - 2 0 1 4 -berujung-di-mahkamah-konstitusi-t a p i - d i t o l a k - y u s r i l - m e n t a h -mentah-673500.html
Metzger, M. J. (2003). (2003). Credibility for the 21st century: Integrating
perspectives on source, message, and media credibility in the contemporary media environment. Dalam Communication Yearbook 27 (hal. 293 - 335).
Munir. (2014, Mei 30). Jumat di Sunda Kelapa, Jokowi Disuguhi Khatib “Pentingnya Amanah”. Dipetik Juli 13, 2014, dari kompasiana: http://politik.kompasiana.com/2014/05/30/jumat-di-sunda-kelapa- jokowi-d u s u g u h i - k a h t i b - p e n t i n g n y a -amanah-655689.html
Subakti, E. (2014, Juli 19). Kepada Penulis Surat Terbuka untuk Luhut Pandjaitan. Dipetik Juli 22, 2014, dari Kompasiana: file:///E:/Gubes/Penelitian%20UNS%202014/New%20Media/Bahan%20Kompasian/31%20Mei/Kepada%20Penulis%20Surat%20Terbuka%20untuk%20Luhut%20Pandjaitan.htm
Subekti, E. (2014, Mei 31). Tak Berhenti Karangan Fitnah terhadap Jokowi. Dipetik Juli 14, 2014, dari kompasiana: h t t p : / / l i f e s t y l e . k o m p a s i a n a .com/catatan/2014/05/31/tak-berhenti-karangan-fitnah-terhadap-jokowi-661580.html
Sundar, S. S. (2008). The MAIN Model: A Heuristic Approach to Understanding Technology Effects on Credibility. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning, 73-100.
Thorson, K. V., & Ekdale, B. (2010). Credibility in Context: How Uncivil Online Commentary Affects News Credibility. Mass Communication & Society, 3(3), 289-313.
Yang, S.-U., & Lim, J. (2009). The effects of blog-mediated public relations on relation trust. Journal of Public Relations Research, 21(3), 341-359.
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 177
Peran Komunikator dalam Ritual Hajatan(Studi Kasus Peran Tokoh Terop dalam Hajatan Etnis
Madura di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)
Adi Inggit HandokoProgram Studi Ilmu Komunikasi Univesitas Muhammadiyah Ponorogo
AbstractThis study discusses the role of communicators in a hajatan, communicators in the region of ethnic Madurese research object called is tokoh terop, pemilik hajatan, penanggung jawab, pengurus, pendamping and pelandang. This study was a descriptive qualitative research, with intrinsic case study approach. To collect the data, two methods were used: in-depth interview and document study (in this case invitation text). The results of research were as follows. (a) At the invitation text level: (1) The role of character terop used by the owner of celebration in an effort to attract the masses prospective contributors. (2) The existence of terop fi gures as a form of hegemony owner of celebration to the society. (3) The role of character terop as personal selling, invitation as well as a media promotion of the owner celebration. (4) The existence of characters terop as a form of celebration of the owner’s inability to attract the masses contributor.(b) At the planning level of celebration: (1) At the stage of the role of character terop through mind, it was found that the fi gure terop attempt to pass down cultural celebration with teropan concept to the younger generation of ethnic Madurese. The role of character terop in celebration as an effort to expand of cultural adoption teropan to the public. (2) On the role of character terop with power, that what the fi gure as a form of refl ection society cooperations. (3) At this stage of the role of character terop with the service, it was found that the celebration is a source of livelihood the “terop” group.(c) At the level of organization, the creation of terop groups is an effort to strengthen the Madura ethnic group. The teropan is a way for the fi gures of terop to meet and gathering. The establishment of a celebration with teropan concept is intended also as an effort to reduce confl icts between people or terop group.(d) At the level of implementation of the celebration: the role of the leader in charge of terop are in charge of security implementation celebration, in addition to securing the passage of a celebration, the person in charge must bear the fi nancial shortfall during a celebration held. The organizer completes all requirements during the celebration takes place. The companion will accompany the owner of celebration at the time celebartion took place.Keywords: Communication, Role Communicator, Celebration and Hajatan
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 177-190
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
178 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Pendahuluan
Indonesia merupakan sebuah konsep yang terdiri dari keberagaman etnik, masing-masing etnis mengembangkan sifat komunalisme secara otonom. Menurut Van der Kroef masyarakat komunalisme tradisional (tradisional communalism) memiliki ciri-ciri (a) high inter-relatedness of all domains of communality life (in totally) (b) super natural power (c) kuatan ikatan teritorial dan kekerabatan (kindship) (d) kuatnya batas teritorial menyebabkan semakin tegasnya batas-batas budaya yang dapat dikenali. Dari Sabang sampai Merauke masing-masing etnis memiliki perilaku budayanya sendiri yang hidup berkembang dengan wajar dan alamiah dalam bentuk-bentuknya yang spesifi k (Salim: 3)
Pasuruan adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, terletak sekitar 65 km sebelah tenggara dari Kota Surabaya. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Probolinggo di Timur, Kabupaten Malang di selatan, Kota Batu di barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan tujuan wisata. Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah suku Jawa, selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti suku Madura serta masyarakat keturunan Tionghoa-Indonesia, Arab dan India.
Dari keberagaman masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pasuruan, peneliti memfokuskan pada etnis Madura yang tinggal di Desa Karanglo Kecamatan Grati. Etnis Madura yang tinggal di wilayah ini mengembangkan sifat komunalisme otonomnya dengan menciptakan tradisi yang unik yang diwujudkan dalam kegiatan hajatan. Alasan lain memilih etnis
Madura karena pada umumnya penelitian tentang suku Madura kebanyakan hanya berfokus pada tindak kekerasan (seperti Carok), logat bahasa, dan profesi orang Madura. Namun ternyata di sisi yang lain etnis Madura memiliki keunikan dan ciri khas mereka yang tidak ditemukan di Pulau Madura sebagai tempat asal etnis Madura. Bahkan kegiatan hajatan yang demikian tidak akan dijumpai pada suku atau etnis lain yang tinggal di Indonesia. Pendapat peneliti yang demikian diperkuat dengan berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti kepada informan di lapangan, bahwa desain undangan dengan menampilkan foto-foto tokoh hanya dimiliki oleh etnis Madura yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan yang lebih tepatnya etnis Madura yang tinggal di daerah pinggiran Kabupaten Pasuruan sampai ke daerah perbatasan dengan wilayah Probolinggo.
Hajatan pada masyarakat umumnya dimaknai sebagai sesuatu yang sakral, namun hajatan bagi etnis Madura yang tinggal di wilayah ini dimaknai sebagai tempat untuk arisan (arisan karena pada gilirannya ketika seseorang telah menyumbang (bowoh atau buwuh: bahasa lokal etnis Madura Pasuruan) kepada orang lain, maka seseorang tersebut pasti akan mengadakan suatu pesta. kadang-kadang bukan pesta dalam skala besar, namun orang yang merasa pernah dititipi sumbangan akan datang untuk mengembalikan sumbangannya) atau menitipkan (menitipkan karena biasanya seseorang yang dalam waktu dekat akan mengadakan hajatan, sehingga kadang-kadang jumlah sumbangan akan melebihi jumlah nominal pada umumnya. Dimaknai sebagai menitipkan karena pada dasarnya sumbangan yang pernah disumbangkan wajib hukumnya untuk seseorang mengembalikan. Biasanya orang yang dalam waktu dekat akan
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 179
mengadakan pesta, ketika datang pada hajatan orang lain, sumbangan berupa uang akan diselipkan pada undangan hajatan miliknya yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat) dan hajatan juga dimaknai sebagai tempat penyambung tali silaturahmi antar warga yang tinggal di wilayah ini. Pertama, hajatan dimaknai sebagai ajang arisan atau penitipan adalah karena pada dasarnya setiap seseorang yang pernah bowoh atau buwuh (Jenis sumbangan bisa berupa sejumlah nominal uang atau berupa sembako) pada orang lain, maka orang yang merasa pernah disumbang wajib hukumnya untuk mengembalikannya. Pengembalian jenis sumbangan ini sesuai dengan jenis sumbangan yang diberikan di awal. Apabila penyumbang pertama memiliki hajat dan orang yang pernah disumbang tidak hadir pada hajatan tersebut, maka pemilik hajat berhak menagih dengan mendatangi rumah seseorang tersebut atau memberikan surat teguran secara tertulis. Kedua, hajatan dimaknai sebagai penyambung tali silaturahmi adalah karena dalam tradisi sumbangan apabila seseorang mengembalikan jumlah dan jenis yang sama tanpa memberi imbuhan sumbangan maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pemutus tali silaturahmi antar individu. Selain pemutus tali silaturahmi keadaan demikian bisa juga dianggap sebagai impas.
Tradisi lain yang terjadi dalam kegiatan hajatan pada etnis Madura di wilayah ini membuat desain undangan dengan memajang foto yang punya hajatan (baca: pesta) beserta para panitia dalam hajatan. Jika diamati, undangan hajatan tersebut sepintas seperti kartu pencontrengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan tokoh yang dipajang dalam desain undangan diharapkan mampu menarik minat seseorang untuk menyumbang kepada pemilik hajatan. Sebelum foto seseorang
dipajang dalam desain undangan, biasanya yang akan memiliki hajatan meminta izin terlebih dahulu kepada orang-orang yang fotonya akan ditempatkan dalam desain undangan. Pemilik hajatan memilih dan menentukan tokoh yang akan ditempatkan pada desain undangan, seperti: pemilik hajatan, penanggung jawab, pendamping, pengurus, dan pengundang. Foto orang-orang yang akan dipajang dalam desain undangan biasanya merupakan tokoh yang berpengaruh di wilayah ini. Dengan harapan bahwa tokoh yang berpengaruh tersebut membawa dampak banyaknya tamu undangan yang hadir pada hajatan. Penempatan tokoh pada desain undangan secara otomatis bahwa tokoh-tokoh tersebut membantu suksesnya pelaksanaan hajatan.
Ketokohan seseorang yang berada di dalam desain undangan sepertinya memberikan makna sentral bagi orang-orang yang menerima undangan hajatan. Selain itu pula bisa dipastikan bahwa pemilihan tokoh yang dilakukan oleh pemilik hajat bukanlah suatu tindakan yang tanpa disengaja atau hanya kebetulan semata. Namun penempatan tokoh ini sudah berdasarkan pemilahan dan seleksi yang dilakukan oleh pemilik hajat. Tokoh yang dipilih pun bisa berasal dari relasi sosial yang selama ini dijalin dengan baik antara pemilik hajat dengan tokoh yang dipilihnya. Begitu juga dengan tokoh itu sendiri, dengan maksud tetap terjalinnya suatu hubungan yang dinamis, mereka merelakan foto dan juga namanya terdapat di dalam desain undangan tanpa adanya sebuah imbalan.
Dari hasil pengamatan dan interview kepada narasumber di lapangan, peneliti menemukan tradisi unik lainnya. Tradisi unik lain dalam rangkaian hajatan ini disebut dengan hajatan koalisi. Hajatan koalisi (Hajatan koalisi bagi masyarakat
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
180 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
etnis Madura disebut juga rejengan) yakni, apabila seseorang yang akan memiliki hajat masih kekurangan biaya untuk menyelenggarakannya, atas dasar kesepakatan bersama mereka akan menggelar suatu hajatan yang biayanya berasal dari mereka berdua. Dalam mendesain undangan mereka menegaskan dengan memajang foto kedua belah pihak yang memiliki hajat dan menegaskan pemberian dua kotak sumbangan dengan sebutan Rejeng (Banyaknya kotak sumbangan atau rejeng tergantung dari berapa orang yang bergabung dalam hajatan).
Jika dikaitkan komunikasi partisipatif dengan tindakan komunikasi yang digagas oleh Habermas dalam Littlejohn (2008:333) bahwa masyarakat memiliki tiga jenis kepentingan dalam berpartisipasi. Pertama, teknis adalah kepentingan untuk menyediakan sumber daya yang natural. Kedua adalah interaksi karena pada dasarnya sebuah hubungan kerjasama sosial sangat penting untuk bertahan hidup, minat ini dinamakan minat praktik (practical interest). Minat kedua ini sangat penting karena dalam hal ini mencakup kebutuhan-kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi dan praktek-prakteknya. Ketiga adalah kekuasaan. Tatanan sosial secara alamiah cenderung pada distribusi kekuasaan, namun pada saat yang sama juga memiliki kepentingan untuk membebaskan diri dari dominasi. Kekuasaan mengarah pada distorsi terhadap komunikasi, namun dengan menjadi sadar akan adanya ideologi-ideologi yang dominan di masyarakat, suatu kelompok kemudian dapat memberdayakan dirinya untuk mengubah keadaan. Maka kepentingan kekuasaan adalah kepentingan yang emansipatoris.
Menurut Habermas komunikasi yang ideal itu bebas dari dominasi,
semua berjalan seimbang, tanpa adanya tingkatan-tingkatan strata sosial yang melatarbelakanginya. Namun, pada kenyataannya etnis Madura yang tinggal di wilayah ini dalam melaksanakan kegiatan hajatan belum terbebas dari adanya dominasi, dan seperti ada kekuatan maupun ketakutan-ketakutan tersendiri bagi mereka ketika diundang namun tidak menghadiri. Sedangkan menurut Sastropoetro (1986:57) menyatakan bahwa untuk menciptakan partisipasi yang efektif harus terbebas dari paksaan dan tekanan. Paksaan dan tekanan seharusnya dihindari agar tidak menimbulkan ketegangan. Pernyataan Sastropoetro tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz yang dikemas dalam karyanya Religion of Java, dalam satu sub pembahasan Geertz (2013:7-8) tentang makna slametan bahwa dalam kegiatan slametan ini semua orang diperlakukan secara sama. Hasilnya bahwa dalam suatu kondisi masyarakat berbaur pada suatu kegiatan tak seorang pun merasa berbeda dari yang lain, tak seorang pun merasa lebih rendah dari yang lain dan tak seorang pun punya keinginan untuk mengucilkan diri dari orang lain.
Dari pemaparan fenomena hajatan diatas, peneliti akan menganalisis fenomena hajatan ini berdasarkan unsur-unsur komunikasi. Dari kelima unsur komunikasi inilah akan terjadi sebuah aktivitas komunikasi, proses-proses komunikasi dapat diamati dalam acara hajatan etnis Madura yang menetap di wilayah ini. Unsur komunikasi ini sejalan dengan pengertian komunikasi menurut Harold Laswell, bahwa komunikasi adalah who, say what, in which chanel, to whom, with what effect (Mulyana, 2008:147).
Unsur pertama adalah komunikator, penempatan tokoh-tokoh dalam desain undangan dalam kajian komunikasi
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 181
bisa diartikan sebagai komunikator. Komunikator dalam desain undangan ini memiliki peranan penting, karena komunikator disini digunakan untuk menarik massa untuk datang pada sebuah hajatan. Komunikator juga bisa dijadikan tolak ukur tingkat kepercayaan seseorang ketika dirinya hendak memberikan sumbangan. Dilain sisi komunikator disini bisa menggantikan kekuatan (power) atau image dari siapa sipemilik hajatan. Ketika pemilik hajat tidak memiliki pengaruh apapun di masyarakat, maka posisi komunikator akan bisa menggeser posisi ini.
Unsur kedua adalah pesan, pesan dalam fenomena hajatan ini disimpulkan peneliti sebagai konten acara yang akan diselenggarakan oleh sipemilik hajatan. Konten acara yang dimaksudkan peneliti adalah hajatan pernikahan, khitanan, ulang tahun, pindah rumah, mendoakan orang sudah meninggal, dan kelahiran. Apakah dari banyaknya konten acara yang akan diselenggarakan oleh etnis Madura memiliki kesamaan dalam penyusunan pesan dan desain undangannya.
Ketiga Chanel, chanel dalam konteks fenomena hajatan ini berarti adalah jenis dan desain undangan. Karena disini peneliti melihat ada perbedaan desain undangan. Desain undangan pertama yang digunakan untuk sesama etnis Madura atau untuk golongan dengan tingkat stratifi kasi sosialnya setara. Desain undangan ini digunakan dengan menampilkan foto-foto para tokoh. Sedangkan desain undangan kedua merupakan desain undangan yang bentuknya lebih umum yang tidak menampilkan foto para tokoh. Undangan jenis ini kemudian digunakan untuk mengundang mereka yang tingkat status sosialnya lebih tinggi.
Unsur keempat adalah penerima, masyarakat yang tinggal dan menetap di
wilayah Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ini beragam, tidak seratus persen etnis Madura. Kemudian menjadi menarik karena apakah dalam pemberian undangan dan perlakuannya juga berbeda antara yang sesama etnis Madura dan yang diluar etnis Madura.
Unsur kelima adalah efek, efek dalam konteks penelitian ini adalah keputusan untuk datang dalam acara hajatan. Berdasarkan uraian diatas bahwa alasan seseorang untuk datang dalam kegiatan hajatan beragam. Ada yang datang karena kenal kepada pemilik hajatan, ada yang datang karena pernah merasa dititipi sumbangan sebelumnya, ada yang datang karena silaturahmi, ada juga yang datang karena merasa tidak enak terhadap komunikator yang dipajang fotonya dalam desain undangan.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Menurut Yin (2013:1) secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaannya suatu penelitian berkenaan dengan how dan why. Kasus menurut Louis Smith dalam Denzin (2009:300) adalah suatu sistem yang terbatas. Dalam ilmu-ilmu sosial dan layanan kemanusiaan, kasus memiliki bagian operasional, bisa jadi bertujuan dan bahkan memiliki jiwa. Kasus adalah sistem yang padu bagian-bagian tidak harus beroperasi dengan baik, tujuan bisa jadi irasional, namun itu tetaplah sebuah sistem. Sedangkan menurut Stoufer seorang peneliti kasus biasanya mencari sesuatu yang umum dan khusus dari sebuah kasus, namun hasil akhirnya seringkali memberikan sesuatu yang menarik dan unik Denzin (2009:302). Menurut Faisal (2003: 22) studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Berbagai
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
182 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
variabel ditelaah dan ditelusuri termasuk juga antar variabel yang ada. Menurut jenisnya, pendekatan studi kasus yang dipakai peneliti adalah Intrinsic case study. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu. Namun karena, dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaan kasus tersebut menarik minat. Dalam kesimpulannya pada penelitian studi kasus jenis ini tidak dapat digeneralisasikan, melainkan kesimpulan yang akan diambil peneliti hanya untuk kalangan tertentu saja.
Rumusan Masalah
1. Mengapa masyarakat etnis Madura di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan menyelenggara-kan hajatan dengan konsep teropan?
2. Bagaimana peran tokoh terop dalam ritual hajatan etnis Madura di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan?
Tinjauan Pustaka
Konsep Dasar Komunikasi
Menurut Fiske (2012:2-3) ilmu komunikasi dibagi menjadi dua mahzab utama. Pertama, kelompok yang melihat komunikasi sebagai transmisi pesan, kelompok ini fokus dengan bagaimana pengirim dan penerima, mengirim dan menerima (pesan). Kelompok ini sangat memperhatikan dengan hal-hal sebagai efi siensi dan akurasi. Pandangan ini melihat komunikasi sebagai proses dimana seseorang mempengaruhi perilaku atau cara berpikir orang lain. Jika efek yang muncul berbeda atau kurang yang diinginkan, mahzab ini cenderung untuk berbicara dengan istilah-istilah seputar kegagalan komunikasi, dan melihat berbagai tahapan didalam proses komunikasi untuk menemukan dimana kegagalan terjadi.
Mahzab ini disebut mahzab “proses”. Kedua, melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Kelompok ini fokus dengan bagaimana pesan, atau teks berinteraksi dengan manusia di dalam rangka untuk memproduksi makna; artinya, pandangan ini sangat memperhatikan peran teks di dalam budaya kita.
Pembagian defi nisi komunikasi menurut Fiske di atas sepertinya sangat mempermudah bagi kita memahami komunikasi. Fiske membagi komunikasi ke dalam dua mahzab, pertama mahzab proses dan kedua mahzab produksi dan pertukaran makna. Jika mengacu kepada dua mahzab ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa defi nisi komunikasi yang dirasa sesuai dengan tema penelitian ini adalah mahzab “proses”. Defi nisi ini dimaksudkan seperti apa yang dikatakan oleh Littlejohn bahwa difi nisi memberi gambaran serta mempermudah mana yang termasuk ke dalam cakupan komunikasi dan mana yang bukan termasuk ke dalam cakupan dalam tema penelitian ini.
Menurut model Sannon dan Weaver dan Laswell, model komunikasi diatas tampak adanya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup, yang merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Komponen tersebut adalah: sumber (komunikator), pesan, komunikan, dan saluran. 1) sumber, adalah orang atau individu
titik pertama pesan itu berasal, dalam prakteknya sumber ini bertindak sebagai komunikator. Perannya dalam menyampaikan pesan sangat menentukan apakah dia sebagai komunikator yang kredibel atau tidak. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai komunikator adalah pemilik hajatan, penanggung jawab, pendamping, pengurus, pelandang.
2) Pesan, adalah yang dikirim ke penerima
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 183
bisa berupa lambang atau stimulus dengan makna yang sudah diolah dan dikemas berupa informasi ke penerima. Terutama pesan itu melalui proses pematangan, kemudian dikemas dengan baik agar makna dan efek yang akan ditimbulkan mudah dimengerti dan di cerna oleh komunikan. Artinya setelah melalui proses, pesan itu akan mendapatkan respon berupa umpan balik, setelah pesan itu dimengerti dengan baik akhirnya penerima akan bereaksi positif artinya pesan yang disampaikan komunikator merupakan faktor penentu akan keberhasilan dari komunikasi itu.
3) Penerima, bisa merupakan individu atau kelompok sebagai dari tujuan pesan. Dia juga berperan apakah pesan dapat dimngerti akan makna dari pesan itu, bagaimana feedback atau respon yang ditimbulkannya.
4) Saluran, pesan yang sudah dikemas tadi dikirim melalui saluran bisa berupa pesan cetak atau media elektronik, radio atau lisan baik langsung atau melalui media telepon kepada penerima. Dalam menyampaikan pesan dalam penelitian ini digunakan dua media penyampai pesan hajatan yakni undangan secara tatap muka secara langsung antara pemilik hajatan (komunikator) dan orang-orang (komunikan) yang akan diminta kesediaan perannya dalam pelaksanaan hajatan. Selain saluran tatap muka langsung komunikator menggunakan media undangan tertulis untuk menyampaikan pesan kepada komunikan.
Untuk mempermudah pemahaman tentang peran komunikator dalam peneliti-an ini, peneliti akan mengganti istilah peran dengan partisipasi. Sebagai catatan bahwa istilah partisipasi ini memiliki tahapan dan juga bentuk-bentuk yang jelas, sehingga mampu digunakan untuk
membantu peneliti dalam menganalisa peran komunikator dalam ritual hajatan.
Komunikasi Ritual
Komunikasi ritual erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif, komunikasi ritual ini dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup. Yang disebut oleh antropolog sebagai rites of passage. Mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, hingga upacara kematian. Dalam upacara-upacara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka. (Mulyana, 2008:27)
Habermas dan Teori Tindakan Komunikatif
Dalam pidatonya sebagai guru besar di Universitas Frankfurt yang berjudul Knowledge and Human Intersts Habermas tidak hanya berpendapat bahwa paham kebebasan nilai ilmu-ilmu sosial itu keliru dan berbahaya, tetapi juga menunjukkan bahwa tujuan ilmu-ilmu kritis, dengan kepentingan emansipatorisnya adalah membantu masyarakat mencapai otonomi dan kedewasaan. Ditunjukkan pula bahwa otonomi kolektif ini berhubungan dengan pencapaian konsensus bebas dominasi. Sampai pada tahun 1980-an Habermas mengandaikan bahwa konsensus macam itu dapat dicapai dalam sebuah masyarakat yang refl ektif (cerdas) yang berhasil melakukan komunikasi yang memuaskan. Dalam komunikasi, para partisipan membuat lawan bicaranya memahami maksud dan berusaha mencapai apa yang disebut Habermas sebagai klaim-klaim
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
184 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
kesahihan (Validity claims). Klaim-klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil konsensus. (Hardiman, 2009:17-18)
Teori tindakan komunikatif mengambil sikap kritis baik terhadap ilmu-ilmu sosial dewasa ini maupun kenyataan sosial yang dilukiskan. Ia kritis terhadap masyarakat maju sejauh mereka ini tidak sepenuhnya memanfaatkan kemampuan belajar kebudayaan yang tersedia bagi mereka itu, melainkan membenamkan diri ke dalam sebuah pertumbuhan kompleksitas yang tak terkendali. Akan tetapi ia juga kritis terhadap pendekatan ilmiah yang tidak mampu menjelaskan paradoks rasionalisasi kemasyarakatan karena pendekatan itu membuat sistem sosial yang kompleks sebagai objek mereka hanya dari salah satu sudut pandang abstrak, tanpa memperhitungkan asal usul historis bidang objek mereka (Hardiman, 2009:11)
Menurut Habermas teori tindakan komunikatif ini memiliki tujuan yang terkait satu sama lain (McCharty, 2006:Vii): 1. Mengembangkan konsep rasionalitas
yang tidak lagi terikat pada, dan dibatasi oleh, premis-premis subjektif fi lsafat modern dan teori sosial.
2. Mengkonstruksi konsep masyarakat dua level yang mengintegrasikan dua kehidupan dan paradigma sistem.
3. Mengsketsakan, berdasarkan latar belakang diatas, teori kritis tentang modernitas yang menganalisis dan membahas patologi-patologinya dengan suatu cara yang lebih menyarankan adanya perubahan arah daripada pengabdian proyek pencerahan.
Menurut Habermas dalam Littlejohn (2008:333-334), masyarakat memiliki tiga jenis kepentingan yang masing-masing memiliki pendekatan dan rasionya masing-masing. Kepentingan pertama
adalah teknis, adalah kepentingan untuk menyediakan sumberdaya natural. Kepentingan yang kedua adalah interaksi. karena kerjasama sosial amat dibutuhkan untuk bertahan hidup, Habermas menamakannya kepentingan “praktis”. Ia mencakup kebutuhan-kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi beserta praktek-prakteknya. Kepentingan yang ketiga adalah kekuasaan. Tatanan sosial, secara alamiah cenderung pada distribusi kekuasaan, namun pada saat yang sama juga memiliki kepentingan untuk membebaskan diri dari dominasi. Kekuasaan mengarah pada distorsi terhadap komunikasi, namun dengan menjadi sadar akan adanya ideologi-ideologi yang dominan di masyarakat, suatu kelompok kemudian dapat memberdayakan dirinya untuk mengubah keadaan. Maka, kepentingan kekuasaan adalah kepentingan yang “emansipatoris”.
Metodologi
Penelitian ini dilakukan di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur. Sebelum penelitian ini dilangsungkan, peneliti melakukan prasurvei pada bulan Oktober 2012, dan dilanjutkan kembali pelakasanaan penelitian pada Agustus- November 2013.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan jenis studi kasus intrinsic case study.
Subjek penelitian adalah tokoh-tokoh yang terdapat dalam desain undangan dan masyarakat penerima undangan, tokoh tersebut diantaranya: penanggung jawab, pendamping, pengurus, pemilik hajat yang tinggal di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, studi dokumentasi Dalam studi dokumen ini yang dilakukan
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 185
adalah analisis undangan hajatan yang dibuat oleh etnis Madura di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Analisis yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (content analysis).
Sajian dan Analisis Data
a. Tahap Partisipasi Etnis Madura dalam Hajatan
Menurut Sastropoetro (1986:56) bentuk dan jenis partisipasi dapat dilihat sebagai: (1) partisipasi dengan pikiran, (2) partisipasi dengan tenaga, (3) partisipasi tenaga dan pikiran atau partisipasi aktif, (4) partisipasi dengan keahlian, (5) partisipasi dengan barang, (6) partisipasi dengan uang, (7) partisipasi dengan jasa. Berdasarkan dari tujuh bentuk dan jenis partisipasi menurut Sastropoetro, mula-mula peneliti akan mengklasifi kasikan jenis dan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh etnis Madura dalam hajatan berdasarkan temuan peneliti dilapangan. Pertama tahap perencanaan yang meliputi: (1) partisipasi dengan pikiran, (2) partisipasi dengan tenaga, (3) partisipasi dengan jasa. Tahap pelaksanaan (1) partisipasi dengan barang, (2) partisipasi dengan uang. Partisipasi dengan keahlian dan partisipasi dengan pikiran dan tenaga tidak termasuk didalam bentuk dan jenis partisipasi yang dilakukan oleh etnis Madura dalam hajatan. Karena pada temuan dilapangan tidak ditemukan partisipasi yang menggabungkan partisipasi dengan pikiran dan tenaga menjadi satu bentuk partisipasi.
1. Tahap Perencanaan HajatanTahap perencanaan merupakan bagian
awal dari rencana kegiatan hajatan, pada tahap ini pemilik hajatan mengharapkan partisipatif aktif dari pihak keluarga inti dan dari pihak masyarakat. Tahap perencanaan hajatan dimulai dengan partisipasi dengan
pikiran. Pada tahap perencanaan hajatan pemilik hajatan melibatkan partisipasi internal keluarga inti pemilik hajatan serta pihak eksternal. Pihak eksternal meliputi tokoh-tokoh terop atau tokoh yang dituakan di desa penyelenggara hajatan. Dalam tahap perencaan ini partisipasi internal adalah musyawarah menentukan hari baik dan menentukan jumlah pertisipan pada saat pelaksaan hajatan. Pada tahap perencaan, pihak eksternal mengupayakan agar hajatan dengan konsep teropan meluas, pada tahap perencaan ini juga pihak eksternal mengupayakan agar hajatan dengan konsep teropan ini menjadi ciri khusus budaya etnis Madura di wilayah Pasuruan. Dengan dilibatkannya pihak eksternal, diharapkan pula mampu meningkatkan pendapatan sumbangan pemilik hajatan.
Tahap kedua dalam perencanaan hajatan adalah partisipasi dengan tenaga. Dalam partisipasi dengan tenaga diharapkan bahwa adanya adat kegotong royongan antar warga tetap terjalin. Namun pada kasus hajatan di wilayah ini, orang-orang yang terlibat dalam gotong royong harus diminta bantuannya. Artinya bahwa pemilik hajatan harus meminta langsung kepada calon partisipan dalam hajatannya. Jika pemilik hajatan tidak meminta langsung kepada partisipan maka meskipun rumah partisipan berada di depan rumah pemilik hajatan, ia tidak akan mendatangi hajatan yang diselenggarakan.
Tahap ketiga perencanaan hajatan adalah partisipasi dengan jasa, dalam partispasi dengan jasa ditemukan bahwa hajatan ini dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian ini diantaranya adalah jasa pendistribusi undangan(Pelandang), selain pendistribusi undangan pelandang juga menerima jasa penitipan sumbangan ketika seseorang yang diundang kemungkinan tidak bisa
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
186 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
hadir, dan mata pencaharian yang lain adalah membuka peluang pekerjaan untuk juru tulis sumbangan dan pembawa cara. Pelandang, Juru tulis sumbangan, dan pembawa acara biasanya memang orang khusus yang dipercayai oleh pemilik hajatan.
2. Tahap Pelaksanaan HajatanTahap pelaksaan hajatan ini
merupakan tahap hajatan berlangsung, pada saat hajatan ini berlangsung diharapkan orang-orang yang sudah diminta bantuannya untuk berpartisipasi bisa berada pada tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Misalnya, para panitia penerima tamu, penerima tamu ini ditempatkan di area pintu masuk lokasi hajatan. Dalam pelaksaan hajatan etnis Madura yang sudah diminta dan diundang akan mengahdiri hajatan. Dalam pelaksaan hajatan etnis Madura berpartisipasi dengan menyumbang dengan uang dan menyumbang dengan barang. Menyumbang dengan uang dimaksudkan sebagai upaya etnis Madura menabung, karena pada dasarnya mereka kurang percaya dengan Bank, bagi mereka menabung di Bank itu rugi, karena tidak mendapat bunga dan menabung di Bank bisa diambil kapanpun mereka mau. Selain menyumbang dengan uang, etnis Madura juga menyumbang dengan barang, menyumbang dengan barang dimaksudkan bahwa etnis Madura mengantisipasi gejolak ekonomi. Karena pada kenyataannya sumbangan yang pernah disumbangkan harus dikembalikan dengan jumlah dan bobot yang sama. Mereka yang sudah menyumbang tidak mau tahu bahwa pada saat ini harga dipasaran melambung tinggi, yang paling penting adalah barang yang sudah disumbangkan dikembalikan dengan bobot yg sama.
b. Persepsi Masyarakat Tentang HajatanMemperbincangkan persepsi dalam
topik ini, peneliti akan melihat persepsi budaya dari masyarakat etnis Madura terkait dengan kegiatan hajatan yang dilakukan oleh mereka. Menurut Larry Samovar dan Ricard E. Porter (Mulyana,2008:214) ada enam unsur budaya yang secara langsung mempengaruhi persepsi kita berkomunikasi dengan orang dari budaya lain. Dari enam pengaruh persepsi yang dikemukakan oleh Samovar dan Porter, peneliti akan melihat dari dua unsur yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan hajatan yang dilakukan oleh etnis Madura, diantaranya adalah (1) kepercayaan, nilai, dan sikap; (2) orientasi kegiatan. Dalam konsep kepercayaan nilai dan sikap, masyarakat menganggap bahwa hajatan merupakan wadah tali silaturahmi antar warga masyarakat baik yang etnis Madura maupun yang non Madura. Selain wadah silaturahmi dan kerukunan, nyatanya bahwa etnis Madura memegang nilai bhala (teman) dan moso (musuh).
Ketika seseorang terus melakukan tanggung jawabnya dalam hajatan maka dirnya dianggap sebagai bhala, namun ketika seseorang tidak mematuhi tanggung jawabnya maka akan dianggap moso. Misalnya seseorang yang bergabung dalam kelompok terop dan terus menjalin interaksi diantara kelompok terop dan selalu menyumbang, maka seseorang akan dikategorikan sebagai bhala. Namun ketika seseorang tidak mengembalikan sumbangan dan sudah ditagih tapi tidak mengembalikan maka akan dianggap sebagai moso pada kelompok terop satu dan kelompok terop yang lain, bahkan juga bisa jadi dianggap moso ditengah masyarakat. Dalam orientasi kegiatan hajatan, masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok terop atau yang tidak bergabung
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 187
memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Orientasi kegiatan hajatan yakni: menabung uang yang dimiliki, mengenalkan diri kepada masyarakat dan menjaring massa. Menjaring massa ini terkait dengan komunikasi politik.
c. Bentuk Kesenjangan Dalam HajatanBentuk kesenjangan yang terjadi
dalam pelaksaan hajatan ini terkait sekali dengan stratifi kasi sosial seseorang yang datang dalam hajatan. ketika seseorang memiliki tingkat stratifi kasi sosial yang tinggi ditengah masyarakat etnis Madura di wilayah ini maka akan mendapatkan perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa ini biasanya dalam bentuk sajian makanan, pembedaan tempat duduk dan biasanya perlakuan pemilik hajatan terhadap tamu sengan stratifi kasi sosial tinggi akan lebih menghormati.
d. Hajatan dan Teori Tindakan Komuni-katif
Menurut Habermas (Littlejohn dan Foss, 2008:472), ia mengajarkan bahwa ketika masyarakat bertindak itu memiliki tiga minat utama, yaitu: minat pekerjaan, minat interaksi dan minat kekuasaan. Dari ketiga minat ini, etnis Madura mewujudkan dalam bentuk kegiatan hajatan yang mereka lakukan.
Pertama, minat pekerjaan terjawab dari temuan peneliti bahwa hajatan merupakan wadah pengenalan diri seseorang, ketika seseorang ini memutuskan untuk bergabung dalam teropan maka secara otomatis bahwa apa yang dilakukan olehnya merupakan jalan pembuka usaha yang sedang dijalankan menjadi banyak pelanggan. Selain itu pula keputusan seseorang bergabung dalam teropan diharapkan ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan maka akan mendapatkan pekerjaan dari relasi yang dibagun dengan tokoh terop. Karena
biasanya tokoh terop ini mengupayakan anggotanya yang mengalami kesulitan dibantu untuk keluar dari kesulitan pekerjaan.
Kedua, minat interaksi merupakan aplikasi dari bahasa dan sistem simbol dalam komunikasi. Interaksi sosial ini merupakan cara yang dibangun untuk kerjasama sosial, karena adanya kerjasama sosial inilah manusia mampu bertahan hidup, sifat minat interaksi ini adalah praktis. Kondisi interaksi ini pula yang kemudian diterapkan oleh etnis Madura dalam kegiatan hajatan, keinginan individu yang terlibat di dalam hajatan serta merta menjadikan seseorang memperluas jaringan interaksi diantara mereka. Perluasan jaringan komunikasi diantara para pelaku hajatan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang terlibat di dalam hajatan. interaksi yang dibangun antara anggota tokoh terop dan individu yang hendak bergabung pada kelompok terop diharapkan mampu membawa keuntungan bagi dirinya.
Minat ketiga adalah kekuasaan, kekuasaan ini diwujudkan oleh pelaku hajatan dengan membentuk kelompok-kelompok terop, disadari atau tidak bahwa kelompok ini mendominasi kekuasaan diwilayah ini. Secara struktural pemerintah kelompok terop tidak memiliki posisi jabatan apapun, namun secara struktural masyarakat kelompok terop memiliki struktur sosial yang tinggi. Keikutsertaan kelompok terop dalam hajatan nyatanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki background politis, sehingga kondisi demikian sangat menguntungkan bagi mereka. Dominasi kekuasaan selain terlihat dalam ranah politis, dominasi ini juga terlihat pada ranah individu (ranah privat), ini tercermin dari adanya ketidakmampuan masyarakat etnis Madura dalam menentukan
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
188 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
kemauan individu untuk datang dalam hajatan. Prilaku mendatangi hajatan hanya dimaksudkan karena tekanan dari siapa pelandang dan siapa tokoh terop dibelakangnya yang mendukung hajatan tersebut.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan hasil analisis sesuai dari rumusan masalah dalam tesis dengan judul: Peran Komunikator Dalam Ritual Hajatan (Studi Kasus Peran Tokoh Terop Dalam Hajatan Etnis Madura di Desa Karanglo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Dibentuknya grup-grup kelompok terop merupakan usaha yang dilakukan etnis Madura untuk mempererat golongan. Hajatan teropan merupakan “wadah” para tokoh terop ini bertemu dan berkumpul, dalam hajatan teropan ini terjadi kontak silaturahmi. Dibentuknya hajatan dengan konsep teropan ini dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meredam konfl ik antar masyarakat atau para kelompok terop, meskipun bahwa tidak menutup kemungkinan hajatan teropan ini juga mampu memicu konfl ik. Selain sebagai tempat silaturahmi antar kelompok terop, hajatan teropan ini sarat dengan alasan motif-motif ekonomi. Pemilik hajatan mampu mengumpulkan uang dengan total nominal dari puluhan juta bahkan hingga ratusan juta rupiah dalam waktu satu malam, besar kecilnya buwuhan yang diperoleh pemilik hajatan tergantung dari siapa pemilik hajatan, dan seberapa sering pemilik hajatan melakukan buwuh terhadap orang lain. kegiatan hajatan yang dilaksanakan oleh etnis Madura diwilayah ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan dari kelompok dominan, kelompok dominan dalam hal ini adalah para komunikator yang terlibat
dalam aktivitas hajatan. selain mendapat pengawasan dari kelompok dominan, uang menjadi alat kontrol sosial dan pengendali sosial masyarakat etnis Madura.
Peran komunikator yaitu pemilik hajatan, penanggung jawab, pengurus, pendamping, pengundang, pelandang tidak lebih hanya digunakan sebagai penarik massa untuk menyumbang. Dalam perannya, tanggung jawab yang dilakukan oleh komunikator terjadi secara tumpang tindih. Meskipun pemilik hajatan sudah menetapkan bahwa individu A sebagai pendamping, individu B sebagai pengurus dan sebagainya, namun dalam melaksanakan perannya komunikator yang ditunjuk sebagai pengurus, pendamping, pengundang justru bisa juga bertindak sebagai pelandang. Dalam peran komunikator, tanggung jawab yang lebih jelas adalah peran penanggung jawab hajatan dan peran pelandang.
Dalam menyiapkan dan merancang pesan terkait pesan hajatan, komunikator menyiapkan pesan dengan logika pesan yang digagas oleh Barbara O’Kefee. Logika pesan yang dipakai adalah rhetorical desain logic. Untuk menempatkan konteks komunikasi sebagai bentuk negosiasi. Pemilik hajatan menempatkan komunikator dalam hal ini adalah tokoh terop. Tokoh terop yang dipilih adalah orang yang memiliki kekuatan yang mampu menarik massa untuk datang berpartisipasi menyumbang. Ketika pemilik hajatan tidak punya kemampuan untuk menarik massa, maka pemilik hajat menempatkan tokoh terop yang mampu menarik massa. Sebagai konteks komunikasi, di dalam hajatan ini mereka menjalin sebuah interaksi, pada temuan penelitian ini interaksi antar orang-orang yang hadir dalam teropan bertujuan sebagai personal selling dan group selling. Sebagai medium penyampai pesan, undangan juga dimaksudkan
Adi Inggit Handoko. Peran Komunikator dalam ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 189
sebagai context redefi nition: (1) undangan itu sifatnya urgensi, (2) undangan sebagai bentuk pemaksaan pemilik hajatan terhadap calon penyumbang, (3) undangan sebagai bentuk ketidakmampuan pemilik hajatan dalam menjangkau satu persatu calon penyumbang, (4) Ketidakmampuan pemilik hajatan dalam menarik massa, (5) hegemoni pemilik hajatan terhadap masyarakat calon penyumbang, dan (6) undangan meredifi nisi profesi pemilik hajatan, undangan sebagai media promosi individu pemilik hajatan.
Dalam menyampaikan pesan, pemilik hajatan menggunakan dua media pe-nyampai pesan. (1) melalui undangan teks dan (2) melalui tatap muka secara langsung (face to face). Media undangan teks diberikan kepada calon penyumbang yang tempatnya berjauhan dengan lokasi pemilik hajatan dan media tatap muka adalah undangan dari pemilik hajatan dengan berbicara langsung kepada orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah pemilik hajatan. Undangan ini sangat diperlukan di wilayah ini, tanpa undangan mereka tidak akan berpartisipasi.
Daftar PustakaDenzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S.
2009. Handbook Of Qualitative Research edisi satu (Handbook Of Qualitative Research (1997) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, Jhon Rinaldi). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Geertz, Clifford. 2013. The Religion Of Java (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa” oleh Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, cet. Pertama oleh komunitas Bambu). Komunitas Bambu: Depok.
Faisal, Sanapiah. 2003. Format-Format Penelitian Sosial cet.6. RajaGrafi ndo
Persada: Jakarta.
Fiske, John. 2012. Introduction To Communication Studies (Diterjemahkan ke Dalam Bahasa Indonesia dengan Judul “Pengantar Ilmu Komunikasi eds.3” oleh Hapsari Dwiningtyas). Rajagrafi ndo Persada: Jakarta.
Hardiman, F. Budi. 2009. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Posmodernisme Mennurut Jurgen Habermas. Kanisius: Yogyakarta.
Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A. 2008. Theorties of Human Comunication 9th edition. Singapore: Thomson Wadsworth.
McCarthy, Thomas. 2006. Theorie des Kommunikativen Handelns, Band 1: Handlungsrationalitat und Gesellschaftliche Rationalisierung (diterj: Nurhadi dengan judul: Teori Tindakan Komunikatif: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat) Kreasi Wacana: Yogyakarta.
Mulyana, Deddy. 2008. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Remaja Rosdakarya: Bandung.
Salim, Agus. 2006. Stratifi kasi Etnik kajian mikro sosiologi interaksi etnis Jawa dan Cina. Tiara Wacana: Yogyakarta.
Sastropoetro, Santoso. 1986. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan. Penerbit Alumni: Bandung.
Yin, Robert K. 2013. Case Study Research: Design and Methods cet. 12. Diterj: M.Djauzi Mudzakir. RajaGrafi ndo Persada: Depok.
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 191
Pemikiran Harold Innis terhadap Pengembangan Ilmu Komunikasi
A. Eko SetyantoChristina Tri Hendriyani
NuryantoProgram Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
AbstractThere are many new concepts Innis contributed to the development of political economy as well as the science of communication. Donation was obtained through research Innis Innis who roam until meandered Canada, among others, about the fur trade, the development of the railway network and the trans-Pacifi c trade raw goods, to study communication, Innis found that technology will determine the development of civilization. Media Communication is not something neutral. The media is very biased against time and space (time-biased media and space-biased media). A biased media is media that focus on duration and durable. Such media are usually not practical to carry around and weighs heavy. While media bias is a media space that emphasizes mastery of space or territory. Such media are usually mild and very easy to carry so it is more practical. Replacement of the media bias of media bias media bias time into space, usually infl uenced by developments in technology. If the shared media bias that accompanies determine civilization, the technology that converts media bias also contribute to the change. In other words, technology will change communication (media) and in time will change civilization. This argument put forward Innis in his research that venture into remote-Peloso inland through in-depth interviews and record the oral history of sites visited.Keywords: Harold Innis, communications science, political economy
Pendahuluan
Kegiatan berkomunikasi adalah kegiatan yang melekat pada diri manusia. Bahkan komunikasi itu ada berbarengan dengan keberadaan manusia sebagai homo-sociocus. Oleh karena itu, komunikasi melekat pada eksisitensi manusia. Dua hal ini, manusia dan komunikasi, dapat disamakan dengan dua sisi dari sekeping mata uang. Perkembangan peradaban
manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi.
Kemampuan manusia untuk berkomunikasi semakin lama menjadi semakin rumit dan kompleks sehingga dapat menjadi pembeda antara dunia manusia dengan dunia binatang. Selanjutnya Littlejohn mengatakan:
”Communication is one of the most pervasive, important, and complex aspects of human life. The ability to
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 191-202
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
192 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
communicate on a higher level separates humans from other animals. Our daily lives are strongly affected by our own communication with others as well as by messages from unknown persons from other parts of the world and from the past. If there is a need to know about our world, surely communication deserves our careful attention”. (Littlejohn, 1996, 3).
Komunikasi yang dikembangkan oleh manusia sarat dengan berbagai simbol dan karena itu hanya dapat dicerna oleh manusia itu sendiri. Fenomena komunikasi secara serius dipelajari sejak jaman Yunani maupun Romawi kuno dalam kemampuan rhetorika. Selain di eropa, fenomena komunikasi pun dipelajari di India maupun di China. Bahkan kertas sebagai alat/media berkomunikasi ditemukan pertama kali di China sekitar tahun 105M.
Aktivitas komunikasi menjadi semakin intensif ketika ditemukannya alat mesin cetak oleh Guttenberg pada tahun 1457. Alat ini membawa revolusi dalam berkomunikasi, terutama komunikasi cetak yang mampu menebar ide dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang relatif singkat.
Pada awalnya, kegiatan komunikasi yang semakin masif berupa propaganda untuk menyiarkan agama, baik di Eropa untuk penyiaran agama Kristen maupun di Jazirah Arab untuk penyiaran agama Islam. Penemuan mesin cetak pada awalnya dipergunakan untuk mencetak buku-buku injil.
Fenomena komunikasi yang sudah dicermati sejak jaman Yunani Kuno ternyata tidak segera melahirkan kajian tersendiri yang dikenal sebagai Ilmu Komunikasi sampai akhir abad 19. Baru pada awal abad 20, fenomena komunikasi dipelajari secara serius oleh ahli-ahli politik, matematika, psikologi, linguistik dan sebagainya. Kajian-kajian mereka ini pada akhirnya melahirkan ilmu baru yaitu Ilmu Komunikasi. Kajian-kajian para ahli tersebut antara lain Harold
Lasswell (ilmu politik), Kurt Lewin (Psikologi sosial), Carl Hovland (psikolog), Paul Lazarsfeld (sosiolog) dan Harold Innis (ekonomi-politik).
Kegiatan akademik pada awal kelahiran Ilmu Komunikasi sudah menggambarkan bahwa fenomena komunikasi merupakan suatu obyek yang dapat diteliti oleh berbagai disiplin ilmu. Dengan kata lain, komunikasi bukanlah suatu disiplin ilmu. Ia hanya sekedar obyek kajian dari disiplin ilmu yang sudah ada. Pada perkembangan selanjutnya, seorang ahli yang bernama Wilbur Schramm mengemas menjadi disiplin ilmu tersendiri yang terpisah dari disiplin ilmu-ilmu lainnya.
Awal abad 20 merupakan momentum lahirnya disiplin Ilmu Komunikasi karena ada beberapa faktor yang mendorongnya. Faktor-faktor tersebut antara lain penemuan-penemuan baru dibidang sains dan tehnologi ditambah dengan adanya Perang Dunia I dan II yang menggunakan komunikasi terutama propaganda dalam strategi memenangkan perang. Selanjutnya Littlejohn mengatakan:
“Although communication has been studied since antiquity, it became an especially important topic in the 20th century. One author describes this development as a ‘revolutionary discovery’, largely caused by the rise of communications technologies such as radio, television, telephone, satellites and computer networking, along with industrialization, big business, and global politics. Clearly, communication has assumed immense importance in our time.Intense interest in the academic study of communication began after WW I, as increasing technologies and literacy made communication a topic concern. The subject was given impetus by the popular 20th century philosophy of progressivism and pragmatism, which stimulated a desire to improve society through widespread social change” (Littlejohn, 1996, 4).
Selepas Perang Dunia II, Ilmu Komunikasi berkembang pesat sejalan
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 193
dengan penemuan-penemuan mutakhir teknologi komunikasi dan komputer serta semakin berkembangnya kegiatan di bidang perdagangan/pemasaran, khususnya bidang periklanan dan public relations.
Sejalan dengan kemajuan aktivitas komunikasi, kajian-kajian di bidang komunikasi juga semakin berkembang dan semakin canggih. Namun demikian, kajian-kajian tentang formasi ketika ilmu komunikasi dibentuk, masih jarang dilakukan. Kajian-kajian dengan berbasis pendekatan biografi personal para pelopor Ilmu Komunikasi tidak banyak yang mempelajarinya. Beberapa diantaranya antara lain Everett Rogers (1994) mengkaji sejarah ilmu komunikasi dengan pendekatan biografi personal. Nuryanto (Juli, 2011) meneliti pemikiran Wilbur Schramm dalam upaya membentuk disiplin Ilmu Komunikasi dan Eko Setyanto (2012) meneliti sumbangan pemikira Harold Lasswell di bidang komunikasi. Sementara itu, masih banyak tokoh-tokoh intelektual pelopor Ilmu Komunikasi yang pemikirannya patut dikaji secara mendalam. Salah satunya adalah Harold Adams Innis (1894-1952).
Revolusi Industri di Eropa membawa dampak signifi kan bagi perkembangan peradaban manusia, terutama ketika terjadi penemuan-penemuan tehnologi komunikasi. Dampak sosial tehnologi komunikasi telah banyak diteliti, terutama dampak dari penemuan mesin cetak, telegram, telepon, fi lm dan televisi. Memasuki tahu 1970an terjadi revolusi tehnologi komunikasi dengan ditemukannya prosesor mikro komputer, televisi kabel, satelit dan tehnologi pesan elektronik yang membawa perubahan baru dalam studi komunikasi dan sudah barang tentu membawa perubahan sosial masyarakat secara sangat signifi kan. Pada
posisi inilah Innis menyerukan supaya para ahli komunikasi memperhatikan dan mencermati secara mendalam peran tehnologi komunikasi beserta dampaknya pada masyarakat luas. Innis percaya bahwa perubahan tehnologi menyebabkan perubahan masyarakat. Teorinya ini dikenal sebagai technological determinism.
Meskipun Harold Innis telah memberikan sumbangan besar dalam perkembangan Ilmu Komunikasi, tradisi keintelektualannya yang multi-disiplin belum banyak dikaji. Padahal kajian-kajian semacam ini penting untuk diketahui oleh mahasiswa komunikasi atau siapa saja yang baru belajar ilmu komunikasi agar mereka dapat memahami secara utuh tradisi intelektual para pendiri ilmu komunikasi.
Konsep-konsep yang dikembangkan Innis
a) Sejarah Canadian Pacifi c Railways (CPR).
Harold Innis menulis tesis PhD-nya tentang sejarah jaringan kereta api Kanada di bagian Pasifi k Canadian Pacifi c Railway (CPR). Penyelesaian jaringan kereta api benua pertama tahun 1885 itu telah menjadi saat yang menentukan dalam sejarah Kanada. Disertasi ini akhirnya diterbitkan sebagai buku pada tahun 1923, dapat dilihat sebagai upaya awal untuk mendokumentasikan pentingnya kereta api itu dari titik seorang sejarawan ekonomi terpandang. Kajiannya menggunakan analisa statistik canggih untuk mendukung argumen. Innis menyatakan bahwa proyek konstruksi ini sulit dan mahal ditopang oleh kekhawatiran aneksasi Amerika dari Kanada Barat.
Innis berpendapat bahwa “sejarah Canadian Pacifi c Railroad terutama adalah sejarah penyebaran peradaban Barat atas bagian utara benua Amerika
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
194 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Utara”. Sebagai catatan pakar Robert Babe menyatakan bahwa, kereta api membawa industrialisasi, mengangkut pasokan batubara dan bangunan ke tempat manufaktur. Itu juga jenis media komunikasi yang berkontribusi terhadap penyebaran peradaban Eropa.
Pakar Arthur Kroker berpendapat bahwa studi Innis tentang the Canadian Pacifi c Railway adalah yang pertama di mana ia berusaha untuk menunjukkan bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang eksternal untuk Kanada, tetapi sebaliknya, adalah kondisi yang diperlukan dan konsekuensi logis dari eksistensi Kanada.
b) Teori StaplesInnis mengembangkan teori staples
(stok bahan mentah), dan metode penyelidikan intelektual, melalui kontribusi besar untuk sejarah ekonomi selama tahun 1920-an dan 1930-an. Pada saat itu, Kanada terutama mengekspor komoditas mentah ke Eropa. Innis berpendapat bahwa pencarian dan eksploitasi komoditas mentah tertentu (atau “staples”) seperti ikan, bulu, kayu, produk pertanian dan mineral, menciptakan perekonomian daerah di Kanada. Ia menggambarkan hubungan antara wilayah Kanada sebagai salah satu “jantung” untuk “hinterland.” Menurut Innis, jenis tertentu hubungan ekonomi dan politik tumbuh dari dominasi Toronto-Montreal koridor perkotaan selama pinggiran timur, utara dan barat. Pinggiran, atau pedalaman, didominasi oleh inti, atau jantung.
Karena jantung itu tergantung pada pencarian dan akumulasi staples (yang terletak di pedalaman) untuk mengabadikan ekonomi, ia berusaha untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi dan politik dengan memanfaatkan pedalaman. Sebagai contoh, Innis mengklaim bahwa sebagian besar perdagangan bulu
ditentukan batas Kanada. Pentingnya bulu sebagai produk pokok mengakibatkan, terutama, di bagian utara benua yang tersisa Inggris. Meskipun Kanada telah menyatakan kemerdekaannya dari kekuasaan kolonial, itu tetap tergantung pada Inggris untuk perdagangan. Perdangan berdasarakan bahan mentah adalah perdagangan yang rentan. Selain dipengaruhi fl uktuasi permintaan dan penawaran, ia juga diperngaruhi oleh kondisi geografi dan alam. Maka untuk menjamin ekspor staples ini dimungkinkan melalui perbaikan jaringan transportasi yang mencakup sungai, dan kemudian kereta api.
c) “Dirt” Research (Penelitian Lapangan)Pada tahun 1920, Innis bergabung
dengan departemen ekonomi politik di Universitas Toronto. Dia ditugaskan untuk mengajar mata kuliah perdagangan, sejarah ekonomi dan teori ekonomi. Dia memutuskan untuk fokus penelitian ilmiah tentang sejarah ekonomi Kanada, subjek yang sangat diabaikan, dan ia meneliti perdagangan bulu sebagai ranah pertama studinya.
Perdagangan bulu telah membawa pedagang Perancis dan Inggris ke Kanada, memotivasi mereka untuk melakukan perjalanan barat sepanjang saling danau dan sungai sistem benua ke pantai Pasifi k. Innis menyadari bahwa ia tidak akan hanya perlu mencari dokumen arsip untuk memahami sejarah perdagangan bulu, tetapi juga harus melakukan perjalanan negara sendiri mengumpulkan massa informasi langsung dan mengumpulkan apa yang disebutnya “kotoran” pengalaman.
Dengan demikian, Innis bepergian secara luas dimulai pada musim panas 1924. Ia dan temannya menyusuri Sungai Perdamaian dengan perahu sampai ke
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 195
Danau Athabasca; kemudian menyusuri Sungai Slave ke Great Slave Lake. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri Mackenzie, sungai terpanjang Kanada, ke Samudra Arktik. Selama perjalanannya, Innis tidak hanya meneliti perdagangan bulu namun juga mengumpulkan informasi tentang produk pokok lainnya seperti kayu, pulp dan kertas , mineral, biji-bijian dan ikan. Di mana-mana Innis pergi, metode penelitiannya adalah sama. Ia mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan produksi produk pokok dan mendengarkan cerita mereka.
d) Perdagangan Bulu di KanadaKetertarikan Harold Innis pada
hubungan antara negara induk dan koloni dikembangkan dalam studi klasiknya, The Fur Trade di Kanada: Sebuah Pengantar Sejarah Ekonomi Kanada (1930). Buku ini menceritakan perdagangan bulu dari awal abad ke-16 untuk tahun 1920-an. Buku ini berfokus pada petualang orang Eropa yang menjelajahi padang gurun Kanada. Ia menyimpulkan sebagian besar perdagangan bulu menentukan batas-batas Kanada.
The Fur Trade di Kanada juga menggambarkan interaksi budaya di antara tiga kelompok orang: orang Eropa di pusat-pusat metropolitan; pemukim Eropa kolonial yang melihat bulu sebagai barang pokok yang dapat diekspor untuk membayar barang-barang manufaktur, dan masyarakat Bangsa Pertama yang memperdagangkan bulu untuk barang-barang industri seperti pot logam, pisau, senjata, dan minuman keras. Innis menggambarkan peran sentral masyarakat bangsa-bangsa pertama dimainkan pengembangan perdagangan bulu. Tanpa teknik berburu terampil mereka, pengetahuan tentang wilayah dan alat-alat canggih seperti sepatu salju, kereta salju dan kano birch-kulit kayu, perdagangan
bulu tidak akan ada. Tidak seperti banyak sejarawan yang melihat sejarah Kanada sebagai diawali dengan kedatangan orang Eropa, Innis menekankan kontribusi budaya dan ekonomi masyarakat Bangsa Pertama.
The Fur Trade di Kanada menyimpul-kan dengan menyatakan bahwa sejarah ekonomi Kanada dapat dipahami dengan memeriksa bagaimana satu produk pokok (bulu) memberi jalan perdagangan kayu, dan kemudian gandum serta mineral. Ketergantungan pada staples menyebabkan Kanada secara ekonomi tergantung pada banyak negara industri maju dan terjadi pergeseran dari satu pokok ke pokok yang lain yang pada gilirannya menyebabkan gangguan dalam kehidupan ekonomi negara.
Teori komunikasi yang dikembangkan
Studi Innis melalui penjelajahan sungai dan danau akhirnya memicu minatnya dalam hubungan ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan system transportasi dan komunikasi.
Selama tahun 1940-an, Innis juga mulai mempelajari industri pulp dan kertas, industri penting pada perekonomian Kanada. Penulis biografi Paul Heyer menulis bahwa Innis melalui studi pulp dan kertas akhirnya menenuju penelitian tentang koran dan jurnalistik. Dengan kata lain, dari melihat industri berbasis sumber daya alam yang mengalihkan perhatian ke industri budaya informasi.
Salah satu kontribusi utama Innis untuk studi komunikasi adalah untuk menerapkan dimensi waktu dan ruang untuk berbagai media. Ia membagi media kedalam dua kategori yakni media yang diikat waktu (time binding media) dan media yang diikat ruang (space binding media). Time binding media adalah tahan lama. Media semacam ini termasuk tanah
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
196 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
liat atau batu tablet. Space binding media umurnya lebih singkat. Mereka termasuk media modern seperti radio, televisi, dan surat kabar sirkulasi massa.
Fokus utama studi Innis ‘adalah sejarah sosial media komunikasi; ia percaya bahwa stabilitas relatif budaya tergantung pada keseimbangan dan proporsi media mereka. Untuk mengerti apa yang dimaksud Innis, ada tiga pertanyaan utama yang perlu dijawab:1. Bagaimana teknologi komunikasi
tertentu beroperasi?2. Asumsi apa yang mereka ambil dari
dan memberikan kontribusi kepada masyarakat?
3. Bentuk kekuasaan seperti apa yang mereka mendorong?
Bagi Innis, kunci untuk perubahan sosial ditemukan dalam pengembangan media komunikasi. Dia mengklaim bahwa setiap media mewujudkan bias dalam hal organisasi dan kontrol informasi. Setiap kerajaan atau masyarakat umum-nya berkaitan dengan durasi waktu ke waktu dan ekstensi dalam ruang.Media Waktu-bias, seperti batu dan tanah liat, tahan lama dan berat. Karena mereka sulit untuk bergerak, mereka tidak mendorong perluasan wilayah; Namun, karena mereka memiliki umur panjang, mereka mendorong perluasan kerajaan dari waktu ke waktu. Innis terkait media ini dengan adat, suci, dan moral. Media Waktu-bias memfasilitasi pengembangan hierarki sosial, seperti archetypally dicontohkan oleh Mesir kuno. Untuk Innis, pidato adalah media waktu-bias.Space-bias media yang ringan dan portabel; mereka dapat diangkut jarak besar. Mereka terkait dengan masyarakat sekuler dan teritorial; mereka memfasilitasi perluasan kerajaan atas ruang. Contohnya adalah kertas, ia mudah diangkut, namun memiliki umur yang relative pendek.
Bagi Innis, organisasi kerajaan tampak nya mengikuti dua model utama. Model pertama adalah militeristik dan peduli dengan penaklukan ruang. Model kedua adalah agama dan peduli dengan penaklukan waktu. Secara Relatif, media yang mendukung menaklukkan militer-ruang biasanya lebih ringan, sehingga kendala jarak yang jauh bisa berkurang. Media yang mendukung kerajaan teokratis memiliki daya tahan relatif sebagai karakteristik utamanya sehingga mereka dapat mendukung konsep hidup yang kekal.
Innis memeriksa naik turunnya kerajaan kuno sebagai cara melacak efek media komunikasi. Dia memandang peran media yang menyebabkan pertumbuhan kerajaan; namun juga sekaligus mempercepat keruntuhan kerajaan itu. Dia mencoba untuk menunjukkan bahwa ‘bias’ Media terhadap waktu atau ruang yang terkena timbal balik yang kompleks yang diperlukan untuk mempertahankan kerajaan. Timbal balik ini termasuk kemitraan antara pengetahuan (dan ide-ide) yang diperlukan untuk membuat dan memelihara sebuah kerajaan, dan kekuatan (atau kekuatan) yang diperlukan untuk memperluas dan mempertahankannya. Untuk Innis, interaksi antara pengetahuan dan kekuasaan selalu merupakan faktor krusial dalam pemahaman kerajaan. Innis berpendapat bahwa keseimbangan antara kata yang diucapkan dan tulisan berkontribusi terhadap berkembangnya Kerajaan Yunani kuno pada zaman Plato. Keseimbangan antara time-biased media melalui kata-kata dan space biased media melalui tulisan kadang-kadang diperlukan. Menurut Innis, tradisi ucapan dapat menjadi dasar ke tradisi tulisan sebagaimana ditunjukkan beralihanya peradaban Yunani ke Imperium Romawi. Pendek kata menurut Innis, suasana permusuhan antara time-biased media
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 197
dan space biased media, dimana salah satu tradisi meminggirkan yang lain, mengarah pada penciptaan monopoli pengetahuan.
Peradaban barat hanya bisa diselamatkan, menurut Innis, dengan memulihkan keseimbangan antara ruang dan waktu. Baginya, itu berarti menghidupkan kembali tradisi lisan dalam universitas dan membebaskan institusi pendidikan tinggi dari tekanan politik dan komersial. Dalam esainya, A Plea untuk Time, ia menyarankan bahwa dialog yang tulus dalam universitas dapat menghasilkan pemikiran yang kritis yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan antara kekuasaan dan pengetahuan. Kemudian, universitas bisa mengumpulkan keberanian untuk mengkritisi monopoli yang selalu membahayakan peradaban.
Orang-orang yang mengendalikan pengetahuan melalui media yang dominan dari masyarakat tertentu (baik itu ilmiah, pemerintah, elit agama atau profesional) juga mengendalikan realitas, dalam arti bahwa mereka berada dalam posisi untuk menentukan apa pengetahuan yang sah. Dengan cara ini, monopoli pengetahuan mendorong senralisasi kekuasaan.
Bias Komunikasi
Dalam bukunya “The Bias Commu-nication” Innis menganggap penting nya komunikasi untuk peningkat an maupun penurunan sifat budaya. Dia menetapkan dialektika antara media dengan bias waktu dan orang-orang dengan bias ruang.
Menurut karakteristik media komunikasi mungkin lebih cocok untuk transportasi, atau untuk penyebaran pengetahuan dari waktu ke waktu, lebih daripada ruang, terutama jika media tersebut berat dan tahan lama dan tidak cocok untuk transportasi, atau untuk penyebaran pengetahuan lebih ruang
daripada dari waktu ke waktu, terutama jika media ringan dan mudah diangkut.Dia menyimpulkan bahwa “penekanan relatif tepat waktu atau ruang akan menyiratkan bias signifi kansi budaya di mana ia tertanam. Empires yang, dengan kata lain, ditandai dengan media yang mereka gunakan secara efektif, sebagian karena itulah bagaimana orang lain datang untuk mengetahui prestasi mereka. Kemudian ia menunjukkan bagaimana bias ini mempengaruhi naik turunnya kerajaan dari Mesir, Sumeria dan Babilonia, pada abad ke-20 Amerika Utara dan kerajaan-kerajaan Eropa.
Jika kita membandingkan dengan perkamen papirus atau kertas, misalnya, berat badan bukanlah benar-benar unsur yang menentukan. Hal ini lebih berguna untuk memikirkan bias media yang terkait dengan kemampuan pesan untuk bertahan hidup transmisi dan berdampak atas ruang atau dari waktu ke waktu. Ini bukan beratnya batu yang selalu membuat media-waktu bias, melainkan kemampuannya untuk bertahan hidup elemen dan bencana alam sehingga mungkin masih berkomunikasi abad pesan atau ribuan tahun kemudian. Piramida, kuil, jembatan, dan katedral dunia masih dapat berkomunikasi sesuatu makna penting mereka kepada kami hari ini, kalau saja kita tahu bagaimana untuk memecahkan kode kerajaan-gedung mereka. Pesan-pesan yang telah berlangsung cenderung bias pandangan kita tentang sejarah kerajaan:Menulis di lapangan tanah liat dan batu telah diawetkan lebih efektif dibandingkan pada papirus. Karena komoditas tahan lama menekankan waktu dan kontinuitas, studi peradaban seperti Toynbee cenderung memiliki bias terhadap agama dan untuk menunjukkan pengabaian masalah ruang, terutama administrasi dan hukum.
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
198 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Kita tahu tentang sejarah kerajaan sebagian besar dari dokumen-waktu bias yang selamat. Innis menunjukkan bahwa media diadopsi oleh peradaban tertentu akan membentuk “karakter pengetahuan” ditularkan oleh budaya itu, tidak hanya di awal pengiriman, tetapi juga dalam penerimaan akhirnya kami.Dalam ide ini adalah asal McLuhan “medium adalah pesan.” Analisis Innis ‘dapat menjadi kompleks dan multi-dimensi karena ia memahami bahwa umur panjang kekaisaran tergantung pada kemampuan mereka untuk memperpanjang sendiri selama waktu dan ruang. Hal ini sering pertanyaan keseimbangan. Misalnya, ia mengklaim bahwa peradaban Mesir “tampaknya telah sangat dipengaruhi oleh karakter. Pemanfaatan Nil banjir periodik tergantung pada kontrol terpadu dari otoritas mutlak.” Penemuan dan adopsi kalender dengan kepastian tanggal untuk festival keagamaan [sidereal kalender diukur waktu oleh pergerakan bintang-bintang] memfasilitasi pembentukan sebuah monarki absolut dan pengenaan otoritas Osiris dan Ra, sungai Nil dan Sun, di Mesir atas. Sukses monarki dalam memperoleh kontrol atas Mesir dalam hal ruang mengharuskan perhatian dengan masalah kontinuitas dari waktu ke waktu. Penemuan kalender menjadi cara untuk memperpanjang sebuah kerajaan atas waktu dan ruang.
Bagian ini menggambarkan apa yang McLuhan sebut sebagai Innis ‘”mosaik”, yakni pendekatan untuk mengembangkan ide-idenya. Unsur terkait disandingkan, meninggalkan kesenjangan yang membutuhkan pembaca untuk membuat koneksi. Hasilnya adalah sebuah “interface” - “interaksi zat dalam iritasi saling baik,” menurut McLuhan. “Ini adalah bentuk alami dari percakapan atau dialog ketimbang wacana tertulis. Dalam penulisan, kecenderungannya adalah untuk mengisolasi aspek beberapa materi
dan mengarahkan perhatian pada aspek yang stabil. Dalam dialog ada interaksi sama alami beberapa aspek hal apapun. ini interaksi aspek dapat menghasilkan wawasan atau penemuan.
Berulang-ulang, Innis menekankan kebutuhan kesinambungan dengan ke-butuhan untuk mengklaim wilayah, ke-seimbangan kekhawatiran pusat perusahaan bangunan kerajaan, dan secara signifi kan ditentukan oleh media komunikasi: “Monopoli pengetahuan yang berpusat di sekitar batu dan hieroglif terkena persaingan dari papirus sebagai media baru dan lebih efi sien “. Hal ini benar-benar “monopoli pengetahuan” yang dipertaruhkan dalam umur panjang kerajaan. Media baru mengancam untuk menggantikan monopoli sebelumnya pengetahuan, kecuali media-media tersebut dapat mendaftarkan diri dalam pelayanan struktur kekuasaan sebelumnya. Jika imam dapat memperoleh monopoli atas papirus dan menulis, maka mereka akan mendapatkan kekuasaan relatif terhadap raja yang tergantung pada monumen batu. Batas-batas pergeseran kerajaan, meluas dan kontraktor. Pergeseran persepsi mengubah “pengetahuan,” apa yang di klaim kekuasaan perlu diketahui. Kesetiaan baru terbentuk dan monopoli baru mulai dibuat.
Dalam waktu sekarang ini, kita telah menyaksikan pergeseran monopoli seperti dalam penyampaian berita kepada massa dari koran radio televisi ke internet. Setiap media memiliki bias, bias yang berubah dalam kaitannya dengan pentingnya orang lain dalam kesadaran budaya. Media, menurut Innis, saling terkait dalam dampaknya terhadap kelangsungan hidup kerajaan.
Budaya-budaya yang dibuat kuat melalui mantan monopoli pengetahuan mereka berdasarkan pada fi lm, cetak, atau televisi menjadi rentan terhadap
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 199
serangan dari budaya yang memanfaatkan teknologi komunikasi baru. Dalam Fuzzy Logic, Matthew Friedman menceritakan bagaimana EZLN - gerakan Zapatista revolusioner Chiapas, Meksiko - menggunakan website untuk melawan propaganda negatif dari pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat yang berusaha mendistorsi sifat revolusi kerakyatan ini
Innis sering kembali ke drama berkembang bahasa sebagai sarana penting komunikasi. “Sebuah alfabet fl eksibel disukai pertumbuhan perdagangan, pengembangan kota-kota perdagangan Fenisia, dan munculnya negara-negara yang lebih kecil tergantung pada bahasa yang berbeda”. Tuntutan pidato ditampung ketika vokal ditambahkan ke skrip yang ditulis oleh orang-orang Yunani. Tak pelak, bagaimanapun, “dampak menulis dan pencetakan pada peradaban modern meningkatkan kesulitan memahami peradaban yang didasarkan pada tradisi lisan.
Akhir Karier
Pada tahun 1940, Harold Innis mencapai puncak pengaruhnya di dua lingkup yaitu akademisi dan masyarakat Kanada. Pada tahun 1941, ia membantu mendirikan Asosiasi Sejarah Ekonomi dan Jurnal Sejarah Ekonomi. Dia kemudian menjadi presiden kedua dari asosiasi ini. Innis memainkan peran sentral dalam mendirikan dua sumber penting bagi pendanaan penelitian akademik yaitu the Canadian Social Research Council (1940) dan Humanities Research Council of Canada (1944).
Pada tahun 1944, University of New Brunswick memberi Innis gelar kehormatan, seperti yang dilakukan almamaternya, Universitas McMaster. Université Laval, University of Manitoba dan University of Glasgow juga menganugerahkan gelar
kehormatan direntang 1947-1948. Pada 1945, Innis menghabiskan hampir satu bulan di Uni Soviet di mana dia telah diundang untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-220 menandai berdirinya Akademi negara of Sciences. Perjalanan Innis ke Moskow dan Leningrad terjadi sesaat sebelum persaingan AS-Soviet yang menyebabkan permusuhan Perang Dingin. Ia melihat Soviet sebagai penyeimbang menstabilkan penekanan dari Amerika tentang komersialisme, individu dan perubahan yang konstan.
Pada tahun 1946, Innis terpilih sebagai presiden Royal Society of Canada. Pada tahun 1947, Innis diangkat Universitas dekan Toronto studi pascasarjana. Pada tahun 1948, ia menyampaikan kuliah di University of London dan Nottingham University. Dia juga memberi kuliah di Oxford, kemudian catatan kuliahnya diterbitkan dalam bukunya Empire and Communication. Pada tahun 1949, Innis diangkat sebagai komisaris di Royal Commission pemerintah federal Transportasi, posisi yang melibatkan perjalanan yang luas pada saat kesehatannya mulai memburuk. Pada dekade terakhir karirnya selama dia bekerja, studi komunikasi adalah waktu yang menyenangkan bagi Innis. Dia boleh dikatakan adalah akademis terisolasi karena rekan-rekannya di bidang ekonomi tidak bisa mengikuti jalan pikirannya. Membayangkan pun masih sulit, bagaimana hubungan perdagangan bahan mentah dengan komunkasi.
Innis tutup usia pada tahun 1952 akibat kanker prostat beberapa hari setelah merayakan ulang tahunnya ke 58. Ia meninggalkan seorang isteri dan empat anak. Namanya kemudian diabadikan dalam bentuk Innis College di Universitas Toronto, dan Innis Library di Universitas McMaster.
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
200 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Kesimpulan
Pembentukan disiplin Ilmu Komunikasi pada awalnya dipelopori oleh para pakar ilmu social yang berlatar belakang dari berbagai bidang ilmu antara lain ilmu politik, psikologi, matematika, sastra, sosiologi dan ekonomi-politik. Maka pada perkembangan berikutnya Ilmu Komunikasi sebagai disiplin ilmu yang utuh cenderung bersifat ekletik dan multi-disipliner. Ilmu ekonomi-politik memberi sumbangan besar terhadap lahirnya Ilmu Komunikasi melalui pemikiran Harold Innis yang juga seorang professor ilmu ekonomi-politik di UniversitasToronto. Walaupun pemikiran Innis mempunyai kontribusi besar terhadap pembentukan Ilmu Komunikasi terutama melalui teori technological determinism, peran Innis ini masih jarang dikaji.
Ada banyak konsep-konsep baru yang disumbangkan Innis terhadap pengembang-an ilmu ekonomi politik dan juga ilmu komunikasi. Sumbangan itu diperoleh Innis melalui penelitian Innis yang menjelajah sampai kepedalaman Kanada antara lain tentang perdagangan bulu, pengembangan jaringan kereta api trans pasifi k dan perdagangan barang-barang mentah,
Untuk Kajian komunikasi, Innis menemukan bahwa tehnologi sangat menentukan perkembangan peradaban. Media Komunikasi bukanlah sesuatu yang netral. Media sangat bias terhadap waktu dan ruang (time-biased media and space-biased media). Media yang bias waktu adalah media yang menitikberatkan pada durasi waktu dan tahan lama. Media semacam ini biasanya tidak praktis untuk dibawa-bawa dan berbobot berat. Sedangkan media yang bias ruang adalah media yang mementingkan penguasaan ruang atau territorial. Media semacam ini biasanya ringan dan sangat mudah di bawa sehingga lebih praktis.
Penggantian terhadap bias media dari
media yang bias waktu menjadi media yang bias ruang, biasanya dipengaruhi oleh perkembangan tehnologi. Jika media bersama bias yang menyertai menentukan peradaban, maka tehnologi yang merubah bias media juga berperan terhadap perubahan itu. Dengan kata lain, tehnologi akan merubah komunikasi (media) dan pada saatnya akan merubah peradaban. Argumen ini dikemukakan Innis dalam penelitiannya yang menjelajah ke pelosok-peloso pedalaman melalui wawancara mendalam dan mencatat oral history dari lokasi yang dikunjungi.
Daftar PustakaAnonim, Defi nition Personality, dalam
http://dict.die.net/personality/personality
Gendlin, Eugene T, A Theory of Personality Change, http://www.focusing.org/personality_change.html#Personality%20Theory%20and%20Personality%20Change.
Harold Adams Innis (1894-1952). http://www.collectionscanada.gc.ca/innis-mcluhan/030003-1000-e.html
Harold Adams Innis: The Bias of Communications & Monopolies of Power. http://www.media-studies.ca/articles/innis.htm
Harold Innis. http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Innis
Heyer, Paul. (2003). Harold Innis. Lanham-Maryland: Rowman & Littlefi eld Publishers
Huberman, A Michael dan Miles Mattew B. (2009). “Manajemen Data dan Metode Analisis”, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Key Concepts. http://www.col lec t ionscanada.gc .ca/innis -mcluhan/030003-1010-e.html
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 201
Littlejohn, Stephen W. (1996). Theories of Human Communication, fi fth edition, Belmon: Wadsworth.
Monopolies of Knowledge. http://www.collectionscanada.gc.ca/innis-mcluhan/030003-1040-e.html
Nuryanto. (2011). Ilmu Komunikasi Dalam Konstruksi Pemikiran Wilbur Schramm, Laporan Penelitian FISIP UNS, tidak diterbitkan.
Nuryanto. (Juli 2011). “Ilmu Komunikasi Dalam Konstruksi Pemikiran Wilbur Schramm”. Jurnal Komunikasi Massa. (4), 2.
Revolutions in Communications Technology. http://www.col lec t ionscanada.gc .ca/innis -mcluhan/030003-1050-e.html
Rogers, Everett M. (1994). A History of Communication Study: A Biographical Approach, Canada: The Free Press.
Smith, Louis M. (2009), ”Metode Biografi s” dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Staples Theory. http://www.col lec t ionscanada.gc .ca/innis -mcluhan/030003-1020-e.html
Time- and Space-Bias. http://www.col lec t ionscanada.gc .ca/innis -mcluhan/030003-1030-e.html
Yoseph, Iyus, Hand-out Perkuliahan Psikologi, Yayasan Persatuan Perawat Nasional Indonesia – Akademi Keperawatan PPNI Jawa Barat, tanpa tahun.
A. Eko Setyanto, dkk. Pemikiran Harold Innis ...
202 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 203
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 203-214
Film, Feminisme, dan Budaya: Kajian Feminisme Pada Karakter M dalam Serial James Bond
Dewanto Putra FajarJurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya Malang
Abstract Feminism as a social movement emerged as an effort to obtain equal rights for women, especially in many areas, including the social and political fi eld. Until now, the feminism movement has been getting a lot of opposition from groups who think negatively about the purpose of that movement. Interestingly, mass media give a relatively large attention about that movement by displaying the discourses of feminism on many occasions, including in the movies. James Bond series is one movie that carries messages about feminism, which is shown through the M character. Since 1995, M is no longer played by male actors, but played by a female actor. This situation indicates the emergence of feminist discourse and thinking on the James Bond movie series, which has been always considered to highlight the male dominance. This article seeks to discuss the construction of the M and the discourse of feminism that appears. Key words: Feminism, Constructionism, Mass Media, Movies, Fictional Character, James
Bond.
Pendahuluan
Kajian tentang feminisme merupakan kajian yang relatif menarik untuk diamati, karena merupakan kajian yang seringkali menuai kontroversi dari masyarakat. Ironisnya, kajian tersebut seringkali menjadi pesan-pesan dalam media massa termasuk fi lm. Hal itu menjadikan pesan-pesan feminisme dalam fi lm menjadi wacana dalam masyarakat, sehingga kemungkinan besar membawa perubahan pada masyarakat atau setidaknya dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Karena itu pesan-pesan feminisme dalam fi lm berhubungan dengan peran dari
karakter-karakter (tokoh dalam fi lm) perempuan yang muncul dalam fi lm tersebut.
Keadaan demikian menjadikan karakter-karakter perempuan dalam fi lm bisa digambarkan dalam banyak peran dan fungsi tertentu yang menunjukkan bahwa perempuan bisa sejajar dengan laki-laki. Hal yang sama juga terjadi dalam fi lm-fi lm James Bond, pada tujuh fi lm terakhir, yang ditunjukkan oleh karakter M perempuan. Karakter tersebut merupakan karakter perempuan yang muncul secara dominan dan konsisten dalam semua fi lm-fi lm James Bond mulai tahun 1995 hingga 2012.
Karakter M perempuan yang
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
204 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
diperankan oleh aktris asal Inggris, Judi Dench, menjadi satu tokoh kunci yang berpengaruh dalam serial tersebut, karena memerankan pemimpin tertinggi MI6 dan 00 Section, yang selama ini dikenal sebagai divisi agen rahasia dengan tugas-tugas khusus.
MI6 (Military Intelligent Section 6) atau SIS (Secret Intelligent Sevice) merupakan dinas intelejen Inggris dengan yurisdiksi pada semua aktivitas intelejen di luar negeri. James Bond, pada semua novel dan fi lm, diceritakan bekerja sebagai agen rahasia dari MI6. 00 Section merupakan divisi fi ktif dari MI6, yang hanya ada dalam novel dan fi lm James Bond. Divisi ini beranggotakan para agen rahasia dengan tugas beberda dengan agen rahasia biasa. Semua agen dalam divisi tersebut diberi kode angka dengan awalan 00, serta memiliki sertifi kasi License to Kill (izin membunuh). Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah agen 00 pada divisi tersebut, beberapa penulis, termasuk Ian Fleming sendiri, menyatakan mereka hanya berjumlah sembilan orang, mulai dari agen 001 hingga 009, namun beberapa penulis lainnya menyatakan lebih dari itu.
Sebagai pimpinan MI6, M, menampilkan karakter yang tegas, tangguh, serta memiliki kemampuan luar biasa untuk menggerakkan semua potensi dari MI6, terutama para agen 00, untuk menjalankan tugas rahasia, bahkan mungkin juga mematikan. M tidak segan-segan memaksa semua agen rahasia berjalan menuju misi berbahaya, bahkan jika para agennya harus tewas menjalankan tugas darinya. Menariknya, semua agen rahasia mematuhi perintahnya, tanpa banyak bertanya.
Keunikan, karakter M terletak pada penggambaran satu sosok perempuan yang memiliki kemampuan sama dengan karakter laki-laki yang juga muncul dalam
serial tersebut. Pada beberapa situasi, M justru memiliki kemampuan lebih tinggi, keberanian lebih baik, serta mengambil keputusan lebih logis dibandingkan dengan karakter laki-laki. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perempuan bisa memiliki kemampuan memimpin lebih baik daripada laki-laki, bahkan mengendalikan karakter lain, yang kebanyakan laki-laki.
Keadaan tersebut menjadikan konstruksi karakter M perempuan rupanya mendobrak fakta, dan nilai-nilai yang dibawa oleh fi lm-fi lm James Bond selama sekitar 35 tahun sebelumnya. Karakter M perempuan menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya dipandang sebagai ‘tempelan’ atau bagian dari objektifi kasi seksual semata, namun lebih sebagai satu karakter yang berpengaruh besar pada karakter lainnya terutama pada sisi birokratis, serta kemampuan mendominasi terhadap karakter lainnya.
Hal itu menunjukkan indikasi penting bahwa fi lm-fi lm James Bond yang notabene selalu dianggap sebagai fi lm ‘laki-laki’, karena menampilkan adegan-adegan aksi serta pertarungan yang seru, mulai memberikan perhatian pada kemampuan dan ketangguhan perempuan yang secara tidak langsung direpresentasikan pada banyak sosok perempuan, termasuk M. Karena itu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sosok M dikonstruksikan, diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang wacana tentang feminisme yang secara inplisit muncul pada fi lm-fi lm James Bond, setidaknya selama hampir sekitar dua dekade terakhir.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka artikel ini setidaknya berusaha men-jawab dua pertanyaan penting. Pertama, bagaimana karakter M perempuan
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 205
dikonstruksikan pada fi lm-fi lm James Bond?. Kedua, bagaimana media massa membawa wacana tentang feminisme, dihubungkan dengan konstruksi karakter M perempuan, serta konteks sosial yang ada?
Dengan demikian, artikel ini diharapkan bisa memberikan gambaran jelas tantang kajian feminisme dalam media massa, terutama pada karakter M perempuan yang muncul dalam serial James Bond. Selain itu, artikel ini juga bertujuan menunjukkan bahwa media massa, terutama fi lm, berperan pada upaya menyebarluaskan wacana tentang feminisme dan budaya kepada masyarakat.
Konstrusi Karakter M
Upaya memahami konstruksi karakter M perempuan berhubungan dengan pemikiran dan pandangan dua orang ilmuwan dan fi losof besar, yaitu Plato dan Vladimir Proop. Keduanya berada pada satu posisi yang sama ketika membahas peran serta fungsi suatu individu. Bedanya, Plato memfokuskan pemikirannya dalam membagi peran individu sebagai warga negara, sedangkan Proop memberikan pandangan tentang peran individu sebagai sebuah karakter dalam suatu karya fi ksi. Plato berpendapat bahwa warga negara dibagi menjadi beberapa kedudukan, salah satunya fi losof-raja (Getachew, 2008: 53-54).
Pandangan tesrebut menunjukkan dominasi posisi sosial tersebut terhadap posisi sosial yang lain, sehingga memunculkan perbedaan status sosial dan kedudukan sosial di masyarakat luas dalam suatu negara, atau setidaknya dalam suatu organisasi. Pemikiran dan pandangan Plato menunjukkan bahwa posisi sebagai fi lusuf-raja dikelilingi oleh para pengwal yang lahir untuk dilatih menjadi pengawal bagi raja tersebut,
dengan latihan yang keras dan ketat (Taylor, 2011: 20). Singkatnya kelompok fi lusuf-raja bisa menggerakkan semua pengawal dan semua potensi yang dimiliki demi kepentingan fi lusuf-raja itu sendiri, bahkan jika ia harus mengorbankan semua pengawalnya itu.
Sifat dan ciri-ciri fi losof-raja dalam karakter M muncul pertama kali pada adegan ketika ia menunjukkan sikap sarkastisnya ketika, kepala staf MI6, Bill Tanner, mengatakan bahwa M sebagai sosok ‘ratu yang jahat’ dalam fi lm “Goldeneye” (1995). Dialog yang muncul pada adegan tersebut menunjukkan sikap M yang tenang namun tampak sedikit jengkel ketika menerima pandangan sinis dari bawahannya tersebut.
Tanner: “Seems your hunch was right, 007. It’s too bad the Evil Queen of Numbers wouldn’t let you play it...” (“Sepertinya kau benar, 007, Buruk sekali Ratu Angka yang Jahat membiarkanmu memainkannya.”)M: “You were saying?” (“Apa yang sudah kau katakan?”)Tanner: “No, no, I was just...” (“Tidak, tidak, aku hanya ...”)M: “Good, because if I want sarcasm, Mr Tanner, I’ll talk to my children, thank you very much.” (M agak marah ketika dipanggil dengan sebutan itu). (“Bagus, karena jika aku ingin bertindak kasar, Mr Tanner, aku akan katakan pada anak-anakku terima kasih banyak.”) (Goldeneye, 1995)
Pada adegan ketika M memberikan perintah kepada James Bond, juga menampakan fakta bahwa ia secara tidak langsung tidak ingin dibandingkan dengan para pendahulunya. Pada situasi yang sama M juga menampakkan posisinya sebagai penguasa dengan pernyataannya yang tegas kepada James Bond sebelum ia menjalankan tugasnya. Pada saat itu M menyatakan “Good, because you are sexiest mysoginst dinosaurs, a relic of Cold War. ... I’m no commencing about sending you to your death.
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
206 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
...” (“Bagus, karena kau hanya orang seksi dari masa lalu yang membenci pernikahan, sisa dari perang dingin. ... Aku tidak ragu untuk mengirimmu ke kematianmu sendiri. …”) (Goldeneye, 1995). Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa M memiliki kekuasaan mutlak untuk menggerakkan semua potensi dari agen-agennya bahkan jika itu bisa membahayakan diri agen itu sendiri, dengan kata lain M bisa mengorbankan semua agennya jika memang itu diperlukan.
Situasi serupa muncul dalam fi lm “Die Another Day” (2002), pada adegan ketika M menemui James Bond yang baru diselamatkan dari penyanderaan oleh pihak militer Korea Utara. Saat itu, M menunjukkan sikapnya yang tegas, yang secara tidak langsung James Bond hanya sebagai alat yang bisa dikorbankan kapan saja, jika alat tersebut rusak atau tidak lagi berguna.
...Bond: “You don’t seem to please to see me.” (“Kau tampak tidak senang ketika melihatku.”)M: “If I did my way, you still be in North Korea.” (“Jika mengikuti kemauanku kau masih ada di Korea Utara.”)Bond: ???M: “Your freedom came with high price.” (“Kebebasanmu dibayar mahal.”)Bond: “Zao...” (“Zao...”)...M: “Know he’s free.” (“Sekarang dia Bebas.”)Bond: “I never ask to be traded. I rather died in prison than let him loose.” (“Aku tidak pernah minta ditukar. Aku lebih baik mati di tahanan daripada dia bebas.”)...M: “The top American Agent in the North Korea high command has execute a week ago. The American can decrypt their signal from your prison naming.” (Agen teratas Amerika Serikat di komando tertinggi di Korea Utara telag dibunuh minggu lalu. Pihak Amerika Serikat memecahkan kode dari sinyal yang
berasal dari seseorang di tahanan.)Bond: “And he think is me?” (“Mereka pikir itu aku?”)M: “You were a union made.” (“Kau yang melakukannya”)M: “They conclude you are crack when tourching to the information, we have to get you out.” (“Mereka menyimpulkan bahwa kau membocorkan informasi itu ketika kau disiksa, karena itu kami membawamu keluar.”)Bond: “And what about you think?” (“Bagaimana pendapatmu?”)... M: “You no use for anyone now.” (“Saat ini kau tidak berguna bagi siapapun.”) (Die Another Day, 2002).
Keputusan M untuk membuang James Bond, ketika tidak lagi bisa berguna, menunjukkan bahwa M mengambil keputusan logis, serta kekuasaan mutlak M terhadap semua bawahannya—meskipun secara normatif tampak sangat egois. Hal itu mengindikasikan hubungan antara M dengan James Bond hanya terfokus pada hubungan profesionalisme yang ketat, tanpa mencampurkan perasaan dan sisi emosional pada interarksinya. Karena itu, James Bond pada dasarnya tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap semua aktivitas profesionalnya, selain hanya alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, M hanya menganggap James Bond sebagai sosok yang berguna, jika memang ada saatu keuntungan yang bisa disumbangkan oleh James Bond terhadap M sendiri, dan mungkin juga pemerintah Kerajaan Inggris. Fakta tersebut ditunjukkan pada adegan ketika M menemui James Bond di stasiun bawah tanah untuk kembali merekrut James Bond, karena M menganggap James Bond kembali berguna bagi dirinya. Perhatikan dialog di bawah ini
...M: “What you expect that apology?” (“Apa kau mengharapkan permintaan maaf?”)
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 207
Bond: “I know, you do whatever you take to get job done.” (“Aku tahu, kau melakukan apapun asalkan pekerjaanmu selesai.”) (Die Another Day, 2002) M: ...
Dialog di atas menunjukkan secara mendalam bahwa M merupakan tipikal pemimpin dengan yang dengan tegas tidak menyesali semua perbuatan yag sudah dilakukannya sedikitpun, dengan pernyataan yang tidak menunjukkan sikap tidak mau meminta maaf. Sederhanya permohonan maaf merupakan bentuk sederhana sebagai bentuk ungkapan penyesalan. Sebaliknya, M justru mengatakan “What you expect that apology?” (“Apa kau mengharapkan permintaan maaf?”) (Die Another Day, 2002). Hal itu sama seperti yang ditunjukkan M dalam fi lm Skyfall (2012), ketika mengetahui bahwa James Bond ternyata masih hidup, sejak misi terakhirnya di Turki, kemudian mulai meragukan semua keputusan M. Saat itu, M mengatakan “...What you expected, a bloody apology?” (“...Apa yang kau harapkan, permintaan maaf sialan itu?”) (Skyfall, 2012), yang menunjukkan sikap M yang begitu tegas terhadap James Bond.
Karakterisasi M begitu menarik, karena menampilkan sosok pemimpin yang tangguh pada satu sisi namun juga humanis pada sisi yang lain. Seringkali ia rela mengorbankan James Bond, dalam banyak tugas dan misi, namun juga cenderung memberikan perlindungan kepada James Bond, jika ia terancam. Keadaan itu menunjukkan bahwa M memiliki pemikiran yang logis serta mempertimbangkan situasi yang paling menguntungkan bagi misi dan dirinya sendiri. Karena itu, M juga pernah menunjukkan sikap, bahwa ia mengakui bahwa James Bond, memang menjadi salah satu agennya yang terbaik, meskipun
ia tidak secara langsung mengatakan di depan James Bond.
Pernyataan M, dalam fi lm “The World is Not Enough” (1999), menunjukkan sikapnya yang begitu menghargai James Bond dan secara langsung memujinya. Ketika itu ia mengatakan, di depan Elektra King, “He is best we have, but I never to tell em.” (“Dia adalah agenku yang terbaik, meskipun aku tidak pernah mengatakan kepadanya.”) (The World is Not Enough, 1999). Pada fi lm “Goldeneye” (1995), dan “Quantum of Solace” (2008), M juga memberikan pernyataan yang hampir mirip, yang nadanya tampak begitu menghargai James Bond, seperti, “Bond..., come back alive.” (“Bond..., kembalilah hidup-hidup.”) (Goldeneye, 1995), atau “He is my agent, and I trust him. ...” (Dia agenku, dan aku percaya padanya. ...”) (Quantum of Solace, 2008). Pernyataan tersebut jelas bertolakbelakang dengan sikap M yang begitu tegas, hingga seakan-akan bisa mengorbankan James Bond dalam setiap misinya. Kenyataan demikian menunjukkan karakterisasi M yang relatif dinamis, meskipun ia hanya muncul sebagai karakter pendukung dalam banyak fi lm James Bond.
Pandangan dan sikap M terhadap James Bond rupanya juga didorong oleh situasi dan konteks yang muncul ketika ia mengambil keputusan. Legalitas M dan kekuasannya yang tinggi, ketegasan, serta kepeduliannya pada semua agen menjadikannya sosok pemimpin yang mampu mengambil keputusan dalam kondisi apapun, bahkan ketika ia harus berhadapab dengan seseorang yang memiliki jabatan struktural lebih tinggi. Pada adegan ketika Gareth Mallory menemui M serta mempertanyaakan keputusan M kembali merekrut James Bond sebagai agen rahasia, M menanggapinya dengan santai, dan tenang.
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
208 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
M: “I’am just been reviewing Bond’s test.” (Aku baru memeriksa hasil tes Bond.)M: “Seems you pass...mad the skin you tease.” (Tampaknya kau lulus...hampir.”)M: “You back to active service.” (Kau bisa kembali bertugas.”) (Skyfall, 2012)....M: “When he says ready, he’s ready.” (“Kalau dia bilang siap, maka dia siap.”)Mallory: “Perhaps you can’t see at all, maybe you won’t.” (“Mungkin kau tidak bisa melihat semuanya, atau tidak mau melihat.”)M: “What exact do you implying?” (“Apa maksudmu?”)Mallory: “You sentimental about him.” (Kau terlalu sentimentil terhadapnya.) (Skyfall, 2012)...M: “As long as I head this department, I choose my own operative.” (“Selama aku memimpin departemen ini, aku memilih sendiri agen-agenku.”)Mallory: “Fair enough.” (“Cukup adil.”) (Skyfall, 2012)
Tekanan yang diberikan oleh Gareth Mallory justru menunjukkan bahwa M memiliki kekuasaan penuh pada bidangnya, sehingga wajar jika ia pada akhirnya harus membuat Gareth Mallory harus puas terhadap semua keputusan M. Pernyataan M, “As long as I head this department, I choose my own operative.” (“Selama aku memimpin departemen ini, aku memilih sendiri agen-agenku.”) (Skyfall, 2012), tidak hanya menunjukkan bahwa M berkuasa penuh di MI6, tapi juga mennunjukkan bahwa ia bisa bertindak bebas, bahkan dalam tekanan. Hal yang sama juga pernah dilakukan M ketika berbeda pendapat dengan Laksamana Roebuck, kepala staf Angkatan Laut Kerajaan Inggris, yang pada saat itu tampak merendahkan saran M kepada menteri pertahanan, pada fi lm “Tomorrow
Never Dies” (1997). Dialog di bawah ini menunjukkan situasi tersebut.
...Admiral Roebuck: In incident of decesive action, you want to investigate ... (Dalam kejadian kekerasan ini, kau hanya ingin menyelidiki ...)M: My goes is prevent World War Three, admiral. And I don’t think sending an armada in to the recovery area is the best way we do it. (Tujuanku hanya mencegah Perang Dunia Tiga, laksamana. Dan aku tidak berpikir untuk mengirimkan armada menuju wilayah tersebut merupakan pilihan yang terbaik.)Defense Minister: Where exactly to the mysterious GPS signal come from? (Dari mana tepatnya sinyal GPS misterius itu datang?)M: We still investigate. (Masih kami selidiki.)Admiral Roebuck: Investigating. (Menyelidiki.)Admiral Roebuck: With all your respect M, sometimes I don’t think you have the ball for this job. (Dengan segala hormat M, kadangkala aku berpikir kau tidak punya nyali dalam pekerjaan ini.)M: Perhaps, but the advantages I don’t have a sinking all of time (Mungkin, kapi keuntungannya aku tidak akan punya banyak kapal yang tenggelam.) (Tommorow Never Dies, 1997)
Dialog tersebut menunjukkan posisi M yang tegas ketika menghadapi tekanan, serta tipikal pemimpin yang mampu mengambil keputusan sulit, bahkan ia tampil berani menghadapi atasannya yang bersikap merendahkan posisi atau keputusannya. Hal ini menjadikan M merupakan satu karakter penting yang secara langsung ikut menentukan semua aktivitas serta apa yang seharusnya dilakukan oleh James Bond. Menariknya, sikap M tersebut menjadikan James Bond begitu mematuhi M dan semua keputusannya, tidak pernah muncul satupun adegan yang menunjukkan bahwa James Bond menentang sikap M tesrebut.
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 209
Pada fi lm “Skyfall” (2012), M tampak begitu tangguh menghadapi seoarng penjahat besar, Thiago Rodrigues Silva, yang dulu merupakan mantan agen terbaik MI6. Pada adegan tersebut M tampil dengan sikapnya yang tangguh, angkuh, namun tetap tenang, tanpa sedikitpun menampilkan rasa takut atau gentar.
M: “Regresion is unprofessional.” (“Penyesalan itu tidak profesional.”)Silva: Hahaha...”Regret is unprofessional”. (“Menyesal tidak profesional.”)Silva: “But they made me suffer and suffer...” (“Tapi mereka membuatku menderita, semakin menderita, semakin menderita...”)Silva:”... and suffer. Until I realize, it was you who betrayed me. You betrayed me.” (“... dan menderita. Sampai aku sadar, kau yang menghianatiku. Kau menghianatiku.”)...M: “Well... I hope it’s worthed.” (“Aku harap itu setimpal.”)M: Mr Silva, you could be transfers to Belmarsh prison... (“Tuan Silva, kau akan dipindahkan ke penjara Belmarsh...”)M:”... in your mark of custody, until the Crown Prosecution Service deal you fi t to sent trial...” (“...sebagai bentuk penahananmu, sampai pengadilan memutuskanmu untuk menjalani...”)...M: “Your name is on the memorial wall of vary building you attack...” (“Namamu berada di monument peringatan di gedung yang kau hancurkan...”) M: “And I will strack off... soon your past in non existed as you future. I never see you again.” (“Dan aku akan menghapusnya...segera masa lalumu akan lenyap sama seperti masa depanmu. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi.”) (Skyfall, 2012)
Hal itu menjadi bukti kuat bahwa sikap M yang tenang, dan tanpa rasa penyesalan menjadikannya sebagai sosok pemimpin yang tangguh serta mungkin agak berdarah dingin. Namun sikap
demikian menjadikan M tampil sebagai seoarang pemimpin yang mungkin lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Ketika M mengatakan, “And I will strack off... soon your past in non existed as you future. I never see you again.” (“Dan aku akan menghapusnya...segera masa lalumu akan lenyap sama seperti masa depanmu. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi.”) (Skyfall, 2012), sebenarnya ia hendak menunjukkan bahwa ia mampu melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya, termasuk jika hal itu berarti bahwa M harus mengorbankan agen-agennya. Hal itulah yang menjadikan James Bond mengatakan, “I know, you do whatever you take to get job done.” (“Aku tahu, kau melakukan apapun asalkan pekerjaanmu selesai.”) (Die Another Day, 2002).
Dengan demikian, M muncul sebagai satu sosok yang sangat tegas dan berani di sisi lain, namun juga begitu tenang dan perhatian kepada agen-agennya di sisi yang lain. Keberanian M mengambil keputusan serta bertindak arogan dengan mengorbankan agen-agennya, termasuk James Bond, dalam satu tugas tertentu, sebenarnya dilandasi pada pemikirannya yang logis, kecakapannya, serta kekuasaannya yang tinggi di MI6. Hal itu juga membuat M mampu menghindari tekanan-tekanan struktural, baik itu berasal dari atasannya langsung atau kepala staf Angkatan Laut sekalipun. Kondisi demikian menjadikan M muncul sebagai karakter yang secara umum merefl eksikan bentuk-bentuk feminisme dalam fi lm-fi lm James Bond, yang notabene menjadi bagian dari media massa. Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa fi lm-fi lm James Bond secara tidak langsung mulai membawa pesan-pesan feminisme yang secara langsung ditempelkan dalam karakterisasi M, sebagai pemimpin tertinggi di MI6.
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
210 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Menariknya, masuknya pemeran perempuan dalam karakter M tampaknya berhubungan langsung dengan kondisi sosial yang berlaku kala itu. Era tahun 90-an mungkin merupakan era munculnya wacana-wacana tentang feminisme, pada mayarakat dunia. Keadaan itu kemungkinan besar mempengaruhi konstruksi fi lm-fi lm James Bond, dari fi lm yang penuh dengan tema maskulinitas, serta menunjukkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, menjadi fi lm-fi lm yang memberikan keluasan peran dan karakterisasi pada tokoh-tokoh perempuan. Hal itu diindikasikan oleh peran M, sebagai sosok pemimpin tertinggi MI6 yang memiliki dominasi lebih baik, serta peranan lebih kompleks, jika dibandingkan dengan pemeran M laki-laki pada fi lm-fi lm James Bond di bawah tahun 1995. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka paparan tentang wacana feminisme yang berada di belakang karakter M menjadi satu pokok bahasan yang menarik untuk dikaji.
Wacana Feminisme dalam Karakter M
Penjelasan tentang konstruksi karakter M pada dasarnya berhubungan erat dengan konstruksi feminisme yang muncul pada masyarakat dunia dan mungkin berkembang pesat pada dekade 90-an. Hal itu ditunjukkan oleh fakta bahwa pemikiran feminisme mengalami perkembangan pesat, pada akhir abad 20, yang dikenal sebagai pandangan post-feminism. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa perempuan kontemporer memiliki kesempatan yang jauh lebih besar tentang persamaan hak dengan laki-laki, terutama bidang-bidang seperti pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, serta gaya hidup (Macdonald, 208: 1769).
Hal itu dikuatkan oleh pandangan Angela McRobbie (2004) bahwa dekade 90-
an merupakan titik balik ketika kelompok feminis mulai mengenalkan gaya hidup baru yang dikenal sebagai “individualisasi perempuan serta memasukkan perempuan sebagai bagian dari pandangan politik kelompok feminis” (Macdonald, 2008: 1768). Berdasarkan hal itu, tampak bahwa munculnya karakter M yang diperankan oleh perempuan sebenranya masih berhubungan dengan kondisi serta situasi yang berkembang di dunia pada saat itu, yaitu pemikiran-pemikiran bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dalam bidang pekerjaan. Meskipun M merupakan karakter fi ksi yang muncul dalam fi lm James Bond, namun karakter M bisa merepresentasikan fakta bahwa perempuan memiliki persamaan hak, kewajiban, serta kemampuan setara dengan laki-laki, bahkan mungkin lebih baik lagi.
Fakta-fakta yang muncul pada masa tersebut tampaknya mendukung pemikiran Angela McRobbie (2004), bahwa dekade 90-an merupakan masa ketika perempuan mulai tampil lebih banyak pada sektor publik (pekerjaan formal di luar rumah), lepas dari stereotipe bahwa perempuan hanya mampu tampil pada sektor domestik (wilayah rumah tangga) semata. Hal itu dibuktikan dengan tampilnya tokoh-tokoh penting perempuan yang secara formal memiliki kesetaraan pada bidang pekerjaan dengan laki-laki, seperti yang ditunjukkan oleh Stella Rimington di Inggris. Stella Rimington merupakan sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi MI5 pada rentang tahun 1992 hingga 1996 (jamesbond.wikia.com/wiki/M_(Judi_Dench)). MI5 (Military Intelligent Section 5) atau juga dikenal sebagai SS (Security Service) merupakan badan intelejen yang bertanggungjawab pada aktivitas intelejen dalam negeri. MI5 berada pada yurisdiksi Departemen Dalam Negeri Kerajaan Inggris.
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 211
Lebih lanjut, Daily Telegraph menyata-kan bahwa Stella Rimington merupakan sosok perempuan yang menghasilkan kebijakan mengawasi semua saluran telepon, e-mail, dan web site di dalam negeri sebagai salah satu langkah strategis dalam aktivitas intelejen di dalam negeri (www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/10083058/Spy-on-your-neighbours-says-former-MI5-head-Stella-Rimington.html). Hal itu menunjukkan bahwa karakter M yang juga diperankan oleh perempuan kemungkinan besar terinspirasi dari sosok Stella Rimington yang menjadi sosok perempuan pertama yang memimpin dinas intelejen Inggris. Kecuali hal itu, hadirnya karakter perempuan sebagai sosok pemimpin tertinggi MI6 dalam fi lm James Bond menjadi satu upaya untuk menunjukkan bahwa pada beberapa situasi perempuan cenderung bisa mendominasi laki-laki, bukan sebaliknya.
Kenyataan bahwa sosok perempuan memiliki kemampuan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan laki-laki tidak hanya muncul pada dunia nyata, fenomena tersebut juga menjadi suatu wacana dalam media massa. Sosok karakter M pada fi lm-fi lm James Bond menjadi bentuk reprsesntasi munculnya wacana tentang feminisme dalam media massa. M digambarakan sebagai sosok yang dominan, tangguh, serta meungkin lebih unggul dibandingkan dengan karakter laki-laki dalam fi lm tersebut. Dalam fi lm, hal itu muncul ketika M tidak ingin disamakan dengan para pendahulunya, termasuk pada sisi kebiasan atau mungkin tradisi yang berkembang pada para pemimpin MI6 sebelumnya. Indikasi tersebut muncul dalam adegan percakapan antara James Bond dan M, sebelum M memberikan intruksi pada James Bond.
Bond: Your predessesor keeps some Conag in the top of drawer. (Pendahulumu biasanya meletakkan Conag di atas laci.)
M: I prefer Bourbon. (Aku lebih memilih Bourbon.)M: Ice? (Es?)Bond: Yes. (Ya.) (Goldeneye, 1995)
Ucapan James Bond bahwa para pendahulu nya selalu menempatkan Conag—salah satu jenis minuman keras— serta seakan-akan mengingatkan M, yang baru, bahwa ada tradisi yang dipegang oleh para pendahulunya, yaitu bahwa pemimpin tertinggi MI6 selalu memilih Conag daripada jenis minuman yang lain. Menariknya, M, manyatakan bahwa ia lebih memilih Bourbon—jenis minuman keras yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa M secara tidak langsung hendak menentang tradisi yang sudah alam dibangun oleh para pemimpin MI6 sebelumnya, yang notabene laki-laki, meskipun ia tidak menolak tradisi meminum minuman keras seperti yang dilakukan pendahulunya. Dengan kata lain M ingin menunjukkan superioritas, keunggulan, dan mungkin juga egoismenya sebagai seorang pemimpin. Hal ini secara tidak langsung me nunjuk kan munculnya wacana tentang feminisme pada fi lm-fi lm James Bond.
Menariknya, tokoh M tidak hanya ditampilkan dengan satu kondisi yang menolak penyamaan dirinya dengan para pendahulunya, namun juga ditampilkan sebagai sosok yang sangat berkuasa, bahkan ia tampak berani menentang perintah atasannya. Perhatikan dialog, ketika M berselisih pendapat dengan Gareth Mallory, yang saat itu merasa bahwa M terlalu membela James Bond.
M: “What exact do you implying?” (“Apa maksudmu?”)Mallory: “You sentimental about him.” (Kau terlalu sentimentil terhadapnya.) M: “As long as I head this department, I choose my own operative.” (“Selama aku memimpin departemen ini, aku memilih sendiri agen-agenku.”)Mallory: “Fair enough.” (“Cukup adil.”) (Skyfall, 2012)
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
212 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Dialog tersebut menunjukkan secara jelas bahwa M merasa tersinggung ketika otoritasnya hampir tidak diakui oleh Gareth Mallory, yang menyatakan bahwa M terlalu mendukung serta membela James Bond. Kontan saja hal itu membuat M harus menunjukkan otoritasnya yang tinggi kepada pimpinannya itu dengan mengatakan “As long as I head this department, I choose my own operative.” (“Selama aku memimpin departemen ini, aku memilih sendiri agen-agenku.”) (Skyfall, 2012). Sikap serta pernyataan-pernyataan M yang dominan menunjukkan bahwa ada wacana feminisme yang muncul secara jelas bersama-sama karakter M dalam fi lm James Bond.
Dominasi, ketangguhan, serta sikap M pada semua situasi menunjukkan bentuk-bentuk feminisme liberal dalam diri karakter tersebut. Secara umum feminisme liberal dipahami sebagai satu bentuk feminisme yang menekankan persamaan posisi antara laki-laki dan perempuan pada semua bidang, termasuk mungkin juga pernikahan (Zeisler, 2008: 49).
Hal itu secara samar-samar menjelas-kan bahwa kelompok pendukung feminis-me liberal muncul dalam banyak sektor publik, serta menekankan posisi yang benar-benar sejajar dengan laki-laki. Kelompok tersebut digambarkan masih menerima pernikahan, namun harus ada persamaan hak dan kewajiban antara posisi suami dan istri. Indikasi munculnya wacana tentang feminisme liberal pada sosok M ditunjukkan pada adegan ketika M melakukan public hearing dengan menteri pertahanan dan parlemen Inggris. Saat itu M mengatakan, “My late husband was a great lover of poetry, ...” (Mendiang suamiku merupakan pencinta puisi ...”) (Skyfall, 2012).
Pernyataan iitu menunjukkan bahwa M merupakan sosok perempuan yang
memiliki suami, sama seperti kebanyakan perempuan yang lain. Kenyaataan tesrebut juga mengindikasikan bahwa M bukanlah perempuan yang menolak pernikahan. Namun demikian, bagi M pernikahan dan sosok suami bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Dengan kata lain, berdasarkan pandangan Zeisler (2008), kelompok feminisme liberal memandang pernikahan bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan, bahkan kehadiran sosok suami juga bukan menjadi satu bagian penting dalam kehidupan perempuan, karena feminisme liberal menganggap bahwa perempuan mampu memenuhi semua kebutuhannya. Karena itu, ungkapan, “My late husband…” tidak hanya menunjukkan bahwa suami M sudah meninggal, tapi juga menunjukkan bahwa M sama sekali tidak membutuhkan kehadiran seorang suami. Dengan begitu muncul satu kondisi yang logis bahwa semua bentuk ketangguhan, dan dominasi M, pada semua situasi rupanya dijiwai oleh pemikiran feminisme liberal.
Kesimpulan
Konstruksi karakter M, dalam fi lm-fi lm James Bond, menunjukkan munculnya suatu fakta penting bahwa wacana feminisme bukan lagi suatu wacana yang dianggap tabu untuk disampaikan, melainkan suatu wacana yang menjadi salah satu pokok pembahasan di media global. Dengan kata lain, saat ini pemikiran tentang feminisme menjadi salah satu pemikiran penting dalam upaya menyetarakan hak-hak perempuan di masyarakat. Bagi media massa, wacana dan pemikiran tentang feminisme muncul dalam banyak budaya pop, termasuk fi lm, khususnya fi lm-fi lm James Bond. Wacana dan pemikiran tersebut muncul pada hampir semua karakter perempuan pada serial tersebut, namun demikian
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 213
karakter M menjadi sosok dominan yang merepresentasikan pemikiran dan wacana tentang feminisme. Karena itu, konstruksi karakter M dalam fi lm-fi lm James Bond menjadi fokus untuk mengkaji dan memahami pemikiran dan wacana tentanng feminisme.
Sejak kemunculan karakter M pertama kali, pada tahun 1995, karakter tersebut menampilkan konstruksi pemikiran yang sangat berhubungan dengan pemikiran dan wacana feminisme. Karakter M hadir dengan sikap-sikap yang tegas, tangguh, dominan, serta lebih unggul dibandingkan dengan karakter laki-laki pada fi lm yang sama. M merasa enggan disamakan dengan para pendahulunya, yang notabene laki-laki, sebagai satu bukti munculnya pemikiran feminisme pada diri sosok M. hal itu membawa konsekuensi besar pada karakter itu sendiri serta pengaruhnya pada James Bond. Pemikiran serta wacana feminisme pada karakter M menjadikan ia bisa dengan mudah mendominasi karakter lainnya, termasuk James Bond, bahkan M bisa langsung mencampakkan James Bond ketika ia dianggap tidak lagi berguna bagi M. Fakta tersebut hadir, bukan hanya karena M merupakan atasan langsung James Bond di MI6, tapi lebih menampakkan bahwa M memiliki kekuasaan penuh, dominasi, serta keberanian, jauh melebihi James Bond sendiri, sebagai hasil konstruksi dari wacana dan pemikiran feminisme.
Lebih lanjut, wacana dan pemikiran feminisme yang muncul pada karakter M bukan hanya bagian dari upaya media massa untuk menjadikan feminisme sebagai suatu wacana global, tapi juga muncul sebagai hasil dari fakta-fakta sosial yang berkembang pada dekade 90-an, tentang feminisme. Kemunculan karakter M, yang diperankan perempuan, secara tidak langsung dipengaruhi oleh
fakta sosial munculnya Stella Rimington, sebagai perempuan pertama yang menjadi pemimpin tertinggi MI5 pada tahun 1992-1996. Dengan kata lain karakter M tampil sebagai representasi wacana dan pemikiran feminisme di dunia nyata, serta didorong oleh fakta penting bahwa sosok perempuan juga mampu menjadi seorang pemimpin, bahkan pemimpin dinas intelejen Inggris. Dengan demikian pemikiran tentang persamaan hak perempuan, dewasa ini, hadir pada banyak bidang dan secara langsung didukung oleh media massa, serta hadir menjadi sebuah wacana penting di masyarakat modern. Karena itu, wacana dan pemikiran tentang feminisme muncul sebagai suatu petunjuk penting bahwa sosok perempuan tidak hanya bisa tampil begitu lembut, tapi juga hadir menjadi sosok yang sangat tangguh, sama seperti yang dikatakan oleh M kepada Gareth Mallory, pada saat wawancara, “What the hell with dignity, I leave when the jobs done.” (“Persetan dengan kebanggaan, aku pergi setelah tugasku selesai.”) (Skyfall, 2012).
Daftar PustakaFlynn, E, A. (2002). Feminism Beyond
Modernism. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Getachew, M, T. (2008). Bagaimana Hidup (dan Bagaimana Mati), dalam James B. South dan Jacob M. Held (editor) James Bond and Philosophy, Question Are Forever. Ilyas Hasan (penerjemah): 41-66. Jakarta: Lentera.
Macdonald, M. (2008). Femininity and Feminine Values. dalam Wolfgang Donsbach (editor) International Encyclopedia of Communication: 1764-1769. Malden: Blackwell Publishing.
Proop, V. (1984). Theory and History of Folklore. Ariadna Y Martin dan Richard P. Martin (penerjemah). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Dewanto Putra Fajar. Film, Feminisme, dan ...
214 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Taylor, A. F. (2011). Buku-Buku yang Mengubah Dunia, Lebih dari 50 buku yang peling berpengaruh dalam sejarah manusia. O.V.Y.S. Damos (penerjemah). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Zeilser, A. (2008) Feminism dan Pop Culture. Berkeley: Seal Press.
James Bond Wikia. (n.d). M (Judi Dench). Diakses pada 10 September 2014 dari http://jamesbond.wikia.com/wiki/M_(Judi_Dench)
Whithead, T. Furness, H. (2013). Spy on Your Neighbours, Says Former MI5 Head, Stella Rimington. Diakses pada 10 September 2014 dari http:// www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/10083058/Spy-on your-neighbours-says-former-MI5-head-Stella-Rimington.html.
Goldeneye. Dir. Martin Campbell. Perf. Pierce Brosnan, Isabella Scorupco, Famke
Janssen, Sean Bean, Judi Dench, Samantha Bond. MGM/UA, 1995.
Tomorrow Never Dies. Dir. Roger Spottiswoode. Perf. Pierce Brosnan, Michelle Yeoh, Jonathan Pryce, Teri Hatcher, Judi Dench, Samantha Bond. MGM/UA, 1997.
The World Is Not Enough. Dir. Michael Apted. Perf. Pierce Brosnan, Sophia Marceau,Robert Carlyle, Denise Richardson, Judi Dench, Samantha Bond. MGM/UA, 1999.
Die Another Day. Dir. Lee Tamahori. Perf. Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby
Stephens, Rosamund Pike, Madonna, Judi Dench, Samantha Bond. MGM/UA, 2002.
Quantum of Solace. Dir. Marc Foster. Perf. Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Gemma Arterton, Judi Dench. MGM/Columbia Pictures, 2008.
Skyfall. Dir. Sam Mendes. Perf. Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Berenice Lim Marlohe, Ben Wishaw. Judi Dench. MGM/Columbia Pictures, 2012.
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 215
Jurnal Komunikasi MassaVol. 7 No. 2, Juli 2014: 215-224
Perempuan di Media Online: Representasi Perempuan dalam Website www.kompas.com
Monika Sri YuliartiProgram Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
AbstrakThe pattern of consumption of mass media in today’s society is changing. This is partly due to the developments in information technology. Now, the world is experiencing the digital age, where all aspects of life and the relationship humans have a very close relationship with the internet technology, where it was thanks to the Internet era, when it began to give birth to online media. The online media eventually become the people’s choice in meeting their needs for information. At the level of academic and scientifi c research related to the impact of mass media on society as a mass media users have been carried out. From the research that has been there is, in general, resulted in fi ndings that impact negatively trend and strong enough for the people who act as a mass audience. Look at this, the contents of the mass media should be a concern, so the impact is a positive impact.Newspapers, as one form of print media, today has been pretty much the mengkonvergensikan products with online media forms as well. With online media, of information submitted more up to date than the printed version of the newspaper only. This paper is the result of a study document, in this case is the article on the online newspaper with local and national scope. In this study analyzed data is the contents of the article of the rubric “women” contained on the website www.kompas.com. Selection of the website as the research object is motivated by the coverage of different online media, the scope of local and national scope. Furthermore, they are also a source of information that is fairly large in scope respectively. The results are expected to enrich the depth information based on the reference and academic perspective, of how women are represented in the media, especially in this context is the online media. Research on the representation of women in the media spelled already pretty much done. However, this study also incorporate aspects of locality and nationality, which can be known how the local media and national media presented online represent women through the articles contained within the rubric of “woman”.Keywords: representation, women, online media.
Pendahuluan
Setiap hari, manusia melakukan proses komunikasi, bahkan saat tidak disadari sekalipun. Komunikasi
yang dilakukan tersebut bisa berupa komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, maupun komunikasi massa. Bentuk komunikasi
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
216 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
yang dilakukan pun bermaca-macam, mulai dari komunikasi secara langsung atau face to face maupun komunikasi dengan menggunakan perantara saluran atau media tertentu. Komunikasi massa merupakan salah satu bentuk dari level komunikasi yang memiliki cakupan paling luas di antara level-level yang lainnya.
Komunikasi massa ini merupakan komunikasi tak langsung yang membutuhkan media sebagai perantara untuk menghubungan antara sumber pesan atau komunikator dengan sasaran pesan atau komunikan. Perkembangan media massa sendiri dewasa ini semakin pesat. Jika pada masa lampau proses transfer pesan secara massa hanya bisa dilakukan melalui media cetak, pada perkembangan selanjutnya proses komunikasi massa juga bisa dilakukan dengan menggunakan media audio dan media audio visual. Selanjutnya, pada akhir tahun 1990-an, muncullah internet yang pada akhirnya memunculkan gaya berkomunikasi secara massa yang berbeda.
Berawal dari kemunculan internet itulah, muncul istilah old media dan new media. Yang disebut dengan old media adalah media-media komunikasi massa yang muncul sebelum era internet, yaitu media cetak (misal: buku, surat kabar, tabloid, dan majalah), media audio (misal: radio, musik yang direkam dalam compact disc atau CD) serta musik yang direkam dalam mp3), dan media audio visual (misal: televisi, fi lm yang diputar di bioskop maupun yang direkam dalam video compact disc atau VCD serta digital video disc atau DVD). Sementara itu, yang disebut dengan new media adalah media-media komunikasi massa yang melibatkan unsur internet, seperti portal berita online, misalnya. Dewasa ini, muncul pula konvergensi antara old media dengan new media, seperti streaming radio, website
surat kabar, website stasiun televisi, dan website program-program yang terdapat dalam stasiun televisi.
Kemudian, apa sesungguhnya yang disebut dengan internet itu? Setidaknya terdapat tiga hal utama jika berkaitan dengan internet. Pertama, internet merupakan keterhubungan melalui sistem alamat global (global address system). Kedua, dalam internet terdapat penggunaan bentuk umum protokol transmisi. Yang ketiga, internet memungkinkan terjadinya komunikasi publik dan komunikasi pribadi (Wood & Smith, 2005: 37).
Berdasarkan dengan hal tersebut maka bisa diketahui bahwa dengan internet, keterhubungan antar manusia akan semakin besar. Selain itu, penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa konsep yang dicetuskan oleh McLuhan mengenai global village akan semakin menjadi hal yang sangat masuk akal dan memungkinkan, di mana dunia yang sangat luas dan besar ini merupakan desa global yang penduduknya mampu menerima informasi yang sama dalam waktu yang bersamaan, tanpa adanya kendala waktu yang sebelumnya ditemui.
Perkembangan media komunikasi massa yang melibatkan teknologi baru tersebut memunculkan karakteristik yang berbeda. Salah satu karakter yang berbeda adalah masyarakat sekarang lebih leluasa untuk memilih informasi apa yang diinginkan atau dibutuhkannya. Dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, tentu isi media menjadi suatu hal yang amat penting. Salah satu tema yang menjadi isi media adalah tema mengenai perempuan. Dewasa ini, tema mengenai perempuan sudah semakin banyak dimunculkan di media massa. Berbicara mengenai perempuan di media tentu tak bisa dilepaskan dari permasalahan gender (Littlejohn & Foss, 2005: 323).
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 217
Gender menjadi salah satu isu yang menarik dalam isi media. Dari tahun ke tahun, terdapat tren yang berbeda mengenai bagaimana gender direpresentasikan di media. Pada tahun 1970-an misalnya. Kala itu, isu gender dimunculkan sehubungan dengan kemunculan aliran gerakan feminisme. Beberapa aliran gerakan feminisme di antaranya adalah feminisme liberal dan feminisme radikal. Feminisme liberal lebih menitikberatkan fokusnya pada gagasan mengenai keadilan yang berhubungan dengan jaminan hak kesetaraan bagi semua manusia, baik itu pria maupun wanita. Sebaliknya, feminisme radikal meyakini bahwa penindasan terhadap perempuan sesungguhnya lebih dari sekedar ketidaksetaraan dalam bidang politik saja, melainkan sudah menjalar pada struktur sosial, yaitu patriarkal (Littlejohn & Foss, 2005: 323).
Riset terkait dengan representasi perempuan di media juga telah banyak dilakukan, baik secara spesifi k meneliti mengenai representasi perempuan pada media online atau media massa lain. Riset ini sendiri akan lebih fokus pada representasi perempuan dalam artikel pada website surat kabar Kompas (www.kompas.com). Riset ini penting dilakukan karena salah satu fungsi media massa adalah sebagai media sosialisasi nilai yang akan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain (Dominick, 2005: 41-42).
Pemilihan website Kompas didasari alasan, pertama, memiliki nama dan reputasi yang baik sebagai surat kabar nasional. Alasan kedua, pemilihan obyek ini adalah, Kompas merupakan media massa yang melakukan konvergensi antar old media dan new media.
Tinjauan Pustaka
Era media massa dewasa ini telah memasuki era new media (media baru),
atau tak jarang digunakan pula istilah media online. Dalam era ini, keterlibatan teknologi memegang peranan yang sangat besar. Keterlibatan teknologi tersebut memunculkan pola konsumsi yang berbeda di kalangan masyarakat. Media massa yang semula memiliki arti bahwa masyarakat secara massal bisa mengaksesnya secara bersama-sama, dengan media baru, maka media massa menjadi seolah-olah media pribadi. Hal ini terjadi karena dengan mengkonsumsi isi media online, maka masyarakat memiliki keistimewaan untuk memilih sendiri mana yang ingin dikonsumsi dan mana yang tidak diinginkan.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gunter (2003: 1), yang menyatakan ekspansi media massa ke dalam era online tidak saja memunculkan kompetisi antara sesama produsen media massa, melainkan juga memberikan dampak di kalangan masyarakat pengguna media massa tersebut. Masyarakat atau dalam hal ini adalah khalayak media massa, cenderung mnejadi lebih terfragmentasi jika dibandingkan dengan mereka saat mengkonsumi media massa konvensional. Selain itu, dampak yang diakibatkan dari penggunaan media online tersebut juga semakin signifi kan karena semakin terdapatnya keterbukaan dalam mendapatkan informasi.
Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa tema perempuan merupakan salah satu tema yang banyak diangkat untuk dijadikan sebagai isi dari produk media. Berbicara mengenai perempuan tentu tak bisa dipisahkan dari kajian mengenai feminisme. Kajian mengenai feminisme memang berasal dari negara Barat. Aris (dalam Syahri, 2009: 201) menulis bahwa tidak dapat dipungkiri, gerakan feminis di Barat adalah reaksi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
218 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
pada lingkungan sosial masyarakat di sana. Beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab utama gerakan tersebut adalah adanya pandangan “sebelah-mata” terhadap perempuan atau yang juga biasa disebut dengan misogyny, serta adanya bermacam-macam anggapan buruk atau stereotype yang dilekatkan kepada perempuan serta aneka citra negatif yang mengejawantah dalam tata-nilai masyarakat, kebudayaan, hukum, dan politik.
Feminisme sendiri merupakan sebuah gerakan yang berisi tuntutan adanya kesetaraan antara wanita dan pria. Gerakan ini muncul karena pada masanya, wanita tidak mendapatkan hak yang setara dengan kaum pria, sehingga pembahasan mengenai feminisme ini bertujuan untuk mengekspos kekuatan-kekuatan dan batasan-batasan dari pembagian dunia berdasarkan jenis kelamin ini. Banyak teori feminis memberi penekanan pada adanya pengekangan dari hubungan jenis kelamin di bawah dominasi patriarki. Sehubungan dengan hal tersebut, maka feminisme banyak mempelajari mengenai distribusi kekuasaan di antara jenis-jenis kelamin.
Asumsi awal dari teori feminisme ini adalah bahwa jenis kelamin merupakan sebuah kategori umum dari pengalaman. Teori ini bertujuan untuk menentang asumsi-asumsi yang berlaku tentang jenis kelamin di masyarakat dan untuk menemukan cara-cara yang lebih liberal bagi wanita dan pria untuk eksis di dunia. Kritik feminis sudah semakin populer dalam studi komunikasi. Para ilmuwan komunikasi feminis meneliti cara-cara bagaimana bias bahasa kaum pria mempengaruhi hubungan antar jenis kelamin, cara-cara bagaiman dominasi kaum pria telah membatasi komuikasi bagi wanita, cara-cara bagaimana kaum wanita telah mengakomodasi dan menolak pola-
pola pembicaraan dan bahasa kaum pria, kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk komunikasi kaum wanita.
Beberapa riset mengenai perempuan di media massa telah banyak dilakukan, di antaranya adalah “Peningkatan Gender dalam Jurnalisme”, penulis Iwan Awaluddin Yusuf. Dalam riset ini diperoleh temuan bahwa media massa dan jurnalisme di Indonesia masih kurang sensitif terhadap isu kesetaraan gender, utamanya dalam hal: (1) bagaimana jurnalis menyampaikan fakta; (2) posisi media; (3) posisi jurnalis dan produk jurnalistik (Yusuf, 2004: 351). Riset selanjutnya mengenai perempuan di media massa adalah “Wajah Perempuan dalam Media Massa”, penulis Nurul Arifi n. Temuan dalam riset tersebut adalah bahwa dengan kekuatannya, media massa di Indonesia cenderung membentuk dan menampilkan realitas tersendiri tentang wanita. Namun, sayangnya realitas tersebut tidak disertai dengan sensitivitas gender dalam berbagai penyajian (Arifi n, 2001: 199).
Abrar (2004: 392) juga melakukan riset mengenai perempuan dengan judul “Tantangan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pers di Indonesia”. Risetnya ini menghasilkan rekomendasi terkait dengan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan suasana baru di mana pers Indonesia lebih menghargai keberadaan perempuan, yaitu dengan: (1) mengamandemen UU No. 40 tahun 1999; (2) meningkatkan pengawasan pelaksanaan KEWI; (3) meningkatkan jumlah wartawati; (4) menggusur budaya diskriminatif; dan (5) menciptakan suasana adil gender.
Habsari (2013) melakukan riset mengenai Stereotype dan labelling perempuan dalam media cetak. Dari riset tersebut diperoleh temuan bahwa Representasi beberapa perempuan yang
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 219
terlibat dalam tindak kejahatan korupsi dalam sampul majalah Tempo merupakan penggambaran visualisasi perempuan secara variatif dan mempunyai penekanan pada khalayak yang dituju. Lebih lanjut, sistem kapitalisme dan budaya patriarki yang menghegemoni media di Indonesia saat ini memposisikan perempuan dalam konstruksi nilai-nilai feminitas yang tidak menguntungkan perempuan.
Dari beberapa riset yang telah dilakukan tersebut bisa diketahui bahwa riset mengenai representasi perempuan di media massa sesungguhnya telah banyak dilakukan, namun belum ada yang menganalisis mengenai representasi perempuan pada media online yang merupakan bentuk konvergensi dengan media massa kuno atau konvensional. Untuk itulah, riset ini muncul sehingga diharapkan bisa memberikan temuan yang bermanfaat untuk melengkapi temuan-temuan riset yang telah ada.
Dalam representasi, terdapat suatu permasalahn penting, utamanya dalam kaitannya dengan bagaimana realitas atau obyek tersebut ditampilkan. Fiske (dalam Eriyanto, 2001) menyebutkan bahwa terdapat tiga proses dalam menampilkan obyek, peristiwa, gagasan, kelompok, atau seseorang. Level pertama akan berhubungan dengan peristiwa yang ditandai sebagai realitas. Dalam bahasa gambar, hal ini umumnya berhubungan dengan aspek seperti pakaian, lingkungan, ucapan, dan ekspresi.
Selanjutnya level kedua akan berhubungan dengan waktu saat kita memandang sesuatu sebagai realitas dan bagaimana realitas itu digambarkan. Sehubungan pada level yang kedua ini, maka yang digunakan disini adalah perangkat secara teknis, misalnya adalah kata atau kalimat, yang mana pada akhirnya kata dan kalimat ini akan
membawa makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. Terakhir, level ketiga, akan berhubungan dengan bagaimana peristiwa tersebut diorganisir ke dalam konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis. Selain itu, level terakhir ini juga berhubungan dengan bagaimana kode-kode representasi dihubungakan dan diorganisikan ke dalam koherensi sosial seperti kelas sosial, atau kepercayaan dominan yang ada dalam masyarakat.
Lebih lanjut, representasi dalam teori konstruksi sosial merupakan representasi simbolik, di mana bahasa memiliki peran penting dalam proses obyektivasi terhadap tanda-tanda yang ada. Hal ini terjadi karena karena bahasa mampu membangun bangunan-bangunan representasi simbolis seperti halnya dalam kehidupan nyata (Berger & Luckmann, 1966: 55). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka representasi perempuan akan bisa diketahui dengan mengelaborasi simbol-simbol yang ada pada obyek yang dianalisis.
Menurut Hall (1997: 25), terdapat tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan peran bahasa dalam representasi. Ketiga pendekatan tersebut adalah the refl ective, the intentional dan the contructionist approach. Pada the refl ective approach, makna ditujukan untuk mengelabui obyek yang dimaksudkan, baik itu orang, ide ataupun suatu kejadian di dunia yang nyata, dan fungsi bahasa sebagai cermin, untuk merefl eksikan maksud sebenarnya seperti keadaan yang sebenarnya di dunia. Sedangkan intentional approach merupakan pendekatan yang berkaitan erat dengan pembicara atau penulis yang menekankan pada diri sendiri mengenai pemaknaan yang unik di dunia ini melalui bahasa. Kata-kata yang dihasilkan memiliki makna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis.
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
220 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Metode Penelitian
Riset ini merupakan riset deskriptif kualitatif, yaitu riset yang mendeskripsikan kondisi, proses, hubungan mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian, serta fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat secara rinci dan mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif ini juga bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Bungin, 2007). Obyek penelitian adalah artikel-artikel yang terdapat dalam website kompas, utamanya yang terdapat pada rubrik wanita.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Teknik analisis data akan dilakukan secara induktif interaktif, di mana proses analisis bisa dilakukan sesegera mungkin, tanpa harus menunggu proses pengumpulan data dilakukan. Lebih lanjut, interaktif di sini maksudnya adalah ada interaksi atau sintesa yang akan dilakukan terkait dengan data-data yang nanti terkumpul.
Metode analisis yang akan digunakan dalam riset ini adalah analisis wacana. Cook (dalam Eriyanto, 2001: 9) menjelaskan bahwa analisis wacana berhubungan erat dengan tiga hal; yaitu teks, konteks, dan wacana. Teks adalah semua bentuk bahasa, konteks adalah situasi dan hal dari luar yang berpengaruh, dan wacana adalah adanya interaksi antara teks dan konteks. Metode analisis wacana yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana model Sara Mills.
Sara Mills lebih melihat bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks (posisi subyek-obyek). Dalam arti siapa yang menjadi subyek penceritaan dan siapa yang menjadi obyek penceritaan. Dengan demikian akan didapatkan bagaimana struktur teks dan bagaimana
makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain itu Sara Mills juga menggunakan metode posisi penulis-pembaca. Dalam kaitannya dengan posisi penulis-pembaca ini, maka analisis yang dilakukan berhubungan dengan bagaimana penulis menampilkan diri yang pada saatnya akan menentukan bagaimana respon atau penerimaan pembaca.
Pembahasan
Pada website Kompas, menu untuk menuju pada rubrik perempuan bisa diakses dari halaman muka, dengan tag “female”. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam menu “female”, maka akan terlihat beberapa sub menu-sub menu selanjutnya, yaitu “home”, “ibu & anak”, “etalase”, “cantik & gaya”, “karier”, “relationship”, “bugar dan sehat”, “beranda”, dapur”, “konsultasi”, dan “kolom”.1. Posisi Subyek-Obyek
Berkaitan dengan posisi subyek-obyek, maka hal-hal yang akan dianalisis adalah siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subyek), siapa yang diposisikan sebagai obyek yang diceritakan (obyek), serta aktor dan kelompok sosial mana yang mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri serta gagasannya.
Dilihat dari posisi subyek-obyek, artikel-artikel yang terdapat pada rubrik perempuan dalam website kompas (yang dalam hal ini disebut dengan rubrik “female”) menunjukkan bahwa memang artikel-artikel tersebut ditujukan untuk kaum perempuan, di mana perempuan diposisikan sebagai obyek yang diceritakan. Namun demikian, pembagian sub-sub tema cukup menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak hanya ditampilkan dalam urusan domestik saja, walaupun sub tema yang menyangkut dengan urusan
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 221
domestik masih cukup mendominasi. Kasiyan (2008: 56-57) menyatakan bahwa fenomena dan realitas peran domestik yang dikenakan kepada perempuan pada akhirnya mengejawantahkan konsep ‘pengiburumahtanggaan’ atau ‘domestikasi’ atas perempuan di masyarakat. Konsep ini jika dicermati cenderung bermakna diskriminatif bagi perempuan dalam representasinya. Dalam rubrik “female” website kompas, domestikasi perempuan tampak dari sub tema-sub tema sebagai berikut: (1) “ibu & anak”, yang kemudian dibagi lagi menjadi “kehamilan & menyusui” dan “parenting”; (2) “etalase”, yang kemudian dibagi lagi menjadi “produk baru”, “info kegiatan”, dan “direktori”; (3) “cantik & gaya”, yang kemudian dibagi lagi menjadi “kecantikan”, “fashion”, “galeri”; (4) “relationship”, kemudian dibagi lagi menjadi “rahasia pria”, “anda & dia”, dan “seks”; (5) “bugar & sehat”, yang kemudian dibagi lagi menjadi “diet” dan “bugar”; (6) “beranda”, yang dibagi lagi menjadi “isu wanita” dan “gaya hidup”; (7) “dapur”, yang kemudian dibagi lagi menjadi “koleksi resepsi” dan “tips memasak”; dan (8) “konsultasi”, yang dalam hal domestikasi perempuan kemudian lebih dispesifi kkan lagi ke dalam “konsultasi gizi”.
Sementara itu, selain menampilkan domestikasi perempuan, rubrik “female” website Kompas juga menampilkan perempuan di ranah publik. Hal ini bisa diamati dari sub tema-sub tema yang ada, seperti: (1) “karier”, yang kemudian dibagi lagi menjadi “dunia kerja” dan “keuangan” dan (2) “konsultasi”, yang dalam hal representasi perempuan dalam konteks ruang publik dibagi lagi menjadi “konsultasi keuangan”, “pengembangan diri”, dan “fashion”.
Dari pemaparan di atas bisa diketahui
bahwa secara umum, representasi perempuan pada rubrik perempuan di kompas secara umum masih cenderung merepresentasikan wacana perempuan di ranah domestik, walaupun perempuan di ranah publik juga sudah ditampilkan, dengan pembagian sub tema yang cukup jelas. Dalam kaitannya dengan posisi subyek- obyek, artikel-artikel yang terdapat pada rubrik “female” website Kompas berdasarkan sub tema-sub tema yang ada, perempuan tidak selalu diposisikan sebagai pencerita.
Hal ini bisa dilihat dari artikel dengan judul “Tak Ingin Rambut Rontok? Jangan Diet Berkepanjangan!” padasub tema “kecantikan” (http://female.kompas.com/read/2014/11/20/133000320/Tak.Ingin.Rambut.Rontok.Jangan.Diet.Berkepanjangan.). Artikel ini berisi mengenai tips yang harus dijalankan oleh seorang perempuan mengenai salah satu bahaya melakukan diet terlalu ketat. Pada artikel ini, posisi pencerita awalnya seolah-olah menggambarkan seorang perempuan. Namun, pada bagian selanjutnya artikel ini memamaparkan hasil penelitian dari seorang ahli yang adalah seorang pria. Sehingga, keseluruhan isi dari artikel tersebut juga seolah-olah merupakan saran pria kepada kaum perempuan bagaimana caranya agar diet yang ia lakukan tidak memberikan dampak yang buruk bagi unsur kecantikan perempuan yang lain, yaitu rambut yang rontok.
Contoh lain yang menampakkan bahwa perempuan tidak direpresentasikan sebagai pihak pencerita adalah pada artikel yang berjudul “Ajari Bayi Tidur Sendiri dengan Metode ‘Menangis’” yang terdapat pada sub tema “Ibu & Anak” (http://female.kompas.com/read/2014/09/21/200000620/Ajari.Bayi.Tidur.Sendiri.dengan.Metode.Menangis.). Artikel ini berisi mengenai teknik
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
222 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
menidurkan bayi dengan membiarkannya menangis sebelum tidur. Posisi pencerita dalam artikel ini juga ditampilakan sebagai seorang pria, karen pada artikel ini juga memasukka materi mengenai sumber pemberitaan dari kaum pria, yaitu penulis buku tentang bayi dan juga dokter serta peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan tema yang terdapat dalam artikel.
Kedua contoh di atas merupakan contoh yang diambil dari artikel yang merepresentasikan perempuan di ranah domestik. Untuk artikel yang merepresentasikan perempuan di ranah publik juga sesungguhnya tidak jauh berbeda. Seperti hal nya pada artikel yang terdapat pada sub bagian “karier”. Pada bagian ini terdapat artikel yang menunjukkan bawa pihak pencerita dalam artikel ini bukanlah digambarkan sebagai seorang peremuan, melainkan seorang laki-laki. Artikel ini berjudul “Studi Membuktikan, Olahraga Bisa Buat Performa Kerja Melesat” (http://female.kompas.com/read/2014/11/27/141500520/Studi.Membuktikan.Olahraga.Bisa.Buat.Performa.Kerja.Melesat.).
Seperti halnya artikel yang lain, untuk meyakinkan pembacanya, artikel ini juga memasukkan hasil studi yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti tersebut adalah seorang laki-laki. Terlebih lagi dalam artikel tersebut tertulis: “Olahraga memang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, menyehatkan jantung, dan bentuk tubuh pun menjadi lebih menarik”.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kaum pria lah yang seolah-olah berbicara, karena merekalah yang mengklaim diri mereka paling mengerti bagaimana bentuk tubuh perempuan yang menarik menurut versi mereka, walaupun sesungguhnya artikel ini terdapat pada sub bagian “karier”, sub bagian yang merupakan
ranah publik, di mana tidak ada unsur domestikasi di dalamnya. Namun pada kenyataannya, setelah membaca artikel tersebut, semakin jelas bahwa walaupun terdapat sub bagian yang bukan merupakan domestikasi perempuan, tetap saja isi dari artikel tersebut memasukkan unsur domestikasi, bahkan dalam hal pencerita yang digambarkan sebagai seorang pria, bukan seorang perempuan.
Artikel lain yang berada pada sub bagian ranah publik, yaitu “konsultasi” terutama pada bagian “konsultasi fashion” juga menampilkan pencerita yang seorang pria. Pada artikel yang berjudul “Kebaya Berhijab untuk Wisuda” (http://female.kompas.com/read/2013/08/21/1326550/K e b a y a . B e r h i j a b . u n t u k . W i s u d a ) . Dalam artikel tersebut, identitas yang berkonsultasi adalah seorang perempuan muda, sementara konsultan yang menjawab pertanyaan adalah seorang pria, ia juga seorang desainer yang memang memiliki reputasi baik dalam bidang fashion. Dengan memasang seorang pria sebagai konsultasn, maka artikel tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa pria lah yang menjadi subyek pencerita dan berperan lebih aktif dibandingkan dengan perempuan yang salam hal ini menjadi obyek pencerita.
Dari semua analisis terkait dengan posisi subyek-obyek di atas, maka jika dilihat dari kelompok sosial yang ditampilkan, setiap artikel memiliki kekhasannya masing-masing. Namun, karena setiap artikel pasti sudah jelas tema dan pembahasannya, tentu saja kelompok sosial yang ditampilkan pada masing-asing artikel pun sudah sangat spesifi k, tergantung dari artikelnya tersebut. Misalnya saja pada artikel terakhir, artikel mengenai konsultasi fashion. Pada artikel ini perempuan yang ditampilkan adalah perempuan yang sesuai dengan tema dari
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 223
sub bagian ini, yaitu konsultasi fashion. Pada artikel ini yang melakukan konsultasi adalah seorang perempuan dengan usia 17 tahun. Sehingga ketika konsultan memberikan jawabannya pun maka kelompok sosial yang terwakili adalah kelompok sosial yang sama dengan gadis berusia 17 tahun yang memakai jilbab, dan mencoba mencari saran mengenai busana yang akan ia kenakan dalam wisudanya. Dengan spesifi knya artikel tersebut, maka semakin spesifi k pula kelompok sosial yang terwakili dalam artikel tersebut.2. Posisi Penulis-Pembaca
Dalam kaitannya dengan posisi penulis-pembaca, artikel-artikel yang terdapat dalam rubrik “female” pada website Kompas secara umum didominasi oleh tulisan saduran dari website lain. Namun, gaya bahasa yang digunakan sudah disesuaikan dengan sasaran atau target dari website tersebut. Representasi perempuan yang ditampilkan dalam artikel-artikel yang ada dalam rubrik “female” website Kompas memposisikan penulis sebagai pemberi saran yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai topik-topik dalam artikel-artikel yang ada.
Penulis umumnya memasukkan hasil riset tertentu yang mendukung isi artikel sehingga artikel tersebut lebih memiliki nilai plus dan semakin menunjukkan fakta-fakta yang mampu semakin meyakinkan para pembacanya. Dengan posisi penulis yang sedemikian rupa, hal ini memungkinkan posisi pembaca juga seakan menjadi inferior, karena begitu banyaknya data dan hasil penelitian yang ikut ditampilkan oleh penulis.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang terdapat pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan temuan bahwa website Kompas yang lingkupnya adalah nasional
(pun website ini bisa juga memiliki lingkup yang lebih luas karena ia pun bisa diakses secara global dari siapapun dan lokasi manapun) cenderung merepresentasikan perempuan pada ranah domestik, walau terdapat sub bagian yang mampu mewakili ranah publik seorang perempuan. Namun secara umum, dengan kuantitas yang tidak berimbang dan tidak signifi kan, representasi perempuan dalam ranah domestik masih terlihat mendominasi.
Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka bisa diberikan rekomendasi betapa pentingnya menggalakkan pembelajar-an penggunaan media online di kalangan masyarakat agar masyarakat bisa secara lebih bijak melakukan pengkonsumsian-nya. Selain itu, media online literacy yang dimaksud mampu mengoptimalkan transfer pesan yang terjadi dari media kepada khalayaknya.
ReferensiAbrar, Ana Nadhya. (2004). Tantangan
dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pers di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 7, nomor 3, Maret 2004, Hal 377-392.
Arifi n, Nurul. (2001). Wajah perempuan dalam media massa. dalam Mediator, vol 2, Hal 199-202.
Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. (1991). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. London: Penguin Books.
Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
Dominick, Joseph R. (2004). The Dynamics of Mass Communication: Media in the Digital Age, 8th edition. Boston: McGray Hill.
Monika Sri Yuliarti. Perempuan di Media ...
224 Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014
Eriyanto. (2001). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.
Habsari, Sinung U.H. (2013). Studi Awal Metodel Kajian Bias Gender dalam Jurnalistik: Stereotype & Labelling Perempuan dalam Media Massa Cetak. Riptek Vol. 7, No. 1, Tahun 2013, Hal. 47-58.
Hall, Stuart. (ed.). (1997). The Work of Representation dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications.
Kasiyan, 2008. Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan. Yogyakarta: Ombak
Syahri, Moch. (2009). Konstruksi Feminisme di Media Massa. Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 43, Edisi Khusus, 2009, hlm. 201-218
Wood, Andrew F. & Smith, Matthew J. (2005). Online Communication: Linking technology, identity, & culture. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Association.
Yusuf, Iwan Awaluddin. (2004). Peningkatan kepekaan gender dalam jurnalisme. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 7, nomor 3, Maret 2004, hal 351-376.
female.kompas.com
h t t p : / / f e m a l e . k o m p a s . c o m /read/2013/08/21/1326550/Kebaya.Berhijab.untuk.Wisuda
h t t p : / / f e m a l e . k o m p a s . c o m /read/2014/09/21/200000620/Ajari.Bayi.Tidur.Sendiri.dengan.Metode.Menangis.).
h t t p : / / f e m a l e . k o m p a s . c o m /read/2014/11/20/133000320/Tak.Ingin.Rambut.Rontok.Jangan.Diet.Berkepanjangan
h t t p : / / f e m a l e . k o m p a s . c o m /read/2014/11/27/141500520/Studi.Membuktikan.Olahraga.Bisa.Buat.Performa.Kerja.Melesat
Jurnal Komunikasi Massa Vol. 7 No. 2, Juli 2014 225
Syarat-syarat Penulisan Artikel
1. Artikel merupakan hasil refl eksi, penelitian, atau kajian analitis terhadap berbagai fenomena komunikasi, khususnya komunikasi massa, yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan panjang tulisan antara 6.000-8.000 kata, diketik di halaman A4, spasi tunggal, margin atas dan kiri 4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm, menggunakan font Times New Roman 11 point. Artikel dilengkapi dengan abstrak sepanjang 100-150 kata dan 3-5 kata kunci.
3. Artikel memuat: Judul, Nama Penulis, Instansi asal Penulis, Alamat Kontak Penulis (termasuk telepon dan email), Abstrak, Kata-kata kunci, Pendahuluan (tanpa anak judul), Sub-sub Judul (sesuai kebutuhan), Penutup atau Simpulan, Catatan-catatan dan Daftar Kepustakaan.
4. Kata atau istilah asing yang belum diubah menjadi kata/istilah Indonesia atau belum menjadi istilah teknis, diketik dengan huruf miring.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai endnotes.6. Kutipan langsung 5 baris atau lebih diketik dengan spasi tunggal dan diberi baris
baru. Kutipan langsung kurang dari 5 baris dituliskan sebagai sambungan kalimat dan dimasukkan dalam teks di antara dua tanda petik. Kutipan tidak langsung (parafrase) ditulis tanpa tanda petik.
7. Daftar Kepustakaan diurutkan secara alfabetis, dan hanya memuat literatur yang dirujuk dalam artikel. Penulisan referensi menggunakan sistem American Pschycological Association (APA)
Contoh: Fakih, M. (1997). .Analisis gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. Holmer-Nadesan, M. (1986). “Organizational Identity and Space ofAction”, 17 (1), 1986, hal. 49-81.
8. Penulis diminta menyertakan biodata singkat.9. Artikel dikirimkan kepada Tim Penyunting dalam bentuk fi le MicrosoftWord (.doc
atau .rtf) disimpan dalam disket, CD, USB fl ashdisk, ataupun sebagai attachment dalam e-mail.
10. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah diberitahukan kepada penulis melalui surat atau email. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kepada penulis, kecuali atas permintaan penulis.
11. Penulis yang artikelnya dimuat akan menerima ucapan terima kasih berupa nomor bukti 3 eksemplar.
12. Artikel dikirimkan ke alamat di bawah ini:
JURNAL KOMUNIKASI MASSAProdi. Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta 57126. Tlp. (0271)632478Email: [email protected]