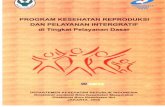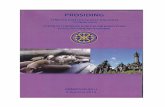MANAJEMEN REPRODUKSI BABI
Transcript of MANAJEMEN REPRODUKSI BABI
TUGAS MANAJEMEN DAN PENYAKIT BABI
MANAJEMEN REPRODUKSI BABI
Oleh:
Agatha Serena L. Tobing NIM: 1209005066
RA. C. Noorputri NIM: 1209005067
Saruedi Simamora NIM: 1209005068
Bianca Violanda Junus NIM: 1209005069
I Made Wira Diana Putra NIM: 1209005085
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan berkat-Nya yang diberikan kepada penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaian makalah ini dengan
baik dan tepat pada waktunya.
Adapun judul makalah ini berjudul Manajemen
Reproduksi Babi. Penulis membahas tentang manajemen
reproduksi babi yang meliputi pubertas, estrus,
perkawinan, kebuntingan,kelahiran, laktasi dan
efisiensi reproduksi.
Penulis menyadari bahwa paper ini belum sempurna,
namun penulis merasa gembira dan bangga apabila tulisan
ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan dengan
kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan
saran yang membangun demi penyempurnaan paper ini.
Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.
Denpasar, April
2014
Penulis
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................ii
DAFTAR ISI...............................................iii
BAB I PENDAHULUAN..........................................1
1.1 Latar Belakang......................................1
1.2 Rumusan Masalah.....................................1
1.3 Tujuan..............................................2
1.4 Manfaat........................................2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA....................................3
2.1. Pubertas............................................3
2.2. Siklus Birahi (Estrus)..............................5
2.3. Perkawinan..........................................9
2.4. Kebuntingan dan Kelahiran..........................11
2.5. Laktasi............................................22
BAB III PENUTUP...........................................24
3.1. Kesimpulan.........................................24
DAFTAR PUSTAKA............................................25
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peternakan Babi di Indonesia sejak zaman
kemerdekaan sampai saat ini sudah semakin berkembang
dan telah mencapai kemajuan yang cukup pesat.
Perkembangan peternakan khususnya ternak babi ke arah
peternakan komersial sudah ditata sejak puluhan tahun
yang lalu, bahkan pada saat ini peternakan Babi di
Indonesia sudah banyak yang bersekala industri.
Perkembangan ini tentu saja harus diimbangi dengan
pengelolaan yang profesional dan disertai dengan tata
laksana yang baik.
Tanpa pengelolaan dan tata laksana yang baik,
produksi ternak yang akan dihasilkan tidak akan sesuai
dengan harapan, bahkan peternak bisa mengalami
kerugian. Sehingga di harapkan Peternak atau segenap
pelaku usaha di bidang peternakan haruslah mengelola
dengan baik Sapta peternakan khususnya, karena Sapta
peternakan merupakan landasan kita untuk mengembangkan
dunia peternakan. Sapta peternakan itu meliputi :
bibit, pakan, kandang, pencegahan penyakit, reproduksi,
pemasaran dan pasca panen. Manajemen Reproduksi babi
merupakan suatu pola pemeliharaan yang harus dilakukan
oleh peternak, meliputi pubertas, siklus
1
birahi(estrus), perkawinan, kebuntingan, kelahiran, dan
masa laktasi serta efisiensi reproduksi.
1.2 Rumusan Masalah
1) Bagaimana manejemen reproduksi babi pada saat
pubertas?
2) Bagaimana manejemen reproduksi babi pada saat
estrus?
3) Bagaimana manejemen reproduksi babi pada saat
perkawinan?
4) Bagaimana manejemen reproduksi babi pada saat
kebuntingan?
5) Bagaimana manejemen reproduksi babi pada saat
kelahiran?
6) Bagaimana manejemen reproduksi babi pada saat
laktasi?
7) Bagaimana manejemen reproduksi babi pada saat
efisiensi reproduksi?
2
1.3 Tujuan
1) Untuk mengetahui manajemen pubertas
2) Untuk mengetahui manajemen estrus
3) Untuk mengetahui manajemen perkawinan
4) Untuk mengetahui manajemen kebuntingan
5) Untuk mengetahui manajemen kelahiran
6) Untuk mengetahui manajemen laktasi
7) Untuk mengetahui manajemen efisiensi reproduksi
1.4 Manfaat
Makalah ini bermanfaat untuk menambah referensi
bacaan bagi mahasiswa Kedokteran Hewan dan khalayak
umum yang menempuh bidang peternakan.
3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pubertas
Pubertas adalah periode saat organ-organ
reproduksi babi pertama kali berfungsi dan
menghasilkan telur atau sperma dewasa. Umur saat
pubertas dicapai berlainan antara bangsa-bangsa
ternak dan juga antara anak babi yang kelahirannya
sama. Faktor-faktor hormonal yang berperan untuk
merangsang pubertas pada babi jantan dan babi betina
belum banyak diketahui. Organ utama yang mengontrol
munculnya pubertas adalah kelenjar pituitary yang
letaknya di dasar otak. Kelenjar ini menghasilkan
dua hormone, yaitu FSH dan LH yang merangsang testis
dan ovarium. FSH, LH dan Testosteron yang
dihasilkan dalam testis adalah yang bertanggung
jawab untuk meningkatkan perkembangan dan pemasakan
sel-sel sperma pada jantan. Seekor babi jantan akan
mencapai pubertas pada umur 5- 6 bulan meskipun
tidak digunakan sampai mencapai umur 7- 8 bulan dan
hanya sebagai pejantan serap.
Hormon FSH mengakibatkan pertumbuhan dan
pemasakan sel-sel telur yang banyak terpendam dalam
ovarium. Hormon LH merangsang pelepasan telur-telur
dari folikel. Pubertas/birahi pada babi dara muncul
pada umur 5-6 bulan dengan rata-rata bobot badan
4
70-110 kg akan tetapi tidak dikawinkan sebelum umur
8 bulan atau pada periode estrus/birahi yang ketiga
hal ini berguna untuk produksi anak yang lebih
banyak dan lama hidup induk lebih panjang. Agar
diperoleh anak yang lebih banyak maka induk
dikawinkan pada 12 – 24 jam setelah tanda
estrus/birahi. Estrus atau birahi pada induk babi
adalah karena aktifitas dari hormon estrogen yang
dihasilkan oleh ovarium, kejadian ini terjadi selama
3 – 4 hari dengan perubahan tingkah laku seperti
suka mengganggu pejantan, kegelisahan meningkat,
menaiki betina lainnya dan nafsu makan menurun serta
mengeluarkan suara yang khas, kalau ditekan atau
diduduki punggungnya diam saja, vulva yang
membengkak dan memerah serta lendir keruh dan
mengental muncul, bila tanda tanda ini terlihat
berarti babi betina tersebut siap kawin. Dalam
praktek dengan dua kali perkawinan yaitu 12 dan 24
jam setelah tanda estrus dimulai supaya ovum banyak
dibuahi dan jumlah anak (litter size tinggi).
Berbagai faktor berpengaruh terhadap munculnya
pubertas pada babi betina.
1. Faktor Genetis
Babi betina Landrace mencapai pubertas lebih
dini daripada babi betina Hampshire, Yorkshire dan
Duroc, yang diamati dari banyaknya yang birahi pada
umur 6 bulan. Babi betina hasil persilangan juga
5
mencapai pubertas yang lebih dini daripada babi
betina murni.
2. Faktor Makanan
Makanan yang baik pada saat pertumbuhan akan
mempercepat terjadinya pubertas dan sebaliknya
makanan yang kurang saat pertumbuhan akan
memperlambat pubertas.
3. Faktor Musim
Di Negara-negara subtropics babi betina lebih
lama mencapai pubertas dibandingkan daerah musim
panas dan mungkin hal ini disebabkan oleh kondisi
klimat yang panas dan lembab.
4. Faktor Cahaya
Babi betina yang dipelihara terkurung dengan
kegelapan yang komplet memperpanjang umur pencapaian
pubertas. Babi betina yang dipilih untuk bibit
seharusnya memperoleh cahaya 18 jam per hari, karena
cahaya yang lebih banyak akan mempercepat terjadinya
pubertas
5. Faktor Perkandangan
Babi betina yang dipelihara terkurung lebih
lambat mencapai pubertas dari pada yang dipelihara
bebas. Babi betina yang dikandangkan atau ditambat
individual juga menunda pubertas dan menekan tanda-
tanda birahi. Kebersihan dan kepadatan kandang juga
menetukan terhadap kejadian pubertas.
6. Pengaruh Pejantan
6
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
introduksi pejantan ke sekelompok babi betina yang
sebelumnya tidak berkontak dengan pejantan,
merangsang dan menyebabkan sebagian babi betina
tersebut berahi pada umur 4 bulan
2.2. Siklus Birahi (Estrus)
Estrus yang dikenal dengan istilah birahi yaitu
suatu periode secara psikologis maupun fisiologis
pada hewan betina yang bersedia menerima pejantan
untuk kopulasi. Siklus estrus dibagi menjadi
beberapa fase yang dapat dibedakan dengan jelas yang
disebut proestrus, estrus, metestrus dan diestrus
(Frandson, 1996).
Estrus merupakan periode seksual yang sangat
jelas yang disebabkan oleh tingginya level
estradiol, folikel de Graaf membesar dan menjadi
matang, uterus berkontraksi dan ovum mengalami
perubahan kearah pematangan. Metestrus adalah
periode dimana korpus luteum bertambah cepat dari
sel-sel graulose folikel yang telah pecah dibawah
pengaruh Luteinizing hormone (LH)
dari adenohyphophysa. Diestrus adalah periode terlama
dalam siklus estrus dimana korpus luteum menjadi
matang dan pengaruh progesterone terhadap saluran
reproduksi menjadi nyata. Diestrus adalah periode
dimana folikel de Graaf bertumbuh dibawah
7
pengaruh follicle stimulating hormone (FSH) dan
menghasilkan sejumlah estradiol bertambah.
Siklus birahi pada setiap hewan berbeda antara
satu sama lain tergantung dari bangsa, umur, dan
spesies (Partodiharjo, 1992). Interval antara
timbulnya satu periode berahi ke permulaan periode
berikutnya disebut sebagai suatu siklus berahi.
Siklus berahi pada dasarnya dibagi menjadi 4 fase
atau periode yaitu ; proestrus, estrus, metestrus,
dan diestrus (Marawali, dkk., 2001; Sonjaya, 2005).
Berikut ini adalah keadaan korpus luteum dan folikel
pada ovarium sapi selama siklus estrus.
Proestrus
Proestrus adalah fase sebelum estrus yaitu
periode pada saat folikel de graaf tumbuh di bawah
pengaruh FSH dan menghasilkan sejumlah estradiol
yang semakin bertambah (Marawali, dkk, 2001).
Estradiol meningkatkan jumlah suplai darah ke
saluran alat kelamin dan meningkatkan perkembangan
estrus, vagina, tuba fallopi, folikel ovarium
(Toelihere, 1985).
Fase yang pertama kali dari siklus estrus ini
dianggap sebagai fase penumpukan atau pemantapan
dimana folikel ovarium yang berisi ovum membesar
terutama karena meningkatnya cairan folikel yang
berisi cairan estrogenik. Estrogen yang diserap dari
8
folikel ke dalam aliran darah merangsang peningkatam
vaskularisasi dan pertumbuhan sel genital dalam
persiapan untuk birahi dan kebuntingan yang terjadi
(Frandson, 1992).
Pada fase ini akan terlihat perubahan pada alat
kelamin luar dan terjadi perubahan-perubahan tingkah
laku dimana hewan betina gelisah dan sering
mengeluarkan suara-suara yang tidak biasa terdengar
(Partodiharjo, 1980).
Estrus
Estrus adalah periode yang ditandai dengan
penerimaan pejantan oleh hewan betina untuk
berkopulasi. Pada umumnya memperlihatkan tanda-tanda
gelisah, nafsu makan turun atau hilang sama sekali,
menghampiri pejantan dan tidak lari bila pejantan
menungganginya. Menurut Frandson (1992), fase estrus
ditandai dengan sapi yang berusaha dinaiki oleh sapi
pejantan, keluarnya cairan bening dari vulva dan
peningkatan sirkulasi sehingga tampak merah. Pada
saat itu, keseimbangan hormon hipofisa bergeser dari
FSH ke LH yang mengakibatkan peningkatan LH, hormon
ini akan membantu terjadinya ovulasi dan pembentukan
korpus luteum yang terlihat pada masa sesudah
estrus. Proses ovulasi akan diulang kembali secara
teratur setiap jangka waktu yang tetap yaitu satu
siklus birahi. Pengamatan birahi pada ternak
9
sebaiknya dilakukan dua kali, yaitu pagi dan sore
sehingga adanya birahi dapat teramati dan tidak
terlewatkan (Salisbury dan Vandenmark, 1978).
Metestrus
Metestrus ditandai dengan berhentinya puncak
estrus dan bekas folikel setelah ovulasi mengecil
dan berhentinya pengeluaran lendir (Salisbury dan
Vandenmark, 1978). Selama metestrus, rongga yang
ditinggalkan oleh pemecahan folikel mulai terisi
dengan darah. Darah membentuk struktur yang disebut
korpus hemoragikum. Setelah sekitar 5 hari, korpus
hemoragikum mulai berubah menjadi jaringan luteal,
menghasilkan korpus luteum atau Cl. Fase
ini sebagian besar berada dibawah pengaruh
progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum
(Frandson, 1992). Progesteron menghambat sekeresi
FSH oleh pituitari anterior sehingga menghambat
pertumbuhan folikel ovarium dan mencegah terjadinya
estrus. Pada masa ini terjadi ovulasi, kurang lebih
10-12 jam sesudah estrus, kira-kira 24 sampai 48 jam
sesudah birahi.
Diestrus
Diestrus adalah periode terakhir dan terlama
pada siklus berahi, korpus luteum menjadi matang dan
pengaruh progesteron terhadap saluran reproduksi
menjadi nyata (Marawali, dkk, 2001).
10
Ovulasi
Proses ovulasi dapat didefinisikan terlemparnya
cairan folikel serta ovum ke rongga peritoneal
disekitar inpendibullum oviduk atau tuba uterin.
Kebanyakan hewan mamalia, ovulasi sangat berkaitan
dengan birahi (estrus) karena absorbsi sejumlah
besar estrogen ke dalam aliran darah terjadi sesaat
sebelum ovulasi (Frandson, 1996).
Menurut Toelihere (1993) ovulasi didefinisikan
sebagai pelepasan ovum dari folikel de Graaf dan
secara umum dikenal bahwa ovulasi disimulir oleh LH,
tetapi mekanisme yang sebenarnya tidak diketahui,
mungkin LH menyebabkan pengendoran dinding folikel
sehingga lapisan-lapisan pecah dan melepaskan ovum
dan cairan folikel.
Apabila tidak terjadi fertilisasi, korpus
luteum berregresi yang disebut korpus albican.
Korpus albican ini dimulai regresi 14-15 hari
sesudah estrus. Namun jika terjadi fertilisasi lalu
kebuntingan korpus luteum akan terus bertahan selama
kebuntingan sebagai korpus luteum kebuntingan yanga
menghasilkan hormon progesteron untuk mempertahankan
kebuntingan (Toelihere, 1993).
11
Fisiologi Reproduksi Pada Babi Betina
Babi adalah ternak mamalia yang menghasilkan
anak dalam jumlah besar sekaligus dengan interval
generasi yang lebih singkat dari pada domba, sapi,
kerbau atau kuda. Sifat-sifat tersebut membuat babi
sebagai jenis ternak dengan potensi reproduksi yang
tinggi untuk produksi ternak komersial (Toelihere,
1993).
Pubertas adalah periode saat organ-organ
reproduksi babi pertama kali berfungsi dan
menghasilkan telur atau sperma dewasa. Umur saat
pubertas dicapai berlainan antara bangsa-bangsa
ternak dan juga antara anak babi sekelahiran
(Sihombing, 1997). Pubertas terjadi sebagai akibat
pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut dari
folikel-folikel dan pembentukan hormon-hormon
ovarial oleh folikel yang matang.
Seekor babi betina mencapai pubertas pada umur
5-8 bulan dan umur rata-rata yang dianjurkan untuk
perkawinan pertama adalah 8-10 bulan (Toelihere,
1993). Babi betina yang berahi memperlihatkan suatu
respon diam atau sikap kawin yang jelas apabila
ditekan punggungnya oleh pejantan. Respon ini sangat
bermanfaat dalam deteksi bukan saja permulaan birahi
tetapi juga tingkatan birahi karena suatu sikap yang
lebih tenang dan kaku diperlihatkan selama
pertengahan periode berahi (Toelihere, 1993).
12
Siklus etrus berlangsung kira-kira 21 hari dan
estrus sendiri berlangsung selama 3-5 hari (Smith
dan Mangkoewidjojo, 1988). Ada empat fase yang jelas
dalam siklus berahi babi yaitu:
1. Proestrus : terjadi sebelum estrus dan terjadi
selama 3-4 hari
2. Estrus : berlangsung selama 2-3 hari dan pada
periode tersebut betina memiliki seksual reseptif
terhadap pejantan. Periode ini biasanya lebih
pendek pada babi dara dibandingkan babi induk.
Pada saat estrus akan terjadi ovulasi.
3. Metestrus: terjadi setelah ovulasi, corpus luteum
terbentuk dalam setiap folikel yang pecah dalam
waktu 6-8 hari.
4. Diestrus: adalah waktu inaktivitas yang pendek
yang ditandai oleh penghancuran corpus luteum
setelah 14 hari dari puncak berahi. Dalam 3-4
hari serombongan folikel baru mulai berkembang
dan siklus tadi akan terulang sendiri.
5. Siklus estrus pada babi
6. Birahi pada babi berlangsung 2 sampai 3 hari
dengan variasi antara 1 sampai 4 hari. suatu
batasan yang nyata antara permulaan dan akhir
estrus sulit ditentukan karena estrus adalah
suatu fenomena yang berlangsung gradual.
7. Babi betina yang birahi memperlihatkan suatu
respon diam atau sikap kawin yang jelas apabila
13
ditekan punggungnya baik oleh pejantan, oleh
betina lain atau penunggu ternak. Respon ini
sangat bermanfaat dalam deteksi bukan saja
permulaan birahi tetapi juga tingkatan birahi
karena suatu sikap yang lebih tenang dan kaku
diperlihatkan selama pertengahan periode birahi.
8. Ovulasi terjadi selama estrus pada babi betina
dan sebagian besar ova dilepaskan 38 sampai 42
jam sesudah permulaan estrus. Lama proses ovulasi
adalah 3,8 jam. Ovulasi terjadi kira-kira 4 jam
lebih cepat pada betina yang sudah dikawinkan
dibandingkan dengan pada betina yang belum kawin.
9. Siklus birahi pada babi mencapai 19 sampai 23
hari, rata-rata 21 hari, dan relatif konstan.
Estrus terjadi sepanjang tahun. Corpora lutea
bertumbuh sempurna dalam waktu 6-8 hari dan,
kalau hewan tidak bunting, beregresi kembali pada
hari ke 14 sampai ke-16 siklus birahi.
2.3. Perkawinan
Hanya pada saat-saat birahi saja, babi mau
menerima pejantan atau dapat dikawinkan. Tanpa
timbul birahi, babi tidak dapat dipaksakan kawin.
Oleh karena itu peternak secara cepat mengetahui
masa birahinya. Rata-rata interval tiap sesi proses
yang mempengaruhi fertilisasi babi adalah sebagai
berikut:
14
a) Umur saat pubertas : 4-7 (bulan) rata-rata 6
(bulan)
b) Lama birahi : 1-5 (hari) rata-rata 2-3
(hari)
c) Panjang siklus birahi : 18-24 (hari) rata-rata
21 (hari)
Untuk mengetahui saat birahi seekor babi secara
tepat, kita perlu mengetahui tanda-tanda birahi.
Tanda-tanda birahi yang dapat ditemukan pada seekor
babi adalah sebagai berikut :
a) Babi nampak gelisah dan berteriak-teriak
b) Kemaluan bengkak, pada vulva nampak merah, bagi
babi induk yang sudah sering beranak biasanya tak
begitu nampak merah
c) Selalu mencoba menaiki temannya, atau ingin
keluar dari kandang
d) Bila punggung diberi beban atau diduduki diam
saja.
e) Dari kemaluan sering keluar lendir.
Menurut penelitian, ovulasi dimulai dengan
terlepasnya sel telur dari indung telur 30-35 jam
atau hari kedua setelah gejalah birahi terlihat.
Sedang sel jantan (sperma) yang ada didalam vagina
cervix akan saling bertemu pada saluran telur
(oviduc) bagian atas dekat ovarium.
Didalam alat reproduksi betina, sperma dapat
hidup 24-48 jam. Dan untuk mencapai oviduc
15
memerlukan waktu 4-6 jam. Akan tetapi perlu
diketahui bahwa ada sperma yang hidupnya lebih
pendek, kurang dari 24 jam setelah terjadi ovulasi
dan tidak semua sel telur bisa dibuahi. Jumlah sel
telur bisa 12-16, yang masak bersama-sama dan bisa
dibuahi. Akan tetapi sering juga sampai 20 buah:
sebaliknya, juga tidak jarang hanya 3 atau 4 buah.
Kita mengawinkan babi harus betul-betul tepat pada
waktunya, yakni babi dikawinkan pada hari kedua
setelah nampak birahi. Terkecuali babi dara (gilt)
bisa dikawinkan pada hari pertama dari masa birahi.
Karena birahnya babi dara lebih pendek dibanding
babi-babi yang pernah beranak. Apabila babi yang
sedang birahi itu tidak dikawinkan, birahi akan
terulang kembali pada 18 – 24 hari, atau rata-rata 3
minggu (21 hari)
Khususnya untuk babi dara diperlukan perlakuan
khusus. Babi mulai baliq pada umur 5-6 bulan, sudah
birahi tapi sebaiknya jangan dikawinkan dulu, karena
kedewasaan tubuh baru tercapai pada umur 8-10 bulan
dengan berat badan + 100-120 kg.Untuk mencapai
konsepsi (pembuahan) yang tinggi hendaknya, babi itu
dikawinkan 2 kali selama masa birahi. Babi yang baru
dikawinkan hendaknya ditempatkan tepisah dari babi-
babi lain, selama 2 hari, diberikan makanan yang
baik dan ditempatkan dilingkungan tenang.
16
Untuk induk yang pernah beranak yang akan
dikawinkan kembali, sebelumnya dilakukan penyapian
terlebih dahulu. Induk yang habis menyapih pada
umumnya akan birahi lagi 3-10 hari. Biasanya babi
yang baru menyapi akan kurus, maka sebaiknya
perkawinan ditunda dulu sampai babi gemuk dan sehat
kembali.
Untuk mengawinkan babi bisa dilakukan dua
sistem yakni:
1. Perkawinan Alam
Pada umumnya perkawinan bisa berlangsung selama
10 – 15 menit. Babi betina yang birahi dimasukkan
dalam kandang pejantan, bisa dikawinkan sampai dua
kali untuk mendapatkan hasil yang optimal. Betina
yang kecil dan jantan yang besar bisa dibantu dengan
membuat kandang secara khusus. Perbandingan jantan
dan betina : jantan usia 1 tahun adalah 1jantan :
15-20 betina; umur jantan setahun keatas adalah 1
jantan : 30 betina.
2. Perkawinan buatan = Artificial Insimination (AI)
= Insiminasi buatan (IB)
Perkawinan ini adalah memasukkan serma kedalam
kelamin betina dengan tindakan manusia.
Keuntungan AI atau IB antara lain dapat
memanfaatkan seekor pejantan bisa diperbesar.
Perkawinan bisa dilakukan diantara hewan yang
tempatnya berjauhan, misalnya babi Indenesia dengan
17
Autralia atu Belanda. Dengan IB, tidaklah setiap
peternak memelihara pejantan sendiri sehingga bisa
hemat biaya. Pemacek yang karena sesuatu hal,
misalnya pejantan terlalu besar, pincang, dst sulit
dilakukan, dengan IB dapat dikerjakan.
Sedangkan kelemahan IB yaitu tidak semua
inseminator mempunyai pengalaman yang cukup,
sehingga hasil kurang terjamin. Kemungkinan akan
terbawanya bagian penyakit senantiasa ada, karena
pelaksanaannya yang ceroboh. Menyebarkan keturunan
yang jelek. Misalnya karena sperma diambil tanpa
memilih pejantan yang bagus. Terlalu banya babi yang
memiliki keturunan yang sama (inbreed)
2.4. Kebuntingan dan Kelahiran
1. Pemeliharaan Induk Bunting Awal
Segera setelah babi dara (calon induk) atau
induk dikawinkan secara tepat, perlu dilakukan
pengecekan setiap 20-21 hari selama dua kali
berturut-turut untuk memastikan kebuntingan sudah
terjadi, yaitu tidak memperlihatkan tanda-tanda
estrus. Hari kebuntingan dihitung saat babi
dikawinkan, dan hari partus 115 hari kemudian. Bila
setelah dikawinkan masih ada tanda estrus, berarti
kebuntingan belum terjadi dan induk harus dikawinkan
ulang. Sampai tanda estrus tidak nampak setelah
kawin ulang, maka tanggal kawin ulang tersebut
18
ditetapkan sebagai hari awal kebuntingan dan partus
ditetapkan 115 hari berikutnya.
Jika keadaan memungkinkan, setelah babi dara
atau induk positif bunting, maka pemeliharaannya
harus terpisah dari induk kering/babi dara lainnya
yaitu pada kandang khusus induk bunting. Hal ini
dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan, seperti perkelahian dan sebagainya.
Sampai 2,5 bulan pertama tidak ada hal-hal istimewa
yang perlu dilakukan dalam menangani induk bunting
awal ini. Makanan diberi dalam jumlah biasa, yaitu
2,5 kg/ekor/hari.
2. Pemeliharaan pada akhir kebuntingan
Sebulan sebelum tanggal penetapan kelahiran
disebut sebagai masa kebuntingan akhir. Jika
memungkinkan, persiapkan kandang khusus untuk
partus. Pada akhir kebuntingan ini, induk tidak
dicampur dengan induk kering atau status lainnya.
Kandang harus cukup ruangan untuk induk berjalan-
jalan (exercise) guna memperlancar peredaran darah
saat proses kelahiran. Induk dan kandang harus
selalu bersih. Seminggu sebelum partus, induk
diperkenalkan dengan kandang beranak. Hal ini perlu
untuk induk beradaptasi dengan lingkungan kandang
yang baru. Sebelum dimasuki induk untuk beranak,
19
kandang didesinfeksi; dan induk dimandikan,yakni
dibersihkan dengan sabun dan air hangat.
Tujuan memelihara induk yaitu menghasilkan dan
membesarkan anak-anaknya sampai saat penyapihan.
Semakin efisien tugas induk semakin besar profit
suatu usaha peternakan babi. Profit di dalam usaha
peternakan babi secara sederhana diukur dengan
rumus: profit = output – input cost (hasil penjualan
dikurangi biaya produksi). Bila lama laktasi 6
minggu, maka hitungan siklus melahirkan induk adalah
365 : 163 = 2,23 kali/tahun.
3. Pemberian makan induk bunting
Keinginan memberikan makan induk babi sebanyak
mungkin agar menghasilkan air susu sebanyak mungkin,
mempertahankan kondisi tubuh jumlah besar anak-anak
tetap berat. Agar supaya induk babi dapat
menghasilkan panas sekitarnya dan mencegah untuk
bergerak maka tempatkan induk babi tersebut dalam
luasan kandang terbatas sehingga akan memudahkan
juga penggunakan kandang sapihan. Penggunaan panas
kandang dengan lampu rumah yang sulit bagi sebagian
masyarakat akan memberikan pengaruh pada induk babi.
Pembuktian cara alternatif yang ekonomis dan lebih
efisien dan jauh lebih maju harus terus dilakukan.
Jumlah konsumsi induk babi tergantung pada suhu
lingkungan. Suhu kandang yang ideal untuk induk babi
20
bunting adalah antara 64-68° F, tetapi yang ideal
untuk anak babi pada 102°F. Perbedaan ini merupakan
kesulitan utama. Untuk setiap peningkatan 2° F suhu
lingkungan di atas 68° F, induk babi akan mengurangi
jumlah konsumsi 0,5 kg pakan per hari. Setelah
periode penyapihan, penting memberikan pakan induk
hingga terus meningkat pada hari ke-10 masa laktasi.
Tetapi pemberian makanan berlebihan bagi induk
bunting, akan membuat nafsu makannya menurun.
Peningkatan gizi harus mencerminkan peningkatan
volume produksi air susu induk.
Proses kelahiran (partus) merupakan salah satu
faktor paling kritis dalam keseluruhan proses
produksi ternak babi, dalam hubungan dengan
kesejahteraan induk babi dan anak-anaknya. Berbagai
hal dapat terjadi yang dapat menyebabkan kematian
atau setidaknya menurunkan efisiensi pemeliharaan
induk dan anak-anaknya. Oleh sebab itu penting
sekali untuk menghasilkan suatu kelahiran normal,
dan mengetahui secara dini bila ada kelainan supaya
dapat diambil tindakan secepatnya.
4. Proses beranak (farrowing process)
Pernahkah terpikir bahwa saat anak babi lahir,
maka sistem produksi induk akan terpengaruh? Proses
kelahiran anak babi merupakan perubahan drastis suhu
yang konstan 103° F menjadi 36° F. Dari suhu hangat
21
tubuh induk anak babi akan keluar berpindah melalui
leher rahim menuju ke suatu tempat dengan kondisi
dalam keadaan basah serta dingin berangin. Anak babi
keluar dan terjatuh ke tempat di tengah-tengah alas
kering yang sebagian merupakan tumpukan kotoran
babi.
Hal seperti ini sering terjadi tetapi sebagian
besar anak-anak babi mampu bertahan. Tetapi, apabila
terjadi stress dalam proses kelahiran atau tidak
berjalan baik, maka akan berpengaruh negatif pada
potensi produktivitas babi. Jika hal itu terjadi
pada proses beranak (partus), dapat mengakibatkan
anak babi tidak bertumbuh dengan baik sehinga tidak
mencapai berat ideal saat pemotongan.
Karena laju pertumbuhan berkurang, rendah pula
konversi pakan menjadi daging selama proses
pertumbuhan anak babi. Dari sudut ekonomi, masih
lebih baik anak babi mati pada saat masih kecil,
dianggap sebagai risiko kerugian pada tahap awal.
Sementara itu induk dapat menyusui mereka yang
selamat untuk mendapatkan pengganti energi
cadangannya yang rendah. Induk akan mendapatkan
sumber panas tubuh dari putingnya sehingga dapat
melanjutkan produktivitasnya.
Pada proses partus, ada persyaratan unik yang
harus diperhatikan bagi anak babi. Setiap individu
harus dirawat tersendiri agar dapat mengurangi
22
stress yang dialaminya. Idealnya anak-anak babi
harus dikeringkan pada saat lahir, dan dimasukkan ke
dalam iklim mikro pada 102 °F, dan disusui segera
setelah induknya siap. Pada umumnya proses partus
terjadi pada malam hari tanpa pengawasan, kecuali
kalau ada perlakuan prostaglandin untuk mengatur
waktu partus.
Tubuh anak babi memiliki luas permukaan yang
relatif sangat besar dibandingkan dengan berat
badannya sehingga dengan cepat akan kehilangan panas
dan cadangan energi, maka kebutuhan panas dalam
keadaan kering sangat penting. Setelah selesai
proses partus, persyaratan lingkungan anak babi
dapat disiapkan dengan menyediakan tempat beriklim
mikro yang sesuai. Tempat itu harus dekat dengan
induknya, tapi masih melindungi anak dari tindihan
induk babi (crushing), dan meminimalisasi pengaruh
panas induk babi. Tempat tersebut disebut kandang
sapihan (brooder) yang harus mudah dikontrol.
5. Proses partus induk babi
Tanda-tanda induk akan memasuki periode partus
adalah setelah gangguan bergerak teratasi, induk
mulai terlihat duduk dan mencoba membuat sarang
untuk persiapan partus meskipun tidak tersedia
material baginya. Selanjutnya peternak akan
mengarahkan induk babi ke kandang tempat beranak,
23
suhu tubuhnya meningkat, dan mulai terlihat tanda
kesakitan. Kontraksi datang cepat, dan terlihat
mulai ganas karena rasa sakitnya. Setelah mengalami
kelelahan beberapa jam, induk tua dapat mengatur
kondisi otot yang baik sebelum proses partus. Jika
beranak dengan jumlah ’litter size’ 13 dalam selang
waktu 20 menit per kelahiran, maka akan memakan
waktu rata-rata 260 menit atau 4 jam lebih.
Apabila kondisinya lemah, induk akan cepat
menjadi lelah sehingga proses pengeluaran foetus
lebih lama, yang akan mengakibatkan anak babi mati
lemas, dan hasilnya lahir mati. Anak babi yang lain
akan kekurangan oksigen (anoxia) dan akan cacat
permanen walaupun dapat bertahan hidup. Karena
aktivitas otot dan sumber panas punggungnya, induk
babi pun menjadi rentan terhadap panas yang
disebabkan kelelahan, sehingga akan melahirkan anak-
anak babi yang sudah mati.
6. Pemberian makanan pada induk menyusui
Setelah beranak atau proses partus sampai
beberapa hari, nafsu makan induk babi pun menurun.
Karena itu perlu pemberian air minum yang banyak.
Setelah 3 hari, ransum makanan induk diberikan agar
produktivitas air susu induk sesuai dengan jumlah
anak.
24
7. Pemeliharaan anak-anak babi yang baru lahir
Tiga hari pertama setelah beranak merupakan masa
kritis, sebab anak babi sangat peka terhadap berbagai
bahaya. Tanpa bulu-bulu yang cukup untuk melindungi
tubuhnya, anak-anak babi sangat peka terhadap udara
dingin. Kemungkinan terinjak atau terhimpit oleh
induk, atau kelaparan bila produksi susu induk jelek
sehingga anak kekurangan gizi dan lemah.
Perhatikan baik-baik anak-anak babi ini bila
menjerit lapar. Perhatikan dan periksa puting susu
atau ambing induknya: bila terasa sangat panas atau
sangat dingin, segera panggil dokter hewan untuk
dibedah. Setelah 3 hari pertama masa kritis berlalu,
anak-anak babi akan menjadi lebih baik. Pada masa
setelah kelahiran (post farrowing), adalah penting
mengarahkan anak-anak babi sampai ke ambing supaya
mendapatkan konsumsi kolostrum.
Ternak muda memiliki kemampuan untuk menyerap
antibodi secara langsung ke dalam aliran darah untuk
beberapa jam pertama setelah lahir. Kemampuan
tersebut kemudian akan berkurang karena penambahan
usia, dan terutama setelah cairan pertama tertelan.
Oleh karena itu penting bahwa semua anak-anak babi
harus dapat menyusui kolostrum yang kaya antibodi.
Dalam kandang besar, praktik perlakuan yang baik
adalah mengumpulkan anak babi yang pertama lahir, dan
membatasi mereka di daerah ‘creep feeder’ supaya akses
25
Gambar Kandang sapihan (brooder) tradisional
ke ambing anak-anak babi yang lahir kemudian tidak
terhalang.
8. Pemeliharaan Anak Babi
a. Pemotongan Taring dan Ekor
Anak babi yang baru lahir mempunyai gigi yang
tajam yang dapat menimbulkan rasa sakit pada
puting induk saat menyusu. Ujung gigi ‘canin’ dan
‘pre molar’ ini harus dihilangkan dengan
menggunakan gunting yang tajam (pinset gigi).
Dalam proses perkembangan selanjutnya, juga
sering dilakukan pemotongan terhadap ekor anak
babi. Ekor anak babi akan cukup merugikan dalam
proses perkembangan dan pertumbuhannya. Beberapa
hal merugikan apabila ekor ternak babi dibiarkan,
yaitu mudah terjadi perkelahian atau gigitan
antarternak pada ekor; hal lainnya ekor juga akan
menyebabkan ternak babi turut mengibaskan kotoran
26
ke tempat makan atau ke sesama ternak dalam
kandang.
Pemotongan taring dan ekor dilakukan pada
saat masih anak babi agar mudah dilaksanakan dan
mengurangi resiko terlalu banyak pendarahan,
tetapi harus dilakukan secara steril dan higienis
untuk menghindari serta mengurangi terjadinya
infeksi penyakit yang sangat mudah menyerang anak
babi. Operator pemotongan taring dan ekor
sebaiknya sangat memperhatikan kemungkinan adanya
anak babi yang sakit agar tidak ditempatkan
bersama-sama dengan ternak yang sehat.
b. Penyuntikan Ferrum
Zat besi di dalam tubuh anak babi sangat
terbatas, padahal zat itu sangat esensial untuk
pembentukan hemoglobin, yaitu pigmen dalam sel
darah merah yang bertanggung jawab membawa oksigen
ke seluruh tubuh. Defisiensi zat besi ini
menyebabkan anemia, yaitu suatu penyakit yang
lazim terjadi pada anak-anak babi yang dipelihara
dalam kandang. Kadar zat besi di dalam air susu
induk sangat sedikit, karena itu sangat perlu
menambahkan zat besi pada anak babi yang baru
lahir. Penambahan ini dapat diberikan melalui oral
atau dengan injeksi.
c. Penimbangan pada umur 3 minggu
Sangat dianjurkan menimbang anak babi sebab
27
hal ini menjadi indikator tentang kemampuan induk
mensuplai air susu, karena berat anak babi (litter)
pada umur 3 minggu semata-mata tergantung pada
penampilan induk babi akan kemampuannya
menghasilkan dan memberi makan anak-anaknya.
Gambar Timbangan Ternak Modern
9. Pemeliharaan Masa Penyapihan
a. Penyapihan
Penyapihan ternak atau hewan adalah suatu
periode transisi dari hewan mamalia muda, dari
ketergantungan gizi dan sosial secara menyeluruh
terhadap induknya, menjadi bebas dari
ketergantungan pada induknya. Proses penyapihan
pada umumnya sulit dan lambat. Dalam periode
tersebut hewan/ternak muda mulai menunjukkan
28
perilaku dewasa dalam memenuhi kebutuhan berbeda
seturut umurnya.
Umur anak babi bebas/tidak tergantung pada
induknya dapat tercapai dalam kondisi alamiah,
tergantung pada interaksi yang rumit antara
kepentingan sepihak sang induk dan anak babi muda
(off spring).
Optimalisasi untuk menyelesaikan proses
penyapihan, dari sudut pandang induk, akan berbeda
ketika induk telah berinvestasi cukup pada babi
muda dalam memaksimalkan peluang berkembang biak
mereka sesuai dengan peningkatan usia hidup,
diiringi dengan konsistensinya untuk
mempertahankan tingkat energi yang cukup tinggi
agar mereka berhasil dalam berkembang biak. Ternak
muda biasanya memiliki ketergantungan yang lebih
pada induknya untuk bertahan lebih lama memenuhi
kebutuhan mereka yang tinggi dari induk supaya
mendapatkan pertumbuhan yang optimal.
Untuk menentukan akhir proses penyapihan
perlu memperhatikan keseimbangan antara berbagai
faktor, seperti kondisi gizi induk, kemungkinan
berkembang biak lagi, kondisi gizi ternak muda,
dan jumlah perawatan yang masih disediakan oleh
induk secara alami setelah penyapihan.
Untuk dapat melahirkan dua kali setahun, maka
induk babi harus menjaga anaknya paling lambat
29
pada umur 2 bulan (8 minggu). Tetapi dengan
kemajuan teknologi dalam kandang dan manajemen,
maka tak perlu menunggu sampai 8 minggu. Banyak
peternak melakukan penyapihan pada umur 5 minggu
(berat badan <13 kg).
Di negara maju seperti USA, bahan-bahan pakan
yang tinggi protein, seperti dadih (whey kering),
yaitu bahan hasil sisa pembuatan keju, dan susu
skim kering tidak diijinkan sebagai ransum babi
starter (anak babi). Karena itu, penyapihan
dilaksanakan tidak lebih awal dari umur 28 hari.
Karena baru setelah umur tersebut, sistem
pencernaan anak babi sudah mampu mencerna secara
efektif makanan yang berbasis butiran, seperti
sereal gandum, dan tidak berefek buruk bagi
kesehatan dan penampilan produksi ternak babi,
maka para ahli menyarankan agar penyapihan
dilakukakan pada usia >35 hari.
Dalam proses penyapihan, cara yang baik
dilakukan adalah induk dipisahkan dari anak (induk
keluar dari kandang beranak) dan bukan sebaliknya.
Hal ini berarti bahwa anak-anak babi tetap dalam
lingkungan kelompok yang sama sehingga mengurangi
stress pada anak babi. Pemeliharaan anak babi yang
disapih bertujuan untuk keuntungan potensial masa
depan. Penyapihan dan pemeliharaan yang tepat akan
menjamin kerja dan eksistensi masa depan usaha
30
peternakan. Memelihara dengan baik akan menjadi
permulaan yang baik dan sangat penting bagi masa
depan kinerja dan profitabilitas usaha.
b. Proses penyapihan
Penyapihan adalah masa pemeliharaan yang
sangat traumatis bagi anak babi. Peternak akan
mengganti atau memindahkan sumber utama makanan
dan air dari kandang dan mengelompokkan anak-anak
babi keluar dari induknya. Di banyak peternakan,
kelompok anak babi akan digabungkan dengan
sejumlah besar ternak babi lain; dipindahkan
dengan memasukkan mereka ke dalam gerobak atau
trailer, atau lebih buruk lagi dengan angkutan
tanpa pelindung, dan dibawa dan dipindahkan ke
kandang yang baru. Ada yang tetap dalam kandang
mereka, tetapi yang lain dipindahkan dan
dicampuradukkan dengan ternak babi lain yang lebih
besar dan berbeda jenis, yang mana per kandang
(pen) dapat bervariasi jumlah anak babinya, dari
sepuluh hingga ratusan.
31
c. Tujuan utama penyapihan
Tujuan utama penyapihan adalah mendapatkan
anak-anak babi yang baik dan mengkonsumsi pakan
secepat mungkin. Anak-anak babi diberi makan
secara ‘ad libitum’ dengan makanan hangat, steril,
dan bergizi tinggi untuk pengganti air susu induk
babi. Makanan dan minuman yang memadai tersebut
harus tersedia bagi semua anak babi supaya mereka
makan dan minum bersama.
Air bersih harus tersedia secara bebas di
tempat minum yang terbuka di kandang. Jika anak
babi tidak minum maka ia akan berhenti makan dan
mengalami dehidrasi sangat cepat. Dehidrasi adalah
risiko terbesar pasca penyapihan. Harus selalu
diperhatikan dengan sangat bahwa sistem pengairan
bekerja dengan benar, dan tempat air pada jaringan
pipa tangki harus bersih untuk ketersediaan air
bersih dan segar. Apakah tidak tersedia sistem air
minum dalam bentuk putting, maka sistem
pemeliharaan air harus baik. Sistem ketersediaan
32
Gambar Kandang sapihan (brooder) modern
air minum berada di sekitar kandang agar
memudahkan anak babi sapihan mengakses air.
Dalam beberapa hari pertama, air segar dan
makanan harus diberikan sesering mungkin dalam
kandang (pen) anak babi sapihan. Sedikit tetapi
sering adalah yang terbaik. Butiran (creep feed)
tidak boleh disimpan dalam tempat tertutup atau
kantung tertutup dalam gudang penyimpanan karena
pakan tersebut akan menyerap bau dan menjadi cepat
basi.
Jika terlalu banyak tersedia pakan segar bagi
anak babi sapihan, maka akan banyak pakan yang
terbuang–jika sudah mencapai lebih dari 10% maka
itu–merupakan biaya pemborosan yang besar untuk
usaha ternak babi.
Induk babi sering menyusui pada malam hari
dan setelah itu anak babi akan mencari makanan.
Karena itu disarankan kandang sapihan (brooder)
perlu diberikan penerangan lampu supaya anak babi
bisa bergerak di malam hari, dan untuk
mempertahankan suhu tetap hangat di lingkungan
kandang. Ternak babi memiliki penglihatan kurang
pada malam hari. Pemberian makanan anak babi
sapihan harus pada malam hari, diberi makan dan
minum malam dan pagi hari esoknya.
Tempat makan harus selalu dalam keadaan
bersih dari sisa makanan lama setiap pemberian
33
makan. Tetapi sisa makanan ini dapat diberikan
kepada babi lebih tua. Hal rutin yang berguna
adalah menempatkan alas kayu solid atau nampan di
lantai kandang untuk beberapa hari pertama sebagai
tempat pakan butiran.
2.5. Laktasi
Proses pelepasan susu dipengaruhi oleh hormone
dan mekanismenya adalah melalui stimulasi dari
hipotalamus, oksitosin dari kelenjar hipofisis
posterior yang disekresikan ke dalam darah, akan
menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitel disekeliling
alveoli dan saluran susu. Namun pelepasan oksitosin
ini bisa dihambat oleh pelepasan adrenalin dan
epineprin akibat terjadi ketakutan maupun kegelisahan
dari hewan. Adrenalin menyebabkan vasokontriksi
sehingga suplai darah dan oksitosin akan berkurang
didalam mamae (Toelihere, 1985).
Pada saat laktasi, produksi susu induk yang
maksimal dicapai pada minggu ketiga dari masa laktasi,
setelah itu akan menurun secara teratur. Untuk
mempertahankan laju pertumbuhan anak babi perlu
diberikan pakan tambahan. Pakan tambahan ini disebut
Krip.
Manfaat krip ini adalah untuk :
1. Manambah bobot badan anak babi saat disapih.
34
2. Mempertahankan kondisi induk babi saat
anaknya disapih.
3. Memperkecil hambatan pertumbuhan anak babi
lepas sapih.
Makanan krip awal yang diberikan berupa susu skim
ataupun lemak tambahan, dengan sedikit bahan produk
bukan susu seperti pati, sukrosa dan tambahan protein
bukan susu berkualitas baik.
Mekanisme dan Hormon yang berpengaruh pada laktasi
Pertumbuhan dari kelenjar mamae dapat dipengaruhi
oleh beberapa hormone diantaranya adalah:
a. Estrogen, hormone pertumbuhan dan kortisol,
menyebabkan awal pertumbuhan dari sistem saluran.
b. Progesteron : Menyebabkan pertumbuhan lebih lanjut
dari sistem saluran atau duktus serta perkembangan
alveolar.
c. Prolaktin : Perkembangn alveoli, mulai sekresi
susu dan mempertahankan laktasi (Toelihere, 1985).
Dalam merangsang laktasi prolaktin harus
bekerjasama dengan hormone lain seperti Cortisol,
GH, hormone tyroid, dan Insulin.
Laktasi terdiri dari dua fase yaitu sekresi susu
dan pelepasan susu,
1. Sekresi susu terdiri dari:
a. Sintesa penyusun susu dalam sel alveoli
35
b. Pengangkutan secara intramuscular dari unsur-unsur
pembentukan susu
c. Pengeluaran penyusun susu dari sel ke dalam lumen
alveoli.
2. Pelepasan susu terdiri dari:
a. Pelepasan pasif susu dari penampung susu dan
duktus besar
b. Pancaran susu secara reflex dari alveoli
(Tomaszewska, 1991).
2.6.
36
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Manajemen Reproduksi babi merupakan suatu pola
pemeliharaan yang harus dilakukan oleh peternak.
Adapun manajemen reproduksi tersebut meliputi pubertas
sampai proses laktasi. Pubertas adalah periode saat
organ-organ reproduksi babi pertama kali berfungsi dan
menghasilkan telur atau sperma dewasa. Faktor yang
mempengaruhi pubertas adalah genetik, makanan, musim,
cahaya, kandang, dan lingkungan. Setelah masa pubertas,
babi betina mengalami 5 siklus estrus yang berlangsung
selama 21 hari. Babi betina hanya menerima pejantan
pada masa birahi saja. Pada saat inilah terjadi
perkawinan. Lama perkawinan pada babi sekitar 10-20
menit. Pada masa kebuntingan terjadi selama 114 hari,
dan proses kelahiran pada babi 1-12 jam. Setelah proses
kelahiran perlu diperhatikan apakah induk menyusui, hal
ini harus diperhatikan karena pemberian air susu induk
24 jam pertama mengandung kolostrum yang bermanfaat
bagi anak babi.
37
DAFTAR PUSTAKA
Frandson,R.D.1992.Anatomi dan Fisiology Ternak,edisi ke-4
diterjemahkan oleh Srigandono,B dan Praseno,K.Gadjah Mada
University Press.Yogyakarta
Frandson, R.D., 1996, Anatomi dan Fisiologi Ternak, Edisi ke-
7, diterjemahkan oleh Srigandono, B dan Praseno,
K, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.http://beternakcara.blogspot.com/2013/
11/pubertas-pada-ternak-babi.html
Najibulloh, Muhamad. 2012. Pola dan Sistem Produksi pada
Ternak. http://najibdhevie.blogspot.com/2012/12/pola-dan-
sistem-produksi-pada-ternak.html. Diakses pada tanggal 3
Juni 2014.
Marawali, A., M.T. Hine, Burhanuddin, H.L.L.
Belli. 2001. Dasar-dasar ilmu reproduksi ternak.
Departemen pendidikan nasional direktorat
pendidikan tinggi badan kerjasama perguruan
tinggi negeri Indonesia timur. Jakarta.
Partodiaharjo, S. 1992. Ilmu Reproduksi Hewan. PT. Mutiara
Sumber Widya. Jakarta Lopez, H., L. D. Satter,
and M. C. Wiltbank.2004. Relationship between
level of milk production and estrous behavior of
lactating dairy cows. Anim. Reprod. Sci. 89:209–
223.
38