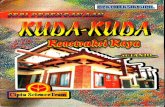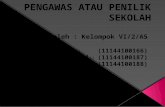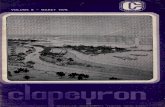Konstruksi Teori John Rawls Dikaitkan dengan Etika Profesi Hukum
Transcript of Konstruksi Teori John Rawls Dikaitkan dengan Etika Profesi Hukum
REVIEW ARTICLE
MATA KULIAH TANGGUNG JAWAB PROFESI
THE SECOND PRINCIPLE AND DISTRIBUTIVE JUSTICE
R.M. AGUNG PUTRANTO WIBOWO
1206209684
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
2015
Konstruksi Pemikiran John Rawls dalam Suatu Etika Penegakan
Hukum yang Baik oleh Profesi Hukum
Abstrak
Kisruh yang terjadi belakangan ini antar sesama lembaga
penegak hukum menjadikan penulis sejenak berpikir, mengapa
persoalan hukum begitu terangnya dipertontonkan sebagai ajang
kepentingan politik? Ternyata memang benar bunyi adagium
politik dan hukum yang diibaratkan sebagai tulang dan daging.
John Rawls dalam teorinya mengemukakan dua persyaratan
kelembagaan yang dikenakan oleh fair equality of opportunity, yaitu
mencegah akumulasi properti dan kekayaan yang berlebihan, dan
mempertahankan kesempatan yang sama terhadap pendidikan untuk
semua.
Pada prakteknya di Indonesia, pengangkatan para pejabat
institusi penegak hukum tidak hanya dilihat berdasarkan unsur
pendidikan dan pengalamannya saja, namun terdapat pula
keterlibatan unsur politik dalam hal pengangkatan pejabat
institusi penegak hukum. Sehingga apabila berkaca dari teori
Rawls, maka kesempatan yang sama untuk dapat mengisi jabatan
pada suatu institusi penegak hukum tidak terlepas dari campur
tangan politik.
Fair Equality of Opportunity
Pemikiran mengenai fair equality of opportunity berkembang
karena adanya penolakan dari keturunan bangsawan, dan ide
bahwa orang-orang yang ditugaskan menempati posisi atau
jabatan pada saat itu dilihat dari kelahiran. Equal opportunity
adalah cara lain dari pemikiran liberal yang menggabungkan
nilai kesetaraan (selain persamaan hak dan kebebasan dasar).
Konsekuensi logis dari konsepsi negara hukum sebagaimana
yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah
bahwasanya pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan
Julius Stahl terkait 4 unsur dari negara hukum (rechtstaat),
yakni perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan atau
pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-
negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica),
pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van
bestuur), dan peradilan administrasi dalam perselisihan.1
Dalam sistem hukum negara Indonesia, peraturan-peraturan
yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari unsur politis
sebagai konsekuensi logis dari sistem pemilihan kepala
pemerintahan negara Indonesia yang mana tugas itu diemban oleh
Presiden yang dipilih melalui suatu pemilihan umum.2 Adapun
peserta pemilihan umum adalah partai politik, sehingga mau
tidak mau, suka tidak suka, politik akan selalu bersinggungan
erat di dalam sistem negara hukum.
Rawls berpendapat terdapat tiga alasan terhadap prinsip
fair equality of opportunity, yaitu yang pertama, bahwa FEO adalah
bagian integral dari warga negara yang bebas memiliki status
dan kedudukan yang sama dan sederajat. Seperti kebebasan dasar
yang sama, FEO merupakan salah satu dasar sosial mengenai
kehormatan diri. Untuk dikecualikan dari posisi sosial atas
dasar ras, jenis kelamin, agama, dan sebagainya, hal itu1 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia
Pustaka, 1998).2 Lihat Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945
merupakan penghinaan terhadap martabat seseorang sebagai
pribadi dan warga negara yang sama. Kedua, orang-orang yang
kehilangan kesempatannya. Alasan utama yang ketiga terhadap
FEO adalah bahwa hal itu melengkapi the difference principle. "Peran
prinsip fair opportunity adalah untuk memastikan bahwa sistem
kerjasama merupakan salah satu keadilan prosedural murni.
Prinsip Perbedaan, kemudian bekerja bersama-sama dengan FEO;
keduanya diperlukan untuk membuat distribusi yang adil dari
pendapatan dan kekayaan.
Terkait dengan profesi hukum, Abdulkadir Muhammad
menegaskan bahwa profesi hukum merupakan salah satu profesi
yang menuntut pemenuhan nilai moral dalam pengembanannya. Hal
itu disebabkan seorang penegak hukum bertanggung jawab
terhadap diri sendiri, anggota masyarakat bahkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa.3 Sehingga wajar jabatan seorang penegak hukum
adalah suatu jabatan yang mulia di masyarakat.
Memang dalam hal perekrutan calon pejabat penegak hukum
tidak menyimpangi prinsip fair equality of opportunity secara umum,
akan tetapi terdapat pembatasan hal itu di Indonesia melalui
Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang
Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana
bidang hukum bertujuan untuk mengahasilkan sarjana hukum yang:
1. Menguasai hukum Indonesia
2. Mampu menganalisis masalah hukum di masyarakat
3. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk
memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap
berdasarkan prinsip-prinsip hukum
3 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
4. Menguasai dasar ilmiah untuk dapat mengembangkan ilmu
hukum dan hukum itu sendiri
5. Peka terhadap masalah keadilan dan masalah sosial
Pada dasarnya, FEO ditafsirkan sebagai semacam
kompensasi bagi mereka yang secara sosial kurang beruntung
namun secara alami diuntungkan, sehingga memungkinkan mereka
untuk sepenuhnya mendidik kapasitas mereka dan bersaing pada
masa sekolah yang sama dengan mereka yang memiliki bakat alami
dengan yang lahir dari keadaan sosial yang lebih baik. Dalam
hal ini yang penting adalah secara sosial ada jaminan terhadap
harga diri semua warga negara tanpa memperhatikan kemampuan
alami mereka.
Poinnya adalah bahwa tujuan utama dari FEO untuk
memberikan warga pada umumnya, tidak hanya sekedar bakat alami
berbakat, dengan sarana untuk mengembangkan dan melatih
kemampuan alami mereka sehingga mereka dapat mengambil
keuntungan penuh dari berbagai peluang terbuka bagi orang-
orang dengan kemampuan yang sama, dan mencapai harga diri
dalam status mereka sebagai warga negara yang setara.
Jika teori tersebut ditarik kepada konteks profesi
hukum, maka yang hendak Rawls perjuangkan melalui teori FEO-
nya yakni adanya peluang yang sama bagi para sarjana hukum
untuk dapat mengisi pos-pos jabatan penegakan hukum agar
tercipta suasana meritrokasi pada sistem hukum Indonesia. Hal
tersebut juga berimplikasi pada pencegahan praktek nepotisme
yang marak terjadi pada institusi-institusi penegak hukum
tertentu, misalnya seorang anak Kapolri mendapat hak istimewa
dalam hal rekrutmen Polri karena orang tuanya merupakan
pejabat tinggi di institusi tersebut.
The Difference Principle atau Prinsip Perbedaan pada Profesi
Hukum
Menurut John Rawls, Prinsip Perbedaan merupakan sebuah
prinsip untuk institusi, bukan untuk perseorangan. Hal ini
tidak berarti bahwa Prinsip Perbedaan tidak dapat diterapkan
kepada perseorangan, bahkan prinsip ini membuat banyak
kewajiban kepadanya. Pengertiannya lebih mengarah kepada
Prinsip Perbedaan diaplikasikan dalam langkah pertama dalam
mengatur konvensi ekonomi dan institusi hukum agar berjalan
sebagaimana mestinya; keadilan sosial.
Rawls berpendapat bahwa hukum sebagai keadilan, daripada
bertujuan untuk mengamankan kemanfaatan yang sama dari
kebebasan dasar, tujuannya untuk memaksimalkan kemanfaatan
nilai dari kebebasan yang lebih buruk. Bahwa Prinsip Perbedaan
merupakan prinsip utama sebagai pedoman musyawarah masyarakat
demokrasi untuk mencapai kata mufakat, ketika terjadi
perdebatan antara mereka mengenai kebaikan umum dan keputusan
legislator saat mereka membuat hukum terkait kebaikan umum
untuk masyarakat demokrasi. Dapat terlihat bahwa Prinsip
Perbedaan berlaku kepada perseorangan secara tidak langsung.
Pengaturan mengenai penerapan langsung Prinsip Perbedaan
terhadap struktur institusi ekonomi dan penerapan tidak
langsungnya kepada masyarakat ditunjukkan pada pendapat Rawls
yang menyatakan bahwa “subjek utama keadilan adalah struktur
dasar masyarakat”. Struktur dasar masyarakat terdiri atas
penyusunan dari institusi politik, sosial dan ekonomi yang
membuat kerjasama sosial menjadi mungkin dan produktif.
Institusi dasar yang merupakan bagian dari struktur dasar
termasuk diantaranya adalah:
a. pertama, konstitusi politik dan bentuk pemerintahan
juga sistem hukum yang mendukung
b. kedua, sistem kekayaan, baik publik maupun privat yang
berlaku di seluruh masyarakat untuk memperjelas siapa
yang memiliki hak eksklusif dan tanggung jawab untuk
menggunakan barang dan sumber daya diantara
perseorangan
c. ketiga adalah sistem pasar dan seluruh pembelian dan
penjualan terhadap barang ekonomi dan lebih umum lagi
kepada struktur dan norma dari sistem produksi,
penjualan dan distribusi barang dan sumber daya
diantara perseorangan
d. keempat adalah keluarga sebagai unit terkecil dalam
suatu masyarakat dalam beberapa bentuk yaitu dari
sebuah perspektif politik yang merupakan mekanisme
utama yang wajib dimiliki seluruh masyarakat untuk
mengasuh dan mendidik anak
Peran the difference principle adalah sebagai suatu syarat agar
keadilan sosial dapat berjalan dengan baik, sebab keadilan
akan sulit tercipta di tengah arus kebebasan politik yang
cenderung melumat kaum miskin sebagai penghambat kesejahteraan
dan kemakmuran dunia. Untuk mencegah hal demikian terjadi,
perlu adanya penerapan Prinsip Perbedaan pada profesi hukum.
Sejatinya Prinsip Perbedaan pada profesi hukum berbicara
tentang perilaku dan cara mengambil keputusan seorang pejabat
penegak hukum, bagaimana seorang penegak hukum mampu
memberikan rasa adil di masyarakat, bagaimana ia menggunakan
hukum untuk membela kaum tertindas, bagaimana hukum berperan
sebagai pelindung bagi masyarakat yang membutuhkan, juga bagi
mereka yang hak-haknya terancam dibinasakan oleh keserakahan
politik.
Dengan demikian Prinsip Perbedaan menurut diaturnya
struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga
kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan,
pendapatan, dan otoritas (kewenangan) seorang penegak hukum
diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang
diuntungkan terutama dari golongan miskin.
Misalnya saja penanaman modal (investasi) yang besar
dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja
serta tersedianya barang dan jasa. Dalam hal menambah lapangan
kerja dan memproduksi barang dan jasa, penanaman modal akan
sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang
paling kurang diuntungkan. Dengan begitu, penanaman modal akan
amat berprospek pada kenaikan pendapatan mereka yang kurang
diuntungkan, melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang
baru. Meskipun demikian, orang (investor) tak akan bersedia
menanggung resiko investasi besar-besaran jika tidak punya
peluang untuk memperoleh keuntungan yang besar pula dari
usahanya. Dalam keadaan demikian itulah pajak keuntungan yang
rendah dapat menciptakan insentif penanaman modal. Prinsip
Perbedaan akan menuntut peraturan pajak seperti itu jika para
investor dituntut untuk memaksimalkan prospek hidup golongan
yang paling kurang diuntungkan. Oleh karena itu para investor
harus menikmati bagian kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar
daripada orang lain dalam masyarakat. Menurut Prinsip
Perbedaan, ketidak samaan dalam prospek kebutuhan-kebutuhan
utama harus dibenarkan jika memang dimaksudkan serta bertujuan
untuk memaksimalkan prospek hidup mereka yang paling kurang
diuntungkan.4
Fair Equality of Opportunity and The Difference Principle
Teori kedua (second principle) dari Rawl adalah mengenai
“Equality Principle”, yang membagi menjadi dua prinsip yaitu; Fair
Equality of Opportunity (FEO) dan Prinsip Perbedaan (the difference
principle). Secara umum, konsep FEO berbicara tentang setiap
orang punya kesamaan dasar yang sama melekat pada mereka,
sehingga semua orang dianggap sejajar. Ketika John Rawls
menyadari bahwa ada perbedaan antara manusia dengan manusia
lainnya, maka Prinsip Perbedaan (the difference principle) yang
memperhatikan mereka yang paling kurang beruntung. Secara
sederhana Prinsip Perbedaan dapat dimaknai sebagai prinsip
yang memandang bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus
diatur agar memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang
paling kurang beruntung. Dalam hal ini, FEO berperan penting
untuk menunjang agar prinsip ini dapat diterapkan. FEO
menunjukkan peluang bagi mereka yang paling kurang mempunyai
peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan
otoritas. Mereka inilah yang diberikan perlindungan khusus.
Beberapa ahli berpendapat bahwa seharusnya Prinsip
Perbedaan harus dipisahkan dari Kerjasama Sosial dan digunakan
sebagai Prinsip Keadilan Global. Hal ini dimungkinkan apabila
Prinsip Perbedaan dan Keadilan Distribusi (distributive justice)
dilihat secara lebih umum seperti halnya Keadilan Alokasi yang
dikemukakan Rawls. Adapun Keadilan Alokasi adalah suatu
kondisi di mana seluruh kekayaan dikumpulkan tanpa
4 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” Jurnal TAPIs Vol.9 No.2, (Juli-Desember 2013) hal 35-36.
memperhatikan dari mana asalnya, kemudian dibagikan kepada
setiap individu berdasarkan aturan tertentu. Dalam perspektif
ini, individu yang merasakan nikmat belum tentu terlibat
proses menghasilkan nikmat tersebut. Keadilan Alokasi
selanjutnya bisa mengarah kepada utilitarianisme yang memahami
bahwa pendistribusian produksi secara agregat dilakukan tanpa
mempedulikan bagaimana atau siapa yang memproduksinya, untuk
memberikan kenikmatan yang maksimal.
Telah dijelaskan di atas bahwa Prinsip Perbedaan,
kemudian bekerja bersama-sama dengan FEO yang mana diperlukan
untuk membuat distribusi yang adil dari pendapatan dan
kekayaan. Terlepas dari bobroknya politik dan hukum di
Indonesia, dengan mengamini bahwa harus terdapat kesempatan
yang sama pada setiap orang untuk dapat memperoleh pekerjaan
yang akan berimplikasi pada kesejahteraan orang yang
bersangkutan sebagai tolak ukur kelayakan hidup, minimal
saluran-saluran politik dan institusi-institusi penegak hukum
di Indonesia harus memiliki ideologi berupa keadilan dan
kesejahteraan sosial serta berfokus pada hal tersebut. Meski
pada prakteknya acap kali ditemukan penyimpangan yang berujung
pada usaha memperkaya diri sendiri.
Adapun peran Prinsip Perbedaan (the difference principle),
sebagai suatu syarat yang menjamin tujuan ideal dari konsep
FEO bagi masyarakat. Prinsip Perbedaan hadir di masyarakat
untuk menjamin hak-hak masyarakat yang kurang diuntungkan,
akan tetapi mereka punya bakat alami untuk dapat berkontribusi
secara maksimal di lingkungan masyarakat. Disinilah hukum
mengisi ketidak pastian akan nasib masyarakat yang kurang
diuntungkan. Hukum harus selalu berpihak kepada keadilan,
karena hukum yang tidak berpihak pada keadilan rentan
menimbulkan konflik di masyarakat akibat kesenjangan sosial
dan ketidak puasan terhadap para penguasa. Adapun penguasa
yang dimaksud adalah para pejabat eksekutif pemerintahan yakni
Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Republik Indonesia dan para penegak hukum yang secara teknis
bekerja dalam ruang lingkup kekuasaan yudikatif berdasarkan
teori pemisahan kekuasaan (trias politica).
Untuk menjamin tegaknya keadilan, para penegak hukum
sebagai pembela kepentingan masyarakat yang kurang
diuntungkan, terlebih dahulu harus memperoleh jaminan
keadilan. Jika dikaitkan dengan profesi hukum, maka jelas
jaminan keadilan itu berupa upah dan tunjangan yang layak demi
mencegah praktek kolusi, korupsi dan nepotisme terjadi dan
akan mencabik-cabik supremasi hukum. Menurut hemat penulis,
prinsip jaminan keadilan yang terlebih dahulu harus diperoleh
oleh para penegak hukum adalah prinsip keadilan distributif
(distributive justice).
Keadilan Distributif Terhadap Profesi Hukum
Prinsip-prinsip keadilan distributif sangat bervariasi.
Meskipun demikian, ada tiga prinsip yang paling sering
diterapkan. Prinsip pertama dikenal dengan teori equity. Secara
garis besar prinsip ini mengandung dua hal pokok. Bagian yang
diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang
diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, maupun
yang lain. Di samping itu, kesebandingan bagian yang diterima
seseorang juga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang
lain. Karenanya, bagian yang diterima berdasarkan sumbangan
yang diberikan juga harus sebanding dengan bagian orang lain
yang juga berdasarkan sumbangan orang yang bersangkutan.5
Dalam hal ini, negara selaku yang memberikan upah kepada
para pejabat penegak hukum harus memperhatikan sumbangsih
mereka atas jasanya di masyarakat. Dengan memperhatikan
tanggung jawab terhadap publik yang begitu besar, bahkan ada
profesi hukum yang pertanggung jawabannya kepada Tuhan Yang
Maha Esa, maka pejabat penegak hukum harus pula dilindungi
hak-haknya melalui keadilan distributif. Apabila keadilan
distributif itu tidak diterapkan kepada profesi penegak hukum,
maka kemungkinannya mereka akan menjadi makelar perkara hukum
demi mendapatkan keuntungan yang bertujuan memperkaya diri
sendiri maupun kelompok. Praktek seperti ini sudah sangat
lumrah terjadi di Indonesia, bahkan cakupannya tidak hanya
diantara para pejabat penegak hukum saja melainkan hingga ke
kalangan legislator.
Prinsip kedua yang dapat digunakan dalam distribusi
adalah kesetaraan atau ekualitas. Bila prinsip ini digunakan,
akan terdapat variasi penerimaan yang kecil. Dimungkinkan ada
variasi bila ada jenis-jenis pekerjaan atau bagian-bagian
dalam satu organisasi atau kelompok. Variasi itu terjadi antar
kelompok, bukan di dalam masing-masing kelompok. Kritik paling
banyak terhadap prinsip ini datang berkaitan dengan pengabaian
terhadap potensi dan produktivitas kerja. Orang yang lebih
pandai, terampil atau produktif mestinya mendapat imbalan
lebih tinggi, sementara prinsip ini tidak terlalu
mempertimbangkannya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa
prinsip ini tepat diterapkan pada pola hubungan bukan kerja,
5 Faturochman, “Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi”, Buletin Psikologi VII No.1 (Juni 1999) hal 5-6.
misalnya keluarga. Dalam suasana kerja, prinsip ini dapat
diterapkan bila orientasinya adalah keharmonisan hubungan
sesama pekerja.6
Berkaitan dengan profesi hukum, hal seperti pada prinsip
di atas sebenarnya relevan dengan profesi seorang advokat.
Meski pada prakteknya advokat bekerja secara tim, namun tim
yang mampu memenangkan suatu perkara biasanya akan memperoleh
imbalan lebih tinggi dibandingkan dengan tim yang tidak
berhasil memenangkan suatu perkara. Penulis sepakat pada
prinsip keadilan distributif yang menekankan pada kesetaraan,
mampu membuat keharmonisan hubungan sesama pekerja, karena
justru di antara sesama penegak hukum harusnya menjalin
hubungan dalam hal mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki.
Prinsip ketiga mengutamakan kebutuhan sebagai
pertimbangan untuk distribusi. Di sini dapat diinterpretasi
bahwa sesorang akan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya
dan dalam hubungan kerja makin banyak kebutuhannya maka makin
besar upah yang diterima. Jika dikaitkan dengan profesi
penegak hukum yang notabene melakukan pekerjaannya pada sektor
jasa, maka kebutuhan yang diperlukan pun tidak terlalu banyak.
Telah dipaparkan sebelumnya bahwa Prinsip Perbedaan
tidak dapat diterapkan tanpa FEO. Ada sedikitnya tiga cara
bagaimana FEO melengkapi Prinsip Perbedaan, antara lain:
1. FEO membatasi derajat ketidaksetaraan pendapatan dan
kekayaan yang diperbolehkan dalam Prinsip Perbedaan
serta meningkatkan posisi relatif dari pihak yang
paling kurang beruntung
2. FEO meningkatkan posisi absolut dari pihak dengan
pendapatan terburuk dengan cara yang tidak terdapat
6 Ibid
dalam Prinsip Perbedaan. Bandingkan dua kelompok
masyarakat, Democratic Equality dan Natural Aristocracy, yang
pertama menerapkan FEO sedangkan yang kedua hanya
menerapkan Prinsip Perbedaan. Kelompok pertama
menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh
masyarakatnya tentu dengan proporsi yang didasarkan
atas faktor-faktor tertentu, sedangkan kelompok kedua
tidak, dikarenakan FEO hanya terdapat dalam kelompok
pertama tadi. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi
masyarakat dengan kondisi terburuk pada kelompok
pertama (yang tidak bisa memperoleh pendidikan dan
kesehatan tanpa FEO). Hasilnya, masyarakat pada
Democratic Equality lebih makmur daripada Aristocratic Natural.
3. FEO mengatur konsentrasi kekayaan yang diperbolehkan
dalam difference principle. Hal ini terjadi karena FEO
berimplikasi bahwa sistem pasar bebas harus berada
dalam kerangka institusi politik dan hukum yang
mengendalikan tren ekonomi untuk mencegah konsentrasi
kemakmuran dan dominasi politik.
Profesi Hukum dan Perspektif Moral
Karakteristik tertentu dari individu telah terbukti
sangat berperan dalam menilai keadilan. Mereka yang memiliki
sifat hedonis, berorientasi politis, dan ingin cepat maju
berbeda dalam menilai keadilan bila dibandingkan dengan orang
yang pro sosial dan spiritualitasnya tinggi. Kelompok pertama
biasanya kurang setuju dengan prinsip distribusi ekual,
sementara kelompok kedua justru sebaliknya.7
7 N.T. Feather, “Human Values and Their Relation to Justice”, Journal of Social Issues No.50 (1994).
Pada kasus-kasus pejabat penegak hukum yang melakukan
perbuatan menyimpang, sistem hukum di Indonesia juga turut
memberikan kontribusi. Celah untuk disuap dan menyuap para
pejabat penegak hukum menjadikan diri sendiri sebagai satu-
satunya benteng pertahanan tiap individu.
Sejatinya hukum lahir dari masyarakat, untuk itu hukum
harus mengadopsi nilai-nilai mulia yang dianut oleh manusia
beradab. Hukum dibentuk secara umum dengan tujuan menegakan
keadilan tanpa pandang bulu, misalnya penggunaan terminologi
“barangsiapa” pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan
manusia selaku yang berbuat dan menindak hukum, adalah seorang
individu yang bebas dan kontroversial, hal itu dikarenakan
manusia terlahir dengan hak-hak asasi yang sama dan setara
namun pada perjalanannya, ia dibentuk oleh lingkungan sekitar.
Hukum bersifat institusional, moralitas bersifat kontroversial
dan personal. Hukum bersifat otoriter, mengatasi masalah
dengan tindakan otoriter pula. Sedangkan moralitas berbeda dan
mandiri, dalam arti moralitas selalu terbuka terhadap adu
argumentasi untuk mencapai kata-kata yang sama. Hukum bersifat
heterogen yang mengikat kita tanpa terkecuali, sedangkan
moralitas bersifat otonomi yang mengikat kita dengan keputusan
dan keinginan kita sendiri.
Dalam hukum, terdapat suatu moralitas hukum yang
spesifik, yang terdiri atas pencerminan pendapat-pendapat
moral yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan yang
dikembangkan dalam praktek di bidang hukum dan yang terikat
dalam lembaga-lembaga dan ajaran-ajaran hukum. Moralitas hukum
ini merupakan bidang khusus para ahli hukum dan para sarjana
hukum. Seringkali moralitas ini harus dilindungi terhadap
pendapat mayoritas dan terhadap kepentingan-kepentingan
politik dan sosial yang penting, misalnya saja proses hukum
yang wajar dalam pengadilan-pengadilan terhadap intervensi
politik. Oleh karena itu good law enforcement governance adalah
salah satu acuan bagi profesi hukum sebagai seni atau gaya
moral penegakan hukum yang baik demi terciptanya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian yang
dimaksudkan dengan “baik” dalam istilah “penegakan hukum yang
baik”, lebih memerlukan suatu butir-butir moral-legal dalam
pelaksanaannya.
Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik
(good law enforcement governance), adalah pemahaman atas prinsip-
prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan
hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolak ukur kinerja suatu
penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan
penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah
bersinggungan dengan seluruh unsur prinsip-prinsip penegakan
hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan
elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas,
perlindungan bagi hak asasi manusia, kebebasan, transparansi,
pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu,
suatu pelaksanaan penegakan hukum oleh profesi hukum dapat
disebut berperspektif moral baik, apabila pelaksanaannya
memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi tersebut.
Dengan demikian membangun “penegakan hukum yang baik”
sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku para pejabat penegak
hukum. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk
dikembangkan dalam pembinaan sumber daya insani, karena
kejujuran tidak ada modulnya. Kejujuran sangat dipengaruhi
oleh keimanan dan integritas seseorang. Sebagai konsekuensi,
pemerintah dengan sendirinya dituntut untuk meningkatkan
kemampuan sumber daya insaninya sesuai dengan bidang tugasnya,
kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap dan perilakunya,
agar mampu berpikir dengan baik dan benar.8
Implementasi Good Law Enforcement Governance di Indonesia
Penegakan hukum dalam definisinya yang luas, tidak hanya
berkenaan dengan apa yang dilakukan para pejabat di wilayah
yudisial semata, tetapi juga yang berlangsung di wilayah
eksekutif, administrasi dan legislatif. Maka, wacana tentang
syarat gaya moral pelaksanaan penegakan hukum yang baik,
dimasukkan pula ke dalam proses bagaimana hukum itu dibentuk
dan ditegakkan. Pentingnya memahami penegakan hukum yang baik,
dengan hak dan kewajiban yang dimiliki agar masyarakat
mengetahui bahwa tolak ukur yang diperlukan guna menilai
kinerja para pejabat penegakan hukum itu ada, kemudian
didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial
secara optimal, sehingga dapat diharapkan kualitas keputusan-
keputusan para pejabat penegak hukum akan terjaga. Tingginya
kualitas keputusan-keputusan para pejabat penegak hukum yang
tertengarai memenuhi tolak ukur predictability, accountability,
transparency dan widely participated, akan mengindikasikan tingginya
kadar demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Merupakan tuntutan dalam kehidupan hukum yang demokratis
dan
berwawasan kemasyarakatan untuk memberikan tolok-ukur setiap
proses penegakan hukum oleh para pejabat yang berwenang, atas
8 Kusnu Goesniadhie, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik”, Jurnal Hukum No.2 Vol.17 (April 2010).
dasar kriteria mengenai gaya moral pelaksanaannya. Para
pejabat penegakan hukum dan anggota masyarakat yang
berkepentingan mesti sama-sama mengetahui kriteria untuk
memberikan tolak ukur ada atau tidaknya penegakan hukum yang
baik dalam praktek-praktek penegakan hukum yang akan berdampak
pada kehidupan mereka. Dengan memahami secara baik seluk-beluk
dan liku-liku penegakan hukum yang baik, para penegak hukum
dan para pejabat pemerintahan akan berhati-hati dalam
bertindak guna menjaga kualitas moral-politik dan moral-legal
segala bentuk keputusan-keputusannya.
Sementara itu, dengan mengetahui apa yang dimaksud
dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat pun akan dapat
memberikan tolak ukur dan menilai apakah badan legislatif,
baik di pusat maupun di daerah, telah menguasai dan mampu
melaksanakan gaya moral penegakan hukum yang baik atau belum.
Masyarakat akan dapat menilai kepatuhan anggota-anggota badan
legislatif pada ketentuan-ketentuan yang ada mengenai
mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan demi terjaganya
sistem hukum nasional. Kepatuhan pada mekanisme dan prosedur
serta sistem yang ada, pada gilirannya akan menjamin
terpenuhinya tuntutan predictability dan accountability. Dengan
mengetahui apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang baik,
masyarakat akan dapat mengamati dan memberikan tolak ukur
apakah para pelaksana penegakan hukum sebagai fungsionaris
dalam suatu proses peradilan, hakim, jaksa, polisi dan
pengacara, telah bertindak sesuai dengan persyaratan gaya
moral penegakan hukum yang baik atau belum. Pengetahuan dan
kepahaman masyarakat mengenai sesuatu yang baik dalam wilayah
yudisial, juga akan dapat digunakan untuk menilai proses
penyelesaian berbagai perkara hukum yang telah atau yang masih
harus diselesaikan melalui pengadilan.9
The Just Saving Principle
John Rawls dianggap sebagai tokoh yang pertama kali
mencetuskan pemikiran mengenai adanya suatu “utang” yang
dimiliki masyarakat generasi saat ini kepada masyarakat
generasi masa depan. Ia berargumen bahwa tugas utama dari
generasi mendatang adalah menggunakan modal materiil dengan
secukupnya guna mempertahankan kebiasaan untuk hidup secara
berkelanjutan dari waktu ke waktu. John Rawls menyebut tugas
utama ini sebagai Just Savings Principle. Meskipun Just Savings Principle
hanya merupakan salah satu aspek kecil dari pemikirannya
mengenai teori keadilan, prinsip ini telah banyak
diperbincangkan dan dikritisi karena ajarannya terbilang
sangat berkontradiksi dengan prinsip-prinsip lain pada umumnya
yang berkaitan dengan keadilan antar generasi.
Johh Rawls menyatakan pemikirannya tersebut
dilatarbelakangi oleh kesadarannya bahwa apa yang dihutangkan
generasi saat ini kepada generasi mendatang bergantung pada
bagaimana standar kehidupan minimum pada masyarakat
ditetapkan. Ia mengklaim bahwa suatu standar kehidupan minimum
dapat digunakan untuk menentukan pada tingkat mana sebuah
masyarakat memaksimalkan ekspektasi terhadap standar
kehidupannya terutama pada masyarakat kelas bawah. Pada
dasarnya, Just Savings Principle merupakan sebuah teori tambahan atas
teori Prinsip Perbedaan atau Difference Principle yang didesain
untuk memberikan suatu batasan pada generasi mendatang.
9 Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum dan Moral Pemerintahan yangBaik”, Jurnal Analisis Hukum (2002).
Apabila Difference Principle tidak memiliki komponen antar generasi,
maka kita sebagai masyarakat generasi saat ini secara langsung
maupun tidak langsung akan mengeksploitasi masyarakat paling
kurang beruntung pada generasi mendatang semata-mata untuk
keuntungan paling kurang beruntung pada generasi saat ini.
Pemikiran mengenai Just Saving Principle sangat penting untuk
didalami. Apabila dikaitkan dengan teori Difference Principle maka
kita sebagai manusia generasi saat ini tidak akan meningkatkan
apapun untuk generasi mendatang, melainkan hanya untuk
bertahan hidup saja dengan kondisi saat ini atau yang sudah
ada sebelumnya tanpa perhitungan mengenai apa yang akan
dialami oleh generasi mendatang.
Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan konteks profesi
hukum, maka yang dapat ditinggalkan oleh para sarjana hukum
generasi saat ini terhadap generasi yang akan datang selain
produk hukum yang pro sosial dan pro terhadap hak-hak asasi
manusia, juga meninggalkan yurispridensi yang dapat menjadi
acuan bagi putusan-putusan hakim pada generasi mendatang,
dengan tujuan menjaga supremasi hukum sebagai suatu norma yang
mulia di masyarakat agar selalu berjalan berdampingan
mengikuti perkembangan masyarakat yang cepat berubah.
Penutup
Profesi penegak hukum menuntut individu untuk berwawasan
luas dan berperspektif keadilan bagi mereka yang paling kurang
diuntungkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu adanya
suatu pemahaman bahwa profesi hukum merupakan profesi yang
istimewa dan luhur di masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal
mengisi jabatan penegak hukum di Indonesia perlu dibuka
seluas-luasnya kepada publik dan diberikan kesempatan yang
sama untuk mengisi jabatan tersebut.
Adapun pada prakteknya, dibenarkan adanya Prinsip
Perbedaan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
sebagai amanat Pancasila, sila ke-5 dapat teraplikasikan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip
Perbedaan berfungsi melindungi golongan yang paling kurang
diuntungkan, bagaimana hal itu dapat terwujud tentu kembali
pada karakteristik individu para profesi penegak hukum.
Terwujudnya asas penegakan hukum yang baik di masyarakat
tidak terlepas dari adanya kesadaran tiap profesi penegak
hukum untuk saling bekerja dan mencari keadilan di masyarakat,
dan kesemuanya membutuhkan gaya moral yang baik yang
mencerminkan sikap tindak dan cara berpikir para penegak
hukum.
Adapun yang tak kalah pentingnya, bagaimana kemudian
hukum positif yang hidup dan berkembang pada generasi saat ini
mampu menjaga marwah supremasi hukum pada generasi yang akan
datang, hal itu diperlukan untuk menjaga konsistensi asas
penegakan hukum yang baik antar generasi.
Daftar Pustaka
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Pustaka. 1998
Dwisvimiar, Inge. “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu
Hukum”. Jurnal Dinamika Hukum 3 Vol. 11 (September 2011).
Fadhillah. “Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness
Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan”.
Jurnal Madani 2 (Nopember 2007).
Faturochman. “Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi”.
Buletin Psikologi 1 (Juni 1999): 13-27.
Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”. Jurnal
TAPIs 2 Vol. 9 (Juli-Desember 2013).
Feather, N.T (1994). Human Values and Their Relation to
Justice. Journal of Social
Issues 50: 129-151.
Goesniadhie, Kusnu. “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang
Baik”. Jurnal Hukum 2 Vol. 17 (April 2010): 195-216.
Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya
Bakti. 1997
Wignjosoebroto, Soetandyo, “Hukum dan Moral Pemerintahan yang
Baik”. Jurnal
Analisis Hukum. 2002. Jangan Tunggu Langit Runtuh.
hukumonline.com.