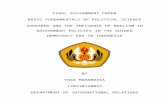KOMPARASI STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA (BEBAS AKTIF) PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO DAN ...
Transcript of KOMPARASI STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA (BEBAS AKTIF) PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO DAN ...
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring perkembangan waktu dan perkembangan zaman,
kita tidak akan pernah melupakan peristiwa-peristiwa
yang dilakukan oleh para petinggi negeri untuk
berpolitik. Seperti cara-cara mereka berpolitik membela
negara kita tercinta ini dengan bahasa-bahasa
diplomasinya. Seperti kita ketahui bahwasannya
Indonesia dapat berkembang pesat sebagai negara yang
memiliki kedaulatan dan sudah mulai dianggap oleh
negara-negara lain tidak terlupakan dari adanya peran-
peran penting dari sistem politik luar negerinya itu
sendiri. Sistem politik luar negeri Indonesia inilah
sangat bermacam-macam strateginya. Seperti kita ketahui
juga bahwa setiap kepala pemerintahan khususnya kepala
1
pemerintahan Indonesia sangat berbeda dari segi
strategi politik luar negerinya.
Politik luar negeri adalah strategi dan taktik
yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya
dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik
luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh
suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara
lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses
pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan
tertentu.
Pada dasarnya setiap prinsip politik luar negeri
Indonesia di buat melihat unsur penting yaitu
kepentingan nasional atau national interest. Bukan hanya
Indonesia tetapi juga negara-negara lain di dunia.
Selain komitmen pada kepentingan nasioanal (national
interest), politik luar RI juga tetap mengedepankan
perinsip dasar bangsa Indonesia yang anti kolonialisme.
Dalam memutuskan setiap kebijakan politik luar negeri
Indonesia mengedepankan nilai-nilai dan prinsip yang
2
dijunjung teguh. Politik luar negeri bebas aktif
menjadi dasar pelaksanaan setiap kebijakan yang akan
dibuat, selain melihat kondisi dalam negeri pemerintah
Indonesia juga mengedepankan prinsip-perinsip yang
telah tertera dalam pembukaan UUD 1945.
Di bidang hubungan luar negeri, sikap politik luar
negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan selalu
diarahkan untuk mendukung terciptanya perdamaian dunia,
telah menempatkan Indonesia dalam posisi dan peranan
yang makin mantap dan dipercaya dalam percaturan
politik regional dan global. Di samping itu telah
berhasil pula ditingkatkan kerjasama bilateral dan
multilateral dengan berbagai negara sahabat dan
berbagai lembaga internasional untuk mendukung
kepentingan pembangunan nasional.
Tampak jelas bahwa ide dasar politik luar negeri
bebas aktif yang dikemukakan oleh Hatta sama sekali
bukan retorika kosong mengenai kemandirian dan
kemerdekaan, akan tetapi dilandasi pemikiran rasional
3
dan bahkan kesadaran penuh akan prinsip-prinsip
realisme dalam menghadapi dinamika politik
internasional dalam konteks dan ruang waktu yang
spesifik. Bahkan dalam pidato tahun 1948 tersebut,
Hatta dengan tegas menyatakan, percaya akan diri
sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri
tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil
keuntungan daripada pergolakan politik internasional.
1.2 Fokus Masalah
Penyusun memfokuskan penyusunan makalah ini pada
masalah sistem politik luar negeri RI pada masa
pemerintahan Soekarno dan Gus Dur mengenai perbedaan-
perbedaan strategi dari sistem politik luar negerinya.
1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan,
maka peneliti merumuskan masalah penelitian tersebut
sebagai berikut :
4
“KOMPARASI STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA (BEBAS
AKTIF)
PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO DAN GUS DUR”
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan makalah ini mencakup dua
maksud yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus :
1.4.1 Tujuan Umum
Diharapkan dapat mengetahui perbedaan
strategi politik luar negeri Indonesia (Bebas
Aktif) pada masa pemerintahan Soekarno dan pada
masa pemerintahan Gus Dur.
1.4.2 Tujuan Khusus
Untuk mengetahui seperti apa keberhasilan
dari strategi politik luar negeri Indonesia (Bebas
5
Aktif) dengan masing-masing presiden yang berbeda
pada era nya.
1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis
1.5.1.1 Sebagai sumbangan bagi pengembangan
kajian tentang strategi politik luar negeri
Indonesia pada masa Soekarno dan pada masa
Gus Dur
1.5.2 Manfaat Praktis
Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi
tugas mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia
pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal
Achmad Yani.
1.6 Sistematika Penulisan
6
Penyusun membagi makalah ini kedalam lima bab yang
disesuaikan dengan penelitian ini. Adapun sistematika
penulisannya ialah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang melandasi
penyusunan penulisan yang berisi antara lain : Latar
Belakang Penelitian, Fokus Masalah, Perumusan Masalah,
Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN DAN TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tentang kajian atau studi literatur
dalam menyusun landasan atau kerangka teori yang
relevan dengan masalah yang disusun, penyusun
menggunakan kerangka berfikir untuk membantu dalam
melakukan penelitian masalah yang dikaji. Kerangka
pemikiran itu berupa pendekatan teori yang dianggap
relevan untuk digunakan dalam menganalisis masalah yang
dikaji.
7
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini memaparkan secara singkat metode
penelitian kualitatif, strategi penelitian kualitatif,
lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan
teknik pengujian keabsahan data.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dipaparkan mengenai strategi
politik luar negeri Indonesia pada masa jabatan
Soekarno dan strategi politik luar negeri Indonesia
pada masa jabatan Gus Dur.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan
hasil penelitian dan saran, baik bagi pihak-pihak
terkait, maupun bagi penelitian berikutnya.
8
2.1 Kerangka Pemikiran
Dalam setiap menganalisis sebuah permasalahan,
maka diperlukan kerangka pemikiran yang sangat penting
sebagai perangkat untuk membedah, membahas, dan
menelaah setiap gejala, kejadian, peristiwa dan
fenomena dalam hubungan internasional. Kerangka
pemikiran sangat dibutuhkan untuk menganalisis sebuah
permasalahan sehingga hasil analisis akan bersifat
valid, reliabel, logis, dan objektif. Kerangka
pemikiran akan menuntun penyusun untuk terfokus,
terarah dan terpusat pada analisis yang tajam dan
ilmiah. Demikian pula dengan penelitian dalam bentuk
makalah ini yang sangat diperlukan sebuah kerangka
pemikiran.
Pada umumnya ide dasar politik luar negeri bebas
aktif yang dikemukakan oleh Hatta sama sekali bukan
retorika kosong mengenai kemandirian dan kemerdekaan,
akan tetapi dilandasi pemikiran rasional dan bahkan
10
kesadaran penuh akan prinsip-prinsip realisme dalam
menghadapi dinamika politik internasional dalam konteks
dan ruang waktu yang spesifik. Bahkan dalam pidato
tahun 1948 tersebut, Hatta dengan tegas menyatakan,
percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan
kita sendiri tidak berarti bahwa kita tidak akan
mengambil keuntungan daripada pergolakan politik
internasional.
2.2 Tinjauan Pustaka
Tinjauan / Studi Pustaka pada dasarnya berkaitan
dengan kajian teoritis dan referensi lain yang relevan
dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan
pustaka merupakan hasil penelusuran tentang pustaka
atau literatur yang mengupas topik yang relevan dengan
penelitian yang sedang dilakukan, baik yang mendukung
maupun yang bertentangan dengan pendapat peneliti. Hal
ini merupakan bukti pendukung bahwa topik atau materi
yang diteliti merupakan suatu permasalahan yang penting
11
karena merupakan concern banyak orang, sebagaimana
ditunjukkan oleh pustaka yang dirujuk.
Dengan demikian, diperoleh gambaran yang lengkap
tentang pokok dan duduk permasalahan yang akan
diteliti. Studi pustaka juga dapat berupa teknik,
metode, strategi atau pendekatan yang dipilih dalam
melaksanakan penelitian. Dalam kaitan ini, akan
diuraikan dua tinjauan pustaka yang ditetapkan dalam
makalah ini sehingga dapat dibedah untuk dijelaskan apa
isi atau substansinya, apa kesamaan dan perbedaannya
dengan makalah yang peneliti tetapkan.
BAB III
12
METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan rencana dan prosedur
penyusunan meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-
metode rinci dalam mengumpulkan dan analisis data.
Rancangan tersebut melibatkan sejumlah keputusan.
Secara keseluruhan, keputusan ini melibatkan rancangan
seperti apa yang seharusnya digunakan untuk meneliti
topik tertentu.
Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan metode
Penyusunan Kualitatif, yang merupakan metode-metode
untuk mendemakalahkan dan memahami makna yang oleh
sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap
berasal dari masalah sosial kemanusiaan. Proses
penyusunan kualitatif ini melibatkan upaya-upaya
penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan
prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari
para partisipan, menganalisis data secara induktif
mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.
13
Laporan akhir untuk penyusunan ini memiliki struktur
atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat
dalam bentuk penyusunan ini harus menerapkan cara
pandang penyusunan yang bergaya induktif, berfokus
terhadap makna individual, dan menterjemahkan
kompleksitas suatu persoalan.1
1 John Creswell W, 2010, Research Design : Pendekatan Kualitatif,
Kuantitatif dan Campuran, fYogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 1-5.
Penyusunan kualitatif adalah penyusunan yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penyusunan misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, serta aktivitas.2
3.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif
analisis. Istilah deskriptif berasal dari bahasa
Inggris to describe, yang berarti memaparkan atau
menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kejadian,
peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian,
yang dimaksud dengan penyusunan deskriptif adalah
14
sebuah penyusunan yang dimaksudkan untuk menyelidiki
keadaan, kejadian, atau peristiwa tertentu, dan setelah
selesai lalu memaparkan hasilnya dalam bentuk laporan
penelitian.3
Penyusunan deskriptif yaitu penyusunan yang
berusaha mendemakalahkan suatu gejala, peristiwa yang
terjadi pada saat itu (masalah aktual). Dalam
penyusunan ini, penyusun berusaha memotret peristiwa
yang menjadi pusat perhatiannya kemudian dilukiskn
sebagaimana adanya. Masalah yang disusun adalah masalah
yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan,
sehingga pemanfaatan temuan penyusunan ini berlaku pada
saat itu dan belum tentu relevan jika digunakan dimasa
yang akan datang. Karena itu, penelitian deskriptif
tidak selamanya menuntut hipotesis.
2 Lexy J Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, edisi
revisi, Bandung, hlm.10.
3 Wasilah Chaedar, 2004, Pokoknya Kualitatif, Bandung, Pustaka
Jaya Setia, hlm. 28.
15
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuat
pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau
daerah tertentu. Penelitian deskriptif merupakan metode
penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau
subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan
tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan
karakteristik objek yang diteliti secara tepat.4
Dari batasan di atas diketahui bahwa dalam
penelitian deskriptif, ketersediaan data secara detail
merupakan hal yang vital. Sebab, sesuai dengan
karakteristik penelitian ini yang bersifat memaparkan,
maka penelitian ini akan mengutamakan pemaparan
informasi sejelas mungkin.
Oleh sebab itu, tidak jarang dalam penyusunan
deskriptif dujumpai banyak ilustrasi menggunakan
gambar, grafik, dan ilustrasi lain yang bertujuan untuk
mendukung penjelasan yang diberikan terhadap objek yang
dikaji.5
16
3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penyusunan ini, penyusun
menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu
sebagai berikut:
4 Nasution, 1992, Metode Research, Bandung, Jemmars, hlm. 39.
5 Sudyana Nana dan Ibrahim, 1998, Penelitian dan Penilaian Pendidikan,
Bandung, Penerbit Sinar Baru, hlm. 52.
Studi Kepustakaan
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam
bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini
tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi
peluang kepada penyusun untuk mengetahui hal-hal yang
pernah terjadi di waktu silam.
Teknik ini dilakukan dengan mempelajari dan
menyusun dokumen yang berhubungan dengan objek yang
disusun dan diharapkan dapat memberikan dukungan
17
terhadap data yang diperoleh. Misalnya mempelajari
buku, jurnal, laporan pemerintah daerah, dokumen
pemerintah, atau data-data yang bersumber dari media
massa seperti informasi yang diakses melalui internet.
3.3 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan
uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditekankan
tema. Ada tiga langkah cara untuk menganalisis data
kualitatif yaitu:
a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah penyusun untuk mengumpulkan data
selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.6
6 Ibid., hlm. 247.
18
a. Display Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan data sehingga data
terorganisasikan, tersusun pola hubungan dan mudah
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang
bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan
mempermudah untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
telah dipahami tersebut.7
a. Kesimpulan dan Verifikasi Data
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.8
Kesimpulan dalam penyusunan kualitatif adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan
19
dapat berupa deskripsi, hubungan kausal/interaktif,
hipotesis atau teori.
7 Ibid., hlm. 249.
8 Ibid., hlm. 253.
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Pembahasan
4.1.1 Strategi Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam mempelajari politik luar negeri, penegertian
dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri
itu pada dasarnya merupakan “action theory”, atau
20
kebijakasanaan suatu negara yang ditujukan ke negara
lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara
pengertian umum, politik luar negeri (foreign policy)
merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah
serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan
memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan
dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya
merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan
baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta
sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam
isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.9
Politik luar negeri adalah strategi dan taktik
yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya
dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik
luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh
suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara
lain.
21
9 Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D., - , Politik Luar Negeri,
Bandung, Unpad, http://pustaka.unpad.ac.id/archives/50129/.
diakses pada 2 Januari 2014 pukul 22:29 WIB.
Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan
keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.
Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar
negeri diartikan sebagai “Suatu kebijaksanaan yang
diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan
dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan
nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah
memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam
masyarakat antar bangsa”.
Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui
bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk
mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat
gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta
kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik
luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan
22
keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang
didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor
internal serta faktor-faktor internasional sebagai
faktor eksternal.
Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri
Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea
IV. Alinea I menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Selanjutnya pada
alinea IV dinyatakan bahwa “ ... dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial”. Dari dua kutipan di atas,
jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai
landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena
diatur di dalam Pembukaan UUD 1945. Selain dalam
pembukaan terdapat juga dalam beberapa pasal contohnya
23
pasal 11 ayat 1, 2,3; pasal 13 ayat 1,2,3 dan lain-
lain.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain.
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional
lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian
internasional diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
24
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.*).10
10 A.T. Sugeng Priyanto dkk, Buku Sekolah Elektronik, hlm. 76 -91
4.1.1.1 Pada Masa Pemerintahan Soekarno (Orde
Lama)
Kekuasaan dan politik Soekarno ketika memimpin
Indonesia, pernah mengalami berbagai pergantian sistem
pemerintahan. Pada awal pemerintahannya, Soekarno dan
Hatta menetapkan bahwa Indonesia menganut sistem
demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Namun seiring berjalannya waktu, ternyata dalam
kepemimpinannya terjadi beberapa friksi, mungkin karena
politik Indonesia masih “bayi” jadi Soekarno mudah
dipengaruhi oleh unsur luar, bahkan puncak friksi
tersebut, membuat Moh. Hatta tak lagi sejalan dengan
25
kekuasaan Soekarno, dan mengundurkan diri dari jabatan
wakil presiden.
Periode Orde Lama dimulai ketika Soekarno
menyatakan dekrit 1959 yang berisi tentang pemberlakuan
kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan
menghapus UUD RIS. Akan tetapi secara teknis, Soekarno
memimpin era ini semenjak kemerdekaan Indonesia pada
tahun 1945. Dengan demikian, ulasan mengenai politik
luar negeri RI pada era Orde Lama tidak bisa hanya
dipantau semenjak tahun 1959 semata, melainkan ditarik
semenjak awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun
1945.
Dalam memimpin, Soekarno dipandang sebagai sosok
yang sangat kontroversial namun populer. Sejarahnya
yang penuh dengan orasi kebangsaan yang mampu membakar
semangat segenap pemuda bangsa menunjukkan bahwa ia
seorang yang penuh percaya diri dan daya tarik. Di
masanya, Soekarno merupakan sosok pemimpin yang penuh
inisiatif dan inovatif. Kekayaannya akan ide dan
26
gagasan baru didukung dengan keberanian dalam mengambil
keputusan yang saat itu dinilai tidak biasa. Salah satu
tindakan Soekarno yang drastis dan populer pasca
kemerdekaan ialah nasionalisasi aset- aset negara yang
dulu dimiliki Belanda juga Jepang, serta melakukan
sosialisasi kedaulatan Republik Indonesia sebagai
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang
sampai Merauke kepada dunia internasional.11 Hal ini
menjadi agenda utama kebijakan luar negeri Soekarno
yang dilandasi dengan prinsip- prinsip pancasila
sebagai ideologi negara dan amanat UUD 1945 sebagai
tolak ukur pembangunan pasca kemerdekaan yang anti
terhadap imperialisme Barat.
Sikap anti Soekarno terhadap imperialisme Barat
semakin kental pada tindakannya yang menyeru negara-
negara di dunia untuk tidak tunduk terhadap blok- blok
yang saling berseteru di kala itu sehingga kemudian
lahir Gerakan Non-Blok yang diinisiasi dari Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok di Bandung pada tahun
27
1955.12 Indonesia kemudian menjadi inisiator Gerakan
Non- Blok yang banyak mendorong kemerdekaan di negara-
negara Asia- Afrika pada masa itu. Banyaknya inisiatif
yang muncul dari kebijakan luar negeri Indonesia pada
masa itu menunjukkan bahwa
11 http://umum.kompasiana.com/2010/01/31/sang-presiden-%E2%80%93-
kebijakan-politik-luar-dan-dalam-negeri-sambungan-menyerah-tanpa-
syarat/ diakses pada 2 Januari 2014 pukul 22:36 WIB.
12 http://politik.kompasiana.com/2011/01/16/periodisasi-politik-
luar-negeri-indonesia-dari-masa-orde-lama-hingga-masa-reformasi-
335055.html diakses pada 2 Januari 2014 pukul 22:41WIB.
Soekarno secara serius mengagendakan pengakuan
eksistensi Indonesia di mata internasional dan
pembentukan aliansi anti kolonialisme serta imperialism
Barat dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia. Hal
ini selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas
aktif yang dianut Indonesia. Prinsip ini dicetuskan
oleh Muhammad Hatta melalui pidatonya di depan Komite
28
Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 2 September 1948
yang berisikan pernyataan bahwa Indonesia tidak boleh
memihak baik ke Blok Barat maupun Blok Timur dalam
politik internasional demi tercapainya cita- cita
Indonesia Merdeka. Pidato yang kemudian dikenal dengan
judul “Mendayung Di Antara Dua Karang” ini meskipun
esensinya tidak lantas langsung dimasukkan ke dalam
konstitusi negara, namun ia kemudian menjadi landasan
moral yang membentuk politik luar negeri Indonesia pada
masa itu.
Meskipun demikian, sejarah perjuangan Soekarno
dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme
Barat telah membentuk pandangan Soekarno menjadi anti
terhadap Barat. Sehingga secara sikap politik pun,
Soekarno nampak cenderung pro terhadap ideologi kiri
atau timur. Kedekatan ini ditunjukan dengan
keberpihakan Soekarno terhadap Partai Komunis Indonesia
(PKI) yang kemudian membawa Soekarno terhadap peristiwa
pidato penyampaian pidato manifesto politik (manipol)
29
yang mengidentifikasikan imperialis barat sebagai musuh
nasional.13
13 http://rofiuddarojat.wordpress.com/2011/11/03/284/ diakses pada
2 Januari 2014 pukul 22:44 WIB.
Hal ini ditunjukkan secara gamblang dalam ketidaksukaan
Soekarno terhadap keberadaan Belanda di Irian Barat.
Tindakan militer kemudian diambil untuk mengambil alih
kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal
membuat Belanda angkat kaki dari Irian Barat. Dukungan
Amerika Serikat yang kemudian didapatkan Soekarno
muncul sebagai akibat konfrontasi kedekatan Jakarta
dengan Moskow.
Taktik yang konfrontatif ini kemudian digunakan
kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara
Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan negara
federasi Malaysia yang dianggap Indonesia pro terhadap
imperialisme Barat. Hal ini dianggap mengancam
keberkembangan Nefos (New Emerging Forces) oleh Oldefos
(Old Established Forces), yakni dua kategorisasi negara
30
yang dibentuk oleh Soekarno. Berbagai kebijakan luar
negeri kemudian muncul dengan landasan kepentingan
nasional yang berorientasi pada penguatan eksistensi
Indonesia dan Nefos. Salah satu tindakan yang paling
terkenal ialah pembentukan poros Jakarta-Peking dimana
Indonesia pada saat itu menjadi sangat dekat dengan
China. Tidak hanya sampai di situ,Jakarta pada era
tersebut digambarkan sebagai pusat pemerintahan yang
akrab dengan Moskow, Beijing dan Hanoi serta garang
terhadap Washington dan sekutu Barat.14
14 http://www.scribd.com/doc/24673774/Politik-Luar-Negeri-
Indonesia-Kebebasaktifan-Yang-Oportunis diakses pada 2 Januari
2014 pukul 22:47 WIB.
Sebagai dampak, ruang gerak Indonesia di forum
internasional menjadi terbatas pada seputar negar-
31
negara komunis semata. Hal ini pun mencederai prinsip
politik luar negeri Indonesia yang bebas- aktif.
Munculnya kebijakan Dwikora pada 3 Mei 1964
menunjukkan bahwa Soekarno secara serius ingin
menyingkirkan Barat dari seputar Indonesia karena
dinilai dapat memojokkan Indonesia. Kebijakan Dwikora
tersebut berisi tentang perintah untuk memperhebat
ketahanan revolusi Indonesia dan untuk membantu
perjuangan rakyat Malaysia membebaskan diri dari
neokolonialisme Inggris. Hal ini lantas disusul dengan
pencetusan Politik Mercusuar yang mendorong Indonesia
untuk tampil megah agar terlihat sebagai pemimpin Nefos
yang mampu menerangi jalan baru bagi negara- negara
Nefos lainnya. Puncak sikap kontra Soekarno terhadap
Barat ditunjukkan dengan keluarnya Indonesia dari PBB
pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk
ketidaksukaan Indonesia terhadap pengangkatan Malaysia
yang dinilai pro Barat sebagai anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB.
32
Namun sayangnya kebijakan- kebijakan luar negeri
yang diinisiasi Soekarno untuk Indonesia rupanya kurang
memperhatikan sektor domestic. Di kala Soekarno dengan
gencar melancarkan politik luar negeri yang garang,
aktif dan militant, kondisi perekonomian dalam negeri
tampak morat-marit akibat inflasi yang terjadi secara
terus- menerus, penghasilan negara merosot sedangkan
pengeluaran untuk proyek- proyek Politik Mercusuar
seperti GANEFO (Games of The New Emerging Forces) dan
CONEFO (Conference of The New Emerging Forces) terus
membengkak. Belum lagi kecamuk politik dalam negeri
yang diwarnai dengan bentrok antara militer dan PKI
membuat situasi di Indonesia pada saat itu semakin
carut marut. Puncak kecarut- marutan ini ialah
terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang
kemudian membuat kepemimpinan Soekarno di Indonesia
melemah dan bahkan terpojok. Tahun 1968 menjadi akhir
dari kepemimpinan Soekarno di Indonesia yang dengan
demikian mengakhiri pula era Orde Lama di Indonesia.
33
Secara umum, kepentingan nasional yang terus
menjadi agenda utama Indonesia di era Orde Lama ialah
kepentingan untuk menjaga kesatuan dan persatuan NKRI,
mempromosikan Indonesia sebagai negara berkekuatan yang
baru merdeka, menunjukkan eksistensi Indonesia di dunia
internasional dan menunjukkan sikap pro-perdamaian yang
anti-kolonialisme Barat. Metode yang ditempuh Soekarno
untuk memenuhi kepentingan nasional ini sangat beragam,
mulai dari cara negosiasi, pengerahan kekuatan militer,
containment, politik berdikari hingga mengundang bantuan
asing. Karakter utama yang banyak ditunjukkan politik
luar negeri Indonesia pada masa ini ialah karakter high
profile yang tegas namun masih belum terarah.15
15
http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/01/change_and_co
ntinuity_in_indonesia_for eign_policy.pdf diakses pada 2 Januari
2014 pukul 22:51 WIB.
34
Meskipun banyak penyimpangan yang terjadi pada
masa ini di mana prinsip moral bebas-aktif politik luar
negeri Indonesia justru dilangkahi oleh kedekatan
Indonesia terhadap blok Timur, namun tidak dipungkiri
banyak keberhasilan yang dicapai pada masa Orde Lama
yang hingga kini imbas baiknya masih dapat dirasakan.
Sejumlah keberhasilan politik luar negeri pada masa
Soekarno atau pada era Orde Lama antara lain:
1. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari
Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
2. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya Gerakan
Non- Blok melalui KTT Asia- Afrika di Bandung pada
tahun 1955
3. Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut
diperhitungkan oleh kedua blok raksaksa dunia pada masa
itu
Sejumlah halangan yang banyak mengusik keberlangsungan
politik luar negeri Indonesia pada era Orde Lama yaitu:
35
1. Baru terbentuknya NKRI sehingga masih banyak ancaman
disintegrasi nasional
2. Instabilitas politik dan perekonomian domestik
3. Situasi Perang Dingin dan terbentuknya dua blok
raksaksa dunia yang saling berusaha mendominasi
4. Infrastruktur yang baru dibangun tidak sesuai dengan
ambisi Soekarno untuk segera membuat Indonesia menjadi
negara adidaya
4.1.1.2 Pada Masa Pemerintahan Gus Dur
(Reformasi)
Semasa reformasi pemerintah Indonesia dianggap
tidak memiliki seperangkat formula kebijakan luar
negeri yang tepat dan tegas dalam menunjukan citra
negara Indonesia. Pemerintah semasa reformasi dari
kepemimpinan Gus Dur, Megawati hingga Susilo Bambang
Yudhoyono mengklaim bahwa pemerintahannya tetap
menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
36
Menelaah kembali semasa pemerintahan presiden Gus
Dur, dimana Indonesia baru memasuki tahapan baru dalam
pemerintahannya. Setelah menggulingkan rezim presiden
Soeharto yang dianggap rezim yang diktator, Indonesia
memasuki tahapan dimana Demokrasi lebih ditegakkan.
Pemerintahan Gus Dur dianggap yang paling
kontroversial, beliau ingin membuka hubungan diplomatik
dengan Israel namun menuai begitu banyak tentangan dari
dalam negeri. Politik luar negeri yang dijalankannya
masih menggunakan formula lama yaitu politik luar
negeri bebas aktif
Mengingat situasi internasional selalu berkembang,
politik luar negeri suatu negara kerap mengalami
perubahan. Indikator dari perubahan itu di antaranya
dalam hal gaya pelaksanaan, dari low profile menjadi high
profile atau mungkin sebaliknya; dalam hal titik berat,
dari titik berat di bidang politik ke bidang ekonomi
atau dari bidang ekonomi ke militer atau mungkin
sebaliknya; atau dalam hal arah hubungan, dari yang
37
berorientasi ke salah satu negara adikuasa ke Dunia
Ketiga atau sebaliknya.
Bagaimana pun situasi internasional merupakan
salah satu faktor yang harus diantisipasi dan
diperhitungkan secara matang oleh setiap negara dalam
rangka pembuatan kebijakan luar negerinya. Alasannya,
karena situasi internasional tidak statis, melainkan
selalu berkembang secara dinamis.
Dari pemaparan secara umum di atas mengenai
politik luar negeri masing-masing presiden, tampak
perubahan-perubahan gaya pelaksanaan politik luar
negeri Indonesia yang pada masa Soekarno (1945-1965),
politik luar negeri Indonesia bersifat high profile,
flomboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-
imperialisme dan kolonialisme serta konfrontasi, begitu
juga Gus Dur masih bergaya High Profile, namun hingga masa
presiden-presiden berikutnya menjadi semakin Low profile.
38
Sisi lain dari kepemimpinan Gus Dur sebagai
presiden adalah dominasinya dalam pelaksanaan politik
luar negeri. Dominasi itu ditunjukkan ”tur keliling
dunia” yang menghabiskan 23 dari 40 hari pertama masa
pemerintahannya, rekor baru yang fantastis dalam
sejarah kepresidenan.
Wajar Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar
Tandjung mengkritik Gus Dur jangan terlalu sering
melawat karena banyak persoalan domestik yang harus
diselesaikan, seperti konflik Aceh. Namun Gus Dur
menjawab, tujuan tur mengembalikan nama baik Indonesia,
berharap investor menanamkan modal lagi, dan mencari
dukungan internasional terhadap keutuhan Aceh sebagai
bagian dari kita.
Dominasi Gus Dur bukan penyimpangan politik luar
negeri. Bung Karno dan Pak Harto juga merupakan figur
dominan dengan gaya berbeda. Bagi mereka bertiga,
menteri luar negeri merupakan pembantu aktif yang
39
menjalankan diplomasi dan wajib mengikuti panduan
kepala negara.
Ada beda sedikit: Pak Harto lebih bersikap pasif
menyerahkan otoritas kepada para menlu, sedangkan Bung
Karno dan Gus Dur jauh lebih aktif bukan cuma
menentukan arah, tetapi juga nuansa-nuansanya.
Peranan kepala negara vital karena posisi politis
dan geografis Indonesia yang amat strategis. Negara-
negara Asia dan Afrika mengandalkan kepemimpinan
Indonesia di Gerakan Non blok, Asia Tenggara
menempatkan kita sebagai saka guru ASEAN.
Saat Perang Dingin berkecamuk, Indonesia menjadi
rebutan Blok Barat dan Timur. Barat menjalankan
kebijakan subversif agar Indonesia tidak jatuh ke
tangan komunis, China dan Uni Soviet ingin menjadikan
kita sebagai satelit.
Dominasi Bung Karno tampak dari peranannya
menggalang Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Nonblok, dan
40
Conference of New Emerging Forces (Conefo). Bung Karno
bahkan memerintahkan Perwakilan Tetap RI di New York
memutuskan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-
Bangsa.
Di tingkat regional, Bung Karno menggagas
pembentukan poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Beijing-
Pyongyang yang cenderung berkiblat ke Blok Timur. Sikap
agresif Bung Karno ditunjukkan pula melalui politik
konfrontasi terhadap Malaysia.
Dominasi Pak Harto tecermin dari perubahan
orientasi politik luar negeri yang pro-Barat dan
”diabdikan untuk pembangunan ekonomi”. Bantuan dana
untuk Orde Baru berdatangan dari negara-negara Barat
berkat politik luar negeri yang antikomunis. Pak Harto
memutuskan hubungan diplomatik dengan China.
Politik luar negeri Pak Harto berhasil menjaga
kesinambungan kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara
dengan melanjutkan gagasan Bung Karno mengenai kerja
41
sama regional melalui pembentukan ASEAN lewat Deklarasi
Bangkok 8 Mei 1967. Ini tindak lanjut dari cita-cita
Bung Karno membentuk Association of Asian States (ASA)
31 Juli 1961 dan Maphilindo (5 Agustus 1963).
Pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia
menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara
efektif. Peranan Indonesia pada masa Orde Baru terlihat
jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat
dunia. Kerjasama diperluas dalam berbagai sektor
terutama sektor perekonomian, Indonesia juga secara
cepat memberikan tanggapan akan isu-isu yang muncul
dalam dunia internasional. Politik Luar negeri
Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat
membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun beberapa
pihak menilai bahwa pada masa presiden Soeharto yang
jelas anti komunisme hubungan dengan negara-negara
komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan
Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada
42
negara-negara Barat yang pada masa presiden Soekarno
terabaikan.
Parlemen Orde Lama dan Orde Baru tidak terlalu
mempersoalkan dominasi kepala negara kecuali untuk isu-
isu kontroversial. Keterlibatan aktor-aktor masyarakat
terbatas karena tak begitu peduli dengan proses
pengambilan keputusan politik luar negeri yang elitis.
Namun, saat Gus Dur memimpin, asumsi itu berubah.
Globalisasi memaksa rakyat dan parlemen giat mengikuti
perkembangan internasional dan regional yang
berpengaruh terhadap situasi domestik. di era
pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4
Republik Indonesia, mulai menapaki terminologi dari
sebuah Demokratisasi yang baru. George Kahin dalam
bukunya Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence
(1976), menyebutkan bahwa politik luar negeri Indonesia
senantiasa sangat dipengaruhi oleh politik domestik.
Hal ini terbukti ketika dimulainya masa pemerintahan
presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa “Gus
43
Dur” ini. Jika dilihat kembali beberapa karakteristik
cara diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno hingga
Habibie yang cenderung melakukan diplomasi yang
multilateral, dalam pemerintahan Gus Dur ketika
memimpin Republik Indonesia ini, lebih mengedepankan
diplomasi secara Bilateral. Gus Dur selalu menampakan
moment-moment pertemuan antar negara dengan sikap yang
bisa dikatakan fun. Fun disini berarti bahwa ketika Gus
Dur melakukan kunjungan kenegaraan, suasana yang bisa
dibilang “formal” bisa dibuat menjadi terkesan lucu
atau dapat mencairkan suasana yang memanas. Teori fun
yang dilakukan untuk mencairkan suasana ini dapat
memudahkan transaksi kepentingan dan bahkan mempermulus
pertarungan strategis, dan juga bisa meningkatkan
bargaining position terhadap posisi Indonesia yang saat
itu sedang melemah.
Memang benar, posisi Indonesia ketika dipimpin
oleh presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 ini
mengalami depresi yang teramat berat. Ketika Indonesia
44
dihadapkan dengan tragedi kerusuhan Mei 1998, kemudian
Negara Timur Leste yang memerdekakan diri, dan beberapa
kasus-kasus lainnya, mengakibatkan bahwa Gus Dur harus
mampu memulihkan citra positif dari Indonesia. Hal ini
dibuktikan, ketika Gus Dur melakukan lawatan atau
kunjungan ke Luar Negeri lebih sering, tercatat bahwa
Gus Dur pernah melakukan kunjungan ke 10 Negara Eropa –
Asia hanya dalam waktu 17 hari saja. Walaupun hal ini
terkesan sebagai sebuah Tour presiden, namun lebih
menekankan bahwa kunjungan kenegaraan ini digunakan
untuk menghadirkan citra positif bagi bangsa Indonesia
dan kemudian dapat terbentuknya lagi bantuan
perekenomian dari negara-negara Eropa maupun Asia. Tak
mudah menilai sukses tur keliling dunia Gus Dur karena
usia pemerintahannya yang pendek.
Pernyataan politik luar negeri perdana Gus Dur
mengumumkan rencana pembukaan hubungan dagang dengan
Israel. Ada dua alasan: pertama, menggairahkan hubungan
dengan lobi Yahudi. Indonesia paling tidak bisa minta
45
tokoh Yahudi, George Soros, tak mengacaukan pasar
uang/modal untuk menghindari krisis moneter. Kedua,
meningkatkan posisi tawar Indonesia menghadapi Timur
Tengah yang tak pernah membantu Indonesia mengatasi
krisis moneter.
Melalui Menlu Alwi Shihab, Gus Dur memperkenalkan
tiga elemen politik luar negeri. Pertama, menjaga jarak
sama dengan semua negara, kedua hidup bertetangga baik,
dan ketiga ”kebajikan universal”.
Seperti Bung Karno, Gus Dur berambisi mewujudkan
”poros kekuatan” di Asia. Ia sempat memulai prakarsa
tersebut dengan menggagas Forum Pasifik Barat yang
terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Papua Niugini,
Australia, dan Selandia Baru yang sempat disuarakan ke
sembilan negara ASEAN.
Masih segar dalam ingatan, Gus Dur membujuk
Singapura menyetujui pembentukan Forum Pasifik Barat
dalam KTT ASEAN di Singapura, November 2000. Menteri
46
Senior Lee Kuan Yew menolak permintaan itu. Wajar jika
Gus Dur langsung ngamuk, membuat Singapura gempar.
”Pada dasarnya orang Singapura melecehkan Melayu. Kita
dianggap tak ada. Lee Kuan Yew menganggap saya sebentar
lagi turun (dari jabatan presiden). Singapura mau
enaknya sendiri, cari untungnya saja,” kata Gus Dur.
Sebelum itu Gus Dur mengemukakan pembentukan poros
(axis) Indonesia-China-India. Tak lama kemudian ia
memprakarsai pula poros ekonomi Indonesia, Singapura,
China, Jepang, dan India. Sayang, sejumlah negara Barat
dan beberapa sekutu mereka di kawasan ini—merasa
khawatir dengan fenomena ”kebangkitan Asia” ala Doktrin
Wahid ini.
Gus Dur minta bantuan Mensesneg Bondan Gunawan dan
sejumlah teman untuk merumuskan pembentukan organisasi
Dewan Keamanan Nasional. Sebagai presiden, Gus Dur juga
menampakkan ketegasannya seperti ia berkeinginan setiap
sarapan sudah di-brief tentang perkembangan politik dan
keamanan regional/internasional yang mutakhir dan apa
47
Seperti yang dipaparkan di atas mengenai strategi
dan gaya diplomasi dalam politik luar negerinya masing-
masing, presiden atau kepala pemerintahan pada masa itu
cenderung berbeda, adapun perbedaan itu yakni strategi
dan gaya diplomasinya. Soekarno merupakan sosok
pemimpin yang penuh inisiatif dan inovatif. Kekayaannya
akan ide dan gagasan baru didukung dengan keberanian
dalam mengambil keputusan yang saat itu dinilai tidak
biasa menjadi tolak ukur keberhasilan strategi politik
luar negeri Indonesia pada masa itu. Soekarno pada
masanya cenderung melakukan strategi atau gaya
diplomasi yang multilateral. Sedangkan Gus Dur lebih
menekankan strategi atau gaya diplomasi bilateral. Gus
Dur selalu menampakan moment-moment pertemuan antar
negara dengan sikap yang bisa dikatakan fun. Fun disini
berarti bahwa ketika Gus Dur melakukan kunjungan
kenegaraan, suasana yang bisa dibilang “formal” bisa
dibuat menjadi terkesan lucu atau dapat mencairkan
suasana yang memanas. Teori fun yang dilakukan untuk
mencairkan suasana ini dapat memudahkan transaksi
49
kepentingan dan bahkan mempermulus pertarungan
strategis, dan juga bisa meningkatkan bargaining
position terhadap posisi Indonesia yang saat itu sedang
melemah.
Gus Dur memperkenalkan tiga elemen politik luar negeri.
Pertama, menjaga jarak sama dengan semua negara, kedua
hidup bertetangga baik, dan ketiga ”kebajikan
universal”.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan ini
yakni keberhasilan dari strategi politik luar negeri
Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama)
yakni sejumlah keberhasilan politik luar negeri pada
masa Soekarno atau pada era Orde Lama antara lain:
1. Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari
Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
2. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya Gerakan
Non- Blok melalui KTT Asia- Afrika di Bandung pada
tahun 1955
50
3. Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut
diperhitungkan oleh kedua blok raksaksa dunia pada masa
itu
Sejumlah halangan yang banyak mengusik keberlangsungan
politik luar negeri Indonesia pada era Orde Lama yaitu:
1. Baru terbentuknya NKRI sehingga masih banyak ancaman
disintegrasi nasional
2. Instabilitas politik dan perekonomian domestik
3. Situasi Perang Dingin dan terbentuknya dua blok
raksaksa dunia yang saling berusaha mendominasi
4. Infrastruktur yang baru dibangun tidak sesuai dengan
ambisi Soekarno untuk segera membuat Indonesia menjadi
negara adidaya.
Sedangkan sejumlah keberhasilan politik luar
negeri pada masa Gus Dur atau pada era Reformasi ialah
perbaikan citra Indonesia sehingga investasi asing pun
dapat mengalir membantu perekonomian Indonesia yang
51
masih terseok akibat krisis. Kebanyakan keberhasilan
Gus Dur lebih berpusat pada pengelolaan konflik melalui
agregasi kepentingan yang baik. Namun dengan
kepemimpinan yang banyak dianggap menyimpang, Gus Dur
tidak sempat menghasilkan catatan keberhasilan lebih
banyak dari apa yang telah direncanakan.
Berikut sejumlah hambatan yang muncul pada era
kepemimpinan Gus Dur:
1. Transisi demokrasi menyebabkan ketidakstabilan
politik
2. Perekonomian masih belum bangkit dari krisis
3. Konflik horizontal dan vertical semakin bermunculan
dan mengancam keamanan nasional
4. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap citra
Indonesia yang memburuk
5. Kurangnya dukungan dari dalam negeri terhadap
kebijakan yang diambil Gus Dur
52
6. Transisi politik dan demokrasi menyebabkan
kepercayaan terhadap pemerintah dari rakyat masih
minim.
5.2 Saran
Saran untuk kajian ini, yakni saya berharap
pemerintah sekarang atau pemerintah yang menjabat lebih
mempertimbangkan lagi setiap pengambilan kebijakan
politik luar negeri Indonesia dengan harus berlandaskan
alasan atau disesuaikan dengan kepentingan negaranya
itu sendiri, bukan malah menjerumuskan negaranya.
Maksud dari menjerumuskan disini yakni pemerintah
Indonesia harus bisa membagi tugas untuk menyelesaikan
permasalahan dalam negeri dan luar negeri tanpa
melupakan permasalahan lain yang lebih penting seperti
kemiskinan atau krisis ekonomi di dalam negeri, seperti
kita ketahui tadi saat Gus Dur sedang intim-intimnya
memperjuangkan nama baik negara atau citra negara di
percaturan internasional namun rakyatnya sendiri
malahan memiliki masalah kemiskinan atau krisis
53
ekonomi. Mungkin masalah citra lebih baik namun masalah
lain muncul yakni krisis ekonomi mulai melanda. Jadi
yang saya inginkan pemerintah lebih bijak dalam membagi
tugas (permasalahan luar negeri / International Issue dan
permasalahan dalam negeri / Domestic Issue).
DAFTAR PUSTAKA
W, John Creswell, 2010, Research Design : Pendekatan
Kualitatif, Kuantitatif dan jjjjjjjjjjjjCampuran,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
54
Moleong , Lexy J, 2006, Metode Penelitian Kualitatif,
edisi revisi, Bandung.
Chaedar, Wasilah, 2004, Pokoknya Kualitatif, Bandung,
Pustaka Jaya Setia.
Nasution, 1992, Metode Research, Bandung, Jemmars.
Sudyana Nana dan Ibrahim, 1998, Penelitian dan
Penilaian Pendidikan, Bandung, jjjjjjjjjjjjPenerbit
Sinar Baru.
Ikrar Nusa Bhakti. Reinterpretasi Politik Luar Negeri
Indonesia dan Kemandirian Regional Asia Tenggara
(Studia Politika 2). Jakarta:1998.
Ananda, Azwar dan Junaidi Indrawati (2008) Hubungan
Internasional konsep dan teori. UNP Press: Padang
MacDonald, David B., Robert G. Patman and Betty Mason-
Parker (2007) THE ETHICS OF FOREIGN POLICY. Ashgate
Publishing Company: Burlington USA
55
http://pustaka.unpad.ac.id/archives/50129/. diakses
pada 2 Januari 2014 pukul 22:29 WIB.
A.T. Sugeng Priyanto dkk, Buku Sekolah Elektronik, hlm. 76 -
91
http://umum.kompasiana.com/2010/01/31/sang-presiden-
%E2%80%93- kebijakan-politik-luar-dan-dalam-negeri-
sambungan-menyerah-tanpa- syarat/ diakses pada 2
Januari 2014 pukul 22:36 WIB.
http://politik.kompasiana.com/2011/01/16/periodisasi-
politik-luar-negeri- indonesia-dari-masa-orde-lama-
hingga-masa-reformasi-335055.html diakses pada 2
Januari 2014 pukul 22:41WIB.
http://rofiuddarojat.wordpress.com/2011/11/03/284/
diakses pada 2 Januari 2014 pukul 22:44 WIB.
http://www.scribd.com/doc/24673774/Politik-Luar-Negeri-
Indonesia- Kebebasaktifan-Yang-Oportunis diakses
pada 2 Januari 2014 pukul 22:47 WIB.
56
http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/01/
change_and_continuity_in _indonesia_for eign_policy.pdf
diakses pada 2 Januari 2014 pukul 22:51 WIB.
57