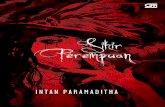KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ...
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
DI INDONESIA
Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP
Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Rizqi Abdurrahman Masykur
1112112000012
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK
DI INDONESIA
Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP
Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Rizqi Abdurrahman Masykur
1112112000012
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul:
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA
Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI
Jakarta Pada Pemilu 2014
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan umtuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya saya
atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 9 Januari 2017
Rizqi Abdurrahman Masykur
NIM: 111211200012
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Rizqi Abdurrahman Masykur
NIM : 1112112000012
Program Studi : Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA
STUDI TENTANG PEROLEHAN SUARA PEREMPUAN PARTAI PPP DI
PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2014
dan telah diuji pada tanggal 9 Januari 2017.
Jakarta, 9 Januari 2017
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Dr. Iding Rosyidin, M.Si.
NIP: 197010132005011003
Menyetujui,
Pembimbing,
Dra. Gefarina Djohan, MA.
NIP: 196310241999032001
ii
PENGESAHAN PANITIA SKRIPSI
SKRIPSI
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA
STUDI TENTANG PEROLEHAN SUARA PEREMPUAN PARTAI PPP DI
PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2014
Rizqi Abdurrahman Masykur
1112112000012
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 9
Januari 2017 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S. Sos) Pada Program Studi Ilmu Politik.
Ketua, Sekretaris,
Dr. Iding Rosyidin, M.Si. Suryani. M.Si
NIP: 197010132005011003 NIP: 197704242007102003
Penguji I,
Dr. Haniah Hanafie, M.Si
NIP: 196105242000032002
Penguji II
Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si.
NIP: 197204122003121002
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 9 Januari 2017
Ketua Program Studi
FISIP UIN Jakarta
Dr. Iding Rosyidin, M.Si.
NIP: 197010132005011003
iv
ABSTRAKSI
Skripsi ini berjudul Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia:
Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta
Pada Pemilu 2014. Indonesia sejak pemilu tahun 2004 telah menetapkan batas
minimum caleg perempuan dalam pencalonan legislati sebesar 30%, harapannya
tercapainya keterwakilan perempuan yang representatif. Namun setelah kebijakan
tersebut berjalan sampai pemilu tahun 2014 belum menampakkan hasil yang
cukup signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen.
PPP secara nasional pada pemilu tahun 2014 berhasil meningkatkan
jumlah perempuan pada fraksinya menjadi 10 kursi dari 5 kursi pada pemilu 2009.
Namun hal ini berbanding terbalik dengan perolehan PPP pada kursi perempuan
di DPRD DKI Jakarta yang hanya memperoleh satu kursi untuk perempuan dari
10 kursi yang didapat. Penilitian ini membahas tentang upaya PPP dalam
meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya, dan faktor-faktor penghambat
perolehan suara perempuan di DKI Jakarta pada umumnya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif
untuk menggambarkan permasalahan yang ada di PPP pada umumnya dan
wilayah DKI Jakarta khususnya tentang keterwakilan perempuan. Teori yang
penulis gunakan adalah teori gender tentang feminisme liberal dan konsepsi
patriarki, lalu teori kuota perempuan, serta terakhir teori oligarki partai politik.
Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa stereotipe masyarakat
tentang perempuan yang lemah, masih menjadi penyebab minimnya perolehan
suara perempuan secara umum dalam pemilu, pada partai PPP ditemukan bahwa
basis massa partai yang notabene banyak dari kalangan Islam tradisional
menyebabkan caleg perempuan kurang diminati, adapun satu perempuan yang
terpilih juga karena yang bersangkutan mempunyai modal sosial yaitu majlis
taklim sebagai basis massanya dan pada kenyataannya pada calon tersebut
merupakan bagian dari oligarki partai.
Kata kunci: Perempuan, Keterwakilan, Perolehan suara, PPP.
v
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah yang merajai segala raja dan menguasai segala ilmu
pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Berkat rahman dan rahim-Nya penulis
dapat menyelesaikan tugas akhir di waktu yang tepat. Shalawat beserta salam
selalu dan terus terucah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing
umatnya menuju jalan kebenaran yaitu Islam.
Skripsi merupakan awal dari kehidupan akademis penulis. Karena dari
skripsi ini penulis terpacu untuk memberikan karya tulis yang terbaik di masa
yang akan datang. Sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di sana-sini,
penulis mengharapkan kritik dan saran. Penyelesaian sksipsi ini tentu tak lepas
dari campur tangan orang-orang di sekitar penulis baik langsung maupun tidak
langsung. Dengan bangga penulis ucapkan terima kasih yang kepada:
1. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr.
Dede Rosyada, MA.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif
HidayatullahJakarta, Prof. Dr. Zulkifli, MA.
3. Ketua Prodi Ilmu Politik, Dr. Iding Rasyidin, M.Si, dan Sekretaris Prodi
Ilmu Politik, Suryani M.Si.
4. Dosen pembimbing Dra. Gefarina Djohan, MA, yang telah banyak
meluangkan waktu untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam
membimbing penulis.
vi
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Uung Masykur dan Ibu Watini terima
kasih atas doa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis
selama ini.
6. Kedua adik penulis, Fauzan Abdurrahman Masykur dan Ihsan
Abdurrahman Masykur yang selalu memberikan anasir-anasir baru
dalam penulisan skripsi ini.
7. Usep Hasan Sadikin selaku Peneliti pada Perludem (Perkumpulan Untuk
Pemilu dan Demokrasi). Terima kasih telah meluangkan waktu untuk
penulis wawancarai.
8. Drs. H. Arifuddin Halking, M.Si. selaku wakil ketua bidang OKK
(Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi) DPW PPP DKI Jakarta.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk penulis wawancarai.
9. H. Abdul Aziz Suaedy, S.E. selaku ketua DPW PPP DKI Jakarta.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk penulis wawancarai.
10. Hj. Marie Amadea Ismayani, S.Si. Ketua KPPI (kaukus Perempuan
Politik Indonesia) DKI Jakarta. Terima kasih telah meluangkan waktu
untuk penulis wawancarai.
11. Teman-teman Ilmu Politik 2012 kelas A, Alfia, Cendy, Amin, Fauzan,
Sambung, Fahrul, Ferry, Kartika, Faqih, Devi, Alice, Nisa, Ruhul,
Fahmi, Rozi, Zizi, Dipo, Rahmat, Hatta, Mabrur, Pakde fakih, Cak Ipul,
Helmi, Yusuf, Abrar dan teman-teman yang lain yang tak dapat penulis
sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segalanya yang telah tercipta.
vii
12. Teman-teman Kontrakan Anti-Gober, Bang Yusran, Bang Isnan, Bang
Along, Ahmad Rifani, Fachry Fauzan, Afif Hasan N, Muslih Muhaimin,
Vanny El Rachman.
13. Teman-teman “lorong kemalingan ASPA”, Aziz, Rio, Fahmi, Rahmat
14. Teman-teman koloni KKN Lebah, terima kasih telah mewarnai
kehidupan penulis.
15. Teman-teman PK FISIP IMM, Ruhul, Neng Sofi, Fawaz, Aqil, Zul,
Rizki Ikhwani, Angga serta kanda Beni, kanda Farhan, kanda Reza dan
senior-senior komisariat yang lain terima kasih atas pengalaman yang
luar biasa yang telah penulis dapat. Maaf jika ada kesalahan laku dan
ucap dalam mengemban amanah di Komisariat.
16. Terakhir kepada semua pihak, yang tak bisa disebutkan satu persatu.
Terima kasih atas dukungan moral dan material selama penulis kuliah
dan menyusun skripsi ini.
Segala terima kasih penulis haturkan kepada mereka yang telah membatu
penulis menyusun skripsi ini. Semoga Allah yang maha bijaksana membalas
segala kebaikan serta melindunginya dari kejahatan dunia.
Jakarta, 9 Januari 2017
Penulis
Rizqi Abdurrahman Masykur
1112112000012
viii
DAFTAR ISI
ABSTRAK …………………………………………….….…….. iv
DAFTAR ISI …………………………….…..……………………. viii
DAFTAR TABEL ………..……………………….……………. x
BAB I PENDAHULUAN …..……….…………………………. 1
A. Pernyataan Masalah……..……………………………… 1
B. Pertanyaan Penelitian …….………………………..…… 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……….……………….… 8
D. Tinjauan Pustaka …….……..……….…………….…… 10
E. Metode Penelitian ..………….………..………………… 14
F. Sistematika Penulisan…………..……..……..…….……. 16
BAB II KERANGKA TEORI …………...……….……………… 18
A. Teori Gender dan Budaya Patriarki…………………….. 18
B. Teori Kuota Perempuan Dalam Politik ………………… 29
C. Teori Oligarki Dalam Partai Politik…….………………. 35
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PPP DAN KIPRAHNYA DI
DKI JAKARTA………..……….……….…….…………….………….. 39
A. Profil PPP …..………………………….……………..…… 39
B. Platform PPP…....……..………..……….……….…..……. 44
C. PPP dan Perspektif Representasi Perempuan di Politik….… 45
BAB IV PPP DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM
PEMILU DI DKI JAKARTA..………..……..…….…….………….. 49
A. Perolehan Suara Untuk Caleg Perempuan
Pada Pileg 2014 di DKI Jakarta……………….……………….. 49
B. Faktor-faktor Penyebab Minimnya Perolehan Suara Untuk
Caleg Perempuan Pada Pileg 2014 di DKI Jakart…..……….. 60
1. Popularitas………………..…….……………….…… 65
2. Modal Sosial…………………………………………. 66
3. Oligarki Partai ………………………………………. 67
4. Stereotipe dan Budaya Patriarki …………………….. 69
C. PPP dan Perolehan Suara
Pada Pileg 2014 di DKI Jakarta............................................... 70
ix
BAB V PENUTUP .............................................................. ……………... 81
A. Kesimpulan ................................................................................. 81
B. Saran............................................................................................ 82
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 85
LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel IV.A.1 Prosentase keterwakilan Perempuan Pada Tahap Pencalonan
Legislatif DPRD DKI Jakarta Pada tahun 2014-2019…………………. 52
Tabel IV.A.2 Penempatan Nomor urut 1-3 Pada Perempuan Dalam Tahap
Pencalonan Legislatif DPRD DKI Jakarta Pada tahun 2014-2019……… 53
Tabel IV.A.3 Caleg Perempuan Terpilih DPRD DKI Jakarta 2014-2019… 55
Tabel IV.C.1 Caleg Terpilih PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019………… 73
Tabel IV.C.2Perbandingan Prosentase Jumlah Suara dan Kursi Perempuan
Dalam Fraksi di DPR RI dengan DPRD DKI Jakarta tahun 2014-2019….. 75
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Manusia merupakan makhluk zoon politicon menurut filsuf Aristoteles
yang berarti makhluk sosial. Hal tersebut menandakan bahwa manusia
membutuhkan manusia lain untuk hidup serta bekerja sama.1 Pada perwujudannya
manusia terbagi dalam dua jenis yakni laki-laki dan perempuan. Namun
Aristoteles juga memberikan gambaran tentang perempuan, bahwa kehidupan
perempuan hanya bersifat fungsional, perempuan bagian untuk menyediakan
kebutuhan hidup.2 Pandangan Aristoteles tentang perempuan ini bertentangan
dengan apa yang dikatakannya sebagai zoon politicon. Sebagaimana diketahui
dalam alam demokrasi Yunani klasik perempuan tidak mendapatkan hak politik
bahkan suara, hanya laki-laki yang mempunyai keleluasaan dalam ruang publik
begitupun dalam politik. Kekuasaan yang besar didapat laki-laki bisa disebut
sebagai bentuk dari patriarki.
Patriarki atau patrilineal adalah sebuah paham dimana laki-laki dipandang
lebih superior dibanding dengan lawan jenisnya yakni perempuan. Paham ini
mungkin berkembang sudah sangat lama dan tampaknya sudah membudaya,
1Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, cetakan kedua, 2012), hal. 19 2M. Adji, Lina Meilinawati dan Baban Banita, Perempuan Dalam Kuasa
Patriarki, laporan penelitian/Buku Fakultas Sastra Universitas Padjajaran tahun 2009,
hal. 21
2
maka dari itu bisa disebut sebagai budaya patriarki atau patrilineal. Sejarawan
terkenal John Tosh menjabarkan bahwa patriarki adalah sebuah konsep dimana
kaum laki-laki memperbesar jaringan kekuasaannya dengan tanggungan kaum
perempuan baik dalam level fisik maupun sosial.3
Selanjutnya tesis tentang patriarki dikemukakan oleh Sylvia Walby,
menurutnya patriarki itu bisa dibedakan menjadi dua yakni patriarki privat dan
patriarki publik. Patriarki privat ialah patriarki yang terdapat pada keluarga,
sedangkan patriarki publik ialah bentuk patriarki yang berdiaspora dan meluas ke
wilayah-wilayah publik, seperti pengambilan kebijakan dan sebagainya yang
menjadikan pria lebih dominan di segala segi kehidupan tak terkecuali wilayah
politik.4
Menurut Gadis Arivia, sejarah tentang perempuan yang mulai peka dalam
menyuarakan hak-haknya bahkan menuntut partisipasi yang lebih dalam bidang
politik dapat dilacak pada tahun 1848, ketika itu perwakilan perempuan dari
seluruh dunia sebanyak kurang lebih 300 orang berkumpul dan mengadakan
konvensi dalam pertemuan Seneca Falls untuk mempertanyakan tentang hak-hak
perempuan dan kurangnya partisipasi perempuan dalam ranah politik.5
3Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 10 No. 1, April 2008, UI Press,
hal. 42 4Jurnal KOMUNIKA, Vol, 8 No. I, 2005. LIPI, hal. 59
5Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kata Hati (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 12
3
Beberapa puluh tahun kemudian, partisipasi perempuan dalam ruang
publik mulai didengungkan kembali hal ini mungkin tindak lanjut dari pertemuan
Seneca Falls. Dimotori oleh Selandia Baru pada tahun 1894 yang memberikan
hak perempuan dalam memilih disusul oleh Australia dan dua negara Skandinavia
yakni Finlandia dan Norwegia dua puluh tahun setelahnya.6
Di Indonesia sendiri partisipasi perempuan dalam hal hak pilih misalnya,
sudah ada sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Walaupun perempuan
dibolehkan dalam hal memilih namun tak serta merta juga keberadaan perempuan
dalam pemerintahan baik di eksekutif dan legislatif seimbang dengan laki-laki.
Gerakan perempuan pada masa Orde Lama dan Orde Baru hanya sebatas
emansipasi,7 dalam artian perempuan memperjuangkan hal-hal formal seperti
pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Barulah pada dekade 90an haluan dan arah gerakan perempuan mulai
berubah yang tadinya menyoroti hal-hal formal menjadi menyoroti hal-hal yang
bersifat kesetaraan gender seperti representasi perempuan dalam ruang publik
khususnya dalam politik. Gerakan perempuan pada masa ini sudah mulai
dimasuki oleh ideologi feminisme-feminisme Internasional yang concern pada
banyak permasalahan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.8
6Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kata Hati, hal. 12
7Amelia Fauzia, Tentang perempuan Islam: Gerakan dan Wacana, ( Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama), hal. 79 8Amelia Fauzia, Tentang perempuan Islam: Gerakan dan Wacana, hal. 79
4
Menurut Firmanzah, pergerakan di Indonesia yang memperjuangkan
tentang kesetaraan gender dan representasi perempuan dalam ranah politik tak
lepas dari terpaan-terpaan arus ideologi feminisme yang memang transnasional
dan mulai masuk ke berbagai belahan dunia yang pada umumnya adalah negara-
negara berkembang mengingat negara-negara ini dalam hal representasi
perempuan menunjukkan statistik yang tak sebesar negara-negara maju di
Amerika dan Eropa.
Agenda utama gerakan feminis adalah mensejajarkan perempuan dalam
partisipasi politik. Kaum feminis berontak terhadap dominasi laki-laki
yang terlalu kuat dalam dunia politik—dan sesungguhnya nyaris dalam
semua bidang kehidupan yang ‗penting‘, kecuali di beberapa bidang
seperti kecantikan—sehingga kurang memberikan ruang bagi kaum
perempuan untuk memperjuangkan nasib mereka. Dalam era sebelumnya,
kaum perempuan merupakan kaum marjinal dalam kehidupan politik.
Karena itu perlu ‗political will‘ untuk mengangkat dan meningkatkan
peran serta perempuan dalam dunia politik. Melalui jaringan internasional,
banyak LSM melakukan edukasi sekaligus memberikan ‗tekanan‘ kepada
negara-negara yang partisipasi perempuannya masih kurang dalam
kehidupan politik.9
Akhirnya setelah beberapa tahun bergulir reformasi, pemerintah
mengeluarkan peraturan yang merupakan jawaban pada kelompok-kelompok
yang menginginkan representasi perempuan lebih kuat dan terkesan seimbang
pada ranah legislatif. Pemerintah Indonesia dengan bijak telah meratifikasi
amanat konferensi Beijing yang menginginkan affirmative action dengan hadirnya
30% perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan mulai mendapat pijakan
9Firmanzah, Marketing politik antara pemahaman dan realitas (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2008), hal. 33
5
hukumnya ketika DPR mensahkan UU No. 12/2003 pada awalnya tentang
pemilihan umum, dan sekarang memakai UU No. 8/2012 yang mengharuskan
partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontestasi di
ajang pemilu legislatif baik di DPR pusat sampai DPRD tingkat II atau tingkat
kabupaten/kota. Namun UU pemilihan umum tersebut tak serta merta meloloskan
30% pula ke kursi dewan hal inilah yang menjadi masalah, apakah keterwakilan
30% hanya sampai pada kuantitas calon perempuan dalam pemilu legislatif lalu
berhenti disana. Lantas bagaimana dengan representasi yang riil, yakni kuantitas
perempuan di dalam parlemen itu sendiri.
Hasil pemilu legislatif tahun 2014 suara perempuan di tingkat pusat yakni
DPR-RI sebesar 17.3% atau sama dengan 97 kursi dari 560 kursi yang
diperebutkan dalam 77 daerah pemilihan (Dapil), perolehan ini boleh dibilang
kurang menggembirakan,10
pasalnya jika membandingkan dengan perolehan yang
di dapat perempuan pada tahun 2009 yakni 18% atau memperoleh 103 kursi di
parlemen pusat, praktis apa yang didapat oleh caleg perempuan pada pileg di
tahun 2014 mengalami penurunan sebesar enam kursi dibanding apa yang didapat
pada tahun 2009 lalu.
Menurut Puskapol UI, penurunan hasil suara perempuan pada pileg tahun
2014 tersebut layak dikritisi karena jika membandingkan dengan ukuran tingkat
10
http://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/analisis-perolehan-suara-
dalam-pemilu-2014-oligarki-politik-dibalik-keterpilihan-caleg-perempuan.html diunduh
pada 26 Mei 2016
6
pencalonan perempuan pada pileg 2009 dan 2014 yang mengalami tren kenaikan,
pileg 2009 hanya mencalonkan 33.6% perempuan untuk maju dalam kontestasi di
tingkat pusat sedangkan di pemilu berikutnya di tahun 2014 pencalonan
perempuan naik kurang lebih 4% ke prosentase 37% hal ini seiring dengan
peraturan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang lebih tegas tentang 30%
minimum perempuan dalam daftar calon legislatif dalam tiap partai. Temuan
dalam pemilu di atas menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan bagi
keterpilihan perempuan dalam parlemen tidak secara otomatis teratasi dengan
dikeluarkannya peraturan teknis yang secara formal ditujukan untuk mengawal
proses pencalonan perempuan.11
Jika melihat hasil perolehan kursi yang didapat oleh perempuan di DPR RI
pada Pileg 2014 memang mengalami penurunan, namun hal ini tidak berlaku pada
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang jumlah kursi perempuannya naik
sampai 100% dibanding dengan apa yang diraih partai tersebut pada Pileg 2009.
PPP berhasil mendapatkan 10 kursi untuk wakil perempuannya di DPR Pusat
jumlah tersebut sama dengan 26% dari keseluruhan kursi yang didapat oleh PPP
yakni sebesar 39 kursi.
Perolehan pada Pileg tahun 2014 tersebut bisa dikatakan mengalami
kenaikan yang cukup signifikan bagi PPP bila dilihat dari pemilu legislatif
11
http://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/analisis-perolehan-suara-
dalam-pemilu-2014-oligarki-politik-dibalik-keterpilihan-caleg-perempuan.html diunduh
pada 26 Mei 2016
7
sebelumnya pada tahun 2009 yang hanya mendapatkan 5 kursi untuk perempuan
dari 38 kursi yang dimiliki oleh partai tersebut. Cukup baik bila melihat apa yang
dapat diraih PPP dalam Pileg 2014 terlebih untuk keterwakilan perempuan,
walaupun PPP bisa dibilang partai dengan perolehan suara nasional cukup kecil
yakni 6.63% dan menempati urutan 9 dari 10 partai nasional yang berhasil lolos
parliamentary treshold.
Apa yang terjadi pada keterwakilan perempuan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dalam Pileg 2014 nampaknya tidak serta merta terjadi pula
di Pileg DPRD DKI Jakarta, PPP hanya bisa mendapatkan 10 persen suara untuk
perempuan dari 10 kursi yang didapatkan, artinya hanya ada satu calon
perempuan yang lolos ke DPRD DKI Jakarta dari partai PPP, perolehan tersebut
tidak terlalu menggembirakan dibandingkan dengan apa yang didapat PPP di
tingkat pusat. tetapi perlu diketahui bahwa PPP bukanlah satu-satunya partai yang
kurang dalam raihan kursi perempuan di DPRD DKI Jakarta masih ada Hanura,
PAN, Golkar, PKB, dan NasDem yang bahkan tidak mampu sama sekali meraih
kursi untuk calon perempuannya.
Ada beberapa hal mengapa perlunya representasi perempuan di suatu
instansi publik apalagi yang menyangkut dengan pembuatan kebijakan seperti
pada ranah legislatif ini. Perempuan diperlukan suaranya atau pendapatnya pada
tahap formulasi atau penggodokan kebijakan utamanya yang menyangkut anak-
anak dan perempuan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya pembuatan kebijakan
8
mengenai KDRT dan kejahatan terhadap anak, jika anggota legislatif banyak
dalam segi kuantitas maka kebijakan yang diputuskan sesuai dengan apa yang
diharapkan.
B. Pertanyaan Penelitian
Atas dasar latar belakang masalah terdapat dua pertanyaan, sebagai
berikut:
1. Bagaimana kondisi umum perolehan suara pada perempuan dalam Pemilu
2014 di DKI Jakarta ?
2. Bagaimana political will partai PPP dalam peningkatan keterwakilan
perempuan pada pemilu 2014 di DKI Jakarta ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
a) Untuk menjelaskan kondisi umum perolehan suara pada
perempuan dalam Pemilu 2014 di DKI Jakarta, dan untuk
menjelaskan faktor-faktor umum penghambat perolehan suara
perempuan
b) Untuk menggambarkan sejauh mana political will dari PPP
kaitannya dengan affirmative action pada pemilu legislatif DPRD
DKI Jakarta tahun 2014.
9
2. Manfaat Penelitian
a) Manfaat Akademis
Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian
dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu politik, dan
berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang
melakukan kajian terhadap fenomena pemilu dengan permasalahan
keterwakilan perempuan dalam parlemen.
b) Manfaat Praktis
Memberi informasi kepada masyarakat umumnya bahwa kebijakan
yang mendukung representasi perempuan dalam parlemen belumlah
cukup, kebijakan itu harus dibarengi dengan kesadaran segenap
elemen masyarakat dan institusi politik akan pentingnya kehadiran
perempuan dalam tiap rruang publik tak terkecuali institusi legislatif.
D. Tinjauan Pustaka
Literature review atau tinjauan pustaka adalah bahan rujukan dan bahan
pembeda penelitian yang penulis lakukan dengan orang lain yang meneliti seputar
masalah yang sama dan berkaitan. Tinjauan pustaka juga merupakan bukti bahwa
penelitian yang nantinya dilakukan orisinil atau tidak. Karena dalam penelitian ini
penulis akan mendalami permasalahan seputar mekanisme kebijakan partai dalam
mengakomodasi dan menempatkan caleg-caleg perempuan, serta bagaimana
partisipasi perempuan dipandang dalam sebuah partai politik.
10
Tinjauan pertama diambil dari sebuah Tesis yang berjudul Penerapan
Affirmative action sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam
Parlemen Indonesia, dari Irma latifah Sihite, Magister Ilmu Hukum UI 2011,
Tesis ini berisi tentang penerapan affirmative action di Indonesia yang dirasa
tidak berjalan beriringan dengan hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut,
faktanya kurang lebih setengah penduduk Indonesia adalah perempuan namun
pada kenyataannya perempuan tidak dapat mengirimkan wakil yang representatif
dalam hal kuantitas di parlemen, alih–alih mendapatkan wakil yang representatif
secara kuantitas menembus batas 30% dari affirmative action pun tidak bisa.
Penjelasan selanjutnya menyebutkan bahwa masih kurangnya kemauan
politik dari partai politik dan pemerintah. Pendidikan politik terhadap perempuan
tidak berjalan secara optimal sehingga kesadaran politik mereka cenderung
rendah. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harusnya bisa bersinergi
untuk lebih memperhatikan pendidikan politik bagi kaum perempuan.
Pembangunan kesadaran partai politik akan arti penting partisipasi perempuan,
sampai dengan jaminan hukum terhadapnya, hal ini berarti pengaplikasian
affirmative action harus sampai dari hulu ke hilir. Tesis ini adalah lingkup makro
(nasional) dari penelitian yang akan penulis teliti di DKI Jakarta (mikro) dengan
objek yakni partai PPP, lebih lanjut penelitian ini menggambarkan tentang
penerapan affirmative action, sedangkan penelitian penulis adalah tentang
11
menganalisis perolehan suara caleg perempuan sebagai ouput dari affirmative
action.
Tinjauan ke dua berasal dari Tesis Dina Anggita Lubis, Magister Studi
Pembangunan USU 2009, dengan judul Tesis yakni Partisipasi Politik
Perempuan Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan (Persoalan,
Hambatan, dan Strategi). Tesis ini dengan jelas menggambarkan keadaan dan
kondisi perempuan di DPP PKS Kota Medan yang secara Intelegensia dan potensi
sejajar dengan laki-laki namun secara kuantitas di ranah legislatif kota Medan
tertinggal dari laki-laki, hal ini menurut Dina disebabkan oleh faktor budaya, ini
yang paling dominan. Diikuti dengan faktor kurang dikenalnya caleg perempuan
PKS di Kota Medan. PKS harus mengejar ketertinggalannya dikarenakan setiap
orang mempunyai hak yang sama dan didukung oleh penerapan affirmative action
diharapkan perempuan PKS melihat celah yang ada tersebut untuk masuk ke
dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengingat potensi yang ada dalam
perempuan DPP PKS Kota Medan yang amat sayang bila tidak digunakan dan
terlibat dalam pembangunan. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang
penulis teliti, perbedaannya ada pada lokasi dan objek penelitian, lokasi yang
akan penulis ambil adalah Ibukota negara Indonesia dengan segala
kemajemukannya yang tentunya tantangan terhadap keterwakilan perempuan
akan berbeda pula dengan yang ada di Medan, dan yang akan penulis kaji sebagi
12
objek adalah partai PPP partai yang cukup dikatakan lebih ―senior‖ dibanding
dengan PKS.
Selanjutnya skripsi dari Mila Kamilatul Arsya, Ilmu Politik UIN Jakarta
2015 dengan judul; Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif. Skripsi ini
menampilkan gambaran mengenai representasi perempuan DPRD kota Depok
yang mencapai angka 38% pada pemilu tahun 2014 ini. Tentunya raihan yang
dicapai oleh Depok dalam keterwakilan perempuan sangat menggembirakan, hal
ini sekaligus membuat posisi perempuan cukup diperhitungkan dari segi kuantitas
di parlemen DPRD kota Depok, namun pertanyaan besarnya adalah apakah
dengan 38% representasi perempuan di parlemen kota depok tersebut diikuti
dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dari masing-masing anggota
legislatif perempuan tersebut? ternyata dalam temuannya di kota Depok
menunjukkan bahwa representasi yang besar dan kapasitas tidak berjalan
beriringan, mengingat besarnya sebanyak 38% namun suara yang dihasilkan
mereka tidak kuat atau bisa dibilang kapasitas dan kapabilitas wakil perempuan
tersebut kurang, bahkan dalam tiga fungsi pokok parlemen yakni legislasi,
anggaran dan pengawasan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini
adalah tentang fokus masalah penelitian, jika penelitian ini berfokus pada analisis
kapabilitas dan kapasitas caleg perempuan yang kuantitasnya mencapai 38% di
parlemen, maka penulis mengambil fokus pada tindakan apa yang dilakukan
institusi politik dalam hal ini partai politik untuk meningkatkan suara perempuan.
13
Tinjauan selanjutnya berkisar mengenai pola rekrutmen caleg dari skripsi
Wengky Saputra, Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas (2012) dengan judul asli
Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai
Demokrat dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten
Agam). Hasil temuan yang amat penting dari skripsi ini adalah bahwa betapapun
proses penjaringan caleg dilaksanakan dengan kebebasan yang sama kepada
semua warga negara tetapi rekrutmen yang dilakukan oleh DPC partai Demokrat
kabupaten Agam pada Pileg tahun 2009 bersifat tertutup karena masih terdapat
oligarki yakni dominannya ketua DPC dalam menetapkan caleg. Penelitian ini
menarik karena bersinggungan dengan apa yang penulis teliti tentang perolehan
suara, Oligarki dalam partai seringkali mempengaruhi kebijakan partai dalam
proses penentuan nomor urut caleg yang biasanya cukup menentukan dalam besar
kecilnya perolehan suara suatu calon.
Literatur selanjutnya yakni skripsi dari Tresia Febriani, Jinayah Fakultas
Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015) berjudul; Kuota 30%
Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Publik Perspektif Etika Politik Islam,
menggambarkan tentang pandangan etika Islam yang berlandaskan Al-Quran dan
As-Sunnah terhadap anggota legislatif perempuan. Hasil penelitian ini sebetulnya
cukup mengejutkan yakni kuota 30% untuk perempuan perlu dievaluasi, karena
kuota 30% hanya membuat partai politik fokus pada peningkatan kuantitas bukan
kualitas sehingga kuota yang tujuan awalnya menjadi peluang berubah menjadi
14
paksaan, bahkan peneliti berani memberikan solusi untuk tidak perlu adanya
kuota 30%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian
ini menggunakan perspektif Islam sebagai kacamata berpikir sehingga mungkin
agak menafikan peran perempuan dalam politik maupun ruang publik lainnya.
E. Metode Penelitian
Penelitian ini dibuat dengan analisis data kualitatif, analisis data kualitatif
dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kulitatif berupa
kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat di
susun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi, analisis kualitatif
menggunakan kata-kata yang biasanya di susun ke dalam teks yang diperluas, dan
tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu
tulis.12
Analisis kualitatif dapat menggali informasi secara dalam, oleh karena itu
wawancara yang dilakukan disebut deep interview atau wawancara mendalam.
1. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara dengan terstruktur dan mendalam dilakukan untuk
mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam partai dan juga
perlakuannya terhadap caleg perempuan, penulis nantinya akan
mewawancarai para narasumber, narasumber ini terdiri dari para
12
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aitama, 2009), hal.
339
15
pengurus partai politik dan juga beberapa pegiat LSM yang concern
terhadap perjuangan perempuan dalam politik.
b. Dokumentasi
Literatur tentang berbagai permasalahan persoalan perempuan dan
politik khususnya dalam pemilu dirasa penting untuk memperkaya
data dan interpretasi penulis dalam karya skripsi ini.
2. Sumber dan Jenis Data
a. Data primer, data primer adalah data utama yang dipakai dalam
penulisan ini, data primer bersumber dari hasil wawancara terstruktur
dan mendalam antara penulis dengan para narasumber nantinya.
b. Data sekunder, data sekunder adalah data pendukung dan penunjang
dari data primer, yakni seperti buku-buku dan juga literatur yang
mendukung baik hard copy maupun soft seperti jurnal dan situs-situs
yang concern dengan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini.
3. Analisis Data Penelitian
Penelitian ini nantinya akan memakai teknik deksriptif analisis,
artinya penelitian akan menggambarkan secara apa adanya yang terjadi di
lapangan. penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan
secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu,
atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau
16
frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain
dalam masyarakat.13
F. Sistematika Penulisan
Guna mensistematisasi penulisan agar terlihat terstruktur dan rapih,
penulis akan memaparkan apa-apa yang akan dibahas pada penelitian ini,
terangkum dalam lima bab peneliti akan memusatkan perhatian pada observasi
yang penulis lakukan langsung dengan cara wawancara mendalam dan terstruktur
terhadap para narasumber.
Bab I, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang
masalah, pertanyaan masalah yang akan menjadi fokus masalah ini, dan akan
dimuat juga tujuan dan manfaat dari penulisan ini, serta metodologi penelitian
yang akan dipakai juga sistematika penulisan dalam penelitian ini.
Bab II, penulis akan memaparkan secara umum tentang teori-teori yang
akan penulis pakai dalam penelitian ini, yakni teori kuota, teori patriarki dan juga
teori oligarki yang penulis ambil lewat sudut pandang oligarki dalam partai.
Bab III akan berisi penjelasan tentang fokus masalah yang penulis angkat
yakni perolehan suara perempuan pada PPP, yang akan penulis gambarkan mulai
dari sejarah pendirian partai, profil partai yang berisi platform partai dan juga
13
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hal. 28
17
penulis akan menggambarkan PPP kaitannya dengan pandangan terhadap
representasi perempuan, serta capaiannya dalam pemilu.
Bab IV, berisi analisis penulis dari wawancara terstrukttur yang telah
penulis lakukan dengan para narasumber, juga analisis penulis dari data-data
sekunder yakni semisal data-data dari hasil pemilu maupun data-data dari LSM
yang concern terhadap masalah yang penulis teliti.
Bab V, bab ini adalah bagian terakhir dari serangkaian bab yang ada
dalam penelitian ini, berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan juga saran dari
penulis sendiri yang diharapkan solutif dalam menjawab permasalahan dalam
penelitian ini.
18
BAB II
KERANGKA TEORI
A. Teori Gender dan Budaya Patriarki
Pembahasan tentang gender biasanya dimaknai sebagai pemisahan
manusia ke dalam dua jenis yakni perempuan dan laki-laki. Padahal jika ditinjau
lebih lanjut makna yang seperti diatas tak ubahnya dengan istilah sex lantas apa
yang berbeda dari kedua istilah tersebut sex dan gender. Gender adalah
pemaknaan atas perempuan dan laki-laki yang didasari pada konstruksi sosial,
biasanya sering berkaitan dengan peran, sifat, tanggung jawab, nilai, perilaku,
mentalitas dan karakteristik emosional atas kedua jenis kelamin tersebut.14
Pembedaan atas gender ini seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam
banyak aspek, semisal ketika perempuan bekerja mereka biasanya mendapat upah
lebih sedikit dibanding dengan laki-laki, juga ditempatkan di sektor yang
dianggap bisa dikerjakan oleh perempuan yang banyak dianggap sebagai makhluk
yang secara fisik dianggap lemah. Kemudian ada beban ganda (double burden)15
yang diterima perempuan ketika ia memutuskan untuk bekerja ia juga tidak boleh
melupakan yang menurut sebagian besar budaya masyarakat adalah tugas utama
dan pokok dari perempuan utamanya yang sudah berkeluarga yakni mengurus
14
Ida Rosyidah dan Hermawati, Relasi Gender dalam Agama-Agama (Jakarta:
UIN Jakarta Press, 2003), hal. 13 15
Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1997), hal. 150
19
urusan domestik seperti urusan keluarga dan rumah, serta masih banyak
ketidakadilan lainnya yang diterima oleh perempuan.
Berbicara tentang gender tentu saja tak terlepas dari membincangkan
ketidakadilan pada perempuan yang terdapat di dalam masyarakat baik
masyarakat tradisonal, maupun modern sekalipun melingkupi banyak ruang privat
dan publik, ruang privat biasa dikenal dengan institusi keluarga, sedangkan ruang
publik ada berbagai macam sektornya tidak terkecuali dalam hal politik.
ketidakadilan dalam keluarga terletak pada diposisikannya perempuan (ibu/isteri)
dibawah dari laki-laki (ayah/suami).
Keadaan asimetris yang didapat perempuan ini tidak hanya dirasakan di
ruang privat dalam artian keluarga saja, tetapi juga banyak terdapat pada ruang
publik semisal ranah politik, perempuan sering terpinggirkan secara halus dengan
justifikasi stereotipe dan konstruksi sosial di masyarakat yang menyatakan bahwa
perempuan akan lebih baik dan berguna bila hanya mengurusi keluarga (privat)
dan sebisa mungkin tidak mempunyai banyak peranan di luar (publik) karena
dengan seperti itu membuat konsentrasinya terpecah antara memprioritaskan salah
satu ruang privat atau publik. Karena itu perempuan sering mendapat peran lebih
rendah (subordinat), yang terbatas sebagai ibu rumah tangga dan terasing dalam
urusan publik.16
16
Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa
Depannya (Yogyakarta: Qalam, 2004), hal. 381
20
Ada beberapa ilmuwan sosial yang mengamini keterasingan perempuan di
ruang publik sebagai sesuatu yang wajar dan dianggap normal, John Locke
misalnya dengan tanpa alasan menegasikan akan hak-hak politik dan hak sipil ke
dalam hak perempuan. Lebih halus dari itu JJ. Rousseau memberikan alasan yang
agak pesimistis ke dalam diri perempuan, bahwa perempuan dengan sifat seksnya
yang sedemikian rupa lebih cocok untuk menjadi penyenang kaum laki-laki dan
mengurus keluarga ketimbang harus berjibaku di ranah publik dengan laki-laki.17
Argumen-argumen yang sedemikian naif tentang justifikasi perempuan
agar selalu berada di ranah privat baru dipertentangkan sehabis digulirkannya
Revolusi Perancis, revolusi ini membuka pandangan-pandangan umum
masyarakat Eropa tempo itu dan mengarahkannya kepada pandangan yang lebih
terbuka akan persamaan hak dan keadilan, yang berarti keterasingan perempuan
dan ketidakadilan yang diderita kaum tersebut perlahan harus digusur dan diganti
dengan hak-hak yang dibutuhkannya termasuk hak politik dan sipil.
Ideologi liberal adalah ideologi yang pertama-tama mendukung gerakan
kesetaraan dan keadilan yang dituntut oleh kaum perempuan, untuk selanjutnya
gerakan ini disebut gerakan feminis. Para pendukung feminis dengan sudut
pandang liberal berasumsi bahwa agar tercipta individu yang otonomi dan
17
Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir, hal. 381
21
independen haruslah didahului dengan terciptanya masyarakat yang adil,18
maka
dari itu kesetaraan dan keadilan pada perempuan atas hak-haknya diperlukan
untuk menunjang itu semua. Tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk
menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang.
Hanya di dalam masyarakat seperti itu, perempuan dan juga laki-laki dapat
mengembangkan diri.19
Kendatipun demikian gerakan feminis pada prakteknya
tetap merujuk pada teori yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan yang mendukung
gerakan tersebut, semata-mata sebagai panduan untuk arah gerakan selanjutnya.
Menurut Mansour Fakih, pemikiran-pemikiran tentang feminisme terbagi
kedalam beberapa aliran yang berbeda satu dengan yang lainnya yakni feminisme
liberalis, feminisme radikal, feminisme marxis, serta feminisme sosialis. Keempat
aliran tersebut menurut Fakih bisa ditelaah dari dua paradigma besar dunia
keilmuan sosial yaitu paradigma fungsionalis atau status quo dan paradigma
sosiologi-konflik, kedua paradigma ini berkontribusi untuk menjelaskan
bagaimana feminisme menjadi aliran yang tak hanya sekadar praktik namun
berlandaskan pula pada ranah teori.20
Paradigma fungsionalisme atau status quo dapat menjelaskan aliran
feminisme liberal yang berfondasi pada keyakinan bahwa perempuan haruslah
18
Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif
kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hal. 16 19
Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought, hal. 18 20
Mansour Fakih, Analisis gender dan Transformasi Sosial, hal. 79
22
mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dengan yang dimiliki oleh laki-laki,
metode inilah yang kiranya diadopsi untuk penerapan affirmative action di
Indonesia juga dipakai dalam landasan gerakan feminisme di Indonesia.
Paradigma fungsionalisme, paradigma ini juga dikenal sebagai paradigma
status quo yang berpandangan bahwa konflik mesti dihindari di setiap masyarakat
dan harus menjaga pola yang normatif karena pola yang non-normatif dianggap
akan melahirkan gejolak yang nantinya memunculkan konflik dalam masyarakat,
tokoh yang mempelopori ini adalah Talcott Parsons dan Robert Merton yang
harus dijaga menurut paradigma ini adalah equilibrium atau keseimbangan yang
menyangkut pula pada beberapa sistem yakni pendidikan, agama, keluarga hingga
struktur politik dan sebagainya, tak terkecuali kesetaraaan antara perempuan dan
laki-laki. Teori ini kemudian juga dapat menjelaskan tentang aliran feminisme
liberalis.21
Feminisme liberal adalah aliran yang mainstream di dunia, khususnya
dunia ketiga yang beranggapan bahwa perempuan semestinya diberi kesempatan
dan hak yang sama. Jika sudah diberi hak yang sama namun perempuan masih
dianggap pasif maka hal demikian adalah kesalahan dari perempuan sendiri,
aliran ini merasa perempuan harus diberi pemahaman dan pengetahuan mendalam
akan hak dan kesempatannya supaya perempuan dapat mencapai kesetaraan
dengan laki laki, namun banyak yang mengkritik aliran ini karena dianggap
21
Mansour Fakih, Analisis gender dan Transformasi Sosial, hal. 80
23
menafikan budaya patriarki yang membelenggu perempuan menjadi pasif
meskipun sudah diberi kesempatan dan haknya.
Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan
dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum
perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan
menuntut hak-haknya.22
Beberapa persoalan yang dituntut kesetaraannya pada
masa-masa awal gerakan feminisme adalah mengenai pendidikan, upah buruh
perempuan. Kemudian berlanjut pada abad ke 19 dengan hak-hak politik seperti
memilih pada pemilu dan lainnya.
Membincang feminisme liberal kurang lengkap jika tidak membawa nama
Mary Wollstonecraft (1759-1799) seorang penulis yang meletakkan dasar
feminisme liberal dalam karyanya A Vindication of the Rights of Woman.
Wollstonecraft yang hidup sekitar abad 18 mengatakan bahwa sudah selayaknya
perempuan dan laki-laki ditempatkan sama. Zaman Wollstonecraft hidup memang
zaman dimana perempuan dipandang sebelah mata sebagai makhluk yang lemah
secara fisik dan nalar.23
Mary Wollstonecraft menyangkal adanya pandangan bahwa kondisi
alamiah perempuan menyebabkan perempuan kurang memiliki intelektualitas dan
kemampuan fisik seperti laki-laki. Agar perempuan dapat berkembang seperti
22
Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal
Kritik Sastra Feminisme, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hal 51. 23
Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought, hal. 18
24
laki-laki, maka perempuan harus berpendidikan sama seperti laki-laki.24
Kesetaraan dan kesamaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki menjadi
dasar pemikiran Wollstonecraft yang cenderung anti-mainstream pada zamannya.
Lebih lanjut Wollstonecraft mengemukakan bahwa wanita, khususnya dari
kalangan menengah, merupakan kelas tertindas yang harus bangkit dari belenggu
rumah tangga. Oleh kalangan feminis masa kini, Wollstonecraft dipandang
sebagai tokoh revolusioner yang menentang kekuasaan patriarkal.25
Wanita kelas
menengah bagi Wollstonecraft merupakan kelas yang paling tertindas karena pada
zamannya wanita-wanita borjuis hidup seperti dalam sangkar laki-laki meskipun
mempunyai kekayaan yang cukup langkahnya pada ruang publik dan
bersinggungan dengan masyarakat luas terbatas sehingga terkesan hanya sebagai
seremonial-seremonial belaka. Berbeda dengan wanita-wanita dari kalangan
bawah yang banyak bekerja umumnya sebagai buruh, meski terkena double
burden karena harus bekerja demi ketercukupan kebutuhan rumah tangga, tetapi
karena berada di lingkungan kerja (publik) praktis wanita-wanita tersebut dapat
berorganisasi, semisal mengikuti organisasi serikat buruh. Sehingga
kehidupannya tidak melulu berada dalam ruang privat.
24
M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2005), hal. 20 25
Soenarjati Djajanegara, Kritik Sastra Feminisme: Sebuah Pengantar, (Jakarta:
Gramdeia Pustaka Utama, 2000), hal. 30
25
Dengan didapatkannya akses pendidikan bagi perempuan maka
perempuan seyogyanya bisa mandiri dari laki-laki, hal ini menurut Wollstonecraft
dapat menjauhkan diri dari orang yang memandang perempuan hanya sebatas
objek bukan manusia yang mempunyai nilai lebih. Satu abad setelah gagasan
feminisme liberal Wollstonecraft hadir, muncul pula gagasan dari John Stuart
Mill dan Harriet Taylor (Mill) yang menulis dan melanjutkan apa yang dicitakan
oleh Wollstonecraft.26
John Stuart Mill dan Taylor meyakini bahwa jika masyarakat ingin
mencapai kesetaraan seksual, atau keadilan gender, maka masyarakat harus
memberi perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama
yang dinikmati oleh laki-laki seperti kata Wollstonecraft. Lebih jauh Taylor
dalam Enfranchisement of Woman (1851) mengatakan bahwa tugas laki-laki dan
perempuan untuk ―mendukung‖ kehidupan.27
John Stuart Mill menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh
feminisme liberal dengan agak sedikit menyinggung tentang patriarki seperti yang
diungkapkan Rosemarie Putnam Tong dalam bukunya Feminist Thought: A More
Comprehensive Introduction (1998) yang telah diterjemahkan oleh penerbit
Jalasutra (2004) bahwa;
Mill berpikir lebih jauh daripada Wollstonecraft dalam menentang asumsi
tak berdasar atas superioritas intelektual laki-laki. Dengan menekankan
26Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought, hal.22
27Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought, hal.24
26
bahwa kemampuan intelektual laki-laki dan perempuan adalah sama
jenisnya, Wollstonecraft, bagaimanapun, menerima pemikiran bahwa
perempuan mungkin tidak akan mampu mencapai tingkat pengetahuan
yang sama dengan laki-laki. Mill menyampaikan pendapatnya ini dengan
tidak ada pengecualian sama sekali. Ia bersikeras bahwa perbedaan
pencapaian intelektual antara perempuan dan laki-laki adalah semata-mata
hasil dari pendidikan yang lebih lengkap yang diterima oleh laki-laki, dan
posisi laki-laki yang lebih diuntungkan (Patriarki).28
Selanjutnya adalah penjelasan tentang Budaya Patriarki sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari diskursus tentang gender dan kesetaraan perempuan.
Patriarki sebenarnya adalah sebuah konsepsi yang amat tua, yang ada karena
stigma atau prasangka lebih tepatnya konstruksi sosial di masyrakat tentang
bagaimana laki-laki dan perempuan dilihat secara abstrak dan sangat kasar. Istilah
patriarki adalah istilah yang merujuk pada nilai-nilai atau sebuah sistem atas dasar
ke-bapak-an atau boleh dibilang nilai-nilai yang menitikberatkan pada laki-laki
sebagai unsur yang utama dalam suatu keluarga. Patriarki biasanya terjadi karena
terdapat pandangan atau pemahaman tentang gender yang salah sehingga
membuat laki-laki dipandang dan dianggap jauh lebih hebat dibanding
perempuan, juga gender membuat sifat-sifat yang ada dalam laki-laki dan
perempuan menjadi terkotak-kotakan. Anggapan tersebut menjadikan perempuan
ter-subordinasi atas laki-laki dan melahirkan patriarki, sederhananya
ketidakadilan dalam gender nantinya akan berujung pada tumbuhnya patriarki
secara luas di masyarakat.
28
Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought, hal.28
27
Sejarah hadirnya patriarki di masyarakat menurut Engels tidak terlepas
dari pemahaman manusia itu sendiri dengan kepemilikan pribadi, dan
pengetahuan masyarakat akan sistem kelas. Bahkan menurut Erich Fromm
patriarki sudah ada di masyarakat sejak 6000 tahun silam,29
kedua pernyataan dari
ilmuwan sosial tersebut sangat berdasar pasalnya kehidupan laki-laki dan
perempuan mulai terkotak-kotakan sejak zaman prasejarah dimana manusia
dahulu kala mulai berpindah dari food gathering menjadi food producing dan
budaya hidup nomaden juga mulai ditinggalkan dan beralih ke hidup menetap
dan bertahan hidup dengan cara food producing serta sesekali berburu. Sejak
itulah perempuan mulai terjebak dalam ranah privat dan laki-laki dapat leluasa
diranah privat maupun publik
Sylvia Walby mengkonsepsikan patriarki dalam enam bentuk yang
menjadikan patriarki seperti sebuah pandangan yang terstruktur. Pertama patriarki
dalam pembagian kerja, kedua patriarki dalam pembagian upah, patriarki dalam
hubungannya dengan keadaan seperti kejahatan perempuan, patriarki dalam
hubungannya dengan nafsu syahwat/kebirahian, patriarki dalam hubungannya
dengan suatu budaya yang meliputi, agama, media dan pendidikan.30
29
M. Adji, Lina Meilinawati dan Baban Banita, Perempuan dalam Kuasa
Patriarki Laporan Penelitian /Buku Fakultas Sastra Universitas Padjajaran tahun 2009,
hal. 9 30
Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1990), hal.
177
28
Lebih lanjut Walby membedakan patriarki dalam dua bentuk yakni
patriarki privat dan patriarki publik, patriarki privat biasanya terdapat pada rumah
tangga, dimana kepala keluarga (laki-laki) memiliki andil yang lebih besar
daripada perempuan dalam urusan kebijakan atau keputusan yang menyangkut
dengan rumah tangga, sistem patriarki privat mengeksploitasi perempuan dengan
tidak mengizinkan istri memasuki ruang publik, semisal bekerja. Sementara itu
patriarki publik adalah bentuk patriarki yang didapat oleh perempuan dalam
domain yang lebih besar daripada rumah tangga, patriarki publik mengizinkan
perempuan memasuki ruang publik, dalam hal ini bekerja. Tetapi tetap terdapat
pemisahan dan eksploitasi pada perempuan, semisal upah yang tidak sama dengan
laki-laki, atau penghargaan yang tidak sama dengan laki-laki.31
Jika ditarik kembali dalam diskursus tentang politik, patriarki menjelma
dalam bentuk-bentuknya yang lain seperti pembatasan dan stigma-stigma negatif,
tercermin dalam pencalonan legislatif misalnya, perempuan sering mendapat
tanggapan dalam masyarakat bahwa mereka tidak pantas berada di wilayah politik
dan sebagainya yang cenderung mendiskreditkan perempuan. Akibatnya
keengganan perempuan memasuki domain tersebut dan menjadikan laki-laki
leluasa dalam merumuskan kebijakan dan seringkali menafikan perempuan dalam
banyak kebijakan yang dihasilkan dalam politik.
31
Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, hal. 179
29
B. Teori Kuota Perempuan Dalam Politik
Perjuangan perempuan lewat gerakan feminisme telah membuahkan hasil,
perlahan tapi pasti beberapa negara di dunia menerapkan priviledge sendiri bagi
ketersediaan kursi untuk perempuan ataupun dalam kontestasi pemilu legislatif,
nampaknya beberapa negara sadar betul bahwa demokrasi yang baik adalah
demokrasi yang merepresentasikan semua pihak tak terkecuali perempuan, maka
keterasingan perempuan dari dunia politik harus digusur dengan cara-cara yang
menyertakan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan itu sendiri.
Kaum feminis berpandangan bahwa perempuan terus menerus terasing
dan kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan adalah cermin dari
kurangnya keadilan yang diterima oleh mereka, di sisi lain laki-laki memegang
peranan yang cukup penting dan signifikan dalam hal tersebut. Kaum feminis juga
menganggap pengmarginalisasian perempuan dalam bidang politik hanya akan
membuat hakikat dari demokrasi semakin sempit, karena sejatinya demokrasi
menghimpun seluruh aspirasi dan representasi suara masyarakat bukan kaum
tertentu apalagi jenis kelamin tertentu.32
Kuota gender adalah jawaban atas tuntutan-tuntutan gerakan feminis yang
telah diperjuangkan sejak lama, dalam sejarahnya India adalah negara yang
pertama kali mengadopsi kuota gender untuk perempuan dalam politik pada tahun
32
Homa Hoodfaar dan Mona Tajali, Electoral Politics : Making Quota Work For
Women (London: WLUML, 2011) hal. 42
30
1930an, saat itu India yang masih dalam jajahan kolonial Inggris mengadopsi
kuota dalam kepegawaian pemerintahan rendahnya, semacam wilayah
adiministratif Kelurahan jika ingin disamakan dengan Indonesia. Barulah pada
tahun 1935 India memberikan kursi kepada perempuan untuk ranah legislatif
pusat yang terdiri dari berbagai macam kalangan dan kasta.33
Guna meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen, kuota
gender adalah sebuah cara yang bisa dibilang amat baik dan cukup fleksibel.
Terlepas apapun pendekatannya dari mulai secara sukarela sampai yang terkesan
dipaksakan, biasanya negara-negara yang menerapkan kuota gender dengan
pendekatan yang terkesan dipaksakan adalah negara-negara dengan tingkat
demokrasi yang belum mapan atau belum stabil.
Negara-negara berkembang seperti Pakistan, Ghana, Bangladesh, Uganda,
adalah negara-negara awal yang menerapkan kuota perempuan di parlemen
dengan model reserved quotas,34
hal ini mungkin terkesan agak dipaksakan untuk
perempuan berpartisipasi dalam politik, namun cara ini dianggap paling ampuh
guna meningkatkan representasi perempuan secara signifikan dalam politik
khususnya parlemen pada negara-negara dunia ketiga. Pada dasarnya penerapan
kuota gender terbagi kedalam tiga jenis yang akan dijabarkan lebih lanjut yakni;
1. Political party quotas, 2. Legislative quotas, 3. Reserved seats.
33
Homa Hoodfaar dan Mona Tajali, Electoral Politics, hal. 43 34
Homa Hoodfaar dan Mona Tajali, Electoral Politics, hal. 43
31
1. Political Party Quotas
Sistem ini adalah sistem yang paling umum dalam penggunaan kuota
gender untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen. Sistem ini
secara sukarela dianut oleh partai dan bukan lewat mandat hukum atau
konstitusi,35
hal demikian menjadikan representasi perempuan dalam parlemen
nantinya lebih kuat secara kapasitas dan kapabilitas dibanding dua jenis
penerapan kuota gender lainnya. Pasalnya partai berhak menentukan dan
menyeleksi tiap kader perempuannya untuk berkontestasi dalam pemilu. Lebih
lanjut sistem ini umumnya diterapkan pada negara-negara yang demokrasinya
telah mapan seperti negara-negara Skandinavia di Eropa Barat.
Partai-partai yang menganut sistem ini secara sukarela umumnya partai
beraliran kiri, semisal Partai Buruh di Skotlandia dan sebagainya.36
Hal ini
ditunjukkan mungkin untuk menarik simpati masyarakat bahwa partai-partai yang
beraliran kiri peduli terhadap kesetaraan dan keadilan, bahkan untuk perempuan.
Sistem political party quotas juga paling cocok diterapkan dalam negara yang
memilih menggunakan jenis single-member district sebagai sistem
pemilihannya.37
35
Homa Hoodfaar dan Mona Tajali, Electoral Politics, hal. 46 36
Joni Lovenduski, Politik Berparas Perempuan (Yogyakarta: Kanisius, 2008),
hal. 225 37
Homa Hoodfaar dan Mona Tajali, Electoral Politics, hal. 47
32
2. Legislative Quotas
Jenis penerepan kuota perempuan ini tergolong jenis baru, kuota
perempuan melalui mandat dari hukum atau konstitusi negara yang memakainya
mensyaratkan minimum 30% dari total calon legislatif yang diajukan oleh partai
adalah perempuan, hal ini berlaku dalam seluruh partai tanpa terkecuali di negara
yang menerapkan sistem ini, negara-negara yang menerapkan sistem ini
cenderung negara berkembang seperti negara-negara di Amerika Latin, Timur
Tengah dan beberapa negara di Asia seperti Indonesia.38
Titik tekan dari penerapan kuota gender jenis ini adalah kekutan hukum
yang mengikatnya, jika sanksi terhadap partai yang tak menyertakan perempuan
pada calon legislatif seminimalnya 30% adalah lemah bahkan cenderung tidak ada
sanksi jangan harap bahwa representasi perempuan dalam parlemen di negara
tersebut akan naik dengan segera,39
masalah komposisi dan posisi calon legislatif
perempuan dalam penerapan kuota perempuan jenis ini memang pelik, pasalnya
kebanyakan negara yang menerapkan jenis ini memilih sistem pemilihan terbuka
dengan nomor urut sehingga biasanya partai menempatkan perempuan di posisi
―tak jadi‖ atau ―kritis‖.40
38
Homa Hoodfaar dan Mona Tajali, Electoral Politics, hal. 48 39
Zaitunah Subhan, Perempuan Dan Politik Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2004), hal. 82 40
Zaitunah Subhan, Perempuan Dan Politik Dalam Islam, hal. 82
33
3. Reserved Quotas
Penerapan kuota perempuan jenis ini merupakan jenis yang amat
kontroversial kalau boleh dikatakan, pasalnya perempuan mendapat hak yang
lebih istimewa dalam kursi parlemen dibanding dengan dua jenis diatas, dalam
reserved quotas calon perempuan telah dipisahkan kursinya terlebih dahulu di
parlemen atau dalam istilah bahasa Indonesia telah diberi jatah terlebih dahulu,
dalam jenis ini perempuan telah mendapat jaminan kursi otomatis seperti di
Pakistan, dimana partai tiap mendapat jatah kursi untuk perempuan tentunya hal
ini berbeda dengan sistem political party quotas dan legislative quotas.41
Penjaminan kursi bagi perempuan dalam parlemen bukan tanpa alasan,
dikarenakan negara yang menerapkan kuota perempuan jenis ini adalah negara
yang rawan konflik dan keadaaan demokrasinya masih jauh dari kata stabil, agar
perempuan turut serta dan dapat menjadi representasi masayarakat dalam
parlemen perlu penerepan kuota jenis ini, walau agak terkesan dipaksakan karena
kuota jenis ini juga setidaknya diatur oleh konstitusi sebagaimana legislative
quotas namun kuota ini lebih menjamin kehadiran perempuan dalam parlemen,
negara-negara yang menganut penerepan kuota perempuan jenis ini adalah
Bangladesh, Pakistan, Rwanda, Afghanistan, dan Jordania.42
41
Mona Lena Krook, Quotas for women in politics : gender and candidate
selection reform worldwide (New York : Oxford University Press, 2009), hal. 57 42
Homa Hoodfaar dan Mona Tajali, Electoral Politics, hal. 49
34
Dari ketiga jenis penerapan kuota perempuan yang telah dijabarkan
berikut dapat disimpulkan bahwa penerapan kuota perempuan di tiap negara-
negara berbeda-beda tergantung dari tingkat demokrasinya, kalau boleh dikatakan
seperti itu. Negara dengan tingkat ke-stabilan nasional rendah sperti Rwanda dan
Pakistan membutuhkan penerapan kuota perempuan yang lebih ampuh serta lebih
ke arah dipakasakan agar representasi perempuan lebih terjamin keberadaannya.
Lain dengan yang terjadi di negara-negara Skandinavia, mereka lebih
memilih penerapan kuota perempuan yang lebih soft, lebih ke arah sukarela
dibanding kedua jenis yang lain, hal ini dimungkinkan karena negara-negara
tersebut telah stabil secara keamanan dan ekonomi. Adapun demokrasi yang
mereka jalankan terlihat lebih ajeg dibanding negara-negara yang lain sehingga
keterwakilan perempuan adalah isu yang dapat mereka angkat guna menaikkan
suara partai-partai mereka.
Jenis yang lain yakni legislative quotas membutuhkan kesungguhan dan
ketegasan dari penerapan konstitusi, namun jenis ini juga memungkinkan untuk
terjadi deviasi dalam perekrutan 30% calon legislatif perempuan, semisal oligarki
partai yang justru menjadikan calon-calon perempuan ini kekurangan kapasitas
dan kapabilitas apabila penjaringannya hanya melalui kedekatan dengan para elit
partai.
35
C. Teori Oligarki dalam Partai Politik.
Sejatinya ada dua sudut pandang dalam melihat oligarki secara abstrak,
dua ilmuwan berbeda zaman yakni Robert Michels dalam bukunya Political
Parties: A Sociological Study of The Oligarchical Tendencies of Modern
Democracy, memberikan gambaran bahwa oligarki yang ada dalam suatu
organisasi yakni kepartaian yang diangkat oleh Michels sebagai suatu kasus,
didapat karena kekuasaan yang tak tergantikan selama kurun waktu yang panjang
dan membuat kekuasaan yang didapat oleh penguasa tersebut seolah takdir yang
ada dalam dirinya, hal ini tentunya tak lepas dari kemalasan suatu massa untuk
kritis terhadap kekuasaan itu sendiri, dan membiarkan apa yang disebut Michels
sebagai ―terimakasih massa‖ secara lama kepada penguasa, hingga terjadilah
oligarki di suatu organisasi baik dalam kepartaian ataupun dalam negara.
Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarchy menjelaskan oligarki tidak
seperti yang Michels jelaskan diatas, Winters melihat oligarki berpangkal kepada
kekayaan yang super melimpah yang didapat oleh sekelompok kecil minoritas
masyarakat dibanding dengan mayoritas masyarakat yang ada di sekitarnya.
Implikasi dari kekayaan yang melimpah ini adalah pengaruhnya si oligark (orang
yang melakukan oligarki) terhadap kekuasaan di suatu organisasi baik di partai
atupun di negara, jelas sudut pandang ini yang kelihatannya ter-alpa-kan dari
penjelasan Michels, bahkan Winters menyalahkan Michels yang menyebut
36
teorinya sebagai ―Hukum Besi Oligarki‖ adalah salah alamat, seharusnya teori elit
dan bukan oligarki.43
Tentunya dua ilmuwan sosial yang berbeda pandang tersebut merupakan
hal yang lumrah, terlebih keduanya menggunakan sudut pandang berbeda dalam
menyelami satu diskursus yakni oligarki, kemudian perbedaan bisa dilihat dari
dua zaman yang berbeda yang diambil oleh Michels dan Winters, Michels pada
akhir abad 19 dengan melihat partai sosialis di Jerman sebagai suatu kasus yang ia
angkat guna menjelaskan oligarki, sedangkan Winters melakukan penelitian pada
abad 20an yang dimana memang manusia-manusia kaya dan para multimiliuner
memegang peranan yang cukup signifikan untuk kekuasaan meskipun kadang
mereka tak berkuasa dalam pemerintahan.44
Penulis nantinya akan mengambil sudut pandang yang diambil oleh
Michels dalam melihat oligarki di partai politik, karena betapapun kekayaan
material berpengaruh terhadap kekuasaan tetap saja penguasa pada akhirnya yang
mengetok palu akan suatu kebijakan atau keputusan yang dilakukan suatu
organisasi baik partai politik maupun negara sekalipun. Lebih lanjut dari itu tiap
elit di partai politik pastinya memiliki kekayaan material yang banyak walaupun
mungkin tak semelimpah oligark yang digambarkan oleh Winters, jika keduanya
43
Jeffrey A. Winters, Oligarki (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal.
410 44
Jeffrey A. Winters, Oligarki, hal. 411
37
dikombinasikan antara kekuasaan dan kekayaan material maka tak ayal tahta sang
elit akan langgeng untuk waktu yang cukup lama.
Pertama-tama Michels dalam bukunya menyoroti masa jabatan yang lama
sebagai pangkal dari oligarki di tubuh organisasi partai politik, atas dasar itu
Michels menyatakan bahwa seharusnya massa memberikan batas waktu untuk
sebuah kekuasaan agar hakikat demokrasi berjalan semestinya, semakin lama
suatu jabatan diduduki, semakin besar pengaruh pemimpin atas massa dan karena
itu semakin besar pula kebebasannya, konsekuensinya adalah pemilihan secara
sering diperlukan untuk menghambat virus oligarki dalam satu organisasi.45
Michels menyalahkan kemalasan massa yang tidak membuat tandingan
dan sirkulasi kepemimpinan atas pemimpinnya atau bergerak menjadi oposisi atas
elit dari satu organisasi, inilah yang membuat menurutnya jabatan yang ada pada
elit tersebut seperti ditakdirkan oleh Tuhan.46
Lebih lanjut Michels menjelaskan
jika di setiap organisasi oligarki mencapai tingkat perkembangan lebih lanjut,
para pemimpin mulai mengidentifikasi dengan diri mereka lembaga-lembaga
kepartaian dan juga milik partai.47
Hal ini yang menurut Hanta Yuda persis dengan sebagaimana yang terjadi
di Indonesia. Figur pemimpin partai identik dengan partai itu sendiri, seperti
45
Robert Michels, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi
(Jakarta: CV Rajawali, 1984), hal. 108 46
Robert Michels, Partai Politik, hal. 109 47
Robert Michels, Partai Politik, hal. 256
38
kuatnya personalisasi figur Megawati di PDIP dan Susilo Bambang Yudhoyono di
Partai Demokrat. Dengan konstelasi seperti ini, mudah untuk mentransformasikan
kehendak personal menjadi kehendak institusi. Bahkan pandangan dan harapan
pribadi figur sentral akan dimaknai sebagai ideologi bagi aktivis dan simpatisan
partai politik.48
Dengan semakin kuatnya kepemimpinan seseorang atau elit dalam tubuh
organisasi partai maka sejalan dengan itu kemungkinan untuk membentuk suatu
pola hubungan yang kolutif dan koruptif dalam tubuh partai politik terbuka
lebar.49
Kedekatan seseorang dengan pemimpin atau elit politik dalam suatu partai
menjadikan jenjang karir kader menjadi lebih cepat dan dihormati oleh yang lain.
Terakhir Michels memberi argumen bahwa organisasilah yang melahirkan
kekuasaan tokoh-tokoh yang terpilih atas para pemilih, para penerima mandat atas
para pemberi mandat, dan para wakil atas massa yang mengutus mereka.
Barangsiapa berbicara mengenai organisasi maka ia berbicara oligarki, lebih dari
itu Michels menambahkan bahwa organisasi lah yang menampilkan corak oligarki
walaupun dalam ranah kekuasaan yang demokrasi.50
48
Hanta yuda, Presdensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 123 49
Adhyaksa Dault, Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik,
Renungan Seorang Anak Bangsa. (Jakarta: Renebook, 2012), hal. 201 50
Robert Michels, Partai Politik, hal. 445
39
BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG PPP DAN KIPRAHNYA DI DKI
JAKARTA
A. Profil PPP
Pada tahun 1973 pemerintah melakukan penyederhanaan jumlah
organisasi politik menjadi tiga, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan
Partai Demokrasi Indonesia. Alasan yang dikemukakan pemerintah antara lain
adalah untuk memperkecil sumber potensi konflik di tengah masyarakat, dan juga
timbulnya ketidakstabilan di dalam masyarakat terutama di bidang politik. Tetapi
sudah umum juga diketahui bahwa itu merupakan bagian strategi pemerintah
untuk melemahkan peranan ideologi – termasuk yang berbau agama – di dalam
partai-partai politik.51
PPP atau Partai Persatuan Pembangunan adalah partai gabungan hasil dari
peraturan fusi partai pada awal Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto
terdapat satu partai lagi yang merupakan partai gabungan (fusi) yakni Partai
Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai PPP pada awalnya dibentuk untuk
memfasilitasi masyarakat yang ideologinya berlandaskan pada agama, tentunya
PPP pada skema awal bukan ditujukan untuk partai Islam saja tetapi juga kepada
partai Kristen diantaranya Partai Katolik Indonesia dan Partai Kristen Indonesia
51
Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia, (Jakarta:
BPK Gunung Mulia, 2004), hal. 377
40
(Parkindo). Pada perkembangan selanjutnya PPP diisi oleh penggabungan empat
partai, keseluruhannya partai Islam yakni; Partai Nadhlatul Ulama, Partai
Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan
Partai Islam Perti (persatuan tarbiyah Indonesia). Sedangkan Partai Katolik
Indonesia dan Parkindo lebih memilih PDI (Partai Demokrasi Indonesia) sebagai
saluran politiknya.52
Pendirian PPP diprakarsai oleh lima deklarator, empat dari masing-masing
partai yang berfusi menjadi PPP dan satu orang ketua fraksi Persatuan
Pembangunan di parlemen saat itu. Lima deklarator tersebut yakni; KH. Idham
Chalid (NU), H.M Syafaat Mintaredja (PARMUSI), H. Anwar Tjokroaminoto
(PSII), H Rusli Halil (PERTI), dan terakhir H. Mayskur, Ketua Kelompok
Persatuan Pembangunan DPR.53
Isi deklarasi menegaskan bahwa keempat partai
tersebut akan menyatu dalam pemilu dan di parlemen tetapi pada wilayah
organisasi tetap berjalan sendiri-sendiri.
Pada tanggal 3 Februari 1973 Idham Chalid terpilih menjadi Presiden
Partai dan Mintaredja sebagai Ketua Dewan Pusat. KH. Bisjri Sansuri terpilih
sebagai Rais Am (Ketua Umum) Majelis Syura (Dewan Konsultatif). Selama
periode awal fusi (1973-1978) kelompok-kelompok Islam dalam PPP masih
52
Saiful Mujani, Kuskridho Ambardi dan R William Liddle. Kuasa Rakyat:
Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Pasca-Orde
Baru, (Mizan Publika: Jakarta, 2012), hal. 119 53
http://ppp.or.id/page/ppp-dalam-lintasan-sejarah/index/ diunduh pada 18
Oktober 2016
41
bersatu dengan kuat, terutama dalam menanggapi isu yang menyangkut
kepentingan umat Islam di Indonesia.54
Tetapi kemudian menurut Jan S. Aritonang dalam bukunya Sejarah
Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia menyatakan bahwa perpecahan PPP
dimulai setelah KH. Bisjri Sansuri meninggal ada tahun 1980. Perpecahan kian
meningkat pada masa selanjutnya, membuat PPP tidak mampu berfungsi penuh
sebagai penyalur aspirasi politik Islam.55
Membicarakan perpecahan yang terjadi di dalam tubuh PPP tidak lengkap
jika tidak membicarakan satu langkah besar yang ditempuh NU dalam sejarahnya
khususnya dalam bidang politik yakni ―kembali ke khittah 1926‖, langkah
tersebut ditempuh dikarenakan NU merasa ada ketidakadilan dalam pembagian
kursi parlemen. Hal ini membuat kemerosotan suara PPP pada pemilu 1987 dan
ditenggarai terjadi karena NU mendeklarasikan diri kembali ke khittah 1926, yang
diputuskan pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984. Keputusan tersebut
mengandung arti bahwa warga NU memiliki kebebasan untuk masuk ke partai
politik mana pun.56
Efeknya langsung terasa bagi PPP suara partai Islam ini
langsung merosot cukup signifikan ke angka 15.97% atau hanya mendapat
13.701.428 suara sah nasional.
54
Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Islam & Kristen, hal. 378 55
Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Islam & Kristen, hal. 378 56
Fathurin Zen, NU Politik: Analisis Wacana Media, (Yogyakarta:LkiS, 2004),
hal. 36
42
Penyebabnya merosotnya suara PPP antara lain adalah pemerintahan Orde
Baru yang memaksakan azas tunggal pancasila sehingga lambang PPP berganti
dari Ka‘bah menjadi bintang, juga karena NU sudah keluar dari PPP membuat
ulama-ulama NU berpindah ke lain partai dalam preferensi politiknya praktis hal
ini diikuti oleh masyarakat tradisional NU.57
PPP sendiri sampai hari ini telah mengikuti sembilan kali perhelatan
pemilu dari tahun 1977, dengan perolehan suara yang cenderung menurun terlebih
lagi setelah NU kembali ke khittah 1926 perolehan suara PPP turun drastis dari
tahun ke tahun. Pada pemilu tahun 1977 merupakan pemilu dimana PPP meraih
suara sah nasional terbanyak selama PPP mengikuti perhelatan demokrasi ini,
pada tahun tersebut PPP mendapatkan 29.29% dan memperoleh 99 kursi dari 360
kursi yang diperebutkan. Pada saat itu suara PPP di DKI Jakarta bahkan
mengalahkan Golkar juga di Daerah Istimewa Aceh, hal ini terjadi karena banyak
tokoh dari Masyumi, partai yang dilarang pada akhir Orde Lama, tampil ke
permukaan dan mendukung PPP sebagai partai yang berazas Islam satu-satunya
saat itu.58
Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa PPP adalah hasil fusi dari
beberapa partai Islam, hal inilah yang menyebabkan PPP sendiri berhaluan Islam
sekalipun tetap setia kepada UUD 1945 dan Pancasila baik pada zaman Orde Baru
57
Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Inonesia, (Ciputat: Lemlit UIN Jakarta,
2011), hal. 110 58
Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Inonesia, hal. 108
43
(karena memang tuntutan kebijakan azas tunggal) maupun setelah reformasi 1998,
PPP juga mendeklarasikan partainya sebagai ―Rumah Besar Umat Islam‖ partai
berlambang Ka‘bah ini walaupun sempat berubah lambang menjadi bintang pada
saat penerapan azas tunggal pancasila era Orde baru memang bisa disebut partai
Islam tertua yang masih survive dalam perpolitikan Indonesia hingga kini.
Setelah Pemilu tahun 2014 PPP diguncang persoalan yang cukup pelik,
yakni dualisme kepemimpinan. Terdapat dua Ketua Umum dari dua muktamar
yang berbeda antara muktamar Surabaya dan muktamar Jakarta. Persoalan
semakin pelik ketika kubu muktamar Jakarta yang dengan ketua umumnya Djan
Faridz menggugat pemerintah ke Mahkamah Konstitusi.59
Namun perlahan tapi pasti dengan campur tangan pemerintah yang
diwakili Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hingga Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly, kemudian kemenkumham menginisiasi untuk mengaktifkan lagi
kepengurusan muktamar Bandung, yang dianggap menaungi kedua kubu antara
kubu muktamar Jakarta dan Surabaya untuk mengadakan Islah, dan terpilihlah
Romahurmuzy sebagai Ketua Umum dengan cara aklamasi pada muktamar Islah
Pondok Gede, dengan terbitnya surat kemenkumham bernomor M.HH-
06.11.012016.60
maka disahkan lah PPP yang diketuai Rohmahurmuzy.
59
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/06350171/PPP.dan.Islah.yang.Tak
.Sempurna diunduh pada 14 Oktober 2016 60
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/27/15241031/Menkumham.Sahkan.K
epengurusan.PPP.Hasil.Muktamar.Islah diunduh pada 14 Oktober 2016
44
Sementara itu kubu Djan Faridz menganggap mukatamar Pondok gede
hanya sebagai muktamar lucu-lucuan dan tetap menempuh jalan peradilan di
Mahkamah Konstitusi sebagai jalan keluar dari persoalan dualisme kepengurusan
ini. Meskipun Djan sendiri menurut Romahurmuzy akan diposisikan pada tempat
terhormat di kepengurusan yang baru untuk Djan.
B. Platform PPP
Visi
Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara
Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya
supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM),
serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial
yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.61
Misi
1. PPP berupaya mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Allah SWT
lewat semangat ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim).
2. PPP berupaya untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan
kewajiban dasar manusia sesuai dengan ukhuwah basyariyah
(persaudaraan sesama manusia).
3. PPP berupaya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa lewat semangat
ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa).
61
http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/ diunduh pada 24 September
2016
45
4. PPP berupaya menciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan kedaulatan
rakyat sebagai supremasi tertinggi dan ditegakkannya musyawarah untuk
mufakat.
5. PPP memperjuangkan dan mengupayakan Indonesia yang adil, makmur
dan diridhai Allah SWT sehingga menjadikan Indonesia negara yang
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.62
C. PPP dan Perspektif Representasi Perwakilan Perempuan di Politik
PPP pada awal pelaksanaan kebijakan yang menyangkut batas minimum
kuota perempuan dalam pemilu tahun 2004 yakni UU. No 12 tahun 2003 boleh
dibilang tidak terlalu aware terhadap isu ini. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan
Hamzah Haz di Media Indonesia dan Kompas pada 12 maret 2003.
―Sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan berapa orang yang dimunculkan, 60
persen pun kalau memang rakyat memberikan kepercayaan kepada politikus
perempuan di parlemen mengapa tidak? … sebab bukan kuota yang menentukan
tapi pemilihnya.”63
Lebih lanjut Ani Soetjipto menyampaikan bahwa;
Partai Persatuan Pembangunan secara jujur mengakui mereka memang
mengalami kesulitan menjaring caleg perempuan. Ini sebagian berkaitan
dengan terbatasnya kader parpol perempuan, tapi yang utama karena
kultur dan tradisi sebagai partai yang berbasiskan agama sehingga mereka
tidak spesifik membahas masalah perempuan. Isu perempuan, bagi
mereka, tidak popular untuk dijual pada konstituennya yang kebanyakan
berada di daerah pedesaan yang belum mengerti betul masalah kesetaraan
dan keadilan jender. Dalam proses internal, partai juga banyak masalah
62
http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/ diunduh pada 24 September 2016 63
Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-esai pilihan
(Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 176
46
karena selama ini perempuan di Ormas pendukung PPP sulit masuk ke
jajaran pengambilan keputusan dan kepengurusan karena dinamika konflik
yang tinggi, kurangnya transparansi, dan arena lobi serta negosiasi yang
sering mengabaikan perempuan.64
Selepas pemilu tahun 2004, pemilu yang pertama kali mensyaratkan partai
untuk mencalonkan minimal 30% perempuan dengan legitimasi UU No. 12 tahun
2003 digelar, PPP dalam Muktamar ke IV memutuskan untuk mendirikan banom
(Badan Otonom) perempuan yang bernama WPP (Wanita Persatuan
Pembangunan). Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi perempuan di PPP
untuk memiliki kesempatan dan peluang yang lebih besar dalam bidang
pengembangan dan pendidikan politik mereka.65
Kemudian pada pemilu terakhir tahun 2014 lalu didapati gambaran umum
mengenai perolehan suara dan kursi PPP yang menggembirakan untuk
perempuan. PPP memang secara suara sah nasional berada di urutan ke Sembilan
atau ke dua dari terkahir sebelum Partai Hanura yang berada pada posisi sepuluh
jumlah perolehan suara nasional, akan tetapi jika dilihat dari proporsi kursi
perempuan dan laki-laki pada fraksi partai di parlemen pusat Partai PPP
mempunyai 10 orang perempuan dari 39 total kursi yang dimilikinya, selebihnya
29 kursi dimiliki oleh laki-laki.66
64
Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana, hal. 212 65
Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana, hal. 79 66
www.puskapol.ui.ac.id/opini/menghadirkan-kepentingan-perempuan-dalam-
representasi-politik-di-indonesia.html diunduh pada 24 September 2016
47
Hal ini sungguh sebuah prestasi sendiri bagi partai berlambang Ka‘bah ini,
pasalnya PDI-Perjuangan pun yang notabene juara pemilu tahun 2014 lalu dengan
raihan suara 23 juta suara lebih hanya berhasil meloloskan perempuan dengan
prosentase sebesar 19,27% atau sama dengan 21 kursi dari 109 kursi yang diraih
oleh partai berlambang banteng dengan mocong putih tersebut.
Raihan kursi perempuan pada tingkat parlemen pusat di tahun 2014 lalu
juga melebihi apa yang pernah dicapai oleh Partai PPP di tahun 2009, jika pada
tahun 2009 proporsi kursi untuk perempuan hanya 5 kursi dari 38 kursi yang di
dapat oleh Partai PPP maka pada pemilu tahun 2014 lalu angka kursi perempuan
naik dua kali lipat dengan catatan jumlah keseluruhan kursi yang di dapat pada
pemilu 2009 hampir sama dengan apa yang di dapat partai tersebut pada 2014
selisihnya hanya sebesar satu kursi.
Perolehan suara caleg perempuan PPP pada tingkat pusat dalam pemilu
2014 lalu memang harus diberikan penghargaan yang tidak sedikit. Tetapi di sisi
lain yakni tingkat daerah atau provinsi khususnya DKI Jakarta suara caleg
perempuan PPP sangatlah minim, walaupun masih ada partai yang bahkan tidak
dapat menempatkan wakil perempuannya sama sekali di parlemen DKI Jakarta
pada pemilu legislatif 2014.
Kurangnya perwakilan perempuan secara kuantitatif di parlemen
seyogyanya ditanggapi dengan serius. Pasalnya dengan adanya keterwakilan
48
perempuan secara kuantitatif diharapkan akan berdampak langsung pada produk-
produk legislasi yang dihasilkan, dan tentunya diharapkan wakil perempuan juga
akan pro terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami perempuan serta
memberikan solusi yang baik.
PPP sendiri dalam platform partainya pada bidang politik menekankan
bahwa PPP menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi.
PPP juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan platform politik
yang demikian diharapkan PPP dapat berperan aktif mendukung kesetaraan
gender, dan serius pula mendukung affirmative action.
49
BAB IV
PPP DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU DI DKI
JAKARTA
A. Perolehan Suara Untuk Caleg Perempuan Pada Pileg 2014 di DKI
Jakarta
Dalam alam demokrasi yang modern, representasi setiap masyarakat
menjadi penting, agar kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya diterima oleh
seluruh masyarakat. Tidak terkecuali untuk representasi perempuan, keterlibatan
perempuan dalam pengambilan keputusan adalah sebuah sine qua non di dalam
demokrasi.67
Saat ini Indonesia telah menjalankan affirmative action (tindakan
khusus sementara) untuk meningkatkan representasi perempuan dalam hal
kuantitas lewat UU No. 8 tahun 2012 yang mana poin pentingnya adalah
―memaksa‖ partai politik untuk mengirimkan minimal 30% calon legislatif
perempuan di setiap tingkatan, dari pusat sampai kota/kabupaten, serta
kepengurusan dalam partai juga di isi minimal 30% perempuan.
Lebih lanjut angka 30% yang menjadi penekanan UU Pemilu tersebut
mengacu pada angka critical mass di banyak negara. Hal ini juga di jelaskan oleh
Perludem (perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi) yang mengatakan bahwa
banyak negara dengan angka perempuan dalam parlemennya lebih dari 30% maka
kebijakannya juga lebih banyak berpihak pada perempuan, dan kebijakan yang
67
Chusnul Mar‘iyah dalam Julie Ballington (ed), (terj.), Perempuan di Parlemen:
Bukan Sekadar Jumlah, (Jakarta:International IDEA, 2002), hal. 1
50
penting pada aspek kehidupan lainnya seperti kesehatan, kekerasan pada
perempuan dan anak dan lain sebagainya bisa dihasilkan dengan lebih ramah
gender.68
Indonesia sendiri menganut apa yang dinamakan sebagai legislative quota
dalam affirmative action dengan sistem pemilu yang menyertakan daftar nama
calon legislatif atau yang seringkali disebut proporsional terbuka, serta dengan
sistem nomor urut yang menggunakan semi-zipper system. Sistem proporsional
terbuka dirasa tepat untuk menghadirkan representasi yang massif bagi
pencalonan perempuan. Karena menurut Richard E. Matland, proporsionalitas
sering dianggap paling baik kalau diraih dengan memanfaatkan daftar partai, di
mana partai-partai politik mengajukan daftar kandidat pada pemilihan tingkat
nasional atau regional, dan di mana ada banyak anggota dipilih dari setiap distrik,
dengan demikian kemungkinan representasi kelompok-kelompok minoritas
menjadi lebih besar.69
Namun ketika sistem proporsional disandingkan dengan sistem kepartaian
yang multipartai ekstrim, cita-cita agar perempuan mendapat kursi 30% di
parlemen menjadi seolah ―mental‖ kembali dikarenakan ketidaksinkronan antara
sistem pemilu dan sistem kepartaian seperti yang terjadi di Indonesia saat ini,
68
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet. 69
Richard E. Matland ―Meningkatkan partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen
Legislatif dan Sistem Pemilihan‖ dalam Julie Ballington (ed), (terj.), Perempuan di
Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah, hal. 73
51
sebabnya adalah bila perolehan kursi tersebar ke banyak parpol hal demikian
menjadikan peluang perempuan lebih kecil karena parpol yang hanya mendapat
sedikit kursi.70
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan yang menyebutkan bahwa
sistem proporsional terbuka adalah sistem yang menekankan pada suara
terbanyak, pada akhirnya perempuan berjuang-sendiri-sendiri dan bukan hanya
mengalahkan laki-laki, tetapi juga bagaimana mengalahkan perempuan yang
lain.71
Pada akhirnya dapat diketahui bahwa kecilnya suara perempuan dalam
perolehan suara yang terjadi, dialami oleh seluruh partai yang berkontestasi dalam
pemilu. Sistem pemilihan proporsional terbuka dan sistem kepartaian yang multi
partai ekstrim kaitannya dengan affirmative action hanya menekankan
representasi pada tahap pencalonan saja dan bukan keterwakilan riil di parlemen.
Hal ini jelas suatu kelamahan UU pemilu di Indonesia yang penulis sebut sebagai
―akal-akalan representasi‖.
Perolehan suara perempuan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif tanpa
pernah menyentuh angka critical mass 30% di parlemen pada umumnya . Partai-
partai setelah ada UU Pemilu yang mengharuskan untuk menyertakan minimal
30% calon legislatif perempuan pada umumnya justru menjadikan angka 30%
70
Pramono, Sidik, ed., Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan
Kebijakan Afirmasi, Kemitraan partenership, hal. 6 71
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem Tebet
52
sebagai patokan prosentase perempuan yang cukup. Tentunya hal tersebut
mengindikasikan tidak adanya political will dari partai untuk membuat angka
representasi pada tahap pencalonan jauh lebih besar dari 30% atau sampai pada
50%. Kenyataannya pada Pileg 2014 DPRD DKI Jakarta lalu prosentase terbesar
pada pencalonan perempuan dimiliki oleh partai PPP dengan prosentase 36% dari
calon yang diajukan, lebih jelasnya ada pada tabel di bawah ini;
Tabel IV.A.1
Prosentase Keterwakilan Perempuan Pada Tahap Pencalonan
Legislatif DPRD DKI Jakarta Pada tahun 2014-2019
Sumber: KPU DKI Jakarta
Dari data di atas kita dapat mengetahui bahwa; pertama, pencalonan
perempuan pada kontestasi Pileg 2014 DPRD DKI Jakarta yang terdiri dari 12
partai berkisar diangka 30%-36% dengan nilai tenngah 34%. Hal ini menandakan
bahwa semua partai yang berkontestasi di Pileg 2014 DPRD DKI Jakarta telah
53
melampaui sayarat administrasi 30% keterwakilan perempuam dalam pencalonan
legislatif.
Kedua, jika dianalisis lebih lanjut maka akan terlihat bahwa hampir semua
partai mencalonkan 106 caleg untuk memperebutkan 106 kursi yang ada di DPRD
DKI Jakarta, hanya partai PKS yang mencalonkan 101 caleg pada Pileg 2014
DPRD ini. Kontestan yang banyak tentunya membuat peluang terpilih akan
semakin kecil karena kursi akan relatif tersebar ke banyak partai.
Ketiga, partai PPP adalah partai yang paling banyak dalam hal pencalonan
perempuan pada Pileg 2014 DPRD ini, sebanyak 38 caleg perempuan atau 36%
dari proporsi kontestan Pileg pada partai PPP. Tetapi pencalonan yang banyak
oleh PPP layak dikritisi karena dari segi penempatan nomor urut caleg
perempuan, PPP sedikit kurang memprioritaskan perempuan dalam semi-zipper
System. Data lengkap penempatan nomor urut tiap partai dapat dilihat pada tabel
di halaman berikutnya.
Tabel IV.A.2
Penempatan Nomor urut 1-3 Pada Perempuan Dalam Tahap Pencalonan
Legislatif DPRD DKI Jakarta Pada tahun 2014-2019
No Partai Nomor Urut
1 2 3
1 NasDem 3 1 6
2 PKB - 1 9
3 PKS 1 - 9
4 PDI-Perjuangan 3 3 7
5 Golkar 1 1 8
6 Gerindra 2 3 5
54
7 Demokrat 1 6 5
8 PAN 2 1 7
9 PPP 1 2 8
10 Hanura - 1 9
11 PBB 1 2 8
12 PKPI 1 - 9
Jumalah 15 21 90
Sumber: KPU DKI Jakarta
Dari tabel penempatan nomor urut caleg perempuan 1-3 di atas kita dapat
mengetahui bahwa, PDI-Perjuangan adalah partai yang paling banyak
memprioritaskan perempuan pada nomor urut satu, tercatat sebanyak 3 caleg
perempuan ditempatkan oleh PDI-Perjuangan di nomor urut pertama, sedangkan
partai Demokrat adalah partai yang paling banyak menempatkan caleg perempuan
pada nomor urut dua.
Di sisi lain kita bisa melihat bahwa PPP di DKI Jakarta hanya
menempatkan satu caleg perempuan pada nomor urut satu dan dua orang caleg
perempuan pada nomor urutan ke dua, hal ini membuktikan bahwa PPP dalam
pencalonan anggota legislatifnya di DKI Jakarta kurang memprioritaskan
perempuan untuk maju di nomor urut pertama. Padahal nomor urut pertama masih
merupakan faktor determinan dan mendominasi keterpilihan calon legislatif
dalam Pileg 2014 ini, bisa dilihat pada tabel selanjutnya.
55
Tabel IV.A.3
Caleg Perempuan Terpilih DPRD DKI Jakarta 2014-2019
No. Nama Calon PARPOL DAPIL No. Urut Jml. Suara
1 Hj. Yusriah Dzinnun PKS DKI Jakarta 2 3 12.649
2 Hj. Rifkoh Abriani, S.Pdi PKS DKI Jakarta 8 1 12.982
3 Ellyzabeth CH. Mailoa PDI-Perjuangan DKI Jakarta 1 4 7.814
4 Meity Magdalena Ussu, MBA. PDI-Perjuangan DKI Jakarta 2 6 7.563
5 Hj. Ida Mahmudah PDI-Perjuangan DKI Jakarta 3 1 14.637
6 Hj. Indrawati Dewi PDI-Perjuangan DKI Jakarta 7 3 7.702
7 Yuke Yurike, MM. PDI-Perjuangan DKI Jakarta 8 2 8.902
8 Serelda Tambunan, S.I.P PDI-Perjuangan DKI Jakarta 8 3 8.124
9 Ong Yenny PDI-Perjuangan DKI Jakarta 9 11 18.931
10 CN. DR. Siegvrieda Lauwani PDI-Perjuangan DKI Jakarta 9 1 15.264
11 Merry Hotma, SH. PDI-Perjuangan DKI Jakarta 10 1 36.099
12 Nuraina GERINDRA DKI Jakarta 7 1 8,740
13 Ir. Endah Setia Dewi, MM. GERINDRA DKI Jakarta 8 3 4.683
14 Hj. Rani Maulani GERINDRA DKI Jakarta 9 1 8.478
15 Rina Aditya Sartika GERINDRA DKI Jakarta 10 2 12.991
16 Hj. Neneng Hasanah, SE. P DEMOKRAT DKI Jakarta 2 2 4,880
17 Nur Afni Sajim, SE. P DEMOKRAT DKI Jakarta 9 1 7.277
18 Hj. Nina Lubena PPP DKI Jakarta 4 7 5.358
Sumber: Pemilu 2014 Dalam Angka, KPU DKI Jakarta
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pertama, ada beberapa partai
yang tidak berhasil meloloskan caleg perempuannya yakni; Golkar, PKB,
NasDem, Hanura dan PAN, hal demikian dapat terjadi dikarenakan sistem
pemilu dengan daftar terbuka dan disandingkan dengan multi partai ekstrim
seperti yang terjadi di Indonesia membuat peluang perempuan untuk lolos
menjadi kecil, karena sebaran kursi yang ada diperebutkan oleh banyak partai
dengan banyak calon legislatif. Perludem merekomendasikan untuk
56
membatasi jumlah caleg dalam kontestasi Pileg, karena jika kontestan terlalu
banyak hanya akan memperkecil peluang seorang caleg untuk terpilih, dan
yang dirugikan dalam hal ini adalah caleg perempuan.72
Kedua, bahwa dengan absennya perempuan dalam lima partai (Golkar,
PKB, NasDem, Hanura dan PAN) tersebut membuat partai makin bercorak
patriarki. Kemungkinan hal ini akan berlanjut pada tataran pandangan fraksi
partai dalam parlemen tersebut yang juga akan bercorak patriarki. Hal demikian
juga dibenarkan Perludem, dengan menyatakan bahwa dalam konteks apapaun,
lembaga apapun bila tidak ada upaya pengarus utamaan gender atau afirmasi
perempuan akan diskriminatif karakter lebaganya, termasuk lembaga politik.73
Terlebih bila dalam suatu partai sama sekali tidak ada perempuan, maka semakin
besar peluang partai tersebut untuk tidak adil gender dalam setiap pandangan
kebijakan nantinya. Ketua KPPI DKI Jakarta juga menerangkan permasalahan
tersebut, sebagai berikut;
Itulah masalahnya (keterwakilan perempuan yang minim), bahwa
kenyataannya (perempuan) sangat sulit diberi kesempatan oleh teman-
teman kita sendiri (laki-laki) disana. Itu yang kita kejar (perjuangkan),
tentunya kita kejar dengan kapasitas yang kita punya dengan kemampuan
yang tidak hanya sekadarnya saja. Ini sekarang kan sedang diusulkan
bahwa undang-undang keterwakilan perempuan yang 30% perempuan itu
dimulai juga dari partai, yaitu kita mengusulkan tiap partai menempatkan
kader perempuannya di kepengurusan hariannya sebanyak 30%. Itu harus
72
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet. 73
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin
57
dimulai dari situ, kalau tidak susah untuk mendapat posisi yang setara dan
berimplikasi pada keterwakilan yang minim. Jadi tidak hanya dalam
undang-undang untuk memasukkan perempuan dalam kontestasi
pemilihan legislatif sebanyak 30%, tapi 30% itu harus diikuti juga oleh
kepengurusan partai, nah itulah yang sedang kita perjuangkan di DPR
RI.74
Ketiga, sepuluh dari delapan belas calon perempuan yang terpilih untuk
mengisi kursi DPRD DKI Jakarta tahun 2014-2019 adalah anggota baru yang
berarti delapan lebihnya adalah incumbent atau petahana, data ini cukup
menggembirakan pasalnya dari data ini menggambarkan bahwa terdapat sirkulasi
wakil rakyat perempuan di parlemen. Hal ini sebenarnya yang dijadikan alasan
oleh para aktivis perempuan mengapa memilih daftar terbuka, harus diakui bahwa
sistem daftar terbuka sukses untuk membuat para kontestan turun ke masyarakat,
mau tidak mau caleg perempuan juga ikut belajar tentang kampanye, konsolidasi
massa, berbicara tentang politik serta hal-hal yang berkenaan dengan pemilu. Ini
sebenarnya nilai tambah dari sistem proporsional daftar terbuka, Disadari atau
tidak pemilu dengan sistem proporsional terbuka membuat banyak perempuan
bisa berkesempatan berpolitik secara riil. 75
Keempat, didapati fakta bahwa nomor urut masih menjadi preferensi
politik bagi pemilih di Jakarta bahkan untuk caleg perempuan, hal tersebut terlihat
dari jumlah caleg yang lolos dari nomor urut kecil yakni 1-3 sebanyak 14 caleg, 4
74
Wawancara dengan Hj. Marie Amadea Ismayani, S.Si. Ketua KPPI (kaukus
Perempuan Politik Indonesia) DKI Jakarta, Sekaligus mantan Anggota DPRD DKI
Jakarta 2009-2014 Fraksi Demokrat. Pada tanggal 12 Januari 2017. 75
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet.
58
caleg lainnya berasal dari nomor urut besar. Menurut Ketua KPPI DKI Jakarta,
nomor urut memang masih determinan menjadi faktor terpilihnya calon legislatif,
di lain sisi perempuan sering ditempatkan di nomor urut ke tiga dalam semi-zipper
system, hal inilah yang menjadi landasan dari KPPI untuk menuntut partai
memprioritaskan perempuan dalam nomor urut satu.76
Sedangkan menurut Usep
nomor urut besar yang terpilih lebih disebabkan karena mempunyai modal massa
dan modal uang yang kuat, seperti yang ditegaskan dalam kutipan wawancara
berikut;
Saya cenderung ke yang nomor urut besar terpilih ini punya basis massa
dan modal uang yang banyak. Tapi gini ya ki, secara keseluruhan memang
iya nomor urut kecil masih jadi favorit orang karena kita kan susunan
calegnya hirarkis nomornya (kebawah), sedangkan masyarakat masih
banyak yang menganggap nomor urut satu itu yang paling bagus‖.77
Dengan daftar calon terbuka ini menjadi sebuah keuntungan sendiri bagi caleg
perempuan jika mendapat nomor urut kecil.
Kelima, PDI-Perjuangan adalah partai pemenang pemilu yang memiliki
jumlah perempuan terpilih paling banyak diantara partai-partai lain untuk DPRD
Jakarta, yakni sebanyak Sembilan orang atau setengah dari jumlah keseluruhan
perempuan terpilih DPRD DKI Jakarta, hal ini tentu saja diikuti dengan harapan
76
Wawancara dengan Hj. Marie Amadea Ismayani, S.Si. Ketua KPPI (kaukus
Perempuan Politik Indonesia) DKI Jakarta, Sekaligus mantan Anggota DPRD DKI
Jakarta 2009-2014 Fraksi Demokrat. Pada tanggal 12 Januari 2017. 77
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet.
59
bahwa PDI-Perjuangan dengan kuantitas perempuannya yang banyak akan
berperan penting dalam kebijakan-kebijakan yang adil gender, walaupun dalam
inisiasi kebijakan datangnya dari tiap-tiap komisi di parlemen, PDI-Perjuangan
setidaknya bisa memberi pandangan yang lebih ramah gender dalam pandangan
fraksi dibanding partai lain. Narasumber penulis dari Perludem mempunyai
pandangan lain, jika PDI-Perjuangan masih mengandalkan suplai kadernya
daripada aktivis, kemungkinan kebijakannya akan lebih adil gender. Tetapi perlu
diingat juga bahwa setiap partai mempunyai kecenderungan watak yang
patriarkis, meskipun dalam fraksi PDI-Perjuangan kuantitas perempuan lebih
besar dari partai lainnya di DPRD DKI Jakarta hal tersebut sebenarnya masih
belum menjamin.78
Keenam, didapati fakta bahwa dapil lima adalah dapil yang sama sekali
tidak menyumbangkan wakil perempuan atau bisa dibilang caleg perempuan tidak
mendapatkan kursi pada dapil ini. Penulis berasumsi bahwa di dapil ini masih
melekat budaya patriarki yang ditopang oleh agama, yang dimana keduanya
diakomodasi oleh budaya betawi, perlu diketahui juga bahwa daerah Jatinegara,
Duren Sawit dan Kramat jati, adalah daerah yang masih kental dengan budaya
betawi walaupun dari segi kependudukan umumnya wilayah Jakarta adalah
wilayah yang heterogen. Patriarki ini menjadi semakin susah ketika dia menyatu
78
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet.
60
dengan agama dan kedua ketika dia menyatu dengan kesukuan atau etnis, dan
Betawi ini nuansa agamanya cukup kental dalam etnis. Jika merujuk pada variable
equality dari freedom house ada kecenderungan demikian. Tentunya hipotesis
demikian harus di riset lebih jauh secara kuantitatif agar valid dan dapat diterima
secara keilmuan.79
B. Faktor-faktor Penyebab Minimnya Perolehan Suara Untuk Caleg
Perempuan Pada Pileg 2014 di DKI Jakarta
Menyoal kendala-kendala yang dihadapi oleh para caleg perempuan dan
terjadi pada umumnya di seluruh belahan dunia, penulis perlu mengutip tulisan-
tulisan Nadezhda Shvedova di Jurnal International IDEA tentang hal tersebut,
menurutnya perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik, menemukan
kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya dan sosial sering tidak
bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan mereka. Lebih lanjut Nadezhda
membagi kendala-kendala tersebut ke dalam tiga wilayah yakni kendala politik,
sosio-ekonomi, dan kendala ideologis-psikologis.80
Nadezhda mengkonsepsikan
kendala politik ke dalam lima bentuk yakni;
1. Politik masih terlalu ―maskulin‖, artinya politik seakan tercipta hanya
untuk kaum laki-laki, karena terlalu banyaknya laki-laki dalam politik
79
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet. 80
Nadezhda Shvedova, ―Kendala-kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam
Parlemen‖ dalam Julie Ballington (ed), (terj.), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar
Jumlah, hal. 19
61
maka seakan sebuah hal yang tabu ketika perempuan masuk juga ke dalam
ruang politik.
2. Kurangnya dukungan partai, terbatasnya akses jaringan politik: partai
karena terlalu lama asyik dengan model ‖maskulin‖ ketika ada perempuan
masuk menjadikan perempuan terpinggir dan tak diindahkan, perempuan
yang bukan ―siapa-siapa‖ membuat geraknya terhambat, partai seringkali
hanya mementingkan perempuan yang ada ―kaitannya‖ dengan elit
meereka.
3. Kurangnya hubungan kerja sama, hubungan kerja sama antara organisasi
dan perempuan penting untuk perempuan dalam politik, karena biasanya
organisasi dapat mengusahakan keterwakilan perempuan lewat advokasi
ataupun lewat dukungan riil di dalam pemilu.
4. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik,
perempuan karena masih awam dalam ruang publik apalagi ruang politik
perlu bimbingan dan pengedukasian tentang politik secara mendalam.
5. Hakikat sistem pemilihan, sistem pemilihan juga penting untuk perempuan
dalam politik, di Indonesia sistem pemilihan yang memakai daftar
proporsional terbuka dengan nama calon lalu partai yang berkontestasi
62
memperebutkan kursi terlalu banyak (multipartai) membuat caleg
perempuan menjadi minim untuk terpilih pada pemilihan legislatif.81
Kemudian kendala selanjutnya yakni kendala sosio-ekonomi;
1. Kemiskinan dan pengangguran.
2. Kurangnya sumber-sumber keungan yang memadai.
3. Buta huruf dan terbatasnya akses ke pendidikan dan pemilihan profesi.
4. Beban ganda mengenai tugas rumah tangga dan kewajiban-kewajiban
professional.82
Kendala yang terakhir dalam pandangan Nadezhda adalah kendala
Ideologis dan psikologis;
1. Ideologi gender dan pola-pola kultural dalam masyarakat.
2. Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri.
3. Persepsi perempuan tentang politik sebagai permainan ―kotor‖.
4. Cara bagaiaman perempuan digambarkan dalam media massa.83
Hal-hal mengenai hambatan dalam konteks Indonesia selanjutnya
diterangkan oleh Khofifah Indar Parawansa, yang berpandangan bahwa dalam
81
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet. 82
Nadezhda Shvedova, ―Kendala-kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam
Parlemen‖, hal. 28 83
Nadezhda Shvedova, ―Kendala-kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam
Parlemen‖, hal. 32
63
negara yang menganut sistem patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan
perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatasi karena persepsi masyarakat
mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias
kearah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Ada empat faktor
utama menurut Khofifah yang mempengaruhi pola seleksi antara perempuan dan
laki-laki. Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang
masih kental asas patriarkalnya, faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi
dalam partai politik, ketiga berhubungan dengan media yang berperan penting
dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan
dalam parlemen, keempat tidak adanya jaringan antar organisasi massa, dan
selebihnya adalah faktor-faktor seperti pendidikan, pengaruh keluarga dan sistem
multi partai.84
Sesungguhnya sudah ada jalan keluar yang coba ditempuh yaitu dengan
berdirinya KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) yang merupakan jaringan
antara perempuan pada partai-partai politik Indonesia dan umumnya aktivis
perempuan di Indonesia. Pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya pernah
dimunculkan oleh Nadezhda dan Khofifah yamg memiliki relevansi dengan
problem-problem perempuan dalam politik dan khususnya pada proses
keterpilihan saat ini.
84
Khofifah Indar Parawansa, ―Hambatan terhadaap Partisipasi Politik Perempuan
di Indonesia‖ dalam Julie Ballington (ed), (terj.), Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar
Jumlah, hal. 49
64
Peneliti ingin memfokuskan masalah hambatan pada perempuan dalam
keterpilihan di parlemen ke dalam empat faktor yang menurut asumsi peneliti saat
ini penting untuk di telaah lebih lanjut, faktor-faktor penyebabnya secara umum
adalah popularitas dan memiliki modal sosial yang cukup atau tidak, hal ini sama-
sama penting bagi perempuan maupun laki laki, akan tetapi ada beberapa faktor
lain yang mungkin hanya menjadi hambatan bagi perempuan sementara tidak bagi
laki-laki, seperti masih banyak berkembangnya stereotip di masyarakat bahwa
perempuan belum pantas naik panggung untuk wilayah publik terlebih lagi
wilayah politik yang dominan diisi oleh laki-laki.
Hambatan selanjutnya adalah pengaruh oligarki yang besar pada suatu
parpol, oligarki bagi caleg perempuan bagai pisau bermata dua, di satu sisi
berguna di sisi lain bisa menghambat. Puskapol UI dalam kajiannya terhadap
pemilu 2014 menganggap ada korelasi antara oligarki dan keterpilihan caleg
perempuan, Puskapol menyebutkan bahwa jaringan kekerabatan dengan elit
politik menjadi kategori dengan nilai teringgi yakni 37% atas keterpilihan caleg
perempuan, bahkan menurut Puskapol UI lebih lanjut menerangkan bahwa pada
tahun 2009 indikasi peran oligarki dalam keterpilihan caleg perempuan sampai
pada angka 42%,85
tentunya dari segi kuantitas oligarki partai mempunyai peran
yang cukup signifikan dalam proses keterpilihan caleg perempuan, namun pada
85
http://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/analisis-perolehan-suara-
dalam-pemilu-2014-oligarki-politik-dibalik-keterpilihan-caleg-perempuan.html diunduh
pada 26 Mei 2016
65
segi kualitas dikhawatirkan nantinya perempuan hanya menjadi perpanjangan
partai akan kebijakannya dan secara tidak langsung oligarki partai juga menafikan
caleg perempuan yang sebenarnya sangat diharapkan keberadaannya, yaitu caleg
perempuan yang kritis memperjuangkan hak kaumnyanya dalam parlemen.
Faktor-faktor penyebab kecilnya perolehan suara perempuan, yakni;
1. Popularitas
Popularitas dalam KBBI bisa disamakan dengan keterkenalan, jika ditarik
dalam wilayah politik pada tahapan pencalonan, popularitas diartikan sebagai
dikenal tidaknya calon legislatif oleh pemilih atau konstituennya. Popularitas dan
politik memang bersinggungan bahkan seringkali berjalan beriringan, jalan untuk
menjadi pemimpin atau wakil rakyat sekalipun harus mengandalkan popularitas.
M. Alfan Alfian dalam bukunya Menjadi Pemimpin Politik memasukkan
popularitas ke dalam hal yang patut diperbincangkan lebih serius.86
Popularitas bisa didapat oleh pengaruh seseorang dalam suatu masyarakat,
baik ia sebagai pembuat kebijakan bahkan publik figur sekalipun. Sistem pemilu
Indonesia yang kini menganut sistem proporsional terbuka mengharuskan calon
legislatif dikenal oleh masyarakat, karena itu popularitas menjadi aspek yang
penting bagi keterpilihan suatu calon terlebih saat ini sistem pemilu di Indonesia
menganut sistem proporional terbuka dimana calon harus diingat dan setidaknya
diketahui oleh sang pemilih nantinya agar dapat meraih banyak suara.
86M. Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan
Kekuasaan, (Jakarta: Gramdeia Pustaka Utama, 2009), hal. 76
66
Asumsi tersebut dibenarkan oleh Perludem bahwa banyak dari pemilih
yang memilih caleg artis disebabkan oleh pemilih yang merasa ada keterikatan
dengan caleg tersebut karena mereka sering muncul di publik.87
Hal ini tentu saja
membuat partai politik melihat popularitas sebagai salah satu pertimbangan
rekrutmen calon legislatifnya hanya untuk menjadi vote getter, dan implikasinya
adalah partai mulai mengesampingkan aspek-aspek lainnya seperti kapasitas dan
kapabilitas. Popularitas tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi calon
perempuan utamanya yang berprofesi hanya diranah privat, kecuali calon
perempuan seperti publik figur yang sudah dikenal masyarakat.
2. Modal Sosial
Modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma
informal yang dimiliki bersama di antara para anggota kelompok yang
memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka, bentuk yang nyata dari
hal tersebut adalah lahirnya suatu kepercayaan antar anggota kelompok.88
Modal
sosial menjadi penting bagi para calon legislatif bukan hanya untuk perempuan,
juga untuk laki-laki. Tentunya sudah menjadi rahasia umum bahwa caleg yang
terpilih adalah caleg-caleg yang memiliki modal sosial yang kuat, terlebih pada
87
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet.
88
Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta: Media
Pressindo, 2007), hal. 52
67
negara yang memakai sistem proporsional dengan daftar terbuka seperti Indonesia
ini.
Tetapi perlu diingat juga bahwa bisa berlaku sebaliknya, modal sosial
yang kurang bisa menghambat calon dalam hal keterpilihan. inilah sebenarnya
yang menjadi hambatan bagi perempuan karena pada umumnya perempuan-
perempuan yang menjadi caleg tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan
pemilih akibat dari seringnya perempuan berada di ruang privat, bukan publik.
Dalam sistem proporsional terbuka ini seharusnya ada keterikatan yang
kuat antara pemilih dengan caleg, bukan hanya semata-mata karena uang (money
politics) atau popularitas, karena masyarakat dewasa ini lebih menyikapi politik
uang secara ―nakal‖ maka modal sosial dirasa perlu dimiliki caleg, dan ini yang
sering tidak dimiliki oleh caleg perempuan pada umumnya.89
3. Oligarki Partai
Oligarki dapat dimaknai dengan melihat dua sisi kekuasaan. Pertama,
oligarki sebagai tatanan kekuasaan yang disusun secara memusat atas kendali
kelompok elit yang amat kecil. Kedua, oligarki diartikan sebagai tatanan elit
dalam jumlah kecil yang mampu menentukan kebijakansanaan publik,
89
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet.
68
pemahaman yang pertamalah yang berkaitan dengan partai dan sistem
rekrutmennya.90
Oligarki partai menjadi hambatan tersendiri untuk caleg yang bukan
berasal dari garis kekerabatan dengan elit partai dan juga yang mempunyai
materiil sedikit, hal ini digambarkan dengan jelas oleh Puskapol UI dalam
Analisisnya terhadap keterpilihan caleg perempuan. Rekrutmen caleg yang
condong untuk memilih jaringan kekerabatan praktis mengindikasikan stagnasi
sempitnya landasan rekrutmen caleg perempuan oleh partai. Ini semua
menandakan bahwa adanya ketergantungan perempuan pada basis kekuasaan laki-
laki.91
Politik masih identik dengan sifat maskulin, partai adalah sebuah institusi
dalam politik yang pada umumnya diisi oleh laki-laki yang dominan dan dalam
kuantitas yang mayoritas sedang perempuan hanya menjadi minoritas di
dalamnya. Jika partai memiliki oligarki yang cukup kuat bukan hanya
mempersempit rekrutmen caleg dengan dasar jaringan kekerabatannya melainkan
caleg yang berasal dari jaringan kekerabatan bila sudah terpilih akan menjadi
kepanjangan tangan dari partai di parlemen. kemudian ada persoalan bila caleg
yang terpilih bukan dari jaringan kekerabatan, besar kemungkinan untuk tidak
90
Syamsuddin Haris, ed. Pemilu Langsung Di tengah Oligarki Partai: Proses
Nominasi dan Seleksi Calon Anggota Legislatif Pemilu 2004 (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2005), hal. 194 91
http://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/analisis-perolehan-suara-
dalam-pemilu-2014-oligarki-politik-dibalik-keterpilihan-caleg-perempuan.html diunduh
pada 26 Mei 2016
69
mampu bersuara kritis akibat dari dominannya fraksi dalam kebijakan partai di
parlemen.92
4. Stereotip dan Budaya Patriarki
Stereotip didasarkan pada gambaran-gambaran yang sangat
disederhanakan mengenai seluruh kelompok masyarakat, hematnya stereotip
adalah gambaran umum yang dibentuk secara subjektif dan dibenarkan oleh
masyarakat sehingga menjadi suatu kebenaran umum.93
Stereotip dan budaya
patriarki menjadi variabel yang terkait satu sama lain. Masyarakat umum
menganggap bahwa tempat perempuan adalah pada ranah domestik atau privat
sedang politik adalah ranah publik yang biasanya secara kuantitas lebih banyak-
laki-laki ketimbang perempuan, maka tak pelak kecilnya perolehan suara
perempuan turut didasari oleh stereotip atau konstruksi sosial yang telah lama
melekat pada masyarakat dan selalu dipengaruhi oleh budaya patriarki. Perludem
juga menyatakan hal yang sama bahwa;
Budaya patriarki masih menjadi penyebab sulitnya keterpilihan
perempuan, sulitnya pemilih itu sadar pentingnya memilih perempuan
karena kebijakan pro gender, kebijakan pro perempuan, kebijakan pro
anak itu masih jauh di Indonesia, yah masih relevan, sangat relevan
malah.94
Lebih lanjut Ketua KPPI DKI Jakarta menambahkan bahwa;
92
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem
Tebet. 93
Bernard T. Adeney, Etika Sosial Lintas Budaya, Yogyakarta: Pustaka Kanisius,
2000), hal. 292 94
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor Perludem Tebet
70
(perempuan) hambatannya banyak, banyak sekali. Bahwa perempuan
selama ini dianggap tidak sejajar dengan kaum lelaki itu kan karena ada
hubungannya dengan agama ya mas yah, terus adat istiadat, sejak zaman
dulu adat timur kan memang kurang mengapresiasi perempuan dalam
ruang publik ya mas... iya dimana-mana masih seperti itu (Patriarki), dan
kita berjuang sangat keras untuk mengatasi masalah itu. Walaupun mereka
(laki-laki) mengatakan perempuan itu mempunyai potensi dalam politik,
tetapi tetap saja persaingan politik sangat ketat untuk kita mas. Ya balik
lagi kaitannya dengan faktor seperti agama yang masih sangat kuat bahwa
tidak bisa perempuan menjadi pemimpin.....95
Musdah Mulia dalam bukunya Menuju Kemandirian Politik Perempuan,
menyatakan bahwa, dunia politik selalu digambarkan dengan karakter maskulin:
keras rasional kompetitif, tegas, yang serba ―kotor‖ dan menakutkan sehingga
hanya pantas buat laki-laki. Implikasinya adalah perempuan menjadi terbelenggu
pada konstruksi sosial yang demikian dan pada akhirnya menyebabkan
perempuan terasing dalam polik dan lebih parahnya lagi banyak dari mereka
seakan a politis terhadap wilayah publik khususnya ranah politik.96
C. PPP dan Perolehan Suara Pada Pileg 2014 di DKI Jakarta
Pemilu tahun 2014 adalah pemilu yang ke 4 pasca reformasi pada tahun
1998. Dalam skala nasional pemilu ini diikuti oleh 11 partai politik namun tidak
semua partai politik yang ikut dalam pemilu ini lolos parliamentary tresshold
(PT). Terdapat dua partai yang tidak lolos PT yakni PBB dan PKPI karena jumlah
total suara nasional kedua partai ini tidak tembus lebih dari 2.5% suara sah
95
Wawancara dengan Hj. Marie Amadea Ismayani, S.Si. Ketua KPPI (kaukus
Perempuan Politik Indonesia) DKI Jakarta, Sekaligus mantan Anggota DPRD DKI
Jakarta 2009-2014 Fraksi Demokrat. Pada tanggal 12 Januari 2017. 96
Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya
Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia (Yogyakarta: KIBAR Press, 2007),
hal. 173
71
nasional, artinya kedua partai ini tidak berhak menempatkan wakilnya dalam
dewan legislatif pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pada Pileg DPRD DKI Jakarta terdapat 10 Dapil dari 5 Kota Administratif
dan 1 kabupaten yakni Kep. Seribu. Untuk kursi DPR pusat sendiri DKI Jakarta
mengirimkan 21 anggota legislatif yang berarti ada 7 Caleg yang lolos ke Senayan
di tiap Dapil yang terdiri dari tiga Dapil tersebut. Sementara itu untuk DPRD
DKI Jakarta sendiri terdapat 106 Caleg yang lolos untuk menjadi anggota dewan
untuk periode 2014-2019.
Sementara itu jika menyoal dengan representasi perempuan yang ada pada
daerah pemilihan di DKI Jakarta baik dalam pemilihan legislatif tingkat DPR
pusat dan DPRD provinsi kuantitasya lumayan baik. Artinya memang terdapat
30% atau lebih calon perempuan yang diajukan oleh partai.97
Hal ini sudah
termasuk cukup dan mengikuti persyaratan minimal pada UU No. 8 tahun 2012
tentang partai politik, tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak sampai 30%
representasi perempuan yang lolos ke DPR atau DPRD pada daerah pemilihan
DKI Jakarta.
UU No. 8 tahun 2012 hanya menyoal tentang batas minimal calon
legislatif perempuan yang 30% tetapi tidak dapat menjamin calon legislatif
perempuan yang lolos ke DPR ataupun DPRD sebesar 30% juga. Dari daerah
97
Lihat Tabel IV.A.1 tentang Prosentase Keterwakilan Perempuan Pada Tahap
Pencalonan Legislatif DPRD DKI Jakarta Pada tahun 2014-2019
72
pemilihan DKI Jakarta ada empat orang calon legislatif perempuan yang lolos
untuk menjadi anggota dewan di DPR, sedangkan untuk DPRD terdapat delapan
belas calon legislatif perempuan.
PPP bisa dibilang adalah partai yang cukup kuat di Jakarta, pasalnya pada
pemilu tahun 2009 PPP masih termasuk dalam lima besar partai pemenang di
Jakarta dengan raihan 7 kursi, begitupun dengan pemilu sebelumnya yakni pemilu
2004. PPP sama raihannya dengan Golkar yakni 7 kursi, jika dipetakan raihan
kursi PPP dari tahun 2004, 2009, dan 2014 memang mengalami kenaikan
walaupun tidak signifikan setidaknya raihan kursinya sampai tahun 2014 tidak
pernah turun dari angka 7.
Secara umum PPP di DPR mengalami kenaikan kursi yang cukup
signifikan dalam hal representasi perempuan di parlemen, lain lagi bila menarik
kasus yang sama dengan partai yang sama namun dengan cakupan yang berbeda
yakni provinsi, dalam hal ini provinsi DKI Jakarta. PPP hanya berhasil
menempatkan satu orang wakil perempuannya di DPRD, raihan ini memang lebih
baik dari Partai yang lain semisal NasDem, PKB, Golkar, PAN, dan Hanura yang
sama sekali tidak berhasil meloloskan calon perempuannya untuk duduk di kursi
DPRD. Berikut adalah calon legislatif yang lolos dari PPP;
73
Tabel IV.C.1
Caleg Terpilih PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019
Nama Daerah pemilihan No. Urut Jumlah Suara
Riano P. Ahmad, S.H. DKI Jakarta 1 2 11.069
H. Maman Firmansyah, S.H DKI Jakarta 2 1 10.999
Hj. Nina Lubena DKI Jakarta 4 7 5.358
Belly Bilalusalam, S.H. DKI Jakarta 5 1 28.251
Drs. H. Samsudin DKI Jakarta 5 10 7.683
H. Matnoor Tindoan, S.H. DKI Jakarta 6 1 27.009
H. Ichwan Zayadi, S.E. DKI Jakarta 7 2 9.068
H. Rendhika D Harsono, M.Sc DKI Jakarta 8 1 11.057
H. Usman Helmy, S.H. DKI Jakarta 9 2 7.451
H. Lulung AL, S.H. DKI Jakarta 10 1 28.038
Sumber: KPU DKI Jakarta
Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa; pertama, hampir sebagian besar
calon yang lolos adalah calon dengan nomor urut kecil hanya dua calon yang
lolos dengan nomor urut besar yakni Hj. Nina Lubena dari dapil empat dan Drs. H
Samsudin dari dapil lima, hal ini juga menandakan bahwa sebagian besar pemilih
PPP cenderung memilih berdasarkan nomor urut teratas, hal yang membuat
mereka terpilih tidak lain karena memiliki modal sosial yang kuat seperti yang
diutarakan oleh Arifuddin Halking;
74
Ya dia (Hj. Nina Lubena) punya masjid orang ini, dan memang suaminya
anggota DPR H. Sofyan Usman. Ya memang Majelis taklim sebagai
modal sosial di punya itu, punya majelis taklim artinya kan punya massa,
massa nya banyak bu Nina itu dan di rawat (koordinir) dan diperhatikan
dengan baik oleh dia, sehingga untuk modal sosial dia udah punya sebagai
caleg, kalau pak Syamsuddin itu kan dia dari Gerindra sekarang masuk
PPP dapat (kursi) dia karena punya duit, punya modal dan dia juga turun
(kampanye) ke bawah (masyarakat).98
Kedua, PPP tidak bisa meloloskan wakilnya pada dapil 3 yang melingkupi
tiga kecamatan yakni; kecamatan Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan
dengan total suara partai terendah dibanding dengan ke sembilan dapil yang lain
dengan 15.303 suara.
Ketiga, PPP meloloskan dua wakil sekaligus pada dapil 5, ini
menunjukkan bahwa dapil ini yakni wilayah Kecamatan Jatinegara, Duren Sawit,
dan Kramat Jati merupakan wilayah dengan basis massa pemilih PPP paling
banyak diantara 9 dapil yang lain dengan total suara 70.259 suara, di daerah ini
PPP hanya kalah dari PDI-Perjuangan. PPP di Jakarta Timur dan Jakarta selatan
menurut penuturan H. Arifuddin Halking adalah Dapil dengan kantong-kantong
suara PPP paling banyak dibanding Dapil lain di Jakarta, berikut kutipan
wawancara peneliti dengan narasumber;
Jakarta timur kan ada tiga dapil tapi empat kita dapat kursi. Iya memang
Jakarta timur ini semua lumbung suara PPP sebenarnya juga dengan dapil
di Jakarta selatan, Cuma kemarin kan selatan dua dapil kita dapat dua.
Jakarta selatan itu pada pemilu (1997) sebelum Orde Baru lengser menang
PPP kalah Golkar, itu Orde Baru masih berkuasa, bagaimana bukan basis?
98
Wawancara dengan Drs. H. Arifuddin Halking M. Si, Wakil Ketua Bidang
OKK DPW PPP Jakarta, 17 November di Kantor DPW PPP Jakarta, Buaran.
75
Keempat, calon perempuan yang lolos yakni Hj. Nina Lubena mendapat
suara paling kecil diantara 10 calon yang lolos tersebut dengan total suara 5.358.
Sebenarnya jika ditarik kembali kecilnya perolehan suara perempuan dalam hal
ini pada kasus PPP bisa terlihat dengan mengurutkan suara terkecil caleg per
dapil, hasilnya adalah terdapat tujuh caleg perempuan yang mendapat suara paling
kecil di tiap dapil yang ada di Jakarta tersebar dari dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 10
sedangkan tiga dapil diataranya yakni dapil 7, 8, dan 9 perolehan suara paling
minim dimiliki caleg laki-laki, hal ini menandakan kecilnya perolehan suara
perempuan memang benar adanya, setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh partai
PPP.
Tabel IV.C.2
Perbandingan Prosentase Jumlah Suara dan Kursi Perempuan Dalam Fraksi di
DPR RI dengan DPRD DKI Jakarta tahun 2014-2019
DPR
RI
DPRD DKI
Jakarta
no Partai Jumlah
kursi
partai
kursi
Perempuan
dalam
fraksi (%)
no Partai Jumlah
kursi
partai
Kursi
Perempuan
dalam
fraksi (%)
1 PDI-
Perjuangan
109 19 1 PDI-P 28 36
2 Golkar 91 17 2 Gerindra 15 27
3 Gerindra 73 25 3 PPP 10 10
4 Demokrat 61 21 4 PKS 11 18
5 PKB 47 21 5 Demokrat 10 20
6 PAN 49 18 6 Golkar 9 0
7 PKS 40 3 7 Hanura 10 0
8 NasDem 35 11 8 PKB 6 0
9 PPP 39 26 9 NasDem 5 0
10 Hanura 16 12 10 PAN 2 0
Sumber: Diolah dari data Puskapol UI dan KPU DKI Jakarta
76
Dari data di atas tersebut jelaslah bahwa raihan suara PPP yang minim di
tingkat nasional ternyata di sisi lain yakni keterwakilan perempuan memiliki
perolehan yang cukup baik bahkan perempuan PPP yang terbesar prosentasenya
dibanding partai lain, tetapi bila dibandingkan dengan raihan suara di DKI Jakarta
yang hampir mencapai 10% justru keterwakilan perempuannya minim, apalagi
jika disangkutkan dengan data bahwa PPP adalah partai yang paling banyak
mengirimkan wakil perempuan dalam tahap pencalonan sebanyak 36%.99
Bila ditelusuri lebih lanjut tentang caleg-caleg perempuan terpilih PPP
baik DPR RI maupun DPRD DKI Jakarta memang tidak bisa dilepaskan dari
temuan Puskapol UI yang menyatakan bahwa oligarki partai politik berperan
penting dalam terpilihnya calon-calon perempuan. Hal demikian juga bisa dilihat
dari partai PPP di DPR RI sendiri yang menunjukkan bahwa 6 dari 10 caleg yang
terpilih terindikasi merupakan kerabat dekat dari elit politik PPP nasional maupun
daerah.100
Pada DPRD DKI Jakarta sendiri satu-satunya perempuan terpilih dari
PPP juga menunjukkan indikasi demikian. Walaupun banyak dari mereka juga
berkarir dan menjadi kader sudah sejak lama di PPP namun tidak dipungkiri
bahwa kedekatan dengan elit partai membuat nilai lebih sendiri bagi mereka
99
Lihat Tabel IV.A.1 tentang Prosentase Keterwakilan Perempuan Pada Tahap
Pencalonan Legislatif DPRD DKI Jakarta Pada tahun 2014-2019 100
Indikasi Oligarki pada caleg terpilih perempuan PPP. Fatmawati Rusdi (Istri
Bupati Sidrap, Rusdi Masse), Kartikha Yudhisti (Putri Suryardhama Ali), Wardatul
Asriyah (Istri Suryadharma Ali), Ermalena (Staf Khusus Suryadharma Ali ketika
menjabat Menteri Koperasi&UKM 2004-2009 dan Menteri Agama 2009-2014), Irma
Narulita (Istri Dimyati Natakusuma), Nurhayati (Istri Suharso Monoarfa)
77
dibanding calon-calon perempuan lainnya yang tidak sama sekali memiliki
kedekatan dengan elit politik.
Membicarakan affirmative action dalam tubuh PPP peneliti menganalisis
wawancara peneliti dengan narasumber yakni Abdul Aziz sebagai ketua DPW
PPP DKI Jakarta, pertama-tama menurutnya ―afirmasi soal perempuan itu di
undang-undang paling tidak menjadi tindakan ―pemaksaan‖ buat partai,
pemaksaan dalam tanda kutip sehingga partai mau tidak mau harus mengikuti itu
(peraturan)‖101
memang afirmasi perempuan ini mempunyai kekuatan hukum atas
nama UU No. 8 tahun 2012 sehingga partai terpaksa bekerja keras untuk
memenuhi afirmasi perempuan tersebut, terlebih partai-partai yang memiliki basis
agama yang berorientasi tradisonal seperti PPP yang massanya cukup banyak.
Lebih lanjut Abdul Aziz memberikan kesan terhadap afirmasi perempuan ini
sebagai ―pemaksaan‖ berkonotasi positif untuk memberikan kesempatan kepada
perempuan berkiprah di politik secara langsung dalam pemilu.
Menurut Ani Soetjipto dalam bukunya Politik Bukan Gerhana: Esai-esai
pilihan 2005, membenarkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai
besar yang kesulitan untuk menjaring caleg perempuan,102
hal ini dimungkinkan
karena sejak awal partai ini menganggap isu keterwakilan adalah isu yang kurang
101
Wawancara dengan H. Abdul Aziz, SE. Ketua DPW PPP DKI Jakarta, 30
November 2016 102
Ani Widyani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-esai pilihan
(Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005) hal. 212
78
popular, sehingga bisa jadi partai ini tidak aware dengan isu-isu berbau gender,
PPP adalah partai Islam dengan visi-misi serta platform yang kental dan tak
terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, terlebih dalam awal pembetukannya PPP
adalah partai fusi dari golongan yang boleh dibilang tradisional, maka dari itu isu-
isu seperti kesetaraan gender dan sebagainya yang dianggap sebagai bentuk
pemordenisasian pemikiran kurang begitu mendapat tempat dalam tubuh PPP.
Kemudian untuk meningkatkan representasi perempuan dalam PPP juga
guna mengedukasi perempuan, PPP membuat banom (badan otonom) yang
khusus menjadi lokus bagi wanita bernama WPP (wanita persatuan
pembangunan) seperti yang disampaikan juga oleh Abdul Aziz bahwa ―WPP
memang di design untuk melakukan pembinaan pada perempuan di PPP, jadi kan
secara realistis perempuan perlu diberikan pendalaman secara khusus materi
pembinaan, kepemimpinan dan sebagainya, WPP itu wadah positif buat
pemberdayaan perempuan di PPP.‖103
Dalam hal pencalonan Abdul Aziz mengungkapkan bahwa tidak ada
perlakuan khusus sama sekali untuk tiap caleg baik perempuan maupun laki-laki,
―tidak ada perbedaan, tidak ada perlakuan khusus itu pertama, karena kita
mengangggap sama semuanya, laki dan perempuan kita harus samakan
103
Wawancara dengan H. Abdul Aziz, SE. Ketua DPW PPP DKI Jakarta, 30
November 2016
79
kualitasnya, dari segi kualitas kapabilitas dan seterusnya itu sama‖104
hal ini
menurut hemat penulis sangat disayangkan, mengingat ketertinggalan antara laki-
laki dan perempuan selama ini harusnya bisa dihilangkan dengan priviledge
khusus untuk perempuan selain pendidikan kepemimpinan dan karakter yang di
dapat lewat WPP, seharusnya partai dalam hal ini PPP secara sadar
memprioritaskan perempuan dalam nomor urut partai yg memakai zipper 3
banding satu, atau dengan membuat proporsi perempuan jauh diatas 30% dalam
daftar caleg, hal ini bisa dilakukan jika ada political will dari PPP terkait
affirmative action.
Kemudian ketika peneliti menanyakan tentang raihan perempuan di PPP
yang hanya satu kursi apakah suatu capaian yang memang diharapkan atau tidak,
Abdul Aziz menjawab bahwa
Kita berharap tetap ada 30% (perempuan) yang masuk yah, mestinya tiga
kan yah tetapi karena pemilihan langsung (proporsional terbuka) baru satu
yang masuk…. kita sih proporsional saja mas dari sepuluh orang ini
mestinya 30% persen yang jadi ya perempuan, karena sesuai kan dengan
afirmasi perempuan.105
Pernyataan tersebut menurut penulis cenderung paradoks mengingat upaya yang
dilakukan PPP dalam hal afirmasi perempuan umumnya hanya menitik beratkan
kepada peran WPP, dan upaya dari PPP umumnya hanya mengikuti mandat dari
undang-undang yang ―memaksa‖ dalam konotasi positif.
104
Wawancara dengan H. Abdul Aziz, SE. Ketua DPW PPP DKI Jakarta, 30
November 2016. 105
Wawancara dengan H. Abdul Aziz, SE.
80
Secara umum raihan suara PPP di DKI Jakarta dalam Pileg tingkat DPRD
lumayan besar, PPP menempati urutan ketiga perolehan suara di DKI Jakarta
dibawah PDI-Perjuangan dan Gerindra walaupun dalam raihan kursi PPP kalah
satu kursi dengan PKS yang menempati peringkat keempat dalam kuantitas kursi
di parlemen,106
tetapi raihan suara yang lumayan besar itu jika dianalisis lebih
lanjut akan didapati fakta bahwa suara banyak terpusat di caleg laki-laki, hal
tersebut menurut pandangan penulis tidak lepas dari basis pemilih PPP yang
kebanyakan diisi oleh pemilih tradisional seperti yang diungkapkan oleh
Arifuddin Halking dalam petikan wawancara ―.....PPP ini masih banyak massa
yang tradisional.....‖107
sehingga preferensinya menurut hemat penulis banyak
dipengaruhi oleh pertama agama, kedua patriarki, dan budaya setempat (dalam hal
ini Betawi), adapun peran atau upaya PPP dan WPP yang kurang maksimal
dalam rangka afirmasi perempuan juga penulis rasa turut memberikan andil
terhadap kecilnya suara perempuan PPP pada pileg DPRD DKI tahun 2014 ini.
106
Wawancara dengan H. Abdul Aziz, SE. Ketua DPW PPP DKI Jakarta, 30
November 2016. 107
Wawancara dengan Drs. H. Arifuddin Halking M. Si, Wakil Ketua Bidang
OKK DPW PPP Jakarta, 17 November di Kantor DPW PPP Jakarta, Buaran.
81
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Persoalan representasi perempuan di parlemen memang menjadi persoalan
yang, berlarut dan alot, affirmative action hadir pasca reformasi dengan
mensyaratkan partai menyertakan minimal 30% caleg perempuannya
untuk berkontestasi dalam pemilu. Hal tersebut dilaksanakan partai
dengan ogah-ogahan mengingat susahnya menjaring kader apalagi
perempuan untuk mau maju menjadi caleg pada pemilu legislatif. Dalam
penerapannya, kebijakan 30% caleg perempuan pada pemilu menunjukkan
terdapat peningkatan yang cukup berarti dalam hal kuantitas caleg di
parlemen, walaupun prosentasenya masih jauh dari 30% yang
diharapakan, tetapi setidaknya hal ini telah mendorong peningkatan minat
perempuan terhadap politik.
2. Berbicara tentang perolehan suara perempuan, budaya patriarki dan
stigma-stigma negatif pada perempuan dalam ruang politik rupanya masih
ditemui sebagai preferensi pemilih dalam pemilu 2014 di DKI Jakarta,
sehingga perolehan suara perempuan minim dan implikasinya adalah
sedikitnya perempuan yang masuk dalam parlemen sehingga tidak
mencapai 30% critical mass. Dimana angka 30% critical mass tersebut
82
mempunyai korelasi positif terhadap kebijakan-kebijakan yang akan
dikeluarkan nantinya akan pro terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
3. Tuntutan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pemilu sudah
dilaksanakan oleh PPP DKI Jakarta, hal itu juga sesuai anjuran JUKLAK
(Petunjuk Pelaksanaan) DPP PPP. Perempuan dalam PPP juga telah
diberikan tempat khusus untuk pengembangan dan pengedukasian dalam
politik yakni WPPP, setelah sebelumnya hanya menjadi lokus dari
departemen wanita pada masa Orde Baru. Namun hal itu semua dirasa
belum cukup, mengingat keterwakilan perempuan di Fraksi PPP DPRD
DKI Jakarta belum mencapai 30%, bahkan pada tahun 2009 PPP DKI
Jakarta tidak mempunyai wakil perempuan dalam DPRD. Hal ini
menandakan belum ada upaya yang optimal dan serius dari seluruh
stakeholder PPP dalam penigkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
B. Saran
1. Penerapan 30% minimal calon perempuan pemilu legislatif menemui
permasalahan ketika caleg perempuan yang terpilih tetap dibawah 30%.
Hal ini terjadi karena partai banyak menganggap 30% sebagai persyaratan
yang harus dilewati dengan cara normative. Sistem semi-zipper yang
mengharuskan minimal ada satu caleg perempuan di setiap tiga daftar
caleg sering dimaknai tekstual oleh partai politik, sehingga perempuan
sering ditempatkan pada nomor terakhir dalam semi-zipper tersebut,
83
padahal seharusnya perempuan mendapat prioritas pada nomor awal
dalam semi-zipper jika mengikuti affirmative action. Terlebih kontestan
pileg yang terlalu banyak juga akan menyulitkan perempuan dalam hal
keterpilihan. Penulis memberi solusi bahwa harus ada langkah yang
―radikal‖ untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik
secara signifikan dengan cara, mengubah semi-zipper menjadi zipper
murni yang akan membuat daftar caleg selang-seling antara laki-laki dan
perempuan dan susunannya horizontal (kiri-kanan), serta pembatasan
kontestan pileg, dengan pembatasan kontestan pileg akan membuat
peluang caleg perempuan untuk terpilih semakin besar.
2. Memberikan pendidikan sadar gender dalam masyarakat, pendidikan ini
harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya oleh partai dan
penyelenggara pemilu atau LSM yang concern terhadap pemilu dan
perempuan saja, tetapi masyarakat juga dituntut aktif untuk sadar gender,
bahwa perempuan juga bisa dan mampu berkecimpung dalam ruang-ruang
publik khususnya dalam ruang politik, sebagai lokus pembuatan kebijakan
baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.
3. Partai PPP harus menambah basis massa dari kalangan baru dan jangan
hanya terpaku pada basis tradisional saja. PPP juga harus mengintenskan
peran perempuan dalam pengambilan keputusan partai misalnya, dan
jangan hanya mengandalkan WPP sebagi lokus pengembangan dan
84
pemberdayaan perempuan saja, tetapi harus ditarik dalam kepengurusan
partai secara massif. Dalam hal keterwakilan perempuan, PPP DKI Jakarta
bisa menduplikasikan penempatan nomor urut di Dapil IV Jakarta yang
proporsinya 50:50 antara laki-laki dan perempuan ke semua Dapil yang
ada di Jakarta.
85
DAFTAR PUSTAKA
Adams, Ian, 2004. Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa
Depannya , Yogyakarta: Qalam.
Adeney, Bernard T. 2000 Etika Sosial Lintas Budaya, Yogyakarta: Pustaka
Kanisius.
Adji, M. Lina Meilinawati dan Baban banita. 2009. Perempuan Dalam Kuasa
Patriarki, laporan penelitian/Buku Fakultas Sastra Universitas Padjajaran.
Aritonang, Jan. S. 2004. Sejarah Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia, ,
Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Arivia, Gadis. 2006. Feminisme: Sebuah Kata Hati, Jakarta: Kompas.
A. Winters, Jeffrey. 2011. Oligarki , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Ballington, Julie., ed. 2002. Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah,
Jakarta: International Idea.
Budiardjo, Miriam. 2012. Cetakan kedua, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Dault, Adhyaksa. 2012. Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik,
Renungan Seorang Anak Bangsa. Jakarta: Renebook.
Djajanegara, Soenarjati. 2000. Kritik Sastra Feminisme: Sebuah Pengantar,
Jakarta: Gramdeia Pustaka Utama.
Fakih, Mansour. 1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Fauzia, Amelia. 2004. Tentang perempuan Islam: Gerakan dan Wacana, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Firmanzah. 2008. Marketing politik antara pemahaman dan realitas, Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Hanafie, Haniah dan Suryani. 2011. Politik Inonesia, Ciputat: Lemlit UIN Jakarta
86
Haris, Syamsuddin, ed. 2004 Pemilu Langsung Di tengah Oligarki Partai: proses
nominasi dan seleksi calon anggota legislatif Pemilu, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Hoodfaar, Homa dan Mona Tajali. 2011. Electoral Politics : Making Quota Work
For Women , London: WLUML.
Krook, Mona Lena. 2009. Quotas For Women in Politics : Gender and
Candidate Selection Reform Worldwide , New York : Oxford University
Press.
Lovenduski, Joni. 2008. Politik Berparas Perempuan , Yogyakarta: Kanisius.
Mujani, Saiful, Kuskridho Ambardi dan R William Liddle. 2012. Kuasa Rakyat:
Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan
Presiden Pasca-Orde Baru, Mizan Publika: Jakarta.
Mulia, Siti Musdah. 2007. Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya
Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia), Yogyakarta: KIBAR
Pres
Nurruzzaman, M. 2005. Kiai Husein Membela Perempuan, Yogyakarta: Pustaka
Pesantren.
Pramono, Sidik, ed., 2014. Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan
Kebijakan Afirmasi, Kemitraan partenership.
Robert Michels, Robert. 1984. Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam
Birokrasi, Jakarta: CV Rajawali.
Rokhmansyah, Alfian, 2016. Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman
Awal Kritik Sastra Feminisme, Yogyakarta: Garudhawaca.
Rosyidah, Ida dan Hermawati. 2003. Relasi Gender dalam Agama-Agama ,
Jakarta: UIN Jakarta Press.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama.
Subhan, Zaitunah. 2004. Perempuan Dan Politik Dalam Islam, Yogyakarta:
Pustaka Pesantren.
87
Tong, Rosemarie Putnam. 2004. Feminist Thought: Pengantar Paling
Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, Yogyakarta:
Jalasutra.
Walby, Sylvia. 1990. Theorizing Patriarchy, Oxford: Basil Blackwell Ltd.
Widyani Soetjipto, Ani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-esai
pilihan , Jakarta; Penerbit Buku Kompas.
Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta:
Media Pressindo.
Yuda, Hanta. 2010. Presdensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi ,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Zen, Fathurin. 2004. NU Politik: Analisis Wacana Media, Yogyakarta:LkiS.
Sumber Jurnal dan Website
Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 10 No. 1,
KOMUNIKA, Vol, 8 No. I, 2005. LIPI
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/06350171/PPP.dan.Islah.yang.Tak.S
empurna diunduh pada 14 Oktober 2016
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/27/15241031/Menkumham.Sahkan.Kep
engurusan.PPP.Hasil.Muktamar.Islah diunduh pada 14 Oktober 2016
http://ppp.or.id/page/ppp-dalam-lintasan-sejarah/index/ diunduh pada 18 Oktober
2016
http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/ diunduh pada 24 September 2016
www.puskapol.ui.ac.id/opini/menghadirkan-kepentingan-perempuan-dalam-
representasi-politik-di-indonesia.html diunduh pada 24 September 2016
http://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/analisis-perolehan-suara-dalam-
pemilu-2014-oligarki-politik-dibalik-keterpilihan-caleg-perempuan.html
diunduh pada 26 Mei 2016
88
Sumber Wawancara
Wawancara dengan Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perludem, Pegiat Isu-isu
keterwakilan Perempuan, 15 November 2016 jam 11:30-12:45, di Kantor
Perludem Tebet
Wawancara dengan Drs. H. Arifuddin Halking M. Si, Wakil Ketua Bidang OKK
DPW PPP Jakarta, 17 November di Kantor DPW PPP Jakarta, Klender.
Wawancara dengan H. Abdul Aziz, SE. Ketua DPW PPP DKI Jakarta, 30
November 2016.
Wawancara dengan Hj. Marie Amadea Ismayani S.Si, Ketua KPPI (Kaukus
Perempuan Politik Indonesia) DKI Jakarta, 12 Januari 2017