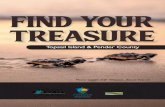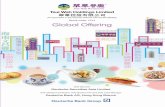KARAKTERISTIK PENDER DI RSUP Dr. WAH PERIODE ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of KARAKTERISTIK PENDER DI RSUP Dr. WAH PERIODE ...
KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDISITIS RAWAT INAP
DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO
PERIODE JANUARI
DIBAWAKAN DALAM RANGKA TUGAS KEPANITERAAN KLINIK
BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
ILMU KEDOTERAN KOMUNITAS
AGUSTUS 2013
KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDISITIS RAWAT INAP
DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2012
Oleh:
Muhammad Syahrir
C 111 06 108
Supervisor :
dr. Sri Asriyani, SpRad
DALAM RANGKA TUGAS KEPANITERAAN KLINIK
BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT-
ILMU KEDOTERAN KOMUNITAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013
SKRIPSI
AGUSTUS 2013
KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDISITIS RAWAT INAP
DALAM RANGKA TUGAS KEPANITERAAN KLINIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
Skripsi dengan judul
RAWAT INAP DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO PERIODE JANUARI
DESEMBER 2012 ” telah diperiksa, disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim
Penguji Skripsi Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu
Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Anggota I
(dr. Suryani Tawali, MPH
PANITIA SIDANG UJIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
Skripsi dengan judul “KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDISITIS
RAWAT INAP DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO PERIODE JANUARI
telah diperiksa, disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim
Penguji Skripsi Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran
Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada :
: Rabu, 21 Agustus 2013
: 13.00 WITA
: Ruang Seminar PB.662 IKM dan IKK FK Unhas
Ketua Tim Penguji :
(dr. Sri Asriyani, Sp.Rad)
Anggota Tim Penguji :
dr. Suryani Tawali, MPH)
Anggota II
(Dr. dr. Sri Ramadhani, M.Kes
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDISITIS
RAWAT INAP DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO PERIODE JANUARI -
telah diperiksa, disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim
Kedokteran
Ruang Seminar PB.662 IKM dan IKK FK Unhas
Dr. dr. Sri Ramadhani, M.Kes)
BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ILMU KEDOKTERAN KOMUNITAS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
“KARAKTERISTIK PENDERITA
WAHIDIN SUDIROHUSODO PERIODE JANUARI
TELAH DISETUJUI UNTUK DICETAK DAN DIPERBANYAK
BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DAN ILMU KEDOKTERAN KOMUNITAS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
Judul Skripsi :
KARAKTERISTIK PENDERITA APPENDISITIS RAWAT INAP DI RSUP Dr.
WAHIDIN SUDIROHUSODO PERIODE JANUARI - DESEMBER 2012
TELAH DISETUJUI UNTUK DICETAK DAN DIPERBANYAK
Makassar, Agustus 2013
Pembimbing
dr. Sri Asriyani, Sp.Rad
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
APPENDISITIS RAWAT INAP DI RSUP Dr.
DESEMBER 2012 ”
TELAH DISETUJUI UNTUK DICETAK DAN DIPERBANYAK
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul
“Karakteristik Penderita Appendisitis Rawat Inap di RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo Periode Januari - Desember 2012”. Penulisan skripsi ini dilakukan
dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas
kepaniteraan klinik di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran
Komunitas untuk mencapai gelar Dokter Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai
pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyususnan skripsi ini, sangatlah sulit
bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan
terimaasih kepada:
(1) Dr. Sri Asriyani, SpRad, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan
waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan
skripsi ini;
(2) Kepala Bagian dan staf pengajar Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu
Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Makassar;
(3) Kepala Bagian Rekam Medik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin
Sudirohusodo yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data
yang saya perlukan;
(4) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan
material dan moral; dan
(5) Teman-teman sesama koass yang telah banyak membantu saya dalam
menyelesaikan skripsi ini.
v
Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa
manfaat bagi pengembangan ilmu.
Makassar, Agustus 2013
Penulis
vi
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat
dan Ilmu Kedokteran Komunitas
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Skripsi, Agustus, 2013
Muhammad Syahrir, (C 111 06 108)
dr. Sri Asriyani, SpRad
Karakteristik Penderita Appendisitis Rawat Inap di RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo Periode Januari - Desember 2012
(xv + 94 Halaman + 13 Tabel + 39 Gambar + 1 Skema + 8 lampiran)
ABSTRAK
Latar Belakang : Appendisitis merupakan penyakiti nflamasi pada appendiks
vermiformis. Appendisitis merupakan salah satu dari banyak bedah emergensi
yang sering, dan merupakan salah satu penyebab nyeri perut paling sering.
Appendisitis dapat terjadi pada negara maju dan negara berkembang. Insidens di
negara maju lebih tinggi daripada di negara berkembang. Mungkin karena diet di
negara berkembang lebih tinggi serat daripada diet di negara maju. Appendisitis
dapat mengenai segala usia, mulai dari bayi, anak, dewasa, dan usia lanjut; baik
laki-laki maupun perempuan.
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan
desain penelitian deskriptif cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dalam
satu kurun waktu tertentu.yaitu periode Januari - Desember 2012 melalui
penggunaan rekam medik sebagai data penelitian. Metode pengambilan sampel
dengan menggunakan metode total sampling.
Hasil : Penelitian karakteristik penderita appendisitis didapatkan bahwa sebagian
besar penderita appendisitis berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang (57,4%),
pada kelompok umur 17 - 25 tahun dan 26 - 35 tahun, masing-masing sebanyak
16 orang (23,5%), dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 3 orang
(4,4%) dan tidak bekerja sebanyak 4 orang (5,9%). Sebagian besar penderita
vii
appendisitis terdapat pada klasifikasi klinis appendisitis akut sebanyak 67 orang
(98,5%), dengan gejala klinis khas sebanyak 40 orang (58,8%), dan tanda klinis
dengan ditemukan salah satu tanda klinis khas sebanyak 67 orang (98,5%). Tanda
klinis khas yang paling banyak ditemukan adalah nyeri tekan titik McBurney
sebanyak 66 orang (97,1%). Sebagian besar penderita appendisitis terdapat pada
hitung jumlah leukosit dengan hasil leukositosis sebanyak 57 orang (83,8%) dan
gambaran USG kesan appendisitis sebanyak 39 orang (57,4%), dengan skor
Alvarado 7 - 10 sebanyak 59 orang (86,8%). Sebagian besar penderita appendisitis
terdapat pada penatalaksanaan dengan appendektomi terbuka sebanyak 53 orang
(77,9%),dengan komplikasi tidak ada sebanyak 40 orang (58,8%).
Kata Kunci : Karakteristik, Appendisitis, Rawat Inap
viii
Department of Public Health
and Community Medicine
Faculty of Medicine, Hasanuddin University
Scription, August, 2013
Muhammad Syahrir, (C 111 06 108)
dr. Sri Asriyani, SpRad
Characteristics of Hospitalization Appendicitis Patient in Dr. Wahidin
Sudirohusodo Hospital Periode January - December 2012
(xv + 94 Pages + 13 Table + 39 Figure + 1 Schematic + 8 Attachment)
ABSTRACT
Background : Appendicitis is inflammatory disease of the appendix vermiformis.
Appendicitis is one of the many frequent surgical emergency, and is one of the
most frequent causes of abdominal pain. Appendicitis can occur in developed
countries and developing countries. The incidence is higher in developed
countries than in developing countries. Perhaps because of the diet in developing
countries higher fiber diet than in developed countries. Appendicitis can affect all
ages, ranging from infants, children, adults, and the elderly; both men and women.
Methods : This study was an observational study design using a descriptive cross-
sectional study. Data collection was conducted in the certain periode, is namely
the period January-December 2012 through the use of medical records as research
data. The sampling method using total sampling method.
Results : The study found that the characteristics of patients with appendicitis
most patients with appendicitis male sex as many as 39 people (57.4%), in the age
group 17-25 years and 26-35 years, respectively 16 persons (23.5 %), with the
level of university education as much as 3 person (4.4%) and did not work as
much as 4 people (5.9%). Most people with appendicitis present in the clinical
classification of acute appendicitis were 67 men (98.5%), with the typical clinical
symptoms of 40 people (58.8%), and clinical signs found one with typical clinical
ix
signs as many as 67 people (98, 5%). Typical clinical signs are most commonly
found are the McBurney point tenderness as many as 66 people (97.1%). Most
people with appendicitis present in the leukocyte count leukocytosis result as
many as 57 people (83.8%) and ultrasound picture of appendicitis suggests as
many as 39 people (57.4%), with the Alvarado score 7-10 were 59 men (86.8% ).
Most people are on the management of appendicitis with open appendectomy as
many as 53 people (77.9%), with no complications by 40 people (58.8%).
Keywords : Characteristics, Appendicitis, Hospitalization
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... iii
KATA PENGANTAR ................................................................................. iv
ABSTRAK .................................................................................................. vi
ABSTRACT ................................................................................................ viii
DAFTAR ISI ............................................................................................... x
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiv
DAFTAR SKEMA ...................................................................................... xvi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xvii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................. 1
1.2. Rumusan Masalah ............................................................ 3
1.3. Tujuan Penelitian .............................................................. 3
1.4. Manfaat Penelitian ............................................................ 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 6
2.1. Appendiks Vermiformis ................................................... 6
2.2. Appendisitis ..................................................................... 13
BAB III KERANGKA KONSEP ............................................................. 40
3.1. Dasar Pemikiran Variabel ................................................. 40
3.2. Kerangka Konsep ............................................................. 45
3.3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif ........................ 46
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN ................................................. 54
4.1. Desain Penelitian .............................................................. 54
4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................ 54
4.3. Populasi dan Sampel ......................................................... 55
4.4. Jenis Data dan Instrumen Penelitian .................................. 56
4.5. Manajemen Penelitian ...................................................... 56
xi
4.6. Etika Penelitian ................................................................ 57
BAB V GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr.
WAHIDIN SUDIROHUSODO ................................................. 58
5.1. Identitas Badan Layanan Umum RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo .................................................................... 58
5.2. Sejarah Berdirinya RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ....... 59
5.3. Visi dan Misi RSUP Wahidin Sudirohusodo ..................... 60
BAB VI HASIL PENELITIAN ............................................................... 62
6.1. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Jenis Kelamin ................................................................... 62
6.2. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Umur ................................................................................ 63
6.3. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Tingkat Pendidikan ........................................................... 65
6.4. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Pekerjaan .......................................................................... 66
6.5. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Klasifikasi Klinis .............................................................. 67
6.6. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Gejala Klinis ..................................................................... 69
6.7. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Tanda Klinis ..................................................................... 70
6.8. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Hitung Jumlah Leukosit .................................................... 72
6.9. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Gambaran USG ................................................................ 73
6.10. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Skor Alvarado .................................................................. 74
6.11. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Penatalaksanaan ................................................................ 76
xii
6.12. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Komplikasi ....................................................................... 77
BAB VII PEMBAHASAN ........................................................................ 79
7.1. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Jenis
Kelamin ............................................................................ 79
7.2. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Umur ... 80
7.3. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Tingkat
Pendidikan ........................................................................ 81
7.4. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan
Pekerjaan .......................................................................... 82
7.5. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan
Klasifikasi Klinis .............................................................. 82
7.6. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Gejala
Klinis ................................................................................ 83
7.7. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Tanda
Klinis ................................................................................ 84
7.8. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Hitung
Jumlah Leukosit ............................................................... 85
7.9. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan
Gambaran USG ................................................................ 86
7.10. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Skor
Alvarado ........................................................................... 87
7.11. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan
Penatalaksanaan ................................................................ 88
7.12. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan
Komplikasi ....................................................................... 88
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 90
8.1. Kesimpulan ...................................................................... 90
8.2. Saran ................................................................................ 90
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 92
LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 6.1. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Jenis Kelamin ........................................................................ 62
Tabel 6.2. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Umur ..................................................................................... 64
Tabel 6.3. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Tingkat Pendidikan .............................................................. 65
Tabel 6.4. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Pekerjaan .............................................................................. 67
Tabel 6.5. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Klasifikasi Klinis .................................................................. 68
Tabel 6.6. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Gejala Klinis ......................................................................... 69
Tabel 6.7.1. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Tanda Klinis .......................................................................... 70
Tabel 6.7.2. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Tanda Klinis Khas ................................................................. 70
Tabel 6.8. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Hitung Jumlah Leukosit ........................................................ 72
Tabel 6.9. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Gambaran USG ..................................................................... 73
Tabel 6.10. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Skor Alvarado ....................................................................... 75
Tabel 6.11. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Penatalaksanaan .................................................................... 76
Tabel 6.12. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Komplikasi ............................................................................ 77
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Anatomi sistem digestif ......................................................... 6
Gambar 2 Anatomi Appendiks vermiformis .......................................... 7
Gambar 3 Variasi arteri sekalis dan appendikularis ................................ 9
Gambar 4 Vena usus halus dan colon .................................................... 10
Gambar 5 Pembuluh limfe dan kelenjar getah bening kolon .................. 11
Gambar 6 Histologi appendiks vermiformis ........................................... 12
Gambar 7 Histologi appendiks vermiformis ........................................... 13
Gambar 8 Letak appendiks vermiformis ................................................ 19
Gambar 9 Perjalanan appendisitis .......................................................... 20
Gambar 10 Nyeri yang berpindah dari regiou mbilikus keregioi liaka
kanan pada appendisitis ......................................................... 21
Gambar11 Persepsi nyeri viseral terlokalisasi di regio epigastrium,
umbilkus atau suprapubik sesuai dengan asal embriogenik
organ yang mengalami kelainan ............................................ 23
Gambar 12 Kronologi peristiwa yang terlibat dalam terjadinya demam ... 24
Gambar 13 Nyeri tekan titik McBurney pada appendisitis ....................... 25
Gambar 14 Tanda appendisitis ................................................................. 26
Gambar 15 Tanda Psoas pada appendisitis ............................................... 27
Gambar 16 Tanda Obturator pada appendisitis ........................................ 28
Gambar 17 Pemeriksaan USG pada appendisitis menunjukkan sekum dan
appendiks dengan dinding tebal yang berisi cairan ................ 29
Gambar 18 Pemeriksaan CT scan pada appendisitis menunjukkan
dinding appendiks dilatasi dan menebal ................................. 29
Gambar 19 Insisi pada appendektomi terbuka .......................................... 31
Gambar 20 Insisi Grid Iron ...................................................................... 32
Gambar 21 Insisi Rutherford Morisson .................................................... 32
Gambar 22 Insisi transversal Lanz ........................................................... 33
Gambar 23 Insisi low midline .................................................................. 34
Gambar 24 Insisi paramedian dekstra ...................................................... 34
xv
Gambar 25 Teknik appendektomi terbuka ............................................... 35
Gambar 26 Insisi pada appendektomi terbuka .......................................... 37
Gambar 27 Teknik appendektomi laparoskopi ......................................... 37
Gambar 28 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
jenis kelamin ......................................................................... 63
Gambar 29 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
kelompok umur ..................................................................... 64
Gambar 30 Diagram pie persentase penderita appendisitis berdasarkan
tingkat pendidikan ................................................................. 66
Gambar 31 Diagram pie persentase penderita appendisitis berdasarkan
pekerjaan ............................................................................... 67
Gambar 32 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
klasifikasi klinis .................................................................... 68
Gambar 33 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
gejala klinis ........................................................................... 69
Gambar 34 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
tanda klinis ............................................................................ 71
Gambar 35 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
hitung jumlah leukosit ........................................................... 72
Gambar 36 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
gambaran USG ....................................................................... 74
Gambar 37 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
skor Alvarado ........................................................................ 75
Gambar 38 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
penatalaksanaan .................................................................... 76
Gambar 39 Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan
komplikasi ............................................................................ 78
xvi
DAFTAR SKEMA
3.2 Kerangka Konsep ............................................................................... 45
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 Halaman Persetujuan Seminar Proposal Penelitian
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis - Pelayanan Perizinan
Terpadu kepada Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Lampiran 4 Surat Persetujuan Izin Penelitian di RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo
Lampiran 5 Halaman Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
Lampiran 6 Riwayat Hidup Penulis
Lampiran 7 Kuesioner
Lampiran 8 Data Sekunder
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Appendisitis merupakan salah satu dari banyak bedah emergensi yang
sering, dan merupakan salah satu penyebab nyeri perut paling sering. Insidens
appendisitis di negara maju lebih tinggi daripada di negara berkembang.
Appendisitis dapat ditemukan pada semua umur. Di Amerika Serikat, 250.000
kasus appendisitis dilaporkan setiap tahun. Insidens appendisitis tiap tahun 10
kasus setiap 100.000 populasi. Appendisitis terjadi pada 7% populasi Amerika
Serikat, dengan insidens 1.1 kasus setiap 1000 orang setiap tahun.1
Di Amerika Serikat appendisitis pada anak memiliki insidens 70.000 kasus
setiap tahun. Insidens antara bayi baru lahir dan 4 tahun 1 - 2 kasus setiap 10.000
anak setiap tahun. Insidens meningkat menjadi 25 kasus setiap 10.000 anak setiap
tahun antara 10 - 17 tahun. Perbandingan laki-laki : perempuan sekitar 2 : 1.2
Di negara-negara Asia dan Afrika, insidens appendisitis akut mungkin lebih
rendah karena kebiasaan diet penduduk negara georafik ini. Insidens appendisitis
lebih rendah pada kebiasaan pola hidup dengan intak diet serat tinggi. Serat diet
diperkirakan menurunkan viskositas feses, menurunkan transit time kolon, dan
menghambat pembentukan fekalit, yang mempredisposisi seseorang mengalami
obstruksi pada lumen appendiksnya.1
Appendisitis terjadi pada semua kelompok umur tetapi jarang pada
bayi.Appendisitis paling sering pada kehidupan dekade kedua (umur 10 - 19
tahun), terjadi 23.3 kasus setiap 10.000 kasus setiap tahun. Kemudian insidens
terus menurun, walaupun appendisitis terjadi pada dewasa dan sampai usia tua.2
Insidens appendisitis meningkat secara perlahan sejak lahir, puncaknya pada
akhir belasan tahun, dan menurun secara perlahan pada usiageriatrik. Usia rata-
rata ketika appendisitis terjadi pada populasi pediatrik 6 - 10 tahun. Hiperplasia
limfoid ditemukan lebih sering diantara bayi dan dewasa dan terlibat dalam
peningkatan insidens appendisitis pada kelompok umur ini.1
2
Menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 2006, appendisitis
menempati urutan keempat penyakit terbanyak di Indonesia setelah dispepsia,
gastritis dan duodenitis, dan penyakit sistem cerna lain dengan jumlah pasien
rawat inap sebanyak 28.040.3
Di Indonesia insidens appendisitis pada bayi, 80 - 90% appendisitis baru
diketahui setelah terjadi perforasi. Anak kurang dari 1 tahun jarang dilaporkan.
Bayi dan anak < 2 tahun1% atau kurang. Anak 2 - 3 tahun 15%. Anak 5 tahun ke
atas frekuensi mulai meningkat dan mencapai puncaknya pada usia 9 - 11 tahun.
Insidens tertinggi pada kelompok umur 20 - 30 tahun. Insidens pada laki-laki dan
perempuan umumnya sama, kecuali pada kelompok umur 20 - 30 tahun, laki-laki
lebih tinggi.4,5
Diagnosis harus ditegakkan sedini mungkin dan penatalaksanaan harus
dilaksanakan secara cepat dan tepat untuk menghindari terjadinya komplikasi
berupa perforasi dengan segala akibatnya.4
Pada penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sejak 1
Februari sampai 30 September 2004 diperoleh 97 sampel penderita, terdiri dari 44
perempuan (45,4%) dan 53 laki-laki (54,6%), berumur 16 - 56 tahun. Kelompok
umur 16 - 30 tahun merupakan kelompok umur terbanyak (76,3%). Pada
umumnya mempunyai tingkat pendidikan SLTA ke atas dan sebagian (53,6%)
tidak bekerja.6
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan rumah sakit pendidikan bagi
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tentunya memiliki data rekam
medik yang lengkap yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan
penelitian. Selain itu, RSUP Dr. Wahidin merupakan rumah sakit pusat rujukan
bagi Indonesia bagian Timur sehingga dapat dilakukan penelitian untuk
mengetahui distribusi penyakit yang terdapat di Indonesia bagian Timur ini. Oleh
karena itu, peneliti memilih RSUPDr. Wahidin Sudirohusodo sebagai lokasi
penelitian.
3
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Karakteristik penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo periode Januari - Desember 2012”.
1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. WahidinSudirohusodo Periode Januari - Desember 2012.
1.3.2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan jenis kelamin.
b. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan umur.
c. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan tingkat pendidikan.
d. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan pekerjaan.
e. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan klasifikasi klinis.
4
f. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan gejala klinis.
g. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan tanda klinis.
h. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan hitung jumlah leukosit.
i. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan gambaran USG.
j. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan skor Alvarado.
k. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan penatalaksanaan.
l. Untuk mengetahui distribusi penderita appendisitis rawat inap di Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012 berdasarkan komplikasi.
1.4. Manfaat Penelitian
a. Bagi peneliti : Menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal
appendisitis.
b. Bagi peneliti selanjutnya : Sebagai referensi, melanjutkan atau memperbaiki
penelitian yang telah dilakukan.
c. Bagi klinisi : Sebagai acuan dalam hal melakukan diagnostik dan terapeutik.
5
d. Bagi instansi terkait:
1. Fakultas Kedokteran : Sebagai pengabdian kepada masyarakat,
menambah jumlah penelitian, sebagai referensi untuk penelitian
selanjutnya.
2. Rumah Sakit : Sebagai data administrasi tahunan, meningkatkan
upaya pelayanan kesehatan dalam hal promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.
3. Dinas Kesehatan : Sebagai data administrasi tahunan, meningkatkan
upaya pelayanan kesehatan dalam hal promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.
e. Masyarakat : Meningkatkan upaya kesehatan dalam hal preventif sehingga
dapat mewujudkan Indonesia Sehat.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Appendiks Vermiformis
2.1.1. Anatomi Appendiks Vermiformis
Sistem pencernaan manusia (sistem digestif) terdiri atas saluran pencernaan
(saluran alimentari) dan organ digestif asesori. Saluran pencernaan dimulai dari
kavum oris, faring, esofagus, gaster, intestinum tenue (duodenum, jejunum, dan
ileum), intestinum mayor (sekum yang bersambung dengan appendiks
vermiformis, kolon asendens, kolon transversum, kolon desenden, kolon
sigmoid), rektum, dan anus. Organ digestif asesori terdiri dari gigi, lidah, kelenjar
saliva, hati, kandung empedu, pankreas.7
Gambar 1. Anatomi sistem digestif
Dikutip dari kepustakaan 7
Appendis vermiformis terletak pada permukaan posteromedial sekum.
Appendiks vermiformis memiliki bentuk seperti cacing, sehingga disebut
7
appendiks vermiformis. Tiga taenia coli bertemu pada persambungan sekum
dengan appendiks. Appendiks vermiformis memiliki ukuran bervariasi, mulai dari
yang terkecil kurang dari 1 cm sampai yang terbesar lebih dari 30 cm, tetapi
ukuran rata-ratanya sekitar 6 - 9 cm.7,8
Gambar 2. Anatomi Appendiks vermiformis
Dikutip dari kepustakaan 9
Appendiks vermiformis merupakan organ imunologik yang ikut serta dalam
sekresi immunoglobulin, terutama immunoglobulin A (IgA). Walaupun appendiks
merupakan komponen dari sistem gut-associated lymphoid tissue (GALT),
fungsinya tidak penting.8
2.1.2. Inervasi Appendiks Vermiformis
Apendiks vermiformis diinervasi oleh saraf Th. 10, sama dengan inervasi
saraf somatik pada kulit yang melingkupi umbikus. Appendiks vermiformis dan
peritoneum viseral yang menutupinya diinervasi oleh saraf simpatis dan
parasimpatis dari pleksus mesenterikus superior. Saraf afferent viseral yang
membawa sensasi distensi dan tekanan memediasi gejala nyeri yang dirasakan
selama tahap awal inflamasi appendiks vermikularis. Sama dengan struktur
lainnya yang berasal dari midgut, sensasi ini awalnya dirasakan samar-samar, dan
8
dirasakan di daerah pusat (periumbilikus) abdomen. Hal itu tidak hingga jaringan
parietal yang berbatasan dengan appendiks vermiformis menjadi terlibat dalam
setiap proses inflamasi dimana nosiseptor somatik terstimulasi, dan terdapat suatu
perubahan yang berkaitan dalam hal sifat dan lokasi nyeri.10,11
2.1.3. Vaskularisasi Appendiks Vermiformis
2.1.3.1. Arteri
Cabang arteri mesenterika superior, antara lain:12
a. Arteri pankreatikoduodenal inferior
1. Cabang anterior
2. Cabang posterior
b. Cabang jejunal dan ileal
Vasa recta
c. Arteri ileokolika
1. Cabang superior
2. Cabang inferior
3. Arteri kolika asenden
4. Arteri sekalis anterior dan posterior
5. Arteri appendikularis
6. Cabang ileal
d. Arteri kolika dekstra
1. Cabang asenden
2. Cabang desenden
e. Arteri kolika media
1. Cabang dekstra
2. Cabang sinistra
Arteri appendikularis utama, cabang dari bagian bawah arteri ileokolika,
berjalan di belakang ileum terminal dan masuk mesoappendiks jarak dekat dari
9
pangkal appendiks. Di sini memberikan cabang rekuren, yang beranastomosis
pada pangkal appendiks dengan cabang arteri sekalis posterior: anastomosis
kadang-kadang luas. Arteri appendikularis utama mendekati ujung organ, awalnya
berada di dekat, kemudian di tepi, mesoappendiks. Bagian ujung arteri berada
pada dinding appendiks dan dapat menjadi trombosis pada appendisitis, yang
berakibat gangren atau nekrosis di distal. Arteri asesoris sering didapatkan, dan
banyak orang memiliki dua atau lebih arteri yang memperdarahi appendiks
vermikularis.11
Gambar 3. Variasi arteri sekalis dan appendikularis
Dikutip dari kepustakaan 13
10
2.1.3.2. Vena
Appendiks vermiformis dialiri melalui satu atau lebih vena appendikularis
ke vena sekalis posterior atau vena ileokolika dan kemudian ke vena mesenterika
superior.11
Gambar 4. Vena usus halus dan colon
Dikutip dari kepustakaan 13
2.1.3.3. Pembuluh limfe
Pembuluh limfe pada appendiks vermiformis banyak, terdapat banyak
jaringan limfoid di dindingnya.Pada korpus dan apeks appendiks 8 - 15 pembuluh
darah berjalan ke atas pada bagian mesoappendiks, dan kadang-kadang terputus
11
oleh satu atau lebih kelenjar limfe. Pembuluh limfe tersebut bergabung
membentuk tiga atau empat pembuluh yang lebih besar yang berjalan ke dalam
pembuluh limfe yang mengaliri kolon asenden, dan berakhir di kelenjar limfe
rantai ileokolika inferior dan superior.11
Gambar 5. Pembuluh limfe dan kelenjar getah bening kolon
Dikutip dari kepustakaan 13
2.1.4. Histologi Appendiks Vermiformis
Dinding usus besar berbeda dengan usus halus.Mukosa kolon merupakan
epitel kolumnar sederhana. Karena sebagian besar makanan diabsorpsi sebelum
mencapai usus besar, tidak terdapat lipatan sirkuler, tidak ada vili, dan hampir
tidak ada sel yang mensekresi enzim pencernaan. Akan tetapi, mukosanya lebih
12
tebal, kriptenya yang banyak lebih dalam, dan terdapat jumlah sel goblet yang
banyak pada kripte. Mukus yang dihasilkan oleh sel goblet memudahkan
perjalanan feses dan melindungi dinding usus dari iritasi asam dan gas yang
dilepaskan oleh bakteri yang hidup di kolon.7
Dinding appendiks vermiformis sesuai dengan dinding kolon. Dinding
appendiks disusun oleh:7
a. Lapisan serosa
b. Lapisan otot
Lapisan otot disusun oleh lapisan otot longitudinal dan sirkuler. Pada
pangkal appendiks, otot longitudinal membuat suatu penebalan yang
berhubungan dengan semua taenia sekum.
c. Lapisan submukosa
Lapisan submukosa berisi banyak sekumpulan jaringan limfoid.
d. Lapisan mukosa
Gambar 6. Histologi appendiks vermiformis
Dikutip dari kepustakaan 7
13
Gambar 7. Histologi appendiks vermiformis
Dikutip dari kepustakaan 9
2.1.5. Fisiologi Appendiks Vermiformis
Appendiks vermiformis memiliki massa jaringan limfoid, dan sebagai
bagian dari mucosa associated lymphoid tissue (MALT). Jaringan limfoid ini
memainkan peran penting dalam imunitas tubuh. Akan tetapi, appendiks
vermiformis memiliki kelemahan struktur yang penting. Struktur melengkungnya
memungkinan suatu lokasi ideal bagi bakteri enterik untuk berakumulasi dan
bermultiplikasi.7
2.2. Appendisitis
2.2.1. Definisi
Appendisitis merupakan penyakit inflamasi pada appendiks vermiformis.
Appendisitis dapat mengenai segala usia, mulai dari bayi, anak, dewasa, dan usia
lanjut; baik laki-laki maupun perempuan.1,2,10
14
2.2.2. Epidemiologi
Appendisitis merupakan penyakit inflamasi pada appendiks vermiformis.
Appendisitis ini dapat menyerang siapa saja. Insidens appendisitis di negara maju
lebih tinggi daripada di negara berkembang. Appendisitis merupakan salah satu
dari banyak bedah emergensi yang sering, dan merupakan salah satu penyebab
nyeri perut paling sering.1
Di Amerika Serikat, 250.000 kasus appendisitis dilaporkan setiap tahun.
Insidens appendisitis tiap tahun 10 kasus setiap 100.000 populasi. Appendisitis
terjadi pada 7% populasi Amerika Serikat, dengan insidens 1.1 kasus setiap 1000
orang setiap tahun.1
Sedangkan di negara-negara Asia dan Afrika, insidens appendisitis akut
mungkin lebih rendah karena kebiasaan diet penduduk negara georafik ini.
Insidens appendisitis lebih rendah pada kebiasaan pola hidup dengan intak diet
serat tinggi. Serat diet diperkirakan menurunkan viskositas feses, menurunkan
transit time kolon, dan menghambat pembentukan fekalit, yang mempredisposisi
seseorang mengalami obstruksi pada lumen appendiksnya.1
Appendisitis dapat mengenai laki-laki dan perempuan. Insidens pada laki-
laki dan perempuan umumnya sama, kecuali pada kelompok umur 20 - 30 tahun,
laki-laki lebih tinggi.4,5
Di Indonesia insidens appendisitis pada bayi, 80 - 90% appendisitis baru
diketahui setelah terjadi perforasi. Anak kurang dari 1 tahun jarang dilaporkan.
Bayi dan anak < 2 tahun1% atau kurang.2 - 3 tahun 15%. 5 tahun ke atas
frekuensi mulai meningkat dan mencapai puncaknya pada usia 9 - 11 tahun.
Insidens tertinggi pada kelompok umur 20 - 30 tahun. Morbiditas dan mortalitas
appendisitis sesuai dengan umur. Semakin tinggi umur seseorang maka morbiditas
dan mortalitasnya meningkat.4,5
Tingkat pendidikan dapat menggambarkan seberapa besar pengetahuan dan
perhatian seseorang dalam menjaga kesehatannya. Hal ini dapat menggambarkan
cepat lambatnya seseorang untuk memeriksakan diri ke tempat pelayanan
kesehatan jika mendapatkan adanya gejala dan tanda penyakit pada tubuhnya.5
15
Pekerjaan mempengaruhi pola hidup seseorang setiap hari, termasuk pola
makan. Penelitian epidemiologi menunjukkan peranan pola kebiasaan makan
makanan rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya appendisitis.5
Pada penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sejak 1
Februari sampai 30 September 2004 diperoleh 97 sampel penderita, terdiri dari 44
perempuan (45,4%) dan 53 laki-laki (54,6%), berumur 16 - 56 tahun. Kelompok
umur 16 - 30 tahun merupakan kelompok umur terbanyak (76,3%). Pada
umumnya mempunyai tingkat pendidikan SLTA ke atas dan sebagian (53,6%)
tidak bekerja.5,6
Appendisitis dapat terjadi berupa appendisitis akut maupun kronik.
Appendisitis kronik jarang terjadi. Keberadaan appendisitis kronik sebagai suatu
kumpulan penyakit yang benar ada telah dipertanyakan selama beberapa tahun.
Meskipun data klinis yang terbaru membuktikan keberadaan penyakit yang jarang
ini. Pada appendisitis kronik, beberapa pasien mengalami nyeri perut persisten.
pasien tidak mengalami gejala khas apendisitis akut. Justru, pasien mengalami
nyeri perut kanan bawah selama mingguan sampai tahunan. dan mungkin telah
mendapatkan berbagai pengobatan. Diagnosis dapat sulit, karena pemeriksaan
laboratorium dan radiologi secara khas normal. Karena diagnosis preoperatif
sering tidak jelas, maka laparoskopi dapat menjadi peralatan berguna untuk
memungkinkan eksplorasi abdomen.8,14
Appendisitis dapat menimbulkan gejala yang bervariasi. Gejala klinis khas
dari appendisitis adalah adanya nyeri di daerah umbilikus yang bersifat samar dan
tumpul. Kemudian beberapa jam nyeri berpindah ke kuadaran kanan bawah,
tepatnya titik McBurney. Sifatnya nyerinya menjadi jelas dan tajam. Ini terjadi
pada 66% pasien appendisitis. Anoreksia merupakan gejala awal sebelum timbul
nyeri perut pada 95% pasien appendisitis. Muntah terjadi pada 75% pasien
appendisitis.5,8,15
Kadang appendisitis tidak menimbulkan gejala nyeri perut kuadran kanan
bawah yang didahului nyeri umbilikus, tetapi timbul dengan gejala konstipasi.Hal
ini sering menjadikan dokter untuk memberikan obat pencahar. tindakan ini
16
berbahaya karena bisa mempermudah terjadinya perforasi appendiks dengan
segala konsekuensinya.5
Appendisitis dapat menimbulkan tanda yang bervariasi. Tanda klinis khas
dari appendisitis adalah nyeri tekan titik McBurney, nyeri ketok titik McBurney,
tanda Rovsing, tanda Blumberg, tanda Psoas, dan tanda Obturator. Tanda klinis
dari appendisitis tergantung dari letak appendiks yang meradang. Letak
appendiks, antara lain pelvik 21%, preileal 1%, postileal 5%, subsekal 1,5%,
retrosekal 74%, parasekal 2%. Ini menunjukkan bahwa tanda psoas lebih sering
didapatkan dalam praktek sehari-hari.5,16
Appendisitis dapat menunjukkan hitung jumlah leukosit normal atau
meningkat. Pasien appendisitis umumnya mengalami leukositosis, yaitu jumlah
leukosit > 10.000/mm3. Peningkatan leukosit dalam darah menunjukkan adanya
proses infeksi dalam tubuh. Pada appendisitis, leukosit akan bermigrasi dari
lumen pembuluh darah ke tempat yang mengalami peradangan untuk memfagosit
agen-agen infeksi. Penelitian yang dilakukan oleh Kamran10 di Pakistan,
menyimpulkan bahwa jumlah leukosit dapat membantu dokter dalam
mendiagnosis apendisitis. Penelitian yang dilakukan oleh Krishnan 11 di Rumah
Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, menunjukan terdapat leukositosis
pada 73,7% pasien apendisitis.3,8,10
Appendisitis dapat menunjukkan gambaran USG spesifik seperti dinding
appendiks yang dilatasi dan menebal, dan tidak spesifik. Diagnosis appendisitis
melalui pemeriksaan USG dilaporkan memiliki sensitivitas 55 sampai 96% dan
spesifisitas 85 sampai 98%. Hasil negatif palsu dapat terjadi jika appendisitis
terbatas pada ujung appendiks, lokasi appendiks retrosekal, appendiks membesar
dan dikira usus halus, atau jika appendiks perforasi dan sebab itu appendiks yang
meradang dapat dikempiskan.8
Diagnosis appendisitis akut tidak mudah ditegakkan hanya berdasarkan
gambaran klinis. Keadaan ini menghasilkan angka appendektomi negatif sebesar
20% dan angka perforasi sebesar 20-30%. Salah satu upaya meningkatkan
kuantitas dan kualitas pelayanan medis ialah membuat diagnosis yang tepat. Telah
banyak dikemukakan cara untuk menurunkan insidensi appendektomi negatif,
17
salah satunya adalah dengan instrumen skor Alvarado. Skor Alvarado adalah
sistem skoring sederhana yang bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan kurang
invasif. Morbiditas dan mortalitas appendisitis akut masih cukup tinggi. Hal ini
disebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan pembedahan.17
Penatalaksanaan appendisitis dapat berupa konservatif atau bedah. Bedah
dapat dilakukan dengan appendektomi terbuka atau appendektomi laparoskopi.
Sejak era post-antibiotik, Coldrey mempresentasikan penelitian retrospektifnya
pada 471 pasien dengan appendisitis yang diobati dengan antibiotik. Pengobatan
ini gagal pada sekurang-kurangnya 57 pasien, dengan 48 membutuhkan
appendektomi dan 9 membutuhkan drainase akibat abses appendiks.14
Komplikasi appendisitis dapat berupa perforasi atau abses appendiks.
Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah perforasi, baik berupa perforasi
dengan atau tanpa adanya walling off. Walling off terbentuk dari appendiks,
sekum, usus halus dan omentum. Perforasi juga bisa disertai atau tanpa disertai
dengan peritonitis generalisata.5
Adanya fekalit di dalam lumen, umur (orang tua atau anak kecil), dan
keterlambatan diagnosis, merupakan faktor yang berperan dalam terjadinya
perforasi appendiks. Massa appendiks terjadi bila appendisitis gangrenosa atau
mikroperforasi tertutupi atau terbungkus oleh omentum dan atau lekuk usus
halus.5
2.2.3. Etiologi
Appendisitis terjadi akibat dari sumbatan (sering akibat feses) yang
membawa bakteri infeksius ke dalam lumen appendiks vermiformis. Karena
appendiks tidak dapat mengosongkan isi lumennnya, maka appendiks
membengak, menekan drainase pembuluh darah vena, yang dapat menyebabkan
iskemia dan nekrosis appendiks. Jika appendiks ruptur, feses yang berisi bakteri
menyemprot ke permukaan isi abdomen, menyebabkan peritonitis.7
18
a. Obstruksi
Obstruksi lumen sebanyak 70% disebabkan oleh fekalit, korpus alienum,
tumor appendiks atau tumor sekum, parasit, atau fibrous band.10
b. Infeksi
Infeksi bakteri pada appendiks vermiformis, antara lain:8
Aerobik dan Fakultatif Anaerobik
Gram-negative bacilli
E. coli
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella species
Gram-positive cocci
Streptococcus anginosus
Streptococcus species
Enterococcus species
Gram-negative bacilli
Bacteroides fragilis
Bacteroides species
Fusobacterium species
Gram-positive cocci
Peptostreptococcus species
Gram-positive bacilli
Clostridium species
2.2.4. Klasifikasi
Klasifikasi appendisitis, antara lain:
a. Berdasarkan letak appendiks, antara lain:17
1) Anterior: pelvik, preileal, postileal
2) Posterior: subsekal, retrosekal, parasekal
19
Gambar 8. Letak appendiks vermiformis
Dikutip dari kepustakaan 18
b. Berdasarkan klinis, antara lain:8
1) Appendisitis akut
2) Appendisitis kronik
Syarat-syarat penegakan diagnosis appendisitis kronik, antara lain:5
1. Riwayat nyeri perut kanan bawah lebih dari 2 minggu
2. Radang kronik appendiks secara makroskopik dan mikroskopik
Kriteria mikroskopik:
a. Fibrosis dinding appendiks secara menyeluruh.
b. Sumbatan lumen appendiks parsial atau total.
c. Adanya jaringan parut dan ulkus lama pada mukosa
appendiks.
d. Infiltrasi sel inflamasi kronik.
3. Keluhan menghilang setelah dilakukan appendektomi.
20
Appendisitis akut kataralis
Appendisitis akut supuratif
Appendisitis akut gangrenosa
Appendisitis akut perforasi
Walling off (-) Walling off (+)
Infiltrat periappendikuler
Sembuh Appendisitis kronik Perforasi
Disertai dengan peritonitis generalisata Tanpa disertai dengan peritonitis generalisata
2.2.5. Patofisiologi
Gambar 9. Perjalanan
appendisitis
21
2.2.6. Diagnosis
2.2.6.1. Anamnesis
Gejala
Gejala appendisitis akut tergantung dari letak appendix vermiformis. Nyeri
perut berawal dirasakan di umbilikus atau periumbilikus (peritoneum viseral),
kemudian 4 - 8 jam atau 1 - 12 jam berpindah ke perut kuadran kanan bawah
(peritoneum parietal) (titik McBurney’s). Nyeri seluruh perut jika terjadi
peritonitis generalisata. Nyeri perut bertambah jika bergerak.8,10
a. Nyeri perut kanan bawah
Nyeri perut kanan bawah didahului nyeri periumbilikus.Nyeri periumbilkus
menandakan adanya inflamasi pada peritoneum viseral. Setelah inflamasi
mencapai peritoneum parietal maka nyeri dirasakan di perut kuadran kanan
bawah.4
Gambar 10. Nyeri yang berpindah dari regio umbilikus ke regio iliaka kanan pada appendisitis
22
Mekanisme nyeri perut secara umum, antara lain:15
a. Inflamasi peritoneum parietal
Nyeri pada inflamasi peritoneum parietal sifatnya terus menerus dan nyeri
dan lokasinya langsung berada di atas daerah yang mengalami inflamasi.
daerahnya sesuai daerah inflamasi karena ditransmisikan oleh saraf somatik
yang menginervasi peritoneum parietal.
Nyeri pada inflamasi peritoneum diperberat tanpa kecuali oleh tekanan atau
perubahan tegangan peritoneum, apakah ditimbulkan oleh palpasi atau
pergerakan.Misalnya batu dan bersin.
b. Obstruksi lumen organ visera
Nyeri pada obstruksi lumen visera abdomen digambarkan secara khas
sebagai nyeri yang intermiten, atau kolik.Nyeri kolik pada obstruksi kolon
intensitasnya kurang dibandingkan nyeri kolik pada obstruksi usus halus dan
sering berlokasi di daerah infraumbilikal. Penjalaran nyeri ke daerah lumbal
sering pada obstruksi kolon.
c. Gangguan vaskuler
Nyeri yang berhubungan dengan gangguan vaskuler intraabdominal bersifat
tiba-tiba dan katastropik. Nyeri pada gangguan vaskuler bersifat difus dan
berat.
d. Dinding abdomen
Nyeri yang timbul pada dinding abdomen biasanya konstan dan nyeri.
Pergerakan, berdiri yang lama, dan tekanan menimbulkan rasa tidak nyaman
dan spasme otot.
23
Gambar 11.Persepsi nyeri viseral terlokalisasi di regio epigastrium, umbilkus atau suprapubik
sesuai dengan asal embriogenik organ yang mengalami kelainan.
Dikutip dari kepustakaan 19
b. Demam
Demam merupakan suatu peningkatan suhu badan yang melebihi variasi
suhu harian normal. Demam terjadi dalam kaitannya dengan peningkatan pada set
point hipotalamus.15
Patogenesis demam secara umum, antara lain:
a. Pirogen
Pirogen merupakan suatu substansi yang menyebabkan demam. Pirogen
eksogen berasal dari luar tubuh manusia. Sebagian besar merupakan hasil
mikroba, toksin mikroba, atau semua tubuh mikroorganisme.15
b. Sitokin pirogen
Sitokin merupakan protein kecil (massa molekuler, berat 10.000 - 20.000
Da) yang mengatur proses imun, inflamasi, dan hematopoiesis. Beberapa
sitokin menyebabkan demam, dahulu disebut pirogen endogen, sekarang
disebut sitokin pirogen. Sitokin pirogen termasuk IL-1, IL-6, tumor necrosis
factor (TNF), ciliary neurotropic factor (CTNF), dan interferon (IFN) α.
Spektrum luas hasil bakteri dan jamur menginduksi sintesis dan pelepasan
sitokin pirogen, begitu juga virus. Akan tetapi, demam dapat menjadi
manifestasi penyakit tanpa adanya infeksi mikroba, seperti pada proses
inflamasi, trauma, kematian jaringan, dan kompleks antigen-antibodi.15
24
c. Peningkatan set point hipotalamus akibat sitokin
Selama demam, kadar prostaglandin E2 (PGE2) meningkat pada jaringan
hipotalamus dan ventrikel otak ketiga. Konsentrasi prostaglandin E2 (PGE2)
lebih tinggi dekat organ vaskuler sirkumventrikuler (organum vasculosum
lamina terminalis) (jaringan kapiler yang melebar sekeliling pusat regulasi
hipotalamus).15
Gambar 12.Kronologi peristiwa yang terlibat dalam terjadinya demam.
AMP, adenosine 5'-monophosphate; IFN, interferon; IL, interleukin;
PGE2, prostaglandin E2; TNF, tumor necrosis factor.
Dikutip dari kepustakaan 15
c. Anoreksia, mual, dan muntah
Anoreksia hampir selalu menyertai appendisitis. Meskipun muntah terjadi
pada hampir 75% pasien appendisitis, muntah terjadi tidak sering atau tidak lama
25
dan sebagian besar pasien appendisitis muntah hanya sekali atau dua kali. Muntah
dapat terjadi karena stimulasi saraf dan adanya ileus.8
2.2.6.2. Pemeriksaan Fisis
a. Nyeri tekan titik McBurney
Keluhan appendisitis berawal dari nyeri periumbilikus yang bersifat samar-
samar dan tumpul (nyeri viseral). Kemudian beberapa jam nyeri berpindah ke
kuadran kanan bawah di titik McBurney yang bersifat jelas dan tajam (nyeri
somatik). Pada saat ini didapatkan nyeri tekan dan ketok pada titik McBurney.5
Pemeriksaan dilakukan dengan menekan titik McBurney. Pemeriksaan
positif jika dirasakan nyeri pada titik McBurney. 5
Gambar 13.Nyeri tekan titik McBurney pada appendisitis
b. Nyeri ketok titik McBurney
Keluhan appendisitis berawal dari nyeri periumbilikus yang bersifat samar-
samar dan tumpul (nyeri viseral). Kemudian beberapa jam nyeri berpindah ke
26
kuadran kanan bawah di titik McBurney yang bersifat jelas dan tajam (nyeri
somatik). Pada saat ini didapatkan nyeri tekan dan ketok pada titik McBurney.5
Pemeriksaan dilakukan dengan mengetok titik McBurney. Pemeriksaan
positif jika dirasakan nyeri pada titik McBurney. 5
c. Tanda Rovsing
Pemeriksaan dilakukan dengan menekan regio iliaka sinistra. Pemeriksaan
positif jika dirasakan nyeri pada titik McBurney. 5
d. Tanda Blumberg
Pemeriksaan dilakukan dengan menekan regio iliaka sinistra kemudian
melepaskannya secara tiba-tiba. Pemeriksaan positif jika dirasakan nyeri pada titik
McBurney.5
Gambar 14. Tanda appendisitis
A. Tanda Rovsing
B. Tanda Blumberg
27
e. Tanda Psoas
Tanda psoas dapat dilakukan dengan 3 cara, antara lain:
1. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan hiperekstensi pada sendi panggul
kanan. Pemeriksaan positif jika dirasakan nyeri pada titik McBurney.5
2. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan hiperfleksi pada sendi panggul
kanan. Pemeriksaan positif jika dirasakan nyeri pada titik McBurney.5
3. Pemeriksaan dilakukan dengan menempatkan tangan di atas paha setengah
distal kemudian pasien memfleksikan paha secara aktif pada sendi panggul
melawan tahanan. Pemeriksaan positif jika dirasakan nyeri pada titik
McBurney.5,20
Ketiga pemeriksaan menandakan peradangan pada appendiks letak
retrosekal.5,20
Gambar 15. Tanda Psoas pada appendisitis
Dikutip dari kepustakaan 20
28
f. Tanda Obturator
Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan rotasi internal pada sendi
panggul kanan. Pemeriksaan positif jika dirasakan nyeri pada titik McBurney. Ini
menandakan peradangan pada appendiks letak pelvik.5,10
Gambar 16. Tanda Obturator pada appendisitis
Dikutip dari kepustakaan 20
2.2.6.3. Pemeriksaan Penunjang
2.2.6.3.1. Pemeriksaan Laboratorium
Pada appendisitis, leukosit dapat normal atau meningkat. Kadar leukosit
normal (4 - 10).103/mm
3.8,10
2.2.6.3.2. Pemeriksaan Radiologi
Pemeriksaan USG pada appendisitis memiliki sensitivitas 55 - 96 persen
dan spesifisitas 85 - 98 persen.8
29
Gambar 17. Pemeriksaan USG pada appendisitis
menunjukkan sekum dan appendiks dengan dinding tebal yang berisi cairan.
Dikutip dari kepustakaan 10
Pemeriksaan CT scan juga digunakan untuk menegakkan diagnosis
appendisitis. Pada CT scan appendiks yang mengalami inflamasi menunjukkan
dinding dilatasi dan menebal.8
Gambar 18. Pemeriksaan CT scan pada appendisitis
menunjukkan dinding appendiks dilatasi dan menebal.
Dikutip dari kepustakaan 21
30
Skor Alvarado untuk diagnosis Appendisitis8,17
Manifestasi Nilai
Gejala Nyeri perut periumbilikal berpindah ke iliaka
kanan 1
Anoreksia 1
Mual/muntah 1
Tanda Nyeri tekan 2
Nyeri lepas 1
Demam 1
Laboratorium Leukositosis ( leukosit > 10.000/mm3) 2
Neutrofil bergeser ke kiri (neutrophil > 75%) 1
Total nilai 10
Interpretasi:
1. 1 - 4 : Bukan appendisitis
2. 5 - 6 : Suspek appendisitis
3. 7 - 10 : Appendisitis
2.2.7. Penatalaksanaan
2.2.7.1. Konservatif
Penatalaksanaan konservatif diberikan pada pasien yang datang terlambat
dengan massa appendiks. Cairan intravena, obat antibiotik, dan observasi klinis
teratur dilakukan. Akan tetapi, jika kondisi pasien berubah, bedah darurat akan
diperlukan. Drainase abses secara radilogis merupakan pilihan bagi pasien dengan
risiko operasi buruk, dan appendektomi tertunda dapat dilakukan beberapa bulan
kemudian.22
Penatalaksanaan konservatif, antara lain:
a. Pasang jalur intravena sesuai kondisi pasien.8
b. Antibiotik spektrum luas.8
- Nonperforasi: 24 - 48 jam
31
- Perforasi: 7 - 10 hari
Antibiotik diberikan sampai hitung leukosit normal dan pasien tidak demam
selama 24 jam.
Antibiotik yang diberikan berupa antibiotik intravena, yaitu Cefuroxime dan
Metronidazol.22
2.2.7.2. Bedah
2.2.7.2.1. Appendektomi terbuka10
Gambar 19. Insisi pada appendektomi terbuka
Dikutip dari kepustakaan 10
Macam-macam teknik appendektomi terbuka, antara lain:
1. Insisi small oblique (insisi McBurney, insisi Lanz, insisi Grid Iron)
Insisi Grid Iron pada titik McBurney. Garis insisi parallel dengan otot
oblikus eksternal, melewati titik McBurney yaitu 1/3 lateral garis yang
menghubungkan spina iliaka anterior superior kanan dan umbilikus.22,23
Insisi Grid Iron dilakukan jika diagnosis appendisitis sudah pasti.10
2. Insisi suprainguinal (insisi Rutherford Morisson)
Merupakan insisi perluasan dari
Morisson dilakukan jika apendiks terletak di parasekal atau retrosekal dan
terfiksir.24
3. Insisi transversal Lanz
Insisi dilakukan pada 2 cm di baw
midklavikula-midinguinal. Mempunyai keuntungan kosmetik yang lebih baik dari
pada insisi Grid Iron.10,16
32
Gambar 20. Insisi Grid Iron
Dikutip dari kepustakaan 23
Insisi suprainguinal (insisi Rutherford Morisson)
Merupakan insisi perluasan dari insisi McBurney. Insisi Rutherford
Morisson dilakukan jika apendiks terletak di parasekal atau retrosekal dan
Gambar 21. Insisi Rutherford Morisson
Dikutip dari kepustakaan 16
Insisi transversal Lanz
Insisi dilakukan pada 2 cm di bawah pusat, insisi transversal pada garis
midinguinal. Mempunyai keuntungan kosmetik yang lebih baik dari
10,16
insisi McBurney. Insisi Rutherford
Morisson dilakukan jika apendiks terletak di parasekal atau retrosekal dan
ah pusat, insisi transversal pada garis
midinguinal. Mempunyai keuntungan kosmetik yang lebih baik dari
Insisi transversal Lanz dapat dilakukan pada diagnosis appendisitis yang
sudah pasti dan belum pasti.
3. Insisi low midline
Insisi low midline dilakukan jika diagnosis appendisitis belum pasti. Insisi
low midline dilakukan untuk memberikan pemeriksaan kavum peritoneum lebih
luas. Ini terutama dilakukan pada orang tua dengan kem
divertikulitis. Insisi low midline juga dilakukan jika sudah terjadi perforasi dan
peritonitis generalisata.8,10,24
33
Insisi transversal Lanz dapat dilakukan pada diagnosis appendisitis yang
sudah pasti dan belum pasti.10
Gambar 22. Insisi transversal Lanz
Dikutip dari kepustakaan 16
Insisi low midline dilakukan jika diagnosis appendisitis belum pasti. Insisi
low midline dilakukan untuk memberikan pemeriksaan kavum peritoneum lebih
ma dilakukan pada orang tua dengan kemungkinan keganasan atau
ulitis. Insisi low midline juga dilakukan jika sudah terjadi perforasi dan
8,10,24
Insisi transversal Lanz dapat dilakukan pada diagnosis appendisitis yang
Insisi low midline dilakukan jika diagnosis appendisitis belum pasti. Insisi
low midline dilakukan untuk memberikan pemeriksaan kavum peritoneum lebih
ungkinan keganasan atau
ulitis. Insisi low midline juga dilakukan jika sudah terjadi perforasi dan
34
Gambar 23. Insisi low midline
Dikutip dari kepustakaan 24
4. Insisi paramedian dekstra
Insisi vertikal paralel dengan midline, 2,5 cm di bawah umbilikus sampai di
atas pubis.24
Gambar 24. Insisi paramedian dekstra
Dikutip dari kepustakaan 24
35
Insisi paramedian dekstra dilakukan jika diagnosis appendisitis belum pasti.9
a b
c d
Gambar 25.Teknik appendektomi terbuka.
Abdomen dibuka melalui insisi oblik atau transversal yang dipusatkan pada titik McBurney’s.
a. Appendiks dijepit kemudian ditarik, dan arteri appendikuler dipotong diantara dua ligasi.
b. Appendiks didiseksi pada pangkalnya.
c. Pada tempat appendiks diligasi, dipotong di bagian distalnya, dan dilepaskan.
d. Puntung appendiks diinversi ke dalam sekum dengan menggunakan jahitan pursestring.
Dikutip dari kepustakaan 10
2.2.7.2.2. Appendektomi laparoskopi
Laparoskopi sebaiknya dilakukan pada perempuan usia subur untuk
mengkonfirmasi diagnosis.22
Appendektomi laparoskopi dilakukan dengan anestesi umum. Nasogastric
tube dan kateter urin dilakukan sebelum membuat pneumoperitoneum.
Appendektomi laparoskopi biasanya membutuhkan penggunaan tiga port. Empat
36
port kadang-kadang dapat menjadi penting untuk memobilisasi appendiks letak
retrosekal. Dokter bedah biasanya berdiri di sebelah kiri pasien. Satu asisten
dibutuhkan untuk mengoperasikan kamera. Satu trokar ditempatkan pada
umbilikus (10 mm), dengan trokar kedua ditempatkan pada posisi suprapubik.
Beberapa dokter bedah akan menempatkan port kedua ini pada kuadran kiri
bawah. Trokar suprapubik berukuran 10 atau 12 mm, bergantung pada apakah
stapler linear yang akan digunakan. Penempatan trokar ketiga (5 mm) bervariasi
dan biasanya pada kuadran kiri bawah, epigastrium, atau kuadran kanan
atas.Penempatan berdasarkan lokasi appendiks dan keinginan dokter bedah.
Awalnya, abdomen dieksplorasi secara keseluruhan untuk mengeliminasi patologi
(penyakit) lain. Appendiks diidentifikasi dengan menelusuri taenia anterior
sampai pangkalnya.Diseksi pada pangkal appendiks memungkinkan dokter bedah
membuat suatu celah antara mesenterium dan pangkal appendiks. Mesenterium
dan pangkal appendiks kemudian dilindungi dan dipotong secara terpisah. Ketika
mesoappendiks terlibat dalam proses inflamasi, sering lebih baik memotong
appendiks lebih dulu dengan stapler linier, dan kemudian memotong
mesoappendiks yang berdekatan dengan appendiks dengan klip, elektrokauter,
skalpel Harmonik, atau staples. Pangkal appendiks tidak diinversi.Appendiks
dilepas dari kavum abdomen melalui tempat trokar atau dalam kantong
retrieval.Pangkal appendiks dan mesoappendiks seharusnya dievaluasi untuk hal
hemostasis.Kuadran kanan bawah seharusnya diirigasi. Trokar dilepas dibawah
pengamatan langsung.8
37
Gambar 26. Insisi pada appendektomi terbuka
Dikutip dari kepustakaan 10
Gambar 27.Teknik appendektomi laparoskopi.
A. Sebuah celah dibuat di mesoappendiks dekat pangkal appendiks.
B. Stapler linier kemudian digunakan untuk memotong appendiks pada pangkalnya.
C. Akhirnya mesoappendiks dapat dengan mudah dipotong dengan menggunakan stapler linier
Dikutip dari kepustakaan 8
38
2.2.8. Diagnosis Banding
Diagnosis banding appendisitis, antara lain:16
a. Anak-anak: gastroenteritis akut, limfadenitis mesenterika, divertikulitis
Meckel, intussusepsi, purpura Henoch-Schonlein, pneumonia lobaris dan
pleurisy.
b. Dewasa laki-laki: ileitis terminalis, kolik ureter, pielonefritis dekstra akut,
perforasi ulkus peptik, torsio testis, pankreatitis akut, hematom otor rektus.
c. Dewasa perempuan: salpingitis, mittelschmerz, torsio/perdarahan kista
ovarium, kehamilan ektopik.
d. Usia lanjut: divertikulitis sigmoid, obstruksi intestinal, karsinoma sekum,
nyeri preherpetik saraf dorsal 10 dan 11 dekstra.
2.2.9. Komplikasi
Komplikasi appendisitis dapat berupa perforasi atau abses appendiks.
Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah perforasi, baik berupa perforasi
dengan atau tanpa adanya walling off. Walling off terbentuk dari appendiks,
sekum, usus halus dan omentum.5
1. Perforasi
Adanya fekalit di dalam lumen, umur (orang tua atau anak kecil), dan
keterlambatan diagnosis, merupakan faktor yang berperan dalam terjadinya
perforasi appendiks. Perforasi bisa disertai atau tanpa disertai dengan peritonitis
generalisata.5,18
39
2. Abses appendiks (periappendikuler infiltrat = infiltrat periappendikuler =
infiltrat appendiks = massa appendiks)
Massa appendiks terjadi bila appendisitis gangrenosa atau mikroperforasi
tertutupi atau terbungkus oleh omentum dan atau lekuk usus halus. Abses
appendiks terbentuk pada hari ke-4 sejak peradangan mulai apabila peritonitis
generalisata tidak terjadi. Abses appendiks lebih sering dijumpai pada pasien
berumur lima tahun atau lebih karena daya tahan tubuh telah berkembang dengan
baik dan omentum telah cukup panjang dan tebal untuk membungkus proses
radang.4,5,18
2.2.10. Prognosis
Angka morbiditas sesuai dengan angka mortalitas. Faktor yang terlibat
dalam morbiditas dan mortalitas yaitu usia pasien dan ada tidaknya komplikasi
yang terjadi.8
40
BAB III
KERANGKA KONSEP
3.1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian
a. Jenis kelamin
Appendisitis dapat mengenai laki-laki dan perempuan. Insidens pada laki-
laki dan perempuan umumnya sama, kecuali pada kelompok umur 20 - 30 tahun,
laki-laki lebih tinggi.
b. Umur
Appendisitis dapat ditemukan pada semua umur. Di Indonesia insidens
appendisitis pada bayi, 80 - 90% appendisitis baru diketahui setelah terjadi
perforasi. Anak kurang dari 1 tahun jarang dilaporkan. Bayi dan anak < 2
tahun1% atau kurang.2 - 3 tahun 15%. 5 tahun ke atas frekuensi mulai meningkat
dan mencapai puncaknya pada usia 9 - 11 tahun. Insidens tertinggi pada kelompok
umur 20 - 30 tahun. Morbiditas dan mortalitas appendisitis sesuai dengan umur.
Semakin tinggi umur seseorang maka morbiditas dan mortalitasnya meningkat.
c. Tingkat pendidikan
Tingkat pendidikan dapat menggambarkan seberapa besar pengetahuandan
perhatian seseorang dalam menjaga kesehatannya. Hal ini dapat menggambarkan
cepat lambatnya seseorang untuk memeriksakan diri ke tempat pelayanan
kesehatan jika mendapatkan adanya gejala dan tanda penyakit pada tubuhnya.
Pada penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sejak 1
Februari sampai 30 September 2004 diperoleh 97 sampel penderita, terdiri dari 44
perempuan (45,4%) dan 53 laki-laki (54,6%), berumur 16 - 56 tahun. Dari 97
41
sampel penderita didapatkan 52 sampel tidak bekerja (53,6%), 22 sampel pegawai
negeri (22,7%), 23 sampel pegawai swasta (23,7%).
d. Pekerjaan
Pekerjaan mempengaruhi pola hidup seseorang setiap hari, termasuk pola
makan. Penelitian epidemiologi menunjukkan peranan pola kebiasaan makan
makanan rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya appendisitis.
Pada penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sejak 1
Februari sampai 30 September 2004 diperoleh 97 sampel penderita, terdiri dari 44
perempuan (45,4%) dan 53 laki-laki (54,6%), berumur 16 - 56 tahun. Dari 97
sampel penderita didapatkan 52 sampel tidak bekerja (53,6%), 22 sampel pegawai
negeri (22,7%), 23 sampel pegawai swasta (23,7%).
e. Klasifikasi klinis
Appendisitis dapat terjadi berupa appendisitis akut maupun kronik.
Appendisitis kronik jarang terjadi. Keberadaan appendisitis kronik sebagai suatu
kumpulan penyakit yang benar ada telah dipertanyakan selama beberapa tahun.
Meskipun data klinis yang terbaru membuktikan keberadaan penyakit yang jarang
ini.Pada appendisitis kronik, beberapa pasien mengalami nyeri perut persisten.
pasien tidak mengalami gejala khas apendisitis akut. Justru, pasien mengalami
nyeri perut kanan bawah selama mingguan sampai tahunan.dan mungkin telah
mendapatkan berbagai pengobatan. Diagnosis dapat sulit, karena pemeriksaan
laboratorium dan radiologi secara khas normal. Karena diagnosis preoperatif
sering tidak jelas, maka laparoskopi dapat menjadi peralatan berguna untuk
memungkinkan eksplorasi abdomen.
42
f. Gejala klinis
Appendisitis dapat menimbulkan gejala yang bervariasi. Gejala klinis khas
dari appendisitis adalah adanya nyeri di daerah umbilikus yang bersifat samar dan
tumpul. Kemudian beberapa jam nyeri berpindah ke kuadaran kanan bawah,
tepatnya titik McBurney. Sifatnya nyerinya menjadi jelas dan tajam.
Kadang appendisitis tidak menimbulkan gejala nyeri perut kuadaran kanan
bawah yang didahului nyeri umbilikus, tetapi timbul dengan gejala konstipasi. Hal
ini sering menjadikan dokter untuk memberikan obat pencahar. tindakan ini
berbahaya karena bisa mempermudah terjadinya perforasi appendiks dengan
segala konsekuensinya.
g. Tanda klinis
Appendisitis dapat menimbulkan tanda yang bervariasi. Tanda klinis khas
ari appendisitis adalah nyeri tekan titik McBurney, nyeri ketok titik McBurney,
tanda Rovsing, tanda Blumberg, tanda Psoas, dan tanda Obturator. Tanda klinis
dari appendisitis tergantung dari letak appendiks yang meradang.
h. Hitung jumlah leukosit
Appendisitis dapat menunjukkan hitung jumlah leukosit normal atau
meningkat. Pasien appendisitis umumnya mengalami leukositosis, yaitu jumlah
leukosit > 10.000/mm3. Peningkatan leukosit dalam darah menunjukkan adanya
proses infeksi dalam tubuh. Pada appendisitis, leukosit akan bermigrasi dari
lumen pembuluh darah ke tempat yang mengalami peradangan untuk memfagosit
agen-agen infeksi.
43
i. Gambaran USG
Appendisitis dapat menunjukkan gambaran USG spesifik seperti dinding
appendiks yang dilatasi dan menebal, dan tidak spesifik. Diagnosis appendisitis
melalui pemeriksaan USG dilaporkan memiliki sensitivitas 55 sampai 96% dan
spesifisitas 85 sampai 98%. Hasil negatif palsu dapat terjadi jika appendisitis
terbatas pada ujung appendiks, lokasi appendiks retrosekal, appendiks membesar
dan dikira usus halus, atau jika appendiks perforasi dan sebab itu appendiks yang
meradang dapat dikempiskan.
j. Skor Alvarado
Diagnosis appendisitis akut tidak mudah ditegakkan hanya berdasarkan
gambaran klinis. Keadaan ini menghasilkan angka appendektomi negatif sebesar
20% dan angka perforasi sebesar 20-30%. Salah satu upaya meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan medis ialah membuat diagnosis yang tepat. Telah banyak
dikemukakan caraa untuk menurunkan insidensi appendektomi negatif, salah
satunya adalah dengan instrumen skor Alvarado. Skor Alvarado adalah sistem
skoring sederhana yang bisa dialkauakn dengan mudah, cepat, dan kurang invasif.
Morbiditas dan mortalitas appendisitis akut masih cukup tinggi. Hal ini
disebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan pembedahan.
k. Penatalaksanaan
Penatalaksanaan appendisitis dapat berupa konservatif atau bedah. Bedah
dapat dilakukan dengan appendektomi terbuka atau appendektomi laparoskopi.
Sejak era post-antibiotik, Coldrey mempresentasikan penelitian retrospektifnya
pada 471 pasien dengan appendisitis yang diobati dengan antibiotik. Pengobatan
ini gagal pada sekurang-kurangnya 57 pasien, dengan 48 membutuhkan
appendektomi dan 9 membutuhkan drainase akibat abses appendiks.
44
l. Komplikasi
Komplikasi appendisitis dapat berupa perforasi atau abses appendiks.
Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah perforasi, baik berupa perforasi
dengan atau tanpa adanya walling off. Walling off terbentuk dari appendiks,
sekum, usus halus dan omentum. Perforasi juga bisa disertai atau tanpa disertai
dengan peritonitis generalisata.
Adanya fekalit di dalam lumen, umur (orang tua atau anak kecil), dan
keterlambatan diagnosis, merupakan faktor yang berperan dalam terjadinya
perforasi appendiks. Massa appendiks terjadi bila appendisitis gangrenosa atau
mikroperforasi tertutupi atau terbungkus oleh omentum dan atau lekuk usus halus.
45
3.2. Kerangka Konsep
Variabel Independen Variabel Dependen
Jenis Kelamin
Umur
Tingkat Pendidikan
Hitung Jumlah Leukosit
Gambaran USG
Skor Alvarado
Pekerjaan
Klasifikasi Klinis
Gejala Klinis
Tanda Klinis
Penatalaksanaan
Komplikasi
Appendisitis
46
3.3. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif
3.3.1. Variabel Dependen
Appendisitis
Definisi:
Appendisitis merupakan peradangan pada appendiks vermiformis.
3.3.2. Variabel Independen
3.3.2.1. Jenis Kelamin
a. Definisi :
Suatu akibat dari dismorfisme seksual (perbedaan sistematik tampakan dari
luar antar individu yang mempunyai perbedaan jenis kelamin dalam spesies
yang sama) sesuai dengan yang tercantum pada rekam medik.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel jenis kelamin sesuai dengan yang tercantum pada
rekam medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Laki-laki
2. Perempuan
47
3.3.2.2. Umur
a. Definisi :
Satuan waktu yang mengukur lamanya seseorang hidup mulai dari saat lahir
sampai usianya pada saat masuk RSUP Wahidin Sudirohusodo yang
dinyatakan dalam tahun seperti yang tercatat dalam rekam medik.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel umur sesuai dengan yang tercantum pada rekam
medik.
d. Kriteria Objektif :
Kategori umur menurut Depkes RI (2009)
1. 0 - 5 tahun (masa balita)
2. 5 - 11 tahun (masa kanak-kanak)
3. 12 - 16 tahun (masa remaja awal)
4. 17 - 25 tahun (masa remaja akhir)
5. 26 - 35 tahun (masa dewasa awal)
6. 36 - 45 tahun (masa dewasa akhir)
7. 46 - 55 tahun (masa lansia awal)
8. 56 - 65 tahun (masa dewasa akhir)
9. > 65 tahun (masa manula)
3.3.2.3. Tingkat Pendidikan
a. Definisi :
Suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui
pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh
departemen pendidikan.
b. Alat ukur :
Kuesioner
48
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel tingkat pendidikan sesuai dengan yang tercantum
pada rekam medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Belum/tidak pernah sekolah
2. SD
3. SLTP/sederajat
4. SLTA/sederajat
5. Perguruan Tinggi
3.3.2.4. Pekerjaan
a. Definisi :
Usaha (mata pencaharian) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat
biaya penghidupan.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel umur sesuai dengan yang tercantum pada rekam
medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Tidak bekerja
2. Pegawai negeri
3. Pegawai swasta
3.3.2.5. Klasifikasi Klinis
a. Definisi :
Klasifikasi appendisitis berdasarkan gejala dan tanda klinis yang ditemukan.
b. Alat ukur :
Kuesioner
49
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel klasifikasiberdasarkan klinis sesuai dengan yang
tercantum pada rekam medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Appendisitis akut
2. Appendisitis kronik
3.3.2.6. Gejala Klinis
a. Definisi :
Data subyektif berupa keluhan pada tubuh pasien yang timbul akibat
penyakit yang diderita yang diperoleh melalui anamnesis.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel gejala klinis sesuai dengan yang tercantum pada
rekam medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Gejala klinis khas
2. Gejala klinis tidak khas
Gejala klinis khas:
Nyeri perut periumbilikus kemudian berpindah ke perut kuadran kanan
bawah
3.3.2.7. Tanda Klinis
a. Definisi :
Data obyektif berupa kelainan pada tubuh pasien yang timbul akibat
penyakit yang diderita yang diperoleh melalui pemeriksaan fisis.
b. Alat ukur :
Kuesioner
50
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel tanda klinis sesuai dengan yang tercantum pada
rekam medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Ditemukan salah satu tanda klinis
2. Tidak ditemukan salah satu tanda klinis
Tanda klinis:
a. Nyeri tekan titik McBurney
b. Nyeri ketok titik McBurney
c. Tanda Rovsing
d. Tanda Blumberg
e. Tanda Psoas
f. Tanda Obturator
3.3.2.8. Hitung Jumlah Leukosit
a. Definisi :
Data obyektif berupa jumlah leukosit pada tubuh pasien yang timbul akibat
penyakit yang diderita yang diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel hitung jumlah leukosit sesuai dengan yang
tercantum pada rekam medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Normal (4.000 - 10.000/mm3)
2. Leukositosis (> 10.000/mm3)
51
3.3.2.9. Gambaran USG
a. Definisi :
Data obyektif berupa gambaran hasil USG pada tubuh pasien yang timbul
akibat penyakit yang diderita yang diperoleh melalui pemeriksaan USG.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel gambaran USG sesuai dengan yang tercantum
pada rekam medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Mendukung diagnosis appendisitis
a. Kesan appendisitis
b. Kesan suspek appendisitis
2. Tidak mendukung diagnosis appendisitis
3.3.2.10. Skor Alvarado
a. Definisi :
Skor yang digunakan untuk menilai derajat appendisitis dan menentukan
tindak lanjut.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel skor Alvarado sesuai dengan yang tercantum
pada rekam medik.
52
d. Kriteria Objektif :
Skor Alvarado
Manifestasi Nilai
Gejala Nyeri perut periumbilikal berpindah ke
iliaka kanan 1
Anoreksia 1
Mual/muntah 1
Tanda Nyeri tekan 2
Nyeri lepas 1
Demam 1
Laboratorium Leukositosis ( leukosit > 10.000/mm3) 2
Neutrofil bergeser ke kiri (neutrophil > 75%) 1
Total nilai
10
Interpretasi:
1. 1 - 4 : Bukan appendisitis
2. 5 - 6 : Suspek appendisitis
3. 7 - 10 : Appendisitis
3.3.2.11. Penatalaksanaan
a. Definisi :
Segala upaya yang akan dilaksanakan untuk menghilangkan atau
mengurangi gejala dan tanda penyakit yang diderita pasien.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel penatalaksanaan sesuai dengan yang tercantum
pada rekam medik.
53
d. Kriteria Objektif :
1. Konservatif
2. Bedah
a. Appendektomi terbuka
b. Appendektomi laparoskopi
3.3.2.12. Komplikasi
a. Definisi :
Segala hal yang diakibatkan oleh penyakit yang diderita pasien sebagai
akibat perjalanan penyakitnya.
b. Alat ukur :
Kuesioner
c. Cara ukur :
Dengan mencatat variabel komplikasi sesuai dengan yang tercantum pada
rekam medik.
d. Kriteria Objektif :
1. Komplikasi ada
2. Komplikasi tidak ada
Komplikasi
a. Perforasi disertai dengan peritonitis generalisata
b. Perforasi tanpa disertai dengan peritonitis generalisata
c. Abses appendiks
54
BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
4.1. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan
desain penelitian deskriptif cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan
dalam satu kurun waktu tertentu. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan
dengan pengukuran semua variabel dilakukan pada saat tertentu yang sama,
periode Januari - Desember 2012, untuk mengetahui karakteristik penderita
appendisitis yang dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melalui
penggunaan rekam medik sebagai data penelitian.
4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian
4.2.1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini direncanakan dilakukan pada tanggal 1 Juli sampai 12
Juli 2013.
4.2.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini direncanakan dilakukan di Bagian Rekam Medik
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
55
4.3. Populasi dan Sampel Penelitian
4.3.1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah penderita appendisitis yang dirawat di
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai dari bulan Januari sampai bulan
Desember 2012.
4.3.2. Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah penderita appendisitis yang dirawat di
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo mulai dari bulan Januari sampai bulan
Desember 2012.
4.3.2.1. Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampeldengan menggunakan metode total sampling,
yaitu semua populasi dijadikan sampel.
4.3.2.2. Kriteria Seleksi
a. Kriteria Inklusi
Memiliki data rekam medik
b. Kriteria Eksklusi
Terdapat data yang tidak lengkap dari rekam medik dari salah satu data
berikut:
1) Pemeriksaan laboratorium
2) Pemeriksaan USG
3) Menolak tindakan medis
4) Pulang atas permintaan sendiri
56
4.4. Jenis Data dan Instrumen Penelitian
4.4.1. Jenis Data Penelitian
Jenis data penelitian dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
diperoleh dari rekam medik sebagai subyek penelitian.
4.4.2. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lembar
kuesioner yang berisi tabel-tabel tertentu untuk mencatat data yang dibutuhkan
dari rekam medik.
4.5. Manajemen Penelitian
4.5.1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan setelah meminta perizinan dari pihak RSUP
Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian nomor rekam medik penderita appendisitis
dalam periode yang telah ditentukan dikumpulkan di bagian Rekam Medik RSUP
Dr. Wahidin Sudirohusodo.Setelah itu, dilakukan pengamatan dan pencatatan
langsung ke dalam kuesioner yang telah disediakan.
4.5.2. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan data rekam medik yang
dibutuhkan ke dalam kuesioner dengan menggunakan program SPSS 17.0 dan
Microsoft Excell untuk memperoleh hasil statistik deskriptif yang diharapkan.
57
4.5.3. Penyajian Data
Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram untuk
menggambarkan karakteristik penderita appendisitis yang dirawat inap di RSUP
Dr. Wahidin Sudirohusodo terhitung sejak Januari - Desember 2012.
4.6. Etika Penelitian
Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian ini, antara lain:
a. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit
setempat sebagai permohonan izin untuk melakukan kegiatan.
b. Berusaha menjaga kerahasiaan identitas pasien yang terdapat pada rekam
medik, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas
penelitian yang dilakukan.
c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak
yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang telah disebutkan
sebelumnya.
58
BAB V
GAMBARAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO
5.1. Identitas Badan Layanan Umum RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan rumah
sakit kelas A pendidikan dengan status Badan Layanan Umum Rumah Sakit
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23Tahun 2005,
Kesehatan RI Nomor : 1243/MenKes/SK/VII/2005, dan Surat Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor : 1677/MenKes/Per/XII/2005, dengan identitas sebagai
berikut:
1. Nama Rumah Sakit : RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
2. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11, Tamalanrea
Makassar (90245)
3. Telepon : Kantor (0411) 584675, (0411) 584677, Rumah
Sakit (0411) 583333, 584888
4. Fax : (0411) 587676
5. Pemilikan : Departemen Kesehatan Republik Indonesia
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo memiliki luas gedung 33.372 m2,dengan
batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Menuju Daya, terdapat kantor dan asrama Kodam VII
dan jalan poros Makassar-Pare-pare.
b. Sebelah Timur : Terdapat kantor Dians Departemen Kesehatan
Propinsi Sulawesi Selatan.
c. Sebelah Selatan : Terdapat tanah milik dan bangunan Lembaga
Penelitian Unhas yang diantarai DAM buatan.
d. Sebelah Barat : Terdapat perkuliahan dan perkantoran Unhas.
Merujuk pada peraturan tersebut Perjan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
akan mengembangkan unggulan Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian di bidang
59
Kegawat Daruratan, Urologi, Kanker, Jantung, Lipid, dan Endokrin beserta
pelayanan penunjangnya.
5.2. Sejarah Berdirinya RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Pada tahun 1947 didirikan Rumah Sakit dengan meminjam 2 (dua) bangsal
Rumah Sakit Jiwa yang telah berdiri sejak tahun 1942 sebagai bangsal bedah dan
penyakit dalam yang merupakan cikal bakal berdirinya Rumah Sakit Umum
(RSU) Dadi.
Pada tahun 1957 RSU Dadi yang berlokasi di jalan Lanto Dg. Pasewang No.
43 Makassar sebagai Rumah Sakit Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan dan pada
tahun 1993 menjadi Rumah Sakit dengan klasifikasi B. Pengembangan RSU
dipindahkan ke Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar, berdekatan dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
Pada tahun 1994 RSU Dadi berubah menjadi Rumah Sakit vertikal milik
Departemen Kesehatan dengan nama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.
Wahidin Sudirohusodo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.
540/SK/VI/1994 sebagai Rumah Sakit kelas A dan sebagai Rumah Sakit
Pendidikan serta sebagai Rumah Sakit Rujukan tertinggi di Kawasan Timur
Indonesia.
Pada tanggal 10 Desember 1995 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
ditetapkan menjadi Rumah Sakit unit Swadana dan pada tahun 1998 dikeluarkan
Undang-undang No. 30 tahun 1997 berubah menjadi Unit Pengguna Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dengan terbitnya peraturan Pemerintah R.I. No. 125 tahun 2000, RSUP Dr.
Wahidin Sudirohusodo beralih status kelembagaan menjadi Perusahaan Jawatan
(Perjan), yang berlangsung selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2005.
Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang
pengelolaaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor : 1243/MenKes/SK/VII/2005 tanggal 11 agustus 2005
tentang penetapan 13 Eks Rumah Sakit PERJAN menjadi UPT DEPKES dengan
60
penerapan pola PPK-BLU, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :
1677/MenKes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan tata kerja RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo Makassar, maka sejak tahun Januari tahun 2006 kelembagaan
RSWS berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Depkes dengan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo memiliki fasilitas dan kemampuan
menyelenggarakan hampir semua jenis pelayanan kedokteran baik spesialis
maupun subspesialis, sehingga layak menjadi pusat layanan rujukan di kawasan
timur Indonesia. Luas lahan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah 8,4 HA
serta luas bangunan 39.246 m2.
Kapasitas tempat tidur berjumlah 659 buah terdiri dari kelas utama 50 buah,
kelas I 63 buah, kelas II 164 buah, dan kelas III 299 buah, serta 50 tempat tidur
dialokasikan di pelayanan lainnya seperti Intensif 43 buah, Intermediate 30 buah,
dan kamar isolasi sebanyak 10 buah tempat tidur.
Pada tahun 2009 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo membangun Private
Care Centre (PCC) yang merupakan pengembangan pelayanan kelas VIP dari
Ruang Paviliun Palem dan Paviliun Sawit. Daya tampung 2 Ruang VIP tersebut
sangat terbatas yakni hanya menampung 50 tempat tidur, di gedung PCC
bertambah menjadi 90 tempat tidur. Selain PCC juga melakukan pengembangan 5
centre unggulan lainnya, yaitu: Cardiac Centre, Gastroenterohepatologi Centre,
Intensive Care Centre, Infection Centre, dan Mother and Child Centre.
5.3. Visi dan Misi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
5.3.1. Visi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 2015
"Menjadi Rumah Sakit dengan layanan berstandar Internasional".
61
5.3.2. Misi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas yang terintegrasi,
holistik dan professional.
b. Menumbuhkembangkan sistem kerja yang aman, nyaman dan produktif
c. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang menunjang dan
terintegrasi dengan pelayanan
62
BAB VI
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo, mulai tanggal 8 - 9 Juli 2013. Proses pengumpulan data dilakukan
dengan mencatat Rekam Medik sebagai data sekunder penderita appendisitis yang
teregistrasi sebagai penderitas rawat inap pada periode Januari - Desember 2012.
Data yang diperoleh dari Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo sebanyak 79 penderita appendisitis yang dirawat inap di RSUP Dr.
Wahidin Sudirohusodo pada periode Januari - Desember 2012. Dari 79 sampel, 68
memenuhi kriteria inklusi dan kemudian diolah dengan menggunakan program
SPSS 17.0 dan Microsoft Excell dengan hasil sebagai berikut.
6.1. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Jenis
Kelamin
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu jenis kelamin. Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.1.
Tabel 6.1. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Jenis
Kelamin
Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%)
Laki-laki
Perempuan
39
29
57,4
42,6
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
63
Gambar 28. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan jenis kelamin
Berdasarkan tabel 6.1. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat inap
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada laki-laki sebanyak 39 orang
(57,4%) dibandingkan dengan perempuan sebanyak 29 orang (42,6%).
6.2. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Umur
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu umur.Adapun distribusinya
dapat dilihat pada tabel 6.2.
64
Tabel 6.2. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Umur
Umur (Tahun) Frekuensi (n) Persentase (%)
0 - 5
6 – 11
12 – 16
17 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
> 65
1
5
12
16
16
8
5
4
1
1,5
7,4
17,6
23,5
23,5
11,8
7,4
5,9
1,5
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
Gambar 29. Diagram bar frekuensi penderita appendisitis berdasarkan kelompok umur
Berdasarkan tabel 6.2. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat inap
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada kelompok umur 17 - 25 tahun
65
dan 26 - 35 tahun, masing - masing sebanyak 16 orang (23,5%); dan terendah
pada kelompok umur 0 - 5 tahun dan > 65 tahun, masing-masing sebanyak 1
orang (1,5%) .
6.3. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu tingkat pendidikan.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.3.
Tabel 6.3. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Tingkat Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%)
Belum/Tidak Pernah Sekolah
SD
SLTP/Sederajat
SLTA/Sederajat
Perguruan Tinggi
1
1
0
1
3
1,5
1,5
0
1,5
4,4
Total 6 8,9
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
66
Gambar 30. Diagram pie persentase penderita appendisitis berdasarkan tingkat pendidikan
Berdasarkan tabel 6.3. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat inap
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada tingkat pendidikan Perguruan
Tinggi sebanyak 3 orang (4,4%), dan terendah pada tingkat pendidikan
belum/tidak pernah sekolah, SD, dan SLTA/sederajat, masing-masing sebanyak 1
orang (1,5%). Dari 68 sampel, hanya 6 sampel yang memiliki data mengenai
tingkat pendidikan dan 62 sampel yang tidak memiliki data mengenai tingkat
pendidikan.
6.4. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Pekerjaan
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu pekerjaan.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.4.
67
Tabel 6.4. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan Frekuensi (f) Persentase (%)
Tidak Bekerja
Pegawai Negeri
Pegawai Swasta
4
1
0
5,9
1,5
0
Total 5 7,4
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
Gambar 31. Diagram pie persentase penderita appendisitis berdasarkan pekerjaan
Berdasarkan tabel 6.4.dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat inap
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada penderita yang tidak bekerja
sebanyak 4 orang (5,9%), dan terendah pada penderita dengan pekerjaan pegawai
negeri sebanyak 1 orang (1,5%). Dari 68 sampel, hanya 5 sampel yang memiliki
data mengenai pekerjaan dan 63 sampel yang tidak memiliki data mengenai
pekerjaan.
6.5. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Klasifikasi
Klinis
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu klasifikasi klinis.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.5.
68
Tabel 6.5. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Klasifikasi
Klinis
Klasifikasi Klinis Frekuensi (f) Persentase (%)
Appendisitis akut
Appendisitis kronik
67
1
98,5
1,5
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
Gambar 32. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan klasifikasi klinis
Berdasarkan tabel 6.5. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat inap
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada klasifikasi klinis appendisitis
akut sebanyak 67 orang (98,5%) dibandingkan dengan klasifikasi klinis
appendisitis kronik sebanyak 1 orang (1,5%).
69
6.6. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Gejala Klinis
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu gejala klinis.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.6.
Tabel 6.6. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Gejala Klinis
Gejala Klinis Frekuensi (f) Persentase (%)
Gejala klinis khas
Gejala klinis tidak khas
40
28
58,8
41,2
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
Gambar 33. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan gejala klinis
70
Berdasarkan tabel 6.6. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat inap
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada gejala klinis khas sebanyak 40
orang (58,8%) dibandingkan dengan gejala klinis tidak khas sebanyak 28 orang
(41,2%).
6.7. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Tanda Klinis
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu tanda klinis.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.7.
Tabel 6.7.1. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Tanda
Klinis
Tanda Klinis Khas Frekuensi (f) Persentase (%)
Ditemukan 67 98,5
Tidak ditemukan 1 1,5
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
Tabel 6.7.2. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Tanda
Klinis Khas
Tanda Klinis Frekuensi (f) Persentase (%)
Nyeri tekan titik McBurney
Nyeri ketok titik McBurney
Tanda Rovsing
Tanda Blumberg
Tanda Psoas
Tanda Obturator
66
17
46
31
7
2
97,1
25
67,6
45,5
10,2
2,9
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
71
Gambar 34. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan tanda klinis
Berdasarkan tabel 6.7.1. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat
inap di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada tanda klinis dengan
ditemukan salah satu tanda klinis khas sebanyak 67 orang (98,5%) dibandingkan
dengan tanda klinis dengan tidak ditemukan salah satu tanda klinis khas sebanyak
1 orang (1,5%).
Berdasarkan tabel 6.7.2. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat
inap di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada tanda klinis khas dengan
nyeri tekan titik McBurney sebanyak 66 orang (97,1%), terendah pada tanda kilnis
khas dengan tanda Obturator sebanyak 2 orang (2,9%).
72
6.8. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Hitung
Jumlah Leukosit
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu hitung jumlah
leukosit.Adapun distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.8.
Tabel 6.8. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Hitung
Jumlah Leukosit
Hitung Jumlah Leukosit Frekuensi (f) Persentase (%)
Normal
Leukositosis
11
57
16,2
83,8
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
Gambar 35. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan hitung jumlah leukosit
73
Berdasarkan tabel 6.8. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat inap
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada hitung jumlah leukosit dengan
hasil leukositosis sebanyak 57 orang (83,8%) dibandingkan dengan hitung jumlah
leukosit dengan hasil normal sebanyak 11 orang (16,2%).
6.9. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Gambaran
USG
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu gambaran USG.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.9.
Tabel 6.9. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Gambaran
USG
Gambaran USG Frekuensi
(f)
Persentase
(%)
Mendukung diagnosis
appendisitis
Kesan appendisitis 39 57,4
Kesan suspek
appendisitis 9 13,2
Tidak mendukung diagnosis appendisitis 20 29,4
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
74
Gambar 36. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan gambaran USG
Berdasarkan tabel 6.9. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat inap
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada gambaran USG kesan
appendisitis sebanyak 39 orang (57,4%), kemudian gambaran USG tidak
mendukung diagnosis appendisitis sebanyak 20 orang (29,4%), dan terendah pada
gambaran USG kesan suspek appendisitis sebanyak 9 orang (13,2%).
6.10. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Skor
Alvarado
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu skor Alvarado.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.10.
75
Tabel 6.10. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Skor
Alvarado
Skor Alvarado Frekuensi (f) Persentase (%)
1 – 4 (bukan appendisitis)
5 - 6 (suspek appendisitis)
7 - 10 (appendisitis)
3
6
59
4,4
8,8
86,8
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
Gambar 37. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan skor Alvarado
Berdasarkan tabel 6.10. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat
inap di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada skor Alvarado 7 - 10
sebanyak 59 orang (86,8%), kemudian skor Alvarado 5 - 6 sebanyak 6 orang
(8,8%), dan terendah pada skor Alvarado 1 - 4 sebanyak 3 orang (4,4%).
76
6.11. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Distribusi
Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Penatalaksanaan
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu penatalaksanaan.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.11.
Tabel 6.11. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan
Penatalaksanaan
Penatalaksanaan Frekuensi
(f)
Persentase
(%)
Konservatif 13 19,1
Bedah
Appendektomi terbuka 53 77,9
Appendektomi
laparoskopi 2 2,9
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
Gambar 38. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan penatalaksanaan
77
Berdasarkan tabel 6.11. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat
inap di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada penatalaksanaan dengan
appendektomi terbuka sebanyak 53 orang (77,9%), kemudian penatalaksanaan
dengan konservatif sebanyak 13 orang (19,1%), dan terendah pada
penatalaksanaan dengan appendektomi laparoskopi sebanyak 2 orang (2,9%).
6.12. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Komplikasi
Karakteristik yang diperoleh dari kuisioner yaitu komplikasi.Adapun
distribusinya dapat dilihat pada tabel 6.12.
Tabel 6.12. Distribusi Frekuensi Penderita Appendisitis Berdasarkan Komplikasi
Komplikasi Frekuensi
(f)
Persentase
(%)
Komplikasi ada Perforasi
Disertai dengan
peritonitis generalisata 5 7,4
Tanpa disertai dengan
peritonitis generalisata 7 10,3
Abses appendiks 16 23,5
Komplikasi tidak ada 40 58,8
Total 68 100
Sumber: Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, 2012
78
Gambar 39. Diagram bar persentase penderita appendisitis berdasarkan komplikasi
Berdasarkan tabel 6.12. dapat dilihat bahwa penderita appendisitis rawat
inap di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tertinggi pada komplikasi tidak ada
sebanyak 40 orang (58,8%), kemudian komplikasi dengan abses appendiks
sebanyak 16 orang (23,5%), kemudian komplikasi dengan perforasi tanpa disertai
dengan peritonitis generalisata sebanyak 7 orang (10,3%) dan terendah pada
komplikasi dengan perforasi disertai dengan peritonitis generalisata sebanyak 5
orang (7,4%).
79
BAB VII
PEMBAHASAN
7.1. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan berjenis kelamin
perempuan.
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Adityawarman di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2004 dengan jumlah
penderita appendisitis 97 orang dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 53
orang (54,6%) lebih banyak dibandingkan dengan berjenis kelamin perempuan
sebanyak 44 orang (45,4%).6
Hasil penelitian yang berbeda didapatkan pada penelitian yang dilakukan
oleh Anggi di RSU Dokter Soedarso Pontianak tahun 2011 dengan jumlah
penderita appendisitis 100 orang dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46
orang (46%) lebih sedikit dibandingkan dengan berjenis kelamin perempuan
sebanyak 54 orang (54%). Hasil penelitian lain yang berbeda juga didapatkan
pada penelitian yang dilakukan oleh Mangema di RS Pendidikan FK USU Medan
tahun 2008 dengan jumlah penderita appendisitis 51 orang dengan berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 23 orang (45,1%) lebih sedikit dibandingkan dengan
berjenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang (54,9%).3,16
Penelitian epidemiologi menunjukkan peranan pola kebiasaan makan
makanan rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya appendisitis.
Konstipasi akan menaikkan tekanan intrasekal yang mengakibatkan timbulnya
sumbatan fungsional appendiks dan mengakibatkan pertumbuhan kuman flora
kolon. Hal ini akan memudahkan timbulnya appendisitis. Appendisitis lebih
sering mengenai laki-laki dibandingkan perempuan mungkin akibat laki-laki
memiliki pola makan dengan rendah serat dibandingkan perempuan. Sedangkan
80
perempuan memiliki pola makan dengan tinggi serat untuk menjaga berat badan
ideal.5
Sedangkan pada penelitian dengan hasil perempuan lebih banyak
dibandingkan laki-laki diperkirakan karena adanya beberapa penyakit yang
dialami wanita yang memberikan gejala menyerupai appendisitis seperti penyakit
infeksi pada pelvis (Pelvic Inflamatory Disease) dan proses menstruasi. Gejala
klinik appendisitis pada wanita hamil juga dapat menyebabkan terjadinya salah
diagnosis, sehingga terlihat angka kejadian appendisitis pada perempuan lebih
tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki.3
7.2. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Umur
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada kelompok umur 17 - 25 tahun dan 26 - 35 tahun,
kemudian kelompok umur 12 - 16 tahun.
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Anggi di RSU Dokter Soedarso Pontianak tahun 2011 dengan jumlah penderita
appendisitis 100 orang dengan kelompok umur 15 - 21 tahun sebanyak 32 orang
(32%), kemudian kelompok umur 22 - 28 tahun sebanyak 20 orang (20%).3
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Adityawarman di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2004 dengan jumlah
penderita appendisitis 97 orang dengan kelompok umur 16 - 30 tahun sebanyak 74
orang (76,3%), kemudian kelompok umur 31 - 45 tahun sebanyak 20 orang
(20,6%), dan kemudian kelompok umur 46 - 60 tahun sebanyak 3 orang (3,1%).6
Hasil penelitian yang sama juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan
oleh M. Safaei, L. Moeinei, dan M. Rasti dalam Journal of Research in Medical
Science tahun 2004 dengan jumlah penderita appendisitis 18 orang dengan
kelompok umur > 25 tahun sebanyak 9 orang (50%), kemudian kelompok umur
15 - 25 tahun sebanyak 6 orang (31,25%), dan kemudian kelompok umur < 15
tahun sebanyak 3 orang (18,75%).25
81
Usia 20 - 40 tahun bisa dikategorikan sebagai usia produktif, dimana orang
yang berada pada usia tersebut melakukan banyak sekali kegiatan, walaupun hal
ini tidak terjadi pada semua orang. Hal ini menyebabkan orang tersebut
mengabaikan nutrisi makanan yang dikonsumsinya. Kebanyakan orang memakan
makanan cepat saji agar tidak mengganggu waktunya,padahal makanan-makanan
cepat saji itu tidak mengandung serat yang cukup. Akibatnya terjadi kesulitan
buang air besar yang akan menyebabkan peningkatan tekanan pada rongga usus
dan pada akhinya menyebabkan sumbatan pada saluran apendiks.3
Gejala appendisitis pada anak tidak khas. Gejala awalnya sering hanya
rewel dan tidak mau makan. Anak sering tidak dapat menggambarkan rasa
nyerinya. Dalam beberapa jam kemudian akan timbul muntah-muntah dan anak
menjadi lemah dan letargik. Karena gejala yang tidak khas ini, appendisitis sering
diketahui setelah terjadi perforasi. Sedangkan pada usia lanjut, appendisitis agak
sulit didiagnosis sehingga tidak ditangani dengan cepat dan tepat sehingga tejadi
komplikasi.5
7.3. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Dari 68 sampel, hanya 6
sampel yang memiliki data mengenai tingkat pendidikan dan 62 sampel yang
tidak memiliki data mengenai tingkat pendidikan. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi, kemudian tingkat
pendidikan SD dan SLTA/sederajat.
Hasil penelitian yang berbeda didapatkan pada penelitian yang dilakukan
oleh Adityawarman di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2004 dengan
jumlah penderita appendisitis 97 orang dengan tingkat pendidikan SLTA
sebanyak 69 orang (71,1%), kemudian tingkat pendidikan AK/PT sebanyak 24
orang (24,7%), dan kemudian tingkat pendidikan SD dan SLTP, masing-masing
sebanyak 2 orang (2,1%).6
82
Tingkat pengetahuan seseorang mempengaruhi perilaku hidup sehat
seseorang. Orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki perilaku hidup
sehat dan sangat memperhatikan kesehatannya sehingga jika mengalami gejala
penyakit cepat ke tempat pelayanan kesehatan untuk memperoleh penanganan.
7.4. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Dari 68 sampel, hanya 5
sampel yang memiliki data mengenai pekerjaan dan 63 sampel yang tidak
memiliki data mengenai pekerjaan. Sebagian besar penderita appendisitis terdapat
pada penderita yang tidak bekerja, kemudian penderita dengan pekerjaan pegawai
negeri.
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Adityawarman di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2004 dengan jumlah
penderita appendisitis 97 orang dengan penderita yang tidak bekerja sebanyak 52
orang (53,6%), kemudian penderita dengan pekerjaan pegawai swasta sebanyak
23 orang (23,7%), dan kemudian penderita dengan pekerjaan pegawai negeri
sebanyak 22 orang (22,7%).6
Pekerjaan mempengaruhi pola hidup seseorang setiap hari, termasuk pola
makan. Penelitian epidemiologi menunjukkan peranan pola kebiasaan makan
makanan rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya appendisitis.5
7.5. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Klasifikasi Klinis
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada klasifikasi klinis appendisitis akut dibandingkan dengan
klasifikasi klinis appendisitis kronik.
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Fatih, Sabriye, Muzaffar, dan Huseyin dalam Turk J Med Science tahun 2002
83
dengan jumlah penderita appendisitis 72 orang dengan klasifikasi klinis
appendisitis akut sebanyak 64 orang (88,9%), kemudian klasifikasi klinis
appendisitis kronik sebanyak 3 orang (4,2%), dan kemudian appendiks normal
sebanyak 5 orang (6,9%).26
Appendisitis dapat terjadi berupa appendisitis akut maupun kronik.
Appendisitis kronik jarang terjadi. Keberadaan appendisitis kronik sebagai suatu
kumpulan penyakit yang benar ada telah dipertanyakan selama beberapa tahun.
Meskipun data klinis yang terbaru membuktikan keberadaan penyakit yang jarang
ini. Pada appendisitis kronik, beberapa pasien mengalami nyeri perut persisten.
pasien tidak mengalami gejala khas appendisitis akut. Justru, pasien mengalami
nyeri perut kanan bawah selama mingguan sampai tahunan.dan mungkin telah
mendapatkan berbagai pengobatan. Diagnosis dapat sulit, karena pemeriksaan
laboratorium dan radiologi secara khas normal. Karena diagnosis preoperatif
sering tidak jelas, maka laparoskopi dapat menjadi peralatan berguna untuk
memungkinkan eksplorasi abdomen.8,14
7.6. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Gejala Klinis
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada gejala klinis khas dibandingkan dengan gejala klinis
tidak khas.
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Mangema di RS Pendidikan FK USU Medan tahun 2008 dengan jumlah penderita
appendisitis 51 orang dengan gejala klinis khas sebanyak 39 orang (76,5%) lebih
banyak dibandingkan dengan gejala klinis tidak khas sebanyak 12 orang
(23,5%).16
Appendisitis dapat menimbulkan gejala yang bervariasi. Gejala klinis khas
dari appendisitis adalah adanya nyeri di daerah umbilikus yang bersifat samar dan
tumpul. Ini terjadi ketika appendisitis akut stadium kataralis. Kemudian beberapa
jam nyeri berpindah ke kuadran kanan bawah, tepatnya titik McBurney ketika
84
terjadi appendisitis akut stadium supuratif. Sifatnya nyerinya menjadi jelas dan
tajam. Ini terjadi pada 66% pasien appendisitis.Anoreksia merupakan gejala awal
sebelum timbul nyeri perut pada 95% pasien appendisitis. Muntah terjadi pada
75% pasien appendisitis.5,8,15
Kadang appendisitis tidak menimbulkan gejala nyeri perut kuadran kanan
bawah yang didahului nyeri umbilikus, tetapi timbul dengan gejala konstipasi.Hal
ini sering menjadikan dokter untuk memberikan obat pencahar.tindakan ini
berbahaya karena bisa mempermudah terjadinya perforasi appendiks dengan
segala konsekuensinya.5
Gejala appendisitis pada anak tidak khas. Gejala awalnya sering hanya
rewel dan tidak mau makan. Anak sering tidak dapat menggambarkan rasa
nyerinya. Dalam beberapa jam kemudian akan timbul muntah-muntah dan anak
menjadi lemah dan letargik. Karena gejala yang tidak khas ini, appendisitis sering
diketahui setelah terjadi perforasi. Sedangkan pada usia lanjut, appendisitis agak
sulit didiagnosis sehingga tidak ditangani dengan cepat dan tepat sehingga tejadi
komplikasi.5
7.7. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Tanda Klinis
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada tanda klinis dengan ditemukan salah satu tanda klinis
khas dibandingkan dengan tanda klinis dengan tidak ditemukan salah satu tanda
klinis khas.
Tanda klinis khas yang paling banyak ditemukan, yaitu nyeri tekan titik
McBurney sebanyak 66 orang (97,1%), kemudian tanda Rovsing sebanyak 46
orang (67,6%), kemudian tanda Blumberg sebanyak 31 orang (45,5 %), kemudian
nyeri ketok titik McBurney sebanyak 17 orang (25%), kemudian tanda Psoas
sebanyak 7 orang (10,2%), dan kemudian tanda klinis khas yang paling sedikit
ditemukan, yaitu tanda Obturator sebanyak 2 orang (2,9 orang).
85
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Marisa di RSUD Sleman tahun 2008 - 2009 dengan jumlah penderita appendisitis
186 orang dengan tanda klinis nyeri tekan titik McBurney sebanyak 68 orang
(36,50%), kemudian tanda Psoas sebanyak 33 orang (17,70%), kemudian tanda
Obturator sebanyak 24 orang (12,90%),kemudian tanda Rovsing sebanyak 16
orang (8,60%),kemudian nyeri lepas tekan sebanyak 6 orang (3,20%), dan
kemudian tidak ada gejala sebanyak 2 orang (1,00%).27
Appendisitis dapat menimbulkan tanda yang bervariasi. Tanda klinis khas
dari appendisitis adalah nyeri tekan titik McBurney, nyeri ketok titik McBurney,
tanda Rovsing, tanda Blumberg, tanda Psoas, dan tanda Obturator. Tanda klinis
dari appendisitis tergantung dari letak appendiks yang meradang. Letak
appendiks, antara lain anterior dan posterior. Letak appendiks anterior terdiri dari
letak pelvik, preileal, dan postileal. Sedangkan letak appendiks posterior terdiri
dari letak subsekal, retrosekal, dan parasekal.5,10,16
Nyeri tekan dan nyeri ketok titik McBurney menandakan appendiks letak
anterior. Tanda Rovsing menandakan appendiks letak pelvik. Tanda Blumberg
menandakan appendiks letak pelvik. Tanda Psoas menandakan appendiks letak
retrosekal. Tanda Obturator menandakan appendiks letak pelvik.5,10,16
Pada penelitian ini didapatkan sebagian besar penderita appendisitis
mengalami nyeri tekan titik McBurney yang menunjukkan bahwa sebagian besar
penderita memiliki appendiks letak anterior.
7.8. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Hitung Jumlah
Leukosit
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada hitung jumlah leukosit dengan hasil leukositosis
dibandingkan dengan hitung jumlah leukosit dengan hasil normal.
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Anggi di RSU Dokter Soedarso Pontianak tahun 2011 dengan jumlah penderita
86
appendisitis 100 orang dengan hitung jumlah leukosit dengan hasil leukosit
10.000 - 18.000 sel/mm3 sebanyak 54 orang (54%), kemudian hitung jumlah
leukosit dengan hasil leukosit 5.000 - 10.000 sel/mm3 sebanyak 27 orang (27%),
dan kemudian hitung jumlah leukosit dengan hasil leukosit > 18.000 sel/mm3
sebanyak 19 orang (19%). Sehingga sebagian besar penderita appendisitis terdapat
pada hitung jumlah leukosit dengan hasil leukositosis sebanyak 73 orang (73%),
lebih banyak dibandingkan dengan hitung jumlah leukosit dengan hasil normal
sebanyak 27 orang (27%).3
Appendisitis dapat menunjukkan hitung jumlah leukosit normal atau
meningkat.Pasien appendisitis umumnya mengalami leukositosis, yaitu jumlah
leukosit > 10.000/mm3. Peningkatan leukosit dalam darah menunjukkan adanya
proses infeksi dalam tubuh. Pada appendisitis, leukosit akan bermigrasi dari
lumen pembuluh darah ke tempat yang mengalami peradangan untuk memfagosit
agen-agen infeksi. Penelitian yang dilakukan oleh Kamran10 di Pakistan,
menyimpulkan bahwa jumlah leukosit dapat membantu dokter dalam
mendiagnosis apendisitis. Penelitian yang dilakukan oleh Krishnan 11 di Rumah
Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, menunjukan terdapat leukositosis
pada 73,7% pasien apendisitis.3,8,10
7.9. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Gambaran USG
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada gambaran USG kesan appendisitis, kemudian gambaran
USG tidak mendukung diagnosis appendisitis, dan kemudian gambaran USG
kesan suspek appendisistis.
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Adityawarman di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2004 dengan jumlah
penderita appendisitis 97 orang dengan gambaran USG appendisitis akut sebanyak
89 orang (91,8%), kemudian gambaran USG bukan appendisitis akut sebanyak 8
orang (8,2%).6
87
Sebagai salah satu pemeriksaan penunjang yang dianjurkan untuk
membantu menegakkan diagnosis appendisitis akut, USG diharapkan dapat
membantu menurunkan angka appendekomi negatif.6
Appendisitis dapat menunjukkan gambaran USG spesifik seperti dinding
appendiks yang dilatasi dan menebal, dan tidak spesifik. Diagnosis appendisitis
melalui pemeriksaan USG dilaporkan memiliki sensitivitas 55 sampai 96% dan
spesifisitas 85 sampai 98%. Hasil negatif palsu dapat terjadi jika appendisitis
terbatas pada ujung appendiks, lokasi appendiks retrosekal, appendiks membesar
dan dikira usus halus, atau jika appendiks perforasi dan sebab itu appendiks yang
meradang dapat dikempiskan.8
7.10. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Skor Alvarado
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada skor Alvarado 7 - 10, kemudian skor Alvarado 5 - 6,
dan kemudian skor Alvarado 1 - 4.
Hasil penelitian yang sama didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Mangema di RS Pendidikan FK USU Medan tahun 2008 dengan jumlah penderita
appendisitis 51 orang dengan skor Alvarado 7 - 10 sebanyak 48 orang (94,2%),
kemudian skor Alvarado 5 - 6 sebanyak 3 orang (5,8%).16
Diagnosis appendisitis akut tidak mudah ditegakkan hanya berdasarkan
gambaran klinis. Keadaan ini menghasilkan angka appendektomi negatif sebesar
20% dan angka perforasi sebesar 20-30%. Salah satu upaya meningkatkan
kuantitas dan kualitas pelayanan medis ialah membuat diagnosis yang tepat. Telah
banyak dikemukakan cara untuk menurunkan insidensi appendektomi negatif,
salah satunya adalah dengan instrumen skor Alvarado. Skor Alvarado adalah
sistem skoring sederhana yang bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan kurang
invasif.Morbiditas dan mortalitas appendisitis akut masih cukup tinggi. Hal ini
disebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan pembedahan.17
88
Sebenarnya masih ada skor diagnosis yang lain untuk menegakkan
diagnosis appendisitis, yaitu skor Labbeda, skor Kalesaran. Pada penelitian ini
didapatkan sebagian besar penderita appendisitis memiliki skor Alvarado 7 – 10,
yang berarti mengalami appendisitis. Hal ini menunjukkan bahwa skor Alvarado
dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis appendisitis secara praktis.
7.11. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Penatalaksanaan
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
appendisitis terdapat pada penatalaksanaan dengan appendektomi terbuka,
kemudian penatalaksanaan dengan konservatif, dan kemudian penatalaksanaan
dengan appendektomi laparoskopi.
Penatalaksanaan appendisitis dapat berupa konservatif atau bedah.Bedah
dapat dilakukan dengan appendektomi terbuka atau appendektomi laparoskopi.
Sejak era post-antibiotik, Coldrey mempresentasikan penelitian retrospektifnya
pada 471 pasien dengan appendisitis yang diobati dengan antibiotik. Pengobatan
ini gagal pada sekurang-kurangnya 57 pasien, dengan 48 membutuhkan
appendektomi dan 9 membutuhkan drainase akibat abses appendiks.14
Komplikasi appendisitis dapat berupa periappendikuler infiltrat. Pada
penderita dengan periappendikuler infiltrat ditangani dengan cara konservatif
terlebih dahulu dengan pemberian antibiotik dan observasi terhadap suhu tubuh,
ukuran massa, dan luasnya peritonitis. Setelah penderita tidak mengalami demam,
periappendikuler infiltrat mereda, dan hitung jumlah leukosit normal, maka
penderita boleh dipulangkan dan appendektomi elektif dilakukan 2 - 3 bulan
kemudian agar perdarahan akibat perlengketan dapat ditekan sekecil mungkin.5
7.12. Karakteristik Penderita Appendisitis Berdasarkan Komplikasi
Berdasarkan data di Bagian Rekam Medik RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo didapatkan 68 penderita appendisitis. Sebagian besar penderita
89
appendisitis terdapat pada komplikasi tidak ada, kemudian komplikasi dengan
abses appendiks, kemudian komplikasi dengan perforasi tanpa disertai dengan
peritonitis generalisata, dan kemudian komplikasi dengan perforasi disertai
dengan peritonitis generalisata.
Komplikasi appendisitis dapat berupa perforasi atau abses
appendiks.Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah perforasi, baik berupa
perforasi dengan atau tanpa adanya walling off. Walling off terbentuk dari
appendiks, sekum, usus halus dan omentum. Perforasi juga bisa disertai atau tanpa
disertai dengan peritonitis generalisata.5
Adanya fekalit di dalam lumen, umur (orang tua atau anak kecil), dan
keterlambatan diagnosis, merupakan faktor yang berperan dalam terjadinya
perforasi appendiks. Massa appendiks terjadi bila appendisitis gangrenosa atau
mikroperforasi tertutupi atau terbungkus oleh omentum dan atau lekuk usus
halus.5
90
BAB VIII
KESIMPULAN DAN SARAN
8.1. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian mengenai karakteristik penderita appendisitis
rawat inap di RSUP Dr. Wahididn Sudirohusodo Periode Januari - Desember
2012, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Sebagian besar penderita appendisitis berjenis kelamin laki-laki, pada
kelompok umur 17 - 25 tahun dan 26 - 35 tahun, dengan tingkat pendidikan
Perguruan Tinggi dan tidak bekerja. Sebagian besar penderita appendisitis
terdapat pada klasifikasi klinis appendisitis akut, dengan gejala klinis khas, dan
tanda klinis dengan ditemukan salah satu tanda klinis khas. Tanda klinis khas
yang paling banyak ditemukan adalah nyeri tekan titik McBurney. Sebagian besar
penderita appendisitis terdapat pada hitung jumlah leukosit dengan hasil
leukositosis dan gambaran USG kesan appendisitis, dengan skor Alvarado 7 - 10.
Sebagian besar penderita appendisitis terdapat pada penatalaksanaan dengan
appendektomi terbuka, dengan komplikasi tidak ada.
8.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran-
saran yang diajukan adalah sebagai berikut.
1. Semua Rumah Sakit, baik pendidikan maupun non pendidikan sebaiknya
memiliki data rekam medik yang lengkap sehingga dapat dijadikan data
penelitian untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kesehatan dan
kedokteran.
2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan agar faktor risiko dan penyebab
appendisitis dapat diketahui sehingga angka morbiditas dan mortalitas
appendisitis dapat diturunkan.
91
3. Penegakan diagnosis yang lebih akurat dibutuhkan, melalui anamnesis,
pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang yang tepat.
4. Penatalaksaan sesuai protap yang berlaku.
92
DAFTAR PUSTAKA
1. Craig S. 2012, Appendicitis, [on line]. Dari: http:www.emedicine.com [16
Juni 2013]
2. Minkes RK. 2013, Pediatric Appendicitis, [on line]. Dari:
http:www.emedicine.com [16 Juni 2013]
3. Nasution AP. Hubungan Antara Jumlah Leukosit dengan Appendisitis Akut
dan Appendisitis Perforasi di RSU Doker Soedarso Pontianak tahun 2011
[Naskah Publikasi]. Pontianak: Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Tanjungpura; 2013.
4. Pusponegoro AD, Kartono D, Hutagalung EU, Sumardi R, Luthfia C, Ramli
M, dkk. Editor: Reksoprodjo S. Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah. Jakarta:
Bagian Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah
Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo; 1995.
5. De Jong W, Sjamsuhidajat R. Buku Ajar Ilmu Bedah. Edisi Ke-2. Jakarta:
EGC; 2005.
6. Adityawarman. Peranan Ultrasonografi Dalam Membantu Menegakkan
Diagnosis Appendisitis Akut. Makassar: Program Pendidikan Dokter
Spesialis I Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Makassar; 2004.
7. Marieb EN, Hoen K. Chapter 23. The Digestive System. Human Anatomy
and Physiology. 7th Edition. New York: Pearson Education, Inc; 2007
8. Brunicardi, FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Pollock
RE, Editors. Chapter 29. The Appendix. Schwartz’s Principles of Surgery.
8th Edition. New York: The McGraw-Hill Companies; 2007.
9. Putz R, Pabst R. Sobotta Atlas of Human Anatomy. Volume 2 Trunk,
Viscera, Lower Limb. 14th Edition. Germany: Elsevier; 2006.
10. Debas HT. Chapter 9. Appendix. Gastrointestinal Surgery Pathophysiology
and Management. New York: Springer; 2004
11. Susan, Standring. Gray’s Anatomy The Anatomical Basis of Clinical
Practice. 39th Edition. New York: Elsevier Churchill Livingstone; 2008.
93
12. Uflacker, Renan. Atlas of Vascular Anatomy: An Angiographic Approach.
2nd Edition. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.
13. Netter FH. Atlas of Human Anatomy. 5th Edition. Saunders
14. Zinner MJ, Ashley SW. Chapter 21. Appendix and Appendectomy.
Maingot’s Abdominal Operations. 11th Edition. McGraw-Hill’s Access
Surgery.
15. Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, dkk. Part 2. Cardinal
Manifestations and Presentation of Diseases. Harrison’s Principles of
Internal Medicine. 17th Edition. New York: The McGraw-Hill Companies;
2008.
16. Juniar M. Hubungan Antara Skor Alvarado dan Temuan Operasi
Appendisitis Akut di Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara. [Tesis]. Medan: Departemen Ilmu Bedah
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara; 2009.
17. Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ. Sleisenger, Fordtran’s. Chapter 113.
Appendicitis. Gastrointestinal and Liver Disease
Pathophysiology/Diagnosis/management. 8th Edition. Philadelphia:
Saunders; 2006
18. Epstein O, Perkin GD. Clinical Examination. 2nd Edition. London: Mosby;
1997.
19. Berg D, Worzala K. Atlas of Adult Physical Diagnosis. 1st Edition.
California: Lippincott Williams and Wilkins; 2006.
20. Brant WE, Helms CA. Fundamentals of Diagnostic Radiology. 2nd Edition.
California: Lippincott William and Wilkins; 2007.
21. Lim E, Loke YK, Thompson A. Section 4.8. Diseases of The Small Intestine
and Appendix. Medicine and Surgery An Integrated Textbook. New York:
Elsevier Churchill Livingstone; 2008.
22. Skandalaki JE, Colborn GL, Weidman TA, et al. Editors. Chapter 17.
Appendix. Skandalakis’ Surgical Anatomy. New York: McGraw-Hill’s
Access Surgery; 2004.
94
23. Patnalk VG, Singla RK, Bansal VK. Surgical Incisions-Their Anatomical
Basis. J Anatomy Society India 50 (2) 170 - 178 (2001).
24. Russell RCG, Williams NS, Bulstrode CJK. Editors. Bailey and Love’s
Short Practice of Surgery. 24th Edition. London: Arnold; 2004.
25. Safaei M, Moeinei L, dan Rasti M. Recurrent Abdominal Pain and Chronic
Appendicitis. Journal of Research in Medical Science 2004; 1: 11 - 4
26. Andiran F, Dayi S, Caydere M, dan Oston H. Chronic Recurrent
Appendicitis in Children: An Insidious and Neglected Cause of Surgical
Abdomen. Turk Journal Medicine Science 32 (2002) 351 - 4
27. Sahara M. Karakteristik Appendisitis Akut di RSUD Sleman Periode
Januari 2008 - Desember 2009. Fakultas Kedokteran Universitas Islam
Indonesia.