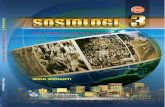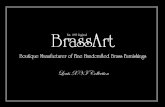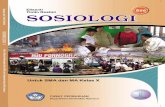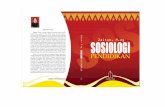Jurnal Sosiologi Pendidikan Louis Althusser
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Jurnal Sosiologi Pendidikan Louis Althusser
SUMBANGAN TEORI LOUIS ALTHUSSERTERHADAP SOSIOLOGI PENDIDIKAN
(Ideologi, Negara dan Pendidikan)Oleh:
Tria Septi WulandariFakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5, Malang 65145
Abstrak: Althusser merupakan pembaca pemikiranMarxisme, yang dilakukannya adalah menerima apa yangmenurutnya tepat dan mengkritisi apa yang menurut Marxtidak tepat untuknya. Marx yang mengungkapkan bahwasemua permasalahan social bertumpu pada masalahekonomi. Ternyata ia mempunyai pandangan lain tentanghal itu, dia berpikir bahwa bukan ekonomi yangmemegang kendali tersebut. Althusser beranggapan bahwaideology adalah penggerak dari segala aspek kehidupanini ‘tak ada sesuatupun di luar ideologi’. Konsep yangdiajukan oleh Althusser adalah State Apparatus (SA)dan Ideological State Apparatus (ISA), interpelasi,Tesis 1: ideologi merepresentasikan relasi individuyang imajiner pada kondisi-kondisi nyata darieksistensinya, Tesis 2: ideologi memiliki eksistensimaterial, dll. Dalam karyanya, Althusser menguraikantentang bagaimana ekonomi mempengaruhi posisi individudalam masyarakat serta ideologinya.Kata Kunci: Marxisme, Ideologi, Ekonomi
SEKILAS TENTANG LOUIS ALTHUSSER
Louis Althusser adalah filsuf Perancis yang lahir di
Algeria pada tahun 1918 dan meninggal di Paris pada tahun
1990. Studi filsafat diperolehnya di École Normale
Supérieure di Paris, dimana ia kemudian menjadi profesor
filsafat. Ia juga merupakan intelektual yang bergabung
1
dengan Partai Komunis Perancis. Argumen-argumennya
kebanyakan adalah tanggapan terhadap serangan-serangan yang
ditujukan pada dasar-dasar ideologi partai itu. Termasuk
diantaranya empirisme yang mempengaruhi tradisi sosiologi
dan ekonomi Marxis, serta ancaman dari orientasi humanitik
dan sosial demokrat yang dipandangnya sebagai sebuah
ancaman yang mulai mereduksi kemurnian orientasi partai-
partai komunis Eropa. Jadi, Louis Althusser dalam hal itu
dapat dikategorikan sebagai seorang filsuf Marxis yang
lebih ortodoks, karena mencoba mempertahankan dasar-dasar
pemikiran Marx dan melihatnya sebagai sebuah ilmu
pengetahuan tentang masyarakat yang harus mengikuti dasar-
dasar ilmiah. Pada tahun 1980 ia membunuh istrinya Helene
Rytmann dan mengakibatkan ia dikirim untuk menjalani
rehabilitasi mental di pusat rehabilitasi selama 3 tahun.
Semasa hidupnya, ia lebih dikenal sebagai seorang
teorisi dan kritikus marxis. Louis Althusser adalah seorang
filsuf beraliran Marxis yang paling berpengaruh pada dekade
1960-an dan 1970-an. Karyanya yang berjudul "Untuk Marx"
(dalam bahasa Perancis Pour Marx) dan "Membaca Modal"
(dalam bahasa Perancis Lire le Capital) membuat Althusser
menjadi terkenal di kalangan intelektual Perancis dan
menarik perhatian pembaca di luar negeri. Terjemahan dalam
bahasa Inggris atas kedua karya tersebut pada tahun 1969
dan 1970, mendorong berkembangnya pemikiran Marxis di
tempat-tempat yang memakai bahasa Inggris selama tahun
1970-an.
2
Sumbangan Louis Althusser
Salah satu kontribusi Althusser yang paling dikenal
adalah pembabakannya atas pemikiran Marx ke dalam tahap
“Marx muda” dan “Marx matang”. Sesungguhnya pembabakan yang
dibuat Althusser tidaklah sesederhana dikotomi di muka.
Namun, sebelum melihat detail pembabakan itu, kita mesti
memeriksa terlebih dahulu prinsip pembabakan itu sendiri.
Bagi Althusser, prinsip pembabakan ini terletak dalam
sebuah pertanyaan krusial: Apa problemnya? Dengan kata
lain, apabila Marx menawarkan kepada kita sebuah gugus
pengetahuan yang baru, lantas apa problem yang hendak
dijawab olehnya, sebuah problem yang secara spesifik
dipermasalahkannya (dan tidak dipermasalahkan oleh para
pemikir sebelumnya)? Bagi Althusser, pendirian sebuah gugus
pengetahuan yang baru mengandaikan adanya cara mengajukan
pertanyaan yang baru pula, atau kerangka problem yang
sepenuhnya berbeda dari kerangka problem yang diusung oleh
gugus pengetahuan yang lama. Agar teori Marx dapat
dikatakan sebuah teori yang baru, maka kita harus dapat
membuktikan kebaruan itu melalui investigasi tentang apakah
problem spesifik yang dipersoalkan oleh Marx. Dalam
kerangka inilah Althusser berbicara tentang “patahan
epistemologis” (coupure epistémologique) — sebuah kategori
yang dipinjamnya dari filsuf epistemologi, Gaston
Bachelard.1 Patahan epistemologis atau patahan pengetahuan
1 Lih. Louis Althusser, For Marx diterjemahkan oleh Ben Brewster (London:Verso), 1997 (aslinya: 1965), hlm. 32.
3
adalah kondisi yang disyaratkan oleh kemunculan setiap
pengetahuan baru. Suatu pengetahuan dikatakan baru apabila
ia berhasil merumuskan problemnya sendiri terlepas dari
perumusan problem oleh pengetahuan sebelumnya. Begitu
problem yang hendak dijawab berubah, maka terjadilah
patahan epistemologis. Inilah yang akan kita saksikan dalam
pembabakan Althusser atas tahap pemikiran Marx.
Althusser memang membagi sejarah pemikiran Marx ke
dalam dua periode utama: periode “ideologis” pra-1845 dan
periode “saintifik” pasca-1845.2 Kita perlu mengklarifikasi
arti term-term yang dipakai Althusser itu. Term “ideologi”
mengacu pada superstruktur yang dibicarakan Marx dalam
pandangan materialisnya tentang sejarah. Term ini digunakan
Althusser untuk menunjukkan periode ketika Marx masih
berkubang dalam medan problematik Idealisme Jerman yang
menjadi konteks sejarahnya. Dengan kata lain, dalam periode
ini pemikiran Marx masih bercampur dengan ideologi pada
masa itu. Term “saintifik” digunakan Althusser untuk
menunjukkan periode ketika Marx telah berhasil merumuskan
problem spesifiknya sendiri lepas dari horizon problematik
Idealisme Jerman yang ideologis. Dengan kata lain, periode
saintifik ini adalah masa di mana Marx telah berhasil
merumuskan sains tentang sejarah atau materialisme historis
yang menyatakan bahwa bukan ideologi (ide, agama, norma,
dst.) yang menentukan sejarah melainkan kontradiksi pada
modus produksi.
2 Ibid., hlm. 34.4
Pentahapan ini lalu dirinci ke dalam empat tahap.
Berikut adalah bentuk skematik dari empat tahap tersebut:3
1. 1840-1844 atau Karya Awal
Dalam periode ini Althusser mengelompokkan semua karya
Marx sejak Disertasi Doktoralnya tentang Epikuros sampai
Manuskrip Ekonomi dan Filsafat 1844 (atau Manuskrip Paris)
dan Keluarga Suci. Althusser juga membagi periode “Karya
Awal” ini ke dalam dua tahap:
- Tahap “humanisme liberal-rasionalis” yang tampak dalam
artikel-artikel Marx dalam Die Rheinische Zeitung
(sampai dengan tahun 1842). Konteksnya adalah kritik
terhadap sensor pemerintah despotik Prusia, hukum
feodal Rhein dan kebebasan pers. Althusser merumuskan
pandangan Marx dalam periode ini: “Hanya esensi
manusia lah yang menciptakan sejarah, dan esensi ini
adalah kebebasan dan rasio.”4 Oleh karena penekanan
pada kebebasan dan rasio inilah Althusser
mendeskripsikan juga periode ini sebagai periode
“Kantio-Fichtean”—sebab masih kental dengan nuansa
filsafat Immanuel Kant dan Fichte. Seruan filsafat,
sebagaimana dinyatakan Marx, adalah: “Filsafat
menuntut agar Negara menjadi Negara kodrat manusia
[the State of human nature].”5 Jadi sifatnya masih sebatas
3 Ibid., hlm. 35.4 Ibid., hlm. 223-224.5 Pernyataan Marx dalam Rheinische Zeitung tanggal 14 Juli 1842, sebagaimana dikutip dalam ibid., hlm. 224.
5
“seruan moril” atau kritik yang berbasis pada sentimen
kemanusiaan.
- Tahap “humanisme komunalis-rasionalis” yang tampak
dalam tulisan-tulisan Marx antara tahun 1842-1845.
Althusser mengartikan periode ini sebagai periode
“Feuerbachian” oleh sebab Marx berkutat dalam medan
problematik Feuerbach. Ini nampak dalam pengertian
baru Marx tentang esensi manusia, kini tak lagi
sebagai kebebasan dan rasio, melainkan sebagai
“makhluk komunal” (Gemeinwesen) dan sejarah adalah
sejarah alienasi esensi komunal ini sebuah sejarah
yang akan ditebus oleh revolusi komunis, yakni
komunisme sebagai realisasi esensi diri manusia
sebagai makhluk komunal.6 Medan problematik ini
dikatakan bersifat Feuerbachian karena Feuerbach lah
yang melihat esensi manusia pada dimensi organis-
komunalnya: manusia sebagai species (Gattung), sebagai
totalitas eksistensi individual.7 Komunisme Feuerbach,
dengan demikian, lebih menyerupai “komunisme” jemaat
Kristen purba yang tersusun oleh komunitas-komunitas
kecil yang mendasarkan diri pada prinsip cinta kasih
dan persaudaraan.8 Marx, tentu saja, tidak menerima
mentah-mentah elaborasi nostalgis-romantik Feuerbach
ini. Namun medan problematiknya masih serupa. Upaya
Marx selanjutnya, adalah menggeser medan problematik
6 Ibid., hlm. 226.7 Louis Althusser, On Feuerbach dalam The Humanist Controversy, op.cit., hlm. 142.8 Lih. Ibid., hlm. 148.
6
ini: problemnya bukan lagi realisasi esensi manusia,
realisasi species manusia, yang mana sejarah nampak
sebagai sejarah penebusan umat manusia, melainkan
sesuatu yang akan menjadi ciri spesifik teori Marx.
2. 1845 atau Karya Patahan9
Periode patahan ini mencakup dua karya, yakni Tesis-
Tesis tentang Feuerbach dan Ideologi Jerman. Dalam kedua
karya inilah, menurut Althusser, Marx mengajukan medan
problematik yang baru, yang berbeda dari yang dirumuskan
oleh para pemikir sebelumnya. Pergeseran medan problematik
ini terwujud dalam pergeseran dari titik pijak humanis ke
titik pijak “anti-humanis”. Ini terlihat, misalnya, dalam
Tesis VI tentang Feuerbach:
Feuerbach mengubah esensi agama menjadi esensi
manusia. Namun esensi manusia bukanlah abstraksi yang
inheren dalam setiap individu. Sejatinya, ia adalah
kumpulan relasi sosial [ensemble of social relations].
Feuerbach, yang tak masuk ke dalam kritisisme atas
esensi riil ini, kemudan terpaksa:
9 Penempatan tahun 1845 sebagai tahun patahan dalam sejarah pemikiranMarx adalah kontribusi spesifik Althusser untuk wacana periodisasipemikiran Marx. Althusser sendiri menyadari kebaruan kontribusinyaini, sebagaimana nampak dalam perbandingannya dengan Lucio Collettidan Galvano Della Volpe, dua orang Marxis besar dari Italia, yangmenempatkan patahan itu “terlalu dini”, yakni pada tahun 1843 yangditandai dengan tulisan Marx, Pengantar menuju Kritik atas Filsafat Hukum Hegel.Louis Althusser, For Marx, op.cit., hlm. 37-38.
7
a. Mengabstraksikan dari proses historis dan menetapkan
sentimen religius sebagai sesuatu yang ada dengan
sendirinya dan mempostulatkan suatu individu manusia yang
abstrak, terisolasi.
b. Esensi hanya dipahami sebagai ‘Gattung’, sebagai
generalitas internal yang bodoh yang secara
alamimempersatukan banyak individu.10
Artinya, Marx mulai mengkritik visi komunal-spekulatif
Feuerbach dengan menggeser medan problematiknya dari
problem realisasi esensi manusia (humanisme) ke problem
relasi sosial. Selanjutnya, dalam Ideologi Jerman, problem
relasi sosial ini diolah dengan memecahnya ke dalam konsep-
konsep yang khas Marxis: konsep formasi sosial, kekuatan
produktif, relasi produsi, superstrukur, ideologi dan
sebagainya.11
3. 1845-1857 atau Karya Transisional
Dalam periode ini tercakup karya-karya berikut:
Kemiskinan Filsafat, Kerja Upahan dan Kapital, Manifesto
Partai Komunis, artikel-artikel dalam Neue Rheinische
Zeitung, Sambutan Komite Sentral kepada Liga Komunis,
Perjuangan Kelas di Prancis, Brumaire Kedelapanbelas Louis
Bonaparte dan terakhir Grundrisse. Apabila dalam periode
sebelumnya, rumusan Marx atas medan problematik yang khas
Marxis masih bersifat negatif—dalam arti, diwujudkan masih
10 Karl Marx, Early Writings diterjemahkan oleh Rodney Livingstone danGregor Benton (London: Penguin), hlm. 423.11 Louis Althusser, For Marx, op.cit., hlm. 227.
8
dalam batas kritik atas pandangan sebelumnya—maka dalam
periode ini, bagi Althusser, Marx mulai mengkonstruksi
secara positif medan problematiknya sendiri. Mulai tahap
inilah “patahan epistemologis” itu dinyatakan secara
positif: tidak lagi sebagai kritik melainkan sebagai
bangunan teoretik. Menurut Althusser, patahan ini menjadi
positif dalam pendirian “dua disiplin teoretik yang berbeda
namun berkelindan”,12 yakni materialisme historis dan
materialisme dialektis.
4. 1857-1883 atau Karya Matang
Tahap terakhir ini mencakup karya-karya seperti
Kontribusi bagi Kritik atas Ekonomi-Politik, Kapital I-III
beserta berbagai draf dan revisinya, Upah, Harga dan Laba,
Perang Saudara di Prancis, Kritik atas Program Gotha dan
seterusnya. Pada tahap ini, konsepsi utuh tentang
materialisme historis dan materialisme dialektis tampil
menggantikan keseluruhan sisa ideologi borjuis (humanisme).
Artikulasi paling utuh dari konsepsi ini adalah Kapital.
Jika hendak diringkaskan, keseluruhan periodisasi yang
distruktur oleh patahan epistemologis ini dapat diterangkan
dalam dua aspek:13
a. Transisi dari ideologi tentang sejarah (sejarah sebagai
horizon penebusan esensi manusia) menuju sains sejarah
12 Ibid., hlm. 33.13 Louis Althusser, The Humanist Controversy, op.cit., hlm. 231.
9
(materialisme historis—sejarah yang ditentukan, pada pokok
terakhir oleh kontradiksi pada modus produksi).
b. Transisi dari “idealisme rasionalis Neo-Hegelian” (Hegel
yang dibaca dalam kerangka Kantian), melalui “materialisme
humanis Feuerbach” (1842), lantas ke “empirisisme
historisis” dalam Ideologi Jerman (1845-1846), dan akhirnya
(mulai 1857), ke filsafat yang baru secara radikal, yakni
materialisme dialektis.
A. Absolut dan Relatif
Pemikiran Althusser bertumpu pada sisi nyata kehidupan
manusia dengan mengabaikan metafisika. Metafisika hanya
dianggap sebagai candu, sama seperti Marx, yang lalu ingin
membenarkan segalanya dan menjawab semua pertanyaan.
Althusser pun tidak sepenuhnya setuju pada Marx. Jika Marx
menyatakan bahwa sisi ekonomi adalah suatu determinisme
dalam struktur dasar, Althusser menyanggahnya dengan
mengatakan bahwa struktur dasar itu tidak terlalu
memengaruhi supra struktur.14 Althusser tidak sepenuhnya
menyanggah Marx karena ia berangkat dari pemikiran Marx,
namun ia berpandangan bahwa aspek ekonomi hanyalah sekedar
relatif dalam dunia supra struktur. Tatanan kehidupan
dipengaruhi oleh suatu aspek perantara yang mengatasi kedua
struktur tersebut. Dengan demikian, Althusser menolak
determinisme ekonomi pula seperti digagas Marx.
14 Hans Bertens dan Joseph Natoli (ed.), 2002, Postmodernism: The Key Figures, Blackwell Pub:Oxford, hal. 11.
10
Aspek perantara yang relatif tersebut adalah ideologi.
Aspek perantara ini bukan berarti berada di tengah-tengah,
namun ia lebih pada penunjukan diri di dalam basis dan
supra struktur.15 Dalam hal ini, Althusser menyatakan
ideologi dalam interpretasi atas gagasan ekonomi yang nyata
dipergunakan untuk kepentingan manusia. Ideologi ini sudah
penuh dengan tafsir sepihak dari manusia yang secara
otomatis juga berdampak pada dunia kedua struktur di atas.
Dalam hal ini, ideologilah yang membentuk struktur itu
sendiri. Manusia sebagai makhluk yang reflektif tidak
mencerna ide secara langsung, namun melalui tafsir-tafsir
yang dibentuk dan sekaligus membentuk manusia. Pada sisi
inilah kondisi sosial tersusun dalam struktur tafsir
melalui tingkatan-tingkatan otonom sosial budaya dengan
berpusat pada ekonomi.16 Tafsir ini secara jelas dalam
totalitas kehidupan legal formal dinyatakan sistematis
dalam sistem negara. Sistem negara adalah suatu sistem
publik yang mengatur hidup bermasyarakat. Sistem ini
dibentuk melalui ide akan adanya keluarga, pendidikan,
agama, serta kepentingan bersama. Bukan hanya bersifat
vertikal dari keluarga mengarah pada negara atau
sebaliknya, dalam hal ini ideologi membuat sistem negara
menjadi sistem yang kompleks yang sekaligus menjadikan
segala aspek manusia terhubung.
15 Louis Althusser, 2001, Lenin and Philosophy and other essays, Monthly Review Press:New York, hal. 91.16 John Lechte, 2001, Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas, Kanisius:Yogyakarta, hal. 66.
11
Althusser membedakan dua konsep tentang ideologi;
Repressive State Apparatus (RSA) dan Ideological State
Apparatus (ISA).17 RSA lebih menunjuk pada aktor-aktor yang
berperan penting menginterpretasikan sekaligus
mengaplikasikan ideologi antar sesama manusia. Pada aspek
ini, Althusser memandang RSA sebagai pemilik kuasa represif
untuk dengan tegas menerapkannya pada setiap warga negara.
ISA mengarah pada ideologi itu sendiri yang masuk ke dalam
setiap kehidupan manusia. Ideologi ini terangkum dalam
aspek keagamaan, pendidikan, hukum, keluarga, politik,
komunikasi, serta moralitas.18 Pada sisi ini, Althusser
menekankan sisi produksi dan reproduksi material dalam
ideologi. Produksi tidak mungkin ada tanpa reproduksi
karena proses pembentukan memerlukan sesuatu untuk
dibentuk. Hubungan antar manusia menjadi basis penting
dalam ideologi, bukan hanya sekedar pemilik modal dan
buruh, melainkan juga antara pemilik kuasa ideologis dan
sasaran ideologis itu sendiri. Setiap ada proses produksi
ideologis, maka disitu pula ada reproduksi ideologis yang
digunakan untuk melanggengkan ideologi itu sendiri. Dengan
demikian, bukan hanya sikap antar manusia yang menjadi
fokus dari ideologi, melainkan juga tatanan sosial yang
terus-menerus membentuk ulang ideologi itu. Althusser
menyebutnya sebagai overdeterminasi guna mengatasi
ketunggalan esensi ekonomi dalam ideologi.19 Proses17 Louis Althusser, 2010, Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Ctudies, Jalasutra: Jakarta, hal. 19.18 Bertens, Op. Cit., hal. 197.19 Lechte, Loc. Cit., hal. 70.
12
produksi dan reproduksi memang berasal dari aspek ekonomi,
namun dalam perkembangannya, ideologi menjadi suatu esensi
otonom yang bukan hanya merengkuh sisi ekonomi, namun juga
sosial budaya. Proses ekonomi ini memang tidak langsung
terungkap dalam ideologi atau kesadaran, melainkan muncul
sebagai akibatnya dalam bentuk realitas sosial akan
gagasan-gagasan.
Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga, anak tentu
diwajibkan untuk patuh kepada orang tua. Hal ini bukan
hanya sekedar sisi ekonomi, misalnya karena orang tua
memberikan sangu kepada anak lalu anak harus menurutinya.
Demikian pula dengan keinginan orang tua kepada anak supaya
bisa memberi uang yang banyak kepada mereka. Para pemikir
humanis dan historis mengandalkan aspek cinta kasih dalam
hubungan ini, bahwa karena anak telah dilahirkan dan
dirawat oleh orang tua maka anak sudah seharusnya mematuhi
perintah orang tua. Jika demikian, maka seharusnya semua
perlakuan anak kepada orang tua ataupun sebaliknya adalah
seragam dengan keluarga yang lainnya, namun mengapa ada
anak yang tidak patuh kepada orang tua atau ada orang tua
yang sampai tega membunuh darah dagingnya sendiri? Ataupun
juga jika hubungan ini dilandaskan atas cinta kasih, lalu
mengapa didikan orang tua ada yang berhasil dan tidak?
Melalui penjelasan Althusser, kasus ini bukan dalam
pandangan humanis dan historis, melainkan dengan kacamata
ideologis. Dalam mendidik anak, orang tua menerapkan13
ideologinya kepadanya. Ia secara tidak langsung dipaksa
untuk meniru apa yang diperbuat orang tuanya baik secara
langsung maupun tidak. Dalam hal ini, pengalaman berperan
penting dalam sisi ideologis. Bisa saja orang tua itu tidak
tahu cara mendidik anak yang tepat karena ia dulu juga
diperlakukan tidak tepat oleh orang tuanya. Selain itu,
bisa saja ada faktor eksternal ideologi lain yang
menginterupsi internalisasi orang tua kepada anak, misalnya
saja pergaulan dengan teman dan lingkungan sekitar.
Pendidikan anak oleh orang tua ini bukan hanya dalam sisi
keluarga secara eksklusif saja, namun juga dibentuk oleh
nilai-nilai lain misalnya agama dan komunikasi. Seorang
anak biasanya menganut agama yang sama dengan orang tuanya
karena orang tua secara tidak langsung menginternalisasikan
nilai agama kepada anaknya. Mungkin saja orang tua itu
tidak memaksakan suatu agama kepada anaknya, namun proses
internalisasi ideologis yang terus menerus tidak disadari
menjadi faktor pendorong anak itu untuk memeluk agama yang
sama dengan orang tuanya.
B. Kesadaran Palsu dan Ketidaksadaran
Dalam ideologi, sangat sulit untuk membedakan apakah
aktor ideologis itu berperan dalam proses produksi dan
reproduksi dalam kerangka kesadaran palsu atau
ketidaksadaran. Meskipun demikian, kedua hal tersebut
sangat berhubungan dan dapat ditelusuri lebih lanjut.
Ideologi melihat individu dan tatanan sosial dalam kerangka
subjek sekaligus objek. Tidak seperti pandangan subjek14
terhadap objek menurut Sartre, ideologi memandang individu
sebagai objek untuk menjadi subjek.20 Hal ini dikarenakan
proses produksi dan reproduksi yang selalu berjalan
sekaligus. Ketika individu menerapkan suatu ideologi kepada
yang lain, ia pasti telah menginternalisasi ideologi dari
yang lain sebelumnya. Dalam hal ini, ideologi membangkitkan
individu untuk menjadi subjek dengan sekaligus
mengobjekkannya layaknya barang produksi dan reproduksi.21
Kesadaran subjek dalam subjektivitas pun dipertanyakan
demikian pula dengan objektivitas. Subjek mungkin saja
sadar dengan apa yang dilakukannya adalah dalam tatanan
ideologis, namun itu adalah kesadaran palsu karena ia tidak
sadar telah masuk dalam tatanan ideologis itu sendiri
dengan menjadi objek. Tidak ada yang dominan maupun tidak
dominan karena ideologi telah masuk sekaligus keluar dari
individu.
Ide tentang kesadaran dari para eksistensialis menjadi
dipertanyakan karena baik le regard menurut Sartre dan cinta
kasih menurut Marcel adalah ideologi itu sendiri. Sartre
sangat terpengaruh oleh kondisi keluarga dan lingkungannya
yang mengabaikan dirinya sehingga ia menganggap orang lain
sebagai neraka bagi dirinya. Demikian pula dengan Marcel,
bahwa meskipun cinta kasih itu ada dalam setiap diri
manusia, namun ia tidak dapat mengelak bahwa pemikirannya
sangat dipengaruhi oleh konteks agama Katolik. Sartre dan
20 Lechte, Op. Cit., hal. 71.21 Fredric Jameson, 1991, Posmodernism Or, The Cultural Logic of Late Capitalism, London:Verso, hal. 403.
15
Marcel mengatakan bahwa eksistensi manusia adalah menemukan
realitas dirinya sendiri. Pada kenyataannya, realitas diri
adalah kompleksitas berbagai tatanan ideologis yang
membentuknya. Manusia tidak akan mungkin menemukan dirinya
sendiri secara utuh karena ia pasti dibentuk dan sekaligus
membentuk perbuatan individu lain. Bahkan jika ia menolak
suatu ideologi, ia pun akan memunculkan suatu ideologi baru
yang terlihat dalam proses reproduksi.
Ideologi, menurut Althusser, adalah representasi
imajiner antara individu dan kondisi nyata.22 Representasi
ini adalah materi inderawi ataupun bukan yang membentuk
dasar pengambilan keputusan seseorang. Pada sisi ini,
manusia telah kehilangan eksistensinya karena ia secara
tidak sadar (ataupun sadar secara palsu) telah
menginternalisasi ideologi di dalam dirinya. Kalaupun
manusia sadar dalam mengambil keputusannya yang didasarkan
atas tatanan ideologis lalu menelusurinya, ia pun akan
menemukan bahwa titik awalnya juga adalah ideologi. Maka
bisa dikatakan ia sebenarnya tidak sadar didalam
pengambilan keputusannya karena ia sudah dikuasai oleh
ideologi. Dari sisi negara, hal ini pun sama karena pada
dasarnya negara adalah represif menurut Althusser. Sikap
represif negara itulah yang melanggengkan proses
internalisasi ideologi ke masyarakat. Karena negara
dianggap sebagai representasi publik dalam sebuah konsensus
imajiner, individu pun harus patuh akan tindakan negara.
22 Althusser, Op. Cit., hal. 52.16
Pada titik inilah RSA juga mencerminkan ISA, bahwa ada
keterkaitan erat antara tindakan represif dan ideologi
represif itu sendiri. Adanya kepatuhan dari warge negara ke
negara bukan semata-mata demi kepentingan publik, namun
lebih kepada doktrin ideologis yang pelan-pelan dan secara
terus menerus disuntikkan oleh negara.
Althusser menekankan pemikirannya dalam sisi esensial
subjek dengan mengesampingkan eksistensi individu dengan
bertumpu pada representasi ideologi. Jika eksistensialisme
menekankan subjek sebagai eksistensi, maka Althusser
menyatakan material sebagai eksistensi ideologi.23 Struktur
ideologi inilah yang setiap saat manusia bicarakan, yang
baik secara langsung atau tidak terinternalisasi ke dalam
diri manusia. Proses internalisasi ini disebut oleh
Althusser sebagai interpelasi melalui bahasa dan citra.24
Interpelasi ini sangat erat dengan kekuasaan, bukan saja
dalam negara, namun juga dalam setiap diri individu. Setiap
individu dalam masyarakat telah mengalami praktek sosial
yang secara otomatis melibatkan dirinya di dalam struktur
tersebut. Proses interpelasi ini tidak dapat dihindari
dalam masyarakat, bahkan ketika manusia berpikir akan
dirinya sendiri karena individu adalah cerminan dari
komunitas sosial yang membentuknya secara ideologis.
Kontroversi Kurikulum Pendidikan 2013 adalah contoh
tepat tentang adanya sisi ideologis dalam tata negara.
23 Althusser, Op. Cit., hal. 42.24 Jameson, Op. Cit., hal. 345.
17
Sebagai representasi negara, Mendikbud tentunya mempunyai
kuasa untuk menerapkan kurikulum baru. Secara represif, ia
melakukannya dalam kapasitas aparat negara melalui ideologi
kurikulum tersebut. Pendidikan memang ranah publik, namun
dengan keberadaan ideologi, hal ini dipengaruhi sekaligus
memengaruhi sisi privat. Hal ini dikarenakan pendidikan
juga menyangkut sistem sosial budaya di masyarakat yang
dengan jelas menyentuh ranah individu pelajar. Dalam kasus
ini, sikap represif negara sangat terlihat dengan berdalih
pada pembentukan sistem pendidikan yang lebih baik.
Interpelasi yang dilakukan kepada tatanan legislatif dan
masyarakat pun telah dilakukan, namun itu bukan berarti ada
perubahan pada rencana kurikulum tersebut. Hal yang terjadi
adalah komunikasi sepihak yang dilakukan hanya untuk
menyebarluaskan informasi tentang keberadaan rencana
kurikulum baru dan bukan diskusi tentang ideologi yang akan
diterapkan. Ide yang dianut pemerintah adalah mewujudkan
pendidikan yang lebih baik lalu ditafsirkan ke dalam
ideologi bentuk kurikulum yang baru. Ideologi ini
diterapkan secara represif dengan anggapan bahwa rakyat
harus percaya pada pemerintah bahwa ia akan membawa
pendidikan di negeri ini ke arah yang lebih baik.
Permasalahan kurikulum ini adalah tentang sisi praktis
yang sangat ditonjolkan oleh pemerintah. Pemerintah
mengatakan bahwa mata ajaran sudah seharusnya ditujukan
18
untuk mengatasi gap antara lulusan dan pasar tenaga
kerja.25 Pemerintah menyiratkan gagasan bahwa Indonesia
harus mampu beradaptasi dengan perekonomian global yang
semakin praktis. Dengan berbasis kompetensi, siswa memang
akan dibawa pada pengembangan diri, namun jika tanpa
pengembangan karakter, itu hanya akan membentuk mereka
menjadi manusia yang konsumtif. Mereka akan menjadi pelahap
segalanya tanpa ada nilai yang membatasi mereka. Kurikulum
ini jelas adalah fokus pemerintah pada pembangunan
infrastruktur. Dengan membangun pelajar menuju pada
kesiapan di bidang pekerjaan praktis, maka hal ini sejalan
dengan program pemerintah yang mengandalkan investasi dalam
pembangunan. Padahal jika dianalisis lebih lanjut, analogi
investasi adalah seperti bangunan yang besar namun dibangun
di atas konstruksi yang lemah. Sistem ekonominya pun adalah
mengambang yang sangat bergantung pada fluktuasi pasar.
Jika hal ini tidak diimbangi dengan pembangunan karakter,
maka dampaknya sudah dapat dilihat dengan contohnya korupsi
dan penyelewengan otoritas dimana-mana. Selain itu, sistem
yang dikembangkan dalam kurikulum ini adalah mandiri dengan
salah satu penekanannya pada entrepeneurship. Hal ini bagus
karena mampu membuka lapangan kerja bagi yang lain ketika
sudah lulus, namun hal ini tidak begitu saja dapat
menyentuh pembangunan di bidang sosial budaya. Hidup bukan
hanya tentang mencari kerja demi uang saja, namun ada sisi
25 Anon, 2013, SBY: Kurikulum Tentukan Mutu Pendidikan, (online) dalam http://news.okezone.com/read/2013/04/02/373/785031/sby-kurikulum-tentukan-mutu-pendidikan, diakses 17 Juni 2013.
19
sosial yang harus diperhatikan. Fokus kurikulum tersebut
untuk menambah jam dalam mata ajaran agama juga menjadi hal
yang dipertanyakan.26 Agama memang bagus untuk mengawal
moral siswa, namun di sisi lain, dampak ideologis penerapan
hal ini begitu besar. Indonesia saat ini penuh dengan
pertentangan antar agama terutama yang mayoritas dan
minoritas. Bayangkan saja bila sejak kecil seorang anak
terlalu banyak diajarkan tentang agama dan bukan konteks
kesetiakawanan sosial, maka mereka akan dengan mudah
menerapkan stereotype kepada yang lain. Mereka menganggap
diri mereka sukses dengan memiliki uang dan berbakti pada
agamanya saja, namun bisa dengan mudah mengabaikan orang
lain yang berbeda agama dan miskin. Akibatnya, manusia
hanya akan hidup setengah-setengah, menganggap bahwa hanya
dengan memberikan sumbangan dalam ketetapan agama dianggap
sudah cukup. Belum lagi ditambah dengan perbedaan ras,
suku, budaya, dan lain-lain. Mereka bisa saja menjadi
mandiri, namun juga dengan mudah melupakan orang lain.
Kurikulum ini hanya akan banyak mengajarkan siswa tentang
know-how dan bukan know-what apalagi know-why. Pendidikan
akan semakin dibawa ke ranah ideologi yang praktikal dengan
perlahan-lahan meninggalkan kemampuan manusia untuk
berpikir kritis. Sisi kritis yang dikembangkan adalah bukan
mengembangkan diri mencari kebenaran, namun kritis dalam
26 Anon, 2013, Kontra dan Pro Kurikulum 2013, (online) dalam http://www.radaronline.co.id/berita/read/24155/2013/Kontra-dan-Pro-Kurikulum-2013, diakses 17 Juni 2013.
20
menekuni suatu bidang saja. Akibatnya, nilai etis pun akan
semakin tergerus oleh kurikulum yang semacam ini.
C. Ideologi, Kesadaran Manusia, dan Kapitalisme
Althusser memang mengatakan bahwa bukan eknomi saja
yang menjadi titik penting dari dunia struktur dan supra
struktur. Pada perkembangannya saat ini, banyak hal yang
lalu dikaitkan erat dengan ekonomi. Banyak orang yang tidak
menyadari ini dan baru memahaminya ketika mereka depresi,
bahkan banyak pula yang malah menenggelamkan diri dalam
kenikmatan dunia tanpa menyadari siapa mereka. Kemunculan
ideologi tidak sepenuhnya membunuh eksistensialisme sebagai
dasar subjektif kesadaran manusia. Ideologi memang bergerak
dalam tatanan ketidaksadaran yang menidakkan kesadaran.
Meskipun demikian, hal ini bukan berarti bahwa manusia
harus tunduk pada ideologi saja. Ia harus tahu dan berpikir
tentang apa yang ada dibalik setiap hal karena tidak ada
hal yang hadir begitu saja tanpa ada tujuannya. Kita
mungkin tidak bisa lepas dari ideologi, namun berpikir
tentang adanya ideologi adalah jalan keluar bagi
pembentukan diri yang lebih baik. Dunia sedang penuh dengan
modernitas akan segala hal yang instan tanpa memikirkan
efek samping dari hal tersebut. Tugas manusia berziarah di
bumi ini bukan menenggelamkan diri di dalamnya, namun
melampauinya dengan mulai bertanya tentang segalanya.
Ide posmodernisme memang penuh dengan kritik mendasar
tentang kehidupan. Ia sekaligus menolak filsafat yang
21
terlalu spekulatif dan tidak menyentuh kehidupan praktis.
Para posmodernis lebih mengarahkan kritiknya sebagai solusi
atas disorientasi itu sendiri.27 Meskipun demikian, itu
tidaklah cukup dalam mengatasi problem kehidupan. Manusia
perlu terus mencari diri sendiri. Kendati manusia tahu ia
tidak bisa lepas dari ideologi, namun ia harus terus
menemukan ideologi akan kebenaran. Hal ini penting supaya
ide akan kebenaran juga akan terus dicari. Jadi bukan hanya
sekedar tafsir atas kebenaran saja, namun tafsir itu mesti
terus ditelusuri untuk terus memaknai kehidupan secara
reflektif baik secara individual maupun dalam tatanan
sosial di masyarakat.
Tesis Althusser Tentang Ideologi
Althusser punya dua tesis tentang ideologi. Tesis
pertamanya mengatakan bahwa ideologi itu adalah
representasi dari hubungan imajiner antara individu dengan
kondisi eksistensi nyatanya. Yang direpresentasikan disitu
bukan relasi riil yang memandu eksistensi individual,
tetapi relasi imajiner antara individu dengan suatu keadaan
dimana mereka hidup didalamnya.
Tesis yang kedua mengatakan bahwa representasi gagasan
yang membentuk ideologi itu tidak hanya mempunyai
eksistensi spiritual, tetapi juga eksistensi material. Jadi
bisa dikatakan bahwa aparatus ideologis negara adalah
27 I. Bambang Sugiharto, 1996, Posmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat, Kanisius:Yogyakarta, hal. 29.
22
realisasi dari ideologi tertentu. Ideologi selalu eksis
dalam wujud aparatus.
Eksistensi tersebut bersifat material. Eksistensi
material menurut Althusser ini bisa dijelaskan sebagai
berikut: kepercayaan seseorang atau ideologi seseorang
terhadap hal tertentu akan diturunkan dalam bentuk-bentuk
material yang secara natural akan diikuti oleh orang
tersebut. Misalnya jika kita percaya kepada Tuhan dan
termasuk penganut agama tertentu, maka kita akan pergi ke
gereja untuk mengikuti misa, pergi ke masjid untuk
sembahyang lima waktu. Atau kalau kita percaya keadilan,
maka kita akan tunduk pada aturan hukum, menyatakan protes,
atau bahkan ikut ambil bagian dalam demonstrasi, jika
ketidakadilan menimpa kita.
Bagi Althusser, kekuatan ideologi lahir dari
kesanggupannya untuk melibatkan kelas subordinat dalam
praktik, hingga dapat menuntun mereka pada identitas
konstruk sosial, ataupun subjektivitas tertentu yang
melibatkan diri mereka dengan ideologi tersebut, yang
jelas-jelas berlawanan dengan kepentingan sosial politis
mereka sendiri (2004 : xi). Lebih lanjut doi mengatakan
ideologi lebih merupakan partisipasi segenap kelas sosial,
bukan sekadar seperangkat ide yang dipaksakan oleh suatu
kelas terhadap kelas sosial lainnya. Fakta bahwa segenap
kelas berpartisipasi di dalam praktek tersebut tidak
berarti bahwa praktik itu sendiri tidak melayani
kepentingan kelas dominan. Yang dimaksud oleh Althusser23
adalah bahwa ideologi bersifat lebih efektif dibandingkan
apa yang diberikan oleh Marx, karena ideologi bekerja dari
dalam, bukan dari luar, dan secara mendalam
menginskripsikan cara berpikir dan cara hidup tertentu pada
segenap kelas.
Ideologi menurut Althusser telah menjerat dan
melingkupi manusia sejak kali pertama manusia dilahirkan.
Ideologi menjerat dengan menggunakan pendekatan analisis
psikologis gaya Lacan seperti yang dipaparkan oleh Bagus
Takwin, ia menjelaskan bahwa semua itu dilakukan dengan
menumbuhkan harapan. Seorang calon bayi yang bakal
terlahir, sejak dalam kandungan sudah dibebani dengan
harapan-harapan ibu bapaknya. Dia sudah dipersiapkan
menjadi pelengkap struktur keluarga, berperan sebagai anak
yang akan menyandang nama ayahnya, dan dipersiapkan untuk
menjalankan tugas-tugas yang dikandung perannya (2004 :
xiii – xix). Inilah awal beroperasinya sebuah ideologi
dalam kehidupan manusia. Takwin menjelaskan bahwa Althusser
menggunakan dua pendekatan untuk menjabarkan bagaimana
ideologi memanggil dan menempatkan individu sebagai subjek.
a) Pertama, pendekatan psikoanalisis Freudian yang
ditafsirkan oleh Jacques Lacan yang menunjukkan bahwa
individu selalu telah menjadi subjek, bahkan sebelum lahir.
Menurut Lacan sebelum kelahirannya, seorang anak selalu
telah diangkat di dalam dan oleh konfigurasi ideologi
keluarga yang khusus, yang “diharapkan” telah dipahami
bersama. Dari sinilah Althusser meminjam paham Freud.24
Menurut paham psikoanalisis asumsi dasar kehidupan manusia
adalah adanya insting hidup yang mendorong individu untuk
mempertahankan hidupanya dan menjaga kelangsungan
spesiesnya. Insting inilah yang menjadi dasar mengapa orang
tua ingin anaknya kelak menjadi sosok yang berguna,
berhasil dalam hidup, bahkan melebihi keberhasilan orang
tuanya. Muncullah harapan-harapan itu ! Fakta menunjukkan
bahwa keunggulan manusia dari makhluk hidup lainnya adalah
kualitas psikologisnya yang jauh di atas rata-rata makhluk
hidup lain. Kualitas psikologis itu memungkinkan manusia
untuk bertahan hidup dan melanggengkan spesiesnya lalu
dipolakan dalam kebudayaan dan peradaban, menjelma struktur
yang kemudian membentuk individu-individu baru sebagai
subjek penerus spesies manusia.
b) Pendekatan kedua bersandar sepenuhnya pada ide
materialisme Marx. Takdir manusia yang tidak bisa hidup
sendirian dalam mengarungi kehidupan memunculkan dua pola
dasar pilihan perilaku : bermusuhan atau berteman.
Kebutuhan bagi individu untuk berkelompok menimbulkan
kebutuhan kelompok untuk memelihara kepentingan setiap
anggotanya. Lahirlah upaya setiap individu untuk bersatu
dalam kelompok demi menjaga tetap eksisnya usaha pemenuhan
kebutuhan. Wujud konkret semua itu adalah produksi. Usaha
itu terus dilakukan dan setiap usaha yang dianggap baik
bagi produksi dipertahankan, dibakukan, dan diwariskan
kepada generasi penerus (direproduksi). Selain reproduksi
itu menciptakan sumber daya manusia dalam wujud tenaga
25
kerja yang terampil guna menghasilkan sumberdaya pemenuh
kebutuhan, juga ada reproduksi kesiapsediaan dan kepatuhan.
Reproduksi inilah yang sejalan dengan ide Antonio Gramsci
tentang hegemoni. Althusser mengatakan bahwa segala bentuk
institusi semacam sekolah, tentara, bahkan institusi
keagamaan berperan melanggengkan kebutuhan reproduksi
kepatuhan tersebut. Dalam penjelasan Althusser, semua agen
produksi, eksploitasi dan represi, termasuk para
‘profesional dari ideologi’, dengan cara sedemikian rupa
harus ikut bergerak seirama dalam ideologi yang mendukung
produksi agar dapat menjalankan tugasnya dengan ‘teliti’
dan ‘berguna’ bagi reproduksi produksi. Berbagai pihak
dalam masyarakat terlibat dalam proses reproduksi dan
produksi dalam relasi produksi yang terus dipertahankan dan
dikembangkan (2004 : xxii – xxiv).
Dari dua pendekatan itu sampailah kita pada kesimpulan
Althusser tentang ideologi. Menurutnya manusia itu
sebenarnya memiliki karakter dasar sebagai manusia
ideologi. Dengan tegas Althusser mengatakan “ dalam posisi
ini, sama saja bila dikatakan bahwa tidak ada sesuatu
apapun yang berada di luar ideologi (bagi dirinya sendiri),
atau pada saat yang sama, tidak ada sesuatu apapun yang
tidak berada di luar ideologi (bagi ilmu dan realitas).”
Jadi manusia telah dan akan terus terbenam dalam ideologi,
sejak sebelum jadi bayi hingga mati.
Kesimpulan
26
Dari pandangan-pandangan dan kritik-kritik Althusser
maka dapat diidentifikasi permasalahan-permahasalahan
maupun fenomena sosial yang ada. Misalnya pengaruh kekuatan
ekonomi dan politik dalam kehidupan bangsa bahkan
pengaruhnya secara global yakni mengeasi dan mengendalikan
proses-proses yang ada didunia. Dalam pergaulan antar
bangsa, kekuatan politik dan ekonomi memegang peranan
penting dalam pengambilan keputusan-keputusan maupun
langkah-langkah yang ditempuh dalam urusan-urusan yang
melibatkan banyak orang atau berdampak gobal. Selain itu
pandangan Althusser mengenai ideologi juga menjadi sebuah
pemahaman baru tentang ideologi manusia. Althusser melihat
ideologi sebagai suatu bagian kelengkapan anusia yang ada
sejak ia dilahirkan sehingga selama manusia hidup, maka
ideologi yang dianutnyapun akan hidup.
Contoh paling nyata adalah bagaimana marxisme,
komunisme dan atheisme yang masih ada dan terus dibicarakan
bahkan dipraktekkan di banyak negara. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun bagi sebagian orang pandangan sosialis
merupakan suatu ancaman terhadap kemerdekaan, namun banyak
pula yang beranggapan bahwa pandangan sosialis merupakan
pandangan yang terbaik dalam membangun suatu negara ataupun
komunitas. Pada masa perang dingin, Amerika dan blok barat
yang berhaluan kapitalisme liberal mengalahkan uni soviet
dan blok timur yang beraliran sosialis. Meskipun uni soviet
bubar namun paham sosialis tetap dianut oleh negara-negara
pecahan uni soviet tersebut. Meskipun para pemimpin blok
27
timur telah mati, ideologi yang dicetuskan oleh mereka
tetap masih dianut oleh para penerus mereka. Hal inilah
yang oleh Althusser dikatakan bahwa, ideologi tetap ada
selama manusia hidup.
Konsep Althusser mengenai aparatus juga terlihat di
masa kini dengan adanya berbagai alat kelengkapan suatu
negara yang memiliki aparan penegakan hukum, pengadilan
serta pembinaan ideologis seperti gereja, pura, wihara dan
lain-lain. Pandangannya mengenai penggunaan metode
represif oleh aparatus negara juga merupakan pandangan yang
hingga kini masih dapat dilihat. Seperti upaya pembubaran
demonstrasi dengan menggunakan kekuatan bersenjata serta
tindakan represif dari aparat dengan membubarkan paksa
kerumunan massa serta melakukan penahanan terhadap tokoh-
tokoh yan dianggap bertanggungjawab atas terjadinya
kerumunan massa tersebut. Konsepnya mengenai tindakan
represif ini dapat dijadikan suatu dasar dalam pembuatan
kebijakan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta
aturan yang membatasi tindakan represif yang boleh
dilakukan oleh aparatus negara dan aparatus ideologi
negara.
Konsep Althusser mengenai ideologi menjadi dasar
pembinaan ideologi oleh negara-negara di dunia. Althusser
memang merupakan ahli yang banyak berkutat di bidang
ekonomi, politik dan ideologis, sehingga tidak heran jika
banyak tulisannya yang berhubungan dengan politik, ekonomi
dan ideologis serta kritiknya tentang tokoh-tokoh serta28
teori-teori yang ada dari ketiga perspektif ilmu
pengetahuan tersebut. Kritiknya mengenai basis dan
superstruktur ditentang keras oleh para penganut marxis
tradisional karena mereka menganggap bahwa marxisme
merupakan suatu doktrin yang justru akan membawa manusia
menuju kebebasan kemanusiaan dalam lingkup dunia sosialis.
Mereka menganggap bahwa kapitalisme justru menyebabkan
manusia berada dalam keadaan yang terbelenggu sehingga
perlu untuk dibebaskan. Konsepnya mengenai ideologi yang
diyakininya tak akan mati menjadi dasar pertimbangan untuk
melarang disosialisasikannya doktrin-doktrin yang
bertentangan dengan dasar negara atau bertentangan dengan
hak asasi manusia. Karena setiap manusia berhak untuk
menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan dari
siapapun juga selama pilihannya tidak menyebabkan kerugian
bagi orang lain atau merusak tatanan ideologis yang ada.
29
Daftar Pustaka
———————, 2010, Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies,(terj.) Jalasutra: Jakarta
——-, 2013, SBY: Kurikulum Tentukan Mutu Pendidikan, (online) dalam (http://news.okezone.com/read/2013/04/02/373/785031/sby-kurikulum-tentukan-mutu-pendidikan), diakses 17 Januari 2015
_____. 2012. Ideologi Dan Praktek Kebudayaan. (Online), (http://www.anekamakalah.com/2012/03/ideologi-dan-praktek-kebudayaan.html), diakses 13 Januari 2015.
Althusser, Louis, 2001, Lenin and Philosophy and other essays, Monthly Review Press:New York
Anon, 2013, Kontra dan Pro Kurikulum 2013, (online) dalam (http://www.radaronline.co.id/berita/read/24155/2013/Kontra-dan-Pro-Kurikulum-2013), diakses 17 Januari 2015
Bertens, Hans dan Joseph Natoli (ed.), 2002, Postmodernism:The Key Figures, Blackwell Pub:Oxford
Damsar.2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Prenada
Media.
Felagonna, Utche P.2006.Tentang Louis Althusser: Catatan Awal Investigasi (Online), (http://tomixpribadi.blogspot.com/2006/11/tentang-louis-althusser-catatan-awal.html1), diakses 14 Januari 2015.
FX Widyatmoko, 2009, Louis Althusser, Sekilas, (online) dalam (http://dgi-indonesia.com/louis- althusser-sekilas/), diakses 17 Januari 2015
30
Jameson, Fredric, 1991, Posmodernism Or, The Cultural Logicof Late Capitalism, London:Verso
Lechte, John, 2001, Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas, Kanisius:Yogyakarta
Lewis, William, 2009, Louis Althusser, (online) dalam (http://plato.stanford.edu/entries/althusser/#TheIde), diakses 17 Januari 2015
Maliki, Zainuddin. 2008. “Sosiologi Pendidikan”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Sugiharto, I. Bambang, 1996, Posmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat, Kanisius:Yogyakarta
31