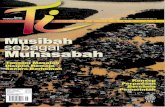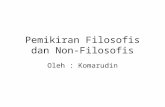Implementasi Pemikiran Hasyim Asyari pada Pesantren
Transcript of Implementasi Pemikiran Hasyim Asyari pada Pesantren
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari lahir pada hari
Selasa Kliwon, 24 Dzulqa’dah 1287 H, bertepatan dengan
tanggal 14 Februari 1871 M di Desa Gedang, satu kilometer
sebelah utara Kota Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama
Kiai Asy’ari berasal dari Demak, Jawa Tengah. Ibunya
bernama Halimah, puteri Kiai Utsman, pendiri Pesantren
Gedang.1 Dilihat dari garis keturunan itu, beliau termasuk
putera seorang pemimpin agama yang berkedudukan baik dan
mulia.
Semenjak masih anak-anak, Ia dikenal cerdas dan rajin
belajar. Mula-mula beliau belajar agama dibawah bimbingan
ayahnya sendiri. Otaknya yang cerdas menyebabkan ia lebih
mudah menguasai ilmu-ilmu pengetahuan agama, misalnya: Ilmu
Tauhid, Fiqih, Tafsir, Hadits dan Bahasa Arab. Karena
kecerdasannya itu, sehingga pada umur 13 tahun ia sudah
diberi izin oleh ayahnya untuk mengajar para santri yang
usianya jauh lebih tua dari dirinya. Selama bertahun-tahun
Ia berkelana dari pondok satu ke pondok yang lain, bahkan
beliau bermukim di Makkah selama bertahun-tahun dan berguru
kepada ulama-ulama Makkah yang termasyhur pada saat itu,
1 Drs. H.M. Laily Mansur, L.PH. Ajaran dan Teladan Para Sufi, hlm. 305.1 | P a g e
seperti: Syekh Muhammad Khatib Minangkabau, Syekh Nawawi
Banten dan Syekh Mahfudz At Tarmisi.2
Pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal
31 Januari 1926, K.H. Hasyim Asy’ari bersama K.H. Abdul
Wahab Hasbullah serta para ulama yang lain mendirikan
Jam’iyah Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam
terbesar di Indonesia. Hampir seluruh kiai di Jawa
mempersembahkan gelar “Hadratus Syekh” yang artinya “Maha
Guru” kepadanya, karena beliau adalah seorang ulama yang
secara gigih dan tegas mempertahankan ajaran-ajaran
madzhab. Dalam hal madzhab, beliau memandang sebagai
masalah yang prinsip, guna memahami maksud sebenarnya dari
Al Quran dan Hadits. Sebab tanpa mempelajari pendapat
ulama-ulama besar khususnya Imam Empat: Hanafi, Maliki,
Syafi'i dan Hanbali, maka hanya akan menghasilkan pemutar
balikan pengertian dari ajaran Islam itu sendiri.
Dalam rangka mengabdikan diri untuk kepentingan umat,
maka K.H. Hasyim Asy’ari mendirikan pesantren Tebuireng,
Jombang pada tahun 1899 M. Dengan segala kemampuannya,
Tebuireng kemudian berkembang menjadi “pabrik” pencetak
kiai. Dari sini dapat dilihat betapa besar pengaruh
Tebuireng dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Jawa
pada awal abad XX. Ribuan kiai di Jawa hampir seluruhnya
hasil didikan Tebuireng.
Pengabdian Kiai Hasyim bukan saja terbatas pada dunia
pesantren, melainkan juga pada bangsa dan negara. Beliau
2 Ibid., hlm. 305.2 | P a g e
seringkali ditemui tokoh-tokoh pejuang nasional seperti
Bung Tomo maupun Jenderal Soedirman guna mendapatkan saran
dan bimbingan dalam rangka perjuangan mengusir penjajah.
Pada saat Jepang berkuasa mereka memaksakan budaya
‘Saikerei’ yaitu menghormati Kaisar Jepang “Tenno Heika”
dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap ke
arah Tokyo, yang harus dilakukan oleh seluruh penduduk.
K.H. Hasyim Asy’ari menentangnya karena beliau beranggapan
hal itu haram. Membungkukkan badan semacam itu menyerupai
‘ruku’ dalam sholat, yang hanya diperuntukkan menyembah
Allah SWT. Akibat penolakkanya itu, pada akhir April 1942,
K.H. Hasyim Asy’ari ditangkap dan dijebloskan ke dalam
penjara di Jombang. Ribuan santri dan kiai alumni Tebuireng
berunjuik rasa, mereka meminta dipenjarakan bersama-sama
Kiai Hasyim sebagai tanda setia kawan dan pengabdian kepada
guru dan pemimpin mereka. Peristiwa itu cukup membakar
dunia pesantren dalam memulai gerakan bawah tanah menentang
dan menghancurkan Jepang. Pihak pemerintah Jepang agaknya
mulai takut, hingga kemudian pada 6 Sya’ban 1361 H
bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 1942, Kiai Hasyim
dibebaskan.
Pada Oktober 1943, NU dan Muhammadiyah bersepakat
membentuk organisasi gabungan menggantikan MIAI (Al
Majlisul Islamil A’la Indonesia) dan diberi nama MASYUMI
(Majlis Syuro Muslimin Indonesia) yang non politik,
pimpinan tertingginya dipercayakan kepada K.H. Hasyim
Asy’ari. Dan pada tahun 1944 beliau diangkat oleh
3 | P a g e
pemerintah Jepang menjadi Ketua SHUMUBU (Kantor Pusat
Urusan Agama). Pada masa-masa akhir pemerintahan Jepang di
Indonesia, Masyumi melatih pemuda-pemuda Islam khususnya
para santri dengan latihan kemiliteran yang kemudian diberi
nama Hizbullah.
Pada tanggal 7 Ramadlan 1366 bertepatan dengan tanggal
25 Juli 1947, K.H. Hasyim Asy’ari berpulang ke Rahmayullah.
Atas jasa beliau, pemerintah Indonesia menganugerahi gelar
“Pahlawan Nasional”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengajukan
satu pertanyaan umum, yaitu:
1.2.1 Bagaimana pemikiran Hasyim Asy’ari terhadap
pendidikan Islam di Indonesia?
1.2.2 Bagaimana implementasi pemikiran Hasyim
Asy’ari dalam Pesantren Tebuireng?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Penulis menetapkan ruang lingkup masalah secara
temporial yang digunakan dalam makalah ini yaitu dari tahun
1899 hingga tahun 1947. Tahun 1899 dipilih sebagai awal
perioderisasi dalam makalah ini karena tahun tersebut K.H.
Hasyim Asy’ari tiba di Indonesia setelah memperdalam Ilmu
Agama di Mekah sejak tahun 1893. Pada tahun tersebut pula
K.H. Hasyim Asy’ari pertama kalinya mendirikan Pesantren
Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Sedangkan tahun 1947
4 | P a g e
dipilih penulis sebagai akhir perioderisasi bahasan makalah
ini karena pada tahun tersebut K.H. Hasyim Asy’ari wafat.
Dengan begitu otomatis kepemimpinan Tebuireng diwariskan
kepada anaknya yaitu Wahid Hasyim.
Sedangkan ruang lingkup masalah secara spasial yang
ditetapkan oleh penulis adalah Indonesia. Karena pemikiran
K.H. Hasyim Asy’ari berkembang selama ia menuntut ilmu di
berbagai pelosok daerah dan bertemu dengan santri-santri
lain dari penjuru Indonesia. Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari
beserta Pesantren Tebuireng pun membawa pengaruh yang
besar bahkan menjadi suatu pembaharuan bagi banyak
pesantre-pesantren di Indonesia, khususnya Jawa Timur.
1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui
sejauh mana peranan K.H. Hasyim Asy’ari dalam rangka
memajukan umat lewat Pondok Pesantren Tebuireng yang Ia
bangun. Mengingat Pondok Pesantren Tebuireng adalah salah
satu pesantren yang membawa pengaruh dan perubahan besar
pada pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Selain itu
makalah ini juga dibuat untuk mengtahui bagaimana pemikiran
K.H. Hasyim Asy’ari terhadap pendidikan Islam di Indonesia
yang menjadi dasar perkembangan dari Pondok Pesantren
Tebuireng itu sendiri.
1.5 Metode Penulisan
5 | P a g e
Dalam penulisan makalah ini penulis memilih
menggunakan metode penulisan sejarah yang mana tahapannya
antara lain;
1.5.1 Heuristik
Penulis mencari sumber-sumber yang berkaitan
dengan tema makalah berupa buku teks di Perpustakaan
Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional RI. Selain
itu penulis juga mendapat kemudahan dengan dipinjamkannya
buku teks dari dosen mata kuliah yang bersangkutan. Penulis
juga mengakses website dan mendapatkan sebuah artikel.
1.5.2 Kritik
Setelah mendapatkan sumber-sumber tersebut
selanjutnya penulis memberikan kritik terhadap sumber-
sumber tersebut. Baik kritik intern maupun ekstern.
1.5.3 Interpretasi
Tahap berikutnya penulis memberikan interpretasi
pada sumber-sumber yang sudah ditetapkan dan menarik
kesimpulan dari beberapa sumber tersebut.
1.5.4 Historiografi
Tahap terakhir penulis mengembangkan kerangka
tulisan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah
dengan sistematika dan cara penlisan yang lebih rapih
dan tertata.
1.6 Sumber Data
6 | P a g e
Seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis
mendapatkan sumber-sumber untuk penulisan makalah ini di
Perpustakaan Universitas Indonesia dan Perpustakaan
Nasional RI, serta sebuah sumber dari dosen mata kuliah
yang bersangkutan dan sebuah artikel dari website. Sumber-
sumber tersebut antara lain:
Arifin, Imron. 1993. Kepemimpinan Kiyai: Kasus : Pesantren
Tebuireng. Malang: Kalimasahada Press.
Bashri, Yanto dan Retno Suffatni. 2005. (ed) Sejarah
Tokoh Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
Dhofier, Zamakhsyari. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang
Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: Penerbit LP3ES.
Khuluq, M.A., Drs. Lathiful. 2000. Fajar Kebangunan Ulama
Biografi K.H. Hasyim Asy’ari. Yogyakarta: LkiS.
Nata, Prof. Dr. H. Abuddin. 2011. Sejarah Pendidikan Islam.
Jakarta, Kencana.
Noer, Deliar. 1996. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 –
1942. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Mansur, L.PH., Drs. H.M. Laily. 1999. Ajaran dan Teladan
Para Sufi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Rifai, Muhammad. 2009. K.H. Hasyim Asy’ari Biografi Singkat
1871–1947. Yogyakarta: Garasi.
Steenbrink, Karel A. 1994. Pesantren, Madrasah, Sekolah:
Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen. Jakarta: PT Pustaka
LP3ES Indonesia.
Soekadri, Heru. 1982. Kiyai Haji HASYIM ASY’ARI. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat7 | P a g e
Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Naisonal.
http://www.nu.or.id.a,public-m,dinamic-s,detail-
ids,46-id,38786-lang,id-c,pesantren-t,Kisah+Tebuireng+
+dari+Mbah+Hasyim+hingga+Gus+Dur-.phpx (Diakses pada
14 April 2013 pukul 08.00 WIB)
1.7 Sistematika Penulisan
Penulis menyusun makalah ini ke dalam empat bab,
yaitu:
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang
menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode
penulisan, serta sistematika penulisan.
BAB II: PEMIKIRAN HASYIM ASY’ARI TERHADAP PENDIDIKAN
ISLAM DI INDONESIA
Bab kedua ini merupakan bab isi yang membahas
perluasan dari perumusan masalah pertama yaitu
Pemikiran Hasyim Asyari Terhadap Pendidikan Islam di
Indonesia.
BAB III: IMPLEMENTASI PEMIKIRAN HASYIM ASY’ARI DALAM
PESANTREN TEBUIRENG
Bab ketiga masih merupakan bab isi yang membahas
perluasan dari perumusan masalah kedua yaitu
8 | P a g e
Implementasi Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam Pesantren
Tebuireng. Dalam bab ini terdapat pula dua sub-bab mengenai
berdirinya Pesantren Tebuireng dan Perkembangan
Pesantren Tebuireng
BAB IV: PENUTUP
Pada bab keempat ini terdapat satu bab-bab yaitu
kesimpulan yang merupakan simpulan dari bab-bab
sebelumnya.
BAB II
PEMIKIRAN HASYIM ASY’ARI
TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
2.1 Pemikiran Hasyim Asy’ari
9 | P a g e
K.H. Hasyim Asy’ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871
(24 Dzulqadah 1287 H) dan wafat pada 25 Juli 1947. Masa
hidupnya selama 76 tahun banyak diwarnai oleh momen ataupun
fase penting dalam kondisi sosial dan politik Indonesia.
Fase-fase tersebut3 :
Akhir abad ke-19 yang sering disebut dengan second
Islamic Wave
kebijakan Politik Etis yang mulai diberlakukan pada
tahun 1900
Pertumbuhan organisasi modern seperti Budi Utomo pada
tahun 1908
Tercapainya konsensus gerakan nasionalisme sejak
tahun 1924
Perang Kemerdekaan
Kehidupan beliau sendiri terbagi dalam beberapa fase.
Fase pertama lahir dan dibesarkan dalam lingkungan
pesantren. Orangtua dan kakeknya merupakan pemimpin
pesantren di Jombang. Sejak kecil hingga beranjak dewasa,
K.H. Hasyim Asy’ari banyak berguru di berbagai pesantren di
pulau Jawa. Berkat bakat kepemimpinan dan kecerdasan yang
dimilikinya, beliau kemudian dinikahkan dengan salah satu
anak dari pemimpin pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo,
yaitu Kiyai Ya’qub. Fase kedua adalah ketika K.H. Hasyim
Asy’ari diberangkatkan haji ke Mekkah kemudian memperdalam
ilmu agama di sana. Setelah tujuh bulan, Hasyim kembali ke3 Prof Bernhard Dahm, dalam bukunya History of Indonesia in Twentieth Century (London: Pall Mall Press: 1971)
10 | P a g e
tanah air, sesudah istri dan anaknya meninggal. Tahun 1893,
beliau kembali ke tanah suci dan belajar di sana selama
tujuh tahun. Beliau memperdalam ilmu agama kepada banyak
guru, salah satunya Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau.
K.H. Hasyim Asy’ari lebih banyak memusatkan perhatian pada
ilmu hadits, yang merupakan kegemarannya.
Sekembalinya beliau ke Indonesia, K.H. Hasyim Asy’ari
mengajar di Pesantren Nggedang, sebuah pesantren yang
didirikan oleh kakeknya, KH. Utsman. Beberapa santri yang
beliau ajar di pesantren tersebut kemudian menjadi “pondasi
awal” terbentuknya pesantren yang didirikan oleh K.H Hasyim
Asy’ari di Tebuireng, Jombang. Santri yang diajak pada
awalnya berjumlah 8 orang, yang kemudian hanya dalam waktu
3 bulan bertambah menjadi 28 orang.
Di pesantren inilah, KH. Hasyim Asy’ari banyak
melakukan aktifitas tidak hanya berperan sebagai pimpinan
pesantren secara formal, melainkan juga sebagai pemimpin
masyarakat secara informal. Sebagai pemimpin pesantren, KH.
Hasyim Asy’ari melakukan pengembangan institusi
pesantrennya, termasuk mengadakan pembaruan sistem dan
kurikulum pesantren. Sedangkan perannya sebagai pemimpin
informal, KH. Hasyim Asy’ari menunjukkan kepeduliannya
terhadap kebutuhan masyarakat melalui bantuan pengobatan
kepada masyarakat yang membutuhkannya, termasuk juga kepada
keturunan Belanda.
11 | P a g e
Sistem pengajaran yang diterapkan Pesantren Tebuireng
sejak berdirinya (1899) sampai tahun 1916 adalah dengan
menggunakan sistem sorogan4 dan bendongan/halaqah5. Kedua
sistem tersebut digunakan sebagai metode utama dalam
mentransformasikan ilmu-ilmu agama kepada santrinya.
Pada 1916-1919, pelajaran umum di samping pelajaran
agama seperti Bahasa Melayu, Matematika dan Ilmu Bumi,
dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah. Sejak tahun 1926
ditambah dengan bahasa Belanda dan Sejarah Indonesia. Kedua
pelajaran terakhir ini diperkenalkan oleh Kyai Ilyas,
keponakan K.H. Hasyim Asy’ari yang telah menamatkan
pelajarannya di HIS6 Surabaya.
Perhatian K.H Hasyim Asy’ari yang begitu besar kepada
Pesantren Tebuireng sebenarnya bisa ditelusuri dari
pandangan dan pemikiran beliau terhadap pendidikan.
Pandangan dan pemikiran beliau terhadap pendidikan
diejawantahkan dalam kitab yang berjudul Adab al-Alim wa
al-Muta’allim. Kitab yang ditulis oleh K.H. Hasyim Asy’ari
ini membahas etika (adab) dalam mencari ilmu pengetahuan.
Menuntut ilmu merupakan pekerjaan agama yang sangat luhur,
4 santri membaca sendiri materi pelajaran kitab kuning di hadapan guru
5 kyai membaca kitab dan santri memberi makna
6 Hollandsch-Inlandsche School,12 | P a g e
sehingga orang yang mencarinya harus memperlihatkan etika-
etiak yang luhur pula.
Latar belakang kitab ini dipengaruhi oleh perubahan
yang cepat dan perubahan dari pendidikan klasik menuju
pembentukan pendidikan modern, di mana hal tersebut
dipengaruhi oleh penjajahan Belanda di Indonesia. Kitab
tersebut dibuat untuk memasukkan nilai etis, moral, seperti
nilai menjaga tradisi yang baik dan perilaku santun dalam
bermasyarakat, tanpa menolak kemajuan atau perubahan zaman.
Beliau menerima kemajuan dan perubahan zaman dengan syarat
tidak mengubah nilai substantifnya (melestarikan nilai-
nilai lama yang positif dan mengambil nilai-nilai baru yang
lebih positif)
Di dalam kitabnya ini, K.H Hasyim Asy’ari menyebutkan
bahwasanya pendidikan itu penting sebagai sarana mencapai
kemanusiaannya, sehingga menyadari siapa sesungguhnya
penciptanya, untuk apa diciptakan, melakukan segala
perintahnya dan menjauhi segala larangannya, untuk berbuat
baik di dunia dengan menegakkan keadilan, sehingga layak
disebut makhluk yang lebih mulia disbanding dengan makhluk-
makhluk lain yang diciptakan Tuhan.
Menurut beliau, tujuan diberikannya sebuah pendidikan
pada setiap manusia ada dua, yaitu:
13 | P a g e
1. Menjadi insan purna yang bertujuan mendekatkan diri
kepada Allah Swt.
2. Insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan
dunia dan akhirat
K.H. Hasyim Asy’ari membagi ilmu pengetahuan itu menjadi
tiga bagian :
1. Ilmu pengetahuan yang tercela dan dilarang. Artinya,
ilmu pengetahuan yang tidak dapat diharapkan
kegunaannya, baik di dunia maupun di akhirat, seperti
ilmu sihir, nujum, ramalan nasib dan sebagainya
2. Ilmu pengetahuan yang dalam keadaan tertentu menjadi
terpuji, tetapi jika mendalaminya menjadi tercela.
Artinya, ilmu yang sekiranya mendalami akan
menimbulkan kekacauan pikiran, sehingga dikhawatirkan
menimbulkan kufur. Misalnya, ilmu kepercayaab dan
kebatinan, ilmu filsafat
3. Ilmu pengetahuan yang terpuji, yakni ilmu pelajaran-
pelajaran agama dan berbagai macam ibadah. Ilmu-ilmu
tersebut dapat menyucikan jiwa, melepaskan diri dari
perbuatan-perbuatan tercela, membantu mengetahui
kebaikan dan mengerjakannya, mendekatkan diri kepada
Allah swt, mencari rida-Nya dan mempersiapkan dunia
ini untuk kepentingan di akhirat
14 | P a g e
Sementara itu, terdapat kesamaan pandangan antara K.H.
Hasyim Asy’ari dan Al-Ghazali mengenai hukum mempelajari
ilmu pengetahuan, yaitu :
1. Fardhu Ain. Artinya kewajiban mencari ilmu dibebankan
kepada setiap Muslim (setiap individu)
2. Fardhu Kifayah. Artinya ilmu yang diperlukan dalam
rangka menegakkan urusan duniawi
Apa yang menjadi inti seorang santri (atau pelajar)
bukan sekadar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, di mana pun
jua dengan belajar yang rajin dan penuh disiplin. Tapi
bagaimana ilmu yang sudah didapat itu harus dipraktikkan
atau bisa dimanfaatkan. Ilmu bukan hanya untuk dirinya
sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan khalayak umum. Itu
semua merupakan bekal untuk kehidupan di dunia dan akhirat.
BAB III
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN HASYIM ASY’ARI
DALAM PESANTREN TEBUIRENG
3.1 Berdirinya Pesantren Tebuireng
15 | P a g e
Pada akhir abad 19 saat itu di Indonesia dikenal dua
sistem pendidikan bagi penduduk pribumi. Pertama yaitu
sistem pendidikan Barat yang dikenalkan oleh pemerintah
kolonial Belanda dengan tujuan menyiapkan para siswa untuk
menempati posisi-posisi administrasi pemerintahan. Kedua
adalah sistem pendidikan yang disediakan untuk para santri
Muslim di pesantren yang fokus pengajarannya adalah ilmu
agama.7Metode utama sistem pengajaran di lingkungan
pesantren ialah sistem bandongan atau seringkali juga
disebut weton. Dalam sistem ini sekelompok murid (antara 5
sampai 500) mendengarkan seorang guru yang membaca,
menerjemahakan, menerangkan dan seringkali mengulas buku-
buku Islam dalam bahasa arab.8 Sebelum mereka belajar di
pesantren mereka telah lebih dulu mendapatkan pembelajaran
dasar secara individual atau sorogan oleh seorang ulama.
Jika mereka benar-benar ingin memetik keberhasilan dari
sistem di pesantren, maka lebih dulu mereka harus
memantapkan ilmu-ilmu dasar mereka.
Sudah menjadi seperti suatu hal yang diwajibkan bahwa
setiap santri yang belajar agama pastilah akan mengabdi
demi kemajuan umat. Sebagian besar dari mereka membagikan
ilmunya di pesantren-pesantren, sedangkan sebagian lagi
mendirikan pesantren mereka sendiri dalam menyebarkan
ilmunya. Setelah memperdalam agama Islam di Mekkah selama
7 Drs. Lathiful Khuluq, M.A., Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy’ari, hlm.21.
8 Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, hlm. 21.
16 | P a g e
hampir tujuh tahun sejak 1893 akhirnya K.H. Hasyim Asy’ari
kembali ke Indonesia pada 1899. Setibanya ia di Indonesia,
sempat sebentar ia ikut mengajar di pesantren milik
ayahnya. Seperti ulama lain yang ingin mengabdi demi
kemajuan umat melalui penyebaran ilmu dengan mendirikan
pesantren, K.H. Hasyim Asy’ari pun mulanya ingin mendirikan
pesantren di Plemahan (Kediri), tempat tinggal mertuanya.
Sayang rencananya itu gagal. Akhirnya ia memutuskan untuk
mendirikan pesantren di desa Tebuireng. Menurut cerita
masyarakat setempat, nama Tebuireng berasal dari kata kebo
ireng. Konon, ketika itu ada seorang penduduk yang memiliki
kebo yang berkulit kuning. Suatu hari kebo itu menghilang
entah ke mana. Setelah dicari kesana kemari, menjelang
senja barulah kebo tersebut ditemukan dalam keadaan hampir
mati karena terperosok ke dalam rawa-rawa yang banyak
dihuni lintah. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh lintah,
sehingga kulit kerbau yang semula kuni berubah menjadi
hitam. Karena saking terkejutnya, pemiliknya berteriak-
teriak: “kebo ireng..kebo ireng..kebo ireng”. Sejak saat itu desa
tersebut dikenal dengan nama Kebo Ireng.9 Desa Tebuireng
terletak di Kelurahan Cukir, sekitar 8 KM tenggara Jombang
dengan sistem transportasi yang terjangkau kendaraan
umum.10 Kelurahan cukir sudah cukup modern dan ramai di
masa itu, penduduknya sudah banyak yag bersifat urban
mengingat di daerah itu berdiri sebuah pabrik gula milik
9 Muhammad Rifai, K.H. Hasyim Asy’ari Biografi Singkat 1871–1947, hlm. 41.
10 Drs. Lathiful Khuluq, M.A., Op.Cit., hlm. 30.17 | P a g e
Belanda yang sudah pasti banyak pula pegawai-pegawai
Belanda yang tinggal di daerah itu. Namun sebagian besar
penduduk Kelurahan Cukir bermatapencaharian sebagai tani
dan buruh. Sehingga jelas terlihat kesenjangan sosial
maupun ekonomi di daerah tersebut. Tebuireng juga dikenal
sebagai desa yang penduduknya berperilaku sangat buruk.
Maka banyak pula yang menyebut Tebuireng sebagai desa yang
mirip dengan jaman jahiliyah.
Pesantren milik K.H. Hasyim Asy’ari tersebut dibangun
tidak jauh dari sebuah pabrik gula milik Belanda tersebut.
Menjadi suatu hal yang sangat menarik ketika sebuah
pesantren dibangun di dekat pabrik milik bangsa barat yang
dianggap sebagai simbol modernisasi. Sedangkan saat itu
Islam dianggap sebagai agama yang konservatif dan anti
modernisasi. Setelah diberlakukannya ekonomi liberal pada
1870 banyak investor asing yang menanamkan modalnya di
Indonesia, maka munculah banyak pabrik-pabrik milik
pengusaha asing hingga di pelosok desa. Pabrik-pabrik ini
kemudian mempekerjakan penduduk yang tinggal di sekitar
pabrik untuk bekerja menjadi buruh pabrik. Penduduk sekitar
kemudian diberikan upah atas pekerjaannya berupa uang.
Barulah pada masa itu para penduduk mengenal ekonomi uang
karena pada sistem-sistem ekonomi sebelumnya masyarakat
tidak benar-benar dikenalkan dengan uang kecuali pada masa
sewa tanah. Karena mereka tidak biasa menggunakan uang
akhirnya uang tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang
buruk seperti berjudi dan meminum minuman keras. Lambat
18 | P a g e
laun tingkat kriminalitas di desa itu pun semakin
meningkat, tidak hanya berjudi dan meminum minuman keras,
tapi mereka juga banyak yang mencuri, merampok, berkelahi,
hingga berzina. Hal itulah yang menjadi alasan Tebuireng
mulanya sering disebut seperti desa pada jaman jahiliyah.
Niat K.H Hasyim Asy’ari untuk mendirikan pesantren di
daerah yang penduduknya berperilaku buruk seperti itu jelas
menuai tentangan baik dari keluarganya maupun para
sahabatnya. Mereka menganggap pesantren tidak bisa
didirikan ditempat yang penduduk sekitarnya berakhlak buruk
seperti di Tebuireng tersebut. Namun K.H. Hasyim Asy’ari
menjawab:
“Menyebarkan agama Islam berarti meningkatkan kualitaskehidupan manusia. Jika manusia sudah mendapat kehidupanyang baik, apa lagi yang harus ditingkaatkan darimereka? Lagi pula, menjalankan jihad berarti menghadapi
kesulitan dan mau berkorban, sebagaimana yang telahdilakukan Rasul kita dalam perjuangannya.”11
Dengan kebulatan tekad akhirnya K.H. Hasyim Asy’ari
membeli tanah kepunyaan seorang dalang yang terkenal di
desa Tebuireng. Letak tanah tersebut hampir berhadapan
dengan pabrik gula Cukir, kira-kira 200 meter di sebelah
barat laut pabrik gula Cukir.12 Di atas tanah tersebut
dibangun Pesantren Tebuireng. Pesantren Tebuireng berdiri
di atas dua bidang tanah. Satu bidang diperuntukan mengajar
para santri dan satu bidang lainnya digunakan sebagai
11Ibid., hml. 30. (Dikutip dalam Salam. K.H. Hasyim Asy’ari, 31)
12 Imron Arifin, Kepemimpinan Kiyai: Kasus : Pesantren Tebuireng, hlm. 47.19 | P a g e
tempat tinggal K.H. Hasyim Asy’ari sekeluarga. Pada mulanya
bangunan tersebut terbuat dari bambu. Selanjutnya tanggal
26 Rabu’ul Awal 1317 Hijriyah atau 1899 Masehi ditetapkan
sebagai hari kelahiran Pesantren Tebuireng. Mula-mula K.H.
Hasyim Asy’ari membawa delapan santri dari pesantren
Ayahnya, hal tersebut merupakan suatu hal yang mengartikan
ia telah mendapat dukungan dari Ayahnya untuk mendirikan
pesantrennya sendiri. Santri-santri tersebut merupakan
santri yang sudah cukup berilmu sehingga mereka bisa
membantu K.H. Hasyim Asy’ari memberikan pengajaran pada
santri-santri dasar lainnya.13
3.2 Perkembangan Pesantren Tebuireng
Dalam mengembangkan Pesantren Tebuireng, Hasyim
Asy’ari tidak melakukannya sendiri. Dia di bantu oleh para
asistennya yang berkompeten seperti Kyai Awi, Kyai Ma’sun,
Kyai Baidlawi, Kyai Ilyas dan Kyai Wahid Hasyim. Antara
tahun 1899-1916 Pesantren Tebuireng mengikuti sistem
pengajaran sorongan dan bandongan. Jumlah santri menjadi
banyak dari 28 orang santri pada tahun 1899 menjadi lebih
dari 200 orang santri menjelang akhir 1910-an. Pada 10
tahun berikutnya jumlah santri terus meningkat, hampir
mencapai 2000 orang santri. Pada awalnya luas Pesantren
Tebuireng kurang lebih hanya satu hektar pesergi. Dengan
menambahnya jumlah santri, pembangunan pondok-pondok untuk
13 Drs. Lathiful Khuluq, M.A., Op.Cit., hlm. 29.20 | P a g e
para santri di tingkatkan. Pada tahun 1923, kompleks baru
dibuat di Seblak. Hal inilah yang membuat semakin luasnya
wilayah Pondok Pesantren Tebuireng. Pada tahun 1906,
Belanda mengakui ada Pesantren Tebuireng karena semakin
berkembangnya pesantren ini.bPesantren Tebuireng yang kuat
dengan dasar pesantrennya dan tidak mau tunduk dengan
Belanda, pesantren ini di tuduh sebagai perkumpulan
ekstrimis islam. Sehingga pada tahn 1913 Pesantren
Tebuireng di hancurkan oleh Belanda. Pemerintah Belanda
memaksa NU untuk menghapus sistem pesantre. Namun NU
menolak perintah kolonial Belanda. Untuk menghadapi masalah
tersebut, selain memperdalam ilmu agama para santri di
berikan pengetahuan yang lain dari pendidikan sekuler.
Kyai Ma’sum adalah menantu pertama Hasyim Asy’ari,
yang pertama kali memperkenalkan sistem Madrasah Salafiyah
Syafi'iyah pada tahun 1916. Pada tahun 1916-1934 Pesantren
Tebuireng membuka tujuh jenjang kelas dan dibagi ke dalam
dua tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan sifir awal
dan sifir tsani, yaitu masa persiapan untuk dapat memasuki
madrasa lima tahun berikutnya.14 Para tingkatan pertama dan
kedua ini khusus dididik untuk memahami bahasa arab sebagai
landasan penting dari madrasah. Pada kurun waktu 1916-
1919, kurikulum madrasah terdiri dari pengetahuan agama
islam saja. Dari tahun 1919 sampai tahun 1926 mulai
ditambahkan pelajaran-pelajaran Bahasa Indonesia (Melayu),
14 Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: Penerbit LP3ES. 1982, Hal 104
21 | P a g e
Matematika, Ilmu Bumi, Bahasa Belanda dan Sejarah. Dalam
tahun 1934, pembelajaran madrasah diperpanjang menjadi 6
tahun, karena semakin meluasnya kurikulum pengetahuan.
Antara tahun 1932-1933 Kyai Wahid Hasyim mengusulkan
kepada Kyai Hasyim Asy’ari suatu perubahan yang radikal
dalam sistem pengajaran pesantren. Usul itu antara lain
agar sistem bandongan diganti dengan sistem tutorial yang
sistematis dengan tujuan untuk mengembangkan inisiatif dan
kepribadian para santri.15 Kyai Hasyim Asy’ari tidak
menyetujui usul Kyai Wahid Hasyim. Menurut Hadratus-Syekh
perubahan radikal akan menciptakan kekacauan antara sesama
pemimpin pesantren. Putra tertua Hadratus-Syekh ini juga
mendirikan perpustakaan. Para santri dianjurkan untuk
membaca majalah dan surat kabar sebanyak mungkin. Dengan
demikian para santri memperoleh penerangan yang cukup
mengenai soal-soal sosial, ekonomi, dan politik baik dalam
negeri maupun luar negeri. Perkembangan lain yang penting
pada Pesantren Tebuireng dalam tangan Kyai Hasyim Asy’ari
ialah mulai diperkenalkannya kursus-kursus pidato, Bahasa
Belanda, Inggris dan mengetik.
Pada masa pemerintahan Jepang, Pesantren Tebuireng
tidak mau melakukan Saikere (penghormatan pada bendera
Jepang). Kegiatan surat-menyurat dalam bahasa latin juga
dilarang oleh pemerintahan Jepang. Pada tahun 1942, Kyai
Hasyim Asy’ari ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang.
Setelah Kyai Hasyim Asy’ari dipenjarakan, dia dibebaskan15 Ibid, Hal 105
22 | P a g e
tanpa syarat dan diberi jabatan tinggi di Jawa Hokokai.
Pada masa menjelang kemerdekaan, Posisi Tebuireng sangat
sentral. Bersamaan dikeluarkannya Resolusi Jihad 22 Oktober
1945, para pimpinan Nasional baik Bung Karno, Tan malaka
dan Bung Tomo selalu berkordinasi ke Tebuireng untuk
menghadapi sekutu.16
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
16 http://www.nu.or.id.a,public-m,dinamic-s,detail-ids,46-id,38786-lang,id-c,pesantren-t,Kisah+Tebuireng++dari+Mbah+Hasyim+hingga+Gus+Dur-.phpx
23 | P a g e