Laporan Akhir PKMP UNAND Rayap (Isoptera) pada rumah adat Minangkabau DEFFI SN[1]
Hukum adat masyarakat Minangkabau (mamas)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Hukum adat masyarakat Minangkabau (mamas)
Bab I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Manusia diciptakan Tuhan menjadi suatu mahluk sosial yang
saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Mereka akan
memiliki fase dimana ia akan berkeluarga, bermasyarakat, dan
bernegara. Tatanan dan cara yang mereka lakukan dalam
berinteraksi dengan orang lain diatur berdasarkan perilaku dan
akal pikiran mereka nasing-masing. Perilaku yang terus menerus
dilakukan perorangan ini menimbulkan suatu kebiasaan pribadi.
Kebiasaan pribadi ini, apabila ditiru oleh orang lain maka ia
akan mengikuti kebiasaan orang tersebut. Kemudian, jika
didalam suatu kelompok masyarakat yang saling melakukan
interaksi satu dengan yang lainnya melakukan kebiasaan
tersebut, maka lambat laun kebiasaan itu akan menjadi adat dari
kelompok masyarakat itu. Seiring dengan berjalannya waktu,
adat yang telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat itu,
dijadikan sebagai suatu adat yang seharusnya berlaku bagi
semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat.1 Namun,
dikalangan masyarakat umum istilah “hukum adat” jarang
digunakan. Biasanya yang banyak dipakai ialah istilah “adat”
saja. Dengan menyebut kata “adat”, maka yang dimaksud adalah
1
? Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. 1992. Bandung : Mandar
Maju. Hal : 1.
Page | 1
suatu kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam suatu
masyarakat tertentu.
Negara Indonesia memiliki banyak sekali hukum adat yang
terdapat di berbagai penjuru daerah. Salah satunya yaitu hukum
adat atau adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau2 pada
umumnya menganut agama Islam dan dapat ditemui suatu susunan
masyarakat yang diatur dan dijalankan menurut tertib hukum ibu
(matrilinial). Mulai dari lingkungan keluarga, “paruik”,
hingga lingkungan hidup yang paling atas, atau yang disebut
sebagai “nagari”, dapat dilihat faktor turunan darah menurut
garis ibu. Garis turunan inilah yang mengatur organisasi
masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, kehidupan yang diatur
menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah
sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat atau hukum adat.
Uraian diatas menjelaskan bahwa dasar masyarakat adat
Minangkabau bersifat genealogis-matrialinial, yang merupakan
suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya
terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu
leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah
(keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian
2 Minangkabau atau yang biasa disingkat Minang adalah kelompok etnik
Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut
kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara
Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya
Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Wilayah Minangkabau pada
mulanya didiami oleh masyarakat Minangkabau yang menyebut dirinya sebagai “
urang awak ”.
http://fhuk.unand.ac.id (diunduh pada tanggal 7 Februari 2012 pukul 20.30
WIB)
Page | 2
perkawinan atau pertalian adat.3 Sedangkan menurut bentuknya,
masyarakat Minagkabau merupakan masyarakat hukum adat bentuk
bertingkat, dimana di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat
atasan dan beberapa masyarakat hukum adat bawahan, yang tunduk
pada masyarakat hukum adat atasan tersebut.4 Oleh karenanya,
masyarakat Minangkabau terdiri dari kesatuan-kesatuan keluarga
kecil yang disebut “paruik” sebagai kesatuan dari “suku” atau
“kampuang” (kampung) sebagai tempat kediaman. Dalam satu
kampung terdiri dari beberapa “paruik” atau “suku” yang
berbeda-beda. Sehingga ada kemungkinan kesatuan keluarga
“paruik” dari satu kesatuan “suku” mendiami kampung yang
berlainan. Kesatuan yang formal adalah “suku” yang dipimpin
oleh seorang Penghulu Suku dan “kampuang” yang dipimpin oleh
seorang Penghulu Andiko atau Dateuk Kampuang.5 Disampaikan pula
sebagai berikut (Soerjono Soekanto 1973 : 48)
“Minangkabau which lies on the west coast of Sumatra, is
one of the most Islamized regions in Indonesia which is
highly matrilineal in respect to its social organization.
In examining its social structure and social organization
one should distinguish the Koto Piliang from the Bodi
Caniago system, but before examining the difference,
first of all we have to deal with the elements of the
whole context. The matrilocal extended family is called
kaum or parui, though the parui may also be composed of a
number of separate kaum. Several parui comprise a suku
3 Opcit. Hal : 108.4 Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. 1983. Jakarta : Rajawali Pers.
Hal : 159.5 Opcit. Hal : 123.
Page | 3
which is in Bodi Caniago a sub-clan. Within the Koto
Piliang system, the sub-clan is called kampuang and
several kampuang form a suku which is a federation af
sub-clans. The apex of both system is the nagari which
has its own territory within the Koto Piliang as well as
the Bodi Caniago. The difference is that the suku of the
Koto Piliang have to territory, while the other hand some
suku of the Bodi Caniago have territories; others have
none.”6
Selain itu, harus dipahami pula susunan masyarakat
beserta adat-adat yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau.
Aturan-aturan adat yang digunakan sebagai aturan hidup yang
mengatur kehidupan yang selalu dinamis, merupakan aturan-
aturan yang tidak tertulis. Sehingga lebih mudah bagi aturan
tersebut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang
dibutuhkan zaman agar tidak terlihat kaku. Akan tetapi,
walaupun aturan-aturan tersebut telah banyak melakukan
penyesuaian dengan kebutuhan hidup modern, namun masih belum
dapat sama sekali terlepas dari ikatan susunan lama yang
mengikuti tertib hukum ibu (matrilinial).
1.2 Tujuan Penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk :
1. Memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum
adat.
6 Opcit. Hal : 129.
Page | 4
2. Memahami definisi hukum adat Indonesia secara umum.
3. Meninjau hukum adat di wilayah Sumatra Barat khususnya
Minangkabau, berdasarkan susunan masyarakat dan macam-
macam adat istiadatnya.
4. Menambah pemahaman wawasan mengenai hukum adat yang
berada di Indonesia, terutama yang berada di wilayah
Minangkabau.
1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di
atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kemukakan adalah
:
1. Apakah yang dimaksud dengan hukum adat Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum adat yang berada di
wilayah Minangkabau ditinjau dari susunan masyarakat
dan adat istiadatnya?
1.4 Metode Penelitian
Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan tinjauan
pustaka sebagai metode penelitiannya. Penulis juga mengambil
referensi dari beberapa buku dan mencari melalui beberapa
website di internet untuk mendapatkan informasi yang terkait
serta teori dan konsep yang mendukung penulisan.
1.5 Sistematika Penulisan
Page | 5
Bab I merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan latar
belakang masalah, tujuan penulisan, rumusan masalah, metode
penulisan, dan sistematika penulisan.
Bab II merupakan pembahasan makalah yang menjelaskan
tentang Hukum Adat Minangkabau yang terdiri dari Definisi
Hukum Adat, Asal Usul Minangkabau, Susunan Masyarakat
Minagkabau, dan Adat Istiadat Masyarakat Minangkabau.
Bab III merupakan kesimpulan dari materi yang telah
disampaikan penulis pada pembahasan sebelumnya.
Bab II
Hukum Adat MinangkabauPage | 6
2.1 Definisi Hukum Adat
Telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa hukum adat
merupakan perpanjangan dari adanya suatu cara berperilaku yang
dilakukan oleh seorang individu yang mana jika cara itu
dilakukan secara terus menerus maka akan terbentuklah suatu
kebiasaan yang apabila kebiasaan tersebut diikuti oleh individu
yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga
kelompok masyrakat tersebut mengikuti juga kebiasaan tersebut,
maka kebiasaan tersebut akan menjadi suatu adat dari kelompok
masyarakat tersebut. Kemudian lambat laun kelompok masyarakat
itu menjadikan adat tersebut sebagai adat yang seharusnya
dipakai oleh anggota masyarakat setempat, sehingga lahirlah
yang dimaksud dengan hukum adat yang diterima dan harus
dilaksanakan masyarakat yang bersangkutan.
Pada umumnya, di dalam sistem hukum Indonesia tradisional
terdapat hukum yang tidak tertulis serta hukum yang tidak
dikodifikasikan di dalam suatu kitab undang-undang. Hukum yang
tidak tertulis itu dinamakan hukum adat, yang merupakan
sinonim dari pengetian hukum kebiasaan.7 Istilah “hukum adat”
sendiri merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda
adatrech, yang dipakai pertama kali oleh Snouck Hurgronje.
Istilah adatrecht kemudian dikutip dan dipakai oleh Van
Vollehoven sebagai istilah teknis-juridis. Dalam perundang-
undangan, istilah adatrech itu baru muncul pada tahun 1920,
7Soekanto, Soerjono. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia. 1982.
Jakarta : kurnia Esa. Hal : 10.
Page | 7
yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda
mengenai perguruan tinggi di Belanda. Tetapi pada permulaan
abad ke-20, lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan,
istilah adatrech makin sering dipakai dalam literatur
(kepustakaan) tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh
Nederburgh, Juynboll, Scheuer.8
Selain itu, istilah hukum adat juga berasal dari kata-
kata Arab yaitu Huk’um yang berarti ketentuan dan Adah yang
berarti kebiasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa “hukum adat”
adalah hukum kebiasaan.9
Adapun pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. C. Van
Vollenhoven yaitu aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi
orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu
pihak memiliki sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak
tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat). Sedangkan menurut
Prof. Dr. B. Ter Haar Bzn yang menjadi Guru Besar pada Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum (RHS-Rechts Hoge School) di Jakarta, hukum
adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-
keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang
mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam
pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh
hati.
8 Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar. 2002. Jakarta : PT.
Pradnya Paramita.
Hal : 1-29 Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. 1992. Bandung : Mandar
Maju. Hal : 8.
Page | 8
Prof. Dr. R. Soepomo, yang merupakan Guru Besar dalam
ilmu hukum adat sejak tahun 1938 di RHS Jakarta dan tahun 1941
menggantikan kedudukan Ter Haar sebagai Guru Besar hukum adat,
memberikan pengertian tentang hukum adat sebagai hukum non-
statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan
sebagian kecil hukum Islam. Menurutnya pula, bahwa hukum adat
tidak tertulis. Istilah “hukum adat” ini dipakai sebagai
sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan
legislatif.10
Bagi masyarakat Indonesia, hukum yang menjadi patokan
untuk berperilaku adalah hukum adat. Hukum adat dianggap
sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam
masyarakat. Dengan mempelajari hukum adat, maka kita akan
memahami budaya Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat
sembilan belas wilayah hukum adat yang memiliki ciri-ciri khas
yang memberi tanda kenal pada hukum adat wilayah yang
bersangkutan. Hal ini tentunya dapat mempermudah mempelajari
sistematik hukum adat itu di suatu wilayah. Sehingga kita
dapat memperoleh suatu ikhtisar sistematis tentang hukum adat
di Indonesia. Sembilan belas wilayah hukum adat tersebut
antara lain sebagai berikut :11
1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak
2a. Nias (Nias Selatan)
10 Ibid. Hal : 14-18.11 Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar. 2002. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Hal : 94-95.
Page | 9
3. Tanah Minagkabau (Padang, Agam, Tanahdatar, Limapuluh
Kota, Tanah Kampar, Korinci)
3a. Mentawai (orang Pagai)
4. Sumatra Selatan (Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi)
5. Tanah Malayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatra Timur,
orang Banjar)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu,
Kalimantan Tenggara, Mahakam-Hulu, Pasir, Dayak Kenya,
Dayak Klemanten, Dayak Landak dan Dayak Tayan, Dayak
Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timai, Long Glatt, Dayak
Maanyan-Patai, Dayak Maanyan-Siung, Dayak Ngaju, Dayak
Ot-Danum, Dayak Penyabung-Punan)
8. Minahasa (Menado)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree,
Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To
Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai)
11. Sulawesi Selatan (orang Bugis, Bone, Gowa, Laikang,
Ponre, Mandar, Makassar, Salayar, Muna)
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmaheira,
Tobelo, Kepulauan Sula)
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar,
Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru,
Kisar)
14. Irian
Page | 10
15. Kepulauan Timor (Timot Timur, Timor Barat, Timor
Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timor, Kodi,
Flores, Ngada, Roti, Savu, Bima)
16. Bali dan Lombok (Bali, Tnganan, Pagringsingan,
Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok,
Sumbawa)
17. Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Madura (Jawa Tengah,
Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya,
dan Madura)
18. Daerah Kerajaan (Solo dan Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten
2.2 Asal Usul Minangkabau
Kerajaan Minangkabau memiliki sejumlah kisah yang panjang
dimulai dari awal abad ke-7 M sejak masih berdirinya kerajaan-
kerajaan Hindu Budha pada masa itu. Diawali oleh Kerajaan
Malayu (Melayu Tua) terletak di Muara Tembesi (kini masuk
wilayah Batanghari, Jambi), berdiri sekitar Abad 6 – awal 7 M.
Kemudian Kerajaan Sriwijaya Tua terletak di Muara Sabak (kini
masuk masuk wilayah Tanjung Jabung, Jambi), berdiri sekitar
tengah Abad 7 – awal 8. Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya di
Palembang, Sumatra Selatan pada akhir abad 7 – 11 M.
Kesultanan Kuntu terletak di Kampar, sekitar Abad 14 M.
Kerajaan Malayu (Melayu Muda) atau Dharmasraya terletak di
Page | 11
Muara Jambi, abad 12-14 M. Hingga berdirinya Kerajaan
Pagaruyung yang dipimpin oleh Adityawarman pada tahun 1347.
Mengenai asal-usul nama Minangkabau, terdapat beberapa
versi mengenainya, antara lain seperti yang disampaikan oleh
Drs . Zuber Usman.12 Dalam bukunya kesusastraan lama Indonesia
menyatakan bahwa dalam buku Tun Sri Lanang berjudul” Hikayat
Raja Raja Pasai” disebutkan bahwa patih Gajah Mada pergi
menaklukkan pulau perca dengan membawa Seekor Kerbau Hikmat
yang akan diadu dengan kerbau patih sewatang perdana menteri
kerajan Minangkabau. Patih sewatang menyediakan seekor anak
kerbau yang kepalanya diberi tanduk dengan benda tajam dan
runcing yang beberapa hari tidak diberi susu oleh induknya,
waktu kerbau itu diadu anak kerbau tersebut menyeruduk ke
perut kerbau besar sehingga perutnya tembus oleh tanduk yang
dipasang pada anak kerbau sehingga saat itu orang orang minang
bersorak manang kabau (menang kerbau), sehingga disebutlah
daerah itu dengan Manangkabau yang akhirnya berubah menjadi
Minangkabau.
Lain halnya menurut tambo yang telah diterima secara
turun temurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal
dari keturunan Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) dari
Macedonia. Ia memiliki tiga orang anak yaitu Maharajo Alif,
Maharajo Japang dan Maharajo Dirajo yang sedang melakukan
pelayaran bersama. Mereka bertiga lalu berpisah. Maharajo Alifmeneruskan perjalanan ke Barat dan menjadi Raja di Bizantium,
Maharajo Japang ke Timur lalu menjadi Raja di China dan Jepang.
12 http://fhuk.unand.ac.id (diunduh pada tanggal 7 Februari 2012 pukul 20.30
WIB)
Page | 12
Manakala Maharajo Dirajo ke Selatan sedang perahunya terkandas di
puncak Gunung Merapi karena banjir. Begitu banjir surut, dari puncak
gunung Merapi yang diyakini sebagai asal alam Minangkabau turunlah
rombongan Maharajo Dirajo. Ia kemudian menjadi raja dari
Minangkabau. 13 Mulanya wujud Teratak lalu berkembang menjadi Dusun
lalu jadi Nagari lalu jadilah Koto dan akhirnya menjadi Luhak yang
selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak nan Tigo, yang terdiri
dari Luhak Limo Puluah, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar.14
Van Vollenhoven menyatakan bahwa Minangkabau adalah salah
satu adatrechkring (wilayah hukum adat) yang terdapat di wilayah
Hindia Belanda, yaitu suatu wilayah yang terletak di Sumatera
Tengah bagian Barat, sistem kemasyarakatan Matrilineal,
mempunyai bahasa pengantar bahasa minang, sistem perkawinannya
sistem sumando, sedangkan susunan kemasyarakatannya terdiri
dari persekutuan hukum adat genealogis berbentuk suku, paruik,
kaum yang terhimpun menjadi persekutuan hukum adat territorial
yang disebut dengan nagari yang terhimpunpula kedalam luhak
dan Rantau. Di samping itu Minangkabau digunakan untuk
menyebut salah satu etnis dari masyarakat Indonesia, yaitu
etnis Minangkabau.
2.3 Susunan Masyarakat Minangkabau
2.3.1 Masyarakat Hukum Adat
13 Nasroen, M. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta : Pasaman. Hal : 13. 14 http://udaeko.wordpress.com (diunduh pada tanggal 7 Februari 2012 pukul
21.00 WIB)
Page | 13
Suasana lingkungan masyarakat Indonesia merupakan
suatu persekutuan-persekutuan yang disebut sebagai
persekutuan hukum. Masing-masing persekutuan hukum tersebut
merupakan kesatuan yang mempunyai anggota-anggota di dalam
lingkungannya, terdapat orang-orang yang berkuasa atas nama
persekutuan tersebut, dan mereka memiliki hubungan yang
erat antara anggota dengan kesatuannya.
Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan
persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh
faktor yang bersifat territorial dan genealogis. Masyarakat hukum
territorial menurut para ahli hukum adat di zaman Hindia
Belanda, adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang
anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah
kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat
kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat
pemujaan terhadap roh-roh leluhur (Ter Haar, 1960 : 17).15
Sedangkan, yang dimaksud dengan masyarakat hukum yang
bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang
teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis
keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung
karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak
langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. 16
Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda,
masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga
macam, yaitu yang bersifat patrilinial (garis keturuan
15 Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. 1992. Bandung : Mandar
Maju. Hal : 106.16 Ibid. Hal : 108.
Page | 14
bapak), matrilinial (garis keturunan ibu), dan bilateral
(susunan masyarakatnya ditarik meurut garis keturunan orang
tua, bapak dan ibu secara bersama-sama).
Pada masyarakat Minangkabau, masyarakat adatnya
bersifat genealogis-matrilinial. Sebagai suatu kesatuan
dasar dari organisasi masyarakat Minang, terdapat suatu
persekutuan hukum yang bernama paruik (satu keluarga besar).
Kemudian paruik berkembang menjadi suatu suku. Pertalian yang
mengikat suku hanyalah pertalian darah menurut garis ibu,
sama sekali tidak terikat kepada suatu daerah tersebut. Di
mana saja anggota-anggota suku itu berada, mereka tetap
merasakan pertalian darah dengan segenap sanak-sanak mereka
yang sesuku. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa suku
menempati suatu daerah tertentu yang bernama nagari. Di dalam
nagari biasanya dijumpai sedikitnya empat buah suku.17
A. Paruik
Paruik adalah persekutuan hukum yang dapat diartikan
sebagai keluarga. Dengan bertambahnya anggota, maka
sebuah paruik membelah diri di dalam kesatuan-kesatuan
baru yang lebih kecil yang dinamakan jurai. Walaupun
pada masyarakat Minangkabau berdasarkan garis ibu,
namun yang berkuasa di dalamnya selalu orang laki-laki
dari garis ibu. Maka yang berkuasa di dalam jurai
ialah mamak, saudara laki-laki yang tertua dari ibu.
Di dalam sebuah paruik yang berkuasa juga orang laki-
laki dari garis ibu yang dinamakan kapalo paruik atau
17 Anwar, Chairul. Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau. 1997.
Jakarta : Rineka Cipta. Hal : 9-23.
Page | 15
biasanya disebut panghulu andiko. Kapalo paruik dipilih
dari jurai yang tertua dari paruik tersebut.
B. Suku
Dari sebuah paruik kemudian berkembang menjadi suatu
suku yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat
oleh pertalian darah menurut garis ibu. Orang-orang
yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis ibu,
dan satu sama lain mereka merasakan dirinya
berdunsanak (bersaudara). Sehingga tidak
diperbolehkanlah melakukan perkawinan di dalam suku
sendiri. Di Minangkabau terdapat empat buah suku asal,
yaitu Koto, Piliang, Bodi, Caniago.
C. Nagari
Nagari adalah persekutuan hukum yang berdiri di atas
faktor teritorial dan faktor genealogis. Di dalam
nagari terdapat suatu batas-batas dan harus terdapat
sekurang-kurangnya empat buah suku. Hal ini dinyatakan
dalam kata adat sebagai berikut :
Nagari bakaampek suku
Nan bahindu babuah paruik
Kampuang batuo
Rumah batungganai
Datuk Katamanggunan beserta Datuk Parpatih Nan
Sabatang telah membuat aturan-aturan bagi alam
Minangkabau. Salah satu aturan tersebut terkenal
dengan nama Nagari Nan Ampek, ada juga yang menyebutnya
Koto Nan Ampek atau di perpendek menjadi Koto Ampek, yang
dimaksudkan ialah Teratak (kediaman yang letaknya jauhPage | 16
terpencil dari kampuang atau nagari), Dusun
(perkembangan dari teratak, yang pada umumnya jika
telah mempunyai tiga buah suku didalamnya dinamakanlah
dusun), Koto (daerah pusat yang akan berkembang menjadi
suatu nagari), dan Nagari (persekutuan hukum yang dapat
diumpamakan sebagai suatu kesatuan kenegaraan).
2.3.2 Sistem Kepengurusan18
Dilihat dari sistem kepengurusan dalam pemerintahan
adatnya dapat dibedakan dari dua kelarasan, yaitu laras atau
lareh Bodi Caniago dan Koto Piliang. Tata adat kelarasan
Bodi Caniago dihubungkan pada tokoh Datuk Parpatih Nan
Sabatang, yang menunjukkan corak kepribadian Melayu yaitu
pemerintahan demokrasi terbuka. Pemerintahan ini
mementingkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan
peribahasa “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Jadi
kedudukan para penghulu andiko itu sejajar yang satu dan
yang lain dalam menetapkan keputusan. Sistem pemerintahan
menurut adat Bodi Caniago terdapat di daerah Agam.
Sedangkan menurut tata adat kelarasan Koto Piliang
yang dihubungkan dengan tokoh legendarisnya Datuk
Katamanggunan, menunjukkan pemerintahan yang bercorak
otokrasi atau demokrasi yang terkendali. Jadi, kepenghuluan
di laras Koto Piliang tidak dipilih seperti di laras Bodi
Caniago, mereka tetap sebagai penghulu yang turun temurun
menurut sub-klennya masing-masing. Para penghulu ini tunduk
18 Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. 1992. Bandung : Mandar
Maju. Hal : 124.
Page | 17
kepada Penghulu Suku, dan para Penghulu Suku tunduk pada
Penghulu Pucuk (Pucuk Nagari). Dalam pelaksanaan
pemerintahan adat sesungguhnya bukan kato mupakat para
penghulu gabungan suku yang lebih besar pengaruhnya,
melainkan kebijaksanaan dan tindakan yang dilakukan “Urang
Ampek Jinih” (orang empat jenis), yaitu “Penghulu” (Pucuk
Nagari), “Manti” sebagai penulis, “Malim” untuk urusan
keagamaan, dan “Dubalang” untuk urusan keamanan dengan
bantuan dan dukungan para penghulu suku. Daerah yang
memakai sistem pemerintahan menurut adat Koto Piliang ada
di daerah L Koto.
2.4 Adat Masyarakat Minangkabau
Pada umumnya, di kalangan masyarakat tidak ada pembedaan
antara istilah “adat” dengan “hukum adat”. Jadi dengan
mengatakan “adat” berarti sudah meliputi “hukum adat”, baik
adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi. Di
masyarakat Minangkabau terdapat empat adat yang telah
dilaksanakan secara turun temurun, yaitu :19
1. Adat Nan Sabana Adat (adat yang sebenarnya)
Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala
sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak
Allah SWT, jadi yang telah merupakan undang-undang alam
yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti :
murai bakicau (murai berkicau), jawi malanguah (sapi
melenguh), dan kabau mangowek (kerbau menguek). Adat
19 Opcit. Hal : 56-58.
Page | 18
nan sabana adat ini juga dimaksudkan segala yang
diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturab yang
terdapat di dalam Al-Qur’an atau disebut juga sebagai
adat yang datang dari Allah SWT.
2. Adat Nan Diadatkan
Merupakan adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur
tata alam Minagkabau yaitu Datuk Ketumanggungan beserta
Datuk Perpatih Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat
adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah
seperti dalam pepatah : indak lakang dek paneh, indak lapuak
dek hujan.
Adat ini terdiri dari : Cupak nan Duo (Cupak usali dan
cupak buatan); Kato nan Ampek (Kato pusako, Kato
mufakat, Kato dahulu ditempati, dan Kato kemudian kato
dicari); Undang-undang nan Ampek (Undang-undang
luhak/rantau, Undang-undang nagari, Undang-undang di
dalam nagari, Undang-undang nan duo puluah); Nagari nan
Ampek ( Teratak, Dusun, Koto, Nagari).
3. Adat Nan Teradat
Merupakan kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena
tiru-meniru di antara anggota masyarakat. Karena
perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa terpakai, maka
tidak baik untuk ditinggalkan. Misalnya, dikalangan
orang Minangkabau sudah teradat apabila ada kaum
kerabat yang meninggal, atau untuk menyambut tamu
agung, mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna
hitam.
4. Adat Istiadat
Page | 19
Yang dimaksud adat istiadat ialah adat sebagai aturan
(kaidah) yang telah ditentukan oleh nenk moyang
(leluhur), yang bagi masyarakat Minangkabau dikatakan
berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatih
Nan Sabatang di balai Balairung Periangan Padang
Panjang. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-
kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak
zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang. Aturan
kebiasaan ini pada umunya tidak mudah berubah.
Bab III
Kesimpulan
Hukum adat merupakan suatu proses perubahan dalam diri
manusia yang didasari oleh adanya pikiran, kehendak, dan cara
Page | 20
berperilaku. Hal ini bermula dari kebiasaan pribadi individu
yang kemudian apabila kebiasaan ini diikuti oleh individu lain
di dalam suatu kelompok masyarakat, maka kebiasaan pribadi
seseorang tersebut akan berubah menjadi suatu adat. Lama
kelamaan, adat ini dijadikan oleh sekelompok masyarakat
sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi seluruh kelompok
masyarakat, sehingga dinamakan hukum adat.
Hukum yang dianalisir telah ada sejak zaman Hindia
Belanda ini, banyak digunakan oleh sejumlah kelompok
masyarakat yang berada di Indonesia. Menurut Ter Haar,
terdapat sekitar sembilan belas wilayah adat yang tersebar di
Indonesia, salah satunya adalah kelompok masyarakat (etnis)
Minangkabau yang berada di Sumatra Barat.
Masyarakat Minangkabau terkenal sekali dengan masyarakat
adatnya yang bersifat genealogis-matrilinial, yaitu suatu
kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya
terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu
leluhur, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Oleh
karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilinial,
maka susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan ibu.
Selain itu, masyarakat Minangkabau menjadi masyarakat adat
terbesar di dunia yang masih mempertahankan sifat
matrilinialnya tersebut.
Dalam hukum adat Minangkabau, terdapat sejumlah aturan-
aturan dan susunan masyarakat yang masih besar pengaruhnya
hingga saat ini. Susunan masyarakat Minangkabau sendiri
terdiri dari kelompok terkecil, paruik, hingga terbentuklah
Page | 21
suatu nagari. Adat istiadatnya juga masih sangat besar
pengaruhnya hingga saat ini, yaitu Adat Nan Sabana Adat (adat yang
sebenar adat), Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Teradat, dan Adat Istiadat.
Dengan mempelajari hukum adat yang berada di Indonesia,
khususnya dalam hal ini adalah Minangkabau, kita mengetahui
bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang menggunakan hukum-
hukum yang dibuat secara tidak tertulis dan dijadikan sebagai
pedoman masyarakat setempat secara turun-temurun.
Daftar Pustaka
1. Sumber Pustaka
Anwar, Chairul. Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat
Minangkabau. 1997.
Jakarta: Rineka Cipta.
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. 1992.
Bandung :
Mandar Maju.
Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar. 2002.
Jakarta :
PT. Pradnya Paramita
Nasroen, M. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta : Pasaman.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. 1983. Jakarta :
Rajawali Pers.
Page | 22
Soekanto, Soerjono. Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia. 1982.
Jakarta :
Kurnia Esa.
2. Sumber Website
http://fhuk.unand.ac.id (diunduh pada tanggal 7 Februari
2012 pukul 20.30 WIB)
http://udaeko.wordpress.com (diunduh pada tanggal 7
Februari 2012 pukul 21.00 WIB)
Page | 23























![Laporan Akhir PKMP UNAND Rayap (Isoptera) pada rumah adat Minangkabau DEFFI SN[1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631a5b3fb41f9c8c6e0a28e8/laporan-akhir-pkmp-unand-rayap-isoptera-pada-rumah-adat-minangkabau-deffi-sn1.jpg)



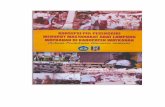




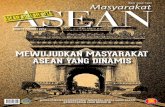


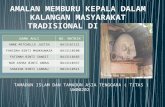
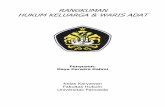

![Kearifan Lokal [Huma-Talun; Masyarakat Adat Suku Sunda]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ae14a80cc3e9440059387/kearifan-lokal-huma-talun-masyarakat-adat-suku-sunda.jpg)





