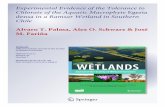HALAMAN SAMPUL SKRIPSI ANALISIS YURIDIS RAMSAR ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of HALAMAN SAMPUL SKRIPSI ANALISIS YURIDIS RAMSAR ...
i
HALAMAN SAMPUL
SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS RAMSAR CONVENTION 1971 TERHADAP
PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DI INDONESIA
OLEH:
GALANG RAMADHAN
B 111 14 053
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
ii
HALAMAN JUDUL
ANALISIS YURIDIS RAMSAR CONVENTION 1971 TERHADAP
PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DI INDONESIA
Diajukan sebagai Skripsi dalam Penyelesaian Studi Strata Satu
Pada Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum
OLEH
GALANG RAMADHAN
B 111 14 053
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan
semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang
senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan
skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata
Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W.
yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu
berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga
semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai
ibadah di sisi-Nya.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang
tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Tettaku Marsuki
Rapi dan Ibunda Hasnah Jinne yang senantiasa merawat, mendidik dan
memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada kakak-kakak
penulis, Muh.Tahir Nur, S.E., Haslinda, Hamsinah, Sultan dan Halijah
yang turut serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A. selaku Rektor
Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas
vii
Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan,
yaitu Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin
Muchtar, S.H., M.H., dan Prof.Dr.Hamzah Halim, S.H., M.H.
atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah
diberikan kepada penulis.
3. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H.,M.H. dan Dr. Maskun, S.H., LLM.
Selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
yang senantiasa memotivasi dan sabar membimbing penulis.
4. Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H., Prof. Dr. Alma
Manuputty, S.H., M.H. dan Dr. Laode Abdul Gani, S.H.,M.H.
selaku dewan penguji skripsi penulis atas segala masukan dan
arahannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Suryaman Mustari Pide, S.H.,M.H. selaku penasehat
akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada
penulis selama di bangku kuliah.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang
telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat
serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta seluruh
staff/pegawai akademik yang senantiasa dengan sabar
membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pihak Perpustakaan Hukum Unhas, Ibu Nurhidayah,
S.Hum.,M.M dan Kakak Nurdin,S.IP yang rela direpotkan oleh
viii
penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Beasiswa Yayasan
Karya Salemba Empat yang telah banyak membantu penulis
baik dalam hal bantuan Finansial maupun pelatihan-pelatihan
yang diberikan.
9. Pihak Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (BP2LHK) Makassar serta Yayasan Hutan
Biru-Blueforest yang telah berkenan untuk memfasilitasi
penulisan ini pada tahap penelitian.
10. Keluarga Muh. Idris Leo dan Hasrah Kenna yang telah
menjaga dan merawat penulis selama masa-masa
perkuliahan.
11. Sahabat-sahabatku, Alif Imam Dzaki, S.H., Moch.Arief Agus,
S.H., dan Kun Arfandi Akbar Anzari, S.H. yang telah menjadi
sahabat bureng dalam perkuliahan maupun dalam kompetisi-
kompetisi yang diikuti penulis.
12. Sahabat-sahabat Beauty and the Beast, Rezky Amalia
Syafiin,Huriah Nur Insani, Kun Arfandi Akbar Anzari S.H., Dian
Qhalbi Pratidina,S.H. Ayu Ashari, Viyani Annisa Permatasari
Maasba, Mithayani Suci Isnaeni Arifin, Annisa Fadilah Rosadi,
Andi Nurul Asmi,S.H., Ridwan Purwo Saputro,S.H., dan A.Muh
Yunansyah. Terima kasih untuk segala kegilaan yang telah kita
ciptakan bersama.
ix
13. Kakanda,Teman-teman dan adik-adik di LDA MPM FH-UH
kakanda Hidayat Pratama Putra,S.H.,M.H., Afif Mahmud,
S.H.,M.H. Yahya Muhaymin Hatta,S.H., Muh. Asyraf, Reynaldi,
S.H. Teman-teman pengurus, Nurkhalish Daud, Suyanto,
Asrullah, A.Ikhsan Alfakih,S.H., Moch,Arief Agus,S.H., Aditya
Nugraha, Muh.Yusran, Muh.Afdal Magfirah, Muh.Idris,
A.Muh.Irvan. Serta adik-adik Supardi, Supriadi,Muslim, Auzan,
Fauzan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Senior andalan GH a.k.a XXX Girls Return Arif Rachman
Nur,S.H., Nurhalida Zaenal,S.H., Siti Syahrani Nasiru,S.H.,
Melisa, S.H., Nurindah Damai Lestari,S.H. Kun Arfandi Akbar
Anzari,S.H. Yang senantiasa memberikan dukungan dan
pembelajaran hidup yang sangat bermakna.
15. Teman-teman Pecinta Imam, A.Muh. Ikhsan S.H., Abd. Azis
Alwi, Syamsuriadi Syarief, Moch.Arief Agus,S.H., Muh Afdal
Magfirah, Ahmad Jazuly, Yacob Efendy, Fitrahansyah, Yudi
Reynaldi, Ridwan Purwo Saputro, S.H., A.Muh.Yunansyah,
Fauzan Cakra Darmawan, Anugrah,S.H., Hasyim Hamid dan
Anriyan Ridwan Tahir. Yang telah menjadi wadah
pengembangan diri penulis dalam menjalani kehidupan.
16. Klinik Hukum Universitas Hasanuddin, Khususnya Ibu Birkah
Latif,S.H,.LL.M, Bapak Achmad, S.H.M.H. dan
Dr.Maskun,S.H.LL.M yang begitu saya kagumi dan telah
x
memberikan penulis banyak pembelajaran dan kesempatan
yang besar dalam mengembangkan diri. Serta teman-teman
klinik yang begitu luar biasa,Arief, Kholish, Ira Muin, Enab,
Rahmi, Dilla,Dian, Ira P, Ningsih, Wana, Tuti, Anti, Aurel, Anita,
Matet dan lain-lain .
17. Klinik PKM Fakultas Hukum Unhas, ibu Amaliyah, S.H,M.H, ibu
Dr. Ratnawati Sudirman, S.H.M.H, serta teman-teman The
Mentors Nilasari, Windaryani, Rezky Amalia S, Kun Arfandi,
S.H., Jemmi, S.H, Mirdawati,S.H., Ayu Ashari, Ruslianto
Sumule,S.H.,Anugrah,S.H.,Juhardiyanti, Surya Yudistira dan
Ramdan Yulia. Terima kasih untuk pengalaman luar biasa
yang telah kita lakukan bersama.
18. Teman-teman bagian Hukum Internasional, yaitu Alif,
Sheby,Anrose, Indah, Ipul, Ira, Enab, Tuti, Angel, Dettol,
Sharon, Yati, Riska,dan lain-lain. Terima kasih atas semua
bantuan, pelajaran, dan kerja samanya.
19. Senior, teman-teman dan adik-adik di Paguyuban KSE Unhas,
Kak Rio, Kak Chid, Kak Typo, Kak Indah, Oka, Darmin, Irfan,
Uki,Kiki,Yuyun,Wulan,Anti, Dian, Ulva, Mage, Edna, Tita, Ekki,
Ayu, Amran, Fifit,Faldi, Dasti, dan lain-lain yang tidak bisa
disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan
serta kerjasamanya selama ini.
20. Sahabat-sahabatku di UGoesP, Nasrullah,Riefqy, Abash,
xi
Awal, Awi, Dian, Nanang, Tiwi, Evi, Mey dan lain-lain yang
tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk
persahabatan yang telah kita jalin sejak masa SMA hingga
sekarang.
21. Teman-teman seangkatan 2014 (Diplomasi). Terima kasih atas
segala bantuan, keceriaan, pertemanan, pengetahuan, dan
seluruh pengalaman selama ini.
22. Teman-teman dan Supervisor Delegasi KKN Tematik
Kebangsaan Gorontalo Unhas. Sahabat-sahabatku yang luar
biasa menginspirasi PACE SQUAD, Inggrid Heksa (UNMUL),
Mega Shintya (UNS), Devi Putri (UNDANA), Sadrak
Enninggugop (UNMUS), Satrio Setiawan serta Yun Paca
(UNG) dan DPL yang luar biasa bapak Manda
Rohandi,M.Kom. Dan tentunya seluruh warga Desa Panggulo
yang telah menerima dan mendukung kami selama
melaksanakan KKN.
Semoga Allah SubhanahuWata’ala senantiasa membalas segala
kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya.
Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya
jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada
manfaat yang dapat diambil, terutama dalam perkembangan hukum di
Indonesia.
xii
ABSTRAK
Galang Ramadhan (B111 14 053), Analisis Yuridis Ramsar Convention 1971 terhadap Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia. Dibimbing oleh Juajir Sumardi sebagai Pembimbing I dan Maskun sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana perlindungan
hukum hutan mangrove menurut Ramsar Convention 1971; dan untuk 2)
mengetahui implementasi Ramsar Convention 1971 terhadap
perlindungan hutan mangrove di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data
primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui metode
wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian di analisis secara
kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ramsar Convention
1971 telah meletakkan dasar pengaturan terkait perlindungan hukum
hutan mangrove; 2) Pada dasarnya Indonesia telah melaksanakan segala
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini. Namun masih
terdapat berbagai permasalahan terkait implementasi Konvensi ini. Oleh
karena itu, dibutuhkan komitmen dan kinerja yang lebih dari seluruh pihak
terkait dalam memberikan perlindungan terhadap hutan mangrove di
Indonesia.
Kata kunci: Ramsar Convention 1971, Hutan Mangrove, Perlindungan Hukum
xiii
ABSTRACT
Galang Ramadhan (B111 14 053), Juridical Analysis Of Ramsar Convention 1971 toward the Protection of Mangrove Forest in Indonesia. Supervised by Juajir Sumardi as Supervisor I and Maskun as Supervisor II.
The purpose of this Research is 1) to determine how the legal protection
of mangrove forest according Ramsar Convention 1971; and 2) to
determine implementation of Ramsar Convention 1971 toward the
protection of mangrove forest in Indonesia.
This is a normative research that use primary and secondary data. Data is
collected through interview method and literature study which is analyzed
qualitatively and presented descriptively.
Based on the research shows that: 1) The Ramsar Convention 1971 had
set the basis of regulations related to legal protection of mangrove forest;
2) Basically, Indonesia has carry out all its obligations as regulated in this
convention. However, there are still various problems related to the
implementation of this Convention. Therefore, it requires stronger
commitment and performance from all related parties to provide protection
of mangrove forest in Indonesia.
Keywords: Ramsar Convention 1971, Mangrove Forest, Legal Protection
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ................................................................................ i
HALAMAN JUDUL ...................................................................................ii
PENGESAHAN SKRIPSI .........................................................................iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............................................................iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI........................................v
KATA PENGANTAR ................................................................................vi
ABSTRAK ...............................................................................................xii
DAFTAR ISI ........................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xvii
DAFTAR TABEL .................................................................................. xviii
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN ................................................ xix
BAB I. PENDAHULUAN ...........................................................................1
A. Latar Belakang Masalah .....................................................................1
B. Rumusan Masalah ............................................................................13
C. Tujuan Penelitian ..............................................................................13
D. Manfaat Penelitian ............................................................................14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................15
A. Hukum Lingkungan Internasional .....................................................15
1. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional ................................15
2. Objek Hukum Lingkungan Internasional ........................................16
3. Subjek Hukum Lingkungan Internasional ......................................19
4. Sumber-sumber Hukum Lingkungan Internasional ........................21
5. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional ...........................22
B. Perjanjian Internasional ....................................................................30
1. Pengertian Perjanjian Internasional ...............................................30
xv
2. Konvensi (Convention) ..................................................................32
3. Implementasi Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional .....33
C. Hutan Mangrove ...............................................................................35
1. Pengertian Hutan Mangrove..........................................................35
2. Jenis-jenis Mangrove ....................................................................37
3. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove ...........................................39
4. Kondisi Hutan Mangrove ..............................................................41
5. Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia ..........45
D. Ramsar Convention 1971 .................................................................49
1. Latar Belakang Lahirnya Ramsar Convention 1971 ......................49
2. Tujuan Ramsar Convention 1971 ..................................................52
3. Situs Ramsar ................................................................................53
BAB III. METODE PENELITIAN ............................................................57
A. Lokasi Penelitian ...........................................................................57
B. Tipe Penelitian ..............................................................................57
C. Jenis dan Sumber Data ................................................................58
D. Teknik Pengumpulan Data ...........................................................60
E. Analisis Data .................................................................................60
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...............................61
A. Perlindungan Hukum Hutan Mangrove Menurut Ramsar Convention 1971 ..................................................................................................61
1. Komitmen Utama dalam Ramsar Convention 1971 .......................61
2. Resolution 5.1:The Kushiro Statement and the Framework for the Implementation of the Convention ................................................68
3. Resolution VII.21: Enhancing the Conservation and Wise Use of Intertidal Wetlands .......................................................................70
4. Resolution VIII.11: Guidance for Identifying and Designating Peatlands, Wet Grasslands, Mangroves and Coral Reefs as Wetlands of International Importance ...........................................72
xvi
5. Resolution VIII.32: Conservation, Integrated Management,and Sustainable Use of Mangrove Ecosystems and their Resources ..78
B. Implementasi Ramsar Convention 1971 terhadap Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia ....................................................................82
1. Praktik Implementasi Ramsar Convention 1971 terhadap Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia .................................82
a. Implementasi dalam Penetapan Situs Ramsar Indonesia .........82
b. Implementasi Wise Use Wetlands dalam Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia ..............................................................85
c. Implementasi dalam Upaya Reserve and Training terhadap Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia ............................ 110
d. Implementasi dalam Kerjasama Internasional Perlindungan Hutan Mangrove Indonesia ..................................................... 113
e. Upaya Konservasi Mangrove Indonesia .................................. 118
2. Analisis Implementasi Ramsar Convention 1971 terhadap Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia ............................... 122
a. Implikasi Pengesahan Ramsar Convention 1971 melalui Keputusan Presiden ................................................................ 123
b. Konflik Kewenangan Pengelolaan Hutan Mangrove di Indonesia ................................................................................................... 124
c. Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove di Indonesia .............................................................................. 126
d. Belum Optimalnya Upaya Konservasi Hutan Mangrove di Indonesia ................................................................................ 127
e. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum .................... 129
BAB V. PENUTUP ................................................................................ 133
A. Kesimpulan ................................................................................. 133
B. Saran .......................................................................................... 135
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 136
LAMPIRAN ........................................................................................... 144
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Bakau (Rhizopora sp.). .......................................................... 39
Gambar 2. Tancang (Bruguiera sp.) ........................................................ 39
Gambar 3. Bogem (Sonneratia sp.) ......................................................... 39
Gambar 4. Api-api (Avicennia sp.) ........................................................... 39
Gambar 5. Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove berdasarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2012 ............................................ 104
Gambar 6. Pelaksanaan Penanaman Mangrove Tahun 2012-2016 ...... 119
xviii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Publikasi Perkiraan Luas Hutan Mangrove di Indonesia ............ 44
Tabel 2. Kriteria Situs Ramsar Untuk Kepentingan Internasional ............. 55
Tabel 3. Situs Ramsar Indonesia ............................................................. 83
Tabel 4. Target Pemulihan Ekosistem Mangrove................................... 119
xix
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN
AEWA : African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement
Bakosurtanal : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPHM : Balai Pengelolaan Hutan Mangrove
BP2LHK : Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
DAS : Daerah Aliran Sungai
DLHK : Dinas Lingkungan Hidup Kota
Dirjen : Direktorat Jenderal
FAO : Food and Agricultural Organization
HPH : Hak Pengusahaan Hutam
ICBP : International Council for Birds Preservation
IUCN : International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources
ISME : International Society for Mangrove Ecosystems
IWRB : International Waterfowl Research Bureau
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
KKP : Kementrian Kelautan dan Perikanan
KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KNLB : Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan
Basah
LAPAN : Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional
MoU : Memorandum of Understanding
NGO : Non Governmental Organization
xx
OECD : Organisation for Econommic Co-operation and
Development
REDD : Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation
SNPEM : Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
TN : Taman Nasional
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
WCED : World Commission on Environent and Development
WCMC : World Conservation Monitoring Center
WII : Wetlands International Indonesia
WSSD : World Summit on Sutainable Development
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi
kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Hal ini dianggap sangat
penting karena apa yang terjadi terhadap lingkungan hidup akan sangat
memengaruhi kehidupan mahluk hidup yang tinggal didalamnya.
Termasuk juga dalam hal ini apabila terjadi kerusakan terhadap
lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup, baik secara langsung
maupun tidak langsung akan memengaruhi pola dan tata kehidupan
mahluk hidup, termasuk manusia. Memandang pentingnya hal ini, maka
sudah sewajarnya lingkungan hidup yang ada harus selalu dijaga dan
dilestarikan.
Kebakaran hutan, pemanasan global, hilangnya keanekaragaman
hayati baik didarat maupan dilaut, perubahan iklim, kekeringan,
pencemaran air maupun udara dan timbulnya penyakit-penyakit baru
merupakan contoh nyata terjadinya kerusakan lingkungan yang
mengancam kehidupan umat manusia. Faktanya sebagian besar
kerusakan yang terjadi disebabkan oleh perbuatan manusia. Perilaku
hidup manusia yang lalai, egois dan tidak bertanggungjawab dalam
mengeksploitasi sumber daya alam menjadi faktor utama semakin
tingginya laju kerusakan lingkungan.
2
Richard Stewart dan James E Krier membagi masalah lingkungan
kedalam tiga hal:1 Pertama, pencemaran lingkungan (pollution); Kedua,
penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah (land missue); dan
ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya
sumber daya alam (natural resource depletion). Jika ditarik lurus,
terganggunya kualitas lingkungan, seperti habisnya sumber daya alam,
tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan
sumber daya alam yang serampangan dan berlebihan (over exploitation of
natural resources).
Kasus-kasus lingkungan klasik seperti kasus penyakit Minamata
dan Itai-itai di Jepang, ledakan reaktor nuklir Chernobyl di Rusia, bocornya
pabrik pestisida di Bhopal, India hingga kasus-kasus lingkungan diera
milenial seperti kasus kebakaran hutan yang melanda kawasan hutan
gambut di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Indonesia serta sederet
kasus-kasus lingkungan yang lain yang tentunya bukan hanya
menimbulkan kerugian materil tetapi juga korban jiwa.
Maraknya kasus-kasus lingkungan yang terjadi memicu kesadaran
masyarakat internasional akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan
yang sehat. Kesadaran inilah yang kemudian berperan dalam tumbuh dan
berkembangnya hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan
internasional merupakan upaya masyarakat global untuk meletakkan
landasan dan strategi melalui aturan dan prinsip-prinsip hukum untuk
1 Richard Stewart dan James E Krier dalam Laode M Syarief dan
Andri.G.Wibisana (ed), 2015, Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus, USAID, Jakarta, hlm.2.
3
mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang semakin parah
dan memprihatinkan.2
Hukum lingkungan internasional sebagai suatu perangkat hukum
yang mengatur hubungan transnasional tentang pengelolaan lingkungan
hidup telah berkembang dengan pesat semenjak diproklamirkannya
Deklarasi Stockhlom 1972. Deklarasi ini telah berhasil meletakkan dasar-
dasar hukum lingkungan internasional modern, dimana pertumbuhan
hukum lingkungan internasional semakin intensif dengan lahirnya
deklarasi Rio 1992 dan Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan pada KTT
Bumi atau World Summit on Sutainable Development (WSSD), yang
menekankan pada penciptaan dan pembentukan sikap-sikap pemerintah
di dunia terhadap pola pembangunan berkelanjutan.3
Lahirnya deklarasi ini kemudian menjadi pemicu kesadaran
masyarakat internasional terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup
sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Selain itu,
deklarasi ini juga ikut andil dalam lahirnya Konvensi-Konvensi
internasional yang berkonsentrasi terhadap perlindungan lingkungan
hidup. Diantara beberapa Konvensi internasional tersebut antara lain
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES),
Convention on Bilogycal Diversity, Climate Change Convention dan lain-
lain.
2 Sefriani, 2016, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional
Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.277. 3 Ibid, hlm.2.
4
Salah satu aspek lingkungan yang sangat menarik untuk dikaji
secara lebih mendalam adalah permasalahan lahan basah (Wetland).
Menurut pasal 1 Ramsar Convention 1971 yang dimaksud dengan lahan
basah adalah:
“Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial,
permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh
brackish or salt, including areas of marine water the depth of which
at low tide does not exceed six meters”
(Daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan; tetap
atau sementara; dengan air yang tergenang atau mengalir; tawar,
payau, atau asin; termasuk wilayah perairan laut yang
kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut),4
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa cakupan lahan basah di
wilayah pesisir meliputi terumbu karang, padang lamun, dataran lumpur
dan dataran pasir, mangrove, wilayah pasang surut, maupun estuari.
Sedangkan di daratan cakupan lahan basah meliputi rawa-rawa baik air
tawar maupun gambut, danau, sungai, dan lahan basah buatan seperti
kolam, tambak, sawah, embung, dan waduk.5
Lahan basah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan
manusia. Fungsi lahan basah tidak saja dipahami sebagai pendukung
kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat
beraneka ragam mahluk, tapi juga memiliki berbagai fungsi ekologis
4 Lihat Pasal 1 Ramsar Convention 1971
5 Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah,2004, Strategi Nasional
dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah di Indonesia, Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm.1.
5
seperti pengendali banjir, pencegah intrusi air laut, erosi, pencemaran,
dan pengendali iklim global.6
Pengaturan mengenai ekosistem lahan basah secara global
terdapat dalam suatu Konvensi Internasional yang diinisiasi oleh IUCN
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).
Konvensi ini dikenal dengan nama Conventions on Wetlands of
International Importance, especially as Waterfowl Habitat atau yang lebih
dikenal dengan nama Ramsar Convention 1971.7
Konvensi ini merupakan Konvensi internasional pertama yang
mengatur habitat tertentu. Adapun tujuan dari Konvensi ini adalah untuk
melindungi dan melestarikan lahan basah yang penting bagi dunia
internasional khusususnya sebagai habitat burung air. Untuk itu, semua
negara peserta harus menunjuk lahan-lahan basah tertentu dalam
wilayahnya untuk dimasukkan dalam daftar Wetland Of International
Importance atau yang lebih dikenal dengan istilah Situs Ramsar dengan
memperhatikan signifikansinya dalam ekologi, botani, zoologi dan
hidrologi.8
Misi yang ingin dicapai oleh Konvensi ini adalah memberikan
perlindungan dan pemanfaatan secara bijaksana (wise use) setiap lahan
basah melalui implementasi rencana aksi lokal dan nasional, dan
kerjasama internasional sebagai sebuah usaha mencapai pembangunan
6 Ibid
7 G.V.T Matthews, 1993, The Ramsar Convention on Wetlands: its History and
Development, Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland hlm.5. 8 Lihat pasal 2 ayat 1-2 Ramsar Convention 1971
6
berkelanjutan di dunia.9 Konsep penggunaan secara bijak (wise use)
dalam Konvensi ini berlaku untuk semua lahan basah dan sumber daya
alam lainnya terkait lahan basah disetiap wilayah negara peserta , tidak
hanya situs-situs yang ditunjuk sebagai wetlands of international
importance. Penerapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa lahan
basah dapat terus memberikan peran vital dalam mendukung
pemeliharaan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan
manusia untuk generasi mendatang.10
Melihat betapa pentingnya lahan basah dalam menunjang
kehidupan manusia , maka upaya untuk menjaga kelestariaannya pun
harus menjadi fokus utama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya,
konversi lahan basah yang telah terjadi diberbagai belahan dunia telah
menjadi faktor utama terjadi kerusakaan terhadap jutaan lahan basah di
dunia. Data menunjukkan sekitar 64% lahan basah dunia telah hilang dan
dapat terus meningkat apabila tidak diperhatikan dengan baik. Padahal
lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia mencari nafkah langsung dari
lahan basah ini.11
Indonesia memiliki sekitar 40,5 juta hektar lahan basah sehingga
tergolong sebagai negara dengan lahan basah terluas di Asia setelah
9 Anonim, 2016, An Introduction to the Ramsar Convention on Wetlands, 7th ed.
(previously The Ramsar Convention Manual), Gland, Switzerland, Ramsar Convention Secretariat,hlm.9.
10 Ramsar Liquid Assets, 2011, 40 years of the Convention on Wetlands, Ramsar
Convention Secretariat Rue Mauverney 28 CH – 1196, Gland, Switzerland, hlm. 11. 11
Anonim, 2014, The Ramsar CEPA Programme, https://www.ramsar.org/activity/the-ramsar-cepa-programme, diakses pada 27 Desember 2017
7
China.12 Oleh karena itu, sebagai wujud tanggung jawab serta kepedulian
Indonesia terhadap perlindungan lahan basah, maka diratifikasilah
Ramsar Convention 1971 ini. Indonesia meratifikasi Konvensi Ramsar
pada tanggal 19 Oktober 1991 melalui Keputusan Presiden Nomor 48
Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International
Importance especially as Waterfowl Habitat dan menetapkan Taman
Nasional Berbak di Jambi sebagai Situs Ramsar pertama di Indonesia.13
Dan mulai berlaku (entry into force) di Indonesia sejak 8 Agustus tahun
1992. Ratifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia ingin turut
andil dalam melestarikan ekosistem lahan basah yang ada di Indonesia,
sebagai bagian penting ekosistem dunia.
Hingga tahun 2017, terdapat tujuh situs ramsar yang ada di
Indonesia yaitu Taman Nasional Berbak (Jambi), Taman Nasional
Sembilang (Sumatera Selatan), Taman Suaka Margasatwa Pulau Rambut
(DKI Jakarta), Taman Nasional Danau Sentarum (Kalimantan Barat),
Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Sulawesi Tenggara), Taman
Nasional Wasur (Papua) dan yang terbaru adalah Taman Nasional
Tanjung Puting (Kalimantan Tengah) yang ditetapkan pada bulan Januari
12
Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Op.cit., hlm. IV. 13 Wetland international, 2013, Laporan Kegiatan Peringatan Hari Lahan Basah
Sedunia, 2 Februari 2012 Di Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka, https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/wwd/12/Indonesia_report.pdf, diakses pada 02 januari 2018..
8
2014.14 Adapun total luas wilayah yang menjadi situs ramsar di Indonesia
yaitu 1.372.976 hektar.15
Salah satu lahan basah yang banyak terdapat di Indonesia adalah
hutan mangrove yang memiliki beragam manfaat, baik dari sisi ekologi
maupun ekonomi. Lebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat pesisir, ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan
basah wilayah pesisir dan menjadi sistem penyangga kehidupan dan
kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu upaya
perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk
kesejahteraan masyarakat.
Ekosistem mangrove mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis.
Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain sebagai pelindung garis
pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari
makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery
ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota perairan,
serta sebagai pengatur iklim mikro.16 Hutan mangrove juga berperan
dalam menyerap karbondioksida dan menghasilkan oksigen. Kemampuan
hutan mangrove menyerap karbondioksida ini sangat berguna dalam
14
Yus Rusila Noor, 2016, Lahan Basah untuk masa depan kita, https://indonesia.wetlands.org/id/berita/opini-lahan-basah-untuk-masa-depan-kita/, dikases pada 27 Desember 2017.
15 Lihat https://www.ramsar.org/wetland/indonesia, diakses pada 20 Desember
2017. 16
Abdul Hafidz Holii, 2010, Analisa Kebijakan Pengelolaan Pesisir Dan Mangrove Di Teluk Tomini Wilayah Propinsi Gorontalo, Tomini Bay Sustainable Coastal Livelihoods and Management (SUSCLAM), Gorontalo, hlm.1.
9
usaha mengurangi pemanasan global.17 Sedangkan dari segi ekonomi,
hutan mangrove merupakan penghasil keperluan rumah tangga, penghasil
keperluan industri, dan penghasil bibit.18
Adapun perkiraan luas mangrove di seluruh dunia sangat beragam.
Beberapa peneliti seperti Lanly menyebutkan bahwa luas mangrove di
seluruh dunia adalah sekitar 15 juta hektar, sedangkan Spalding,
menyebutkan 18,1 juta hektar. Benua Asia merupakan wilayah dengan
luas hutan mangrove terbesar di duna , yakni diperkirakan antara 32%
sampai 41.5% mangrove dunia.19
Namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan
perkembangan industri, kawasan hutan mangrovepun semakin terancam.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Food and Agricultural
Organization (FAO), diseluruh dunia telah kehilangan sekitar 3,6 juta
hektar hutan mangrove dari 18,8 juta hektar pada tahun 1980 menjadi
15,2 juta hektar pada tahun 2005. Hal ini setara dengan menghilangnya
20% keseluruhan hutan mangrove yang ada.20 Bahkan menurut data dari
17
Natalia Trita Agnika, 2016, Lahan Basah Asset Penting Bagi Lingkungan Hidup, https://www.wwf.or.id/?45402/Lahan-Basah-Aset-Penting-bagi-Lingkungan-Hidup, diakses pada 30 Desember 2017.
18 Abdul Hafidz Holii, Loc.cit. 19
Spalding dalam Yus Rusila Noor, M. Khazali dan I N.N. Suryadiputra, 2006, Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia, Wetland International (Indonesia Programme), Bogor, hlm.1.
20 FAO, 2008, Loss of mangroves alarming 20 percent of mangrove area
destroyed since 1980 – rate of loss slowing, http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000776/index.html, diakses pada tanggal 28 Desember 2017.
10
Wetlands Internasional sebanyak 67% dari mangrove yang dulunya ada,
telah hilang ataupun mengalami degradasi.21
Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan ekosistem
mangrove terluas di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati yang
paling tinggi. Dengan panjang garis pantai sebesar 95,181 kilometer
persegi, Indonesia mempunyai luas mangrove sebesar 3.489.140,68
hektar di tahun 2015. Jumlah ini setara dengan 23% ekosistem mangrove
dunia yaitu dari total luas 16.530.000 hektar.22 Bukan hanya dari segi luas
wilayah, hutan mangrove di Indonesia juga kaya akan keberagaman
spesies. Menurut FAO, ada 48 spesies mangrove di Indonesia, yang
membuat Indonesia menjadi pusat penting keanekaragaman hayati
mangrove di dunia.23
Namun, ternyata dari luas mangrove di Indonesia, diketahui hanya
1.671.140,75 hektar yang berada dalam kondisi baik, sedangkan areal
sisanya seluas 1.817.999,93 hektar dalam kondisi rusak.24 Dalam
pertemuan International Conference on Sustainable Mangrove Ecosystem
in Bali, 18-21 April 2017 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), yang diwakili oleh Dirjen Pengendalian DAS dan
Hutan Lindung, Hilman Nugroho, menguraikan bahwa setiap tahunnya
21
Wetlands international, 2017, More Mangrove Please, https://indonesia.wetlands.org/id/berita/more-mangroves-please/, diakses pada 30 Desember 2017.
22 Data ini dikemukakan oleh Direktur Bina Pengelolaan Kawasan Ekosistem
Esensial, Antung Deddy Radiansyah pada komunikasi publik di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (Selasa, 14/03/2017, diakses melalui http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/561 pada tanggal 27 November 2017
23 Akhmad Solihin (Dkk),2013, Laut Indonesia dalam Krisis, Greenpeace
Southeast Asia (Indonesia), Jakarta, hlm.1. 24
Antung Deddy Radiansyah, Loc.cit.
11
Indonesia kehilangan 5 - 6% luasan mangrove atau setara dengan sekitar
200.000 hektar pertahun.25
Pemanfaatan sumberdaya mangrove yang tidak didasarkan
kepentingan ekologis, pada kenyataannya merupakan ancaman terbesar
bagi tingginya laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia. Hilangnya
kawasan hutan mangrove ini banyak disebabkan karena konversi lahan
menjadi tambak, penggunaan kayu mangrove untuk bahan industri, kayu
bakar dan reklamasi pantai yang makin marak. Selain itu, Pertumbuhan
penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir
dengan berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, dan
lain-lain), juga semakin meningkatkan tekanan ekologis terhadap
ekosistem pesisir, khususnya ekosistem hutan mangrove.26
Pemerintah juga dinilai memiliki andil besar mendorong degradasi
hutan mangrove melalui berbagai kebijakan yang cenderung mendukung
dan mamanjakan para petambak. Penghancuran kawasan mangrove
secara masif dimulai ketika pemerintah pusat mencanangkan program
Intam tahun 1984 yang tersebar di 12 provinsi. Program ini memicu
ekstensifikasi tambak udang yang berdampak pada penghancuran hutan
mangrove secara besar-besaran untuk dijadikan tambak.27 Ironisnya,
25
Lihat https ://indonesia.wetlands.org/id/berita/international-conference-on-sustainable-mangrove-ecosystem/, diakses pada 27 November 2017.
26 Bengen dalam Maulinna Kusumo Wardhani,2011, Kawasan Konservasi
Mangrove: Suatu Potensi Ekowisata, Jurnal KELAUTAN, Volume 4, No.1 April 2011, hlm. 61.
27 Wahyu Chandra, 2014, Kebijakan Pemerintah Picu Degradasi Hutan
Mangrove,https://www.mongabay.co.id/2014/03/26/kebijakan-pemerintah-picu-degradasi-hutan-mangrove/, diakses pada 28 Desember 2017.
12
ketika terjadi penurunan produksi tambak akibat berbagai macam
penyakit, tambak-tambak ini ditinggalkan begitu saja., dan kemudian para
petambak ini memperluas ekspansi ke daerah-daerah lain. Hal ini tentu
sangat berpengaruh terhadap semakin luasnya wilayah hutan mangrove
yang mengalami kerusakan.
Kerusakan hutan mangrove hampir terjadi diseluruh wilayah
Indonesia. Di Pulau Jawa misalnya, berdasarkan data dari Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), yang
menyatakan titik terparah kerusakan hutan mangrove di pulau Jawa
terjadi di kawasan pantai utara (Pantura) dimana 3,7% mangrove rusak
pertahunnya.28 Sementara itu di Sulawesi Selatan, kondisi hutan
mangrove tidak kalah memprihatinkan. Pada 1970-an, masih terdapat
sekitar 214 ribu hektar hutan mangrove, sementara di 2014 diperkirakan
hanya tersisa 23 ribu hektar. Sedangkan di Tanjung Panjang,Gorontalo.
Hutan mangrove di kawasan cagar alam ini berkurang drastis, dari 3.000
hektar tersisa 200 hektar.29 Hal ini bertambah ironis melihat statusnya
sebagai cagar alam yang sepatutnya mendapat perlindungan khusus,
namun justru mengalami kerusakan yang tinggi.
Semakin tingginya laju kerusakan hutan mangrove ini tentunya
akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Adapun dampak yang telah
dirasakan dalam beberapa dekade terakhir adalah dengan meningkatnya
28
Imam Solehudin,2017, Duh Kerusakan Hutan Mangrove di Pulau Jawa Makin Parah, https://www.jawapos.com/read/2017/09/09/156036/duh-kerusakan-hutan-
mangrove-di-pulau-jawa-makin-parah, diakses pada 27 Desember 2017. 29 Wahyu Chandra, Loc.cit.
13
suhu global dan kenaikan permukaan laut. Efek ini pada akhirnya
berkontribusi pada peningkatan kejadian cuaca ekstrem dan terjadinya
bencana alam, seperti angin topan dan banjir parah.30 Salah satu
contohnya adalah terjadinya abrasi yang menyebabkan hilangnya tiga
desa dikawasan Pantai Muara Gembong, Bekasi. Hal ini diketahui sebagai
akibat dari 93,5% hutan mangrove yang ada dikawasan tersebut beralih
fungsi menjadi tambak dan lahan pertanian31 Kondisi ini menjadi bukti
nyata bahwa di Indonesia mengalami laju kerusakan hutan mangrove
yang sangat masif dan tentunya sangat mengancam kehidupan.
Melihat tingginya laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia serta
dampak negatif yang ditimbulkan, tentunya memunculkan pertanyaan
besar terkait sejauh mana peran dan komiten Indonesia selaku negara
yang telah meratifikasi Ramsar Convention 1971 ini dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap hutan mangrove di Indonesia, sebagai
bagian penting dari lahan basah dunia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah
yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
30
IUCN, 2017, Mangroves and REDD New Component,
https://www.iucn.org/news/asia/201711/mangroves-and-redd-new-component-mff, diakses pada 20 Desember 2017.
31Anonim,2013, Mangrove Muara Gembong Rusak Parah 3 Desa Hilang
https://www.mongabay.co.id/2013/03/11/mangrove-muara-gembong-rusak-parah-3-desa-hilang/, diakses pada 20 Desember 2017.
14
1. Bagaimanakah perlindungan hukum hutan mangrove menurut
Ramsar Convention 1971?
2. Bagaimanakah implementasi Ramsar Convention 1971
terhadap perlindungan hutan mangrove di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hutan
mangrove menurut Ramsar Convention 1971.
2. Untuk mengetahui implementasi Ramsar Convention 1971
terhadap perlindungan hutan mangrove di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat
menjadi referensi acuan mengenai penelitian lain yang terkait
dengan Ramsar Convention 1971 terhadap perlindungan hutan
mangrove di Indonesia.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi untuk para pembuat kebijakan
dalam menyusun pengaturan lainnya tentang bagaimana
perlindungan hukum terkait hutan mangrove berdasarkan
Ramsar Convention 1971.
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Lingkungan Internasional
1. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional
Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan
yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memengaruhi kualitas
lingkungan, baik secara alami maupn buatan manusia, sebagaimana
dikemukakan oleh Mac Adrews dan Chia Lin Sien berikut ini:32
The nature of environmental law is such that the subject defies precies delineation. As a simple working definition, we might say that environmental law is the set of legal rules addressed spesifically to activities which potentially affect the quality of environment, whether natural or man-made. But it will be immediately apparent that even such a general definition raises a host of subsidiary issues which, in some cases, call for drawing of essentially arbitrary lines.
Sementara itu, secara lebih spesifik Ida bagus wyasa putra
mendefinisikan hukum lingkungan internasional sebagai:33
Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah,azas-azas, lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional, yang berobjek pada lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat Negara-negara, termasuk subjek hukum internasional bukan Negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.
32
Siti Sundari Rangkuti dalam Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.55.
33 Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, Hukum Lingkungan Internasional dalam
Perspektif Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.
16
Pengertian mengenai hukum lingkungan internasional juga
dikemukakan oleh Alexandre Kiss yang menyatakan bahwa:34
International environmental law is a branch of public international law. While agreements devoted to aspects of environmental protection have developed their own particularities, the structures and norms of international law provide the basic legal framework for the field. Within this framework, international rules having quite varied objectives often need to be includes as aa part of international environmental law, because they have a significant environmental impact. The first treaties, for example, were primarily intended to pervert conflict between fishermen of different nationalities and to protect local economies. Fulfillment of these objecctives nonetheless fostered concept of sustainable exploitation, permitting then maintenance and renewal of fish stocks. Similiry, norms to standardize the performance of internal combustion engines, originally adopted by the European Union in order to facilitate trade within region, have led to cleaner technology and reductions in engine noise and the emission of noxious gases. In sum, the field of international environmental law encompasses large arts of public international law as well as being subsumed within its basic structure.
2. Objek Hukum Lingkungan Internasional
Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, objek hukum internasional
berdasarkan pendekatan hukum internasional dan ekologi, dapat
diklasifikasikan atas tiga bagian yaitu:35
a. Lingkungan Hidup Sebagai Bagian Wilayah Suatu Negara
(Under National Juridiction)
Dijelaskan bahwa sebagai suatu wilayah suatu Negara, lingkungan
hidup tunduk pada kedaulatan dan yurisdiksi suatu Negara, karenanya
terhadap lingkungan hidup dalam status demikian berlakulah prinsip-
34
Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, 2007, Guide to International Environmental Law, Koninklijke Brill NV, Leiden,Belanda, hlm.1.
35 Ida Bagus Wyasa Putra, Op.cit, hlm.6-9.
17
prinsip kedaulatan dan yurisdiksi Negara, sebagaimana yang dijelaskan
dalam resolusi umum PBB No.3281 (XXIX) tentang Charter of Economic
Rights and Duties of States bahwa “Every state has and shall freely
exercises full permanent sovereignty, including prosession, use and
disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities”
Namun demikian, kedaulatan suatu Negara atas haknya dalam
pemanfaatan sumber daya alamnya tersebut yang merupakan bagian
wilayahnya tetap diimbangi dengan kewajiban untuk memastikan bahwa
pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak menimbulkan kerugian
terhadap Negara atau pihak lain yang berada diluar wilayah yurisdiksinya.
Sebagaimana yang termuat dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972
(Declaration of the United Nations Conference on the Human
Environment) bahwa:
“states have, in accordance with charter of the united nations and the principles of international law the sovereign right to exploit their own natural resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdictions ”
b. Lingkungan Hidup yang berada diluar wilayah suatu Negara
(beyond the limits of national jurisdiction)
Lingkungan hidup yang berada di luar wilayah suatu Negara baik
karena sifatnya yang tidak mungkin dikuasai maupun karena masyarakat
ineternasional menyepakati untuk tidak menempatkan kawasan-kawasan
18
demikian itu sebagai bagian wilayahnya adalah seperti laut bebas (high
sea) dan ruang angkasa (outer space ).
Terhadap kedudukan lingkungan hidup demikian itu berlakulah
kesepakatan negara-negara, baik yang dikukuhkan melalui suatu
perjanjian maupun yang lahir dari hukum kebiasaan internasional
(international customary law).
c. Lingkungan Hidup sebagai Suatu Keseluruhan (Global
Environment)
Sejak tahun 1970-an berkembang pandangan tentang lingkungan
hidup, lebih tegas lagi disebutkan sebagai lingkungan hidup bumi, sebagai
suatu keseluruhan (wholeness), yang diberi lingkungan hidup global
(global environment). Pandangan ini memandang lingkungan hidup bumi
sebagai suatu ekosistem besar, tempat satu-satunya dimana manusia
hidup dan menggantungkan kehidupannya, yang keberlanjutan daya
dukungnya tergantung pada stabilitas kualitas elemen-elemennya. World
Commission on Environment and Development (WCED) dalam laporan
studinya yang diberi judul Our Common Future menulis permulaan
laporan dengan menyatakan:
“In the middle of the 20th century, we saw our planet from space for first tim …. From space, we see a small and fragile ball dominated not by human activity and edifice but by a pattern of clauds, oceans, greeny, and soils. … we can see and study the earth as an organism whose health depends on the health of all it parts.
Pandangan demikian melahirkan konsep baru dalam pengaturan
internasional perihal pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup,
19
yang antara lain ditandai dengan lahirnya konsep global environment,
lingkungan hidup sebagai warisan bersama ummat manusia (common
heritage of mankind), lingkungan hidup sebagai objek kepentingan
bersama (common interest), krisis global (global atau interlocking crisis),
usaha bersama untuk mengatasi masalah lingkungan (common efforts),
dan lain-lain.
Oleh karenanya pandangan tentang konsep global environment
semakin menguat, bahwa elemen-elemen lingkungan global pada
hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan
membentuk serta memengaruhi kualitas lingkungan hidup secara
keseluruhan, yaitu lingkungan hidup yang teridiri dari elemen-elemen
yang berada di dalam wilayah suatu negara, seperti air, tanah, hutan,
flora, fauna dan keragaman hayati, dan elemen-elemen lain yang karena
sifat atau letaknya tidak dapat dijadikan objek pemilikan suatu negara,
seperti ozon, udara yang senantiasa bergerak, lapisan atmosfir, dan
elemen-elemen lain yang berada di luar wilayah setiap negara. Sehingga
memungkinkan gerakan-gerakan, usaha-usaha dan partisipasi yang
bersifat internasional, yang menembus batas-batas kedaulatan negara,
untuk bersama-sama mengatur pemanfaatan dan pengelolaan elemen-
elemen lingkungan hidup bumi.
3. Subjek Hukum Lingkungan Internasional
Berdasarkan definisi hukum lingkungan internasional yang telah
dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum lingkungan internasional
20
merupakan bagian dari hukum internasional publik, oleh karenanya
hukum internasional merupakan kerangka dasar dari hukum lingkungan
internasional. Sehingga subjek hukum lingkungan internasional adalah
subjek hukum internasional pada umumnya, seperti negara-negara,
organisasi-organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum
internasional bukan negara lainnya.
Adapun yang dimaksud bahwa hukum lingkungan internasional
memiliki corak tersendiri, hal tersebut dideskripsikan melalui objek hukum
lingkungan internasional yang telah dijelaskan sebelumnya36 Sehingga
dalam konteks hukum lingkungan internasional, ada peningkatan peran
subjek-subjek bukan negara, terutama subjek-subjek privat yang
sebenarnya tidak diterima sebagai subjek hukum internasional, sebab
atas dasar konsep Global Environment yang dideskripsikan dalam objek
hukum lingkungan internasional, ada pemberian kesempatan dan
pengakuan oleh negara-negara terhadap peran subjek-subjek seperti itu,
dan atas dasar gerakan humanisme universal yang lahir dari konsep
Global Environment yang menempatkan manusia sebagai suatu
keseluruhan atau mengatasnamakan keseluruhan untuk bergerak
bersama-sama dalam gerakan lingkungan internasional untuk menetukan
sikap terhadap tindakan yang bersifat merusak lingkungan hidup.37
36 Ibid, hlm.10. 37
Yusran Adrian Nisar, 2016, “Implementasi Convention on Biological Diversity
1992 Pada Sektor Kelautan di Indonesia”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,hlm.28.
21
4. Sumber-Sumber Hukum Lingkungan Internasional38
Sebagaimana halnya dengan sumber-sumber hukum internasional,
hukum lingkungan internasional memiliki sumber-sumber hukum seperti
perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum
umum, putusan mahkamah internasional, dan doktrin para ahli yang
disebutkan dalam Pasal 38 statuta mahkamah internasional. Meskipun
hanya diatur dalam statuta mahkamah internasional, sumber- sumber
hukum tersebut telah diterima dan diakui sebagai suatu sumber hukum
yang menciptakan aturan yang mengikat bagi negara-negara.
Hanya saja Pasal 38 tidak secara eksplisit mengatur sumber-
sumber hukum tersebut secara hirarkis, khususnya diantara tiga sumber
hukum pertama yang disebutkan, yang ada adalah hubungan keterkaitan
yang kompleks. Umumnya, Perjanjian internasional diinterpretasikan
sesuai dengan hukum kebiasaan yang memungkinkan, namun dengan
perjanjian pula suatu hukum kebiasaan juga dapat diubah asalkan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.
Praktik masyarakat internasional saat ini banyak mengandalkan
aktivitas-aktivitas organisasi-organisasi internasional yang berbeda yang
dapat berkontribusi terhadap perkembangan aturan hukum baru,
khususnya dengan mengadopsi non-binding text (naskah tidak mengikat)
atau non binding normative instrument (instrumen hukum tidak mengikat)
atau umumnya dikenal sebagai soft law. Instrumen hukum seperti itulah
38 Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, Op.cit., hlm. 3-16.
22
saat ini yang banyak memegang peranan dalam pembentukan hukum
internasional pada umumnya dan hukum lingkungan khususnya.
Instrumen hukum tersebut banyak digunakan sebab dinilai lebih
fleksibel sehingga seluruh kehendak subjek hukum internasional bahkan
termasuk subjek hukum yang tidak diterima sebagai subjek hukum
internasional. Subjek-subjek hukum tersebut dapat menempatkan
normative statements (pernyataan- pernyataan hukum) dan persetujuan-
persetujuan. Bahkan instrumen hukum demikian dinilai lebih mudah sebab
negosiasi atau perundingan dalam memformulasikannya dapat lebih cepat
daripada dalam bentuk perjanjian lainnya. Instrumen hukum seperti itu
juga dinilai lebih mudah untuk diimplementasikan, selain itu peserta
perunding akan mudah menggunakan tekanan politik untuk memengaruhi
peserta lainnya walau tidak ada tuntutan untuk menyesuaikan norma
hukum yang termuat dengan hukum nasional suatu negara peserta,
sehingga instrumen hukum tersebut sarat dengan nilai pengetahuan
ilmiah dan dinilai lebih ampuh dapat mendorong kesadaran publik untuk
melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
5. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional
a. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development)
Pengertian dari sustainable development adalah pembangunan
yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi
kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.
23
Definisi ini diberikan oleh World Commision on Environment and
Development (WCED) atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan
Pembangunan sebagaimana tersaji dalam laporan komisi yang terkenal
dengan komisi “Brutland” yang terumuskan berupa : “if it meets the needs
of the present without compromising the ability of future generation to
meet their own needs” (pembangunan yang berusaha memenuhi
kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang
untuk memenuhi kebutuhan mereka).39
b. Prinsip Keadilan Antargenerasi ( Principle of Intergenerational
Equity)
Berdasarkan prinsip ini negara dalam harus melestarikan dan
menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan
generasi sekarang dan mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi ini
terumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan hak untuk melakukan
pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi
sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam
memenuhi kebutuhannya. (the right to development must be fulled so as
to equitably meet developmental and environmental needs of present and
future generations).40
Beberapa elemen kunci dari intergenerational principle ini terurai
dalam rumusan yang dibuat oleh suatu konferensi internasional di
39
Laode M Syarief, Maskun, dan Birkah Latif, 2015, Evolusi Kebijakan dan
Prinsip-prinsip Lingkungan Global, dalam Laode.M Syarief Andri G Wibisana (ed), Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus, USAID-Kemitraan, Jakarta, hlm.49.
40 N.H.T Siahaan dalam ibid, hlm.50.
24
Canberra pada 13-16 November 1994 yang lazim disebut Fenner
Coference on the Environment. Prinsip ini dirumuskan dalam konferensi
tersebut:41
1) Setiap masyarakat di dunia ini antara satu generasi dengan
generasi lainnya berada dalam kemitraan (global partnership);
2) Generasi kini tidak semestinya memberikan beban
eksternalitas pembangunan bagi generasi berikutnya;
3) Setiap generasi mewarisi sumber-sumber alam dan habitat
yang berkualitas dan mewariskannya pula pada generasi
selanjutnya dengan mana generasi ini memiliki kesempatan
yang setara dalam kualitas fisik, ekologi, ekonomi, dan sosial;
4) Generasi kini tidak boleh mewariskan generasi selanjutnya
sumber-sumber alam yang tidak dapat dibarui secara pasti
(eksak).
c. Prinsip Keadilan Intragenerasi ( Principle of Intragenerational
Equity)
Keadilan intragenerasi merupakan keadilan yang ditujukan pada
mereka yang hidup di dalam satu generasi. Keadilan intragenerasi ini
terkait dengan distribusi sumber daya secara adil, yang berlaku pada
tingkat nasional maupun internasional.42 Lebih dari itu, disamping terkait
41
Ibid, hlm.49-50. 42
R. C. Bishop, Endangered Species and Uncertainty: the Economics of a Sale Minimum Standard”. Amerian Journal of Agricultural Economics, dikutip dalam Andri G. Wibisana, “Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam
25
dengan distribusi sumber daya dan manfaat/ hasil pembangunan. Konsep
keadilan intragenerasi juga bisa dikaitkan dengan distribusi risiko/biaya
sosial dari sebuah kegiatan pembangunan.
Keadilan intragenerasi merupakan prioritas pertama dari
pembangunan berkelanjutan. Hal ini, menurut Langhelle, ditunjukkan
dalam bagian pertama dari definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu
“development that meets the needs of the present…”. Bagian inilah yang
menunjukkan adanya komitmen dari negara-negara terhadap keadilan,
termasuk redistribusi dari pihak yang kaya kepada yang miskin, baik
dalam level nasional, maupun internasional. Selanjutnya, Prof. Ben Boer,
pakar hukum lingkungan dari Universitas Sidney, menunjuk kepada
gagasan bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu
generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati
lingkungan yang bersih serta sehat. Keadilan intragenerasi dapat
diartikan, baik secara nasional, maupun internasional.43
d. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)44
Pernyataan tentang prinsip ini terdapat dalam Deklarasi Rio (Rio
Declaration) yang dianggap sebagai salah satu ketentuan yang paling
penting, yaitu pada prinsip 15 yang berbunyi:
“In order to protect the environment, the precautionary principle
shall be widely applied by states according to their capabilities.
Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of
Hukum Lingkungan”, 2013 akan dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan (forthcoming), hlm. 22. 43
N.H. T Siahaan, Op. cit., hlm.53. 44
Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, Op.cit. ,hlm. 94-95.
26
full scientific certainty shall not be used a reason for postponing
cost-effective measures to prevent environmental degradation.”
Bahwa dalam rangka melindungi lingkungan hidup, prinsip kehati-
hatian harus diterapakan secara luas oleh negara-ngeara sesuai dengan
kemampuan mereka. Dimana ada ancaman kerusakan yang serius atau
ireversibel, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk
menunda langkah-langkah pembiayaan efektif untuk mencegah terjadinya
degradasi lingkungan hidup. Perumusan prinsip ini memang masih relatif
baru, tetapi sejak tahun 1992 prinsip ini telah muncul hampir di seluruh
instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Pada umumnya prinsip ini dianggap sebagai pengembangan dari
prinsip pencegahan yang tetap menjadi asas umum untuk hukum
lingkungan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kehati-hatian berarti
mempersiapkan untuk suatu potensi, hal yang tidak tentu, atau bahkan
ancaman hipotesis, ketika ada bukti yang takterbantahkan bahwa
kerusakan akan terjadi. Tindakan demikian merupakan bentuk
pencegahan yang didasari pada kemungkinan ataupun kontinjensi, tetapi
tidak sertamerta dapat menghilangkan semua resiko yang diklaim, sebab
ada klaim resiko yang kurang ilmiah, seperti ramalan bintang atau
penglihatan-penglihatan fisik.
e. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)45
Prinsip ini berusaha menekankan agar kerugian yang timbul akibat
pencemaran lingkungan hidup ditanggung pihak yang melakukan
45
Ibid, hlm. 95-97.
27
pencemaran. Prinsip ini dirumuskan oleh the Organisation for Econommic
Co-operation and Development (OECD) sebagai sebuah prinsip dengan
pendekatan ekonomi dan merupakan langkah yang paling efisien untuk
mengalokasikan biaya dari pencegahan pencemaran dan langkah-
langkah pengendalian yang diajukan oleh otoritas publik terhadap negara-
negara anggota. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan yang
rasional terhadap sumber daya lingkungan hidup yang langka dan untuk
menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam perdagangan
perdagangan internasional dan penanaman modal.
Rumusan prinsip ini termuat dalam Rio Declaration pada prinsip 16
yang berbunyi:
“National authorities should endeavor to promote the internalization
of environmental costs and the use of economic instruments, taking
into account the approach that the polluter should, in principle, bear
the cost of pollution, with regard to the public interest and without
distorting international trade and investment.”
Bahwa Otoritas nasional harus berusaha mempromosikan
internalisasi biaya lingkungan hidup dan penggunaan instrumen ekonomi,
dengan mempertimbangkan pendekatan yang pencemar harus, pada
prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan
kepentingan umum dan tanpa mendistorsi perdagangan internasional dan
penanaman modal.
f. Prinsip Langkah Pencegahan (Principle of Preventive Action)
Prinsip ini menyatakan bahwa lebih baik mencegah kerusakan
lingkungan daripada menanggulangi kerusakan lingkungan dan/atau
28
memberikan ganti rugi atas kerusakan lingkungan.46 Prinsip ini
dirumuskan dalam prinsip 11 Rio Declaration on Environment and
Development yang menyatakan “States shall enact effective
environmental legislation….” Prinsip ini menekankan pentingnya langkah-
langkah antisipasi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan setiap
negara diberi kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan
dan tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan terjadi47
Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara diberi kewajiban
untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh
melakukan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berasal
dari kejadian di dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya
kerusakan lingkungan.48
g. Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary Principle)49
Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau
pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan
untuk menunda upaya-upaya mencegah kerusakan lingkungan. Dalam
rumusan Prinsip 15 Deklarasi Rio dinyatakan sebagai berikut:
”In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientic certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environment degradation”.
46 Elli Louka, 2006, International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and
World Order, Cambridge University Press, New York, hlm. 50. 47
Laode M Syarief dan Andri.G. Wibisana (ed), Op.cit, hlm.61. 48
ibid 49
Ibid, hlm.62.
29
Prinsip ini merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan
lingkungan yang didasarkan kepada satu hal yang perlu dalam melakukan
prevensi atau penanggulangan hanya akan dapat dilakukan jika telah
benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan. Sungguh sangat merugikan
sekali jika sesuatu yang sudah berpotensi atau sudah terjadi kerusakan
lingkungan, baru dapat diambil sebuah keputusan setelah diketahui atau
dibuktikan lebih dahulu secara pasti.
h. Prinsip Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara (Sovereign
Rights and Environmental Responsibility)50
Di dalam Deklarasi Rio terdapat perumusan prinsip mengenai
kedaulatan negara untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya
alam tanpa merugikan negara lain (right to explosit resources but
responsible do not to cause damage to the environment of other states)
yang tercantum pada prinsip 2. Secara korelasi prinsip 2 ini diadopsi dari
Deklarasi Stockholm, yaitu pada prinsip 21 yang berbunyi:
States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of otherStates or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
Pada dasarnya prinsip tanggungjawab negara ini memiliki dua dimensi,
yaitu:
1) Memeberikan hak kedaulatan kepada negara untuk memanfaatkan
50 Ibid, hlm.64.
30
Sumber daya alam berdasarkan kebijakan lingkungan masing-
masing;
2) Memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan
bahwa aktivitas dalam yurisdiksinya tidak akan menyebabkan
kerusakan lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan diluar
batas yurisdiksi nasional.
B. Perjanjian Internasional
1. Pengertian Perjanjian Internasional
Merujuk pada Vienna Convention on the Law of Treaties 1969,
pengertian perjanjian internasional yaitu:51
“Treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and what ever its particular designation”.
Hal ini berarti perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan
yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum
internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih
instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya.
Sementara itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, memberikan definisi tersendiri untuk perjanjian
internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur
51 Lihat pasal 2 ayat 1 (a) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969
31
dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan
hak dan kewajiban dibidang hukum publik.52
Pada kerangka teoritis Mochtar Kusumaatmadja merumuskan
definisi perjanjian internasional yaitu perjanjian yang diadakan antara
anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan mengakibatkan akibat
hukum tertentu.53
Suatu perjanjian internasional disebut sebagai perjanjian
internasional apabila perjanjian itu diadakan oleh anggota-anggota
masyarakat internasional sehingga suatu perjanjian internasional dapat
diadakan antara negara dengan negara lain atau negara-negara lain,
antara negara dengan organisasi internasional, antara organisasi
internasional yang satu dengan organisasi internasional lainnya, antara
negara atau organisasi internasional dengan subjek hukum internasional
lain seperti Vatikan (Tahta Suci), Organisasi Pembebasan, Kaum
Beligerensi, ataupun subjek hukum bukan negara (Non States Entities).54
Terdapat berbagai istilah atau nomenklatur yang dapat digunakan
pada perjanjian internasional. Ada istilah yang dinamakan Treaty atau
traktat, Agreement atau persetujuan, Convention atau Konvensi,
Covenant atau kovenan, Declaration atau deklarasi, Protocol atau
protokol, Pact atau pakta, Act atau akta, Statue atau statuta, Charter atau
52
Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional 53
Mochtar Kusumastmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, hlm. 117.
54 Muhammad Ashri, 2012, Hukum Perjanjian Internasional, Arus Timur,
Makassar,hlm.3.
32
piagam, Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman,
Exchange of notes atau pertukaran nota, Modus Vivendi, Letter of Intent
serta masih banyak istilah atau penamaan yang dapat dipakai pada
pengertian perjanjian internasional.55
2. Konvensi (Convention)
Konvensi merupakan salah satu nomenklatur atau penamaan dari
perjanjian internasional yang diakui dalam statuta mahkamah
internasional, yang diatur dalam pasal 38 ayat 1. Konvensi adalah bentuk
perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi
yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat Law Making Treaty
yang dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi
masyarakat internasional.56
Pengertian Konvensi secara terminologi, yaitu:57
a. Dalam pengertian umum, terminologi convention juga mencakup
pengertian perjanjian internasional secara umum. Dalam hal ini
pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menggunakan
international conventions sebagai salah satu sumber hukum
internasional. Dengan demikian pengertian umum convention
dapat disamakan dengan pengertian umum treaty;
b. Dalam pengertian khusus, terminologi convention yang dalam
bahasa Indonesia desebut sebgai “Konvensi, digunakan
55
Ibid, hlm.10. 56
Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian internasional: Kajian Teori dan raktik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.33.
57 Muhammad Ashri, Op.cit., hlm.15.
33
sebagai penamaan bagi perjanjian multilateral yang melibatkan
sejumlah besar negara peserta sebagai peserta perjanjian.
Disamping itu, instrumen hukum internasional yang
dirundingkan atas prakarsa dan disepakati melalui organisasi
internasional, umumnya juga diberi nama Konvensi.
Pada umumnya Konvensi ini digunakan untuk perjanjian-perjanjian
internasional multilateral yang mengatur tentang masalah yang besar dan
penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum
internasional yang dapat berlaku secara luas, baik dalam lingkup regional
maupun umum.58
3. Implementasi Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional
Terkait pengertian implementasi perjanjian internasional , Anderas
Pramudianto menjelaskan adanya hubungan antara hukum internasional
dengan hukum nasional disebabkan oleh adanya tindakan implementasi.
Kemudian ia mengutip pendapat Siswanto terkait pengertian implementasi
dalam konteks ini, yaitu bahwa implementasi merupakan berlakunya
hukum internasional ke dalam hukum nasional.59 Kemudian Boer Mauna
menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan implementasi perjanjian
internasional adalah membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung
apa yang diatur di dalam perjanjian yang telah diterima. Tanpa adanya
58
I Wayan Parthiana, 2002, Perjanjian Internasional bagian 1, Mandar Maju, Bandung,hlm.28.
59 Andreas Pramudianto, 2014, Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional
(Implementasi Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia), Setara Press, Malang,hlm.199.
34
perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian di mana Indonesia telah
menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan
tidak ada gunanya60
Andreas Pramudianto menambahkan bahwa upaya tersebut yaitu
upaya menerapkan atau memberlakukan perjanjian internasional ke
dalam hukum nasional yaitu di antaranya melalui pembentukan perangkat
hukum nasional tindak lanjut membentuk perangkat perundang-undangan
nasional, baik sektor maupun daerah, perangkat pengaturan sistem
kelembagaan atau institusi serta praktek dan putusan peradilan yang
menyatakan keberadaan dokumen atau perjanjian internasional yang
ditegaskan melalui putusannya.61
Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum
internasional atau perjanjian internasional ke dalam hukum nasional dapat
terlaksana melalui pengaturan hukum internasional atau perjanjian
internasional tertentu ke dalam peraturan perundang-undangan atau
sistem hukum nasional diikuti dengan penegakan hukum, berkaitan
dengan pembentukan sistem kelembagaan atau institusi dalam hal
tertentu dan juga persoalan aparatur penegak hukum.
60
Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), PT. Almuni, Bandung, hlm. 145.
61 Andreas Pramudianto, Op.cit., hlm.200.
35
C. Hutan Mangrove
1. Pengertian Hutan Mangrove
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
mengartikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.62 Adapula yang mendefinisikan hutan sebagai suatu kawasan
yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya,
yang berfungsi sebagai penampung karbondioksida (Carbon Dioxide
Sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah dan
merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.63
Sedangkan kata mangrove merupakan perpaduan Bahasa Melayu
manggi-manggi dan bahasa Arab el-gurm menjadi mang-gurm, keduanya
sama-sama berarti Avicennia (api-api), pelatinan nama Ibnu Sina, seorang
dokter Arab yang banyak mengidentifikasi manfaat obat tumbuhan
mangrove.64 Sedangkan menurut Macnae kata mangrove merupakan
perpaduan Bahasa Portugis mangue (tumbuhan laut) dan bahasa Inggris
grove (belukar), sehingga mangrove dapat diartikan sebagai belukar yang
tumbuh di tepi laut. 65
62
Lihat Pasal 1 UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan 63
Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.18.
64 Jayatissa, L.P., F. Dahdouh-Guebas, and N. Koedam. 2002. A review of the
floral composition and distribution of mangroves in Sri Lanka. Botanical Journal of the Linnean Society 138, hlm.23.
65 Macnae, W. 1968. A general account of the fauna and flora of mangrove
swamps and forests in the Indo-West-Pacific region. Advances in Marine Biology 6, hlm. 73.
36
Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropika yang
didominasi oleh beberapa spesies pohon bakau yang mampu tumbuh dan
berkembang pada kawasan pasang surut pantai berlumpur. Komunitas ini
pada umumnya tumbuh pada kawasan intertidal dan supertidal yang
mendapat aliran air yang mencukupi, dan terlindung dari gelombang besar
dan arus pasang surut yang kuat. Karena itu hutan mangrove banyak
dijumpai di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan kawasan-
kawasan pantai yang terlindung.66
Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidal forest, coastal
woodland, vloedbosschen dan hutan payau (bahasa Indonesia). Selain itu,
hutan mangrove oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara
lainnya yang berbahasa Melayu sering disebut dengan hutan bakau.
Penggunaan istilah hutan bakau untuk hutan mangrove sebenarnya
kurang tepat, karena bakau hanyalah nama lokal dari marga Rhizophora,
sementara hutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga
dan jenis tumbuhan lainnya. Oleh karena itu, penyebutan hutan mangrove
dengan hutan bakau sebaiknya dihindari.67
Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau,dan
dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di
tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik.
66
Yuniarti S dalam Konny Rusdianti dan Satyawan Sunito, 2012, Konversi Lahan Hutan Mangrove Serta Upaya Penduduk Lokal Dalam Merehabilitasi Ekosistem Mangrove (Mangrove Forest Conservation and The Role of Local Community in Mangrove Ecosytems Rehabilitations), Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6, No. 1 2012, hlm.3.
67Kusmana dalam Irwanto, 2010, Hutan Mangrove dan Manfaatnya,
irwantomangrove.webs.com, diakses pada15 November 2017.
37
Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di
sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur
yang dibawanya dari hulu.68
Menurut Soerianegara hutan mangrove mempunyai pengertian
sebagai hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di
daearah teluk dan di muara sungai yang dicirikan oleh: 1) tidak
terpengaruh iklim; 2) dipengaruhi pasang surut; 3) tanah tergenang air
laut; 4) tanah rendah pantai; 5) hutan tidak mempunyai struktur tajuk; 6)
jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri dari Api-api (Avicenia sp.), Pedada
(Sonneratia sp.), Bakau (Rhizophora sp.), Lacang (Bruguiera sp.), Nyirih
(Xylocarpus sp.) dan Nipah (Nypa sp.).69
2. Jenis- jenis Mangrove
Indonesia sebagai negara pusat keanekaragaman hayati di dunia
tercatat memiliki 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon,
5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit dan
1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 jenis pohon
dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati (true
mangrove), sementara jenis lain ditemukan disekitar mangrove dan
dikenal sebagai jenis mangrove ikutan (associate mangrove).70
Mangrove merupakan suatu komponen ekosistem yang terdiri atas
68
Nurhenu Karuniastuti, 2013, Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup, Forum Manajemen Vol. 06 No. 1 2013, Diakses Dalam Http://Pusdiklatmigas.Esdm.Go.Id/File/M1_Peranan_Hutan__________Nurhenu_K.Pdf
69 ibid
70 Yus Rusila Noor, M. Khazali dan I N.N. Suryadiputra, Op.cit .,hlm.2.
38
komponen mayor dan komponen minor. Komponen mayor merupakan
komponen yang terdiri atas mangrove sejati, yakni mangrove yang hanya
dapat hidup di lingkungan mangrove (pasang surut). Komponen minor
merupakan komponen mengrove yang dapat hidup di luar lingkungan
mangrove (tidak langsung kena pasang surut air laut). Mangrove yang
merupakan komponen mayor disebut juga dengan mangrove sejati,
sedangkan mangrove yang termasuk komponen minor disebut dengan
mangrove ikutan.71
Adapun Yang termasuk mangrove sejati meliputi Acanthaceae,
Pteridaceae, Plumbaginaceae, Myrsinaceae, Loranthaceae,
Avicenniaceae, Rhizophoraceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae,
Asclepiadaceae, Sterculiaceae, Combretaceae, Arecaceae, Myrtaceae,
Lythraceae, Rubiaceae, Sonneratiaceae, Meliaceae. Sedangkan untuk
mangrove ikutan meliputi Lecythidaceae, Guttiferae, Apocynaceae,
Verbenaceae, Leguminosae, Malvaceae, Convolvulaceae,
Melastomataceae.72
Dari sekian banyak jenis mangrove di Indonesia, jenis mangrove
yang banyak ditemukan antara lain adalah jenis Api-api (Avicennia sp.),
Bakau (Rhizophora sp.), Tancang (Bruguiera sp.), dan Bogem atau
Pedada (Sonneratia sp.), merupakan tumbuhan mangrove utama yang
banyak dijumpai.
71
Lihat http://indonesia.wetlands.org/Infolahanbasah/Spesies,Mangrove/, diakses pada tanggal 3 Januari 2018 Pukul 08:20 WITA.
72 Yus Rusila Noor, M. Khazali dan I N.N. Suryadiputra, Op.cit, hlm.10.
39
Gambar 1. Bakau (Rhizopora sp.)
73 Gambar 2.Tancang (Bruguiera sp.)74
Gambar 3. Bogem (Sonneratia sp.)75 Gambar 4. Api-api (Avicennia sp.)76
3. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove
Hutan Mangrove memberikan perlindungan kepada berbagai
organisme baik hewan darat maupun hewan air untuk bermukim dan
berkembang biak. Hutan Mangrove dipenuhi pula oleh kehidupan lain
seperti mamalia, amfibi, reptil, burung, kepiting, ikan, primata, serangga
dan sebagainya. Selain menyediakan keanekaragaman hayati
73
Anonim, 2016, Sat 1.Png https, //i0.wp.com/agroteknologi.web.id/wp-content/uploads/2016/03/sat1-1.png?fit=547%2C353, diakses pada 02 Januari 2018.
74 Arief Rudiyanto,2016 ,Lindur Mangrove Tancang Bruguiera-Gymnorrhiz.
http://www.biodiversitywarriors.org/lindur-mangrove-tancang-bruguiera-gymnorrhiza.html, diakses pada 02 Januari 2018.
75 Arief Rudiyanto,2016 Bogem, Apel Mangrove Sonneratia alba,
http://www.biodiversitywarriors.org/bogem-prapat-padada-bogem-prepat-apel-mangrove.html, diakses pada 02 Januari 2018.
76 Universitas Multi Media Nusantara, 2014, Jenis-jenis tanaman di hutan
Mangrove, https://wearemangroove.weebly.com/blog/-jenis-jenis-tanaman-di-hutan-mangrove, diakses pada diakses pada 02 Januari 2018.
40
(biodiversity), ekosistem mangrove juga sebagai plasma nutfah
(geneticpool) dan menunjang keseluruhan sistem kehidupan di sekitarnya.
Habitat mangrove merupakan tempat mencari makan (feeding ground)
bagi hewan-hewan tersebut dan sebagai tempat mengasuh dan
membesarkan (nursery ground), tempat bertelur dan memijah (spawning
ground) dan tempat berlindung yang aman bagi berbagai ikan-ikan kecil
serta kerang (shellfish) dari predator.77
Berikut beberapa fungsi dan manfaat dari hutan mangrove yaitu:78
a. Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara fisik antara lain;
1) Penahan abrasi pantai.
2) Penahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan.
3) Penahan badai dan angin yang bermuatan garam.
4) Menurunkan kandungan karbondioksida (CO2) di udara
(pencemaran udara).
5) Penghambat bahan-bahan pencemar (racun) diperairan
pantai.
b. Fungsi dan manfaat hutan bakau secara biologi antara lain;
1) Tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung, mencari
makan, pemijahan maupun pengasuhan.
2) Sumber makanan bagi spesiesspesies yang ada di sekitarnya.
3) Tempat hidup berbagai satwa lain, misal kera, buaya, dan
burung.
77
Irwanto, 2010,Hutan Mangrove dan Manfaatnya, irwantomangrove.webs.com, diakses pada15 November 2017
78 Yus Rusila Noor, M. Khazali dan I N.N. Suryadiputra Op.cit hlm.3-4.
41
c. Fungsi dan manfaat hutan bakau secara ekonomi antara lain;
1) Tempat rekreasi dan pariwisata.
2) Sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar.
3) Penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan
lainnya.
4) Bahan penghasil obat-obatan seperti daun Bruguiera sexangula
yang dapat digunakan sebagai obat penghambat tumor.
5) Sumber mata pencarian masyarakat sekitar seperti dengan
menjadi nelayan penangkap ikan dan petani tambak.
4. Kondisi Hutan Mangrove
a. Kondisi Hutan Mangrove di Dunia
Saat ini di seluruh dunia terjadi peningkatan hilangnya sumberdaya
mangrove yang disebabkan adanya pemanfaatan yang tidak
berkelanjutan serta pengalihan peruntukan. Berdasarkan data yang
dikeluarkan FAO, total wilayah mangrove telah menurun dari 18,8 juta
hektar pada tahun 1980 menjadi 15,2 juta hektar pada tahun 2005. Benua
Asia menderita kerugian terbesar sejak tahun 1980, dengan lebih dari 1,9
juta hektar hutan mangrove hancur, terutama karena adanya perubahan
dalam penggunaan lahan. Amerika Utara dan Tengah dan Afrika juga
berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan luas mangrove,
dengan kehilangan masing-masing sekitar 690.000 dan 510.000 hektar
42
selama 25 tahun terakhir.79 Sementara itu, Sekitar 17% mangrove di
Benua Australia telah hancur sejak pemukiman Eropa. Mangrove di dekat
pusat-pusat pengembangan telah hancur dan rusak secara sistematik,
salah satunya Teluk Moreton yang terletak di dekat kota Brisbane dimana
diperkirakan 20% wilayah mangrove di daerah tersebut terkena
reklamasi.80
Adapun penyebab hilangnya kawasan hutan mangrove ini antara
lain konversi lahan, konsentrasi penguasaan lahan, industri budidaya
udang, industri pertambakan garam, proyek pariwisata, bendungan,
industri kelapa sawit dan perkebunan gula, ekstraksi minyak dan gas dan
konstruksi jalan layan dan pelabuhan besar.81
b. Kondisi Hutan Mangrove di Indonesia
Data perkiraan luas areal mangrove di Indonesia sangat beragam
sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar penurunan
luas areal mangrove tersebut. Meskipun mangrove tidak terlalu sulit untuk
dikenali dari foto penginderaan jarak jauh dan dipetakan, kenyataannya
memperoleh data yang memadai mengenai luas mangrove pada masa
79
FAO, 2008, Loss of mangroves alarming 20 percent of mangrove area
destroyed since 1980 – rate of loss slowing,
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000776/index.html, diakses pada 12
Desember 2017. 80
Mangrove Watch Australia, 2013, Mangrove Watch, A New Monitoring Program that Partners Mangrove Scientists and Community Participants,http://www.mangrovewatch.org.au/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=300161, diakses pada 02 Januari 2018.
81 The World Rainforest Movement, 2014, “Blue Carbon” and “Blue REDD”:
Transforming coastal ecosystems into merchandise, Redmanglar Internacional, Kiara,
CPP, Canco Montevideo, Uruguay, hlm.7.
43
yang lalu dan saat ini tidak terlalu mudah. Departemen Kehutanan pada
tahun 1997 menyebutkan luas yang diambil dari berbagai sumber berkisar
antara 2,49-4,25 juta hektar. Namun, terdapat jumlah luasan mangrove
yang lain yaitu 4,54 juta hektar yang berasal dari ISME (International
Society for Mangrove Ecosystems) dan 3,53 juta hekar yang berasal dari
Proyek Inventarisasi Hutan Nasional.82
Perbedaan perkiraan luas tersebut setidaknya dipengaruhi oleh tiga
hal.83 Pertama, sangat sedikit dilakukan penghitungan areal mangrove
berdasarkan kondisi yang sebenarnya di alam, sehingga data yang
sebenarnya telah kadaluwarsa dan diacu berulang-ulang. Kedua,
perkiraan luas untuk Irian jaya yang merupakan komponen luasan
terbesar sangat berbeda antara satu penulis dengan penulis lainnya,
mulai dari 1,38 - 2,94 juta hektar. Hal ini kembali disebabkan kurang
tersedianya data serta peta yang memadai. Ketiga, adanya perbedaan
metode yang digunakan dalam menduga luasan mangrove.
Salah satu publikasi terbaru tentang status mangrove Indonesia
adalah buku Peta Mangrove Indonesia (Indonesian Mangrove Atlas) yang
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(Bakosurtanal) pada tahun 2009. Badan ini yakin bahwa angka yang
disajikan untuk wilayah mangrove nasional dalam publikasi ini adalah
yang paling akurat karena perkiraan ini didasarkan pada analisis satelit
yang mencakup seluruh wilayah pesisir Indonesia. Perkiraan luas
82
Yus Rusila Noor, M. Khazali dan I N.N. Suryadiputra Op.cit, hlm 23 83
ibid
44
mangrove bangsa selama lima tahun terakhir disajikan pada di bawah
ini.84
Tabel 1. Publikasi Perkiraan Luas Hutan Mangrove di Indonesia.
Source and year of
Publication
Mangrove Estimate Data Source
Area (ha) Year
Giesen et al (2006)
2,930,000 2000 FAO (2003); Spalding et
al. (1997)
FAO (2007) 2,900,000 2005
Dephut (2003) and other supporting sources
RLPS-MoF (2007) 7,758,410 2000
Peta sistem lahan nasional 1995 – 2000
Spalding (2010) 3,062,300 2003 MoF (2003)
Bakosurtanal (2009)
3,244,018 2009 Satellite Images Analysis
Terlepas dari perdebatan tentang luas hutan mangrove yang ada di
Indonesia, maka hal yang perlu diketahui adalah fakta terkait tingginya laju
kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Indonesia. Studi literatur yang
dilakukan oleh Widodo menunjukkan bahwa hutan mangrove di Indonesia
menyusut secara drastis dari total luas 5,21 juta menjadi 3,24 juta hektar
dalam lima tahun (1982-1987). Penurunan ini berlanjut sampai hanya 2,5
juta hektar pada tahun 1993. Sementara itu Anwar dan Gunawan pada
2006, menyatakan bahwa laju kerusakan mangrove di Indonesia telah
mencapai 530.000 hektar pertahunnya. Hal ini membuktikan laju
kerusakan jauh lebih cepat dari laju rehabilitasi mangrove, yang
diperkirakan hanya sekitar 1.973 hektar pertahun.85
84 Muhammad Ilman, Iwan Tri Cahyo Wibisono, dan I Nyoman N. Suryadiputra,
2011, State of the art information on mangrove ecosystems in Indonesia, Bogor: Wetlands International Indonesia Programme,hlm.2.
85 Ibid, hlm.3.
45
Sementara itu Direktur Bina Pengelolaan Kawasan Ekosistem
Esensial, Antung Deddy Radiansyah menyatakan bahwa hingga tahun
2015 luas hutan mangrove di Indonesia hanya tersisa 3.489.140,68 hektar
Namun, ternyata dari luas mangrove di Indonesia, diketahui hanya
1.671.140,75 hektar yang berada dalam kondisi baik, sedangkan areal
sisanya seluas 1.817.999,93 hektar dalam kondisi rusak.86
5. Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia87
a. Tambak Udang
Budidaya udang merupakan salah satu usaha yang paling diminati
yang dilakukan di daerah mangrove. Penebangan pohon mangrove untuk
dijadikan tambak udang menjadi penyebab terbesar hilangnya mangrove
di Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan
pada tahun 2005, ekspansi tambak telah bertanggung jawab atas
penghancuran hutan mangrove sekitar 750 ribu hektar. Dengan
menggunakan perkiraan moderat (1,5 juta hektar) dari penipisan tutupan
hutan mangrove di Indonesia, ini berarti bahwa ekspansi tambak telah
menyumbang 50% dari hilangnya mangrove di Indonesia.
b. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit
Euforia untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit telah
menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memacu pembukaan
hutan (termasuk hutan mangrove) menjadi perkebunan kelapa sawit.
86
Deddy Radiansyah, Loc.cit. 87
Muhammad Ilman, Iwan Tri Cahyo Wibisono, dan I Nyoman N. Suryadiputra,
Op.cit, hlm.4-10.
46
Wetlands International Indonesia Programme (WIIP) telah mengidentifikasi
setidaknya tiga kasus konversi tutupan lahan dari mangrove ke kelapa
sawit, yaitu: 1) Di Sumatera Utara, 2.000 hektar hutan mangrove telah
dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. 2) Di Bandar Pasir Mandoge
(Kabupaten Asahan), hutan mangrove di sepanjang pantai telah
dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit baik oleh masyarakat
setempat maupun oleh perusahaan swasta. Sayangnya, tidak ada angka
yang tersedia untuk area yang dikonversi. Dan 3) Di Aceh Tamiang
(Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 17.000 hektar (sekitar 85% dari
total 20.000 hektar) hutan mangrove telah dikonversi menjadi kelapa
sawit.
c. Konversi Mangrove Menjadi Lahan Pertanian
Di Indonesia, diperkirakan sekitar 200.000 hektar hutan mangrove
dikonversi untuk pertanian pada tahun 1969 - 1974 (Burung dan
Ongkosongo, 1980). Konversi fungsi hutan mangrove ke lahan pertanian
tercatat di beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat,
Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Di provinsi-provinsi ini, hutan
mangrove benar-benar ditebang dan lahannya digunakan untuk sawah
dan hortikultura.
d. Konversi Mangrove menjadi Tambak Garam
Meski tidak meluas, beberapa hutan mangrove di Indonesia juga
telah dikonversi menjadi tambak garam. Tambak garam di Indonesia
diperkirakan mencakup sekitar 36.000 hektar di berbagai provinsi -
47
provinsi di Indonesia seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa
Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
e. Pembangunan di Wilayah Pesisir
Perencanaan tata ruang wilayah pesisir merupakan salah satu
alasan mengapa ekosistem mangrove dapat dikorbankan untuk proyek
pembangunan. Giesen pada tahun 2006 menyatakan bahwa kontribusi
perkembangan pesisir terhadap konversi ekosistem mangrove untuk
tujuan lain sangat besar, yakni sekitar 1,1 juta hektar.
Situasi ini semakin diperburuk pada era reformasi dan
desentralisasi pemerintah yang dimulai pada tahun 1998, karena
pemerintah daerah memperoleh kebebasan yang sangat besar untuk
mengendalikan pembangunan daerah mereka. Keinginan kuat untuk
mempercepat pembangunan ekonomi pesisir di daerah mereka telah
mendorong pemerintah daerah untuk mengambil jalan pintas dengan
mengorbankan ekosistem mangrove.
f. Pembalakan
Seperti halnya hutan terestrial, hutan mangrove juga ditebang, baik
secara legal maupun ilegal. Pembalakan legal biasanya dilakukan oleh
perusahaan kayu yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
sementara pembalakan liar biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat.
Hal ini menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan mangrove.
7. Pertambangan
48
Informasi tentang kegiatan penambangan di ekosistem mangrove di
Indonesia sangat terbatas. Namun, faktor pertambangan yang merusak
hutan mangrove ini dapat dilihat dari beberapa kasus. Di Provinsi Bangka
Belitung, kegiatan penambangan timah di tahun 2009/2010 menimbulkan
70 persen dari total 122.000 hektar hutan mangrove terdegradasi. Pada
tahun 2007, empat perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi
di provinsi Kalimantan Selatan (PT BCMP, PT Borneo Inter Nusa, CV
Antara, CV Rahma dan PT Adibara Pelsus) dilaporkan telah
menghancurkan hutan mangrove di Pantai Serongga, Kabupaten
Kotabaru Dilaporkan bahwa kegiatan penambangan batubara ini juga
menyebabkan bahan kimia berbahaya bagi hutan mangrove dan
ekosistem lainnya di wilayah Kabupaten Kota Baru. Selain itu, hutan
mangrove di Pulau Batam dilaporkan telah mengalami degradasi parah
akibat penggalian pasir.
g. Bencana Alam
Terletak di "ring of fire" yang aktif secara vulkanologis, Indonesia
dikenal sebagai negara yang sangat rentan terhadap bencana. Bencana
alam ini juga bertanggungjawab atas kerusakan berbagai jenis ekosistem,
yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Dari bencana yang
disebutkan di atas, tsunami merupakan ancaman terbesar bagi ekosistem
pesisir, termasuk hutan mangrove. BAPPENAS (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional) melaporkan bahwa hutan mangrove yang hancur
akibat tsunami berjumlah 25.000 hektar. Angka yang berbeda dilaporkan
49
oleh LAPAN yang menyatakan bahwa kawasan hutan mangrove yang
hancur akibat tsunami adalah sebanyak 32.000 hektar, yang sebagian
besar berada di pesisir utara dan timur Aceh.
D. Ramsar Convention 1971
1. Latar Belakang Lahirnya Ramsar Convention 1971
Konvensi Ramsar tahun 1971 merupakan suatu instrumen
perjanjian internasional yang telah dibuat dan dibentuk untuk memobilisasi
tindakan dan melindungi wilayah lahan basah dari kehilangan yang cepat
di seluruh dunia. Konvensi ini diawali oleh diselenggarakannya konferensi
MAR pada tahun 1962 di Camargue, Perancis. Konferensi ini
diselenggarakan oleh International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN), International Waterfowl Research
Bureau (IWRB) dan International Council for Birds Preservation (ICBP)
menyusul kekhawatiran akan tingginya laju reklamasi pada daerah rawa-
rawa dan lahan basah lainnya di Eropa yang menyebabkan menurunnya
populasi burung air.88
Delapan tahun berikutnya, teks Konvensi kembali dinegosiasikan
melalui serangkaian pertemuan internasional diantaranya (St.Andrews,
1963; Noordwijk, 1966; Leningrad, 1968; Morges, 1968; Vienna, 1969;
Moscow, 1969; Espoo, 1970), yang diselenggarakan oleh IWRB dibawah
bimbingan G.V.T Mattewes dari Belanda. Pada awalnya Konvensi ini
dikhususkan pada perlindungan habitat unggas air tetapi kemudian
88 Ramsar Secretariat, 2016, An Introduction to the Ramsar Convention on
Wetlands, 7th ed. (previously The Ramsar Convention Manual). Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland., hlm.19.
50
berkembang pada konservasi habitat lahan basah atas saran seorang ahli
hukum bernama Cyrille de Klemm. Akhirnya pada tahun 1971 diadakan
sebuah pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh Eskandar
Firouz Direktur Iran’s Game and Fisherman Department. Pertemuan ini
berhasil mendeklarasikan lahirnya Conventions on Wetlands of
International Importance, especially as Waterfowl Habitat atau yang lebih
dikenal dengan sebutan Ramsar Convention. Konvensi yang terdiri atas
12 pasal ini ditandatangani di Kota Ramsar, Iran oleh 18 negara peserta
yang hadir pada pertemuan tersebut dan dinyatakan berlaku bada bulan
September 1975 setelah deposit terakhir dilaksanakan oleh pemerintah
yunani.89
Konvensi ini berada dalam daftar perjanjian internasional United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang
mewakili organisasi internasional dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa.
Kedudukan Sekretariat Jenderal Konvensi ini berada di kota Gland, Swiss
dan memiliki kantor cabang di kota Slambridge, Inggris..90
Sejak diadopsi, Konvensi Ramsar ini telah diubah sebanyak dua
kali melalui Paris Protocol pada Desember 1982 serta melalui
Amandemen Regina pada tahun 1987. Protokol Paris diadopsi pada
Konferensi Luar Biasa Para Pihak yang diadakan di markas besar
UNESCO di Paris pada bulan Desember 1982. Protokol ini, mulai berlaku
89 ibid 90
Dugan, P.J, 1987, The World Wetland Resources – Status and Trend, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides, UICN-Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss hlm 6.
51
pada tahun 1986, yang menetapkan sebuah prosedur untuk mengubah
Konvensi dengan menambahkan Pasal 10 bis. Sedangkan Amandemen
Regina menghasilkan amandemen Pasal 6 dan 7 yang diterima pada
Konferensi Luar Biasa Para Pihak yang diadakan di Regina, Kanada,
pada tahun 1987. Hal ini tidak memengaruhi prinsip-prinsip dasar
Konvensi, namun hanya terkait dengan operasinya. Secara singkat,
amandemen tersebut mendefinisikan wewenang konferensi para pihak,
pembentukan Komite Tetap Internasional, dan Sekretariat Permanen serta
anggaran untuk Konvensi tersebut. Amandemen ini sendiri mulai berlaku
pada tanggal 1 Mei 1994.91
Terkait ketentuan untuk mengikatkan diri dalam Konvensi ini diatur
dalam pasal 9 yang menyatakan:
1. This Convention shall remain open for signature indefinitely. 2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized
Agencies or of the International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the International Court of Justice may become a Party to this Convention by: a) signature without reservation as to ratification; b) signature subject to ratification followed by ratification; c) accession.
3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of ratification or accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as “the Depositary”).
Kemudian dalam pasal 10 mengatur bahwa:
1. This Convention shall enter into force four months after seven States have become Parties to this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9.
2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party four months after the day of its signature without
91 Anonim , Op.cit, hlm.19.
52
reservation as to ratification, or its deposit of an instrument of ratification or accession.
2. Tujuan Ramsar Convention 1971
Tujuan dari terbentuknya Konvensi ini adalah untuk mencegah alih
fungsi lahan dan menghindari hilangnya lahan basah baik saat ini maupun
di masa yang akan datang92, mengingat fungsi lahan basah yang sangat
penting sebagai pengendali tata air dan habitat bagi flora dan fauna yang
khas.93
Ramsar Convention 1971 sebagai Konvensi Internasional yang
pertama mengenai lahan basah, ternyata telah mampu menarik perhatian
berbagai pemerintah dan masyarakat internasional khususnya dalam
menangani sumber-sumber alam yang ada pada lahan basah dan hewan
migrasi (migran spesies) yang sangat tergantung pada sumber-sumber
makanan di lahan basah. Hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan
kerusakan serta polusi yang terjadi secara lintas batas terhadap lahan
basah ini. Sehingga menuntut adanya penyelesaian secara internasional
dengan perlunya melibatkan kerjasama antarnegara khususnya dalam
pengelolaan serta pelestarian flora serta fauna yang termasuk dalam
kategori spesies migran.94
Tindakan-tindakan untuk melaksanakan Konvensi telah dilakukan
antara lain dengan membentuk Ramsar Convention`s Database. Dengan
92
Lihat bagian Desiring The Contracting parties Ramsar Convention 1971 93
Lihat bagian Considering The Contracting parties Ramsar Convention 1971 94
Ade Masya Eta, 2014, Wetland International, http://studioriau.com/uk/artikel/lingkungan/wetland-international.html, diakses pada 12 desember 2017.
53
suatu kerjasama antara World Conservation Monitoring Center (WCMC)
dan dengan IWRB telah dikembangkan suatu konsep data dasar lokasi
lahan basah berdasarkan Konvensi Ramsar. Dengan dukungan
pemerintah Swiss dan Inggris proyek ini telah didemonstrasikan dalam
pertemuan keempat para pihak penandatangan Konvensi Ramsar di kota
Montreux , Swiss tahun 1990.95
3. Situs Ramsar
Situs ramsar atau Ramsar Sites, yaitu areal konservasi dan
pemanfaatan lahan basah. Situs Ramsar ini dikenal secara global, dan
mencakup lahan basah pesisir dan darat dari semua jenis di enam wilayah
Ramsar. Situs ramsar pertama di dunia terdapat di Semenanjung Cobourg
di Australia, yang ditetapkan pada tahun 1974. Sedangkan Situs terbesar
adalah Ngiri-Tumba-Maindombe di Republik Demokratik Kongo dan Teluk
Ratu Maud di Kanada, Situs ini masing-masing mencakup lebih dari
60.000 kilometer persegi. Adapun Negara dengan situs terbanyak adalah
Inggris dengan 170 situs. Saat ini terdapat 2.290 Situs Ramsar dengan
total luas lahan basah yang didaftarkan sekitar 225.411.940 hektar yang
tersebar di 169 negara.96
Ketika sebuah negara menyetujui Konvensi Ramsar ini, maka
negara tersebut harus menunjuk setidaknya satu lahan basah sebagai
lahan basah untuk kepentingan internasional. Informasi tentang Situs
Ramsar pertama ini dikirim dengan dokumen aksesi ke UNESCO, tempat
95
ibid 96
Lihat https://www.ramsar.org/sites-countries/ramsar-sites-around-the-world,
diakses pada 28 Desember 2017, Pukul 12:01 WITA.
54
penyimpanan Konvensi.97 Ketentuan penunjukan Situs Ramsar ini diatur
dalam pasal 2 Konvensi ini:
Each contracting party shall designate suitable wetlands within is territory for inclusion in a list of wetlands of international importance, hereinafter referred to as the “list”….the boundaries of each wetland shall be precisely described and also delimated on a map and they incorporate riparian and coasta zones adjacent to wetlands,and islands or bodies of marine water deeper than six metres.. (Masing-masing Pihak harus menunjuk lahan basah yang sesuai di dalam wilayahnya untuk dimasukkan dalam Daftar Lahan Basah yang Penting, yang selanjutnya disebut "Daftar"… Batas-batas setiap lahan basah harus dijelaskan secara tepat. dan juga dibatasi pada peta dan mereka mungkin menggabungkan daerah tepi sungai dan pesisir yang berdekatan dengan lahan basah, dan pulau atau badan air laut lebih dalam dari enam meter saat air surut tergeletak di dalam lahan basah) [...].
Sementara dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan:
wetlands should be selected for the list account of their international significance in terms of ecology, botany,zoology, limnology, or hydrology…(Lahan basah harus dipilih untuk Daftar tersebut karena kepentingan internasional mereka dalam hal ekologi, botani, zoologi, limnologi atau hidrologi.)
Oleh karena itu, setiap lahan basah yang memenuhi setidaknya
satu dari kriteria untuk sebagai lahan basah yang penting secara
Internasional dapat ditunjuk oleh otoritas nasional yang sesuai untuk
ditambahkan ke Daftar Ramsar.
97
Lihat https://www.ramsar.org/sites-countries/designating-ramsar-sites, diakses
pada 27 Desember 2017 Pukul 12:01 WITA.
55
Tabel 2. Kriteria Ramsar untuk Kepentingan Internasional.98
A Keterwakilan langka atau unik, yaitu :
Kriteria 1
Lahan basah tersebut merupakan suatu contoh keterwakilan, langka atau unik dari tipe lahan basah alami atau yang mendekati alami, sesuai dengan karakteristik wilayah biogeografisnya.
B Konservasi keanekaragaman hayati, yaitu:
Kriteria 2
Lahan basah tersebut mendukung spesies rentan,
langka atau hampir langka, atau ekologi komunitas
yang terancam.
Kriteria 3
Lahan basah tersebut mendukung populasi jenis-jenis tumbuhan dan/ atau hewan yang penting bagi pemeliharaan keanekaragaman hayati di wilayah biogeografi yang sesuai,
Kriteria 4
Lahan basah tersebut mendukung jenis-jenis
tumbuhan dan/ atau hewan yang kritis dalam
siklus hidupnya atau merupakan tempat
perlindungan bagi jenis-jenis tersebut saat
melewati masa kritis dalam siklus hidupnya
C Kriteria khusus Waterfowl (Burung Air), yaitu :
Kriteria 5
Lahan basah tersebut secara teratur
mendukung/dihuni oleh 20.000 atau lebih jenis
burung air
Kriteria 6
Lahan basah tersebut secara teratur
mendukung/dihuni oleh individu-individu dari satu
spesies/sub spesies burung air hingga 1% dari
total populasi spesies/sub spesies burung air
tersebut.
D Kriteria khusus ikan, yaitu :
Kriteria 7
Lahan basah tersebut mendukung/dihuni oleh
proporsi yang nyata dari species/sub species/famili
ikan-ikan asli, perkembangan sejarah kehidupan
dan interaksi satu sama lainnya sehingga
menunjukan adanya nilai-nilai atau kontribusi
penting dari lahan basah tersebut terhadap
98 Ramsar Convention Secretariat , Op.cit, hlm 44.
56
keanekaragaman hayati global.
Kriteria 8
Lahan basah tersebut merupakan sumber
makanan yang penting bagi ikan-ikan, tempat
berpijah dan asuhan dan/atau sebagai jalur
migrasi untuk stok ikan yang berada di lahan
basah tersebut atau tempat lain di luar lahan
basah tersebut.
57
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul skripsi penulis “Analisis Yuridis Ramsar
Convention 1971 terhadap Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia”
dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan sebagai bahan
penulisan, maka penulis merencanakan penelitian akan dilaksanakan di
lokasi penelitian sebagai berikut:
1. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Makassar
2. Yayasan Hutan Biru-Blueforest
3. Perpustaakan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
B. Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative research)
yang didukung dengan data primer yang diperoleh melalui metode
wawancara sebagai data penunjang. Penelitian ini menggunakan
beberapa metode pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan
menelaah peraturan perundang-undangan99 yang berkaitan dengan
isu hukum yang diteliti yakni Ramsar Convention 1971 terhadap
perlindungan hutan mangrove di Indonesia.
99
Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, hlm. 96.
58
2. Pendekatan sejarah (historical approach), yaitu dengan pelacakan
sejarah aturan hukum dari waktu ke waktu100 terkait perlindungan
hutan mangrove di Indonesia. Hal ini berguna bagi peneliti untuk
membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang
diteliti.
3. Pendekatan perbandingan (comparative approach), yaitu dengan
mengadakan studi perbandingan hukum.101Menurut Van
Apeldoorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi
ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan
menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang
ada dengan sistem hukum lain.102
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil
wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berwenang
di bidangnya.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan
terhadap bebagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan
objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal, artikel,
dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang dilengkapi dengan bahan nonhukum yang terkait isu
100
Ibid, hlm.166. 101
Ibid, hlm.172. 102 P. Van. Dijk, dalam Ibid, hlm. 173.
59
hukum yang dikaji. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari:
1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Adapun
bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
a. Ramsar Convention 1971 (Conventions on Wetlands of
International Importance, Especially as Waterfowl Habitat);
b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012
Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
2. Bahan hukum sekunder te rdiri dari literatur-literatur yang terkait
dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku,
jurnal, surat kabar, pendapat ahli dan artikel dari internet.
3. Bahan nonhukum meliputi data yang relevan dengan isu hukum
yang diteliti.
60
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis
adalah sebagai berikut :
1. Penelitian Pustaka (Literature Research), teknik mengumpulkan
data ini dilakukam dengan penelitian pustaka, denga cara
mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan
bacaan, baik buku, jurnal, majalah, koran,internet atau karya tulis
lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.
Dari penelitian kepustakaan ini diharapkan diperoleh landasan teori
mengenai kajian dan analisis dari perspektif hukum internasional;
2. Penelitian Lapangan (Field Research), teknik ini dilakukan dengan
cara melakukan interview (wawancara) guna memperoleh informasi
yang diperlukan dan lebih meyakinkan karena dilakukan dengan
cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap
memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang
dibahas dalam skripsi ini.
E. Analisis Data
Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah
dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut
diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat
dipahami dan terarah perihal implementasi Ramsar Convention 1971
terhadap perlindungan hutan mangrove di Indonesia.
61
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Hutan Mangrove menurut Ramsar
Convention 1971
Ramsar Convention 1971 merupakan instrumen hukum
internasional yang lahir atas dasar kepedulian masyarakat internasional
akan pentingnya menjaga lingkungan demi kelangsungan manusia kini
dan dimasa yang akan datang. Sebagai perjanjian internasional yang
berkonsentrasi pada lahan basah dunia, menjadikan Konvensi ini sangat
penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lahan basah
khususnya terkait hutan mangrove di berbagai belahan dunia.
1. Komitmen Utama dalam Ramsar Convention 1971
Ramsar Convention 1971, berupaya untuk mendorong setiap
negara anggota untuk aktif dalam memberikan perlindungan terhadap
ekosistem lahan basah termasuk didalamnya hutan mangrove yang
memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan. Dalam
Konvensi ini sendiri, terdapat empat komitmen utama yang harus
dijalankan oleh setiap negara anggota konvensi, yaitu:
a. Listed Sites
Kewajiban pertama menurut Konvensi ini adalah masing-masing
anggota harus menunjuk lahan basah yang cocok dalam wilayahnya untuk
dimasukkan dalam daftar lahan basah penting Internasional, selanjutnya
62
disebut “List”.103 Penunjukan setidaknya satu lahan basah untuk
dimasukkan dalam list merupakan kewajiban yang harus dilakukan pada
saat penandatanganan Konvensi ini atau ketika menyerahkan instrumen
ratifikasi atau aksesi.104 Dengan kriteria lahan basah yang didaftarkan
harus memiliki nilai penting secara internasional dalam hal ekologi, botani,
zoologi, limnologi atau hidrologi.105
Kemudian pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap anggota harus
menginformasikan sedini mungkin jika terjadi perubahan karakter ekologis
lahan basah di wilayahnya, termasuk di dalamnya perubahan terhadap
lahan basah yang dimasukkan pada “List”, baik sedang dalam proses
perubahan atau ada tanda-tanda berubah sebagai hasil dari
perkembangan teknologi, polusi atau gangguan manusia lainnya.
Informasi tentang perubahan tersebut harus disampaikan sesegera
mungkin pada organisasi atau pemerintah yang bertanggung jawab, lalu
diteruskan kembali pada biro yang telah ditunjuk.
b. Wise Use Wetlands
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dari Konvensi para anggota wajib
merumuskan dan melaksanakan perencanaan yang telah dibuat untuk
mengkampanyekan konservasi lahan basah yang telah masuk dalam
“List”, dan sejauh mungkin melakukan pemanfaatan lahan basah secara
bijaksana di wilayah mereka. Konsep “wise use” berlaku untuk semua
103
Lihat Pasal 2 ayat 1 Ramsar Convention 1971 104
Lihat Pasal 2 ayat 4 Ramsar Convention 1971 105
Lihat Pasal 2 ayat 3 Ramsar Convention 1971
63
lahan basah dan sumber daya air di suatu wilayah dari setiap negara
peserta, tidak hanya pada lokasi yang ditetapkan sebagai lahan basah
untuk kepentingan internasional. Penerapan konsep ini sangat penting
untuk memastikan bahwa lahan basah dapat terus memberikan peran
vitalnya dalam mendukung pemeliharaan keanekaragaman hayati dan
kesejahteraan manusia.
Dalam COP Ke-3 di Regina, Canada pada 1987, diadopsi sebuah
definisi dari wise use of wetlands yaitu:
“The wise use of wetlands is their sustainable utilization for the
benefit of humankind in a way compatible with the maintenance of
the natural properties of the ecosystem”.
Ketentuan wise use wetlands ini berlaku untuk semua lahan basah
dan sistem pendukungnya di dalam wilayah negara anggota, baik lahan
basah yang ditunjuk sebagai Situs Ramsar maupun keseluruhan lahan
basah lainnya. Konsep penggunaan bijaksana ini berupaya untuk
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lahan basah sebagai
bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam menerapkan konsep wise use of wetlands ini, maka pada
COP Ke-empat ditetapkan sebuah panduan terkait implementasi dari
konsep wise use tersebut, yaitu:106
106Lihat Recommendation 4.10: Guidelines for the implementation of the wise use
concept
64
1. Pembentukan kebijakan lahan basah nasional. Kebijakan nasional
ini terkait, (1) tindakan untuk meningkatkan kelembagaan dan
pengaturan organisasi; (2) tindakan untuk menunjuk suatu Undang-
undang dan kebijakan pemerintah; (3) tindakan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap lahan basah
dan nilai-nilainya; (4) tindakan untuk meninjau status, dan
mengidentifikasi prioritas untuk semua lahan basah dalam konteks
nasional dan (5) tindakan untuk mengatasi masalah di lokasi lahan
basah tertentu.
2. Melaksanakan tindakan prioritas di tingkat nasional. Tindakan
prioritas yang dimaksud yaitu: (1) mengidentifikasi masalah yang
membutuhkan perhatian paling mendesak; (2) mengambil tindakan
terhadap satu atau lebih masalah dan (3) mengidentifikasi lokasi
lahan basah yang membutuhkan tindakan paling mendesak.
3. Melaksanakan tindakan prioritas pada lokasi lahan basah tertentu.
Tindakan prioritas yang dimaksud adalah: (1) integrasi dari awal
pertimbangan lingkungan dalam perencanaan proyek yang
mungkin mempengaruhi lahan basah (termasuk penilaian penuh
dampak lingkungan mereka sebelum persetujuan); (2) evaluasi
berkelanjutan selama pelaksanaannya; dan (4) implementasi penuh
tindakan lingkungan yang diperlukan
.
65
c. Reserves and Training
1) Reserves
Pasal 4 ayat 1 menetapkan bahwa setiap anggota wajib
mempromosikan konservasi lahan basah dan burung air dengan
mendirikan cagar alam pada lahan basah, baik mereka termasuk dalam
list atau tidak, dan melakukan pengamanan yang memadai.
Dalam COP Ke-4 di Montreux, Swiss menghasilkan rekomendasi
tentang Establishment of wetland reserves yang mengakui bahwa
pembentukan cagar alam di lahan basah dengan beragam jenis dan
ukurannya memiliki peran dalam mempromosikan pendidikan konservasi
dan kesadaran publik akan pentingnya konservasi lahan basah dan tujuan
Konvensi itu sendiri. Oleh karena itu, melalui rekomendasi ini mendesak
negara peserta Konvensi untuk:107
1. membentuk jaringan nasional cagar alam yang mencakup lahan
basah baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar;
2. membuat kerangka hukum yang memadai, atau meninjau
mekanisme hukum yang ada untuk definisi, pendirian dan
perlindungan yang efektif dari cagar alam lahan basah;
3. mengembangkan program pendidikan konservasi yang terkait
dengan jaringan cadangan lahan basah;
107
Ramsar Convention secretariat, 2004, The Ramsar Convention Manual: a Guide
to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971), 3rd ed. Gland, Switzerland: Ramsar
Convention Secretariat, hlm.43.
66
4. menginventalisir cadangan lahan basah nasional dengan merinci
lokasi dan nilainya; dan
5. mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen terpadu
untuk cadangan lahan basah.
2) Training
Pasal 4 ayat 5 dari Konvensi menyatakan bahwa para anggota
wajib mempromosikan pelatihan personil untuk meningkatkan kompetensi
di bidang penelitian lahan basah, manajemen dan pengamanan.
Personil yang terlatih tersebut, khususnya di bidang manajemen,
pendidikan dan administrasi sangat penting dalam menunjang konservasi
yang efektif serta penggunaan lahan basah yang bijaksana. Jenis-jenis
pelatihan relevansi khusus untuk para profesional yang terlibat dalam
praktik penggunaan bijaksana adalah:108
1. pelatihan manajemen terpadu (menyatukan spesialis dari berbagai
bidang untuk menghasilkan pemahaman dan pendekatan umum);
2. pelatihan tentang pengelolaan lahan basah (termasuk informasi
tentang teknik paling terkini);
3. pelatihan untuk staf lapangan (mencakup pemahaman dasar
konsep penggunaan bijaksana, penegakan hukum, dan kesadaran
publik)
Kegiatan pelatihan ini harus bersifat katalitik, melibatkan organisasi
pemerintah dan non-pemerintah, mentransfer pengetahuan yang
108 Ibid,hlm 43-44.
67
diperoleh, misalnya, dari tingkat daerah ke pelatih potensial di tingkat
lokal. Buku pedoman pelatihan dan materi sumber lainnya harus
dikembangkan dan diperbarui sebagai proses yang berkelanjutan.
d. International Cooperation
Pasal 5 Konvensi Ramsar menyatakan bahwa para anggota akan
saling berkonsultasi tentang pelaksanaan kewajiban yang timbul dari
Konvensi terutama pada lahan basah yang membentang melalui lebih dari
satu negara anggota atau pada sistem air lintas negara. Negara anggota
akan berusaha untuk mengkoordinasikan dan mendukung kebijakan
mengenai konservasi lahan basah, serta flora dan fauna yang ada di
dalamnya, saat ini maupun di masa-masa mendatang.
Untuk membantu para anggota dalam pelaksanaan kewajiban
Konvensi ini, COP ke-7 (Mei 1999) mengadopsi panduan untuk kerja
sama internasional dibawah Konvensi Ramsar (Resolusi VII.19). Panduan
mencakup bidang-bidang berikut:
a) Mengelola lahan basah dan cekungan sungai bersama;
b) Mengelola secara bersama spesies-spesies yang terkait dengan
lahan basah;
c) Ramsar bekerja dalam kemitraan dengan Konvensi dan lembaga
lingkungan internasional / regional;
d) Berbagi pengalaman dan informasi;
e) Bantuan internasional untuk mendukung konservasi dan
pemanfaatan lahan basah secara bijak.
68
2. Resolution 5.1 The Kushiro Statement and the framework for
the Implementation of the Convention
Resolusi 5.1 disepakati pada COP Ke-5 Konvensi yang
dilaksanakan di Kushiro, Jepang pada 1993. Resolusi ini merupakan
ketentuan yang bertujuan untuk menjabarkan isi Konvensi sebagai
kerangka untuk pelaksanaan Konvensi Ramsar. Adapun bebarapa
ketentuan yang disepakati dalam resolusi ini yaitu sebagai berikut:109
a) Konservasi lahan basah
Setiap negara anggota melaksanakan konservasi lahan basah, yang
meliputi:
1) Menunjuk suatu lahan basah untuk ditetapkan kedalam daftar lahan
basah untuk kepentingan internasional;
2) merumuskan dan melaksanakan perencanaan sehingga dapat
mempromosikan konservasi situs-situs yang terdaftar;
3) memberi saran kepada sekretariat tentang setiap perubahan
karakter ekologis dari situs-situs yang terdaftar;
4) mengkompensasi hilangnya sumber lahan basah jika lahan basah
yang terdaftar dihapus atau dibatasi;
5) menggunakan kriteria Ramsar untuk mengidentifikasi lahan basah
yang penting secara internasional;
6) menggunakan datasheet Ramsar dan sistem klasifikasi untuk
mendeskripsikan situs-situs yang terdaftar; untuk
109 Lihat Resolution 5.1 The Kushiro Statement and the framework for the
Implementation of the Convention, hlm 3-4.
69
mempertimbangkan langkah-langkah dan manajemen yang tepat
setelah penunjukan dan, bila perlu, untuk menggunakan Rekaman
Montreux dan [Mekanisme Penasihat Ramsar], untuk merumuskan
dan melaksanakan perencanaan sehingga dapat mempromosikan
penggunaan lahan basah secara bijak;
7) mengadopsi dan menerapkan panduan untuk penerapan konsep
penggunaan yang bijaksana, terutama dalam hal elaborasi dan
implementasi kebijakan lahan basah nasional, dan panduan
tambahan tentang penggunaan yang bijaksana;
8) membuat penilaian dampak lingkungan sebelum transformasi lahan
basah;
9) membangun cagar alam di lahan basah dan melakukan
pengawasan terhadap cagar alam tersebut;
10) meningkatkan populasi unggas air melalui pengelolaan lahan
basah yang sesuai;
11) membuat inventarisasi lahan basah nasional yang akan
mengidentifikasi lokasi utama untuk keanekaragaman hayati lahan
basah; penelitian, manajemen, dan pengawasan.
b) Promosi kerjasama internasional dalam konservasi lahan
basah
1) mempromosikan konservasi lahan basah dengan
menggabungkan kebijakan nasional yang berpandangan jauh
ke depan dengan aksi internasional terkoordinasi;
70
2) berkonsultasi dengan pihak-pihak lainnya tentang pelaksanaan
kewajiban yang timbul dari Konvensi, terutama mengenai lahan
basah dan sistem air bersama dan spesies yang dibagikan;
3) mempromosikan keprihatinan konservasi lahan basah dengan
lembaga bantuan pembangunan;
4) membangun proyek-proyek restorasi lahan basah.
c) Membina komunikasi tentang konservasi lahan basah
1) mendorong penelitian dan pertukaran data;
2) menghasilkan laporan nasional untuk konferensi para pihak;
3) meningkatkan jumlah pihak penandatangan.
d) Mendukung kerja dari Konvensi
1) untuk mengadakan dan menghadiri konferensi para pihak;
2) untuk mengadopsi Protokol Paris dan Amandemen Regina;
3) untuk memberikan kontribusi keuangan pada anggaran
Konvensi dan dana hibah.
3. Resolution VII.21: Enhancing the Conservation and Wise Use
of Intertidal Wetlands
Resolusi ini disepakati pada COP7 Ramsar Convention di San Jose
Costa Rica pada 10-18 Mei 1999. Resolusi ini berfokus pada peningkatan
konservasi dan pemanfaatan secara bijaksana lahan basah intertidal
termasuk didalamnya mangrove, tidal flat, rawa-rawa dan padang lamun
yang memiliki nilai ekonomi,sosial dan lingkungan terutama untuk
71
perikanan, keanekaragaman hayati, perlindungan pantai, rekreasi,
pendidikan, dan dalam kaitannya dengan kualitas air.
Berdasarkan ketentuan dari resolusi ini setiap negara peserta
memilki kewajiban untuk:110
a. mendokumentasikan tingkat kehilangan lahan basah intertidal yang
telah terjadi di masa lalu dan menginventarisir lahan basah
intertidal yang tersisa serta status konservasi mereka;
b. bekerjasama dengan Biro Ramsar, Mitra Organisasi Internasional,
dan kelompok yang relevan untuk menyebarkan informasi tentang
tingkat kehilangan lahan basah intertidal dan dampaknya serta
strategi pengembangan alternatif untuk daerah intertidal yang
tersisa agar dapat membantu mempertahankan karakter
ekologinya;
c. meninjau dan memodifikasi kebijakan yang ada yang berdampak
buruk terhadap lahan basah intertidal, berusaha memperkenalkan
langkah-langkah untuk konservasi jangka panjang dan memberikan
saran tentang keberhasilan atau sebaliknya dari tindakan-tindakan
yang telah dilakukan dalam Laporan Nasional mereka ke Ramsar
COP8;
d. mengidentifikasi dan menetapkan lahan basah intertidal khususnya
tidal flat yang lebih besar dan luas sebagai lahan basah untuk
kepentingan internasional serta memprioritaskan situs-situs yang
110
Lihat Resolution VII.21: Enhancing the conservation and wise use of intertidal wetlands hlm 2.
72
penting bagi penduduk asli dan komunitas lokal, dan mereka yang
memegang spesies lahan basah yang terancam secara global
seperti didorong oleh Resolusi VII.11; dan
e. menangguhkan promosi, pembuatan fasilitas baru, dan perluasan
aktivitas tambak yang tidak lestari dan berbahaya bagi lahan basah
pesisir sampai saat penilaian dampak lingkungan dan sosial dari
kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengidentifikasi langkah-
langkah yang ditujukan untuk membangun sistem budidaya tambak
berkelanjutan yang selaras dengan lingkungan dan masyarakat
setempat.
4. Resolution VIII.11: Guidance for identifying and designating
peatlands, wet grasslands, mangroves and coral reefs as
Wetlands of International Importance
Lahan gambut, mangrove dan terumbu karang diakui oleh Global
Review of Wetland Resources and Priorities for Wetland Inventory dalam
laporan COP7 sebagai salah satu ekosistem lahan basah yang paling
rentan dan terancam akibat semakin meningkatnya laju degradasi dan
hilangnya habitat. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan prioritas yang
mendesak untuk memastikan konservasi dan penggunaan yang
bijaksana.111
111
Lihat bagian introduction Resolution VIII.11: Guidance for identifying and designating peatlands, wet grasslands, mangroves and coral reefs as Wetlands of International Importance, hlm.1.
73
Berdasarkan hal tersebut dalam COP Ke-8 di Kota Valencia
Spanyol pada November 2002 disepakati suatu resolusi tentang panduan
tambahan terkait identifikasi dan penunjukan lahan gambut, padang
rumput basah, hutan mangrove, dan terumbu karang sebagai Wetlands of
International Importance (Situs Ramsar).
Resolusi VIII.11 ini pada pokoknya mengatur tentang identifikasi
dan penunjukan mangrove serta penerapan kriteria Ramsar dalam
menetapkan suatu kawasan mangrove sebagai wetlands international
importance.
a. Identifikasi dan Penunjukan Mangrove
Identifikasi mangrove yang dimaksud meliputi definisi, fungsi dan
faktor penyebab kerusakan mangrove. Dari identifikasi definisi, mangrove
yang dimaksud adalah tanaman berkayu yang toleran garam dengan
adaptasi morfologi, fisiologis, dan reproduktif yang memungkinkan mereka
untuk menjajah habitat litoral. Yang termasuk kedalam lahan basah laut /
pesisir (hutan basah intertidal) dalam sistem klasifikasi Ramsar untuk tipe
lahan basah.
Mangrove menjalankan fungsi yang penting terkait dengan
pengaturan air tawar, penyedia nutrisi, dan berperan dalam pengendalian
pencemaran melalui kemampuannya dalam menyerap polutan. Mangrove
juga berperan dalam menjaga siklus kehidupan dari berbagai macam
hewan seperti ikan,burung dan krustasea. Dari segi ekonomi Mangrove
mangrove merupakan sumber mata pencaharian yang sangat penting,
74
sarana perikanan komersial dan rekreasi, selain itu juga mangrove
menyediakan banyak barang dan jasa baik langsung dan tidak langsung
kepada masyarakat. Adapun faktor yang menyebabkan terdegradasinya
hutan mangrove adalah praktek eksploitasi yang tidak berkelanjutan,
perusakan habitat, perubahan hidrologi serta faktor meningkatnya polusi.
b. Penerapan Kriteria Ramsar pada Mangrove untuk ditetapkan
sebagai Wetlands of International Importance
Dalam menetapkan suatu kawasan mangrove sebagai Wetlands of
International Importance, maka harus memperhatikan beberapa hal,
yaitu:112
1. Prioritas khusus harus diberikan pada mangrove yang membentuk
bagian dari ekosistem yang utuh dan berfungsi secara alami serta
mencakup jenis lahan basah lainnya, seperti terumbu karang,
padang lamun, dataran pasang surut, laguna pantai, dataran
garam, dan/atau kompleks estuari, hal ini penting untuk menjaga
bagian-bagian ekosistem mangrove. Dalam sebagian besar
keadaan, tidak diperbolehkan penetapan hutan mangrove sebagai
situs Ramsar tanpa menyertakan bagian terkait lainnya dari
ekosistem pesisir.
2. Jaringan situs yang ingin didaftarkan memiliki nilai lebih dari
wilayah hutan mangrove yang hanya merupakan bagian kecil yang
dikelola secara individual, karena mangrove tersebut berkontribusi
112
Lihat bagian Applying the Ramsar Criteria to mangroves dalam Ramsar COP8 Resolution VIII.11, hlm 9-10.
75
pada penguatan bentang alam dan bentang laut secara
keseluruhan. Penunjukan area mangrove yang mencakup seluruh
bentang alam dan bentang laut merupakan hal yang berharga
untuk menjaga proses pesisir yang penting. Dan pertimbangan
harus pula diberikan apabila penetapan Situs Ramsar tersebut
merupakan bagian dari kerangka kerja manajemen pengelolaan
zona pesisir.
3. Dalam menentukan batas-batas yang tepat untuk penunjukan
lokasi, haruslah mempertimbangkan beberapa aspek berikut:
a. pencantuman bagian habitat yang kritis, komunitas tertentu,
atau bentang alam yang berfokus pada tindakan konservasi dan
manajemen;
b. ketentuan untuk tindakan konservasi dalam bagian bentang
alam yang didominasi manusia, karena wilayah yang didominasi
manusia yang lebih ramah dapat membantu mengurangi efek
negatif;
c. ketentuan untuk konservasi dan penggunaan yang bijaksana
dari area yang luas dengan akses manusia yang relatif terbatas
d. masuknya seluruh unit bentang alam (kompleks laguna-
estuarin, dataran garam, delta atau mudflat / sistem tidal flat);
e. pemeliharaan ketahanan hidrografi dan kualitas air, termasuk
dalam konteks pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
76
f. ketentuan terkait dampak kenaikan permukaan laut dan
perubahan iklim yang disebabkan perbuatan manusia yang
mungkin menyebabkan hilangnya habitat dan proses genetik;
dan
g. pertimbangan kemungkinan perpindahan mangrove kearah
daratan sebagai respon terhadap kenaikan permukaan laut.
4. Dalam menerapkan kriteria 1 Ramsar pada mangrove, perhatian
khusus harus diberikan pada proses pendataan wilayah yang
berada dalam kondisi asli atau memiliki kepentingan biogeografi
atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kebutuhan
perlindungan;
5. Konservasi mangrove harus dibagi berdasarkan unit penggunaan
yang paling tepat seperti untuk perlindungan, restorasi,
pemahaman dan kenikmatan warisan alam, dan konservasi yang
menekankan pada pemanfaatan berkelanjutan. Ukuran minimum
sebuah situs adalah yang memiliki keragaman jenis habitat
terbesar, termasuk habitat yang mendukung spesies rentan, langka
atau hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam.
"Kealamian" harus dipertimbangkan ketika memilih situs kandidat,
yaitu, sejauh mana suatu area telah terlindungi atau belum
mengalami perubahan yang disebabkan manusia. Proses ekologi,
demografi dan genetik juga harus dipertimbangkan karena hal ini
77
dapat menjaga ketahanan struktural dan fungsional serta kapasitas
yang dapat mempertahankan diri dari lokasi yang ditentukan.
6. Ketika mendefinisikan batas situs, harus dipertimbangkan bahwa
semakin kompleks suatu sistem maka situs yang besar tersebut
haruslah efektif dalam menjalankan tujuan konservasi. Namun,
definisi batas akan menjadi lebih sulit apabila unit tersebut semakin
kecil. Jika ragu, situs harus dibuat lebih besar daripada yang lebih
kecil.
7. Untuk mangrove, perhatian khusus harus diberikan pada
penerapan kriteria 7 dan 8 karena sistem mangrove sangat penting
sebagai tempat pemeliharaan dan pengasuhan untuk ikan dan
kerang. Dan penerapan kriteria 4 sebagai pengakuan atas fakta
bahwa karena ekologi yang kompleks, geomorfologi dan struktur
fisik tersebut mangrove dapat bertindak sebagai tempat
perlindungan dan berperan penting bagi kelangsungan hidup dari
banyak spesies yang bermigrasi mapun yang tidak bermigrasi.
Penentuan daerah-daerah tersebut harus mempertimbangkan
bahwa habitat yang berbeda dari kompleks pesisir mangrove,
padang lamun, dan terumbu karang memiliki nilai penting dalam
siklus hidup dari berbagai spesies yang berbeda.
78
5. Resolution VIII.32: Conservation, Integrated Management, and
Sustainable Use of Mangrove Ecosystems and their Resources
Pada November 2002 COP Ke-8 Ramsar Convention dilaksanakan
di Kota Valencia Spanyol, dimana dalam pertemuan ini disepakati suatu
resolusi VIII.32 tentang konservasi, pengelolaan terpadu dan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem mangrove dan sumber dayanya.
Resolusi VIII.32 ini melahirkan beberapa ketentuan yang ditujukan
bagi setiap negara anggota dan juga pihak terkait lainnya, dalam
melaksanakan konservasi, pengelolaan terpadu dan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem mangrove dan sumber dayanya. Ketentuan
tersebut antara lain:113
a) Meminta negara anggota untuk mengakaji ulang ekosistem
mangrove di wilayahnya dan bersedia untuk mengubah kebijakan
dan strategi nasional mereka yang dapat membahayakan ekosistem
ini, dan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi dan
mengembalikan nilai dan fungsinya bagi populasi manusia,
mengenali haknya, penggunaan adat istiadat, pemeliharaan
keanekaragaman hayati, dan bekerjasama di tingkat internasional
untuk menyetujui strategi regional dan global terhadap perlindungan
mangrove;
113 Lihat Resolution VIII.32: Conservation, integrated management, and
sustainable use of mangrove ecosystems and their resources
79
b) Juga meminta negara anggota untuk mengkampanyekan konservasi
ekosistem mangrove di wilayah mereka, pengelolaan terpadu dan
penggunaan yang berkelanjutan dalam konteks kerangka kebijakan
dan peraturan nasional dan agar sesuai dengan penilaian lingkungan
dan strategi dari kegiatan yang dapat mempengaruhi, baik secara
langsung atau tidak langsung struktur dan fungsi ekosistem
mangrove;
c) Mendesak negara anggota untuk memperbaharui informasi
mengenai tutupan ekosistem mangrove, status konservasinya,
bentuk dan tingkat penggunaannya kemudian memberikan informasi
tersebut ke Biro Ramsar dan (Convention of Scientific and Technical
Review Panel / STRP) untuk membantu tugas mereka seperti yang
disebut dalam Resolusi VIII.8 tentang status dan kecenderungan di
lahan basah;
d) Juga mendesak negara angota yang memiliki ekosistem mangrove di
dalam wilayahnya untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan
konservasi, pengelolaan terpadu dan penggunaan berkelanjutan,
terutama apabila melibatkan partisipasi penuh masyarakat lokal dan
masyarakat adat;
e) Meminta Biro Ramsar dan STRP sebagai badan resmi dan para
pihak untuk berkontribusi dalam menginisiasi pertukaran teknologi
ramah lingkungan sebagai upaya pengelolaan ekosistem mangrove
secara lestari dan menyediakannya pagi para penggunanya.
80
f) Juga meminta negara anggota yang memiliki ekosistem mangrove di
dalam wilayahnya termasuk wilayah-wilayah tanggungannya, sesuai
dengan kapasitas dan peraturan nasional mereka, agar menunjuk
ekosistem mangrove yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan
kedalam daftar lahan basah untuk kepentingan internasional.
Sehingga menciptakan sebuah jaringan nasional dan internasional
yang koheren dari situs Ramsar yang ditunjuk sebagaimana
disyaratkan dalam kerangka strategis dan visi untuk daftar lahan
basah yang penting secara Internasional (Resolusi VII.11), dan juga
memperluas situs ramsar yang sangat penting bagi penduduk lokal
dan masyarakat adat dalam hal keberadaan dan nilai-nilai adat
mereka;
g) Juga meminta semua pihak terkait untuk menyadari pentingnya
ekosistem mangrove bagi burung migrasi maupun nonmigrasi, dan
menunjuk suatu wilayah sebagai Situs Ramsar yang memenuhi
syarat berdasarkan kriteria 4, 5, dan 6 dalam kerangka strategis
yang disahkan melalui Resolusi VII.11. Sehingga dapat berkontribusi
pada pembentukan kerjasama jaringan skala besar dari Situs
Ramsar sesuai dengan rencana kerja gabungan Konvensi Ramsar,
Convention on Migratory Species, dan African-Eurasian Migratory
Waterbird Agreement (AEWA) sebagaimana disahkan melalui
Resolusi VIII.5 dan Konvensi lainnya atau perjanjian terkait ;
81
h) Mendorong semua pihak terkait agar memeperhitungkan situs
Ramsar yang berkaitan dengan ekosistem mangrove dalam Rencana
pengelolaan, menerapkan New Guidelines for management planning
for Ramsar sites and other wetlands dan panduan lainnya yang
diadopsi oleh pertemuan ini (Resolusi VIII.1, VIII.4, dan VIII.14),
faktor ekologi dan sosio-ekonomi yang terjadi di daerah aliran sungai
dan zona lindung dimana mereka terkait, dan memastikan bahwa
perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan tidak berdampak
buruk pada ekosistem mangrove, seperti melalui pengenalan
polutan, modifikasi aliran air, masuknya sedimen dan spesies
eksotis;
i) Juga mendorong semua pihak terkait untuk mengenali sepenuhnya
peran ekosistem mangrove dalam mengurangi perubahan iklim dan
kenaikan permukaan laut terutama di daerah dataran rendah dan
pulau kecil negara-negara berkembang, dan merencanakan
pengelolaan termasuk tindakan adaptasi yang diperlukan untuk
memastikan bahwa ekosistem mangrove dapat merespon dampak
yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kenaikan permukaan air
laut;
j) Mendesak semua pihak terkait untuk mengidentifikasi faktor-faktor
yang dapat menurunkan kualitas ekosistem mangrove yang berada
diwilayahnya dan berupaya mengembalikan ekosistem tersebut.
Dengan menggunakan panduan mengenai masalah ini yang diadopsi
82
melalui pertemuan ini (Resolusi VIII.16), sehingga mereka dapat
menyampaikan jangkauan nilai dan fungsinya; dan
k) Meminta Biro Ramsar untuk melakukan semua upaya yang mungkin
untuk mendapatkan sumber keuangan dan memajukan kerja sama
teknis untuk mengenalkan konservasi, pengelolaan terpadu, dan
pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan serta
sumber daya yang dimilikinya melalui kemitraan dan kesepakatan
yang ada dengan organisasi internasional dan regional.
B. Implementasi Ramsar Convention 1971 terhadap Perlindungan
Hutan Mangrove di Indonesia
Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat komitmen utama
yang harus dijalankan oleh setiap anggota dari Ramsar Convention
sebagai wujud tanggung jawab dalam perlindungan lahan basah termasuk
hutan mangrove yang menjadi objek kajian utama dalam penulisan ini.
Berikut uraian terkait implementasi Ramsar Convention 1971 terhadap
perlindungan hutan mangrove di Indonesia.
1. Praktik Implementasi Ramsar Convention 1971 Terhadap
Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia
a. Implementasi dalam Penetapan Situs Ramsar Indonesia
Kewajiban pertama dari setiap negara yang mengikatkan diri dalam
Ramsar Convention 1971 adalah menetapkan lahan basah yang berada
diwilayah negaranya sebagai lahan basah untuk kepentingan internasional
83
(Situs Ramsar). Indonesia sendiri hingga tahun 2017 telah memiliki tujuh
Situs Ramsar dengan luas 1,372,976 ha.
Tabel 3. Situs Ramsar Indonesia
Site Date of
designation
Region,
province, state Area Coordinates
Berbak National
Park 19/11/1991 Jambi Province,
Sumatra
162,700
ha
01°24'S
104°16'E
Danau Sentarum
Wildlife reserve 30/08/1994
West
Kalimantan
80,000
ha
00°51'N
112°06'E
Wasur National
Park 16/03/2006
Merauke
Regency
413,810
ha
08°38'S
140°23'E
Sembilang
National Park 03/06/2011
South Sumatra
Province
202,896
ha
01°57'S
104°36'E
Rawa Aopa
Watumohai
National Park
06/03/2011
Province of
South East
Sulawesi
105,194
ha
04°28'S
121°59'E
Pulau Rambut
Wildlife Reserve 11/11/2011
DKI Jakarta
Province 90 ha
05°58'S
106°42'E
Tanjung Puting
National Park 12/11/2013
Central
Kalimantan
408,286
ha
03°03'S
112°00'E
Dari ketujuh situs Ramsar yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, terdapat
beberapa situs yang memiliki hutan mangrove didalamnya, yaitu:
1) Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Sulawesi Tenggara)
Taman Nasional Rawa Aopo Watumohai ditetapkan sebagai Situs
Ramsar pada 6 Maret 2011 dengan luas 105.194 ha yang terletak di
Sulawesi Tenggara. Lahan basah di taman nasional ini terdiri atas
ekosistem hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan rawa air tawar. Aneka
satwa yang hidup di kawasan pelestarian alam ini di antaranya burung
kacamata Sulawesi (Zosterops consobrinorum), maleo (Macrocephalon
84
maleo), dan berbagai satwa langka lainnya. Adapun luas Hutan mangrove
yang berada dalam kawasan ini adalah sekitar 6.000 ha.114
Salah satu kebijakan konservasi yang telah ditetapkan oleh
pengelola TNRAW adalah mengoptimalkan potensi kawasan dalam
rangka mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan
menjamin keberadaan keanekaragaman hayati melalui peningkatan
pengelolaan jenis. Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai telah
menyusun rencana pengelolaan Taman Nasional jangka menengah
(RPJM TNRAW) antara lain: (1) pengembangan kawasan konservasi dan
ekosistem esensial dan (2) pengembangan konservasi spesies dan
genetik.115
2) Suaka Margasatwa Pulau Rambut (DKI Jakarta)
Suaka Margasatwa Pulau Rambut ditetapkan Situs Ramsar
Keenam yang dimiliki oleh Indonesia pada tanggal pada 11 November
2011 dengan luas wilayah 90 ha.116 Sebagai salah satu rantai penting
lahan basah di sepanjang Jalur Terbang Asia Timur-Australasia, situs ini
merupakan tempat transit penting bagi burung air terutama dari oktober
hingga desember yang bermigrasi dari belahan bumi utara ke Australia.
Situs Ramsar ini memiliki 15 spesies mangrove yang membentuk
114
Rini Purwanti, 2011, Nilai Manfaat Hutan Mangrove Taman Nasioanl Rawa AOPA Watumohai: Balai Penelitian Kehutanan Makassar, hlm 22.
115Kangkuso Analuddin dkk, 2016, Struktur Hutan Mangrove Sebagai Habitat
Hewan Endemik Anoa Dataran Rendah (Bubalus Sp.) Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Jurnal Biowallacea, Vol. 3 (2), Hal : 384-395, Oktober, 2016, hlm 385
116 Ramsar, 2012, Indonesias Newest Ramsar Site,
https://www.ramsar.org/news/indonesias-newest-ramsar-site, diakses pada 13 Februari 2018
85
komunitas kompleks dan menyediakan habitat bagi banyak burung air,
termasuk Little Cormorant (Phalacrocorax niger), Glossy Ibis (Plegadis
falcinellus), dan ardeidae seperti Night Heron (Nycticorax nycticorax).117
3) Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah118
Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah merupakan
Situs Ramsar terbaru yang dimiliki oleh Indonesia. Taman Nasional ini
ditetapkan sebagai Situs Ramsar pada 12 November 2013 dengan total
luas wilayah 408.286 ha. Taman ini adalah salah satu kawasan
konservasi terpenting di Kalimantan Tengah, berfungsi sebagai tempat
penampungan air dan merupakan salah satu habitat terbesar yang tersisa
dari orangutan Kalimantan Pongo pygmaeus yang terancam punah. Situs
ini terdiri dari tujuh jenis rawa, termasuk hutan rawa gambut, hutan hujan
tropis dataran rendah, hutan rawa air tawar dan juga hutan mangrove dan
hutan pantai. Ini mendukung sejumlah besar spesies endemik flora dan
fauna yang beradaptasi dengan lingkungan rawa gambut yang dominan
asam.
b. Implementasi Wise Use Wetlands dalam Perlindungan Hutan
Mangrove di Indonesia
Penerapan wise use wetlands sebagai upaya perlindungan lahan
basah khususnya bagi hutan mangrove sangat berkaitan erat dengan
117
ibid 118
Marina Monzeglio, 2014, Pemerintah Indonesia Mengukuhkan TN Tanjung Putting di Kalimantan Tengah sebagai Situs Ramsar, https://indonesia.wetlands.org/id/news/pemerintah-indonesia-mengukuhkan-tn-tanjung-puting-di-kalimantan-tengah-sebagai-situs-ramsar/, diakses pada 15 Februari 2018
86
tersedianya peraturan-peraturan serta kelembagaan yang efektif dalam
mewujudkan penggunaan secara bijaksana dari hutan mangrove yang
ada. Oleh karena itu, Indonesia sendiri telah memiliki beberapa peraturan
perundang-undangan serta lembaga-lembaga terkait dalam upaya
perlindungan hutan mangrove di Indonesia, sebagai bentuk penerapan
wise use wetlands.
1) Peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hutan
Mangrove Indoesia
a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari,
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.119
Yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan
dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional,
mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi,
fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan,
sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, meningkatkan
kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan
sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta
ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.120
119
Lihat Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 120
Lihat Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
87
Dalam pasal 13 UU/41/1999 tentang Kehutanan juga menjelaskan
terkait inventarisasi hutan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan
memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan
alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi ini
dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora
dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di
dalam dan di sekitar hutan meliputi inventarisasi hutan tingkat nasional,
tingkat wilayah, tingkat daerah aliran sungai, dan tingkat unit pengelolaan.
Kemudian dalam rangka pengelolaan hutan, UU ini mengatur
bahwa pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan
dan konservasi alam. Sementara itu, dalam penjelasan pasal 41 UU
Kehutanan ini sendiri menegaskan bahwa rehabilitasi hutan bakau dan
hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana pada
hutan lainnya. Artinya pengelolaan kawasan hutan mangrove juga harus
menjadi fokus dalam hal menjaga kawasan hutan di Indonesia.
Serangkaian aturan dalam UU Kehutanan tersebut tentunya sangat
bersinergi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ramsar Convention,
mulai dari upaya konservasi, perencanaan, pengelolaan dan inventarisasi
dari setiap lahan basah termasuk didalamnya hutan mangrove.
88
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Mangrove merupakan bagian penting dari sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil yang tentunya perlu mendapatkan perlindungan dan
pelestarian. Dalam pasal 1 angka 19 menyatakan bahawa konservasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya pelindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta
ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud dalam UU ini adalah suatu pengoordinasian perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu
pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu dalam UU ini juga mewajibkan Pemerintah Pusat dan
Pemda untuk memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan
kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional melalui pemanfaatan
pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-
pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini
mengindikasikan bahwa selain upaya konservasi, UU ini juga
89
mengamanatkan pemanfaatan secara lestari khususnya bagi masyarakat
lokal.121
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Implementasi Ramsar Convention dalam Undang-undang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) sendiri dapat
dilihat asas, ruang lingkup serta tujuannya. Dimana dalam UUPPLH
memiliki asas122 kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, manfaat,
kehatihatian, keadilan, partisipatif dan kearifan lokal serta ruang lingkup
yang meliputi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini tentu sejalan
dengan misi yang dicapai dalam Ramsar Convention yaitu perlindungan
dan penggunaan secara bijaksana dan berkelanjutan dari setiap lahan
basah termasuk didalamnya kawasan hutan mangrove.
Selain itu, tujuan dari dari UUPLH sendiri sangat berkorelasi
dengan perlindungan hutan mangrove sebagai bagian penting lahan
basah dunia, yaitu:123
1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
121
Lihat Pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
122 Lihat Pasal 2 Undang-undang No.32 tahun 2009 Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup 123
Lihat Pasal 3 Undang-undang No.32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
90
3) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 4) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan
hidup; 5) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 6) Mengantisipasi isu lingkungan global.
d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
Undang-undang 23 tahun 2014 ini merupakan peraturan pengganti
UU Pemerintah Daerah yang lama yakni UU 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Lahirnya UU Pemda yang baru ini membawa
pengaruh besar terkait kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah
provinsi dengan pemerintah kabuten/kota.
Kemudian dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyatakan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,
serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Daerah Provinsi. Sementara kewenangan pemerintah kab/kota hanya
berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya (Tahura). Implikasi
tersebut tentunya juga berpengaruh terkait kewenangan pengelolaan
hutan mangrove yang sebelumnya menjadi kewenangan dari pemerintah
kabupaten/kota menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi.
e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan
Penyelenggaraan perlindungan hutan sebagaimana yang diatur
dalam PP ini bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan
91
dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi
produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Dengan prinsip mencegah
dan membatasi kerusakan hutan serta mempertahankan dan menjaga
hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan dan
hasil hutan.
f) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Peraturan pemerintah tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan ini
dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menjalankan
kewajibannya selaku bagian dari Konvensi Ramsar yang berfokus pada
upaya perlindungan dan penggunaan yang bijaksana setiap lahan basah
yang ada khususnya hutan mangrove yang memiliki peran sangat vital.
Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi hutan dan lahan adalah
upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi
hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya
dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sementara
itu reklamasi hutan merupakan usaha untuk memperbaiki atau
memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat
berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Melalui peraturan
ini, diharapkan mampu menjembatani upaya pemulihan hutan yang
mengalami kerusakan serta meningkatkan peran hutan dalam menyangga
kehidupan.
92
g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991
Tentang Pengesahan Convention On Wetlands Of
International Importance Especially As Waterfowl Habitat
Keppres No.48 tahun 1991 ini merupakan dasar pemberlakuan
Ramsar Convention 1971 di Indonesia. Melalui Ratifikasi ini maka,
Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan segala
ketentuan dari Konvensi ini. Adapun dasar pertimbangan Indonesia dalam
mengikatkan dalam Konvensi ini adalah:
1. bahwa di Ramsar, Iran, pada tanggal 2 Pebruari 1971 telah diterima
Convention on Wetlands of International Importance especcially as
Waterfowl Habitat sebagai hasil Konferensi United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
mengenai lahan basah dipandang dari kepentingan internasional
khususnya sebagai habitat burung air;
2. bahwa Konvensi tersebut bertujuan melestarikan lahan basah
berikut flora dan faunanya yang pelaksanaannya memerlukan
keterpaduan antar kebijaksanaan internasional.
h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012
Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ekosistem
mangrove tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dimana
dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem
93
mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan
wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan DAS diperlukan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan
lembaga. Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua
upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses
terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem
mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem
Mangrove (SNPEM) ini maka diharapkan pengelolaan ekosistem
mangrove menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan
nasional, seperti pada pasal 2 ayat (1) yaitu SNPEM bertujuan untuk
mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove
yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan
peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat
ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan
masyarakat.
i) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 Tentang
Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan
proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang
telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.124
124
Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
94
Rehabilitasi wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil. Apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang
melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi. Rehabilitasi ini
sendiri meliputi terumbu karang, mangrove, padang lamun,estuari, laguna
dan lain-lain.
Dalam Perpres ini kegiatan rehabilitasi dilakukan melalui tiga
tahapan. Pertama perencanaan yakni dengan melakukan kegiatan
identifikasi penyebab kerusakan, identifikasi tingkat kerusakan dan
penyusunan rencana rehabilitasi. Kemudian tahapan pelaksanaan dengan
melakukan pengayaan sumber daya hayati, perbaikan habitat,
perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara
alami, dan ramah lingkungan. Sedangkan pada tahapan pemeliharaan
dilakukan dengan cara menjaga dan mempertahankan komponen biotik
ekosistem atau populasi, menjaga keserasian siklus alamiah komponen
abiotik, menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan fisik,
dan/atau mempertahankan dan menjaga kondisi ekosistem atau populasi
yang telah direhabilitasi dari pengaruh alam atau kegiatan manusia.
Perpres ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan mangrove
sebagai objek rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan
regulasi khususnya bagi kawasan mangrove yang telah mengalami
95
kerusakan. Hal ini tentu sangat sejalan dengan tujuan yang dicapai oleh
Konvensi Ramsar yakni mengkampanyekan dan melaksanakan
konservasi ekosistem lahan basah termasuk mangrove sehingga tercapai
pengelolaan terpadu dan penggunaan yang berkelanjutan.
j) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia selaku ketua Pengarah tim koordinasi nasional
pengelolaan ekosistem mangrove Nomor 47 tahun 2017 tentang
kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja pengelolaan
ekosistem mangrove nasional.
Pemerintah menegaskan pentingnya pengelolaan ekosistem
mangrove melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian (Permenko) No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi,
Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional
(Stranas Mangrove).
Permenko ini mengatur berbagai sasaran, strategi, program dan
kegiatan pada empat nilai penting pengelolaan ekosistem mangrove yaitu
ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan dan perundang-undangan.
Permenko ditujukan sebagai pedoman dan acuan bagi pemerintah,
pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dan para pihak lain
dalam mengelola ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah
masing-masing.
96
2) Pihak-Pihak Terkait Perlindungan Hutan Mangrove Indonesia
a. Pihak Pemerintah
1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kewenangan KLHK dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan
mangrove didasarkan pada statusnya sebagai hutan. Dimana dalam
Pasal 1 ayat 2 UU kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Kemudian dalam Pasal 10 ayat 2 Pengurusan hutan meliputi
kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan,
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan
kehutanan,dan pengawasan. Hal ini juga didukung melalui Pepres nomor
16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yang menyatakan bahwa KLHK mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Yaitu
dengan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, pelaksanaan,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pelaksana
bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup
secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya.125
125
Lihat Pasal 2 Perpres Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
97
Dalam menjalankan fungsinya dalam hal pengelolaan, KLHK
membentuk Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM) yang merupakan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang berada di
bawah Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial.
Balai Pengelolaan Hutan Mangrove dibentuk berdasarkan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor:P.04/Menhut-II/2007. BPHM mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan
kelembagaan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi
pengelolaan hutan mangrove. Sedangkan fungsinya adalah sebagai
berikut :
1) Penyusunan rencana dan program rehabilitasi, perlindungan,
pengawetan dan pemanfaatan lestari hutan mangrove;
2) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, koleksi, sortasi, pengelolaan
informasi sumberdaya hutan mangrove;
3) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan mangrove;
4) Pengembangan kelembagaan yang meliputi model, sumberdaya
manusia, jejaring kerja dan penyebarluasan informasi
5) Pelaksanaan urusan tata usaha Balai.
2. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan atas
mangrove dalam mengelola hutan/ekosistem hutan mangrove
berdasarkan kawasannya atau ekosistemnya yaitu wilayah pesisir.
Wilayah Pesisir sendiri adalah daerah peralihan antara ekosistem darat
98
dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dimana
diketahui bahwa ekosistem mangrove berada pada wilayah ini. Sehingga
hal inilah yang mendasari KKP memiliki wewenang dalam pengelolaan
hutan mangrove sebagai bagian dari sumberdaya pesisir.
Dalam menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan ruang laut, konservasi
keanekaragaman hayati serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
KKP membentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.126 Pada
tahun 2016 terdapat beberapa program di Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut yang secara langsung menyasar masyarakat
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, melestarikan
lingkungan dan sumber daya alam laut dan pesisir serta peningkatan
kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim yang secara umum
dengan hasil output yang sangat memuaskan.127
Khusus dibidang pengelolaan mangrove, Ditjen PRL juga
melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir dengan penanaman
Mangrove 496.930 Batang. Serta membangun pusat restorasi dan
pembelajaran mangrove dan dua lokasi traking mangrove yang berlokasi
di Kab. Pengandaran dan Kab. Sinjai.128
126
Lihat pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan
127Brahmantya Satyamurti Poerwadi, 2017, Siaran Pers Nomor : SP. /PRL/I/2017
Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Upaya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam Memacu Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, http://kkp.go.id/djprl/artikel/890-refleksi-2016-dan-outlook-2017-upaya-direktorat-jenderal-pengelolaan-ruang-laut-dalam-memacu-pembangunan-sektor-kelautan-dan-perikanan, diakses pada 20 Maret 2018
128 ibid
99
3. Pemerintah Daerah
Mengingat kebanyakan hutan mangrove berada didaerah-daerah,
maka pihak yang tidak kalah penting dalam pengelolaan hutan mangrove
tentunya adalah Pemerintah Daerah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa
lahirnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa
pengaruh yang besar terkait pengelolaan hutan termasuk hutan mangrove
yang semula merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota
menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.
Dalam hal perizinan di sektor kehutanan, provinsi mempunyai dua
kategori kewenangan perizinan. Pertama, izin pemanfaatan hutan yang
wataknya tidak eksploitatif sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan
terhadap perubahan tutupan maupun bentangan alam dalam kawasan
hutan. Termasuk dalam kategori ini adalah Izin Usaha Pemanfaatan
Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon tetap
merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan Izin pemungutan hasil
hutan bukan kayu (IPHHBK). Kedua, izin pemanfaatan hutan yang
implikasi penggunaannya akan mempengaruhi tutupan hutan. Termasuk
dalam kategori ini adalah Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada kawasan Hutan Produksi Konversi dan
kawasan hutan dengan Izin Pinjam Pakai.
Secara khusus kewenangan pada tingkat implementasi di sektor
kehutanan berkaitan erat dengan kewenangan terkait dengan Kesatuan
100
Pengelolaan Hutan (KPH). Kewenangan yang sebelumnya berada di
bawah Kabupaten/Kota maupun Provinsi saat ini semuanya ditarik ke
Provinsi. Hal ini mempunyai implikasi bahwa provinsi yang akan
menjalankan fungsi-fungsi KPH yakni merancang tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan
perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan konteks yurisdiksi
provinsi.
4. Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah
(KNLB)129
Komite ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.
226/Kpts-VI/94 tanggal 9 Mei 1994. Komite ini merupakan suatu komite
yang bersifat adhoc yang beranggotakan instansi-instansi dari
Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Kementerian Lingkungan
Hidup, BPN, Departemen Perhubungan, LIPI, TNI, Departemen Dalam
Negeri, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen
Pertambangan dan Energi, Bakosurtanal, dan Wetlands International-
Indonesia Programme.
Tugas dari KNLB yang terbentuk pada tahun 1994 tersebut
diantaranya :
1) Merumuskan kebijaksanaan dan langkah-langkah penanganan
masalah pemanfaatan sumberdaya alam dan ekosistem-ekosistem
129
Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Op.cit hlm 49-50.
101
lahan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2) Menyusun strategi nasional pengelolaan sumberdaya alam dan
ekosistem-ekosistem lahan basah secara terpadu melalui upaya
pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan ekosistem-
ekosistem lahan basah secara serasi, selaras, dan seimbang;
3) Mengembangkan dan menetapkan kriteria pengelolaan
sumberdaya alam dan ekosistem-ekosistem lahan basah
berdasarkan strategi nasional tersebut;
4) Mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan
sumberdaya alam dan ekosistem-ekosistem lahan basah beserta
prosedur pengendaliannya;
5) Meneliti masalah yang timbul dalam pemanfaatan sumberdaya
alam dan ekosistem-ekosistem lahan basah di daerah-daerah, dan
memberikan pengarahan serta saran pemecahannya kepada
pemerintah daerah.
Kemudian menindaklanjuti keputusan Menteri Kehutanan tentang
pembentukan komite nasional pengelolaan ekosistem lahan basah, maka
dikeluarkan pula Keputusan Direktur Jenderal PHPA selaku Ketua I
Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, Nomor
105/Kpts/DJ-VI/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Tim Pelaksana
Kesekretariatan dan Konsultan Teknis Komite Nasional Pengelolaan
Ekosistem Lahan Basah.
102
Saat ini baik KNLB maupun tim pelaksana kesekretariatannya tidak
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kendala tersebut terjadi antara
lain karena nama-nama yang tercantum dalam tim pelaksana sudah tidak
berada pada posisi sebagai pengelola lahan basah atau pada institusinya
dan karena terbentuknya institusi-institusi baru (seperti Departemen
Kelautan dan Perikanan) yang belum terakomodir dalam komite tersebut,
padahal DKP merupakan salah satu pemangku kepentingan utama di
dalam pengelolaan lahan basah di Indonesia.
e) Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM)
maka dibentuklah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem
Mangrove yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional.130 Adapun
susunan keanggotaan Tim Koordinasi Nasional terdiri atas dua bagian
yaitu:
1) Pengarah
Tim pengarah ini bertugas untuk memberikan arahan dalam
penyusunan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja
pengelolaan mangrove serta menetapkan kebijakan, strategi, program,
dan indikator kinerja pengelolaan mangrove. Tim pengarah ini diketuai
oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota yang
terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan
130
Lihat Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
103
Hidup, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional;
2) Pelaksana
Sementara itu, tim pelaksana memiliki tugas dalam menyusun
kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove
serta mengoordinasikan pelaksanaan SNPEM yang menyangkut
perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan,
pelaporan dan sosialisasi; dan mengoordinasikan penyiapan dukungan
pembiayaan/anggaran untuk pelaksanaan SNPEM.
Adapun susunan tim dari tim pelaksana ini, terdiri atas ketua dari
Menteri Kehutanan, Menteri KKP selaku ketua Alternate, Sekretaris dari
Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial,
Kementerian Kehutanan, dan Wakil Sekretaris Direktur Jenderal Kelautan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
serta jajaran anggota. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi Nasional, ketua pelaksana membentuk Kelompok Kerja
Mangrove Tingkat Nasional (KKMN).
Dalam melaksanakan SNPEM di provinsi maupun
kabupaten/kota,maka Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan strategi
pengelolaan ekosistem mangrove tingkat provinsi dan kabupaten/kota
serta membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem
Mangrove Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk mendukung
pelaksanaan tugas tim koordinasi strategi pengelolaan ekosistem
104
mangrove tingkat provinsi dan kabupeten/kota, maka ketua tim koordinasi
strategi pengelolaan ekosistem mangrove provinsi dan kabupeten/kota
membentuk kelompok kerja mangrove tingkat provinsi serta
kabupeten/kota.
Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Tingkat Nasional, Tim
Koordinasi Tingkat Provinsi, dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota
bersifat koordinatif dan konsultatif. Sementara dalam hal pendanaan yang
diperlukan untuk melaksanakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem
Mangrove dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Gambar 5.Kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove berdasarkan Perpres 73 tahun 2012.
105
b. Non Governmental Organization (NGO)
Perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove tidak hanya
menjadi tanggung jawab pihak pemerintah semata. Melainkan pula
membutuhkan peran berbagai pihak dalam mendukung upaya tersebut.
Salah satunya adalah peran lembaga non pemerintahan/ Non
Governmental Organization (NGO). Berikut adalah dua NGO yang banyak
bergerak dibidang perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove di
Indonesia.
1. Blue Forests
Blue Forests merupakan salah satu organisasi nirlaba yan semula
bernama MAP (Mangrove Action Project) yang merupakan afiliasi dari
MAP di Florida, Amerika Serikat. Blue Forests ini pada awalnya hanya
berfokus pada upaya restorasi dan rehabilitasi mangrove di Indonesia.
Namun, kemudian berkembang bukan hanya pada kawasan mangrove
semata, melainkan pula pada alur sungai yang tentunya berdampak pada
mangrove. Tidak hanya itu, NGO ini juga senantiasa berupaya untuk
mendorong resialiasi dari masyarakat khususnya masyarakat pesisir
dengan prinsip global to local and local to global.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Blue Forests,
Yusran Nurdin Massa, menyatakan bahwa terdapat 4 program utama
yang diajalankan Blue Forests di Indonesia. Pertama, Restorasi dan
Rehabilitasi Mangrove, yang bertujuan untuk memastikan tercapainya
upaya restorasi dan rehabilitasi terhadap kawasan hutan mangrove yang
106
mengalami kerusakan serta menjaga kawasan hutan mangrove yang ada
agar tetap lestari. Kedua, Livelihood yang berupaya untuk mendorong
masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dalam memanfaatkan
mangrove yang ada disekitarnya tentunya melalui pemanfaatan secara
lestari sehingga masyarakat dapat berdaya secara ekologi.
Kemudian ketiga adalah pendidikan lingkungan hidup, dimana Blue
Forests senantiasa mendorong masyarakat agar menjaga lingkungan
dengan menerapkan metode cara belajar particapotory action, yaitu
belajar dan melakukan aksi. Hal ini penting agar masyarakat bukan hanya
memiliki pengetahuan terhadap perlindungan mangrove melainkan juga
masyarakat didorong untuk terlibat aktif melakukan aksi nyata dalam
menjaga kawasan mangrove. Sedangkan program yang terakhir adalah
advokasi dan penyebarluasan informasi. Dalam program ini Blue Forests
berupaya untuk menjembatani pihak pemerintah dengan masyarakat, agar
kebijakan yang ada mampu mengakomodasi kemampuan masyarakat.
Dalam melaksanakannya, maka dibutuhkan kapasitas yang setara dari
pemerintah dengan masyarakat.
Kantor pusat Blue Forests berada di Makassar dengan beberapa
kantor cabang yang terletak di Demak, Jogja dan Timika. Blue Forests
sendiri telah menjalankan programnya diberbagai wilayah Indonesia
seperti di Tomohon Sulawesi Utara, Tanah langkat, Tanakeke Sulawesi
selatan dan beberapa wilayah di Papua dan telah merestorasi 512 ha
kawasan mangrove. Selain itu juga, Blue Forests juga berhasil
107
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan mangrove
melalui pembuatan produk olahan mangrove dengan tentunya melalui
pamanfaatan secara lestari.
2. Wetlands International Indonesia
Wetlands International Indonesia (WII) adalah lembaga yang
bergerak dalam kegiatan perlindungan, dan rehabilitasi ekosistem lahan
basah, penyadartahuan dan peningkatan kapasitas multistakeholder,
pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta advokasi
kebijakan lahan basah. WII sendiri merupakan bagian dari Wetlands
International yang merupakan organisasi non pemerintah yang bersifat
global dan bergerak di bidang konservasi dan restorasi lahan basah dunia.
Dalam perkembangannya Wetland International Indonesia telah banyak
berperan dalam berbagi upaya dalam perlindungan dan pengelolaan
hutan Mangrove Indonesia, diantaranya:
a) Restorasi Mangrove
Wetlands International telah bekerja dalam upaya pelestarian
ekosistem mangrove selama lebih dari 30 tahun, termasuk di Indonesia
yang memiliki mangrove terluas di dunia. Pada dekade pertama, peran
WII lebih ditujukan kepada kegiatan inventarisasi untuk memetakan
berbagai lokasi penting wilayah mangrove, termasuk potensi dan
kondisinya. Salah satu capaian penting WII adalah memfasilitasi
108
pengukuhan 2 (dua) Taman Nasional lahan basah di Sumatra, yang
kemudian juga ditunjuk sebagai lokasi Ramsar di Indonesia.131
Dekade selanjutnya, lebih ditujukan untuk mempertahankan ekosistem
mangrove yang masih baik. Pada saat yang sama melakukan rehabilitasi
dan restorasi terhadap ekosistem mangrove yang telah mengalami
kerusakan dengan mengikutsertakan secara aktif masyarakat lokal dan
pemerintah daerah setempat. Lebih dari 4 juta bibit, termasuk di lokasi
yang terkena dampak tsunami di Flores dan Nangroe Aceh Darussalam,
telah ditanami mangrove bersama masyarakat lokal melalui mekanisme
program Bio-Rights.132
b) Advokasi
Selain melakukan upaya restorasi mangrove, WII juga senantiasa
menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengadakan advokasi.
Salah satunya bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota
(DLHK) Serang dan Wetlands International Indonesia (WII) mengadakan
lokakarya bertajuk “Penguatan kebijakan Daerah untuk Perlindungan
Ekosistem Mangrove Kota Serang”. Lokakarya ini dilatar belakangi oleh
absennya kebijakan daerah yang melindungi kawasan ekosistem
mangrove di Kota Serang. Untuk itu, lokakarya ini menjadi ajang
penggalangan dukungan rencana penyusunan produk hukum daerah
131
Anggita kalistaningsih, 2017, More Mangrove Please, https://indonesia.wetlands.org/id/berita/more-mangroves-please/, diakses pada 23 Maret 2018
132 Ibid
109
terkait rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kota Serang
yang akan diusung oleh DLHK.133
c) Pelibatan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi mangrove
merupakan suatu keniscayaan untuk mendukung tingkat keberhasilan
yang tinggi. Wetlands International telah melakukan kegiatan
pemerangkapan sedimen untuk pertumbuhan alami mangrove tersebut di
wilayah Banten, Flores, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah.
Upaya tersebut dilakukan dengan teknologi sederhana, tidak terlalu
mahal dan menggunakan bahan-bahan yang tersedia setempat.
Masyarakat diikutsertakan secara penuh dalam berbagai kegiatan
tersebut, dan untuk mereka yang mengikuti kegiatan kemudian diberikan
pinjaman tanpa bunga untuk modal kerja guna meningkatkan mata
pencaharian masyarakat. Jika dalam waktu tertentu yang disepakati
kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh masyarakat membuahkan
hasil yang mencukupi, maka kemudian pinjaman tanpa bunga tersebut
akan dirubah menjadi hibah. Mekanisme pinjaman tanpa bunga bersyarat
tersebut dikenal sebagai mekanisme Bio-Rights.134
133
Anonim, 2017, Siaran pers lokakarya penguatan kebijakan daerah untuk perlindungan ekosistem mangrove di Kota Serang, https://indonesia.wetlands.org/id/news/siaran-pers-lokakarya-penguatan-kebijakan-daerah-untuk-perlindungan-ekosistem-mangrove-di-kota-serang/, diakses pada 24 Maret 2018 Pukul 22:43 WITA.
134Nyoman Suyadiputra, 2017, Keterlibatan Masyarakat pada kegiatan
Rehabilitasi Mangrove, https://indonesia.wetlands.org/id/news/keterlibatan-masyarakat-kegiatan-rehabilitasi-mangrove/, diakses pada 24 Maret 2018.
110
c. Implementasi dalam Upaya Reserve and Training terhadap
Perlindungan Hutan Mangrove Indonesia
1. Reserve
Merujuk pada Pasal 4 ayat 1 bahwa setiap anggota wajib
mempromosikan konservasi lahan basah dan burung air dengan
mendirikan cagar alam pada lahan basah, baik mereka termasuk dalam
“List” atau tidak, dan melakukan pengamanan yang memadai. Dalam hal
ini, Indonesia sendiri telah menjalankan komitmen tersebut melalui upaya
perlindungan dan pengelolaan mangrove yang berada dalam kawasan
perlindungan. Baik itu Cagar alam, suaka margasatwa maupun taman
nasional yang tersebar diberbagai provinsi Indonesia. seperti di Cagar
alam Riung, Kepulauan Karimata, Tanjung Panjang Pohuwatu, TN
Kepulauan Seribu, TN Karimun Jawa dan TN Bunaken, TN Kep.Togean,
Suaka Margasatwa Muara angke dan lain-lain yang memiliki beragam
vegetasi mangrove didalamnya.135
Namun, permasalahan tata kelola menjadi permasalahan besar
dalam perlindungan hutan mangrove. Dimana kawasan konservasi yang
seharusnya menjadi pusat perlindungan mangrove justru ditelantarkan
dan banyak mengalami perubahan peruntukan. Hal ini dikemukakan oleh
Direktur Blue Forests, yang menyatakan bahwa hutan mangrove yang
berada dalam kawasan konservasi, juga rentan mengalami kerusakan.
135
Dirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam, 2014,Stasitik Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014, Jakarta:: Kementrian kehutanan, Sekretariat Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, hlm. 25-26.
111
Contohnya Cagar Alam Tanjung Panjang, Pohuwatu, Gorontalo, yang
dulunya memiliki luasan mangrove sekitar 3.000 hektar kini tersisa 500
hektar saja. Selain itu, Suaka Margasatwa di Mampie di Polewali Mandar,
Sulawesi Barat dimana mangrovenya dikonversi menjadi tambak dan
ketika tidak produktif lagi kemudian ditelantarkan. Contoh paling unik
adalah di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Sulawesi
Tenggara (Situs Ramsar). Dimana didalam kawasan tersebut
mangrovenya cukup terjaga namun sangat berbeda dengan yang terjadi di
luar kawasan.
Hal ini mengindikasikan masih belum terciptanya tata kelola
kawasan konservasi yang baik di Indonesia, sehingga mengakibatkan
banyak kawasan konservasi yang ada belum mampu menjaga fungsinya
dalam memberikan perlindungan.
2. Training
Dalam pasal 4 ayat 5 dari Konvensi menyatakan bahwa para
anggota wajib mempromosikan pelatihan personil untuk meningkatkan
kompetensi di bidang penelitian lahan basah, manajemen dan
pengamanan. Dalam menerapkan kewajiban ini, pihak-pihak terkait
pengelolaan hutan mangrove di Indonesia sendiri memiliki program-
program tersendiri terkait upaya pelatihan personil ini.
Seperti halnya KLHK yang memiliki Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM (PSD2M) yang berperan dalam menjamin
ketersediaan SDM yang cukup dengan kualitas yang memadai sesuai
112
dinamika pembangunan LHK. Pada tahun 2016, telah diselenggarakan
pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dimaksudkan untuk
mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM yang terampil,
professional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.. Selain
pelatihan kepada staf KLHK, diadakan pula kegiatan penyuluhan yang
meliputi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari pemula
menjadi madya, pembentukan lembaga pemagangan LP2UKS, fasilitasi
pos penyuluhan kehutanan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
konservasi. Hal ini sebagai wadah peningkatan kapasitas masyarakat
untuk ikut andil dalam menjaga lingkungan.136
Dalam rangka meningkatkan intensitas penguasaan teknologi dan
diseminasi informasi mangrove, KLHK juga mengembangkan Pusat
Rehabilitasi Mangrove (Mangrove Centre). Pusat rehabilitasi mangrove ini
berperan dalam mempertahankan fungsi mangrove sebagai penyangga
kestabilan ekosistem daerah pesisir. Selain itu juga berfungsi membantu
dalam bidang pendidikan sebagai laboratorium alam untuk penelitian dan
konservasi berbagai jenis mangrove dan fauna yang ada di dalamnya.
Selain itu mangrove center juga dapat dijadikan sebagai tempat ekowisata
yang pro lingkungan.
136
Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, Statistik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2016, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,hlm.307.
113
d. Implementasi dalam Kerjasama Internasional Perlindungan
Hutan Mangrove Indonesia
1. Kerjasama Indonesia dengan JICA
Kementerian Kehutanan Melalui Direktorat Jenderal Bina
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS)
bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)
terkait pengelolaan hutan mangrove di Indonesia. Kerjasama dengan
pemerintah Jepang sudah dimulai Sejak tanggal 1 Desember 1992
mengenai pengembangan hutan mangrove hingga tahun 1999. Adapun
hasil kerjasama ini adalah dihasilkannya manual silviculture, nursery,
mangrove handbook, dan model pengelolaan mangrove yang
berkelanjutan.137
Setelah itu kerjasama dilanjutkan dengan proyek Mangrove
Information Center Project (MIC) semenjak bulan Mei 2001 sampai Mei
2004 dengan perpanjangan selama 2 tahun (s.d Mei 2006). Output yang
didapatkan melalui kegiatan ini adalah Gedung Mangrove Information
Center yang berlokasi di Bali, didalamnya terdapat museum mangrove
dan informasi mengenai ekosistem mangrove di Indonesia dan juga di
seluruh dunia. Selain itu juga terdapat beberapa training program yang
sampai saat ini masih dipergunakan untuk kepentingan peningkatan SDM
di bidang konservasi hutan mangrove. Kerjasama tahap berikutnya
137 Budi hidayat, 2011, Kemenhut-JICA Jalin Proyek MECS, http://redd-
indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=356:kemenhut-jica-jalin-kerjasama-proyek-mecs&catid=35:berita-dari-kementrian-kehutanan-&Itemid=75, diakses pada 24 Maret 2018.
114
dimulai dari Januari 2007 sampai dengan Januari 2010 dengan proyek
berjudul Sub Sectoral program on Mangrove Project. Dari proyek ini
dihasilkan panduan untuk pembentukan model area pengelolaan
mangrove yang berkelanjutan.138
Kemudian pada tahun 2011 kerjasama dilanjutkan dengan
menyepakati proyek kerjasama teknis, yaitu “The Project on Mangrove
Ecosystem Conservation and Sustainable Use in The ASEAN Region
(MECS)”. Kerjasama ini berlangsung selama 3 tahun (s.d bulan Juni
2014). MECS bertujuan membanguan mekanisme berbagi pengalaman
dan pembelajaran (Shared-Learning) terhadap konservasi mangrove
sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir di negara -negara Asia
Tenggara. Metode Shared – Learning Workshop dipromosikan sebagai
salah satu cara untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi antar dinas
terkait serta masyarakat di Indonesia khususnya dan di wilayah Asia
Tenggara pada umumnya.139
138
Ibid 139
Pande Gede Aditya Parama Putra, dkk, 2016, Peranan JICA dalam Konservasi Mangrove di Indonesia Sebagai Bagian dari Program The Project For Mangrove Ecosystem Conservation And Sustainable Use in the ASEAN Region (MECS), Bali: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, hlm.2.
115
2. Science for Protection of Indonesian Coastal Ecosystems
(SPICE)
SPICE merupakan sebuah program kerjasama antara Leibniz-
Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT), sebuah lembaga penelitian
Jerman yang berfokus pada upaya perlindungan dan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem pesisir tropis dengan Kementerian Riset dan
Teknologi RI (Kemenristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
(KKP).
Program SPICE ini bertujuan untuk mengatasi isu-isu ilmiah, sosial
dan ekonomi terkait dengan pengelolaan ekosistem pesisir Indonesia
serta sumber daya yang tersedia. Program ini sendiri telah dilaksanakan
dalam 3 tahap, yaitu SPICE Tahap I (2003-2007), SPICE Tahap II (2007-
2010) dan SPICE Tahap III yang tengah berjalan (Maret 2012 - Pebruari
2015). SPICE Tahap I memfokuskan pembelajaran mengenai struktur dan
fungsi ekosistem pesisir yang meliputi hutan mangrove, terumbu karang,
sistem pesisir dan rawa gambut serta berbagai perubahan yang dialami
karena faktor manusia. SPICE Tahap II memfokuskan pada ilmu-ilmu
alam yang dilengkapi dengan ilmu sosial yang bertujuan untuk memahami
dimensi sosial perubahan ekosistem pesisir, untuk menganalisis dinamika
sosial ekologis serta meningkatkan keketerkaitan antara penelitian dan
pembuatan keputusan. Sedangkan SPICE Tahap III mengangkat topik
penelitian mengenai:
116
a) Dampak pencemaran laut terhadap keanekaragaman hayati dan
kehidupan pesisir;
b) Penyerapan karbon di laut-laut Indonesia dan maknanya secara
global;
c) Pemahaman dan pengelolaan ketahanan terumbu karang serta
sistem sosial yang terkait;
d) Pengaruh terestrial (kebumian/terkait tanah) ekologi mangrove dan
keberlanjutan sumber daya mangrove;
e) Iklim vs antropogenik (emisi gas yang bersumber dari aktivitas
manusia, seperti penggundulan hutan) yang berdampak terhadap
perubahan lingkungan dan mempengaruhi laut Indonesia, pesisir
dan ekosistem darat;
f) Potensi energi terbarukan di laut Indonesia.140
SPICE Final Conference dilaksanakan pada tanggal 20-21 Januari
2016 di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Konferensi ini bertujuan
untuk mempresentasikan kegiatan-kegiatan dalam fase SPICE I (2003-
2007), SPICE II (2008-2011), dan SPICE III (2012-2015).Berbagai topik
yang dipresentasikan dalam konferensi ini, yakni (1) Carbon
Sequestration,(2) Marine Geology and Biogeochemistry, (3) Renewable
Energy, (4) Governance of Coastal and Marine Ecosystems, (5)
Understanding Ecological and Socio Economic Dynamics of Mangrove
Ecosystems Under Pressure, (6) Pollution, Aquaculture,(7) Stakeholder
Consultation, dan (8) Coral Reef-Based Ecosystems.Kemristekdikti, KKP,
140
Anonim, 2014, Kerjasama Pengelolaan Ekosistem Pesisir Indonesia sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia, https://www.kjrihamburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=461:kerjasama-pengelolaan-ekosistem-pesisir-indonesia-sebagai-salah-satu-upaya-memperkuat-ketahanan-pangan-indonesia&catid=42&lang=id&Itemid=407, diakses pada 18 April 2018
117
BPPT, LIPI dan berbagai universitas sebagai pelaksana program SPICE
turut berpartisipasi dalam konferensi akhir SPICE tersebut.141
3. International Conference on Sustainable Mangrove
Ecosystem
Dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan
untuk mencapai pengelolaan hutan lestari, maka pada tanggal 18-21 April
2017, bertempat di Provinsi Bali dilaksanakan International Conference on
Sustainable Mangrove Ecosystem. Konferensi internasional ini
dilaksanakan bersama oleh International Timber Trade Organization
(ITTO), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan
International Society for Mangrove Ecosystem (ISME). Berkolaborasi
dengan the Center for International Forestry Research (CIFOR), the Asia-
Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation
(APFNet), AFoCo, dan lainnya.142
Konferensi yang dihadiri oleh 272 dari 24 negara ini bertujuan untuk
mempromosikan pengelolaan ekosistem mangrove dengan membangun
pembelajaran dari banyak inisiatif dan proyek-proyek dari dalam dan luar
negeri yang telah dilakukan untuk perlindungan, restorasi, pengelolaan
dan pemanfaatan hutan mangrove dan jasa ekosistem serta
141
Kemenristekdikti, 2016, Kerjasama Riset Indonesia-Jerman Untuk Melindungi Ekosistem Perairan Indonesia https://ristekdikti.go.id/12-tahun-kerjasama-riset-indonesia-jerman-untuk-melindungi-ekosistem-perairan-indonesia/, diakses pada 25 Maret 2018
142 Luh De Suryani, 2017, begini Rekomendasi untuk pelestarian ekosistem
mangrove dunia, http://www.mongabay.co.id/2017/04/24/begini-rekomendasi-untuk-pelestarian-ekosistem-mangrove-dunia/, diakses pada 12 Maret 2018.
118
mengidentifikasi cara-cara meningkatkan mata pencaharian masyarakat
sekitar hutan mangrove untuk kesejahteraan.143
Dalam konferensi ini dihasilkan beberapa rekomendasi terkait
upaya pelestarian ekosistem mangrove dunia, yaitu:144 1) promosi
pengelolaan ekosistem mangrove; 2) mengatasi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim; 3) pemulihan hutan mangrove dan ekosistem
terdegradasi; 4) meningkatkan mata pencaharian masyarakat terkait
mangrove; 5) penguatan tata kelola, penegakan hukum dan sistem
pemantauan; 6) valuasi jasa lingkungan; dan 7) penelitian dan pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan ekosistem mangrove.
e. Upaya Konservasi Mangrove Indonesia
Salah satu aspek penting dalam melihat sejauhmana komitmen
Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Ramsar adalah terkait upaya
konservasi yang dilakukan Indonesia melalui program restorasi dan
rehabilitasi. Mengingat banyak kawasan hutan mangrove yang telah
mengalami kerusakan akibat berbagai faktor khususnya akibat alih fungsi
lahan mangrove untuk peruntukan lain yang tidak lestari.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KLHK, dari tahun 2012
hingga tahun 2016 KLHK telah melaksanakan kegiatan penanaman
mangrove seluas 22.261 ha diberbagai wilayah Indonesia.
143
Direktorat BPEE, 2017, http://ksdae.menlhk.go.id/berita/594/konferensi-internasional-ekosistem-mangrove-, berkelanjutan.html, diakses pada 12 Maret 2018
144 Leh De Suryani, Op.cit.
119
Gambar 6. Pelaksanaan Penanaman Mangrove Tahun 2012 – 2016145
Kemudian dalam Permenko No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan,
Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Nasional (Stranas Mangrove), Dengan memperhatikan kondisi ekosistem
mangrove yang rusak cukup luas yakni sebesar 1,80 juta hektar serta laju
kerusakan yang cukup tinggi maka ditetapkan target tutupan mangrove
yang baik pada tahun 2045 sebesar 3,49 juta hektar, dengan tahapan
sebagai berikut:
Tabel 4. Target Pemulihan Ekosistem Mangrove
No Tahun Luas Mangrove yang baik (juta ha)
1 2017 1,69
2 2019 1,75
3 2024 1,95
4 2029 2,27
5 2034 2,69
6 2039 3,15
7 2044 3,47
8 2045 3,49
145
Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Op.cit,
hlm 136
120
Ditengah target pemulihan ekosistem mangrove yang ditetapkan
pemerintah tersebut, kemungkinan kegagalan restorasi mangrove juga
mengancam upaya tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Yusran (Direktur Blue Forests) yang menyatakan bahwa dari sekian
banyak upaya restorasi yang dilakukan pemerintah, presentase
keberhasilan mangrove yang tumbuh hanya sekitar 10 %.
Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan kegagalan restorasi mangrove di Indonesia. Pertama,
penanaman dilakukan di lokasi yang masyarakat setempat tidak
mendukung. Dalam kondisi ini, masyarakat akan cenderung menjadikan
wilayah restorasi sebagai lokasi pengembangan ekonomi sesaat, seperti
pembukaan tambak. Kedua, penanaman jenis tunggal, sehingga tidak
fungsional dan menyediakan manfaat yang minimum. Ketiga, penanaman
jenis yang salah di tempat yang salah, tidak memperhatikan pasang surut,
ombak, tingkat erosi maupun kondisi substrat. Keempat, penanaman di
lokasi yang akar permasalahan hilangnya mangrove belum teratasi.
Kelima, penanaman di lokasi yang secara alami sedang berlangsung
proses regenerasi, sehingga dapat mengganggu proses regenerasi
tersebut. Dan terakhir, penanaman di lokasi yang secara historis tidak
pernah diketahui sebagai lokasi tumbuhnya mangrove.
Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh
Rini Purwanti selaku staf peneliti di Lembaga penelitian dan
pengembangan lingkungan hidup dan Kehutanan Makassar. Yang
121
mengakui bahwa upaya restorasi mangrove yang dilakukan oleh
pemerintah masih belum berjalan efektif disebabkan karena:146
1. Program penanaman bibiit mangrove diberbagai kawasan hanya
berorientasi pada pelaksanaan “Proyek” semata. Maksudnya
penanaman yang dilakukan tidak diimbangi dengan upaya
pemeliharaan yang berkelanjutan.
2. Faktor masih mininimnya pengetahuan masyarakat akan
pentingnya kawasan hutan mangrove sebagai penyangga
kehidupan. Akibatnya, keterlibatan masyarakat juga masih rendah.
3. Faktor ekonomi, dimana masyarakat menganggap bahwa
mangrove yang ditanam akan mengurangi kawasan penanaman
rumput laut yang menjadi komoditi utama sebagaian masyarakat
pesisir.
Oleh karena itu, menurut Yusran dibutuhkan enam langkah
strategis dalam mendukung tata kelola mangrove yang baik di Indonesia,
yaitu:147
1) Pertama, mendorong moratorium konversi mangrove untuk
peruntukan lain. Moratorium yang dimaksud bukan moratorium
penebangan mangrove, tapi (penghentian) konversi untuk
peruntukan lain, karena ternyata dilahan konsesi mangrove yang
ada di Indonesia terlihat bahwa jika logging-nya dikelola dengan
baik justru mangrove-nya bisa tumbuh dengan baik juga;
146
Hasil wawancara dengan Rini Purwanti selaku staf peneliti BP2LHK Makassar tanggal 9 April 2018
147 Hasil Wawancara dengan Yusran Nurdin Massa ( Direktur Blue Forests)
Tanggal 3 April 2018
122
2) Kedua, adalah perbaikan tata kelola kawasan konservasi
mangrove, Taman Nasional, Cagar Alam dan Suaka matgastwa.
Selama ini, banyak kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
perlindungan mangrove namun ternyata ditelantarkan;
3) Ketiga, adalah program konservasi perlindungan mangrove harus
berbasis masyarakat. Karena selama ini banyak program
konservasi atau rehabilitasi yang gagal karena tidak melibatkan
masyarakat sekitar;
4) Keempat, adalah perlu ada upaya rehabilitasi kembali lahan
tambak yang terlantar menjadi hutan mangrove, karena sekitar 60
persen mangrove di Indonesia hilang karena dikonversi menjadi
tambak;
5) Kelima, adalah perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
rehabilitasi di Indonesia untuk meningkatkan tingkat keberhasilan;
6) Terakhir adalah penguatan dan pemberdayaan pembudidaya
tambak menuju tata kelola budidaya berkelanjutan. Bagaimana
mengelola tambak secara efisien dan menghasilkan di suatu
kawasan tertentu yang tidak merangsang untuk perambahan
wilayah.
2. Analisis Implementasi Ramsar Convention 1971 terhadap
Perlindungan Hutan Mangrove di Indonesia
Pada dasarnya Indonesia telah menjalankan kewajibannya
sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Ramsar. Namun, tidak
dapat dipungkuri bahwa masih terdapat banyak permasalahan, sehingga
mengakibatkan belum optimalnya perlindungan hutan mangrove di
Indonesia. Berikut merupakan beberapa analisis yang penulis uraikan
terkait faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan Ramsar
123
Convention 1971 dalam memberikan perlindungan terhadap hutan
mangrove di Indonesia.
a. Implikasi Pengesahan Ramsar Convention 1971 melalui
Keputusan Presiden
Konsekuensi ikut sertanya suatu negara dalam suatu perjanjian
internasional adalah kesediaannya untuk mengimplementasikan kedalam
hukum nasional. Adapun yang dimaksud implementasi atau penerapan
perjanjian internasional pada peraturan perundang-undangan adalah
membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian yang diterima. Tanpa adanya perundang-
undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam perjanjian dimana suatu negara menjadi pihak didalamnya, maka
perjanjian tersebut tidak ada gunanya.148
Permasalahan yang kemudian muncul dalam implementasi
Konvensi Ramsar di Indonesia adalah terkait cara pengesahannya yang
hanya menggunakan Keppres. Padahal materi muatan yang diatur dalam
Konvensi ini terkait masalah lingkungan hidup yang pada hakikatnya
merupakan permasalahan kompleks yang harusnya disahkan dengan
menggunakan UU. Terlepas dari pengesahan Konvensi ini yang diadakan
sebelum lahirnya UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
yang mengamanatkan perjanjian internasional yang muatannya terkait
148 Kholish Roisah, Op.cit hlm. 88.
124
lingkungan hidup harus disahkan dengan undang-undang.149 Namun
ketika melihat betapa pentingnya Konvensi dalam memberikan
perlindungan lahan basah di Indonesia, tentunya menimbulkan persepsi
bahwa ada ketidakseriusan pemerintah pada saat itu untuk menjaga lahan
basah termasuk mangrove yang ada di Indonesia.
Implikasi dari pengesahan Konvensi Ramsar ini yang hanya
menggunakan Keppres tentunya sangat berkaitan erat dalam kedudukan
hukum dari Konvensi dalam tata hukum nasional. Hal ini karena
kedudukannya sebagai Keppres telah mempersulit untuk dikeluarkannya
Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah guna
mengimplementasikan Konvensi ini. Sehingga produk hukum setingkat
Undang-undang maupun peraturan pemerintah yang memiliki tujuan yang
sama dengan Konvensi ini tidak bisa merujuk atau mendasarkan pada
Konvensi Ramsar ini. Sehingga hingga saat ini, penggunaan Konvensi
Ramsar sebagai dasar pengelolaan mangrove di Indonesia pun belum
ada.
b. Konflik Kewenangan dalam Pengelolaan Hutan Mangrove
Indonesia
Salah satu permasalahan dalam pengelolaan mangrove yang
terjadi selama ini di Indonesia adalah terkait tumpang tindih kewenangan
antara satu lembaga dengan lembaga lain yang disebabkan karena
149
Lihat Pasal 10 bagian (c) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
125
adanya ketidaksinkronan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya
dalam hal pengelolaan hutan mangrove. Khususnya konflik kewenangan
yang terjadi antara KLHK dengan KKP yang sama-sama memiliki
kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove.
KLHK sendiri mengklaim bahwa pengelolaan hutan mangrove
merupakan kewenanganya, hal ini didasarkan pada status mangrove
sebagai hutan sebagaimana diatur dalam UU No.41 tahun 1999 tentang
kehutanan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga
beranggapan bahwa mereka memiliki kewenangan dalam mengelola
hutan/ekosistem hutan mangrove berdasarkan kawasannya atau
ekosistemnya (wilayah pesisir), dimana habitat dari mangrove berada
pada wilayah pesisir sebagaimana yang diatur dalam UU No.1 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal inilah
yang kemudian memunculkan konflik kewenangan dalam pengelolaan
hutan mangrove di Indonesia.
Namun pada dasarnya pemerintah telah berupaya untuk mengatasi
konflik kewenangan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.4 Tahun 2017 tentang
Kebijakan, Strategi, Program dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem
Mangrove Nasional (Stranas Mangrove). Permenko ini mengatur berbagai
sasaran, strategi, program dan kegiatan pada empat nilai penting
pengelolaan ekosistem mangrove yaitu ekologi, sosial ekonomi,
126
kelembagaan dan perundang-undangan. Permenko ditujukan sebagai
pedoman dan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi
maupun kabupaten/kota dan para pihak lain dalam mengelola ekosistem
mangrove sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Diharapkan
melalui Permenko ini dapat memperbaiki ketidaksinkronan peraturan yang
ada dan mampu mendorong kerjasama dari berbagai pihak dalam rangka
pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia.
c. Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove di
Indonesia
Pengelolaan hutan mangrove yang multisektoral tentunya
membutuhkan koordinasi yang kuat antar lembaga maupun badan-badan
pelaksana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun,
berkaca pada masih tingginya laju kerusakan hutan mangrove di
Indonesia, padahal telah dibentuk bebagai lembaga maupun badan
pelaksana, tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait efektifitas dari
kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya selaku pihak yang
memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan mangrove.
Lemahnya koordinasi antar sektor serta adanya egoisme sektoral
pada dasarnya merupakan akar dari kurang efektifnya badan-badan
pelaksana pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove baik itu
Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional, Provinsi maupun
Kabupaten/Kota serta Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM) dalam
127
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Permasalahan lain yang juga mendera kelembagaan pengelolaan
mangrove Indonesia adalah sudah tidak berfungsinya lagi Komite
Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah (KNLB) maupun tim
pelaksana kesekretariatannya. Hal ini tentu sangat merugikan, karena
pada dasarnya komite ini merupakan wujud implementasi dari
kelembagaan pengelola lahan basah Indonesia.
Melihat serangkaian permasalahan kelembagaan pengelolaan dan
perlindungan hutan mangrove di Indonesia tersebut, maka sudah
sepatutnya pemerintah bergerak secara cepat dalam memperbaiki tata
kelola kelembagaan yang ada, karena apabila tidak ditangani dengan baik
maka akan berdampak pada semakin tingginya laju kerusakan mangrove
di Indonesia.
d. Belum Optimalnya Upaya Konservasi Mangrove Indonesia
Faktor yang tidak kalah penting dalam perlindungan hutan
mangrove di Indonesia adalah upaya pemerintah terkait konservasi
mangrove yang ada. Hal ini sangat penting dalam proses menjaga dan
menghentikan laju kerusakan mangrove yang terus menerus terjadi. Tidak
dapat dipungkuri bahwa minimnya lahan basah Indonesia yang
didaftarkan sebagai Situs Ramsar khususnya kawasan yang memiliki
hutan mangrove menjadi pertanyaan besar, terkait komitmen pemerintah
Indonesia dalam menyelamatkan lahan basah dunia. Terlebih lagi banyak
128
kawasan konservasi mangrove di Indonesia yang seharusnya menjadi
tempat perlindungan, justru mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh
tata kelola serta penegakan hukum yang masih lemah.
Upaya restorasi yang juga dicanangkan pemerintahpun masih
belum berjalan optimal dalam memperbaiki kawasan hutan mangrove
yang mengalami kerusakan. Dimana penanaman mangrove yang
dilakukan tidak memperhatikan kondisi penanaman, kemudian tidak
diimbangi dengan proses pemeliharaan yang baik sehingga persentase
keberhasilan restorasi yang dilakukan juga masih sangat minim.
Hal yang tidak kalah penting dalam mencapai keberhasilan
konservasi mangrove di Indonesia adalah pelibatan masyarakat,
khususnya masyarakat pesisir dalam menjaga dan turut serta mengelola
hutan mangrove. Hal ini penting mengingat kegagalan restorasi mangrove
sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya sedikit banyak dipengaruhi
oleh minimnya pelibatan masyarakat baik dalam hal pengambilan
kebijakan maupun ditahap pengeloaan hutan mangrove.
Selain itu, menguatkan kembali nilai-nilai keraifan lokal yang
memiliki kaitan dengan upaya menjaga lingkungan juga harus senantiasa
digalakkan. Contohnya yang kearifan lokal yang telah turun-temurun
dipahami dan dijalankan oleh masyarakat lokal Tanakeke untuk menjaga
sebagian dari wilayah hutan mangrovenya dalam bentuk hutan mangrove
yang dilestarikan/dilindungi (local community-based protected mangrove
129
forest) dalam bentuk hutan mangrove yang tidak boleh diganggu (“bangko
panganreang” dan “bangko tappampang”).150
Selain itu, pemerintah seharusnya menjalin kerjasama yang kuat
dengan NGO yang sudah teruji dalam melaksanakan konservasi
mangrove, agar keberhasilan yang telah dicapai oleh NGO ini dapat pula
diterapkan oleh pemerintah. Sehingga target perbaikan kawasan hutan
mangrove yang ditatapkan ditahun 2045 tersebut dapat benar-benar
terwujud.
e. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum
Lemahnya pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan
hukum baik ditingkat masyarakat maupun pemerintah juga berperan besar
dalam meningkatnya laju kerusakan hutan mangrove di Indonesia.
Meskipun pada dasarnya telah banyak peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah terkait perlindungan hutan mangrove, namun pada
kenyataannya peraturan-peraturan tersebut, banyak tidak
diimplementasikan dengan baik.
Lemahnya penegakan hukum dibidang kehutanan dapat diamati
dari hanya sedikit pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang berhasil
dituntut dan para pengusaha sebagai pelaku utama justru dapat
150
Irwansyah, Maskun, Birkah Latif, Irham Rapy, 2013, Kajian EfektifitasRegulasi Pemanfaatan Hutan Mangrove di Kabupaten Takalar, Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Unhas, Vol. 2 (1).
130
menghindari hukuman. Bukti lemahnya pengawasan dan penegakan
hukum ini dapat dilihat dari beberapa kasus dibawah ini:
1. Pengerusakan hutan mangrove terjadi di kawasan hutan pesisir
Mangrove di Aceh Tamiang. Dari 24.013,5 ha total luas kawasan
hutan mangrove yang mencakup 109,24 ha hutan lindung, serta
18.904,26 ha hutan produksi, 80% berada dalam kondisi rusak akibat
berbagai aktifitas ilegal. Seperti perambahan dan illegal logging.
Perambahan dilakukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit
serta pembangunan tambak. Sedangkan hasil dari illegal logging
dijadikan sebagai bahan baku arang. Aktifitas illegal logging sebagian
besarnya dibiayai oleh pemilik dapur arang yang saat ini telah
mencapai lebih dari 200 unit, dan secara umum di indikasikan tidak
memiliki izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi
faktor utama, aktifitas ilegal tersebut terus terjadi. Terlebih,
masyarakat mengakui oknum pemerintah ikut terlibat dan memiliki
usaha dapur arang di lokasi.151
2. Kasus pembabatan hutan mangrove juga terjadi di dusun Kuri
Lompo, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
Sulsel. Dimana kawasan hutan mangrove yang berada diwilayah
tersebut telah dialihkan menjadi tanah garapan dan telah terbit surat
ketetapan pajak. Pembabatan hutan mangrove diwilayah ini telah
151
Muhammad Nur. 2018, Seluas 85% Kawasan Hutan Mangrove Aceh Tamiang Rusak, http://walhiaceh.or.id/seluas-85-kawasan-hutan-mangrove-aceh-tamiang-rusak/, diakses pada 12 april 2018.
131
dilakukan secara sistematis, bahkan didukung oleh pemerintah
setempat. Padahal di Kabupaten Maros sendiri telah terbit Perda
terkait perlindungan mangrove.152
3. Lemahnya penegakan hukum juga tercermin dalam rendahnya
tuntutan jaksa terhadap terdakwa pelaku pembalakan dan reklamasi
liar di hutan mangrove dalam kawasan konservasi Tahura Ngurah
Rai khususnya di Kelurahan Tanjung Benoa Bali 11 Desember 2017
yang kemarin. Dalam tuntutannya, Jaksa hanya menuntut terdakwa
Made Wijaya delapan bulan penjara dan denda Rp.10 juta serta lima
terdakwa lainnya dengan enam bulan penjara. Padahal dalam
Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan hukumannya paling singkat satu
tahun dan paling lama lima tahun penjara. Hal ini berbanding terbalik
dengan yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur 2014 yang lalu,
dimana seorang nenek berusia 58 tahun divonis dua tahun penjara
dan denda Rp.2 miliar karena menebang tiga pohon mangrove untuk
kayu api.153 Minimnya tuntutan jaksa ini bertolak belakang dengan
semangat pemerintah khususnya Menteri Lingkungan Hidup dan
152
Muh basir, 2018,Tak hanya dibabat Lahan Mangrove di Maros ternyata telah
dialihfungsikan, http://www.inikata.com/tak-hanya-dibabat-lahan-mangrove-di-maros-ternyata-telah-dialifungsikan/, diakses pada 12 April 2018.
153 Kabarnusa.com, 2017, FPM Kecewa, Pelaku Reklamasi Liar di Tanjung
Benoa Dituntut Ringan, https://www.kabarnusa.com/2017/12/fpm-kecewa-pelaku-reklamasi-liar-di.html, diakses pada 12 April 2018.
132
Kehutanan dalam menjaga lingkungan dan memerangi perusakan
lingkungan.
Lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pihak
yang dengan sengaja melakukan pengerusakan dan konversi lahan
mangrove ini menjadi suatu bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia
masih belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hutan
mangrove yang ada.
133
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Ramsar Convention 1971 merupakan instrumen hukum
internasional yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan lahan
basah termasuk hutan mangrove dari laju kerusakan yang semakin
hari semakin terancam akibat ulah manusia. Konvensi Ramsar
telah meletakkan dasar pengaturan terkait perlindungan hutan
mangrove. Dimana dalam menjalankan Konvensi ini setiap negara
anggota memiliki kewajiban untuk senantiasa melindungi hutan
mangrove yang ada diwilahyahnya sebagai bagian dari lahan
basah untuk kepentingan internasional. Kewajiban tersebut antara
lain listed sites, wise use wetlands, reserve and training,
international cooperation yang dimuat dalam Konvensi maupun
ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur melalui resolusi-resolusi
yang ditetapkan.
2. Pada dasarnya Indonesia telah melaksanakan segala
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini. Mulai dari
impelementasi dalam hal penetapan lahan basah yang dimiliki
Indonesia sebagai Situs Ramsar, terdapatnya berbagai peraturan
perundang-undangan serta kelembagaan yang berfokus pada
perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove serta implementasi
dalam hal pencadangan dan pelatihan serta kerjasama
134
internasional sebagai wujud tanggung jawab Indonesia dalam
menjaga hutan mangrove yang ada. Namun, tidak dapat dipungkuri
masih banyak dijumpai permasalahan-permasalahan perlindungan
hutan mangrove di Indonesia. Mulai dari tidak adanya peraturan
pelaksana dari Ramsar Convention 1971, tidak sinkronnya antara
satu peraturan dengan peraturan lainnya dalam hal kewenangan
pengelolaan mangrove, serta adanya tumpang tindih kewenangan
antara lembaga-lembaga terkait perlindungan mangrove. Ditambah
lagi dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta
kurang berhasilnya upaya-upaya konservasi mangrove yang
dilaksanakan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian serius dari
berbagai pihak untuk turut andil dalam mengimplementasikan
Konvensi Ramsar ini di Indonesia, sehingga tujuan dari Konvensi
ini dapat betul-betul terlaksana di Indonesia.
B. Saran
1. Menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih
menguatkan komitmennya selaku negara peratifikasi Konvensi
Ramsar khususnya dalam hal perlindungan hutan mangrove. Mulai
dari perbaikan tata kelola kelembagaan, penguatan kerjasama baik
ditingkat lokal, regional maupun internasional serta mendaftarkan
lebih banyak lahan basah termasuk hutan mangrove yang dimiliki
Indonesia sebagai Situs Ramsar;
135
2. Menyarankan kepada pemerintah untuk menyetujui moratorium
konversi lahan mangrove. Hal ini penting dalam menjaga kawasan
hutan mangrove yang tersisa dari ancaman konversi lahan
mangrove untuk peruntukan lain;
3. Pelibatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir maupun
lembaga non pemerintah baik dalam hal pengambilan kebijakan
pengelolaan hutan mangrove maupun dalam rangka upaya
konservasi hutan mangrove di Indonesia.
136
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao. 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
Alexandre Kiss dan Dinah Shelton. 2007. Guide to International Environmental Law, Koninklijke Brill NV. Leiden,Belanda.
Andreas Pramudianto. 2014. Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional (Implementasi Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia). Setara Pres. Malang.
Boer Mauna. 2003. Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global). PT. Almuni. Bandung.
Damos Dumoli Agusman. 2010. Hukum Perjanjian internasional: Kajian Teori dan raktik Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung.
Dirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam. 2014. Stasitik Direktorat Jenderal PHKA tahun 2014. Jakarta. Kementrian kehutanan. Sekretariat Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
Elli Louka. 2006. International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order. Cambridge University Press. New York
G.V.T Matthews. 1993. The Ramsar Convention on Wetlands: its History and Development. Ramsar Convention Bureau. Gland, Switzerland.
Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. Hukum Lingkungan Internasional dalam Perspektif Bisnis Internasional. Refika Aditama. Bandung.
I Wayan Parthiana. 2002. Perjanjian Internasional bagian 1. Mandar Maju Bandung.
Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah. 2004. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan Basah di Indonesia. Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
Laode M Syarief dan Andri G. Wibisana. 2015. Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan studi kasus.USAID. Jakarta.
Mochtar Kusumastmadja dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. PT Alumni. Bandung.
137
Muhammad Akib. 2014. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Muhammad Ashri. 2012. Hukum Perjanjian Internasional. Arus Timur. Makassar.
Muhammad Ilman. Iwan Tri Cahyo Wibisono, and I Nyoman N. Suryadiputra. 2011. State of the art information on mangrove ecosystems in Indonesia. Wetlands International Indonesia Programme. Bogor.
Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
Ramsar Liquid Assets. 2011. 40 years of the Convention on Wetlands. Ramsar Ramsar Convention Secretariat Rue Mauverney 28 CH – 1196 Gland, Switzerland.
Ramsar Secretariat. 2016. An Introduction to the Ramsar Convention on Wetlands, 7th ed. (previously The Ramsar Convention Manual). Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland.
Sefriani. 2016. Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer. Rajawali Pers.Jakarta.
Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Statistik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2016. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sukanda Husin. 2016. Hukum Lingkungan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta.
Yus Rusila Noor, M. Khazali dan I N.N. Suryadiputra. 2006. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Wetland International Indonesia Programme. Bogor.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
138
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 Tentang Pengesahan Convention On Wetlands Of International Importance Especially As Waterfowl Habitat
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku ketua Pengarah tim koordinasi nasional pengelolaan ekosistem Nomor 47 tahun 2017 tentang kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja pengelolaan ekosistem mangrove nasional.
Perjanjian internasional
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969
Ramsar Convention 1971 (Conventions on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat)
Stockholm Declaration 1972
Rio Declaration 1992
Recommendation 4.10: Guidelines for the implementation of the wise use concept
Resolution 5.1 The Kushiro Statement and the framework for the Implementation of the Convention
Resolution VII.21: Enhancing the conservation and wise use of intertidal wetlands
Resolution VIII.11: Guidance for identifying and designating peatlands, wet grasslands, mangroves and coral reefs as Wetlands of International Importance
Resolution VIII.32: Conservation, integrated management, and sustainable use of mangrove ecosystems and their resources
139
Jurnal
Irwansyah,Maskun, Birkah Latif, Irham Rapy. 2013. Kajian Efektifitas Regulasi Pemanfaatan Hutan Mangrove di Kabupaten Takalar. Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Unhas, Vol. 2 (1).
Jayatissa, L.P., F. Dahdouh-Guebas, and N. Koedam. 2002. A review of the floral composition and distribution of mangroves in Sri Lanka. Botanical Journal of the Linnean Society.
Kangkuso Analuddin dkk. 2016. Struktur Hutan Mangrove Sebagai Habitat Hewan Endemik Anoa Dataran Rendah (Bubalus Sp.) Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Jurnal Biowallacea, Vol. 3 (2), Hal : 384-395, Oktober, 2016.
Maulinna Kusumo Wardhani.2011. Kawasan Konservasi Mangrove: Suatu Potensi Ekowisata. Jurnal Kelautan, Volume 4. No.1 April 2011.
Nurhenu Karuniastuti. 2013. Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup. Jurnal Forum Manajemen Vol. 06 No. 1 2013.
NKT Martuti. 2013. Keanekaragam Mangrove Di Wilayah Tapak, Tugurejo, Semarang. Jurnal MIPA Universitas Negeri Semarang Volume 36 No.2 Oktober 2013.
R. C. Bishop 2013. Endangered Species and Uncertainty: the Economics of a Sale Minimum Standard. Amerian Journal of Agricultural Economics, dikutip dalam Andri G. Wibisana. “Elemen-elemen Pembangunan Berkelanjutan dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan”.
Yuniarti S dalam Konny Rusdianti dan Satyawan Sunito. 2012. Konversi Lahan Hutan Mangrove Serta Upaya Penduduk Lokal Dalam Merehabilitasi Ekosistem Mangrove (Mangrove Forest Conservation and The Role of Local Community in Mangrove Ecosytems Rehabilitations). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6, No. 1 2012.
Artikel Ilmiah
Abdul Hafidz Holii. 2010. Analisa Kebijakan Pengelolaan Pesisir Dan Mangrove Di Teluk Tomini Wilayah Propinsi Gorontalo. Gorontalo.Tomini Bay Sustainable Coastal Livelihoods and Management (SUSCLAM).
140
Akhmad Solihin, dkk. Laut Dalam Indonesia Dalam Krisis. Greenpeace Southeast Asia (Indonesia). Jakarta.
Dugan, P.J. 1987. The World Wetland Resources – Status and Trend, dalam Aspect Juridiques de la Protection des Zones Humides, UICN-Union Mondiale Pour la Nature, Gland, Swiss.
Macnae, W. 1968. A general account of the fauna and flora of mangrove swamps and forests in the Indo-West-Pacific region. Advances in Marine Biology.
Pande Gede Aditya Parama Putra, dkk. 2016. Peranan JICA dalam Konservasi Mangrove di Indonesia Sebagai Bagian dari Program The Project For Mangrove Ecosystem Conservation And Sustainable Use in the ASEAN Region (MECS). Bali. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
The World Rainforest Movement. 2014. “Blue Carbon” and “Blue REDD”: Transforming coastal ecosystems into merchandise. Montevideo, Uruguay: Redmanglar Internacional, Kiara, CPP, Canco.
Internet
Ade Masya Eta. 2014. Wetland International. http://studioriau.com/uk/artikel/lingkungan/wetlandinternational.html.
Anggita Kalistaningsih. 2017. More Mangrove Please. https://indonesia.wetlands.org/id/berita/more-mangroves-please/.
Anonim. 2013. Mangrove Muara Gembong Rusak Parah 3 Desa Hilang https://www.mongabay.co.id/2013/03/11/mangrove-muara-gembong-rusak-parah-3-desa-hilang/.
Anonim. 2014. The Ramsar CEPA Programme. https://www.ramsar.org/activity/the-ramsar-cepa-programme.
Anonim. 2014. Kerjasama Pengelolaan Ekosistem Pesisir Indonesia sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia,https://www.kjrihamburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=461:kerjasama-pengelolaan-ekosistem-pesisir-indonesia sebagai-salah-satu-upaya-memperkuat-ketahanan-pangan indonesia&catid=42&lang=id&Itemid=407.
Anonim. 2016. Sat 1.Png https, //i0.wp.com/agroteknologi.web.id/wp-content/uploads/2016/03/sat1-1.png?fit=547%2C353.
141
Anonim. 2017. Siaran pers lokakarya penguatan kebijakan daerah untuk perlindungan ekosistem mangrove di Kota Serang. https://Indonesia.wetlands.org/id/news/siaran-pers-lokakarya penguatan-kebijakan-daerah-untuk-perlindungan-ekosistem-mangrove-di-kota-serang/.
Arief Rudiyanto. 2016. Bogem, Apel Mangrove Sonneratia alba. http://www.biodiversitywarriors.org/bogem-prapat-padada-bogem-prepat-apel-mangrove.html.
Lindur Mangrove Tancang Bruguiera-Gymnorrhiz. http://www.biodiversitywarriors.org/lindur-mangrove-tancang-bruguiera-gymnorrhiza.html.
Brahmantya Satyamurti Poerwadi. 2017. Siaran Pers Nomor : SP. /PRL/I/2017 Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Upaya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam Memacu Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, http://kkp.go.id/djprl/artikel/890-refleksi-2016-dan-outlook-2017-upaya-direktorat-jenderal-pengelolaan-ruang-laut-dalam-memacu-pembangunan-sektor-kelautan-dan-perikanan
Budi Hidayat. 2011. Kemenhut-JICA Jalin Proyek MECS, http://redd-Indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=356:kemenhut-jica-jalin-kerjasama-proyek-mecs&catid=35:berita-dari-kementrian-kehutanan-&Itemid=75.
Direktorat BPEE. 2017. http://ksdae.menlhk.go.id/berita/594/konferensi-internasional-ekosistem-mangrove-, berkelanjutan.html.
Direktur Bina Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Antung Deddy Radiansyah pada komunikasi publik di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta diakses melalui http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/561.
FAO. 2008. Loss of mangroves alarming 20 percent of mangrove area destroyed since 1980 – rate of loss slowing, http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000776/index.html.
Imam Solehudin. 2017. Duh Kerusakan Hutan Mangrove di Pulau Jawa MakinParah.https://www.jawapos.com/read/2017/09/09/156036/duh-kerusakan-hutan-mangrove-di-pulau-jawa-makin-parah.
Irwanto. 2010. Hutan Mangrove dan Manfaatnya, irwantomangrove.webs.com
142
IUCN. 2017. Mangroves and REDD New Component, https://www.iucn.org/news/asia/201711/mangroves-and-redd-new-component-mff.
Kabarnusa.com. 2017. FPM Kecewa, Pelaku Reklamasi Liar di Tanjung Benoa Dituntut Ringan, https://www.kabarnusa.com/2017/12/fpm-kecewa-pelaku-reklamasi-liar-di.html.
Kemenristekdikti. 2016. Kerjasama Riset Indonesia-Jerman Untuk Melindungi Ekosistem Perairan Indonesia https://ristekdikti.go.id/12-tahun-kerjasama-riset-Indonesia-jerman-untuk-melindungi-ekosistem-perairan-Indonesia/.
Luh De Suryani.2017. Begini Rekomendasi Untuk Pelestarian Ekosistem Mangrove Dunia. http://www.mongabay.co.id/2017/04/24/begini-rekomendasi-untuk-pelestarian-ekosistem-mangrove-dunia/.
Mangrove Watch Australia. 2013. Mangrove Watch, A New Monitoring Program that Partners Mangrove Scientists and Community Participants,http://www.mangrovewatch.org.au/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=300161.
Marina Monzeglio. 2014. Pemerintah Indonesia Mengukuhkan TN Tanjung Putting di Kalimantan Tengah sebagai Situs Ramsar. https://Indonesia.wetlands.org/id/news/pemerintah-Indonesia-mengukuhkan-tn-tanjung-puting-di-kalimantan-tengah-sebagai-situs-ramsar/.
Muh Basir. 2018. Tak hanya dibabat Lahan Mangrove di Maros ternyata telah dialihfungsikan, http://www.inikata.com/tak-hanya-dibabat-lahan-mangrove-di-maros-ternyata-telah-dialifungsikan/.
Muhammad Nur. 2018. Seluas 85% Kawasan Hutan Mangrove Aceh Tamiang Rusak. http://walhiaceh.or.id/seluas-85-kawasan-hutan-mangrove-aceh-tamiang-rusak/.
Natalia Trita Agnika. 2016. Lahan Basah Asset Penting Bagi Lingkungan Hidup. https://www.wwf.or.id/?45402/Lahan-Basah-Aset-Penting-bagi-Lingkungan-Hidup.
Nyoman Suyadiputra. 2017. Keterlibatan Masyarakat pada kegiatan Rehabilitasi Mangrove. https://Indonesia.wetlands.org/id/news/keterlibatan-masyarakat-kegiatan-rehabilitasi-mangrove/
Ramsar. 2013. Laporan Kegiatan Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia, 2 Februari 2012 Di Desa Reroroja Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka.
143
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/wwd/12/Indonesia_report.pdf.
Ramsar. Ramsar sites around the world. https://www.ramsar.org/sites-countries/ramsar-sites-around-the-world.
.2012. Indonesias Newest Ramsar Site. https://www.ramsar.org/news/Indonesias-newest-ramsar-site. Ramsar. Wetland Indonesia. https://www.ramsar.org/wetland/Indonesia. Universitas Multi Media Nusantara. 2014. Jenis-jenis tanaman di hutan
Mangrove, https://wearemangroove.weebly.com/blog/-jenis-jenis-tanaman-di-hutan-mangrove.
Wahyu Chandra. 2014. Kebijakan Pemerintah Picu Degradasi Hutan Mangrove. https://www.mongabay.co.id/2014/03/26/kebijakan-pemerintah-picu-degradasi-hutan-mangrove/.
Wetlands International. international sustainable mangrove ecosystem https://Indonesia.wetlands.org/id/berita/international-conference-on-sustainable-mangrove-ecosystem/.
.Apa lahan basah itu. https://Indonesia.wetlands.org/id/wetlands/apa-lahan-basah-itu/.
2017. More Mangrove Please. https://Indonesia.wetlands.org/id/berita/more-mangroves-please/.
Yus Rusila Noor. 2016. Lahan Basah untuk masa depan kita, https://Indonesia.wetlands.org/id/berita/opini-lahan-basah-untuk-masa-depan-kita/.
145
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat
Ramsar, Iran, 2.2.1971 as amended by the Protocol of 3.12.1982 and the Amendments of 28.5.1987
Paris, 13 July 1994 Director, Office of International Standards and Legal Affairs United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
The Contracting Parties,
RECOGNIZING the interdependence of Man and his environment; CONSIDERING the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of water regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna, especially waterfowl; BEING CONVINCED that wetlands constitute a resource of great economic, cultural, scientific, and recreational value, the loss of which would be irreparable; DESIRING to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in the future; RECOGNIZING that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers and so should be regarded as an international resource; BEING CONFIDENT that the conservation of wetlands and their flora and fauna can be ensured by combining far-sighted national policies with co-ordinated international action;
Have agreed as follows:
Article 1
146
1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres. 2. For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent on wetlands.
Article 2
1. Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory for inclusion in a List of Wetlands of International Importance, hereinafter referred to as "the List" which is maintained by the bureau established under Article 8. The boundaries of each wetland shall be precisely described and also delimited on a map and they may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetlands, and islands or bodies of marine water deeper than six metres at low tide lying within the wetlands, especially where these have importance as waterfowl habitat. 2. Wetlands should be selected for the List on account of their international significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In the first instance wetlands of international importance to waterfowl at any season should be included. 3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive sovereign rights of the Contracting Party in whose territory the wetland is situated. 4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included in the List when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification or accession, as provided in Article 9. 5. Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands situated within its territory, to extend the boundaries of those wetlands already included by it in the List, or, because of its urgent national interests, to delete or restrict the boundaries of wetlands already included by it in the List and shall, at the earliest possible time, inform the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8 of any such changes. 6. Each Contracting Party shall consider its international responsibilities for the conservation, management and wise use of migratory stocks of waterfowl, both when designating entries for the List and when exercising its right to change entries in the List relating to wetlands within its territory
147
Article 3
1. The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far as possible the wise use of wetlands in their territory. 2. Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible time if the ecological character of any wetland in its territory and included in the List has changed, is changing or is likely to change as the result of technological developments, pollution or other human interference. Information on such changes shall be passed without delay to the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8. Article 4
1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or not, and provide adequately for their wardening. 2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts the boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible compensate for any loss of wetland resources, and in particular it should create additional nature reserves for waterfowl and for the protection, either in the same area or elsewhere, of an adequate portion of the original habitat. 3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and publications regarding wetlands and their flora and fauna. 4. The Contracting Parties shall endeavour through management to increase waterfowl populations on appropriate wetlands. 5. The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in the fields of wetland research, management and wardening. Article 5
The Contracting Parties shall consult with each other about implementing obligations arising from the Convention especially in the case of a wetland extending over the territories of more than one Contracting Party or where a water system is shared by Contracting Parties. They shall at the same time endeavour to coordinate and support present and future policies and regulations concerning the conservation of wetlands and their flora and fauna.
148
Article 6
1. There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review and promote the implementation of this Convention. The Bureau referred to in Article 8, paragraph 1, shall convene ordinary meetings of the Conference of the Contracting Parties at intervals of not more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at the written requests of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary meeting of the Conference of the Contracting Parties shall determine the time and venue of the next ordinary meeting. 2. The Conference of the Contracting Parties shall be competent:
a) to discuss the implementation of this Convention; b) to discuss additions to and changes in the List; c) to consider information regarding changes in the ecological character of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3; d) to make general or specific recommendations to the Contracting Parties regarding the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna; e) to request relevant international bodies to prepare reports and statistics on matters which are essentially international in character affecting wetlands; f) to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning of this Convention.
3. The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for wetlands management shall be informed of, and take into consideration, recommendations of such Conferences concerning the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna. 4. The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for each of its meetings. 5. The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under review the financial regulations of this Convention. At each of its ordinary meetings, it shall adopt the budget for the next financial period by a two-third majority of Contracting Parties present and voting. 6. Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of contributions adopted by unanimity of the Contracting Parties present and voting at a meeting of the ordinary Conference of the Contracting Parties.
149
Article 7
1. The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should include persons who are experts on wetlands or waterfowl by reason of knowledge and experience gained in scientific, administrative or other appropriate capacities. 2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote, recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple majority of the Contracting Parties present and voting, unless otherwise provided for in this Convention. Article 8
1. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources shall perform the continuing bureau duties under this Convention until such time as another organization or government is appointed by a majority of two-thirds of all Contracting Parties. 2. The continuing bureau duties shall be, inter alia:
a) to assist in the convening and organizing of Conferences specified in Article 6; b) to maintain the List of Wetlands of International Importance and to be informed by the Contracting Parties of any additions, extensions, deletions or restrictions concerning wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 5 of Article 2; c) to be informed by the Contracting Parties of any changes in the ecological character of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3; d) to forward notification of any alterations to the List, or changes in character of wetlands included therein, to all Contracting Parties and to arrange for these matters to be discussed at the next Conference; e) to make known to the Contracting Party concerned, the recommendations of the Conferences in respect of such alterations to the List or of changes in the character of wetlands included therein.
Article 9
1. This Convention shall remain open for signature indefinitely. 2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agencies or of the International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the International Court of Justice may become a Party to this Convention by:
a) signature without reservation as to ratification; b) signature subject to ratification followed by ratification; c) accession.
150
3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of ratification or accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as "the Depositary"). Article 10
1. This Convention shall enter into force four months after seven States have become Parties to this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9. 2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party four months after the day of its signature without reservation as to ratification, or its deposit of an instrument of ratification or accession. Article 10 bis
1. This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties convened for that purpose in accordance with this article. 2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party. 3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the organization or government performing the continuing bureau duties under the Convention (hereinafter referred to as "the Bureau") and shall promptly be communicated by the Bureau to all Contracting Parties. Any comments on the text by the Contracting Parties shall be communicated to the Bureau within three months of the date on which the amendments were communicated to the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Contracting Parties all comments submitted by that day. 4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in accordance with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written request of one third of the Contracting Parties. The Bureau shall consult the Parties concerning the time and venue of the meeting. 5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting. 6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties which have accepted it on the first day of the fourth month following the date on which two thirds of the Contracting Parties have
151
deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each Contracting Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into force on the first day of the fourth month following the date of the deposit of its instrument of acceptance. Article 11
1. This Convention shall continue in force for an indefinite period. 2. Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five years from the date on which it entered into force for that party by giving written notice thereof to the Depositary. Denunciation shall take effect four months after the day on which notice thereof is received by the Depositary. Article 12
1. The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this Convention as soon as possible of:
a) signatures to the Convention; b) deposits of instruments of ratification of this Convention; c) deposits of instruments of accession to this Convention; d) the date of entry into force of this Convention; e) notifications of denunciation of this Convention.
2. When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention. DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the English, French, German and Russian languages, all texts being equally authentic* which shall be deposited with the Depositary which shall send true copies thereof to all Contracting Parties.
* Pursuant to the Final Act of the Conference to conclude the Protocol, the Depositary provided the second Conference of the Contracting Parties with official versions of the Convention in the Arabic, Chinese and Spanish languages, prepared in consultation with interested Governments and with the assistance of the Bureau.