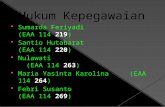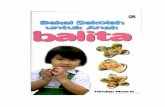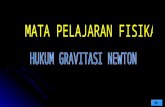Dialektika Hukum Progresif: Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo
Transcript of Dialektika Hukum Progresif: Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo
4
Dialektika Hukum Progresif
Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto
Rahardjo
Diandra Preludio R • Benny Prasetyo • Unu P
Herlambang • Muhtar Said • AP Edi Atmaja •
Benny Karya Limantara • Syandi Rama
Sabekti • Alfajrin A Titaheluw • Rian Adhivira
• Nindi Achid Arifki • Rahmad Syahroni
Rambe • Lilik Haryadi • James Marihot
Panggabean
Kaum Tjipian
2014
5
Dialektika Hukum Progresif
Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo
Diandra Preludio R, Benny Prasetyo, Unu P Herlambang,
Muhtar Said, AP Edi Atmaja, Benny Karya Limantara, Syandi
Rama Sabekti, Alfajrin A Titaheluw, Rian Adhivira, Nindi
Achid Arifki, Rahmad Syahroni Rambe, Lilik Haryadi, James
Marihot Panggabean
© Kaum Tjipian, 2014
Diterbitkan pertama kali dalam format buku digital (e-book)
Desember 2014
140 halaman; 12 x 18 cm
1. Ilmu Hukum 2. Satjipto Rahardjo
3. Hukum Progresif
Penyunting: AP Edi Atmaja
Perancang Sampul: AP Edi Atmaja
Penata Isi: AP Edi Atmaja
Kaum Tjipian
d/a Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, SH, Nomor 1, Semarang
Cetakan I: 2014
6
Sekapur Sirih
BUKU ini memuat serampai karangan mengenai sebagian
(kecil) buku-buku anggitan Prof Dr Satjipto Rahardjo, SH.
Sang begawan hukum yang karib disapa Prof Tjip itu
mewariskan banyak sekali buku pasca-wafatnya, bahkan ada
buku yang terbit benar-benar setelah Prof Tjip meninggal
dunia.
Karangan-karangan dalam buku ini tidak (pernah)
berpretensi untuk memfatwakan kebenaran. Bahkan dari
teks yang paling terang-benderang pun pasti tersembunyi
keremang-remangan. Bukan maksud buku ini untuk
meringkus dan meringkas pemikiran Prof Tjip dalam sebutir
tablet yang siap-minum—kendati mesti diakui bahwa para
pengarang (kami menyebutnya “pemantik”) terdiri dari
golongan yang boleh dibilang “penafsir garda depan”
pemikiran Prof Tjip.
Para pemantik yang seluruhnya merupakan mahasiswa
dan alumnus Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro,
itu tergabung dalam komunitas diskusi yang menamakan
diri Kaum Tjipian.
Kaum Tjipian, entah generasi yang keberapa, saban
Senin sore, tepat pukul 15.00 WIB, menyelenggarakan
diskusi (kami menyebutnya “jagongan”) perihal buku-buku
Prof Tjip. Lokasinya nomaden, sesuai pesanan. Di ruang
kelas yang suntuk, di bawah pohon beralaskan tikar
ditemani semilir angin sepoi-sepoi laiknya Rabindranath
7
Tagore dan murid-muridnya, hingga di emperan gedung di
mana para gadis berseliweran menggoda iman pun jadilah.
Alhasil, dari kongko-kongko yang mempertaruhkan iman
itu lahirlah buku mungil yang tak bisa lebih tebal dari
Nietzsche (2012) ini.
Barangkali terasa kasip mengingat karangan-karangan
ini berhasil dijilid dan terbit lebih dari dua tahun setelah
mereka disampaikan dalam jagongan rutin. Namun, adakah
yang terlambat untuk ide-ide? Kami hanya coba merawat
pemikiran guru kami, Profesor Satjipto Rahardjo. Syukur-
syukur kalau buku ini dapat memantik letupan lanjutan yang
jauh lebih bermutu.
Akhirnya, buku ini hanyalah kado dari anak-anak muda
ingusan yang mengaku-aku sebagai penafsir garda depan
Prof Tjip, yang lahir pada 15 Desember 1930. Tapi apalah
arti penafsir garda depan jikalau memperkenankan pikiran
menampik penolakan, kritik, dan makian. Oleh sebab itu,
melalui penerbitan buku ini, kami Kaum Tjipian mengharap
penolakan dari siapa pun Anda.
Pekanbaru, 28 Desember 2014
Penyunting
8
Senarai Isi
Sekapur Sirih — 6
Senarai Isi — 8
Bab I Sebelum
Hukum dalam Jagat Ketertiban — 11
Diandra Preludio R
Diskursus mengenai Hukum dan Masyarakat — 23
Benny Prasetyo
Mempelajari Keteraturan, Menjumpai Ketidakteraturan:
Pembacaan Seorang Cantrik — 36
Unu P Herlambang
Sosiologi Hukum: Pengamat atau Pemberi Solusi? — 43
Muhtar Said
Bab II Semasa
Kapita Selekta Hukum Progresif: Pada Mulanya adalah Koran — 56
AP Edi Atmaja
Dasar-dasar Hukum Progresif — 65
Benny Karya Limantara
Hukum Progresif dan Keberanian Kita — 73
Syandi Rama Sabekti
9
Kredo Penegakan Hukum Progresif — 78
Alfajrin A Titaheluw
Bab III Sesudah
Dinamika dalam Mengikuti Perubahan Sosial — 85
Rian Adhivira
Mendudukkan Undang-Undang Dasar? — 94
Nindi Achid Arifki
Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia — 105
Rahmad Syahroni Rambe
Polisi Indonesia di Tengah Perubahan Sosial — 115
Lilik Haryadi
Rakyat Bahagia di Negara Hukum — 122
James Marihot Panggabean
Para Pemantik — 135
11
Hukum dalam Jagat Ketertiban1
DIANDRA PRELUDIO RAMADA
“… Law grows with the growth, and strengthens with the
strength of the people, and finally dies away as a nation
loses its nationality …” –Karl Von Savigny
SUNGGUH, penulis menyimpan kedukaan yang sangat
mendalam ketika tanpa alasan yang jelas penulis memilih
buku ini untuk diceritakan kembali menurut pemahaman
penulis sendiri. Kesedihan itu datang saat penulis merasa
bahwa penulis belum sanggup menyerap seluruh inti sari
dari buku Hukum dalam Jagat Ketertiban ini. Jadi, penulis
mengharap pemakluman yang teramat sangat bagi Anda
yang telanjur membaca tulisan ini.
Apa yang dipaparkan dalam kumpulan tulisan Prof
Satjipto Rahardjo ini merupakan penjelajahan yang tak
kunjung henti dari seorang musafir pencari kebenaran.
Keprihatinan Prof Tjip (sebutan akrab bagi Prof Satjipto
Rahardjo) terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, yang
dinyatakan baik berupa lisan maupun tulisan, sering
membuat banyak kalangan, para akademisi, serta praktisi
1 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Hukum dalam JagatKetertiban (Jakarta: UKI Press, 2006) anggitan Satjipto Rahardjo, inidisampaikan dalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada 19 November 2012di Beranda Auditorium Imam Bardjo, SH, Universitas Diponegoro.
12
hukum terhenyak dan mengerutkan kening. Salah satu
kritiknya adalah hukum telah cacat sejak dilahirkan—yang
dianggap Prof Tjip sebagai tragedi hukum.2
Modernisasi, industrialisasi, rasionalisasi, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa dekade
terakhir dipengaruhi gelombang besar di mana negara-
negara di dunia berusaha mencapai status yang lebih baik.
Tak dapat dimungkiri, kita masih berada pada
keterbelakangan ekonomi, politik, sosial, ilmu, dan
sebagainya sehingga, mau tidak mau, hukum modern itulah
yang kemudian dijadikan pisau bedah terhadap masalah-
masalah hukum yang timbul. Tatkala para praktisi “latah”
membaca dan memaknai undang-undang dari perspektif
yuridis-normatif belaka dan berujar bahwa hukum harus
diutamakan agar membawa ketertiban, ketenteraman, dan
kesejahteraan bagi masyarakat. Prof Tjip mengambil sikap
berbeda. Menurut dia, hukum itu menempati satu sudut
kecil dalam jagat ketertiban.3
2 Masyarakat diatur oleh hukum yang penuh cacat, karenaketidakmampuannya merumuskan secara tepat hal-hal yang ada dimasyarakat. Tentu saja kritik tersebut merupakan palu godam bagilembaga legislatif, penegak hukum, dan insan hukum yang hanyamelandaskan hukum hanya sebagai peraturan perundang-undangan.Padahal menurut refleksi kritis Prof Tjip, hukum dilukiskan sebagaiperilaku manusia, yang didasarkan pada pemikiran filosofis bahwa hukumuntuk manusia dan bukan sebaliknya. Satjipto Rahardjo, “Tidak menjadiTawanan Undang-undang”, dalam Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm 120.3 Hukum tidak bisa menepuk dada dalam menyelesaikan segalapersoalan. Ilmu hukum harus membuka diri terhadap ilmu-ilmu lain agardapat memosisikan diri menurut jati dirinya. Bandingkan dengan FrancisFukuyama yang mempertanyakan “Where do norms come from?” dalamFrancis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and theReconstitution of Social Order (London: Profile Books, 1999), hlm 143-153).
13
Wajah Hukum dalam Perkembangan
Buku Hukum dalam Jagat Ketertiban ini berisi kumpulan
karya tulis Prof Tjip. Dia mengawalinya dengan sebuah
konstruksi tentang sejarah hukum. Dimulai dengan Rene
Descartes yang memisahkan manusia sebagai makhluk
“yang mengetahui” dari alam “yang untuk diketahui”,
dengan ucapan terkenalnya cogito ergo sum. Descartes
ingin menyatakan bahwa manusia baru memperoleh makna
setelah dengan rasionya memberi arti.4
Pemikiran tersebut
memberi pengaruh yang sangat besar terhadap
perkembangan teorisasi ilmu pengetahuan. Logika dan
rasionalitas menjadi sesuatu yang sangat bermakna dalam
pencarian manusia terhadap dirinya. Namun, seiring dengan
perkembangan pengetahuan tentang manusia sebagai
makhluk seutuhnya yang berperasaan dan berketuhanan,
kecerdasan intelektual (IQ) yang dulu begitu dibanggakan
harus diimbangi dengan kecerdasan emosional (EQ) dan
kecerdasan spiritual (SQ) dalam rangka membangun
4 Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata (Yogyakarta: Duta WacanaUniversity Press, 1990), hlm 246.
Satjipto Rahardjo (1930-2010)
14
kecerdasan berlipat (multiple intelligence).
Positivisme menanamkan kaki ilmu pengetahuan dengan
mengamati alam dan kehidupan di sekelilingnya. Sekalian
peristiwa yang tidak terdapat di situ tidak boleh dijadikan
objek ilmu pengetahuan. Semua harus bisa diamati secara
fisik, diukur dan ditimbang. Menggunakan rasio sebagai alat
analisis sejak Francis Bacon (metode induksi) dan Descartes
(metode rasional) di Abad Pencerahan (Enlightment,
Aufklarung), maka ilmu pengetahuan mulai secara agresif
berusaha menguasai objeknya dengan cara mengotak-
kotakkan, memisah-misahkan, memfragmentasi, menyis-
temisasi, mengorganisasi, dan sebagainya.
Ilmu pengetahuan memang berkembang dengan sangat
pesat dengan metode seperti itu, namun perkembangannya
membawa problem tersendiri. Ternyata, dengan hilangnya
keutuhan itu, hilang pulalah kebenaran sejati. Akhirnya,
suatu entitas utuh tidak berhasil didekati, apalagi dijelaskan
oleh sains atau teori yang telah mereduksi keutuhan itu
menjadi kepingan-kepingan yang terbatas. Agar teori
seperti itu tetap bisa digunakan, dilakukanlah manipulasi
kebenaran, yaitu dengan cara membuang sebagian realitas
sehingga menyisakan realitas yang hanya bisa dijelaskan
oleh teori itu.
Tidak ketinggalan ilmu hukum juga ikut menggunakan
model positivisme tersebut. Apabila abad kesembilan belas
disebut sebagai abad positivisme, itu akan sangat bisa
dimengerti seiring kehadiran hukum modern yang menjadi
bagian penataan masyarakat secara rasional. Sejak saat itu,
hukum menjadi institusi yang terang (distinct), baik dalam
15
substansi, metodologi, maupun administrasinya.5
Studi
hukum di awal abad keduapuluh diawali dengan
perkembangan menarik, yakni studi hukum yang ditarik
keluar dari ranah peraturan perundang-undangan dengan
kemunculan aliran sociological jurisprudence yang
dipelopori oleh Roscoe Pound.
Berkembanglah sistem produksi ekonomi kapitalis yang
mendasarkan pada perhitungan efisiensi yang bercirikan
semuanya harus bisa dihitung dengan jelas dan pasti.
Berapa barang dan ongkos produksi, penjualan, pembelian,
dan sebagainya. Ini berbeda dengan sistem ekonomi lama
yang didasarkan atas kebutuhan, bukan perhitungan.
Rasionalisasi sistem ekonomi tersebut membutuhkan orde
sosial baru yang harus dapat dimasukkan ke dalam
komponen produksi dan bisa dihitung. Sedangkan orde
sosial lama dengan konsep struktur yang tidak eksak dan
terkesan kacau (chaotic) dapat mengganggu kelancaran
sistem produksi ekonomi yang telah menjadi rasional dan
kapitalis.
Hukum modern tampil menjawab kebutuhan zaman itu.
Capaian hukum modern yang menjawab tantangan tersebut
adalah tertulis dan publik. Ini sangat mendukung kebutuhan
sistem ekonomi baru yang membutuhkan prediktabilitas.
Negara dan hukum modern adalah sebuah rekonstruksi
rasional yang dibangun di atas puing-puing tatanan lama.
Namun, seperti diketahui, modernisme sejak awal telah
menyimpan bibit penyakit dari modernisasi itu sendiri.
Semakin jauh berjalan, cacat dan penyakit itu semakin
5 Dalam hal substansi, hukum mengandalkan peraturan yang ia produksisendiri, yaitu legislated rules. Roberto Mangabeira Unger, Law in ModernSociety (New York: Free Press, 1976).
16
terlihat dan terbuka. Hukum modern dengan asas kepastian
hukumnya meluluh-lantakkan orde sosial lama yang bersifat
lebih otentik, alami, dan sosiologis. Hukum modern secara
gamblang menyamaratakan eksistensi tiap-tiap kelompok
masyarakat yang nyata-nyata berbeda. Pondasi hukum
modern yang dibangun berdasarkan rasionalitas dianggap
tidak mampu untuk melingkupi segala bentuk permasalahan
yang terjadi di masyarakat.
Boaventura de Sousa Santos berpendapat bahwa kita
sekarang berada di tengah-tengah dinamika
ketidakseimbangan, antara prinsip regulasi dan emansipasi
yang oleh dia disebut sebagai transisi paradigmatik
(paradigmatic transition).6
Posmodernisme dimulai dari
pemikiran kritis mengenai modernitas itu sendiri. Balkin
berpendapat bahwa posmodernisme adalah kelanjutan
dalam bentuk perkembangan dan reaksi terhadap suatu
periode dalam sejarah manusia yang disebut modernitas.7
Hukum dalam Jagat Ketertiban
Bagian kedua buku ini memuat kajian Prof Tjip mengenai
jagat ketertiban. Jagat ketertiban menampilkan suatu
6 Menurut Santos, kita sekarang berada dalam masa transisi yang selamaduaratus tahun berlangsung ekses regulasi atas kerugian emansipasi. Titikberat ada pada regulasi, istilah yang dipakai Santos untuk modernisme,yang mencoba untuk mengubah keadaan chaos menjadi tertib. Arahemansipasi adalah dari ketidaktahuan menuju keadaan tahu, yang olehSantos disebut dari kolonialisme menuju solidaritas. Di sini,posmodernisme ingin membalikkan keadaan dinamikaketidakseimbangan itu menjadi keuntungan emansipasi (to reassess theknowledge-as-emancipation and grant its primacy over knowledge-as-regulation). Boaventura de Sousa Santo, Toward A New Common Sense:Law, Science, and Politics in Paradigmatic Transition (New York:Routledge, 1995).7 JM Balkin, “What is Postmodern Constitutionalism?” dalam DennisPatterseon (ed.), Postmodern and Law (Darmouth: Aldershot, 1994).
17
jaringan yang kompleks. Jagat ketertiban itu meliputi dan
menerima kehadiran komunitas yang majemuk sehingga
ketertiban juga menjadi kompleks. Kompleksitas inilah yang
menjadi basis ketertiban-ketertiban lain. Ketertiban
ekonomi, misalnya, juga tidak dapat meminggirkan
ketertiban lain, seperti hukum dan politik.
Sejak hukum menempati satu sudut saja dalam jagat
ketertiban yang jauh lebih luas dan sejak hukum negara
ingin memegang hegemoni, kita pantas mempertanyakan
bagaimana hukum negara itu berinteraksi dengan
komunitas-komunitas lain dalam jagat ketertiban.8
Komunitas lain tersebut ternyata tidak bisa ditundukkan
oleh kekuasaan dan kedaulatan hukum negara. Saat
berbicara tentang akses terhadap keadilan, Marc Galanter
berbicara tentang apa yang ia sebut sebagai “justice in many
rooms”.9
Sekalipun perkara dibawa ke pengadilan untuk
diselesaikan, tidak selalu pengadilan yang benar-benar
memutus.
Ellickson mengatakan bahwa yang lebih menentukan
bagaimana ketentuan-ketentuan dalam hukum diwujudkan
bukanlah hukum itu sendiri, melainkan rakyat sebagai
adressat hukum.10
Ellickson menambahkan, betapa banyak
8 Komunitas lain ini adalah kaidah-kaidah sosial yang didukung olehkomunitasnya masing-masing. Satjipto Rahardjo, Hukum dalam JagatKetertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm 100.9 Tulisan Galanter memberitahu kita tentang kompleksitas dari institusipengadilan yang tidak bisa dimonopoli oleh pengadilan negara. Kalaudikatakan bahwa orang mencari keadilan bagi perkara yang dihadapi,muncul pertanyaan: di mana keadilan itu? Di mana tempatnya? Siapaatau apa yang memberikan keadilan itu? Marc Galanter, “Justice in ManyRooms” dalam Mauro Cappelletti (ed.), Acces to Justice and the WelfareState (Sijthoff: Alphen aan den Rijn, 1981).10 Peraturan hanya sebagai titik tolak. Rakyatlah yang akan menawarperaturan itu untuk keuntungan mereka. Robert C Ellickson, Order
18
segmen kehidupan sosial itu tidak dibentuk oleh atau
merupakan karya hukum, melainkan oleh komunitas itu
sendiri. Jadi tidak benar ungkapan “hukum dan ketertiban”
di mana digambarkan bahwa negara mengontrol perilaku
anggota masyarakat. Itu bohong sama sekali.11
Hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks
sosio-kultural. Itulah awal dari apa yang kita sebut sebagai
budaya hukum. Bagaimanapun, hegemoni hukum negara itu
tidak pernah sepenuhnya berhasil memastikan apa yang
diwajibkan berlaku dalam masyarakat. Masyarakat akan
menuntun, membatasi, dan menentukan seberapa jauh dan
bagaimana hukum itu akan nyata-nyata berjalan, bekerja,
dan berlaku dalam masyarakat. Mengatur masyarakat tidak
berarti harus melakukannya secara penuh atau total. Maka
dari itu, pengaturan tidak perlu melakukan intervensi dan
penetrasi penuh ke dalam kehidupan masyarakat. Jika
kepedulian kita adalah manusia dan masyarakat, maka bisa
dengan membuat suatu skema besar, sedangkan proses-
proses nyata diserahkan kepada masyarakat. Inilah yang
disebut mengatur kehidupan yang sudah berjalan.12
without Law: How Neighbors Settle Disputes (Cambridge: HarvardUniversity Press, 1991).11 Ketertiban lebih sering muncul secara serta merta. Peraturan yangdibuat oleh negara akan dilengkapi bahkan isinya bisa diganti denganaturan menurut mereka sendiri. Ellickson menepis anggapan bahwanegara atau pemerintahlah yang mengendalikan koordinasi danmengarahkan. Loc. cit.12 Jepang merupakan contoh bagus untuk penggambaran tentang ini.Dengan keteguhan mempertahankan tradisi nilai-nilai Jepang,penegakkan hukum formal di Jepang tergolong lemah. Hukum memangada, tetapi ia hanya sebatas kekuasaan untuk mengatur, sedangkanpelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat. Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm 89.
19
Dari segala pemaparan di atas, sampailah kita pada apa
yang selalu Prof Tjip dengung-dengungkan. Ya, benar:
hukum progresif. Dijelaskan oleh Prof Tjip dalam buku ini,
bahwa yang akan secara penuh diorientasikan untuk
dibicarakan adalah mengenai penafsiran hukum yang
progresif.
Sejak hukum dikodifikasikan menjadi teks, pembacaan
terhadap teks menjadi penting sekali. Maka, penafsiran
hukum tidak dapat dihindarkan, dan hampir tidak mungkin
hukum dapat dijalankan tanpa membuka pintu bagi
penafsiran. Lalu diajukanlah sebuah adagium, “membaca
hukum adalah menafsirkan hukum”, dan yang mengatakan
bahwa teks hukum sudah jelas adalah suatu cara saja bagi
pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-
diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk
memberikan penjelasan.13
Pertama, persoalan bahasa. Pertanyaan dasarnya,
mampukah bahasa mewadahi pemikiran yang akan kita
sampaikan? Menurut saya tidak. Hemat saya, tiap kali suatu
pemikiran akan dituangkan ke dalam kalimat, ia akan
mengalami risiko kegagalan. Artinya, pemikiran tersebut
menjadi kurang utuh begitu dirumuskan ke dalam bahasa.
Selalu ada nuansa, makna yang tercecer, atau tidak
terwadahi dalam bahasa tulis.
Kemudian, yang mengejutkan, jika bahasa menjadi
kendaraan untuk menyampaikan pemikiran ke dalam
undang-undang, maka sesungguhnya hukum Indonesia
pascakolonial harus dibaca lewat teks yang asli, yaitu bahasa
Belanda. Dengan demikian, teks-teks terjemahan dari
bahasa Belanda itu tidak sah, baik secara linguistik maupun
13 Ibid., hlm 163.
20
secara hukum. Jadi selama ini hukum di Indonesia itu
dijalankan berdasarkan konvensi atau tradisi saja. Sebagai
akibatnya, andaikata ada dua orang menerjemahkan teks
asli Belanda ke bahasa Indonesia, kemungkinan besar akan
ada dua naskah terjemahan yang berbeda dan keduanya
adalah “sah”. Dalam bukunya tentang Mahkamah
Agung Indonesia, Sebastian Pompe menunjuk pada
kemampuan berbahasa Belanda di kalangan para hakim
yang hampir nol, sebagai salah satu penyebab menurunnya
kualitas putusan pengadilan di Indonesia.14
Kedua, penafsiran itu sendiri dalam membaca teks
peraturan hukum tertulis. Pembuatan dan penafsiran
merupakan dua sisi dari barang yang sama, yaitu hukum.
Teks hukum tidak lain adalah suatu rumusan bentuk
konseptualisasi dari apa yang terjadi di alam. Misalnya,
pencurian yang merupakan peristiwa alam yang dirumuskan
ke dalam teks hukum. Setiap perumusan adalah pencitraan
tentang suatu hal. Pencitraan adalah pembuatan konsep.
Pembuatan konsep melahirkan pembeda antara apa yang
dirumuskan dengan yang tidak. Sedangkan perumusan
konsep pemikiran menjadi tekstual akan berhadapan
dengan risiko kegagalan yang hampir pasti.
Menurut Jakob Sumardjo, dalam adat Jawa terdapat
setidaknya limabelas macam pencurian. Hal itu berarti untuk
komunitas Jawa, Pasal 362 KUHP mengandung cacat besar,
karena pasti tidak mampu merumuskan kelimabelas macam
itu secara benar hanya dalam satu kalimat.15
Sehingga, di
14 Sebagai negeri bekas jajahan Belanda, banyak teks hukum yangberbahasa Belanda, yang sialnya masih dirujuk oleh para hakim denganpengetahuan bahasa Belanda yang sangat rendah. S van HoeijSchilthouwer Pompe, The Indonesia Supreme Court: Fifty Years of JudicialDevelopment, Disertasi, 1996.15 Jakob Sumardjo dalam Satjipto Rahardjo, op. cit.., hlm 166.
21
sinilah peran penafsiran sebagai jembatan untuk jurang
yang menganga antara objek yang dirumuskan dan
perumusannya.
Pekerjaan merumuskan akan melibatkan penilaian. Ini
mengapa legislatif mereduksi kenyataan menjadi seperti ini
atau itu, yang ditentukan oleh penilaian manusia-manusia di
belakangnya. Oleh karena itu, rumusan yang diproduksi
tidak bebas nilai, dan karena itu terbuka untuk penilaian
yang berbeda. Maka dari itu, penafsiran adalah pekerjaan
untuk dapat “membenarkan”, “meluruskan”, “membumikan”,
dan “mengadilkan” hukum.
Memasuki ranah penafsiran adalah memasuki ranah
yang luas yang di dalamnya dipenuhi pemikiran dan aliran-
aliran. Ada pendapat yang mengatakan bahwa menafsirkan
hukum tidak boleh melalui batas-batas yang sudah dibuat
oleh legislatif dalam ranah rumusan hukum tersebut.
Pendapat ini menganggap bahwa teks hukum memiliki
otonomi mutlak sehingga tidak boleh ada hal baru dalam
penafsiran. Pemikiran tersebut melebarkan jurang yang
memisahkan hukum dengan masyarakat. Hukum benar-
benar menjadi dunia yang esoteris. Kekakuan pandangan
seperti itu menjauhkan hukum dari keadilan dan kebutuhan
masyarakat.
Kemudian, pendapat kedua yang menganggap bahwa
hukum hanya sebagai aturan yang kadang bisa ditepiskan.
Melihat hukum sebagai institusi yang ada dalam masyarakat,
pendapat yang dipelopori aliran realisme ini memilih untuk
melakukan pembebasan penafsiran yang bisa keluar dari
lingkup rumusan peraturan yang ada. Maka, Paul Scholten
22
mengatakan bahwa “keadilan dalam hukum itu ada, tetapi
masih harus ditemukan”.16
Hukum progresif berpegangan pada paradigma “hukum
untuk manusia”. Kemanusiaan menjadi primus pada saat kita
memberi kedudukan terhadap hukum dan masyarakat.
Hukum berawal tidak dari hukum itu sendiri, melainkan dari
manusia dan kemanusiaan. Membicarakan hukum haruslah
lebih dahulu diawali dengan membicarakan dan
menuntaskan pembicaraan mengenai kemanusiaan. Kita pun
tidak dapat membicarakan hukum dengan menutup pintu
bagi kemanusiaan karena kemanusiaan akan terus mengalir
memasuki hukum. Maka, jadilah hukum bukan untuk dirinya
sendiri melainkan untuk mengabdi dan melestarikan
kemanusiaan.
Demikian sang begawan telah merintis jalan pembuka
bagi penerus-penerusnya. Kini tinggal kita para penerus Prof
Tjip melakukan apa yang kita harus dan bisa lakukan.
Kerinduan yang sangat sederhana dan lugas tapi sangat
dalam dari dirinya adalah agar para mahasiswanya menjadi
lilin-lilin pembawa terang dalam kegelapan yang
menyelimuti nuansa keilmuan di dunia, khususnya ilmu
hukum. Dengarlah pesan terakhir Sang Guru:
“...di pundak saudara-saudaralah hukum progresif itu
memperoleh bentuknya. Saya hanya merintis jalan…” []
16 Paul Scholten dalam Satjipto Rahardjo, op. cit., hlm 171.
23
Diskursus mengenai Hukum dan
Masyarakat17
BENNY PRASETYO
BAGI negara-negara yang sedang berkembang, yaitu negara
yang memperoleh kemerdekaannya sesudah Perang Dunia
II, pembangunan merupakan semacam panacea, satu-
satunya jalan yang harus ditempuh untuk memerdekakan
diri dari segala tuntutan dan kesulitan. Indonesia juga tidak
merupakan kekecualian dalam hal ini. Sejak Soeharto
mengambil alih tampuk kekuasaan, secara pasti negara ini
menempatkan diri di barisan negara sedang berkembang
yang memberikan prioritas pertama kepada pembangunan.
Memperhatikan fungsi hukum dalam masyarakat, yang
memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif
antaranggota masyarakat, kiranya sulit bagi kita untuk
memikirkan suatu masyarakat yang dapat berjalan tanpa
menerima pelayanan hukum. Keadaan ini menjadi lebih jelas
lagi apabila kita berhadapan dengan masyarakat yang ridak
lagi tradisional di mana kontak-kontak pribadi serta konflik-
konflik kepentingan terjadi lebih intensif. Keadaan ini tidak
berubah pada masyarakat yang sedang berada dalam masa
17 Karangan, yang merupakan ringkasan dari buku Hukum danMasyarakat (Bandung: Angkasa, 1980) anggitan Satjipto Rahardjo, inidisampaikan dalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada 15 Oktober 2012 diRuang C104, Gedung Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
24
pembangunan. Sekalipun demikian, di masa seperti itu,
kedudukan hukum menjadi problematis berhubungan
dengan adanya pergeseran dalam prioritas kegiatan negara.
Lalu, sampailah pada masalah hubungan antara hukum
dan pembangunan. Hukum merupakan suatu kebutuhan
yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu
sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama
anggota masyarakat, sehingga
terdapat kepastian dalam lalu
lintas hubungan itu. Dengan
demikian, mudah dimengerti
bahwa perubahan-perubahan
yang terjadi di masyarakat
pada gilirannya akan
menyebabkan terjadinya
perubahan pada hukum yang
harus melayani masyarakat itu.
Apabila untuk keperluan
pembangunan dibutuhkan
masuknya modal luar negeri,
perombakan susunan kepemilikan tanah, penyediaan tanah
untuk pembuatan jalan-jalan, pabrik, jembatan, dan
sebagainya, maka hukum akan diminta jasanya untuk
menyusun peraturan-peraturan atau sistem peraturan baru
yang memungkinkan dilaksanakannya rencana tersebut.
Pada 1972, suatu pertemuan yang menghimpun ahli-ahli
yang menaruh minat pada studi tentang hukum dan
pembangunan (law and development) telah mencoba untuk
menyusun satu kesepakatan pendapat mengenai seluk-
beluk penelitian di bidang hukum dan pembangunan.
Disebutkan bahwa pertalian antara hukum dan
pembangunan sebagai suatu proses mengubah masyarakat
itu dapat bermacam-macam. Hukum dapat dilihat sebagai
25
suatu alat yang digunakan secara sadar oleh manusia untuk
mengubah lingkungan hidupnya.
Pendapat tadi mempunyai banyak pengikut sekalipun
mereka tidak sepaham mengenai kegunaan dan pentingnya
hukum untuk menimbulkan perubahan sosial. Kelompok lain
lagi berpendapat bahwa hukum merupakan suatu nilai, atau
suatu proses yang fundamental dalam perwujudan nilai-nilai
tertentu, sehingga ia menjadi terkait erat dengan nilai-nilai
itu sendiri. Misalnya saja, banyak orang percaya bahwa
hukum itu penting untuk melindungi perorangan serta
perwujudan kesamaan. Mereka juga percaya bahwa
pengembangan lembaga-lembaga hukum serta proses-
prosesnya, sehingga menjadi efektif, akan dapat
memberikan bantuannya untuk memperkuat hak-hak
seseorang dan untuk mencapai kesamaan.
Dari pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa
orang mulai mengkaji tentang fungsi hukum di masyarakat.
Dan pada itu juga dapat dilihat bahwa sasaran pembicaraan
bukan berkisar pada hukum sebagai suatu sistem yang
konsisten, logis, dan tertutup, melainkan sebagai sarana
untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan dalam
pembangunan atau perubahan masyarakat. Dengan
demikian, pembicaraan mengenai hukum telah membaurkan
diri dengan pembicaraan tentang aksi-aksi sosial, tentang
hukum sebagai proses dan sebagainya.
Tingkat studi tentang hukum dewasa ini masih lebih
banyak berkisar pada pemahaman dan analisis hukum
secara dogmatis: melihat hukum terutama sebagai suatu
sistem yang logis dan konsisten. Keadaan yang demikian itu
menyebabkan bahwa dewasa ini dibutuhkan adanya
perubahan dalam pemahaman kita mengenai hukum atau
26
secara lebih tepat mengenai hubungan antara hukum dan
masyarakat.
Studi terhadap Hukum dan Masyarakat
Pemikiran hukum sosiologis
Pemikiran hukum sosiologis mulai dikembangkan tidak
lebih awal dari permulaan abad keduapuluh. Sebelum itu,
apabila orang memikirkan tentang hukum dan keadilan, ia
tidak segera melihat perkaitannya dengan tertib masyarakat
yang lebih luas di mana hukum itu berlaku atau di mana ide-
ide tentang keadilan itu dianut.
Rescoe Pound membedakan antara ahli hukum dengan
kerangka berpikir sosiologis dan ahli hukum dari aliran yang
lain. Perbedaan itu, menurut Pound, adalah bahwa mereka
yang termasuk aliran sosiologis ini:
lebih mengarahkan penglihatannya kepada beker-
janya hukum daripada kepada isinya yang abstrak;
memandang hukum sebagai suatu lembaga sosial
yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia
dan menganggap kewajiban mereka untuk mene-
mukan cara–cara terbaik dalam memajukan dan
mengarahakan usaha sedemikian itu;
lebih menekankan kepada tujuan-tujuan sosial yang
dilayani oleh hukum daripada sanksinya;
menekankan bahwa aturan-aturan hukum itu harus
lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai
hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat dan
tidak sebagai kerangka yang kaku.
27
Hukum dan nilai-nilai masyarakat
Tentang bekerjanya hukum di masyarakat, Robert B
Seidman menguraikan dalil-dalil sebagai berikut.
Setiap peraturan hukum memuat tentang bagaimana
pemegang peranan (masyarakat/role occupant)
diharapkan untuk bertindak.
Bagaimana seorang pemegang peranan akan
bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan
hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang
ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari
lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan
kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya.
Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan
bertindak sebagai respons terhadap peraturan
hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan
hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-
sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan
sosial, politik, dan lainnya, yang mengenai diri
mereka serta umpan-umpan balik (feedback) yang
datang yang datang dari pemegang peranan.
Bagaimana para pembuat undang-undang akan
bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan
yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-
sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan
sosial, politik, ideologis, dan lain-lain, mengenai diri
mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari
pemegang peranan serta birokrasi.
Dari dalil-dalil tersebut, dapatlah diketahui bahwa setiap
anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan
tingkah lakunya oleh peranan yang diharapkan, baik oleh
norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di
luar hukum.
28
Regenerasi atau penerapan hukum hanya dapat terjadi
melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor
manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya
dalam hubungan dengan bekerjanya hukum, membawa kita
kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya
manusia di masyarakat.
Dalam pembentukan hukum, di mana dijumpai
pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan,
Schuyt menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan yang
dapat timbul, yakni (1) sebagai sarana untuk mencairkan
pertentangan (conflict loosing) dan (2) sebagai tindakan
yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut
(conflictversterking).
Hukum diciptakan untuk dijalankan. “Hukum yang tidak
pernah dijalankan pada hakikatnya telah telah berhenti
menjadi hukum,” demikian Scholten. Hukum tidak dapat
bekerja atas dasar kekuatannya sendiri. Dengan perkataan
lain, hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia.
Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk
pelaksanaan hukum yang telah dibuat masih diperlukan
campur tangan manusia.
Schuyt menambahkan, tujuan hukum yang kemudian
harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksananya itu adalah
sangat umum dan kabur sifatnya. Ia menunjuk pada nilai-
nilai keadilan, keserasian, dan kepastian hukum sebagai
tujuan-tujuan yang harus diwujudkan hukum dalam
kehidupan sehari-hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan
yang hendak dilaksanakan hukum inilah, sekalipun
organisasi-organisasi yang dibentuk bertujuan untuk
mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ
itu dipakai untuk mengembangkan pendapatnya sendiri-
sendiri mengenai tujuan hukum. Dengan demikian,
29
organisasi-organisasi seperti pengadilan, kepolisian,
lembaga legislatif, dan sebagainya, menjalani kehidupannya
sendiri, serta mengejar tujuannya sendiri pula.
Selznick mengatakan, dewasa ini dapat dikenali adanya
konflik antara dua pandangan hukum: yang pertama melihat
hukum sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja,
sementara yang kedua berpendapat bahwa hukum itu
mencita-citakan tercapainya tujuan-tujuan moral.
Dalam konsep hukum yang normatif, yaitu yang
membebani hukum dengan tugas-tugas untuk mewujudkan
nilai-nilai, kehadiran hukum di masyarakat itu tidak hanya
sekadar didorong oleh keharusan sosial, melainkan juga
karena ada tugas-tugas yang harus dijalankannya. Konsep
tersebut selanjutnya menerima adanya nilai-nilai laten yang
terdapat dalam hukum, yang akan bekerja sebagai sumber
referensi bagi penilaian terhadap hukum. Nilai-nilai yang
menjadi dasar penilaian itu bukannya diadakan oleh orang
yang melakukan pengamatan, melainkan ia berada secara
inheren dalam fenomena ketertiban itu sendiri (inner order
of the phenomenon).
Dalam pengertian rule of law, Selznick melihat adanya
ide hukum yang dikaitkan dengan suatu tertib tertentu.
Sekalipun ungkapan rule of law itu hanya dimaksudkan
untuk hanya bekerja secara deskriptif dan bebas dari nilai
tertentu, ungkapan tersebut sebetulnya bersifat konotatif
dan merupakan ide yang sarat dengan nilai.
30
Hukum dan Perubahan Sosial
Perubahan sosial
Timbulnya golongan menengah telah merubah susunan
dan keseimbangan masyarakat yang semula ditentukan oleh
golongan ningrat, perwira, dan agama. Selanjutnya,
timbulnya golongan buruh sebagai buah perindustrian telah
kuasa pula mengubah susunan masyarakat pada masanya.
Pranata-pranata sosial juga disesuaikan pada perubahan-
perubahan tersebut, sehingga menimbulkan kultur hukum
yang memiliki karakteristik untuk zamannya.
Bermacam-macam alasan dapat dikemukakan, yang
dapat dipandang sebagai bagian dari timbulnya suatu
perubahan di masyarakat. Perubahan dalam penerapan hasil
teknologi modern dewasa ini banyak disebut sebagai salah
satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial. Penemuan-
penemuan baru di bidang teknologi tidak hanya
memberikan tambahan kekayaan kebudayaan material,
melainkan juga menimbulkan kebutuhan untuk melakukan
penyesuaian pada penggunaan hasil teknologi yang baru
tersebut.
Keadaan perubahan sebagai perkembangan itu
merupakan suatu hal yang kini banyak banyak dipikirkan di
negara sedang berkembang, sekarang dalam ungkapan
pembangunan, modernisasi, dan istilah lainnya lagi.
Masalahnya dapat lebih jelas apabila kita mengarahkannya
pada perubahan tertentu pada masyarakat negara sedang
berkembang tersebut, yaitu perubahan dari masyarakat
tradisional ke masyarakat yang modern. Komitmen pada
modernisasi adalah komitmen pada usaha perubahan sosial
yang mendalam dan sangat jauh jangkauannya,
sebagaimana dikatakan Huntington, bahwa untuk dapat
31
melaksanakan modernisasi dengan berhasil suatu sistem
politik itu pertama-tama harus mampu untuk melakukan
pembaruan kebijakan, yaitu untuk memajukan kehidupan
sosial dan ekonomi dengan perombakan melalui tindakan-
tindakan kenegaraan.
Kita juga tidak dapat melihat kehidupan hukum, yang
merupakan salah satu sistem dalam kehidupan sosial,
terlepas dari bidang-bidang yang lain, serta juga dari
perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Hukum,
di samping mempunyai kepentingannya sendiri untuk
mewujudkan nilai-nilai tertentu di masyarakat, tetap terikat
pada bahan-bahan yang dapat disediakan oleh
masyarakatnya. Dengan demikian, secara singkat hendak
dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh
perubahan-perubahan di sekelilingnya.
Sekalipun hukum merupakan sarana untuk mengatur
kehidupan sosial, satu hal yang menarik adalah bahwa justru
ia hampir senantiasa tertinggal di belakang objek yang
diaturnya. Ketika peraturan-peraturan menjadi kompleks
sifatnya, justru dengan semakin meluasnya pengaturan oleh
hukum itu dan hubungan-hubungan sosial lebih banyak
dituangkan ke dalam bagan-bagan yang abstrak, semakin
besar pula kemungkinan bagi tertinggalnya hukum di
belakang peristiwa dan perikelakuan yang nyata. Kenyataan
mengenai tertinggalnya hukum di belakang masalah yang
diaturnya sering dikatakan sebagai ciri hukum yang khas.
Menurut Yehezkel Dror, ketertinggalan itu hanya akan
terjadi apabila terjadi lebih dari sekadar ketegangan yang
tertentu, apabila hukum itu secara nyata tidak memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perubahan-
perubahan sosial yang besar yang apabila tingkah laku
sosial dan kesadaran akan kewajiban yang biasanya tertuju
32
kepada hukum berbeda dengan jelas dari tingkah laku yang
dikehendaki oleh hukum.
Hukum represif dan restitutif
Durkheim membuat perbedaan antara hukum yang
menindak (repressive) dan hukum yang mengganti
(restitutive). Hukum yang menindak ini adalah hukum
pidana. Hukum yang menindak mencerminkan masyarakat
yang bersifat kolektif. Hukum restitutif mencerminkan
masyarakat yang memiliki diferensiasi dan spesialisasi
fungsi-fungsinya. Dalam konsep hukum restitutif, hukum
yang dibutuhkan bukan lagi hukum yang cara bekerjanya
adalah dengan cara menindak, membatasi, tetapi yang
memberikan penggantian sehingga keadaanya menjadi
pulih lagi seperti semula. Yang membedakan sanksi ini
adalah bahwa ia tidak bersifat mengenakan denda tetapi
semata-mata hanya untuk memulihkan pada keadaan
semula.
Apakah hukum mempunyai kemampuan untuk
menggerakkan perubahan dalam masyarakat? Savigny,
pelopor aliran sejarah, dengan tegas menyangkal
kemungkinan penggunaan hukum sebagai sarana untuk
melakukan perubahan. Pendapatnya didasari oleh
konsepsinya mengenai hukum, yang melihat hukum sebagai
sesuatu yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan
masyarakat itu sendiri.
Dalam bentuk lebih modern, kita dapat menjumpai
pendapat yang sealiran dengan pandangan yang
dikemukakan dalam teori Marx. Marx mengakui bahwa
bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat
lambat laun akan tecermin pula di dalam hukumnya, tetapi
ia sama sekali menolak kemungkinan penggunaan hukum
33
untuk menimbulkan perubahan di bidang teknologi dan
ekonomi yang menjadi basis dari adanya hukum itu sendiri.
Apapun dikemukakan oleh teori-teori yang menentang
penggunaan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan
perubahan sosial secara sadar, namun kenyataan yang kita
hadapi sekarang menunjukkan bahwa perundang-
perundangan merupakan sandaran negara untuk
mewujudkan kebijaksanaannya. Seperti yang dikatakan
Seidman, tata hukum itu merupakan saringan yang
menyaring kebijaksanaan pemerintah, sehingga menjadi
tindakan yang dapat dilaksanakan.
Hukum sebagai sarana rekayasa sosial
Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di
dalam masyarakat, yaitu (1) sebagai sarana kontrol sosial
dan (2) sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial
(social engineering). Sebagai sarana kontrol sosial, hukum
bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap berada
dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Dalam
perannya yang demikian itu, hukum hanya mempertahankan
apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap diterima di
masyarakat—atau hukum sebagai penjaga status quo.
Tetapi di luar itu, hukum masih dapat menjalankan
fungsinya yang lain dengan tujuan untuk mengadakan
perubahan-perubahan di masyarakat.
Dalam kaitannya dengan rekayasa sosial, dapat
digambarkan sebagai berikut: Orang mempelajari lahirnya
undang-undang, efek sampingnya yang negatif ataupun
positif, orang mempelajari apakah tujuan yang dicantumkan
di dalam undang-undang itu seringkali merupakan endapan
dari perjuangan politik atau keinginan-keinginan politik. Ia
merupakan sarana yang dipergunakan orang untuk
34
mencoba menimbulkan suatu keadaan tertentu di dalam
masyarakat, atau untuk mengendalikan keadaan. Kadang-
kadang, orang ingin menggunakan undang-undang itu
untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata.
Penguasaan atau pengarahan proses sosial ini disebut
sebagai rekayasa sosial.
Batas-batas Kemampuan Hukum
Edwin M Schrur berpendapat bahwa para penulis hukum
biasanya mengakui bahwa peraturan-peraturan hukum itu
memberikan pengarahan, pengaruh dan efek yang
memperkuat. Pertanyaannya adalah seberapa banyak?
Pada umumnya, pengaruh hukum terhadap bidang-
bidang kehidupan sosial adalah tidak sama. Ada bidang-
bidang yang dengan mudah menerima pengaruh perubahan
yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan bidang yang lain
tidak dapat dipengaruhi semudah itu atau bahkan tidak
dapat dipengaruhi sama sekali. Yehezkel Dror berpendapat
bahwa tindakan-tindakan di dalam masyarakat yang
semata-mata bersifat instrumental, seperti dalam kegiatan
komersial, dengan nyata sekali dapat menerima pengaruh
dari peraturan-peraturan hukum yang baru.
Sebaliknya, bidang-bidang kehidupan sosial yang erat
hubungannya dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga
yang bersifat dasar, serta yang berhubungan dengan
tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi dari keyakinan-
keyakinan akan mengalami perubahan yang kecil sekalipun
dikeluarkan peraturan yang mencoba memberi bentuk dan
pengarahan kepada bidang-bidang tersebut, termasuk ke
dalam bidang-bidang ini adalah kehidupan keluarga dan
perkawinan.
35
Sekalipun banyak diakui bahwa bidang-bidang yang
bersifat “bebas dari unsur keyakinan, kepercayaan dan nilai-
nilai” lebih mudah digarap dan diarahkan oleh hukum,
penyelidikan membuktikan bahwa dalam bidang-bidang
yang netral pun hukum tidak dapat sepenuhnya menguasai
keadaan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. []
36
Mempelajari Keteraturan,
Menjumpai Ketidakteraturan:
Pembacaan Seorang Cantrik18
UNU P HERLAMBANG
JALAN yang dilalui seorang pendekar silat yang waskita
tidak pernah mulus. Untuk sampai pada pikiran yang lurus,
jalan yang lempeng-mulus adalah mustahil. Demikian Pak
Tjip: Awal perjalanannya memasuki dunia ‘persilatan’, sekitar
tahun 1950-an, dimulai di Fakultas Paedagogi Universitas
Gajah Mada; tidak lama kemudian, karena merasa kurang
puas, beliau pindah ke Fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masyarakat Universitas Indonesia. Dalam babakan kedua di
bangku akademisi inilah yang kemudian mengantarkan Pak
Tjip menjadi suhu besar. Sedari awal, hukum tidak dilihatnya
sebagai media profesi, namun sebagai objek keilmuan
berdasarkan rasa keinginan tahu (curiosity). Sehingga, pada
waktu belajar hukum, beliau “selalu berusaha untuk melihat
kaitan dengan hal-hal di belakang hukum” (hlm 192).
Keinginannya untuk melihat logika sosial dari hukum lebih
besar daripada logika hukum atau peraturan perundang-
18 Karangan, yang merupakan ulasan dari pidato mengakhiri masa jabatansebagai Guru Besar Tetap yang berjudul “Mengajarkan Keteraturan,Menemukan Ketidakteraturan” dalam buku Sosiologi Hukum: Esai-esaiTerpilih (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), anggitan Satjipto Rahardjo,ini disampaikan dalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada 5 November2012 di Beranda Auditorium Imam Bardjo, SH, Universitas Diponegoro.
37
undangan. Walaupun konsekuensi dari kepo hukum itu,
beliau harus memakan waktu selama delapan tahun untuk
menyelesaikan pendidikan dan menjadi meester in de
rechten (sebutan untuk sarjana hukum waktu itu).
Dengan berbekal ijazah meester in de rechten, Pak Tjip
mulai memasuki kancah sebagai guru untuk ‘mengajarkan
hukum’ di Universitas Diponegoro. Menjadi bagian dari
sistem pendidikan hukum yang berlaku, mulanya beliau juga
turut meyakinkan mahasiswa bahwa hukum itu satu sistem
peraturan yang tersusun secara
logis, bahwa hukum menciptakan
keteraturan, kepastian hukum, dan
lain-lain (lihat hlm 192). Disadari
sepenuhnya bahwa berdiri di depan
mahasiswa yang nantinya akan
mengisi profesi di bidang hukum—
jaksa, advokat, dan hakim—beliau
pun ikut melarutkan diri ke dalam
wacana profesional: hukum sebagai
sistem yang rasional. Kerena itu
beliau “turut memasukkan ke dalam
pikiran mahasiswa tentang berbagai keharusan, dogma,
adagia, doktrin, asas, dan sebagainya yang biasa menjadi
kelengkapan bagi para profesional di bidang hukum” (hlm
194). Diakuinya sendiri, pada masa awal-awal itu beliau
belum banyak mempunyai waktu untuk merenungkan
secara lebih saksama kebenaran dari yang diajarkan kepada
mahasiswa.
“Artinya, yang dapat diajarkan sebetulnya barulah
berada pada aras konteks positif atau peraturan perundang-
undangan saja. Tetapi para mahasiswa saya tentu masih
ingat betapa saya senantiasa membedakan antara ‘fakultas
hukum’ dan ‘fakultas perundang-undangan’. Di situ sudah
38
dapat dikenali adanya kegelisahan kecil terhadap ilmu
hukum yang diajarkan kepada para mahasiswa” (hlm 194).
Cara berhukum (modern) ini, yang kita terima sebagai
warisan penjajahan Belanda, membuat perundang-
undangan memiliki kedudukan sangat sentral dalam
kehidupan berhukum Indonesia. Padahal, hukum dibaca
sebagai undang-undang. Hukum yang berkelindan dengan
undang-undang, adalah fenomena yang relatif baru
dibanding masa ribuan tahun sebelumnya: selama masa
ribuan tahun itu cara berhukum manusia tidak berputar di
seputar undang-undang, melainkan di seputar keadilan itu
sendiri.
Seiring mengalirnya waktu, akumulasi dari ‘kegelisahan
kecil’ itu lantas beliau tularkan kepada para mahasiswa
melalui buku Ilmu Hukum yang terbit pada awal 1980an:
“Esensi yang dituangkan ke dalam buku tersebut merupakan
semacam otokritik terhadap paham-paham absolut legal-
dogmatik yang waktu lalu turut saya komunikasikan kepada
mahasiswa” (hlm 195). Lewat Ilmu Hukum, mahasiswa dan
masyarakat umum diajaknya untuk melihat hukum sebagai
suatu institusi manusia dan bukan semata-mata media
profesi. Dengan nada provokatif beliau memaparkan
bahwasanya hukum modern yang kita terapkan bukan
merupakan hasil dari perkembangan di ‘alam’ Indonesia,
melainkan sebagai sesuatu yang ‘imposed from outside’.
Hukum: Perdebatan antara Profesi dan Ilmu
Tentunya saya (atau kita?) pernah berpikiran praktis,
yang dulu ketika memutuskan untuk melanjutkan
pendidikan Program Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum hanya
sebagai batu loncatan untuk masuk ke bidang profesi: jaksa,
hakim, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Sebagai awam-
39
hukum, kita (atau saya?) melihat hukum adalah hukum yang
“ada untuk dirinya sendiri”. Sebuah sistem rasional yang
punya logika internalnya sendiri: logis, matematis, dan kaku-
positivistik. Hukum semata-mata mengenai ‘peraturan’ dan
‘sanksi’ dalam cita-citanya untuk mewujudkan keteraturan.
Tidak salah memang, nampaknya demikian yang terjadi
dalam sistem pendidikan tinggi hukum (dan pendidikan
tinggi lain). Program S-1 adalah program ketrampilan (skill),
sedangkan program pascasarjana (S-2 dan S-3) adalah
program keilmuan. Program yang disebut belakangan ini
“pada intinya adalah perburuan terhadap kebenaran
(searching for truth)” (hlm 199). Maka, program S-1 tidak
dapat disebut pendidikan keilmuan dalam arti yang
sebenarnya, melainkan sekadar ilmu praktis (practical
science). Menyangkut hal ini, lebih lanjut secara ringkas
beliau menjelaskan:
“Hukum sebagai objek studi program profesi adalah
lawyer’s law atau law for the lawyer atau law for the
professionals yang berbeda sekali dari hukum sebagai
objek studi program ilmu. Kebenaran mengenai hukum
jauh lebih luas dan dalam daripada hukum yang sudah
direduksi menjadi (sekadar) lawyer’s law” (hlm 199).
Dengan demikian, sejak dibuka pendidikan tinggi hukum
di Indonesia (program pascasarjana baru lahir pada
pertengahan 1980an), maka hukum yang menjadi kajian
intelektual di negeri ini mulai saat itu hingga berpuluh-
puluh tahun kemudian sesungguhnya adalah lawyer’s law
atau law for the lawyer atau law for the professionals. Maka
tidak mengherankan, konsep hukum para profesionallah
yang dominan, tidak hanya di kalangan mereka sendiri,
melainkan meluas sampai ke masyarakat. Dengan lain kata,
bagi masyarakat, hukum yang lawyer’s law itulah yang
diterima sebagai hukum yang sebenarnya. Bicara mengenai
40
hukum adalah bicara mengenai hukum sebagai profesi. Di
luar itu tidak ada hukum.
Untuk mendiskusikan masalah tersebut, Pak Tjip
membuat konsep yang mampu menerangi masalah yang
dihadapi. Konsep itu adalah tatanan (order). Tatanan (order)
merupakan suatu wilayah yang amat luas dan sangat pantas
menjadi rujukan dalam mempelajari hukum secara ilmiah.
Tatanan adalah ‘hukum’ yang lebih utuh, sedangkan hukum
positif atau lawyer’s law hanya menempati satu sudut kecil
saja dalam peta tatanan yang utuh dan besar tersebut.
Beliau membagi ‘tatanan’ menjadi tiga bagian, yaitu (1)
tatanan transendental (transcendental order); (2) tatanan
sosial (social order); (3) tatanan politik (political order).
Secara luas, pembicaraan mengenai hukum akan berada
dalam tiga tatanan tersebut: “Maka tentu saja, apabila kita
berada dalam ranah keilmuan, kita tidak dapat meniadakan
salah satu dari tiga itu, semata-mata karena tidak benar lagi”
(lihat hlm 201).
“Kalau ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai institusi
pencarian kebenaran,” demikian kata Pak Tjip, “maka pada
waktu yang sama kita juga harus mengatakan, pencarian
kebenaran adalah proses yang dramatis” (hlm 204). Dalam
perburuannya, ilmu pengetahuan menyadari bahwa,
kebenaran itu sendiri (kebenaran absolut), tidak akan pernah
ditemukan. Seperti runtuhnya era fisika Newton yang
digantikan fisika kuantum. Sehingga garis perbatasan ilmu
pengetahuan, dalam misinya memburu kebenaran, selalu
berubah, bergeser labih maju.
Mencari Sebuah Keutuhan
Suasana akademis dan intelektual menjelang peralihan
ke abad ke-21 menunjukkan sebuah pergerakan
41
meninggalkan cara berpikir yang linear dan terkotak-kotak
menuju kepada pemikiran yang lebih utuh (wholism,
wholistic). Pak Tjip melihat puncaknya dengan
diterbitkannya buku Danah Zohar dan Ian Marshall yang
berjudul Spiritual Intellegence pada tahun 2000. Sejak
permulaan abad ke-20, IQ-lah yang menjadi pusat
perhatian. Manusia dijebak dan dibuai oleh rasionalitas yang
kemudian memerangkap dirinya sendiri ke dalam situasi
yang irrasional. Hukum yang legal-dogmatis-positivistik
dianggap telah jauh meninggalkan tujuannya: keadilan. Hal
ini disebabkan kecongkakan hukum sebagai sistem rasional,
menyingkirkan unsur-unsur lain yang dianggap tidak
rasional sebagai bukan hukum.
Spiritual Intellegence mengakomodasi pentingnya
perangkat emotional qoutient (EQ) dan spiritual qoutient
(SQ), selain IQ, dalam mengukur kualitas manusia. Saya
menduga (sekali lagi: menduga) bahwa Pak Tjip mengutip
Zohar dan Marshall untuk menjelaskan konsepnya mengenai
‘tatanan’. Bahwa tatanan politik (social order), yang meliputi
lawyer’s law di dalamnya, adalah representasi dari
penggunaan IQ; tatanan transenden (transcendental order)
representasi penggunaan SQ; dan tatanan sosial (social
order) adalah representasi penggunaan EQ. Ketiga
perangkat kecerdasan itu mestinya digunakan bersama-
sama dalam menjalankan ketiga tatanan tadi. Sehingga
tercapai apa yang disebut sebagai ultimate intellegence
untuk membawa kita kepada puncak pemahaman, yaitu
menjangkau sampai ke konteks makna.
Sedangkan teori hukum positif hanya menyoroti
sebagian dari tatanan yang besar, yaitu apa yang termasuk
ke dalam tatanan politik, atau lebih khusus lagi tatanan yang
berbasis pada negara. Tak dapat diterima kehadiran tatanan
lain yang tidak dapat dikaitkan kepada tatanan negara
42
tersebut, meskipun jenis tatanan ini ada dan hidup dalam
tatanan masyarakat. penerimaan suatu tipe tatanan lain di
luar yang positif tersebut akan mengganggu kebenaran
sistem rasional dari teori tersebut.
Jika dilihat dari optik ini, maka ketiadaan atau kegagalan
dari hukum positif (tatanan politik negara) berarti
keambrukan bagi ‘tatanan’. Padahal ini tidak berarti dari
keambrukan seluruh tatanan yang besar. Karena itu, ketika
hukum negara tidak dapat memberikan pengayoman
kepada masyarakat, orang akan bingung dan kehabisan cara
(dan kata), yang lantas menyalahkan hukum sebagai biang
keladi kemunduran negara ini. Tentu hal ini disebabkan
karena pandangan sempit masyarakat yang menganggap
hukum negara adalah satu-satunya pemegang legitimasi
sebagai ‘hukum’, sehingga apabila hukum negara gagal
bekerja, ‘hukum’ (dalam arti luas dan sebenarnya) adalah
ketidakaturan itu sendiri. []
43
Sosiologi Hukum: Pengamat atau
Pemberi Solusi?19
MUHTAR SAID
JUJUR, pertama kali masuk fakultas hukum, saya bangga
sekali, karena saya bermimpi bisa menjadi dewa penyelamat.
Sebab, semua persoalan di masyarakat dalam impian saya
langsung bisa teratasi dengan mudah. Permasalahan pidana,
perdata, sampai urusan rumah tangga akan saya selesaikan
dengan menggunakan pengetahuan hukum yang saya
punyai, terutama dengan penguasaan undang-undang.
Undang-undang menjadi alat untuk melancarkan
pergerakan saya dalam menyelesaikan permasalahan, sebab
waktu itu yang saya ketahui bahwa hanya orang-orang yang
belajar di fakultas hukum itulah yang mengerti tentang
undang-undang. Inilah yang membuat saya bangga dan
menjadikan diri saya seolah-olah mempunyai nilai lebih
daripada orang lain.
Impian yang indah itu ternyata berubah menjadi cerita
yang berbeda dari angan-angan yang ada di mimpi saya itu.
Dimulai dari datangnya persoalan-persoalan nyata yang
menghampiri saya (terutama permasalahan yang berkaitan
dengan sengketa yang melibatkan orang yang mempunyai
19 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Sosiologi Hukum,Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Yogyakarta: GentaPublishing, 2010), anggitan Satjipto Rahardjo, ini disampaikan dalamjagongan rutin Kaum Tjipian pada 27 September 2012 di Ruang C104,Gedung Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
44
kuasa dan modal lebih, seperti kasus tanah di Bandungan,
penggusuran pedagang kaki lima di Semarang, sertifikat
tanah ganda yang kebanyakan mucul di pedesaan). Saat itu,
sebagai orang yang mengenyam pendidikan fakultas
hukum, pertama kali yang saya jadikan senjata adalah dalil-
dalil yang tertulis dalam perundang-udangan. Dengan wajah
agak sombong saya berharap permasalahan tersebut
langsung bisa selesai.
Namun, walaupun segenap pengetahuan saya tentang
hukum sudah saya keluarkan, permasalahan belum juga
dapat selesai, malah menjadi tambah semrawut tak karuan.
Niatnya ingin menyelesaikan masalah, tetapi malah
menambah masalah, bertambah pusing lagi ketika
berhadapan dengan orang-orang yang sama, lulusan
fakultas hukum. Pasal-pasal yang saya keluarkan bisa
dilawan dengan pasal, asas dilawan dengan asas, dan lain
sebagainya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia mengeluarkan
dalil-dalilnya saya juga membantah dengan dalil-dalil saya,
terus seperti itu sampai pertemuan buntu. Padahal,
persoalan yang kami perdebatkan adalah masalah kecil yang
seharusnya bisa langsung diselesaikan secara singkat,
namun malah menjadi sangat rumit dan memakan waktu
yang lama. Sungguh memakan waktu dan energi yang
hebat.
Persoalan yang hampir sama juga pernah menjadi topik
panas di negeri ini, gara-gara sandal jepit yang harganya
lebih murah daripada rokok Sampoerna Mild (rokok
kesukaan saya) ternyata cara penyelesaiannya memakan
waktu yang lama, malah bisa menimbulkan permusuhan
yang berkelanjutan. Peristiwa terjadi di lembaga penegak
hukum yang seharusnya bisa mengatasi masalah dengan
mudah, namun masalah tersebut malah menimbulkan
masalah lain serta memakan banyak biaya, transportasi,
45
memberikan kesibukan pada hakim, seolah-olah masalah
kecil seperti itu mengesampingkan permasalahan yang lebih
besar namun tidak teratasi secara tuntas, seperti korupsi dan
lain sebagainya. Seharusnya, kasus pencurian sandal seperti
itu cukup diselesaikan dengan memberi sanksi kepada
pelaku untuk menguras kamar mandi, misalnya.
Pencurian sandal jepit tersebut
saya anggap sebagai permasalahan
kecil dan seharusnya tidak dibawa
kemeja hijau yang akan
membutuhkan waktu lama.
Penyelesaian permasalahan seperti
ini sungguh disesalkan, apalagi
peristiwa tersebut terjadi di negara
yang menjunjung tinggi asas
musyawarah mufakat. Perlu
diketahui, di Greenland (Denmark),
kasus ringan seperti itu sanksinya
tidak sampai masuk penjara, namun hukumannya berupa
sanksi sosial: terpidana dihukum dengan hukuman sosial.
Dari pengamatan kasus tersebut, diri saya agak
tercerahkan. Ternyata penegakan hukum memang tidak
semudah membalikkan telapak tangan.
Penegakan hukum dilaksanakan guna menjaga
ketertiban dan kedamaian masyarakat. Orang lain boleh
bilang, penegakan hukum itu tinggal menerapkan pasal-
pasal perundang-undangan terhadap orang yang membuat
masalah, supaya permasalahan langsung selesai. Walaupun
sudah mengikuti pedoman undang-undang, permasalahan
masih juga belum selesai. Hal itu disebabkan di dalam
permasalahan itu terdapat banyak permasalahan lain yang
sangat kompleks.
46
Permasalahan itulah yang dikesampingkan oleh
kebanyakan ahli hukum, pengacara, polisi, dan lain
sebagainya, yang hanya berpegang teguh pada kaidah
hukum normatif, dengan tidak mempertimbangkan ilmu
lainnya, terutama sosiologi hukum. Padahal, sosiologi
hukum merupakan ilmu yang empiris, yang bisa
memberikan data dan fakta mengenai permasalahan
tersebut. Marc Galanter menggambarkan sosiologi hukum
dapat melihat hukum dari ujung teleskop yang lain (from
the other end of the telescope).20
Jika aliran normatif
mengamati permasalahan dengan sudut kacamata undang-
undang, maka sosiologi hukum memandang permasalahan
tersebut dengan menggunakan banyak cara.
Inilah yang membedakan cara berpikir sosiologi hukum
dengan cara berpikir positivistik-legalistik, di mana cara
berpikir positivistik-legalistik berangkat dari peraturan
hukum, sedangkan sosiologi hukum berangkat dari kejadian
yang nyata dari lapangan. Di sinilah letak perbedaan
sosiologi hukum terhadap cara berpikir positivistik-
legalistik.21
Perlu diketahui juga bahwa sosiologi hukum
20 Marc Galanter, dalam Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum,Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (Yogyakarta: GentaPublishing, 2010), hal 190.21 Bukan bermaksud menyingkirkan aliran positivistik-legalistik. Aliran inimemang mempunyai pengaruh besar terhadap tegaknya hukum, karenatersirat adanya kepastian hukum. Namun, untuk mencapai kebenaranyang subtantif, aliran sosiologi hukum lebih mempertimbangkan banyakhal, termasuk budaya yang berkembang di masyarakat. Inilah yang tidakdilakukan oleh aliran positivistik-legalistik. Tidak berarti aliran ini tidakjuga membahas mengenai keadilan. Aliran ini juga membahas mengenainilai-nilai keadilan, tetapi keadilan yang bersifat formal. Dari kajiantersebut, bukan berarti sosiologi hukum dalam mengkaji hukum danmenganalisis sebuah kasus meninggalkan undang-undang. Sosiologihukum juga menggunakan peraturan normatif sebagai pintu masuk gunamenyelami akar permasalahan yang timbul, sebab di mana ada konflik disitulah sosiologi hukum berada. Misalnya, seseorang mencuri sandal di
47
merupakan ilmu yang boleh dibilang masih muda. Karena
masih muda, ilmu ini kurang mendapat tempat di perguruan
tinggi, terutama di strata satu (S-1). Sebab mahasiswa strata
satu memang diarahkan untuk menjadi seorang profesional,
pengacara, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Jadi, dituntut
untuk mempunyai keahlian dalam menerapakan pasal-pasal.
Keahlian yang dipunyai bukan berarti tidak bermanfaat bagi
penegakan hukum, melainkan sangat bermanfaat guna
menegakkan kepastian hukum dan juga memunculkan
keadilan. Namun, keadilan itu bersifat formal karena
diperoleh atau dicari dengan menaati prosedur-prosedur
yang telah ditetapkan oleh hukum.
Hukum adalah undang-undang, merupakan pemaknaan
hukum yang terlalu sempit, bahkan bisa merendahkan
hukum itu sendiri. Jika memang hukum dimaknai sebagai
undang-undang saja, maka tidak perlu bertahun-tahun
belajar di fakultas hukum, cukup dengan mengikuti
perkembangan undang-undang baru yang akan dibuat oleh
lembaga legislatif dan kemudian membaca serta
menghafalkannya, pasti akan menjadi pakar hukum yang
terkenal.
Saat ini, hukum yang berkembang adalah hukum dari
para professional. Jadi, seolah-olah hukum dikeluarkan
untuk menjadi alat para profesional, bukan hukum
masjid. Dalam kasus tersebut akan segera ditanggapi oleh orang yangberaliran positivistik-legalistik dengan hanya berpedoman pada Pasal 362KUHP: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atausebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Namun, laincerita jika kasus tersebut dilihat oleh orang yang beraliran sosiologihukum. Ia akan membongkar akar permasalahan, mengapa bisa terjadikasus seperti itu, dan mengkaji sanksi yang akan diterapkan itubermanfaat ataukah tidak.
48
dikeluarkan untuk menjaga ketertiban. Jadi, ilmu hukum saat
ini sudah melenceng jauh dari kodratnya, yaitu dari
memberikan pengayoman kepada masyarakat menjadi
memberikan pundi-pundi uang bagi para pekerja
profesional. Hakim dalam aliran positivistik-legalistik hanya
terpaku pada undang-undang belaka sehingga
mengesampingkan dasar keyakinan hakim sebagai dasar
untuk melakukan vonis. Padahal, untuk memberikan rasa
yakin pada hati nurani hakim dibutuhkan penggalian-
penggalian yang lebih mendalam lagi, bahkan bisa saja
keluar dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Jika
memang peraturan perundang-undangan dirasa belum
cukup memberikan keyakinan hakim, maka bisa keluar dari
itu. Hal ini juga dilakukan seorang polisi yang mengatur lalu
lintas yang padat dan macet. Untuk memberi kelancaran
bagi pengguna jalan, seorang polisi bisa melakukan
terobosan untuk melanggar perundang-undangan lalu
lintas, karena mengabaikan lampu lalu lintas. Cara seperti itu
dilaksanakan sebab bisa berguna bagi masyarakat banyak.
Mengulas lagi mengenai aliran positivistik-legalistik yang
mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19, aliran ini
bisa besar karena memang mendapatkan dukungan dari
kaum profesional. Jika dilihat secara kasat mata, aliran ini
dirasa bisa dengan cepat dan praktis digunakan untuk
memecahkan masalah. Akan tetapi, pada kenyataannya,
permasalahan belum juga berakhir walaupun sudah ada
vonis dari hakim.22
Seperti kasus yang dulunya sangat
22 Penggunaan sosiologi hukum memang sangat ampuh untukmenyelesaiakan permasalahan. Namun, hal itu membutuhkan waktu yanglama dan juga niat dan ketulusan yang dibarengi dengan konsistensi yangtinggi. Di Solo, jarang terdengar pertengkaran antara Satpol PP dan parapedagang kaki lima, karena Wali Kota Solo (waktu itu) Joko Widodo dalammenertibkan pedagang kaki lima tidak menggunakan kekuatannyadengan mengerahkan pasukan Satpol PP, namun melalui pendekatan
49
moncer, yaitu masalah pencemaran nama baik yang
dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni
International. Permasalahan tidak akan berlarut-larut dan
menjadi terkenal apabila tidak dibawa ke lembaga yang
berwenang, melainkan diselesaikan dengan tatap muka.
Pemikiran hukum yang terlalu kaku juga membuat para
intelektual hukum merasa dirinya terpenjara dalam
kekakuan hukum pada saat itu. Padahal zaman sudah
berubah dan tentunya harus ada inovasi terhadap hukum itu
sendiri. Tidak mungkin cara-cara lama bisa digunakan pada
permasalahan yang baru muncul. Harus ada modifikasi dan
pemikiran baru untuk menerapkan cara-cara tersebut.
Sekarang, sudah tidak mempan lagi seorang laki-laki
ketika ingin mendapatkan wanita pujaannya hanya
melakukan lobi-lobi cinta kepada orang tua wanita yang dia
incar. Strategi seperti itu kurang bisa secara langsung
mendapat targetnya jika tidak ada terobosan selain itu,
seperti melakukan pendekatan kepada wanita incarannya itu
sendiri.
Zaman dahulu mencari jodoh itu mudah: jika orang tua
setuju, anaknya pasti ngikut. Namun, cara seperti itu tidak
berlaku di zaman sekarang. Oleh karena itu, harus
mempersiapkan banyak strategi. Begitu juga dengan ilmu
hukum dalam mengatasi permasalahan yang selalu
berkembang. Pada abad ke-18-19, mungkin, pemikiran
normatif sangat ampuh diterapkan. Namun, bisa jadi hal itu
antarmanusia. Pemindahan pedagang kaki lima memakan proses waktuyang lama, sampai bertahun-tahun, dan Joko Widodo datang langsung.Cara seperti ini tidak akan ditiru oleh para hakim, di mana hakim harusturun ke lapangan untuk mencari akar permasalahan guna menciptakanvonis yang adil secara subtantif, karena cara pandang hakim adalahdidatangi (pasif).
50
tidak mempan lagi jika diterapkan pada zaman sekarang
karena semakin kompleksnya permasalahan. Untuk
menjawab itu semua para penegak hukum dituntut untuk
tidak mengandalkan teks-teks perundang-undangan
semata, harus ada perkembangan terhadap ilmu
pengetahuan yang akan digunakan.
Berbicara masalah perkembangan ilmu pengetahuan,
tidak akan melupakan nama Thomas Kuhn, yang
mengemukakan bahwa ilmu dari waktu ke waktu selalu
mengalami revolusi dimulai dengan perubahan dalam
paradigma yang digunakan. Contoh peristiwa besar
mengenai revolusi ilmu, yaitu berakhirnya era Newton
melalui suatu revolusi. Padahal, pada zaman itu, menurut
fisika dan paradigma Newton yang baru, seluruh alam
dianggap telah dapat dilihat dalam suatu susunan yang
tertib. Tetapi era Newton bukan akhir segalanya. Alam masih
menyimpan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan atau
dijangkau oleh teori Newton.23
Memang pada waktu teori Newton dirasa tidak bisa
menjawab persoalan fisika, muncullah teori kuantum yang
pada kenyataannya lebih mampu menjawab persoalan-
persoalan fisika yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan.
Kejadian tersebut memberi dampak pada dunia pemikiran
mengenai realitas alam. Gambaran pergeseran dari teori
Newton ke kuantum seolah-olah memosisikan ilmu
pengetahuan dalam posisi yang selalu labil, karena akan
terfalsifikasi oleh ilmu pengetahuan yang akan datang yang
muncul akibat tuntutan zaman.
23 Satjipto Rahardjo, Merintis Visi Program Doktor Hukum Undip(Semarang, 2003), hlm 9.
51
Perselingkuhan Hukum dengan Ekonomi
Mencermati kondisi perkembangan ilmu pengetahuan
seperti yang dijelaskan tadi, kemudian ditangkap dengan jeli
oleh Satjipto Rahardjo yang memasukan ide-ide tersebut ke
dalam ilmu hukum. Ketika pemikiran pada umumnya
memosisikan hukum sebagai disiplin ilmu yang independen,
tidak bisa dimasuki oleh disiplin ilmu lain, Satjipto berani
memasukan antardisiplin ilmu ke dalam pembahasan ilmu
hukum. Memang pada kenyataannya ilmu akan selalu
berputar dan saling menyambung antara ilmu satu ke ilmu
yang lain. Hal itu juga diamini oleh Wilson, yang
berpendapat bahwa kemajuan sains merupakan awal untuk
melajukan penyatuan (unifikasi) antara sains alam, sains
sosial, dan sain kemanusiaan. Pencarian hubungan
antardisiplin merupakan tugas penting, dan Wilson
menghimpun beberapa disiplin secara luas dan anggun.24
Sebab ilmu hukum saat ini bukan hanya mengkaji
mengenai masalah pencarian keadilan, sekarang posisi
hukum juga dijadikan alat untuk melakukan perubahan
sosial, seperti yang didermakan oleh Roscoe Pound. Di
negara-negara modern, peranan hukum sangat penting
untuk memberikan legitimasi bekerjanya negara. Dalam
melaksanakan kinerjanya, aparat negara harus mempunyai
payung hukum. Dalam situasi ini, hukum mempunyai
peranan sebagai pencegah agar negara tidak terlalu otoriter
terhadap masyarakatnya.
Namun, dalam pandangan kritis seperti yang diutarakan
oleh Karl Marx, hukum merupakan tatanan peraturan untuk
24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, danPencerahan (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm 18.
52
kepentingan kelas yang berpunya dalam masyarakat.25
Derma Marx mungkin patut dibetulkan, karena bangunan
hukum rawan dengan perselingkuhan dengan ekonomi
yang cenderung kapitalistik. Golongan borjuis sudah sadar
bahwa untuk melancarkan misinya dalam mengeksploitasi
kekayaan alam demi kekayaan dirinya, mereka harus
mempunyai landasan hukum supaya dianggap sah dan
apabila ada perlawanan mereka bisa menunjukkan surat
keterangan sahnya itu. Suap kepada aparat negara menjadi
alat ampuh untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang
akan dikeluarkan agar memberikan keuntungan bagi
golongan borjuis.
Kekuatan ekonomi yang dipunyai oleh kalangan borjuis
jelas sangat ampuh untuk bisa memengaruhi kinerja birokasi
atau penguasa setempat untuk memberikan kebijakan-
kebijakan yang condong atau melanggengkan usahanya
agar tidak tersaingi oleh kalangan kecil yang akan merintis
usahanya. Hukum dijadikan penghambat bagi kalangan kecil
yang ingin merintis usahanya.
Penelitian yang dilakukan oleh De Soto di Peru
menemukan hasil bahwa untuk memulai usaha secara sah
(legal) dibutuhkan biaya yang mahal. Inilah yang tidak bisa
dijangkau oleh rakyat kecil, namun bisa dijangkau oleh kelas
borjuis. Akhirnya, karena tidak bisa memenuhi biaya yang
disyaratkan oleh hukum, mereka melakukan usaha secara
ilegal dan apabila ketahuan oleh pemerintah mereka akan
digusur dan dirampas dagangannya. Contoh ini memberi
opini bahwa hukum sebagai alat penguasa untuk
melanggengkan kekuasaannya memang benar-benar terjadi.
25 Satjipto Rahardjo, op. cit., hlm 74.
53
Bagi penganut Marxis klasik, untuk melawan kezaliman
semacam itu, harus dilakukan revolusi. Sebab, tidak ada
celah lagi bagi kaum proletar untuk bisa membuat jalan atau
berjuang untuk memperbaiki nasibnya secara legal:
selamanya mereka akan menjadi kaum buruh di pabrik-
pabrik kapital.
Di Indonesia, sudah bukan rahasia lagi bahwa produk
hukum jika tidak ada yang mensponsori pembuatannya
tidak akan pernah jadi walaupun rancangan undang-undang
tersebut dinilai sangat urgen untuk masyarakat. Seperti
permasalahan Konsep KUHP yang sudah bertahun-tahun
tidak pernah disahkan oleh lembaga legislatif. Lembaga ini
malah lebih senang mengeluarkan undang-undang yang
berbau komersial dan politik. Hal itu disebabkan konsep
KUHP bukanlah proyek yang menghasilkan uang untuk
mereka.
Inilah menjadi bukti bahwa hukum tidak akan pernah
terlepas dari nilai-nilai yang berada di luar hukum itu sendiri.
Banyak faktor yang memengaruhi pembentukan hukum, dan
saat bekerjanya hukum itu sendiri. Orang selalu sibuk
dengan perdebatan mengenai penerapan pasal-pasal
perundang-undangan, namun jarang membahas mengenai
bekerjanya hukum. Wilayah ini merupakan ranah di mana
ilmu sosiologi hukum menampakan dirinya.
Dalam ranah bekerjanya hukum, akan banyak faktor
yang memengaruhi peraturan perundang-undangan itu
dapat diberlakukan secara maksimal atau tidak. Polisi
mempunyai semboyan sebagai pengayom masyarakat dan
itu selalu dikampanyekan oleh mereka lewat iklan, baliho,
serta spanduk yang tertempel di jalan raya. Namun, jika
menggunakan analisis sosiologi hukum, maka akan muncul
sebuah pertanyaan yang mempertanyakan kinerja kepolisian
54
sebagai pengayom masyarakat, karena dalam sosiologi
memberikan pertanyaan kepada polisi: masyarakat yang
mana yang akan diayomi. Banyak peritiwa yang terjadi
seperti di Bima dan Mesuji, di dua daerah tersebut “seolah-
olah” memberikan gambaran bahwa polisi melindungi kelas
bojuis.
Padahal, di lembaga-lembaga hukum yang ada di negara
ini, kepolisian merupakan lembaga yang paling
memperlihatkan sifat sosiologisnya dalam bekerja. Hal itu
disebabkan polisi mempunyai keterlibatan langsung dengan
masyarakat secara intens.
Dalam masyarakat terdiri dari berbagai individu. Tetapi,
masing-masing individu tidak bisa dikatakan langsung bisa
bermasyarakat. Hal itu disebabkan ada juga individu yang
tidak mempunyai rasa sosial. Oleh karena itu, untuk
menggabungkan mereka dalam masyarakat dibutuhkan
suatu tindakan yang bisa dikatakan sebagai pemaksaan
untuk menjadikan individu tersebut bermasyarakat.
Sesunggunya, tindakan inilah yang merupakan hakikat
dari pekerjaan polisi, sebab tugas polisi sesuai dengan Pasal
13 butir (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.” Memasyarakatkan individu merupakan salah
satu fungsi dari pengayoman. Karena, ketika individu sudah
bisa hidup bermasyarakat, akan tercipta iklim yang
harmonis. Namun, tugas seperti ini ternyata terpinggirkan. []
56
Kapita Selekta Hukum Progresif:
Pada Mulanya adalah Koran26
AP EDI ATMAJA
DULU, dulu sekali, saya benar-benar mengagumi
(almarhum) Prof Dr Satjipto Rahardjo, SH. Sosok yang
kemudian kita kenal sebagai Prof Tjip itu begitu melegenda
di Fakultas Hukum, lalu Universitas Diponegoro, lalu Jawa
Tengah. Belakangan, Prof Tjip ternyata—meminjam frasa
Prof Arief Hidayat—“aset nasional”. Artinya, dia telah
menjadi “kekayaan” bangsa Indonesia. Lebih belakangan
lagi, saya semakin takjub, sebab Prof Tjip ternyata juga “aset
internasional”: pendekar hukum Indonesia yang
kepakarannya bahkan dikagumi (almarhum) Prof Daniel S
Lev, Indonesianis terkemuka asal Amerika Serikat. Prof Lev,
tutur Prof Tjip, suatu kali pernah berkata kepadanya, “Saya
tidak bisa menulis lagi soal hukum Indonesia, karena tidak
bisa mencium aromanya. Aroma itu saya baca dari tulisan-
tulisan Anda.”27
Baik, itu dulu. Kini, kekaguman itu barangkali telah
menghilang. Namun, hilangnya kekaguman itu bukan berarti
26 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Penegakan HukumProgresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), ini disampaikan dalamjagongan rutin Kaum Tjipian pada 8 Oktober 2012 di Ruang C104, GedungMagister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.27 Subur Tjahjono, “Satjipto, 33 Tahun Menulis Artikel”, dalamhttp://nasional.kompas.com/read/2008/06/27/05383141/satjipto.33.tahun.menulis.artikel (diakses pada 1 Oktober 2012).
57
buruk. Kini, seiring bertambahnya usia, semakin beragamnya
bacaan yang mengenalkan saya pada pemikir-pemikir
(hukum) lain di dunia, kekaguman saya kepada Prof Tjip
berubah menjadi rasa hormat. Hormat pada perjuangan tak
kenal lelah Prof Tjip dalam menyebarkan ilmu yang
dipopulerkannya sebagai sosiologi hukum itu: ilmu yang
mencoba mengawinkan hukum dengan kemasyarakatan,
dus kemanusiaan. Pemikir hukum yang berjuang di jalan itu,
sepengetahuan saya, bahkan di dunia, masih amat langka.28
Perjumpaan saya buat kali pertama dengan Prof Tjip
terjadi dalam ruang kelas yang suntuk. Perkuliahan
mahasiswa tingkat sarjana (S-1), kita tahu, demikian
menjemukannya. Adalah sangat langka dosen yang mampu
meramu kuliah yang dapat merangsang keingintahuan
mahasiswa akan persoalan hukum kontemporer. Kuliah
hukum lebih sering saya habiskan dengan melamun, paling
sial tertidur. Ini, saya ketahui belakangan, ternyata pernah
jadi sasaran kritik Prof Tjip.29
28 Segelintir yang bisa disebut antara lain Brian Z Tamanaha, Roberto MUnger, Paul Scholten, William J Chambliss, Robert D Seidman, MarcGalanter, Philippe Nonet, Philip Selznick, dan Talcott Parsons.29 Lihat Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia:Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin (Yogyakarta: Genta, 2009). Dalam babbertajuk “Peranan Baru dari Pendidikan Hukum dan Ahli Hukum” (hlm127), Prof Tjip menyigi riwayat pendidikan hukum Indonesia sejak zamanpenjajahan hingga pascakemerdekaan. Pendidikan hukum kita yangberambisi untuk menciptakan “tukang-tukang” (craftmanship) ditengaraiProf Tjip sebagai warisan kolonial yang tak mudah dihapuskan bahkanoleh pemimpin serevolusioner Soekarno. Tersebab orientasi pendidikanpada soal bagaimana sarjana hukum memperoleh pekerjaan, bukanmengembangkan keilmuan hukum, materi hukum yang dikuliahkanadalah yang menunjang atau berguna bagi pekerjaan. Jadilah dosen,ketika menyampaikan kuliah, cenderung monoton, mengulang-ulangmateri yang pernah dipakai bergenerasi-generasi sebelumnya, sebagaihafalan yang kebal dari daya kritisisme.
58
Dalam suasana hati yang sebal dengan suasana kuliah di
kampus itulah saya mengenal Prof Tjip.
Malam-malam, di rumah, saya iseng baca-baca majalah
usang koleksi bapak saya. Majalah Tempo edisi 15
Desember 1990. Baru sebentar membaca, di halaman 26,
saya mendapati artikel, sebuah kolom, berjudul The Dirty
Harry. Pengarangnya lamat-lamat saya ingat pernah
disinggung dosen matakuliah Pengantar Ilmu Hukum tadi
pagi. Sepertinya kenal, saya membatin. Saya teruskan
membaca.
Luar biasa. Cara orang ini merangkai kata demikian
ciamik-nya. Renyah. Esainya—berkisah tentang seorang
polisi yang gandrung puisi—disajikan dengan manusiawi. So
human. Tulisannya adalah sebentuk kritikan terhadap
pemerintah Orde Baru yang waktu itu melarang pementasan
penyair WS Rendra. Nama pengarang esai itu, tertera di
bawah judul, tercetak tebal: Satjipto Rahardjo.
Sejak saat itu, saya memburu segala informasi tentang
pria kelahiran Banyumas, 15 Desember 1930, itu. Dalam
perburuan, saya menemukan bahwa nama Prof Tjip, dalam
industri media cetak, rupanya bukanlah anak ingusan
kemarin sore. Tulisan opininya mengenai persoalan hukum
tersebar di mana-mana. Di harian Kompas, misalnya, tulisan
Prof Tjip mencapai angka ratusan. Belum di Suara Merdeka,
Tempo, dan media lain yang belum lagi saya ketahui.
Tentang “kegilaannya” itu, saya baca satu reportase tentang
Prof Tjip, mengenang kepulangannya pada awal 2010 lalu:
Dengan menulis di surat kabar, akademisi bisa membagi
pengetahuannya ke publik yang luas, tidak terbatas
seperti pada jurnal ilmiah. Dengan kemampuannya
membuat tulisan ilmiah populer di suratkabar itu, Pak
59
Tjip membuktikan, ilmu hukum bukanlah ilmu yang
kering dan tidak menarik. Hukum kalau ditulis dari sisi
teknis memang tidak menarik, tetapi kalau dilihat dalam
hubungan dengan masyarakatnya, hal itu tidak akan ada
habis-habisnya. Berbagai macam ide segar menyangkut
bidang yang ditekuninya itu ditumpahkannya pula dalam
artikel-artikelnya.30
***
PADA mulanya adalah koran. Pengantar yang bernuansa
sedikit curahan hati di atas tentu ada relevansinya dengan
materi yang hendak saya bahas dalam kesempatan kali ini.
Ya, pada mulanya adalah koran.
Buku bersampul warna cokelat berhias wajah Satjipto
Rahardjo yang kita bedah dalam kesempatan kali ini bisa
dikatakan adalah buku pertama Prof Tjip yang terbit setelah
dia wafat. Mengapa pertama? Sebab, saya yakin, buku-buku
lain akan lekas terbit kendati pengarangnya telah tiada.
Pertama, karena nama Prof Tjip sebagai akademisi-cum-
pengarang telah demikian masyhur sehingga buku-buku
lamanya kemungkinan besar akan dicetak ulang dan bakal
laris manis tanjung-kimpul. Kedua, karena kebanyakan buku
Prof Tjip adalah kumpulan artikelnya di koran-koran.31
Padahal, kita tahu, artikelnya itu berjumlah ratusan, yang
belum semuanya diterbitkan dalam bentuk buku.
Buku Penegakan Hukum Progresif ini—berisi artikel-
artikel yang pernah dimuat di harian Kompas—adalah buku
30 Subur Tjahjono, op. cit.31 Andreas Harsono punya sebutan jenaka untuk buku jenis ini, yaitu“buku-bukuan”: buku berisi artikel lepas yang awalnya tidak dimaksudkansebagai buku dalam pengertian umum. Lihat Andreas Harsono, AgamaSaya adalah Jurnalisme (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
60
Prof Tjip paling gres yang diterbitkan Penerbit Buku
Kompas. Sebelumnya telah terbit, antara lain, Sisi-sisi Lain
dari Hukum di Indonesia (2003), Membedah Hukum
Progresif (2006), Biarkan Hukum Mengalir (2007), dan
Hukum dan Perilaku (2009). Menurut editornya, Aloysius
Soni BL de Rosari, buku Penegakan Hukum Progresif ini
adalah “kapita selekta Satjipto Rahardjo”, sebab isinya artikel
pilihan dari buku-buku itu.32
Lantaran pada awalnya tidak
ditujukan sebagai buku utuh
(babon), buku ini lekat dengan
pengulangan di sejumlah tempat.
Apalagi mengingat bahwa ia juga
merupakan “perulangan” dari
buku-buku yang telah terbit
sebelumnya. Sehingga, kadang
cukup sulit bagi kita untuk tidak
merasa “bosan” dengan
pengulangan itu, alih-alih
menjadi semakin terjelaskan.
Namun, buku ini tetap kita
anggap berharga untuk memahami sekaligus memetakan
teori hukum progresif yang digagas Prof Tjip.
Buku Penegakan Hukum Progresif terbagi ke dalam lima
bab. Kelima bab itu adalah Apa dan Bagaimana Penegakan
Hukum Progresif, Implementasi Penegakan Hukum Progresif
di Indonesia, Penguasa dan Penegakan Hukum Progresif,
Penegakan Hukum Progresif, dan Peran Masyarakat dalam
Penegakan Hukum Progresif.
32 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Yogyakarta: PenerbitBuku Kompas, 2010), hlm ix.
61
Dalam tulisan bertajuk “Di Luar Pengadilan”, Prof Tjip
mengkaji soal penyelesaian perkara yang dapat dilakukan
tanpa melalui mekanisme peradilan formal. Bagi para
pemikir formal-legalistik, demikian Prof Tjip, penyelesaian
perkara di luar pengadilan (out of court settlement)
dianggap sebagai sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa.
Namun, bagi mereka yang melihat persoalan itu melalui
optik sosiologi hukum, itu adalah hal yang biasa, lumrah
adanya. Sebab, penganut sosiologi hukum mengutamakan
fungsi, bukan bentuk seperti halnya pemikir formal-
legalistik.
Tatkala hukum dibakukan dalam sebuah teks
perundang-undangan, maka panggung hukum berganti
menjadi panggung hukum tertulis. Hukum yang tertulis itu
erat kaitannya dengan negara modern yang embrionya telah
ada sejak abad ke-18.33
Sejak saat itu, seluruh institusi
kemasyarakatan didominasi negara. Terjadilah hegemoni
negara, mulai dari hukum negara, pengadilan negeri,
undang-undang, dan seterusnya.
Padahal, menurut Prof Tjip, ketika hukum diundangkan
dan dialih-bentuk menjadi teks (legislated law), bahasa
(talig) memegang kendali. Saat itu, cara berhukum
memasuki dimensi baru, yakni cara berhukum melalui
skema—yang terdiri dari kalimat dan kata-kata. Kalimat dan
kata-kata memiliki daya jangkau yang terbatas untuk
mencerap realitas. Jadi, berhukum dengan skema melalui
bahasa sejatinya tengah mereduksi makna hukum yang
hakiki. Hukum pun lalu segera cacat kala dilahirkan, ketika
diutarakan dalam kalimat dan kata-kata.
33 Ibid., hlm 4.
62
Sudah barang tentu ada yang tercecer di sana, dari
hukum yang diformulasikan menjadi kalimat dan kata-kata
itu. Prof Tjip memisalkan munculnya konsep “pencurian” dari
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pencurian yang
konon dalam masyarakat Jawa terdiri dari sepuluh macam,
seperti maling, jambret, copet, ngutil, nggarong, dan
seterusnya, dirumuskan kembali oleh KUHP menjadi
“barangsiapa dengan sengaja mengambil barang milik
orang lain”. Dan hukumannya juga disamaratakan: tidak lagi
melihat kadar (kuantitas dan/atau kualitas) barang yang
“dicuri”.
Lebih lanjut, Prof Tjip mengatakan, buat mengatasi
keterceceran tadi, hukum mesti dipahami pula sebagai
perilaku. Hukum adalah perilaku kita sendiri. Di sini, hukum
yang oleh kaum positivis dilihat sebagai teks yang
mengeliminasi faktor dan peran manusia dikoreksi besar-
besaran dengan menempatkan manusia sebagai posisi
sentral cara berhukum. Maka, konsep hukum yang telah
mapan mesti diubah: bukan lagi semata aturan (rule), tetapi
juga perilaku (behavior).
Dalam “Biasa dan Luar Biasa dalam Berhukum”, Prof Tjip
mengemukakan gagasan radikal tapi sejatinya diperlukan
dalam praksis hukum dewasa ini. Keadaan dunia tidak
selamanya berjalan dalam suasana yang ayem-tentrem,
normal tanpa gejolak. Ada kalanya, hukum bekerja di ruang
yang penuh gejolak, konflik, dan kekacauan (chaos). Saat
itulah sesungguhnya diperlukan suatu cara berhukum yang
luar biasa. Apabila cara-cara biasa atau normal disebut
sebagai rule making, maka cara luar biasa disebut rule
breaking. Berhukum dengan cara luar biasa berarti
melakukan suatu penerobosan hukum yang ada.
63
Ilmu yang berkembang sekarang ini, baik eksak maupun
sosial, kata Prof Tjip, semakin mendewasa: tidak lagi berpikir
secara hitam-putih, melainkan mengakui kompleksitas,
ketidakpastian, kekelabuan, atawa relativitas. Era Newton,
Descartes, dan Bacon di abad ke-17, yang sarat kepastian,
rasionalitas, dan determinisme, sudah berlalu. Struktur dunia
fisik tidak lagi mekanis-masinal ibarat mesin yang bekerja
otomatis, melainkan sudah menjadi kenyataan yang non-
mekanis. Ketertiban (order) tidak lagi berlawanan dengan
kekacauan (chaos), tetapi berjalin kelindan dan sama-sama
diperlukan. Hukum tidak pernah lagi otonom, melainkan
senantiasa dipengaruhi oleh segala hal yang berada di
dalam ataupun di luar dirinya.
Sebetulnya, cara berpikir yang mengakui kompleksitas
dan relativitas telah jauh merasuk di lubuk hati bangsa-
bangsa Timur. Namun, hal itu terpinggirkan oleh dominasi
(peradaban) Barat, oleh arus dominan cara berpikir yang
rasional-Cartesian dan eksperimental-Baconian. Ikon sains
saat ini, yang mengedepankan relativisme dan
ketidakpastian, sesungguhnya amat lazim di kalangan
bangsa-bangsa Timur, yang memandang segala hal tidak
dengan kecerdasan emosional, melainkan kecerdasan
spiritual.
Dengan menyinggung cara berpikir bangsa Timur, akan
terbuka ruang bagi kita untuk lebih jauh memahami
bagaimana tujuan hukum bagi kita, bangsa Indonesia. Prof
Tjip pun melontarkan pertanyaan: “Kita bernegara hukum
untuk apa? Hukum itu mengatur masyarakat semata-mata
untuk mengatur atau untuk suatu tujuan yang lebih besar?”
Di sinilah titik menariknya. Bahwa, kata Prof Tjip, “Hukum
hendaknya memberi kebahagiaan kepada rakyat dan
bangsanya.” Ini menarik, karena tujuan hukum ternyata tidak
64
hanya kepastian, kemanfaatan, atau keadilan, melainkan
juga kebahagiaan.
Prof Tjip meramalkan kebuntuan, kemacetan, kegagalan,
dan akhirnya kematian hukum. Sebab hukum buntu, macet,
gagal, lalu mati, menurut Prof Tjip, adalah ketidakmampuan
hukum (yang diperlakukan) otonom untuk mengakomodasi
perubahan sosial yang bergerak dinamis. Hukum terlalu
berasyik-masyuk dengan diktum “hukum ada untuk hukum
itu sendiri”, terjebak dalam urusan kepastian, sistem, dan
logika peraturan yang tak bisa memberi respons yang baik
atas problem sosial.
Buat mengatasi sekalian persoalan itu, Prof Tjip
merumuskan semacam manifesto atau tesis tentang hukum
yang mampu memerdekakan manusia—yang disebutnya
dengan hukum progresif. Hukum progresif mengandung
empat karakteristik utama.34 Pertama, paradigma hukum
progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia.
Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan
keadaan status quo (mapan) dalam berhukum.
Ketiga, jika diakui bahwa peradaban hukum tertulis akan
memunculkan sekalian akibat dan risiko, maka cara kita
berhukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana
mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan
hukum tertulis tersebut. Keempat, hukum progresif memberi
perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam
hukum. []
34 Ibid., hlm 61-66.
65
Dasar-dasar Hukum Progresif35
BENNY KARYA LIMANTARA
PEMBENAHAN perundang-undangan bukannya tidak perlu,
tetapi bukanlah satu-satunya cara. Di tengah kesibukan
membenahi perundang-undangan, gerakan supremasi
hukum ternyata kurang memberi hasil. Dunia dan kehidupan
hukum kita masih berjalan di tempat dengan segala karut-
marutnya. Lalu, di mana salahnya? Apanya yang salah?
Dari pengamatan terhadap praktik hukum selama ini
tampak “intervensi perilaku” terhadap normativitas hukum.
Orang membaca peraturan dan berpendapat bahwa orang
harus bertindak semacam itu. Tetapi yang terjadi ternyata
berbeda atau tidak persis seperti yang dimengerti orang.
Inilah yang disebut sebagai intervensi perilaku. Kemudian,
dibangun teori bahwa hukum bukan hanya urusan peraturan
(a business of rules), tetapi juga perilaku (matter of
behavior). Dalam suatu peraturan, misalnya, jelas tercantum
secara limitatif bahwa yang boleh mengajukan peninjauan
kembali (PK) terhadap perkara pidana adalah terpidana atau
ahli warisnya. Tetapi, suatu kali jaksa pernah mengajukan PK
dan diterima pengadilan. Jadi, perwujudan hukum PK telah
diintervensi oleh perilaku jaksa.
35 Karangan, yang merupakan ringkasan dari buku Membedah HukumProgresif (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006) anggitan SatjiptoRahardjo, ini disampaikan dalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada 22Oktober 2012 di Kompleks Pedagang Kaki Lima Universitas Diponegoro,Pleburan, Semarang.
66
Van Doorn, seorang sosiolog hukum, mengutarakan
secara lain. Hukum yang merupakan skema yang dibuat
untuk menata (perilaku) manusia itu sendiri ternyata
cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan
baginya. Ini disebabkan oleh faktor pengalaman, pendidikan,
tradisi, dan lain-lain, yang memengaruhi dan membentuk
perilakunya. Maka, dalam usaha untuk membenahi hukum
di Indonesia, kita perlu menaruh perhatian yang saksama
terhadap masalah perilaku bangsa. Kehidupan hukum tidak
hanya menyangkut urusan teknis, seperti pendidikan hukum,
tetapi juga menyangkut soal pendidikan dan pembinaan
perilaku individu sosial yang lebih luas.
Sebenarnya, ada
contoh dalam Undang-
Undang Da-sar 1945
(UUD): “Sekalipun dibuat
UUD yang bersifat
perseorangan, UUD
tidak ada gunanya.” Ini
adalah satu isyarat untuk
memberi perhatian
kepada aspek perilaku
dan kultur konstitusi.
Dengan pencantuman
kata-kata seperti itu,
sesungguhnya para penyusun UUD sudah melakukan suatu
tindakan yang jenius karena sudah merambah ke wilayah
“kultur hukum”. Jenius karena pada saat itu (1940an) kultur
hukum belum banyak dibicarakan, bahkan di dunia
akademis. Ilmu hukum baru diperhitungkan sebagai unsur
sistem pada 1960an. Maka, meski perubahan UUD sudah
beres, sebetulnya masalah masih jauh dari selesai. Kita masih
akan berurusan dengan aspek perilaku dari orang-orang
67
yang akan menjalankannya. Seseorang pernah mengatakan,
”Berikan pada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan
hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.” Jadi,
sekali lagi diingatkan mengenai pentingnya faktor perilaku
atau manusia dalam kehidupan hukum.
Dengan membicarakan perilaku, sampailah pada aspek
human capital (HC). Pertanyaannya, apakah kita memiliki HC
untuk bangun dari keterpurukan bangsa? Jawabannya, kita
punya. Tapi, jumlah mereka terlalu sedikit dan tenggelam
dalam potret hukum kita. Mereka ada di kejaksaan,
pengadilan, atau di tempat lain. Seorang mantan jaksa
mengatakan kepada rekan-rekannya yang sibuk
mengumpulkan sejumlah bukti-bukti bahwa hanya dengan
beberapa bukti ia dapat membawa orang itu ke pengadilan.
Kita sering menyatakan kebanggaan diri sebagai bangsa
yang berbudi luhur, bermoral, bersifat kekeluargaan,
kebersamaan, dan semacamnya. Tetapi, semua itu tidak
menyentuh sampai kultur hukum kita. Kultur hukum malah
cenderung ke individualisme dan moralitas belum menjadi
social capital (SC). Hukum membutuhkan SC-nya sendiri dan
setiap bangsa membawa bekal SC masing-masing.
Malangnya, kita tidak mampu menunjukkan SC dan baru
sampai pada omongan, kendati sudah didorong proyek
penataran Pancasila dan segala macam yang bernilai
miliaran rupiah.
Jepang dan Amerika Serikat memiliki SC masing-masing
sebagai penyokong konsepsi negara hukumnya. Orang AS
amat rasional dalam menjalankan hukum, sedangkan Jepang
menggunakan hati nuraninya. Diceritakan bahwa ada dua
orang, berkewarganegaraan AS dan Jepang, akan
menyeberang jalan tetapi tertahan lampu merah. Ketika
sudah tidak ada kendaraan lewat, orang AS mengajak
68
menyeberang saja. Tetapi, orang Jepang mengatakan, “Kalau
saya menyeberang, sedangkan lampu masih merah, muka
saya mau ditaruh mana?”
Itulah perbedaan dalam SC antarbangsa yang membawa
kepada perilaku dan kultur yang berbeda. Perilaku
merupakan modal amat penting sebelum kita berbicara
tentang hukum. Tanpa perubahan cara berhukum seperti itu,
hukum hanya akan menjadi permainan kepentingan dan
gagal membawa bangsa ini kepada kesejahteraan, keadilan,
kebahagiaan, dan kemuliaan.
Hukum Hendaknya Membuat Bahagia
Karakteristik hukum modern yang menonjol adalah sifat
rasional dan bisa berkembang pada tingkat “rasionalitas di
atas segalanya” (rationality above else). Tidak mengherankan
jika para penyelenggara hukum, baik legislator, penegak
hukum, dan lainnya, akan mengambil “sikap rasional” seperti
itu pula. Bukan keadilan yang diciptakan “cukup” agar
dijalankan dan diterapkan secara rasional. Dalam
perkembangan selanjutnya, ternyata masyarakat tidak puas
dan ingin agar hukum aktif dalam menyelenggarakan
kesejahteraan masyarakat. Jadi, kelahiran hukum modern
(yang liberal) bukan akhir dari segalanya, tetapi alat untuk
meraih tujuan lebih jauh, yaitu kesejahteraan dan
kebahagiaan masyarakat.
Dorongan ke arah kebahagiaan dapat kita amati pada
negara-negara Timur seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan
Indonesia. Kendati Jepang menggunakan hukum modern,
itu dilakukannya karena tidak ingin ketinggalan dari
masyarakat-masyarakat lain di dunia. Ini terlihat saat struktur
kehidupan Jepang yang terdiri dari omote (bagian muka)
dan ura (bagian belakang) atau latemae (luar) dan honne
69
(dalam) ditarik juga ke bidang hukum. Maka, meski di luar
menerima penggunaan hukum modern, bila sudah sampai
tahap pelaksanaannya, mereka mendahulukan penyelesaian
dengan cara-cara Jepang.
Kemajuan ilmu pengetahuan tentang cara berpikir
manusia sudah menampilkan keragaman. Seratus tahun lalu,
hanya ada satu ukuran yang dipakai untuk mengukur
kemampuan berpikir seseorang, yaitu IQ (intellectual
quotient). Namun, selain kecerdasan rasional, kini ditemukan
dua macam cara berpikir lain, yang memakai (1) perasaan
dan (2) spiritualitas. Sekitar akhir abad ke-20, muncul model
berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari
makna dan nilai yang tersembunyi dalam objek yang sedang
ditelaah, yang disebut cara berpikir spiritual atau kecerdasan
spiritual. Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima
keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam
kreativitasnya, ia mungkin dapat bekerja dengan
mematahkan patokan yang ada (rule breaking) sekaligus
membentuk yang baru (rule making).
Menarik apa yang dikatakan Paul Scholten bahwa hukum
memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus
ditemukan. Kini, pendapat itu memperoleh dukungan dan
pembenaran kuat berdasar psikologi dengan ditemukannya
suatu macam kecerdasan manusia yang tertinggi, yaitu
kecerdasan spiritual. Hukum bukan buku telepon yang
hanya memuat daftar peraturan dan pasal, melainkan
sesuatu yang sarat makna dan nilai.
Penggunaan kecerdasan spiritual untuk membangkitkan
keterpurukan hukum memberi pesan penting kepada kita
untuk berani mencari jalan baru (rule breaking) dan tidak
membiarkan diri terkekang dengan cara menjalankan
hukum yang lama dan “tradisional”, yang jelas-jelas lebih
70
banyak melukai rasa keadilan. Pencarian makna lebih dalam
hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum
dan bernegara hukum. Kita semua dalam kapasitas masing-
masing (sebagai hakim, jaksa, birokrat, pendidik, dan lain-
lain) didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani
tentang makna hukum lebih dalam. Hukum hendaknya
dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan
perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan
(compassion) terhadap bangsa. Segala daya dan upaya
hendaknya dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan dan
menggugat cara berpikir yang membuat susah.
Mendorong bangkitnya orang-orang baik di sektor
publik adalah salah satu usaha untuk mengatasi kerisauan
atas fenomena kekasaran dan kekerasan massa yang kian
meningkat akhir-akhir ini. Demokrasi belum memunculkan
golongan rakyat yang memiliki standar kualifikasi mental,
tetapi lebih berupa “massa tanpa standar kualifikasi”.
Lembaga-lembaga yang seharusnya terhormat telah
diduduki oleh mereka yang tidak memiliki kualifikasi. Meski
mungkin jumlah orang-orang baik di negeri ini tidak sedikit,
umumnya mereka tidak atau tidak bisa muncul. Istilah “baik”
dipakai untuk menyebut mentalitas dan kualitas yang
terpuji. Manusia-manusia Indonesia yang baik kurang
memperoleh kesempatan untuk tampil sebagai pemimpin
dan pengatur masyarakat. Kita amat senang dengan
pergumulan untuk memunculkan elite, pemimpin, dan
golongan yang benar-benar berkualitas, bagaimana pun
cara untuk mencapai hal itu
Bernegara dengan Makna
Lebih dari setengah abad Indonesia berdiri, namun terus
saja negara ini mengalami gejolak dan pergolakan kendati,
71
dalam kapasitas formal, negara ini tetap berdiri dan diterima
oleh komunitas negara-negara (system of states) di dunia.
Bernegara secara spasial-formal tidak cukup. Diinginkan
juga negara yang bisa membuat rakyat bahagia. Wilayah-
wilayah yang semestinya sakral, seperti pendidikan,
pengadilan, parlemen, dan pelayanan publik, dijarah oleh
nafsu menumpuk materi dengan semangat kapitalis. Hampir
semuanya menjadi komoditas yang dihargai sebagai barang
ekonomi dan diburu serta diperjualbelikan.
Sejak didirikan, negara yang bernama Indonesia ini sarat
dengan ideologi, sarat dengan kehendak untuk melakukan
pencitraan diri (self defining) secara kultural, seperti UUD
yang bersifat kekeluargaan dan kemudian menyusul
membangun Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Hal itu
berarti bahwa kita tidak ingin sekadar bernegara secara
spasial dan memenuhi standar formal saja.
Negara, pemerintahan, dan bangsa yang berusaha untuk
membangun citra diri hanya bisa didukung dan diawaki oleh
pelaku-pelaku penuh dedikasi, empati, dan kreasi. Pelaku-
pelaku semacam itulah yang senantiasa ingin memberi arti
penuh kepada jabatan dan profesinya. Untuk mencapai
standar tersebut memang sangat berat, karena sudah masuk
ke dalam dimensi bernegara secara spiritual. Bekerja tidak
untuk mencari imbalan keduniaan, tetapi semata-mata
pengabdian: hanya ikhlas kepada Tuhan.
Penutup
Hukum progresif harus dimaknai sebagai pemahaman
skala besar dari sebuah ideologi baru yang sejatinya timbul
dari segala pergolakan realitas sosial. Esensi hukum
progresif berawal dari sikap dan perilaku manusia yang
diimbangi dengan harapan tentang nilai moral dan
72
kecerdasan spiritual. Tujuan akhir hukum progresif adalah
menciptakan masyarakat yang bahagia.
Dasar pemikiran hukum progresif sebenarnya masih
berupa konstruksi berpikir yang dini. Berupa embrio dari
sebuah aliran besar yang bisa ditarik ke belakang ataupun
ke depan. Hubungannya bisa diimbuhkan dengan
kehidupan bernegara yang penuh makna. Dalam
hubungannya dengan kehidupan bernegara, makna
progresivitas harusnya dapat menjadi pemicu untuk dapat
mengubah cara pandang para penegak hukum.
Segala hal-ihwal dari hukum progresif perlu didalami
lebih lanjut karena hukum progresif masih dalam taraf
pengembangan. Mungkin saja ke depan dapat kita temukan
hukum neoprogresif atau posprogresif. Dan itulah tugas kita
sebagai penerus Prof Satjipto Rahardjo. Mari berjuang. []
73
Hukum Progresif dan Keberanian
Kita36
SYANDI RAMA SABEKTI
TIDAK berbeda. Mungkin hal ini yang awalnya terlintas
dalam pikiran saya, seperti layaknya diskusi-diskusi
sebelumnya. Saya termasuk baru dalam urusan hukum
progresif. Saya mengenal istilah ini setelah menduduki
bangku Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro,
bersama-sama dengan para sahabat yang memiliki ciri khas,
pemikiran, opini, dan suku yang berbeda-beda.
Dalam pikiran saya, hukum progresif merupakan suatu
gagasan paling menantang dan menarik dalam literatur
hukum Indonesia saat ini. Betapa tidak. Hukum progresif
secara berani menggugat keberadaan hukum modern yang
dianggap telah mapan.
Pesona dari hukum progresif, menurut pemahaman saya,
terletak pada adanya suatu tawaran alternatif dalam cara
berhukum kita saat ini. Hukum progresif membongkar, dari
berbagai sudut pandang, mengenai hukum yang dianggap
telah mapan dan tidak tersentuh. Ketika hukum, saat ini,
dianggap tidak lagi dapat menyelesaikan persoalan yang
36 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Hukum Progresif: SebuahSintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), inidisampaikan dalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada 10 Desember 2012di Beranda Gedung Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
74
dihadapi oleh bangsa Indonesia, malah semakin menambah
potret buram tentang hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan kali ini, saya berusaha memberi
sedikit ulasan tentang pemikiran yang terkandung dalam
buku Prof Tjip, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum
Indonesia ini.
Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut
dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana
manusia melihat dan menggunakannya. Sebab, manusia
adalah penentunya meski dalam menghadapkan manusia
pada hukum akan menimbulkan pilihan-pilihan yang rumit.
Oleh karenanya, hukum harus terus berkembang. Hukum
secara terus menerus harus membangun dan mengubah
dirinya menuju suatu tingkat kesempurnaan yang lebih baik.
Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi”
(law as a process, law in the making).
Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban
(order) hanya bekerja melalui institusi-insititusi kenegaraan.
Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju
kepada hukum ideal dan menolak status quo, karena hukum
progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai suatu
teknologi yang tidak bernurani melainkan sebagai institusi
yang bermoral.
Hukum progresif selalu berlawanan dengan tradisi
analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek karena aliran
tersebut hanya memandang ke dalam hukum hukum dan
menyibukkan diri dengan pembahasan ke dalam hukum
yang dipandang sebagai suatu bangunan peraturan yang
dinilai sebagai sistematis dan logis. Sementara hal-hal yang
berada di luar hukum seperti manusia, masyarakat, dan
kesejahteraan ditepis oleh tradisi ini. Hukum progresif lebih
75
berbagi paham dengan legal realism dan freirechtslehre
karena, menurut paham itu, hukum tidak dilihat hanya dari
kacamata hukum, melainkan juga dari tujuan sosial yang
hendak dicapai beserta akibat-akibat yang timbul dari
bekerjanya hukum.
Hukum progresif tidak bergerak pada arah legalistik-
dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada arah
sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum
positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi hukum
juga bisa bergerak pada arah nonformal.
Hukum progresif merupakan
papan penunjuk yang selalu
memperingatkan bahwa hukum harus
terus menerus merobohkan,
mengganti, dan membebaskan hukum
yang mandek karena tidak mampu
melayani lingkungan yang selalu
berubah. Kehidupan manusia yang
selalu penuh dengan dinamika dan
berubah dari waktu ke waktu tidak
mungkin bisa diwadahi secara ketat ke dalam satu hukum
yang dianggap selesai dan tidak boleh diubah.
Memasuki Era Reformasi sejak tumbangnya Orde Baru
pada 1998 tidak membuat Indonesia berhasil dalam
membangun sistem hukum yang mendekati taraf ideal,
malah menimbulkan kekecewaan, meski pada pemerintahan
Habibie tercapai rekor produksi peraturan perundang-
undangan dalam masa transisi yang pendek. Saat itu, ada
anggapan bahwa dengan memproduksi peraturan
perundang-undangan secara massal telah dapat
menyelesaikan masalah. Tetapi, fakta berbicara berbeda
karena reformasi hukum bahkan tidak bergeming sesudah
76
diterbitkannya sejumlah undang-undang baru. Saya kira,
ada kekeliruan dalam cara bangsa ini berhukum.
Salah satu cara berhukum yang dirisaukan oleh hukum
progresif adalah ketika hukum secara mutlak berpegangan
pada kata-kata atau kalimat dalam teks hukum. Hukum
adalah suatu skema dan suatu skema yang final (finite
scheme). Hukum adalah teks dan akan tetap seperti itu
sebelum diubah oleh lembaga legislatif. Cara berhukum
semacam itu menjadikan hukum tidak mudah untuk
mengikuti dinamika kehidupan.
Memang, untuk menjadi seorang yang menjalankan
hukum secara bermakna, menemui banyak halangan. Hal ini
disebabkan oleh karena mengikuti apa yang tertulis
dianggap sebagai cara berhukum yang benar, sedangkan
menggali makna dari apa yang tertulis akan menyebabkan
seorang tersebut menemui masalah yang lebih besar. Oleh
karenanya, dibutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan
untuk menjalankan hukum progresif, yakni keberanian.
Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah
kesediaan untuk membebaskan diri dari status quo. Ide
tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan
faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri pelaku
(aktor) hukum, yaitu keberanian. Masuknya faktor
keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu
tidak hanya mengedepankan aturan, tetapi juga melihatnya
dari segi perilaku. Berhukum tidak hanya tekstual, melainkan
juga melibatkan predisposisi personal.
Berdasarkan pemahaman tadi, progresivitas menyangkut
peran pelaku maupun sistem itu sendiri, karena hukum
progresif memiliki dua ranah, yaitu sistem dan manusia.
Sistem hukum tidak kunjung menjadi progresif apabila kita
77
tidak memiliki badan pembuat undang-undang yang
progresif pula. Apabila produk legislatif tidak memberi
peluang kepada muncul dan berperannya kekuatan-
kekuatan progresif dalam hukum, maka sistem hukum hanya
akan menjadi sumber dari ketidakprogresifan. Hukum
progresif menghendaki cara berhukum yang aktif mencari
dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran
hukum dalam masyarakat menjadi lebih meningkat. Oleh
karenanya, hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-
pikiran yang inovatif dalam hukum untuk menembus
kebuntuan dan kemandekan.
Hukum progresif memang muncul dari kerisauan
masyarakat mengenai cara berhukum bangsa ini untuk
memecahkan problem-problem besar bangsa dan negara
kita. Cara-cara berhukum yang lama, yang hanya
mengandalkan penerapan undang-undang, sudah waktunya
ditinjau kembali. Selama ini, cara berhukum tersebut dirasa
kurang mampu untuk memecahkan problem sosial.
Penegakan hukum memang sudah dilakukan, tetapi belum
menyelesaikan problem sosial.
Suatu cara berhukum yang baru perlu dilakukan untuk
menembus kemacetan. Sejak hukum progresif menyimpan
banyak alternatif terhadap cara berhukum yang lama, semua
inti dan pokok dari hukum progresif sendiri perlu
dikeluarkan, mulai dari pengkonsepan kembali hukum,
paradigma, penegakan hukum, pembuatan hukum,
pendidikan hukum, dan lain-lain.
Melihat dan memahami, terlebih menerapkan, hukum
progresif mungkin akan membuat orang lain berpikir betapa
sulitnya menerapkan hukum progresif itu. Padahal, yang kita
butuhkan hanya kejujuran, empati, dan dedikasi, serta
keberanian. Pertanyaannya, beranikah kita? []
78
Kredo Penegakan Hukum
Progresif37
ALFAJRIN A TITAHELUW
REFORMASI serta kritik-kritik negatif terhadap sistem dan
penegakan hukum Indonesia memberikan kesempatan
kepada kita untuk memikirkan tentang apa yang akan kita
lakukan untuk keluar dari situasi buruk. Tetapi, bagaimana
pun, suasana keterpurukan masih menyisakan berkah, yaitu
memberikan kesempatan kepada kita untuk memikirkan
perubahan secara tidak tanggung-tanggung pada akar
filsafatnya.38
Pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-
konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang
abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak, termasuk ide
tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial
(Radbruch, 1961: 36).
Hukum yang masih abstrak tersebut perlu untuk
diwujudkan atau dijabarkan pada tatanan inilah yang
disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum
adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita
37 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Penegakan Hukum: SuatuTinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), ini disampaikandalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada 29 Oktober 2012 di BerandaAuditorium Imam Bardjo, SH, Universitas Diponegoro.38 Satjipto Raharadjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit BukuKompas, 2006), hlm 36.
79
yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum ke dalam
masyarakat. Ketika hukum dibuat dan wajib dilaksanakan,
penegakan hukum kemudian menjadi bagian yang tak
terpisahkan.
Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari
masyarakat sebagai basis dari bekerjanya hukum. Hukum
berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide yang bersifat
abstrak dengan dengan dunia
kenyataan sehari-hari. Oleh
karena hukum bergerak di antara
dua dunia yang berbeda,
akibatnya sering terjadi
ketegangan pada saat hukum
diterapkan. Saat hukum yang
sarat dengan nilai-nilai atau ide-
ide hendak diwujudkan, hukum
sangat terkait erat dengan
berbagai macam faktor yang
mempengaruhi dari lingkungan
seperti politik, sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat di mana hukum itu diberlakukan.
Misalnya saja kejadian di masa lalu ketika Undang-Undang
Pornografi mendapat tantangan dan penolakan oleh warga
Papua dikarenakan kondisi budaya masyarakatnya berbeda
dan bertolak belakang dengan undang-undang tersebut.
Dalam proses penegakan hukum, dibutuhkan sebuah
organisasi yang bisa menerapkan atau mengkonkretkan
hukum tersebut ke dalam masyarakat, seperti pengadilan,
kepolisian, dan lain-lain. Karena pada dasarnya hukum tidak
dapat dijalankan tanpa adanya sebuah organisasi yang
berfungsi mewujudkan atau merealisasikan hukum di
masyarakat.
80
Pembahasan penegakan hukum lebih dikhususkan pada
organisasi pengadilan. Penegakan hukum mengandung
supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak
hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi menjadi
tempat untuk mencari keadilan (searching of justice), tetapi
malah bergeser menjadi lembaga yang berkutat pada aturan
main dan prosedur. Dengan kata lain, pengadilan hanya
sebagai lembaga penerapan peraturan undang-undang dan
prosedur.
Dalam hukum modern, lembaga peradilan telah
kehilangan ruhnya sebagai house of justice. Hal ini sudah
menjadi rahasia umum, bahkan pada tatanan substansi
hukum pun dibuat secara khusus oleh lembaga khusus dan
mengikuti prosedur khusus yang disebut dengan legislasi.
Metode yang dipakai juga unik, yang didasarkan pada kredo
“peraturan dan logika”. Jadi, wajar saja jika pengadilan
sebagai organiasasi yang mewujudkan hukum yang bersifat
abstrak itu dikonkretisasi dalam kehidupan nyata bergeser
fungsinya menjadi lembaga penerapan peraturan
perundang-undangan atau, dengan kata lain, hakim adalah
corong undang-undang yang kadang dibutakan oleh kredo
peraturan tadi.
Menggunakan hukum modern tidak begitu saja
menjamin keadilan dapat diberikan secara otomatis. Hal ini
sangat tergantung pada bagaimana aparat penegak hukum
“menggunakan” atau “tidak menggunakan hukum”.
Walaupun aparat penegak hukum terlihat begitu sibuk
bekerja siang dan malam, situasi dunia berhukum kita tidak
berubah dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hukum
tetap gagal memberikan keadilan di tengah penderitaan dan
kemiskinan yang hampir melanda sebagian besar
masyarakat, supremasi hukum yang didengung-dengungkan
hanyalah menjadi tanda (sign) atau simbol tanpa makna.
81
Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (language
game) yang cenderung menipu dan mengecewakan karena
lebih mementingkan kaum borjuis atau kaum setan pemuja
kekayaan dan kekuasaan (istilah penulis untuk koruptor),
salah satunya adalah Gayus Tambunan yang bisa menonton
tenis di Bali dan masih banyak lagi koruptor-koruptor
lainnya yang tidur dan makan dengan nyenyak hasil
merampok uang penguasa negeri ini, yaitu rakyat. Sungguh
menyedihkan cara berhukum kita!
Lebih memalukan lagi, korupsi sudah merajalela pada
tingkatan lembaga penegak hukum yang melibatkan aktor
penegak hukum, mulai dari jaksa, hakim, panitera, dan
advokat, serta masyarakat pencari keadilan. Berbagai
perilaku kolutif sudah menjadi ciri khas ketika orang
berurusan dengan aparat penegak hukum, mulai tingkat
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai peninjauan
kembali di Mahkamah Agung. Kejahatan ini merupakan
bagian kecil dari potret gelap dunia penegakan hukum kita,
yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap
hukum dan tumbangnya keadilan. Sehingga, muncul
perkataan atau pernyataan bahwa “berikan saya jaksa dan
hakim (penegak hukum) yang baik, maka dengan jaksa dan
hakim baik tersebut saya akan mengubah hukum yang
buruk”.
Melihat realitas cara berhukum kita tadi, pada tatanan
penyelesaian hukum kita membutuhkan cara berhukum
yang luar biasa. Salah satu cara luar biasa yang ditawarkan
oleh sang begawan hukum Indonesia, Prof Satjipto
Rahardjo, untuk menghadapi kemelut dalam dunia
penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum
progresif.
82
Seyogianya hukum ditempatkan pada dimensi hakiki
atau filosofinya, sehingga hukum bisa menjadikan dirinya
sebagai anak yang tidak durhaka atas ibu (baca: masyarakat)
yang melahirkan serta membesarkannya. Penegakan hukum
progresif mengajak kita untuk melihat hukum secara
komprehensif atau utuh dan tidak memakai kacamata kuda
atau parsial. Penegakan hukum progresif menekankan pada
dua hal, yaitu, pertama, hukum ada untuk manusia dan
bukan manusia ada untuk hukum. Hukum tidak bisa bekerja
sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk
menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum,
sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomat
yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya
urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan
juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia
sebagai bagian dari perwujudan hukum. Melibatkan peranan
manusia adalah cara berhukum untuk keluar dari stagnasi
dominan yang membabi buta kepada teks undang-undang.
Kedua, hukum seyogianya tidak mempertahankan status
quo. Kita tidak harus terpenjara dalam undang-undang. Jika
undang-undang memiliki kontradiksi dengan pencapaian
keadilan, maka pilihan mengesampingkan undang-undang
bisa dilakukan demi menciptakan keadilan hukum dalam
masyarakat. Karena sesungguhnya semua teks tertulis
membutuhkan penafsiran, menjadi keliru jika mengatakan
hukum atau undang-undang itu sudah jelas. Undang-
undang cacat sejak lahir karena undang-undang memiliki
banyak kelemahan terutama masalah penggunaan bahasa.
Bahasa tulisan tidak bisa mengakomodiasi semua gagasan,
ide, cita hukum yang murni dalam masyarakat, yang sering
disebut oleh Prof Satjipto Rahardjo sebagai makna yang
tercecer.
83
Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum
tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan
(according to the letter), melainkan menurut semangat dan
makna lebih dalam (to the very meaning) dari undang-
undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan
kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan
spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang
dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi,
komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai
keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa
dilakukan.
Ide penegakan hukum progesif bukan muncul sebagai
sekadar latah yang diakibatkan kegemasan intelektual untuk
menjawab hiruk pikuk kemelut dunia berhukum kita yang
buta serta tuli dengan perasaan penguasa negara ini, yaitu
rakyat, melainkan ide penegakan hukum progresif lahir dari
refleksi intelektual yang cukup panjang. Pembahasan
penegakan hukum progresif tadi merupakan salah satu
rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal
kenapa penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe
penegakan hukum alternatif.
Tibalah kita pada sebuah kesimpulan bahwa “Kebenaran
hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai
kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai
kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-
undang“. Teruskan semangat penegakan hukum progresif
untuk kemaslahatan bangsa tercinta dan kebahagiaan
masyarakat. Salam Merah-Putih! []
85
Dinamika Hukum dalam Mengikuti
Perubahan Sosial39
RIAN ADHIVIRA
HUKUM tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat,
begitulah yang saya tangkap ketika membaca Hukum dan
Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta
Pengalaman-pengalaman di Indonesia. Dalam menjelaskan
perubahan yang terjadi, Satjipto Rahardjo, sang begawan,
menggunakan kerangka berpikir Parsonsian, di mana
tindakan menurut Parsons dapat diuraikan dalam beberapa
subsistem yang masing-masing subsistem tersebut memiliki
fungsi pokoknya.
39 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Perubahan Sosial: SuatuTinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), ini disampaikan pada jagonganrutin Kaum Tjipian pada 26 November 2012 di Beranda Auditorium ImamBardjo, SH, Universitas Diponegoro.
86
Terdapat hubungan di antara keempat subsistem
tersebut dengan fungsinya masing-masing, yaitu hubungan
antara tingkat informasi di mana subsistem sosial memiliki
tingkat yang paling tinggi, dan tingkat energi yang dimiliki
oleh organisme kelakuan yang disebut sebagai hubungan
sibernetika.40
Jadi, satu subsistem bersifat dependen karena
terpengaruh oleh subsistem-subsistem lainya. Sebagaimana
telah kita mengerti bersama, hukum dalam kerangka
berpikir Parsons menurut Satjipto Rahardjo terletak di
tengah-tengah proses keluaran dan masukan yang berasal
dari subsistem-subsistem tersebut.41
Dengan demikian, hukum, sebagaimana disampaikan
pula pada kesempatan lain oleh Satjipto Rahardjo dalam
Ilmu Hukum, adalah bidang ilmu yang senantiasa
terpengaruh oleh bidang keilmuan lain, interdependen.42
Karena hukum tidak bisa dipisahkan dari kondisi faktual
yang hendak diaturnya, hukum tidak dapat dilepaskan pula
40 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Teoretis sertaPengalaman-pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing,2009), hlm 25.41 Ibid., hlm 27. Lihat lebih jauh pada hlm 28-29. Masukan di bidangekonomi adalah bagaimana penyelesaian sengketa itu dilihat sebagaisuatu proses untuk mempertahankan kerjasama yang produktif danmenghasilkan keluaran berupa pengorganisasian atau penstrukturanmasyarakat. Pada bidang politik, masukan dan keluarannya adalahpetunjuk tentang apa dan bagaimana menjalankan fungsinya berupaproses politik. Masukan bidang budaya adalah adanya sosialisasi untukmenerima kehadiran institusi-institusi hukum yang keluarannya berupakeadilan.42 “lmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner di mana berbagaidisiplin ilmu pengetahuan diperlukan untuk membantu menerangkanberbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dimasyarakat.” Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hlm 7.
87
dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, di
mana dalam perubahan sosial tersebut menimbulkan pula
permasalahan-permasalahan sosial. Terdapat beberapa
aspek perubahan sosial yang berhubungan pula dengan
perubahan hukum, antara lain pendudukan, habitat fisik,
teknologi, dan struktur masyarakat dan kebudayaan.
Rasanya, ketiga perubahan
sosial yang disebutkan di awal
tidak perlu dijelaskan lagi. Yang
menarik untuk dibicarakan adalah
struktur masyarakat dan
kebudayaan. Dalam masyarakat
dan struktur kebudayaan terjadi
diferensiasi, yang mengurai
masyarakat pada bidang
spesialisasi masing-masing.
Perkembangan masyarakat menjadi
kompleks ketika diferensiasi ke
dalam komponen-komponen yang baru tersebut
menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar dibandingkan
dengan kemampuan dari komponen-komponen yang
digantikannya dalam menjalankan fungsi-fungsi primernya.
Berarti yang harus dilakukan di sini adalah bagaimana
menyatukan kembali komponen-komponen baru tersebut
dalam rangka mempertahankan stabilitas sosial. Di sinilah
diperlukan adanya hukum formal, terlebih dengan adanya
alat tukar universal, yaitu uang. Satjipto Rahardjo
menambahkan, masyarakat pada negara berkembang
mengalami perubahan yang kurang sempurna yang disebut
sebagai masyarakat prismatik, yang sudah mulai bergerak
meninggalkan struktur asli yang menyatu, namun belum
sampai kepada struktur masyarakat yang terpecah secara
baik. Artinya, fungsi-fungsi primer belum memperoleh
88
otonominya ataupun diferensiasi internalnya secara
sempurma.43
Lalu, bagaimana dengan posisi hukum dalam
menghadapi perubahan sosial tersebut? Mengharapkan
perubahan pada hukum tertulis akan memakan waktu dan
proses politik yang lama dibandingkan dengan kenyataan
faktual yang terus berubah. Perubahan hukum dituntut
untuk hadir apabila kesenjangan antara perubahan sosial
dan peraturan tertulis mencapai suatu titik tertentu yang
menimbukan kebutuhan mendesak. Karena apabila
kesenjangan tersebut dibiarkan, jarak yang ada antara
hukum dan kenyataan faktual membuat hukum tertulis
menjadi tidak berfungsi. Mengingat fungsinya sebagai
sarana pengintegrasi, sebenarnya ada fungsi lain yang
melekat pada hukum selain sebagai sarana kontrol sosial,
yaitu hukum sebagai sarana konstruksi sosial (social
engineering). Hukum sebagai sarana konstruksi sosial berarti
selain menjadi alat untuk meredam konflik, juga merupakan
sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.
Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai hal
tersebut, pembicaraan mengenai perubahan hukum
menurut Satjipto Rahardjo akan berkaitan dengan
perbincangan seputar lembaga pembentuk perundang-
undangan dan lembaga peradilan.44
Di antara kedua
lembaga tersebut, dalam menghadapi perubahan sosial,
Satjipto Rahardjo menaruh harapannya pada lembaga
peradilan.45
Dibandingkan dengan lembaga pembentuk
43 Satjipto Rahardjo, op. cit., hlm 49.44 Ibid., hlm 57.45 “Berhadapan dengan keadaan tersebut, maka memang beralasankiranya untuk berpendapat, perubahan hukum yang timbul sebagaijawaban terhadap tuntutan perubahan sosial itu relatif lebih lancarapabila terjadi melalui pengadilan.” Ibid., hlm 59.
89
perundangan (legislatif) yang memakan waktu lebih lama
dan proses politik yang panjang, lembaga peradilan dapat
menyesuaikan perubahan sosial dengan hukum yang ada
tanpa mengubahnya dengan melakukan penafsiran atasnya
yang kemudian terjawantahkan dalam bentuk putusan atau
yurisprudensi.
Dua Aspek Hukum
Sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, menurut
Satjipto Rahardjo, terdapat dua aspek hukum, yaitu sebagai
sarana kontrol sosial dan konstruksi sosial. Hukum sebagai
sarana kontrol sosial memiliki fungsi sebagai, pertama,
pembuat norma-norma, baik yang memberikan peruntukan
maupun yang menentukan hubungan antara orang dan
orang. Kedua, penyelesaian sengketa. Ketiga, menjamin
keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal
terjadi perubahan-perubahan.46
Mengingat kembali
kerangka Parsons, maka kita tidak dapat lagi melihat hukum
secara otonom saja. Dalam konteks bagaimana hukum
berhadapan dengan perubahan-perubahan yang ada, maka
bukan lagi bagaimana mempengaruhi tingkah laku orang
agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam keadaan
sekarang ini, melainkan menyangkut masalah perubahan-
perubahan yang dikehendaki.47
Yang demikian itu adalah
hukum sebagai sarana konstruksi sosial.
Hukum sebagai sarana kontrol sosial lebih
menitikberatkan pada pengaturan tingkah laku masyarakat,
yaitu sekadar mempertahankan pola-pola hubungan yang
ada pada masa sekarang. Meski demikian, hukum sebagai
sarana kontrol sosial juga turut pula berperan dalam
46 Ibid., hlm 111.47 Ibid., hlm 112.
90
perubahan sosial yang terjadi, yaitu dengan penentuan
perilaku-perilaku yang dikehendaki dan tidak dikehendaki
oleh lembaga legislatif yang berujung pada peraturan dan
penggunaannya berupa putusan pengadilan.
Di sisi lain, hukum sebagai sarana konstruksi sosial
adalah hukum yang secara sadar digunakan untuk mencapai
suatu keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau
untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.48
Menurut Hart, terdapat dua sistem hukum, yaitu, pertama,
adalah primary rules of obligations, yang menyandarkan
dirinya pada peraturan moral sehingga mengandung
beberapa kelemahan. Yang kedua adalah secondary rules of
obligations. Di sini, Hart memandang bahwa secondary rules
ini lebih dapat memberi kemanfaatan sebagai hukum
modern dibandingkan dengan primary rules. Menurut
Satjipto Rahardjo, fungsi hukum sudah mengalami
pergeseran untuk menjadi lebih aktif yang tidak merupakan
suatu perkembangan yang berdiri sendiri.49
Maka,
mengingat kurun waktu kemerdekaan Indonesia sampai
dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa telah terjadi
pergeseran hukum melalui kurun waktu tersebut.50
48 Ibid., hlm 129.49 Ibid., hlm 131.50 Di sini, Satjipto Rahardjo menyadur Roscoe Pound mengenai enamkriteria yang harus diamati sebagai sosiologi hukum antara lain (1)mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum; (2) melakukan studi sosiologis dalam rangkamempersiapkan peraturan perundangan [...] dengan turut pulamempertimbangkan efek yang ditimbulkan; (3) melakukan studi tetntangbagaimana membuat peraturan-peraturan hukum menjadi efektif (4);memperhatikan sejarah hukum; (5) penyelesaian individual; (6) segalatuntutan sebelumnya merupakan arena untuk mencapai suatu tujuan,yaitu tentang bagaimana mengusahakan secara lebih efektif agar tercapaitujuan-tujuan hukum itu. Ibid., hlm 135.
91
Jadi, pandangan hukum sebagai sarana konstruksi sosial
memandang hukum sebagai sarana untuk menimbulkan
akibat tertentu yang dikehendaki. Namun, tentu saja tujuan
tersebut tidak dapat dicapai semata dari segi peraturan
perundangan, melainkan pula mencakup pula aktivitas
birokrasi pelaksanaannya. Contoh yang diberikan dalam
buku ini mengenai hukum sebagai sarana konstruksi sosial
adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 yang selain
berfungsi sebagai dasar negara juga merupakan tiang
pancang tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, contoh lain
yang diberikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang
hendak menghilangkan corak kepemilikan tanah
sebelumnya agar kebih sesuai dengan perkembangan
zaman.
Modernisasi dan Pembangunan Hukum
Sebagaimana disinggung di awal, kerangka berpikir
Parsonsian dalam menjelaskan perihal perubahan sosial
menjelaskan bahwa perubahan sosial diiringi pula dengan
diferensiasi di mana struktur-struktur masyarakat menjadi
semakin mengkhususkan diri membentuk unit-unit khusus.
Modernisasi Indonesia tidak berasal dari dalam,
melainkan berawal dari sentuhan dengan pihak luar, yaitu
saat terjadinya kolonialisasi di mana budaya asli berhadapan
dengan pendatang.51
Pada masa itu, dengan proses
liberalisasi, turut memberikan dampaknya pada kehidupan
Indonesia, yaitu melalui perdagangan dan industrialisasi
yang pada awalnya lebih banyak dipegang oleh masyarakat
etnis Tionghoa. Keadaan berubah ketika Indonesia
memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945. Proses
51 Ibid., hlm 185.
92
perubahan yang tadinya berasal dari luar kini berasal dari
dalam, termasuk perihal pembangunan hukum.
Pembangunan hukum menurut Satjipto Rahardjo
mengandung makna ganda. Pertama, dia diartikan sebagai
suatu usaha untuk memperbarui hukum positif. Sementara,
kedua, pada sisi lain dapat pula diartikan sebagai suatu
usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa
pembangunan, yaitu dengan turut mengadakan perubahan-
perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat
yang sedang membangun.52
Dalam pembangunan hukum
tersebut, hal yang tidak dapat dihindarkan adalah bahan
dasar dari pembangunan tersebut, di mana nilai-nilai
Indonesia asli berhadapan dengan nilai-nilai modern. Maka,
terdapat sebuah hubungan di mana sistem hukum dan
perubahan sosial adalah dua hal yang saling memengaruhi.
Ada hal paradoksal yang dapat diangkat di sini. Pada
satu sisi, hukum adat menurut Satjipto Rahardjo memiliki
kelemahan dalam penggunaannya untuk mencapai tujuan-
tujuan pembangunan dan modernisasi. Namun, di sisi lain,
mengingat perubahan sosial yang terjadi karena
modernisasi dan pembangunan yang melahirkan
masyarakat plural, pada hukum positif yang berlaku bisa jadi
tidak diakui karena tidak sesuai dengan nilai-nilai asli.
Mengingat semakin sebuah peraturan terinstitusionalisasi,
semakin jauh pula jaraknya dari kenyataan masyarakat.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana
mengatasi permasalahan tersebut? Satjipto Rahardjo
mencontohkan kondisi masyarakat negara berkembang di
Afrika yang terpecah menjadi tiga bagian: traditional
societies, traditional-modernized, dan wholly modernized.
Pada masyarakat Afrika tersebut terjadi suatu proses adaptif,
52 Ibid., hlm 203.
93
di mana norma-norma dan lembaga-lembaga adat ternyata
dapat melayani kebutuhan akan modernisasi dan
pembangunan.53
Maka, dalam konsep pembangunan hukum, terdapat
beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:
pembuatan peraturan;
penyampaian isi peraturan;
kesiapan para pelaksana hukum untuk menjalankan
peranannya;
kesiapan warga negara untuk berbuat sesuai
dengan peranan yang diharapkan darinya;
pengamatan mengenai bekerjanya hukum dalam
masyarakat sehari-harinya.
Dengan menggunakan teori-teori sosial, Satjipto
Rahardjo dalam Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu
Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di
Indonesia, menggambarkan bagaimana keterkaitan antara
hukum dan hal yang hendak diaturnya, yang tidak dapat
dipisahkan. Demikianlah, maka giliran kita sekarang untuk
meneruskan semangat beliau. Suatu tugas yang berat. []
53 Ibid., hlm 210.
94
Mendudukkan Undang-Undang
Dasar?54
NINDI ACHID ARIFKI
BAGAIKAN sayur tanpa garam, itulah salah satu lirik dari
penyanyi Inul Daratista yang dulu sempat menjadi tren
pecinta lagu dangdut di Indonesia. Ungkapan tersebut
setidaknya cocok untuk menjelaskan fungsi undang-undang
dasar dengan tujuan dan cita bangsa. Undang-undang dasar
merupakan suatu tipe perundang-undangan yang khas,
yang sifatnya umum, sehingga mempunyai konsep yang
lebih luas dibandingkan dengan peraturan perundang-
undangan yang lain. Konsep ini berada dalam konteks
hukum dan masyarakatnya, sehingga tidak lagi dibatasi
sebagai urusan peraturan semata. Berdasarkan pemikiran
tersebut, undang-undang dasar dalam kedudukannya
sebagai dasar dari peraturan perundang-undangan yang
ada merupakan konstitusi yang mengekspresikan sejarah
dan cita-cita bangsa.
Sejarah pembentukan undang-undang dasar ini diawali
dengan adanya pembentukan komunitas politik oleh
54 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Mendudukkan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum,(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), inidisampaikan pada jagongan rutin Kaum Tjipian pada 12 November 2012di Beranda Auditorium Imam Bardjo, SH, Universitas Diponegoro.
95
manusia dalam suatu wilayah tertentu.55
Yang dimaksud di
sini bukan hanya hadir secara fisik melainkan ada secara
bersama-sama. Komunitas manusia ini tidak hanya menata
diri sendiri dari kelompoknya melainkan berinteraksi dengan
komunitas di luar kelompok tersebut.
Komunitas politik yang besar bisa disebut suatu negara.
Negara modern, dalam hal ini, merupakan bangunan
manusia dan politik dengan batas-batas yang jelas serta
mempunyai warga negara yang jelas pula, sehingga
melahirkan apa yang disebut kedaulatan. Seperti halnya
Indonesia, bertolak dari masa pelepasan penjajahan,
Indonesia lahir sebagai bangsa baru di mana dalam
melakukan pembentukan bangunan manusia dan bangunan
politiknya pertama tersebut menghasilkan Proklamasi dan
Undang-Undang Dasar, di mana undang-undang dasar
tersebut adalah dokumen yang menentukan arah dan cita-
cita suatu bangsa.
Kedudukan Undang-Undang Dasar
Undang-undang dasar merupakan konstitusi yang
bersifat sakral, yang mempunyai nilai-nilai sejarah sampai
persoalan cita-cita bangsa. Hal ini yang menjadikan undang-
undang dasar sebagai sesuatu yang masih dipertahankan
kesakralannya karena ikatan emosional yang ada, meskipun
sekarang adalah era modern, di mana hal-hal semacam
irasional dan sakral mulai bergeser keberadaannya. Begitu
pun yang terjadi pada konstitusi Indonesia yang berbentuk
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945).
55 Satjipto Rahardjo, Mendudukkan Undang-Undang Dasar: SuatuPembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum (Semarang: Badan PenerbitUniversitas Diponegoro, 2007), hlm 9.
96
Hal yang terus dipertahankan adalah mengenai makna
dari undang-undang tersebut, dilihat dari nilai historis dan
tujuan dari undang-undang dasar, sehingga akan terasa
khidmat bila kita mengerti apa yang terpenting dari makna
sebuah undang-undang dasar tersebut. Tidak hanya di
Indonesia, banyak negara yang mengangkat masalah latar
belakang historis mereka, sampai cita-cita bangsa tertuang
dalam sebuah konstitusi. Dengan demikian, dapat
dimengerti fungsi konstitusi itu sendiri adalah untuk
mengutuhkan kembali bangunan hukum suatu bangsa.56
Undang-undang dasar
merupakan suatu perjanjian
khidmat yang dibuat oleh bangsa
Indonesia, sehingga ia lebih
merupakan dokumen rohani
daripada teks hukum.57
Hal ini
dikarenakan sifatnya yang bersifat
umum. Hans Kelsen menyebutkan
bahwa semakin tinggi posisi dalam
orde normatif akan semakin kaya
akan kandungan moral atau asas-
asas umum dan semakin rendah
posisi itu menjadi semakin konkret
dan makin tipis kandungannya.58
Teori Hans Kelsen ini dikenal dengan teori stufenbau,
yaitu teori mengenai hierarki dari peraturan perundang-
undangan. Teori stufenbau menyebut mengenai norma
dasar dari suatu sistem hukum. Menurut Hans Kelsen, sistem
norma yang disebut sebagai tata hukum adalah suatu sistem
56 Ibid., hlm 31.57 Ibid., hlm 34.58 Ibid., hlm 35.
97
yang dinamis. Dalam hal ini, validitas norma hukum tidak
karena dirinya sendiri atau karena norma dasar memilikinya
dan, dengan demikian, memiliki kekuatan mengikat dengan
sendirinya.59 A norm is a valid legal norm by virtue of the
fact that it has been created according to a definite rule and
by virtue theoreof only.60Sehingga, dalam hal ini, norma
dasar merupakan suatu tata aturan hukum yang digunakan
sebagai norma pada tahap menerima atau kehilangan suatu
validitas.
Dalam konteks hukum di Indonesia, norma dasar
dimaksud adalah UUD 1945, yang merupakan suatu aturan
yang bersifat superior. UUD 1945 merupakan landasan
utama dalam sistem hukum terkait dengan pembentukan
peraturan perundang-undangan. UUD 1945 bersifat sebagai
norma superior karena ia menentukan pembuatan norma
yang lain, sementara peraturan di bawahnya merupakan
norma inferior. Kaitan antara norma superior dan inferior
merupakan titik dasar dari sistem hierarki pada teori
stufenbau dari Hans Kelsen. Hans Kelsen menyebutkan
bahwa “the relation between the norm regulating the
creation of another norm and this other norm may be
presented as a relationship of super- and sub-ordination,
which a spatial figure of speech. The norm determining the
creation of and other norm is the superior, the norm created
according to this regulation, the inferior norm.”61
Mengenai hierarki tersebut, Hans Kelsen membagi ke
dalam dua bentuk, yaitu Grundnorm dan Norm. Grundnorm
lebih diarahkan kepada Staatsfundamentalnorm, sedangkan
59 Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI2006), hlm 96.60 Ibid., hlm 113.61 Ibid., hlm 124.
98
Norm meliputi Staatsgrundgesetz, Fornelle Gesetz,
Verordnung, dan Autonome Satzung, seperti yang
dikemukakan oleh muridnya, Hans Nawiasky.
Jika dihubungkan dengan hierarki peraturan perundang-
undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan terdiri atas (a) UUD 1945; (b) Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan
Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah
Provinsi; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jika bentuk
hierarki ini dihubungkan dengan teori stufenbau, dapat
dilihat seperti pada bagan sebagai berikut.
Menurut Hans Kelsen, norma dasar adalah norma yang
menjadi sumber utama dan pengikat di antara semua norma
yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan
99
norma.62
Sehingga, undang-undang dasar merupakan
norma dasar yang berupa konstitusi formal yang merupakan
suatu dokumen resmi. Yang dimaksud dokumen resmi di
sini adalah seperangkat norma hukum yang dapat diubah di
bawah pengawasan ketentuan khusus, yang tujuannya
adalah untuk membentuk norma-norma hukum yang
bersifat umum.
Prof Satjipto Rahardjo dalam bukunya, Mendudukkan
Undang-Undang Dasar, menyebutkan bahwa reduksi dari
sebuah norma dasar akan mengalami sebuah perubahan
yang sangat besar, yang mendegradasikan suatu ide
menjadi semata-mata bentuk. Kaitannya dengan hukum
modern adalah bahwa undang-undang dasar lebih
diarahkan dalam bentuk hukum positif dan kehilangan isinya
sebagai sesuatu yang bernilai, seperti moral dan
kebenaran.63
Konstitusi dan Perwujudan Moral
Buku Mendudukkan Undang-Undang Dasar ini
menyebutkan mengenai tujuan hukum adalah untuk
manusia,64
sehingga yang menjadi objek permasalahan
adalah manusianya, bukan hukum atau peraturannya.
Sehingga pada hakikatnya kita memakanai hukum adalah
dengan menempatkan manusia pada titik pusat
permasalahannya. Ini dimaksudkan agar manusia terlindungi
harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga tidak
terjadi reduksi dalam penggunaan skema hukum. Melihat
keadaan tersebut, Prof Satjipto Rahardjo mengemukakan
bahwa sebaiknya hukum, undang-undang dasar, dan
62 Hans Kelsen,General Theory of Law and State (Massachusetts: HarvardUniversity Press, 1949) hlm 159.63 Satjipto Rahardjo, op. cit.., hlm 47.64 Ibid., hlm 36.
100
konstitusi dimaknai sebagai suatu dokumen antropologi,
karena begitu dalam dan luas dalam menyentuh kehidupan
manusia.65
Membaca undang-undang tidak hanya sekedar
membaca teksnya, dalam arti mengeja undang-undang.
Diartikan bahwa membaca undang-undang haruslah
ditekankan pada pendalaman maknanya. Undang-undang
dasar berisikan tentang hal-hal atau asas-asas umum
(general principle),66
sehingga dalam membaca undang-
undang tidak seperti membaca suatu dokumen moral, yang
menurut Prof Satjipto, dokumen moral cenderung bersifat
konkret, eksperimental dan kuantitatif.67
Sehingga, jika
terjadi demikian, pemaknaan undang-undang dasar menjadi
dangkal.
Hukum hidup di masyarakat, setiap ada kehidupan
manusia hukum itu ada (ubi societas ibi ius), sehingga
keberadaan hukum sifatnya abadi. Tetapi, ketika hal yang
terkandung dalam kehidupan tersebut diwujudkan dalam
sebuah hukum tertulis, ia menjadi tidak abadi lagi.68
Karena
ketika hukum berbentuk tertulis, keadaan yang ada hanyalah
bersifat abstrak, tidak dapat sesuai dengan nilai dasar dan
ideal yang ada di masyarakat yang sifatnya dimungkinkan
terjadi perubahan pada tatanan sosialnya, seperti yang
dikatakan Lon Fuller bahwa salah satu kegagalan membuat
hukum adalah apabila peraturan itu sering diubah-ubah,
sehingga “the subject can not orient his action by them.”69
Sehingga permasalahannya lebih ditekankan kepada
eksistensi hukum dalam keberadaannya mengatur bangsa
65 Ibid., hlm 40.66 Ibid., hlm 42.67 Ibid., hlm 42.68 Ibid., hlm 43.69 Ibid., hlm 45.
101
dan negara. Undang-undang dasar adalah hukum yang
mengatur eksistensi bangsa dan negara untuk tetap hadir
selama-lamanya, sehingga tidak mudah untuk
mengubahnya.70
Undang-undang, dalam keberadaannya, merupakan
hasil dari produk legislasi. Menurut Trubeck, sejak hukum
menjadi produk legislatif, maka ia tergolong ke dalam hasil
dari suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja
(purposive human action).71
Hukum dalam keberadaannya
telah mulai bergeser dari suatu ide menjadi suatu bentuk,
sehingga dalam memaknai hukum sekarang ini hanyalah
terfokus pada sebuah bentuk semata, sehingga akan
kehilangan makna nilai yang terkandung di dalamnya,
seperti nilai keadilan dan moral. Hukum tidak lagi diartikan
sebagai bentuk nilai yang bertujuan untuk keadilan,
melainkan diartikan sebagai bentuk format, prosedur, dan
pasal-pasal dalam undang-undang, sehingga makna hukum
yang sebenarnya telah tereduksi dalam sebuah bentuk
semata-mata, dan terjadi amputasi pada pemaknaan hukum
tersebut.
Berangkat dari hal tersebut, hukum sekarang ini tidaklah
utuh keberadaannya, bentuknya sudah terkotak-kotak, yang
sering dalam penyebutannya adalah perundang-undangan
yang terkotak-kotak dan mempunyai logikanya sendiri.72
Pemaknaan hukum yang terkotak-kotak tersebut
menjadikan hukum cenderung memisahkan diri satu dengan
yang lainnya. Ketika keutuhan hukum menjadi hilang atau
setidaknya tereduksi pemaknaannya, tujuan hukum yang
sebenarnya pun tidak akan tercapai.
70 Ibid., hlm 46.71 Ibid., hlm 47.72 Ibid., hlm 50.
102
Prof Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum yang
semula utuh dalam kepala pembuat hukum hilang
keutuhannya menjadi teks undang-undang. Teks undang-
undang ini hanyalah skeleton atau skema belaka dari
sesuatu yang pada awalnya utuh, sehingga dalam hal ini
seharusnya mengusahakan seperti yang disinggung
Tamanaha “the jurisprudence” menjadi “a general
jurisprudence of law and society”.73
Di atas telah dikatakan bahwa undang-undang dasar
merupakan general jurisprudence, sehingga dapat diartikan
berfungsi sebagai pemersatu peraturan perundang-
undangan yang terpisah-pisah atau terkotak-kotak tadi.
Dalam hal ini, asas-asas umum yang lebih ditekankan bukan
konkret pada memuat aturan suatu permasalahan, sehingga
kualitasnya disebut Prof Satjipto Rahadjo sebagai teks
moral. Mengacu pada undang-undang dasar sebagai asas
umum, hendaknya peraturan perundang-undangan yang
lain lebih berperspektif ke arah undang-undang dasar ini.
Sehingga, kedudukan undang-undang dasar sangat sentral
dan strategis, baik bagi pembuatan hukum maupun
pelaksanaannya.74
Dalam hal keberadaannya, undang-undang dasar
merupakan tipe undang-undang yang memuat kaidah serta
arah kepada produk-produk legislatif yang ada. Tetapi,
sekalipun dikehendaki bahwa undang-undang dasar
seharusnya dirumuskan kepada bahasa asas, kaidah, atau
moralitas, tetapi tidak selalu mudah berbuat seperti itu.75
73 Ibid., hlm 54.74 Ibid., hlm 61.75 Ibid., hlm 65.
103
Melihat kenyataan tersebut, ada sedikit asumsi yang
menyatakan bahwa undang-undang dasar dalam
keberadaannya sebagai suatu asas dan kaidah, merupakan
pandangan yang spesifik bersifat filsafat pada sebuah
negara. Meskipun disebutkan bahwa hukum tertulis tidak
abadi keberadaannya, diharapkan undang-undang dasar
lebih lama bertahan dibandingkan peraturan perundang-
undangan yang lain, karena sifat kaidah yang dikandungnya
itu.
Prof Satjipto Rahardjo menyinggung amendemen
konstitusi Amerika Serikat. Bahwa amendemen tersebut
dituangkan dalam bahasa yang khas, yaitu bahasa asas,
sehingga lebih difungsikan sebagai penutup kekurangan
pada undang-undang dasar, dan nantinya tidak
memorosotkan kualitas undang-undang dasar menjadi
peraturan biasa.
Selain itu, disinggung juga mengenai tesis Ronald
Dworkin. Pendapat Dworkin lebih menekankan pada
pembacaan konstitusi sebagai pembacaan terhadap asas
atau moralitas politik, sehingga Dworkin sering terjatuh
pada apa yang namanya interpretasi. Dikarenakan, moralitas
politik yang dijadikan rujukan itu bukan sesuatu yang jelas
dan intinya tidak pasti serta penuh dengan hal-hal yang
kontroversial karena merujuk pada kaidah moral yang
abstrak. Tetapi, Dworkin telah melakukan pembelajaran
yang baik tentang bagaimana konstitusi mampu
menjalankan fungsinya untuk memberikan panduan.
Dalam pembentukan konstitusi saat ini terjadi sindrom
struktur dan organisasi, sehingga sejarah kehidupan
manusia memasuki era formalisme. Undang-undang dasar
pun dianggap sebagai dokumen dasar yang menggerakkan
kehidupan bernegara dalam hal strukturasi konstitusi.
104
Namun, sekarang ini terdapat kelemahan dalam karakteristik
undang-undang dasar yang demikian itu, yang
menyebabkan batas antara undang-undang dasar dan
undang-undang biasa menjadi kabur. []
105
Pendidikan Hukum sebagai
Pendidikan Manusia76
RAHMAD SYAHRONI RAMBE
Membangun Fakultas Hukum sebagai Kekuatan
Sosial
Fakultas hukum adalah lembaga pembelajaran hukum
tingkat universiter. Dalam lembaga tersebut, berhimpun
tenaga-tenaga yang berijazah sarjana hukum yang disebut
sebagai dosen.77
Beberapa dekade terakhir, Indonesia
menghadapi banyak persoalan besar, bahkan mendasar.
Tetapi respons Fakultas Hukum belum terasa memadai.
Fakultas hukum juga belum tampil sebagai suatu kekuatan
sosial, waktu bangsa diterpa badai korupsi. Padahal, orang
sudah mulai bicara mengenai adanya suatu keadaan darurat.
Fakultas hukum belum tampil dengan mengatakan, “Di
sinilah saya, saya berdiri di sini, dan saya akan turut aktif
memberikan gagasan pemberantasan korupsi.”78
Urusan Indonesia tidak dapat hanya diserahkan kepada
pemerintah, partai-partai politik, dan kekuatan sosial lainnya
76 Karangan, yang merupakan ringkasan dari buku Pendidikan Hukumsebagai Pendidikan Manusia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), inidisampaikan dalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada 7 Januari 2013 diWarung Burjo, Pleburan, Semarang.77 Satjipto Rahardjo, Pendidikan hukum sebagai Pendidikan Manusia(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 1.78 Ibid., hlm 4.
106
dalam masyarakat. Dunia akademis juga perlu merebut
tempat dan menampilkan diri sebagai suatu kekuatan sosial
yang juga merasa memiliki saham untuk membantu secara
aktif agar Indonesia keluar dari kesulitan dan
keterpurukannya. Akademisi perlu membangun kepercayaan
diri karena akademisi adalah suatu komunitas dan suatu
kekuatan sosial yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu,
akademisi perlu secara aktif menyampaikan kontribusi,
dimulai dengan kepedulian terhadap permasalahan bangsa,
khususnya di bidang hukum dan sosial.79
Hukum dan Pendidikan Hukum dalam Masa Pem-
bangunan
Pendidikan hukum sebaiknya secara sistematis
dibicarakan dalam konteks sosialnya. Pendidikan hukum
sebagai konteks sosial memberikan isyarat bahwa sifatnya
terbuka untuk menampung dan memantau perkembangan
yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam suasana
perubahan sosial, bidang yang pertama sekali terkena
imbasnya adalah hukum. Indonesia adalah negara
berdasarkan hukum, sehingga karakteristik yang menonjol
dari manajemen berdasarkan hukum adalah selalu berusaha
untuk mencari landasan keabsahan suatu tindakan pada
hukum yang berlaku. Manajemen tersebut mempunyai ciri
prosedural yang sangat kuat. Tolok ukur yang dikenakan
kepada suatu tindakan adalah apakah tindakan itu
mempunyai dasar peraturan yang jelas. Dasar hukum lebih
luas dari dasar peraturan, dan dasar peraturan termasuk ke
dalam dasar hukum.80
79 Ibid., hlm 5-6.80 Ibid., hal. 7-8.
107
Apabila dikaitkan dengan pembangunan, pembangunan
membutuhkan kebebasan yang lebih besar daripada yang
diberikan oleh hukum yang lebih bersifat mengikat.
Sekalipun Indonesia berdasarkan hukum, sifat otonominya
mengalami pertukaran dengan kekuatan-kekuatan di luar
hukum, di mana sifat otonominya mengalami pertukaran
yang tinggi antara hukum dan kekuasaan. Hukum
menonjolkan ciri instrumentalnya karena hukum menjadi
saluran untuk menjalankan keputusan-keputusan politik
yang diambil. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial
merupakan contoh yang baik mengenai hal tersebut.81
Sistem hukum mempunyai
strukturnya sendiri yang dibangun
dari asas, konsep, keterpaduan
antarunsur, bidang, dan bagian, dan
sebagai kekuatan yang membentuk
bangunannya adalah prinsip
konsistensi logis. Terdapat dua
kategori yang termasuk dalam
pembangunan hukum, yakni,
pertama, sebagai upaya
menegakkan keadilan, kebenaran,
dan ketertiban. Kedua, untuk memantapkan dan
mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-
hasilnya. Mengkaitkan secara sistematik hukum kepada
pembangunan merupakan cara pendekatan terhadap
hukum secara antardisiplin. Dalam hubungannya, muncul
pengertian sarjana hukum sebagai “arsitek sosial”, yang
menunjuk kepada peranannya, baik sebagai pengendali
maupun perekayasa masyarakat pada umumnya dan
pembangunan pada khusunya. Fungsi pengendalian sosial
menunjuk kepada keadaan yang bersifat statis, yaitu
81 Ibid., hlm 9.
108
mempertahankan struktur tertentu dalam masyarakat. Di sini
hukum menjalankan fungsi pelayanan, yang memberi
kerangka hukum terhadap proses yang sudah memiliki
bentuk yang sedikit banyak sudah mapan.82
Masyarakat dan pembangunan adalah pengertian
abstrak. Oleh karena itu, apabila hukum ingin masuk serta
melibatkan diri secara aktif ke dalam pembangunan, maka
kedua pengertian itu harus dikonkretkan. Peranan hukum
dalam pembangunan berkaitan dengan kemampuan hukum
dalam menangani permasalahan dalam masyarakat.
Pemikiran tentang hukum dalam pembangunan dituangkan
dalam beberapa hal pokok, yakni sifat konseptual, secara
sistematis berorientasi kepada masa depan, kajiannya tidak
hanya normatif, tetapi interdisipliner, dan studi hukum
merupakan kajian yang terbuka dan peka terhadap
perubahan.83
Pendidikan Hukum Indonesia
Pemerintah kolonial Belanda tergolong lambat dalam
membangun institusi pendidikan menengah dan tinggi di
Indonesia. Dari sekitar 300 tahun penjajahannya terhadap
Indonesia, hanya lebih kurang 25 tahun terakhir digunakan
untuk membangun pendidikan menengah dan tinggi. Dan,
82 Ibid., hlm 9-12.83 Ibid., hlm 13-16.
109
pembelajaran hukum dilakukan melalui pemahaman secara
abstrak dan umum untuk kemudian turun membicarakan
hal-hal yang lebih konkret. Namun demikian, segalanya
berlangsung dalam bingkai sistem hukum positif atau
peraturan perundang-undangan. Pembelajaran hukum
diawali dari konsep-konsep abstrak yang harus “dikunyah”
para mahasiswa muda, jauh dari realitas hukum di
masyarakat.84
Rechtshogeschool didirikan di Jakarta pada 1924.
Pemerintah kolonial membangun sekolah-sekolah dan
pendidikan tinggi sebagai balas jasa terhadap Indonesia
yang telah dikeruk kekayaannya selama ratusan tahun.
Indonesia pada waktu itu menjadi pilar-pilar Belanda. Hal ini
dapat dilihat dari kalimat “Indie verloren ruinpspoed
geboren” (kehilangan Indonesia berarti malapetaka). Pada
awal pembukaan pendidikan hukum di Indonesia,
pendidikan dirancang untuk menyiapan tenaga terampil
dalam menggunakan hukum positif. Lulusannya bergelar
meester in de rechten (Mr) yang berlaku untuk para lulusan
sampai tahun 1962. Rancangan tersebut tercermin dari
nama Ilogeschool (sekolah tinggi) yang berkonotasi
pendidikan keterampilan (skill development), bukan
pendidikan ilmu hukum (rechtswetenschap) yang
sebenarnya.85
Pada awal kemerdekaan, Indonesia memiliki dua fakultas
hukum negeri, yaitu Universitas Indonesia (Jakarta), sebagai
kelanjutan dari Rechtshogeshool dan Universitas Gadjah
Mada (Yogyakarta). Berbeda dengan politik pendidikan
hukum dimasa kolonial, di masa kemerdekaan dirasakan
perlunyaperubahan sesuai dengan situasi sebagai negara
84 Ibid., hlm 17.85 Ibid., hlm 18-20.
110
merdeka. Perubahan-perubahan penting baru dirasakan dua
dekade setelah kemerdekaan di mana pola
mempertahankan status quo sudah mulai diubah menjadi
lebih dinamis. Pendidikan hukum di Indonesia berubah
menjadi Indonesian-based policy, atau society-based policy
atau development-based policy.
Pendidikan hukum pada tahun 1970-an mengalami
dinamika tidak hanya pada ranah substansi, melainkan juga
metodologi pembelajaran. Pada ranah substantif, hukum
tidak lagi hanya dipahami dalam batas-batas hukum positif
tetapi juga dilihat, dipahami, dan dipelajari dalam konteks
sosial yang lebih luas. Pada metode pembelajaran, konsep
dan teori hukum klasik serta cara-cara pembelajaran yang
menekankan pada lecturing, mulai banyak mendapat
gugatan dan diperkenalkannya metode clinical legal
education yang melibatkan para mahasiswa secara aktif
untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang nyata.86
Pada pertengahan tahun 1980-an terjadi perubahan
sangat besar dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini
dikarenakan adanya tipe pembelajaran baru yang disebut
sebagai pendidikan keilmuan (scientific education, scientific
program). Dokumen hukum yang menjadi dasar
pembentukan pendidikan pascasarjana tidak mencantumkan
pendidikan keilmuan, tetapi Universitas Diponegoro
menafsirkannya sebagai pendidikan keilmuan. Pendidikan
keilmuan tidak menekankan pada pengembangan
keterampilan, melainkan lebih kepada pencarian dan
pengungkapan kebenaran.87
86 Ibid., hlm 23-28.87 Ibid., hlm 30-31.
111
Memperbarui Pendidikan Hukum Indonesia: Untuk
Apa dan Ke Arah Mana?
Pendidikan bukanlah lembaga yang otonom mutlak,
melainkan merupakan bagian dari proses sosial besar yang
melingkupinya. Pertukaran antara dunia pendidikan dan
lingkungan sosial itulah yang menyebabkan timbulnya
dinamika dan tuntutan perubahan terhadap lembaga
tersebut. Pendidikan hukum merupakan sekolah profesional
dan lembaga ilmu, yakni lembaga tempat suatu bidang ilmu
dikaji dan dikembangkan. Oleh karena itu, fakultas hukum
tidak hanya menyiapkan keterampilan, melainkan berurusan
dengan metode-metode yang dipakai dalam mempelajari
objeknya.
Pemikiran hukum rechtsdogmatiek tidak akan mampu
menjangkau dan menjelaskan proses transformasi sosial
yang terjadi. Hal ini dikarenakan pemikiran hukum yang
dogmatis memang tidak disiapkan untuk mengamati
interaksi antara proses perubahan di semua bidang hukum.
Kita dapat melakukannya jika kita mampu memahami
hukum dan proses-prosesnya sebagai bagian dari proses
sosial yang lebih besar. Hukum adalah lembaga yang
kompleks, sehingga tidak hanya dipahami dengan saksama
apabila menggunakan satu cara pendekatan saja.88
Ciri lain dari pendidikan hukum yaitu sebagai suatu
pendidikan umum, artinya membentuk manusia berkualitas
yang lengkap daripada sekedar teknokrat. Fakultas hukum
membekali alumninya dengan suatu sikap dan pengetahuan
dasar untuk nantinya dapat mengembangkan dirinya
sebagai seorang intelektual. Jadi, pendidikan hukum juga
88 Ibid., hlm 39-43.
112
berciri pendidikan suatu kualitas manusia dan intelektual
berkemampuan hukum yang luas.
Sifat pendidikan yang memberikan bekal untuk menjadi
seorang intelektual dengan kemampuan atau potensi yang
luas, pasti akan lebih berguna daripada pendidikan yang
sempit. Dalam hal ini, diperlukan tenaga-tenaga yang tidak
hanya profesional, tetapi juga memiliki dedikasi yang cukup.
Jenjang pendidikan di Indonesia bisa disebut dengan tiga
jenjang pendidikan, yang masing-masing disebut program.
Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.89
Program Tujuan Sifat Pendidikan
S-1 Tenaga terampil untuk masuk
ke pasaran kerja
Vocational training
yang ilmiah
S-2 Pengembangan ilmiah Melihat hukum
dengan
pandangan kritis
ke arah theory
building
S-3 Pengembangan ilmiah lebih
lanjut
SDA.
Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia
Sejak ribuan tahun sebelum kehadiran hukum modern,
berbicara mengenai hukum adalah berbicara mengenai
keadilan dan pencarian keadilan. Hukum dianggap muncul
secara alami dalam interaksi antara para anggota
89 Ibid., hlm 46-51.
113
masyarakat dengan nama yang bermacam-macam. Selama
ribuan tahun dikenal apa yang disebut hukum alam, di mana
dunia hukum menjadi tempat pertarungan hati (keadilan)
daripada pikiran (ratio). Kelahiran hukum modern telah
merombak secara fundamental tatanan sosial yang lama
menjadi suatu tatanan yang terstruktur secara rasional. Salah
satu hal yang terpenting adalah tergusurnya keadilan
sebagai satu-satunya parameter. Sehingga, memasuki dunia
hukum bukan lagi berburu keadilan melainkan
mengoperasikan substansi hukum modern, baik peraturan
maupun prosedurnya. Pengadilan tidak lagi menjadi “rumah
keadilan”, melainkan rumah undang-undang dan prosedur.90
Perlahan-lahan, hukum semakin bergeser menjadi
teknologi. Pekerjaan hukum yang sudah sarat dengan
penerapan undang-undang berikut prosedur, membutuhkan
skill yang bersifat teknis dan teknologis. Maka dapat
dibicarakan tentang teknologi berperkara. Tidak ada satu
pun hal yang berhubungan dengan keadilan, empati,
kejujuran, dan modalitas spiritual lainnya. Pembelajaran
hukum yang menjadi pabrik tempat memproduksi ahli-ahli
hukum tidak dapat secara bebas menentukan apa yang
ingin diajarkannya. Pembelajaran hukum harus menyiapkan
tenaga-tenaga yang nanti menjadi operator yang
menjalankan mesin hukum modern.
Lembaga pendidikan hukum harus mengacu kepada
peta besar hukum modern. Apabila hukum modern sudah
bergeser menjadi teknologi, kurikulum pendidikannya pun
menjadi demikian. Dengan demikian, hukum sudah kurang
dapat dipercaya untuk menjaga kemanusiaan. Selain itu,
masuknya kapitalisme dalam hukum dari pembelajaran
hukum menyebabkan hukum menjadi komoditas di mana
90 Ibid., hlm 57-59
114
persoalan pokoknya adalah bagaimana hukum menjadi alat
dan teknologi untuk mendapatkan keuntungan material.
Orang menjalankan pendidikan hukum untuk menjadi ahli
hukum dengan cita-cita dan harapan untuk mendapat
keuntungan dan kemewahan material, serta memenangkan
suatu perkara dibanding memikirkan dimensi kemanusiaan
hukum.91
Dengan demikian, salah satu gagasan untuk mengubah
itu semua adalah “pendidikan hukum berbasis manusia”.
Untuk itu, pertama harus diusahakan agar pendidikan
hukum bergeser dari profesional menjadi pro-manusia.
Maka, setiap berhadapan dengan masalah hukum kita tidak
langsung berhadapan dengan “perkara hukum”, melainkan
dengan “masalah manusia dan kemanusiaan”.
Pendidikan hukum dijadikan tempat untuk
mematangkan kemanusiaan di mana pendidikan
didahulukan untuk menjadi manusia serta bagaimana
menolong manusia yang susah dan menderita. Pertama-
tama, para mahasiswa baru sudah dihadapkan kepada
persoalan kemanusiaan yang akan menjadi modal dan
landasan mereka begitu melangkah ke dunia hukum.
Gagasan tentang pendidikan hukum berbasis manusia dan
kemanusiaan mendorong para pengelola program
pendidikan hukum untuk mendekonstruksi dan
merekonstruksi hal-hal dan cara-cara yang selama ini
dijalankan.92
[]
91 Ibid., hlm 59-64.92 Ibid., hlm 65-67.
115
Polisi Indonesia di Tengah
Perubahan Sosial93
LILIK HARYADI
BUKU berjudul Membangun Polisi Sipil karangan Prof
Satipto Raharjo ini agaknya menuju kepada pembahasan
wajah hukum dengan kajian sosial. Bagi Prof Tjip, menjadi
semacam khayalan belaka ketika seseorang yang
mempelajari hukum dan pada saat yang bersamaan
menyepelekan faktor sosial. Kajian mengenai kepolisian juga
sempat menjadi hal menarik yang dilakukan di lingkungan
Universitas Diponegoro, yaitu di Pusat Studi Kepolisian,
namun namanya belakangan seakan terlupakan tanpa ada
kajian lagi dan ditinggalkan seperti ruangannya yang tidak
tersentuh lagi. Padahal, Prof Tjip dalam kurun waktu 1991-
2000 menulis sebanyak 178 artikel tentang hukum, sebanyak
36 tulisan dimuat surat kabar selain harian Kompas dan 142
lainnya dimuat di Kompas. Prof Tjip menulis secara khusus
mengenai polisi Indonesia dalam 33 artikel.
Polisi diibaratkan sebagai wajah hukum kita sehari-hari.
Seperti kita ketahui, menurut Friedman, setidaknya ada tiga
faktor, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum. Polisi
dalam perubahan sosial seperti sekarang ini ditempatkan ke
93 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Membangun Polisi Sipil:Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan (Jakarta: Penerbit BukuKompas, 2010), ini disampaikan dalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada17 Desember 2012 di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang.
116
dalam salah satu cabang dari struktur hukum. Meskipun
seharusnya hukum bukan hanya melulu pada struktur,
perilaku dan kelembagaan polisi kerap dianggap sebagai
keadaan hukum di Indonesia.
Dalam membahas polisi di
Indonesia, Prof Tjip agaknya
berada pada kondisi
pemakaian ilmu sosial sebagai
penelaah permasalahan
hukum. Sosiologi digunakan
sebagai tool of analysis dalam
berbagai fenomena hukum
yang dikaji. Dalam buku ini,
sosiologilah yang dipakai
sebagai alat untuk
menjabarkan polisi dalam dua
bidang, yaitu kelembagaan dan
perilaku polisi. Polisi
didudukkan sebagai subjek dalam pengkajian perubahan
atau dinamika sosial yang terjadi dalam dunia hukum.
Perubahan dinamika sosial dalam masyarakat dijadikan
aspek untuk membaca kepolisian Indonesia. Dengan
perubahan sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran modern
dan melahirkan perkembangan ilmu, paradigma terhadap
keadaan hukum berubah. Kemajuan di bidang teknologi
juga menjadi tanda bergeraknya pola kehidupan, dan juga
batas-batas wilayah yang semakin mengglobal memaksa
dunia hukum dan kepolisian Indonesia segera mengubah
paradigma jika lembaga kepolisian Indonesia tidak mau
menjadi sangat usang dalam menghadapi masyarakat
Indonesia yang menuju ke arah globalisasi.
117
Dalam masa demokrasi yang sarat dengan benturan
kepentingan untuk mempertahankan status quo, polisi juga
dihadapkan pada dua pilihan: membela rezim ataukah
berada pada masyarakat yang pro-rakyat. Ini dikatakan
pilihan sulit bagi polisi untuk mendudukan dirinya pada
transisi perubahan sosial. Akankah harus keluar dari militer
dan mencoba membangun karakter sipil sebagai a civilian in
uniform atau masih berada dalam penyambung kekuasaan.
Sejarah panjang polisi yang dipaksa berkarakter militer
sekarang berangsur harus bertindak sebagai sipil.
Menurut Prof Tjip, tantangan perubahan dalam diri
polisi Indonesia adalah bagaimana ia bertindak dan
memperlakukan masyarakat sebagai orang sipil. Polisi harus
menempatkan diri kapan bertindak dengan karaker a strong
hand of society dan kapan harus bertindak dengan karaker
soft hand of society. Paradigma ganda yang dimaksud yang
pertama adalah paradigma kekuasaan. Paradigma ini
menunjukkan, polisi dalam jenjang vertikal berhadapan
dengan rakyat. Oleh hukum, polisi diberi kewenangan untuk
menegakkan hukum. Di sini, hubungan polisi dengan rakyat
adalah atas-bawah atau hierarkis, di mana polisi ada pada
kedudukan yang memaksa, sedangkan rakyat wajib
mematuhi.
Paradigma yang kedua adalah kemitraan dan
kesejajaran. Di sini, polisi dan rakyat berada pada aras yang
sama atau hubungan yang bersifat horisontal. Tugas yang
oleh hukum diberikan kepada polisi adalah mengayomi,
melindungi, membimbing, dan melayani masyarakat. Yang
terjadi sekarang, polisi masih dalam proses menuju, belum
sampai pada sesuatu yang dituju. Kita lihat sekarang ini
makin banyak permasalahan kompleks yang ditimbulkan
oleh polisi Indonesia, tindakan represif pun masih terlihat.
118
Semua itu tidak terlihat mudah begitu saja untuk
dijalankan. Beberapa permasalahan seperti sumber daya
polisi yang belum mampu memahami sepenuhnya makna
hukum secara mendetail, menjadikan hukum berjalan sesuai
dengan tangan polisi yang memegangnya, padahal polisi itu
merupakan tangan pertama dalam penegakan hukum.
Apabila polisi masih berparadigma pemaksaan kekuasaan
negara terhadap rakyat, maka hukum masih dimaknai pula
sebagai perintah penguasa terhadap rakyatnya yang dalam
hal ini masih berada dalam konteks negara jajahan.
Lembaga kepolisian masih berupa lembaga yang
eksklusif bagi penegakan hukum yang berbasis keadilan.
Masih banyak perkara hukum sehari-hari yang
dibengkokkan di depan polisi yang tidak mengerti arti
keadilan. Keadilan acapkali dikesampingkan daripada
kepastian hukum sesuai dengan peraturan tertulis yang
dipegang oleh polisi. Padahal, kehidupan masyarakat yang
dinamis semakin berkembang seiring perkembangan zaman
itu sendiri. Tumbuhnya kreasi modern dengan
perkembangan teknologi mengubah pola kehidupan
modern yang pada akhirnya juga melahirkan tatanan
institusi baru seperti demokrasi, hukum modern, dan
birokrasi. Kepolisian akhirnya dituntut untuk mampu
berakomodasi dengan kemajuan dalam teknologi dan juga
derivat sosialnya tersebut, atau memilih untuk menjadi kuno
dan ketinggalan.
Sedikit menilik ke belakang, sejarah panjang kepolisian
Indonesia yang pada awalnya diposisikan sebagai militer
bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
dengan paradigma militer. Kesalahan mendasar apabila
polisi diposisikan ke dalam tataran militer. Kesalahan
mendasar ini diakhiri dengan dipisahkannya Polri dari ABRI,
dan ini menjadi tonggak perubahan polisi baru. Prof Tjip
119
memberikan pandangan bahwa lebih dari itu harus ada
tonggak baru di mana peralihan dari polisi baru itu ke dalam
polisi sipil dalam masyarakat sekarang ini.
Mengembangkan Polisi Sipil
Lembaga kepolisian terus bertransformasi seiring
dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Namun,
pekerjaan menjadikan polisi Indonesia sebagai polisi sipil
membutuhkan waktu yang panjang, karena posisi Polri
dalam ABRI di masa lalu telah memperparah kerusakan
profesionalisme polisi. Paradigma kepolisian masih belum
sepenuhnya menjadikan polisi berjiwa sipil. Segi sumber
daya polisi juga belum mampu memenuhi kebutuhan untuk
menegakkan hukum; rekrutmen yang dilakukan polisi saat
ini masih rendah. Dalam buku ini, dijelaskan pula tingkat
pendidikan mempengaruhi manusia untuk menerima
tentang keterbukaan, hak asasi manusia, dan perubahan.
Makna polisi yang berwatak sipil dapat dikatakan
dengan sederhana sebagai suatu cara perpolisian yang
menempatkan pada titik pusat perhatian. Artinya, cara-cara
polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan
manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.
Sehingga, dimensi moral menjadi kental dalam pekerjaan
polisi. Bukan hanya menjalankan pekerjaan secara pendek
dengan menggunakan cara yang gampang memaksa dan
menggunakan kekerasan belaka, tetapi juga bersedia
mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan
manusia. Polisi yang berjiwa pada nilai-nilai dan bukan
menjadi boneka yang bergerak atas dasar komando searah
dari atasan kepada bawahan. Tetapi yang terjadi masih
banyak polisi yang tunduk pada peraturan-peraturan yang
mengatur tugas polisi tanpa mau menangkap makna
menyeluruh dari fungsi polisi. Diistilahkan dalam buku ini
120
sebagai “robot-robot hukum belaka” yang bergerak dengan
kaku mendasarkan pada patokan pasti yang itu justru
menjadikan polisi makin jauh dari jiwa sipil.
Polisi kerap kali dikaitkan dengan hak asasi manusia,
seperti dalam sejarah kelam kepolisian Indonesia, di mana
polisi-polisi terlibat dalam Tragedi Trisakti, dan sampai
sekarang masyarakat tidak pernah tahu siapa yang
sebenarnya bertanggung jawab dalam tragedi yang
menewaskan empat mahasiswa itu. Belakangan, polisi juga
menjadi lembaga yang bersinggungan dengan lembaga lain
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses
penyidikan dan penyelidikan dalam kasus korupsi.
Dalam bab akhir buku ini, berjudul “Polisi yang
Progresif”, disebutkan bahwa arah pembangunan kepolisian
Indonesia di masa yang akan datang menjadi polisi yang
progresif yang berjiwa sipil. Pekerjaan polisi sulit diatur
hukum. Mengapa demikian? Karena ia bergelimang interaksi
dengan manusia dan masyarakat. Disebutkan bahwa
karakteristik polisi sebagai penegak hukum jalanan. Polisi
berbeda dari jaksa dan hakim yang disebut sebagai penegak
hukum gedongan. Polisi adalah petugas lapangan, bekerja
tanpa sarung tangan, dan tidak berdiri di belakang loket.
Mereka berada langsung di tengah masyarakat baik dan
jahat. Di Amerika Serikat, jika seorang polisi berpamitan
kepada istri untuk berangkat bekerja, itu menjadi pertanda
salam perpisahan selamanya. Bagaimana dengan di
Indonesia?
Maka dari itu, polisi harus progresif. Nihil apabila polisi
hanya didasarkan kepada peraturan hukum yang ada.
Berapa ratus undang-undang dibutuhkan, berapa ribu
halaman kitab hukum harus disediakan jika pekerjaan polisi
ingin diatur secara tuntas dan rinci. Wacana diskresi dalam
121
kepolisian menjadi contoh keleluasaan dan kelonggaran
yang diperlukan bagi pekerjaan polisi. Kekakuan pengaturan
polisi bisa fatal. Untuk mewadahi keleluasaan dan
kelonggaran itulah, maka ada pilihan untuk melakukan
tindakan (course of action). Semisal bagaimana polisi harus
bertindak ketika ada seorang dekil, miskin, dan kurus
melakukan kejahatan kecil: mungkin bisa saja polisi
membiarkannya pergi dan bahkan memberikannya uang.
Maka, hukum progresif bisa dilaksanakan oleh polisi, dan
berpeluang besar karena hukum menyediakan banyak
peluang agar polisi dapat menjadi pahlawan bagi
bangsanya, dengan bertindak progresif, membuat pilihan-
pilihan tepat dalam pekerjaannya. Namun, peluang itu jika
tidak dijiwai dengan nilai-nilai dapat menjerumuskan polisi
itu ke jurang “kenistaan” dengan menjadi polisi korup, suka
melakukan kekerasan, pelecehan (harassment), dan lain
sebagainya.
Pertanyaan yang diajukan sekarang ini adalah apakah
kepolisian kita sudah memenuhi keadaan dan panggilan
masa, yaitu menjadi alat suatu negara yang merdeka dan
demokratis, dan bukan alat kekuasaan? Dapatkah polisi
bertindak secara sipil dengan hukum yang progresif
berlandaskan nilai-nilai dan tidak sebatas pada prosedural?
Hal itulah yang perlu kita diskusikan bersama. Prof Tjip
tidak memaksakan untuk mengartikan polisi sebagai apa,
namun tetap membiarkan wacana pemikiran terus bergerak
sesuai dengan dinamika sosial agar hasil dari pemikiran
memang benar-benar bermuara kepada tujuan
menyejahterakan rakyat dengan hukum. []
122
Rakyat Bahagia di Negara Hukum94
JAMES MARIHOT PANGGABEAN
MESKI rezim telah berganti, penegakan hukum di negeri ini
semakin terpuruk dan, suka tidak suka, keterpurukan itu
berpengaruh terhadap sektor kehidupan lain, terutama
sektor perekonomian. Sejak dilengserkannya Soeharto dan
bergantinya pemimpin yang baru dalam pemerintahan
berlabel demokrasi dengan landasan negara hukum,
semakin besarlah peran yang diharapkan dari Mahkamah
Agung.
Institusi yang dikenal sebagai Mahkamah Agung (di
negara-negara berbahasa Inggris disebut sebagai The
Supreme Court dan negara-negara berbahasa Belanda
disebut sebagai Hoge Raad) merupakan instrumen yang
terpenting dalam upaya pencarian keadilan, dan bukan
sekadar sebagai tempat di mana hukum formal berproses.
Penulis ingin menyatakan bahwa meski rezim Soeharto telah
runtuh secara formal, namun dalam kenyataan sosiologis,
roh rezim Soeharto masih berkuasa dan hidup dalam jiwa
kepemimpinan saat ini.
Soeharto bersama anak-cucunya masih memiliki
kekuasaan yang masih sangat besar, di mana dengan
94 Karangan, yang merupakan ulasan dari buku Negara Hukum yangMembahagiakan Rakyatnya (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), inidisampaikan dalam jagongan rutin Kaum Tjipian pada 11 Oktober 2012,di Ruang C104, Gedung Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
123
kekuasaan tersebut mereka masih dapat melakukan banyak
hal yang memengaruhi perjalanan kehidupan di negeri ini.
Selain itu, dalam pemerintahan yang sering menamakan diri
sebagai pemerintahan Reformasi ini, dalam kenyataannya
masih terikut sosok-sosok rezim otoriter Soeharto, sosok-
sosok yang sangat terlibat dalam penentuan kebijakan
dalam era Soeharto, sehingga
suka tidak suka, mereka turut
mempunyai saham yang cukup
besar dalam kehancuran
perekonomian dan moral bangsa
Indonesia, yang dilakukan selama
lebih dari tiga dasawarsa.
Penulis akan memulai diskusi
yang diambil dari buku Prof
Satjipto Rahardjo yang berjudul
Negara Hukum Yang
Membahagiakan Rakyatnya
dengan, pertama, berangkat dari pernyataan beliau dalam
kata pengantar buku Membedah Hukum Progresif yang
menyatakan bahwa:95
“Mendirikan negara hukum tidak sama dengan
memancangkan sebuah papan nama dan sim-salabim
semuanya selesai. Itu baru awal dari pekerjaan besar
membangun sebuah proyek raksasa yang bernama
negara hukum. Tanpa memahaminya sebagai demikian,
kita akan mengalami kekecewaan, bahkan mungkin rasa
frustrasi. Disebut proyek raksasa, oleh karena yang kita
hadapi adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan begitu
banyak sektor kehidupan, seperti hukum, ekonomi,
95 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit BukuKompas, 2007), hlm xvii.
124
politik, sosial dan last but not least perilaku kita sendiri.
Dengan demikian, sejak pagi kita perlu bersiap-siap
untuk melakukan pekerjaan yang memakan waktu lama,
membutuhkan kecerdasan, kearifan, keuletan, kesabaran,
dan tentu saja pengerahan energi yang amat besar.”
Dan penulis juga memasukkan suatu pernyataan mantan
hakim Indonesia, yaitu Prof Baharudin Lopa, dalam
penegakan hukum Indonesia yang sangat berkaitan ketika
berbicara mengenai membahagiakan rakyat di negara
hukum, yang menyatakan:96
“Dalam membicarakan persoalan integritas moral tak
dapat dipisahkan budaya malu yang dimiliki seseorang.
Mengapa? Karena, tidak mungkin seseorang tidak
merasa malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia
sudah bermoral sebagaimana diajarkan oleh setiap
agama, bahwa malu adalah sebagian dari iman (moral).
Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan
perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak
melakukan perbuatan itu, bukan karena takut ditangkap
atau dihukum, tetapi karena malu kepada sesama,
terutama malu dan takut kepada Allah. Orang yang
berkepribadian inilah yang mampu menjadi teladan.
Sedangkan unsur keteladanan ini sangat mutlak dimiliki
oleh kalangan atas agar dapat dicontoh dan diikuti oleh
seluruh jajarannya.”
Oleh karena itu, untuk memperbaiki penegakan hukum
demi mencapai kebahagiaan rakyat di negara hukum
Indonesia, beliau menyatakan perlunya terlebih dahulu
dilakukan pembenahan internal secara optimal di dalam
96 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2005), hlm 42.
125
institusi-institusi penegakan hukum, terutama di puncaknya
masing-masing, seperti di kalangan petinggi Kepolisian,
Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan
Mahkamah Agung.97
Kedua, saya akan memulai diskusi saat ini dengan
berangkat dari beberapa gagasan, yaitu (1) konsep negara
hukum antara Rechtstaat dan the Rule of Law dan (2)
bagaimana membahagiakan rakyat di negara hukum.
Konsepsi Negara Hukum Rechtstaat dan the Ruleof Law
Dalam khazanah ilmu hukum, terdapat dua istilah
Rechtstaat and the Rule of Law yang dalam bahasa
Indonesia memiliki kesamaan arti, yaitu negara hukum.
Namun, di balik kesamaan arti tersebut terdapat perbedaan
antara Rechtstaat and the Rule of Law. Sebagaimana
diidentifikasikan oleh Roscoe Pound, Rechtstaat memiliki
karakter administratif, sedangkan the Rule of Law
berkarakter yudisial.98
Rechtstaat bersumber dari tradisi hukum negara-negara
Eropa kontinental yang bersandar pada civil law dan
legisme, yang menganggap hukum adalah hukum tertulis.
Kebenaran hukum dan keadilan dalam Rechtstaat terletak
pada ketentuan, bahkan pembuktian, yang tertulis. Hakim
yang baik menurut paham civil law dalam Rechtstaat adalah
yang dapat menerapkan atau membuat putusan sesuai
dengan bunyi undang-undang. Pilihan pada hukum tertulis
97 Loc. cit.98 Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstutusi(Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2006), hlm 24.
126
dan paham legisme di Rechtstaat didasari oleh penekanan
pada kepastian hukum.99
The Rule of Law berkembang pada tradisi hukum
negara-negara Anglo Saxon yang mengembangkan
common law (hukum tak tertulis). Kebenaran hukum dan
keadilan dalam the Rule of Law bukan semata-mata hukum
tertulis, bahkan di sini hakim dituntut untuk membuat
hukum-hukum sendiri melalui yurisprudensi tanpa harus
terikat secara ketat kepada hukum-hukum tertulis. Putusan
hakimlah yang dianggap hukum yang sesungguhnya
daripada hukum-hukum tertulis. Hakim diberi kebebasan
untuk menggali nilai-nilai keadilan dan membuat putusan-
putusan sesuai dengan rasa keadilan yang digalinya dari
masyarakat.
Hakim yang baik adalah hakim yang dapat membuat
keputusan berdasarkan nilai keadilan yang digalinya dari
masyarakat. Keleluasaan diberikan kepada hakim untuk tidak
terlalu terikat pada hukum-hukum tertulis, karena
penegakan hukum ditekankan pada pemenuhan rasa
keadilan, bukan pada hukum-hukum formal. Perbedaan
konsepsi tersebut terletak pada operasionalisasi atas
substansi yang sama, yakni perlindungan atas hak-hak asasi
manusia, di mana kedua konsepsi negara hukum tersebut
sama-sama bertujuan memberikan perlindungan atas hak-
hak asasi manusia.
Perbedaan itu sebenarnya lebih banyak dilatarbelakangi
oleh sejarah hubungan antara raja (yang ketika itu menjadi
personifikasi pemerintah) dan hakim dalam memutus
perkara yang masuk ke pemerintah. Rechtstaat yang
berkarakter administratif dilatarbelakangi oleh kekuasaan
99 Loc. cit.
127
raja pada zaman Romawi yang ketika itu mempunyai
kekuasaan menonjol dalam membuat peraturan-peraturan
melalui berbagai dekrit.
Raja kemudian mendelegasikan kekuasaan tersebut
kepada pejabat-pejabat administratif untuk membuat
pengarahan tertulis kepada hakim tentang cara memutus
sengketa. Peran besar administratif seperti inilah yang
kemudian mendorong tampilnya sistem kontinental sebagai
rahim pertama yang melahirkan cabang baru dalam bidang
hukum, yakni hukum administrasi yang berintikan hubungan
antara administrasi dan rakyat.
Sedangkan dalam the Rule of Law yang mulanya berasal
dari Inggris, kekuasaan menonjol raja adalah memutuskan
perkara yang kemudian dikembangkan menjadi sistem
peradilan. Raja mendelegasikan kekuasaannya kepada hakim
untuk mengadili dan hakim menerima delegasi itu, tetapi
dalam bertugas mengadili ia bukan melaksanakan kehendak
raja. Ketika itu di Inggris (sebagai induk the Rule of Law)
hakim tidak mengadili berdasarkan dekrit tentang peraturan
seperti yang terjadi di Romawi (sebagai induk Rechtstaat)
melainkan mengadili berdasar “the common custom of
England”.100
Jika di Eropa kontinental yang terjadi adalah bertambah
besarnya peranan administrasi, maka di Anglo Saxon yang
terjadi adalah bertambah besarnya peranan peradilan dan
hakim. Jika Eropa kontinental yang kemudian dipikirkan
adalah cara untuk membatasi kekuasaan administrasi
melalui pembentukan hukum administrasi, maka di Inggris
dan Anglo Saxon yang kemudian dipikirkan adalah cara-cara
untuk membangun peradilan yang adil.
100 Loc. cit.
128
Negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengambil konsep
prismatik atau integratif dari dua konsepsi tersebut,
sehingga prinsip kepastian hukum dalam Rechtstaat
dipadukan dengan prinsip “keadilan” dalam the Rule of Law.
Indonesia tidak memilih salah satunya melainkan memakai
atau memasukkan unsur-unsur baik keduanya. Indonesia
telah melakukan empat kali amendemen terhadap UUD
1945, dan saat ini tidak lagi tercantum istilah “rechstaat”
secara eksplisit.101
Istilah rechtstaat semula tercantum dalam Penjelasan
UUD 1945 pada bagian Umum, subbagian Sistem
Pemerintahan Negara, yang menyebutkan istilah rechtstaat
sampai dua kali, yakni Angka 1 yang berbunyi “Indonesia
ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtstaat), tidak
berdasar kekuasaan belaka (Machtstaat).” Namun, setelah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati bahwa
dalam melakukan amendemen Penjelasan UUD 1945
ditiadakan dari UUD 1945 dan isinya yang bersifat normatif
dimasukkan dalam pasal-pasal, maka istilah rechtstaat ikut
ditiadakan.102
Pada perubahan Ketiga UUD 1945 (tepatnya pada
Sidang Tahunan MPR tahun 2001), prinsip Negara Hukum
kemudian dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) dengan istilah
yang netral (tanpa menyebut Rechtstaat atau The Rule of
Law), yang persisnya berbunyi: “Negara Indonesia adalah
negara hukum.”103
101 Loc. cit.102 Loc. cit.103 Loc. cit.
129
Bahagia di Negara Hukum
Pada 17 Agustus 1945, Indonesia lahir sebagai negara
baru di tengah masyarakat dunia. Kecuali pengumuman
tentang bentuk negara, yaitu republik, Indonesia juga
menyatakan diri sebagai negara berdasar hukum (negara
hukum). Lebih dari setengah abad kemudian, Republik
Indonesia masih harus bergulat dengan berbagai masalah
mendasar yang timbul sebagai akibatnya. Eksistensi
Republik Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata masih
harus terus dibina dan dipertahankan.104
Selain itu, pembangunan negara hukum ternyata belum
juga selesai dengan baik, bahkan yang terjadi adalah
sebaliknya: Indonesia menjadi terkenal di dunia sebagai
negara dengan sistem hukum sangat buruk. Yang dimaksud
dengan pembangunan yang belum kunjung selesai di sini
adalah bagaimana menghadikan negara hukum itu suatu
organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah
yang menyenangkan, menyejahterakan, dan
membahagiakan bagi bangsa Indonesia.
Selama ini, negara hukum hanya dipahami sebatas pada
bagaimana suatu negara mengakui bahkan mengklaim telah
memiliki berbagai syarat-syarat normatif dan secara
otomatis negara tersebut dikatakan sebagai negara hukum.
Ukuran negara hukum ada atau tidak hanya diukur dari
terpenuhinya berbagai unsur-unsur kategoris, seperti
supremasi hukum, persamaan dalam hukum, proses hukum
yang adil, peradilan bebas dan tidak memihak, dan lain
sebagainya. Dan, sebenarnya, kategori-kategori tersebut
belum dianggap selesai.
104 Satjipto Rahardjo, op. cit., hlm 46.
130
Pemahaman negara hukum tersebut telah mengubur
sosok negara hukum yang seharusnya tampil ke permukaan.
Kita terjebak dalam konsep pemahaman yang serba-
normatif-positivistik, padahal negara hukum tidak menjadi
sempurna dan menjadi akhir dari segalanya. Tetapi, negara
hukum merupakan sebuah sosok yang terus menjadi dan
mengada.
Berkaca dari Jepang
Kita dapat melihat pada Jepang yang dulunya berhasil
menutup diri terhadap dunia luar akhirnya mengambil sikap
untuk membuka diri karena adanya todongan meriam dari
Komodor Matthew Perry pada 1853. Itulah awal Jepang
membuka diri dengan dunia dan bangsa-bangsa di luar
Jepang. Pada saat Jepang membuka diri dengan negara lain,
diperkenalkan pula konsep negara hukum dan negara
modern.105
Jepang harus berhadapan dengan hukum dan negara
yang berbeda daripada yang selama ini mereka kenal. Dan,
dapat ditafsirkan, bagi bangsa Jepang, hukum memiliki
makna jalan air, arus yang mengaliri suatu jalan yang dilalui
bersama-sama oleh para anggota masyarakat dalam
suasana harmoni. Tetapi, pemahaman yang demikian itu
segera diguncang oleh masuknya konsep Barat mengenai
hukum dan negara.
Dalam kosakata hukum Jepang asli, tidak ada konsep
dan kata hak. Yang ada hanyalah kewajiban dan tanggung
jawab dan selebihnya berupa karunia yang diberikan oleh
raja. Negara dalam tradisi Jepang adalah Sang Kakak (Big
105 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 32.
131
Brother) yang selalu memikirkan kesejahteraan untuk para
adiknya. Mereka tidak perlu bersusah-susah berjuang untuk
mencapai kesejahteraan, karena Sang Kakak sudah
menyediakan semua yang diperlukan.
Untuk memahami mengapa negara dianggap sebagai
Sang Kakak yang selalu memperhatikan kebutuhan rakyat
tanpa harus diminta, kita perlu mencari penjelasan pada
karakteristik kejiwaan orang Jepang. Takeo Doi adalah
seorang psikiater Jepang yang dibesarkan di Jepang dan
sesudah Perang Dunia II memperdalam ilmu di Amerika
Serikat. Di situlah Doi dihadapkan pada perbedaan
karakteristik antara orang Jepang dan Amerika Serikat.106
Amae adalah sikap kejiwaan yang menggantungkan diri
kepada orang lain dan percaya bahwa orang lain akan
berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, kata Sumanai (rasa
bersalah), yaitu ketika tidak melakukan sesuatu yang
seharusnya dikerjakan, menimbulkan gangguan kepada
hubungannya dengan orang lain. Sekalian karakteristik
kejiwaan tersebut membantu menjelaskan, mengapa rakyat
Jepang begitu percaya kepada negara dan menyerahkan
nasib sepenuhnya kepada negara.107
Hal tersebut mereka
lakukan karena mereka percaya, negara akan memberikan
apa yang mereka butuhkan, tanpa harus menuntutnya. Di
lain pihak, negara akan merasa bersalah apabila tidak
berbuat baik kepada rakyatnya.
Pembelajaran lain yang diberikan kepada kita adalah
konsistensi dan persistensi bangsa Jepang dalam
memegang tradisi budayanya. Lalu pertanyaan yang timbul
pula, apakah Indonesia tidak memiliki budaya sehingga
106 Ibid., hlm 56.107 Loc. cit.
132
pemimpin negara (pemerintah) tidak pernah mendengar
dan melihat penderitaan rakyat selama ini?
Jika demikian di negara Jepang, lalu bagaimana di
negara Indonesia dalam membawa kesejahteraan dan
perlindungan kepada masyarakat? Seperti yang sudah saya
sampaikan dalam awal penulisan ini, bahwa digunakan kata
“negara hukum yang meng-Indonesia”, sekedar untuk
menegaskan, betapa pentingnya untuk menyadari, negara
hukum Indonesia tidak hanya sebuah merek, melainkan
benar-benar dimaknai sebagai proses menjadi Indonesia.
Indonesia Akan Bahagia
Kalau pada 17 Agustus 1945 kita memproklamasikan
kelahiran negara hukum Republik Indonesia, maka yang ada
dalam pikiran kita waktu itu adalah sejak hari pertama itu
kita sudah menjadi negara hukum secara “tuntas-
sempurna”. Ide bagus, namun terlalu bagus sehingga
sebetulnya kita bermimpi. Secara formal memang begitu,
tetapi substansial perjalanannya masih jauh. Membangun
negara hukum adalah proyek yang sangat besar.
Hal ini penting untuk direnungkan sebagai modal
membangun bangsa dari suatu negara hukum. Negara
hukum tidak instan, tetapi harus dibangun. Negara hukum
adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam
masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang impor”. Proses
menjadi negara hukum bukan merupakan bagian dari
sejarah sosial-politik bangsa kita di masa lalu, seperti terjadi
di Eropa. Negara hukum adalah bangunan yang “dipaksakan
dari luar”. Dengan demikian, membangun negara hukum
133
adalah membangun perilaku bernegara hukum,
membangun suatu peradaban baru.108
Di sini, penulis juga akan mengajak untuk melihat
bagaimana kondisi di Eropa hingga sampai menjadi negara
konstitusional seperti yang termuat dalam tulisan Prof
Satjipto Rahardjo. Eropa harus mengalami keambrukan
sistem sosial yang satu disusul keambrukan berikutnya, dari
feodalisme, staendestaat, negara absolut, dan baru
kemudian menjadi negara konstitusional. Masing-masing
keambrukan itu memberikan jalan kepada lahirnya Negara
hukum modern. Eropa, sebagai ajang persemaian konsep
negara hukum, membutuhkan waktu tidak kurang dari
sepuluh abad, sebelum kelahiran rule of law dan negara
konstitusional.
Gagasan bernegara hukum, menjalankan hukum,
janganlah direduksi dan dipersempit menjadi praktik
menjalankan undang-undang secara hitam putih atau
menurut kalimat dalam pasal undang-undang belaka.
Negara hukum juga jangan direduksi menjadi negara
prosedur hukum. Inilah yang membuat kita menjadi tidak
sejahtera dan bahagia hidup di negara hukum. Sekali lagi
dikatakan bahwa membangun negara hukum adalah proyek
yang sangat besar dan karena itu memakan waktu yang
sangat lama dan pengerahan energi yang besar pula.
Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya
cenderung untuk menjadi negara hukum yang progresif, bila
dilihat dari inisiatif yang selalu datang dari pihak negara.
Untuk mewujudkannya, negara akan selalu aktif mengambil
inisiatif untuk bertindak. Bukan rakyat yang harus “meminta-
minta” untuk dilayani oleh negara, melainkan negaralah
108 Satjipto Raharjo, op. cit.., hlm 48.
134
yang aktif datang kepada rakyat. Di sini, gambaran tentang
negara hukum Indonesia yang dicita-citakan menjadi dekat
dengan “benevolent state” pada bangsa Jepang.
Sudah enampuluh tahun lebih Indonesia merdeka dan
bernegara hukum, tetapi sesudah negara itu berdiri ternyata
masih banyak tugas yang harus kita kerjakan ke depan
untuk terus menerus dibangun. Kita bernegara hukum untuk
membawa rakyat merasa bahagia hidup dalam negara
hukum Indonesia dengan adanya penegak hukum yang
memiliki integritas dan moral. Penulis yakin, Indonesia pasti
akan lebih baik di masa depan! []
135
Para Pemantik
DIANDRA PRELUDIO R. Menamatkan studi
pada Magister Ilmu Hukum, Universitas
Diponegoro (2014); Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro (2011); SMA Negeri
1 Semarang; SLTP Negeri 3 Semarang; dan
SD Negeri Kembang Paes. Lahir di Tuban
pada 7 September 1988, ia pernah menjadi
Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro. Dapat dihubungi melalui
[email protected] dan 085640197797.
BENNY PRASETYO. Menamatkan studi pada
Magister Ilmu Hukum, Universitas
Diponegoro (2014); Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro (2011); SMA Negeri 1
Semarang; dan SMP Negeri 8 Semarang.
Lahir di Semarang pada 21 Maret 1989, ia
dapat dihubungi melalui
UNU P HERLAMBANG. Menamatkan studi
pada Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro (2012). Lahir di Madiun pada 16
Desember 1989, ia pernah menjadi
Pimpinan Penelitian dan Pengembangan
Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan
periode 2010-2011. Sekarang sedang
136
menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum,
Universitas Diponegoro, sembari menjadi peneliti Satjipto
Rahardjo Institute. Menamatkan pendidikan dasar di SD
Negeri Kartoharjo 1 Madiun (2002), SMP Negeri 1 Madiun
(2005), dan SMA Negeri 2 Madiun (2008). Dapat dihubungi
melalui [email protected], @unuherlambang, dan
085645929805.
MUHTAR SAID. Lahir di Semarang pada 5
Desember 1988, ia kini adalah Manajer Riset
Democracy Watch Organization (Dewa Orga);
Kepala Sekolah Tan Malaka, Semarang;
pendiri Satjipto Rahardjo Institute; dan
penggagas Pusat Studi Tokoh Hukum
(Pustokum). Menamatkan studi pada
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro (2013). Dapat
dihubungi melalui 085640283987.
AP EDI ATMAJA. Menamatkan studi pada
Magister Ilmu Hukum, Universitas
Diponegoro (2013); Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro (2012); SMA Negeri 5
Semarang (2008); SMP Negeri 28 Semarang
(2005); dan MI Ianatusshibyan Semarang
(2002). Lahir di Kendal pada 17 Juni 1990, ia
pernah menjadi Pimpinan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa
Gema Keadilan periode 2010-2011. Dapat dihubungi melalui
[email protected], @jagunk55, dan 08562690222.
BENNY KARYA LIMANTARA. Menamatkan
studi pada Magister Ilmu Hukum, Universitas
Diponegoro (2014); Fakultas Hukum,
Universitas Bandar Lampung; SMA Negeri 4
Bandar Lampung; SMP Negeri 23 Bandar
Lampung; dan SD Negeri 2 Tanjung Gading,
137
Bandar Lampung. Lahir di Bandar Lampung pada 23 Mei
1990, ia dapat dihubungi melalui 081957464621.
SYANDI RAMA SABEKTI. Menamatkan
studi pada Magister Ilmu Hukum,
Universitas Diponegoro (2014); Fakultas
Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
(2011); SMA Negeri 1 Bebesen; SMP
Negeri 1 Takengon; dan SD Negeri Buntul
Kubu Takengon. Lahir di Takengon pada
22 Februari 1989, ia dapat dihubungi
melalui [email protected], 082325579467, dan
082365690022.
ALFAJRIN A TITAHELUW. Menamatkan
studi pada Magister Ilmu Hukum,
Universitas Diponegoro (2014); Fakultas
Hukum, Universitas 17 Agustus 1945,
Semarang; SMA Negeri 1 Ternate; SMP
Negeri 7 Ternate; dan SD Negeri Pertiwi 2
Ternate. Lahir di Nuku pada 16 Februari
1991, ia dapat dihubungi melalui
[email protected] dan 081228264459.
RIAN ADHIVIRA. Menamatkan studi pada
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(2013). Lahir di Semarang pada 14 Juli 1990,
ia adalah pendiri Komunitas Payung dan
peneliti Satjipto Rahardjo Institute.
Sekarang sedang menempuh studi di
Program Magister Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro sembari merampungkan studi pada Fakultas
Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Menamatkan
pendidikan dasar di SD Negeri Perumnas Krapyak Semarang,
SMP Negeri 1 Semarang, dan SMA Negeri 1 Semarang, ia
138
dapat dihubungi melalui [email protected],
@rianadhivira, dan 085741918065.
NINDI ACHID ARIFKI. Menamatkan studi
pada Magister Ilmu Hukum, Universitas
Diponegoro (2014); Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang (2011); SMA
Negeri 1 Godong; SMP Negeri 1 Godong;
dan SD Negeri 4 Godong. Lahir di Godong
pada 1 Agustus 1989, ia pernah menjadi
Kepala Biro Pendidikan Perhimpunan Mahasiswa Hukum
Indonesia (Permahi) Dewan Perwakilan Cabang Semarang.
Dapat dihubungi melalui [email protected],
[email protected], dan 089669166554.
RAHMAD SYAHRONI RAMBE. Menamatkan
studi pada Magister Ilmu Hukum,
Universitas Diponegoro (2014); Fakultas
Hukum, Universitas Sumatera Utara (2010);
SMA Negeri 3 Plus Rantauprapat; SMP
Negeri 2 Rantauprapat; dan SD 112143
Rantauprapat. Lahir pada 18 April 1988, ia
dapat dihubungi melalui melalui
[email protected] dan 085297022833.
LILIK HARYADI. Menamatkan studi pada
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(2012). Lahir di Klaten pada 10 Mei 1990,
ia pernah menjadi Redaktur Pelaksana
Majalah Lembaga Pers Mahasiswa Gema
Keadilan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro periode 2010-2011.
Sekarang sedang menempuh studi di
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
Menamatkan pendidikan dasar di SD 1 Pundungsari (2002),
139
SMP Negeri 1 Cawas (2005), dan SMA Negeri Cawas (2008),
ia dapat dihubungi melalui [email protected] dan
085729225161.
JAMES MARIHOT PANGGABEAN.
Menamatkan studi pada Magister Ilmu
Hukum, Universitas Diponegoro (2014);
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo
(2011); SMA St Thomas 2 Medan; SMP
St Thomas 3 Medan; dan SD St Thomas
2 Medan. Lahir di Medan pada 25 Maret
1989, ia dapat dihubungi melalui
[email protected] dan 082165008618.