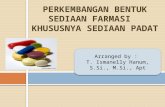Asam Nukleat, Protein, Enzim, Reseptor sebagai Target Kerja Obat dan Transduksi Signal
-
Upload
uin-alauddin -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Asam Nukleat, Protein, Enzim, Reseptor sebagai Target Kerja Obat dan Transduksi Signal
TUGAS PENGGANTI MID
KIMIA MEDISINAL
ASAM NUKLEAT, PROTEIN, ENZIM, RESEPTOR SEBAGAI TARGETKERJA OBAT DAN TRANDUKSI SIGNAL
OLEH :
NI’MA NURMAGFIRAH
70100111054
FARMASI B
DOSEN PENANGGUNG JAWAB :
NURSHALATI TAHAR, S.Farm., M.Si., Apt
JURUSAN FARMASI-FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2014
ASAM NUKLEAT, PROTEIN DAN ENZIM
SEBAGAI TARGET KERJA OBAT
A. Asam Nukleat
Asam nukleat adalah suatu polimer nukleotida
yang berperan dalam pemindahan serta penyimpanan
informasi genetik. Satu nukleotida terdiri atas
tiga bagian yaitu; cincin purin atau pirimidin,
molekul gula dengan lima atom C (pentosa) dan
gugus fosfat. Berdasarkan bagian tersebut, asam
nukleotida terdiri atas asam deoksiribonukleat
(DNA) dan asam ribonukleat (RNA).
Suatu basa yang terikat pada satu gugus gula
disebut nukleosida, sedangkan nukleotida adalah
satu nukleosida yang berikatan dengan gugus
fosfat. Di dalam molekul DNA atau RNA, nukleotida
berikatan dengan nukleotida lain melalui ikatan
fosfodiester. Basa purin dan pirimidin tidak
berikatan secara kovalen satu sama lain, oleh
karena itu, suatu polinukleotida tersusun atas
kerangka-kerangka gula-fosfat yang berselang-
seling dan mempunyai ujung 5’-P dan 3’-OH.
1. DNA sebagai Target Obat
Aksi obat terhadap DNA berdasarkan atas ;
a. Agen Interkalasi, memiliki mekanisme aksi
berdasarkan atas ;
Penyisipan molekul planar ke dalam susunan
basa di dalam heliks ganda
Perubahan molekul DNA sedemikian rupa
sehingga DNA polimerase dapat menyisipkan
atau melewatkan satu atau lebih basa pada
saat replikasi
Beberapa contoh agen interkalasi adalah
proflavin, akridin jingga, dan etidium
bromida
b. Agen Alkilasi, dapat menyebabkan mutasi dengan
mengubah basa secara kimiawi sehingga basa
akan berpasangan dengan basa tertentu yang
bukan basa komplementer normalnya, dengan
ciri-ciri ;
mengandung gugus elektrofilik yang tinggi
dapat bertindak sebagai agen anti tumor
memiliki efek samping toksik
Sedangkan mekanisme aksinya berdasarkan ;
pembentukan ikatan kovalen terhadap gugus
nukleofilik DNA
pencegahan replikasi dan transkripsi
c. Pemotongan rantai oleh Topoisomerase-II, mekanisme
aksinya berdasarkan atas ;
pemisahkan H dari DNA untuk menghasilkan
radikal
reaksi antara radikal dengan oksigen yang
menghasilkan pemotongan rantai
penghambatan bleomisin pada perbaikan enzim
(mekanisme aksi pemotongan oleh Topoisomerase-II)
(pemotongan oleh Topoisomerase-II pada antibiotik)
2. RNA sebagai Target Obat
Aksi obat terhadap RNA berdasarkan atas ;
a. Terapi antisense pada aksi obat
terhadap mRNA, memiliki beberapa
keuntungan antara lain ;
berefek sama sebagai inhibitor enzim atau
antagonis reseptor
sangat spesifik dimana oligonukleotida
adalah 17 nukleotida atau lebih
tingkat dosis lebih kecil diperlukan
dibandingkan dengan inhibitor atau
antagonisme
potensi efek samping berkurang
sedangkan kerugian antara lain ;
menampilkan bagian mRNA yang seharusnya
ditargetkan.
instabilitas dan polaritas oligonukleotida
(farmakokinetik)
waktu hidup pendek oligonukleotida dan
penyerapan malang melintang membrane sel.
b. Dekstruksi RNA-siRNA
(pencampuran RNA-siRNA)
3. Obat Memblokade Asam Nukleat
Pemblokadean obat terhadap asam
nukleat oleh enzim inhibitor
yakni AZT yang terfosforilasi ke
trifosfat dalam tubuh dengan
mekanisme aksi ;
penghambat enzim viral (reverse
transcriptase)
penghambat enzim viral (reverse
transcriptase)
penambahan ke rantai DNA berkembang dan
bertindak sebagai rantai terminator
B. Protein
Berbagai obat mengadakan interaksi dengan
plasma atau jaringan protein atau dengan
makromolekul yang lain seperti melanin dan DNA,
membentuk kompleks makromolekul obat. Formasi
kompleks obat protein disebut protein binding
(pengikatan protein terhadap obat) merupakan
proses reversible (dapat balik) atau irreversible
(tidak dapat balik).
1. Irreversible Drug-Protein Binding
Ikatan obat dengan protein yang tidak
dapat balik (irreversible drug-protein binding)
umumnya merupakan hasil dari aktifasi kimia
obat, dimana kemudian mengadakan pengikatan yang
kuat terhadap protein atau makromolekul dengan
ikatan kimia kovalen. Pengikatan obat yang
tidak dapat balik (irreversible) ditemukan
dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan
berbagai jenis keracunan obat, seperti kasus
karsinogenesis kimia, atau dalam jangka waktu
yang pendek, seperti dalam kasus obat dalam
bentuk perantara (intermediated) kimia yang
reaktip, misalnya: Hepatotoksisitas dari dosis
tinggi acetaminophen, yang akan membentuk
metabolit antara (intermediated metabolite)
reaktif yang berinteraksi dengan protein hati.
2. Reversible Drug-Protein Binding
Umumnya obat akan berikatan atau
membentuk kompleks dengan protein melalui
proses bolak balik (reversibel). Ikatan obat-
protein yang bolak balik menyatakan secara tidak
langsung bahwa obat mengikat protein dengan
ikatan kimia yang lemah, misalnya; ikatan
hidrogen atau ikatan van deer waals. Asam amino
yang menyusun rantai protein mempunyai gugus
hydroxyl, carboxyl, atau berbagai tempat yang
ada, untuk interaksi obat yang bolak balik. Obat
dapat mengikat berbagai komponen makromolekuler
dalam darah, meliputi: albumin, asam
glycoprotein, lipoprotein, erythrocyte (RBC).
a. Albumin
Merupakan komponen terbesar dari
plasma protein yang berperanan dalam
pengikatan obat yang bolak balik. Dalam
tubuh, albumin terdistribusi dalam plasma dan
dalam cairan ekstrasellular dan kulit, otot
dan berbagai jaringan lain.
Banyak obat yang bersifat asam
lemah (anionic) berikatan dengan albumin
dengan ikatan elektrostatik dan hydrophobic.
Obat yang bersifat asam lemah seperti:
salisilat, phenylbutazon, dan penicillin
sangat cepat berikatan dengan albumin. Namun,
kekuatan dari pengikatan obat berbeda untuk
setiap obat.
b. Asam Glikoprotein
Merupakan globulin dengan berat
molekul sekitar 4.000 d. Konsentrasi asam
glycoprotein dalam plasma sangat rendah (0,4
sampai 1 %) dan terutama mengikat obat yang
bersifat basa (kationik) seperti propranolol,
imipramine, dan lidocaine. Globulin berpera
dalam transpor berbagai bahan endogen seperti
corticosteroid. Globulin mempunyai kapasitas
yang rendah tetapi mempunyai affinitas yang
tinggi untuk mengikat bahan endogen ini.
c. Lippoprotein
Lipoprotein adalah kompleks
makromolekul dari lipid dan protein, dan
diklasifikasikan berdasarkan atas densitas
dan pemisahan dengan ultrasentrifuge. Istilah
VLDL, LDL, dan HDL adalah singkatan dari:
very-low-density lipoprotein, low-density
lipoprotein, dan high-density lipoprotein.
Lipoprotein berperan untuk transpor plasma
lipid dan mungkin berperan dalam pengikatan
obat bila tempat albumin telah jenuh.
d. Erythrocytes
Erythrocytes atau sel darah merah
( RBCs ), dapat mengikat baik senyawa endogen
dan eksogen. Kira kira 45% dari volume darah
merupakan RBCs. Phenytoin, pentobarbital, dan
amobarbital diketahui mempunyai rasio RBC/air
plasma = 4 sampai 2, yang menunjukkan
pengikatan istimewa dari obat pada
erythrocytes lebih dari air plasma. Penetrasi
kedalam erythrocytes tergantung pada
konsentrasi bebas obat. Untuk Phenytoin,
level obat dalam RBC meningkat secara liner
dengan peningkatan konsentrasi obat bebas
dalam plasma. Untuk hampir pada semua obat
peningkatan pengikatan obat pada albumin
plasma akan mengurangi konsentrasi obat dalam
RBC. Namun,pengikatan obat pada RBC umumnya
tidak berpengaruh terhadap volume distribusi,
sebab obat selalu berikatan dengan albumin
pada air plasma. Meskipun phenytoin mempunyai
affinitas yang besar untuk RBC, hanya sekitar
25% dari konsentrasi obat dalam darah yang
terdapat pada sel darah, dan 75% terdapat
dalam plasma sebab obat sangat kuat berikatan
dengan albumin. Untuk obat yang berikatan
sangat kuat dengan erythrocytes, maka
hematocrit akan mempengaruhi jumlah total
obat dalam darah.
C. Enzim
Enzim merupakan protein yang berperan
sebagai katalisator berbagai reaksi kimia dan
biokimia dalam tubuh. Obat dapat memproduksi efek
terhadap reaksi enzim, dengan cara: substrat
analog, kompetisi enzim (reversibel atau
ireversibel) dan substrat palsu.
1. Substrat Analog
a. Pencocokan substrat, dengan cara;
situs aktif hampir bentuk yang benar untuk
substrat
ikatan mengubah bentuk enzim (diinduksi)
ikatan dengan ketegangan obligasi dalam
substrat
melibatkan ikatan antarmolekul antara
fungsional kelompok dalam substrat dan
kelompok fungsional di situs aktif
b. Jenis ikatan substrat
2. Kompetisi Enzim (Inhibitor Kompetitif)
Molekul obat sebagai substrat analog
yang beraksi sebagai inhibitor
kompetitif bagi enzim.
a. Inhibitor Kompetitif Reversibel, dengan mekanisme
aksi;
inhibitor reversibel mengikat ke situs
aktif
obligasi antarmolekul terlibat dalam
mengikat
reaksi yang terjadi pada inhibitor
penghambatan tergantung pada kekuatan
inhibitor mengikat dan konsentrasi
inhibitor
substrat diblokir dari situs aktif
meningkatkan konsentrasi substrat
membalikkan penghambatan
inhibitor menyerupai struktur substrat
aktif
b. Inhibitor Non-Kompetitif Irreversibel,
dengan mekanisme aksi;
inhibitor ireversibel mengikat ke situs
aktif
ikatan kovalen terbentuk antara obat dan
enzim
substrat diblokir dari situs aktif
peningkatkan konsentrasi substrat tidak
membalikkan penghambatan
inhibitor menyerupai struktur substrat
c. Inhibitor Non-Kompetitif (Reversibel)
mengikat ke situs alosterik
dengan mekanisme aksi;
Obligasi antarmolekul terbentuk
pencocokan substrat berimbas pada
pengubahan bentuk enzim
situs aktif terdistorsi dan tidak diakui
oleh substrat
meningkatkan konsentrasi substrat tidak
membalikkan penghambatan
inhibitor tidak mirip dengan struktur
substrat
enzim dengan alosentrik sering
dijumpai pada awal biosintesis jalur.
enzim dikendalikan oleh produk akhir
dari jalur
produk akhir mengikat ke situs
alosterik dan enzim nonaktif
inhibitor mungkin memiliki struktur
yang mirip dengan produk akhir
3. Substrat Palsu
Berinteraksi dengan enzim
menghasilkan produk yang salah
dan tidak berfungsi, misalnya;
a. 1. 5-Fluorourasil, menggantikan urasil
dalam biosintesis purin terbentuk
nukleotida palsu “fradulent” nucleotide
fluoro deoxyuridine monophosphate (FDUMP)
atau tidak terbentuk 2’-deoxy-uridilat
monophosphat (DUMP) tidak membentuk
timidilat (DTMP), penghambatan sintesis
DNA, penghambatan pertumbuhan dan
pembelahan sel
b. Metotreksat, menggantikan folat
dalam biosintesis purin, penghambatan
sintesis DNA, penghambatan pertumbuhan dan
pembelahan sel.
RESEPTOR SEBAGAI TARGET OBAT
DAN TRANSDUKSI SIGNAL
A. Reseptor Sebagai Target Obat
Reseptor merupakan komponen makromolekul
sel (umumnya berupa protein) yang erinteraksi dengan
senyawa kimia endogen pembawa pesan (hormon,
neurotransmiter, mediator kimia dalam sistem imun,
dan lain-lain) untuk menghasilkan respon seluler.
Obat bekerja dengan melibatkan diri dalam interaksi
antara senyawa kimia endogen dengan reseptor ini,
baik menstimulasi (agonis) maupun mencegah interaksi
(antagonis). Tipe reseptor antara lain; reseptor
terhubung kanal ion, reseptor terhubung enzim,
reseptor terkopling protein G, reseptor reseptor
nukleat, reseptor nikotin muskarinik dan reseptro
terhubung transkripsi gen.
1. Reseptor Kanal Ion
Reseptor ini berada di membran sel,
disebut juga reseptor ionotropik. Respon terjadi
dalam hitungan milidetik. Kanal merupakan bagian
dari reseptor. Contoh: reseptor nikotinik,
reseptor GABAA, reseptor ionotropik glutamat dan
reseptor 5-HT3
2. Reseptor terhubung Enzim
Reseptor terhubung enzim merupakan
protein transmembran dengan bagian besar
ekstraseluler mengandung binding site untuk ligan
(contoh : faktor pertumbuhan, sitokin) dan bagian
intraseluler mempunyai aktivitas enzim (biasanya
aktivitas tirosin kinase). Aktivasi menginisiasi
jalur intraseluler yang melibatkan tranduser
sitosolik dan nuklear, bahkan transkripsi gen.
Reseptor sitokin mengaktifkan Jak kinase, yang
pada gilirannya mengaktifkan faktor transkripsi
Stat, yang kemudian mengaktifkan transkripsi gen.
Reseptor faktor pertumbuhan terdiri
dari 2 reseptor, masing-masing dengan satu sisi
pengikatan untuk ligan. Agonis berikatan pada 2
reseptor menghasilkan kopling (dimerisasi).
Tirosin kinase dalam masing-masing reseptor saling
memposforilasi satu sama lain. Protein penerima
(adapter) yang mengandung gugus –SH berikatan pada
residu terposforilasi dan mengaktifkan tiga jalur
kinase. Kinase 3 memposforilasi berbagai faktor
transkripsi, kemudian mengaktifkan transkripsi gen
untuk proliferasi dan diferensiasi.
3. Reseptor terkopling Protein G
GPCR, disebut juga reseptor
metabotropik, berada di sel membran dan responnya
terjadi dalam hitungan detik. GPCR mempunyai
rantai polipeptida tunggal dengan 7 heliks
transmembran. Tranduksi sinyal terjadi dengan
aktivasi bagian protein G yang kemudian
memodulasi/mengatur aktivitas enzim atau fungsi
kanal.
4. Reseptor Nikotin Muskarinik
Reseptor ini ditemukan di otot skeletal,
ganglion sistem saraf simpatk dan parasimpatik,
neuron sistem saraf pusat, dan sel non neural.
Mekanisme kerja reseptor ini ditunjukkan
Reseptor ini terdiri dari 5 subunit
(yaitu subunit α1, β1, γ atau ε, dan δ), yang
melintasi membran, membentuk kanal polar (gambar 4a).
Masing-masing sub unit terdiri dari 4 segmen
transmembran, segmen ke-2 (M2) membentuk kanal ion.
Domain N-terminal ekstraseluler masing-masing sub
unit mengandung 2 residu sistein yang dipisahkan oleh
13 asam amino membentuk ikatan disulfida yang
membentuk loop, merupakan binding site untuk agonis.
5. Reseptor terhubung Transkripsi Gen
Reseptor terhubung transkripsi gen
disebut juga reseptor nuklear (walaupun beberapa
ada di sitosol, merupakan reseptor sitosolik yang
kemudian bermigrasi ke nukleus setelah berikatan
dengan ligand, seperti reseptor glukokortikoid).
Contoh : reseptor kortikosteroid, reseptor estrogen
dan progestogen, reseptor vitamin D.
B. Transduksi Signal
Merupakan proses perubahan bentuk
sinyal yang berurutan, dari sinyal ekstraseluler
sampai respon dalam komunikasi antar sel
1. Pengendalian Saluran Ion
Protein Reseptor merupakan bagian dari
kompleks protein saluran ion
Reseptor mengikat seorang utusan yang
menyebabkan fit diinduksi
Saluran Ion dibuka atau ditutup
Kanal ion yang spesifik untuk ion tertentu
(Na+, Ca2+, Cl -, K+)
Ion mengalir melintasi membran sel ke bawah
gradien konsentrasi
Polarisasi atau depolarisasi membran saraf
Mengaktifasi atau menonaktifkan enzim katalis
reaksi dalam tubuh
Membuka situs pengikatan untuk protein sinyal
(G-protein)
mengikat G-Protein, yang stabil kemudian
membaginya
o G-Protein subunit mengaktifkan membran terikat
enzim
Mengikat alosterik situs pengikatan
Pencocokan hasil induksi dalam pembukaan situs
aktif
o Reaksi intraseluler dikatalisis
3. Aktivasi Sisi Aktif Enzim
Protein berfungsi peran ganda - reseptor
ditambah enzim
Reseptor mengikat utusan mengarah ke fit
diinduksi
Protein mengalami perubahan bentuk dan membuka
situs aktif
Reaksi katalisis dalam sel