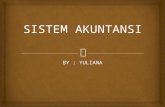akuntansi-perusahaan-industri.pdf - WordPress.com
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of akuntansi-perusahaan-industri.pdf - WordPress.com
SILABUS :
1. Prosedur Pengendalian Intern
2. Akuntansi Untuk Piutang
3. Akuntansi Persediaan
4. Aktiva Tetap
5. Akuntansi Penghentian Aktiva Tetap
6. Kewajiban Lancar
7. Kewajiban jangka panjang
8. Modal saham dan laba ditahan
9. Investasi sementara dan investasi jangka panjang
10. Akuntansi Perusahaan Manufaktur
Referensi :
1.Jusuf, Al Haryono. 2009. Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2,Edisi 7. Yogyakarta:STIE YKPN
2.Tjahjono, Achmad dan Sulastiningsih, 2009. Akuntansi Pengantar 2 Pendekatan
Komprehensip. Yogyakarta: Ganbika
3.Weygandt, Kieso
BAB 1 PROSEDUR PENGENDALIAN INTERN
1. Pengendalian intern
2. Sistem voucher dan pengawasan
3. Rekening giro Bank
4. Tahap-tahap penyusunan rekonsiliasi
5. Pembuatan rekonsiliasi
6. Dana kas kecil
A. Pengendalian intern
Pengendalian intern terdiri atas semua metoda dan tindakan yang saling
berkaitan yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mengamankan aset,
meningkatkan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan
menjamin kesesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Suatu rencana organisasional dan semua tindakan yang dilakukan perusahaan untuk
mengamankan aktiva, mendorong diikutinya kebijakan perusahaan, mendorong
efisiensi operasional, dan menjamin ketepatan dan dapat dipercayainya catatan-
catatan akuntansi.
Pengendalian internal dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Pengendalian akuntansi
Pengendalian ini dirancang untuk mencapai tujuan mengamankan aset
perusahaan, dan menjamin ketepatan dan dapat dipercayainya catatan-
catatan akuntansi.
2. Pengendalian administratif
Pengendalian ini dirancang untuk mendorong efisiensi operasional, dan
mendorong diikutinya kebijakan perusahaan.
A. Pengendalian intern
Pengendalian intern terdiri atas semua metoda dan tindakan yang saling
berkaitan yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk mengamankan aset,
meningkatkan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan
menjamin kesesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Suatu rencana organisasional dan semua tindakan yang dilakukan perusahaan untuk
mengamankan aktiva, mendorong diikutinya kebijakan perusahaan, mendorong
efisiensi operasional, dan menjamin ketepatan dan dapat dipercayainya catatan-
catatan akuntansi.
5 komponen utama Sistem Pengendalian Intern :
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Monitoring
6 prinsip aktivitas pengendalian :
1. Penetapan tanggungjawab
2. Pemisahan tugas
3. Prosedur dokumentasi
4. Pengawasan fisik
5. Verifikasi internal secara independen
6. Pengendalian sumberdaya manusia
Manfaat Pengendalian Intern :
1. Menjamin bahwa semua transaksi dicatat secara lengkap dan akurat
2. Memastikan bahwa hanya transaksi yang telah diotorisasi yang dapat
dilaksanakan
3. Menjamin bahwa semua transaksi didukung dengan dokumen yang memadai
4. Menjamin bahwa aset dan kewajiban perusahaan telah ditetapkan dengan benar,
sehingga dapat digunkan sebgai informasi yang dapat diandalkan untuk
pengambilan keputusan dalam mengoperasikan perusahaan
5. Meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan aset perusahaan
Kelemahan Pengendalian Intern :
1. Pengendalian interen rentan terhadap kelemahan-kelemahan manusiawi
2. Kolusi yang tidak dapat dicegah oleh sistem
3. Pengendalian intern biasanya diterapkan pada transaksi-transaksi yang rutin
harian, sedangkan yang tidak rutin tidak terawasi
4. Faktor biaya menjadi kendala, sehingga tidak semua tujuan pengendalian tercapai
5. Pengendalian yang diterapkan perusahaan seringkali tidak diselaraskan dengan
perkembangan yang terjadi dalam perusahaan
KAS
Aktiva lancar pertama yang ditulis pada neraca sebagian besar perusahaan.
Aset yang mempunyai sifat mudah digelapkan dan disembunyikan
Aset yang menjadi permulaan siklus operasi perusahaan.
Alat pertukaran (pembayaran).
Pos-pos yang tidak dikelompokkan sebagai Kas :
Uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank & lembaga keuangan lainnya.
Deposito ataupun sekuritas utang, deposito ataupun sekuritas utang ini dianggap sebagai setara kas jika pemilikannya bertujuan untuk managemen kas.
Cek mundur, cek yang yang baru dapat diuangkan pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang sehingga cek ini diklasifikasi sebagai piutang
Cek kosong, cek yang tidak cukup dananya sehingga cek ini diperlakukan sebagai piutang
Perangko dan materai, diklasifikasi sebagai bahan habis pakai
2. SISTEM VOUCHER DAN PENGENDALIAN
Pengendalian Internal Kas :
Kas menjadi aset yang paling mungkin untuk dicuri & disalahgunakan oleh
karyawan karena mudah dipindahtangankan.
Contoh praktik untuk menyelewengkan kas:
1. Penerimaan kas dicatat lebih rendah dari yang seharusnya dan selisihnya
dimasukkan ke kantong pribadi.
2. Piutang yang timbul dari penjualan kredit tidak dicatat. Kas yang diterima dari
piutang ini dikemudian hari digelapkan.
3. Cek untuk kepentingan pribadi dibebankan sebagai beban perusahaan.
4. Menunda posting (lapping), yaitu tidak mencatat penerimaan kas dari debitor
tertentu dan kas tersebut segera digelapkan.
Prinsip-prinsip Pengendalian Kas
Pemisahan tugas : tugas mencatat penerimaan dan pengeluaran kas harus
dipisahkan dari tugas menyimpan dan menyetujui pengeluaran kas.
Penyetoran ke bank : semua penerimaan kas harus segera disetor ke bank
dalam rekening giro.
Pemeriksaan mendadak : pemeriksaan terhadap catatan dan fisik kas harus
dilakukan secara mendadak dan tidak dalam interval waktu tertentu.
Menggunakan cek : semua pengeluaran kas (kecuali kas kecil) harus
dilakukan dengan menggunakan cek.
Prosedur pengendalian internal atas penerimaan kas
Perusahaan secara berhati-hati memilih pegawai.
Perusahaan harus mengeluarkan banyak uang untuk melakukan program pelatihan.
Pekerja tertentu akan ditugaskan sebagai kasir, pengawas kasir, atau akuntan untuk penerimaan kas.
Register kas berfungsi untuk mencatat transaksi.
Pelanggan menerima kwitansi sebagai bukti terjadinya transaksi
Rekening koran akan merinci penerimaan kas untuk direkonsilasikan dengan catatan perusahaan.
Audit internal untuk memeriksa transaksi yang dilakukan perusahaan, untuk mengetahui apakah kebijakan perusahaan telah dilaksanakan
Audit eksternal untuk memeriksa proses pengendalian internal perusahaan terhadap penerimaan kas.
Kasir dan pegawai bagian surat menyurat yang menangani penerimaan kas tidak boleh memiliki akses pada catatan akuntansi.
Hanya pegawai yang ditentukan seperti manajer dari suatu departemen yang dapat memberikan perkecualian bagi pelanggan, menyetujui penerimaan kas dalam jumlah tertentu serta memperbolehkan pelanggan untuk membeli secara kredit.
Prosedur pengendalian internal atas pengeluaran kas
Pengeluaran kas dipercayakan pada pegawai tingkat atas.
Petugas tertentu yang akan memberi persetujuan pada dokumen pembelian,
sehingga pembelian tersebut dapat dibayar.
Pengeluaran yang besar harus disetujui oleh pemilik perusahaan atau dewan
direksi untuk menjamin adanya kesesuaian dengan tujuan perusahaan.
Operator komputer dan pegawai lainnya yang menangani cek tidak boleh
memiliki akses terhadap catatan akuntansi.
Audit internal akan memeriksa terhadap transaksi yang dilakukan perusahaan
untuk melihat kesesuaian transaksi tersebut dengan kebijakan perusahaan.
Pemasok mengeluarkan faktur yang memperlihatkan jumlah yang harus
dibayar
Cek yang belum diisi disimpan dalam brankas dan dikendalikan oleh satu
orang tertentu yang tidak memiliki tugas akuntansi.
Rekonsiliasi Bank
Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus
disetorkan ke bank dan sebaliknya pengeluaran perusahaan harus menggunakan
cek. Praktik tersebut sering menyebabkan timbulnya perbedaan antara saldo kas
menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Pada waktu akan
menyusun laporan keuangan, perusahaan harus tahu saldo kas (termasuk kas kecil)
yang tepat untuk dilaporkan di Neraca.
Apabila terjadi perbedaan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan bank
maka harus diadakan rekonsiliasi bank.
Proses penjelasan sebab-sebab perbedaan antara catatan nasabah dengan catatan
bank mengenai rekening nasabah di bank.
Penyebab perbedaan tersebut pada dasarnya ada 2 yaitu :
1. Diakibatkan oleh beda waktu mencatat
2. Diakibatkan kesalahan
Berikut penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut :
No Keterangan Buku Perusahaan Buku Bank
1 Deposit in transit (setoran dalam
perjalanan) :
Setoran perusahaan yang belum
diterima oleh bank / perusahaan
mencatat setoran ini tetapi bank
belum mencatatnya
Sudah menambah
saldo kas
Belum menambah
saldo kas
2 Outstanding check (cek yang sudah
dikeluarkan oleh perusahaan tetapi
belum dibayar oleh bank)
Sudah mengurangi
saldo kas
Belum mengurangi
saldo kas
3 Tagihan wesel & bunga langsung
ditagihkan bank
Belum menambah
saldo kas
Sudah menambah
saldo kas
4 Bunga giro bank Belum menambah
saldo kas
Sudah menambah
saldo kas
5 Biaya administrasi bank Belum mengurangi
saldo kas
Sudah mengurangi
saldo kas
6 Cek kosong Sudah menambah
saldo kas, harus
dikurangi
Tidak mempengaruhi
7 Kekeliruan memasukkan setoran
rekening giro oleh bank
Sudah menambah
saldo kas
Belum menambah
saldo kas
Contoh rekonsiliasi bank :
1. Setoran dalam perjalanan Rp 1.591.630
2. Kesalahan bank, menambah Rp 100.000 ke rekening bank perusahaan
3. Cek-cek dalam peredaran :
No. 337 Rp 286.000
No. 338 Rp 319.470
No. 339 Rp 83.000
No. 340 Rp 203.140
No. 341 Rp 458.530
4. Pendapatan sewa secara Electronik Fund Transfer Rp 904.030
5. Penagihan oleh bank Rp 2.114.000 termasuk pendapatan bunga Rp 214.000
6. Bunga yang dihasilkan dari rekening bank Rp 28.010
7. Kesalahan pada buku perusahaan menambahkan Rp 360.000 ke nilai sisa bank
8. Biaya administrasi bank Rp 14.250
9. Cek kosong dari Rosita Lubis Rp 52.000
10.Pembayaran asuransi secara Electronic Fund Transfer Rp 361.000
11.Saldo menurut bank per 31 januari Rp 5.931.510
12.Saldo menurut perusahaan per 31 januari Rp 3.294.210
Contoh rekonsiliasi bank :
Laporan Rekonsiliasi Bank
Cek kosong dari Rosita
Lubis
Rp 52.000
Pembayaran asuransi
secara elektronik fund
transfer
Rp 361.000
Nilai sisa bank yang
disesuaikan
Rp 6.273.000
Nilai sisa perusahaan
yang disesuaikan
Rp 6.273.000
Kas Kecil (Petty Cash)
Dana yang terdiri dari sejumlah kecil uang kas yang digunakan untuk
membayar pengeluaran yang kecil jumlahnya.
Cash yang yang khusus dibuka untuk melayani pembayaran keperluan-
keperluan perusahaan yang rutin & meliputi jumlah yang relatif kecil.
Pembukuan Petty Cash
1. Metode imprest (dana tetap), metode yang menentukan jumlah petty cash
yang selalu konstan.
2. Metode Fluktuasi, metode yang menentukan jumlah petty cash tidak selalu
konstan.
PEMBUKUAN PETTY CASH
Point Metode Imprest Metode Fluktuasi
Pembelanjaan kas kecil Tidak ada jurnal, hanya
membuat bukti
pembayaran sebagai bukti
pengeluaran kas
Harus di jurnal sesuai
dengan expensenya
Pengisian kembali Sesuai dengan rekening
ledger, sehingga
pengisianya harus sesuai
dengan kebijakan
perusahaan dan sesuai
dengan jumlah kas kecil
saat pertama kali dibentuk
Pengisian sesuai dengan
yang dibutuhkan
CARA PENJURNALAN
Keterangan Metode Imprest Metode Fluktuasi
Debet Kredit Debet Kredit
Pembentukan kas kecil Kas Kecil Kas Kas Kecil Kas
Pemakaian kas kecil - - Biaya Kas Kecil
Penambahan kas kecil Kas Kecil Kas Kas Kecil Kas
Pengisian kembali Biaya Kas Kas Kecil Kas
Contoh Soal Petty Cash :
PT Astria Bersama menetapkan kas kecil untuk pembayaran pengeluaran dalam nominal yang kecil.
Kas kecil tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dengan menerima uang sebesar Rp 2.500.000 dari akun kas.
Berikutnya, kas kecil akan diisi lagi pada setiap tanggal 15 dan 30. Transaksi transaksi pengeluaran yang menggunakan kas kecil selama bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut:
03 januari Dibeli materai Rp 300.000
08 januari Pembayaran beban listrik Rp 320.000 dan air Rp 280.000
11 januari Dibayar biaya iklan di koran jawa pos Rp 250.000
14 januari Kas kecil dianggap terlalu besar Rp 500.000 sehingga disetor kembali ke kas
15 januari Dana kas kecil diisi kembali.
19 januari Dibayar biaya angkut pembelian Rp 240.000
21 januari Dibayar biaya telepon Rp 360.000
29 januari Dibayar untuk biaya pengobatan staf yang sakit Rp 200.000
30 januari Dana kas kecil diisi kembali
DEFINISI PIUTANG
Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu
maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas
(Slamet Sugiri, 2009:43)
Piutang adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si
pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi (Al Haryono Jusup,
2005:52)
Piutang timbul karena adanya penjualan (barang dagangan dan jasa) secara
kredit kepada perusahaan lain.
Setiap transaksi piutang selalu melibatkan 2 pihak :
1. Kreditur
pihak yang mendapat tagihan/ piutang (sebuah aset)
2. Debitur
pihak yang berkewajiban membayar utang (sebuah kewajiban)
JENIS-JENIS PIUTANG
Piutang Dagang / Usaha (Account Receivable)
Piutang yang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa
secara kredit. Rekening piutang ini diharapkan akan terkumpul dalam waktu
30 atau 60 hari.
Piutang Wesel / Wesel Tagih (Notes Receivable)
Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang disertai instrumen
formal kredit yang disebut wesel bayar (promesory note). Diberikan untuk
kredit dengan jangka waktu lebih dari 60 hari.
Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitur (yang
berutang) kepada pihak kreditor (yang memberi utang) untuk membayar
sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu
yang telah ditentukan dimasa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel
pada umumnya paling sedikit 60 hari.
Wesel Bayar : Bagi pihak yang berjanji membayar, instrumen kreditnya
Wesel Tagih : Bagi yang dijanjikan menerima pembayaran, instrumennya
Piutang Lain-lain
Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk
dalam piutang dagang maupun piutang wesel.
Piutang lain-lain meliputi piutang non usaha seperti piutang bunga, piutang
pajak, pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan
maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha.
Jika piutang tersebut dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun,
maka diklasifikasikan sebagai aset lancar.
Piutang
Dagang/Usaha
Piutang Wesel Piutang lain-lain
Jangka waktu kurang
dari 1 tahun 2/10,
n/30
Jangka waktu bermacam-macam
tetapi pada umumnya paling sedikit
60 hari
Jangka waktu lebih dari satu
tahun atau termasuk
dalam piutang jangka panjang.
Dimasukkan dalam
aktiva lancar
Bagian yang jatuh temponya dalam
waktu 1 tahun diperlakukan sebagai
aktiva lancar, sedangkan yang lebih
dari satu tahun piutang jangka
panjang
Pada umumnya termasuk
dalam piutang jangka panjang.
Berkaitan dengan
operasi utama
perusahaan sehingga
harus dapat ditagih
Mensyaratkan adanya jaminan
sehingga jika saat jatuh tempo tidak
dapat melunasi maka jaminan
tersebut dapat dijual
Tidak berkaitan dengan operasi
sehari-hari dan biasanya
dilaporkan dineraca sebagai
kelompok aktiva tidak lancar.
Pengendalian internal atas penerimaan piutang :
1. Ada pemisahan tugas dan fungsi : Pemisahan antara fungsi penjualan dan
fungsi kredit, Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan
dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang.
2. Otorisasi : Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, &
penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang
berwenang.
4. Pencatatan : Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang
(accounts receivable subsidiaty ledger), membuat daftar piutang berdasarkan
umumnya (aging schedule)
5. Prosedur : Prosedur retur, cadangan kerugian piutang dan potongan
penjualan harus dibuat. Serta Prosedur penagihan juga harus dibuat agar
penagihan piutang dapat dilakukan tepat pada waktunya dan bisa
mengurangi kerugian dari piutang tak tertagih.
6
Acctg.
Info
Penerimaan
Kas
Invoice
Acctg.
Info. Akuntansi
Barang
dan jasa
Penjualan
Credit
Info.
Persetujuan
Kredit
PEMISAHAN TANGGUNG JAWAB
YANG TERKAIT DENGAN PIUTANG
A. PIUTANG DAGANG /USAHA
3 permasalahan yang terkait dengan pitang dagang / usaha :
1. Pengakuan Piutang Dagang/Usaha
2. Penilaian Piutang Dagang/Usaha
3. Penyelesaian Piutang Dagang/Usaha
Pengakuan Piutang Dagang/Usaha
Piutang dagang diakui/dicatat pada saat :
a. Akun piutang dagang timbul karena penjualan kredit.
b. Terjadi retur dan potongan penjualan
c. Adanya pelunasan & potongan tunai
d. Perusahaan jasa, piutang timbul bila jasanya belum dibayar
.
Piutang dagang xx
Penjualan xx Retur & Potongan Penjualan xx
Piutang dagang xx
Kas
Potongan Penjualan
xx
xx
Piutang dagang xx
Piutang dagang xx
Pendapatan jasa xx
Coso 1 pengakuan piutang :
Tgl 1 Juli 2012 CV. Merapi menjual barang kepada CV. Merbabu seharga
Rp. 100.000,00 dengan termin 2/10, n/30.
Tgl 5 Juli 2012 barang dikembalikan seharga Rp. 10.000,00.
Tgl 10 Juli 2012 CV. Merapi menerima pembayaran dari CV. Merbabu
sebesar saldo tagihannya
Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut adalah
sebagai berikut :
Tgl Ket Nominal
Penilaian Piutang Dagang/Usaha
Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia:
Piutang Dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas (neto) yang
bisa direalisasi yaitu jumlah kas bersih yang dapat diterima.
Kerugian Piutang :
Adalah Piutang usaha yang tidak dapat ditagih dan dalam akuntansi dicatat
dalam akun kerugian piutang. Beban yang timbul atas tidak tertagihnya
piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebagai Beban Operasional,
dengan nama akun Beban Kredit Macet (Bad Debt Expense), atau Beban
Piutang Ragu-Ragu (Doubtful Accounts Expense), atau Beban Piutang Tak
Tertagih (Uncollectible Accounts Expense).
2 metode pencatatan kerugian piutang :
a. metode penghapusan langsung (direct write off method).
b. metode cadangan (Allowance method)
Piutang dagang xx
CKP (Cadangan Kerugian Piutang) (xx)
Nilai realisasi bersih xx
a. metode penghapusan langsung (direct write off method).
Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil seperti restoran, hotel, rumah
sakit, kantor pengacara, KAP dan toko Eceran
Alasan diterapkan :
1. Ada kepastian piutang debitur tidak dapat ditagih (bangkrut, dll)
2. Kegiatan utama penjualan tunai sehingga tidak material
b. metode cadangan (Allowance method)
Metode ini digunakan bila kerugian yang terjadi besar jumlahnya
Alasan diterapkan :
1. Ada pengalaman masa lalu Dari penjualan kredit
2. Dari saldo piutang dagang
3. Dari analisa umur piutang
2 (dua) Cara Menentukan Besarnya Estimasi atas Piutang Tak Tertagih :
a. Sebesar % Tertentu dari saldo Penjualan Berdasarkan data historis (pendekatan rugi
–laba)
b. Sebesar % Tertentu dari saldo Piutang Usaha, Ada dua metode (pendekatan neraca) :
Berdasarkan % tertentu dari jumlah saldo akhir piutang usaha berdasarkan data
historis
Berdasarkan klasifikasi/pengelompokan umur piutang (aging receivable)
Perbedaan pencatatan metode penghapusan langsung dengan metode
cadangan :
Catatan : Penghapusan piutang akan mengurangi rekening piutang dagang
melalui rekening CKP, tetapi nilai tunai yang dapat direlisasikan dari piutang
tidak berubah.
Metode penghapusan langsung Metode Cadangan
Pencatatan taksiran kerugian piutang :
Kerugian Piutang xx
CKP xx
tidak dilakukan taksiran
Pencatatan Penghapusan langsung :
CKP xx
Piutang Dagang xx
Kerugian Piutang xx
Piutang dagang xx
Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus :
Piutang Dagang xx
CKP xx
(untuk mencatat kembali piutang yang
sudah dihapus)
Kas xx
Piutang Dagang xx
(untuk mencatat penerimaan kas)
Piutang Dagang xx
Kerugian Piutang xx
(mencatat kembali piutang yang sudah
dihapus)
Kas xx
Piutang Dagang xx
(mencatat penerimaan kas)
Coso 2 penilaian piutang :
Pada Agustus 2009 PT Rahadian melakukan penjualan kredit kepada PT
FEDNY sebesar Rp. 5.000.000. Hingga akhir tahun 2009 terdapat piutang
sebesar Rp.500.000 yang belum dapat ditagih. Manajemen memperkirakan
Rp.100.000 tidak akan dapat ditagih. Pada bulan Agustus 2010 bagian
penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar Rp.50.000 dihapus dari
pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya dari PT
FEDNY. Secara tidak terduga pada bulan November 2010 PT FEDNY
melakukan pelunasan utangnya yang belum terbayar.
Diminta :
Buatlah jurnal penyesuaian dan jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat
transaksi diatas baik dengan metode cadangan maupun dengan metode
penghapusan langsung!
Estimasi Berdasarkan Klasifikasi Umur Piutang
Piutang akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan masing-masing karakteristik umurnya, berdasarkan atas tanggal jatuh temponya piutang
Karakteristik Umur Piutang dapat diklasifikasikan menjadi:
Belum Jatuh Tempo
Telah Jatuh Tempo 1 – 30 hari
Telah Jatuh Tempo 31 – 60 hari
Telah Jatuh Tempo 61 – 90 hari
Telah Jatuh Tempo 91 – 180 hari
Telah Jatuh Tempo 181 – 365 hari
Telah Jatuh Tempo di atas 365 hari
Ilustrasi Metode Klasifikasi Umur Piutang :
PT. Abadi Jaya sedang mempersiapkan Laporan Umur Piutang per 30 Juni 2012, dimana terdapat salah satu pelanggannya yang belum membayar hingga saat ini, padahal jatuh temponya tanggal 9 Maret 2012.
Maka lamanya umur piutang yang telah jatuh tempo dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah hari atas piutang yang sudah lewat per akhir Maret 22 hari
Jumlah hari atas piutang yang sudah lewat per akhir April 30 hari
Jumlah hari atas piutang yang sudah lewat per akhir Mei 31 hari
Jumlah hari atas piutang yang sudah lewat per akhir Juni 30 hari
113 hari
PT. Abadi Jaya, pada akhir tahun 2012 memiliki saldo piutang usaha sebesar Rp
86.300.000, dan cadangan kredit macet atas piutang usaha ini diestimasi berdasarkan
masing-masing kelompok umurnya:
Umur Piutang Saldo Estimasi Kredit Macet
% Jumlah
Belum Jatuh Tempo Rp 75.000.000,- 2% Rp 1.500.000,-
Telah Jatuh Tempo 1 – 30 hari 4.000.000,- 5% 200.000,-
Telah Jatuh Tempo 31 – 60 hari 3.100.000,- 10% 310.000,-
Telah Jatuh Tempo 61 – 90 hari 1.900.000,- 20% 380.000,-
Telah Jatuh Tempo 91 – 180 hari 1.200.000,- 30% 360.000,-
Telah Jatuh Tempo 181 – 365 hari 800.000,- 50% 400.000,-
Telah Jatuh Tempo diatas 365 hari 300.000,- 80% 240.000,-
Rp 86.300.000,- Rp 3.390.000,-
Penyelesaian /Pengalihan Piutang Dagang/Usaha
Pengalihan piutang adalah perusahaan mengalihkan piutang usaha yang
dimilikinya kepada pihak lain (lembaga keuangan, bank dan pegadaian
piutang) dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutangnya.
Alasan perusahaan menjual ataupun mengalihkan piutangnya :
a. Kondisi perusahaan sedang sulit
b. Penagihan membutuhkan waktu yang lama dan memakan biaya
Adapun jenis pengalihan piutang antara lain :
Penjualan piutang : piutang usaha dapat dijual kepada bank / lembaga
keuangan lainnya
Penggadaian/penjaminan piutang : dijaminkan untuk memperoleh
pinjaman
Penjualan dengan kartu kredit : Penjualan dengan kartu kredit terdapat
tiga pihak yang terlibat yaitu Penjual; Penerbit kartu kredit dan Pembeli.
Penjualan dengan kartu kredit bagi penjual diperlakukan sebagai
penjualan kredit. Piutang yang timbul bukan kepada pembeli tetapi
kepada penerbit kartu kredit.
Coso 3 Penyelesaian /Pengalihan Piutang :
Penjualan piutang :
Pada tanggal 10 Juli 2005 PT Rahadian menjual piutang usahanya yang
bernilai Rp. 2.500.000 kepada Bank Niaga Syariah. Harga jual piutang usaha
tersebut adalah Rp. 2.250.000. CKP pada tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp.
150.000. Untuk berjaga-jaga, Bank Niaga Syariah menahan 10 % dari harga
jual piutang usaha. Maka :
piutang usaha dijaminkan :
Pada tanggal 1 mei 2005 PT Rahadian memperoleh pinjaman dari Bank Niaga Syariah
dengan jaminan piutang usaha sebesar Rp.2.000.000. Pinjaman yang diterima 90 %
dari piutang yang dijaminkan dipotong biaya administrasi Rp. 25.000. Bunga pinjaman
18 % setahun.
Pada saat menerima pembayaran piutang usaha yang dijaminkan
Pada tanggal 31 mei 2005 PT Rahadian menerima pembayaran piutang yang
dijaminkan sebesar Rp 1.500.000. Bunga bulan mei sebesar Rp. 30.000 (2.000.000
x 18 % x 1/12) sehingga jumlah uang yang dibayar ke bank sebesar Rp. 1.530.000 (rp.
1.500.000 + 30.000).
Jika terdapat retur atau penghapusan piutang maka saldo piutang yang
dijaminkan harus dikurangi. Misal tanggal 5 Juni 2005 PT Rahadian
menerima kembali barang dagangan yang telah dijual sebesar Rp. 50.000.
Jurnal yang dibuat :
Penjualan dengan kartu kredit :
Butik Syahmina menerima pembayaran dengan kartu kredit sebesar Rp.
1.000.000 atas baju, kebaya dan jilbab yang dibeli oleh seorang pembeli yang
menggunakan American Express. Biaya jasa yang diberikan kepada penerbit
kartu kredit sebesar 5 % dari jumlah transaksi sehingga jumlah yang dibayar
oleh American Express sebesar Rp 950.000 ( 5 % x 1.000.000) Jurnal untuk
mencatat transaksi tsb diatas adalah:
A. PIUTANG WESEL
Wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari sipenarik (pembuat
surat) kepada si wajib bayar (yang berutang) untuk membayar sejumlah uang
tertentu. Contoh surat wesel haryono jusup halaman 68.
Promes adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal
tertentu.
Kedua surat tersebut bagi pemegang wesel dan promes merupakan piutang dan
dicatat dalam rekening piutang wesel sedangkan bagi pihak yang berkewajiban
membayar meru pakan utang dan dicatat dalam utang wesel.
Perbedaan wesel dengan promes :
WESEL PROMES
wesel adalah surat perintah untuk membayar promes adalah surat janji untuk
membayar
penarik dan yang berkepentingan terdiri dari
dua pihak
penarik dan pihak yang berkepentingan
berada di satu tangan
yang membuat adalah pihak yang
mempunyai piutang
yang membuat adalah pihak yang
berutang
memerlukan akseptasi tidak memerlukan akseptasi
Wesel dibedakan menjadi dua yaitu :
1. wesel tanpa bunga, nilai jatuh tempo wesel ini sebesar nilai nominalnya.
2. wesel berbunga, nilai jatuh tempo wesel ini sebesar nilai nominal ditambah
bunga selama jangka waktu wesel.
Piutang wesel timbul karena adanya :
1. penjualan kredit
2. pemberian pinjaman
3. perubahan dari piutang menjadi piutang wesel
Catatan : jika ada bunga, bunga
o belum diperhitungkan pada saat pengakuan piutang wesel
o Bunga diakui setelah menerima penyelesaian wesel
Penjualan kredit Pemberian pinjaman Piutang wesel
Piutang Wesel xx
Penjualan xx
Piutang Wesel xx
Kas xx
Piutang Wesel xx
Piutang Dagang xx
Akuntansi untuk mencatat piutang wesel dibagi tiga yaitu :
1. Pengakuan piutang wesel
2. Penilaian piutang wesel/ pelunasan piutang wesel
3. pelimpahan / pengalihan/pendiskontoan piutang wesel.
Pengakuan piutang wesel
Rekening piutang didebit sesuai dengan nominalnya tanpa memperhatikan
apakah piutang wesel tersebut berbunga atau tidak. Jurnalnya :
Coso 4:
PT FEDNY pada tanggal 1 Mei 2005 menjual barang dagangan dengan harga
Rp. 50.000.000 kepada PT BALQIS yang membuat janji akan membayar pada
tanggal 31 Mei 2005.
Penjual Pembeli Bank
Piutang Wesel xx
Penjualan xx
(Untuk mencatat Penjualan
dengan menerima wesel)
Piutang Wesel xx
Kas xx
(Mencatat Pembelian dengan
menyerahkan wesel)
Belum ada jurnal
Jurnalnya : (dalam ribuan)
Pelunasan wesel
Pada saat jatuh tempo, PT. BALQIS melunasi hutangnya sebesar nilaijatuh
temponya. Jika wesel tidak berbunga nilai jatuh temponyasebesar nilai
nominalnya. Jurnalnya : (dalam ribuan)
PT FEDNY PT BALQIS Bank
PT FEDNY PT BALQIS Bank
Jika wesel berbunga nilai jatuh temponya sebesar nilai nominalnya+bunga :
misal wesel berbunga 6 % per tahun :
Nilai nominal wesel Rp. 50.000.000
Bunga 1 bulan (1-31 mei) Rp. 250.000
(50.000.000 x 6% x 1/12)
Nilai jatuh tempo Rp. 50.250.000
Jika Wesel Dilunasi (dalam ribuan)
PT FEDNY PT BALQIS Bank
Kas 50.250
Piutang wesel 50.000
Pend. Bunga 250
(Untuk mencatat
Penerimaan kas dari
pelunasan piutang)
Utang wesel 50.000
Biaya bunga 250
Kas 50.250
(Mencatat Pembayaran
utang wesel kepada PT
Fedny)
Belum ada jurnal
Pendiskontoan piutang wesel
Wesel dagang pada umumnya bersifat Negotiable artinya dapat
diperdagangkan yakni sebelum tanggal jatuh tempo wesel tersebut dapat
dijual.
Menjual wesel sebelum tanggal jatuh tempo disebut “mendiskontokan wesel”
Pendiskontoan piutang wesel pada umumnya nilainya lebih rendah dari nilai
jatuh temponya.
PT FEDNY pada tanggal 1 mei 2005 menerima wesel dengan nilai nominal
Rp. 50.000.000, jangka waktu 90 hari. Pada tanggal 30 mei 2005, wesel
tersebut diidiskontokan ke Bank Syariah Mandiri dengan tingkat diskonto 10%
Jawab:
Jangka waktu wesel : 90 hari
Tgl wesel 1 mei (31-1): 30
Bulan Juni (30 hari): 30
Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2005
Pada tanggal 30 mei wesel tersebut didiskontokan
Cara menghitung nilai wesel yang didiskontokan
Nilai Diskonto = Nilai saat jatuh tempo x % diskonto x jumlah hari yang dipegang bank
Maka nilai diskonto = 50.000.000 x 10 % x 61/360 = 847.220
Jadi jumlah kas yang diterima sebesar (50.000.000-847.220) = 49.152.780
Jurnal untuk wesel tidak berbunga : (dalam ribuan)
Jika wesel berbunga (12 %) :
)
PT FEDNY PT BALQIS Bank
Saat Pelunasan Piutang Wesel Yang Telah Didiskontokan
PT FEDNY PT BALQIS Bank
PT FEDNY 30 juli PT BALQIS3 0 juli Bank 30 juli
DEFINISI PERSEDIAAN
merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali
dalam kegiatan operasional normal perusahaan.
Persediaan pada perusahaan pabrikan terdiri dari persediaan bahan baku,
persediaan dalam proses dan persediaan barang jadi.
Dasar-dasar Persediaan :
Neraca dalam perusahaan manufaktur dan dagang menggambarkan
persediaan merupakan aktiva lancar yang jumlahnya sangat besar.
Laporan rugi laba, persediaan merupakan hal yang sangat menentukan
keuntungan atau hasil usaha.
Pendapatan kotor, (penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan)
diawasi oleh manajemen perusahaan, pemilik maupun pihak-pihak lain.
Karakteristik Persediaan Barang :
1. Barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal
perusahaan.
2. Sistem pencatatan persediaan menggunakan 2 metode yaitu: sistem
persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual.
3. Penilaian persediaan menggunakan 2 cara penilaian yaitu dengan pendekatan
arus harga pokok, dan selain arus harga pokok.
4. Persediaan akhir dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar.
5. Persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal suatu periode akuntansi
disebut persediaan awal.
6. Persediaan yang dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode akuntansi
disebut persediaan akhir.
7. Persediaan akhir suatu periode akan menjadi persediaan awal periode
akuntansi berikutnya.
Karakteristik Persediaan Barang Dagangan
1. Persediaan Barang Dagangan dimiliki oleh perusahaan
2. Dalam bentuk siap untuk dijual
Pengelompokan Persediaan dalam Lingkungan Pabrikan (manufacturing):
1. Persediaan pabrikan mungkin bukan merupakan persediaan yang siap dijual
2. Diklasifikasikan dalam tiga kategori:
a. barang jadi, siap dijual kepada konsumen
b. sedang dalam proses produksi, beberapa tahap produksi (belum selesai)
c. bahan baku atau mentah, komponen atau bahan yang siap untuk
digunakan dalam proses produksi
Penentuan Kuantitas Persediaan
Dalam mempersiapkan laporan keuangan perlu ditentukan:
1. Jumlah unit dalam persediaan dengan cara menghitung, menimbang atau
mengukur jumlah barang persediaan secara fisik yang ada di perusahaan.
2. Kepemilikan barang.
Pengelolaan Fisik Persediaan
Prinsip-prinsip pengendalian intern untuk persediaan meliputi:
1. Pemisahan tugas, penghitungan persediaan dilakukan oleh karyawan yang
bukan bertugas mengawasi persediaan.
2. Penyelenggaraan pertanggungjawaban, masing-masing bagian dalam
pengelolaan persediaan wajib menggunakan otorisasi yang otentik.
3. Verifikasi intern yang independen, penghitungan ulang persediaan oleh
petugas yang lain dan dilakukan penandaan terhadap item barang persediaan.
Penandaan hanya dilakukan sekali.
4. Prosedur pendokumentasian, menggunakan penandaan barang dengan
dokumen yang sudah dinomori sebelumnya (prenumbered)
Kepemilikan Persediaan dalam Perjalanan :
1. Persediaan barang dalam perjalanan, meliputi pihak yang berhak menerima
persediaan.
2. FOB (Free on Board), shipping point. Kepemilikan barang menjadi milik
pembeli pada saat diserahkan penjual kepada penyelenggara transportasi
atau pihak perusahaan pengirim barang yang independen.
3. FOB (Free on Board) destination point. Kepemilikan barang masih berada di
penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli.
Barang Konsinyasi
Konsinyasi: Pemegang atau penjual barang (consignee) bukan merupakan
pemilik barang. Karakteristiknya:
1. Kepemilikan tetap berada ditangan pemilik barang (consignor) sampai barang
tersebut terjual.
2. Barang konsinyasi merupakan persediaan barang dagangan milik consignor,
bukan persediaan milik consignee.
Sistem Akuntansi Persediaan
1. Perpetual (perpetual inventory system)
Sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi
persediaan (pembelian, penjualan, ataupun retur)
2. Periodik (periodic inventory system)
Pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan
periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan (stock
opname of inventories) dengan cara mengukur dan menghitung berapa
jumlah barang yang ada di gudang. Sistem pencatatan ini pada akhir periode
dibutuhkan ayat
jurnal penyesuaian sebagai berikut:
Untuk persediaan awal :
Untuk persediaan akhir:
Ikhtisar Rugi Laba (income summary) xxx
Persediaan (inventories) xxx
Persediaan (inventories) xxx
Ikhtisar Rugi Laba (income summary) xxx
PENILAIAN PERSEDIAAN
Penilaian
Persediaan
Pendekatan Harga Pokok Penjualan
Selain Pendekatan Harga Pokok Penjualan
Sistem Periodik
Sistem Perpetual
1. FIFO
2. LIFO
3. Average
1. FIFO
2. LIFO
3. Average
1. Low cost of market
2. Gross profit method
3. Retail method
PENILAIAN PERSEDIAAN
1. Penilaian dengan pendekatan arus harga pokok (cost basic flow approach)
Dalam pendekatan ini terdapat dua sistem pencatatan persediaan yaitu
Sistem periodik dan sistem perpetual yang masing-masing ada tiga cara
penilaian persediaan, yaitu:
a. FIFO (First in First Out), masuk pertama keluar pertama
Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal
(pertama) masuk akan dijual (digunakan) terlebih dahulu, sehingga
persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir
masuk (dibeli). Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang
nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli.
b. LIFO (Last In First Out), masuk terakhir keluar pertama
Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir
masuk akan dijual (digunakan) terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir
dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal
(pertama) masuk atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan nilai
persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan
yang rendah.
c. Metode Rata-rata (average method)
Dengan menggunakan metode ini nilai persediaan akhir akan menghasilkan
nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO. Metode
ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor.
2. Penilaian Persediaan Selain Arus Harga Pokok
Dalam pendekatan ini ada tiga metode yang digunakan, yaitu:
a. Lower Cost of Market
Yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode
ini dapat diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal, misalnya cacat,
rusak dan kadaluarsa. Pokok dari metode ini adalah membandingkan nilai
yang lebih rendah antara nilai pasar (replacement value) dan nilai perolehan
(cost). Nilai pasar yang akan dipilih harus dibatasi, yaitu tidak boleh lebih
rendah dari batas bawah (floor limit) dan tidak boleh lebih tinggi dari batas
atas (ceiling limit).
Metode ini diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal.
Metode ini membandingkan nilai yang lebih rendah antara nilai pasar dan
nilai perolehan. Nilai pasar yang dipilih harus dibatasi.
Metode LCM ini, prosedur penilaian persediaan yang dilakukan adalah
dengan memilih nilai yang terendah antara harga pokok dengan harga pasar.
Metode ini diterapkan utnuk menilai persediaan yang memiliki nilai di
bawah cost awal yang disebabkan oleh kejadian-kejadian seperti perubahan
tingkat harga, kerusakan dan lain sebagainya. Kondisi tersebut tentu akan
menyebabkan kerugian perusahaan dan barang tentu pula perusahaan harus
mengakui timbulnya kerugian tersebut.
b. Gross Profit Method
Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya.
Biasanya diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan
persediaan, misalnya karena terjadi bencana kebakaran dan banjir. Dasar
penilaian persediaannya adalah pada persentase laba kotor perusahaan
tahun berjalan atau rata-rata selama beberapa tahun.
Metode ini penilaian persediaan bersifat estimasi.
Penilaian persediaan mendasarkan pada persentase laba kotor perusahaan
tahun berjalan atau rata-rata selama beberapa tahun.
Merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menentukan taksiran nilai
persediaan tanpa dilakukannya perhitungan fisik persediaan (stock opname)
dan untuk menguji ketelitian data akuntansi apabila sistem permanen
digunakan.
Langkah-langkah yang dilakukan adalah:
1) 1mengestimasi nilai penjualan tahun berjalan,
2) menghitung nilai harga pokok penjualan berdasarkan pada persentase
laba kotor yang telah diketahui dan
3) menghitung estimasi nilai persediaan akhir dengan mengurangkan harga
pokok penjualan terhadap penjualan
c. Retail Method
Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung
terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Nilaii
persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara
menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan
pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan ritel. Kemudian
rasio yang diperoleh dikalikan dengan persediaan akhir yang dinilai dengan
pendekatan eceran dapat dirumuskan sebagai berikut:
Persediaan
akhir menurut
harga pokok
Persediaan
akhir menurut
eceran
Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan retail dan department
store, yang memperjualbelikan banyak jenis barang dengan frekuensi
perputaran barang yang relatif tinggi.
Tujuan penggunaan Metode Harga Jual Eceran :
1.Untuk menentukan nilai persediaan dalam rangka penyusunan laporan
keuangan jangka pendek, di mana tidak dimungkinkan untuk
melakukan stock opname.
2.Sebagai alat untuk menentukan harga pokok (taksiran) dari kuantitas
barang yang ada di gudang (harga pokok persediaan akhir)
3.Sebagai pengawasan terhadap aktivitas pembelian, penjualan, dan
mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya manipulasi persediaan.
Tahap-tahap penentuan persediaan dengan metode harga jual eceran :
1. Penentuan besarnya barang tersedia untuk dijual dengan harga pokok
dan harga jual eceran
2. Penentuan Cost Ratio
3. Penentuan besarnya Penjualan bersih
4. Penentuan nilai persediaan akhir menurut harga jual eceran
5. Penentuan taksiran harga pokok persediaan akhir
LATIHAN 1:
Dibawah ini terdapat catatan mengenai persediaan PT. Khatulistiwa selama
bulan September 2008 sebagai berikut:
Diminta: tentukan nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba kotor
jika diasumsikan perusahaan menerapkan sistem periodik FIFO dan sistem
perpetual LIFO.
Tanggal Keterangan Kuantitas Harga
1 sept Persediaan awal 100 unit Rp.10.000
5 sept Pembelian,termin 2/10, n/60 500 unit Rp.12.000
12 sept Pembelian,termin 2/10, n/60 100 unit Rp.15.000
22 sept Penjualan 300 unit Rp.25.000
27 sept Pembelian,termin 5/10, n/30 100 unit Rp 20.000
30 sept Penjualan 50 unit Rp.30.000
LATIHAN 2:
Dibawah ini terdapat catatan mengenai persediaan PT. Khatulistiwa selama
bulan September 2008 sebagai berikut:
Diminta: tentukan nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba kotor
jika diasumsikan perusahaan menerapkan sistem periodik FIFO dan sistem
perpetual LIFO.
Tanggal Keterangan Kuantitas Harga
1 Juli Persediaan awal 55 unit Rp. 320
8 Juli Pembelian 25 unit Rp. 325
9 Juli Penjualan 60 unit Rp. 400
13 Juli Pembelian 40 unit Rp. 328
19 Juli Penjualan 30 unit Rp 600
23 Juli Pembelian 50 unit Rp. 330
25 Juli Penjualan 10 unit Rp 620
Latihan 3 retail method :
Latihan 4 gross profit method :
Dari catatan pembukuan yang diperiksa, diperoleh informasi yang berhubungan
dengan persediaan sbb :
Persediaan awal (1 Januari) Rp 75.000,-
Pembelian 705.000,-
Penjualan 930.000,-
Atas dasar tingkat laba kotor sebesar 25 % dari hasil penjualan,maka besarnya
nilai persediaan akhir (31 Desember) adalah ?
HARGA POKOK HARGA JUAL ECERAN
Persediaan Awal 500.000,- 625.000,-
Pembelian 11.250.000,- 14.062.500,-
Penjualan - 13.750.000,-
latihan 5 low cost of market :
Kuantitas Perolehan Pasar
Persediaan Per Unit Per Unit
A 400 Rp 10.25 Rp 9.50 Rp 4,100 Rp 3,800
B 120 Rp 22.50 Rp 24.10 Rp 2,700 Rp 2,892
C 600 Rp 8.00 Rp 7.75 Rp 4,800 Rp 4,650
D 280 Rp 14.00 Rp 14.75 Rp 3,920 Rp 4,130
TOTAL 1400 Rp 15,520 Rp 15,472
Harga
PerolehanHarga PasarKomoditas
JAWABAN SOAL RETAIL METHOD
Tahap Keterangan Harga Jual Eceran Harga Pokok
Persediaan awal Rp 625,000 Rp 500,000
Pembelian Rp 14,062,500 Rp 11,250,000
1 Barang Tersedia Untuk Dijual Rp 14,687,500 Rp 11,750,000
Cost Ratio
(11.750.000 / 14.687.500) x 100% = 80 %
3 Penjualan Rp 13,750,000 -
4 Persediaan Akhir menurut Harga Jual Eceran Rp 937,500 -
Persediaan Akhir menurut Harga Pokok
80 % x Rp 937.500,- Rp 750,000
Harga Pokok Penjualan (Taksiran) Rp 11,000,000
2
5
JAWABAN SOAL GROSS PROFIT METHOD
Penjualan = Rp 930.000
Laba Kotor (25% x Rp 930.000) = Rp 232.500 –
Harga Pokok Penjualan = Rp 697.500
Persediaan awal (01 Januari) = Rp 75.000
Pembelian = Rp 705.000 +
Barang yang tersedia untuk dijual = Rp 780.000
HPP = Rp 697.500 –
Persediaan akhir = Rp 82.500
JAWABAN SOAL LOW OF COST METHOD
Kuantitas Perolehan Pasar Lebih rendah
Persediaan Per Unit Per Unit Perolehan atau Pasar
A 400 Rp 10.25 Rp 9.50 Rp 4,100 Rp 3,800 Rp 3,800
B 120 Rp 22.50 Rp 24.10 Rp 2,700 Rp 2,892 Rp 2,700
C 600 Rp 8.00 Rp 7.75 Rp 4,800 Rp 4,650 Rp 4,650
D 280 Rp 14.00 Rp 14.75 Rp 3,920 Rp 4,130 Rp 3,920
TOTAL 1400 Rp 15,520 Rp 15,472 Rp 15,070
Harga
PerolehanHarga PasarKomoditas
DEFINISI
Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi
perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan
normal perusahaan. (Haryono Jusup, 2005; 153)
Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yan berumur lebih dari satu tahun yang
dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam perusahaan
bukan untuk dijual kembali (Wit & Erhans, 2000; 82)
Aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk
jangka waktu yang lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual
kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran
yang nilainya besar atau material. (Firdaus A. Dunia )
Menurut SAK ETAP 2009 par. 15.2 : Aset tetap/ aktiva tetap adalah aset
berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan
administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.
Aset tetap adalah aset berwujud yang (Slamet Sugiri, 2009; 137) :
a.dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,
untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administratif
b.diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode
Karakteristik Aktiva tetap
1. Perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan, dan bukan untuk
diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Contoh: Mobil yang
digunakan oleh perusahaan untuk antar jemput pegawai bukan untuk
diperdagangkan oleh perusahaan, Mesin-mesin, pabrik, tanah,
bangunan/gedung, perabot, peralatan, kendaraan, dll.
2. Umur atau jangka waktu pemakaiannya yang lebih dari satu tahun. Dikenal
dengan istilah penyusutan (depreciation)
3. Bahwa pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang
nilainya besar atau material bagi perusahaan tersebut.
Diurutkan dalam neraca berdasarkan urutan masa manfaatnya yang paling lama.
Dimulai dari Tanah, Bangunan, dst.
Aset tetap mempunyai
umur yang panjang atau
permanen.
Aset tetap berwujud karena
mempunyai bentuk fisik.
Dimiliki dan digunakan oleh
perusahaan dan tidak untuk
dijual sebagai bagian dari
operasi onal.
SIFAT DASAR ASET TETAP
Yang dibeli
berumur panjang?
Ya
Apa aset itu
digunakan untuk
tujuan produktif?
tidak
Beban
Ya
Aset Tetap
tidak
Investasi
Klasifikasi
Biaya
KLASIFIKASI AKTIVA TETAP
Aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok yaitu (Haryono Jusup,
2005:155):
a. Tanah : seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung
perusahaan
b. Perbaikan tanah : seperti jalan-jalan diseputar lokasi perusahaan, tempat parkir,
pagar dan saluran air bawah tanah
c. Gedung : seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik dan gudang
d. Peralatan : seperti peralatan kantor, mesin pabrik, peralatan pabrik, kendaraan
dan mebel
Pengakuan Awal :
Aktiva tetap diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aktiva
tetap meliputi:
1. Harga beli setelah dikurangi diskon dengan nama apa pun.
2. Biaya langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi sampai siap
dipergunakan sesuai dengan maksud managemen
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya
restorasi lokasi
Pengendalian Internal Aset Tetap
1. Persetujuan untuk pengeluaran aset tetap biasanya dilakukan oleh berbagai
tingkat manajemen, tergantung pada jenis dan harga aset tetap yang
bersangkutan. Contohnya pembelian mesin tik cukup dengan persetujuan
kepala bagian yang memerlukan peralatan ini dan direktur keuangan.
2. Perusahaan harus mempunyai kebijaksanaan keuangan atau akuntansi
secara tertulis mengenai kapitalisasi, untuk membedakan pengeluaran yang
merupakan aset tetap (capital expenditure) dan pengeluaran yang bukan aset
tetap (revenue expenditure) sehingga dapat mencatat aset tetap dengan tepat
3. Adanya kebijaksanaan dan prosedur mengenai pengadaan aset tetap,
penjualan, pembesituaan, dan pemindahannya dari bagian ke bagian lain atau
antarcabang dan sebagainya
4. Menyelenggarakan buku-buku tambahan atau kartu-kartu aset tetap dan
melakukan penghitungan fisik atas aset tetap secara periodik atau berkala
5. Mengasuransikan aset tetap untuk jumlah yang cukup dari bencana tertentu
seperti kebakaran dan kerugian karena kehilangan atau dicuri.
Harga perolehan Aset Tetap meliputi seluruh jumlah yang
dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut.
1. Harga Beli
2. Pajak
3. Ongkos angkut
4. Biaya asuransi selama dalam perjalanan/pengriman/angkutan
5. Ongkos pemasangan
6. Biaya uji coba
7. Biaya survei (misal dalam pembelian tanah/gedung)
8. Komisi perantara (misal dalam pembelian tanah/gedung, kendaraan)
9. Biaya pengurusan surat kepemilikan (misal dalam pembelian
tanah/gedung, kendaraan)
10.Dll.
PENENTUAN HARGA PEROLEHAN AKTIVA TETAP
Prinsip Akuntansi => Aktiva Tetap harus dicatat sesuai dengan Harga
Perolehannya (cost)
Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk
mendapatkan aktiva tetap dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva siap
untuk digunakan (Haryono Jusup, 2005; 155)
Harga perolehan adalah harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperolehnya dan menyiapkan aktiva tetap tersebut sampai siap
digunakan (Wit & Erhans, 2000; 82).
Misal : Sebuah computer merk Dell dibeli dengan harga Rp. 7.500.000 dengan
potongan tunai 10 % biaya yang dikeluarkan untuk install komputer dan
pemasangan hingga siap digunakan sebesar Rp. 250.000 harga
perolehan komputer tersebut dapat dihitung sbb :
Harga beli : 7.500.000
Potongan tunai 10 % : 750.000 –
6.750.000
Biaya install dan pasang : 250.000
Harga Perolehan 7.000.000
Harga tanah Rp 100.000.000
Biaya lainnya:
Komisi makelar Rp 2.500.000
Biaya notaris Rp 500.000
Biaya balik nama Rp 750.000
Total harga perolehan Rp 103.750.000
Ayat Jurnal untuk mencatat perolehan aktiva tetap adalah
Komputer 7.000.000
Kas 7.000.000
Ayat jurnal untuk mencatat pembelian tanah :
Tanah Rp 103.750.000
Kas Rp 103.750.000
Jika dilakukan pembelian beberapa aset tetap maka total harga beli harus
dialokasikan ke masing-masing aset tetap dengan cara taksiran yaitu
menggunakan metode nilai jual relatif.
Terdapat berbagai cara dalam memperoleh aktiva tetap, yang akan
mempengaruhi penentuan harga perolehan. Berbagai cara tersebut antara
lain :
a. pembelian secara tunai;
b. pembelian kredit;
c. pembelian dengan wesel bunga;
d. pembelian gabungan (dalam satu paket);
e. membangun sendiri aktiva dan adanya sumbangan dari pihak lain.
a. pembelian secara tunai;
Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih
setelah dikurangi potongan tunai ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran.
Misal : dibeli mesin pabrik Rp. 55.000.000, pengeluaran yang berkaitan
dengan pembelian mesin antara lain : PPN sebesar Rp. 5.500.000; Premi
asuransi sebesar Rp. 550.000 dan biaya pemasangan sebesar Rp. 1.450.000
maka harga perolehannya :
Harga beli : 55.000.000
PPN : 5.500.000
Premi asuransi : 550.000
Biaya pemasangan : 1.450.000
Harga perolehan 62.500.000
Jurnal :
Mesin pabrik 62.500.000
Kas 62.500.000
b. pembelian kredit;
Pembelian secara kredit jangka panjang pada umumnya melibatkan bunga.
Bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan secara implisit.
Bunga eksplisit dalam pembelian kredit adalah bunga yang ditetapkan secara
jelas/terus terang
Bunga implisit : bunga yang ditetapkan tidak secara terus terang sehingga
harus mencari terlebih dahulu bunganya.
Baik secara eksplisit maupun secara implisit bunga tidak boleh dimasukkan
dalam menghitung harga perolehan karena bunga bukan merupakan
pengorbanan untuk memperoleh aktiva tetap, tetapi pengorbanan untuk
menggunakan dana pihak lain.
c. pembelian dengan wesel bunga;
Dalam pembelian aktiva dengan jumlah rupiah yang besar, kadangkadang
perusahaan membayarnya dengan wesel berbunga. Biasanya pembeli
diwajibkan membayar uang muka dan sisanya dibayar dengan wesel berbunga
dimana bunga wesel dibayar pada saat jatuh tempo wesel tersebut. Harga
perolehan aktiva dihitung dengan jumlah uang muka ditambah nilai nominal
wesel. Sedangkan biaya bunga merupakan biaya pendanaan (financing cost)
yang dicatat dengan mendebet rekening biaya bunga.
:
Contoh :
PT FEDNY membeli peralatan pabrik dengan harga tunai 120.000.000 Uang muka
yang diberikan sebesar 20.000.000 dan sisanya dibayar dengan wesel berbunga
janka waktu 1 tahun bunga 10 %.
Jurnal untuk mencatat pembelian aktiva tetap tersebut :
Peralatan pabrik 120.000.000
Kas 20.000.000
Utang wesel 100.000.000
(untuk mencatat uang muka dan penarikan utang wesel)
Pada saat jatuh tempo wesel, dibayarkan nilai nominalnya ditambah dengan bunga
sebesar 10.000.000 ( 100.000.000 x 10%) dan dicatat dalam jurnal :
Utang wesel 100.000.000
Biaya bunga 10.000.000
Kas 110.000.000
d. pembelian gabungan (dalam satu paket);
Pembelian dalam satu paket (gabungan) sering disebut sebagai pembelian secara
lump-sum. Harga paket (borongan)didasarkan pada harga perolehan masing-
masing aktiva tetap yang ditentukan dengan harga pasar .
Pembelian dalam satu paket (gabungan) sering disebut sebagai pembelian secara
lump-sum. Harga paket (borongan)didasarkan pada harga perolehan masing-masing
aktiva tetap yang ditentukan dengan harga pasar .
Misal:
PT LISA pada tanggal 1 januari 2010 membeli tanah, gedung dan peralatan dengan
harga total 100.000.000 dan harga pasar masingmasing sebesar 45.000.000 untuk
tanah, 75.000.000 untuk gedungnya dan 30.000.000 untuk peralatan. Hitunglah
alokasi harga perolehan masing-masing aktiva tersebut dan buatlah jurnalnya.
Jurnal untuk mencatat pembelian aktiva tetap secara gabungan
Tanah, gedung & peralatan 100.000.000
Kas 100.000.000
Jurnal untuk mencatat alokasi harga perolehan masing-masing aktiva
Tanah 30.000.000
Gedung 50.000.000
Peralatan 20.000.000
Tanah, gedung & peralatan 100.000.000
Golongan Harga Pasar % dari HP & Perhitungan Alokasi
Tanah 45.000.000 30 % x 100.000.000 30.000.000
Gedung 75.000.000 50 % x 100.000.000 50.000.000
Peralatan 30.000.000 20 % x 100.000.000 20.000.000
150.000.000 100 % 100.000.000
e. membangun sendiri aktiva dan.
Perusahaan terkadang membangun sendiri aktiva tetapnya. Misalkan perusahaan
membangun sendiri kantornya, garasi ataupun gudangnya. Harga perolehan aktiva
yag dibangun sendiri oleh perusahaan terdiri dari harga material atau bahan
bangunan yang dipakai, upah tenaga kerja, dan biaya lain-lain meliputi listrikdan
depresiasi aktiva tetap perusahaan yang digunakan untuk membangun.
Dimunkinkan pula adanya biaya bunga jika perusahaan dalam membangun
meminjam dari pihak luar sehingga biaya bunga dimasukkan dalam unsur harga
perolehan tetapi hanya biaya bunga selama masa konstruksi saja. Jika setelah
masa konstruksi belum lunas maka biaya bunga dibebankan sebagai biaya
periodik dalam kelompok biaya diluar usaha dalam laporan laba rugi. Jika harga
perolehan aktiva dengan membangun sendiri lebih kecil dari (lebih rendah) dari
harga aktiva sejenis, perusahaan tidak diperkenankan mengakui adanya
keuntungan akibat membangun sendiri.
f. adanya sumbangan dari pihak lain
Aktiva tetap dapat diperoleh dari sumbangan, misalnya sumbangan dari pemerintah
atau lembaga lain. Meski untuk memperoleh sumbangan tidak ada pengorbanan
yang dikeluarkan, akuntansi tetap mencatatnya karena akuntansi merupakan alat
pertanggugjawaban. Aktiva tetap dari sumbangan didebit dan akun lawannya
adalah modal sumbangan. Nilainya adalah sebesar nilai wajar pada saat
sumbangan itu diterima.
Contoh:
Pada tanggal 27 januari 2010 PT Bejobanget menerima sumbangan dari
pemerintah daerah berupa tanah. Nilai wajar tanah dilokasi setempat adalah
75 juta. Hitunglah harga perolehan tanah dan buatlah jurnal yang diperlukan.
Karena nilai wajar tanah sebesar 75 juta rupiah maka harga perolehan tanah
sumbangan tersebut sebesar 75 juta rupiah juga.
Jurnal :
Tanah 75.000.000
Modal dari sumbangan 75.000.000
DEPRESIASI (PENYUSUTAN)
Depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya
selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis (Haryono Jusup,
2005; hal 162).
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset
selama umur manfaatnya.
Depresiasi/ penyusutan bukan merupakan penilaian aktiva tetap tetapi merupakan
proses pengalokasian harga perolehan. Alokasi dilakukan sepanjang umur manfaat
yang dapat berupa periode waktu atau jumlah produksi/unit yang diharapkan akan
diperoleh dari aktiva tetap tersebut.
Akumulasi depresiasi aktiva tetap menggambarkan jumlah depresiasi yang telah
dibebankan sebagai biaya, bukan menggambarkan dana yang telah dihimpun.
Aset tetap perusahaan terdiri dari 2 sifat yaitu:
1. Tanah, yang mempunyai umur atau jangka waktu pemakaian yang tidak terbatas
dalam memberikan jasa
2. Aset tetap lainnya seperti gedung, peralatan, berkurang kemampuannya untuk
memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu.
Ayat jurnal untuk mencatat penyusutan:
Beban Penyusutan (Depreciation Expense) XXX
Akumulasi Penyusutan (Accumulated Depreciation) XXX
a. Akuntansi untuk penyusutan
Terdapat 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusutan :
1. Harga perolehan (cost)
Harga perolehan suatu aktiva meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan
dengan perolehan dan penyiapannya untuk dapat digunakan.
2. Nilai residual atau nilai sisa (residual value / salvage value)
Jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tersebut
tidak digunakan lagi
3. Masa atau umur manfaat aktiva tetap
Aktiva tetap memiliki masa manfaat terbatas. Keterbatasan tersebut karena
berbagai faktor seperti keausan, kecacatan, kemerosotan nilai, kerusakan
(kecuali tanah)
b. Metode penyusutan
Ada 4 metode penyusutan aktiva tetap yang dikenal secra umum yaitu:
1. Metode Garis Lurus (Straight-Line Method)
2. Metode Unit Produksi (Units-of-Production Method) atau satuan hasil
3. Metode saldo menurun (Declining Balance Method)
4. Metode jumlah angka tahun (Sum-of-the-Years-Digits Method)
.
Ayat jurnal untuk mencatat penyusutan tahunan :
Beban Penyusutan Rp 4.200.000
Akumulasi Penyusutan Rp 4.200.000
Catatan :
Tgl 1-15 dianggap awal bulan
Tgl 16-31 dianggap awal bulan berikutnya
Ayat jurnal untuk mencatat penyusutan tahunan :
Beban Penyusutan Rp 4.200.000
Akumulasi Penyusutan Rp 4.200.000
Jika pembelian dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2011, maka beban
penyusutan tahun pertama adalah :
Rp 4.200.000 x 3 = Rp 1.050.000
12
Jika pembelian dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2011, maka beban
penyusutan tahun pertama adalah :
Rp 4.200.000 x 2 = Rp 700.000
12
Tarif Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa
Manfaat Taksiran dalam jumlah jam
= Rp 11.000.000 – Rp 1.000.000
10.000
= Rp 1.000 / jam
Beban Penyusutan =
Tarif Penyusutan x jumlah unit produksi yang sesungguhnya
= Rp 1.000 x 2.200
= Rp 2.200.000
3. Metode saldo menurun (Declining Balance Method)
Menghasilkan beban penyusutan periodik yang semakin menurun sepanjang
umur estimasi aktiva. Dalam metode ini nilai residu (nilai sisa) tidak
diperhitungkan.
Penyusutan yang dibebankan pada tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya
akan semakin menurun
Persentase yang digunakan adalah perkalian atas tingkat garis lurus yang
dikalkulasikan untuk berbagai masa manfaat sebagai berikut:
Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan x Nilai buku awal tahun
Nilai buku tahun pertama = harga perolehan
Nilai buku tahun kedua = Harga perolehan – Saldo akumulasi penyusutan awal
tahun kedua
Estimasi Masa
Manfaat Dalam
Tahun
Tarif Garis
Lurus
Tarif Garis
Lurus 1,5 kali
Tarif Garis
Lurus 2 Kali
4 25 % 37,5 % 50 %
5 20 % 30 % 40 %
10 10 % 15 % 20 %
20 5 % 7,5 % 10 %
Tanggal 2 Januari 2011 dibeli sebuah kendaraan dengan harga Rp 22.000.000.
Nilai sisa taksiran adalah Rp 1.000.000 dan umur ekonomisnya adalah 5 tahun.
Tarif penyusutan = 100% = 20 % x 2 = 40 %
5
Tahun pertama:
Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan x Nilai buku awal tahun
= 40 % x Rp 22.000.000 = Rp 8.800.000
Tahun kedua:
Beban Penyusutan = Tarif Penyusutan x Nilai buku awal tahun
= 40 % x (Rp 22.000.000 – Rp 8.800.000) = Rp 5.280.000
Tahun kelima:
Beban Penyusutan = Nilai buku akhir tahun keempat – Nilai sisa
= Rp 2.851.200 – Rp 1.000.000
= Rp 1.851.200
METODE JUMLAH ANGKA TAHUN
(SUM OF YEARS DIGITS)
Tahun Harga Perolehan Tarif Nilai Buku Awal
Tahun
Beban
Penyusutan
Akumulasi
Penyusutan
Nilai Buku Akhir
Tahun
1 Rp 22.000.000 5/15 Rp 21.000.000 Rp 7.000.000 Rp 7.000.000 Rp 15.000.000
2 Rp 22.000.000 4/15 Rp 21.000.000 Rp 5.600.000 Rp 12.600.000 Rp 9.400.000
3 Rp 22.000.000 3/15 Rp 21.000.000 Rp 4.200.000 Rp 16.800.000 Rp 5.200.000
4
Rp 22.000.000 2/15 Rp 21.000.000 Rp 2.800.000 Rp 19.600.000 Rp 2.400.000
5 Rp 22.000.000 1/15 Rp 21.000.000 Rp 1.400.000 Rp 21.000.000 Rp 1.000.000
Apabila kendaraan dibeli tanggal 2 oktober 2011. Tahun pertama:
Beban Penyusutan =
3 x 5 X (Rp 22.000.000 – Rp 1.000.000) = Rp 1.750.000
12 15
Tahun 2:
Beban penyusutan =
9 x 5 X (Rp 22.000.000 – Rp 1.000.000) = Rp 5.250.000 12 15 3 x 4 X (Rp 22.000.000 – Rp 1.000.000) = Rp 1.400.000 12 15 Rp 6.650.000
PENGELUARAN MODAL DAN
PENGELUARAN PENDAPATAN Pembedaan antara pengeluaran modal (capital expenditure) dan
pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) bagi perusahaan agar
pendapatan-pendapatan dan beban-beban bisa disandingkan (match)
secara wajar.
Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang diperlakukan
sebagai harga perolehan (cost) dari aset tetap (kapitalisasi) karena
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran hanya
memberi manfaat pada periode yang berjalan atau biaya-biaya yang
terjadi untuk mempertahankan efisiensi operasi yang normal.
PENGELUARAN MODAL DAN PENGELUARAN
PENDAPATAN
Ada 3 jenis pengeluaran modal yang berkaitan dengan aktiva tetap setelah
perolehannya :
1. Penambahan terhadap aktiva tetap (Additions)
2. Perbaikan (Betterment)
3. Perbaikan luar biasa (Extraordinary repair)
Kondisi–kondisi yang menentukan bahwa suatu pengeluaran adalah
pengeluaran modal:
1. Meningkatnya efisiensi operasi aset tetap
2. Menambah kapasitas dari aset tetap
3. Memperpanjang umur atau masa manfaat dari aset tetap
PENAMBAHAN TERHADAP AKTIVA TETAP
Pengeluaran yang menambah suatu aset
tetap tertentu, harus didebit ke akun aset
tetap yang bersangkutan, dan ikut
disusutkan selama masa manfaat dari
penambahan tersebut.
Contoh:
Biaya menambah sistem pendingin pada
gedung.
PERBAIKAN (BETTERMENT)
Pengeluaran yang dapat meningkatkan
efisiensi operasi atau menambah
kapasitas suatu aset tetap.
Pengeluaran ini harus didebit ke akun
aset tetap yang bersangkutan
(dikapitalisasi).
Contoh:
Penggantian unit tenaga dari sebuah
mesin dengan yang baru yang
berkapasitas lebih besar.
PERBAIKAN LUAR BIASA (EXTRAORDINARY REPAIR)
Pengeluaran yang menambah atau memperpanjang umur atau
masa manfaat dari suatu aset tetap.
Pengeluaran ini harus didebit ke akun akumulasi penyusutan
Beban penyusutan untuk periode yang akan datang harus
dihitung atas dasar nilai buku yang baru dan masa manfaat yang
ditaksir masih tersisa
CONTOH :
Sebuah mesin dengan harga pokok atau biaya Rp
50.000.000 memiliki umur manfaat 10 tahun dan tanpa
nilai residu. Mesin telah disusutkan selama 6 tahun,
metode garis lurus (penyusutan Rp 5.000.000). awal
tahun ke 7 reparasi besar dilakukan dengan biaya Rp
11.500.000, meningkatkan umur manfaat mesin
menjadi 7 tahun. penyusutan tahun ke 7 sbb :
Biaya Mesin Rp 50.000.000
Dikurangi Saldo Ak. Peny. :
Peny. 6 Tahun Rp 30.000.000
Reparasi Besar Rp 11.500.000
Saldo Ak. Penyusutan Rp 18.500.000
Nilai Buku Mesin Stl Reparasi Rp 31.500.000
Penyusutan Th Ke 7 DST :
Rp 31.500.000 / 7 = Rp 4.500.000
REVALUASI ASET TETAP
Merupakan penilaian kembali aset tetap
Sesuai dengan IFRS (International Financial Reporting Standards)
Apabila perusahaan akan melaksanakan revaluasi, maka hal itu harus diterapkan
pada semua aset yang ada dalam kelompok aset yang bersangkutan.
Aset-aset yg berdasarkan pengalaman terbukti mengalami perubahan harga yang
cepat harus direvaluasi secara tahunan, akan tetap untuk aset-aset yg tidak
demikian bisa dilakukan lebih jarang.
Contoh :
Pada akhir tahun I, Perusahaan jasa penilai independen (appraisers) menetapkan
bahwa nilai wajar untuk aset tersebut adalah Rp85.000.000. Untuk melaporkan
aset sebesar nilai wajarnya, maka PT Permata harus mengeliminasi akun
akumulasi depresiasi aset tetap, menurunkan aset tetap menjadi sebesar nilai
wajarnya, dan mencatat surplus revaluasi Rp5.000.000 dengan jurnal sbb :
Akum Depresiasi Aset Tetap 20.000.000
Aset tetap 15.000.000
Surplus Revaluasi 5.000.000
PENGHENTIAN ASET TETAP
Saat aset tetap kehilangan manfaatnya dapat dihentikan dengan cara berikut:
1. dibuang / dihapus,
2. dijual, atau
3. ditukar untuk aset yang serupa atau lainnya.
Jurnal yang dibutuhkan bervariasi sesuai tipe penghentian dan keadaannya, tetapi ayat berikut selalu dibutuhkan:
Akun aset harus dikredit untuk mengeluarkan aset dari buku besar, dan
akumulasi depresiasi terkait harus didebit untuk mengeluarkan saldonya dari buku besar.
PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP
Dalam kasus pelepasan aset tetap, nilai buku aset tetap harus dihapus.
Ketika aset sudah tidak memiliki umur ekonomis yang lebih lama dan tidak memiliki nilai
residu atau harga pasar, maka aset bersangkutan biasanya akan dibuang.
Ada 2 kondisi sebagai contoh penghapusan :
1. Menghapus peralatan yang telah disusutkan secara penuh
2. Menghapus peralatan yang baru disusutkan sebagian
Contoh :
Menghapus peralatan yang telah disusutkan secara penuh
Pada tanggal 5 Maret 2010 perusahaan menghapuskan suatu peralatan, harga
perolehan sebesar Rp 10.000.000 telah disusutkan secara penuh dan tidak ada nilai
sisa. Ayat jurnalnya:
Menghapus peralatan yang baru disusutkan sebagian
Pada tanggal 5 Maret 2010 perusahaan menghapuskan suatu peralatan dengan harga
perolehan Rp 10.000.000. Saldo akun akumulasi penyusutan pada tanggal 5 Maret 2010
adalah Rp 8.200.000. Ayat jurnalnya:
Akum. Penyusutan Peralatan Rp 10.000.000
Peralatan Rp 10.000.0000
Akum. Penyusutan Peralatan Rp 8.200.000
Kerugian atas penghapusan akt tetap Rp 1.800.000
Peralatan Rp 10.000.000
PENJUALAN AKTIVA TETAP
Apabila suatu aset tetap dijual, perusahaan mungkin pulang pokok, menderita
rugi, atau memperoleh keuntungan.
Jika harga jual = nilai buku maka perusahaan pulang pokok.
Jika harga jual < nilai buku maka perusahaan menderita kerugian sebesar
selisihnya.
Jika harga jual > nilai buku maka perusahaan memperoleh keuntungan
sebesar selisihnya
Untung dan rugi akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan
atau kerugian lainnya.
Contoh :
Peralatan yang dimiliki perusahaan dengan harga perolehan sebesar Rp
12.000.000, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif
20%, dan tidak ada nilai sisa. Peralatan tersebut dijual tunai pada tanggal 8
Nopember 2010, yakni pada tahun ketiga pemakaiannya. Saldo akumulasi
penyusutan pada tanggal 31 Desember tahun kedua adalah sebesar Rp
4.800.000.
Ayat jurnalnya :
8 Nopember 2010
Saldo akun akumulasi penyusutan : Rp 4.800.000 (Tahun kedua)
Akumulasi penyusutan : Rp 2.000.000 (Tahun ketiga)
Saldo akun akumulasi penyusutan Rp 6.800.000 (Tahun ketiga)
Nilai buku tahun ketiga : Rp 12.000.000 – Rp 6.800.000 = Rp 5.200.000
Jika Harga jual = Harga buku, harga jualnya sebesar Rp 5.200.000.
maka ayat jurnalnya:
8 Nopember 2010
Kas Rp 5.200.000
Akumulasi Penyusutan-Peralatan Rp 6.800.000
Peralatan Rp 12.000.000
Beban Penyusutan Peralatan Rp 2.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp 2.000.000
(Rp 12.000.000 x 20% x 10/12)
Jika Harga jual < Harga buku, harganya jualnya sebesar Rp 4.000.000 maka
ayat jurnalnya:
8 Nopember 2010
Kas Rp 4.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp 6.800.000
Kerugian atas Penjualan Peralatan Rp 1.200.000
Peralatan Rp 12.000.000
Jika Harga jual > Harga buku, harganya jualnya sebesar Rp 6.000.000
maka ayat jurnalnya:
8 Nopember 2010
Kas Rp 6.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp 6.800.000
Peralatan Rp 12.000.000
Keuntungan atas penjualan aktiva tetap Rp 800.000
PENUKARAN AKTIVA TETAP (Trade-In)
Dilakukan dengan aktiva tetap yang sejenis atau dapat ditukar dengan aktiva
tetap yang tidak sejenis.
Contoh : Kendaraan => Kendaraan (sejenis)
Kendaraan => Komputer (tidak sejenis)
Harus ditentukan nilai tukarnya (trade-in allowance), yang jumlahnya mungkin
lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku.
Selisih antara nilai tukar aktiva yang lama dengan harga aktiva yang baru
merupakan jumlah yang harus dibayar atau yang terutang.
Keuntungan (gain) diperoleh dalam pertukaran aktiva tetap apabila nilai tukar
melebihi nilai buku.
Keuntungan atau kerugian atas pertukaran aktiva tetap dicatat dalam
pembukuan perusahaan dan dalam penyajian laporan keuangan, karena
kebanyakan pertukaran mempunyai substansi komersial.
jika tidak melibatkan adanya pembayaran atau penerimaan kas, maka
keuntungan tidak diakui
jika ada kas yang dibayarkan, maka seluruh keuntungan tidak diakui
jika ada kas yang diterima, maka sebagian keuntungan diakui sbb :
A/B X total keuntungan= Keuntungan yang diakui
A = kas diterima
B = kas diterima + nilai wajar aset lain yg diterima
Contoh :
Peralatan A dengan harga perolehan Rp 10.000.000, tanpa nilai sisa, dan saldo
akumulasi penyusutan per 31 desember 2010 adalah Rp 6.000.000. Pada
tanggal 1 Juli 2011 setelah tahun keempat pemakaiannya ditukar dengan
peralatan B yang sejenis seharga Rp 12.000.000. Peralatan A disusutkan
dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun. Nilai tukar peralatan
A adalah Rp 4.000.000. Penghitungan jumlah yang harus dibayar, nilai buku, dan
keuntungan atas penukaran aktiva tetap ?
Perhitungan :
Harga perolehan peralatan B (baru) Rp 12.000.000
Nilai tukar peralatan A (lama) Rp 4.000.000
Jumlah yang harus dibayar Rp 8.000.000
Harga perolehan peralatan A Rp 10.000.000
Akum. Peny. s/d 31 Desember 2010 Rp 6.000.000
Tahun 2011 Rp 1.000.000 Rp 7.000.000
Nilai buku pada saat pertukaran Rp 3.000.000
Nilai tukar Peralatan A Rp 4.000.000
Nilai tukar Peralatan B Rp 3.000.000
Keuntungan atas pertukaran Rp 1.000.000
Ayat jurnal 11 Juli 2011:
Akum. Penyusutan Peralatan Rp 7.000.000
Peralatan B Rp 12.000.000
Kerugian atas pertukaran aktiva Tetap Rp 500.000
Peralatan A Rp 10.000.000
Kas Rp 9.500.000
Jika terjadi kerugian pertukaran, dimana Nilai tukar peralatan A adalah Rp
2.500.000. maka jumlah yang dibayarkan:
Harga perolehan peralatan B (baru) Rp 12.000.000
Nilai tukar peralatan A (lama) Rp 2.500.000
Jumlah yang harus dibayar Rp 9.500.000
Maka kerugian atas penukaran adalah:
Nilai tukar Peralatan A Rp 2.500.000
Nilai tukar Peralatan B Rp 3.000.000
Kerugian atas pertukaran Rp 500.000
Ayat jurnal:
11 Juli 2011
Akum. Penyusutan Peralatan Rp 7.000.000
Peralatan B Rp 12.000.000
Peralatan A Rp 10.000.000
Kas Rp 8.000.000
Keuntungan atas pertukaran aktiva tetap Rp 1.000.000
DEPLESI
Alokasi periodik atas biaya atau harga perolehan dari sumber daya alam (natural
resources) seperti biji logam, minyak, gas, kayu, dan bahan tambang lainnya ke akun
beban.
Saldo akun akumulasi deplesi disajikan dalam neraca sebagai pengurangan atas
harga perolehan dari hak bahan tambang yang bersangkutan.
Ayat jurnalnya :
Beban deplesi XXXX
Akumulasi deplesi XXXX
Contih :
Perusahaan memperoleh dan membayar hak tambang sebesar Rp 6.000.000.000.
Simpanan bahan tambang diperkirakan sebanyak 10.000.000 ton. Selama tahun ini
ditambang sebanyak 200.000 ton.
Tarif penyusutan = Rp 6.000.000.000 = Rp 600 per ton
10.000.000
Beban deplesi = Rp 600 x 200.000 = Rp 120.000.000
Ayat jurnalnya:
Beban deplesi Rp 120.000.000
Akumulasi deplesi Rp 120.000.000
AMORTISASI
Suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara
bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi.
Perbedaan:
Aktiva Tetap : Penyusutan
Aktiva Tidak Berwujud : Amortisasi
Ayat jurnalnya:
Beban Amortisasi XXXX
Aktiva tidak berwujud XXXX
Aktiva Tidak Berwujud adalah aktiva jangka panjang yang secara fisik tidak
bisa dinyatakan dan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi digunakan dalam
kegiatan perusahaan.
Alokasi periodik atas biaya atau harga perolehan dari aktiva tidak berwujud :
amortisasi
Unsur-unsur dari aktiva tidak berwujud adalah :
1. Paten : Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan/seseorang
atas penemuan baru
2. Hak Cipta (copy right) : Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada
perusahaan/seseorang atas karya-karya tulisan dan seni yang dihasilkan
3. Goodwill : Aktiva tidak berwujud yang timbul dari faktor-faktor seperti lokasi,
kualitas produksi, reputasi dan keahlian manajemen
4. Hak merek : Sebuah kata, ungkapan atau simbol yang mengidentifikasi
sebuah perusahaan atau produk tertentu
5. Biaya riset dan pengembangan : Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan
perusahaan dalam kaitan memperoleh hak paten, hak cipta, formula, dan
produk baru.
6. Wara laba (franchises) : Perjanjian kontraktual, dimana pemilik waralaba
memberikan hak kepada pemegang waralaba untuk menjual produk atau
jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang
tertentu, atau melakukan fungsi-fungsi tertentu.
Contoh :
Perusahaan membeli hak paten sebesar Rp 100.000.000. Masa manfaat adalah
17 tahun dan telah dikeluarkan 7 tahun yang lalu sebelum tanggal pembelian.
Masa manfaat yang tersisa adalah 10 tahun (17 tahun – 7 tahun), maka:
Amortisasi per tahun = Rp 100.000.000 = Rp 10.000.000
10 tahun
Ayat jurnalnya:
31 Des Beban Amortisasi Rp 10.000.000
Paten Rp 10.000.000
Kewajiban : Merupakan hutang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi
pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa, di
waktu yang akan datang.
Ciri-ciri yang melekat pada Kewajiban :
Kewajiban sudah ada saat sekarang
Akan terjadi arus keluar di masa mendatang
Transaksi atau kejadian yang menimbulkan kewajiban tersebut telah terjadi di
masa lalu (akibat dari peristiwa masa lalu).
KLASIFIKASI UTANG :
Dasar untuk mengklasifikan utang:
a. Siklus operasi normal (untuk usaha dagang)
b. Waktu satu tahun (bukan utang dagang)
c. Jenis klasifikasi aktiva yang digunakan untuk melunasi (untuk utang usaha
dan utang bukan usaha)
KEWAJIBAN KEWAJIBAN
JANGKA PANJANG
KEWAJIBAN
LANCAR
1. UTANG YANG JUMLAHNYA PASTI
A. Utang Dagang
Timbul karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa secara
kredit. Pencatatan utang usaha umumnya dicatat setelah barang diterima.
Ada dua metode pencatatan, metode bruto dan metode neto.
Jika metode neto dipakai, maka jika potongan tidak dimanfaatkan diakui
sebagai kerugian karena tidak memanfaatkan potongan. Perusahaan yang
selalu membayar dalam periode potongan dianjurkan untuk menggunakan
metode neto.
B. Utang Wesel Bank
Utang yang timbul karena pembelian barang dagangan atau bukan yang
disertai perjanjian secara tertulis. Utang wesel bisa bertentuk jangka pendek,
maupun jangka panjang. Utang wesel bisa berbunga maupun tidak berbunga.
C. Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo Tahun Berjalan
Sebagian utang jk pnjg yang akan jatuh tempo, dicantumkan sebagai utang jk
pendek jika akan dilunasi dengan aktiva lancar.
D. Utang PPh Karyawan
Utang PPh karyawan timbul karena kewajiban perusahaan untuk memotong
pajak kepada karyawan. Pemotongan dilakukan pada waktu pembayaran gaji.
Sedangkan pembayaran ke kas negara beberapa waktu kemudian.
E. Utang Gaji dan Upah
F. Utang PPh Badan
G. Utang PPN Keluaran
H. Penghasilan Diterima Dimuka
Penghasilan diterima dimuka termasuk dalam kategori utang yang jumlahnya
dapat ditentukan dengan pasti.
2. UTANG YANG STATUSNYA PASTI TETAPI JUMLAHNYA DITAKSIR
A. Utang Tunjangan dan Bonus Karyawan
Menurut SAK tunjangan dan bonus harus diakui jika memenuhi syarat:
1. Tunjangan dan bonus telah dihimpun melalui jasa yang telah siap
diserahkan
2. dapat dibebankan pada tahun berikutnya
3. dapat ditaksir jumlahnya dan cukup pasti.
B. Utang Garansi Purna Jual-Gratis
Garansi purna-jual secara gratis menimbulkan kemungkinan yang cukup pasti
bahwa perusahaan akan mengeluarkan kas atau aktiva lain di masa
mendatang. Jadi harus diakui sebagai utang, dan jumlahnya harus ditaksir
karena belum pasti.
Contoh 1: PD Baik menjual kulkas merk "DEK'E" . Perush memberi jaminan layanan-purna jual gratis selama 2
tahun. Pengalaman tahun sebelumnya, kulkas harus diservis pada tahun 1, 20%, dan tahun ke 2 ,10%.
Biaya reparasi per unit rata-rata Rp35.000,00. Tahun 1 dan 2 dapat menjual TV sebanyak 100 dan 120
unit dengan harga jual Rp410.000 per unit. Biaya reparasi yang telah dikeluarkan selama tahun 1
setelah penjualan adalah Rp625.000 (kas Rp400.000 dan suku cadang Rp225.000). Biaya tahun
kedua setelah penjualan sebesar Rp1.080.000 (kas Rp400.000, dan suku cadang Rp680.000).
Tahun I
Jurnal penjualan:
Kas Rp41.000.000
Penjualan Rp41.000.000
Jurnal pengakuan utang garansi:
Biaya garansi Purna Jual Rp1.050.000
Taksiran utang garansi purna jual Rp1.050.000
Tahun II
Taksiran utang garansi PJ Rp625.000
Kas Rp.425.000
Persed. Suku Cadang Rp200.000
Kas Rp49.200.000
Penjualan Rp49.200.000
Biaya garansi purna jual Rp1.260.000
Taksiran utang garansi PJ Rp1.260.000
Taksiran utang garansi PJ Rp1.080.000
Kas Rp400.000
Persed. Suku Cadang Rp680.000
C. Garansi Purna Jual-Tidak Gratis
Jika fee dipungut dimuka, perusahaan harus mencatat ke dalam rekening
"Pendapatan garansi belum direalisasi".
Contoh 2:
Penjualan selama 2001 Rp5 juta, dan untuk biaya garansi purna jual diterima
dimuka Rp500 ribu. Selama setahun dikeluarkan biaya berupa kas Rp50 ribu
dan suku cadang senilai Rp100.000, pend. direalisasi 40%.
Kas 5.600.000
Penjualan 5.000.000
Pend. garansi belum direalisasi 600.000
Pendap garansibelum direalisasi 240.000
Pendapatan garansi purna jual 240.000
Biaya garansi purna jual 150.000
Kas 50.000
Persediaan suku cadang 100.000
D. Utang Hadiah
Diberikan kepada pembeli, dengan cara menukarkan label, kemasan,
kotak atau bukti khusus lainnya yang disyaratkan.
Contoh 3:
Perush Kopi Bubuk menawarkan memberikan sebuah piring jika pembeli
menukarkan 20 lembar bungkus. Untuk persiapan hadiah, perusahan membeli
10.000 buah piring dengan harga Rp2000 per buah. Diperkirakan 40% diantara
bungkus diterima oleh perusahaan. Produk terjual selama tahun 2002 400.000
bungkus dengan harga Rp12.000 per bungkus. Pada akhir tahun perush. telah
menerima 30% dari total bungkus yang terjual.
Piring untuk hadiah 20.000.000
Kas 20.000.000
Kas 480.000.000
Penjualan 480.000.000
Biaya hadiah 12.000.000
Piring untuk Hadiah 12.000.000
(30% x 400.000/20 x Rp2.000 = Rp12.000.000)
Piring yang akan ditebus tahun 2003:
Estimasi yang akan dilunasi (40%) 160.000 buah
Terlunasi selama tahun 2002 120.000 buah
-----------------
Estimasi yang dilunasi masa mendatang 40.000 unit
==========
Estimasi klaim 40.000 / 20 bungkus x Rp2.000Rp4.000.000
Jurnal, 31-12-2002:
Biaya hadiah Rp4.000.000
Utang Hadiah Rp4.000.000
3. UTANG BERSYARAT (CONTINGENT LIABILITY)
A. Piutang Wesel Didiskontokan
Piutang wesel didiskontokan sebelum jatuh tempo merupakan utang bersyarat yang
jumlahnya sudah dapat ditentukan secara pasti.
B.Tambahan Utang PPh Badan
Jika pajak yang dilaporkan melalui SPT ada kemungkinan ditambah.
C. Utang yang Menunggu Vonis Pengadilan
Utang ini timbul jika terdapat tuntutan dari pihak lain dalam perkaran sepertii hak
patent, hak cipta, pelanggaran kontrak, dll.
Definisi Kewajiban Lancar :
Pengorbanan manfaat ekonomis dimasa mendatang yang cukup pasti, yang
timbul dari kewajiban sekarang suatu entitas tertentu untuk menyerahkan
aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai
akibat dari transaksi atau kejadian masa lampau.
Kewajiban lancar adalah kewajiban yang biasanya dibayar dengan menggunakan
aset lancar dan memiliki jatuh tempo yang pendek, biasanya kurang dari satu
tahun
Kewajiban Lancar atau Hutang Lancar (Hutang Jangka Pendek) Yaitu
kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset/aktiva
lancar atau bisa juga dengan menciptakan kewajiban lancar lainnya dan
harus segera dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun
Utang yang diharapkan akan dibayar :
1. Dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal
perusahaan
2. (tergantung mana yang lebih panjang)
3. Dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan
kewajiban lancar yang lain.
JENIS-JENIS KEWAJIBAN LANCAR :
1. Utang Dagang
2. Utang Wesel
3. Utang Pajak (pajak penghasilan karyawan)
4. Pendapatan Diterima Dimuka
5. Bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun ini
6. Utang bunga
7. Utang upah
8. Utang Dividen
9. Utang garansi
10. Kewajiban Kontinjen jangka pendek
11. Jaminan Yang Dapat Dikembalikan
PENYAJIAN UTANG LANCAR DI NERACA
Disajikan di Neraca dengan aturan sebagai berikut:
1. Utang lancar mendahului utang jangka panjang
2. Disajikan berdasarkan jumlah relatifnya.
3. Khusus utang wesel
.
Penyajian di Neraca:
Utang Lancar:
Utang Wesel ................................. Rp 44.500.000
Utang dagang .............................. 35.250.000
Utang Jk Pj Jatuh Tempo .............. 10.000.000
Utang gaji & Upah.......................... 7.500.000
Utang PPh...................................... 6.000.000
Utang PBB...................................... 4.500.000
Uang Dividen ................................. 4.000.000
Pendapatan diterima dimuka........ 1.000.000
Utang Garansi Purna Jual ............ 750.000
--------------------
JUMLAH UTANG LANCAR (Catatan 1) Rp113.500.000
============
UTANG DAGANG
Adalah Kewajiban kepada pihak lain yang timbul akibat pembelian barang dan
jasa dan dari pinjaman jangka pendek dan biasanya tidak memerlukan suatu
perjanjian khusus.
Utang Usaha (Account Payable) timbul pada saat barang atau jasa diterima
sebelum melakukan pembayaran.
Dalam transaksi perusahaan dagang, seringkali perusahaan membeli barang
dagangan secara kredit dari pemasok (supplier) untuk dijual kembali kepada
konsumen / pelanggan
Jurnal Transaksi pembelian secara kredit
Sistem Persediaan Periodik
Sistem Persediaan Perpetual
Jurnal Pelunasan Hutang Usaha
Contoh : Tanggal 1 Desember 2005 dibeli barang dagangan dengan faktur Rp
500.000 syarat pembayaran 2/10, n/30.
a. Jurnal Pembelian dicatat dengan harga bruto
Tgl 1 Desember 2005
Pembelian Rp 500.000
Utang Dagang Rp 500.000
(Sistem Periodik)
Jurnal Pembelian dicatat dengan harga bruto
Tgl 1 Desember 2005
Persediaan Barang Dagang Rp 500.000
Utang Dagang Rp 500.000
(Sistem Perpetual)
Apabila pembayaran sebelum tanggal 10
Tanggal 8 Desember 2005
Utang Dagang Rp 500.000
Potongan Pembelian Rp 10.000
Kas Rp 490.000
(Mencatat saat pelunasan utang dagang dan masih kurang dari 10 hari)
Apabila pembayaran sesudah tanggal 10
Tanggal 15 Desember 2005
Utang Dagang Rp 500.000
Kas Rp 500.000
(Mencatat saat pelunasan utang dagang dan sesudah lebih dari 10 hari)
b. Pembelian dicatat dengan harga neto
Dalam cara ini ada 2 cara mencatat utang yaitu dengan jumlah neto atau
dengan jumlah bruto
Utang dicatat neto Utang dicatat bruto
1 desember 2005
Pembelian (persediaan brng) 490.000
utang 490.000
Pembelian (pers barang) 490.000
Cad pot pembelian 10.000
utang 500.000
10 desember 2005
Utang 490.000
kas 490.000
Utang 500.000
cad pot pembelian 10.000
kas 490.000
Jika pembayaran sesudah tgl 10
Utang 490.000
Pot pembelian yg hilang 10.000
kas 500.000
Utang 500.000
kas 500.000
Pot pembelian yg hilang 10.000
cad pot pembelian 10.000
UTANG WESEL / WESEL BAYAR
Kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka
pendek, dimana utang ini dibuat dalam perjanjian khusus, sebagaimana
diatur peraturan hukum yang berlaku.
Merupakan janji tertulis dicatat sebagai utang wesel
Wesel bayar memerlukan pembayaran bunga dan seringkali diterbitkan untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan (pendanaan) jangka pendek
Wesel diterbitkan oleh debitur ketika sejumlah uang dipinjam dari bank atau
kreditur
Wesel juga dapat diterbitkan untuk menggantikan sementara utang usaha
yang telah jatuh tempo
2 jenis wesel bayar :
1. Wesel Bayar Berbunga (Interest Bearing Notes)
2. Wesel Bayar yang Di-Diskontokan (Discounted Notes)
1. Wesel Bayar Berbunga
Beban bunga akan diakui atau dicatat pada akhir periode akuntansi dan
atau pada saat wesel jatuh tempo
Beban bunga yang dicatat pada akhir periode akuntansi merupakan beban
bunga berjalan (accrued interest) atau bunga yang masih harus dibayar,
terhitung mulai pada saat wesel diterbitkan sampai dengan tanggal tutup
buku perusahaan
Contoh; Wesel berumur 6 bulan yang diterbitkan 1 September 2015 akan
jatuh tempo akhir Pebruari 2016. Beban bunga dari 1 Sept sd 31 Desember
2015 harus diakui dan dicatat saat utup buku perusahaan
Jika tanggal jatuh tempo dan tanggal penerbitan wesel berada dalam satu
periode akuntansi yang sama, maka akun bunga akan diakui sekaligus,
yaitu pada saat wesel tersebut jatuh tempo, sebbesar umur wesel.
Contoh; Wesel berumur 4 bulan yang diterbitkan 1 April 2015 akan jatuh
tempo akhir Juli 2015. Beban bunga sekaligus dicata dalam periode
akuntansi yang sama
Ilustrasi 1 Akuntansi Wesel Bayar Jangka Pendek
Tanggal 1 September 2010, perusahaan meminjam uang ke Bank dengan
menerbitkan wesel bayar sebesar Rp 100.000.000, dengan tingkat bunga 12%
per tahun. Wesel bayar akan jatuh tempo dalam jangka waktu 6 bulan sejak
tanggal penerbitan. Periode akuntansi perusahaan akan berakhir setiap tgl 31
Desember
Diminta: Catatlah transaksi-transaksi yang diperlukan
Ilustrasi 2 Akuntansi Wesel Bayar Jangka Pendek
1 Maret, membeli barang dagangan senilai Rp 30.000.000 dengan syarat
kredit 1/10, n/30. Sistem pencatatan persediaan metode periodik
31 Maret, Untuk menggantikan sementara utang usaha yang telah jatuh tempo
diterbitkan wesel bayar dengan nilai nominal Rp 30.000.000. Wesel ini
berjangka 45 hari dengn tingkat bunga 10% per tahun (asumsi 1 tahun = 360
hari)
15 Mei Perusahaan melunasi utang wesel yang telah jatuh tempo
Catatlah transaksi-transaksi tersebut
Tanggal Nama Perkiraan Debet Kredit
1 Sept 2010 Kas 100.000.000
Hutang Wesel 100.000.000
(Penerbitan Wesel)
31 Des 2010 Beban Bunga 4.000.000
Hutang Bunga 4.000.000
(Bunga berjalan = 4 bulan x 12%/12 bulan x 100
juta)
1 Jan 2011 Hutang Bunga 4.000.000
Beban Bunga 4.000.000
(Jurnal Pembalik)
28 Peb 2011 Hutang Wesel 100.000.000
Beban Bunga 6.000.000
Kas 6.000.000
(Pembayaran Utang Wesel = 6 bulan x 12%/12
bulan x 100 juta)
JAWABAN ILUSTRASI 1
Tanggal Nama Perkiraan Debet Kredit
1 Maret Pembelian 30.000.000
Hutang Usaha 30.000.000
(Pembelian kredit)
31 Maret Utang Usaha 30.000.000
Utang Wesel 30.000.000
(Wesel menggantikan utang usaha)
15 Mei Utang Wesel 30.000.000
Beban Bunga * 375.000
Kas 30.375.000
*(45 hari/360 hari x 10% x 30 juta)
JAWABAN ILUSTRASI 2
2. Wesel Bayar yang Di-Diskontokan
Wesel bayar yang di-diskontokan tidak menyebutkan secara spesifik
besarnya tingkat suku bunga, tetapi kreditur sesungguhnya telah
menetapkan suku bunga
Bunga yang ditetapkan kreditur akan secara otomatis mengurangi nilai
nominal wesel yang diterbitkan debitur
Bunga yang mengurangi nilai nominal wesel dinamakan diskonto
Ilustrasi Akuntansi Wesel Bayar yang Di-diskontokan :
Tanggal 1 September 2010 perusahaan meminjam uang sebesar Rp
100.000.000,- dari bank. Untuk itu perusahaan menerbitkan wesel bayar
dengan tingkat diskonto 12% per tahun. Wesel ini akan jatuh tempo dalam
jangka waktu 6 bulan sejak penerbitan. Periode akuntansi perusahaan akan
berakhir setiap tgl 31 Desember.
Catatlah ayat jurnal yang diperlukan
Tanggal Nama Perkiraan Debet Kredit
1 Sept
2010
Kas 94.000.000
Beban Bunga 6.000.000
Utang Wesel 100.000.0
00
(Penerbitan wesel bayar)
28 Peb
2011
Utang Wesel 100.000.00
0
Kas 100.000.0
00
(Pembayaran Utang Wesel)
JAWABAN ILUSTRASI
UTANG PAJAK
Adalah Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga yang timbul karena perusahaan
memungut kas dari pihak tertentu (misalnya pegawai atau pelanggan) atas nama
pihak ketiga.
Beberapa kewajiban pajak : utang PPN, utang PPH Badan, dan utang PPH karyawan.
Contoh 1 : Tanggal 20 Nopember 2014 PT ABC menjual barang seharga Rp
10.000.000. Atas penjualan tersebut belum termasuk PPN, PT ABC memungut PPN
sebesar 10%. Buatlah jurnal atas transaksi penjualan tersebut ?
Tgl 20 Nopember 2014
Kas Rp 11.000.000
Penjualan Rp 10.000.000
PPN Keluaran Rp 1.000.000
(Mencatat Penjualan Barang Kena Pajak )
Contoh 2 : Tanggal 10 Nopember 2014 PT ABC membeli tunai barang kena pajak
dengan harga beli Rp 9.000.000. belum termasuk PPN Masukan. Tarif PPN adalah
10 % dari harga beli. Buatlah jurnal atas transaksi pembelian tersebut ?
Tgl 10 Nopember 2014
Pembelian Rp 9.000.000
PPN Masukan Rp 900.000
Kas Rp 9.900.000
(Mencatat Pembelian Barang Kena Pajak)
Jurnal untuk mencatat utang PPN:
Tgl 30 Nopember 2014
PPN Keluaran Rp 1.000.000
PPN Masukan Rp 900.000
Utang PPN Rp 100.000
Jurnal untuk mencatat pembayaran utang PPN:
Utang PPN Rp 100.000
Kas Rp 100.000
Pada akhir tahun 2014 PT ABC melaporkan laba sebelum PPH Rp 500.000.
Laba kena pajak menurut perhitungan sesuai aturan perpajakan adalah Rp
540.000. Jika tarif PPH adalah 15 % maka pajaknya adalah Rp 81.000.
Buatlah jurnal untuk mencatat taksiran utang pajak penghasilan dan
mencatat penyetoran PPH ke kas negara ?
Jurnal untuk mencatat taksiran utang pajak penghasilan:
Beban PPH Rp 81.000
Utang PPH Rp 81.000
Jurnal untuk mencatat penyetoran PPH ke Kas Negara :
Utang PPH Rp 81.000
Kas Rp 81.000
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Kewajiban yang timbul karena diterimanya kas dari pelanggan untuk pesanan
barang/jasa yang akan diserahkan dalam periode yang akan datang.
Majalah “Waktu” menerima uang muka untuk berlangganan majalah selama 3
tahun sebesar Rp 360.000. Jurnalnya:
Kas Rp 360.000
Pendapatan diterima dimuka Rp 360.000
Pendapatan diterima dimuka Rp 120.000
Pendapatan Rp 120.000
(mencatat pengakuan pendapatan untuk setiap periode)
UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN INI
Bagian dari utang jangka panjang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari
satu tahun. Seperti pinjaman bank, kewajiban sewa guna usaha, dan penghasilan
ditangguhkan.
UTANG DIVIDEN
Kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba
berupa kas.
Contoh : Tanggal 15 Januari 2008 para pemegang saham memutuskan untuk
membagi sebagian keuntungan perusahaan pada tahun 2007 sebesar Rp 17.500.000.
Tanggal 25 Januari 2008 dividen tersebut benar-benar dibagikan. Buatlah jurnal pada
waktu dividen diumumkan dan dibagikan ?
15 Januari 2008
Saldo laba Rp 17.500.000
Utang dividen Rp 17.500.000
(Mencatat saat diumumkan)
25 Januari 2008
Utang dividen Rp 17.500.000
Kas Rp 17.500.000
(Mencatat saat dibagikan)
UTANG GARANSI
Utang garansi timbul karena perusahaan, misalnya menjamin reparasi gratis atas
produk yang dijualnya.
Pada tahun 2014 Sweet house company menjual 1.000 unit mainan anak-anak dengan
harga rerata per unit Rp 3.000. Harga jual ini meliputi garansi satu tahun untuk suku
cadang. Ditaksir bahwa 50 unit (5 %) akan rusak dan biaya reparasi berjumlah Rp 300
per unit. Di tahun penjualan 2014, perusahaan telah menerima tuntutan 30 unit mainan
tersebut yang rusak dan mereparasinya dengan biaya sebesar Rp 8.400. Buatlah jurnal
untuk mencatat penjualan dan mencatat beban garansi ?
Penjualan:
1.000 unit x Rp 3.000 = Rp 3.000.000
Perhitungan:
Penjualan 1.000 unit
Persentase taksiran yang rusak 5 % x
Jumlah taksiran yang rusak 50 unit
Jumlah unit rusak yang sudah direparasi 30 unit –
Jumlah unit rusak yang ditaksir akan direparasi 20 unit
Jumlah biaya reparasi taksiran per unit Rp 300 x
Utang garansi taksiran Rp 6.000
Kas Rp 3.000.000
Penjualan Rp 3.000.000
(mencatat penjualan 1.000 unit mainan anak-anak)
Beban Garansi Rp 8.400
Suku Cadang/ Utang gaji dan upah Rp 8.400
(mencatat beban garansi)
Beban Garansi Rp 6.000
Utang Garansi Rp 6.000
(penyesuaian untuk mencatat taksiran utang garansi)
KEWAJIBAN KONTINJEN JANGKA PENDEK
Kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui
karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi yaitu: a). Kemungkinan
terjadi bahwa perusahaan akan diwajibkan untuk mentransfer manfaat ekonomik
pada saat penyelesaian, b). Jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal.
Pengungkapan kewajiban kontinjen jangka pendek dalam bentuk catatan
kaki.
Suatu transaksi yang terjadi di masa lampau akan menimbulkan kewajiban
jika kejadian tertentu terjadi di masa mendatang.
Kewajiban potensial ini disebut kewajiban kontinjensi (Contingent Liabilities),
dimana kewajiban belum terjadi pada tanggal neraca.
Kewajiban ini baru akan terjadi secara actual (nyata) tergantung pada adanya
kejadian di masa mendatang.
Contoh: Garansi produk, Kewajiban bagi perusahaan yang mungkin timbul
dari gugatan oleh pihak lain dalam perkara pelanggaran hak cipta.
Jika kewajiban kontinjensi sangat mungkin terjadi (Probable) dan dapat
diestimasi secara layak, maka kewajiban tersebut harus dicatat dalam akun
kewajiban dan disajikan dalam laporan keuangan.
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Wesel (termasuk bunga berjalan Rp 8.000) Rp 308.000
Utang gaji dan upah Rp 78.000
Utang Usaha Rp 120.000
Utang PPh Karyawan Rp 43.000
Utang PPN Rp 21.000
Utang PPh Badan Rp 69.000
Utang jangka panjang jatuh tempo tahun ini Rp 19.000
Utang garansi Rp 600
Jumlah Kewajiban Lancar Rp 658.600 *
*) PERUSAHAAN PADA SAAT INI SEDANG DALAM SENGKETA DENGAN PT XYZ MENGENAI HAK
CIPTA. MENURUT PENGACARA PERUSAHAAN, DIPERKIRAKAN PERUSAHAAN AKAN DINYATAKAN
KALAH OLEH PENGADILAN DAN DIWAJIBKAN UNTUK MEMBAYAR DENDA DAN BIAYA PERADILAN.
OLEH KARENA ITU, JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR DIATAS BELUM MEMASUKKAN KEWAJIBAN
YANG MUNGKIN TIMBUL DARI KEPUTUSAN PENGADILAN INI.
PENYAJIAN DI NERACA
Ilustrasi Kewajiban Kontinjensi :
Misalkan sepanjang bulan Agustus 2013, PT. NetComp telah melakukan
penjualan produk computer desktop senilai Rp 120.000.000,-. Perusahaan
memberikan jaminan atau garansi produk selama 1 (satu) tahun penuh
kepada pembeli atas kemungkinan terjadinya kerusakan produk yang bukan
diakibatkan kesalahan pembeli.
Berdasarkan pengalaman, besarnya rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk
memperbaiki kerusakan produk selama masa garansi adalah 6% dari nilai
jual.
Maka Ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mencatat (mengakui)
estimasi beban garansi di bulan Agustus 2013 adalah:
Menyambung ilustrasi diatas. Misalkan, Tanggal 9 September 2013, seorang
pembeli mengajukan klaim kepada perusahaan atas spare part (suku cadang)
yang rusak sebesar Rp 550.000,-.
Maka ayat jurnalnya:
.
GAJI & PAJAK PENGHASILAN
Gaji (Payroll):
Jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah
disediakan pada periode tertentu.
Gaji (Salary):
Pembayaran untuk tenaga kerja bagian manajerial, administrasi, atau jasa
kantoran sejenis. Besaran gaji biasanya dinyatakan dalam satu bulan atau
satu tahun.
Upah (wage) :
Merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan
kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayaran tenaga
kerja buruh pabrik, baik yang memiliki keahlian ataupun tidak. Besaran upah
biasanya dinyatakan dalam basis per jam atau per minggu.
Gaji dan upah dianggap penting karena:
1.Untuk mempertahankan semangat kerja karyawan yang baik harus diupayakan agar
gaji dan upah dihitung dengan akurat dan dibayarkan sebagaimana yang
dijadwalkan.
2.Pengeluaran gaji dan upah merupakan objek pajak penghasilan.
3.Jumlah beban gaji dan upah serta pajak gaji dan upah mempunyai pengaruh yang
signifikan pada laba bersih.
Gaji kotor (Gross Pay)
Total Penghasilan seorang karyawan untuk satu periode gaji termasuk bonus,
lembur, dan tunjangan lainnya.
Gaji bersih (net pay)
Jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan setelah
dikurangi potongan-potongan tertentu seperti pajak penghasilan karyawan, dan
pensiun.
Kompensasi karyawan bukan hanya gaji dan upah, namun ada juga
tambahan berupa tunjangan-tunjangan
Beberapa bentuk Tunjangan, seperti: Tunjangan transportasi, Tunjangan makan,
Tunjangan keluarga, Tunjangan kesehatan, Dll.
Jaminan Hari Tua (JHT) :
Pembayaran uang secara periodik sebagai antisipasi untuk karyawan yang
pensiun karena usia, ketidakmampuan (cacat fisik) atau berakhirnya masa
kerja. Premi untuk JHT berasal dari pembayaran gabungan oleh perusahaan &
karyawan, dimana karyawan 2 % dari gaji, perusahaan 3,7 % dari gaji
karyawan.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) :
Program JAMSOSTEK yang tidak wajib. Jumlahnya 6 % untuk karyawan yang
telah menikah (maksimal Rp 60.000/bulan) dan 3% untuk karyawan yang
belum menikah (maksimal Rp 30.000/bln)
Pajak Penghasilan :
Setiap pemberi kerja harus memotong sebagian dari penghasilan
karyawannya untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh).
Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran gaji karyawan:
Pada saat utang pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut dari karyawan
disetorkan ke kas Negara, maka ayat jurnal yang dibuat:
KARAKTERISTIK OBLIGASI
1. Obligasi (bonds) yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, biasanya memerlukan suatu kontrak atau surat perjanjian => bond indenture
2. Obligasi yang dikeluarkan biasanya dibagi dalam jumlah obligasi yang lebih kecil nilainya dalam berbagai pecahan (denominations).
3. Nilai pokok yang tercantum dalam masing-masing obligasi disebut nilai nominal (face value).
4. Pembayaran bunga dapat dilakukan secara tahunan, semesteran, dan kuartalan.
5. Apabila perusahaan ingin menawarkan obligasi di bursa efek, harus meminta izin lebih dahulu kepada Badan Pengawas Pasar Modal.
NILAI TEORITIS
Secara teoritis, nilai utang obligasi adalah nilai tunai (present
value) dari bunga periodik di masa mendatang selama
perioda utang dan nilai nominal pada tanggal jatuh tempo.
ALASAN MENGELUARKAN
OBLIGASI
1. Obligasi sebagai alternatif sumber dana bagi perusahaan
untuk membelanjai investasi atau proyek jangka panjang.
2. Dari sudut pemegang saham, obligasi tidak memengaruhi
kontrol para pemegang saham sebelumnya.
3. Bunga utang umumnya bersifat tetap, dan sepanjang
biaya bunga lebih rendah daripada kembalian atas aset
operasi bersih (return on net operating assets), maka
kelebihan return tersebut merupakan manfaat yang akan
dinikmati oleh pemegang saham.
4. Bunga utang menjadi pengurang laba kena pajak,
sedangkan dividen tidak.
OBLIGASI PADA TANGGAL
BUNGA DAN PENCATATAN
Hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Mengeluarkan obligasi tidak dicatat dalam buku jurnal, sedangkan apabila obligasi telah dijual maka dicatat dalam jurnal.
2. Penjualan obligasi laku dijual sebesar nilai nominal, diatas nilai nominal, atau dibawah nilai nominal.
3. Jika bunga nominal melebihi bunga efektif, maka obligasi terjual diatas nilai nominal. (Masyarakat lebih suka memilih obligasi daripada deposito)
4. Jika bunga nominal lebih kecil daripada bunga efektif, maka obligasi terjual dibawah nilai nominal. (Masyarakat lebih suka memilih deposito daripada obligasi)
5. Jika bunga nominal sama dengan bunga efektif, maka obligasi terjual sebesar nilai nominal.
PERHITUNGAN OBLIGASI DAN
PENCATATAN
Obligasi laku sebesar nilai nominal:
Pada tanggal 1 Januari 2013 PT ABC mendapat autorisasi
untuk mengeluarkan 20.000 lembar obligasi dengan nilai
nominal @ Rp 100, bunga nominal 6 % per semester, tanggal
bunga 1/1 dan 1/7, jatuh tempo 1 Januari 2015. Pada tanggal
pengeluaran seluruh obligasi laku dijual dengan harga jual
bersih (setelah dikurangi biaya transaksi seperti komisi
penjamin) sebesar Rp 2.000.000. Oleh karena harga jual
bersih sama dengan nilai nominalnya, maka bunga efektif
sama dengan bunga nominal, yakni 6 % per semester.
Buatlah jurnalnya ?
PERHITUNGAN OBLIGASI DAN
PENCATATAN
Obligasi laku diatas nilai nominal:
Pada tanggal 1 Januari 2013 PT ABC mendapat autorisasi
untuk mengeluarkan 20.000 lembar obligasi dengan nilai
nominal @ Rp 100, bunga nominal 6 % per semester, tanggal
bunga 1/1 dan 1/7, jatuh tempo 1 Januari 2015. Pada tanggal
pengeluaran seluruh obligasi laku dijual dengan harga jual
bersih (setelah dikurangi biaya transaksi seperti komisi
penjamin) sebesar Rp 2.070.919. Oleh karena harga jual
bersih melebihi nilai nominalnya, maka bunga efektif lebih
rendah bunga nominalnya yakni 5 % per semester. Buatlah
jurnalnya ?
PERHITUNGAN OBLIGASI DAN
PENCATATAN
Obligasi laku dibawah nilai nominal:
Pada tanggal 1 Januari 2013 PT ABC mendapat autorisasi
untuk mengeluarkan 20.000 lembar obligasi dengan nilai
nominal @ Rp 100, bunga nominal 6 % per semester, tanggal
bunga 1/1 dan 1/7, jatuh tempo 1 Januari 2015. Pada tanggal
pengeluaran seluruh obligasi laku dijual dengan harga jual
bersih (setelah dikurangi biaya transaksi seperti komisi
penjamin) sebesar Rp 1.932.256 Oleh karena harga jual
bersih lebih rendah daripada nilai nominalnya, maka bunga
efektif lebih tinggi daripada bunga nominal yakni 7 % per
semester. Buatlah jurnalnya ?
PEMBAYARAN BUNGA NOMINAL
1. Perusahaan membayar bunga obligasi di setiap tanggal
bunga untuk masa bunga yang telah lewat.
2. Pada saat pembayaran, perusahaan mendebit akun
beban bunga dan mengkredit kas.
PEMBAYARAN BUNGA NOMINAL
Bunga obligasi PT ABC adalah 6 % per semester,
tanggal bunga 1/1 dan 1/7. Pada 1 Juli 2013 PT
ABC membayar bunga sebesar 6 % dari nilai
nominal untuk masa sejak 1 Januari s/d 1 Juli
2013. Nilai nominal obligasi sebesar Rp 2.000.000.
Hitunglah bunganya dan buatlah jurnalnya ?
PENYESUAIAN
1. Pada setiap tanggal bunga, perusahaan mengamortisasi
agio atau disagio utang obligasi jika pada saat penjualan
surat utang obligasi terbentuk agio atau disagio tersebut.
2. Penyesuaian dapat dilakukan pada setiap akhir tahun
buku.
AMORTISASI AGIO UTANG OBLIGASI
1. Metode amortisasi agio utang obligasi adalah
metode bunga efektif dan garis lurus.
2. Agio utang obligasi diamortisasi selama masa
sejak perusahaan menjual surat utang obligasi
sampai tanggal jatuh tempo.
3. Mengamortisasi agio dilakukan dengan
mendebit akun agio utang obligasi dan
mengkredit akun beban bunga.
AMORTISASI AGIO UTANG OBLIGASI
PT ABC mengeluarkan dan menjual surat utang obligasi dengan harga jual bersih Rp 2.070.919. Nilai nominalnya adalah Rp 2.000.000. Jadi, agio utang obligasi yang terbentuk dari penjualan obligasi pada 1 januari 2013 adalah Rp 70.919. Umur obligasi adalah 4 semester dari 1 Januari 2013 sampai 1 januari 2015. Bunga efektif per semester adalah 5 %. Pertanyaan:
1. Hitunglah amortisasi agio utang obligasi per semester dengan menggunakan metoda bunga efektif ?
2. Buatlah jurnal penyesuaian pada 1 Juli 2013 untuk mencatat amortisasi agio utang obligasi ?
RENCANA AMORTISASI AGIO
UTANG OBLIGASI
Nominal Rp 2.000.000 dan Agio Rp 70.919.
Metode Bunga Efektif
Tanggal Bunga Nominal =
6 % x 2.000.000
Bunga Efektif
5 % x (5) t-1
Amortisasi Agio =
Nominal - Efektif
Nilai Buku Akhir
2.070.919,00
1 Juli 2013
31 Des 2013
1 Juli 2014
31 Des 2014
RENCANA AMORTISASI AGIO
UTANG OBLIGASI
Nominal Rp 2.000.000 dan Agio Rp 70.919.
Metode Garis Lurus
Tanggal Bunga Nominal =
6 % x 2.000.000
Amortisasi
Agio
Bunga Efektif Nilai Buku Akhir
1 Juli 2013
31 Des 2013
1 Juli 2014
31 Des 2014
AMORTISASI DISAGIO UTANG OBLIGASI
1. Metode amortisasi disagio utang obligasi
adalah metode bunga efektif dan metode garis
lurus.
2. Disagio utang obligasi diamortisasi selama
masa sejak perusahaan menjual surat utang
obligasi sampai tanggal jatuh tempo.
3. Mengamortisasi agio dilakukan dengan
mendebit akun Beban Bunga dan mengkredit
akun disagio utang obligasi.
AMORTISASI DISAGIO UTANG OBLIGASI
PT ABC mengeluarkan dan menjual surat utang obligasi dengan harga jual bersih Rp 1.932.256. Nilai nominalnya adalah Rp 2.000.000. Jadi, disagio utang obligasi yang terbentuk dari penjualan obligasi pada 1 januari 2013 adalah Rp 67.744. Umur obligasi adalah 4 semester dari 1 Januari 2013 sampai 1 januari 2015. Bunga efektif per semester adalah 5 %. Pertanyaan:
1. Hitunglah amortisasi disagio utang obligasi per semester dengan menggunakan metoda bunga efektif ?
2. Buatlah jurnal penyesuaian pada 1 Juli 2013 untuk mencatat amortisasi disagio utang obligasi ?
RENCANA AMORTISASI AGIO
UTANG OBLIGASI
Nominal Rp 2.000.000 dan Disagio Rp 67.744.
Metode Bunga Efektif
Tanggal Bunga Nominal =
6 % x 2.000.000
Bunga Efektif
5 % x (5) t-1
Amortisasi Agio =
Efektif - Nominal
Nilai Buku Akhir
1.932.256,00
1 Juli 2013
31 Des 2013
1 Juli 2013
31 Des 2013
RENCANA AMORTISASI AGIO
UTANG OBLIGASI
Nominal Rp 2.000.000 dan Disagio Rp 67.744.
Metode Garis Lurus
Tanggal Bunga Nominal =
6 % x 2.000.000
Amortisasi
Disagio
Bunga Efektif Nilai Buku Akhir
1.932.256,00
1 Juli 2013
31 Des 2013
1 Juli 2013
31 Des 2013
PENGAKUAN BUNGA BERJALAN
1. Penyesuaian juga diperlukan untuk mencatat bunga
berjalan jika tanggal akhir tahun tidak bertepatan dengan
tanggal bunga.
2. Jurnalnya adalah mendebit beban bunga dan kredit utang
bunga.
PENILAIAN DAN PENYAJIAN
DI NERACA
1. Di Neraca, utang obligasi dinilai sebesar nilai tercatat setelah diperhitungkan amortisasi agio/disagio.
2. Nilai tercatat untuk surat utang yang terjual di atas nilai nominal adalah nilai nominal plus agio utang obligasi yang belum diamortisasi.
3. Nilai tercatat untuk surat utang yang terjual dibawah nilai nominal adalah nilai nominal minus disagio utang obligasi yang belum diamortisasi.
4. Penyajian utang obligasi adalah dalam kelompok kewajiban jangka panjang jika jatuh temponya melebihi satu tahun.
5. Penyajian utang obligasi jangka panjang yang jatuh tempo tahun depan diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek jika pelunasannya menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban jangka pendek.
PENILAIAN DAN PENYAJIAN
DI NERACA
Kewajiban Jangka Panjang:
Utang Obligasi (nominal) Rp 2.000.000
(+) Agio Utang Obligasi Rp 70.919
Rp 2.070.919
Kewajiban Jangka Panjang:
Utang Obligasi (nominal) Rp 2.000.000
(-) Disagio Utang Obligasi ( Rp 67.744)
Rp 1.932.256
PELUNASAN PADA SAAT JATUH
TEMPO
1. Perusahaan melunasi kewajibannya sebesar nilai
nominal pada saat jatuh tempo.
2. Ketika membayar jurnalnya akun utang obligasi didebit
sebesar nilai nominalnya.
3. Akun agio ataupun disagio utang obligasi bersaldo nol
pada tanggal jatuh tempo.
PELUNASAN PADA SAAT JATUH
TEMPO
Pada 1 Januari 2015 PT ABC melunasi utang obligasi dengan
nilai nominal Rp 2.000.000. Buatlah jurnalnya ?
1 Januari 2015
PENARIKAN OBLIGASI SEBELUM
JATUH TEMPO DAN PENCATATANNYA
1. Obligasi yang bersifat callable – dapat ditarik kembali sebelum tanggal jatuh tempo atas dasar perjanjian sebelumnya.
2. Obligasi yang sudah go public juga dapat ditarik kembali melalui pembelian di bursa efek tanpa perjanjian lebih dahulu.
3. Ketika utang obligasi yang ditarik sebelum jatuh tempo yang diperlukan adalah :
a. Mencatat amortisasi agio/disagio yang diperlukan
b. Menghapus nilai buku utang per tanggal penarikan
c. Mencatat jumlah kas yang dikeluarkan
d. Mengakui untung (rugi) penarikan seandainya ada perbedaan antara kurs penarikan dan nilai tercatat (buku) utang.
PENARIKAN OBLIGASI SEBELUM
JATUH TEMPO DAN PENCATATANNYA
Pada tanggal 1 Januari 2013 PT ABC mendapat autorisasi untuk mengeluarkan 20.000 lembar obligasi dengan nilai nominal @ Rp 100, bunga nominal 6 % per semester, tanggal bunga 1/1 dan 1/7, jatuh tempo 1 Januari 2015. Pada tanggal pengeluaran seluruh obligasi laku dijual dengan harga jual bersih (setelah dikurangi biaya transaksi seperti komisi penjamin) sebesar Rp 2.070.919. Oleh karena harga jual bersih melebihi nilai nominalnya, maka bunga efektif lebih rendah bunga nominalnya yakni 5 % per semester. Pada akhir tahun 2013 PT ABC menarik utang obligasi dengan utang obligasi pembayaran Rp 2.050.000. Hitunglah nilai tercatat pada saat penarikan dan buatlah jurnal yang diperlukan !
PENARIKAN OBLIGASI SEBELUM
JATUH TEMPO DAN PENCATATANNYA
Agio Utang Obligasi mula-mula Rp 70.919
(-) Amortisasi 1 Jan – 1 Juli 2013 Rp 16.454,05
(-) Amortisasi 1 Juli – 31 Des 2013 Rp 17.276,75
Rp 33.730,80
Saldo agio utang obligasi Rp 37.188,20
Nominal utang obligasi Rp 2.000.000
Nilai buku utang obligasi per 31 Des. 2013 Rp 2.037.188,20
Kurs Penarikan Rp 2.050.000
Rugi Penarikan Rp 12.811,80
PENARIKAN OBLIGASI SEBELUM
JATUH TEMPO DAN PENCATATANNYA
Jurnal :
31 Desember 2013
Agio Utang Obligasi Rp 17.276,75
Beban Bunga Rp 17.276,75
(mencatat amortisasi agio, jika ini belum dicatat)
Utang Obligasi Rp 2.000.000
Agio Utang Obligasi Rp 37.188,20
Rugi Penarikan Utang Obligasi Rp 12.811,80
Kas Rp 2.050.000
PENJUALAN OBLIGASI DILUAR TANGGAL
BUNGA DAN PENCATATANNYA
1. Obligasi yang terjual di antara tanggal-tanggal
pembayaran bunga, maka perusahaan akan mewajibkan
pembeli untuk membayar bunga berjalan.
2. Penerimaan bunga berjalan adalah uang muka yang akan
dikembalikan ke pembeli pada tanggal bunga.
3. Menggunakan 2 pendekatan yaitu laba rugi dan neraca
untuk mencatat bunga berjalan dan pembayaran bunga.
PENJUALAN OBLIGASI DILUAR TANGGAL
BUNGA DAN PENCATATANNYA
Pada tanggal 1 Januari 2013 PT ABC mendapat autorisasi
untuk mengeluarkan 20.000 lembar obligasi dengan nilai
nominal @ Rp 100, bunga nominal 6 % per semester, tanggal
bunga 1/1 dan 1/7, jatuh tempo 1 Januari 2015. Pada tanggal
pengeluaran seluruh obligasi laku dijual dengan harga jual
bersih (setelah dikurangi biaya transaksi seperti komisi
penjamin) sebesar Rp 2.070.919. Oleh karena harga jual
bersih melebihi nilai nominalnya, maka bunga efektif lebih
rendah bunga nominalnya yakni 5 % per semester. Baru
terjual pada 1 Mei 2103 dengan harga jual bersih sebesar
Rp 2.000.000 sebesar nilai nominalnya. Hitunglah jumlah
yang diterima perusahaan pada tanggal 1 Mei 2013 dan
bunga berjalan yang diterima dan buatlah jurnalnya ?
PENJUALAN OBLIGASI DILUAR TANGGAL
BUNGA DAN PENCATATANNYA
Pendekatan Laba Rugi:
1 Mei 2013
Kas Rp 2.080.000
Utang Obligasi Rp 2.000.000
Beban Bunga Rp 80.000
(Mencatat penjualan obligasi sebesar nilai nominal ditambah bunga berjalan 4 bulan)
1 Juli 2013
Beban bunga Rp 120.000
Kas Rp 120.000
(Mencatat pembayaran bunga)
PENJUALAN OBLIGASI DILUAR TANGGAL
BUNGA DAN PENCATATANNYA
Pendekatan Laba Rugi:
Perhitungan:
4/6 x 6% x Rp 2.000.000 = Rp 2.080.000
Beban bunga neto:
Rp 2.000.000 x 2/6 x 6 % = Rp 40.000
PENJUALAN OBLIGASI DILUAR TANGGAL
BUNGA DAN PENCATATANNYA
Pendekatan Neraca:
1 Mei 2013
Kas Rp 2.080.000
Utang Obligasi Rp 2.000.000
Utang Bunga Rp 80.000
(Mencatat penjualan obligasi sebesar nilai nominal ditambah bunga berjalan 4 bulan)
1 Juli 2013
Beban bunga Rp 40.000
Utang Bunga Rp 80.000
Kas Rp 120.000
(Mencatat pembayaran bunga)
Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
• Ekuitas (+) :
1. Setoran tambahan dari pemilik
2. Laba perusahaan
• Ekuitas (-) :
1. Penarikan kembali oleh pemilik
2. Rugi perusahaan
MODAL SAHAM & LABA DITAHAN
• Ekuitas perseroan terbatas (PT) disebut modal pemegang saham.
• Bagi pemegang saham, memiliki saham berarti memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. PT menarik dana dari pemilik dengan mengeluarkan saham.
• Saham diklasifikasi menjadi 2 yaitu:
1. Saham Biasa (Common Share)
2. Saham Istimewa atau Saham Preferen (Prefereed Stock)
EKUITAS PERSEROAN TERBATAS
• Merupakan kepemilikan dasar dari saham dengan hak-hak seperti memilih anggota direksi, memperoleh pembagian laba, membeli saham tambahan.
• Merupakan saham yang mempunyai hak suara, hak residu terhadap pembagian laba setiap tahunnya, dan hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan dilikuidasi.
SAHAM BIASA
• Jenis saham yang memiliki hak istimewa melebihi saham biasa, terutama dalam hal pembayaran dividen dan likuidasi perusahaan.
• Saham yang mempunyai hak preferensi atau prioritas dengan menerima lebih dahulu pembagian laba setiap tahunnya dan aset pada saat perusahaan dilikuidasi.
Saham Preferen
• Saham pada perusahaan yang belum menggunakan paperless, segera dicetak setelah ada autorisasi dari rapat umum pemegang saham (RUPS). Modal saham yang diautorisasi merupakan jumlah maksimum saham yang dapat dikeluarkan.
• Contoh transaksi :
Pada 1 Januari 2014 PT BATAKO adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang konstruksi mendapat autorisasi untuk mengeluarkan saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal per lembar Rp 10.000. (Tidak perlu dicatat dalam buku jurnal)
Pengeluaran Saham Biasa
Pada 15 Januari 2014, sebuah perusahaan bernama PT Wiwaha mengeluarkan saham biasa dan menjualnya 20.000 lembar dengan kurs 120. Nilai nominal per lembar saham adalah Rp 500. Hitunglah jumlah kas yang diterima, tentukan agio ataupun disagio modal saham, dan buatlah jurnalnya !
Perhitungan :
Jumlah kas yang diterima = 20.000 x 500 x 120 % = Rp 12.000.000
Nilai nominal saham biasa = 20.000 x 500 = (Rp 10.000.000)
Agio modal saham biasa = Rp 2.000.000
PENJUALAN SAHAM BIASA
Jurnal :
15 Januari 2014
Kas Rp 12.000.000
Modal Saham Biasa Rp 10.000.000
Agio Modal Saham Biasa Rp 2.000.000
PENJUALAN SAHAM BIASA
Jika saham biasa dijual < nilai nominalnya, maka selisih antara nilai nominal dan harga jual dicatat dalam akun Disagio Modal. Disagio modal saham biasa adalah pengurang modal saham biasa.
Jika saham biasa dijual > nilai nominalnya, maka selisih antara nilai nominal dan harga jual dicatat dalam akun Agio Modal. Agio modal saham biasa adalah penambah modal saham biasa.
PENJUALAN SAHAM BIASA
• Pemecahan nilai nominal tiap lembar saham, tanpa
mengubah nilai nominal saham secara keseluruhan.
• Peristiwa stocks splits-up tidak dicatat dalam buku jurnal.
STOCK SPLITS-UP
• Contoh transaksi:
Sesaat sebelum stocks splits-up, jumlah saham PT
WIWAHA yang beredar adalah 20.000 lembar, nilai
nominal @ Rp 500. Pada 1 Oktober 2014 nilai nominal
saham per lembar dipecah menjadi Rp 100. Dalam kasus
ini, maka jumlah lembar sahamnya menjadi 100.000
lembar, yakni (Rp 500 : Rp 100) x 20.000 lembar.
Bagaimana jurnalnya ?
STOCK SPLITS-UP
• Bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam
bentuk uang tunai.
• Contoh :
Sesaat sebelum pembagian dividen tunai, jumlah saham PT
WIWAHA yang beredar adalah 100.000 lembar, nominal @ Rp
100. Pada 1 Februari 2015 perusahaan mengumumkan dividen
kas Rp 15 per lembar saham dan akan membayarnya pada 20
Februari 2015. Buatlah jurnal yang diperlukan ?
PEMBAGIAN DIVIDEN KAS
1 Februari 2015
Saldo laba Rp 1.500.000
Utang dividen Rp 1.500.000
(mencatat pembagian dividen kepada 100.000 lembar
saham @ Rp 15)
PEMBAGIAN DIVIDEN KAS
20 Februari 2015
Utang dividen Rp 1.500.000
Kas Rp 1.500.000
(mencatat pembagian dividen kas)
PEMBAGIAN DIVIDEN KAS
• Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham biasa dalam bentuk saham sejenis dengan yang dimiliki oleh pemegang saham lama.
• Contoh transaksi :
Pada 1 Agustus 2015, ketika saham yang telah beredar adalah 100.000 lembar, nominal @ Rp 100, PT WIWAHA membagi selembar dividen saham kepada setiap pemegang 20 lembar saham. Jadi, yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham adalah 5.000 lembar (100.000 lembar dibagi 20) saham, nominal @ Rp 100. Pada saat ini nilai wajar saham biasa PT WIWAHA adalah Rp 140. Buatlah jurnalnya ?
PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM
Perhitungan:
Nilai wajar saham = 5.000 x Rp 140 = Rp 700.000
Nilai Nominal Saham = 5.000 x Rp 100 = Rp 500.000
Agio Saham Rp 200.000
PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM
1 Agustus 2015
Saldo Laba Rp 700.000
Modal Saham Biasa Rp 500.000
Agio Modal Saham Biasa Rp 200.000
PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM
Jika nilai wajar saham per lembar pada waktu pembagian dividen saham adalah Rp 80. Maka jurnalnya :
1 Agustus 2015
Saldo Laba Rp 400.000
Disagio Modal Saham Biasa Rp 100.000
Modal Saham Biasa Rp 500.000
PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM
• Laba bersih yang ditahan atau tidak dibayarkan kepada
pemegang saham dalam bentuk dividen.
• Laba yang ditahan ini diakumulasikan dan dilaporkan
pada ekuitas pemilik dalam neraca keuangan.
• Tujuan laba ditahan adalah untuk melakukan
reinvestasi dalam bisnis perusahaan atau juga bisa
untuk melunasi hutang yang ada.
Laba Ditahan
Ada beberapa unsur yang mempengaruhi (faktor) perubahan laba ditahan, antara lain: 1. Adanya laba bersih (net income) atau rugi bersih (net loss) 2. Adanya penyesuaian periode sebelumnya (prior period adjusment) dan
perubahan kebijakan akuntansi (change in accounting policy) 3. Adanya deviden (cash dividend, stock dividend, property dividend dan
scrip dividend) 4. Adanya transaksi atas treasury stock (saham tresuri) 5. Adanya penyesuaian akibat quasi reorganization (prosedur akuntansi
untuk merestrukturisasi perusahaan dengan cara menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban perusahaan pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit tanpa melalui proses reorganisasi secara hukum).
Laba Ditahan
PT BAPAK
Laporan Laba ditahan
Per 31 Desember 2012
Laba ditahan, awal Rp 80.000.000
(-) Penyesuaian periode sebelumnya koreksi depresiasi dibebankan terlalu rendah pada tahun 2011, dikurangi pajak laba Rp 10 juta
(Rp 20.000.000)
Laba ditahan ditetapkan kembali Rp 60.000.000
(+) Laba bersih tahun 2012 Rp 197.000.000
Sub Total Rp 257.000.000
(-) Dividen untuk saham preferen Rp 15.000.000
Dividen untuk saham biasa Rp 35.000.000 (Rp 20.000.000)
Rp 237.000.000
Laba Ditahan
Saham perusahaan yang ditarik kembali dari peredaran untuk sementara waktu dan akan dijual lagi di masa berikutnya.
Contoh transaksi :
Jumlah saham PT WIWAHA yang beredar saat ini adalah 105.000 lembar, nominal @ Rp 100, atau nominal total modal saham biasa adalah Rp 10.500.000. Berikut adalah transaksi terkait dengan saham tresuri pada tahun 2016.
SAHAM TRESURI
1 Maret 2016
Menarik 25.000 lembar saham sebagai saham tresuri
dengan harga Rp 150 per lembar
1 April 2016
Menjual kembali 15.000 lembar saham tresuri dengan
harga Rp 160 per lembar
1 Mei 2016
Menjual kembali 8.000 lembar saham tresuri dengan harga
Rp 140 per lembar
SAHAM TRESURI
1 Maret 2016
Saham Tresuri Rp 3.750.000
Kas Rp 3.750.000
(Mencatat perolehan saham tresuri)
Perhitungan :
25.000 x Rp 150 = Rp 3.750.000
SAHAM TRESURI
1 April 2016
Kas Rp 2.400.000
Saham Tresuri Rp 2.250.000
Agio dari saham Tresuri Rp 150.000
(Mencatat penjualan saham tresuri diatas biaya perolehannya)
Perhitungan :
Kas yang diterima = 15.000 x 160 = Rp 2.400.000
Saham Tresuri = 15.000 x 150 = Rp 2.250.000
SAHAM TRESURI
1 Mei 2016
Kas Rp 1.120.000
Agio dari saham Tresuri Rp 80.000
Saham Tresuri Rp 1.200.000
(Mencatat penjualan saham tresuri diatas biaya perolehannya)
Perhitungan :
Kas yang diterima = 8.000 x 140 = Rp 1.120.000
Saham Tresuri = 8.000 x 150 = Rp 1.200.000
SAHAM TRESURI