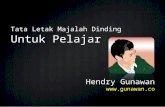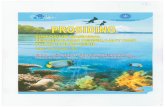2. EKSISTENSI USAHA PEMBUATAN JUKUNG DI PULAU ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 2. EKSISTENSI USAHA PEMBUATAN JUKUNG DI PULAU ...
LAPORAN PENELITIAN
EKSISTENSI USAHA PEMBUATAN JUKUNG DI PULAU SEWANGI,
ALALAK, BARITO KUALA
Tim Peneliti:
Ketua:
Dr. Bambang Subiyakto, M.Hum. (0009025606)
Anggota:
Mutiani, S.Pd., M.Pd. (0007098902)
M. Faisal (1610128110005)
Muhammad Azhari Mutaqin (1910128210020)
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN, 2019
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur diucapkan kepada Allah S.W.T karena atas Berkat dan Rahmat-
Nya penelitian telah rampung dalam waktu yang ditetapkan. Penelitian ini berjudul
“EKSISTENSI USAHA PEMBUATAN JUKUNG DI PULAU SEWANGI,
ALALAK, BARITO KUALA” yang bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan
pembuatan jukung oleh pengrajin di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala, 2)
Mendeskripsikan usaha jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala, dan 3)
Mendeskripsikan kendala keberlangsungan usaha jukung di Pulau Sewangi, Alalak,
Baritokuala.
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat dan semua pihak yang telah
mendukung dan memfasilitasi penelitian ini baik dari segi materiil dan teknis.
Penelitian ini tentu masih memiliki berbagai kekurangan dalam beberapa hal.
Demikian, diperlukan saran dan kritik yang membangun.
Banjarmasin, Januari 2020
Peneliti
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ 1
DAFTAR ISI ........................................................................................................... 2
DAFTAR TABEL ................................................................................................... 3
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. 4
ABSTRAK .............................................................................................................. 5
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN ............................................................ 6
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 7
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................................... 7 B. Rumusan Masalah ................................................................................................... 9 C. Tujuan Penelitian .................................................................................................... 9 D. Manfaat Hasil Penelitian ......................................................................................... 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................ 11
A. Definisi Eksistensi................................................................................................. 11 B. Konsep Usaha Mikro Dan Kecil Menengah (Umkm) ........................................... 12 C. Konsep Transportasi ............................................................................................. 15 D. Transportasi Air .................................................................................................... 17
BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 20
A. Desain Penelitian................................................................................................... 20 B. Lokasi Penelitian ................................................................................................... 21 C. Waktu Penelitian ................................................................................................... 21 D. Subjek Penelitian .................................................................................................. 21 E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................................... 22 F. Instrumen Penelitian ............................................................................................. 24 G. Teknik Analisis Data ............................................................................................. 24 H. Pemeriksaan Keabsahan Data ............................................................................... 26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 28
A. Gambaran Desa Pulau Sewangi, Alalak, Barito Kuala ......................................... 28 B. Deskripsi usaha jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Barito kuala .......................... 38 C. Kendala Keberlangsungan Usaha Pembuatan Jukung di Pulau Sewangi, Alalak,
Barito kuala ................................................................................................................... 47 BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 52
A. Simpulan ............................................................................................................... 52 B. Saran ..................................................................................................................... 53
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 54
3
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No, 20/2008 ................................. 14
Tabel 2. Daftar Nama Narasumber ....................................................................... 22
Tabel 3. Jumlah penduduk berasarkan jenis kelamin Desa Pulau Sewangi .......... 30
Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Pulau Sewangi .................................................. 30
Tabel 5. Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pulau Sewangi .................. 30
Tabel 6. Jumlah penduduk menurut pekerjaan rumah tangga............................... 31
4
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Apak Pada Jukung ............................................................................... 37
Gambar 2. Proses penipisan krongkong jukung menggunakan peralatan katam .. 56
Gambar 3. Finalisasi jukung dengan mengecat body............................................ 56
Gambar 4. Kapal Feri, moda transportasi untuk mencapai Pulau Sewangi .......... 57
Gambar 5. Wawancara bersama pengrajin jukung di Pulau Sewangi .................. 57
Gambar 6. Pemasangan apak pada jukung ............................................................ 58
Gambar 7. Pemasangan tajak untuk disambungkan ke apak pada jukung ............ 58
Gambar 8. Penipisan krongkong menggunakan baji............................................. 59
Gambar 9. Wawancara bersama pengrajin jukung di Pulau Sewangi .................. 59
Gambar 10. Gambar jukung dengan panjang 9 meter........................................... 60
5
ABSTRAK
Jukung merupakan alat transportasi air yang sering digunakan masyarakat sebelum
adanya kapal besar dan jalur darat. Popularitas jukung sebagai moda transportasi
air tergantikan oleh perkembagan infrastruktur darat yang massif. Kondisi ini
berimbas pada usaha yang ada di Pulau Sewangi, Alalak, Barito Kula. Dibalik
perubahan yang terjadi pengrajin terus berusaha menggerakan usaha pembuatan
jukung yang digeluti turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk; 1)
Mendeskripsikan pembuatan jukung oleh pengrajin di Pulau Sewangi, Alalak,
Baritokuala, 2) Mendeskripsikan usaha jukung di Pulau Sewangi, Alalak,
Baritokuala, dan 3) Mendeskripsikan kendala keberlangsungan usaha jukung di
Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala. Pendekatan kualitatif digunakan dalam
penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi tiga tahapan; wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari reduksi, penyajian, dan verifikasi data.
Namun, untuk memberikan data yang jenuh (redundant) triangulasi dilakukan
secara bertahap. Hasil penelitian meliputi tiga aspek, yakni; 1) pembuatan jukung
memerlukan waktu 2-3 minggu. Pembuatan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu;
persiapan, proses pembuatan, dan finalisasi, 2) Pulau Sewangi, Alalak, Barito
Kuala dikenal sebagai sentra penghasil moda transportasi air yakni jukung. Hal in
dikarenakan mayoritas pekerjaan masyarakat adalah pengrajin jukung, 3) kendala
keberlangsungan usaha pembuatan jukung di Pulau Sewangi terjadi karena tiga hal.
Pertama, keterbatasan bahan baku kayu, teknik penjualan jukung melalui sistem
Ready Stock, dan minimnya pemuda menggeluti profesi pengrajin jukung.
Kata kunci; jukung, moda transportasi air, dan pengrajin,
6
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN
EKSISTENSI USAHA PEMBUATAN JUKUNG DI PULAU SEWANGI,
ALALAK, BARITO KUALA
1. Program Studi : Pendidikan IPS
2. Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin
Telpon : 0511-3304914
Fax : 0511-3304914
Email : ips.fkip.unlam.ac.id
3. Koordinator Program Studi : Prof. Dr. Ersis Warmansyah Abbas, M.Pd
4. Ketua Pelaksana : Dr. Bambang Subiyakto, M.Hum.
5. Anggota : Mutiani, S.Pd., M.Pd.
M. Faisal
Muhammad Azhari Mutaqin
6. Biaya : Rp 20.000.000
(Dua Puluh Juta Rupiah)
7. Sumber Dana : DIPA (PNBP) FKIP ULM 2019
Mengetahui, Banjarmasin, Desember 2019
Dekan FKIP, Ketua Pelaksana,
Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si. Dr. Bambang Subiyakto, M.Hum.
NIP. 19650808 199303 1 003 NIP. 19560209 198811 1 001
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 0020
7
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masalah transportasi erat ikatannya dengan perhubungan yang
pengertiannya lebih luas dari sekedar transportasi. Sehubungan dengan hal
perhubungan, masyarakat di Indonesia mengenalnya dalam tiga bagian yaitu bidang
perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Munculnya
pembagian ini secara sederhana dapat dimengerti karena dibedakan berdasarkan
adany unsur alam berupa tanah (darat), air (perairan, laut), dan udara. Dilihat dari
sudut pembedaan fisik tempat berlangsungnya transportasi di Indonesia dibedakan
berdasarkan transportasi darat yang terdiri dari transportasi jalan raya, transportasi
di atas jalan baja (kereta api), dan transportasi perairan daratan; transportasi air
(laut); dan transportasi udara.
Keadaan ini menimbulkan konsekuensi yaitu terdapatnya pembedaan dalam
bentuk dan persyaratan teknis dari sarana dan prasarana masing-masing jenis
angkutan serta membawa pula perbedaan dalam sifat dan kemampuan masing-
masing jenis sarana transportasi itu. Kesemua jenis transportasi tadi memerlukan
pula penggolongan dalam pengaturannya dan perbedaan dalam pembinaannya,
yang dalam hal ini pelaksanaannya ditangani oleh instansi khusus yang diberi
wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
Diskusi mengenai transportasi, di Banjarmasin dengan sebutan kota seribu
sungai. Dengan demikian, idealnya Banjarmasin sangat familiar dengan
transportasi air. Moda transportasi sungai di Banjarmasin yakni jukung dan klotok.
8
Keduanya hingga saat ini masih bisa ditemui. Namun, tidak banyak dari
masyarakat mengetahui dimana pembuatan moda transportasi tersebut. Moda
transportasi tersebut mayoritas diproduksi di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala.
Di tengah perkembangan infrastruktur jalur transportasi darat Pulau Sewangi masih
memiliki geliat aktivitas ekonomi.
Namun, popularitas Pulau Sewangi tidak sebaik dulu (sekitar 10 tahun
terakhir). Jumlah jukung yang ada di Pulau Sewangi, Alalak, Barito Kuala tidak
memiliki kejelasan jumlah. Hal ini sangat tergantung pada pemesanan. Pembelinya
juga beragam tidak dominan satu daerah saja tapi hampir seluruh daerah
Kalimantan Selatan tujuan mereka membeli jukung berbeda-beda. Bagi pengrajin,
aktivitas pembuatan jukung dimulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bagi mereka
yang bekerja harian dibayar setengah harga. Di saat jukung sudah laku maka akan
dibayar upahnya lunas.
Kondisi terakhir, jumlah pengrajin berbeda-beda di setiap rumah mulai dari
2 orang sampai 10 orang. Banyak dari pengrajin jukung kemudian banting setir
bekerja sebagai buruh kasar, petani, maupun pedagang. Hal ini dikarenakan tingkat
pembangunan infrastruktur darat lebih massif dibandingkan sungai. Akan tetapi,
berdasarkan pola pengembangan kota dengan ikon wisata sungai. Moda
transportasi jukung masih digandrungi oleh masyarakat. Dengan demikian, usaha
pembuatan jukung dan klotok masih bisa bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu,
peneliti tertarik mengkaji eksistensi usaha pembuatan jukung yang tidak lekang
oleh waktu.
9
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian adalah bagaimana
eksistensi usaha pembuatan jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala.
Pertanyaan ini dirumuskan secara operasional sebagaimana berikut:
1. Bagaimana pembuatan jukung oleh pengrajin di Pulau Sewangi, Alalak,
Baritokuala?
2. Bagaimana deskripsi usaha jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala?
3. Bagaimana kendala keberlangsungan usaha jukung di Pulau Sewangi, Alalak,
Baritokuala?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang eksistensi usaha
pembuatan jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala. Secara khusus untuk
menjawab ketiga pertanyaan rumusan masalah di atas, antara lain:
1. Mendeskripsikan pembuatan jukung oleh pengrajin di Pulau Sewangi, Alalak,
Baritokuala.
2. Mendeskripsikan usaha jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala.
3. Mendeskripsikan kendala keberlangsungan usaha jukung di Pulau Sewangi,
Alalak, Baritokuala.
D. Manfaat Hasil Penelitian
Penelitian ini penting karena hasil atau temuannya mempunyai kegunaan
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
pengembangan kajian penelitian ilmu sosial.
10
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi
pihak-pihak terkait khususnya pemerintah Baritokuala untuk menjaga eksistensi
usaha pembuatan jukung di Pulau Sewangi.
11
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Definisi Eksistensi
Eksistensi umumya diartikan sebagai sebuah keberadaan. Pada kajian sosial,
eksistensi diartikan tentang keadaan diri seseorang atau keberadaan dirinya sendiri.
Kata eksistensi mengartikan kehidupan manusia bukanlah merupakan suatu
keadaan yang bersifat statis, melainkan kehidupan manusia terus mengalami
perubahan yang disebut dengan dinamis. Proses perubahan ini terjadi karena
manusia memiliki kebebasan untuk bergeak. Ketika kata eksistensi berubah
menjadi bereksistensi maka memiliki arti suatu tindakan berani mengambil
keputusan. Ketidak tidak bereksistensi berarti tidak berani mengambil keputusan
(Crumbaugh & Maholick, 1964).
Eksistensi diartikan sebagai sebuah keberadaan juga memiliki keterkaitan
dengan keadaan ada atau tidaknya seseorang. Keberadaan eksistensitidak hanya
hadir begitu saja, melainkanada karena melalui pemberian orang lain terhadap
seseorang, sebagai buktu bahwa kebaradaan orang tersebut diakui (Sartre & Mairet,
1975). Eksistensi merupakan suatu hal yang penting karena berkaitan dengan
sebuah pembuktia apakah yang telah dilakukan atau sebuah kinerja diakui di
dalam sebuah lingkungan.
Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi
diartikan sebagai diksi keberadaan, bermakna keadaan, “adanya”. Kamus Besar
Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa kata “Eksistensi; kebendaan, adanya”
(Depdiknas, 2008). Dari beberapa penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa eksistensi
memiliki cakupan yang luas. Namun, pada penelitian ini, konsep eksistensi yang
12
dikaji berkaitan dengan sudut pandang budaya dalam konteks perkembangan usaha
jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala.
B. Konsep Usaha Mikro Dan Kecil Menengah (Umkm)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan suatu konsep yang bisa
dikaji tidak hanya dari aspek ketahanan, pembiayaan peminjaman maupun
menajerial sebuah usaha. Di era globalisasi sekarang ini, khususnya dalam hal
integrasi ekonomi di Asia Tenggara (Economic Union) yang ditandai dengan
adanya kegiatan menjadikan Asia Tenggara menjadi sebuah komunitas dalam
kegiatan ekonomi berbasis produksi tunggal membuat UMKM, dengan tujuan agar
mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global
(Setyobudi, 2007).
UMKM sekarang dituntut untuk mampu bersaing dan terus berkreasi untuk
menciptakan produk-produk yang dapat diterima oleh konsumen baik lokal,
nasional hingga luar negeri, khususnya bagi konsumen di Asia Tenggara.
Kehadiran Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalam kehidupan
masyarakat memang sangat diperlukan keberadaannya. Sebagaimana pembuktian
di tengan krisis ekonomi pada Juli 1997, UMKM memainkan peranannya dalam
pembuktian mempertahankan ekonomi suatu bangsa. Kehadiran UMKM juga
merupakan sarana penyerap tenaga kerja. Sebagaimana didapatkan dari Data BPS
dan Kementerian Koperasi, dari seluruh kelas usaha menunjukkan bahwa usaha
skala kecil di Indonesia menempati porsi sekitar 99%, artinya hampir seluruh usaha
di Indonesia merupakan usaha kecil, hanya 1% saja usaha menengah dan besar.
Pada data ini juga terlihat adanya pertumbuhan dan perkmabangan UMKM
13
disetiap tahun. Hal ini terjadi karena, setiap pemerintahan melakukan penekanan
dalam pemberdayaan UMKM, sehingga dapat diartikan bahwa peranan pemerintah
memiliki peranan penting dalam hal menjaga keberadaan UMKM di masyarakat.
Begitu pentingnya peran pemerintah terhadap kehadian UMKM, karena UMKM
merupakan sebuah titik fokus ekonomi suatu bangsa, karena UMKM juga turut
menjad tempat yang dapat menampung tenaga kerja, karena bagi perusahaan-
perusahaan besar saat ini lebih menggunakan pada aspek teknoloi dari pada tenaga
kerja manusia (Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, 2013).
UMKM memiliki peranan penting bagi perekonomian negara, tidak
terkecuali bagi negara Indonesia. Indonesia yang merupakan negara berkembang
sudah seharusnya menjadikan UMKM sebagai sarana untuk memiliki kinerja yang
baik dalam aspek ekonomi seperti memiliki produktivitas tinggi dan mampu hidup
di tengah usaha-usaha besar lainnya. Peranan UMKM juga ditandai dengan
kemampuannya dalam menopang usaha-usaha besar sebagai penyedia bahan
mentah dan bahan-bahan pendukung lainnya. UMKM bagi usaha besar juga dapat
difungsikan sebagai distributor produk ke konsumen.
UMKM memiliki kapasistas yang kokoh bagi sebuah perekonmian bangsa,
karena UMKM mampu bertahan di tengah kondisi yang tidak menguntugkan,
seperti krisis ekonomi dengan meningkatkan kreativitas orang-orang di dalamnya
untuk menciptakan produk yang unik dan kusus sehingga tidak bersaing dengan
produk dari usaha-usaha besar lainnya.
14
1. Pengertian UMKM
UMKM merupakan suatu usaha yang sifatnya produktif dan berdiri sendiri,
dapat dilakukan oleh perorangan maupun sebuah Badan Usaha diberbagai sector
ekonomi (Tambunan, 2012: 2). Secara prinsip konsep UMKM terbagi menjadi
Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar
(UB). Jenis-jenis UMKM tersebut didasarkan oleh besaran nilai asset awal yang
dimiliki, tidak termasuk tanah dan bangunan. Meskipun demikian, disetiap negara
Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap negara.
Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 UMKM didefinisikan sebagai berikut:
a. Usaha Kecil merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang sifatnya
beridiri sendiri, dilakukan orang perorangan maupun badan usaha, bukan
merupakan anak perusahaan, bukan merupakan cabang dari sebuah perusahaan
yang dimiliki maupun dikuasai secara langsung maupun tidak langsung oleh
sebuah usaha besar..
b. Usaha Menengah merupakan sebuah kegiatan ekonomi produktif yang sifatnya
juga berdiri sendiri, oleh perorangan maupun badan usaha, baik secara langsung
maupun tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar. Adapun jumlah
kekayaan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008
tentang UMKM:
Tabel 1. Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No, 20/2008
Ukuran Usaha Asset Omset
Usaha Mikro Minimal 50 Juta Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta Maksimal 3 Miliar
15
Usaha Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2,5 – 50 Miliar
Sumber: UU No. 20/2008
C. Konsep Transportasi
Transportasi umumnya diartikan sebagai sebuah pemindahan suatu barang
maupun manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Dari adanya kegiatan tersebut,
maka diperlukan aspek yaitu apa yang menjadi objek yang akan diangkut, alat
pengangkut, dan ada sarana yang menjadi jalan harus dilalui. Proses perpindahan
yang dimaksud adanya keguatan awal dan diakhiri dengan sampainya ke tempat
tujuan. Kegiatan-kegiatan yang memiliki sifat memindahkan suatu barang maupun
manusia tersebut, maka diperlukan sebuah alat trasportasi untuk menunjang
kegiatan ekonomi (thepromoting sector) dan pemberi jasa (the servicing sector)
bagi perkembangan ekonomi (Koopmans, 1949).
Ada dua peran transportasi bagi keidupan manusia diantaranya: (1) sebagai
alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan, (2) sebagai
prasarana bagi pergerakan manusia dan barang yang timbul akibat adanya kegiatan
di daerah perkotaan tersebut. Sesuai dengan dua peranan tersebut, maka umumnya
peran pertama biasanya digunakan oleh seorang perencana pengambangan sebuah
wilayah. Misalkanya, pengembangan suatu suatu wilayah baru yang mana pada
wilayah tersebut tidak pernah ada peminatnya, ketika wilayah tersebut tidak
disediakan sistem prasarana transportasi. Ketika kondisi ini terjadi, maka keeradaan
transportasi memiliki peranan penting sebagai aksesibilitas menuju wilayah
tersebut, sehingga nantinya berdampak bagi peningkatan minat masyarakat
untuk menjalankan kegiatan ekonomi (Ibanez, et al., 2016). Transportasi juga
16
memiliki peran utama tidak hanya sebagai alat bantu untu pembangunan di
perkotaan, melainkan juga sebagai sarana pergerakan suatu barang maupun
manusia.
Dengan beberapa pejelasan di atas tentang peran dari transportasi dapat dua
peran penting. Pertama, transportasi acapkali digunakan oleh perencana
pengembang wilayah sehingga mampu meningkatkan potensi wilayah. Sebagai
contoh; pengembangan wilayah baru. Kedua, transportasi sebagai nilai tambah
infrastruktur suatu wilayah. Perihal ini berkenaan dengan konsepsi transportasi
yang beriringan fungsi aksesibilitas wilayah. Kedua peran ini berimplikasi
langsung terhadap perkembangan jalannya perekonomian masyarakat di suatu
wilayah.
Transportasi erat kaitannya dengan aksesibilitas, karena dengan transportasi
dapat menentukan susah maupun mudahnya suatu lokasi melakukan interaksi.
Meskipun ukuran susah dan mudah bersifat subyektif dan kualitatif tapi
kenyataannya adanya akses transportasi memudahkan menghubungkan akses antar
daerah (Ke, Chung, & Chen, 2016). Ketika sebuah tempat berdekatan dengan
tempat lainnya, maka terjadi aksesbilitas yang tinggi, dan begitupula sebalinya.
Dari hal itu, dapat dikatakan bahwa antar wilayah memiliki aksesbilitas berbeda.
Hal ini dikarenakan aktivitas wilayah menyebar secara tidak merata di ruang
(konsep spasial). Namun, sebuah lahan sejatinya dalam konteks transportasi harus
memiliki peran aksesiblitas yang baik. Hal ini dimaknai bawah ukuran aksesibilitas
yang diukur berdasarkan jarak dan waktu tempuh.
17
D. Transportasi Air
Transportasi air merupakan jenis transportasi tua dibandingkan konsep
transportasi darat. Hal ini dikarenakan air sebagai media atau sarana pemindahan
yang telah ada sejak zaman dahulu. Pada saat itu, tenaga yan menggerakkan
perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya adalah tenaga manusia dengan
mendayung. Selain itu, langkah yang lebih maju dari penggunaan tenaga manusia
adalah dengan memanfaatkan tenaga angin dengan memasang layar. Oleh karena
itu, dapat dikatakan berawal dari hal ini munculnya istilah pelayaran dengan
meggunakan tenaga mesin. Hingga sekarang ini, kapal sebagai salah satu alat
transportasi banyak digunakan untuk penumpang, mengangkut barang, dan
menangkap ikan (Martínez‐Vilalta & Garcia‐Forner, 2017). Peranan transportasi air
khususnya di daerah studi sangat penting karena daerah yang dipisahkan oleh
danau, untuk menghubungkan penduduk antara satu pulau dengan pulau yang lain
dengan menggunakan angkutan air (Łebkowski, 2018).
1. Sarana Pada Sistem Transportasi Air (Sungai)
Bagi transportasi air, jalan tidak disentuh oleh olah teknologi karenanya
dikenal dengan sifat alami (laut, sungai, danau). Namun, faktual jalur ini juga
dibuat oleh manusia kemudian dikenal dengan sebutan kanal, danau buatan. Untuk
beberapa kepentingan pelayaran jalur air ditatar agar memenuhi persyaratan dengan
diperlebar dan dikeruk. Hal ini lazim terjadi sebab sistem transportasi dipelihara
dengan seksama, berkala serta berkesinambungan. Sistem transportasi yang macet
seringkali dibuat oleh olah manusia. Pola kehidupan dan pemeliharan minim karena
kesadaran tidak menyentuh perilaku sehari-hari berakibat pada terganggunya
ekosistem.
18
Berkenaan dengan sungai, telah menjadi satu urat nadi bagi kehidupan
masyarakat karena menjadi sumber mata pencaharian untuk menambah
penghasilan keluarga dengan menjadi nelayan/penangkap ikan secara tradisional.
Sungai menjadi satu jalur alternatif yang dilalui moda transportasi untuk
mengangkut barang dan orang hingga saat ini (Shang & Zhang, 2017). Transportasi
pengangkutan barang, masyarakat menggunakan moda transportasi ini untuk
mengangkut potensi alam berupa hasil perkebunan, pertanian, dan hasil perikanan.
Sebagai alat mengangkut manusia, moda transportasi ini melayani kegiatan
mobilitas penduduk antar daerah utamanya yang berada di daerah
pesisir/pedalaman.
2. Moda Angkutan Air
Berbicara tentang moda angkutan air, bentuknya beragam mulai dari
perahu, dayung sederhana, rakit hingga kapal dengan daya angkut yang besar.
Berbagai jenis kapal juga berbeda dari aspek pemanfaatannya. Misalnya ada yang
difungsikan Kapal dirancang dengan bentuk yang beragam sesuai dengan
kebutuhan; tanker, kapal perang, pengangkut penumpang, pesiar, hingga moda
transportasi umum. Bagi kapal yang difungsikan sebagai pengangkut barang.
Transportasi khusunya moda angkutan air di Kalimantan Selatan masih memegang
peranan penting. Kapal memiliki daya angkut besar.
Demikian, secara lansgung berimplikasi pada penentuan satuan biaya aspek
perdagangan. Oleh karena itu, kapal menjadi satu-satunya moda transportasi murah
yang bisa mengangkut barang dengan kapasitas besar. Lamanya waktu yang
19
ditempuh pada angkutan air sehingga barang yang dibawa acapkali barang yang
tidak cepat busuk. Pengangkutan dengan memanfaatkan jalur air efisien bagi lalu
lintas hubungan antar tempat (misalnya pemukiman) yang tidak terhubung jalur
darat. Hal ini sejalan dengan kondisi geografis wilayah Indonesia umumnya dan
Kalimantan khususnya yang berpusat pada jalur air sebagai alternatif jalur
transportasi.
20
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Pendekatan kualitatif dipilih untuk menjabarkan eksistensi pembuatan
Jukung di Pulau Sewangi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ketika
diguanakan oleh peneliti untuk mengeksplor fenomena yang harus dideskripsikan
atau dengan kata lain tidak dapat di kuantifikasi. Misalkan seperti proses kerja,
sebuah formula, karaketrisik maupun sebuah konsep tentang objek yang dikaji
(Satori, 2011). Penelitian kualitatif juga dikenal dengan istilah pendekatan yang
berhubungan kaidah filsafat postpositivisme. Filsafat postpositivisme digunakan
untuk memberikan kajian deskriptif berkenaan kondisi latar alamiah. Perihal
dimaksud memposisikan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2014).
Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan mendeskripsikan sebuah fenomena
yang sifatnya alamiah. Namun, seringkali juga terdapat satu situasi rekayasa
manusia yang berkaitan dengan karakteristik, kualitas, maupun kegiatan. Penelitian
deskriptif memiliki titik tolak kaidah anti perlakuan, manipulasi maupun
pengubahan terhadap variable penelitian. Variabel penelitian dikondisikan sebagai
suatu gambaran peristiwa yang dikonstruksi (Sukmadinata, 2011).
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang
bertujuan untuk memperoleh data dengan penekanan pada latar ilmiah dan
menekankan pada penafsiran makna. Peneliti memilih metode penelitian deskriptif
kualitatif karena penelitian ini mengeksplor eksistensi usaha pembuatan jukung di
Pulau Sewangi di Alalak, Kabupaten Baritokuala. Eksplorasi dalam bentuk
21
deskripsi direncanakan secara sistematis dan holistik. Dengan demikian,
pemaknaan setiap peristiwa yang muncul dari masyarakat yang menggeluti
pembuatan jukung tersampaikan baik.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan Pulau Sewangi di Alalak, Kabupaten Baritokuala,
Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh Pulau Sewangi
menjadi pusat pembuatan jukung khas Kalimantan Selatan.
C. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada 2 8 November s.d. 7 Desember 2019. Namun,
penelitian diperpanjang pada 10 s.d. 14 Desember 2019. Kemudian, dirampungkan
pelaporan hingga akhir Desember 2019.
D. Subjek Penelitian
Istilah populasi tidak familiar dalam kaidah penelitian kualitatif. Perihal
tersebut penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu pada situasi sosial. Oleh
karena itu, istilah populasi diubah social situation. Situasi sosial terdiri dari tiga
elemen berbeda, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Ketiganya berinteraksi
sinergis (Moleong, 2004; Nazir, 2009). Berkenaan dengan sampel diistilahkan
dengan narasumber, atau partisipan. Tentunya, penentuan sampel tidak dilakukan
dengan mekanisme statistik tetapi dengan teknik purposive (Nasution, 2003).
Subjek penelitian adalah pengusaha, pengrajin jukung, serta masyarakat di Pulau
Sewangi di Alalak, Kabupaten Baritokuala. Pemilihan subjek didasari oleh
klasifikasi narasumber sebagai sumber data primer maupun sekunder. Di samping
22
itu, narasumber bersifat acak untuk mencapai representatif sumber. Selama
penelitian, subjek penelitian dipaparkan sebagai berikut;
Tabel 2. Daftar Nama Narasumber
No Nama Umur Pekerjaan
1 Paijam 50 tahun Buruh Pengrajin Jukung
2 Imran 50 tahun Pengrajin Jukung
3 Yusuf 58 tahun Pengrajin Jukung
4 Mas’Ud 45 tahun Pengusaha Jukung
5 Ahmad Sanusi 59 tahun Mantan Pengrajin Jukung
6 Akhmad Arsyad 43 tahun Pengrajin Jukung
7 H. Midi 46 tahun Kepala RT 18 (Pengrajin Jukung)
8 Subandi 51 tahun Pengrajin Jukung
9 Rahmat 51 tahun Pengrajin Jukung
10 Suryanata 50 tahun Pengrajin Jukung
Sumber: Peneliti (Desember 2019)
E. Teknik Pengumpulan Data
Data merupakan komponen penting dalam suatu penelitian. Bagi peneliti
data adalah kunci terhadap informasi yang ingin dikaji. Dalam tradisi penelitian
kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga langkah. Pengumpulan
data dilakukan untuk melihat tingkat kejenuhan. Sehingga, karakteristik data tidak
mengalami perubahan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:
1. Observasi
Observasi merupakan kegiatan mendasar yang bersifat non-tes. Observasi
menitikberatkan aktivitas pada pengamatan terhadap lokasi penelitian, aktivitas
masyarakat, pola perilaku. Pencatatan dilakukan secara mendetail. Sehingga narasi
disajikan jelas dan terstruktur berdasarkan peristiwa. Observasi memiliki peran
penting dalam penelitian karena memiliki kemampuan menentukan faktor awal
perilaku individu yang diamati. Observasi dilakukan tanpa merubah latar alamiah
di lokasi penelitian. Hal ini berkenaan dengan keadaan sehari-hari. Berdasarkan
23
hasil observasi didapati bahwa Pulau Sewangi merupakan bagian dari Pulau Alalak
yang mengharuskan penduduk maupun pengunjung untuk mencapainya dengan
menyeberangi menggunakan kapal fery (angkutan) masyarakat.
2. Wawancara
Wawancara merupakan aktivitas pencarian informasi (data) dengan tanya
jawab kepada narasumber. Tanya jawab dilakukan secara langsung dan tidak boleh
diwakilkan oleh orang lain. Aktivitas ini memposisikan peneliti untuk melihat
ekspresi narasumber. Demikian data yang dapat jauh lebih bermakna. Wawancara
dilakukan dengan pedoman sehingga pertanyaan terstruktur. Teknik yang
dilakukan adalah in-depth interview. Oleh karena itu, informasi yang didapat
mendalam dan holistik. Jumlah narasumber yang dilibat untuk mendapatkan
data lisan adalah kesepuluh orang. Kesepuluh orang merupakan pengrajin
jukung di Pulau Sewangi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi atau yang dikenal dengan istilah studi dokumentasi dilakukan
untuk menjawab sisa informasi melalui benda-benda yang berhubungan dengan
penelitian. Kebendaan yang dimaksud berkenaan dengan hasil dokumentasi berupa
jurnal, koran, video recorder, surat keputusan, foto dan sebagainya. Keseluruhan
data digunakan untuk mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian
suatu kejadian (Burhan, 2001). Berdasarkan hasil dokumentasi didapati data yang
diambil dari profil desa Pulau Sewangi. Dokumen tersebut diberikan oleh
sekretaris desa Pulau Sewangi di Alalak, Barito Kuala. Di samping itu, untuk
24
melengkapi pelaporan dokumentasi juga disajikan dalam bentuk voice dan video
recorder, serta foto.
F. Instrumen Penelitian
Bogdan dan Biklen (Satori, 2011) menyatakan bahwa Qualitative research
has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key
instrument. Artinya, penelitian kualitatif memiliki setting alamiah sebagai sumber
langsung. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti diposisikan sebagai pengumpul data
utama. Tidak perwakilan maupun pergantian fungsi peneliti di penelitian
kualitatif. Peneliti melakukan semua aktivitas penelitian sedari perumusan
masalah, eksplorasi data, hingga uji keabsahan data (Sugiyono, 2014).
Panduan pelaksanaan dibuat oleh peneliti untuk teknik pengumpulan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan uji validasi data
yang disesuaikan dengan l.ingkungan penelitian. Peneliti kemudia, memberikan
modal pemahaman untuk membuka penguasaan wawasan terhadap bidang yanag
diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Walaupun penelitian
kualitatif cenderung memunculkan subjektifitas pada penelitian. Akan tetapi,
peneliti dapat memberikan filtrasi dengan analisis dan perbandingan teori atas
temuan penelitian. Sehingga penelitian kualitatif yang memposisikan peneliti
sebagai human instrument bernilai ilmiah.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data dengan
kaidah sistematis. Artinya tidak ada tahapan yang tertukar dalam proses
penelitian. Demikian, dilakukan kategorisasi guna memberikan jabaran unit.
25
Setiap jabaran unit kategori digunakan untuk memberikan perlakukan sintesa
penelitian sehingga tersusun dalam kerangka yang konstruktif. Analisis data
dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah
selesai di lapangan.
Analisis data digunakan dengan model Miles dan Huberman (1992). Model
ini dikenal dengan model interaktif yang dengan tiga langkah, yaitu;
1. Data Reduction (Reduksi data) sebagai pemilihan, penyederhanaan,
pemusatan fokus perhatian, abstraksi hingga transformasi data kasar.
Keseluruhan hasil ini merupakan bentuk penyederhanaan terhadap ragam
data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Adapun pengurangan data dilakukan berdasarkan data yang didapat dari
profil desa Pulau Sewangi. Hal ini dilakukan untuk memberikan fokus
deskripsi penelitian.
2. Data Display (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi (data)
disusun dalam bentuk uraian bersifat deskriptif, di samping itu juga tersaji
dalam bentuk foto, bagan, tabel, grafik, dan sejenisnya. Penyajian data
dimaksudkan untuk data terorganisasikan sehingga mudah dimengerti.
Namun, penyajian data lebih difokuskan pada narasi dan foto.
3. Conclusion Drawing atau Verification (Simpulan atau verifikasi),
merupakan aktivitas Penarikan kesimpulan dimaknai sebagai kegiatan
interpretasi data. Interpretasi data adalah proses penemuan makna dari
data yang dihasilkan. Pengertian analisis data kualitatif merupakan
kegiatan berlanjut, berulang dan terus-menerus. Demikian, patut
26
dipahami bahwa aktivitas analisis data tidak terhenti pada satu data.
Melainkan diperlukan ketekunan untuk terus melihat segala kemungkinan
dari data penelitian. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada
tahap awal didukung oleh bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali
ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang di kemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel (Nawawi, 2003; Nasution, 2003).
H. Pemeriksaan Keabsahan Data
Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini
didasarkan pada kriteria. Penelitian kualitatif seringkali diasumsikan melihat
kebenaran disudut subjektif. Namun, idealnya pendekatan penelitian, kualititatif
memiliki mengungkap kebenaran secara objektif. Keabsahan data dalam sebuah
penelitian kualitatif adalah hal yang pasti. Keabsahan data mampu mengukur
tingkat kredibilitas (kepercayaan) penelitian yang tercapai. Pemenuhan keabsahan
data penelitian ini dilakukan beberapa langkah, seperti: pengecekkan kembali,
perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan
keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi (Moleong, 2004).
Pertama, triangulasi sumber dipilih untuk melakukan uji kredibilitas data
dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan,
triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data melalui kroscek data dari
ragam sumber yang didapat. Triangulasi teknik digunakan oleh peneliti setelah
mendapatkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari ketiga teknik
tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah kesimpulan terkait eksistensi usaha
pembuatan jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Baritokuala.
27
Kedua, Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian yaitu dengan
menggunakan triangulasi. Triangulasi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding data (Mulyana, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua
jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Ketiga, triangulasi waktu, untuk melihat bahwa tidak ada perubahan data
lisan yang diberikan oleh narasumber. Peneliti melakukan wawancara di pagi hari
pada 7 Desember 2019. Jawaban yang diberikan cenderung jelas karena narasumber
antusias. Oleh karena itu, data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu
dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan
pengecekkan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau
situasi yang berbeda. Dan bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka
dilakukan secara berulang-ulang sehingga samapi ditemukan kepastian datanya.
Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim
peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Namun, data yang
diambil hanya data yang sama (jenuh).
28
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Desa Pulau Sewangi, Alalak, Barito Kuala
1. Sejarah Desa
Berdasrkan cerita orang atau tertua masyarakat menyatakan bahwa awalnya
Desa Pulau Sewangi ini merupakan bagian dari Desa Pulau Alalak, namun adanya
pertambahan penduduk dan pembangunan diwilayah ini dengan menjadikan
wilayahnya tersendiri. Oleh karena itu, sekitar tahun 1975 desa Pulau Alalak dibagi
menjadi Tiga Desa, satu dari tiga Desa itu termasuk Desa Pulau Sewangi. Desa
Pulau Sewangi adalah sebuah desa yang terletak digugusan sungai Barito dan
mempunyai luas hamparan wilayah 55 Ha terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT).
Desa Pulau Sewangi sejak awal berdirinya secara definitif, pernah dipimpin oleh:
a. Bapak H. Ali Baderun.
b. Bapak Marhan Abdi (2004 s/d 2009 )
c. Bapak Achmad Noor ( 2009 s/d 2014 )
d. Bapak Husaini ( Pjs Kepala Desa Pulau Sewangi Tahun 2014 s/d 2015 )
e. Bapak Said Hairuddin (Kepala Desa tahun 2015 saampai Sekarang)
2. Sumber Daya Alam
Desa Pulau Sewangi merupakan satu desa di Kecamatan Alalak Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, memilik luas 55 km2. Secara geografis
Desa Pulau Sewangi memiliki batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Pulau Sugara.
b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pulau Alalak.
29
c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Alalak.
d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai Barito.
Jarak antar Ibu Kota dengan Kota Kecamatan ± 15 Km, dapat ditempuh
melalui jalan darat dengn berbagai jenis kendaraan. Ketinggian Desa Pulau
Sewangi antara 0 – 0,20 m dari permukan laut dan kemiringan tanah 0,00% (data),
kondisi daerah berawa-rawa yang dipengruhi oleh pasang surut air laut yang
berpengaruh langsung terhadap Sungai Barito yang mana penduduk desa sebagian
bermukim di daerah pesisir sungai. Wilayah Desa Pulau Sewangi di tengah Sungai
Barito. Melihat kondisi yang terjadi pada saat ini umumnya penduduk berorientasi
ke sungai karena aliran sungai merupakan suatu potensi air yang cukup besar untuk
memenuhi kebutuhan penduduk dan perhubungan/transportasi. Ditinjau dari letak
geografisnya Desa Pulau Sewangi merupakan daerah beriklim tropis. Desa Pulau
Sewangi dipengaruhi oleh musim hujan yang terjadi pada bulan November sampai
April dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Berasarkan data
pengukuran curah hujan, Desa Pulau Sewangi mempunyai curah hujan 976
mm/tahun. Suhu udara rata-rata 30°C, suhu udara terendah 22°C dan suhu tertinggi
33°C dengan kelembaban udara 40% - 100%.
3. Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk Desa Pulau Sewangi berdasarkan Profil Desa tahun 2016
sebanyak 2678 jiwa yang terdiri dari 1.424 laki laki dan 1.358 perempuan. Sumber
penghasilan utama penduduk dari sektor pertanian dan peragangan. Jumlah
Kepadatan Penduduk didesa Pulau Sewangi bisa dilihat pada tabel 4.
30
Tabel 3. Jumlah penduduk berasarkan jenis kelamin Desa Pulau Sewangi
Desa Laki-laki Perempuan Jumlah
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Pulau
Sewangi
1.424
50,5%
1.358
49,5%
2.782
Sumber; Data Profil Desa 2018
a. Letak, Luas wilayah dan Jumlah Kepadatan Penduduk
Jumlah penduduk pada tahun 2016 di Desa Pulau Sewangi sebanyak 2.782
jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat diliht
pada tabel 6 di bawah ini:
Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Pulau Sewangi
Desa
Kependudukan
Jumlah Penduduk Luas Wilayah (Ha) Kepadatan (jiwa/ Ha)
Pulau Sewangi 2.782 jiwa 55 Ha 0,45
Sumber; Data Profil Desa 2018
b. Keadaan Sosial-Ekonomi Penduduk Desa Pulau Sewangi
Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Desa Pulau Sewangi dapat dilihat
pada tabel 8 dibawah:
Tabel 5. Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pulau Sewangi
Tingkat Pendidikan Jumlah
Belum Sekolah 351
Tidak Tamat SD 457
Tamat SD 820
Tamat SMP 530
Tamat SMA 359
Tamat Akademi 50
31
Tamat Strata Satu 35
Sumber; Data Profil Desa 2018
Sumber penghasilan utama di Desa Pulau Sewangi adalah sangat bervariasi,
penghasilan utama adalah disektor pertanian, buruh, maupun jasa pemerintahan dan
sektor perdagangan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :
Tabel 6. Jumlah penduduk menurut pekerjaan rumah tangga
No Jenis Pekerjaan Jumlah Tenaga Kerja
(Jiwa)
Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.
PNS;
TNI/Polri;
Pedagang;
Buruh;
Tukang, Petani, lain-lain
16
400
753
168
950
0,6
17,4
34
7
41
Jumlah 100
Sumber; Data Profil Desa 2018
Berdasarkan paparan data di atas, ilihat bahwa perkejaan sebagai tukang,
petani mendominasi. Hal ini sejalan dengan berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan bahwa penghasilan utama sebagai tukang merujuk kepada profesi
pengrajin jukung. Profesi familiar bagi masyarakat karena diwariskan turun –
temurun. Dimulai dengan pekerjaan yang digeluti oleh para orang tua terdahulu.
Demikian menjadi tolak ukur eksistensi pembuatan jukung di Pulau Sewangi.
A. Tahapan pembuatan jukung oleh pengrajin di Pulau Sewangi, Alalak,
Baritokuala
Setiap pembuatan moda transportasi diperlukan waktu pengerjaan. Perihal
ini memerlukan waktu yang beragam tanpa terkecuali pembuatan jukung.
Umumnya, pembuatan jukung memerlukan waktu 2 – 3 minggu. Hal ini sangat
tergantung pada panjang dari body jukung. Berdasarkan hasil wawancara menurut
Arsyad (43) 2 Desember 2019:
32
“Ulun dalam 2 - 3 minggu itu bisa aja meulah sebuah jukung, tetapi itu
tergantung panjang body jukung nang handak diolah. Amun jukung
Pajang Ampat (panjang 8m) bisa aja ulun menuntungakannya 2 minggu,
amun nang jukung Pajang Tujuh (panjang 12m) biasanya ulun
menuntungkannya 3-4 minggu (Saya dalam 2-3 minggu mampu
membuat satu jukung, tetapi tergantung dari panjang body jukung yang
dibuat. Apabila jukung Pajang empat (panjang 8m) mampu diselesaikan
2 minggu, apabila yang jukung Pajang Tujuh (panjang 12m) biasanya
diselesaikan 3-4 minggu).
Paparan Arsyad memberikan gambaran bahwa pembuatan jukung
memerlukan keterampilan. Keterampilan berbeda untuk pembuatan jukung dengan
panjang yang berbeda pada bagian body. Namun, pada tahapan pembuatan jukung
dilewati tiga langkah utama, sebagai berikut:
1. Persiapan
Persiapan merupakan tahapan pertama dalam pembuatan. Tahapan
persiapan memerlukan perhatian pada perlengkapan dan pemilihan bahan baku.
Disampaikan bahwa peralatan yang digunakan adalah peralatan dasar milik
pengrajin. Berdasarkan hasil wawancara berikut peralatan yang disiapkan:
a. Baji, digunakan untuk membelah kayu bulat yang dijadikan jukung pada
krongkong. Kayu yang digunakan adalah kayu meranti, kayu balau, kayu
cangal, kayu lanan biru, kayu ulin, kayu balangeran (keseluruhan
termasuk pada keluarga Shorea). Baji tersebut digunakan manakala kayu
berwujud kronkong. Krongkong pada dasarnya memerlukan penipisan
pada bagian cekungan. Namun, teknik yang dilakukan untuk
memberikan kemudahan pada penipisan adalah dengan membakar
krongkong. Perihal tersebut dimaksudkan agar kayu lebih lentur dan
mudah dibentuk.
33
b. Bor, digunakan untuk membuat lubang pada jukung dengan jumlah
lubangan 5-7 per papan. Pada pembuatan jukung, lubang membantu
menyambung setiap papan agar menyatu hingga utuh menjadi body yang
diinginkan.
c. Gergaji, digunakan untuk memotong dan membuat kelengkapan pada
proses pembuatan jukung. Potongan itu gunakan untuk menyambung
kayu yang ada di krongkong. Potongan tersebut dilakukan tergantung
dari ukuran jukung yang akan dibuat.
d. Katam atau serut, digunakan untuk meratakan atau menghaluskan body
pada kronkong. Prosesnya hampir sama dengan baji, yang membedakan
adalah untuk penggunaan katam dibagian body kronkong sedangkan
untuk baji dibagian bulatan kronkong. Dokumentasi berkenaan dengan
penipisan kayu menggunakan katam bisa dilihat pada gambar I di bagian
lampiran dokumentasi.
e. Penggodam, digunakan menancapkan baji ketika ingin membelah kayu
bulat. Penggodam sendiri yaitu sejenis palu besar, yang mana prosesnya
itu adalah ketika baji telah ditancapkan ke krongkong kemudian baji
tersebut dipukul menggunakan penggodam.
Kelima peralatan yang disebutkan di atas merupakan peralatan dasar yang
harus dimiliki dan dikuasai penggunaannya oleh pengrajin. Selanjutnya tahapan
persiapan pada bagian bahan baku. Bahan baku yang digunakan oleh pengrajin
lazimnya terdapat lima jenis. Kelima jenis kayu yang digunakan masuk pada jenis
kayu Shorea. Kayu jenis Shorea familiar diantara pengrajin karena komuditas yang
34
mudah ditemui. Kayu jenis Shorea juga ramah bagi kepentingan industri. Berikut
paparan lengkap penggunakan bahan baku:
a. Kayu Balangeran
Kayu Balangeran yang mempunyai nama ilmiah Shorea Balangeran
adalah jenis kayu komersil yang tumbuh ditanah rawa gambut yang
mempunyai pertumbuhan relatif lebih cepat dibandingan jenis-jenis
tumbuhan rawa gambut yang lainnya. Dapat tumbuh mencapai tinggi
pohon 20-25 m, mempunyai batang bebas cabang 15 m, diameter dapat
mencapai 50 cm, tebal kuliatnya 1-3 cm. Kayu Balangeran tergolong
kelas kuat II dan berat jenis 0,86.
b. Kayu Balau
Kayu Balau yang mempunyai nama ilmiah Shorea Lavefolia
memiliki tinggi 40 meter dengan diameter rata-rata adalah 70-90 cm,
keras batangnya antara 880-990 kg/m3, kayunya tergolong kelas awet I
dan kelas kuat I-II.
c. Kayu Cengal
Kayu cengal yang mempunyai nama ilmiah Hopea Sangal Korth
memiliki tinggi 50 meter, panjang batang bebas cabang 15-35 m,
diameternya sampai 120 cm berada pada golongan kelas awet II-III dan
kelas kuat II-III.
d. Kayu Meranti
Kayu Meranti yang mempunyai nama ilmiah Shorea termasuk jenis
kayu keras yang mempunyai kelas awet III, IV dan kelas kuat II, IV yang
35
memiliki ketinggian mencapai 50 dengan diameter bisa mencapai 100
cm, tumbuh di hutan Kalimantan.
e. Kayu Ulin
Kayu Ulin mempunyai nama ilmiah Eusideroxylon zwageri T et B
yang tergolong sebagai kayu sangat berat dan paling awet di dunia yang
memiliki tinggi 50 meter dan diamater batang mencapai 120 cm, berada
pada kelas awet I dan kelas kuat I.
2. Tahapan Pembuatan
Tahapan pembuatan ditentukan oleh bentuk dasar yakni krongkong.
Sebagaimana dipaparkan pada bagian persiapan. Krongkong yang sudah dibentuk
menggunakan katam selanjutnya memasuki tahapan yang jauh lebih rumit yakni
memasang kayu pada bagian body hingga utuh. Namun, krongkong merupakan
bahan yang tidak tersedia secara langsung di Pulau Sewangi. Sehingga diperlukan
pemesanan krongkong sebagai langkah pertama di tahapan pembuatan. Pemesanan
krongkong sebagai body dasar pembuatan jukung di daerah Manusap, Kabupaten
Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Krongkong tersebut awalnya masih berupa
gelondongan kayu yang kemudian dibakar (dibanam) selama sekitar dua jam agar
memuai dan terbuka sehingga tidak lagi keras. Proses tersebut dilakukan supaya
mempermudah ketika di katam pada body krongkong.
Jenis kayu yang dibuat menjadi kronkong adalah jenis kayu yang telah
dipaparkan diatas yang nantinya krongkong tersebut perlu ditipiskan pula dibagian
tengahnya dengan alat baji dan penggodam. Harga krongkong di daerah Manusap
36
bervariasi tergantung dari jenis kayu yang digunakan, hal demikian disampaikan
oleh Bapak Waga (40) 7 Desember 2019:
“Harga krongkong nang ditukari oleh pengrajin di Desa Sewangi ini
bervariasi, tergantung dari jenis kayu apa nang handak bebuahannya
pakai, nang rancak bebuahannya tukari nang jenis kayu klepek/balau
ukurannya nang 6 meter harganya itu 4 juta, untuk nang ukuran 9 meter
harganya itu 9 juta, nang larang itu jenis kayu cengal nang sampai 14
juta dengan ukuran 9 meter (Harga krongkong dibeli oleh pengrajin di
Desa Sewangi ini bervariasi, tergantung dari jenis yang dipakai. Tetapi,
seringkali yang dibeli jenis kayu klepek/balau Untuk ukuran 6 meter
harganya 4 juta, sedangkan ukuran 9 meter harganya 9 juta. Namun, jenis
kayu yang mahal adalah kayu cengal yakni 14 juta dengan ukuran 9
meter)
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk harga kronkong yang
dibeli oleh pengrajin bervariasi, tergantung dari pengrajin mau beli krongkong yang
jenis kayunya seperti apa. Kemudian, harga krongkong dapat menentukan harga
jukung. Hal ini dikarenakan krongkong menjadi bahan dasar utama sebagaimana
dipaparkan oleh pengrajin. Tahapan kedua yang dilakukan oleh pengrajin adalah
memasang apak pada krongkong agar dapat menyeimbangkan jukung. Berikut
tampilan apak pada jukung.
37
Gambar 1. Apak Pada Jukung
Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)
Pemasangan apak dilakukan dengan menggunakan bor dibagian sisi kanan,
tengah dan kiri. Setelah itu dipasangkan sampung pada bagian depan dan belakang
kerongkong untuk memudahkan pemasangan papan pada jukung dengan
menggunakan bor. Pemasangan pasak surui pada bagian kerongkong perlu di bor
terlebih dahulu agar bisa menyambungkan antar papan dengan kerongkong. Pasak
surai terbuat dari kayu ulin. Setelah pasak surui tersambung dengan kronkong
kemudian bagian atas pasak surui diruncingkan kemudian diolesi dengan lumuh
atau bisa menggunakan kulit galam agar dapat merekat dan tidak ada celah antar
papan. Proses penyambungan antar papan diperlukan dua orang untuk memegang
papan dan memukul agar papan tersambung serta menyatu dengan pasak yang telah
diruncingkan, alat yang digunakan untuk memukul adalah godam. Tahap terakhir
38
pembuatan jukung adalah papan yang sudah terpasang diberikan kayu penahan agar
bentuknya melengkung. Setelah itu, kayu penahan di lepaskan dan dipasang tajak
yang di sambungkan ke apak untuk menjaga kesimbangan jukung pada saat
digunakan.
3. Finalisasi
Setelah jukung terbentuk, tahap finalisasinya adalah diberikan lantai pada
bagian dalam jukung dan kemudian di cat. Tahapan ini tidak memerlukan waktu
lama sekitaran 2-3 hari. Secara khusus proses pengecatan tergantung pada kondisi
cuaca di daerah setempat. Jika jukung sudah berbentuk utuh maka pengrajin mulai
memasarkan.Pemasaran dilakukan hanya dengan memajang di halaman rumah atau
melalui media sosial; instagram, facebook maupun what’s up (lihat lampiran
dokumentasi gambar II). Namun, jika jukung ingin diberikan mesin, maka
pada bagian belakang (sampung) diberi papan atau yang lebih dikenal dengan nama
dek untuk meletakkan mesin jukung papan sebutannya bukan jukung lagi
melainnkan klotok.
B. Deskripsi usaha jukung di Pulau Sewangi, Alalak, Barito kuala
1. Jenis Jukung Di Pulau Sewangi
Jukung merupakan alat transportasi air yang sering digunakan masyarakat
sebelum adanya kapal besar dan jalur darat. Melalui tahapan perkembangan zaman
modern dengan munculnya teknologi yang semakin maju, jukung-jukung jenis
tertentu dalam batas-batas tertentu pula masih sanggup bertahan. Sudah sejak lama
jukung Banjar beroperasi di perairan sungai-sungai Kalimantan Selatan dalam
berbagai fungsi. Jukung sebagai alat transportasi, untuk berjualan atau berdagang,
39
mencari ikan, menambang pasir dan batu, mengangkut hasil pertanian, angkutan
barang dan orang dan jasa lain-lain.
Dari berbagai jenis jukung Banjar menurut fungsinya sebagaimana
diuraikan maka sarana ini beroperasi di beberapa alur sungai-sungai Barito,
Martapura, Riam, Nagara, Amandit atau Tabalong dari masa ke masa. Sebagian di
antaranya sudah tidak berfungsi lagi, antara lain karena terdesak oleh adanya kapal-
kapal besar dan kecil yang beroperasi di sungai, adanya speed boat serta
dibangunnya prasarana jalan dan jembatan yang bisa dilewati oleh kendaraan roda
dua maupun roda empat. Sampai kapan dan sejauh mana jukung-jukung Banjar itu
dapat bertahan dalam eksistensinya, agaknya sukar untuk diramalkan dengan pasti.
Namun jukung Banjar tersebut telah memperkaya prasarana daerah ini dalam arti
aset budaya daerah Banjar.
Jukung adalah sebutan untuk perahu tradisional khas Banjar. Dahulu jukung
mempunyai peranan penting bagi masyarakat daerah Banjar, tapi sekarang budaya
jukung semakin memudar dan diabaikan oleh masyarakat Kalimantan itu sendiri.
Ini disebabkan karena pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat
pesat pada alat transportasi darat dan udara sehingga alat transportasi tradisional
seperti jukung kurang diminati dan tidak mampu bersaing lagi dengan alat
transportasi darat dan udara.
Banjar yang dikenal sebuah pulau dengan seribu sungai sudah barang tentu
mengenal jukung. Sekarang ini, dibanding angkutan umum di darat, betapa sulitnya
menunggu taksi kelotok yang reguler mengangkut penumpang terutama sore hingga
menjelang petang hari. Jauh ke belakang dalam sejarah Banjar tempo dulu, saat
40
jukung (kini menjadi prototip kelotok) banyak berseliweran di sungai, tentu tidak
sesulit sekarang. Minimnya akses darat membuat jukung menjadi alat transportasi
penting kala itu. Bahkan lebih jauh lagi sebelum ‘lahirnya’ suku Banjar, jukung
telah digunakan sebagai alat transportasi penting dalam penyebaran penduduk dari
pesisir menuju pedalaman Kalimantan. Seorang Denmark yang menjadi urang
Banjar, Erik Petersen (kini almarhum), banyak meneliti masalah jukung.
Dalam konteks historis, jukung berkembang sebagai tanda perkembangan
budaya banjar sejak jaman Daha di Nagara. Harmoni dan kearifan hidup dengan
alam khususnya sungai yang tidak terasa lagi saat sekarang. Orang dulu memelihara
sungai karena digunakan untuk jalan bepergian dengan jukung. Jukung sekarang
mulai dipinggirkan dan terbukti kelestarian sungai menjadi terabaikan. Lantas
apakah orang diajak kembali menggunakan jukung? Tidak harus begitu, hanya
menegaskan bahwa dengan mengangkat kembali nilai budaya sungai yang positif
berarti juga turut mengembalikan sungai ke fungsi sesungguhnya. Aneh jika
jukung sebagai satu budaya sungai, pusaka warisan nenek moyang yang
menyimpan kekayaan kearifan tidak ternilai justru dianggap biasa oleh masyarakat
Banjar.
Jukung Banjar mempunyai bermacam-macam jenis Jukung tetapi disini
saya akan memberikan penjelasan salah satu jukung saja agar tidak terjadi salah
paham atau pengertian yang pada umumnya yaitu Jukung Sudur karena Jukung ini
yang paling tua. Jukung Sudur terdiri dari satu potongan kayu, dipotong dari
setengah belahan batang pohon dan lebarnya tidak melebihi pembakaran. Menjadi
sebuah konstruksi sederhana dengan pasti sebuah kapal yang bisa dibangun dengan
41
peralatan batu, kapak, beliung, ganjal, dan (untuk sebuah lubang di dalam
konstruksi) sebuah pahatan.
Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang bentuknya ceper dengan
konstruksi yang sederhana, biasanya digerakkan oleh galah lebar dan digunakan
untuk memancing. Sekarang ini ukuran normal Jukung Sudur adalah 6-7 meter,
lebar 60-70 cm, dan dalamnya 20-25 cm. Tetapi di Museum Lambung Mangkurat
Banjarbaru kita dapat melihat Jukung Sudur tua yang panjangnya 15 meter. Jukung
Sudur asli terbuat dari sebuah potongan kayu, dengan tidak adanya tambahan
konstruksi lain. Meskipun begitu ada yang berbeda dari Jukung Sudur, dimana satu
papan ditambahkan di haluan dan buritan belakang kapal, yang sering disebut
Jukung Bakapih. Jukung Sudur merupakan perahu yang ideal untuk berada di
tempat yang dangkal, dimana konstruksinya yang ceper, memudahkan untuk
mengapung pada air ke dalaman 1 cm, digunakan untuk memancing.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama dua minggu di Pulau
Sewangi jenis jukung yang dibuat, seperti; jukung sudur, jukung patai dan jukung
batambit. Kayu yang digunakan untuk membuat jukung adalah kayu lokal yang
diambil dari hutan di wilayah Kalimantan Tengah. Awalnya bahan baku adalah
kayu ulin dan kayu cangal. Namun, komuditas tersebut jarang ditemui. Oleh karena
itu, kekuatan. Jukung maksimal 5-7 tahun karena terbuat bahan kayu kelepek, kayu
madi hirang, kayu lanan biru, dan kayu kasak.
Secara umum, pengrajin menunggu datangnya kerangka atau kerongkong
jukung yang sudah jadi ke para pengrajin jukung di Pulau Sewangi. Peralatan yang
digunakan masih menggunakan alat tradisional seperti balayung atau beliung yaitu
42
jenis kapak yang matanya melintang atau tidak searah dengan tangkainya, parang
pambalokan digunakan untuk menebang dan membentuk dasar jukung serta untuk
melubang badan jukung, katam atau serut digunakan untuk meratakan atau
menghaluskan permukaan bentuk dasar jukung, mal atau pola digunakan untuk
membentuk badan jukung secara keseluruhan, terutama pada bagian haluan dan
bagian belakang jukung, gergaji digunakan pada tahap penyelesaian akhir
pembuatan jukung yakni untuk memotong bagian yang tidak diperlukan dan juga
untuk memotong perlengkapan jukung lainnya, bor dan pahat putar digunakan
untuk merekatkan dan mengikat bagian jukung sehingga menyatu dengan kuat, baji
yaitu kayu yang telah dipotong kecil untuk digunakan membelah kayu bulat,
penggodam yaitu sejenis palu besar yang digunakan untuk menancapkan baji pada
kayu bulat yang akan dibelah.
2. Profil Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pembuatan Jukung di Pulau Sewangi
Pulau Sewangi, Alalak, Barito Kuala dikenal sebagai sentra penghasil moda
transportasi air yakni jukung. Di Desa ini, jukung menjadi produk utama yang
dihasilkan oleh penduduk. Hal in dikarenakan mayoritas pekerjaan mereka adalah
pengrajin jukung. Adapun pekerjaan lain yang digeluti adalah berdagang dan
bertani. Usaha pembuatan jukung tidak bersinar hal ini dilatarbelakangi oleh
sulitnya bahan baku serta bergesernya budaya masyarakat dari budaya sungai
menjadi budaya darat. Pembangunan jalan dan jembatan Berangas yang
menghubungkan Pulau Sewangi dengan daratan utama di Berangas, Kecamatan
Alalak, membuat kualitas hidup masyarakat meningkat karena mudahnya akses ke
43
pusat pemerintahan, sekolah dan sarana publik lainnya. Namun, pembangunan itu
berdampak pada keberlangsungan usaha pembuatan jukung.
Di tahun 2019, terdapat sebagian kecil saja perajin yang masih bertahan.
Satu diantaranya adalah Ketua Rt. 18 sekaligus pengrajin jukung H. Midi berusia
46 tahun. H. Midi sudah 25 tahun lebih menekuni profesi sebagai pengrajin jukung.
Setiap hari, pekerjaan pembuatan jukung dibantu oleh satu-dua orang pekerja.
Namun, kebanyakan dikerjakan sendiri. Sebelum tahun 2000-an usaha jukung di
Pulau Sewangi ramai pembeli. Kondisi ini berbanding terbalik saat ini. Jumlah
pengrajin jukung pun turun drastis, menjadi puluhan rumah tangga saja, dari semula
ratusan rumah tangga yang bermukim di sana.
Meskipun tidak ada pesanan, jika pengrajin memiliki modal maka jukung
terus dibuat. Walaupun tidak ada kepastian apakah dalam hitungan hari pelanggan
akan datang. Sebelum tahun 2000-an, sebulan rata-rata pemesan antara lima sampai
tujuh perahu. Akan tetapi, saat ini satu unit jukung per bulan sudah dianggap rejeki
yang melimpah. Sebagai ketua RT dan pengrajin jukung, H. Midi tidak ingin beralih
mencari usaha lain yang lebih bisa diandalkan. Dirinya beralasan, selain ingin
meneruskan usaha turun-temurun keluarga, juga ingin mengembangkan budaya
bahwa warga di Pulau Sewangi memiliki keahlian membuat perahu dan jukung.
Baginya, proses pembuatan perahu atau jukung tidak memerlukan skets
terlebih dulu. Jukung dibuat dengan mengandalkan feeling dan pengalaman selama
bertahun-tahun. Adapun jenis jukung yang dibuat bermacam-macam ukuran. Ada
yang panjang empat depa atau sekitar 6 meter, ada pula panjang 6 depa atau sekitar
10 meter. Dalam pembuatan jukung bahan baku yang diperlukan kayu beberapa
44
jenis. Misalnya, untuk membuat kerongkongan atau fondasi jukung idealnya
menggunakan kayu jenis cangal. Tapi sekarang kayu jenis itu sulit didapat maka
diganti lanan, supang, mandahirang atau bangkirai (jenis meranti). Kayu ini dipilih
karena kuat dan tahan air. Bahan baku kayu ini mengandalkan suplai dari wilayah
tetangga, yakni di Kabupaten Kapuas, karena sulit didapat di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan kategorinya usaha pembuatan jukung merupakan bagian dari
Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, diperlukan
pemberdayaan UMKM sebagai isu penting dan motor penggerak pertumbuhan dan
peningkatan ekonomi daerah. Perihal ini tentunya usaha jukung memiliki peran
untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah yang ditopang kinerja UMKM yang
efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi. Guna pemberdayaan tersebut,
pemerintah idealnya mengeluarkan kebijkan untuk bersinergi antara pengrajin
jukung sebagai pelaku dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Barito Kuala untuk mempromosikan unit jukung yang dihasilkan.
3. Gotong-Royong Antar Pengrajin Jukung Di Pulau Sewangi
Kata nilai biasa digunakan untuk menunjukan sebuah ukuran atau patokan
dan biasanya dianggap sebagai sesuatu yang penting dan berharga. Namun pada
tatanan keilmuan khususnya ilmu sosiologi kata nilai diartikan berbeda. Nilai
merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu hal yang
tentang baik buruk, benar salah, patut tidak patut, hina mulia, maupun penting tidak
penting.
Sebagai sebuah konsepsi, nilai bermakna eksplisit atau implisit, yang khas
milik seseorang individu atau suatu kelompok, tentang yang seharusnya diiginkan
45
yang mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan
tujuan- tujuan tindakan. Nilai menjadi ukuran standar orang menentukan apa yang
baik dan buruk, indah dan jelek. Nilai mendasari prefensi kita, memandu pilihan
kita, dan mengindikasi apa yang kita anggap berharga dalam hidup ini nilai
berkaitan dengan standar-standar tentang sesuatu yang lebih baik atau buruk,
cantik atau jelek, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sesuai atau tidak sesuai.
Bagi masyarakat, nilai menjadi kontrol baik yang berasal dari dirinya sendiri
maupun dari orang lain. Ketika dalam kehidupan masyarakat peran hukum yang
berlaku telah sulit untuk diterapkan maka norma masyarakat turut berperan dalam
hal tersebut. Salah satunya peran nilai yang dianggap sebagai patokan atau tolak
ukur tindakan seseorang dalam bertindak pada kehidupan bermasyarakat.
Nilai sebagai konsep dapat disandingkan dengan kata lain sehingga
memunculkan makna yang lebih utuh. Adalah nilai gotong royong yang dipegang
oleh masyarakat sebagai satu aset budaya yang terus muncul dalam kehidupan
sehari-hari. Nilai gotong royong sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena
adanya bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan
kelompok sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari masyarakat. Nilai gotong
royong tidak hanya bersifat abstrak, tetapi terinternalisasi melalui aktivitas kerja
sama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu
yang dianggap berguna bagi kepentingan umum.
Gotong royong identik ditemukan pada masyarakat yang berakar pada
tradisi pertanian pedesaan atau agraris, yang disebut Eric Wolf dengan istilah
Peasant Commmunity. Tradisi pertanian mengharuskan masyarakat petani
46
untuk saling bekerja sama sejak mulai menyemai bibit, menanamnya,
merawatnya hingga mema- nennya. Gotong royong menjadi cara hidup, bertahan
hidup dan berelasi di dalam masyarakat agraris yang berbentuk masyarakat
paguyuban atau dalam istilah Ferdinand Tonnies disebut dengan masyarakat
gemein- schaf. Namun, masyarakat Pulau Sewangi yang identik dengan kehidupan
pesisir sungai memiliki nilai gotong royong yang serupa.
Di Pulau Sewangi nilai gotong royong terasa manakala sesama warga saling
membantu dan menolong antar pengrajin jukung. Tidak ada istilah kompetitor antar
pengrajin, tetapi mereka tetap mewujudkan perkerjaan melalui identitas
kebersamaan. Jukung bagi orang Banjar memiliki nilai adaptif, kedekatan dengan
alam, ekonomi, seni, dan identitas kultural. Masyarakat memiliki dan melaksanakan
tanggung jawab dalam menjaga dan kelestarian kebudayaan jukung yang telah
diwariskan dengan cara tetap menjaga karakteristik jukung pembuatannya.
Dimilikinya aktivitas gotong royong dalam kehidupan kehidupan
bermasyarakat merupakan perwujudan dari nilai gotong royong itu sendiri. Nilai
gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan masyarakat
terutama dalam upaya menggerakkan solidaritas antar pengrajin di Pulau Sewangi.
Solidaritas rentan meluntur seiring perubahan jaman, maupun berbagai hal
mengancam konflik lintas pengrajin jukung.
Bekerjanya sistem gotong royong dalam menggerakkan solidaritas sosial
pengrajin nampak pada aktivitas sehari-hari seperti saling membantu untuk
menambatkan jukung ke sungai. Walaupun jukung tersebut di beli dari orang lain.
Unik dari nilai gotong royong pengrajin jukung adalah mereka tidak perlu membuat
47
koperasi untuk menyelesaikan konflik persaingan usaha. Namun, mereka hanya
terikat oleh rasa sungkan untuk berkelahi hanya karena usaha jukung yang digeluti
berbeda jumlah pendapatan. Di samping itu, aktivitas gotong- royong dalam
konteks yang lebih sederhana dilakukan seperti; membantu jalannya hajat tetangga
(baik pernikahan, pengajian, dan seterusnya).
C. Kendala Keberlangsungan Usaha Pembuatan Jukung di Pulau Sewangi,
Alalak, Barito kuala
Lazimnya makna harfiah perkembangan, usaha jukung yang digeluti oleh
pengrajin di Pulau Sewangi, Alalak, Barito Kuala memiliki beberapa kendala.
Kendala klasik yang dialami adalah pembiayaan atau modal usaha. Namun, berbeda
dengan temuan penelitian saat ini. Usaha jukung di Pulau Sewangi memiliki tiga
kendala utama. Ketiga kendala ini dideskripsikan sebagai berikut:
1. Keterbatasan Ketersediaan Bahan Baku Kayu
Sebagaimana dipaparkan bahwa pembuatan jukung membutuhkan kayu
sebagai bahan baku utama. Kayu memiliki kebermanfaatan tinggi. Kebermanfaatan
kayu dikenal sebagai bahan konstruksi, meubel, kerajinan, bahan bakar, dan
kepentingan industri. Fokus kepada kebermanfaatan kepentingan industri jenis
kayu yang digunakan adalah kayu meranti. Kayu meranti dikenal dengan nama latin
Shorea. Kayu meranti dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan
kayu dari hutan alam lain yakni cepat tumbuh (fast growing). Kayu meranti
memiliki rotasi dek, berdiameter kecil dan memiliki sifat fisis dan elastis.
Kayu meranti dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak diimbangi dengan
ketersediaan pasokan kayu. Walaupun dikategorikan sebagai kayu fast growing
48
tetapi kayu meranti memerlukan waktu untuk tumbuh. Idealnya untuk meranti
diperlukan minimal 4-5 tahun sampai siap dimanfaatkan sebagai bahan baku utama.
Perihal ini dikarenakan untuk bahan baku juung diameter 35-50 meter. Kayu
meranti tidak tumbuh di wilayah Alalak. Oleh karena itu pengrajin harus memesan
terlebih dahulu.
Kayu meranti dipilih oleh pengrajin karena lebih murah dibandingkan kayu
ulin. Di samping itu, satu dekade terakhir ketersediaan hanya memposisikan kayu
meranti sebagai bahan baku utama. Pemesanan kayu meranti oleh pengrajin jukung
ditujukan pada daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Demikian,
diperlukan waktu 3-4 hari hanya untuk menunggu kedatangan bahan baku utama.
Perihal ini patut dimaklumi karena komuditas tersebut ditemui pada hutan tropis.
Keterbatasan pada bahan baku kayu meranti juga dikarenakan oleh
kebutuhan industri meubel. Demikian terjadi permintaan yang sama antara
pembuatan jukung dan industri meubel. Sedangkan pemenuhan komuditas didapat
dati kayu meranti kampung, bukan dari perhutani. Kayu meranti kampung adalah
kayu yang diperoleh di lahan milik penduduk dan atau tebangan bebas dari hutan.
Oleh karena itu, pengrajin hanya bisa menunggu datangnya bahan baku dari penjual
kayu di wilayah Kalteng dan Kaltim.
2. Teknik Penjualan Jukung melalui Sistem Ready Stock
Usaha jukung di Pulau Sewangi sudah ada sejak tahun 1950an. Pada saat
itu, sungai masih digandrungi oleh masyarakat khususnya aspek transportasi.
Berkenaan dengan hal tersebut maka banyak dari warga yang memesan jukung.
Popularitas Pulau Sewangi meningkat seiring dengan banyaknya pemesanan jukung
49
oleh warga. Perihal ini kemudian membuat pengrajin terbiasa untuk menjual jukung
dengan sistem ready stock (barang ada).
Istilah ready stock ramah dipemahaman karena diadopsi pada sistem belanja
online. Ready stock merupakan sistem pembelian barang dimana persediaan atau
stok barang sudah tersedia secara langsung atau sudah ada di tangan penjual tanpa
ada estimasi waktu pemesanan. Barang yang sudah dipesan dan dibayar oleh
pembeli langsung dikirimkan oleh penjual. Pengrajin jukung selalu membuat
jukung tanpa harus menunggu pesanan. Sistem ready stok membuat aktivitas
pengrajin sebagai rutinitas harian yang dijalani. Setiap hari pengrajin selalu
membuat 1-2 jukung per bulan. Walaupun tidak ada kepastian pembeli dari jukung
tersebut.
Sistem ready stock yang dilakoni oleh pengrajin mengakibatkan
keterbatasan pada jenis jukung yang dijual (khusunya besar kecil jukung). Jika
jukung yang dibuat tidak laku, maka pengrajin terpaksa menjual dengan harga
modal. Hal ini dikarenakan pengrajin tidak memiliki kepastian perputaran uang
dalam membuat jukung. Pengrajin memiliki keterbatasan wilayah pemasaran.
Pembeli hanya didominasi oleh nelayan di pesisir Takisung- Pelaihari, dan Pagatan-
Tanah Bumbu. Oleh karena itu, bagi pengrajin setiap bulannya tidak ada kepastian
berapa jukung yang bisa terjual.
3. Minimnya Pemuda Menggeluti Profesi Pengrajin Jukung
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tahun 2017-2018 bahwa pemaknaan kata pemuda adalah seluruh penduduk
Indonesia dengan kisaran usia 15-35 tahun. Pemuda dikategorikan sebagai remaja
50
dan siang menjadi bagian dari angkatan kerja. Hal ini dikarenakan pemuda secara
usia di atas dari anak-anak. Terdapat beberapa faktor kenapa pemuda dikategorikan
sebagai angkatan kerja, yakni; putus sekolah, tidak melanjutkan jenjang pendidikan
tertentu, dan tuntutan ekonomi.
Perihal ini senada dengan temuan penelitian berdasarkan hasil observasi dan
wawancara di Pulau Sewangi. Pemuda di Pulau Sewangi memiliki keterbatasan
untuk melanjutkan jenjang pendidikan khususnya level strata satu (Sarjana). Hanya
dikisaran 35-40% yang meneruskan strata satu. Selebihnya memilih untuk langsung
bekerja. Namun, 90% dari pemuda memiliki keinginan untuk bekerja di luar sektor
pembuatan jukung. Pemuda cenderung lebih memilik pekerjaan sebagai pedagang,
pegawai swasta hingga pegawai took di pasar-pasar besar di Banjarmasin.
Ahmad Sanusi (59) memaparkan “pengrajin jukung termuda di Pulau
Sewangi berusia 34-37 tahun”. Sedangkan usia yang lebih muda dibandingkan itu
tidak ada. Perihal ini dimaknai Oleh Arsyad (43) bahwa pemuda cenderung tidak
memiliki motivasi dalam bekerja yang memerlukan tenaga. Di samping tuntutan
keterampilan dasar, diperlukan tenaga dan kondisi fisik yang baik untuk membuat
jukung. Karena, membuat jukung termasuk dengan kategori pekerjaan kasar.
Pandangan pemuda berkenaan dengan minimnya gairah menjadi pengrajin
jukung dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal dan eksternal. Faktor internal
berhubungan denga usia, status sosial dan tingkat pendidikan. Namun, pada faktor
eksternal berhubungan dengan tingkat cosmopolitan dan sosialisasi pekerjaan.
Kedua faktor ini memunculkan satu simpulan yang tumbuh di benak pemuda bahwa
pekerjaan sebagai pengrajin jukung tidak memiliki kejelasan masa depan. Dengan
51
sistem penjualan ready stock serta jumlah pemesanan yang tidak menentu membuat
pemuda memilih pekerjaan yang lebih pasti. Beberapa alasan yang dikemukakan
oleh pemuda secara tidak langsung memberikan dampak potensi hilangnya
eksistensi dari pembuatan jukung di Pulau Sewangi. Hal ini dikarenakan jika tidak
ada penerus pengrajin jukung maka, popularitas Pulau Sewangi sebagai daerah
penghasil jukung hanya menyisakan cerita.
52
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka simpulan merujuk untuk menjawab
rumusan masalah penelitian. Simpulan dipaparkan dalam tiga paragraf yaitu;
Pertama, jukung merupakan alat transportasi air yang sering digunakan masyarakat
sebelum adanya kapal besar dan jalur darat. Secara umum pembuatan jukung
memerlukan waktu 2-3 minggu. Pembuatan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu;
persiapan, proses pembuatan, dan finalisasi. Pertama, tahapan persiapan
memerlukan perhatian pada perlengkapan dan pemilihan bahan baku. Kedua,
tahapan pembuatan ditentukan oleh bentuk dasar yakni krongkong. Ketiga adalah
diberikan lantai pada bagian dalam jukung dan kemudian di cat.
Kedua, Pulau Sewangi, Alalak, Barito Kuala dikenal sebagai sentra
penghasil moda transportasi air yakni jukung. Di Desa ini, jukung menjadi produk
utama yang dihasilkan oleh penduduk. Hal in dikarenakan mayoritas pekerjaan
mereka adalah pengrajin jukung. Usaha pembuatan jukung tidak bersinar hal ini
dilatarbelakangi oleh sulitnya bahan baku serta bergesernya budaya masyarakat dari
budaya sungai menjadi budaya darat. Sebelum tahun 2000-an usaha jukung di Pulau
Sewangi ramai pembeli. Kondisi ini berbanding terbalik saat ini. Jumlah pengrajin
jukung pun turun drastis, menjadi puluhan rumah tangga saja, dari semula ratusan
rumah tangga yang bermukim.
Ketiga, kendala keberlangsungan usaha pembuatan jukung di Pulau
Sewangi terjadi karena tiga hal. Pertama, keterbatasan bahan baku kayu yang hanya
didatangkan dari Kalimantan Tengah dan Timur. Kedua, teknik penjualan jukung
53
melalui sistem Ready Stock sehingga tidak minimnya variasi unit jukung yang
dibuat. Ketiga, minimnya pemuda menggeluti profesi pengrajin jukung. Perihal ini
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut kemudian
memunculkan berasumsi bahwa pendapatan usaha tidak memiliki kepastian dan
memerlukan tenaga banyak
B. Saran
Adapun saran penelitian ditujukan:
1. Peneliti selanjutnya sebagai bahan kajian mengeksplorasi usaha yang
digeluti oleh masyarakat di Pulau Sewangi sebagai bagian dari warisan
budaya untuk terus membuat moda transportasi air (jukung).
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memberikan perhatian
kepada usaha pembuatan jukung. Pada dasarnya pengrajin tidak
memerlukan sosialisasi dalam membuat jukung. Namun, pengrajin
memerlukan bantuan pemerintah kabupaten untuk menggerakkan urat nadi
usaha, mikro, kecil, dan menengah yang digeluti oleh pengrajin turun
temurun.
54
DAFTAR PUSTAKA
Burhan, B. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke
Arah: Ragam Varian Kontemporer . Jakarta : Rajawali Pers.
Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An Experimental Study in
Existentialism: The Psychometric Approach to Frankl's Concept of
Noogenic Neurosis. . Journal of clinical psychology, 200-207.
Depdiknas. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Ibanez, E., Lavrenz, S., Gkritza, K., Mejía, D., Krishnan, V., McCalley, J., &
Somani, A. K. (2016). Resilience and Robustness In Long-Term Planning
of The National Energy and Transportation System. International Journal
of Critical Infrastructures.
Ke, B. R., Chung, C. Y., & Chen, Y. C. (2016). Minimizing The Costs of
Constructing An All Plug-in Electric Bus Transportation System: A Case
Study in Penghu. Applied energy, 649-660.
Koopmans, T. C. (1949). Optimum Utilization of The Transportation System.
Econometrica: Journal of the Econometric Society, 136-146.
Łebkowski, A. (2018). Design of An Autonomous Transport System for Coastal
Areas. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety
of Sea Transportation.
Martínez‐Vilalta, J., & Garcia‐Forner, N. .. (2017). Water Potential Regulation,
Stomatal Behaviour and Hydraulic Transport Under Drought:
Deconstructing The Iso/anisohydric Concept. Plant, Cell & Environment,
962-976.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja.
Rosdakarya.
Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Nawawi. (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada.
University Press.
Nazir, M. (2009). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sartre, J. P., & Mairet, P. (1975). Existentialism is a Humanism. New Haven: Yale
University Press.
Satori, D. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Setyobudi, A. (2007). Peran serta bank Indonesia dalam pengembangan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM). Buletin Hukum Perbankan dan
Kebanksentralan, 29-35.
Shang, M., & Zhang, L. (2017). Study on The Optimization of Comprehensive
Transportation System in China Under the Perspective of Total Factor
Efficiency. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
(pp. Vol. 59, No. 1, p. 012007). IOP Pu.
55
Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM
menghadapi pasar bebas Asean." Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Jakarta
: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta.
Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja.
UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
56
DOKUMENTASI
Gambar 2. Proses penipisan krongkong jukung menggunakan peralatan katam
Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)
Gambar 3. Finalisasi jukung dengan mengecat body
Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)
57
Gambar 4. Kapal Feri, moda transportasi untuk mencapai Pulau Sewangi
Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)
Gambar 5. Wawancara bersama pengrajin jukung di Pulau Sewangi
Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)
58
Gambar 6. Pemasangan apak pada jukung
Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)
Gambar 7. Pemasangan tajak untuk disambungkan ke apak pada jukung
Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)
59
Gambar
8.
Penipisan krongkong menggunakan baji
Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)
Gambar 9. Wawancara bersama pengrajin jukung di Pulau Sewangi Sumber; Dokumentasi Pribadi (Desember 2019)