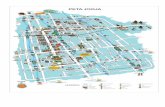visi 27 fix
description
Transcript of visi 27 fix


VISI

VISI | No. 27/Th. XX/2010 3
Redaksi menerima kritik, tulisan dan karya lainnya. Segala jenis tulisan maupun karya lainnya menjadi hak penuh redaksi Majalah Visi untuk diedit tanpa menubah esensi. Alamat redaksi : LPM VISI FISIP UNS Lt.2 Gd.2 FISIP UNS Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126.
E-mail : [email protected] : lpm-visi.blogspot.com & lpmvisi.ormawa.uns.ac.id
Pemimpin UmumAdinda NusantariSekretaris Umum
Ema YulianiStaff Sekretaris Umum
Istiqomah, Sri Sumi HandayaniBendahara Umum
Yulia WidayaniStaff Bendahara Umum
Andy MashudiPemimpin Redaksi
Rizky Pratama NusantaraSekretaris Redaksi Majalah
Alina Dewi HartantiSekretaris Redaksi Terbitan LainImas Ayu Prafitri, Nositaria Defia
Pemimpin UsahaWahyu
Staff Bidang UsahaDepartemen Penggalian Dana Mandiri
Pramanti Putri, Johan Bhimo SukocoDepartemen Produksi dan SirkulasiSesar Ramadhani Aji, Latif syaifudin
Pemimpin Penelitian dan PengembanganAnnisa Rohmah
Staff Bidang LitbangDepartemen Pendukung Penerbitan
Paramita Sari, Anyor Departemen Pewacanaan Eksternal
Intan Nur Arifah, Nanda Bagus Prakosa, Hafish Eskaputra
Pemimpin KaderisasiNur Heni Widyastuti
Staf Bidang KaderisasiDepartemen Skill dan Leadership
Filia Afrani
PelindungTuhan YMEPenasehat
Dekan FISIP UNS
Desain SampulWahyu
LayouterWahyu
Anggota :Yustika Era, Ratna Mega, Laura Rosiana, Adil
Hani, Akfatul Elfata, Anisa Putri, Dian S., Eka Sri, Indira Dwi, Leni Tri, Mukti Hening, Oki Eno, Yulia Bheti, Siti Rohana, Duratun
Nafisah, Fairus Uyun, Faiz Nurbaiti, Mbajeng Putri, Mei Safitri, Triyani, Siti Rofiqoh, Much-
sinati A., Festy Juilita, Yaninta Sani, Windy Jayanti, Dini S., Azizah F., W. N Elya, Pandu
P. Fajarudin, Renia K., Apriyani W., Heru Susanto, Rosinta Intan, Rohmad N., Yosep
Yoga, Yan Budiarto, Yudha Yogi, Habib, Valui Aditya, Agus, Rosyid H, Agatha Ika,
Ivan Andi, Dyah Budiningrum, Aditya Aris, Setyadi Budi, Rini Setyowati, Indah Suryani, Sri Hartini, Nidya Fitri, Duryatin Amal, Wina
Widyanita, Doso April.
Dapur Redaksi
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Begitulah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 pasal 28. Kemudian dijelaskan pada pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dari kedua pasal tersebut terlihat bahwa masyarakat diberikan kekebasan dalam hal berdemokrasi. Pemilihan Legislatif yang berlangsung April lalu memiliki berbagai cerita menarik. Salah satunya adalah adanya calon legislatif (caleg) yang berasal dari kalangan mahasiswa. Seperti yang kita tahu, dalam pemilu-pemilu sebelumnya mahasiswa berada di luar lingkaran politik praktis. Namun, dalam pemilu 2009 ini, mereka (mahasiswa-red) mencoba untuk masuk ke dalam lingkaran tersebut. Ada berbagai motif yang bisa menjelaskan di balik fenomena mahasiswa yang menjadi caleg. Salah satu motif yang diungkapkan adalah para mahasiswa mencoba masuk ke dalam parlemen agar suaranya dapat langsung didengar. Berbeda dengan ketika masih menjadi politisi jalanan, suara mereka hanya dianggap sebagai angin lalu oleh parlemen. Motif lain yang ada adalah mahasiswa digunakan sebagai kendaraan politik oleh para partai politik (parpol) untuk meraih suara pada pemilu April yang lalu. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah mahasiswa nantinya jika mereka terpilih mampu berbuat banyak di dalam parlemen. Pengamat politik memiliki pendapat yang beragam mengenai fenomena ini. Mereka menganggap hal tersebut (mahasiswa yang menjadi caleg-red) adalah sesuatu yang wajar dalam dunia demokrasi. Mengenai permasalahan kapabilitas mahasiswa, beberapa pengamat beranggapan mahasiswa belum mampu masuk dalam parlemen. Namun, ada juga yang beranggapan jika mahasiswa mampu cepat belajar dari lingkungan politik, hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Sebagai bagian dari mahasiswa, VISI ingin mencari tahu sejauh mana fenomena ini bergulir. Bagaimana motif yang ada di balik adanya mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai caleg. Sekali lagi, kebebasan berdemokrasi di negara ini benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh berbagai kalangan salah satunya mahasiswa. Namun, jika nantinya mahasiswa yang diidentikkan dengan ujung tombak rakyat mulai dilemahkan kekuatannya, siapa lagi yang diandalkan membela kepentingan rakyat.Selamat membaca! Jabat Erat,
Redaksi

VISI | No. 27/Th. XX/20104
Daftar Isi
Laporan Khusus 33“Polemik Perparkiran Kota Solo : Dari Lahan, Tarif, Hingga Masalah Regulasi”
Kolom 41Tokoh 43“Pejuang Hak Anak dan Perempuan”
Teropong 45Wawancara 48“Otoritas Dewan Pers di Tengah Kriminalisasi Terhadap Pers”
Refleksi 50Resensi 52“Masih Tersisa Harapan di Penjara”
Puisi 55Cerpen 56“Lentera di Antara Lilin”
Detak 58
Dapur Redaksi 3Surat Pembaca 5Visi Kita 6Podium 7Laporan Utama 8
“Mahasiswa Menuju Parlemen : Layakkah?”
Artikel Utama 18
“Diskontinuitas Gerakan Kaum Muda”
Sekaken 21Spektrum 25“SertifikasiGuru:SudahkahBerhasil?”
Potret 30

VISI | No. 27/Th. XX/2010 5
Surat Pembaca
Pantaskah UNS menyandang slogan WCU??
Saya merasa sangat bangga dapat menimba ilmu di sebuah kampus yang mempunyai slogan “World Class University (WCU)”. Tapi benarkah kita pantas bangga sedangkan menurut pengamatan saya kondisi kampus kita belum menunjang untuk menyandang slogan tersebut? Masih banyak pembenahan yang harus dilakukan, misalnya untuk
hal-hal kecil seperti tempat sampah yang jumlahnya masih kurang baik di tiap-tiap fakultas maupun di wilayah seputeran kampus. Permasalahan kebersihan kamar mandi pun masih perlu pembenahan. Banyak keluhan mengenai kurang terawatnya setiap kamar mandi yang ada. Memang permasalahan tersebut terkesan sepele, namun jika tidak segera teratasi maka bisa menimbulka efek yeng lebih besar. Banyaknya pengemis dan pedagang kaki lima yang berada bahkan bebas riwa-riwi di area kampus juga dapat mengurangi kenyamanan dari para mahasiswa. Saya rasa, lambat laun kampus kita menjadi tidak ada bedanya dengan tempat-tempat umum yang lain. Melihat kondisi tersebut, apakah pantas UNS memiliki slogan WCU? Saya sangat menyangsikannya. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh pihak universitas mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalnya, pihak universitas menyediakan lebih banyak lagi tempat sampah beserta tulisan ”Dilarang membuang sampah di sembarang tempat”. Pihak universitas juga dapat menyediakan tempat khusus bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan agar mereka tidak berjualan di sembarang tempat. Kemudian memperbanyak jumlah petugas kebersihan untuk merawat toilet. Ini tentu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh UNS sebagai sebuah kampus besar yang sudah go internasional.
Lepas dari itu semua, peran mahasiswa juga diperlukan untuk mewujudkan slogan tersebut. Contoh kecilnya, terkait segala permasalahan di atas adalah memiliki kesadaran akan kebersihan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Perbuatan kecil yang menimbulkan efek luar biasa bukan hanya bagi universitas, tetapi juga dunia sekitar.
NuraidaMahasiswa FKIP 2007 UNS
Mahasiswa Harus Kritis dan Solutif
Assalamualaikum Wr.Wb.Sebagai salah satu mahasiswa
yang ikut memantau kondisi green campus UNS tercinta ini, saya menemukan fakta yang pastinya telah diketahui oleh sebagian besar mahasiswa UNS. Hal tersebut adalah terus meningkatnya biaya pendidikan di UNS setiap tahunnya untuk mahasiswa baru sebesar sekitar 10%. Tentunya bukan itu saja yang ingin kita kritisi, satu pertanyaan besar yang muncul di benak saya dan sebagian besar mahasiswa lainnya adalah “Adakah peningkatan sarana dan prasarana kampus seiring dengan terus meningkatnya biaya pendidikan di UNS?” jawaban dari pertanyaan ini tidak akan saya sajikan disini, hanya saja saya ingin kita semua ikut mengkritisi kondisi kampus kita ini, mulai dari sarana dan prasarana pendukung pendidikan seperti perpustakaan maupun fasilitas kesehatan bagi mahasiswa.
Kita semua pasti telah memiliki jawaban versi kita masing-masing atau malah kita tak tahu harus menjawab apa? Disinilah kita perlu berkontribusi, bukan hanya bertanya, menemukan jawaban, namun juga mencari solusi-solusi untuk permasalahan yang kita temui sebagai masukan bagi kampus hijau ini. Dan tentunya VISI sebagai salah satu media kampus memiliki peranan penting sebagai kontrol sosial kondisi yang terjadi di UNS.
Teringat tentang penghuni-penghuni baru, saya ucapkan ”SELAMAT DATANG DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA” siapkan diri kalian untuk berproses ke arah yang lebih produktif dan bermanfaat. Disini
bukan hanya tempat untuk menempuh pendidikan formal di bangku-bangku di dalam ruang kuliah, namun dibuka pintu selebar-lebarnya untuk menemukan berbagai pengalaman yang akan mengasah softskill dan ketrampilan kita. Berbagai kegiatan dan organisasi kemahasiswaan telah disiapkan untuk membantu mahasiswa menemukan jati diri dan sebagai pembekalan diri. Mahasiswa sebagai harapan-harapan baru penggerak roda kehidupan masa depan harus dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai agar bisa menjadkan kehidupan mendatang yang tentunya lebih berat dari saat ini, menjadi sebuah dunia baru yang berisikan kehidupan yang lebih baik. Sekaranglah saatnya kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai kegiatan yang memberikan pembekalan yang bermanfaat bagi masa depan kita, negara dan agama. Wassalamualaikum Wr. Wb.
LEILA RAHMA SAFITRIMahasiswi FISIPJurusan Ilmu Komunikasi 2007UNS

VISI | No. 27/Th. XX/20106
Visi Kita

VISI | No. 27/Th. XX/2010 7
Podium

VISI | No. 27/Th. XX/20108
Laporan Utama
Iklim demokrasi di negara ini agaknya makin terbuka. Setelah dunia politik
diramaikan kalangan artis, kini kalangan mahasiswa juga makin menyemarakkan kancah politik praktis. Memang hal ini bukanlah barang baru, namun kini nampaknya makin berkembang. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Subagyo mengatakan kemunculan mahasiswa di dunia politik memang sudah terjadi sejak dulu. Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Surakarta, Eka Nada Shofa Al Hajar mencotohkan nama-nama seperti Eduta Indah Sari, Budiman Sujatmiko, Pilus yang dulu pernah menjadi caleg ketika berpredikat sebagai aktivis kampus. Di Solo sendiri ada beberapa nama yang terjun dalam dunia politik kala masih mahasiswa. Misalnya, Muhammad Ikhlas Thamrin.
Dulunya, ia adalah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS. Usai lulus, langkahnya sebagai politikus kampus ia lanjutkan dengan menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kondisi ini dinilai Subagyo sebagai bagian dari dinamika politik yang kian terbuka. “Kondisi semacam ini cukup membanggakan. Dimana dalam hal ini, mahasiswa adalah pelopor,” ujar Subagyo di ruang kerjanya (23/4). Selanjutnya, kata Subagyo, mahasiswa harus mampu belajar dari para pendahulunya. Sebab, mahasiswa dinilai memiliki kapasitas untuk terjun dalam politik praktis, termasuk menjadi wakil rakyat. “Saya kira mahasiswa lebih capable dibandingkan dengan wakil rakyat dari kalangan lainnya,” terang Subagyo. Subagyo membenturkannya dengan fenomena maraknya caleg dari kalangan artis, atlet, satpam, dan lainnya. Ia manambahkan, justru dengan
terjun langsung di kancah politik, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh di bangku kuliah.
Butuh Totalitas Namun, menjadi anggota parlemen membawa konsekuensi yang tidak mudah. Apalagi bila masih berstatus mahasiswa. Salah satu konsekuensi ketika menjadi wakil rakyat adalah bekerja dengan totalitas. Sebagaimana diungkapkan dosen FISIP UNS, Ign. Agung Satyawan, M. Si. “Menjadi anggota legislatif tidak hanya dituntut memiliki kemampuan. Namun juga butuh totalitas,” katanya saat ditemui VISI di kantornya, (16/4). Status mahasiswa, dipandang Agung dapat memengaruhi totalitas kerja anggota dewan. “Mahasiswa pasti akan punya kendala rutinitas,” tegasnya. Sebab, anggota dewan memiliki jadwal yang padat. Sedangkan mahasiswa harus tetap menyelesaikan studinya. “Bukankah
Mahasiswa Menuju Parlemen: Layakkah?Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 menyisakan berbagai cerita. Salah satunya makin bertambahnya kandidat anggota dewan yang berasal dari kalangan mahasiswa. Beberapa bahkan terpilih menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).

VISI | No. 27/Th. XX/2010 9
itu malah membuat kerjanya setengah-setengah? Padahal, tugas anggota dewan itu tidak mudah lho,” jelas Agung. Bagi Agung, keadaan itu justru akan menjadi kontra produktif dengan tugas anggota dewan. “Menjadi anggota legislatif ya harus total. Nggak bisa setengah-setengah. Sebab, problem ke depan makin rumit dan membutuhkan konsentrasi penuh untuk memecahkannya. Kalau tidak bisa total, nanti malah mengingkari amanat rakyat,” paparnya sambil membetulkan posisi duduk. Eka Nada pun mengutarakan hal serupa. Menurutnya, menjadi anggota legislatif bukanlah hal yang bisa dilakukan secara instan dan mudah. Idealnya, kata Eka, seharusnya mereka menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Kemudian, menyerap aspirasi masyarakat dengan sepenuhnya. Barulah dia bisa mengabdikan dirinya pada masyarakat. “Jika masih berstatus mahasiswa, saya kira posisinya akan sulit. Sebab, ia punya dua tanggung jawab yang berbeda,” tuturnya kala dijumpai di Sekretariat HMI Cabang Surakarta, Rabu (17/4). Masalah totalitas sebenarnya juga menjadi syarat tersendiri dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR. Salah satu syarat yang disebutkan adalah “bekerja penuh waktu atau fulltime” (Lihat Tabel 1). Agung menyayangkan keputusan parpol mengikutsertakan kadernya yang masih berstatus mahasiswa untuk menjadi caleg. “Barangkali parpol memiliki pemikiran untuk mengambil caleg dari orang yang masih muda. Tetapi kan tidak harus mahasiswa,” jelas Agung. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Surakarta Sukatmi mengaku tidak mempersoalkan totalitas mahasiswa yang menjadi anggota dewan. “Tidak masalah, siapapun bisa menjadi anggota legislatif. Asalkan memenuhi syarat,” terangnya. Subagyo juga menilai mahasiswa mampu menjadi anggota legislatif. “Mereka pasti mampu. Tergantung bagaimana mereka dapat
membaca situasi dan belajar dari lingkungan sekitar,” katanya yakin. Keikutsertaan mahasiswa dalam dunia politik sebagai caleg, merupakan salah satu langkah kaderisasi parpol. Sebagaimana yang diungkapkan pengamat politik sekaligus dosen FISIP Universitas Muhammadiyah (UMS) Surakarta Aidul Fitriciada. Menurutnya, dalam kaderisasi itu nantinya ada senior dan yunior. “Pada periode pertama mungkin mereka yang masih yunior masih belum ahli, tetapi ia pasti akan belajar. Apalagi, mahasiswa pasti lebih cepat beradaptasi,” ungkapnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surakarta, Yayuk Purwani membenarkan hal tersebut. “Kami ingin partai politik memberikan pembelajaran politik bagi kader dari kalangan mahasiswa. Karena mahasiswa merupakan kader potensial, dilihat dari pengalaman dan ilmunya. Dari sana, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran baru,” terang Yayuk. Meski demikian, Aidul menambahkan, anggota legislatif yang
berasal dari mahasiswa hendaknya memiliki latar belakang aktivis gerakan. “Sebab, yang bukan aktivis biasanya memiiki tingkat kecakapan lebih rendah dibanding aktivis mahasiswa. Meski tidak semua yang berasal dari aktivis gerakan selalu lebih baik,” kata dia. Di Surakarta, kebanyakan mahasiswa yang terjun ke dalam politik praktis dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu lalu tidak memiliki latar belakang aktivis atau gerakan. Hidayatul Muslihah, Danur, misalnya. Hidayatul masih tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik (FT) UNS saat menjadi caleg dari
Partai Amanat Nasional (PAN). Dia mengaku tak banyak terlibat dalam kegiatan organisasi mahasiswa. “Saya hanya ikut Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ-red), karena tidak tertarik ikut organisasi semacam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-red) atau Dewan Mahasiswa (Dema-red),” tutur Hidayatul.
Dia menambahkan, keterlibatannya dalam dunia politik lebih banyak dipengaruhi oleh ayahnya yang juga seorang politikus

VISI | No. 27/Th. XX/201010
(anggota DPRD Surakarta- Red). “Saya punya ketertarikan di dunia politik dan mendapat dukungan keluarga. Tetapi, saya memang tidak tertarik untuk menjadi aktivis di kampus. Saya lebih banyak mendapat arahan dari ayah,” kata wanita yang akrab disapa Hida saat ditemui Selasa (25/3) di rumahnya. Danur pun demikian. Ia sama sekali bukan aktivis organisasi, apalagi gerakan. Namun, dirinya yang menjadi Caleg dari PDIP justru berhasil meraih kursi di DPRD Surakarta. Untuk menjalankan tugasnya, ia mengaku akan lebih mengandalkan pengalaman karena tidak banyak bekal dari partai.
Antara Aktivis dan Politik Biasanya, banyak aktivis kampus yang kemudian bermunculan sebagai tokoh-tokoh politik. Seperti Akbar Tanjung, dll. Bekal ketika menjadi aktivis dinilai memberi kemampuan lebih bagi seseorang untuk diterapkan di kancah politik praktis. Maraknya kemunculan aktor-aktor politik “karbitan” sangat disayangkan oleh para aktivis mahasiswa. Misalnya, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta, Eka Nada. Dia meragukan kemampuan mahasiswa yang tidak berasal dari kalangan aktivis. Ketika bertemu dengan realitas di masyarakat, mereka akan lekas putus asa dan kaget karena belum pernah menjumpai dan memikirkan hal semacam itu sebelumnya. “Kalau dari kalangan aktivis, mungkin masih ada idealisme yang dibawa ketika terjun ke kancah politik praktis” ujar Eka.
Padahal nantinya, aktor-aktor politik tersebut harus dapat menggerakkan sisitem pengontrol di parlemen, dan mengubah sistem jika perlu. Padahal Eka mengakui, untuk mengubah sistem dari dalam memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Jangankan mahasiswa, seorang aktivis sosial yang sudah ternama saja ketika sudah masuk ke parlemen masih kesulitan,” lanjutnya.
Hal itu, menurut Eka, disebabkan parahnya sistem yang ada sehingga sulit untuk diubah. “Ketika sudah sampai di parlemen, yang diperjuangkan bukan lagi murni
idealisme, tetapi kepentingan parpol,” tandasnya. Melihat kondisi tersebut, akan sulit bagi aktor politik “karbitan” untuk dapat berperan di sana.
Eka menilai munculnya aktor politik “karbitan” diantaranya karena fungsi parpol di Indonesia belum ideal. Baik fungsi sebagai pendidikan maupun rekrutmen politik. “Keduanya masih bermasalah. Saya melihat, kepentingan mahasiswa untuk masuk di parlemen adalah kepentingan pragmatis. Sebagaimana parpol menggaet artis untuk menjadi kadernya,” jelasnya.
Pengamat politik Kota Solo yang juga dosen FISP UMS Aidul Fitriciada membenarkan pendapat Eka. Menurutnya, aktor politik sebaiknya berasal dari kalangan aktivis mahasiswa. Menurut dia, mereka yang bukan aktivis memiliki tingkat kecakapan lebih rendah. Meski tidak selalu begitu. “Di Golkar, contohnya. Posisi penting diisi alumni ITB (Institut Teknologi Bandung-red) yang dulunya aktivis. Dan hal semacam ini akan berpengaruh pada kualitas parlemen,” paparnya.
Meski demikian, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Gunawan belum yakin bila orang parlemen yang berasal dari aktivis telah memiliki pondasi yang lebih baik. Bagi Gunawan hal ini sangat subjektif. “Kalau menurut saya, hal itu justru akan merugikan pola pergerakan selanjutnya,” tuturnya. Artinya, dunia politik dipandangnya sebagai dunia yang sangat penting. Sehingga untuk masuk di dalamnya tidak dapat dilakukan secara instan. “Misalnya, dengan hanya menjadikan pengalaman organisasi di kampus sebagai landasan terjun di politik praktis. Itu belum cukup,” katanya. Pertama, fungsi parpol di Indonesia belum ideal. Baik fungsi sebagai pendidikan maupun rekruitmen politik, keduanya masih bermasalah. Akibatnya, muncul pemimpin-pemimpin politik yang karbitan. “Saya melihat, kepentingan mahasiswa untuk masuk di parlemen adalah kepentingan pragmatis. Sebagaimana parpol menggaet artis untuk menjadi kadernya,” jelasnya. Bagi Gunawan, alangkah lebih baik bila seorang aktivis yang terjun ke dunia politik memiliki pola
yang matang. Misalnya, dengan membenahi studinya terlebih dahulu sehingga dapat berpikir logis. Selanjutnya adalah mendapatkan akses massa. Jadi, ada tanggung jawab terhadap demokrasi. “Di negara demokrasi, siapa saja boleh menjadi aktor politik. Tetapi, bagaima tanggung jawab terhadap demokrasi itu sendiri jika tak memiliki kapabilitas yang memadai?” tutur Gunawan sembari mengerutkan dahi.
Memang mahasiswa bukan politisi instan. Mereka punya banyak waktu untuk belajar ke arah kepemimpinan partai. “Tidak seperti politisi yang biasanya memulai di usia 40-an. Kalau masuk lebih awal, dia punya kesempatan untuk menempa diri menjadi lebih matang,” ujar Aidul.Sedangkan kader parpol yang instan (tidak berlatar aktivis-red) hanya membuat parpol sebagai mesin caleg yang tidak berkualitas. Akibatnya, partai sebagai mesin pencetak tokoh parpol menjadi tidak lagi memiliki visi-misi dengan kontent yang tidak berkualitas. Singkatnya, hanya mencari kekuasaan.
Dari Panggung Jalanan ke Parlemen Perjuangan mahasiswa selama ini kerap disebut dengan istilah “parlemen jalanan”. Yakni mereka yang berjuang mengkritisi kebijakan pemerintah berkuasa, serta mengadvokasi hak rakyat dari luar sistem. Hingga kini, perjuangan ala parlemen jalanan masih tetap dilaksanakan. Bahkan, untuk menjaga eksistensi dan idealismenya, beberapa organisasi mahasiswa menegaskan untuk tetap bersikap “steril”. Artinya, selama bernaung di bawah organisasi mahasiswa, semua anggota tidak diperkenankan terjun langsung ke politik praktis. Terutama terlibat dalam satu partai politik, apalagi menjadi caleg. Salah satunya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (UMS) Surakarta. Secara tegas organisasi ini tetap memberlakukan perjuangan di luar sistem. “Kami memposisikan diri sebagai oposan pemerintah,” kata Presiden BEM UMS Mochamad Nur. Meski terkadang, pola pergerakan yang dianut tersebut dinilai kuno,

VISI | No. 27/Th. XX/2010 11
namun Nur menilai cara tersebut masih relevan. Dua organisasi eksternal, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta juga menerapkan hal serupa. Kedua organisasi ini mengharuskan anggotanya bersikap “netral”. HMI memiliki kontitusi yang menggariskan bahwa setiap anggota atau pengurus HMI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Jika ada yang terlibat, sanksinya adalah pemecatan. Kecuali kalau sudah keluar dari HMI, maka dia bebas berpolitik di luar. Hal tersebut menurut Eka, dilakukan untuk menjaga independensi HMI. Sehingga, tidak ada hubungan kultural dengan parpol tertentu.
Sementara di IMM secara tegas dinyatakan bahwa anggota IMM yang secara stuktural masih termasuk dalam dewan pempinan baik cabang, ranting, tidak diperbolehkan masuk ke dunia politik. “Kalau mereka ingin masuk ke dunia politik, ya, silahkan. Tetapi, keluar dulu dari struktur IMM,” tegas Ketua IMM Surakarta, Huda.
Namun, Aidul punya pandangan berbeda. Sistem perjuangan dan idealisme gerakan mahasiswa tersebut menurutnya perlu diubah. Sebab, masalahnya selama ini gerakan mahasiswa tidak terintegrasi. Sehingga ada “jarak” antara parpol dengan gerakan mahasiswa. “Harus ada upaya sadar supaya banyak gerakan mahasiswa yang masuk ke parlemen. Problemnya, selama ini terjadi keterlambatan tokoh-tokoh gerakan untuk masuk ke parlemen karena beranggapan parpol itu negatif,” jelas Aidul.
Menurutnya, hal tersebut bukan merupakan “pengkhianatan” terhadap gerakan mahasiswa. “Ini demokrasi. Mahasiswa sekarang masih terobsesi zaman Orde Baru (Orba), mengkritisi sistem negara yang tidak demokratis,” tutur Aidul. Namun, menurut dia, kondisi sekarang berbeda. “Bicara tentang oposisi, sekarang harus oposisi kelembagaan. Bukan oposisi ekstraparlementer lagi,” imbuhnya.
Aidul berpendapat, gerakan mahasiswa harus berorientasi
Syarat Menjadi Calon Anggota Legislatif / Caleg DPR DPD DPRD Undang-Undang No.10 Tahun 2008
Berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bisa mengajukan diri sebagai calon legislatif / caleg, yaitu sebagai berikut di bawah ini :
1. Warga Negara Indonesia / WNI2. Berumur / Berusia Minimal 21 Tahun3. Bertempat Tinggal di Wilayah NKRI (Negara Kesatuan Repubik Indonesia)4. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa5. Minimal Tamat / Lulus SMA atau sederajat6. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 19457. Sehat Jasmani dan Rohani8. Bersedia bekerja penuh waktu / full time9. Terdaftar sebagai pemilih pada pemilu10. Anggota Parta Politik11. Siap bersedia tidak praktek notaris, akuntan dan advokat12. Pegawai / Anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD harus mengundurkan diri13. Bersedia tidak rangkap jabatan negara, badan negara, bumd dan bumn14. Tidak pernah masuk penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih15. Dicalonkan di satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan16. Cakap berbicara, menulis dan membaca dalam Bahasa Indonesia17. Bisa Membaca Al-Quran (khusus caleg lokal NAD)
- Sumber : UU Nomor 10 / 2008 Republik Indonesia
sebagai aktor demokrasi dan harus mampu bekerja sama dengan institusi demokrasi yang lain. “Memang agak sulit. Gerakan mahasiswa tidak boleh masuk parpol, tetap harus menjaga jarak dan bersikap kritis terhadap institusi lain,” jelasnya. Tetapi, gerakan ekstraparlementer saja tidak cukup. “Saat ini, rekrutmen pada mahasiswa boleh dilakukan secara personel, asalkan bukan organisasinya. Partai juga harus memantau perkembangan ini, sehingga terjadi integrasi antara kampus dan sistem demokrasi,” lanjut Aidul.
Saat ini, mahasiswa hanya menjadi pendorong mobil mogok saja. Dalam proses demokrasi sekarang, tokoh-tokoh politik harus masuk partai. “Kecuali pada masa orba, harus ekstraparlementer karena parpol tidak bisa diandalkan,” kata Aidul. Ketika institusi parpol diisi orang-orang non-aktivis, para tokoh gerakan akan berpandangan negatif terhadap parpol. “Akhirnya, banyak tokoh gerakan tersingkir,” tegasnya. (Adinda, Ema, Istiqomah, Ansyor, Eko)

VISI | No. 27/Th. XX/201012
Majunya mahasiswa pada Pemilu Legislatif April 2009 lalu disayangkan
oleh para aktivis. Gunawan misalnya. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) ini mengungkapkan ketakutannya ketika mahasiswa yang menjadi calon legislatif. Ia melihat adanya jabatan tersebut nantinya bukan bisa jadi hanya dimaknai sebatas karir dan lapangan pekerjaan.
Padahal, menurutnya, makna menjadi anggota dewan tidaklah seperti itu. “Harapan saya, orang-orang yang masuk ke ranah publik adalah orang yang memiliki orientasi pengabdian,” ungkapnya ketika diwawancara pada Rabu (15/4) di Graha Keluarga Mahasiswa UNS.
Tidak hanya Gunawan, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Surakarta, Eka Nada Shofa Alkhajar juga mengatakan hal serupa. Dirinya menyatakan masih meragukan kemampuan mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat luas. ”Jika masih berstatus mahasiswa, maka saya kira sulit bagi menjadi wakil rakyat. Sebab ia punya tanggung jawab yang berbeda dan masih berada di bawah naungan almamater kampusnya,” ujarnya ketika diwawancara pada Jumat (17/4) di Sekretariat HMI.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perhitungan suara berdasarkan suara terbanyak membuat perubahan besar. “Baik dalam struktur partai maupun struktur perolehan suara,” ujar dosen FISIP UNS, Kandyawan saat diwawancarai di kantornya, Senin (27/4). Menurut
Kandyawan, yang lebih populerlah yang akan mendapat suara banyak. Sebab, dalam sistem suara terbanyak, pemenang ditentukan berdasarkan perolehan suara masing-masing caleg, bukan berdasarkan nomor urut seperti di pemilu sebelumnya.
“Nah, posisi inilah yang dimanfaatkan beberapa orang yang memiliki basis massa yang kuat untuk masuk sebagai anggota dewan. Meskipun baru mahasiswa,” tambah dia. Peraturan itu yang juga dirasakan Hidayatul Muslihah sebagai peluang baginya untuk dapat maju sebagai caleg. “Saya merasa punya kesempatan karena masih ada kantong-kantong suara, bukan lagi pentingnya nomor urut,” ujar Hidayatul, yang kala itu menjadi caleg Partai Amanat Nasional (PAN). Katika ditemui pada Selasa (25/3) lalu, ia mengaku tidak akan mencalonkan diri jika Pemilu tahun ini tidak menggunakan suara terbanyak.
Calon lain yang berpandangan sama adalah Arif Nur Rohim. Peraturan baru tersebut membuat caleg asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini semakin mantap melenggang ke bursa pencalonan tahun 2009. “Dengan sistem ini saya harus optimis karena peluang terpilihnya semakin besar,” terangnya ketika diwawancara pada Rabu (1/4). Arif yang saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta mengaku tidak khawatir meskipun ia terdaftar sebagai caleg dengan nomer urut paling akhir dari 12 calon lain di daerah pemilihannya.
Faktor lain yang mendorong para mahasiswa untuk mencalonkan diri sebagai caleg adalah faktor
personal. “Artinya, banyak yang coba-coba jadi caleg dengan memanfaatkan peraturan itu,” lanjut Kandyawan. Kandyawan menambahkan, ini baru merupakan awalan. Untuk selanjutnya, sangat tergantung kepada kemampuan tiap individu untuk menciptakan suara atas basis kuasa yang dimilikinya. “Sekarang tren yang muncul memang coba-coba atau ikut-ikutan menjadi caleg. Tanpa kemampuan politik pun, mereka berani bersaing asal banyak pendukung,” ujarnya ketika ditemui VISI Senin (27/4) lalu.
Hal semacam ini terjadi pada Muhammad Barid, Caleg dari Partai Matahari Bangsa (PMB). Meski tidak ikut-ikutan, tetapi alasan yang mendorongnya untuk maju adalah alasan personal. Tepatnya, Barid mengaku maju menjadi caleg karena menggantikan posisi ayahnya. “Awalnya yang dicalonkan adalah ayah saya. Namun, karena permasalahan usia (tidak memenuhi syarat usia- Red), maka saya ditunjuk menggantikan posisi tersebut,” tambah Barid ketika ditemui pada .
Faktor “coba-coba” ini bagi Presiden BEM UNS Surakarta Gunawan dinilai sebagai “peluang kerja”. “Jangan-jangan mereka melihat dunia politik sebagai lahan kerja semata. Bukan sebagai wakil rakyat yang mengabdi pada masyarakat,” katanya.
Namun, menurut para mahasiswa yang mengajukan diri sebagai caleg, mereka tidak hanya sekadar mencalonkan diri. Tetapi, mereka mengaku memiliki visi tersendiri. Salah satunya dikemukakan oleh Calon Legislatif (Caleg) Partai
Kompetensi Mahasiswa Masih Dipertanyakan
Adanya peluang membuat beberapa mahasiswa maju menjadi calon legislatif di Pemilu 2009 lalu. Meski demikian, mereka tetap dituntut memiliki visi dan kemampuan praktis di dunia
politik.

VISI | No. 27/Th. XX/2010 13
Amanat Nasional (PAN), Hidayatul Muslihah. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memperjuangkan hak kaum perempuan jika ia terpilih menjadi anggota dewan. “Kebijakan-kebijakan untuk kaum perempuan harus lebih menjadi perhatian,” ujarnya.
Hidayatul yang merupakan mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Sebelas Maret (UNS) ini mengatakan ia tidak akan fokus sebagai mahasiswa jika terpilih menjadi anggota dewan. “Tapi saya menempatkan diri sebagai warga masyarakat yang mengemban amanah mereka,” terang Hidayatul.
Sama halnya dengan Hidayatul, Sugeng Santoso, mahasiswa Jurusan Sosiologi UNS yang menjadi caleg dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Melalui positioning-nya, ia berkeinginan untuk menyampaikan
aspirasi rekan-rekan mahasiswa yang selama ini menyatu dengan kehidupan kesehariannya.
Walaupun hanya menggantikan posisi ayahnya, Barid yang saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surakarta mengaku sudah ada kesadaran dari dalam dirinya untuk mengabdi kepada masyarakat. “Saya terpanggil untuk maju karena merasa kinerja beberapa dewan di daerah saya kurang maksimal,” terangnya.
Bekal Kemampuan Praktis ”Tren coba-coba menjadi caleg
ini memang tidak hanya terjadi pada kalangan mahasiswa. Berbagai latar belakang pekerjaan sekarang beramai-ramai jadi caleg. Sesuatu yang instan itu tidak baik,” tutur Kandyawan. Menurutnya, jika tren coba-coba ini dialami mahasiswa yang maju jadi
caleg, maka mereka harus bekerja ekstra keras untuk bertugas menjadi penyampai aspirasi rakyat. ”Jadi kalau punya cita-cita harus disertai dengan kemampuan yang memadai,” tambahnya.
Salah satu praktik yang harus dimiliki adalah kemampuan berpolitik. Sebagaimana dikatakan dosen pengajar FISIP UNS Agung Satyawan ketika ditanya tentang kapabilitas mahasiswa menjadi caleg. “Ini merupakan modal untuk kinerja selanjutnya selama 5 tahun. Tugas-tugas dewan itu tidak mudah,” ungkapnya.
Agung menambahkan, bila ada mahasiswa yang maju sebagai wakil rakyat, harus ada pembekalan entah dari parpol atau dari organisasi. Hal ini dikarenakan mahasiswa belum memiliki pengalaman politik secara praktis yakni lebih banyak mengenal politik secara teoritis. Beberapa

VISI | No. 27/Th. XX/201014
parpol mengaku telah menerapkan pembekalan ini melalui pendidikan politik.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS, Sugeng Riyanto, S.S, pengkaderan ini penting secara politik pun harus diberikan kepada setiap kader politik. Hal ini berlaku bagi seluruh kader. “Kami tidak mengkotak-kotakkan status kader. Semua dianggap sama. Jadi tidak ada pengkhususan seperti caleg dari kalangan mahasiswa,” ungkapnya ketika ditemui VISI di rumahnya, Selasa (31/03) lalu.
Pendidikan politik bagi tiap-tiap kader PKS, menurut Sugeng, berupa ajaran islam yang menyeluruh. Ini tidak lepas dari karakter PKS sebagai parpol islam dan tidak hanya mementingkan partai serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. “Ini bertujuan agar kader kami dapat peka dan solutif atas permasalahan sekitar. Yang jelas, tujuannya agar kami menjadi politisi yang seimbang antara lembaga, dakwah, dan partai,” tambahnya.
Beberapa caleg pun mengaku telah mendapatkan pembekalan sebelum maju menjadi caleg maupun ketika menjadi kader partai. Salah satu pengurus DPD PKS, Muhammad Asrori, menambahkan terdapat Training Orientasi Partai yang merupakan agenda tahunan partai untuk membekali kader-kadernya.
Training ini diberikan ketika rekrutmen kader PKS di tingkat cabang. ”Bagi yang mencalonkan diri di Pemilu Legislatif, ada sekolah politik untuk pembekalan mengahadapi Pemilu,” ungkap Asrori yang menjabat sebagai staf Bidang Politik dan Hukum di DPD PKS ini.
Parpol lain yang telah menerapkan pendidikan politik adalah PAN. “Pembekalan itu diberikan dari partai. Disebutnya Latihan Kepemimpinan Dasar. Disitu para kader dilatih tentang kepemimpinan dan nilai dasar partai,” ungkap Hidayatul saat ditanya mengenai pendidikan politik yang didapatnya. Beberapa partai memberikan pengkaderan sebagai bekal kepemimpinan di politik praktis, salah satunya PAN yang sebelumnya disebutkan Hidayatul. Namun, ada pula parpol yang ridak begitu memformalkan pendidikan politik. Melainkan kemampuan tersebut dapat diperoleh melalui learning by doing. Sebagaimana diungkapkan Danur Dwi, caleg PDI Perjuangan yang masih duduk di semester 8 Jurusan Teknik Industri UNS. Ia menyatakan partainya kurang memberikan bekal berpolitik praktis kepada kader-kader, termasuk dirinya. Padahal menurut perhitungan suara terakhir, Danur dipastikan meraih satu kursi di DPRD Sukoharjo. “PDIP memang tidak memberikan pelatihan
secara formal kepada kadernya. Hingga sekarang saya terpilih. Nantinya saya akan learning by doing di DPRD,” tuturnya kepada VISI ketika diwawancara pada Kamis (28/4) di kampusnya.
Kandyawan menambahkan, bekerja di gedung dewan bukan hal yang mudah. Diperlukan kemampuan untuk bekerja sama atas nama rakyat. “Perlu persiapan khusus dan sekali lagi, tidak instan. Hasilnya akan sangat tidak maksimal nantinya, mungkin akan terkooptasi dengan kondisi politik disana. Karena ini berkaitan sekali dengan implementasi mereka menjadi wakil rakyat dalam melaksanakan tugas-tugas legislator,”.
Selain pemupukan pengkaderan dari partai yang harus kuat, latar belakang mahasiswa
yang maju sebagai caleg seharusnya berasal dari kalangan aktivis. Hal tersebut dinyatakan Aidul Fitriciada Ashari, pengamat politik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Ia menyatakan kesiapan untuk menjadi seorang wakil rakyat dapat ditempa ketika mereka banyak berada dalam barisan gerakan mahasiswa dan bukan merupakan produk instan. ”Apabila bukan berasal dari gerakan, kecakapan dan keterampilan mereka akan kurang,” pungkasnya. (Ema, Istiqomah, Adinda, Eko, Ansyor)

VISI | No. 27/Th. XX/2010 15
Organisasi Mahasiswa dan Pembentukan Kader Politik
Kampus. Ketika fungsi pendidikan partai politik tak berjalan optimal, di sanalah tempat alternatif pendidikan politik. Diantaranya melalui organisasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal.
“Lewat organisasi, seseorang dapat lebih mempunyai attitude (sikap-red).” Begitulah yang
diungkapkan Menteri Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Susilo, ketika ditemui di sekretariat BEM UNS beberapa bulan lalu.
Meskipun BEM tidak membayangkan bahwa kader-kadernya akan terjun ke politik praktis, Susilo mengungkapkan tetap ada pendidikan politik yang dilakukan oleh BEM. Kegiatan tersebut antara lain Studi kader bangsa (SKB), diskusi, dan training.
Menurut Susilo, SKB yang dijalankan BEM telah memiliki arahan tersendiri. Secara struktural, program ini dijalankan oleh Departemen Pengembangan Sumberdaya Manusia (PSDM) BEM UNS. “Dalam program ini mahasiswa diberikan pelatihan tentang berbagai wacana sosial politik. Misalnya tentang wawasan nusantara, rekayasa sosial politik, pemahaman pergerakan mahasisa , dan lain sebagainya,” jelasnya.
Menurut Susilo, pengkaderan yang optimal seharusnya justru dilakukan melalui Dewan Mahasiswa (Dema). “Sebab, mereka sudah banyak berinteraksi dengan dunia perlemen, yang terepresentasi dalam perlemen mahasiwa,” kata dia.
Jika BEM UNS telah memiliki SKB sebagai program pelatihan politik yang sudah terstruktur secara kurikulum, BEM FISIP belum memiliki program pendidikan politik tentang kurikulunya sudah terstrutur secara rapi. Hal ini disebabakan dalam satu periode sulit membuat program yang terstruktur sedemikian rupa. Itulah yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri BEM FISIP Wahid Kurniawan.
“Meskipun belun terstruktur kurikulumnya, kita tetap memberikan pendidikan politik berupa diskusi-diskusi. Formatnya FGD (diskusi kelompok yang terarah-red) yang dilakukan sebulan sekali,” ujar Wahid yang kini menjadi Presiden BEM FISIP UNS. Ia menambahkan, dalam diskusi tersebut tidak hanya mengangkat isu plitik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.
Wahid mengatakan, BEM bukanlah partai politik, melainkan representasi negara dalam bentuk student government. Pilihan untuk terjun ke politik praktis adalah keputusan masing-masing kader. Tetapi setidaknya, menurut Wahid, BEM telah memiliki pembekalan politik, pendidikan politik, ataupun pemetaan politik.
Sementara itu, organisasi eksternal kampus seperti Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Surakarta juga mengaku telah melaksanakan pendidikan politik bagi anggotanya. “Meski anggota kami tidak boleh masuk ke politik praktis, namun IMM tetap memberikan pendidikan politik,” kata Ketua IMM Cabang Surakarta Huda. Menurut dia, hal ini bisa bermanfaat bagi aktivis IMM yang ingin terjun ke dunia politik setelah keluar dari IMM.
“Secara formal kita ada pendidikan politik. Misalnya, dengan mengadakan training politik. Selain itu kita juga mangadakan pelatihan secara nonformal,” terangnya. Contoh pelatihan nonformal, kata Huda, yaitu mengadakan diskusi di tingkat pemimpin IMM.
“Kita hanya memberikan informasi dan pendidikan kepada anggota. Terkait nanti mereka mau kemana itu terserah kepada orangnya. Mau terjun ke politik praktis atau tidak
terserah mereka. yang jelas memang kita tidak memiliki jalur ke parleman. Karena IMM tidak memiliki hubungan secara struktural maupun kultural dengan parpol,” tegas Huda.
Meskipun demikian, Huda menyadari bahwa dalam pembangunan negara tetap harus ada yang ke sana. Karena dalam pembangunan tidak hanya dilakukan secara ekstra perlementer tetapi harus dari dua arah. Pembangunan juga dilakukan secara intra parlementer. Hanya saja IMM tidak memilih jalur intraparlementer.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta agaknya sedikit berbeda dalam membekali anggotanya dalam hal politik. Ketua HMI Cabang Surakarta, Eka Nada memaparkan, HMI Surakarta tidak memfasilitasi pembelajaran politik. Menurutnya, HMI hanya mengajarkan nilai-nilai politik yang universal saja. “Lebih tepatnya, HMI tidak mengadakan pendidikan politik kekuasan. Yakni politik yang digunakan oleh partai politik dalam penetapan agenda, penentuan lawan politik, serta mempertahankan kekuasaan,” tuturnya.
Pendidikan politik semacam ini dinilai Aidul justru kurang maksimal bagi pembantukan kader politik. Dalam hal ini, menurutnya gerakan mahasiswa mesti dipelihara, tetapi secara sistematis dan terencana. “Kampus harus memfasilitasi gerakan mahasiswa untuk maju ke politik. Meski secara institusional kampus tetap harus independen,” ungkapnya. Namun, diakui Aidul, pengaturan peran kampus inilah yang sulit. “Takutnya, nanti kampus ikut terseret dan tidak bisa independen,” pungkasnya. (Istiqomah, Adinda, Ema, Ansyor, Eko)

VISI | No. 27/Th. XX/201016
Kesiapan mental tidak terkecuali mahasiswa ketika mencalonkan diri menjadi
anggota legislatif memang menjadi sebuah keharusan. Maka ketika ia diterima ataupun gagal menjadi wakil rakyat tidak akan ada implikasi yang meluas pada pribadi mahasiswa tersebut.
Beberapa kasus stres, depresi, tekanan mental dan gangguan psikologis lain yang menimpa calon legislatif yang gagal, salah satunya disebabkan ketidaksiapan mental. Demikian dipaparkan Tuti Hajrianti, S.Psi, Psi, M.Si, Psikolog sekaligus Dosen Program Studi Psikologi Universitas Sebelas Maret (UNS),
Surakarta. “Itu karena tidak ada kesiapan mental, kalau niatan mereka untuk mengabdi pada rakyat ya sudah, gagal jadi caleg pun masih banyak tempat lain untuk mengabdi untuk rakyat,” tuturnya saat ditemui pada Rabu (29/4).
Tuti juga menegaskan, ketika ingin mencalonkan diri menjadi
Harus Siap Mental Walaupun Gagal
Kegagalan menjadi wakil rakyat tentu akan menjadi pukulan berat bagi calon legislatif dari mahasiswa yang secara psikologis masih labil dan secara politis belum berpengalaman. Bagi yang berhasil, perubahan status sosial menjadi kalangan atas,
sedikit banyak akan mempengaruhi gaya hidup dan pribadi mahasiswa.

VISI | No. 27/Th. XX/2010 17
anggota legislatif, seharusnya mahasiswa memahami konsekuensi yang akan mereka terima. Baik ketika berhasil duduk di gedung dewan maupun jika mereka gagal menjadi wakil rakyat. ”Jadi wakil rakyat itu kan tidak mudah, mereka harus benar-benar menjembatani aspirasi dari bawah ke atas, ” jelas Tuti. ”Ini yang belum dipahami oleh para pemula seperti mahasiswa,” tambahnya.
Selanjutnya Tuti menerangkan, kondisi mahasiswa yang masih labil dan minim pengalaman membuat mahasiswa memang rentan untuk terkena ganggua psikologis pasca kegagalan meraih kursi wakil rakyat. ”Kondisi mahasiswa yang usianya masih muda itu masih labil. Mereka juga belum ada pengalaman sehingga ketika mendapatkan benturan keras, mereka belum siap mental,” Ujar Tuti.
Kekhawatiran akan labilnya mental dan minimnya pengalaman mahasiswa berpengaruh terhadap keadaan mereka setelah menjadi anggota legislatif ditepis oleh partai politik dan calon legislatif dari kalangan mahasiswa. Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, Yayuk Purwani mengatakan partai berharap besar pada mahasiswa. “Kami optimis pada mahasiswa. Kita butuh perubahan dan mahasiswa punya semangat dan inovasi-inovasi segar untuk melakukan itu,” jelas Yayuk saat ditemui pada Senin (30/3).
Sementara itu, calon Legislatif dari Partai Matahari Bangsa (PMB) yang masih berstatus mahasiswa, Barid mengungkapkan, mahasiswa sekarang telah tersebar ke beberapa partai. Itu sebagai bukti perubahan mahasiswa. “Mahasiswa mungkin minim pengalaman tapi sekarang kita sudah mau belajar,” tegasnya.
Tuti menyarankan mahasiswa untuk mengukur kemampuan diri dengan benturan-benturan yang akan dihadapai ketika mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. ”Jangan sampai harapan itu lebih tinggi dari kemampuan, ” ujar Tuti. ”Ini juga bisa memicu gangguan psikologis pada caleg,” tambahnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Si berpendapat, depresi yang banyak dialami calon legislatif
(caleg) yang tidak berhasil duduk sebagai wakil rakyat adalah karena ketidakseimbangan hidup dalam mengahadapi masalah. ”Banyak yang di awal sehat, optimis, punya modal besar dan massa yang kuat. Tapi kemudian ketika hasil akhir mengatakan dia tidak lolos, maka yang terjadi adalah kekecewaan yang luar biasa,” jelasnya.
“Kalau sudah begitu kan, mereka tidak bisa apa-apa. Bisanya cuma merenungkan nasib, ini yang menimbulkan potensi untuk gangguan psikologis. Depresi itu kan diawali gangguan psikologis semacam ini,” tambah Susatyo.
Disinggung apakah depresi yang dialami caleg dari kalangan mahasiswa apakah akan lebih besar atau tidak, Susatyo melihat hal tersebut tergantung dengan skill individu mahasiswa itu sendiri. ”Jika mahasiswa itu terbiasa berinteraksi dengan lingkungan, beragumentasi dan berorganisasi, biasanya mereka akan lebih kuat bertahan, ” tutur Susatyo.
Selanjutnya ia menjelaskan, mahasiswa yang mempunyai kemampuan seperti itu terbiasa bertahan, meski gagal dalam perjuangan. Perjuangan mahasiswa yang masih murni dan tanpa orientasi materi mengajarkan perlu waktu panjang menuju keberhasilan. ”Perjuangan mahasiswa menjadi caleg bukan untuk materi, jadi tak terlalu masalah ketika gagal. Mereka biasa untuk itu ” imbuh Susatyo.
Berkenaan dengan mahasiswa yang berhasil menjadi anggota legislatif, Susatyo mengatakan, hal itu merupakan buah dari kemampuan mahasiswa sendiri. ”Mereka yang pandai beragumentasi, punya mental stabil dan berada pada kendaraan politik yang kuat tentu akan berhasil, ungkapnya pada Kamis (28/5).
Namun Tuti mengingatkan, mahasiswa yang berhasil menjadi anggota legislatif untuk tidak lupa diri. ”Kondisi mental yang belum matang, bisa mengubah pribadi mahasiswa. Sebab mereka tiba-tiba mendapat penghargaan tinggi sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Urgensi Caleg MahasiswaPencalonan anggota legislatif
dari kalangan mahasiswa menurut Susatyo juga cukup penting untuk dilakukan. ”Sistem Pemilu kita sekarang membutuhkan anggota legislatif yang berpendidikan, muda dan punya ideologi, ” jelas Susatyo. Menurutnya kriteria itu ada pada mahasiswa.
Terkait mental mahasiswa sebagai decision maker ketika terpilih sebagai anggota dewan, Susatyo beranggapan hal tersebut dikembalikan ke diri mahasiswa. “Jika sebelum mencalonkan diri dia (mahasiswa-red) aktif mengikuti organisasi mahasiswa, mungkin akan memiliki mental yang baik. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya. Lebih lanjut Susatyo mengatakan, mahasiswa mempunyai keunggulan kognitif, jaringan dan keunggulan pribadi lainnya. Sehingga bukan suatu masalah ketika mahasiswa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. ”Yang sebenarnya harus kita jaga adalah kemampuan mahasiswa mempertahankan ideologi mereka ketika sudah duduk menjadi anggota dewan, ” tegasnya.
Susatyo melihat hal ini belum dapat diwujudkan oleh generasi mahasiswa sebelumnya. “Mahasiswa angkatan reformasi yang sekarang duduk sebagai anggota dewan telah terbawa arus dan megadaikan ideologi mereka,” ujarnya. Ia menggangap, figur-figur yang dulu diharapkan sekarang sudah ikut arus. (Ema, Adinda, Eko, Ansyor, Esti)

VISI | No. 27/Th. XX/201018
Artikel Utama
Selembar potret berwarna hitam putih: memampang fragmen sederhana tentang kaum muda yang mewakili zamannya. Tiga sosok muda yang sedang duduk santai di satu kursi penjalin yang memanjang seraya bercengkrama, yang satu tampak mendengarkan dengan seorang yang lain seperti sedang menyampaikan sesuatu dan lainnya mendengar
sekalipun tampak agak kaku. Nuansa yang hendak disampaikan gambar itu seperti sedang mengabarkan fakta lain tentang sisi lain perjuangan sekaligus hendak mengabaikan fakta tentang sebuah narasi besar yang sedang terjadi yaitu revolusi.
Sosok yang pada gambar tersebut adalah Sjahrir, Soekarno dan Hatta, kaum muda yang mewakili zaman emas entitas keIndonesiaan yang baru disematkan dalam rangkaian tinta sejarah kebangsaan. Lembaran fragmen tersebut adalah bagian dari sejarah yang terlupakan, tertumpuk oleh banyak fragmen orasi-orasi kaum muda diantara lautan
Diskontinuitas Gerakan Kaum Muda oleh Akhmad Ramdhon*

VISI | No. 27/Th. XX/2010 19
massa, terpinggirkan oleh fragmen sengitnya perdebatan dalam sidang-sidang konstituante maupun fragmen perjuangan fisik-bersenjata (yang kemudian diulang-ulang) hingga membuat penegasan tentang arti penting bagi eksistensi mereka yang bersenjata dalam ranah politik maupun publik kelak dikemudian hari.
Mereka yang muda, yang tumbuh bersama kerasnya zaman, tertempa dalam ruang-ruang fisik-politik yang dialektis antara para penjajah dan yang dijajah, untuk kemudian bersama-sama mengurai secara berlahan bangunan negara sebagai sebuah konsepsi baru atas kemerdekaan yang baru saja diraih. Latar belakang dan pilihan politik atas kompleksitas ideologi pada sebuah negara yang sangat muda, tidak menjadikan mereka kehilangan semangat toleransi, kebersamaan maupun perbedaan untuk mewujudkan tatanan yang lebih baik untuk bangsa ini.
Pada titik nasionalisme-lah simpul atas perbedaan yang ada terurai lewat kekuatan argumentasi dalam pertukaran antar pribadi, golongan maupu kepentingan yang harus dipertaruhkan. Hiruk pikuk suara dalam sidang-sidang kaum muda yang hadir diparlemen, terseret pula ke jalananan yang juga menghadirkan kaum muda yang lainnya [MC. Ricklef, 1995]. Optimisme tentang negara baru disepakati menyeruak bersamaan komitmen politik yang teragendakan lewat keputusan konstitusi, pelaksanaan pemilu dan tersedianya jaminan atas keterbukaan media yang menyuarakan kepentingannya masing-masing. Pergulatan tentang perjuangan akan konsepsi Indonesia, gagasan berbangsa dan praktek uji coba demokrasi pada masa itu menjadi kenangan tentang utopia kaum muda yang terwakili oleh fragmen gambar tersebut.
Namun sayang konsistensi akan semangat yang semula terangkai dalam sumpah kaum muda tak berlanjut karena persoalan ketidakseimbangan bandul ideologi. Konflik kekuasaan yang hadir kemudian meniadakan keragaman ideologi yang pernah menjadi motor bagi laju perlawanan atas sejarah kolonialisasi pada awal fase abad
20an. Mereka yang dulu muda dan meletakkan pondasi kesejarahan bangsa, kemudian dibekukan menjadi simbol semata (di-faunding father-kan) oleh kaum muda yang memaksakan dan memonopoli wacana ideologi. Tak ada lagi ruang yang tersisa bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari sejarah perjuangan para muda -yang tak lagi tua- mereka hadir hanya dalam dongeng tentang perjuangan kaum muda dulu namun semangat tentang perjuangan itu tak lagi diajarkan, bahkan disudutkan atas nama kecurigaan.
Slogan tentang kolektivitas pembangunan kemudian menjadi kesepakatan baru yang tak terbantahkan, stabilitas dan kemapanan menjadi tujuan atas semua agenda dirancang. Gerakan kaum muda pada dekade inipun menjadi garda depan yang loyal atas ketiadaan pilihan ideologi yang hadir dalam ranah pengetahuan di negeri ini. Kemapanan ekonomi dan politik menjadi ekspresi sekaligus konsensi bagi mereka yang menggerakkan semangat muda untuk menyepakati ketunggalan sebuah asas bagi negeri yang kompleks ini (Driyarkara, 2002 : hannah arendt dan tindakan politis).
Pembelajaran tak lagi menghadirkan ideologi yang sesungguhnya, pragmatisme tak terhindarkan sebagai konsekuensi bagi pendidikan yang telah kehilangan daya kritisnya (Karl Manheim,1991). Kaum muda kemudian semakin jauh dari apa yang pernah dicita-citakan oleh kaum muda yang sekarang dilekatkan sebagai para pahlawan.
Kondisi tersebut makin berat takkal militerisme ikut merambah ke berbagi relung dan ruang hidup setiap kita tanpa kita mampu untuk menolaknya, birokrasi tumbuh dalam mentalitas yang jauh dari akal sehat, perbedaan dimaknai sebagai konflik yang mesti diintegrasikan, kebohongan menjadi kesepakatan bersama untuk melegitimasi kekuasaan yang arogan dan angka-angka dihadirkan untuk membuat ukuran bahwa kolektivitas pembangunan memang ada pada rel yang seharusnya. Kekuasaan terbangun diatas kekerasan yang ditutup-tutupi, kekuasaan terjaga dari kritik yang dibungkam dan kekuasaan yang direbut dari kaum muda yang
menghargai keragaman ideologi hanya akan mengabsenkan ideologi didalamnya [Kuntowijoyo, 1998].
Kini selepas masa-masa pelemahan kaum muda, kekuasaan yang pernah menjulang diatas manipulasi demokrasi akhirnya tumbang oleh momentum yang dihadirkan oleh kaum muda generasi berikutnya yang telah jenuh atas ketiadaan ruang bagi ekpresi politik. Jalan lapang untuk mengulang kembali sebuah narasi kaum muda yang dulu pernah mengujicobakan demokrasi dalam ragam bentuknya, telah terbuka. Namun absennya ideologi dalam pengetahuan yang diwariskan oleh kekuasaan -yang telah tumbang- sekian lama telah melemahkan makna perjuangan bagi kaum muda kini mencoba membuat garis politiknya sendiri.
Keberjarakan antara apa dipahami dengan apa yang terlihat semakin permanen, pragmatisme yang telah mapan tak mudah dihilangkan begitu saja, keragaman telah pudar bersama jargon-jargon kesatuan, kesadaran dan kekritisan terhapus oleh ketakutan akan ketidasepahaman, bahkan jejaring kekuasaan yang ada serta terikat hanyalah upaya untuk memperlebar lingkup kekuasaan itu sendiri, dimana ironisnya ada berjejal kaum muda yang berdiri mengantri masuk dalam situasi keterjebakan tersebut.
Formasi baru yang datang setelahnya, membuka kran-kran ekspresi politik yang coba dihadirkan dalam euforia perubahan ini, ternyata menghadapi jalan terjal untuk menuju apa yang menjadi titik tolak dari perubahan itu sendiri. Infrastruktur demokrasi yang telah disediakan kini dipenuhi oleh ketidakpastian, yang semakin mengkrucut dari hari ke hari. Konflik kepentingan mengemuka sekaligus menimpa apa-apa yang seharusnya diprioritaskan bagi publik, partisipasi yang menjadi alat ukur bagi berhasil dan tidaknya sistem yang berjalan kini memasuki titik kulminasi yang memprihatinkan; baik atas nama kebebasan, ketidaktahuan maupun administrasi.
Masa depan demokrasi menjadi ajang pertaruhan, bagi mereka yang ingin memapankan kekuasaan serta kepentingannya ataukah mereka

VISI | No. 27/Th. XX/201020
yang tetap percaya bahwa mekanisme dan sistem ini menjadi sarana bagi kita semua merealisasikan cita-cita kita mendirikan negara-bangsa ini. Dan bila ingin mengulang narasi diawal maka pertaruhan ini harus menjadi pilihan bagi gerakan kaum muda yang akan datang untuk tidak mengulang siklus kekuasaan yang senantiasa menghadirkan kerakusan yang memamah tubuhnya sendiri.
Untuk itu, dalam ranah sosiologi-pengetahuan ada prasyarat agar gerakan kaum muda mulai dapat melakukan tawaran atas diskontinuitas gerakan sekaligus menjadikannya sebagai agenda pergerakan. Semuanya diawali dengan semangat untuk membuka kembali cakrawala pengetahuan tentang keragaman ideologi yang ada, tanpa harus membuat penghakiman antara satu dengan lainnya, sebab kehadiran ideologi atas struktur pengetahuan kita memungkinkan keterbangunan kerangka ideal dari abstraksi kenyataan yang ditawarkan.
Dialektika diantara keduanya dan keragaman ideologi akan mensimulasi apa yang seharusnya dilakukan serta apa-apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dari titik inilah subjektifitas terlampaui dan bergerak ke ruang baru yang bernama objektifitas, sehingga anomali kedirian yang tak mempunyai jejak-jejak sejarah akan teredam oleh fakta-fakta kesejarahan yang lainnya. Selepas itu transformasi dari apa yang menjadi bagian dari pengetahuan
secara bertahap tertransformasi dalam ranah yang lebih konkret (Basis, 2003 : edisi piere bourdie). Pengetahuan tak lagi menjadi ruang yang abstrak dalam bentuk imaji, ide maupun teori namun harus dapat diartikulasikan dalam dalam bentuk keterlibatan, keberpihakan maupun keberanian untuk menyatakan; sebab keterlekatan antara apa yang diketahui dengan apa dilakukan menjadi tak terhindarkan.
Dari keduanya, kesadaran secara bertahap terkonstruksi menjadi pengetahuan imanen pada setiap kita. Dalam level gerakan akan terjadi tarik ulur antara keagenan dan struktur yang senantiasa menyerap kekuatan dan kemampuan kita sebagai agen atas perubahan yang akan senantiasa menghadirkan kebaharuan dalam ranah publik yang lebih luas (Robert Mirsel, 2004). Bermula dari kesadaran, keterbukaan menjadi konsekuensi yang terciptakan kemudian. Publik yang mempunyai kesadaran akan terbuka dan komunikatif dalam mengekpresikan semua kepentingannya.
Maka gagasan ruang publik (gagasan Habermas) menemukan urgensinya pada situasi ini dan transformasi yang menjadi gerakan akan mengantarkan publik kemandiriannya (John Lofland, 2003). Pada ruang publiklah, beragam aktivitas individu menjadi aktivitas yang bebas dan setara, individu dapat memaknai relasi komunikasi antar individu dalam pemaknaan-pemaknaan yang subyektif-mendalam,
mampu membangun solidaritas, dimana keterlibatan dan partisipasi menjadi sebuah semangat. Ruang-ruang publik, menjadikan publik mandiri, dalam menentukan sikapnya atas beragam pilihan-pilihan politik yang ada dan secara mandiri pula mampu membangun keberjarakannya dengan kekuasaan, yang sering kali tak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar publik.
Pada posisi inilah ruang publik kemudian melampaui berbagai bayangan tentang keterwakilan mereka oleh infrastruktu politik yang ada. Sehingga terciptalah sebuah artikulasi kepentingan publik yang terorganisir dan tak lagi hanya berupa kepentingan massa yang mudah terbelah, rentan akan intervensi dan termaknai dalam bentuk kepentingan sesaat.
Terakhir, pertanyaan yang mesti diajukan adalah dari mana semua itu bermula. Maka jawabannya adalah bermula dari ruang-ruang yang memberikan proses pembelajaran yang menghidupkan kembali ideologi bersama utopia pada saat yang bersamaan, pembelajaran yang mengurai subjektifitas. Pembelajaran yang memberikan kesadaran sekaligus transformatif dan pembelajaran yang berani melakukan keberpihakan dalam ranah yang lebih luas dari sekedar soal-soal pengetahuan.
Karena disanalah pembelajaran yang sesungguhnya terjadi, diartikulasikan dan direfleksikan sebagai sumber-sumber pengetahuan, kesadaran sekaligus embrio gerakan. Pada pembelajaran tersebut kaum muda-lah yang menjadi subjek atas semua proses yang ada didalamnya, dimana ruang tersebut terbentang dalam medan ruang yang tak terbatas; seperti apa-apa yang pernah di dapat oleh Sjahrir muda Soekarno muda, dan Hatta muda kala itu.
* Penulis adalah Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

VISI | No. 27/Th. XX/2010 21
Sekaken
Mengenalkan UNS lewat media audio visual merupakan langkah
mutakhir yang dilakukan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) UNS. Menurut Kepala Humas dan Kerjasama UNS, Dr. Widodo Muktiyo, SE, M.Comm, alasan dibalik penayangan itu acara sangat erat kaitannya dengan branding UNS. Dimana melalui acara yang memberikan informasi segala hal yang berkaitan dengan UNS tersebut, mampu meningkatkan brand UNS di mata masyarakat. UNS Menyapa sendiri ditayangkan sejak 25 Agustus 2008 di TA TV dan 14 Oktober 2008 di Jogja TV.
Namun, selama berjalannya acara tersebut, masih banyak mahasiswa dan warga Solo yang belum menonton. Handoyo, mahasiswa alumnus Fakultas Ilmu Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS mengatakan, ia belum pernah menonton UNS Menyapa. “Saya belum pernah menonton acara itu, tapi saya tahu dari teman-teman,” ujar Handoyo saat ditemui di tempat tinggalnya di daerah Kentingan Solo, Selasa (28/4).
Kurang gencarnya promosi yang dilakukan oleh Humas UNS terhadap acara ini menjadi alasan. “Saya jarang melihat iklan UNS Menyapa di TA TV,” jelas Handoyo. Ia juga menambahkan bahwa harus ada promosi langsung ke mahasiswa. ”Pihak UNS seharusnya memberitahukan langsung ke mahasiswa mengenai tayangan acara UNS Menyapa, pada seminar-seminar misalnya,” tambah Handoyo.
Sedangkan Madyo Utomo (59), warga Kerten Surakarta mengakau ia tidak tahu acara UNS Menyapa. Namun, setelah VISI menjelaskan format acaranya, ia merasa bahwa
acara tersebut sangat bagus bagi orangtua, ”Ya, bagus untuk orangtua yang belum tahu UNS itu seperti apa, jadi orangtua mengerti apa saja yang dipelajari anaknya,” ujar Madyo saat dihubungi VISI pada Jum’at (8/5).
Ironisnya, masih ada di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surakarta yang belum tahu acara UNS Menyapa. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi mengenai jurusan-jurusan yang ada di UNS sebagai bahan pertimbangan dalam mencari perguruan tinggi.
Salah satu siswa SMA Negeri 3 Surakarta, Awan Bagus, mengatakan bahwa ia lebih sering bertanya kepada teman-temannya yang sudah kuliah di UNS. ”Cari info lewat tanya-tanya ke teman-teman yang sudah kuliah di UNS. Jadi kalau info UNS saya tanya ke orangnya langsung,” terangnya
Tingkatkan Branding Lewat UNS Menyapa
“Selamat sore warga Kota Solo, kita berjumpa lagi di acara UNS Menyapa,” begitulah sepenggal kata yang diucapkan oleh pembawa acara UNS Menyapa di Terang Abadi Televisi (TA TV) Surakarta. Acara yang tayang setiap hari Senin pukul 16.00
ini menyiarkan program-program pendidikan (prodi) yang ada di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

VISI | No. 27/Th. XX/201022
ketika diwawancarai VISI pada Selasa (7/7).
Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diutarakan oleh siswa SMA Negeri 3 Surakarta Hardian Kris Nugraha ketika ditemui VISI pada Selasa (7/7). “Saya, tertarik masuk UNS karena kualitasnya bagus. Saya lebih suka browsing dan datang langsung ke UNS. Pernah sekali nonton UNS Menyapa, menurut saya cukup bagus untuk referensi,” jelasnya.
Berbeda dengan Handoyo dan Madyo, mahasiswa alumnus Fakultas Ekonomi (FE) UNS, Indra Hutama mengatakan bahwa ia sudah pernah menonton acara tersebut, ”Saya pernah beberapa kali menonton acara UNS Menyapa. Namun saya bosan dengan konsep acaranya, karena hanya menampilkan pejabat-pejabat UNS.”
Ia juga mengatakan bahwa konep acaranya belum menarik dan kaku. Sebab, mnurutnya narasumber yang dihadirkan kebanyakan dari pejabat kampus, jarang dari mahasiswa dan UKM.
Selain itu, Indra menambahkan waktu tayang UNS Menyapa dirasa kurang tepat. “UNS Menyapa sebaiknya ditayangkan pada malam hari, karena jika sore hari banyak orang yang tidak menonton karena tidur atau belum pulang dari kantor.”
Menanggapai banyaknya masyarakat yang belum pernah menonton UNS Menyapa, Widodo mengatakan bahwa pihak Humas sudah cukup banyak melakukan promosi. Pihak Humas UNS sendiri melakukan promosi melalui iklan baik
di media elektronik maupun cetak. Widodo juga menambahkan intensitas iklan yang ada juga cukup tinggi. “Rata-rata per hari iklan UNS Menyapa tayang 25-50 kali,” tambahnya.
Namun, Widodo menyayangkan tidak adanya rating mengenai acara-acara di TA TV termasuk acara UNS Menyapa. “Hal ini menyulitkan kami untuk mengetahui seberapa besar tingkat antusiasme masyarakat terhadap acara UNS Menyapa,” tutupnya.
Terlebih Dulu adalah NamaBila ditelusuri secara historis,
berdasarkan dasar hukum pendirian UNS, Keppres Nomor 10 tahun 1976, tertulis bahwa UNS adalah Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang merupakan integrasi dari beberapa perguruan tinggi, diantaranya: IKIP Negeri Surakarta, Akademi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Olahraga Negeri Surakarta, Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional, dan Universitas Gabungan Surakarta, yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi swasta. Singkat kata, UNS, memiliki nama “asli” Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret. Namun seiring dengan berjalannya waktu, singkatan dari UNS juga turut berubah. Dengan berbagai fakta yang dapat dilihat baik melaui surat maupun palang nama UNS di boulevard, pihak universitas menghilangkan nama Universitas Negeri Surakarta dan kemudian hanya menuliskan Universitas Sebelas Maret.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Humas Dr. Widodo Muktiyo, SE, M.Comm, mengatakan UNS adalah Universitas Sebelas Maret. “UNS sangat unik, sudah menjadi brand. Jadi nama UNS tetap digunakan walaupun singkatannya adalah Universitas Sebelas Maret karena nama UNS sendiri berhubungan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, sulit diubah,” Ujar Widodo saat ditemui VISI (27/4) di FISIP.
Menurut Widodo pula, isu perubahan nama UNS menjadi USM (Universitas Sebelas Maret-red) pernah diperdebatkan beberapa waktu lalu. “Tapi nama UNS sudah melekat, bila namanya diganti, kita harus membangun brand image kembali dari nol,” Ucap dosen berkumis itu ramah. “Dan sekarang kami, Humas UNS sedang membangun brand UNS Solo, jadi kami harapkan tidak ada perdebatan tentang nama lagi, lebih baik kita menguatkan brand UNS Solo.”
Dapat kita lihat di website resmi UNS, tertulis Universitas Sebelas Maret (UNS Solo). Agaknya pihak universitas mulai menggalakan nama UNS Solo dari sana. Selain itu, pihak universitas melalui Humasnya, sibuk menyosialiasasikan nama UNS Solo melalui berbagai program, mulai dari branding di setiap spanduk maupun baliho, sampai diproduksinya acara “UNS Menyapa” yang ditayangkan berkala di TA TV dan Jogja TV. (Sesar, Wahyu, Filia)

VISI | No. 27/Th. XX/2010 23
Berawal dari BlogFest Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang
diselenggarakan 22 April lalu, UNS yang digawangi oleh tim Blog Center menyosialisasikan Blog UNS kepada civitas akademika kampus. Anggota tim Blog Center Rudi Susanto mengatakan bahwa acara tersebut dibuat semenarik mungkin untuk menjaring minat civitas akademika supaya turut bergabung di Blog UNS. Acara yang sudah dipersiapkan selama dua bulan itu mendatangkan bintang tamu Raditya Dika dan Melanie Soebono. “Persiapan tersebut melingkupi pengonsepan acara sampai dengan teknis acara,” ujar Rudi yang juga terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) saat ditemui VISI di Pusat Komputer (Puskom) UNS Jum’at (5/6). Sistem penilaian yang dijadikan acuan WCU salah satunya adalah dengan standar Webometrics. Webometrics adalah lembaga yang memetakan kekuatan dunia maya suatu perguruan tinggi di bidang social networking baik internal dan eksternal. “Nantinya jika UNS memiliki tingkat eksistensi yang tinggi maka akan semakin tinggi pula peringkat webometrics yang dimilikinya,” ujar Kepala Kantor Humas Dr. Widodo Muktiyo, SE, M.Comm. Widodo menambahkan indikator penilaian dalam Webometric antara lain tingkat traffic, kunjungan, maupun acuan literatur bagi perkembangan ilmu pendidikan. Saat
ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada Rabu (27/4) Widodo mengatakan bahwa website dan blog merupakan bentuk UNS yang ada di dunia maya. Dalam penilaian webomatric periode bulan bulan Juli 2009, UNS menempati peringkat 1617 dunia, atau peringkat 6 Perguruan Tinggi di Indonesia. Hasil ini jauh meningkat dibandingkan peringkat pada periode Januari 2009, yaitu ke 2159. Peringkat UNS dalam webometrics dapat dilihat di www.webometrics.info.
Penggalakan blog, tingkatkan peringkat
Peringkat yang dicapai oleh UNS di Webometrics tidak didapatkan dengan instan. Namun merupakan kerjasama dan dukungan setiap civitas akademika UNS di dunia maya. Dari perilaku kecil blogger UNS di dunia maya, ternyata berefek besar terhadap peringkat kampusnya di dunia nyata.
Hal tersebut dibenarkan oleh Diah. Namun, ia menyayangkan banyaknya civitas akademika yang masih memandang rendah blog dan tidak tahu apa itu blog. “Jadi harus ada pengenalan lagi tentang blog,” ujar Diah mahasiwa Fakultas Sastra dan
Website ataupun blog tidak hanya menjadi sarana social networking untuk menyampaikan gagasan lewat dunia maya. Aktivitas tersebut juga menjadi salah satu kriteria penilaian apakah suatu perguruan tinggi layak mendapat predikat World Class University (WCU). Bagaimana bisa?
Seni Rupa, Blogger dan anggota komite Blog UNS pada Kamis (11/6).
Hal senada juga diungkapkan Rudi. Ia menambahkan pentingnya menggalakkan blog-blog yang telah ada dan membuat blogger (sebutan untuk pengelola blog) terus berkarya. “Jujur selama ini hal tersebut menjadi salah satu hambatan kami,” jelasnya.
Untuk membangkitkan minat tersebut, Rudy dan timnya berencana untuk mengadakan Blogfest UNS secara berkala. Ia menjelaskan bahwa sejak awal sudah memiliki rencana untuk menstimulus anggota agar tetap aktif dalam bentuk pertemuan yang membahas hal akademik. “Kami ingin pegiat blog UNS terus aktif, tidak hanya bergaung kala blogfest saja,” terang Rudy.
Dalam perkembangannya Rudi berharap makin banyak civitas akademika yang bergabung dengan Blog UNS. “Memang banyak blog-blog yang telah ada. Namun, ada baiknya civitas akademika bangga memiliki blog dengan almamater UNS,” ujarnya sambil menunjukkan blog kesayangannya. Rudi menambahkan sampai saat ini blogger UNS yang terdaftar telah melewati 800 anggota. (Sesar, Wahyu, Filia)

VISI | No. 27/Th. XX/201024
Papikostik merupakan tes manajerial yang mengukur profil kepribadian, antara lain
meliputi peran pemimpin, keinginan berprestasi, penyelesaian tugas, pembuatan keputusan, berfikir teoritis, irama kerja, dukungan kepada atasan, mengikuti aturan dan arahan, bekerja dengan detail, keteraturan, kendali emosi, dll. ”Artinya, tes papikostik adalah tes untuk mengukur kepribadian dan softskill seseorang,” ujar Koordinator tes papikostik UNS Dra. Tuti Hardjajani M. Si, ketika ditemui VISI di lobi Gedung 1 Fakultas Ekonomi UNS, Jumat (11/12).
Senada dengan Tuti, Psikolog Dra. Salmah Lilik menjelaskan, tes papikostik adalah tes untuk memprediksi kepribadian seseorang. ”Tes ini mengungkap need (kebutuhan-red) seseorang. Nah, dari kebutuhan tersebut nantinya akan menggambarkan kepribadiaannya,” kata Salmah saat ditemui VISI di ruang Kepala Jurusan (Kajur) Program Pendidikan (Prodi) Psikologi, Fakultas Kedukteran UNS, Selasa (15/12). Dalam tes tersebut, kata Salmah, peserta akan memilih jawaban yang mencerminkan dirinya. Sehingga hasil dari tes ini dapat mengungkap kepribadian mereka.
Ada beberapa komponen yang diujikan dalam tes papikostik antara lain komponen pekerjaan, kepribadian dan sosial. Hasil tes yang tertera dalam sertifikat yang diberikan kepada peserta meliputi Intelegent Quetion (IQ), kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan logika, kemampuan spasial, kualitas bekerja, kepemimpinan, responsibilitas, kontak sosial, gaya bekerja, temperamen, dan kemampuan melayani. ”Peserta disuruh untuk memilih dua pilihan yang sesuai dengan kondisinya. Dari jawaban tersebut akan menunjukkan kepribadian dirinya,” jelas Salmah.
Digelarnya tes Papikostik tersebut dilatarbelakangi oleh pihak kampus yang tidak memiliki database mengenai softskill mahasiswa. ”Padahal di lapangan kerja, bukan hanya hardskill yang dibutuhkan tapi juga softskill.
Inilah yang kemudian membuat UNS mengadakan tes ini,” tutur Tuti. Ia menambahkan, nantinya tes ini akan selalu diadakan bagi tiap angkatan untuk seluruh jurusan yang ada di UNS.
Diharapkan dengan adanya tes ini nantinya akan bermanfaat bagi lulusan mahasiswa dimasa depan saat mereka terjun ke lapangan kerja. Seperti yang diungkapkan Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Drs. Suyatmi M. Si, ”Tes ini diharapkan akan bermanfaat bagi lulusan mahasiswa saat mencari pekerjaan kelak.”
Tuti juga menyampaikan hal yang serupa. Ia mengatakan dari hasil tes nanti, akan diketahui skornya. ”Skor yang kurang tinggi, tandanya harus diperbaiki. Misalnya, kalau kepemimpinan yang rendah, nanti bisa ditingkatkan. Ini kan tentu bermanfaat bagi dimasa depan mereka kelak,” tuturnya.
Belum SesuaiBermanfaat atau tidaknya tes
tersebut tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Hal tersebut diakui Tuti. Menurutnya dalam pelaksanakan tes papikostik, kendala yang dihadapi berasal dari peserta sendiri. ”Tergantung apakah mereka (mahasiswa-red) sungguh-sungguh mengerjakan atau tidak. Inikan membuat hasilnya malah dipertanyakan,” tekannya.
Hal senada diutarakan Salmah. Hasil yang memenuhi syarat adalah apabila hasil tersebut sesuai dengan kepribadian peserta. ”Kalau misalnya ada yang mengerjakan meniru teman-temannya, hasilnya tentu berbeda dengan yang keadaan yang sebenarnya. Inikan sia-sia,” ujarnya.
Selain itu, Salmah menambahkan kesesuaian hasil tes tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya, keadaan pelaksanaan tes yang tidak kondusif. ”Misalnya, banyaknya peserta dalam
satu ruangan membuat instruksi mengerjakan tidak dikerjakan dengan jelas. Ini berpengaruh juga pada hasil,” ujarnya.
Adanya ujian papikostik ini disambut beragam oleh mahasiswa khususnya yang mengikuti test tersebut. Misalnya, Oryza Devanti, Mahasiswa Komunikasi FISIP UNS angkatan 2007, mengaku baru pertama mengikuti ujian papikostik. Ia berharap hasil test tersebut dapat membantu dirinya dalam memilih spesialisasi di semester selanjutnya.
Sedangkan menurut mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS angkatan 2007 Nurul Dani, menyayangkan kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan ujian tersebut. “Lain kali diperjelas dulu tujuannnya apa, dan lebih disosialisasikan lagi,” tuturnya. Menanggapi hal tersebut, Salmah mengatakan, ”Sebaiknya dalam tes papikostik memang diadakan sosialisasi terlebih dulu, tes papikostik apa, isinya apa.” Sehingga harapannya, mahasiswa tidak menyepelekan tes ini dan akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh.
Salmah menambahkan, untuk idealnya tes papikostik ini harus diawali dari sosialisasi. ”Sosialisasinya adalah mengenai pengertian dan fungsi tes kepribadian. Dan setelah hasilnya keluar, diadakan sosialisasi lagi terkait hasil tesnya.” Dalam sosialisasi itu, kata Salmah, peserta dapat saling berdiskusi membahas hasil tes masing-masing.
Ujian papikostik yang baru berlangsung satu kali ini tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, agar pelaksanaan ujian yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi. Untuk itu PD III FISIP UNS Suyatmi juga berharap semoga ujian papikostik ini tetap terus diadakan. “Dan hasilnya nanti betul-betul bermanfaat bagi lulusan mahasiswa,” imbuhnya sembari tersenyum. (Filia, Sesar, Wahyu)
Mengukur Kepribadian dan Potensi Kerja melalui Papikostik
Pihak Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melakukan inovasi baru daam mengetes kepribadian mahasiswanya. Yakni dengan menyelenggarakan tes papikostik kepada seluruh mahasiswa mulai angkatan 2006 ke atas. Tes itu serentak dilakukan di seluruh fakultas mulai tahun 2009.

VISI | No. 27/Th. XX/2010 25
Spektrum
Wacana sertifikasi guru dimulai sejak akhir 2003 ketika pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 ayat 1 berbunyi Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi.
Dalam pasal tersebut di atas, tertulis jelas pendidik harusah seseorang yang bekerja professional. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penegasan ini
tersurat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagai pembuktian keprofesionalan pendidik, Pemerintah lalu mengadakan uji sertifikasi guru. Upaya ini dilakukan demi kemajuan mutu guru yang diikuti dengan meningkatkanya kesejahteraan guru. ”Tujuan pertama sertifikasi adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Kepala Bagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Surakarta Drs. Rahmat Sutomo,
M. Pd ketika ditemui VISI di ruangannya, Kamis (2/7).
Hal yang sama juga dinyatakan Sekretaris Pelaksana Ujian Sertifikasi Rayon 13, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M. Si ketika ditemui VISI di kantornya, Rabu (08/04). Dia mengungkapkan tujuan sertifikasi guru adalah meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru.
Oleh karena itu, Sajidan menyatakan perlu ada tahapan untuk menguji profesionalisme guru. Tahapan delakukan lewat uji sertfikasi dengan terlebih dahulu mengumpulkan protofolio pendidik selama masa kerja. ”Portofolio tersebut berupa kumpulan berbagai sertifikat penghargaan yang diperoleh guru bersangkutan, lalu akan dinilai berdasarkan tingkatan jangkauan
Sertifikasi Guru: Sudahkah Berhasil?
Sejak akhir 2007, para pendidik mulai berkesempatan menerima tunjangan profesi dari Pemerintah sebesar jumlah gaji pokok pendidik yang bersangkutan. Syaratnya, pendidik harus mengikuti ujian sertifikasi guna membuktikan profesionalitasnya. Alih-alih menjadi profesional, para pendidik justru mementingkan kebutuhan materi.

VISI | No. 27/Th. XX/201026
penghargaan,” tuturnya. Sajidan menyatakan pendidik berhak lolos uji sertifikasi dan mendapat tunjangan sebesar gaji pokok apabila memperoleh skor minimal 850 dan mempunyai jam mengajar 24 jam dalam seminggu, kata.
Dalam website resmi Disdikpora di www.dikpora-solo.net dikatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menter Pendidikan Nasional No.18 Tahun 2007, peserta yang sudah lolos uji sertifikasi akan menerima sertifikat pendidik serta menerima tunjangan sertifikasi. Sedangkan bagi yang tidak lolos direkomendasikan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) selaku lembaga yang ditunjuk menjadi penyelenggara sertifikasi guru, untuk mengikuti Diklat Profesi Guru atau PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru).
Tergiur TunjanganSiapa yang tak tergiur dengan
tunjangan yang besarnya sesuai dengan jumlah gaji pokok yang diterima. Alhasil, sebagian guru lebih mengejar besaran tunjangan yang diterima daripada meningkatkan profesionalitasnya sebagai pendidik. Seperti dilansir dari Solo Pos tanggal 10 Nopember 2007, LPTK menemukan praktik manipulasi dokumen yang dilampirkan sejumlah guru peserta sertifikasi yang terjadi merata di semua rayon yang menggelar sertifikasi.
Tindakan-tindakan semacam itu menurut Sajidan sebenarnya tidak tepat jika dilakukan oleh seorang pendidik. ”Tujuan sertifikasi ini kan untuk meningkatkan profesionalitas guru yang bisa dinilai dengan empat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sehingga tak sepatutnya jika yang menjadi orientasi utama adalah tambahan gajinya,” jelasnya.
Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap guru yang lolos sertifikasi menjadi hal yang penting.”Menurut pengamatan saya selama ini, kurang ada pengawasan untuk guru yang sudah lolos sertifikasi. Jika sudah lolos, terima uang, lalu selesai, tidak ada tindak lanjut,” ungkap guru SMA Batik 1 Surakarta yang belum lolos sertifikasi, Moch mucharom pada Sabtu (30/5).
Hal senada diungkapkan guru
SMA N 1 Surakarta yang sudah lolos uji sertifikasi H. Teguh menyatakan pengawasan dari Dinas belum berjalan. ”Yang ada adalah pengawasan dari internal sekolah,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Rahmat menyatakan “Secara sistematis penanganan guru-guru pasca sertifikasi sebenarnya ada di LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan). “LPMP berfungsi sebagai penanggungjawab tingkat provinsi. Akan tetapi, pengawasan dan pantauan langsung juga dilakukan oleh Kepala Sekolah dimana guru tersebut mengajar. Sedangkan pengawasan dan pantauan oleh pengawas akademik dan Dinas (Disdikpora-red) secara rutin setiap saat,” ungkapnya.
Menurut pengamat pendidikan, Eko Prasetyo, ketidaksinkronan antara tujuan awal adanya sertifikasi dengan realita di lapangan ini lebih disebabkan karena tidak tepatnya aturan tentang sertifikasi itu sendiri. ”Mestinya peserta didik sendirilah yang bisa mengukur kualitas dan mutu guru, bukan dengan cara uji sertifikasi seperti sekarang ini,” tandas Eko. Menurut Eko, sertifikasi itu manipulatif karena dinilai hanya berdasarkan mengikuti kunjungan, ikut seminar, dll yang sifatnya dapt dengan mudah dimanipulasi. Sehingga guru semakin menjadi objek dari kebijakan pemerintah.
”Seharusnya pemerintah sejak dulu sudah menaikkan gaji guru, meskipun tanpa adanya sertifikasi. Sewaktu kongres pendidikan di Bali pada 1997, sudah disepakati oleh negara-negara di Asia bahwa gaji guru harus dinaikkan,” tutur Eko. Ia juga menjelaskan hanya Indonesia saja yang tidak melaksanakan kesepakatan itu, padahal negara-negara seperti Malaysia dan Thailand sudah melaksanakannya sejak kongres tersebut usai. (Paramita, Wida)

VISI | No. 27/Th. XX/2010 27
Selain sebagai evaluasi, monitoring juga sebagai pengawasan terhadap guru
yang sudah mendapat sertifikat pendidik. Seperti yang diungkapkan Sekretaris Rayon 13, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M. Si. “Jangan sampai guru yang sudah tersertifikasi tersebut sama saja kerjanya dengan yang belum sertifikasi. Ini akan menjadi petaka nasional,” tuturnya ketika ditemui VISI di ruang Pembantu Dekanat Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret, Rabu (8/4).
Menurutnya monitoring merupakan semacam penjaminan mutu terhadap guru yang sudah tersertifikasi. Sajidan menyebutnya dengan istilah Sistem Pembinaan Keprofesionalitasan Guru Pasca Sertifikasi. Sistem ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Surakarta dan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Jawa Tengah.
Monitoring secara keseluruhan dilakukan dengan pengujian empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Untuk memenuhi empat kompetensi yang diujikan tersebut, seorang guru yang bersertifikat harus membuat Rencana Program Pembelajaran (RPP) Tahunan, RPP Semesteran, melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi KBM, dan melakukan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dalam bentuk karya ilmiah.
“Hal ini berlaku pada semua guru, bukan hanya yang sudah sertifikasi. Hanya saja yang membedakan adalah guru yang sudah bersertifikat harusnya lebih bagus dan lebih profesional,” terang Kepala Bagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdikpora Kota Surakarta, Drs. Rahmat Sutomo, M. Pd ketika ditemui VISI di kantor Disdikpora Surakarta, Kamis (2/7).
Selain itu, tahun ajaran 2009/2010 Disdikpora Kota Surakarta membuat edaran yang dilayangkan ke sekolah-sekolah untuk semua guru yang sudah tersertifikasi. “Isinya tentang jam mengajar mereka harus sesuai dengan aturan,” jelas Rahmat.
Saat dikonfirmasi tentang peraturan memenuhi batas jam mengajar, Kepala SMA Negeri 3 Surakarta, Drs. Ngadiyo, M.Pd. mengatakan guru yang sudah sertifikasi harus memenuhi 24 jam tatap muka. “Jika tidak dapat jam, ya dilakukan dengan sistem team teaching, yaitu mengajar dengan lebih
dari satu guru dalam satu kelas. Team teaching tersebut saling membantu dan membagi tugas,” terang Ngadiyo ketika ditemui di ruang tamu sekolah, Kamis (23/7)
Jenjang Sistem MonitoringRahmat menjelaskan
sistem monitoring dilakukan secara berjenjang. “Pengawasan dilakukan kepala sekolah. Ada juga pantauan langsung oleh pengawas akademik dan pembinaan langsung oleh Dinas,” ungkapnya. Pernyataan serupa diungkap Pejabat Humas SMA N 1 Surakarta, Drs. H. Teguh, M. Pd., ”Sistem monitoring dilakukan kepada guru-guru oleh kepala sekolah dan dari dinas kepada kepala sekolah,” ungkapnya ketika dimintai keterangan di Lobi SMA Negeri 1 Surakarta, Kamis (23/7).
Sistem pelaporan juga dilakukan melalui kepala sekolah kepada dinas. “Karena kewenangan guru itu berada pada kepala sekolah,” ungkap Rahmat. Namun, bila dalam monitoring ditemukan sebuah pelanggaran oleh guru yang sudah
Monitoring Sertifikasi Menjawab Keraguan
Pelaksanaan sertifikasi guru telah memasuki tahun ke tiga sejak dimulai pada tahun 2007 lalu. Agaknya, keberhasilan sertifikasi guru masih menyisakan keraguan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk itu, monitoring dirasa perlu sebagai evaluasi setelah sertifikasi.

VISI | No. 27/Th. XX/201028
bersertifikat maka guru tersebut akan diberi punishment oleh dinas.
“Guru yang tidak memenuhi persyaratan, baik itu empat kompetensi tadi maupun jam mengajarnya maka akan dihentikan tunjangan sertifikasinya,” jelas Rahmat. Penghentian tunjangan yang disertai dengan pencabutan sertifikat ini dilakukan dengan prosedur Peraturan Pemerintah (PP) no. 30 tentang kedisiplinan PNS. Pertama dengan teguran lisan, kemudian dilanjutkan teguran tertulis, surat peringatan satu, surat peringatan dua dan terakhir punishment tetap yaitu pencabutan sertifikat beserta tunjangannya.
Sampai tahun 2009, pro dan kontra masih muncul dalam pelaksanaan sertifikasi. Program yang direncanakan berakhir tahun 2015 ini diragukan beberapa pihak akan dapat mencapai tujuannya meningkatkan mutu pendidikan.
Sertifikasi telah menuai banyak kritikan. Mulai dari sistem, proses hingga sertifikasi guru selesai dilakukan. Seperti diungkapkan salah seorang guru SMA Batik 1 Surakarta, Moch Mocharom yang mengaku tidak terlalu optimis terhadap program
sertifikasi guru ini. “Saya kurang bisa jamin, sertifikasi ini hanya sebagai formalitas saja atau memang sertifikasi secara utuh,” kata Moch Mocharom ketika ditemui di ruang kerjanya di SMA Batik 1 Surakarta, Sabtu (30/5).
Selain itu, penyelenggaraan monitoring pasca sertifilkasi juga menjadi pokok tuntutan sebagai akibat ketidakpuasan beberapa pihak. Guru SMA N 8 Surakarta, Bambang Sugoto mengungkapkan perlu adanya monitoring terhadap guru pasca mendapatkan sertifikat pendidik.
“Jadi jangan hanya sertifikasi lolos dan selesai. Seharusnya ada tindak lanjutnya meskipun beberapa tahun setelah itu secara berkesinambungan. Jangan mandek, karena akan menimbulkan persepsi bahwa yang sudah sertifikasi enak, blonjone dhuwur,” jelas Bambang, guru Fisika SMA 8 Surakarta ketika ditemui Rabu (13/5) di tempat parkir SMA 8 Surakarta.
Pada saat proses seleksi, terdapat beberapa guru yang tidak lolos dikarenakan sakit, salah satunya adalah Bambang dan Mocharom. Hal ini mengakibatkan keduanya tidak dapat mengikuti proses sertifikasi
hingga selesai dan terhenti pada tahap Pendidikan dan pelatihan Profesi Guru (PLPG).
Baik Bambang maupun Mocharom tetap berharap agar sertifikasi tersebut memang betul-betul akan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena adanya keraguan-keraguan tersebut monitoring dianggap sebagai syarat sertifikasi agar dapat mencapai tujuan. “Asal ada monitoring, ya optimis,” ungkap Bambang.
Berbeda dengan Bambang, Rahmat merasa optimis sertifikasi dapat mencapai tujuannya. “Ya sangat yakin, tapi yang namanya membangun kualitas itu berbeda dengan membangun sebuah bangunan. Ketika bangunan salah bisa dibongkar. Kalau membangun generasi evaluasinya kan harus jangka panjang,” jelas Rahmat.
Jadi, menurut Rahmat, setiap guru nantinya diharapkan akan profesional dan spesialis dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. “Nanti akan ada pendidikan spesialisasi pada lembaga pencetak guru sebagai tindak lanjut program sertifikasi.”(Yulia, Paramita)

VISI | No. 27/Th. XX/2010 29

VISI | No. 27/Th. XX/201030
Potret

VISI | No. 27/Th. XX/2010 31

VISI | No. 27/Th. XX/201032 2010

VISI | No. 27/Th. XX/2010 33
Laporan Khusus
”Parkir sudah mulai ruwet kalau ada acara-acara besar, bahkan sampai makan badan
jalan” terang Dyka Setyaningrum ketika ditemui VISI Rabu (13/5). Dyka juga melihat ketidakteraturan parkir di tempat-tempat yang ramai di kota Solo seperti di Pasar Gede dan Galabo. Selain keruwetan tersebut, mahasiwi Akademi Kebidanan ini juga menyesalkan tarif parkir yang kadang seenaknya sendiri. Pendapat Dyka diatas hanyalah sebagian pendapat miring tentang kondisi parkir di Kota Solo. Walaupun kota Solo sudah nampak ada kemajuan dari segi fisik, namun parkir tetap menjadi tantangan tersendiri yang belum jelas juntrunganya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perpakiran Kota Solo Soetrisno SE merumuskan lima permasalahan mendasar pada kondisi perpakiran di kota Solo. Kelima permasalahan tersebut mencakup terbatasnya ruang parkir, lahan parkir yang tergeser pembangunan, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) petugas parkir dan kelengkapannya, hingga masalah retribusi yang tidak sesuai.
“Sebenarnya untuk secara keseluruhan kondisi parkir di Kota Solo memang belum maksimal. Semakin banyaknya jumlah kendaraan motor belum bisa diimbangi dengan fasilitas yang memadai,” ungkapnya ketika ditemui di tempat kerjanya, Rabu (13/5). Kondisi ini diperparah dengan semakin terbatasnya lahan
parkir yang tersedia. Seperti yang dilansir situs resmi Dinas Perhubungan Kota Solo, di Solo tercatat memiliki 356 titik perparkiran di 13 rayon, baik on street parking (parkir di pinggir jalan) atau off street parking (tidak menggunakan badan jalan). Kesemuanya dikelola oleh 189 pengelola parkir dan diatur langsung oleh 1670 juru parkir (jukir).
Soetrisno mengaku, potensi lahan parkir di kota Solo sudah semakin berkurang. “Misalnya seperti Taman Parkir di utara Pasar Klewer. Sebenarnya tempatnya cukup luas, tapi karena ada penertiban PKL, arealnya semakin berkurang dan tergeser,” tandasnya. Pegeseran lahan parkir tersebut disadari Soetrisno akan berujung pada penyalahgunaan tempat sebagai ruang parkir. Penyalahgunaan semacam itu kini bisa ditemui di sepanjang citywalk Slamet Riyadi. Padahal, citywalk sendiri adalah wilayah bebas parkir.
Pemerhati transportasi di kota Solo, DR. (ENG) Syafii, juga mengakui adanya permasalahan dengan lahan parkir di kota Solo. “Yang kerap menimbulkan masalah adalah on street parking, seperti di depan SGM (Solo Grand Mall-red) yang setiap malam minggu dipakai dua jalur parkir,” ungkap Syafii ketika ditemui VISI di tempat kerjanya, Selasa (5/5).
Syafii berharap kebijakan parkir ke depannya untuk tidak diarahkan menggunakan on street parking lagi. “Harus diperhatikan
oleh pemerintah kota untuk mencoba membuat kebijakan akan tempat parkir yang memadai,” ujarnya. Syafii mencontohkan adanya pembangunan gedung untuk fasilitas parkir. “Namun aspek kenyamanan juga harus diperhatikan oleh pemerintah maupun developer parkir. Karena tidak semua orang mau menggunakan parkir di gedung bila aksesnya susah,” tambah Syafii.
Masalah lahan parkir ini ditanggapi serius dari pihak UPTD. Soetrisno mengaku telah menyiapkan rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk menjawab masalah lahan parkir tersebut. “Untuk jangka pendek dan menengah kita (UPTD Parkir-red) akan lebih fokus pada pembatasan tempat parkir dan dilakukan pemaksimalan parkir on street. Sedangkan untuk jangka panjang akan ada pengembangan parkir off street(parkir dalam gedung),” ujarnya.
Namun, khusus untuk pengadaan parkir di dalam gedung, baru sebatas dilakukannya uji kelayakan oleh pihak UPTD. “Tahun 2009 memang direncanakan ada uji kelayakan pembangunan lahan parkir, apakah akan dibuat basement atau bertingkat,” tegas Soetrisno. Sedangkan untuk pelaksanaan teknisnya, Soetrisno belum mampu berkomentar lebih jauh. “Mungkin baru bisa dilaksanakan tahun depan,” imbuhnya.
Polemik Perparkiran Kota Solo:Dari Lahan, Tarif, Hingga Masalah Regulasi
Semrawut. Kata yang tepat menggambarkan kondisi perparkiran Kota Solo. Tidak hanya dalam artian
penataan parkir dan penarikan retribusi saja, kesemrawutan bahkan mengerucut hingga tataran regulasi yang berlaku. Penyakit ini tentu saja menjadi nilai minus bagi perkembangan kota Solo
yang telah sedemikian pesat.

VISI | No. 27/Th. XX/201034
Ketidaksesuaian Retribusi ParkirSelain semakin sempitnya
lahan parkir, masalah lain yang selalu menjadi keluhan utama pengguna jasa parkir adalah masalah retribusi yang kadang tidak sesuai. Sebagian besar pengguna jasa parkir yang telah diwawancarai VISI mengeluhkan tarif parkir yang di atas normal. Padahal untuk jumlah penarikan retribusi parkir, sedianya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) kota Surakarta nomor 7 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir pada Bab V tentang Retribusi.
Disebutkan dalam Pasal 23 poin pertama tentang tarif parkir yang sesuai dengan ketetapan Perda (lihat tabel). Disebutkan juga pada poin kedua mengenai pemberlakukan tarif parkir progesif, yaitu kenaikan tarif parkir untuk parkir di atas waktu dua
jam sebesar 50 persen dari tarif normal. Tarif ini akan berlaku pada setiap jamnya.
Soetrisno mengaku masalah retribusi parkir sejak dulu memang menjadi sorotan utama. Dia mensinyalir adanya dua alasan yang melatarbelakangi penarikan retribusi di atas ketetapan yang berlaku. Pertama, adanya kesengajaan dari petugas parkir itu sendiri untuk menaikkan harga, kedua bisa jadi karena ketidaktahuan pengguna parkir tentang tarif progesif parkir.
“Misalnya ada penambahan tarif seratus persen untuk parkir lebih dari dua jam pada tempat-
tempat tertentu,” kata Soetrisno mencontohkan. Keluhan bisa saja muncul karena tidak digunakannya timer dalam pemberlakukan tarif progresif, sehingga pengguna jasa parkir akan merasa tidak nyaman.
Tarif parkir “ngawur” yang kadang dilakukan petugas parkir, ditanggapi berbeda oleh Ketua Paguyuban Penata Parkir (P3S) Surakarta, Samuel Rori. Pria yang akrab dipanggil Sammy ini mengungkapkan, terkadang ada alasan tertentu yang mendorong petugas parkir menaikan tarif parkir. “Bisa jadi seorang petugas parkir menaikan tarif karena kesulitan mengejar setoran parkir mereka pada pihak pengelola parkir,” ujarnya ketika ditemui di kediamannya (30/6).
Pengelola yang dimaksudkan Sammy bukanlah dari pihak UPTD
Parkir, namun pemegang tender parkir di wilayah petugas parkir itu bekerja. Pemegang tender tersebut “memenangkan” suatu wilayah parkir tertentu yang dilelang setahun sekali oleh UPTD. Untuk wilayah parkirnya sendiri sebelumnya sudah melalui survey kelayakan terlebih dahulu yang melibatkan perguruan tinggi seperti Universitas Sebelas Maret (UNS), Paguyuban Mitra Pengelola Parkir Surakarta (PMPPS) dan UPTD sendiri. Seorang pemilik tender sendiri bisa berupa perorangan atau badan usaha sekalipun. Sehingga bisa dikatakan pemilik tender adalah pihak yang mempunyai kuasa atas wilayah parkirnya sendiri.
Dalam kacamata Sammy, pemicu utama dari masalah retribusi parkir adalah naiknya harga tender parkir tiap tahunnya. Secara logika, kenaikan harga tender parkir pada akhirnya akan mendorong pemilik tender untuk menaikan setoran yang harus diberikan petugas parkir di wilayahnya. “Kalau sudah begini dampaknya para petugas parkir akan melakukan apa saja untuk dapat mengejar setoran yang kian melonjak,” tandas Sammy.
Pihak UPTD menyebutkan, kenaikan harga tender tersebut dikarenakan rasio jumlah kendaraan motor yang ada. Namun alasan UPTD tersebut dianggap tidak masuk akal oleh Sammy. “Jumlah kendaraan bermotor memang naik terus, tapi tidak untuk lahan parkirnya,” ujar Sammy. Keberadaan lahan parkir cenderung konstan sehingga jumlah kendaraan yang akan parkir akan konstan juga. “Ini belum termasuk faktor cuaca seperti pada musim hujan yang pastinya akan menurunkan pendapatan,” imbuhnya.
Sammy memprediksi, bila kondisi ini tetap dipertahankan hingga beberapa tahun ke depan, maka bukan tidak mungkin petugas parkir tidak akan mendapat penghasilan lagi. “Masalah seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak dulu, namun sampai saat ini belum ada perubahan yang berarti,” tandas Sammy.
Sebagai sosok yang berangkat dari organisasi yang pro kesejahteraan petugas parkir, Sammy juga menyoroti jumlah setoran yang terkadang memberatkan petugas parkir itu

VISI | No. 27/Th. XX/2010 35
sendiri. Jumlah setoran dari petugas parkir tidak berdasarkan pada pendapatan petugas parkir itu sendiri melainkan berdasarkan hasil survey Tim UPTD tentang potensi pendapatan parkir setempat. “Bisa jadi karena didorong masalah ekonomi, tim survei menentukan jumlah rata-rata pendapatan lebih tinggi. Kenaikan tersebut nantinya berimbas pada setoran petugas parkir yang meningkat pula,” tandas Sammy. Imbasnya jika petugas parkir tidak bisa menyanggupi jumlah setoran per harinya, maka akan dihitung sebagai hutang,
Senada dengan yang diutarakan Sammy, Syafii menyadari bahwa petugas parkir tidak bisa secara mutlak disalahkan bila kadang melakukan penarikan tarif. “Kita tidak bisa secara mutlak menyalahkan petugas parkirnya saja, karena pada dasarnya itu menyangkut masalah sosial, basic need (kebutuhan dasar-red) mereka,” ujar Syafii. Menurutnya, para petugas parkir tersebut sudah mengerti batasan tarif yang ditetapkan di Perda, itu memang menyalahi aturan. Petugas parkir akan didorong untuk melakukan tindak yang menyalahi aturan untuk memenuhi kejaran setoran yang dipatok pihak pemenang tender. Masalah sosial ini semakin kentara karena kebanyakan dari mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap.
Wagimin, salah seorang petugas parkir yang beroperasi di belakang kampus UNS mengaku bahwa dirinya hanya membayar ”uang keamanan” sebagai bentuk setoran. ”Uang keamanan tersebut diminta setiap hari
Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Solo
Jenis Tempat Jenis Kendaraan Tarif Sekali Parkir
a. Pelataran/Lingkungan
Sepeda MotorMobil Penumpang/ Mobil BarangBus sedang / Truk SedangBus Besar/Truk Besar
Rp 500,00Rp 1.000,00Rp 2.000,00Rp 3.000,00
b. Taman
Sepeda MotorMobil Penumpang/ Mobil BarangBus sedang / Truk SedangBus Besar/Truk Besar
Rp 500,00Rp 1.000,00Rp 2.000,00Rp 3.000,00
c. Gedung
Sepeda MotorMobil Penumpang/ Mobil BarangBus sedang / Truk SedangBus Besar/Truk Besar
Rp 1.000,00Rp 2.000,00Rp 4.000,00Rp 5.000,00
Sumber : Perda Parkir kota Surakarta no 7 tahun 2004
oleh anak buah pemilik tender parkir. Besaran setoran bisa dari Rp 3000 hingga Rp 5000,” ujarnya.
Sedangkan Agus, petugas parkir di sebuah warung internet di jalan Kartika Ngoresan juga berpendapat hal yang sama. Bentuk setoran yang ia berikan juga berdalih sebagai uang keamanan. ”Setiap hari diminta Rp 3000. Namun sisa penghasilan masuk ke kantong saya,” terang Agus.
Berpangkal pada RegulasiSammy berpendapat, pangkal
permasalahan parkir sebenarnya terletak pada regulasi parkir itu sendiri. Selama ini partisipasi warga masyarakat dalam merumuskan regulasi-regulasi yang berlaku dianggapnya sangat kurang. Selama ini perumusan regulasi dilakukan “orang dalam” sehingga akan terdapat kecenderungan untuk menguntungkan pihak birokrat.
Selain itu perombakan regulasi diungkapkan Sammy juga harus menyentuh pada ranah manajemen pendapatan. Menurut Sammy potensi pendapatan dari sektor parkir cukup besar. “Jika murni dikelola secara mandiri oleh Pemkot, maka potensi pendapatan bisa mencapai 3 milyar, kalaupun dipotong biaya produksi mungkin keuntungan sekitar 2,5 milyar,” tandas Sammy. Namun, yang terjadi pendapatan parkir saat ini hanya 1,7 milyar. Menurunnya potensi pendapatan tersebut diduga Sammy karena pendapatan sebelum disetor ke pihak Pemkot dikelola oleh pengelola parkir (pemenang tender). “Kecurangan di dalamnya sangat
mungkin terjadi,” imbuh Sammy.Senada dengan Sammy, Syafii
juga melihat perlunya perombakan regulasi pada penetapan lahan parkir. Menurut regulasi yang ada, lajur lambat tidak diperbolehkan untuk parkir. Sayfii mengungkapkan penentuan lahan parkir di lajur lambat sudah berbicara mengenai kepentingan. “Satu sisi, keberadaan toko tersebut membayar pajak dan menjadi pendapatan bagi Pemkot. Tapi di sisi lain jika aturan diberlakukan orang tidak boleh parkir di situ atau dibatasi parkirnya, maka usaha orang tersebut akan bangkrut dan sektor riil terhambat,” tandas Syafii.
Syafii mengharapkan adanya kontrol pemerintah dalam pengelolaan parkir. “Jadi pemerintah tidak hanya mentenderkan saja, tapi juga jangan lepas tangan,” ujar Sayfii. Evaluasi akses-akses pada wilayah parkir juga dinilai Syafii masih belum dilakukan optimal. Untuk itu Syafii berharap adanya evaluasi berkelanjutan sebelum wilayah parkir ditenderkan.
Sedangkan Sammy berharap untuk masalah regulasi ke depannya bisa dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang komisarisnya dibagi menjadi tiga yakni perwakilan pengguna jasa parkir, perwakilan tukang parkir dan pemerintah atau dinas terkait. “Dengan begitu wujud partisipatoris warga masyarakat semakin nyata,” tutup Sammy. (Nanda, Putri, Bhimo, Annisa)

VISI | No. 27/Th. XX/201036
Konon, bila di seragan rompi oranye tersebut tergantung Kartu Tanda Anggota (KTA)
dialah jukir legal. Legalitas tersebut bisa diperkuat dengan karcis yang diberikan kepada pemilik kendaraan sebagai bukti bahwa ia parkir di lokasi tersebut. Jika kedua hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang yang mengaku jukir, maka legalitasnya sebagai jukir perlu dipertanyakan.
“Kita bisa melihat legal nggak legalnya petugas parkir itu dengan melihat ID CARD-nya dan rompi yang dikenakan, “ ungkap mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Fatcuroh Milandari, saat ditemui VISI pada Kamis (29/10)
Seringnya jukir mengabaikan fungsi seragam parkir yang
membedakan jukir ilegal dan legal membuat kredibilitas jukir diragukan. “Kalau saya tidak pakai karena saya sudah lama jadi jukir. Kalau yang berseragam dan berkartu identitas adalah jukir baru,” elak Agus, jukir di depan warung internet (warnet) Spidernet Jalan Kartika Ngoresan, Surakarta. Saat ditemui VISI ia mengaku sebenarnya juga punya seragam dan kartu tersebut, hanya saja karena sudah terbiasa tidak memakai maka seragamnya tidak dipakai lagi.
Keraguan itu diperparah dengan adanya beberapa jukir yang berpenampilan “garang” layaknya preman yang membuat pengguna jasa parkir menjadi risau dan tidak respek. Seperti pengakuan warga Surakarta Ima Dian (21), “Sekarang orang kan menilai secara fisik. Kalau fisiknya jukir amburadul, garang, tatoan, rambut acak-acakan, kan orang jadi takut.” Terlebih jika jukir tersebut terbukti jukir ilegal, maka tindakannya menarik uang parkir tergolong sebagai tindakan premanisme perparkiran.
Premanisme PerparkiranMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, premanisme adalah segala
tindakan yang berhubungan dengan pemerasan dan pemaksaan yang bersifat ilegal didepan hukum. Salah satu bentuk premanisme dalam perparkiran ditunjukkan dengan penarikan di luar restribusi yang telah ditetapkan. Ima Dian pernah mendapati jukir yang berbuat curang. Saat menggunakan jasa parkir di
Seragam rompi oranye dan peluit menjadi “senjata” seorang juru parkir (jukir). Namun tidakk semua yang berseragam tersebut adalah jukir legal. Ada juga yang mengaku jukir, tapi ternyata hanya “preman” parkir.
Ada “Preman” Berseragam Oranye

VISI | No. 27/Th. XX/2010 37
pelataran suatu tempat perbelanjaan, jukir menarik retribusi tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam karcis. Tarif yang seharusnya Rp 500 dinaikkan seratus persen lebih tinggi. “Kan kita bayar sesuai tarif di karcis. Tapi tukang parkirnya nyelemong minta seribu,” ujar mahasiswi FISIP UNS ini.
Penarikan biaya parkir yang tidak wajar ini bertentangan dengan peraturan. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2004 tentang penyelenggaraan tempat khusus parkir, pada pasal 23 mengenai tarif retribusi, jenis tempat pelataran dengan spesifikasi kendaraan sepeda motor harusnya mempergunakan tarif Rp 500 sekali parkir. Ketentuan berlaku untuk satu kali maksimum dua jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan 50 persen dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari satu jam dihitung satu jam.
Kenyataan di lapangan, jukir legal pun terkadang menariki tarif tidak sesuai aturan. “Di sini biasanya tarif dinaikkan kalau pas ramai. Untuk motor kalau hari-hari biasa tetap Rp. 500, kalau pas ramai Rp. 1000,” ungkap Tari, pedagang buku di kios “Pelajar” kompleks toko buku Sriwedari, saat ditemui VISI pada Selasa (9/6).
Dewan Muda Complex’s (DMC) Soloraya selaku salah satu organisasi yang bergerak di bidang perparkiran menyadari permasalahan mendasar dalam penarikan retribusi parkir tersebut. “Pengaplikasian hal tersebut sulit, jadi jukir-jukir tersebut mematok tarif Rp 1000 tidak peduli berapa lama mereka (pengguna parkir-red) parkir. Dan itulah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat,” ucap Deni Nurcahyanto selaku ketua DMC saat ditemui VISI pada Rabu (12/5) di sekretariatnya, Nusukan.
Jukir yang menarik tarif di luar harga normal ini lebih banyak terjadi pada jukir ilegal. Hal ini diungkapkan dosen Sosiologi UNS Sudarsana, “Yang tidak tertib itu biasanya ilegal. Dia (jukir ilegal–red) menjalankan tugas sebagai jukir, tetapi kurang mempunyai tanggung jawab dan menarik biaya parkir jauh lebih mahal dari jukir resmi.” Jukir ilegal biasanya memperoleh backing dari para pimpinan-pimpinan preman. Saat ditemui VISI pada Rabu (10/6) di ruang kerjanya Sudarsono mengungkapkan, “Jukir yang ilegal itu, ya preman, tetapi ada pimpinannya. Sehingga mereka berani melakukan pekerjaan yang sifatnya ilegal itu. Kalau tidak, mesti tidak berani.”
Sebagai pengamat sosial, Sudarsana menyebutkan jukir ilegal tersebut memperoleh perlindungan dari pimpinan preman. Sebaliknya, mereka dikenai kewajiban untuk menyetor sejumlah uang pada pimpinan mereka. “Sebut saja, hubungan timbal balik,” imbuhnya lagi. Pernyataan serupa juga dipaparkan mahasiswa Fakultas Hukum UNS Muson, saat ditemui VISI pada Kamis (11/6), “Dari dulu kulturnya memang sudah dikuasai preman. Dan preman itu terorganisir. Pihak preman mempunyai
backing dari belakang, terstruktur, rapi, dan didukung aparat.”
Pelayanan Asal-asalan Bukan hanya penampilan kurang sopan dan
penarikan retribusi di luar perda, pelayanan yang diberikan jukir terkadang juga membuat resah pengguna parkir. Mereka cenderung mengabaikan pelayanan dan ketentuan perparkiran yang berlaku. Saat pengguna jasa memarkir kendaraan, justru juru parkir tidak berada di tempat. Kalaupun ada juga tidak membantu merapikan atau memberi

VISI | No. 27/Th. XX/201038
aba-aba. Giliran pengguna hendak meninggalkan lokasi, sekonyong-konyong juru parkir langsung mendekati mereka. “Kok nggak ada orangnya tiba-tiba parkir. Agak kecewa juga. Saya kira nggak ada tukang parkir,” ungkap Fatcuroh saat ditemui VISI pada Jumat (12/6).
Sudarsana menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan seenaknya sendiri dan tidak punya tanggung jawab terhadap tugasnya, “Banyak jukir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Artinya ketika kendaraan itu hendak parkir, mereka tidak mengatur. Tetapi ketika mereka meninggalkan tempat parkir, jukir datang dan meminta uang (retribusi-red),” tutur Sudarsana.
Sedangkan Muson menganggap tindakan pelayanan harus dilakukan sebagai brntuk kontraprestasi yang jukir tersebut berikan. “Itu kontraprestasi yang diberikan tukang parkir. Minimal mereka memberikan sesuatu untuk kita. Nggak ada apa-apa tahu-tahu dimintai,” ucap Muson dengan mimik serius.
Kastoto, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS jurusan Ilmu Sosial, beranggapan bahwa banyaknya tindak pelanggaran yang dilakukan jukir terjadi akibat kurangnya kontrol manajemen dari pihak pengelola. Jukir-jukir tersebut belum dididik dan diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung. “Biasanya pelaku usaha kan cuek. Hanya menyerahkan pada koordinator. Padahal mereka kan belum ada briefing, pelatihan dan sebagainya. Jadi ketika kita membuat lapangan usaha, harusnya ada pendampingannya.” terangnya lugas.
Sementara dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Surakarta sendiri, kurang menekankan pada pelayanan prima yang seharusnya diberikan juru parkir. “Memang kebanyakan jukir sekarang itu dari mereka-mereka (preman-red). Tapi selama mereka menghormati peraturan, tidak bertingkah yang merugikan masyarakat, ya tidak apa-apa. Kan banyak yang seperti itu, dari pengelolanya juga ada, tetapi ya tidak semuanya,” ucap Kepala Tata Usaha UPTD Perparkiran Mamik Sumarsih.
Untuk meningkatkan
pengetahuan tentang tata cara maupun tarif parkir dan peningkatan pelayanan, sebenarnya pihak UPTD Perparkiran telah memberikan pembekalan Bimbingan Teknis (Bintek) pada jukir. “Dari pembinaannya, setiap satu tahun sekali diadakan Bintek,” jelas Mamik saat disinggung mengenai pengelolaan parkir.
Seperti ditulis dalam website resmi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta, pada tanggal 30 Desember 2008 lalu telah dikumpulkan 189 pengelola parkir seluruh Kota Surakarta dan perwakilan petugas parkir. Dalam acara yang dilakukan di Bale Tawangarum Kompleks Balaikota Surakarta ini dilakukan pengarahan dan dilanjutkan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengelolaan Parkir Tahun 2009 dilanjutkan penyematan KTA kepada jukir. Pengarahan dan Bintek yang hanya dilakukan setahun sekali belum mampu meningkatkan keprofesionalan para jukir di kota Surakarta.
Kurangnya Peran Masyarakat Adanya tindak premanisme
berupa penarikan retribusi di atas tarif normal maupun pelayanan yang asal-asalan ini, nampaknya ditanggapi masyarakat dengan suatu bentuk kelaziman. Mereka cenderung memaklumi perilaku tersebut. “Pada maklum kok yang makai parkir,” begitu tukas Tari saat diminta tanggapannya mengenai penarikan tarif parkir ini. Senada dengan ungkapan Tari, Ima pun memaklumi penarikan retribusi ini. “Ya sudah lah, kita ngalah saja. Daripada nanti ribut. Hitung-hitung amal lah,” ujarnya pasrah.
Pemakluman yang diutarakan masyarakat seperti ini justru akan memperparah kondisi perparkiran. Bisa jadi, pemakluman ini disebabkan karena rasa takut bila melawan pihak jukir. “Masyarakat itu membayar sesungguhnya karena terpaksa. Meraka khawatir akan terjadi apa-apa (lecet atau hilang-red) kalau tidak membayar parkir sesuai yang dikehendaki jukir,” tutur Sudarsana.
Kastoto mengungkapkan, masyarakat memilih diam karena kurangnya kesadaran hukum dari pihak pengguna parkir. Mereka takut jika melawan akan terjadi tindakan anarki dari juru parkir yang
bersangkutan. “Di Indonesia kan sudah ada lembaga yang melindungi konsumen, seharusnya hal ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” paparnya saat ditemui VISI di rumah kostnya.
Pihak Dishub UPTD Kota Surakarta sebenarnya telah menyediakan layanan dalam menindak lanjuti juru parkir yang tidak mengindahkan tarif peraturan daerah. “Kadang-kadang ada yang komplain. Kalau ada yang telepon ke sini, dari pihak sini langsung meluncur ke sana,” ujar Mamik Sumarni tegas. Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan gabungan antara Kkjaksaan, Kepolisian Kota Besar (Poltabes), Corps Polisi Militer (CMP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan juga dari pihak Dishub.
Kastoto juga mengungkapkan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan premanisme di perparkiran. “Kalau ada kerjasama antara Pemda, pelaku usaha, juga koordinator lapangan dari tim parkir sendiri, nanti akan terbentuk kondisi parkir atau suasana bisnis yang bagus,” ucap Kastoto yakin.. Ia menambahkan lagi, antara jukir dengan pengelola maupun dengan pihak UPTD juga harus ada saling keterkaitan. “Masing-masing pihak memiliki andil yang besar dalam penanganan parkir di Kota Surakarta, “imbuhnya.
Dengan kondisi seperti itu diharapkan akan terjadi suasana yang kondusif dalam perparkiran. “Diharapkan semakin hari akan semakin tertib. Dari tertib pengaturan parkir sampai tarif resmi. Akibatnya retribusi menyumbang PAD (Pendapatan Anggaran Daerah-red) juga bagus dan masyarakat terlindungi,” ucap Sudarsana penuh harap. (Bhimo, Nanda, Putri, Annisa)

VISI | No. 27/Th. XX/2010 39
Sedikit ada kesulitan ketika VISI berusaha mewawacarai juru parkir (jukir) satu ini. Januar
Erdian atau lebih akrab dipanggil Pak Gembong adalah jukir di jalan Sutan Syahrir tepatnya di pertigaan Tambak Segaran, Kepatihan Kulon, Jebres, Solo. Pria berumur 31 tahun ini, sudah menjadi jukir sejak tahun 1988 silam.
Kepada VISI, Pak Gembong mengaku bahwa dirinya memang terlahir dalam kondisi tidak sempurna baik fisik maupun mental. Selain cacat fisik yang dideritanya, Pak Gembong juga menderita down syndrome yang sedikit banyak menyulitkan dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain.
Kondisi yang tidak sempurna itulah yang mendorong Pak Gembong
untuk menjadi seorang jukir. “Karena kondisinya cacat seperti ini, ya jadi tukang parkir saja,” ujar Pak Gembong ketika ditemui VISI di masjid Al-Fath Kepatihan Kulon, tempat dia biasa beristirahat, Jum’at (12/6). Menurut Pak Gembong, dengan kondisinya yang seperti itu justru akan menarik simpati pengguna parkir.
Dengan gaya bicaranya yang khas, Pak Gembong menuturkan cerita hidupnya selama menjadi jukir. Awalnya Pak Gembong menjadi jukir di daerah Masjid Solihin sebelum akhirnya dipindah di Kepatihan Kulon hingga sekarang. Kepindahannya dikarenakan Pak Gembong masih tinggal bersama orangtuanya yang memutuskan untuk pindah rumah.
Menjadi seorang jukir merupakan inisiatif Pak Gembong sendiri. “Daripada pengangguran terus melakukan hal-hal yang tidak baik, mending jadi jukir saja,” tutur Pak Gembong sembari tertawa. Disinggung mengenai pendapatan dari menjadi seorang jukir, Pak Gembong mengaku tidak pernah mempermasalahkannya. “Saya santai saja, kadang 10 ribu, 25 ribu tergantung ramai atau tidak, yang penting tidak diam saja,” ujarnya.
Apa yang dialami Pak Gembong sedikit banyak juga dirasakan oleh Sadimun, jukir yang biasa beroperasi di daerah Coyudan Solo. Pria kelahiran 15 Agustus 1943 ini sudah menjalani profesi sebagai jukir sejak 27 tahun yang lalu.
Ketika ditemui VISI disela kesibukannya, Sadimun dengan ramah menuturkan kehidupannya menjadi jukir dengan kondisi yang “berbeda” dengan yang lain. Sebelum memutuskan untuk menjadi jukir seperti sekarang, dulunya Sadimun bekerja di Koperasi Penderita Cacat Harapan di Kentingan Solo. “Di situ saya menjadi karyawan administrasi sejak tahun 1955. Di sana banyak teman-teman yang keadaannya sama-sama kurang, jadi merasa senasib seperjuangan dalam mencari nafkah,” ujar Sadimun.
Dalam sebulan, Sadimun mampu menyetor uang Rp 175.000 kepada pemilik tender. Jika dihitung, penghasilan bersihnya per hari sekitar Rp 20.000. “Kalau sedang beruntung bisa sampai Rp 50.000 per hari, tergantung tingkat keramaian kendaraan yang parkir di daerah saya,” tandas Sadimun.
Jukir-jukir Penyandang Cacat di Kota SoloPerbedaan yang Tidak Membedakan Mereka
Perkataannya sedikit sulit dicerna oleh pendengaran orang pada umumnya. Butuh konsentrasi ekstra untuk dapat mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terkesan “minimalis”

VISI | No. 27/Th. XX/201040
Namun Sadimun berpendapat bahwa penghasilan menjadi jukir sekarang ini cenderung menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dulu sebelum banyak mall dibuka di Solo, wilayah ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan kota Solo. Mulai dari toko batik, emas hingga sepatu ramai dikunjungi masyarakat,” imbuh Sadimun pada VISI. Banyaknya pusat perbelanjaan yang dibangun sekarang ini secara otomatis menyedot jumlah pengunjung yang datang ke Coyudan.
Terlepas dari menurunnya omset pendapatan yang Sadimun rasakan sekarang, penghasilannya sebagai jukir terbukti mampu membiayai kebutuhan pendidikan kelima anaknya. Tidak tanggung-tanggung, kelima anaknya bisa disekolahkan Sadimun hingga mendapat gelar sarjana. Sadimun mengaku bahwa anak-anaknya kini sudah hidup mapan. “Sekarang sudah mapan semua, ada yang buka bengkel di Bali, ada yang menjadi guru olahraga, bahkan anak terakhir saya berkerja di Bursa Efek Jakarta,” katanya bangga.
Karena semua anak-anaknya sudah hidup mapan, Sadimun tidak terlalu dipusingkan dengan biaya hidup sehari-hari. “Penghasilan dari jukir saya gunakan untuk biaya tanggungan acara di kampung, seperti jagong (undangan pernikahan-red) dan melayat. Kalau untuk biaya makan sehari-hari sudah ditanggung anak-anak” terang Sadimun.
Pertimbangan Sisi ManusiawiKetika VISI mencoba
mengonfirmasi nasib jukir cacat ini, Soetrisno selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir kota Solo mengaku tidak bisa berbuat banyak. “Kita tidak bisa menolak jika ada penyandang cacat yang mendaftar menjadi jukir, idealnya memang kita mencari yang mempunyai kemampuan fisik yang baik,” terang Soetrisno ketika ditemui di tempat kerjanya, Rabu (13/5).
Menurut Soetrisno, keberadaan penyandang cacat yang mendaftar menjadi jukir seringkali membuat pihaknya dilematis. “Di satu sisi mereka memang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, namun
kita sebagai manusia juga tidak tega bila melihat keadaan mereka (penyandang cacat-red),” imbuh Soetrisno. Menurutnya seorang jukir tidak hanya dituntut untuk memungut bayaran saja tetapi juga dapat mengarahkan, memberi aba-aba, juga menertibkan lalu lintas areal sekitarnya.
Jika dilihat pada Peraturan Daerah (Perda) kota Solo nomor 7 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir, memang tidak ada pasal yang khusus mengatur kualifikasi seorang Petugas Parkir atau jukir. Pasal yang menyinggung petugas parkir hanya sebatas hak dan kewajibannya saja, tertera pada Bab IV tepatnya pasal 12 dan pasal 15.
Dalam pasal 12 dijelaskan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh setiap petugas parkir. Hak tersebut mengatur tentang perolehan penghasilan sebesar 25 persen dari potensi pendapatan parkir, pungutan retribusi parkir yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak untuk mendapat jaminan sosial dan hak mendapatkan seragam dan kelengkapan lainnya.
Sedangkan dalam pasal 15 diatur mengenai kewajiban petugas parkir untuk menyerahkan bukti retribusi parkir, pelayanan pada pengguna jasa parkir, perlindungan keamanan, pertanggungjawaban kehilangan hingga pemenuhan tarif retribusi yang berlaku.
Saat ditanya VISI mengenai kewajiban-kewajiban tersebut, Sadimun mengaku bisa melakukannya dengan baik. Kendati hanya menggunakan satu tangan, dirinya mampu mengatur tata letak motor yang parkir. “Saya nggak mau kalah dengan jukir yang lain. Jika saya tidak bisa mengatur parkir, bisa-bisa rejeki saya kabur dan tidak bisa memberikan nafkah keluarga,” terang kakek dengan tiga orang cucu ini.
Sambil sesekali menyeka keringatnya yang mengalir, Sadimun kembali menceritakan kisahnya menjadi seorang jukir cacat. “Meskipun cacat, saya tergolong aktif lho,” serunya bersemangat. Semangatnya ditunjukkan dengan pengabdiannya sebagai jukir yang bertanggung jawab. “Buktinya sampai
sekarang belum pernah ada kasus pencurian motor, helm ataupun jaket,” tandasnya.
Jika Sadimun mampu tampil total dalam profesinya sebagai jukir, lain lagi dengan Pak Gembong. Pria murah senyum ini hanya bertugas setengah hari saja. Pihak UPTD memberi dispensasi mengenai pembebasan jam kerja. Kendati dibebaskan jam kerjanya, Pak Gembong adalah jukir resmi dari UPTD. Kelegalannya dibuktikan dengan Katu Tanda Anggota (KTA) yang dimilikinya.
Walaupun jam kerja Pak Gembong bisa dibilang minim, dirinya mengaku sudah mempunyai pelanggan tetap. Kebanyakan pengguna jasa parkir yang akan parkir di wilayahnya sudah hafal dengan Pak Gembong, sehingga memudahkan dirinya untuk berinteraksi dengan mereka.
Ditanya mengenai suka duka menjadi seorang jukir yang “berbeda” dengan lain, baik Sadimun maupun Pak Gembong mengungkapkan hal yang tak jauh beda. Sadimun mengaku lebih banyak suka yang didapat daripada dukanya. “Orang Solo sejak semula sudah menerima keadaan cacat seperti saya. Mereka terbuka sekali, saya yang cacat seperti ini, dianggap seperti orang-orang lainnya,” ujarnya.
Pak Gembong juga mendapati hal yang sama dengan Sadimun. Bahkan dengan mendaftar sebagai jukir, dirinya mendapat bantuan-bantuan dari pihak pemerintah. Kursi roda yang dia pakai sehari-hari merupakan sumbangan dari pihak UPTD.
Sedangkan pihak UPTD sendiri mengaku cukup welcome dengan keberadaan jukir-jukir seperti Pak Gembong dan Sadimun. “Asal tidak ada komplain dari masyarakat, kita tidak akan berbuat apa-apa terhadap mereka. Anggap saja kita membuka lapangan kerja bagi mereka,” terang Soetrisno. (Nanda, Putri, Bhimo, Annisa)

VISI | No. 27/Th. XX/2010 41
Kolom
Ketika kita mendengar kata birokrasi, pastilah akan langsung terpikirkan
mengenai urusan prosedural penyelesaian surat-menyurat yang berkaitan dengan pemerintahan. Birokrasi di Indonesia sekarang ini dipandang sebagai alat dan sistem manajemen pemerintahan yang buruk. Hal ini dikarenakan kita dapat mencium bahwa aroma birokrasi di negeri ini sekarang sudah melenceng dari tujuan awalnya sebagai medium penyelenggaraan tugas-tugas kemanusiaan, yaitu melayani warga masyarakat (publik servis) dengan sebaik-baiknya.
Akan tetapi, yang terjadi dalam birokrasi kini identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang berbelit-belit, dan tidak efisien. Urusan birokrasi hampir selalu menjengkelkan karena selalu berurusan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kontrol secara berantai, aturan-aturan yang ketat yang mengharuskan seseorang melalui banyak sekat-sekat formalitas. Citra buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem ini telah dianggap sebagai
“tujuan” bukan lagi sekedar “alat” untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Terkesan mustahil negara tanpa birokrasi. Tapi birokrasi di Indonesia sekarang ini belum tentu menjanjikan sesuatu kebaikan untuk kita sendiri jika sudah sekian parahnya penyakit yang melekat pada diri birokrasi tersebut. Perlu adanya suatu pembaharuan di dalam tubuh birokrasi di bangsa yang besar ini. Menjelang pemilihan presiden tahun 2009 harus ada suatu revolusi dalam birokrasi agar tercipta suatu sistem yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selama ini birokrasi hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena sistem yang ada di dalamnya tidak menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Sekarang ini birokrasi hanya sebagai alat yang digunakan oleh para pejabat-pejabat yang duduk di kursi pemerintahan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan kepentingan sendiri tanpa memerdulikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibuat sistem birokrasi yang humanis agar tidak berbelit-belit. Bila kita pahami birokrasi
adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala yang besar dengan cara mengoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Birokrasi merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintahan dalam upaya melayani masyarakat. Namun, kenyataan yang terjadi adalah birokrasi hanyalah sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah yang kadang oleh pejabat pemerintah dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan tertentu. Sebuah logika yang terbalik, memang seharusnya birokrasi adalah sistem yang melayani masyarakat dengan berbagai kebijakan yang dihasilkan. Namun dalam kenyataannya ada banyak pihak yang memanfaatkan kebijakan yang telah dihasilkan oleh sistem tersebut. Birokrasi kini telah menjadi “terali besi” yang membuat lemah bangsa ini akibat para penjahat berbaju birokrat tersebut. Bila hal-hal semacam ini terus tumbuh subur maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar di berbagai bidang kehidupan yang pada akhirnya masyarakatlah yang akan menjadi korban.
BIROKRASI INDONESIA MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2009
(REFORMASI BIROKRASI)Oleh : Heru Yanto*

VISI | No. 27/Th. XX/201042
Rasionalitas dan Efisiensi dalam Birokrasi
Di Indonesia, sebagian besar menggunakan tipe ideal birokrasi modern. Tipe ini melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas” yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi. Tipe ideal birokrasi berkeinginan untuk menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Tapi, pada kenyataannya tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan dalam kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Perlu adanya pembaharuan makna dan kandungan secara filosofi birokrasi. Filosofi birokrasi yang diperlukan yaitu birokrasi sebagai organisasi yang mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimalkan efisiensi”. Efisiensi ini digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi.
Dalam hal ini birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengetahuan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi birokrasi mengarah pada fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dapat dikatakan birokrasi yang ada adalah birokrasi yang berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subjektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya yang impersonalitas, melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya.
Rasionalitas dan efisiensi adalah dua hal yang harus ditekankan. Rasionalitas harus melekat dalam tindakan birokratik, dan bertujuan untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi. Kata kunci dalam rasionalitas
birokrasi adalah menciptakan efisiensi dan produktifitas yang tinggi, tidak hanya melalui rasio yang seimbang antara volume pekerjaan dan jumlah pegawai profesional, tetapi juga melalui anggaran, penggunaan sarana, pengawasan, pelayanan kepada masyarakat.
Jika kita cermati, konsep rasionalitas dan efisiensi yang membingkai dalam ramuan birokrasi adalah suatu hierarki, dimana
ukurannya tergantung pada masing-masing zaman. Zaman kita sekarang ini membutuhkan birokrasi yang berorientasi kemanusiaan yang tidak hanya secara konseptual semata tapi juga merambah pada dataran praktis lapangan. Hal ini sangatlah penting untuk mendekatkan birokrasi pada manusia bukan pada mesin. Sebuah teori ini akan diuji menurut kelayakan historis dan kebutuhan sebuah masa. Birokrasi yang humanis tahun 2009 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus serius digarap oleh para pemerhati masalah-masalah
administrasi negara dan kebijakan publik. Itu semua harus menjadi perhatian mengingat kondisi sosial ekonomi bangsa yang semakin menurun sekarang ini.
Sudah saatnya bangsa yang besar ini bangkit kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini semakin memprihatinkan sehingga perlu suatu tatanan yang baik untuk mengembalikan kondisi ekonomi
bangsa Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta keadaan ekonomi yang kondusif dan lebih mementingkan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kita harus memulai semua itu dari dasar yaitu dengan perbaikan sistem birokrasi yang ada di dalam pemerintahan.
Perlu suatu kejujuran dan kerja keras untuk membenahi hal tersebut. Walaupun kita memiliki konsep yang luar biasa namun apabila dalam pelaksanaannya tidak dilandasi kejujuran dari para pihak yang berwenang, maka birokrasi tidak akan pernah berubah dan masih menjadi ajang untuk mencari keuntungan. Bila sistem ini tercipta dengan baik, maka segala proses pemerintahan akan berjalan
dengan baik pula. Jadi, yang terpenting sekarang adalah kebersamaan untuk membangun bangsa Indonesia yang besar ini dengan sistem birokrasi yang mudah dan transparan dengan didasari kejujuran para elit pemerintah. Karena pada akhirnya hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian bukan hal yang mustahil akan tercipta kondisi bangsa yang baik dan sejahtera.
* Penulis adalah Mahasiswa Fakultas TarbiyahUniversitas Muhammadiyah Surakarta

VISI | No. 27/Th. XX/2010 43
Tokoh
Memperjuangkan hak asasi perempuan dan anak-anak sesuai dengan hukum dan kewajiban secara proporsional telah menjadi jalan hidup Ir. Retno Setyowati Gito, MS. Kecintaan terhadap hal itu semakin tumbuh semenjak ia ditunjuk sebagai Focal Point United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk Forum Kelangsungan Hidup Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) Kota Surakarta pada tahun 2003.
“Bisa dikatakan keterlibatan saya dengan UNICEF itu secara tidak disengaja,” ungkap
perempuan yang kerap disapa Retno ini. Saat itu, Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Surakarta diundang UNICEF untuk menghadiri workshop Parsitipatori Action Research on Childern di Jakarta. “Kepala Bidang Sosial Budaya Bapeda (Badan Pembangunan Daerah-red) yang sudah mengenal aktivitas dan idealisme saya, mendaulat saya untuk mewakili undangan tersebut,” paparnya.
Workshop yang berlangsung tahun 2002 tersebut diikuti 44 peserta dari beberapa daerah se-Indonesia. Sebagai trainer workshop tersebut adalah pakar peneliti dari National University of Singapore, Australian National University dan Knowing Children Bangkok. Ketiganya menilai komitmen semua peserta dalam melaksanakan semua kegiatan workshop. “Pada akhir masa workshop dipilihlah 15 orang sebagai peneliti yang akan diterjunkan untuk meneliti Anak yang Dilacurkan (Ayla) di Jawa Timur, Jawa Tengah serta Jawa Barat,” tutur Retno yang ternyata ditunjuk sebagai koordinator penelitiaan di Jateng dan Jabar.
Ketika dihubungi VISI pada Selasa (14/04) Retno bercerita awalnya ia lebih concern terhadap
masalah kependudukan sesuai dengan pendidikannya di Program Pasca Sarjana Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Namun sejak menjadi bagian dari UNICEF, ia berusaha konsisten menjalankan misi UNICEF, salah satunya terhadap permasalahan Eksploitasi Seksual dan Komersial Anak (ESKA). “UNICEF telah membuat saya jatuh hati berbuat sesuatu untuk komunitas anak-anak yang mendapatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi,” ungkap perempuan yang menulis desertasi dengan topik Tradisi dan Civil Society.
Ikatan Emosional dengan ESKARetno pernah menjadi
ketua tim proyek penelitian yang terselenggara berkat bekerjasama UNICEF, Pemerintah Kota Surakarta, dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengenai ESKA di Surakarta. Hasil penelitian
menunjukkan, pada tahun 2004 terdapat 117 anak yang dilacurkan dengan rincian tujuh anak di Kecamatan Jebres, 55 anak di Kecamatan Banjarsari, sepuluh anak di Kecamatan Laweyan, 24 anak di Kecamatan Serengan dan 21 anak di Kecamatan Pasar Kliwon.
Sebagai peneliti partisipatoris, tumbuh ikatan emosional antara Retno dengan para korban ESKA. Interaksinya langsung dengan kehidupan korban ESKA di losmen atau warung remang-remang menimbulkan keprihatinan tersendiri dalam dirinya. “Saya melihat bagaimana anak perempuan mencuci rahimnya dengan sprite karena beranggapan dengan meggocok rahimnya dengan itu akan membubuh kuman-kuman. Itu kan tindakan salah atas ketidaktahuan mereka akan kesehatan alat reprodusi mereka,” tuturnya miris.
Pengalaman yang ia dapatkan dari beragam penelitian dan
Ir. Retno Setyowati Gito, MS, Pejuang Hak Anak dan Perempuan

VISI | No. 27/Th. XX/201044
kegiatan sosial yang ia ikuti ternyata membuahkan hasil. “Dari kerja kita selama tiga tahun dapat mengentaskan lima anak yang dilacurkan. Satu di Solo dan empat di Indramayu,” tutur Retno yang mengaku senang dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat. Retno berusaha melakukan rehabilitasi sosial serta penyembuhan psikologis kepada para ESKA melalui kegiatan yang produktif semisal memberi pelatihan menjahit secara berkelanjutan.
Sebagai seorang peneliti, hal lain yang membuatnya prihatin adalah jika para peneliti yang melakukan penelitian tidak secara indepth. Dalam artian, meneliti hanya karena ingin dapat uangnya, bukan meneliti karena ingin mendalami masalah. “Sehingga hasil risetnya tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi,” tutur Konsultan Nasional Evaluasi 4 tahun tsunami di Nangroe Aceh Darussalam ini. Keprihatinan lain juga diungkapkan Retno jika para stakeholder tidak sadar mengenai upaya penyelamatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Sangat mungkin jika semua pihak terutama pemerintah menerapkan program kesejahteraan sosial, mereka (anak-anak-red) bisa hidup nyaman dalam kondisi tumbuh kembang yang berkualitas dan sesuai dengan hak mereka,” tutur Ketua Peneliti Kekerasan terhadap Anak di Pesantren dan Panti Asuhan di Surakarta dan Klaten ini. Usulan Retno diantaranya adalah memungkinkan semua anak mendapatkan pendidikan gratis dan supremasi hukum atas prostitusi anak dengan pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Anak no 23 tahun 2002 secara konsisten.
Program itu harus didukung dengan pola masyarakat tidak permisif terhadap prostitusi anak. “ESKA itu dapat tumbuh subur karena adanya permintaan terhadap ESKA, hal itu bisa ditekan dengan menerapkan peraturan tentang pelarangan prostitusi anak di losmen, hotel dan sebagianya,” papar Retno. Selain itu ia mengharapkan LSM terus menerus concern terhadap penghapusan ESKA.
Hak Anak dalam KeluargaRetno merasa beruntung
karena profesi dan kegiatan-
kegiatannya mendapat dukungan dari keuarga. Hal konkrit yang Retno lakukan dalam keluarga adalah dengan konvensi hak anak kepada anaknya sendiri. Retno tidak memaksakan anaknya untuk beraktivitas seperti dirinya. Menurutnya, itu sepenuhnya hak mereka atas pilihan hidup mereka. “Tetapi paling tidak, kegiatan sosial yang saya lakukan mestinya membekas juga pada hati mereka. Dan saya kira dalam kehidupan mereka kedepan ada yang diadopsi oleh mereka,” tutur ibu dua putri ini.
Kunci sukses yang Retno terapkan dalam membagi waktu adalah dengan mengurangi time for leisure (bersenang-senang-red). Karena ia menyadari sekarang ini dunia telah terhegemoni oleh nuansa hidup instan dan kehidupan imajiner yang melemahkan idealisme hidup merakyat. Untuk itu, ia tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar dan tidak individualis. “Saya orang yang suka bersosialisai, baik terhadap tetangga, rekan kantor, ataupun rekan suami, karena saya meyakini bahwa, kita adalah makhluk sosial dimana suatu saat kita juga akan membutuhkan orang lain,” tutur Retno. Adaptasi terus menerus dengan berbagai individu dan komunitas adalah satu kunci bagi Retno untuk bisa survive dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Hal yang menjadi keinginan Retno adalah berusaha menjadi orang yang berguna bagi sekitar. Pelajaran tentang pemberian hak yang proporsional kepada anak-anak dan perempuan itu ia tularkan melalui kegiatan di komunitas. “Semisal ketika ada arisan ibu-ibu di wilayah tempat tinggal saya, demikian pula pada komunitas ibu-ibu di tempat kerja suami saya,” ujar Penanggung jawab program Kota Layak Anak di kota Surakarta ini. Tak lupa pelajaran itu juga ia selipkan pada saat memberi kuliah pada mahasiswa S1 dan S2. (Nur Heni dan Retno Dwi S.)
CURRICULUM VITAENama : Ir. Retno Setyowati Gito, MSTempat Tanggal Lahir : Semarang , 12 Oktober 1956Alamat Rumah : Jl. Kutai IX/3, Sumber, Solo Riwayat Pendidikan :
S1 : Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret S2 : Studi Kependudukan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gajah MadaS3 : Program Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Keluarga :Suami : Gito Prastyo D. B.Sc, S.PAnak : Putri Ratna Savitri dan Paramitha Ratna Puspawardani
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Pertanian UNSAktifitas lainnya : malakukan pelatihan, penelitian, dan menulis beberapa buku yang berkaitan dengan kependudukan dan permasalahan anak.

VISI | No. 27/Th. XX/2010 45
Teropong
Pada tahun 1995, Mark Brunnet, seorang produser mempunyai ide yang cemerlang. Ide cerdas yang dipunyai, adalah, memproduksi unscript tv programme - program tv tanpa naskah. Unscript tv programme
–demikian klaimnya. Jelas, sebuah temuan baru. Keberanian, untuk membuka cara ucap baru dalam industri tv. Lantas, idenya tersebut diwujudkan dengan produksi reality show berjudul Eco Challenge. Oleh beberapa kalangan, dianggap tidak masuk akal, tidak punyai nilai ekonomi dan pasti ber-rating rendah. Kerja keras, akhirnya membawa hasil. Namun, Mark Brunnet, tidak putus asa. Malah, ia mengerjakan program reality show lain, berjudul Survivor, Real World dan Fear Factor.
Penonton, mulai menyukai program reality show. Reality show ini dikontruksi tak ubahnya dramaturgi tiga babak. Pola yang sungguh dengan mudah akan dicerna oleh penonton. Lantaran pola dramaturginya telah terbentuk, maka pola-pola bertutur yang wajar dengan mudah diartikulasikan
oleh penontonnya. Entah itu pencapaian resepsi kognitif ataupun artistik. Bisa dikatakan bahwa program reality show telah diidolai dan menjadi satu menu favorit penonton ditengah upaya utuk meredefinisi program musik, news, ataupun opera sabun.
Booming reality show di televisi Eropa Amerika, tak begitu lama. Dan hanya satu dua program reality show yang punya rating tinggi. Reality show menjadi program yang kembali diperbincangkan dan diproduksi kembali oleh banyak stasiun televisi setelah adanya writer strike, dua tahun lalu. Tepatnya ketika para penulis di Hollywood melakukan mogok kerja. Artinya jika industri hiburan tv dan film tidak disupply naskah, bisa dibayangkan apa akibatnya. Banyak produser dan pelaku industri televisi mengambil langkah untuk kembali menaikan program reality show, yang katanya berangkat dari produksi tanpa naskah.
***Untuk Indonesia, reality
show tak punya sejarah yang kuat. Maklum, stasiun televisi kita menganut budaya adopsi. Mana yang laris, mari diproduksi. Jumlah Reality Show di stasiun televisi kita, sungguh mengagetkan. Kisarannya, lebih dari 50 judul program reality show yang menyesaki ruang ruang keluarga. Setiap stasiun, mempunyai lebih dari dua judul reality show yang siap hadir dan datang kapanpun dengan suguhan hiburan –tentunya. Fenomena yang menarik sekalipun masih butuh segenap percakapan tentang keutamaan yang dipunyai oleh program ini.
Berjejalnya program reality show di televisi menjadi satu kontruksi baru dalam industri televisi kita. Booming reality show di televisi telah kita rasakan sejak setahun belakangan ini. Diprediksikan program reality show ini tetap diminati untuk beberapa tahun mendatang. Namun, kenapa
Reality Show yang ( tidak ) RealistisOleh : Tonny Trimarsanto*

VISI | No. 27/Th. XX/201046
reality show menjamur di stasiun televisi kita ?
Realitas ini pada dasarnya tak lepas dari beberapa asumsi. 1) stasiun televisi mulai mengalami antiklimaks dalam peran sosialnya. Belakangan ini, sering muncul gugatan bahwa tayangan televisi kita tidak : cerdas, dibuat-buat, penuh mimpi, tipu muslihat. Semua klaim ini diarahkan pada : tayangan sinetron. Televisi yang tidak sehat. Citra ini tentu buruk. Buruk untuk bisa menarik hati penonton. Ketika sinetron begitu berjejal dan mengandungi nilai-nilai yang tak sehat keutamaan televisi menjadi hilang.
Sinetron, memang menjadi menu andalan banyak stasiun televisi. Nilai yang disuguhakan nampaknya tak lagi mujarab sebagai bentuk tontotan favorit di ruang keluarga. Sinetron adalah karya fiksi rekaan yang
hiperbolik. Logikanya semua tidak realistis di hadapan penontonnya. Tidak realistis tidak jujur dan ekploitatif. Maka penonton mengalami krisis peneguhan. Yang ditonton dari sinetron adalah fiktif, hanya kisah. Bukan realitas itu sendiri. Mengutip para filsuf, hyper-reality televisi telah mencederai penonton.
Untuk mengobati krisis keteguhan penonton, maka -mungkin- reality show akan menawarkan sebuah kandungan yang berbeda. Sinetron fiktif, reality show sangat riil dan mampu meneguhkan tingkat kepercayaan penonton bahwa yang diapresiasi adalah tontonan yang benar-benar realistis. Semua yang dipertontonkan -seakan-akan- faktual riil. Paling tidak ini menjadi satu apologi dan pijakan yang belakangan banyak diamini oleh para produser reality show. Namun apakah benar
demikian faktanya? Fakta sederhanya adalah terjadinya dikotomi cara pandang, yang taken for granted untuk penonton seperti itu. Mereduksi kuantitas sinetron yang fiktif, dengan reality show (yang menurut saya bukan) lebih realistis.
Faktor 2) tuntutan bangun industri televisi untuk bisa memberikan keberagaman tontonan. Idealnya, stasiun televisi dituntut untuk bisa menyuguhkan tayangan yang beragam. Reality show adalah salah satunya. Semakin beragamnya tayangan, tentu akan mampu menjaga kestabilan konsumsi program televisi. Tetapi faktanya adalah wajah televisi kita masih homogen. Keseragaman yang reduksif. Kurang mampu memberikan keberagaman bentuk dan konten yang memang menjadi penting bagi penontonnya.

VISI | No. 27/Th. XX/2010 47
***Lantas, pertanyaannya adalah
apa benar bahwa reality show kita mempunyai aspek yang lebih edukatif dibandingkan dengan jenis tayangan sinetron misalnya? Jujur, saya mungkin tidak sepaham dengan temuan Mark Brunnet, tentang formulasi unscript tv programme. Bisa jadi, awalnya ide unscript mengagetkan. Tetapi maaf ini rezim industri. Televisi butuh mega investasi. Uang, modal besar. Dalam pandangan saya setiap program yang itu dikerjakan oleh dan untuk televisi, tentu mempunyai desain. Pola-pola yang ada dalam reality show adalah drama tiga babak. Ada pengenalan, ada persoalan yang harus dipecahkan dan akhirnya persoalannya akan dikemanakan. Itu polanya. Formulasi ini tidak bisa hanya dibayangkan tanpa dikonsepkan dan discript-kan. Tahapan produksi dalah desain. Desain adalah 50% dari hasil akhir.
Akankah para pelaku industri televisi mau mengorbankannya. Kalkulasinya demikian. Untuk memproduksi reality show, tentu butuh dana segar yang tidak kecil. Ini investasi. Ada planning kerja dan progress output yang akan dicapai. Siapakah yang mau mengeluarkan uangnya, tanpa tahu akan balik modal atau tidak? Sekali lagi ini industri. Tentunya ada batasan dan keterbatasannya. Soal uang, waktu lama produksi dan kualifikasi output yang akan dicapai.
Reality show di televisi kita pun demikian. Sungguh semuanya atas nama script dan batasan waktu produksi. Ironisnya lagi adalah, semua adalah -berkesan- pengadeganan lantaran tuntutan content informasinya. Jangan heran jika reality show di televisi kita tak lebih baik dari sinetron. Baik desain, teknik dan terjadinya pendangkalan itu sendiri. Semua dibuat adegan. Aspek spontanitas sebuah peristiwa justru tak dijumpai. Menonton reality show, adalah menonton adegan sinetron yang diberi judul berbeda saja.
Reality show kita gagal dalam menciptakan sebuah peneguhan. Inginnya reality show itu memberikan peneguhan kepada penonton tentang realitas yang mereka tonton adalah realistis dan riil. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Inginnya
seperti tayangan documenter, tetapi yang muncul adalah dramaturgi yang diciptakan bukan sebuah dramaturgi yang memang menjadi sebuah peristiwa yang spontan dan kuat. Efek selanjutnya adalah terciptanya penangguhan tingkat kepercayaan pada fakta dan peristiwa.
Lalu kenapa masih saja terjadi diskriminasi pada bentuk bentuk tontonan yang mampu meneguhkan diri penonton pada teks? Misalnya pada program dokumenter? Apa bena, jika program dokumenter tidak pernah bisa menjadi idola dalam bangun industri televisi ? Persoalan klasik. Sebuah percakapan yang tak pernah usai nampaknya.
Kita lihat bahwa tak banyak stasiun televisi yang cukup peduli pada penonton. Artinya, nilai-nilai keutamaan program bukanlah tujuan. Televisi hanya media, kendaraan untuk bisa memutar investasi yang besar. Program yang punya rating tinggi akan melahirkan program program baru serupa. Tanpa penah berpijak pada aspek keutamaan, dan konstruktivitasnya bagi penonton. Karena program dokumenter tak pernah ber-rating tinggi, maka yang terjadi adalah tidak berpihaknya stasiun televisi pada dokumenter.
Lalu, apa bedanya reality show kita dengan film dokumenter? Memang, inginnya stasiun televisi memberikan nilai yang konstruktif. Tetapi, reality show kita adalah dunia cangkokan yang tanggung. Pada satu sisi, ingin mengupas sebuah peristiwa riil sehari hari di satu kaki. Pada kaki yang lain justru muncul: wajah-wajah cantik tampan presenter, dan adanya pola-pola yang terdesain dari angle kameranya. Realitas ini tentu menyiratkan bahwa masih ada keraguan soal aspek keberpihakan stasiun televisi program yang memang benar benar konstruktif.
Seharusnya, dibutuhkan sebuah kebijakan baru yang bisa mengatur komposisi tayangan pada setiap stasiun. Atau yang dibutuhkan adalah stasiun televisi publik yang benar-benar bisa menjangkau segenap ruang geografis. Apakah TVRI sudah berperan sungguh? Ataukah memang politik televisi telah menyudutkan definisi televisi publik yang diamanatkan pada TVRI, yang telah
menjadi media politik kepentingan? Tidak mudah memang,
memberi ruang produk audio visual seperti film dokumenter untuk masuk dalam ruang industri. Justru, jika program itu ditayangkan, akan berada pada jam-jam yang tidak popular. Bukankah dokumenter tidak ada wajah cantik dan tampan? Tidak ada pandangan yang bisa membuat penonton betah? Atau malah sebaliknya akan menyinggung kelompok tertentu?
Pernah ada pengalaman. Beberapa film dokumenter saya diminta oleh sebuah stasiun. Katanya ingin ditayangkan. Saya pun bertanya, pada jam berapa film-film saya akan ditayangkan nantinya. Kemungkinan tayang pada jam dua pagi mas, katanya. Nah! Tak banyak ruang bagi bentuk produk audio visual yang berpotensi memberikan nilai keutamaan.
* Penulis merupakan seorang sutradara film dan fasilitator workshop media http://trimarsantofilms.com/

VISI | No. 27/Th. XX/201048
Wawancara
Dewan Pers selaku lembaga independen yang menjaga kemerdekaan pers serta meningkatkan kehidupan pers menjadi ujung tombak dalam melindungi pers melalui payung hukum yang tepat. Sehingga media dan juga pihak yang dirugikan.oleh pemberitaan memperoleh keadilan. Berikut petikan wawancara VISI dengan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A di Ruang Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, Jumat (5/6).
Bagaimana pendapat Dewan Pers dengan adanya kriminalisasi pers akibat pengaduan melalui jalur hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan?Untuk masalah pengaduan, memang semestinya melalui Dewan Pers dulu. Namun jika pengaduan sudah sampai ke pengadilan, Dewan Pers sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi kita berharap agar jaksa atau hakim bertanya terlebih dahulu kepada Dewan Pers.
Apa maksud dari pernyataan Bapak dengan mengatakan “tidak bisa apa-apa”? Dewan pers itu kan memang dasarnya adalah kode etik yang berkaitan dengan moral. Hukuman moral bagi seorang wartawan sangatlah berat. Ketika seorang wartawan terkena hukuman kode etik, ia tidak lagi bisa meneruskan profesinya menjadi wartawan.
Lalu, bagaimana usaha yang dilakukan Dewan Pers untuk meminimalisasi kriminalisasi pers?Setiap kali ada kasus-kasus pers, seringkali Dewan Pers diminta menjadi saksi ahli dalam pengadilan. Fungsi Dewan Pers dalam pengadilan untuk menyatakan apakah berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Lain hal jika berita tersebut tidak berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik. Maka Dewan Pers tidak bisa berbuat apa-apa dalam melindungi kemerdekaan pers.
Bagaimana tingkat pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers dari tahun ke tahun, perihal ketidakpuasan terhadap pemberitaan di media massa?Kasus-kasus pengaduan pers semakin lama semakin besar. Hal ini dapat berarti dua hal yaitu kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Pers semakin tinggi. Dahulu jika ada seseorang yang dirugikan oleh media, maka kantornya akan dihancurkan atau wartawannya akan dipukuli. Namun sekarang tidak, hal ini berarti kepercayaan terhadap Dewan Pers juga semakin tinggi.Tetapi ada sisi negatifnya karena semakin tinggi angka pengaduan tersebut dapat menjadi acuan bahwa kualitas wartawan semakin dipertanyakan.
OTORITAS DEWAN PERS DI TENGAH KRIMINALISASI
TERHADAP PERS
Pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers menjadi hal yang mesti diperhatikan. Terlebih jika pengaduan terkait kasus pemberitaan pers secara sepihak diadukan ke lembaga pengadilan. Maka hal itu dapat mengancam kenyamanan pers dalam kinerjanya, dalam hal ini dinamakan kriminalisasi pers. Padahal pengaduan semacam itu seharusnya melalui Dewan Pers terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

VISI | No. 27/Th. XX/2010 49
Bagaimana prosedur yang tepat jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan pemberitaan oleh media?Jika ada pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan diharuskan membuat hak jawab. Bisa dengan cara dikirimkan langsung ke surat kabar yang bersangkutan atau dikirimkan kepada Dewan Pers. Hak jawab tersebut wajib dimuat di media agar jelas. Kalaupun nanti hak jawab tidak dimuat oleh pers, maka pers bisa mendapat denda, maksimal 500 juta rupiah.
Menurut Dewan Pers, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang wartawan maupun media dalam memberitakan suatu hal?Supaya wartawan tidak terkena denda semacam itu, ya jangan melanggar kode etik donk. Kode etik jurnalistik sebenarnya memang merupakan moral secara umum, misalnya jangan menulis berita bohong, harus rajin chek and re-chek dengan narasumber. Ketika narasumber tidak mau diverifikasi, wartawan
berhak memberitahukan kepada khalayak bahwa memang narasumber enggan untuk diverifikasi. Yang penting, wartawan sudah berusaha penuh untuk mem-verifikasi.
Harapan seperti apa yang ingin disampaikan pada wartawan dan pemilik media dalam berkiprah di dunia jurnalistik? Harapannya, kepada wartawan harus menghayati betul Kode Etik Jurnalistik agar tidak berhadapan dengan hukum. Jika berhadapan dengan hukum akan tetap dalam posisi yang benar, sekalipun terdapat
Nama : Prof Dr Ichlasul Amal MAAlamat Rumah : Pendeansari Blok I No. 5 Condongcatur, Depok, Sleman, YogyakartaPekerjaan : Dosen dan Ketua Dewan PersHobi : Tenis dan berkebun
Karir:- Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM (1967 – sekarang) - Direktur Pusat Antar Universitas (PAU) studi sosial UGM (1986-1988) - Dekan Fisipol UGM (1988-1994) - Direktur Program Pascasarjana UGM (1994-1998) - Rektor UGM (1998-2002)Kegiatan Lain:- Anggota Tim Kajian Penelitian dan Pengembangan Departeman Dalam Negeri (1991) - Pengelola Program S2 Ketahanan Nasional UGM (1991-sekarang)- Ketua Dewan PersOrganisasi:- Ketua HMI Komisariat Fisipol (1966-1967)- Ketua Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) cabang Jogja 1967-1968 - Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama; 2001-2005)
pengaduan-pengaduan. Berbeda hal jika pers memang melanggar Kode Etik Jurnalistik, maka Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi pemberitahuan kepada Redaksi dan organisasi bahwa wartawan itu memang bersalah. Kepada pemilik media, gunakanlah kebebasan sewajarnya mengingat sekarang tidak ada aturan-aturan khusus mendirikan surat kabar. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang tercermin dari reformasi dalam hal kebebasan pers yang bisa seperti pisau bermata dua. Artinya yang satu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat menyerap informasi. Dan di sisi lain bila kebebasan pers digunakan semena-mena bisa berbahaya bagi kebebasan pers karena masyarakat tidak lagi bisa percaya pada pers.

VISI | No. 27/Th. XX/201050
Refleksi
Ganyang Malaysia!
Jargon yang dulu sempat begitu terkenal pada era presiden Soekarno kini semakin marak
diteriakkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Setelah sekian lama hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami pasang surut karena berbagai persoalan, Malaysia kembali berulah. Ulahnya kali ini merupakan suatu bentuk provokasi terhadap Indonesia. Pasalnya selama tahun 2009 ini sudah belasan kali kapal perang Malaysia memasuki perairan Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan.
Nota protes yang sering kali dikirimkan Indonesia atas tindakan Malaysia yang melanggar batas wilayah perairan Ambalat seolah hanya menjadi angin lalu bagi pemerintah Malaysia. Peringatan kapal perang Indonesia di Ambalat pun diacuhkan begitu saja oleh tentara Malaysia Tindakan ini seolah menguji keberanian dan kesiapan pemerintah Indonesia untuk membela kedaulatan wilayahnya setelah sebelumnya Malaysia dengan mudahnya memiliki wilayah Indonesia.
Tahun 2002 menjadi catatan kelam bagi pemerintah Indonesia karena tidak mampu menjaga kedaulatan negaranya. Di tahun itu dua pulau milik Indonesia yakni Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
resmi menjadi milik Malaysia. Sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ini sudah bermula dari tahun 1969 sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Tahun 1998 kedua Negara sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Mahkamah Internasional.
Setelah melalui serangkaian
diplomasi antar kedua Negara yang panjang dan alot serta memakan biaya yang mahal, Indonesia kalah telak dalam persidangan di Mahkamah Internasional. Dari 17 hakim yang ada, 16 hakim memihak pada Malaysia dan hanya satu hakim yang pro pada Indonesia. Hal ini seolah menjadi cermin bagaimana ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi Internasional
guna melindungi wilayahnya sendiri. Pola tindakan yang dilakukan
Malaysia pada waktu kasus Pulau Sipadan dan Ligitan pun menyerupai apa yang terjadi saat ini di perairan Ambalat yakni tindakan provokasi yang akhirnya diarahkan pada sengketa wilayah dan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Saat ini Pulau
Sipadan dan Ligitan kini menjadi salah satu objek tujuan wisata yang sedang gencar dipromosikan oleh Malaysia Pertanyaannya saat ini apakah pemerintah siap untuk menempuh jalur diplomasi sekali lagi?
Motif EkonomiSengketa Ambalat
sebenarnya telah berlangsung cukup lama yakni sejak tahun 2006 tetapi permasalahan ini baru mencuat kembali akhir-akhir ini sejak perusahaan minyak Malaysia Petronas memberikan konsesi eksplorasi kepada perusahaan Belanda, Shell, di kawasan Ambalat pertengahan Pebruari lalu.
Bila kita menelisik lebih jauh, klaim Blok Ambalat oleh Malaysia tidak hanya semata ekspansi wilayah, tetapi lebih karena Blok Ambalat menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa besar. Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun.
Permasalahan lain yang muncul dari sengketa Ambalat adalah
Kedaulatan Diserang, Rakyat Meradang
Oleh : Rizky Amel Amalia*

VISI | No. 27/Th. XX/2010 51
adanya pemberian hak eksplorasi hidrokarbon yang diberikan pihak Malaysia di blok Ambalat Laut Sulawesi kepada Shell dan Petronas Carigall. Pihak Malaysia menyatakan bahwa wilayah di blok Ambalat tersebut masih berada di dalam batas kontinen Malaysia seperti yang tercakup dalam Peta Wilayah Perairan dan Batas Kontinen Malaysia tahun 1979 sehingga Malaysia memiliki hak berdaulat dan hak hukum untuk melakukan ekplorasi dan memanfaatkan (eksploitasi) sumber daya alam di dalam batas kontinennya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982.
Blok yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya itu dinamai Blok Y dan Z atau ND6 dan ND7. Di lain pihak, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa menurut Hukum Laut Internasional perairan Ambalat di Laut Sulawesi merupakan bagian dari Indonesia sehingga konsesi minyak yang diberikan Malaysia kepada Shell telah melanggar kedaulatan Indonesia. Terlebih lagi Pemerintah Indonesia juga telah memberikan nama untuk lokasi serupa masing-masing sebagai Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur dan berencana bekerja sama dengan pihak lain untuk keperluan eksplorasi kekayaan alam yang terdapat di Blok Ambalat. Motif ekonomi seperti ini yang disinyalir sebagai pemicu utama tindakan provokasi yang dilakukan Malaysia di perairan Ambalat.
Keseriusan PemerintahBerbagai reaksi timbul dari
masyarakat Indonesia menanggapi permasalahan Ambalat. Aksi turun ke jalan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat, dialog terbuka sampai aksi di dunia maya melalui tulisan dalam blog maupun situs resmi semuanya bermuara pada satu tujuan yang sama yakni tak ingin Blok Ambalat jatuh ke tangan Malaysia dan peristiwa Sipadan Ligitan babak kedua tidak terjadi. Bahkan beberapa elemen masyarakat menyatakan siap berperang dengan
Malaysia untuk melindungi dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Reaksi masyarakat Indonesia yang sedemikian besarnya membuat gentar pihak Malaysia sampai-sampai para staff di Kedubes Malaysia menjadi gusar karena kuatnya aroma sentimen anti Malaysia
Menyikapi hal ini diperlukan keseriusan dan itikad baik dari pemerintah untuk menjaga setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak peduli besar kecil atau kandungan kekayaaan alam apapun yang berada di wilayah tersebut. Setidaknya ada empat langkah yang bisa diambil pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini dan mencegah agar kasus serupa terjadi karena baru-baru ini pulau Miangas juga telah diklaim kepemilikannnya oleh Filipina yakni pertama segera melakukan pemetaan dan pencatatan ulang dari jumlah pulau dan batas-batas terluar wilayah Indonesia serta mendirikan bangunan yang menjadi simbol kepemilikan Indonesia sesuai dengan aturan dari Hukum Internasional.
Kedua meningkatkan patroli penjagaan batas-batas territorial Indonesia dan segera melakukan tindakan tegas bila ada pihak asing yang melanggarnya. Ketiga memperkuat data-data serta fakta sejarah mengenai wilayah Indonesia dalam rangka memperkuat kekuatan diplomasi Indonesia dan menyiapkan orang-orang yang kompeten untuk mewakili Indonesia dalam diplomasi Internasional. Keempat menyiagakan secara utuh kekuatan militer yang dipunyai Indonesia demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Saat ini pemerintah Indonesia dirasa bergerak cukup lamban dalam penanganan kasus sengketa blok Ambalat. Jalur diplomasi antara kedua Negara tanpa melalui Mahkamah Internasional yang sedang diusahakan pemerintah tidak disertai upaya –upaya lain untuk memperkuat diplomasi seperti pemetaan ulang
wilayah. Kesiapan pemerintah dalam upaya diplomasi dipertanyakan. Bila masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional akankah kita mengalami kekelahan telak dan memalukan seperti dalam kasus Sipadan Ligitan?.
Itikad baik pemerintah Indonesia pun sepertinya tidak diindahkan oleh Malaysia karena selama upaya diplomasi berlangsung kapal perang Malaysia terus saja melakukan provokasi di perairan Ambalat. Hal ini lah yang patut menjadi catatan bahwa upaya diplomasi hanya dapat dilakukan bila kedua belah pihak menghormati tata cara diplomasi dengan tidak melakukan upaya provokasi. Tidak adanya itikad baik dari pihak Malaysia seharusnya menjadi sinyalemen bahwa pemerintah Indonesia perlu menyikapi masalah ini jauh lebih serius dan lebih tegas.
Diplomasi yang ada juga harus dibarengi akan ketegasan pemerintah terhadap tindakan provokasi yang dilakukan Malaysia. Apakah penting sekali untuk bertindak tegas agar pihak Malaysia berhenti untuk bermain-main dengan militer Indonesia. Reaksi luar biasa dari rakyat Indonesia bisa membuat gentar pihak Malaysia. Pemerintah seharusnya jauh lebih berani dari rakyatnya. Ini soal kedaulatan bangsa, soal harga diri bangsa tidak ada kata lemah, tidak ada kata menyerah! Hanya satu kata Berjuang!!
*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) angkatan 2006 Aktif sebagai Menteri Dalam Negeri BEM Fakultas Hukum UNS

VISI | No. 27/Th. XX/201052
Resensi Film
Andy Dufresne (Tim Robbins) adalah seorang bankir yang dijebloskan
ke penjara Shawshank karena dugaan pembunuhan atas istri dan selingkuhan sang istri. Di dalam penjara, karena suatu hal, Andy menjadi berteman baik dengan Ellis Boyd “Red” Redding (Morgan Freeman).
Sekilas, film yang terinspirasi dan berdasarkan novel Stephen King, ’Rita Hayworth and Shawshank Redemption’ ini memang kurang begitu menarik untuk ditonton. Akan tetapi, ternyata di dalam film ini mengandung banyak hal yang membuat penontonnya menjadi sadar akan banyak hal. Film tahun 1994 ini pernah meraih 7 nominasi Oscar, meskipun tidak satupun dimenangkannya.
Right man in the wrong place. Orang yang benar di tempat yang salah, agaknya memang seperti itulah yang terkandung di film ini. Cerita diawali dari si Andy yang disidang akibat diduga membunuh istri dan kekasih gelap sang istri. Meskipun ia bersikukuh bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan itu, akan
tetapi dikarenakan semua bukti mengarah kepadanya akhirnya ia dijebloskan ke penjara. Hal ini mempengaruhi pemikiran Andy bahwa siapapun yang dijebloskan ke penjara adalah orang-orang yang tidak bersalah, dan ia selalu mencari celah untuk bebas.
Di penjara Andy berteman dengan Red. Kehidupan Andy selama dua tahun pertama di penjara sangatlah menyiksa buat dirinya. Red adalah seorang penyuplai barang-barang (yang tentunya tidak bisa didapatkan di penjara) bagi narapidana lainnya, sedangkan Andy, yang notabene adalah seorang bankir, akhirnya malah menjadi seorang akuntan sekaligus konsultan pajak di penjara. Dia mengatur pengeluaran pajak dari para penjaga penjara dan sipir. Bahkan berkat keahliannya ini, Andy menjadi akuntan pribadi kepala penjara Warden Norton (Bob Gunton) yang ternyata melakukan bisnis haramnya dari penjara.
Persahabatan Andy dan Red semakin akrab. Sebagai narapidana dengan hukuman seumur hidup, Red menjadi terbiasa hidup sebagai narapidana. Ia telah merasa dirinya sudah terinstitusi dengan kehidupan penjara yang malah membuat Red ragu apakah ia bisa hidup ketika akhirnya nanti ia bebas. Sampai kemudian harapan untuk bebas pun dihilangkan jauh-jauh dari pikirannya.
Meskipun begitu Andy selalu menguatkan Red agar tetap bertahan, dan selalu berjuang untuk dirinya, untuk kebebasannya. Andy selalu
menunjukkan cita-cita kebebasan. Tapi Red tetap bergeming.
Klimks di film ini ada pada adegan Andy yang karena suatu hal akhirnya memutuskan untuk kabur dari Shawshank. Ia merasa, waktu hampir duapuluh tahun adalah sangat lebih untuk membalas segala perbuatan yang dituduhkan padanya, padahal dia tidak melakukannya. Andy rela melewati lorong pembuangan kotoran sepanjang 500 yard demi kebebasannya. Di lain pihak, Norton Sang kepala penjara harus menebus perbuatannya dengan
bunuh diri. Film yang
unik karena tokoh sentralnya ada dua. Andy dan Red. Monolog oleh Red membari kesan seolah-olah ialah Sang tokoh utama,
padahal justru Andylah yang menjadi pokok ceritanya. Atau dengan kata lainnya, Red hanya sebagai story teller.
Hampir tidak ada kesalahan dalam film ini. Tergarap dengan sinematografi yang apik membuat penonton tidak merasa rugi meluangkan waktunya menonton film ini. Film yang menghibur sekaligus menggugah dengan banyak unsur di dalamnya, kecerdasan, ketekunan, kesabaran, keberanian, harapan, persahabatan, bahkan jiwa kewirausahaan.
Film ini memberikan sebuah pengertian mengenai arti kebebasan dan harapan. Harapan untuk dapat bangkit dari keterpurukan meskipun dengan kebenaran dan kesempatan yang hampir terlihat tidak mungkin. Film yang juga menawarkan makna persahabatan yang sebenarnya. (Alina)
Judul : The Shawshank RedemptionSutradara : Frank DarabontProduksi : Castle Rock EntertainmentDurasi : 120 menitPemain : Tim Robbins, Morgan Freeman
Masih Tersisa Harapan di Penjara
“Remember, Red… hope is a good thing, maybe the best of things, and no good
things ever dies.”(Andy Dufresne)

VISI | No. 27/Th. XX/2010 53
Setiap anak, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Tidak memandang
apakah mereka anak yang baik atau anak yang “istimewa”. Seperti itulah yang digambarkan dalam film ini. Film yang diangkat dari kisah nyata ini pada intinya mengangkat konflik antarras dan konflik antargeng sebagai tema utama. Diceritakan bagaimana seorang guru yang berjuang agar para anak didiknya mendapat hak yang sama dalam pendidikan, dan bahwa perbedaan ras tidak dapat menghalangi mereka untuk memperoleh hak itu.
Erin Gruwell (Hillary Swank) adalah seorang wanita berpendidikan tinggi yang idealis. Ia merasa tertantang untuk mengabdikan diri membantu anak-anak yang bermasalah
di Woodrow Wilson High School. Di kelas 203 Miss-G (begitu ia biasa dipanggil) mengajar. Kelas yang terdiri atas anak-anak bermasalah, yang bahkan hampir semuanya tidak memiliki keinginan untuk belajar.
Di hari pertamanya mengajar, Miss-G menyadari adanya semacam sekat yang membatasi pergaulan antarsiswa. Perbedaan latar belakang (ras dan kelompok) terbawa sampai ke dalam kelas, bahkan konflik antarras yang terjadi di kota ikut pula mempengaruhi suasana kelas. Di dalam kelas
mereka duduk berkelompok menurut ras masing-masing. Tidak seorang pun bersedia duduk di kelompok ras yang berbeda. Perkelahian antarsiswa sangat rentang terjadi meski hanya karena sebuah kesalahpahaman kecil. Inilah yang kemudian menyebabkan suasana kelas tidak kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Keinginan belajar para murid ini menjadi hilang, apalagi didukung pula oleh ketidaksanggupan dan keengganan guru untuk mengajar.
Akan tetapi, oleh Miss-G sekat ini berusaha dihilangkan. Ia yang dari semula memiliki misi memberikan pendidikan yang layak bagi semua anak merasa tertantang dengan kelas yang diajarnya itu. Ia mencoba untuk sedikit-demi sedikit mengenali latar belakang muridnya. Ia kemudian meminta mereka menulis buku harian.
Di buku harian itu, mereka boleh menulis apa pun yang mereka alami, rasakan, dan pikirkan. Di luar dugaan, cara ini ternyata berhasil. Setiap hari, buku harian para murid itu kembali pada Miss-G dengan tulisan tentang segala hal yang mereka alami.
Dari buku-buku harian itu, Miss-G mengerti bahwa konflik antargeng, antarkelompok, antarras memang mempengaruhi keadaan para murid ini. Dia pun harus berusaha menyadarkan para murid bahwa konflik seperti ini bukanlah segalanya. Dia juga berusaha membuat para muridnya sadar bahwa dengan pendidikan mereka akan bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Semua dilakukan dengan cara mengajarnya yang unik.
Akan tetapi memang, untuk mencapai kemenangan bukanlah hal yang mudah. Meskipun usahanya tidak didukung oleh para rekan seprofesinya, ternyata tidak membuat Miss-G gentar. Miss-G malah semakin ingin maju. Bahkan, dia rela mengorbankan waktu luangnya untuk bekerja sambilan demi membeli buku-buku bacaan yang berguna bagi para muridnya.
Film ini memang bukanlah film baru, meskipun dirilis pada awal 2007 tetap membuat film ini patut disaksikan bagi siapa saja. Apalagi bagi mereka yang tertarik pada dunia pendidikan. Film ini menunjukkan bahwa se-”bermasalah” apapun seorang anak, ia tetap berhak mendapat pendidikan. Keyakinan Miss-G pun mengilhami untuk percaya bahwa setiap orang tidak mungkin tidak dapat meraih kesuksesan.
Freedom Writers memiliki alur cerita yang mudah dipahami dan juga dialog yang gampang dimengerti. Monolog-monolog oleh para murid membuat penonton lebih memahami pikiran mereka. Dan di tengah maraknya film remaja yang ceritanya tidak jauh dari cerita cinta, komedi atau horor, Freedom Writers dapat menjadi pilihan cerdas bagi anak muda. (Alina)
Pendidikan Tak Mengenal Perbedaan
Judul : Freedom WritersSutradara : Richard LaGraveneseProduksi : Paramount PicturesPemain : Hilary Swank, Scott Glenn, Imelda Staunton, Patrick Dempsey

VISI | No. 27/Th. XX/201054
Resensi Buku
Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia
dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Fungsi pendidikan ini yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Ada bermacam-macam sistem pendidikan di Indonesia salah satunya adalah pendidikan formal atau disebut sekolah. Pendidikan formal adalah serangkaian jenjang pendidikan yang telah baku yaitu SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.
Hal tersebut jelas menggambarkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Namun, sayangnya di tengah-tengah krisis seperti sekarang ini tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan. Pendidikan menjadi
Judul : Sekolah Bukan Pasar (Catatan Otokritik Seorang Guru)Pengarang : St. KartonoPenerbit : Penerbit Buku Kompas – JakartaCetakan : Pertama, 2009Halaman : x + 221Harga : Rp. 32.000, 00
barang mahal yang hanya bisa dinikmati mereka yang beruntung saja. Terlebih ketika sekolah sudah beralih fungsi menjadi pasar.
Hal ini yang dipermasalahkan St. Kartono, penulis buku ini. Ia menilai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan adalah komoditas. Sudah saatnya sekolah dibebaskan dari suasana bisnis yang dilakukan oleh siapa pun, baik oleh birokrat pendidikan nasional, kepala sekolah atau bahkan guru sekalipun. Fungsi penyelenggara pendidikan, kepala sekolah, dan guru adalah mendidik, bukan sebagai produsen, makelar, atau rentenir bagi berbagai produk industri demi keuntungan pribadi semata. Perpaduan sistem pendidikan yang ada di dalamnya secara berkesinambungan akan merusak sistem pendidikan nasional. Sehingga nantinya sekolah hanyalah sebagai tempat bisnis maupun sebagai ladang mencari keuntungan lewat paket buku pelajaran, kain seragam, alat tulis, biro wisata, atau lembaga kursus, yang pada akhirnya membebani para orang tua dengan berbagai pungutan. Mekanisme yang demikian akan berdampak besar terhadap proses pemiskinan masyarakat yang sudah miskin.
Buku ini merupakan kumpulan artikel-artikel ST. Kartono di salah satu media massa nasional dari kurun tahun 1996 hingga 2008 sebagai upaya kajian perilaku pendidikan di tanah air secara berturut-turut. Secara umum buku ini mengulas tentang kesalahan sistem pendidikan yang bermuara pada ”money interest”. Ke-empat puluh tulisan dalam buku ini dipetakan dalam tiga bagian dengan konteks pendidikan yang beragam. Bab pertama, Sekolah di Zaman Kini, penulis mengulas persoalan-persoalan pendidikan saat ini terutama mengenai sekolah yang berubah menjadi pasar. Mulai dari masalah mahalnya biaya buku, sekolah sebagai proyek dan lain sebagainya. Bab kedua adalah Tergantung pada Guru yang menjelaskan bagaimana peran sesungguhnya seorang guru beserta problematika guru masa kini misalnya guru yang terjerat masalah kelayakan gaji. Dan bab terakhir adalah Mengajarkan Keutamaan, rumusan tulisannya menafsirkan efek pendidikan pasar terhadap objek pendidikan yakni para siswa.
Buku ini sepenuhnya adalah gambaran secara rinci yang sebenarnya terjadi dalam dunia penddidikan di masyarakat kita saat ini. Namun, sayangnya buku ini tidak dilengkapi dengan solusi-solusi yang konkret untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.
Kehadiran buku ini tentunya diharapkan mampu menjadi otokritik dan perlawanan atas kesemrawutan dunia pendidikan di Indonesia, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini dimana kebebasan berpendapat mulai dihormati. Buku ini layak dibaca dan menjadi rujukan oleh semua orang yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan, terutama bagi pengamat pendidikan, guru, birokrat pendidikan dan mahasiswa. (Nositaria)

VISI | No. 27/Th. XX/2010 55
Puisi
Judul : Sekolah Bukan Pasar (Catatan Otokritik Seorang Guru)Pengarang : St. KartonoPenerbit : Penerbit Buku Kompas – JakartaCetakan : Pertama, 2009Halaman : x + 221Harga : Rp. 32.000, 00
Aku hanyalah arang diantara hitamnya tubuhkuAku hanyalah sampah yang sering ditendangDibuang bahkan tiada dipandang orangSiapakah aku?Menjadi tikus-tikus perah budak penipu-penipu kuasa ituLegam tubuhku tak jua legam nyawaku..Karena Aku bermisi misi permisi bahwa TUHAN ITU MAHA ADILKarena Tuhan ciptakan Aku agar mereka-mereka mampuBerfikirBahwa Aku..Aku tetaplah seorang aku yang lemah,Hina dina dicabik usia..Akulah tempat orang-orang meludah murkaAkulah Sang USANG USANG TUA yang tiada lagi punya guna..Aku..Aku..Aku…Selalu saja mereka menyebutAku..Terus saja mereka memekikAku..Hingga Aku pun tersadarAku ini apa?Aku ini tak ubahnyaPasir, debu, kotoran, Menyatu,Menyatu pada tanah pertiwikuYa, pertiwiNamaku PertiwiYang banyak orang bilang Aku iniSial..Aku ini..hanyalah “lumpur jijik”Tapi..Aku adaHarus, mesti..Entahlah..Lalu aku pun membaca sajak tulisanDi atas puing-puing brkas mabuknya patriot-patriotMasa depan yang menyerpihkanDan aku torehkan darahku di atas kaktus perjuanganSerta aku penggal diriku sendiri pada antaraJeruji-jeruji ReformasiPada langit demokrasi aku teriakkanPada awan-awan yang mengarakan
perak-perak kemerdekaanSebagai persembahan Sang Hyang AGUNGNamun terkikis oleh tandus-tandus korupsi..Tapi terhalang oleh sengatan mentari korupsiBelum lagi mendung akan kebobrokan moralSegera datang segaraPada iringan hujan yang deras oleh rintik-rintik kemiskinan..Tertambat tertambal terlambatOleh tulang-tulang kefakiran..Oleh kerajaan kemunafikan yang terapung di atas lautan bening-bening socaBiarlah itu semua terjadiTerjadi padakuKarena AkuAda di tiap-tiap waktuItuAku ituItu AkuAKUAKUAku
Sekali
Lagi
Aku
Farro Durratul Qorri’ana,Mahasiswa FKIP Bahasa Inggris ‘08UNS
Cerita Seorang Pendiam
Sebuah PuisiMelalui mulutnya yang fasih terbungkam,Untaian kata tertancap kokoh di jiwa.Walaupun tidak terdengar,Tapi sangat jelas sekali maknanya.Dengan tatapan matanya yang dingin,Dia hangatkan suasana yang bimbang.Dengan pancaran keheningan,Dia ceriakan setiap sudut hati.Dan melalui keangkuhan sikapnya,Dia mencoba menyapa setiap insan.Tutur katanya lembut,Tapi mampu menggores hati.Dia ajarkan bagaimana berbicara yang benar,Melalui isyarat yang hanya terbaca dengan merasakan,Cukup dengan merasakan.Melalui tampang harunya,Dia coba hibur sekalian manusia,Dengan leluconnya yang membuat setiap pasang mata
Ia lalu bercerita,Cerita yang singkat, namun tiada mengenal akhir.Karena telinga kita tidak sanggup menangkapnya.Hanya dengan hati saja, kita mampu memahami ceritanya.Ia berkata tentang hidupnya,Hidupnya yang sendiri, namun ditemani banyak kenangan.Ia perlakukan nyawa titipan Tuhan ini dengan penuh hati-hati,Ia coba lewati kegelapan dengan lilin yang tidak pernah redup.Ia susuri setiap penderitaan Ia cari kebenaran diantara fitnah dan kebohongan.Ia jaga amanah-Nya, hingga bumi menelan seluruh raganya
Itulah ceritanya. Ceritanya memang telah usai,Namun kisahnya takkan pernah selesai.Walaupun mulutnya tak bisa berkata, tapi hatinya akan terus bercerita.Meskipun ia menderita, tapi jiwanya merasa amat bahagia.Bersediakah kita meneruskan ceritanya…???Salam manis buat seorang pendiam,Ceritanya tak akan pernah bungkam.
Wastu SancokoMahasiswa FE Akuntansi ‘08 UNS
AKU..

VISI | No. 27/Th. XX/201056
Cerpen
“Huh... kenapa waktu begitu cepat berlalu...,” gumanku yang nyaris tak terdengar tersaingi desakan dedaunan yang sudah sejak tadi antri
bersua. “Tera... kamu nggak kuliah nduk? Sudah jam tujuh lebih lho...,” hardik ibuku sambil sesekali mengetuk pintu turut memeriahkan suasana yang bagiku terasa begitu hening ini. “Iya Bu... sebentar,” sahutku singkat seraya meloncat dari tempat tidur yang telah melenakan aku dengan cengkeramannya yang begitu kuat. Dengan setelan baju biru muda dan rok putih dipadukan dengan jilbab putih pula, aku susuri jalan yang masih terasa asing bagiku. Maklumlah, belum genap seminggu aku tinggal disini. Sepanjang jalan hanya hiruk-pikuk yang menemaniku, ditambah lagi bus yang kutumpangi tampak malas memutar rodanya. Sesekali berhenti, sesekali berhenti....*** “Assalamu’alaikum Pak...” “Wa’alaikumsalam, ya... silakan masuk. Lain kali jangan terlambat lagi ya?” “Insya Allah, terima kasih Pak.” Helaan nafas lega tersembur seketika setelah kurebahkan tubuhku di bangku paling pojok dan seperti tak terbendung lagi, puluhan pasang mata menatapku dengan pandangan penuh keasingan. Rasanya tak kuasa lagi aku menahan malu bingung menyembunyikan wajah yang mulai memerah. “Hei, siapa namamu, boleh kenalan nggak?” tanya seseorang yang kebetulan duduk di sampingku dengan berbisik sambil menyodorkan tangannya. “Eh... anu... nama saya Lentera Mbak. Lha Mbaknya sendiri namanya siapa?” sahutku terbata-bata sambil membalas sodoran tangannya. “Kalau aku Lilin. Tenang aja, nggak usah grogi gitu. Eh... jangan panggil aku Mbak donk, kita kan satu angkatan. Panggil Lilin aja ya?” Balasnya sambil menunjukkan deretan giginya. Mengangguk sambil tersenyum simpul.*** “Lentera..!” “Ya, ada apa Lin?” tanyaku sambil menoleh ke arahnya. “Aku pinjem catetanmu yang tadi donk, boleh nggak?” “Ini,” sahutku singkat sambil menyerahkan bukuku. “Oke, makasih ya... pokoknya kamu tenang aja, nggak akan aku rusakin kok bukumu ini. Aku pinjem dulu ya?” balasnya seraya berjalan menjauh, lenyap ditelan kerumunan.***Lilin. Sebuah nama sederhana yang kutaksir telah melekat pada raganya tidak kurang dari 19 tahun. Dia satu-satunya teman yang baru kukenal sejauh ini. Nuansa “gaul” yang disandang kebanyakan wanita di kampus, ada pula pada sosok Lilin. Tapi yang membuat aku heran, kenapa dia
memilih aku untuk jadi temannya. Padahal aku sama sekali nggak “gaul” kayak mereka. Entah pertimbangan apa yang membuatnya mempercayaiku untuk jadi temannya.... Seiring berputarnya jarum jam, aku dan Lilin pun semakin akrab. Dia sering main ke rumahku, begitu pula sebaliknya. Setiap kali aku bertandang ke rumahnya, dia selalu menyambutku dengan gegap gempita. Banyak hal yang selalu dapat kita bicarakan. Dari urusan kuliah sampai pengalaman masa lalu pun tak luput menjadi bahan obrolan kita.*** “Ra, nanti sore aku ke tempatmu ya? Ada yang mau aku omongin nih,” pintanya sambil berjalan beriringan denganku berhamburan ke luar kelas. “Nanti sore ya..? Em... iya deh, kebetulan aku juga lagi nggak ada kerjaan,” jawabku singkat sambil mengerutkan dahi, mengira-ira maksudnya.*** Tok... tok... tok.... “Eh... kamu to Lin. Kenapa nih, kok kelihatannya serius gitu?” “Gini Ra, tapi kamu jangan ngetawain aku ya? Em... aku mau belajar ngaji nih.” “Lho, belajar ngaji kok diketawain sih! Emang bagian mana yang lucu?” “Ya, bukannya gitu Ra. Sudah setua ini aku kan belum bisa ngaji, padahal Adikmu yang baru sepuluh tahun itu aja udah lancar ngajinya. Mbok ya kamu ajarin aku.... Gimana, kamu mau nggak...?” “Ya... mau sih mau, tapi aku juga nggak bisa-bisa amat. Aku ajari sebisaku ya?” “Nah gitu donk Ra, baru asyik namanya.” “Tapi kok tumben kamu mau belajar ngaji. Emang ada angin apa?” “Ya... sebetulnya aku udah bosen hidup kayak gini Ra. Banyak hal yang nggak aku dapetin dari kehidupanku sekarang. Secara materiil ya, tapi secara spirituil sama sekali nggak ada dan kamu sendiri kan tau Ibuku sudah lama meninggal...,” tukasnya yang terhenti tarikan nafas panjang. Hening... sunyi.... Tiba-tiba aroma keseriusan terpancar kuat di wajah Lilin. “Aku ingin membalas jasa Ibuku Ra...,” lanjutnya dengan diiringi mata yang mulai berkaca-kaca. “Aku ingin membahagiakannya, aku ingin Ibuku mendengar lantunan ayat-ayat suci Al Qur’an yang kuucapkan. Aku ingin... aku ingin Ibuku tahu betapa aku menyayanginya. Aku sayang Ibuku Ra... aku rindu sekali padanya... rindu sekali...,” rintihnya yang terhadang oleh air mata yang meleleh menyusuri pipinya sambil berusaha menahan isak. “Sudahlah Lin... yang tabah ya?... Allah Maha Mendengar. Dia mendengar semua niat baikmu dan pasti Ibumu pun akan tersenyum bangga melihatmu sekarang,” hiburku sambil kupeluk tubuhnya erat-erat seraya berdoa; ‘Ya Allah tabahkanlah hati temanku ini. Bimbinglah selalu ia ke jalan yang benar’. Amin.*** Tidak kurang dari sebulan penuh aku mengajarinya
“Lentera Diantara Lilin“oleh : Indra H.

VISI | No. 27/Th. XX/2010 57
dmengaji. Jelas memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi mengingat kemauannya yang begitu keras, tak rela aku mengganjalnya dengan keluhanku. Satu hal yang membahagiakan lagi, lambat laun Lilin mulai mengubah penampilannya. Meskipun belum memakai kerudung, tapi dia telah menanggalkan pakaian minimnya dulu dan berganti dengan busana yang longgar, berusaha untuk menutup aurotnya.
Tapi, akhir-akhir ini....*** “Yang namanya Lilin mana ya?” seru dosenku dengan pandangan yang diarahkan ke seluruh sudut kelas sambil sesekali menggelengkan kepalanya. Seluruh penghuni kelas diam, termasuk aku. “Kalau sekali lagi dia tidak masuk, hampir dipastikan tidak akan diijinkan mengikuti ujian dan tentu saja kemungkinan untuk lulus sangatlah kecil,” lanjutnya dengan aroma ancaman yang begitu kental. “Lilin... kemana saja kamu,” gumanku lirih. Entah kenapa sudah hampir dua bulan ini ia tidak masuk. Aku cari di rumah, rumahnya selalu sepi, aku telpon nggak diangkat, apalagi sms, sampai pegal tanganku nggak dibalas-balas. Padahal sebentar lagi mau ujian, jangankan ngumpulin tugas, masuk aja nggak pernah. “Oiya... terakhir kali aku ketemu dia kan di rumah Neneknya. Mungkin saja dia ada di sana...,” lamunku mengingatnya.*** Sepi. Hanya serumpun melati dan sebatang pohon nangka besar yang menghadangku setiba di rumah neneknya Lilin. “Assalamu’alaikum...,” sapaku seraya mengetuk pintu. ”Wa’alaikumsalam...,” sahutnya pelan disertai rintihan langkah yang terseret. “Eh... Non Tera. Mari masuk. Gimana kuliahnya?” sambutnya dengan mata terbelalak kaget disertai tingkah laku kikuk, gelisah berusaha menenangkan perasaannya dengan berusaha tersenyum.
“Alhamdulillah, baik Nek. Lha Nenek sendiri gimana? Sehat kan?”“Alhamdulillah, berkat doa Non Tera, Nenek sehat?”
sahutnya sekali lagi dengan keramahan. Namun tetap saja nuansa kegelisahan begitu kuat melekat di wajahnya yang berukiran keriput. Sejenak kami pun diam, sesekali aku menoleh padanya sambil mengerutkan dahi mengira-ira gerangan apa yang bersemayam di balik kegelisahannya. Mungkinkah ini mengenai Lilin..? Menarik nafas panjang.
“Nek... Lilin mana Nek?” lanjutku dengan hati-hati seraya menghela nafas.
Hening... sunyi. Tampak wajah nenek yang tidak kuasa menatapku, tertunduk dengan kedua jemari tangan terkait membentuk simpul.
“Anu Non... sebentar ya...,” sahutnya sambil tiba-tiba bangkit dari bangku dan bergegas masuk ke dalam kamar.
Perasaanku seketika menjadi tak menentu. Entah untuk apa nenek masuk ke dalam kamar? Apa yang dia sembunyikan? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Lilin? Apa...? Apa yang terjadi...?
“Ini Non, surat yang ditulis Lilin untuk Non Tera,” hardiknya menghalau kebimbanganku sambil menyodorkan sebuah amplop kecil seraya kembali duduk.
“Apa ini Nek?” tanyaku singkat dengan rasa penasaran yang telah menggebu-gebu.
“Ya... itu Non, saya juga ndak tahu apa isinya. Pokoknya
buat Non Tera. Gitu pesannya,” jawaban singkat yang membuat dahiku semakin berkerut.
Perlahan-lahan kurobek amplop itu dengan hati-hati dan kukeluarkan isinya.
Sebuah foto berukuran postcard menyembul keluar. Senyum simpul terurai dari wajah Lilin dengan balutan baju muslim bermahkotakan jilbab putih bersih. Syukur berlipat aku haturkan. Baru kali ini kulihat Lilin memakai jilbab.
“Nek, ini...,“ ucapku memecah keheningan sambil menunjukkan foto itu kepada nenek.
“Ya, itu foto Lilin dua minggu lalu,” potong nenek.Mengangguk sambil meraih secarik kertas yang
bersanding dengan foto itu. Kuurai lipatannya dengan perlahan sambil menerka apa yang tergores di dalamnya.
To:My Little Wing,Lentera Assalamu’alaikum,
Ra, aku cantik nggak pakai jilbab? Awas ya kalau kamu ngetawain aku. Aku seneng Ra, akhirnya aku bisa pake’ jilbab kayak kamu, meski mungkin aku hanya bisa sebentar make’nya.
Ra, makasih banyak ya, udah jadi temenku. Tenang aja mungkin aku nggak akan pinjem catetan kamu lagi kok? Sorry banget kalau selama ini aku punya salah sama kamu, terutama waktu aku pinjem catetan kamu yang kukembaliin dalam keadaan kucel, he... he... he.... Selamanya aku nggak akan nglupain kamu, seseorang yang bernama “Lentera”.
Jaga diri baik-baik ya Ra? Tenang aja, aku disini baik-baik aja kok. Aku rindu kamu Ra....
Wassalam Kulipat kembali secarik kertas itu dengan ratusan tanda tanya berkecamuk di kepalaku. ‘Sebenarnya apa yang terjadi?’ begitulah mereka bersahut-sahutan. “Nek, sebenarnya apa yang terjadi dengan Lilin? Dimana dia?” tanyaku memelas membujuknya agar bersedia mengusir tanda tanya yang berkecamuk di kepalaku. “Em... sebenarnya sudah hampir setahun ini Lilin mengidap penyakit kanker dan kini dia...” “Dia kenapa Nek? Kenapa dengan Lilin? Bagaimana keadaannya sekarang?” sahutku bertubi-tubi menyongsong ucapan nenek yang terputus. “Lilin telah meninggal dunia seminggu lalu,” seru nenek. “Innalillahi wa Innaillaihi Roji’un,” ratapku menyambut jawaban nenek Seketika hening. Aku hanya tertunduk lemas sambil memejamkan mata berusaha keras agar air mataku tidak mengalir. Perlahan-lahan kupaksa menatap foto itu lagi. Kulihat senyumnya yang semakin lama semakin menjauh. Kudekap foto itu erat-erat, sangat erat, seakan tak ingin rasanya aku melepasnya.
Biodata penulis:Nama : Indra HutamaAlamat : RD PTPN X KlatenTTL : Solo, 8 Juni 1986Hobi : Menulis, membaca
Saat ini penulis tercatat sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi UNS 2004 dan pernah aktif di organisasi Forum Lingkar Pena Solo.

VISI | No. 27/Th. XX/201058
Detak
Umumnya, hobi, pekerjaan, atau kehidupan yang ingin digeluti oleh kebanyakan orang adalah sesuatu yang pasti, aman, dan menjanjikan. Tak
heran, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki pendaftar terbanyak. Namun, dunia ini tak akan berwarna tanpa kehadiran orang-orang bernyali besar yang menantang maut.
Di tengah ribuan orang yang menggeluti kerja kantoran dan hobi yang aman, ada orang-orang yang “abnormal”. Merekalah orang yang menyukai tantangan dan ketidakpastian. Pembalap, pendaki gunung, atau , pereli. Di kepala orang “normal” biasanya terlintas pikiran tentang apa yang sebenarnya mereka cari? Bukankah pembalap Ayrton Sena bahkan tewas saat balapan? Tapi kenapa ada saja orang yang rela mempertaruhkan nyawa dengan mengikuti jejaknya?
Para pembalap itu, bisa saja bekerja di sebuah gedung pencakar langit. Mendapat gaji berlimpah tanpa harus mempertaruhkan nyawa di sirkuit yang panas. Mengapa mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak pasti? Padahal, di dunia ini, beribu, berjuta, atau bahkan bermiliyar orang berlomba untuk mendapat pekerjaan yang memberi kenyamanan. Mereka justru memilih menjadi adrenaline junkie.
Mereka bukannya mencari mati. Jauh dari itu malah. Tapi mereka adalah manusia-manusia yang tidak takut menghadapi ketidakpastian. Manusia yang berani keluar dari wilayah kenyamanan untuk bisa merasakan hidup yang sebenarnya.
Umumnya, banyak orang hidup dalam sebuah rutinitas yang sama. Seperti domba-domba yang digiring oleh sang gembala. Menjadi patuh. Bangun pagi, pergi kerja, mendengarkan omelan bos, permintaan dari kolega, lalu pulang, makan malam, dan tidur. Terus begitu sepanjang hidup. Semua serba pasti.
Kata orang Jawa, hidup itu bagaikan orang mampir ngombe (mampir minum) saja. Sebagian orang berusaha mendapat kehidupan senyaman mungkin selama mampir ngombe itu. Sementara sebagian yang lainnya justru bertanya: untuk apa semua itu? Sekolah, kerja, berpenghasilan, menikah, punya anak, membesarkan mereka, lalu mati dan dikubur di sebuah pemakaman mewah yang sudah dipesan puluhan tahun sebelum kita mati. Apakah itu saja arti hidup?
Manusia hidup dikaruniai akal yang luar biasa. Dengan akalnya itulah manusia mampu mengubah alam dan menjadikannya lebih nyaman dengan berbagai penemuan. Membuatnya jadi lebih nyaman untuk ditinggali.
Baju, rumah, mobil, kendaraan, televisi, radio,
komputer, remote control, handphone, sendok, garpu. Masih banyak lagi perabot atau ciptaan manusia lainnya. Semua itu, tak lain diciptakan manusia dengan akal dan kekuatannya. Tentu saja untuk mewujudkan keinginan membuat hidupnya lebih nyaman.
Tetapi, manusia tetaplah manusia. Makhluk yang diciptakan dengan insting dan adrenalin. Insting yang diciptakan untuk membuat manusia bisa terus survive di dunia. Ketika segalanya nyaman, ketika segalanya mudah, insting manusia berontak. Ketidakpastian justru dicari.
Manusia berusaha menjalani kembali kehidupan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Yang harus berhadapan dengan binatang buas hanya sekadar untuk makan malam. Yang tidak pasti bisa pulang atau tidak setelah buang air kecil di sungai di depan gua tempat tinggal mereka.
Insting purba manusia memaksanya untuk terus mencari ketidakpastian. Sebab, hidup tanpa tantangan bukanlah hidup yang ditakdirkan untuk manusia. Hidup nyaman sama sekali bukan intensi manusia diciptakan. Bukankah manusia adalah makhluk yang diusir Tuhan dari surga yang amat sangat nyaman?
Kalau mau hidup, harus berani menghadapi yang tidak pasti. Karena mencari yang pasti dalam hidup sama saja dengan mencari mati. Bukankah yang pasti dalam kehidupan hanyalah mati?
Itulah yang mungkin ada dalam benak orang-orang yang anti-kenyamanan atau “abnormal”. Orang yang berpikiran di luar batas kewajaran manusia lainnya. Makanya tidak heran kalau mereka begitu berani mengambil resiko dalam hidup. Banyak yang menjadi adrenaline junkie. Seperti para pendaki gunung atau para pembalap. Mereka mencari ketidakpastian dengan mendaki gunung atau melajukan mobilnya kencang-kencang di sirkuit dan jalan bebas hambatan ketika pagi menjelang.
Adinda NusantariPegiat LPM VISI FISIP UNS
NYALIDi dunia ini, ribuan bahkan jutaan orang pasti mendambakan kenyamanan. Namun, banyak pula yang berpikiran sebaliknya.
VISI | No. 27/Th. XX/201058