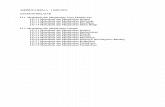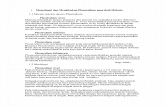skenario 2 IPT
-
Upload
saiiawidia793976295 -
Category
Documents
-
view
87 -
download
0
Transcript of skenario 2 IPT

Sasbel
1. Memahami dan Menjelaskan Morbillivirus
1.1 Menjelaskan Definisi Morbillivirus
1.2 Menjelaskan Morfologi Morbillivirus
1.3 Menjelaskan Klasifikasi Morbillivirus
1.4 Menjelaskan Siklus Hidup Morbillivirus
2. Memahami dan Menjelaskan Campak
2.1 Menjelaskan Definisi Campak
2.2 Menjelaskan Etiologi Campak
2.3 Menjelaskan Epidemiologi Campak
2.4 Menjelaskan Patofisiologi Campak
2.5 Menjelaskan Manifestasi Klinik Campak
2.6 Menjelaskan Pemeriksaan Fisik dan Penunjang Campak
2.7 Menjelaskan Diagnosis Campak
2.8 Menjelaskan Diagnosis Banding Campak
2.9 Menjelaskan Penatalaksanaan Campak
2.10 Menjelaskan Komplikasi Campak
2.11 Menjelaskan Pencegahan Campak
Jawaban
1. Memahami dan Menjelaskan Morbillivirus
1.1 Menjelaskan Definisi Morbillivirus
Virus Campak / Virus Rubella adalah adalah virus RNA beruntai tunggal, dari keluarga Paramyxovirus, dari genus Morbillivirus. Virus campak hanya menginfeksi manusia, dimana virus campak ini tidak aktif oleh panas, cahaya, pH asam, eter, dan tripsin (enzim). Ini memiliki waktu kelangsungan hidup singkat di udara, atau pada benda dan permukaan.
(http://www.kesehatan123.com/1621/virus-campak-sejarah-komplikasi-dan-kasus/) diakses tanggal 09/04/2013 23:49 WIB

1.2 Menjelaskan Morfologi Morbillivirus
Virus campak atau morbilli adalah virus RNA anggota famili paramyxoviridae. Secara morfologi tidak dapat dibedakan dengan virus lain anggota famili paramyxoviridae. Virion (partikel virus lengkap, yang utuh secara struktural dan menular) campak terdiri atas nukleokapsid berbentuk heliks yang dikelilingi oleh selubung virus. Virus campak mempunyai 6 protein struktural, 3 diantaranya tergabung dengan RNA dan membentuk nukleokapsid yaitu; Pospoprotein (P), protein ukuran besar (L), dan nukleoprotein (N). Tiga protein lainnya tergabung dengan selubung virus yaitu; protein fusi (F), protein hemaglutinin (H) dan protein matrix (M). Protein F dan H mengalami glikolisasi (mereduksi atau bahkan merusak fungsi berbagai enzim) sedangkan protein M tidak.
Protein F bertanggung jawab terhadap fusi virus dengan membran sel hospes, yang kemudian diikuti dengan penetrasi dan hemolisis. Protein H bertanggung jawab pada hemaglutinasi (penggumpalan sel darah merah), perlekatan virus, adsorpsi dan interaksi dengan reseptor di permukaan sel hospes. Protein F dan H bersama-sama bertanggungjawab pada fusi virus dengan membran sel dan membantu masuknya virus. Sedangkan protein M berinteraksi dengan nukleokapsid berperan pada proses maturasi virus.
1.3 Menjelaskan Klasifikasi Morbillivirus
Klasifikasi Virus berdasarkan jenis asam nukleat (DNA atau RNA)Virus RNA
a. Famili : PicornaviridaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas positif, segmen tunggal, replikasi RNA melalui
pembentukan RNA komplementer yang bertindak sebagai cetakan sintesis RNA genom.
· Virion : tak berselubung, bentuk ikosahedral, tersusun atas empat jenis protein utama. Diameter virion 28-30 nm.
· Replikasi dan morfogenesis virus terjadi di sitoplasma.· Spektrum hospes sempit.Contoh : virus polio
b. Famili : CalicivirdaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas positif, segmen tunggal.· Virion : tak berselubung, bentuk ikosahedral, tersusun atas tiga jenis protein utama.
Diameter virion 35-45 nm.· Replikasi dan morfogenesis di sitoplasma.· Spektrum hospes sempit.Contoh : virus Sapporo
c. Famili : TogaviridaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas positif, segmen tunggal, replikasi RNA melalui
pembentukan RNA komplementer, yang bertindak sebagai cetakan RNA genom.· Virion : berselubung, nukleokapsid ikosahedral, tersusun atas 3-4 jenis protein utama.
Protein selubung mempunyai aktivitas hemaglutinasi. Diameter virion 60-70 nm.· Replikasi di sitoplasma dan morfogenesis melalui prosesbudding di membran sel.

· Spektrum hospes luas.Contoh : virus Chikungunya, virus rubella
d. Famili : FlaviviridaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas positif, segmen tunggal, replikasi RNA melalui RNA
komplementer yang kemudian bertindak sebagai cetakan bagi sintesis RNA genom.· Virion : berselubung, simetri nukleokapsid belum jelas, tersusun atas empat jenis
protein utama. Protein selubung mempunyai aktivitas hemaglutinasi. Diameter virion 40-50 nm.
· Replikasi di sitoplasma dan morfogenesisnya melalui prosesbudding di membran sel.· Spektrum hospes luas.Contoh : virus demam kuning
e. Famili : BunyaviridaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas negatif, terdiri dari tiga segmen. Pada proses
replikasinya, RNA virion disalin menjadi mRNA dengan bantuan transkriptasa virion. Dengan bantuan produk translasi mRNA selanjutnya disintesis RNA komplementer. Tiap segmen RNA komplementer kemudian menjadi cetakan bagi RNA genom.
· Virion : berselubung, nukleokapsid bentuk helik, tersusun atas empat protein utama. Protein selubung mempunyai aktivitas hemaglutinasi. Diameter virion 90-120 nm.
· Replikasi di sitoplasma dan morfogenesisnya melalui prosesbudding di membran Golgi.Contoh : virus ensefalitis California
f. Famili : ArenaviridaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas negatif, terdiri dari dua segmen.Prinsip replikasi
RNAnya sama dengan Bunyaviridae.· Virion : berselubung, nukleokapsid helik, tersusun atas tiga protein utama. Bentuk
virion pleomorfik. Diameter virion 50-300 nm (rata-rata 110-130 nm).· Replikasi di sitoplasma morfogenesisnya melalui prosesbudding di membran plasma.· Spektrum hospes luas.Contoh : virus lymphatic
g. Famili : CoronaviridaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, terdiri dari satu segmen. Replikasi RNA genom melalui
pembentukan rantai RNA negatif yang kemudian bertindak sebagai cetakan bagi RNA genom.Sintesis RNA negatif disertai sintesis enam jenis mRNA.
· Virion : berselubung, nukleokapsid helik, tersusun atas tiga protein utama. Bentuk pleomorfik. Diameter virion 80-160 nm.
· Replikasi di sitoplasma dan morfogenesisnya melalui prosesbudding di membran intrasitoplasma.
Contoh : coronavirus manusia 229-E dan OC43h. Famili : Rhabdoviridae
Sifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas negatif, satu segmen. Prinsip replikasi RNAnya sama
dengan Bunyaviridae.

· Virion : berselubung, nukleokapsid helik, tersusun atas 4-5 protein. Virion berbentuk seperti peluru dengan selubung beraktivitas hemaglutinasi. Diameter dan panjang virion 70-85 nm dan 130-180 nm.
· Replikasi di sitoplasma dan morfogenesisnya di membran plasma atau intrasitoplasma, tergantung spesies virus.
Contoh : virus stomatitis vesicularisi. Famili : Filoviridae
Sifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas negatif, segmen tunggal.· Virion : berselubung, nukleokapsid helik, tersusun atas tujuh protein utama. Berbentuk
pleomorfik. Diameter virion 80 nm dan panjang mencapai 14.000 nm.· Replikasi di sitoplasma.Contoh : virus Ebola
j. Famili : ParamyxoviridaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, polaritas negatif. Replikasi RNA dimulai dengan sintesis mRNA
dengan bantuan transkriptasa virion. Dengan bantuan produk protein mRNA dibuat RNA cetakan RNA genom.
· Virion : berselubung, nukleokapsid helik, tersusun atas 6-10 protein utama. Berbentuk pleomorfik. Selubung mempunyai aktivitas hemaglutinasi dan menginduksifusi sel. Replikasi di sitoplasma dan morfogenesisnya melalui proses budding di membran plasma. Diameter virion 150-300 nm.
· Spektrum hospes sempit.Contoh : parainfluenza 1-4, viris parotitis
k. Famili : OrthomyxoviridaeSifat penting :· RNA : rantai tunggal, segmen berganda (7 untuk influenza C dan 8 untuk influenza A
dan B), polaritas negatif. Replikasi RNA dimulai dengan sintesis mRNA dengan bantuan transkriptasa virion. Dengan bantuan protein produk mRNA, RNa komplementer dibuat dan dijadikan cetakan pembuatan RNA genom. Sifat segmentasi genom virus memudahkan terjadinya virus mutan.
· Virion : berselubung, nukleokapsid helik, tersusun atas 7-9 protein utama. Bentuk pleomorfik. Selubung beraktivitas hemaglutinasi. Diameter virion 90-120 nm. Pada filamentosa panjangnya mencapai beberapa mikrometer.
· Replikasi RNA di inti dan sitoplasma dan morfogenesis melalui proses budding di membran plasma.
Contoh : virus Influenza A,B, dan Cl. Famili : Reoviridae
Sifat penting :· RNA : rantai ganda, segmen ganda (10 untuk reovirus dan obvirus, 11 untuk rotavirus,
12 untuk Colorado tick fevervirus. Setiap mRNA berasal dari satu segmen genom. Sebagian mRNA dipakai untuk sintesis protein dan sebagian lagi dipakai sebagai cetakan untuk pembuatan rantai RNA pasangannya.
· Virion : tak berselubung, kapsidnya dua lapis dan bersimetri ikosahedral. Diameter virion 60-80 nm.
· Replikasi dan morfogenesis di sitoplasma.

Contoh : Reovirus 1-3m. Famili : Retroviridae
Sifat penting :· RNA : rantai tunggal, terdiri dari dua molekul polaritas negatif yang identik. Replikasi
dimulai dengan pemisahan kedua molekul RNA dan pembuatan rantai DNA dengan cetakan RNA tersebutdengan bantuan reverse transcriptase virion. Setelah molekul RNA-DNA terpisah, dibuat rantai DNA komplementer terhadap pasangan DNA yang sudah ada. DNA serat ganda kemudian mengalami sirkularisasi dan berintegrasi dengan kromosom hospes. Selanjutnya RNA genom dibuat dengan cetakan DNa yang sudah terintegrasi pada kromosom hospes.
· Virion : berselubung, simetri kapsid ikosahedral. Virion tersusun atas 7 jenis protein utama. Diametr virion 80-130 nm. Morfogenesis virus melalui proses budding di membran plasma.
Contoh : HIV 1 dan 2Virus DNA
a. Famili : AdenoviridaeSifat penting :· DNA : rantai ganda, segmen tunggal. Replikasi DNA dan translasinya menjadi protein
komplek.· Virion : tak berselubung, simetri kapsid ikosahedral. Diameter virion 70-90 nm. Virion
tersusun atas paling tidak 10 protein.· Replikasi dan morfogenesis di inti sel.· Spektrum hospes sempit.Contoh : Adenivirus 1-49
b. Famili : HerpesviridaeSifat penting :· DNA : rantai ganda, segmen tunggal. Replikasi DNA komplek.· Virion : berselubung, simetri kapsid ikosahedral. Diameter virion 15-200 nm.· Replikasi di intisel. Morfogenesis melalui proses budding di membran inti. Di dalam
sitoplasma virion dibawa dalam vesikel-vesikelke membran plasma. Di membran plasma, membran vesikel fusi dengan membran plasma.
Contoh : virus herpes simplex 1-2, virus Bc. Famili : Hepadnaviridae
Sifat penting :· DNA : rantai ganda (bagian terbesar) dan rantai tunggal (bagian kecil, di ujung molekul
DNA), segmen tunggal. Pada replikasi genom, bagian rantai tunggalnya harus dibuat rantai ganda. Transkripsi DNA menghasilkan mRNA untuk sintesis protein dan RNA lain sebagai cetakan bagi pembuatan DNA oleh reverse transcriptase.
· Virion : berselubung (HBsAg), diameter 42 nm. Tersusun atas selubung (HBsAg) dan nukleokapsid. Dalam nukleokapsid terdapat core (HBcAg) dan protein penting lain (HBeAg).
· Replikasi di hepatosit terjadi di inti sel sedangkan HBsAg dibuat di sitoplasma.Contoh : virus hepatitis B
d. Famili : PapovaviridaeSifat penting :

· DNA : rantai ganda, segmen tunggal sirkuler. Replikasi DNA komplek dan selama replikasi bentuknya tetap sirkuler. Siklus replikasi DNA dapat melibatkan DNA genom yang episomal maupun yang berintegrasi dengan kromosom sel.
· Virion : tak berselubung, diameter 45 nm (polyomavirus) dan 55 nm (papillomavirus), tersusun atas 5-7 jenis protein utama.
· Replikasi dan morfogenesis di inti sel.· Spektrum hospes sempit.Contoh : papilloma virus manusia
e. Famili : ParvoviridaeSifat penting :· DNA : rantai tunggal, segmen tunggal. Genus Parvovirus lebih banyak mengandung
rantai DNA polaritas negatif sedang dua genus lagi DNA polaritas negatif dan positifnya seimbang. Replikasi DNA komplek.
· Virion : tak berselubung, nukleokapsid bersimetri ikosahedral dan berdiameter 18-26 nm, tersusun atas tiga protein utama.
· Replikasi dan morfogenesis di inti sel dan memerlukan bantuan sel hospes.· Spektrum hospes sempit.Contoh : parvovirus B-19
f. Famili : PoxviridaeSifat penting :· DNA : rantai ganda, segmen tunggal. Replikasi DNA komplek.· Virion : berselubung, berbentuk seperti batu bata dan merupakan virus dengan dimensi
terbesar. Tersusun atas lebih dari seratus jenis protein. Selubung mempunyai aktivitas hemaglutinasi.
· Replikasi dan morfogenesis di sitoplasma yaitu dalam viroplasma (semacam pabrik virus). Hasil morfogenesis dapat berupa virion berselubung maupun tidak.
Contoh : virus cacar sapi
(Waluyo, Lud, Drs.M.Kes. 2007. Mikrobiologi Umum (Edisi Revisi).UMM Press. Malang.)
1.4 Menjelaskan Siklus Hidup Morbillivirus
Secara Umum siklus hidup virus ada 5 macam:
Attachment : Ikatan khas diantara viral capsid proteins dan spesifik reseptor pada permukaan sel inang. Virus akan menyeranf sel inang yang spesifik.
Penetration : Virus masuk ke sel inang menembus secara endytocsis atau melaluimekanisme lain
Uncoating : Proses terdegradasinya viral kapsid oleh enzim viral atau host enzymesyang dihasilkan oleh viral genomic nudwic acid
Replication : Replikasi virus, Litik atau Lisogenik Release : Virus dilepaskan dari sel inang melalui lisis

2. Memahami dan Menjelaskan Campak
2.1 Menjelaskan Definisi Campak
Campak, measles atau rubeola adalah penyakit virus akut yang disebabkan oleh virus campak. Penyakit ini sangat infeksius, menular sejak awal masa prodromal sampai lebih kurang 4 hari setelah munculnya ruam. Infeksi disebarkan lewat udara (airborne).
Campak adalah suatu penyakit infeksi virus aktif menular, ditandai oleh tiga stadium : 1. stadium inkubasi atau kataral sekitar 10-12 hari dengan sedikit, jika ada, tanda-tanda atau gejala-gejala, 2. stadium prodromal dengan enantem (bercak koplik) pada mukosa bukal dan faring, demam ringan sampai sedang, konjungtivitis ringan, koryza, dan batuk yang semakin berat, dan 3. stadium akhir atau konvalesen dengan ruam makuler yang muncul berturut-turut pada leher dan muka, tubuh, lengan dan kaki dan disertai oleh demam tinggi. (Behrman.R.E. et al, 1999).
2.2 Menjelaskan Etiologi CampakPenyakit ini disebabkan oleh virus campak dari famili Paramyxovirus, genus
Morbilivirus. Virus campak adalah virus RNA yang dikenal hanya mempunai satu antigen. Struktur virus ini mirip dengan virus penyebab parotitits epidemis dan parainfluenza.Setelah timbulnya ruam kulit, virus aktif dapat ditemukan pada sekret nasofaring, darah, dan air kencing dalam waktu sekitar 34 jam pada suhu kamar.
Virus campak dapat bertahan selama beberapa hari pada temperatur 0 C dan selama 15 minggu pada sediaan beku. Di luar tubuh manusia virus ini mudah mati. Pada suhu kamar sekalipun, virus ini akan kehilangan inefektifitasnya sekitar 60% selama 3-5 hari. Virus campak akan mudah hancur pada sinar ultraviolet.
Virus campak dapat diisolasi dalam biakan embrio manusia. Perubahan sitopatik, tampak dalam 5-10 hari, terdiri dari sel raksasa multinukleus dengan inklusi intranuklear. Antibodi dalam sirkulasi dapat dideteksi bila ruam muncul. Penyebaran virus maksimal adalah dengan tetes semprotan selama masa prodromal (stadium kataral). Penularan terhadap kontak rentan sering terjadi sebelum diagnosis kasus aslinya. Orang yang terinfeksi menjadi menular pada hari ke 9-10 sesudah pemajanan (mulai fase prodromal), pada beberapa keadaan awal hari ke 7 sesudah pemajanan sampai hari ke 5 sesudah ruam muncul. (Berhman.R.E. et al, 1999)
Cara Penularan Penularan dari orang ke orang melalui percikan ludah dan transmisi melalui udara
( sampai 2 jam setelah penderita campak meninggalkan ruangan ). Waktu Penularan: 4 hari sebelum dan 4 hari setelah ruam. Penularan maksimum pada 3-4 hari setelah ruam.
(http://www.pantirapih.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Apenyakit-campak&catid=51%3Aumum&Itemid=97&limitstart=1) diakses tanggal 09/04/2013 pukul: 23.54 WIB
2.3 Menjelaskan Epidemiologi Campak

Campak merupakan penyakit endemis pada sebagian besar dunia.Di Amerika Serikat jumlah kasus campak pada tahun 1990 hampir mencapai 28.000 kasus. Di negara industri, campak terjadi pada anak-anak berumur 5 hingga 10 tahun, sementara di negara berkembang penyakit ini sering menginfeksi anak-anak dibawah umur 5 tahun.
Angka kejadian campak di Indonesia sejak tahun 1990 – 2002 masih tinggi sekitar 3000 – 4000 pertahun. Umur terbanyak menderita campak adalah <12 bulan, diikuti kelompok umur 1-4 dan 5-14 tahun. Adapun faktor risiko terjadinya campak yaitu : 1. Anak-anak dengan imunodefisiensi, misalnya pada HIV/AIDS, leukemia, atau dengan terapi kortikosteroid. 2. Perjalanan atau kunjungan ke daerah endemi campak atau kontak dengan pendatang dari daerah endemi . 3. Bayi yang kehilangan antibodi pasif dan tidak diimunisasi. Faktor risiko yang mempeberat penyakit campak sehingga dapat menimbulkan komplikasi yang serius, yaitu :
1. Malnutrisi 2. Imunodefisiensi 3. Defisiensi vitamin A
2.4 Menjelaskan Patogenesis Campak
Campak merupakan infeksi virus yang sangat menular, dengan sedikit virus yang infeksius sudah dapat menimbulkan infeksi pada seseorang. Lokasi utama infeksi virus campak adalah epitel saluran nafas nasofaring. Infeksi virus pertama pada saluran nafas sangat minimal. Kejadian yang lebih penting adalah penyebaran pertama virus campak ke jaringan limfatik regional yang menyebabkan terjadinya viremia primer. Setelah viremia primer, terjadi multiplikasi ekstensif dari virus campak yang terjadi pada jaringan limfatik regional maupun jaringan limfatik yang lebih jauh. Multiplikasi virus campak juga terjadi di lokasi pertama infeksi.
Selama lima hingga tujuh hari infeksi terjadi viremia sekunder yang ekstensif dan menyebabkan terjadinya infeksi campak secara umum. Kulit, konjungtiva, dan saluran nafas adalah tempat yang jelas terkena infeksi, tetapi organ lainnya dapat terinfeksi pula. Dari hari ke-11 hingga 14 infeksi, kandungan virus dalam darah, saluran nafas, dan organ lain mencapai puncaknya dan kemudian jumlahnya menurun secara cepat dalam waktu 2 hingga 3 hari. Selama infeksi virus campak akan bereplikasi di dalam sel endotel, sel epitel, monosit, dan makrofag (Cherry, 2004).
Daerah epitel yang nekrotik di nasofaring dan saluran pernafasan memberikan kesempatan serangan infeksi bakteri sekunder berupa bronkopneumonia, otitis media, dan lainnya. Dalam keadaan tertentu, adenovirus dan herpes virus pneumonia dapat terjadi pada kasus campak (Soedarmo dkk., 2002).
2.5 Menjelaskan Manifestasi Klinik Campak
Hari 1-3 : Demam tinggi. Mata merah dan sakit bila kena cahaya. Anak batuk pilek Mungkin dengan muntah atau diare.

Hari 3- 4 :
Demam tetap tinggi. Timbul ruam / bercak-bercak merah pada kulit dimulai wajah dibelakang telinga
menyebar cepat ke seluruh tubuh. Mata bengkak terdapat cairan kuning kental
Bila ruam timbul waktu demam turun dan dengan penyebaran yang tidak khas, dan penderita berumur < 2tahun, bukan merupakan penyakit campak tetapi Eksantema Subitum / Roseola Infantum ( infeksi virus Herpes tipe 6 dan 7)
Hari 4 – 6 :
Ruam berubah menjadi kehitaman dan mulai mengering Selanjutnya mengelupas secara berangsur-angsur Akhirnya kulit kembali seperti semula tanpa menimbulkan bekas Hilangnya ruam sesuai urutan timbulnya.
(http://www.pantirapih.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150%3Apenyakit-campak&catid=51%3Aumum&Itemid=97&limitstart=1) diakses tanggal 09/04/2013 pukul: 23.54 WIB
2.6 Menjelaskan Pemeriksaan Fisik dan Penunjang Campak
Gejala klinis terjadi setelah masa tunas 10-12 hari, terdiri dari tiga stadium : Stadium prodromal, berlangsung 2-4 hari, ditandai dengan demam yang diikuti dengan
batuk, pilek, farings merah, nyeri menelan, stomatitis, dan konjungtivitis. Tanda patognomonik timbulnya enantema mukosa pipi di depan molar tiga disebut bercak Koplik.
Stadium erupsi, ditandai dengan timbulnya ruam makulo-papular yang bertahan selama 5-6 hari. Timbulnya ruam dimulai dari batas rambut di belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah, leher, dan akhirnya ke ekstrimitas.
Stadium penyembuhan (konvalesens), setelah 3 hari ruam berangsur-angsur menghilang sesuai urutan timbulnya. Ruam kulit menjadi kehitaman dan mengelupas yang akan menghilang setelah 1-2 minggu.
Sangat penting untuk menentukan status gizi penderita, untuk mewaspadai timbulnya komplikasi. Gizi buruk merupakan risiko komplikasi berat.
Pemeriksaan PenunjangLabolatorium
Darah tepi : jumlah leukosit normal atau meningkat apabila ada komplikasi infeksi bakteri
Pemeriksaan antibodi IgM anti campak Pemeriksaan untuk komplikasi :
1. Ensefalopati/ensefalitis : dilakukan pemeriksaan cairan serebrospinalis, kadar elektrolit darah dan analisis gas darah

2. Enteritis : feses lengkap 3. Bronkopneumonia : dilakukan pemeriksaan foto dada dan analisis gas darah.
2.7 Menjelaskan Diagnosis Campak
Diagnosis campak biasanya cukup ditegakkan berdasarkan gejala klinis. Pemeriksaan laboratorium jarang dilakukan. Pada stadium prodromal dapat ditemukan sel raksasa berinti banyak dari apusan mukosa hidung. Serum antibodi dari virus campak dapat dilihat dengan pemeriksaan Hemagglutination-inhibition (HI), complement fixation (CF), neutralization, immune precipitation, hemolysin inhibition, ELISA, serologi IgM-IgG, dan fluorescent antibody (FA). Pemeriksaan HI dilakukan dengan menggunakan dua sampel yaitu serum akut pada masa prodromal dan serum sekunder pada 7 – 10 hari setelah pengambilan sampel serum akut. Hasil dikatakan positif bila terdapat peningkatan titer sebanyak 4x atau lebih (Cherry, 2004).
Serum IgM merupakan tes yang berguna pada saat munculnya ruam. Serum IgM akan menurun dalam waktu sekitar 9 minggu, sedangkan serum IgG akan menetap kadarnya seumur hidup. Pada pemeriksaan darah tepi, jumlah sel darah putih cenderung menurun. Pungsi lumbal dilakukan bila terdapat penyulit encephalitis dan didapatkan peningkatan protein, peningkatan ringan jumlah limfosit sedangkan kadar glukosa normal (Phillips, 1983).
Diagnosis dibuat dari gambaran klinis, selama stadium prodormal, sel raksasa multinuklear dapat ditemukan pada apusan mukosa hidung. Virus dapat diisolasi pada biakan jaringan. Angka leukosit cenderung rendah dengan limfositosis relatif. Pungsi lumbal pada penderita dengan ensefalitis campak biasanya menunjukkan kenaikan protein dan sedikit kenaikan limfosit. Kadar glukosa normal. Bercak koplik dan hiperpigmentasi adalah patognomonis untuk rubeola/campak.
2.8 Menjelaskan Diagnosis Banding Campak
Diagnosis banding morbili diantaranya : Roseola infantum. Pada Roseola infantum, ruam muncul saat demam telah menghilang. Rubella. Ruam berwarna merah muda dan timbul lebih cepat dari campak.Gejala yang
timbul tidak seberat campak. Alergi obat.Didapatkan riwayat penggunaan obat tidak lama sebelum ruam muncul dan
biasanya tidak disertai gejala prodromal. Demam skarlatina.Ruam bersifat papular, difus terutama di abdomen.Tanda
patognomonik berupa lidah berwarna merah stroberi serta tonsilitis eksudativa atau membranosa (Alan R. Tumbelaka, 2002).
Campak yang termodifikasi Penyakit campak yang termodifikasi muncul pada orang yang hanya memiliki
setengah daya tahan terhadap campak. Hal tersebut dapat diakibatkan riwayat penggunaan serum globulin maupun pada anak usia kurang dari 9 bulan karena masih terdapatnya antibodi campak transplasental dari ibu. Ditandai dengan gejala penyakit yang lebih ringan. Stadium prodromal akan menjadi lebih pendek. Batuk, pilek dan demam lebih ringan. Bercak Koplik lebih sedikit dan kurang jelas, namun dapat juga tidak muncul sama sekali. Ruam yang muncul sama dengan infeksi campak klasik, tetapi

tidak bersifat konfluens. Pada beberapa orang, infeksi campak yang termodifikasi ini dapat tidak memberikan gejala apapun (Cherry, 2004).
Campak atipikal Didefinisikan sebagai sindroma klinik yang muncul pada orang yang sebelumnya
telah kebal akibat terpajan pada infeksi campak alamiah. Biasanya muncul pada orang yang telah mendapat vaksin dari virus campak yang dimatikan
Masa inkubasi dari campak atipikal sama seperti pada campak yang tipikal yaitu sekitar 7 hingga 14 hari. Stadium prodromal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak (39,5˚C sampai 40,6˚C) dan biasanya sakit kepala.Bisa juga didapatkan gejala nyeri perut, mialgia, batuk non-produktif, muntah, nyeri dada dan rasa lemah.Bercak Koplik jarang ditemui.Dua atau tiga hari setelah onset penyakit muncullah ruam yang dimulai dari distal ekstremitas dan menyebar ke arah kepala.Ruam sedikit berwarna kekuningan, terlihat jelas pada pergelangan tangan dan kaki serta terdapat juga pada telapak tangan dan kaki.Ruam dapat berbentuk vesikel dan terasa gatal.Pada campak atipikal dapat muncul efusi pleura, sesak nafas, hepatosplenomegali, hiperestesia, rasa lemah maupun paresthesia.Diagnosis dari campak atipikal dapat ditegakkan melalui tes serologis.Bila sampel serum awal diambil sebelum atau pada saat onset ruam, CF dan titer HI biasanya kurang dari 1:5. Pada hari ke-10 infeksi kedua titer akan meningkat mencapai 1:1280 atau lebih. Pada campak yang tipikal, di hari ke-10 infeksi titer jarang melebihi 1:160 (Cherry, 2004).
2.9 Menjelaskan Penatalaksanaan Campak
Pengobatan bersifat suportif, terdiri dari : Pemberian cairan yang cukup Kalori yang sesuai dan jenis makanan yang disesuaikan dengan tingkat kesadaran dan
adanya
Komplikasi
Suplemen nutrisi Antibiotik diberikan apabila terjadi infeksi sekunder Anti konvulsi apabila terjadi kejang Pemberian vitamin A.
Indikasi rawat inap : hiperpireksia (suhu > 39,00 C), dehidrasi, kejang, asupan oral sulit, atau adanya komplikasi.
Campak tanpa komplikasi : Hindari penularan Tirah baring di tempat tidur Vitamin A 100.000 IU, apabila disetai malnutrisi dilanjutkan 1500 IU tiap hari Diet makanan cukup cairan, kalori yang memadai. Jenis makanan disesuaikan dengan
tingkat kesadaran pasien dan ada tidaknya komplikasi
Campak dengan komplikasi :

Ensefalopati/ensefalitis Antibiotika bila diperlukan, antivirus dan lainya sesuai dengan PDT ensefalitis Kortikosteroid, bila diperlukan sesuai dengan PDT ensefalitis Kebutuhan jumlah cairan disesuaikan dengan kebutuhan serta koreksi terhadap gangguan
elektrolit Bronkopneumonia :
Antibiotika sesuai dengan PDT pneumonia Oksigen nasal atau dengan masker Koreksi gangguan keseimbangan asam-basa, gas darah dn elektrolit Enteritis : koreksi dehidrasi sesuai derajat dehidrasi (lihat Bab enteritis dehidrasi). Pada kasus campak dengan komplikasi bronkhopneumonia dan gizi kurang perlu
dipantau terhadapadanya infeksi TB laten. Pantau gejala klinis serta lakukan uji Tuberkulin setelah 1-3 bulan penyembuhan.
Pantau keadaan gizi untuk gizi kurang/buruk.
2.10 Menjelaskan Komplikasi Campak
Campak menjadi berat pada pasien dengan gizi buruk dan anak berumur lebih kecil.Kebanyakan penyulit campak terjadi bila ada infeksi sekunder oleh bakteri. Beberapa penyulit campak adalah :
a) Bronkopneumonia Merupakan salah satu penyulit tersering pada infeksi campak.Dapat disebabkan
oleh invasi langsung virus campak maupun infeksi sekunder oleh bakteri (Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, dan Haemophyllus influenza).Ditandai dengan adanya ronki basah halus, batuk, dan meningkatnya frekuensi nafas. Pada saat suhu menurun, gejala pneumonia karena virus campak akan menghilang kecuali batuk yang masih akan bertahan selama beberapa lama. Bila gejala tidak berkurang, perlu dicurigai adanya infeksi sekunder oleh bakteri yang menginvasi mukosa saluran nafas yang telah dirusak oleh virus campak.Penanganan dengan antibiotik diperlukan agar tidak muncul akibat yang fatal.
b) Encephalitis Komplikasi neurologis tidak jarang terjadi pada infeksi campak.Gejala
encephalitis biasanya timbul pada stadium erupsi dan dalam 8 hari setelah onset penyakit. Biasanya gejala komplikasi neurologis dari infeksi campak akan timbul pada stadium prodromal. Tanda dari encephalitis yang dapat muncul adalah : kejang, letargi, koma, nyeri kepala, kelainan frekuensi nafas, twitching dan disorientasi. Dugaan penyebab timbulnya komplikasi ini antara lain adalah adanya proses autoimun maupun akibat virus campak tersebut.
c) Subacute Slcerosing Panencephalitis (SSPE) Merupakan suatu proses degenerasi susunan syaraf pusat dengan karakteristik
gejala terjadinya deteriorisasi tingkah laku dan intelektual yang diikuti kejang. Merupakan penyulit campak onset lambat yang rata-rata baru muncul 7 tahun setelah infeksi campak pertama kali.Insidensi pada anak laki-laki 3x lebih sering dibandingkan dengan anak perempuan.Terjadi pada 1/25.000 kasus dan menyebabkan kerusakan otak progresif dan fatal.Anak yang belum mendapat vaksinansi memiliki risiko 10x lebih

tinggi untuk terkena SSPE dibandingkan dengan anak yang telah mendapat vaksinasi (IDAI, 2004).
d) Konjungtivitis Konjungtivitis terjadi pada hampir semua kasus campak.Dapat terjadi infeksi
sekunder oleh bakteri yang dapat menimbulkan hipopion, pan oftalmitis dan pada akhirnya dapat menyebabkan kebutaan.
e) Otitis Media Gendang telinga biasanya hiperemi pada fase prodromal dan stadium erupsi.
f) Diare Diare dapat terjadi akibat invasi virus campak ke mukosa saluran cerna sehingga
mengganggu fungsi normalnya maupun sebagai akibat menurunnya daya tahan penderita campak (Soegeng Soegijanto, 2002)
g) Laringotrakheitis Penyulit ini sering muncul dan kadang dapat sangat berat sehingga dibutuhkan
tindakan trakeotomi. h) Jantung
Miokarditis dan perikarditis dapat menjadi penyulit campak.Walaupun jantung seringkali terpengaruh efek dari infeksi campak, jarang terlihat gejala kliniknya.
i) Black measles Merupakan bentuk berat dan sering berakibat fatal dari infeksi campak yang
ditandai dengan ruam kulit konfluen yang bersifat hemoragik.Penderita menunjukkan gejala encephalitis atau encephalopati dan pneumonia.Terjadi perdarahan ekstensif dari mulut, hidung dan usus.Dapat pula terjadi koagulasi intravaskuler diseminata (Cherry, 2004).
2.11 Menjelaskan Pencegahan Campak
Pencegahan terutama dengan melakukan imunisasi campak. Imunisasi Campak di Indonesia termasuk Imunisasi dasar yang wajib diberikan terhadap anak usia 9 bulan dengan ulangan saat anak berusia 6 tahun dan termasuk ke dalam program pengembangan imunisasi (PPI). Imunisasi campak dapat pula diberikan bersama Mumps dan Rubela (MMR) pada usia 12-15 bulan. Anak yang telah mendapat MMR tidak perlu mendapat imunisasi campak ulangan pada usia 6 tahun. Pencegahan dengan cara isolasi penderita kurang bermakna karena transmisi telah terjadi sebelum penyakit disadari dan didiagnosis sebagai campak (IDAI, 2004).
Imunitas Struktur antigenik
Imunoglobulin kelas IgM dan IgG distimulasi oleh infeksi campak. Kemudian IgM menghilang dengan cepat (kurang dari 9 minggu setelah infeksi) sedangkan IgG tinggal tak terbatas dan jumlahnya dapat diukur. IgM menunjukkan baru terkena infeksi atau baru mendapat vaksinasi. IgG menandakan pernah terkena infeksi. IgA sekretori dapat dideteksi dari sekret nasal dan hanya dapat dihasilkan oleh vaksinasi campak hidup yang dilemahkan, sedangkan vaksinasi campak dari virus yang dimatikan tidak akan menghasilkan IgA sekretori (Soegeng Soegijanto, 2002). Imunitas transplasental

Bayi menerima kekebalan transplasental dari ibu yang pernah terkena campak. Antibodi akan terbentuk lengkap saat bayi berusia 4 – 6 bulan dan kadarnya akan menurun dalam jangka waktu yang bervariasi. Level antibodi maternal tidak dapat terdeteksi pada bayi usia 9 bulan, namun antibodi tersebut masih tetap ada. Janin dalam kandungan ibu yang sedang menderita campak tidak akan mendapat kekebalan maternal dan justru akan tertular baik selama kehamilan maupun sesudah kelahiran (Phillips, 1983). Imunisasi
Imunisasi campak terdiri dari Imunisasi aktif dan pasif. Imunisasi aktif dapat berasal dari virus hidup yang dilemahkan maupun virus yang dimatikan. Vaksin dari virus yang dilemahkan akan memberi proteksi dalam jangka waktu yang lama dan protektif meskipun antibodi yang terbentuk hanya 20% dari antibodi yang terbentuk karena infeksi alamiah. Pemberian secara sub kutan dengan dosis 0,5ml. Vaksin tersebut sensitif terhadap cahaya dan panas, juga harus disimpan pada suhu 4˚C, sehingga harus digunakan secepatnya bila telah dikeluarkan dari lemari pendingin.
Vaksin dari virus yang dimatikan tidak dianjurkan dan saat ini tidak digunakan lagi. Respon antibodi yang terbentuk buruk, tidak tahan lama dan tidak dapat merangsang pengeluaran IgA sekretori.
Indikasi kontra pemberian imunisasi campak berlaku bagi mereka yang sedang menderita demam tinggi, sedang mendapat terapi imunosupresi, hamil, memiliki riwayat alergi, sedang memperoleh pengobatan imunoglobulin atau bahan-bahan berasal dari darah (Soegeng Soegijanto, 2001).
Imunisasi pasif digunakan untuk pencegahan dan meringankan morbili. Dosis serum dewasa 0,25 ml/kgBB yang diberikan maksimal 5 hari setelah terinfeksi, tetapi semakin cepat semakin baik. Bila diberikan pada hari ke 9 atau 10 hanya akan sedikit mengurangi gejala dan demam dapat muncul meskipun tidak terlalu berat.