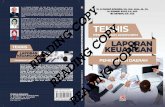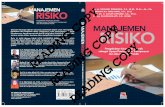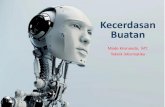Reading Assignmnet AI-2
-
Upload
febrian-wardoyo -
Category
Documents
-
view
248 -
download
0
description
Transcript of Reading Assignmnet AI-2
Di Laut Kita Jaya
Di Laut Kita Jaya?
Jalesveva Jayamahe. Semboyan Angkatan Laut Republik Indonesia ini sungguh menggetarkan: Di Laut Kita Jaya!
Lupakan sejenak olok-olok ataupun cerita-cerita konyol terkait berbagai kasus ketidakmampuan kita menjaga laut Nusantara. Lupakan dulu bahwa 80 persen dari sekitar 7.000 kapal perikanan di laut Nusantara adalah milik asing meski dipasangi bendera Indonesia. Lupakan pula sejenak bahwa hanya 5 persen dari ekspor berbagai komoditas kita yang dilayani kapal domestik, sedangkan 95 persen lainnya oleh kapal-kapal asing.
Sebagai negara kepulauan (archipelagic state), yang dideklarasikan oleh Perdana Menteri Ir Djoeanda pada 13 Desember 1957 dan diterima PBB pada 1982, bukankah sudah sepantasnya bila mimpi sebagai penguasa laut itu bisa diwujudkan? Kalaupun hari ini belum jadi kenyataan, paling tidak impian itu bisa menjadi semacam doa.
Masih dalam suasana peringatan ulang tahun kemerdekaan RI seperti sekarang, ketika nilai-nilai patriotisme muncul dari lorong dan sudut-sudut jalan, mendengar semboyan bahwa Di Laut Kita Jaya seharusnya menggugah kembali semangat bahari pada anak-anak bangsa ini. Ungkapan nenek moyangku orang pelaut, seperti tertuang dalam salah satu bait lagu yang sangat terkenal itu, juga seharusnya tidak sekadar kata-kata kosong tanpa disertai kesadaran untuk mengelola laut Nusantara sebagai sumber hidup dan penghidupan bagi anak bangsa ini.
Namun, yang kerap dilupakan adalah kesadaran bahwa kejayaan tidak datang begitu saja hanya lantaran kita ditakdirkan sebagai bangsa yang memiliki wilayah laut begitu luas. Kejayaan itu mesti dibangun dan direbut. Bukan cuma slogan, apalagi sekadar semboyan yang dimitoskan.
Pertanyaannya, sudahkah bangsa ini mensyukuri karunia Tuhan itu dengan memberi perhatian lebih pada matra kelautan yang dimilikinya? Sudahkah laut ditempatkan sebagai yang utama, sesuatu yang penting, sehingga orientasi kita pun sebagai bangsa lebih diarahkan untuk menatap laut daripada daratan?
Tanpa harus membolak-balik statistik keuangan negara mengenai seberapa besar alokasi dana APBN untuk pembangunan kelautan, atau mengukur komitmen negara lewat aturan perundang- undangan yang diciptakannya sebagai pijakan bagi kebijakan kelautan, dengan gamblang pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menemukan jawabannya sendiri.
Bahwa, setelah 63 tahun Indonesia merdeka, laut masih diabaikan. Perhatian pemerintah masih dan bahkan cenderung akan terus tersedot ke daratan. Sejauh ini laut baru dilihat sebatas potensi tidur.
Ini pula yang menjadi faktor kecilnya perhatian terhadap matra laut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, persoalan besar sebuah negeri dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia (setelah Kanada) bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagaimana memelihara kedaulatan laut dan memanfaatkan potensinya seoptimal mungkin bagi kesejahteraan rakyat, kata Susanto Zuhdi, guru besar sejarah (maritim) dari Universitas Indonesia.
DitinggalkanTiap tanggal 21 Agustus, kalender peringatan hari-hari bersejarah bagi bangsa ini mencatatnya sebagai Hari Maritim. Akan tetapi, seberapa banyak warga-bangsa yang tahu dan peduli bahwa hari itu menandai awal penguasaan laut Nusantara oleh Indonesia yang direbut dari tangan Jepang?
Pada peringatan Hari Maritim 2008, beberapa waktu lalu, hampir tak ada berita di media massacetak maupun elektronik nasional yang menyuarakannya. Perhatian lebih terfokus pada kisruh dunia perpolitikan, kasus aliran dana Bank Indonesia yang kian tak menentu ujungnya, melambungnya harga-harga bahan kebutuhan pokok, hingga gosip-gosip di sekitar kehidupan para selebritas.
Peringatan Hari Maritim pun berlalu tanpa catatan berarti. Laut baru ditoleh dan mendapat tempat dalam pemberitaan ketika ombak mengganas dan kisah tragis tenggelamnya kapal yang menelan banyak korban terjadi. Jangankan peringatan Hari Maritim, kisah heroik para penjelajah pulau-pulau terluar yang dimotori oleh Wanadri pun seperti tenggelam dalam hiruk-pikuk keseharian bangsa bahari yang masih berorientasi ke daratan ini.
Ironis? Memang! Tak berlebihan bila mantan Panglima Armada Barat TNI AL Djoko Sumaryono sampai pada kesimpulan, harus jujur kita akui bahwa budaya maritim yang pernah kita miliki berabad-abad lalu telah lama kita tinggalkan.
Akibatnya bukan saja laut Nusantara kehilangan kendali sepenuhnya oleh sang pemilik, kedaulatan bangsa pun kian terancam. Meski satu-dua kasus penangkapan kapal-kapal ikan asing yang beroperasi di perairan Nusantara sempat mencuat, sesungguhnya jauh lebih banyak yang bebas berkeliaran dalam aksi pencurian ikan di wilayah kedaulatan Indonesia.
Belum lagi berbagai kasus penyelundupan, perompakan, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing yang melintas tanpa izin. Semua itu mengindikasikan ketidakmampuan kita menjaga laut Nusantara. Berbagai potensi kerawanan itu secara tidak langsung ikut meruntuhkan wibawa Indonesia sebagai penguasa laut Nusantara di mata internasional.
Dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, melingkupi pantai sepanjang 81.000 kilometer atau setara dua kali panjang khatulistiwa, bisa dipahami jika potensi kerawanan selalu muncul. Kondisi ini tentunya menuntut perhatian lebih, terutama bila mimpi untuk menjadi penguasa laut Nusantara benar-benar ingin diwujudkan.
Masalahnya, dihadapkan pada kenyataan ini, TNI AL sebagai garda terdepan pengamanan laut Nusantara yang begitu luas hanya memiliki kurang dari 150 kapal perang. Itu pun hanya sepertiganya yang berpatroli secara bergantian, sepertiga lagi dalam posisi siaga, dan sisanya dalam perawatan.
Bahkan, menurut catatan peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jaleswari Pramodhawardani (Jalesveva Jayamahe, Cuma Tinggal Mitos?, 2007), saat ini tinggal 40 persen alat utama sistem pertahanan (alutsista) milik TNI AL yang bisa dikatakan layak pakai. Dari 209 unit KAL (kapal patroli berukuran lebih kecil dibandingkan kapal perang), misalnya, yang dalam kondisi siap operasi tinggal 76 unit. Adapun dari 435 unit kendaraan tempur Marinir, hanya 157 unit dalam kondisi siap.
Keterbatasan itu masih dihadapkan pada kondisi di mana peralatan pertahanan yang dimiliki TNI AL tersebut rata-rata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Sekadar contoh, Jaleswari menunjuk kondisi 79 buah KRI, kapal patroli, dan kapal pendukung yang layak pakai ternyata usia pakainya 20-40 tahun.
Jaleswari bahkan menambahkan, 10 kapal pendukung (usia pakainya) telah lebih dari 40 tahun. Saat ini Marinir (malah) masih mempergunakan kendaraan tempur produksi tahun 1960-an, yang secara teknis telah sangat menurun efek penggetar dan pemukulnya.
Dari paparan singkat tersebut, jelas bahwa kekuatan TNI AL sebagai penjaga laut Nusantara sangat tidak sebanding dengan wilayah laut yang harus mereka awasi. Itu baru satu hal. Sudah bukan rahasia lagi bila kekayaan laut Nusantara lebih banyak dinikmati oleh pihak asing.
Di sektor perikanan, misalnya, sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, dari sekitar 6,7 juta ton ikan hasil tangkapan dari wilayah laut Indonesia per tahun, sebagian besar dinikmati pengusaha-pengusaha asing. Di luar hasil tangkapan yang dicuri nelayan-nelayan asing, 80 persen lebih dari sekitar 7.000 kapal penangkap ikan berizin operasi di perairan Nusantara milik pemodal dari luar yang diberi bendera Indonesia.
Kehadiran nelayan-nelayan asing bukan saja bentuk pelanggaran kedaulatan bangsa, tapi juga kian memarjinalkan posisi nelayan-nelayan domestik. Para nelayan kita terjepit.
Selain harus bersaing dengan nelayan asing yang ditopang permodalan kuat, nelayan-nelayan lokal juga harus menyiasati berbagai kesulitan akibat ketidakberpihakan pemerintah atas nasib mereka, termasuk di dalamnya dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang terus menggila sejak beberapa tahun terakhir. Kearifan lokal yang mereka warisi juga ikut terdesak oleh penggunaan teknologi maju di bidang perikanan.
Bagaimana dengan transportasi laut untuk melayani aktivitas ekspor-impor? Ini jauh lebih mengerikan. Berbagai sumber menyebutkan, 95 persen arus bongkar-muat komoditas ekspor-impor dikuasai kapal-kapal asing. Bahkan, lebih dari 50 persen barang dagangan yang diantarpulaukan pun menggunakan jasa armada pelayaran asing berbendera Merah Putih.
Apa boleh buat! Inilah sebagian dari ironi yang melingkupi sebuah negeri yang telah mengklaim diri sebagai negara kepulauan alias negara bahari. Keinginan untuk menjadi penguasa laut Nusantara yang sesungguhnya, sebuah negara maritim yang berorientasi kelautan, hingga sejauh ini tampaknya masih sebatas harapan.
Memang dibutuhkan keberanian untuk melakukan semacam reorientasi nilai. Paradigma negara konsentris yang bertumpu pada daratan mesti digeserpaling tidak dilakukan bertahapke pengembangan budaya maritim.
Jika tidak, semboyan Jalesveva Jayamahe-nya TNI AL bisa jadi hanya berhenti sebatas slogan sebagaimana kekhawatiran Jaleswari Pramodhawardani. Cuma tinggal mitos! (wad/ken)
ARUNG SEJARAH BAHARI
Menjadi Bangsa yang Ingkar
Jumat, 28 Agustus 2009 | 04:18 WIB
Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945, Muhammad Yamin mengingatkan bahwa calon negara yang tengah mereka persiapkanyang sudah disepakati bernama Indonesiaterutama berupa daerah lautan. Oleh karena itu, kata Yamin, Membicarakan daerah negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian pada pulau dan daratan sesungguhnya berlawanan dengan keadaan sebenarnya.
Sejak awal pendirian republik ini, Yamin sudah menyadari kenyataan bahwa laut Nusantara adalah sumber kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Maka, yang pertama-tama perlu mendapat perhatian seharusnya adalah bagaimana memanfaatkan laut dengan segala potensinya itu untuk kesejahteraan rakyat serta keadilan dan perdamaian.
Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut ibarat mata-telinga sekaligus sumber pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Kesadaran ini pula yang ingin diteguhkan Yamin. Dengan konsep Tanah Air-nya, ia mengawali pemahaman baru tentang ruang kehidupan bagi bangsa yang baru bertumbuh: Indonesia!
Laut diyakini akan jadi tumpuan masa depan umat manusia, lebih-lebih bagi Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa laut. Di dalamnya begitu banyak sumber daya alam yang belum tergarap dan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia.
Sumber daya perikanan melimpah. Begitu banyak jenis yang tersedia di laut, kita bisa langsung memanen tanpa terlebih dahulu harus menanam benihnya. Hanya perlu modal serta teknologi penangkapan dan pengelolaannya.
Belum lagi sumber minyak dan gas. Dari sekitar 60 cekungan yang ada saat ini, 40 cekungan berada di lepas pantai dan 14 cekungan di kawasan pesisir. Jumlah cekungan yang menyimpan kandungan minyak dan gas bumi tersebut boleh jadi baru sebagian kecil dari potensi sebenarnya yang masih tersimpan di dasar laut Nusantara.
Jangan lupa, laut berikut selat-selat yang ada berfungsi bagi pelayaran untuk mengangkut barang dan orang dalam skala besar. Dengan kata lain, selain untuk kesejahteraan, laut juga berperan untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian, kata Susanto Zuhdi, sejarawan maritim dari Universitas Indonesia.
Negara kepulauanSangat boleh jadi, terkandung harapan yang besar semacam itu pula ketika pemerintahmelalui Kabinet Djoeandapada 13 Desember 1957 mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipilagic state).
Lewat deklarasi yang bersifat unilateral tersebut, Indonesia menyatakan, demi keamanan dan kesatuan, laut Indonesia adalah yang berada di sekitar, di antara, dan dalam kepulauan negara RI. Diklaim juga bahwa batas laut teritorial Indonesia diperlebar dari semula hanya 3 mil (4,82 km) menjadi 12 mil (19,3 km) diukur dari garis pantai terluar pada saat air laut surut.
Terlepas dari kenyataan baru 35 tahun kemudian klaim Indonesia ini diterima PBB dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, semua itu memperlihatkan adanya upaya untuk meneguhkan kembali kesadaran sebagai bangsa dan negara maritim. Bukankah sejatinya konsepsi dari sebuah negara kepulauan adalah menempatkan laut sebagai yang utama?
Konsepsi ini sejalan dengan pemahaman tentang daerah inti (heartland) dalam suatu negara kepulauan, sebagaimana diusung Adrian B Lapian. Nakhoda pertama sejarawan maritim Asia Tenggara ini mengingatkan, bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia, apa yang disebut sebagai daerah inti bukanlah suatu pulau atau daratan. Wilayah maritimlah yang memegang peran sentral, ujarnya.
Peran itu bahkan sudah diakui kebenarannya dalam sejarah peradaban bangsa ini sejak tahun-tahun awal abad pertama Masehi. Wilayah Indonesia masa lampau, dengan laut, selat, dan teluk yang menaunginya, menjadi jalur utama perniagaan yang menghubungkan kawasan timur (daratan Tiongkok) dan barat (India, Persia, Eropa).
Peran ini berlangsung selama berabad-abad, dengan tuan dan nakhoda yang datang silih berganti. Sekali masa Portugis mengendalikan perdagangan di kawasan ini. Inggris pun sempat menikmati penguasaan Selat Melaka dan jalur pelayaran di pantai barat Sumatera sebelum diambil alih sepenuhnya oleh pedagang-pedagang Belanda.
Begitulah bila perspektif sejarah digunakan untuk melihat peran sentral laut Nusantara, sekaligus menengok jalinan interaksi sosial-kulturaljuga ekonomi-politikantarpengguna kawasan ini.
Ironisnya, ketika laut jadi incaran banyak orang, ketika dunia makin percaya bahwa masa depan umat manusia berada di laut, kita sebagai bangsa yang lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa laut justru masih saja berpaling ke darat. Laut diposisikan sebagai halaman belakang, sekadar tempat leyeh-leyeh, sembari menikmati senja saat matahari terbenam.
Deklarasi Djoeanda yang menegasikan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam kenyataannya tak diikuti kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan bermatra kelautan. Juga tidak dalam bentuk memperkuat peningkatan kapasitas angkatan laut yang memadai untuk merealisasikan klaim sebagai negara kepulauan tersebut.
Perkembangan politik setelah kemerdekaan, terutama dengan menguatnya peran angkatan darat sebagai kekuatan politik, semakin menegaskan posisi Indonesia yang berorientasi ke darat daripada ke laut, kata Riwanto Tirtosudarmo dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam diskusi di Departemen Pertahanan, akhir Mei lalu.
Sebuah fenomena menarik dari bangsa Indonesia tengah dipertontonkan, yang membuat sejarawan Ong Hok Ham (alm) sampai geleng-geleng kepala. Ia pun berucap, Apakah orang Indonesia hanya (bisa) hidup terpencil dikelilingi gunung berapi dan hidup dari usaha pertanian untuk kemudian dikolonisasi oleh penguasa yang menguasai lautan Indonesia?(KEN)
NEGERI BAHARI
Bukan Tanah Kepungan
Jumat, 28 Agustus 2009 | 04:39 WIB
Oleh Muhammad YaminSalah satu keberhasilan pemerintahan kolonial meninggalkan jejak kekuasaan di bekas negeri jajahannya, Indonesia, adalah sukses mereka membangun ingatan kolektif baru bahwa anak-anak negeri ini bukanlah bangsa pelaut. Dengan satu dan lain cara, kita sebagai bangsa diposisikan sebagai manusia daratan, di mana aktivitas pertanian adalah yang utama. Hingga kini!
Perlahan-lahan kesadaran baru itu pun terus tertanam. Tradisi besar kelautan yang sudah lekat pada nenek moyang bangsa ini berabad-abad lampau, jauh sebelum bangsa-bangsa kolonialis sampai ke Nusantara, dalam kenyataannya seperti hilang tak berbekas.
Kini, yang tertinggal dan dibangga-banggakan justru sebagai bangsa agraris sekalipun faktanya sebagian besar kebutuhan produk pertanian tanaman pangan masih harus didatangkan dari luar. Bahkan beras sebagai makanan pokok sebagian besar anak- anak bangsa ini pun harus diimpor. Sementara pada saat bersamaan, hasil kekayaan laut Indonesia serta jalur perniagaan di laut Nusantara lebih banyak dimanfaatkan oleh asing.
Ironis? Memang! Akan tetapi, inilah risiko dari pilihan sebuah kebijakan yangmeminjam ungkapan Muhammad Yamin saat menyampaikan pandangan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945 berlawanan dengan keadaan sebenarnya. Indonesia yang mestinya berbasis maritim, kelautan, dalam praktiknya justru kian dalam terperosok mengikuti skenario kolonialis: makin terkonstruksi menjadi negara yang lebih berorientasi ke darat.
Di tengah arus besar tarikan ke darat tersebut, menarik apa yang dilakukan Direktorat Geografi Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Melalui kegiatan yang mereka namakan Arung Sejarah Bahari, melibatkan mahasiswa terpilih dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, kita sebagai bangsa seolah diingatkan kembali pentingnya memerhatikan matra laut.
Laut bukan saja dilihat sebagai faktor integratif bangsa, di mana pelabuhan-pelabuhan sebagai pusat perniagaan di masa silam menjadi semacam simpul-simpul perekat keindonesiaan, tapi yang tak kalah penting bahwa laut adalah simbol kedaulatan bangsa sekaligus harus didayagunakan sebagai sumber penghidupan bagi anak-anak negeri ini.
Semangat dan jiwa bahari mesti ditumbuhkan di kalangan generasi muda, kata Endjat Djaenuderadjat, Direktur Geografi Sejarah, terkait kegiatan Arung Sejarah Bahari IV/2009, 20-26 Juli lalu di Provinsi Kepulauan Riau.
Lintasan sejarahJika sebelum kedatangan para kolonialis jalur perniagaan di kawasan ini dikuasai oleh kapal-kapal Nusantara, tapi sejak paruh pertama abad ke-17 peran itu mulai diambil alih oleh Belanda dan Portugis. Bahkan, menjelang abad ke-19, sebagaimana hasil studi Anthony Reid (Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, 2004), peran kesejarahan yang gagal dipertahankan oleh raja-raja, para pelaut sekaligus saudagar Nusantaradia menyebutnya orang kaya Asia Tenggara yang tinggal di luar lingkungan istanaikut berperan melahirkan kemiskinan di kawasan ini.
Apa yang terjadi pada abad ke-17, orang-orang Asia Tenggara (baca: Nusantara) telah disingkirkan dari titik-titik puncak perekonomian, di mana mereka mengendalikan perdagangan, mengatur sumber daya kapal-kapal barang, dan memimpin pelabuhan- pelabuhan niaga di pesisir yang sibuk, tulis Anthony Reid, pengkaji sejarah (maritim) Indonesia dari Australian National University.
Adrian B Lapian, nakhoda pertama sejarawan maritim Asia Tenggara, menyimpulkan bahwa pada abad ke-19 tradisi maritim Nusantara sudah berada dalam masa magrib alias memasuki masa senja. Simpul-simpul perniagaan yang semula merupakan pusat aktivitas perekonomian tentunya juga berimplikasi pada tatanan sosial-politik semasa sudah menjadi wilayah pinggiran yang tak lagi memiliki arti penting.
Pasang surut sebuah kawasan dalam negara kepulauan seperti Indonesia, kata Lapian, memang sangat bergantung pada berbagai dinamika hubungan antara pusat-pusat perdagangan yang membentuk jaringan pelayaran. Begitu pun dinamika perdagangan dan perkembangan kota-kota pelabuhan, diakui atau tidak, sangat ditentukan oleh perubahan peta geopolitik negara-negara yang memiliki armada laut yang besar dan kuat.
Dalam konteks inilah peran negara-negara kolonialis ikut meredupkan jiwa dan semangat bahari bangsa Indonesia. Setelah berhasil menguasai sebagian besar kota pelabuhan utama di pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, serta menghalau pelaut dan pedagang anak- anak negeri ini dari panggung perniagaan di laut Nusantara, praktis hanya kapal-kapal merekalah yang lalu lalangdalam arti berniaga skala besardi kawasan ini.
Sejak itu pula sejarah mencatat, tradisi besar kelautan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia runtuh. Meski hingga akhir abad ke-17 pembuatan kapal-kapal di Banten masih berjalan hingga wilayah ini ditaklukkan Belanda pada 1684, di belahan lain Pulau Jawa tidak lagi tampak aktivitas yang berarti dari wujud tradisi besar tersebut.
Bahkan, sebagaimana dikutip Anthony Reid, Daghregister Batavia melaporkan pada 1677 bahwa orang-orang Mataram bagian timur Jawa saat ini, di samping tidak (lagi) tahu-menahu soal laut, juga tidak memiliki lagi kapal besar sendiri, bahkan untuk keperluan yang dianggap penting.
Kini pun laut Nusantara sebagai kawasan perniagaan masih dikuasai asing. Hampir 95 persen arus bongkar muat berbagai komoditas ekspor impor dikuasai kapal-kapal niaga asing. Bahkan lebih dari 50 persen barang yang diantarpulaukan pun menggunakan jasa pelayaran asing yang dipasangi Merah Putih. Sementara lebih 80 persen dari sekitar 7.000 kapal penangkap ikan berizin operasi di perairan Indonesia berstatus milik pemodal asing.
Jika tradisi besar kelautan sudah hilang, sebagai tradisi kecil punyang masih melekat pada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisirkondisinya sangat menyedihkan. Datanglah ke kampung-kampung nelayan atau pelabuhan rakyat yang tersebar di muara sungai, pesisir pantai, dan pulau-pulau kecil. Kemiskinan dan keterbelakangan menjadi pemandangan umum.
Penyebabnya tak lain karena kurangnya perhatian negara terhadap upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Matra laut dikesampingkan, dan laut Nusantara pun jadi jarahan nelayan-nelayan asing, baik yang beroperasi secara legal maupun ilegal.
Bagaimana nak sejahtera bila untuk dapat modal usaha dari pemerintah saja bukan main susahnya. Masih untung ada tauke di sini yang kasih pinjaman modal beli peralatan menangkap ikan, sewa kapal berikut bahan bakarnya, serta untuk kebutuhan hidup selama melaut. Tapi hasilnya Abang tahu sendirilah. Hanya cukup untuk menutup utang sebelum akhirnya ngutang lagi, kata Atan, seorang nelayan dari Pulau Bintan.
Kembalilah ke akarMeski lewat Deklarasi Djoeanda (1957) kita sebagai bangsa sudah sepakat menyatakan diri sebagai negara kepulauan, di mana dalam konsep negara kepulauan lautlah yang utama, pada kenyataannya laut masih diposisikan sebagai halaman belakang. Kebanggaan sebagai bangsa bahari, yang terkadang muncul dalam bentuk semacam letupan- letupan kecil, hanya sebatas kata-kata tanpa disertai keberpihakan yang jelas oleh pemegang kekuasaan.
Usaha menggelorakan semangat kelautan itu bukan tidak ada. Hingga tahun 1970-an, misalnya, anak-anak di sekolah masih kerap disuguhi kisah-kisah kepahlawanan pelaut-pelaut Nusantara. Cerita rakyat dan mitos- mitos yang berkaitan dengan kehidupan di laut yang penuh misteri, termasuk kisah si Malin Kundang yang pergi berlayar untuk lepas dari kemiskinan; terlepas dari sikap durhakanya di kemudian hari, masih dikisahkan di saat-saat senggang.
Lewat lagu anak-anak yang cukup populer ketika itu, Nenek Moyangku Orang Pelaut, anak- anak bagai diajak menjelajah selasar-selasar laut dan selat dengan penuh keberanian. Juga lagu Rayuan Pulau Kelapa yang tak kalah populeryang sesungguhnya lebih menegaskan status bangsa ini sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautjuga kerap terdengar dan dinyanyikan dengan penuh semangat.
Namun, seiring dengan perkembangan politik yang ditandai kian kuatnya orientasi pembangunan ke daratan, lagu-lagu penyemangat itu berangsur hilang dari peredaran. Anak-anak negeri ini mulai terbiasa pada lagu-lagu yang dibawakan penyanyi anak- anak macam Chicha Koeswoyo, Yoan Tanamal, dan Adi Bing Slametsekadar menyebut beberapa namayang tak banyak bersinggungan dengan urusan kebangsaan. Apalagi setelahnya, semisal lagu Diobok-obok-nya Joshua yang tak jelas juntrungnya itu.
Sejarah sebagai peristiwa memang tak bisa diulang, tetapi roh dan semangat yang ada di belakangnya selalu bisa didaur ulang atau dipupuk untuk disemai kembali. Tentu saja semua itu amat bergantung pada niatan kita sebagai bangsa untuk menempatkan posisinya di masa sekarang.
Jika kita masih setia pada ikrar sebagai negara kepulauan, archipelagic stateyang dalam pengertian dasarnya adalah laut utama dan bukan pulau yang berada di lautsudah sewajarnya bila kita kembali ke akar sejarah sebagai bangsa bahari. Bukan saja fakta memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, berbagai kajian pun menunjukkan bahwa masa depan umat manusia ada di laut.
Muhammad Yamin-lah yang sedari awal mengingatkan bahwa tanah air Indonesia terutama adalah lautan. Pada masa perang, daerah ini hanya meliputi apa yang ia sebut sebagai tanah kepungan (enclaves). Akan tetapi, setelah masa damai, status sebagai tanah kepungan terhadap daerah yang kemudian menjadi wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia itu harus dihilangkan.
Karena, kata Yamin, beberapa paham pun telah mengemukakan bahwa tumpah darah Indonesia yang akan menjadi daerah Republik Indonesia adalah bulat ke luar dan bulat juga ke dalam. Jadi, wilayah Indonesia tanpa enclaves, katanya.
Masalahnya, akankah bangsa ini kembali sebagai bangsa bahari dengan menempatkan laut sebagai yang utama? Ataukah tetap dengan model kekuasaan konsentris yang menempatkan darat sebagai pusat dari segalanya sekaligus meneruskan kebanggaan semu sebagai negara agraris yang terus mengimpor bahan pangan? (KEN)
PELABUHAN LAMA
Merajut Simpul-simpul Keindonesiaan
Jumat, 28 Agustus 2009 | 04:35 WIB
Oleh SUSANTO ZUHDITahun ini sudah keempat kali Arung Sejarah Bahari dilaksanakan oleh Direktorat Geografi Sejarah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Kegiatan yang diadakan pada 21-26 Juli lalu di laut Kepulauan Riau, diikuti sekitar 70 mahasiswa berbagai jurusan/program studi dari universitas di seluruh Indonesia.
Tema utama Arung Sejarah Bahari (Ajari) adalah dari pelabuhan ke pelabuhan merajut simpul-simpul keindonesiaan. Bertujuan untuk menumbuhkembangkan semangat dan memperkuat orientasi generasi muda, khususnya mahasiswa, pada matra laut.
Pentingnya berfokus pada pelabuhan dalam kegiatan Ajari, pertama, karena posisinya merupakan simpul multietnik dengan dinamika kehidupannya yang kompleks. Kedua, posisinya yang strategis untuk memahami konsep Tanah-Air.
Orientasi ini penting bagi pembentukan pola pikir untuk membangun keindonesiaan. Suatu ruang kehidupan yang diciptakan dari keragaman masyarakat etnik dan keunikan bahari sebagai faktor integratif, yang merupakan tempat berbagi dan mewujudkan kesejahteraan bersama.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bahariistilah lain dari lautmemiliki tiga arti: dahulu kala, elok sekali, dan tentang laut. Kalau ketiganya dirangkai menjadi satu, akan didapatkan ungkapan suatu kehidupan di laut pada masa lampau yang elok sekali.
Ungkapan elok sekali sering ditafsir sebagai masa kejayaan. Soalnya adalah mengapa hanya pada masa lampau? Lalu bagaimana dengan masa kini dan masa depan? Jadi, tampaknya diperlukan program untuk memompakan semangat dan orientasi kebaharian melalui perspektif sejarah kepada generasi muda khususnya para mahasiswasebagai kelompok strategis yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsanya ke depan.
Membaca sejarahDengan dasar pemikiran itulah, pada tahun 2006 untuk pertama kali program Ajari digulirkan. Diikuti sekitar 70 mahasiswa, dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani, para peserta mengarungi Laut Jawa, dari Tanjung Priok, Jakarta, ke Tanjung Perak, Surabaya.
Laut Jawa memiliki arti penting dan strategis sebagai faktor yang mengintegrasikan pulau- pulau di Indonesia, termasuk dalam pengertian integrasi ekonomi nasional. Demikian konstatasi Singgih Trisulistyono dalam paparannya di atas kapal.
Dengan mendasarkan pada pendapat AB Lapian tentang laut inti, sejarawan maritim dari Universitas Diponegoro itu melihat bahwa Laut Jawa mirip dengan peran Laut Tengah (The Mediterranean Sea). Sebagaimana dikemukakan Fernand Braudel, Laut Tengah berperan sebagai wahana bagi proses integrasi daratan Eropa, Asia, dan Afrika ke dalam sebuah peradaban, khususnya dalam masa Philip II, pada abad ke-16 dan ke-17.
Dengan perspektif ini, Jawa hendak diposisikan sebagai nama laut, yang berperan strategis, bukan sebagaimana biasanya dilekatkan dan dipahami hanya sebagai nama pulau atau daratan. Tampaknya, selama ini kita sudah telanjur membenarkan adanya dikotomi Jawa dan luar Jawa. Pemerintah kolonial Belanda bahkan mempertegas adanya Java dan uit-Java atau buitengewesten (daerah-daerah di luar Jawa). Sudah tentu pola pikir ini didasarkan pada cara pandang daratan.
Selama di kapal, para peserta mendiskusikan makalah yang mereka buat sebagai syarat dan dilombakan. Selain itu, mereka juga mendapat ceramah dan berdiskusi dengan pakar sejarah maritim. Turun dari kapal, peserta mengunjungi kota-kota pelabuhan: Surabaya, Gresik, Tuban, dan Lasem, lalu kembali lagi ke Surabaya.
Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, kapal singgah di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Di sini, peserta mengunjungi berbagai situs yang berkaitan dengan kemaritiman dan berdiskusi dengan mahasiswa dan dosen dari sejumlah perguruan setempat.
Ajari II diadakan tahun 2007, bertema Mengarungi Laut, Menyusuri Sungai, Menguak Peradaban. Kawasan Kalimantan Barat yang dijadikan sasaran Ajari II/2007 dianggap tepat mewakili konsep perpaduan daratan dan lautan, atau antara daerah belakang (hinterland) dan daerah depan (foreland).
Dalam kaitan ini, kegiatan Ajari ingin mengeksplorasi suatu peradaban yang didukung oleh sistem persungaian, yakni Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dengan mengunjungi situs Kesultanan Pontianak, peserta diajak membayangkan dinamika peradaban masa lampau yang difasilitasi oleh sistem persungaian, yang mampu menghubungkannya dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan di Asia.
Diikuti hampir seratus mahasiswa, Ajari III yang dilaksanakan bulan April 2008 berlangsung di Maluku Utara. Provinsi yang terbentuk tahun 2003 ini memiliki luas laut lima kali dari daratannya. Tema Ajari III/2008 adalah Membangun Kembali Peradaban Bahari dengan Menjelajahi Pusat Perdagangan Rempah- rempah Nusantara.
Ketika Ajari III dilaksanakan, Provinsi Maluku Utara sedang mengalami kekisruhan politik akibat kontroversi seputar pemilihan gubernur. Dengan perspektif historis, Ajari relevan untuk mengingatkan konsep Moluku Kie Raha atau empat gunung di Maluku yang berdiri saling menopang demi keharmonisan Maluku, yang semestinya terpelihara hingga kini.
Keempat gunung itu adalah kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Dari wilayah inilah Dunia Maluku secara keseluruhan kemudian dikenal karena rempah-rempahnya.
Bagaimana mengangkat kembali peradaban masa lampau di kawasan ini menjadi topik utama diskusi? Ketika rempah-rempah tidak lagi menjadi komoditas primadona, tampaknya perikanan menjadi alternatif menjanjikan. Sayangnya, sektor ini belum digarap secara optimal, masih dikerjakan secara tradisional.
Ajari IV tahun 2009 bertema Menguak Jalur Pelayaran di Peradaban Melayu: Tajung Pinang-Lingga-Batam. Kawasan laut ini sangat penting dan strategis bagi pelayaran sejak milenia pertama. Prof Shaharil Talib, sejarawan terkemuka Malaysia, bahkan pernah mengatakan bahwa globalisasi pertama dunia telah berlangsung di kawasan ini.
Di kawasan ini pula pernah berjaya suatu kesultanan yang wilayahnya terdiri atas Riau-Johor-Lingga-Pahang, dengan pusat pemerintahannya secara bergantian berada di Johor, Bintan, dan Lingga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana tingkat kesejahteraan orang Melayu di Kepulauan Riau dapat sebanding dengan orang di seberang paritmeminjam istilah budayawan Riau, Al azhar, untuk negeri Malaysia.
Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah ketika melepas peserta Ajari mengarungi perairan kawasan ini memaparkan masalah yang dihadapi provinsi dengan wilayah daratan hanya 6 persen, dengan lebih dari seribu pulau itu. Laut adalah jalan raya orang kepulauan, sama pentingnya dengan jalan raya di darat.
Berbeda dengan transportasi di darat, penyediaan alat transportasi laut jauh lebih mahal. Jadi, anggaran pembangunan untuk tujuh provinsi yang berkarakter laut di Tanah Air seharusnya berbeda daripada untuk provinsi daratan. Padahal, dalam penghitungan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat, kriterianya adalah luas daratan.
Memaknai masa laluMelihat kondisi geografis Indonesia seperti ini, berapa kali lagi program Ajari harus dilaksanakan. Belum lagi kalau prinsip pengertian bahari hendak dipegang, berapa luasnya laut yang perlu diarungi.
Tidak itu saja, karena kebaharian tidak hanya mengenai laut, tetapi juga perairan lainnya, maka termasuk juga sungai dan danau. Lalu, berapa banyak sungai dan danau yang menunjukkan peradaban sejarah harus diarungi?
Selat dan teluk harus dipandang juga sebagai sistem laut. Selat berperan sebagai penghubung pulau atau daratan. Begitu pun teluk, yang memungkinkan berlangsungnya dinamika masyarakat dan peradaban di pesisirnya. Bagaimana pula dengan laut dan pulau-pulaunya yang berada di wilayah perbatasan negara?
Apa yang diperoleh dari kegiatan Ajari yang hanya enam hari? Tujuan paling substansial adalah menumbuhkembangkan semangat kebaharian, yang dapat menggerakkan kemampuan mahasiswa merumuskan persoalan dan jawaban atas permasalahan bangsa dalam konteks kelautan dari berbagai disiplin ilmu. Sejak dini mereka perlu diajak memikirkan bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan dan integrasi bangsa dengan pendekatan kelautan.
Ajari tentu saja harus mengunjungi pelabuhan, sesuai dengan tema utamanya: menjadikan pelabuhan sebagai simpul perekat keindonesiaan. Sejauh kapal berlayar, ada waktunya berlabuh juga. Sebab, berapa pun lamanya di lautan, sesuai dengan pesan nenek moyang, kita diingatkan jangan lupa daratan.
Ungkapan itu kiranya bukan hanya dalam arti sesungguhnya. Ini metafora yang menunjukkan kearifan bangsa bahari. Ketika orang sudah mabuk dengan kekuasaan dan keserakahan, pesan nenek moyang itu tetap berlaku: jangan lupa daratan.
SEMANGAT BAHARI
Saatnya Berpaling (Lagi) ke Laut
Jumat, 28 Agustus 2009 | 04:37 WIB
Oleh ESTER LINCE NAPITUPULUKejayaan nenek moyang bangsa ini sebagai pelaut ulung bukanlah cerita asing di kalangan anak-anak muda. Akan tetapi, sepertinya bangsa ini menganggap kejayaan masa lalu itu berhenti hanya sebagai sejarah. Generasi muda sekarang pun berpaling makin jauh sebagai cucu dari para pelaut mumpuni yang pernah disegani bangsa-bangsa di dunia.
Kesadaran wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya berupa laut, begitu jauh dari kalangan anak-anak muda. Sebut saja mahasiswa. Kenyataan itu tidaklah mengherankan karena bangsa ini memang tidak jua berpaling pada kekuatan sebagai negara maritim.
Saat bicara soal lautan Indonesia yang luas, yang ada di benak anak-anak muda baru sebatas kekaguman betapa sebenarnya Indonesia ini luar biasa. Angan-angan pun melambung, membayangkan betapa Indonesia bisa jadi negara makmur jika mampu memanfaatkan sumber daya alam di laut yang belum banyak dilirik dalam pembangunan bangsa.
Pengenalan dan pemahaman geografis Indonesia, yang mestinya juga tidak mengabaikan laut, belum tumbuh dengan baik. Dalam realitas kehidupan masyarakat, justru terlihat nyata betapa timpangnya pembangunan dan kemajuan antara masyarakat yang hidup di sekitar laut dan darat.
Akibatnya, pengembangan laut bagi kesejahteraan bangsa pun semakin jauh. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berpihak pada pengembangan potensi bahari masih minim. Pengembangan ilmu kelautan dalam berbagai aspek juga terbatas, antara lain karena bidang ini tak diminati banyak generasi muda sebagai pilihan studi.
Perasaan miris juga muncul saat melihat kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan yang lambat berkembang. Tidak sedikit yang masih terisolasi dengan pulau-pulau lain.
Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah saat menerima rombongan Arung Sejarah Bahari IV/2009, akhir Juli lalu, mengakui memang tidak mudah mengelola sebuah provinsi maritim. Butuh biaya besar. Namun, hingga saat ini anggaran yang dikucurkan pusat untuk wilayah- wilayah maritim masih minim.
Sebagai contoh, untuk menyediakan alat transportasi di darat, seperti bus ber-AC dengan kapasitas 60 tempat duduk, hanya butuh biaya dalam hitungan ratusan juta rupiah. Namun, untuk kapal dengan kapasitas sama bisa mencapai Rp 4,5 miliar. Belum lagi harus disediakan pelabuhan, lalu menjaga supaya laut tidak dangkal.
Pembangunan infrastrukturnya mahal. Meskipun punya banyak sumber daya alam, susah juga memanfaatkannya karena kendala transportasi dan fasilitas lainnya. Potensi wilayah-wilayah maritim diakui besar, tapi baru sebatas pengakuan, belum sampai pada dukungan nyata untuk bisa mengoptimalkan laut dan potensinya.
Kami terus berjuang supaya pemerintah pusat memberikan perhatian yang besar untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta hasil laut. Jika tidak ada keberpihakan, banyak warga pulau yang terbelakang terus, kata Ismeth.
Kondisi itu jauh berbeda dengan Singapura, sebagai negara tetangga yang cukup dekat dengan Indonesia. Peranan pulau-pulau yang tadinya penting dalam jalur perdagangan, termasuk di Kepulauan Riau, tenggelam dengan mencuatnya Singapura. Negeri Singa itu justru berkembang jadi negara maju dengan pelabuhan yang penting bagi dunia.
Wilayah kepulauan yang didominasi perairan membutuhkan pengembangan jaringan pelayaran sebagai salah satu penentu dinamika ekonomi di sana. Dalam dinamika yang tumbuh itu, memungkinkan interaksi dari banyak pihak, yang memunculkan budaya baru bagi berkembangnya peradaban umat manusia.
Peranan Indonesia dalam perniagaan dan peradaban sudah terbukti pada masa lalu. Bukan hanya maju dalam perniagaan semata. Dalam penyebaran budaya juga diakui. Sebagai misal, bahasa Melayu yang berkembang sebagai bahasa penghubung antara pelaut dan pedagang yang kemudian membentuk jaringan kebahasaan di bumi Nusantara hingga ke Malaysia, Thailand, dan Filipina.
Semangat kebaharianKecenderungan yang terus berlanjut di mana orientasi pembangunan lebih terfokus ke darat dan mengabaikan watak dasar keindonesiaan sebagai negara kepulauan yang berbasis maritim mestinya segera dihentikan. Di tangan generasi muda sebagai penerus bangsa seharusnya perubahan itu disiapkan untuk mewujudkan kekuatan Indonesia kembali sebagai negara maritim yang unggul dalam perdagangan dunia.
Tidak banyak yang saya ketahui soal sektor bahari Indonesia. Sebagai anak muda yang besar di kota, saya senang menikmati pantai yang di sekitarnya tumbuh resor-resor bagus. Tetapi, kini saya baru tahu bahwa pemerintah tidak seharusnya menganaktirikan masyarakat yang tinggal di sekitar laut, kata Asrining Tyas, mahasiswa Universitas Indonesia.
Kesadaran yang diungkapkan Tyas muncul saat dirinya bersama sekitar 100 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mengikuti kegiatan Arung Sejarah Bahari IV/2009 di Kepulauan Riau. Perjalanan menyusuri jejak kejayaan bangsa dalam kebaharian seketika menyentak kesadaran mereka.
Mahasiswa lain, Diana AP Korawa, sebenarnya tidak asing dengan laut. Di masa kecilnya di Kampung Samau, Biak Numfor, Papua, mahasiswa tingkat akhir Universitas Cenderawasih itu menikmati mandi di pantai. Dia juga terbiasa melihat masyarakat yang mengandalkan hidup dari hasil laut dengan mengekspor ikan ke negara tetangga.
Namun, seiring waktu karena keterbatasan fasilitas dan pengembangan laut di wilayahnya, nasib nelayan pun lama-lama terpuruk. Kondisi itu membuat Diana sebagai anak muda tidak tertarik untuk bisa mengeksplorasi potensi laut.
Akan tetapi, ketidakpedulian itu seketika memudar saat pengenalan kebaharian diterimanya dalam kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Geografi Sejarah Ditjen Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Saya baru tersadar, seharusnya kita mencintai laut. Saya baru merasa terbuka pikiran untuk bisa menoleh kembali ke laut. Setidaknya, untuk penyusunan skripsi, saya mau membuat penelitian yang berhubungan dengan laut, ujar Diana yang belajar di bidang pendidikan ilmu pengetahuan sosial.
Tengku Munawar, mahasiswa Institut Teknologi Bandung, menekankan bangsa ini harus berpaling kembali ke laut. Di zaman dulu lebih banyak perahu daripada jalan di darat. Tetapi sekarang sangat timpang, kata mahasiswa asal Pulau Lingga, Kepulauan Riau, itu.
Munawar juga melihat anak-anak pulau sendiri lebih tertarik untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau lainnya daripada berkecimpung di laut. Pasalnya, kehidupan nelayan yang ada di pulau jauh dari sejahtera karena terbatasnya peralatan dan keterampilan memberdayakan hidup dari hasil laut.
Kesempatan untuk bisa mengarungi sejarah kejayaan kerajaan maritim Indonesia membuat mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu itu mau berefleksi apa yang sesungguhnya terlupakan dalam pembangunan bangsa ini. Dalam keberbedaan disiplin ilmu, mahasiswa diajak untuk bisa bekerja sama mengembangkan potensi laut yang masih terlupakan.
Endjat Djaenuderadjat, Direktur Sejarah Geografi, mengatakan bahwa semangat kebaharian mesti ditumbuhkan di kalangan generasi muda. Tujuannya supaya mereka paham tentang peradaban maritim dan potensi kelautan dalam peningkatan sumber daya ekonomi.
Selama ini pembangunan terhadap peradaban bahari seolah-olah ditinggalkan sehingga keberadaan pulau-pulau terluar dan pulau kecil sering diabaikan. Begitu juga dengan penggalian sumber daya bahari yang berlimpah belum tergarap dengan baik.
Laut hendaknya tidak hanya dilihat sebagai kumpulan air yang sangat luas. Dalam kebaharian juga menyangkut aspek-aspek kehidupan yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kegiatan Arung Sejarah Bahari ini sebagai kegiatan mengarungi sejarah kehidupan manusia dalam lingkup dan tingkat peradaban yang telah dicapainya.
Dalam kegiatan itu, mahasiswa mengunjungi obyek-obyek yang berkaitan dengan peradaban bahari. Mereka juga mengarungi laut untuk menuju pulau-pulau penting dalam catatan sejarah kejayaan bahari Indonesia. Lalu, mereka juga berdiskusi bagaimana seharusnya kita memandang laut dan apa yang mestinya dilakukan pada laut Indonesia nan luas itu. Tak ada kata terlambat untuk mengajak generasi muda berpaling (lagi) ke laut. Entah kesadaran itu hanya emosi sesaat atau sebagai pencerahan, mahasiswa yang ikut dalam kegiatan Arung Sejarah Bahari bertekad untuk melirik dan mencintai laut.
JALUR PERNIAGAAN
Selat Malaka, Hatinya Lautan
Jumat, 28 Agustus 2009 | 04:37 WIB
Tidak seperti Malaysia, Singapura tidak pernah mengklaim ekspresi budaya negara tetangganya. Namun, terkait keberadaan Selat Malaka sebagai jalur lintas perniagaan, Singapura bukanlah teman seiring dalam upaya menjaga kedaulatan kawasan ini bersama dua negara tetangganya, Malaysia dan Indonesia.
Jika Malaysia dan Indonesia sejak awal menolak tegas setiap gagasan dan upaya yang dapat menjurus ke arah internasionalisasi Selat Malaka, Singapura cenderung sebaliknya. Jika Malaysia dan Indonesia lebih mementingkan fungsi pemeliharaan lingkungan laut untuk menjaga sumber-sumber perikanan, selain sebagai wadah komunikasi/pelayaran, Singapura melihat Selat Malaka terutama sebagai wadah komunikasi/pelayaran demi dan untuk kelangsungan hidup pelabuhan mereka yang sangat bergantung pada lalu lintas kapal-kapal yang melalui kawasan ini.
Kondisi inilah yang oleh pengamat kelautan dan hukum laut, Hasjim Djalal, dinilai sebagai ganjalan penyelesaian garis batas wilayah lautbahkan tak jarang memicu munculnya persoalanantarnegara tetangga ini.
Dengan ikut meramaikan isu bajak laut dan terorisme di Selat Malaka, Singapura bahkan terkesan ikut bermain mata dengan negara-negara pengguna selat inikhususnya Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Dengan mengangkat isu bajak laut dan terorisme, mereka beralasan seharusnya diperbolehkan melakukan berbagai hal, mulai dari mempersenjatai kapal-kapal dagangnya hingga menempatkan angkatan laut masing-masing di perairan Selat Malaka.
Demi menjaga eksistensi pelabuhan dagangnya, Singapura memang lebih menyukai diterapkannya konsep laut bebas atau selat internasional untuk kawasan ini. Konsep ini jelas bertentangan dengan prinsip laut wilayah negara pantai yang diusung Indonesia dan Malaysia yang memiliki wilayah pantai jauh lebih panjang dan dengan kehidupan masyarakat pantainya yang sebagian besar adalah nelayan.
Dalam konsepsi laut bebas, klausul yang diutamakan adalah kepentingan pelayaran internasional. Adapun kepentingan negara pantai dinomorduakan.
Dalam konsepsi laut bebas, campur tangan pihak luar (negara pengguna) untuk terlibat dalam pengaturan dan pengurusan perairan Selat Malaka juga dimungkinkan. Di sinilah titik masalahnya.
Sayangnya, kata Hasjim Djalal ketika berbicara dalam satu seminar yang diselenggarakan Kantor Menteri Sekretariat Negara, permasalahan Selat Malaka kini telah direduksi menjadi persoalan teknis keselamatan pelayaran semata. Isu inilah yang kemudian terus digulirkan sehingga suara-suara untuk menginternasionalisasi kawasan ini pun terus bergema.
Padahal, masalah yang sudah muncul di dalamnya sudah sangat rumit dan kompleks, ujarnya.
Jalur strategisMeski tidak memberikan perspektif baru, diskusi antarmahasiswa peserta Arung Sejarah Bahari IV/2009 di Kepulauan Riau, akhir Juli lalu, juga menyoroti dinamika perkembangan Selat Malaka sebagai jalur strategis perniagaan internasional.
Beragam topik mereka angkat. Mulai dari paparan tentang peranan Kerajaan Melayu-Riau dalam alur perdagangan laut di kawasan ini, kajian tentang sistem kelautan, hubungannya dengan bandar-bandar lain Nusantara, hingga studi kasus terkait kebijakan China sebagai negara pengguna Selat Malaka dalam pengamanan suplai energi mereka.
Jika perspektif sejarah digunakan untuk menguak peran Selat Malaka dan perairan Kepulauan Riau dalam aspek pelayaran dan perdagangan, maka berawal dari milenium pertama kita sudah dapat melihat perannya dalam menghubungkan China dan India, kata Susanto Zuhdi, sejarawan maritim dari Universitas Indonesia, yang bertindak sebagai narasumber.
Selain diramaikan lalu lintas kapal-kapal dagang yang datang dari berbagai penjuru angin, kawasan ini juga memegang peran penting dalam proses pertumbuhan peradaban di Nusantara. Berbagai interaksi sosial-kultural, di samping ekonomi-politik, yang terjadi di kawasan ini pada gilirannya menciptakan apa yang disebut Adrian B Lapiannakhoda pertama sejarawan maritim Asia Tenggarasebagai jaringan maritim Nusantara.
Sejak tahun-tahun awal Masehi, kawasan ini memang telah memainkan peran pentingnya sebagai urat nadi perniagaan Timur dan Barat. Peran itu terus dipegangnya dari waktu ke waktu meski dengan nakhoda yang kerap berganti dari waktu ke waktu hingga memasuki milenium ketiga pada abad ke-21 ini.
Jatuhnya Mesir ke tangan prajurit-prajurit Romawi pada sekitar 30 tahun sebelum Masehi menandai era baru rute perdagangan dunia kala itu. Sejak itu, apa yang dikenal sebagai Jalur Sutra, yang menghubungkan China ke daratan Eropa (baca: Romawi), mulai ditinggalkan. Penyebab utama memang bukan lantaran kemenangan Romawi atas Mesir, tetapi lebih karena hilangnya rasa aman di jalur perdagangan ini.
Lebih-lebih setelah Dinasti Han di China jatuh pada sekitar tahun 20 Masehidan suasana peperangan terus berlangsung selama hampir empat abad sehingga tidak ada periode damai yang panjang di Asia Tengahperdagangan melalui jalur maritim pun akhirnya jadi pilihan. Mengutip catatan sejarah dan kajian arkeologi, Paul Michel Munoz (2006) bahkan berani menyimpulkan, kala itu pengiriman barang melalui laut jauh lebih menguntungkan para pedagang.
Jalur laut memungkinkan para pedagang membawa kargo dalam jumlah besar, hingga 200 ton, dalam sebuah perahu yang membutuhkan kru 20-50 orang saja. Juga tak ada kebutuhan menaik-turunkan barang dagangan ke punggung binatang beban setiap malamnya, seperti kalau melalui jalur darat, tulis Munoz.
Di tengah arus perubahan sarana angkut barang dagangan tersebut, Selat Malaka menjadi semacam gerbang keluar-masuk yang menghubungkan daratan China di timur serta India, Jazirah Arab, dan Eropa di belahan barat. Tidak berlebihan bila AB Lapian menggambarkan Selat Malaka sebagai hatinya lautan yang dapat mengalirkan semua aktivitas dari Atlantik ke kawasan Pasifik setelah melewati Samudra Hindia.
Penuh risikoJika pada awal milenium pertama saja Selat Malaka sudah memiliki peran yang begitu besar sebagai jalur perniagaan, memasuki awal milenium ketiga kedudukannya semakin penting. Intensitas penggunanya pun terus meningkat, tentu dengan kompleksitas persoalan yang juga kian beragam.
Saat ini setiap hari sedikitnya 150-200 kapal yang melintas di kawasan ini. Tidak sedikit dari jumlah itu berupa kapal-kapal tanker raksasa, berukuran di atas 180.000 DWT. Sebagian besar dari kapal-kapal tanker itu mengangkut minyak ke sejumlah tujuan, terutama China, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di sabuk Pasifik.
Makin padatnya lalu lintas kapal-kapal berukuran besar di kawasan ini bukan tanpa risiko, baik terhadap moda angkutan itu sendiri maupun bagi Indonesia dan Malaysia sebagai pemilik wilayah pantai di kawasan ini. Tidak semua alur di sepanjang kawasan Selat Malaka bisa dilayari dengan leluasa sehingga risiko kecelakaan cukup besar.
Di Selat Philip, misalnya, alur pelayarannya sangat sempit. Meski lebar selat yang berada di antara Pulau Kepala Jerih dan Pulau Takung ini secara keseluruhan mencapai 3 mil laut atau di atas 5 kilometer, alur yang bisa dilewati kapal-kapal besar hanya sekitar 800 meter.
Di sekelilingnya juga terdapat pulau-pulau kecil lainnya. Belum lagi adanya kumpulan karang tak jauh dari Pulau Halenmar, juga dasar laut yang di beberapa tempat kurang dari 23 meter saat pasang surut. Risiko lain yang mengadang adalah perubahan arus laut yang tidak teratur, dengan kecepatan hingga 3 mil per jam serta hujan dan angin kuat yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Nelayan-nelayan setempat banyak pula yang menangkap ikan di perairan itu, selain ramainya lalu lintas laut yang memotong antara Singapura dan Batam, kata Hasjim Djalal.
Risiko lain tentu saja menyangkut faktor keamanan. Berbagai kasus perompakan memang kerap terjadi. Akan tetapi, laporan yang dilansir berbagai pihaktermasuk Inter-Governmental Maritime Consultative Organization/International Maritime Organization (IMCO/IMO, organisasi yang menangani masalah-masalah pelayaran dunia)terkadang bias karena mencampuradukkan kasus perompakan dan perampokan.
Banyak kasus yang oleh mereka dikategorikan sebagai perompakan, sesungguhnya kasus pencurian biasa di atas kapal. Akibatnya, berdasarkan laporan-laporan semacam itulah angka kasus perompakan di Selat Malaka dalam statistik mereka terlihat menjadi tinggi.
Berbagai kalangan menduga, upaya mengedepankan isu keamanan lewat pembengkakan statistik kasus-kasus perompakan di Selat Malaka merupakan bagian dari strategi untuk menginternasionalisasikan kawasan ini. Sebaliknya, salah satu butir Konvensi Hukum Laut 1982 (Pasal 43) yang telah disepakati, yang menghendaki negara-negara pemakai selat agar membantu meningkatkan keselamatan pelayaran dan memelihara lingkungan laut di selat tersebutdalam hal ini Selat Malakajustru kewajiban itu tidak mereka laksanakan.
Jadi, ada apa di balik itu semua? (ken)
PAGE 1