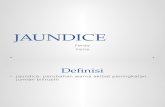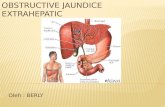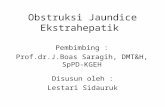Materi Obstructive Jaundice
Click here to load reader
-
Upload
eiy-venni-winta-pratiwi -
Category
Documents
-
view
23 -
download
9
Transcript of Materi Obstructive Jaundice

Ikterus Obstruktif (obstructive jaundice)
Filed under: Bedah,med papers — ningrum @ 6:04 pm
PENDAHULUAN
Munculnya jaundice pada pasien adalah sebuah kejadian yang dramatis secara visual. Jaundice selalu berhubungan dengan penyakit penting, meskipun hasil akhir jangka panjang bergantung pada penyebab yang mendasari jaundice. Jaundice adalah gambaran fisik sehubungan dengan gangguan metabolisme bilirubin. Kondisi ini biasanya disertai dengan gambaran fisik abnormal lainnya dan biasanya berhubungan dengan gejala-gejala spesifik. Kegunaan yang tepat pemeriksaan darah dan pencitraan, memberikan perbaikan lebih lanjut pada diagnosa banding. Umumnya, jaundice non-obstruktif tidak membutuhkan intervensi bedah, sementara jaundice obstruktif biasanya membutuhkan intervensi bedah atau prosedur intervensi lainnya untuk pengobatan. (1)
Jaundice merupakan manifestasi yang sering pada gangguan traktus biliaris, dan evaluasi serta manajemen pasien jaundice merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh ahli bedah. Serum bilirubin normal berkisar antara 0,5 – 1,3 mg/dL; ketika levelnya meluas menjadi 2,0 mg/dL, pewarnaan jaringan bilirubin menjadi terlihat secara klinis sebagai jaundice. Sebagai tambahan, adanya bilirubin terkonjugasi pada urin merupakan satu dari perubahan awal yang terlihat pada tubuh pasien. (2)
Bilirubin merupakan produk pemecahan hemoglobin normal yang dihasilkan dari sel darah merah tua oleh sistem retikuloendotelial. Bilirubin tak terkonjugasi yang tidak larut ditransportasikan ke hati terikat dengan albumin. Bilirubin ditransportasikan melewati membran sinusoid hepatosit kedalam sitoplasma. Enzim uridine diphosphate–glucuronyl transferase mengkonjugasikan bilirubin tak-terkonjugasi yang tidak larut dengan asam glukoronat untuk membentuk bentuk terkonjugasi yang larut-air, bilirubin monoglucuronide dan bilirubin diglucuronide. Bilirubin terkonjugasi kemudian secara aktif disekresikan kedalam kanalikulus empedu. Pada ileum terminal dan kolon, bilirubin dirubah menjadi urobilinogen, 10-20% direabsorbsi kedalam sirkulasi portal. Urobilinogen ini diekskresikan kembali kedalam empedu atau diekskresikan oleh ginjal didalam urin. (2)
DEFINISI
Ikterus (jaundice) didefinisikan sebagai menguningnya warna kulit dan sklera akibat akumulasi pigmen bilirubin dalam darah dan jaringan. Kadar bilirubin harus mencapai 35-40 mmol/l sebelum ikterus menimbulkan manifestasi klinik. (3)
Jaundice (berasal dari bahasa Perancis ‘jaune’ artinya kuning) atau ikterus (bahasa Latin untuk jaundice) adalah pewarnaan kuning pada kulit, sklera, dan membran mukosa oleh deposit bilirubin (pigmen empedu kuning-oranye) pada jaringan tersebut. (4)
ANATOMI SISTEM HEPATOBILIER
Pengetahuan yang akurat akan anatomi hati dan traktus biliaris, dan hubungannya dengan pembuluh darah penting untuk kinerja pembedahan hepatobilier karena biasanya terdapat variasi anatomi yang luas. Deskripsi anatomi klasik pada traktus biliaris hanya muncul pada 58% populasi. (4)
Hepar, kandung empedu, dan percabangan bilier muncul dari tunas ventral (divertikulum hepatikum) dari bagian paling kaudal foregut diawal minggu keempat kehidupan. Bagian ini terbagi menjadi dua bagian sebagaimana bagian tersebut tumbuh diantara lapisan mesenterik ventral: bagian kranial lebih besar (pars hepatika) merupakan asal mula hati/hepar, dan bagian kaudal yang lebih kecil (pars sistika)

meluas membentuk kandung empedu, tangkainya menjadi duktus sistikus. Hubungan awal antara divertikulum hepatikum dan penyempitan foregut, nantinya membentuk duktus biliaris. Sebagai akibat perubahan posisi duodenum, jalan masuk duktus biliaris berada disekitar aspek dorsal duodenum. (4)
Sistem biliaris secara luas dibagi menjadi dua komponen, jalur intra-hepatik dan ekstra-hepatik. Unit sekresi hati (hepatosit dan sel epitel bilier, termasuk kelenjar peribilier), kanalikuli empedu, duktulus empedu (kanal Hearing), dan duktus biliaris intrahepatik membentuk saluran intrahepatik dimana duktus biliaris ekstrahepatik (kanan dan kiri), duktus hepatikus komunis, duktus sistikus, kandung empedu, dan duktus biliaris komunis merupakan komponen ekstrahepatik percabangan biliaris. (4)
Duktus sistikus dan hepatikus komunis bergabung membentuk duktus biliaris. Duktus biliaris komunis kira-kira panjangnya 8-10 cm dan diameter 0,4-0,8 cm. Duktus biliaris dapat dibagi menjadi tiga segmen anatomi: supraduodenal, retroduodenal, dan intrapankreatik. Duktus biliaris komunis kemudian memasuki dinding medial duodenum, mengalir secara tangensial melalui lapisan submukosa 1-2 cm, dan memotong papila mayor pada bagian kedua duodenum. Bagian distal duktus dikelilingi oleh otot polos yang membentuk sfingter Oddi. Duktus biliaris komunis dapat masuk ke duodenum secara langsung (25%) atau bergabung bersama duktus pankreatikus (75%) untuk membentuk kanal biasa, yang disebut ampula Vater. (4)
Traktus biliaris dialiri vaskular kompleks pembuluh darah disebut pleksus vaskular peribilier. Pembuluh aferen pleksus ini berasal dari cabang arteri hepatika, dan pleksus ini mengalir kedalam sistem vena porta atau langsung kedalam sinusoid hepatikum. (4)
METABOLISME NORMAL BILIRUBIN
Bilirubin berasal dari hasil pemecahan hemoglobin oleh sel retikuloendotelial, cincin heme setelah dibebaskan dari besi dan globin diubah menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Biliverdin berubah menjadi bilirubin yang berwarna kuning. Bilirubin ini dikombinasikan dengan albumin membentuk kompleks protein-pigmen dan ditransportasikan ke dalam sel hati. Bentuk bilirubin ini sebagai bilirubin yang belum dikonjugasi atau bilirubin indirek berdasar reaksi diazo dari Van den Berg, tidak larut dalam air dan tidak dikeluarkan melalui urin. Didalam sel inti hati albumin dipisahkan, bilirubin dikonjugasikan dengan asam glukoronik yang larut dalam air dan dikeluarkan ke saluran empedu. Pada reaksi diazo Van den Berg memberikan reaksi langsung sehingga disebut bilirubin direk. (5)
Bilirubin indirek yang berlebihan akibat pemecahan sel darah merah yang terlalu banyak, kekurangmampuan sel hati untuk melakukan konjugasi akibat penyakit hati, terjadinya refluks bilirubin direk dari saluran empedu ke dalam darah karena adanya hambatan aliran empedu menyebabkan tingginya kadar bilirubin didalam darah. Keadaan ini disebut hiperbilirubinemia dengan manifestasi klinis berupa ikterus. (5)
KLASIFIKASI
Gambar 3 berisi daftar skema bagi klasifikasi umum jaundice: pre-hepatik, hepatik dan post-hepatik. Jaundice obstruktif selalu ditunjuk sebagai post-hepatik sejak defeknya terletak pada jalur metabolisme bilirubin melewati hepatosit. Bentuk lain jaundice ditunjuk sebagai jaundice non-obstruktif. Bentuk ini akibat defek hepatosit (jaundice hepatik) atau sebuah kondisi pre-hepatik. (1)
DIAGNOSIS
Langkah pertama pendekatan diagnosis pasien dengan ikterus ialah melalui anamnesis, pemeriksaan fisik yang teliti serta pemeriksaan faal hati. (5)

Anamnesis ditujukan pada riwayat timbulnya ikterus, warna urin dan feses, rasa gatal, keluhan saluran cerna, nyeri perut, nafsu makan berkurang, pekerjaan, adanya kontak dengan pasien ikterus lain, alkoholisme, riwayat transfusi, obat-obatan, suntikan atau tindakan pembedahan. (5)
Diagnosa banding jaundice sejalan dengan metabolisme bilirubin (Tabel 1). Penyakit yang menyebabkan jaundice dapat dibagi menjadi penyakit yang menyebabkan jaundice ‘medis’ seperti peningkatan produksi, menurunnya transpor atau konjugasi hepatosit, atau kegagalan ekskresi bilirubin; dan ada penyakit yang menyebabkan jaundice ‘surgical’ melalui kegagalan transpor bilirubin kedalam usus. Penyebab umum meningkatnya produksi bilirubin termasuk anemia hemolitik, penyebab dapatan hemolisis termasuk sepsis, luka bakar, dan reaksi transfusi. Ambilan dan konjugasi bilirubin dapat dipengaruhi oleh obat-obatan, sepsis dan akibat hepatitis virus. Kegagalan ekskresi bilirubin menyebabkan kolestasis intrahepatik dan hiperbilirubinemia terkonjugasi. Penyebab umum kegagalan ekskresi termasuk hepatitis viral atau alkoholik, sirosis, kolestasis induksi-obat. Obstruksi bilier ekstrahepatik dapat disebabkan oleh beragam gangguan termasuk koledokolitiasis, striktur bilier benigna, kanker periampular, kolangiokarsinoma, atau kolangitis sklerosing primer. (2) Ketika mendiagnosa jaundice, dokter harus mampu membedakan antara kerusakan pada ambilan bilirubin, konjugasi, atau ekskresi yang biasanya diatur secara medis dari obstruksi bilier ekstrahepatik, yang biasanya ditangani oleh ahli bedah, ahli radiologi intervensional, atau ahli endoskopi. Pada kebanyakan kasus, anamnesis menyeluruh, pemeriksaan fisik, tes laboratorium rutin dan pencitraan radiologis non-invasif membedakan obstruksi bilier ekstrahepatik dari penyebab jaundice lainnya. Kolelitiasis selalu berhubungan dengan nyeri kuadran atas kanan dan gangguan pencernaan. Jaundice dari batu duktus biliaris umum
biasanya sementara dan berhubungan dengan nyeri dan demam (kolangitis). Serangan jaundice tak-nyeri bertingkat sehubungan dengan hilangnya berat badan diduga sebuah keganasan/malignansi. Jika jaundice terjadi setelah kolesistektomi, batu kandung empedu menetap atau cedera kandung empedu harus diperkirakan. (2)
Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik meliputi perabaan hati, kandung empedu, limpa, mencari tanda-tanda stigmata sirosis hepatis, seperti spider naevi, eritema palmaris, bekas garukan di kulit karena pruritus, tanda-tanda asites. Anemi dan limpa yang membesar dapat dijumpai pada pasien dengan anemia hemolitik. Kandung empedu yang membesar menunjukkan adanya sumbatan pada saluran empedu bagian distal yang lebih sering disebabkan oleh tumor (dikenal hukum Courvoisier). (5)
Hukum Courvoisier
“Kandung empedu yang teraba pada ikterus tidak mungkin disebabkan oleh batu kandung empedu”. Hal ini biasanya menunjukkan adanya striktur neoplastik tumor (tumor pankreas, ampula, duodenum, CBD), striktur pankreatitis kronis, atau limfadenopati portal. (3)
Pemeriksaan Laboratorium
Tes laboratorium harus dilakukan pada semua pasien jaundice termasuk serum bilirubin direk dan indirek, alkali fosfatase, transaminase, amilase, dan hitung sel darah lengkap. Hiperbilirubinemia (indirek) tak terkonjugasi terjadi ketika ada peningkatan produksi bilirubin atau menurunnya ambilan dan konjugasi hepatosit. Kegagalan pada ekskresi bilirubin (kolestasis intrahepatik) atau obstruksi bilier ekstrahepatik menyebabkan hiperbilirubinemia (direk) terkonjugasi mendominasi. Elevasi tertinggi pada bilirubin serum biasanya ditemukan pada pasien dengan obstruksi maligna, pada mereka yang levelnya meluas sampai 15 mg/dL yang diamati. Batu kandung empedu umumnya biasanya berhubungan dengan peningkatan lebih menengah pada bilirubin serum (4 – 8 mg/dL). Alkali fosfatase

merupakan penanda yang lebih sensitif pada obstruksi bilier dan mungkin meningkat terlebih dahulu pada pasien dengan obstruksi bilier parsial. (2)
Pemeriksaan faal hati dapat menentukan apakah ikterus yang timbul disebabkan oleh gangguan pada sel-sell hati atau disebabkan adanya hambatan pada saluran empedu. Bilirubin direk meningkat lebih tinggi dari bilirubin indirek lebih mungkin disebabkan oleh sumbatan saluran empedu dibanding bila bilirubin indirek yang jelas meningkat. Pada keadaan normal bilirubin tidak dijumpai di dalam urin. Bilirubin indirek tidak dapat diekskresikan melalui ginjal sedangkan bilirubin yang telah dikonjugasikan dapat keluar melalui urin. Karena itu adanya bilirubin lebih mungkin disebabkan akibat hambatan aliran empedu daripada kerusakan sel-sel hati. Pemeriksaan feses yang menunjukkan adanya perubahan warna feses menjadi akolis menunjukkan terhambatnya aliran empedu masuk ke dalam lumen usus (pigmen tidak dapat mencapai usus). (2)
Pemeriksaan Penunjang
USG
Pemeriksaan pencitraan pada masa kini dengan sonografi sangat membantu dalam menegakkan diagnosis dan dianjurkan merupakan pemeriksaan penunjang pencitraan yang pertama dilakukan sebelum pemeriksaan pencitraan lainnya. Dengan sonografi dapat ditentukan kelainan parenkim hati, duktus yang melebar, adanya batu atau massa tumor. Ketepatan diagnosis pemeriksaan sonografi pada sistem hepatobilier untuk deteksi batu empedu, pembesaran kandung empedu, pelebaran saluran empedu dan massa tumor tinggi sekali. Tidak ditemukannya tanda-tanda pelebaran saluran empedu dapat diperkirakan penyebab ikterus bukan oleh sumbatan saluran empedu, sedangkan pelebaran saluran empedu memperkuat diagnosis ikterus obstruktif. (2)
Keuntungan lain yang diperoleh pada penggunaan sonografi ialah sekaligus kita dapat menilai kelainan organ yang berdekatan dengan sistem hepatobilier antara lain pankreas dan ginjal. Aman dan tidak invasif merupakan keuntungan lain dari sonografi. (2)
Pemeriksaan Radiologi
Pemeriksaan foto polos abdomen kurang memberi manfaat karena sebagian besar batu empedu radiolusen. Kolesistografi tidak dapat digunakan pada pasien ikterus karena zat kontras tidak diekskresikan oleh sel hati yang sakit. (5)
Pemeriksaan endoskopi yang banyak manfaat diagnostiknya saat ini adalah pemeriksaan ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio Pancre atography). Dengan bantuan endoskopi melalui muara papila Vater kontras dimasukkan kedalam saluran empedu dan saluran pankreas. Keuntungan lain pada pemeriksaan ini ialah sekaligus dapat menilai apakah ada kelainan pada muara papila Vater, tumor misalnya atau adanya penyempitan. Keterbatasan yang mungkin timbul pada pemeriksaan ini ialah bila muara papila tidak dapat dimasuki kanul. (5)
Adanya sumbatan di saluran empedu bagian distal, gambaran saluran proksimalnya dapat divisualisasikan dengan pemeriksaan Percutaneus Transhepatic Cholangiography (PTC). Pemeriksaan ini dilakukan dengan penyuntikan kontras melalui jarum yang ditusukkan ke arah hilus hati dan sisi kanan pasien. Kontras disuntikkan bila ujung jarum sudah diyakini berada di dalam saluran empedu. Computed Tomography (CT) adalah pemeriksaan radiologi yang dapat memperlihatkan serial irisan-irisan hati. Adanya kelainan hati dapat diperlihatkan lokasinya dengan tepat. (5)

Untuk diagnosis kelainan primer dari hati dan kepastian adanya keganasan dilakukan biopsi jarum untuk pemeriksaan histopatologi. Biopsi jarum tidak dianjurkan bila ada tanda-tanda obstruksi saluran empedu karena dapat menimbulkan penyulit kebocoran saluran empedu. (5)
JAUNDICE OBSTRUKTIF
Hambatan aliran empedu yang disebabkan oleh sumbatan mekanik menyebabkan terjadinya kolestasis yang disebut sebagai ikterus obstruktif saluran empedu, sebelum sumbatan melebar. Aktifitas enzim alkalifosfatase akan meningkat dan ini merupakan tanda adanya kolestasis. Infeksi bakteri dengan kolangitis dan kemudian pembentukan abses menyertai demam dan septisemia yang tidak jarang dijumpai sebagai penyulit ikterus obstruktif. (5)
Patofisiologi jaundice obstruktif
Empedu merupakan sekresi multi-fungsi dengan susunan fungsi, termasuk pencernaan dan penyerapan lipid di usus, eliminasi toksin lingkungan, karsinogen, obat-obatan, dan metabolitnya, dan menyediakan jalur primer ekskresi beragam komponen endogen dan produk metabolit, seperti kolesterol, bilirubin, dan berbagai hormon. (4)
Pada obstruksi jaundice, efek patofisiologisnya mencerminkan ketiadaan komponen empedu (yang paling penting bilirubin, garam empedu, dan lipid) di usus halus, dan cadangannya, yang menyebabkan tumpahan pada sirkulasi sistemik. Feses biasanya menjadi pucat karena kurangnya bilirubin yang mencapai usus halus. Ketiadaan garam empedu dapat menyebabkan malabsorpsi, mengakibatkan steatorrhea dan defisiensi vitamin larut lemak (A, D, K); defisiensi vitamin K bisa mengurangi level protrombin. Pada kolestasis berkepanjangan, seiring malabsorpsi vitamin D dan Ca bisa menyebabkan osteoporosis atau osteomalasia. (4)
Retensi bilirubin menyebabkan hiperbilirubinemia campuran. Beberapa bilirubin terkonjugasi mencapai urin dan menggelapkan warnanya. Level tinggi sirkulasi garam empedu berhubungan dengan, namun tidak menyebabkan, pruritus. Kolesterol dan retensi fosfolipid menyebabkan hiperlipidemia karena malabsorpsi lemak (meskipun meningkatnya sintesis hati dan menurunnya esterifikasi kolesterol juga punya andil); level trigliserida sebagian besar tidak terpengaruh. (4)
Penyakit hati kolestatik ditandai dengan akumulasi substansi hepatotoksik, disfungsi mitokondria dan gangguan pertahanan antioksidan hati. Penyimpanan asam empedu hidrofobik mengindikasikan penyebab utama hepatotoksisitas dengan perubahan sejumlah fungsi sel penting, seperti produksi energi mitokondria. Gangguan metabolisme mitokondria dan akumulasi asam empedu hidrofobik berhubungan dengan meningkatnya produksi oksigen jenis radikal bebas dan berkembangnya kerusakan oksidatif. (4)
Etiologi jaundice obstruktif
Sumbatan saluran empedu dapat terjadi karena kelainan pada dinding saluran misalnya adanya tumor atau penyempitan karena trauma (iatrogenik). Batu empedu dan cacing askaris sering dijumpai sebagai penyebab sumbatan di dalam lumen saluran. Pankreatitis, tumor kaput pankreas, tumor kandung empedu atau anak sebar tumor ganas di daerah ligamentum hepatoduodenale dapat menekan saluran empedu dari luar menimbulkan gangguan aliran empedu. (5)
Beberapa keadaan yang jarang dijumpai sebagai penyebab sumbatan antara lain kista koledokus, abses amuba pada lokasi tertentu, divertikel duodenum dan striktur sfingter papila vater. (5)

Ringkasnya etiologi disebabkan oleh: koledokolitiasis, kolangiokarsinoma, karsinoma ampulla, karsinoma pankreas, striktur bilier. (4)
Gambaran klinis jaundice obstruktif
Jaundice, urin pekat, feses pucat dan pruritus general merupakan ciri jaundice obstruktif. Riwayat demam, kolik bilier, dan jaundice intermiten mungkin diduga kolangitis/koledokolitiasis. Hilangnya berat badan, massa abdomen, nyeri yang menjalar ke punggung, jaundice yang semakin dalam, mungkin ditimbulkan karsinoma pankreas. Jaundice yang dalam (dengan rona kehijauan) yang intensitasnya berfluktuasi mungkin disebabkan karsinoma peri-ampula. Kandung empedu yang teraba membesar pada pasien jaundice juga diduga sebuah malignansi ekstrahepatik (hukum Couvoissier). (4)
Pemeriksaan pada jaundice obstruktif
1. Hematologi (4)
Meningkatnya level serum bilirubin dengan kelebihan fraksi bilirubin terkonjugasi. Serum gamma glutamyl transpeptidase (GGT) juga meningkat pada kolestasis.
Umumnya, pada pasien dengan penyakit batu kandung empedu hiperbilirubinemia lebih rendah dibandingkan pasien dengan obstruksi maligna ekstra-hepatik. Serum bilirubin biasanya < 20 mg/dL. Alkali fosfatase meningkat 10 kali jumlah normal. Transaminase juga mendadak meningkat 10 kali nilai normal dan menurun dengan cepat begitu penyebab obstruksi dihilangkan.
Meningkatnya leukosit terjadi pada kolangitis. Pada karsinoma pankreas dan kanker obstruksi lainnya, bilirubin serum meningkat menjadi 35-40 mg/dL, alkali fosfatase meningkat 10 kali nilai normal, namun transamin tetap normal.
Penanda tumor seperti CA 19-9, CEA dan CA-125 biasanya meningkat pada karsinoma pankreas, kolangiokarsinoma, dan karsinoma peri-ampula, namun penanda tersebut tidak spesifik dan mungkin saja meningkat pada penyakit jinak percabangan hepatobilier lainnya.
1. Pencitraan (4)
Tujuan dibuat pencitraan adalah: (1) memastikan adanya obstruksi ekstrahepatik (yaitu membuktikan apakah jaundice akibat post-hepatik dibandingkan hepatik), (2) untuk menentukan level obstruksi, (3) untuk mengidentifikasi penyebab spesifik obstruksi, (4) memberikan informasi pelengkap sehubungan dengan diagnosa yang mendasarinya (misal, informasi staging pada kasus malignansi)
USG : memperlihatkan ukuran duktus biliaris, mendefinisikan level obstruksi, mengidentifikasi penyebab dan memberikan informasi lain sehubuungan dengan penyakit (mis, metastase hepatik, kandung empedu, perubahan parenkimal hepatik).
USG : identifikasi obstruksi duktus dengan akurasi 95%, memperlihatkan batu kandung empedu dan duktus biliaris yang berdilatasi, namun tidak dapat diandalkan untuk batu kecil atau striktur. Juga dapat memperlihatkan tumor, kista atau abses di pankreas, hepar dan struktur yang mengelilinginya.
CT : memberi viasualisasi yang baik untuk hepar, kandung empedu, pankreas, ginjal dan retroperitoneum; membandingkan antara obstruksi intra- dan ekstrahepatik dengan akurasi 95%. CT dengan kontras digunakan untuk menilai malignansi bilier.

ERCP dan PTC : menyediakan visualisasi langsung level obstruksi. Namun prosedur ini invasif dan bisa menyebabkan komplikasi seperti kolangitis, kebocoran bilier, pankreatitis dan perdarahan.
EUS (endoscopic ultrasound) : memiliki beragam aplikasi, seperti staging malignansi gastrointestinal, evaluasi tumor submukosa dan berkembang menjadi modalitas penting dalam evaluasi sistem pankreatikobilier. EUS juga berguna untuk mendeteksi dan staging tumor ampula, deteksi mikrolitiasis, koledokolitiasis dan evaluasi striktur duktus biliaris benigna atau maligna. EUS juga bisa digunakan untuk aspirasi kista dan biopsi lesi padat.
Magnetic Resonance Cholangio-Pancreatography (MRCP) merupakan teknik visualisasi terbaru, non-invasif pada bilier dan sistem duktus pankreas. Hal ini terutama berguna pada pasien dengan kontraindikasi untuk dilakukan ERCP. Visualisasi yang baik dari anatomi bilier memungkinkan tanpa sifat invasif dari ERCP. Tidak seperti ERCP, MRCP adalah murni diagnostik.
Penatalaksanaan jaundice obstruktif
Pada dasarnya penatalaksanaan pasien dengan ikterus obstruktif bertujuan untuk menghilangkan penyebab sumbatan atau mengalihkan aliran empedu. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan pembedahan misalnya pengangkatan batu atau reseksi tumor. Upaya untuk menghilangkan sumbatan dapat dengan tindakan endoskopi baik melalui papila Vater atau dengan laparoskopi. (5)
Bila tindakan pembedahan tidak mungkin dilakukan untuk menghilangkan penyebab sumbatan, dilakukan tindakan drainase yang bertujuan agar empedu yang terhambat dapat dialirkan. Drainase dapat dilakukan keluar tubuh misalnya dengan pemasangan pipa nasobilier, pipa T pada duktus koledokus atau kolesistotomi. Drainase interna dapat dilakukan dengan membuat pintasan biliodigestif. Drainase interna ini dapat berupa kolesisto-jejunostomi, koledoko-duodenostomi, koledoko-jejunostomi atau hepatiko-jejunostomi. (5)
Diet Penyakit Hati
Menurut Atmarita (2005), terdapat 3 jenis diet khusus penyakit hati. Hal ini didasarkanpada gejala dan keadaan penyakit pasien. Jenis diet penyakit hati tersebut adalah Diet Hati I(DH I), Diet Hati II (DH II), dan Diet Hati III (DH III). Selain itu pada diet penyakit hati ini jugamenyertakan Diet Garam Rendah I.
1. Diet Garam Rendah I (DGR I) Diet garam rendah I diberikan kepada pasien dengan edema, asites dan atau atauhipertensi berat. Pada pengolahan makanannya tidak menambahkan garam dapur. Dihindaribahan makanan yang tinggi kadar natriumnya. Kadar Natrium pada Diet garam rendah I iniadalah 200-400 mg Na.
2. Diet Hati I (DH I) Diet Hati I diberikan bila pasien dala keadaan akut atau bila prekoma sudah dapatdiatasi dan pasien sudah mulai mempunyai nafsu makan. Melihat keadaan pasien, makanandiberikan dalam bentuk cincang atau lunak. Pemberian protein dibatasi (30 g/hari) dan lemakdiberikan dalam bentuk mudah dicerna. Formula enteral dengan asam amino rantai cabang(Branched Chain Amino Acid /BCAA) yaitu leusin, isoleusin, dan valin dapat digunakan. Bilaada asites dan diuresis belum sempurna, pemberian cairan maksimal 1 L/hari.
Makanan ini rendah energi, protein, kalsium, zat besi, dan tiamin; karena itu sebaiknyadiberikan selama beberapa hari saja. Menurut beratnya retensi garam atau air, makanandiberikan sebagai Diet Hati I Garam rendah. Bila ada asites hebat dan tandatanda diuresisbelum membaik, diberikan Diet Garam Rendah I. Untuk menambah kandungan energi, selainmakanan per oral juga diberikan makanan parenteral berupa cairan glukosa.

2.Diet Hati II (DH II) Diet hati II diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati II kepada pasiendengan nafsu makannya cukup. Menurut keadaan pasien, makanan diberikan dalam bentuklunak / biasa. Protein diberikan 1 g/Kg berat badan dan lemak sedang (20-25% dari kebutuhanenergi total) dalam bentuk yang mudah dicerna. Makanan ini cukup mengandung energi, zat
besi, vitamin A & C, tetapi kurang kalsium dan tiamin. Menurut beratnya retensi garam atau air,makanan diberikan sebagai diet hati II rendah garam. Bila asites hebat dan diuresis belum baik,diet mengikuti pola Diet Rendah garam I.
3.Diet Hati III (DH III) Diet Hati III diberikan sebagai makanan perpindahan dari Diet Hati II atau kepada pasienhepatitis akut (Hepatitis Infeksiosa/A dan Hepatitis Serum/B) dan sirosis hati yang nafsumakannya telah baik, telah dapat menerima protein, lemak, mi9neral dan vitamin tapi tinggikarbohidrat. Menurut beratnya tetensi garam atau air, makanan diberikan sebagai Diet Hati IIIGaram Rendah I.
Tujuan Diet
Adapun tujuan Diet Hati secara umum antara lain:
Mencapai dan mempertahankan status gizi optimal tanpa memberatkan fungsi hati,dengan cara: Meningkatkan regenerasi jaringan hati dan mencegah kerusakan lebih lanjut
dan/ataumeningkatkan fungsi jaringan hati yang tersisa. Mencegah katabolisme protein. Mencegah penurunan BB atau meningkatkan BB bila kurang. Mencegah atau mengurangi asites, varises esophagus, dan hipertensi portal. Mencegah koma hepatik.
Syarat Diet
1. Energi tinggi untuk mencegah pemecahan protein, yang diberikan bertahap sesuaikemampuan pasien, yaitu 40-45 kkal/Kg BB.
2. Lemak cukup, yaitu 20-25% dari kebutuhan energo total, dalam bentuk yang mudahdicerna atau dalam bentuk emulsi. Bila pasien mengalami steatorea, gunakan lemakdengan asam lemak rantai sedang. Pemberian lemak sebanyak 45 Kg dapatmempertahankan fungsi imun dan proses sintesis lemak.
3. Protein agak tinggi, yaitu 1.25-1.5 g/Kg BB agar terjadi anabolisme protein. Asupanminimal protein 0.8-1g/Kg BB, protein nabati memberikan keuntungan karenakandungan serat yang dapat mempercepat pengeluaran amoniak melalui feses.
4. Vitamin dan mineral diberikan sesuai dengan tingkat defisiensi. Bila perlu, diberikansuplemen vitamin B kompleks, C, dan K serta mineral Zn dan Fe bila ada anemia.
5. Natrium diberikan rendah, tergantung tingkat edema dan asites. Bila pasien mendapatdiuretika, garam natrium dapat diberikan lebih leluasa.
6. Cairan diberikan lebih dari biasa, kecuali bila ada kontraindikasi.7. Bentuk makanan lunak bila ada keluhan mual dan muntah, atau makanan biasa
sesuaikemampuan saluran cerna.
Bahan Makanan yang Dibatasi:
Bahan makanan yang dibatasi untuk Diet Hati I, II, dan III adalaha dari sumber lemak, yaitusemua makanan dan daging yang banyak mengandung lemak dan santan serta bahanmakanan yang menimbulkan gas seperti ubi, kacang merah, kol, sawi, lobak, ketimun, durian,dan nangka.

Bahan Makanan yang tidak dianjurkan:
Bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk Diet Hati I, II, III adalah makanan yangmengandung alkohol, teh atau kopi kental SIROSIS HEPATIS 1.1 Definisi Sirosis hepatis adalah penyakit yang ditandai oleh adanya peradangan difusdan menahun pada hati yang diikuti proliferasi jaringan ikat, degenerasi danregenerasi sel-sel hati sehingga timbul kekacauan dalam susunan parenkim hati.Sirosis merupakan suatu keadaan patologis yang menggambarkan stadiumakhir fibrosis hepatik yang berlangsung progresif ditandai denga n distorsi daristruktur hepar dan pembentukan nodulus regeneratif.1.2 EpidemiologiLebih dari 40 % sirosis hati asimtomatik, sering ditemukan pada pemeriksaanrutin kesehatan atau pada otopsi. Insiden sirosis hati di Amerika diperkirakan 360 per 100.000 penduduk. Di Indonesia data prevalensi sirosis hati belum ada , hanya adalaporan dari beberapa pusat pendidikan saja. Di RS Sardjito Yogyakarta jumlah pasien sirosis hati berkisar 4,1% dari pasien yang dirawat dibagian penyakit dalamdalam kurun waktu 1 tahun(2004). Dimedan dalam kurun waktu 4 tahun dijumpai pasien sirosis hati sebanyak 819 (4%) dari seluruh pasien di bagian penyakit dalam.Penderita sirosis hepatis lebih banyak ditemukan pada lakilaki jikadibandingkan dengan wanita dengan perbandingan sekitar 1,6 : 1, dengan umur rata-rata terbanyak antara golongan umur 30-59 tahun.1.3 KlasifikasiBerdasarkan morfologi Sherlock membagi sirosis hepatis atas 3 jenis, yaitu:1. Mikronodular (besar nodul kurang dari 3 mm)2. Makronodular (besar nodul lebih dari 3 mm)3. Campuran (yang memperlihatkan gambaran mikronodular dan makronodular)Secara etiologis terdapat tiga pola khas yang ditemukan pada kebanyakankasus, yaitu:1. Sirosis alkoholik (sirosis Laennec / sirosis gizi)2. Sirosis hepatis postnekrotik 3. Sirosis biliarisSecara fungsional, sirosis hepatis terbagi atas:1. Sirosis hepatis kompensata
Sering juga disebut dengan sirosis hepatis laten. Pada stadium kompensata ini belum terlihat gejala-gejala yang nyata. Biasanya stadium ini ditemukan pada saat pemeriksaan screening.2. Sirosis hepatis dekompensataDikenal dengan sirosis hepatis hepatis aktif., dan pada stadium ini gejala-gejalasudah jelas.Lima dari tujuh diagnosis sirosis hepatia dekompensata (kriteria SuharyonoSoebandini)
:-spider nevi-eritema palmaris-kolateral vena- ascites-splenomegali-invers albumin (kadar albumin menurun)-hematemesis/melena1.4 EtiologiDi negara barat sirosis hepatis sering diakibatkan oleh alkoholik sedangkan diIndonesia terutama akibat hepatitis B maupun C. Hasil penelitian di Indonesiamenyebutkan virus hepatitis B mengakibatkan sirosis sebesar 4050% dan virushepatitis C 30-40%, sedangkan 10-20% penyebabnya tidak diketahui (non B-non C).Sebab-sebab sirosis dan/atau penyakit hati kronik :1. Penyakit infeksi-Bruselosis- Ekinokokus-Skistosomiasis-Toksoplasmosis- Hepatitis virus2. Penyakit keturunana dan metabolik -Defisiensi alpha 1 antitripsin-Sindrom fanconi-Galaktosemia- Penyakit Gaucher -Penyakit simpanan glikogen
-Hemokromatosis-Intoleransi glukosa herediter -Penyakit Wilson3. Obat dan toksin-Alkohol-Amiodaron- Arsenik -Obstruksi bilier -Penyakit perlemakan hati non alkoholik -Sirosis bilier primer -Kolangitis sklerosis primer 4. Penyebab lain atau tidak terbukti-Penyakit usus inflamasi kronis-Fibrosis kistik -Pintas jejunoileal-Sarkoidosis1.6. Patogenesis
Sirosis Laenec
Disebut juga sirosis sirosis alkoholik, portal atau sirosis gizi. Hal inidihubungk am dengan penggunaan alkohol. Dan merupakan 50% atau lebih dariseluruh kasus.
Perubahan pertama pada hati yang ditimbulkan alkohol adalah akumulasilemak secara gradual di dalam sel-sel hati (penumpukan lemak). Para pakar umumnyasetuju bahwa minuman beralkohol menimbulkan efek toksik langsung terhadap hati.Akumulasi lemak menunjukan adanya sejumlah gangguan metabolik, termasuk pembe ntukan trigliserida secara berlebihan, pemakaiannya yang berkurang dalam pembentukan lipoprotein, dan penurunaan oksidasi asam lemak. Sebab kerusakan

hatididuga merupakan efek langsung alikohol terhadap sel-sel hati, yang diperberat olehkeadaan malnutrisi. Secara makroskopis, hati membesar, rapuh, dan tampak berlemak dan mengalami gangguan fungsional akibat akumulasi lemak yang banyak tersebut.Pada kasus sirosis laenec yang sangat lanjut, lembaran-lembaran jaringan ikatyang tebal terbentuk pada pinggirpinggir lobulus, membagi parenkim menjadi
Nama Produk : AMINOFUSIN HEPAR Farmasi : Kalbe Farma Komposisi : Kadar tinggi dr rantai cabang amino acids (isoleucine, leucine, valine) & kadar rendah dr methionine, phenylalanine & trytophan. Other amino acids, sorbitol, xylitol & electrolytes. Indikasi : Nutrisi parenterial esensial utk pasien dg insufisiensi hati kronik yg berat. Kontra Indikasi : Koma hepatik endogen, atrogi hepatik akut, hiperkalemia, syok, dekompensasi kordis, intoleransi fruktosa atau sorbitol, defisiensi fruktosa 1, 6- difostat, keracunan metanol, kelainan metabolisme asam amino. Perhatian : - Efek Samping : - Interaksi Obat : - Kemasan : Lar infus 500 mL x 1 (Rp. 118,000), 10 (Rp. 1,180.000) Dosis -Dewasa : 1000 - 1500 mL/hr dg kecepatan infus 2 mL/kgBB/jam atau 40 tetes/mnt.
Asam aspartat (atau sering disebut aspartat saja, karena terionisasi di dalam sel), merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein. Asparagin merupakan asam amino analognya karena terbentuk melalui aminasi aspartat pada satu gugus hidroksilnya.Asam aspartat bersifat asam, dan dapat digolongkan sebagan asam karboksilat. Bagi mamalia aspartat tidaklah esensial. Fungsinya diketahui sebagai pembangkit neurotransmisi di otak dan saraf otot. Diduga, aspartat berperan dalam daya tahan terhadap kepenatan. Senyawa ini juga merupakan produk dari daur urea dan terlibat dalam glukoneogenesis.
Current Articles | Archives | Search Simposium Peranan PPI Injeksi Pantoprazole dalam Penanganan Ulkus PeptikumOleh Kalbe Medical Dept March 20, 2012 09:00
Keseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif mukosa lambung memegang peranan penting dalam patogenitas terjadinya ulkus peptikum. Demikian dikatakan oleh Dr. dr. Murdhani Abdullah, SpPD, KGEH dalam lunch simposium bertajuk “Peranan PPI (Proton pump inhibitor's
Injeksi Pantoprazole dalam Penanganan Ulkus Peptikum” yang diadakan oleh PT. Kalbe Farma pada hari Minggu 18 Maret 2012 lalu di IPB Convention Centre, Bogor.
Lebih lanjut beliau mengatakan faktor agresif yang dimaksud adalah asam lambung itu sendiri, investasi kuman H. pylori, stres, dan obat-obat antiinflamasi nonsteroid. Sementara yang termasuk faktor defensif adalah cairan mukus yang melapisi mukosa lambung, ion bikarbonat, prostaglandin, daya regenerasi, dan sirkulasi mukosa. Ketidakseimbangan antara kedua faktor diatas akan memicu terbentuknya ulkus.
Selain membahas patofisiologi ulkus peptikum, dr. Murdhani juga membahas mengenai penegakan diagnosis ulkus serta penatalaksanaannya. Diagnosis penyakit ulkus peptikum, khususnya yang disebabkan oleh infeksi H. pylori, dapat ditentukan melalui pemeriksaan yang bersifat invasif maupun non invasif. Pemeriksaan invasif berupa endoskopi dan saat ini menjadi standar utama dalam penetapan diagnosis. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan invasif, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang lain, seperti uji napas urea, tes serologi, dan lainnya.
Selanjutnya pembahasan mengenai tata laksana ulkus peptikum, dr. Murdhani mengatakan bahwa jelas harus dikaitkan dengan patofisiologi yang menjadi dasar penyebabnya. Apabila terbukti adanya

investasi H. pylori, pengobatan terapi tripel sesuai standar dapat diberikan, yang salah satu komponennya adalah penghambat pompa proton (PPI).
Pembicara kedua dalam simposium tersebut, dr. Erwin, SpPD, membahas peranan PPI dalam tata laksana perdarahan saluran cerna bagian atas. Beliau menekankan bahwa perdarahan saluran cerna bagian atas merupakan tipe terbanyak di antara seluruh kasus perdarahan saluran cerna (sekitar 100 per 100.000 kasus, dengan angka mortalitas 6-10%, kurang lebih 4-5 kali lebih banyak dibanding kasus perdarahan saluran cerna bawah). Jika dirinci lebih lanjut, penyebab perdarahan ini didominasi oleh ulkus peptikum (35-62%) sehingga pengetahuan mengenai tata laksana ulkus peptikum menjadi penting untuk dipelajari.
Tata laksana ulkus sendiri tergantung dari gambaran endoskopi masing-masing kasus. Secara umum, tiap kasus yang ditemukan memerlukan pengobatan PPI dalam tata laksananya. Untuk kasus yang ringan, dapat diberikan PPI bentuk oral dan tidak perlu perawatan di RS, tetapi untuk kasus yang lebih berat mungkin diperlukan PPI secara intravena, bahkan mungkin diperlukan perawatan di ruang intensif. Dalam simpulannya, dr. Erwin menyampaikan bahwa terapi PPI menurunkan risiko perdarahan ulang, kebutuhan tindakan operasi, dan menurunkan tindakan endoskopi berulang pasien dengan perdarahan akibat ulkus peptikum.
Sebagai pembicara terakhir, dr. Dedyanto Henky dari PT. Kalbe Farma mempresentasikan profil produk PRANZA, yang merupakan salah satu obat yang baru di lansir dengan bahan aktif pantoprazole 40 mg. Beliau menjelaskan mulai dari profil farmakokinetik, farmakodinamik, efikasi, hingga cara penggunaannya.
Kadar kolesterol tinggi dapat diturunkan dengan pemberian obat penurun kadar kolesterol. Obat hiperkolesterol yang beredar di Indonesia dibagi menjadi lima, antara lain Asam Fibrat, Resin, Penghambat HMG-Coa reduktase, Asam nikotinat dan Ezetimibe. 1. Obat yang termasuk golongan asam fibrat adalah Gemfibrozil, Fenofibrate dan Ciprofibrate. Gemfibrozil sangat efektif dalam menurunkan trigliserid plasma. Gemfibrozil meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase sehingga bersihan partikel kaya trigliserid meningkat. Kadar kolesterol HDL juga meningkat pada pemberian Gemfibrozil. Fibrate menurunkan produksi LDL dan meningkatkan kadar HDL. LDL ditumpuk di arteri sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, sedangkan HDL memproteksi arteri atas penumpukkan itu. 2. Obat antihiperlipidemik yang termasuk golongan resin adalah Kolestiramin (Chlolestyramine). Obat antihiperlidemik ini bekerja dengan cara mengikat asam empedu di usus dan meningkatkan pembuangan LDL dari aliran darah. 3. Penghambat HMG-CoA reduktase antara lain Pravastatin, Simvastatin, Rosavastatin, Fluvastatin, Atorvastatin. Golongan ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan kolesterol dengan cara menghambat kerja enzim yang ada di jaringan hati yang memproduksi mevalonate, suatu molekul kecil yang digunakan untuk mensintesa kolesterol dan derivat mevalonate. Selain itu meningkatkan pembuangan LDL dari aliran darah. 4. Asam nikotinat (nicotinic acid) atau Niasin/vitamin B3 yang larut air. Dengan dosis besar asam nikotinat diindikasikan untuk meningkatkan HDL atau kolesterol baik dalam darah.5. Sedangkan Ezetimibe dapat menurunkan total kolesterol dan LDL juga meningkatkan HDL dengan cara mengurangi penyerapan kolesterol di usus
Sumber: http://id.shvoong.com/medicine-and-health/epidemiology-public-health/2094440-obat-kolesterol/#ixzz29SS4zn82

Hipokalemia
Hipokalemia didefinisikan sebagai level potassium yang kurang dari 3,5 mEq/L. Hipokalemia sedang adalah keadaan dimana level serumnya 2,5-3 mEq/L dan hipokalemia berat adalah keadaan dimana level serumnya kurang dari 2,5 mEq/L.
Kondisi ini dapat menjadi keadaan yang membahayakan jiwa. Bahaya utamanya adalah aritmia jantung, kemudian hipoventilasi (biasanya karena kelemahan otot yang diasosiasikan dengan hipokalemia, dan dapat juga terjadi hepatic encephalopathy.
PatofisiologiHipokalemia dapat muncul karena salah satu dari 3 mekanisme patogenesis berikut:
1. Asupan yang kurang.Asupan potassium yang kurang secara sendiri tidak biasa menyebabkan hipokalemia tapi kadang-kadang bisa terlihat pada orang renta yang tidak bisa memasak untuk mereka sendiri atau tidak bisa menunyah dan menelan dnegan baik. Situasi klinik lain dimana hipokalemi dapat muncul adalah pada pasien yang menerima total parenteral nutrition (TPN), dimana suplementasi potassium mungkin kurang adekuat dalam jangka waktu yang lama. 2. Ekskresi yang berlebihan.Peningkatan ekskresi potassium, khususnya seiring dengan asupan yang kurang, adalah penyebab utama hipokalemia. Mekanisme umum yang dapat meningkatkan kehilangan potassium dari ginjal (utama) termasuk tingginya sodium yang masuk ke duktus koligens, seperti pada diuretic; kelebihan mineralokortikoid, seperti pada hiperaldosteronisme primer atau sekunder; atau peningkatan aliran urin, seperti pada diuretik osmotik. Selain itu, K juga dapat hilang melalui saluran gastrointestinal, seperti muntah dan diare. 3. Perpndahan dari ruang ekstraseluler ke intraseluler.Mekanisme pathogenesis ini juga biasa disertai ekskresi yang meningkat, menuju pada efek hipokalemik karena kehilangan berlebihan.
Beberapa kelainan spesifik dimana biasa terjadi hipokalemia diantaranya Bartter’s Syndrome, Gitelman’s Syndrome, Liddle’s Syndrome, Hypokalemic Periodic Paralysis, Hypokalemia Following Vomiting and Diuretics, dan Primary Hyperaldosteronism.