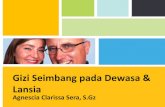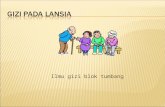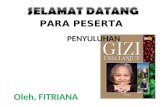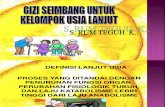Lansia Dan Status Gizi
Transcript of Lansia Dan Status Gizi

2.1 Lanjut Usia (Lansia)
Menurut World Health Organization (WHO), lansia merupakan individu
yang berusia 60 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit namun merupakan
tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan
kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah
keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan
keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan
penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara
individual (Martono, 2010).
WHO telah menetapkan bahwa batasan umur lanjut usia yaitu: usia
pertengahan (middle age) ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia
(elderly) antara 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua (old) antara 75 sampai 90
tahun dan usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun (Nugroho, 2000).
Menurut Undang-Undang No.13 tahun 1998 pada Bab I pasal 1 ayat 2
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang
yang mencapai usia 60 tahun ke atas (Maryam dkk., 2008).
2.1.2 Proses menua
Tahap dewasa merupakan tahap tubuh mencapai titik perkembangan yang
maksimal. Setelah itu tubuh mulai mengalami penurunan karena berkurangnya
jumlah sel-sel yang ada di dalam tubuh. Sebagai akibatnya, tubuh juga akan
mengalami penurunan fungsi secara perlahan-lahan. Itulah yang dikatakan proses
penuaan (Maryam dkk., 2008). Menua merupakan suatu proses menghilangnya
secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan
mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan
dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Dengan demikian tubuh secara
progresif akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi serta terjadi gangguan
metabolisme dan struktural yang disebut penyakit degeneratif (Martono, 2010).
Menurut Setiati dkk. (2010) seiring bertambahnya usia akan berakibat pada
semakin kecil kapasitas lansia untuk membawa dirinya ke keadaan homeostasis
setelah terjadinya suatu challenge (keadaan yang mengganggu homeostasis).
1

Proses menua (aging process) yang terjadi pada lansia secara linear dapat
digambarkan melalui empat tahap, yaitu kelemahan (impairment), keterbatasan
fungsional (functional limitations), ketidakmampuan (disability) dan
keterhambatan (handicap) yang akan dialami bersamaan dengan proses
kemunduran. Pada proses penuaan terjadi degenerasi jaringan serta sel-sel tubuh
yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Proses ini dimulai
sejak usia 30 tahun dan semakin meningkat pada usia 45 tahun ke atas. Biasanya
proses ini ditandai oleh kemunduran fisik, anatomi dan fungsional yang akan
mempengaruhi kemampuan tubuh secara keseluruhan (Hardinsyah, 2000).
Penuaan dapat mengakibatkan perubahan pada sistem organ yang spesifik,
diantaranya sistem saraf, sistem kardiovaskuler, sistem pernapasan, sistem
endokrin, sistem muskuloskeletal dan sistem genitourinaria. Perubahan ini terlihat
pada tabel 2.1 (Fauci dkk., 2008). Meskipun merupakan suatu proses fisiologis,
perubahan yang terlihat dari proses menua sangat bervariasi dan variabilitas ini
semakin meningkat seiring peningkatan usia. Variasi terjadi antara satu individu
dengan individu lain pada umur yang sama, antara satu sistem organ dengan
sistem organ lain, bahkan antara satu sel terhadap sel lain pada individu yang
sama (Setiati dkk., 2010).
2

Tabel 2.1 Beberapa perubahan fisiologi yang berhubungan dengan usia dan konsekuensinya
Organ/ SistemPerubahan fisiologi yang berhubungan dengan usia
Konsekuensinya
UmumPeningkatan lemak tubuh Penurunan air tubuh total
Peningkatan volume distribusi untuk obat yang larut lemak
Penurunan volume distribusi untuk obat yang larut air
Mata/Telinga Presbiopia Penurunan akomodasi
Kekeruhan lensaPeningkatan kerentanan cahaya terang
Penurunan ketajaman pendengaran terhadap suara berfrekuensi tinggi
Kesulitan membedakan kata bila lingkungan sekitar berisik
Endokrin Metabolisme glukosa tergangguPeningkatan kadar glukosa sebagai respon terhadap penyakit akut
Penurunan absorpsi dan aktivasi vitamin D
Osteopenia
RespirasiPenurunan elastisitas paru dan kekakuan dinding dada
Ketidaksepadanan ventilasi/perfusi
KardiovaskularPenurunan kelenturan arteri dan peningkatan TD sistolik
Respon hipotensi terhadap peningkatan denyut jantung, deplesi volume, hilangnya kontraksi atrium
Penurunan daya responsif terhadap β-adrenergik
Penurunan curah jantung dan respon denyut jantung terhadap stress
Renal Penurunan GFRGangguan ekskresi beberapa obat
Penurunan pemekatan/ pengenceran urin
Respon terlambat terhadap restriksi/ pembebanan kelebihan garam atau cairan, nokturia
Genitourinaria Atrofi mukosa vagina/ uretra Dispareuni, bakteriuriaPembesaran prostat Volume urin sisa
Muskuloskeletal Penurunan densitas tulang Osteopeniasistem saraf Atrofi serebri Keadaan mudah lupa
Penurunan sintesis katekolamin otak Depresi
Penurunan sistesis dopaminergik otak Cara jalan yang lebih kaku
Sumber: Fauci dkk., 2008
Berbagai penyakit yang terjadi pada lansia sangat erat kaitannya dengan
masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi berlebih. Hal ini disebabkan oleh
ketidaktahuan, isolasi sosial, hidup seorang diri, gangguan sosial, gangguan
3

mental, kemiskinan, gangguan nafsu makan, gangguan mengunyah, malabsorbsi,
obat-obatan, peningkatan kebutuhan gizi dan lain-lain (Martono, 2010).
2.2 Status Gizi
Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan refleksi dari makanan
yang dikonsumsi sehari-hari. Status gizi dikatakan baik jika pola makan yang
dikonsumsi seimbang. Artinya, jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi sesuai
dengan kebutuhan tubuh. Almatsier (2006) mendefinisikan status gizi sebagai
keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi.
Status gizi dapat diukur dari berat badan dan tinggi badan dengan perhitungan
Indeks Massa Tubuh (IMT) (WHO, 2004).
Makanan merupakan sumber tenaga untuk hidup. Makanan juga merupakan
sumber pembangun dan pertumbuhan serta mengganti bagian-bagian tubuh yang
rusak. Selain itu, makanan diperlukan untuk mengatur proses yang terjadi di
dalam tubuh. Masalah gizi timbul akibat ketidakseimbangan energi yang masuk
dengan energi yang dikeluarkan. Masalah ini sangat berkaitan dengan pola makan.
Pada lansia, terjadi perubahan pola makan yang diakibatkan oleh perubahan
fisiologis dan psikososial (Almatsier, 2004).
2.2.1 Kebutuhan gizi lansia
Pada prinsipnya jenis zat gizi yang dibutuhkan lansia sama seperti usia
muda, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air dan serat. Namun,
bertambahnya usia umumnya disertai dengan menurunnya fungsi organ.
Perubahan itu menyebabkan jumlah kebutuhan gizi pada lansia berubah.
Konsumsi makanan yang cukup dan seimbang akan bermanfaat bagi lansia untuk
mencegah dan mengurangi masalah gizi (Martono, 2010).
Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan suatu taraf asupan atau intake
yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang (Almatsier, 2004).
Departemen Kesehatan (2004) mengemukakan bahwa kecukupan gizi lansia pada
umumnya dihitung berdasarkan kebutuhan kalori atau energi, sebagai berikut:
a. Energi
AKG yang dianjurkan untuk lansia (>60 tahun) pada laki-laki adalah 2050
kalori dan pada wanita adalah 1600 kalori. Kebutuhan energi pada lansia menurun
4

sehubungan dengan penurunan metabolisme basal dan aktivitas fisik yang
cenderung menurun (Martono, 2010).
b. Protein
Kecukupan protein pada lansia adalah sekitar 0,8 gram/kgBB atau 15-25%
dari kebutuhan energi (Soejono, 2010). Jumlah protein yang dibutuhkan menurut
Depkes (2004) untuk lansia laki-laki adalah 60 gram/hari dan wanita 50
gram/hari.
c. Lemak
Lemak berlebih disimpan dalam tubuh sebagai cadangan tenaga dan bila
berlebihan akan ditimbun sebagai lemak tubuh. Lansia dianjurkan untuk
mengkonsumsi lemak tidak lebih dari 15% total energi (Depkes, 2004).
d. Karbohidrat
Karbohidrat merupakan sumber energi utama di dalam menu makanan
Indonesia. Lansia dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat komplek karena
mengandung vitamin, mineral dan juga serat daripada mengkonsumsi karbohidrat
murni seperti gula. Jumlah karbohidrat yang dikonsumsi lansia sebaiknya 55-60%
dari total energi (Stanley dan Patricia, 2006).
e. Vitamin, mineral, air dan serat
Lansia dianjurkan untuk meningkatkan konsumsi makanan vitamin A, D
dan E sebagai antioksidan untuk mencegah penyakit degeneratif. Selain itu,
konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C, B1 dan B12 serta asam
folat juga dianjurkan untuk mencegah penyakit anemia pada lansia (Martono,
2010).
Selain vitamin, lansia juga dianjurkan mengkonsumsi makanan kaya Fe, Zn,
selenium dan kalsium untuk mencegah anemia, pengeroposan tulang serta untuk
meningkatkan daya tahan tubuh. Disamping itu, zat gizi mikro lain seperti pospor,
kalium, natrium dan magnesium juga dibutuhkan untuk proses metabolisme dalam
tubuh (Depkes, 2004).
Air merupakan komponen utama yang paling banyak
terdapat di dalam tubuh manusia. Sekitar 60% dari total berat
badan orang dewasa terdiri dari air. Air sangat penting dalam proses
metabolisme dan mengeluarkan sisa pembakaran tubuh. Air dan serat juga
5

dianjurkan untuk lansia agar buang air besar menjadi lancar. Serat juga dapat
mencegah penyerapan kolesterol dalam tubuh sehingga dapat menurunkan
kolesterol dalam tubuh (Almatsier, 2004).
2.2.2 Pola makan dan menu lansia
Pola makan atau pola konsumsi pangan merupakan susunan jenis dan
jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu
tertentu (Baliwati, 2004). Santoso (2004) mengemukakan bahwa pola
makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran
mengenai macam dan jumlah makanan yang dimakan tiap hari
oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok
masyarakat tertentu.
Perubahan fisiologis pada lansia akan mempengaruhi pola
makan pada lansia. Pola makan lansia mencerminkan sikap dan
kebiasaan selama hidupnya yang dipengaruhi oleh lingkungan.
Makanan pokok di Indonesia yaitu nasi, dikonsumsi hampir
semua orang di Indonesia (95%), termasuk lansia. Nasi
dikonsumsi berdampingan dengan sumber zat gizi lain seperti
protein dan lemak (Darmojo, 2002).
Pola makan masyarakat di Indonesia pada umumnya
diwarnai oleh jenis-jenis bahan makanan yang umum dan
diproduksi di wilayah tersebut. Daerah pegunungan dan
pertanian, masyarakatnya banyak mengkonsumsi sayuran
karena sayuran mudah didapat di wilayah tersebut. Masyarakat
nelayan di daerah pantai seperti halnya di Aceh, ikan merupakan
makanan sehari-hari yang dipilih karena dapat dihasilkan sendiri
(Gunawan, 2002).
Setiap budaya mempunyai keyakinan dan cara sendiri
dalam memperoleh, mengolah dan menyajikan makanan. Hal
tersebut akan terpola dan menjadi kebiasaan suatu kelompok
masyarakat. Lansia pada umumnya lebih menyukai makanan
6

yang berkaitan dengan pengalaman yang menyenangkan atau
berhubungan dengan rumah atau daerah asal (Gunawan, 2002).
Ahli gizi menganjurkan untuk menu lansia yang sehat,
menu sehari-hari adalah (Arisman, 2009):
Tidak berlebihan, tetapi cukup mengandung zat gizi sesuai dengan
persyaratan kebutuhan lansia
Bervariasi jenis makanan dan cara olahnya
Membatasi konsumsi lemak
Membatasi konsumsi gula
Menghindari konsumsi garam yang terlalu banyak, merokok dan minuman
beralkohol
Cukup banyak mengkonsumsi makanan berserat (buah-buahan, sayuran
dan sereal) untuk menghindari sembelit atau konstipasi
Minuman yang cukup
Susunan makanan sehari-hari untuk lansia hendaknya tidak terlalu banyak
menyimpang dari kebiasaan makanan serta disesuaikan dengan keadaan
psikologisnya. Pola makan disesuaikan dengan kecukupan gizi yang dianjurkan
dan menu makanannya disesuaikan dengan ketersediaan dan kebiasaan makan tiap
daerah. Menu makanan lansia dalam sehari dapat disusun berdasarkan konsep gizi
seimbang, sebagai contoh:
Kelompok makanan pokok (utama): nasi (1 porsi= 200 gram)
Kelompok lauk pauk: daging (1 potong= 50 gram), tahu (1 potong= 25
gram)
Kelompok sayuran: bayam (1 mangkok= 100 gr)
Kelompok buah-buahan: pepaya (1 potong= 100 gr)
Susu (1 gelas= 100 gr)
2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi lansia
a. Umur
Pada masa pertumbuhan (bayi, anak-anak dan remaja), semua kebutuhan zat
gizi tinggi. Makin tua seseorang, kebutuhan kalori (lemak dan karbohidrat) akan
menurun. Namun, kebutuhan protein vitamin dan mineral cukup tinggi sebagai
7

antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas yang dapat merusak
sel (Martono, 2010).
b. Jenis kelamin
Umumnya laki-laki memerlukan zat gizi yang lebih banyak karena
perbedaan postur, otot dan luas permukaan tubuh dibandingkan dengan wanita. Di
Indonesia, prevalensi gizi lebih orang dewasa terbesar terjadi pada perempuan
yaitu sebesar 26,1% sedangkan laki-laki sebesar 15,6% (Riskesdas, 2010).
c. Aktivitas fisik dan mental
Orang yang melakukan aktivitas fisik memerlukan zat gizi yang lebih
banyak dibandingkan dengan orang yang hanya duduk atau tidur. Kecukupan gizi
seseorang akan sangat tergantung dari pekerjaan sehari-hari. Semakin berat kerja
seseorang, semakin besar zat gizi yang dibutuhkan. Walaupun aktivitas fisik lebih
banyak membutuhkan zat gizi daripada aktivitas mental namun stress
berkepanjangan dapat mengganggu proses metabolisme tubuh. Aktivitas akan
meningkatkan nafsu makan sehingga intake makanan bertambah. Selain itu
aktivitas juga memperlancar peredaran darah sehingga menigkatkan absorpsi zat-
zat makanan (Rusilanti, 2006).
d. Pendidikan dan pengetahuan gizi
Tingkat pendidikan yang tinggi akan mempermudah seseorang untuk
mendapatkan pengetahuan dan informasi khususnya tentang makanan yang baik
untuk kesehatan. Pendidikan yang baik serta pengetahuan yang memadai
merupakan modal seseorang termasuk lansia dalam mempertimbangkan pemilihan
makanan bukan saja berdasarkan selera tetapi juga pemenuhan kebutuhan gizi
(Adianto, 2003).
e. Status ekonomi
Pendapatan seseorang menentukan pola makan. Pendapatan merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas serta kuantitas
makanan. Disisi lain, kemajuan di bidang ekonomi dapat mempengaruhi pola
konsumsi. Proporsi konsumsi sumber energi dari karbohidrat dapat berkurang
akan tetapi proporsi sumber energi dari lemak dan protein akan meningkat
sehingga apabila tidak terkontrol akan menimbulkan masalah gizi (Adianto,
2003).
8

2.2.4 Masalah gizi pada lansia
Masalah gizi yang umum terjadi pada lansia selain kekurangan gizi juga
kelebihan gizi yang memacu timbulnya penyakit degeneratif seperti penyakit
jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, reumatik, ginjal, sirosis hati dan
kanker (Supariasa, Bakri dan Fajar, 2012). Dengan meningkatkan status gizi pada
lansia diharapkan keadaan kesehatan dapat dipertahankan atau bahkan
ditingkatkan.
a. Kekurangan gizi (Undernutrition)
Kekurangan gizi pada lansia dapat terjadi karena konsumsi energi dari
makanan lebih rendah dari pada kebutuhan tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan
energi maka tubuh akan memecah cadangan lemak menjadi energi. Pemecahan
lemak akan diikuti dengan penurunan berat badan dan apabila kekurangan
konsumsi energi berlangsung lama maka akan mengakibatkan terjadinya kurang
energi kronis (Gibney dkk., 2009).
Faktor lain yang berperan terhadap terjadinya kekurangan gizi pada lansia
adalah terjadinya proses menua pada sistem pencernaan seperti gigi geligi yang
mulai banyak tanggal dan kerusakan gusi menyebabkan lansia merasa sukar untuk
makan makanan yang berkonsistensi keras. Disamping itu, pada lansia juga terjadi
penurunan produksi enzim ptyalin dari kelenjar saliva yang akan berpengaruh
pada proses perubahan karbohidrat kompleks menjadi disakarida serta
berkurangnya fungsi ludah sebagai pelicin makanan sehingga proses menelan
lebih sukar. Sekresi asam lambung juga semakin berkurang dan ukurannya
menjadi lebih kecil sehingga rangsang rasa lapar serta daya tampung makanan
semakin berkurang (Fauci dkk., 2008).
b. Kelebihan gizi (Overnutrition)
Pada lansia, kebutuhan energi menurun sehubungan dengan terjadinya
penurunan metabolisme basal dan aktivitas fisik. Proses metabolisme yang
menurun pada lansia tanpa diimbangi dengan peningkatan aktivitas fisik atau
penurunan jumlah makanan menyebabkan terjadinya kelebihan energi. Kelebihan
energi ini akan diubah menjadi lemak dan disimpan di dalam jaringan adipose
sebagai cadangan energi dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen di dalam
hati dan jaringan otot. Cadangan energi dalam bentuk lemak yang berlebihan akan
9

ditimbun di dalam tubuh terutama di dalam rongga perut, lengan, paha dan organ-
organ lainnya. Terjadinya penimbunan lemak ini disebut sebagai kelebihan berat
badan (overweight) ataupun obesitas (Gibney dkk., 2009).
Kelebihan berat badan dan obesitas pada seseorang merupakan masalah gizi
yang serius karena dapat memicu timbulnya penyakit degeneratif seperti diabetes
mellitus, hipertensi, ginjal, sirosis hati dan kanker (Supariasa, Bakri dan Fajar,
2012). WHO (2005) juga menyebutkan bahwa terjadi peningkatan angka
mortalitas pada seseorang yang mengalami overweight yang diukur dengan skala
IMT.
Secara umum masalah kelebihan dan kekurangan gizi pada orang dewasa
khususnya lansia merupakan masalah penting karena selain mempunyai risiko
penyakit-penyakit tertentu juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh
karena itu pemantauan keadaan tersebut perlu dilakukan oleh setiap orang secara
berkesinambungan (Martono, 2010).
Berat badan kurang dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit infeksi
sedangkan berat badan lebih akan meningkatkan risiko terhadap penyakit
degeneratif. Oleh karena itu, mempertahankan berat badan normal memungkinkan
seseorang untuk dapat mencapai usia harapan hidup lebih panjang (Supariasa,
Bakri dan Fajar, 2012).
2.2.5 Penilaian status gizi
Status gizi dapat diukur secara tidak langsung dan secara langsung.
Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi tiga yaitu survei
konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. Penilaian status gizi secara
langsung dapat dibagi manjadi empat penilaian yaitu klinis, biokimia, biofisik dan
antropometri (Supariasa, Bakri dan Fajar, 2012).
Pengukuran antropometri digunakan secara luas dalam penilaian status gizi,
terutama jika terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan energi dengan protein.
Antropometri lebih banyak digunakan karena lebih praktis dan mudah untuk
dilakukan (Perissinotto dkk., 2002). Pengukuran antropometri merupakan
pengukuran dimensi fisis dan komposisi tubuh yang bertujuan untuk screening
atau tapis gizi, survei gizi dan pemantauan status gizi. Indeks antropometri yang
10

sering digunakan yaitu berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan IMT
(Supariasa, Bakri dan Fajar, 2012).
Indeks massa tubuh (IMT)
Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan salah satu alat untuk memantau
status gizi orang dewasa, khusus yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan
berat badan. Nilai indeks diperoleh dengan perhitungan berat badan dalam
kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan (Depkes RI,
2004).
IMT = BB(Kg)TB2(m2)
Keterangan :
BB : Berat badan (Kg)TB : Tinggi badan (m)
IMT merupakan pengukuran yang paling mudah dan paling banyak
digunakan untuk mengidentifikasi seorang lansia yang memiliki risiko
kekurangan atau kelebihan gizi (Perissonotto dkk., 2002).
Tabel 2.2 Klasifikasi status gizi pada orang dewasa berdasarkan IMT menurut kriteria WHO tahun 2004
Klasifikasi IMT (kg/m2)
Underweight < 18,50
Normoweight 18,50 - 24,99
Pre-obese 25,00 - 29,99
Obese ≥ 30,00
DAFTAR PUSTAKA
Adianto, S. 2003. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Asupan Gizi dan Status Gizi Lansia di Panti Wredha Pucang Gading Semarang. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
Almatsier. 2006. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Baliwati Y.F; A. Khomsan dan C.W. Dwiriani. 2004. Pengantar Pangan dan Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya.
11

Darmojo, B.R. 2002. Trends in Dietary of the Elderly : The Indonesian Case. Asia Pacific J Clin Nutr (11): S351-S354.
Departemen Kesehatan RI. 2004. Tabel Angka Kecukupan Gizi bagi Orang Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat.
Fauci, A.S. 2008. Harrison’s Principle of Internal Medicine 17th ed. USA: The McGraw-Hill.
Gibney, M. J. dkk,. 2009. Gizi Kesehatan Masyarakat. Jakarta: EGC.
Gunawan, R. 2002. Makanan Dalam Perspektif Budaya. Nursing Journal of Padjadjaran University. 4(7), 55-60.
Hardiansyah. 2000. Pengaruh Gizi terhadap Lanjut Usia. Bogor: Pergizi Pangan Indonesia.
Martono, H. H. dan Kris P. 2010. Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut) Ed. 4. Jakarta: Balai Penerbit Universitas Indonesia.
Maryam, Siti; Mia F. E; Rosidawati; Ahmad J; dan Irwan B. 2008. Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya. Jakarta: Salemba Medika.
Nugroho, W. 2000. Keperawatan Gerontik. Jakarta: EGC.
Perissinotto, E; Pisent, C; Sergi, G; Grigoletto, F. dan Enzi, G. 2002. Anthropometric Measurement in the Elderly : Age and Gender Differences. British Journal of Nutrition (2002), 87, 177–186.
Riset Kesehatan Dasar. 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Rusilanti, dan Clara M.K. 2006. Model Hubungan dan Aspek Psikososial dan Aktifitas Fisik dengan Status Gizi Lansia. Jurnal Gizi dan Pangan. 1(1) : 29-35.
Santoso, S. dan Ranti, L.A. 2004. Kesehatan dan Gizi. Jakarta: Rineka Cipta.
Setiati, S; Harimurti, K. dan Roosheroe, A.G. 2010. Proses Menua dan Implikasi Kliniknya. Dalam: Sudoyo, A.W. dkk. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Soejono, C.H. 2010. Pengkajian Paripurna pada Pasien Geriatri. Dalam: Sudoyo, A.W. dkk. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Stanley, M. dan Patricia, G.B. 2006. Buku Ajar Keperawatan Gerontik. Jakarta: EGC.
Supariasa, I.D.N; Bachyar B. dan Ibnu F. 2012. Penilaian Status Gizi Edisi Revisi. Jakarta: EGC.
12

13