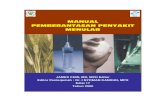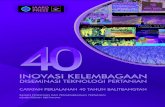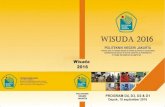ISI PBAM23
-
Upload
wahyuni-harliyanti -
Category
Documents
-
view
286 -
download
1
Transcript of ISI PBAM23
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Air merupakan unsur esensial yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Sebagian besar organisme hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang singkat tanpa air. Kenyataan ini mengakibatkan perkembangan hubungan secara langsung antara melimpahnya air, kepadatan populasi, dan kualitas hidup. Walaupun melimpahnya ketersediaan, air yang tersedia harus memiliki karakteristik tertentu. Kualitas air didefinisikan dalam istilah karakteristik air. Sepanjang sejarah, karakteristik air yang paling penting adalah konsentrasi padatan terlarut (garam), karena adanya hubungan antara garam dan produktifitas lahan. Karena kepadatan populasi meningkat, karakteristik air yang berhubungan dengan kesehatan, seperti adanya mikroorganisme penyebab penyakit (patogen), menjadi lebih penting. Dengan perkembangan industri, karakteristik air seperti suhu (dari air pendingin) dan kandungan ion tertentu mulai diperhatikan. Baru-baru ini, pengenalan zat kimia antropogenik yang memiliki dampak pada kesehatan ketika berada pada jumlah yang sangat kecil telah menjadi suatu masalah. Dua dari perhatian utama dalam pengembangan sumber daya air, tanpa memperhatikan kegunaannya, adalah kuantitas dan kualitas. Dalam keterbatasannya, kuantitas air menjadi lebih penting bila dibandingkan dengan kualitasnya. Kuantitas dan kualitas air diperlukan dalam berbagai kegunaan, karena setiap kegunaan air memiliki sebuah pembatas individual, yang merupakan definisi mutlak kualitas air yang membedakan dengan peruntukan air lainnya. Contohnya seperti air kelas C yang peruntukannya sebagai air irigasi pertanian akan memiliki kualitas berbeda yang merupakan pembatas individualnya dengan air kelas A sebagai air baku air minum dan air kelas B sebagai air untuk budidaya perikanan. Melihat kondisi di atas, tentu saja akan diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang secara jelas mengatur ketersediaan air yang memenuhi
kriteria standar secara kualitas dan kuantitas. Melalui rangkaian kegiatan percobaan terhadap air baku waduk Benanga Lempake, Samarinda Utara yang dilakukan kelompok kami, kami merencanakan dan merancang bangunan pengolah air baku dari waduk tersebut sehingga menjadi air bersih yang dapat dikonsumsi masyarakat. 1.2 Tujuan Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain: Mengetahui karakteristik kekeruhan air baku sampel Waduk
Benanga Lempake, Samarinda Utara. Merencanakan desain pengolahan air minum yang sesuai dengan
karakteristik air baku sampel Waduk Benanga Lempake, Samarinda Utara.
1. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Sedimentasi Sedimentasi adalah pemisahan solid-liquid menggunakan pengendapan
secara gravitasi untuk menyisihkan suspended solid. Pada umumnya, sedimentasi digunakan pada pengolahan air minum, pengolahan air limbah, dan pada pengolahan air limbah tingkat lanjutan. Unit sedimentasi merupakan peralatan yang berfungsi untuk memisahkan solid dan liquid dari suspensi untuk menghasilkan air yang lebih jernih dan konsentrasi lumpur yang lebih kental melalui pengendapan secara gravitasi. Secara keseluruhan, fungsi unit sedimentasi dalam instalasi pengolahan adalah: a. Mengurangi beban kerja unit filtrasi dan memperpanjang umur pemakaian unit penyaring selanjutnya; b. Mengurangi biaya operasi instalasi pengolahan. Pada pengolahan air minum, penerapan sedimentasi khususnya untuk:1. Pengendapan air permukaan, khususnya untuk pengolahan dengan filter
pasir cepat. 2. Pengendapan flok hasil koagulasi-flokulasi, khususnya sebelum disaring dengan filter pasir cepat. 3. Pengendapan flok hasil penurunan kesadahan menggunakan soda kapur. 4. Pengendapan lumpur pada penyisihan besi dan mangan. Bak sedimentasi umumnya dibangun dari bahan beton bertulang dengan bentuk lingkaran, bujur sangkar, atau segi empat. Bak berbentuk lingkaran umumnya berdiameter 10,7 hingga 45,7 meter dan kedalaman 3 hingga 4,3 meter. Bak berbentuk bujur sangkar umumnya mempunyai lebar 10 hingga 70 meter dan kedalaman 1,8 hingga 5,8 meter. Bak berbentuk segi empat umumnya mempunyai lebar 1,5 hingg 6 meter, panjang bak sampai 76 meter, dan kedalaman lebih dari 1,8 meter.
Klasifikasi
sedimentasi
didasarkan
pada
konsentrasi
partikel
dan
kemampuan partikel untuk berinteraksi. Klasifikasi ini dapat dibagi ke dalam empat tipe, antara lain :1) Settling tipe I : Merupakan pengendapan partikel tanpa menggunakan
koagulan. Pengendapan partikel diskrit, partikel mengendap secara individual dan tidak ada interaksi antar partikel. Tujuan dari unit ini adalah menurunkan kekeruhan air baku dan digunakan pada grit chamber. Dalam perhitungan dimensi efektif bak, faktor-faktor yang mempengaruhi performance bak seperti turbulensi pada inlet dan outlet, pusaran arus lokal, pengumpulan lumpur, besar nilai G sehubungan dengan penggunaan perlengkapan penyisihan lumpur dan faktor lain diabaikan untuk menghitung performance bak yang lebih sering disebut dengan ideal settling basin.2) Settling tipe II : Pengendapan material koloid dan solid tersuspensi
terjadi melalui adanya penambahan koagulan, biasanya digunakan untuk mengendapkan flok-flok kimia setelah proses koagulasi dan flokulasi. Pengendapan partikel flokulen, terjadi interaksi antarpartikel sehingga ukuran meningkat dan kecepatan pengendapan bertambah. Pengendapan partikel flokulen akan lebih efisien pada ketinggian bak yang relatif kecil. Karena tidak memungkinkan untuk membuat bak yang luas dengan ketinggian minimum, atau membagi ketinggian bak menjadi beberapa kompartemen, maka alternatif terbaik untuk meningkatkan efisiensi pengendapan bak adalah dengan memasang tube settler pada bagian atas bak pengendapan untuk menahan flokflok yang terbentuk. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efisiensi bak pengendapan adalah: Luas bidang pengendapan; Penggunaan baffle pada bak sedimentasi; Mendangkalkan bak; Pemasangan plat miring.3) Settling tipe III : Merupakan pengendapan dengan konsentrasi koloid
dan partikel tersuspensi adalah sedang, di mana partikel saling berdekatan sehingga gaya antar pertikel menghalangi pengendapan paertikel-paertikel di sebelahnya. Partikel berada pada posisi yang
relatif tetap satu sama lain dan semuanya mengendap pada suatu kecepatan yang konstan. Hal ini mengakibatkan massa pertikel mengendap sebagai suatu zona, dan menimbulkan suatu permukaan kontak antara solid dan liquid. Jenis sedimentasi yang umum digunakan pada pengolahan air bersih adalah sedimentasi tipe satu dan dua, sedangkan jenis ketiga lebih umum digunakan pada pengolahan air buangan. pengendapan pada lumpur biologis, dimana gaya antarpartikel saling menahan partikel lainnya untuk mengendap. 4) Settling tipe IV : terjadi pemampatan partikel yang telah mengendap yang terjadi karena berat partikel. 2.2 Koagulasi Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Mekanisme koagulasi terjadi melalui dua cara, antara lain: 1. Secara fisika koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti :
Pemanasan, kenaikan suhu sistem koloid menyebabkan tumbukan antar partikel-partikel sol dengan molekul-molekul air bertambah banyak. Hal ini melepaskan elektrolit yang teradsorpsi pada permukaan koloid. Akibatnya partikel tidak bermuatan. contoh: darah
Pengadukan, contoh: tepung kanji Pendinginan, contoh: agar-agar
2.
Secara kimia, seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan penambahan zat kimia koagulan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan koloid bersifat netral, yaitu:
Menggunakan Prinsip Elektroforesis. Proses elektroforesis adalah pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan ke elektrode dengan muatan yang berlawanan. Ketika partikel ini mencapai elektrode, maka sistem koloid akan kehilangan muatannya dan bersifat netral.
Penambahan koloid, dapat terjadi sebagai berikut: Koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif (kation), sedangkan koloid
yang bermuatan positif akan menarik ion negatif (anion). Ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi koagulasi. Makin besar muatan ion makin kuat daya tariknya dengan partikel koloid, sehingga makin cepat terjadi koagulasi.
Penambahan Elektrolit. Jika suatu elektrolit ditambahkan pada sistem koloid, maka partikel koloid yang bermuatan negatif akan mengadsorpsi koloid dengan muatan positif (kation) dari elektrolit. Begitu juga sebaliknya, partikel positif akan mengadsorpsi partikel negatif (anion) dari elektrolit. Dari adsorpsi diatas, maka terjadi koagulasi. Dalam proses koagulasi,stabilitas koloid sangat berpengaruh.stabilitas merupakan daya tolak koloid karena partikelpartikel mempunyai muatan permukaan sejenis (negatif). Beberapa gaya yang menyebabkan stabilitas partikel, yaitu:
Gaya elektrostatik yaitu gaya tolak menolak tejadi jika partikelpartikel mempunyai muatan yang sejenis. Bergabung dengan molekul air (reaksi hidrasi) Stabilisasi yang disebabkan oleh molekul besar yang diadsorpsi pada permukaan.
Suspensi atau koloid bisa dikatan stabil jika semua gaya tolak menolak antar partikel lebih besar dari ada gaya tarik massa, sehingga dalam waktu tertentu tidak terjadi agregasi. Untuk menghilangkan kondisi stabil, harus merubah gaya interaksi antara partikel dengan pembubuhan zat kimia supaya gaya tarik menarik lebih besar. Untuk destabilisasi ada beberapa mekanisme yang berbeda: 1) Kompresi lapisan ganda listrik dengan muatan yang berlawanan. 2) Mengurangi potensial permukaan yang disebabkan oleh adsorpsi molekul yang spesifik dengan muatan elektrostatik berlawanan. 3) Adsorpsi molekul organik diatas permukaan partikel bisa membentuk jembatan moleku diantara partikel. 4) Penggabungan partikel koloid kedalam senyawa presipitasi yang terbentuk dari koagulan.
2.3
Filtrasi Filtrasi adalah operasi dimana campuran yang heterogen antara fluida dan
partikel-partikel padatan dipisahkan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel-partikel padatan. Apabila air olahan yang akan difiltrasi berupa cairan yang mengandung butiran halus atau bahan-bahan yang larut, sebelum proses penyaringan sebaiknya dilakukan proses koagulasi atau netralisasi yang menghasilkan endapan. Dengan demikian, bahan-bahan tersebut dapat dipisahkan dari cairan melalui filtrasi. Apabila air olahan mempunyai padatan dengan ukuran seragam, saringan yang digunakan adalah single medium. Sebaliknya, bila ukuran padatan beragam, digunakan saringan dual medium atau three medium. Penyaringan air olahan yang mengandung padatan beragam dari ukuran besar sampai kecil/halus. Penyaringan dilakukan dengan cara membuat saringan bertingkat, yaitu saringan kasar, saringan sedang, sampai saringan halus. Untuk merancang sistem penyaringan ini, perlu adanya penelitian terlebih dahulu mengenai beberapa faktor berikut : a) Jenis limbah padat (terapung atau tenggelam).b) Ukuran padatan: ukuran yang terkecil dan ukuran yang terbesar. c) Perbandingan ukuran kotoran padatan besar dan kecil.
d) Debit air olahan yang akan diolah. Bentuk dan jenis saringan bermacam-macam. Penyaringan bahan padatan kasar menggunakan saringan berukuran 5 20 mm, sedangkan padatan yang halus (hiperfiltrasi) dapat menggunakan saringan yang lebih halus lagi. Saringan ini diusahakan mudah diangkat dan dibersihkan. Bahan untuk penyaringan kasar dapat terbuat dari logam tahan karat seperti stainless steel, kawat tembaga, batu kerikil, batubara, karbon aktif (arang batok kelapa). Penyaringan untuk padatan yang halus dapat menggunakan kain poliester atau pasir. Jenis saringan yang biasa digunakan adalah saringan bergetar, bar screen racks, dan bak penyaringan pasir lambat. Jenis saringan yang banyak digunakan
adalah saringan bak pasir dan batuan. Saringan pasir menggunakan batu kerikil dan pasir. Pasir yang baik untuk penyaringan adalah pasir kuarsa. Jenis saringan menurut konstruksinya dibedakan menjadi saringan miring, saringan pembawa, saringan sentrifugal, dan drum berputar. Kecepatan penyaringan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: filtrasi lambat (0,2 2 liter/menit/ft2), filtrasi cepat (4 8 liter/menit/ft2), dan filtrasi sangat cepat (12 60 liter/menit/ft2). Menurut tipenya, saringan dibedakan menjadi tiga, antara lain:a) Single medium: saringan untuk menyaring air yang mengandung padatan
dengan ukuran seragam.b) Dual medium: saringan untuk menyaring air limbah yang didominasi oleh
dua ukuran padatan.c) Three medium: saringan untuk menyaring air limbah yang mengandung
padatan dengan ukuran beragam. Ukuran pasir menurut klasifikasi USDA (1938) dibagi menjadi: 1) Pasir sangat kasar (very coarse sand): 2,0 1,0 mm 2) Pasir kasar (coarse sand): 1,0 0,5 mm3) Pasir sedang (medium sand): 0,5 0,25 mm
4) Pasir halus (fine sand): 0,25 0,1 mm 5) Pasir sangat halus (very fine sand): 0,1 0,05 mm Sistem aliran air olahan dalam sistem filtrasi terdiri dari beberapa macam. Penentuan aliran ini memperhatikan sifat dari limbah padat yang akan difiltrasi. Sistem aliran tersebut dibagi menjadi empat sistem, yaitu aliran horizontal (horizontal filtration), aliran gravitasi (gravity filtration), aliran dari bawah ke atas (upflow filtration), dan aliran ganda (biflow filtration).
2.4
Desinfeksi Desinfeksi adalah istilah yang berarti penghancuran organisme penyebab
penyakit tertentu. Penghancuran secara keseluruhan disebut sterilisasi. Desinfeksi dalam pengolahan air dan air limbah melibatkan pemaparan organisme penyebab
penyakit dengan sejumlah bahan pembunuh. Metode dan alat yang telah digunakan untuk desinfeksi terdiri dari: 1) Penambahan zat kimia 2) Penerapan agen fisik seperti tekanan dan cahaya 3) Alat mekanis4) Pemaparan dengan radiasi elektromagnetik, akustik, dan partikel.
Penambahan dengan agen kimia merupakan metode umum yang digunakan di seluruh dunia. Metode umum yang digunakan antara lain pemberian gas klorin (Cl2). Sayangnya, penggunaan klorin dapat menghasilkan komponen karsinogenik seperti trihalometan dan kloroform, yang merupakan kelemahan terbesarnya. Di negara-negara Eropa, klorinasi air limbah tidak diterapkan karena kemungkinan terbentuknya hidrokarbon terklorinasi. Dua bentuk halogen lainnya, bromin dan iodin, adalah desinfektan yang cukup baik, namun biaya dan tingkat kesulitan penerapannya yang cukup tinggi telah menghambat penggunaannya secara luas. Ozon digunakan sebagai desinfektan primer di beberapa negara, namun masalah keamanan dan kesehatan yang ditimbulkannya telah membatasi penggunaannya. Ozon memiliki kelemahan karena tidak meninggalkan sisa konsentrasi untuk mencegah reinfeksi pada air yang telah didesinfeksi.
BAB III METODOLOGI PERCOBAAN
3.1 Waktu dan Tempat 3.1.1 Praktikum Settling Coloum Tipe I Hari / Tanggal : Rabu, 27 April 2011 Tempat Waktu : Workshop Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman : 08.00 12.00 WITA
3.1.2 Praktikum Jar Test Hari / Tanggal : Jumat, 13 Mei 2011 Tempat Waktu : Laboratorium Lingkungan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman : 08.00 12.00 WITA 3.1.3 Praktikum Settling Coloum Tipe II Hari / Tanggal : Jumat, 20 Mei 2011 Tempat Waktu 3.2 Alat dan Bahan 3.2.1 Praktikum Settling Coloum Tipe I Alat : a. Settling Coloum setinggi 2 m b. Turbidity meter c. Stopwatch / jam d. Jirigen e. Bekas kemasan air mineral Bahan : a. Sampel air berupa 20 Liter air waduk b. Air mineral : Workshop Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman : 08.00 12.00 WITA
3.2.2 Praktikum Jar Test Alat : a. 4 buah beker glass 800 mL b. 1 buah beker glass 50 mL c. 1 buah pipet tetes d. Peralatan Jar test e. 4 buah kerucut imhoff f. pH meter g. Turbidity meter h. Jirigen Bahan : a. Sampel air berupa 4 liter air waduk b. Tawas c. Aquades 3.2.3 Praktikum Settling Coloum Tipe II Alat : a. Settling Coloum setinggi 1,5 meter b. Turbidity meter c. Neraca Ohauss d. 1 buah labu Erlenmeyer 1000 mL e. Pengaduk f. Bekas kemasan air mineral g. Jirigen Bahan : a. Sampel air berupa 125 Liter air waduk b. Tawas c. Air mineral
3.3 Prosedur Praktikum
3.3.1
Praktikum Settling Coloum Tipe I1. Disiapkan alat dan bahan berupa settling coloum setinggi 2 meter,
turbidity meter, stopwatch / jam, jirigen, bekas kemasan air mineral, 20 liter air waduk, dan air mineral. 2. Dihomogenkan terlebih dahulu 20 liter air waduk yang berada dalam jirigen. 3. Kemudian air waduk sebanyak 20 liter yang telah dihomogenkan ditumpahkan ke dalam settling coloum setinggi 2 meter sampai batas tertinggi alat. 4. Air didiamkan terlebih dahulu dalam settling coloum, kemudian air diambil pada 5 menit pertama dan diletakkan dalam bekas kemasan air mineral. 5. Diambil botol turbidity yang telah dibersihkan dengan air mineral dan dilap dengan tissue, kemudian dimasukkan air yang telah diambil tadi ke dalam botol turbidity. 6. Kemudian botol turbidity yang telah berisi sampel air tersebut dimasukkan ke dalam alat turbidity meter yang telah dikalibrasi. 7. Ditekan tombol on pada turbidity meter, kemudian dibiarkan turbidity meter membaca besar kekeruhan sampel air. 8. Dicatat besarnya kadar kekeruhan yang tercatat pada alat turbidity meter tersebut dalam satuan NTU ( Nephelometric Turbidity Unit). 9. Diulangi prosedur di atas untuk setiap interval 5 menit selanjutnya hingga waktu 25 menit. 3.3.1 Praktikum Jar Test 1. Disiapkan alat dan bahan berupa 4 buah beker glass 800 mL, 1 buah beker glass 50 mL, 1 buah pipet tetes, peralatan jar test, 4 buah kerucut imhoff, pH meter, turbidity meter, jirigen, 4 liter air waduk, tawas, dan aquades. 2. Dihomogenkan terlebih dahulu 3 liter sampel air yang berada dalam jirigen.
3. Kemudian sampel air tersebut dimasukkan ke dalam 4 buah beker glass 800 mL sebanyak 700 mL pada setiap beker glass. 4. Diukur pH sampel air tersebut dengan menggunakan pH universal dan diukur pula kekeruhannya dengan turbidity meter. 5. Dipipet sebanyak 10 mL, 20 mL, 30 mL, dan 40 mL tawas yang telah dilarutkan dengan aquades 6. Kemudian dimasukkan 10 mL tawas ke dalam beker glass pertama, 20 mL tawas ke dalam beker glass kedua, 30 mL tawas ke dalam beker glass ketiga, dan 40 mL tawas ke dalam beker glass keempat. Untuk membedakan, setiap beker glass diberi label. 7. Diletakkan keempat beker glass tersebut dalam peralatan jar test. 8. Ditekan tombol on, kemudian diatur setiap kecepatan dan lama waktunya. a. Diaduk cepat 80 100 rpm selama 1 menit b. Diaduk sedang 40 rpm selama 5 10 menit c. Diaduk lambat 20 rpm selama 1 menit 1. Setelah selesai dalam peralatan jar test, sampel dalam keempat beker glass tersebut ditumpahkan secara serentak ke dalam 4 buah kerucut imhoff. Untuk membedakan keempat kerucut imhoff tersebut juga diberi label. 2. Air dalam kerucut imhoff tersbut didiamkan kemudian dalam setiap interval waktu tertentu dicatat ketinggian endapan floknya. 3. Setelah itu diukur kembali pH sampel air tersebut dengan pH universal dan kekeruhannya dengan menggunakan turbidity meter. 4. Dari hasil catatan ketinggian endapan flok pada setiap kerucut imhoff dapat ditentukan dosis optimum koagulan yang diperlukan dalam praktikum settling coloum tipe II selanjutnya.
3.3.1
Praktikum Settling Coloum Tipe II1. Disiapkan alat dan bahan berupa settling Coloum setinggi 1,5
meter, turbidity meter, neraca Ohauss, 1 buah labu Erlenmeyer
1000 mL, pengaduk, bekas kemasan air mineral, jirigen, 125 liter air waduk, tawas, dan air mineral. 2. Dihomogenkan terlebih dahulu sampel air tersebut. 3. Ditimbang 10 gram tawas dengan menggunakan neraca ohauss 4. Dicampurkan 10 gram tawas tersebut dengan air mineral hingga volume 1000 mL dalam labu Erlenmeyer kemudian diaduk dengan menggunakan pengaduk agar tawas larut. 5. Kemudian larutan tawas tersebut dicampurkan ke dalam sampel air yang telah dihomogenkan sesuai dengan perhitungan dosis optimum pada praktikum jar test sebelumnya. 6. Kemudian ditumpahkan seluruh sampel air yang telah dicampur dengan larutan tawas ke dalam settling coloum setinggi 2 meter hingga batas paling tinggi alat tersebut. 7. Sampel air dalam settling coloum tersebut didiamkan terlebih dahulu, kemudian pada interval 10 menit pertama diambil sampel air tersebut. 8. Saat sampel air diambil 5 keran air harus dibuka secara serentak dan kemudian sampel air tersebut diletakkan dalam kemasan bekas air mineral. 9. Diambil botol turbidity yang telah dibersihkan dengan air mineral dan dilap dengan tissue. 10. Dimasukkan setiap sampel air yang telah diambil ke dalam botol turbidity. 11. Diletakkan botol turbidity tersebut di dalam alat turbidity meter yang telah dikalibrasi, kemudian ditekan tombol on, dan dibiarkan turbidity meter tersebut membaca besar kadar kekeruhan sampel air tersebut. 12. Dicatat besar kadar kelarutan yang tercatat pada alat turbidity meter tersebut untuk setiap sampel airnya. 13. Diulangi prosedur 7-12 untuk interval 10 menit selanjutnya hingga menit ke 60.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pengamatan Tabel nilai kekeruhan tiap waktu untuk perhitungan sedimentasi tipe I Nilai Kekeruhan (NTU) Waktu Pengambilan Sampel Mula-mula 5 menit 10 menit 15 menit 20 menit 25 menit 30 menit I 8,63 4,20 3,30 3,28 3,10 3,07 2,74 II 4,87 3,68 3,15 2,71 2,76 2,18 2,41 III 4,95 3,68 3,22 2,57 2,35 2,55 2,20 Rata-rata 6,15 3,853 3,223 2,853 2,736 2,6 2,45
Tabel nilai kekeruhan untuk perhitungan bak koagulasi Nilai Kekeruhan (NTU) Sebelum diberi tawas 1 2 3 11,16 11,74 11,25 Rata-rata = 11,38 Sesudah diberi tawas 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 11,64 6,17 9,68 8,79
Tabel nilai pH untuk perhitungan bak koagulasi Nilai pH Sebelum diberi tawas pH= 6 Sesudah diberi tawas 10 ml 5
20 ml 30 ml 40 ml
5 5 5
Waktu Pengendapan 2 menit 4 menit 6 menit 8 menit 10 menit 12 menit
Flok yang Terbentuk dalam Imhoff Cone Beker Glass 1 (10 ml tawas) 0 0 0 0,1 0,4 0,8 Beker Glass 2 (20 ml tawas) 0 0 0 0 0,7 1,5 Beker Glass 3 (30 ml tawas) 0 0 0 0 0,1 0,1 Beker Glass 4 (40 ml tawas) 0 0 0 0 0,1 0,1
Tabel pengendapan flok tiap waktu untuk perhitungan bak koagulasi
Tabel nilai kekeruhan awal untuk perhitungan sedimentasi tipe II Pengambilan sampe ke- Nilai Kekeruhan (NTU) 1 2 3 Rata-rata 26,64 27,67 27,50 27,27
Tabel nilai kekeruhan untuk perhitungan sedimentasi tipe II Kedalaman (cm) 50 100 150 200 250 10 21,29 23,3 23,2 23,3 22,17 20 20,2 19,17 22,9 20,6 21,5 Waktu Sampling (menit) 30 16,2 17,7 20,4 19,5 21 40 15,8 13,9 16,4 19,1 19,5 50 12,1 18,6 15,8 13,9 15,7 60 5,67 12,8 13,6 13,3 14,4
4.2
Perhitungan
A. Penentuan Debit dan Kebutuhan Air Diketahui : Asumsi jumlah penduduk Samarinda 6 orang/rumah Kebutuhan air rata-rata 200 liter/orang Jumlah sambungan rumah 5052 sambungan Perencanaan tahun ini Q kebutuhan air domestik = kebutuhan air rata-rata jiwa tiap rumah sambungan rumah = 200 liter/orang/hari 6 orang/rumah 5052 = 6.062.400 liter/hari Q non domestik = 30 % Q domestik = 30 % 6062400 liter/hari = 1.818.720 liter/hari Q produksi = 5 % (Q domestik + Q non domestik) = 5 % (6.062.400 liter/hari + 1.818.720 Liter/hari) = 394.056 liter/hari Q total = Q domestik + Q non domestik + Q produksi = 6.062.400 liter/hari + 1.818.720 liter/hari + 394.056 liter/hari = 8.275.176 liter/hari Pertambahan penduduk 5 tahun ke depan Pr = Po (1+r)n = 30312 (1+0,011)5 = 32.016 orang
Perencanaan 5 tahun ke depan Q domestik = 200 liter/orang/hari 32016 orang = 6.403.200 liter/hari Q non domestik = 30 % Q domestik = 30 % 6.403.200 liter/hari = 1.920.960 liter/hari Q produksi = 5 % (Q domestik + Q non domestik) = 5 % (6.403.200 liter/hari + 1.920.960 liter/hari) = 416.208 Liter/hari Q total = Q domestik + Q non domestik + Q produksi = 6.403.200 liter/hari + 1.920.960 liter/hari + 416.208 liter/hari = 8.740.368 liter/hari Kehilangan air = 15 % Q total = 15 % 8.740.368 liter/hari = 1.311.055,2 liter/hari/orang Kebutuhan air tahun maksimum = 1,3 Q total = 1,3 8.740.368 liter/hari = 11.362.478,4 liter/hari/orang Kebutuhan air jam puncak = 1,75 Q total = 1,75 8.740.368 liter/hari = 15.295.644 liter/hari/orang
B. Sedimentasi dengan Settling Colom Tipe I
Tabel nilai kekeruhan tiap waktu untuk perhitungan sedimentasi tipe I Waktu Pengambilan Sampel Mula-mula 5 menit 10 menit 15 menit 20 menit 25 menit 30 menit I 8,63 4,20 3,30 3,28 3,10 3,07 2,74 Nilai Kekeruhan (NTU) II 4,87 3,68 3,15 2,71 2,76 2,18 2,41 III 4,95 3,68 3,22 2,57 2,35 2,55 2,20 Rata-rata 6,15 3,853 3,223 2,853 2,736 2,6 2,45
Diketahui : Tinggi pipa settling colom = 2 meter Tinggi kran = 30 cm = 0,3 meter Maka perbedaan tingginya = 1,7 meter Diameter pipa = 4 inchi = 10,16 cm Menentukan nilai kecepatan (Vo) tiap waktu pengambilan sampel Vo1 = h / t1 = 1,7 meter / 5 menit = 1,7 meter / 300 sekon = 5,667 10-3 meter/sekon Vo2 = h / t2 = 1,7 meter / 10 menit = 1,7 meter / 600 sekon = 2,833 10-3 meter/sekon Vo3 = h / t3 = 1,7 meter / 15 menit = 1,7 meter / 900 sekon = 1,889 10-3 meter/sekon Vo4 = h / t4 = 1,7 meter / 20 menit = 1,7 meter / 1200 sekon = 1,416 10-3 meter/sekon Vo5 = h / t5 = 1,7 meter / 25 menit = 1,7 meter / 1500 sekon
= 1,133 10-3 meter/sekon Vo6 = h / t6 = 1,7 meter / 5 menit = 1,7 meter / 1800 sekon = 9,444 10-4 meter/sekon Menentukan nilai fraksi tiap waktu pengambilan sampel Fraksi = nilai kekeruhan tiap waktu pengambilan / nilai kekeruhan mula-mula Fraksi 5 menit = 3,853 NTU / 6,15 NTU = 0,626 NTU Fraksi 10 menit = 3,223 NTU / 6,15 NTU = 0,524 NTU Fraksi 15 menit = 2,853 NTU / 6,15 NTU = 0,464 NTU Fraksi 20 menit = 2,736 NTU / 6,15 NTU = 0,445 NTU Fraksi 25 menit = 2,600 NTU / 6,15 NTU = 0,423 NTU Fraksi 30 menit = 2,450 NTU / 6,15 NTU = 0,398 NTU Tabel Hubungan Waktu, Nilai Fraksi dan Kecepatan Waktu (menit) 5 10 15 20 25 30 Kecepatan (Vo) 5,667 10-3 2,833 10-3 1,889 10-3 1,416 10-3 1,133 10-3 9,444 10-4 Fraksi 0,626 0,524 0,464 0,445 0,423 0,398
Menentukan luas daerah kurva Misalnya diambil titik Fraksi = 0,57 dan Vo = 0,004
Tabel luas daerah kurva dF 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 V 0,000925 0,000825 0,000725 0,000475 0,000375 V dF 0,00002775 0,00002475 0,00002175 0,00001425 0,00001125
V dF= V dF = 0,0000998
% removal total R = (1-0,57) + 1 / 0,004 0,0000998 = 0,44 = 44% Perhitungan bak sedimentasi td V0 td V0 = H/V0 = 1,7/0,004 = 425 sekon = 7,083 menit = 0,004 m/s = 7,083 menit 1,75 = 12, 39 menit = 0,004 m/s 0,65 = 0,0026 m/s
Luas permukaan bak AS = Q / V0 = (8.740.368 m3/hari) / (0,0026 m/s) = (0,10116 m3/s) / (0,0026 m/s) = 38,907 m3
Kedalaman bak = (volume bak) / (luas permukaan bak) = td Q/A = 425 sekon 0,10116 m3/s / 38,907 m3 = 1,105 m Bila bak berbentuk lingkaran, maka luasnya : A r2 r = r2 = 12,391 = 3,52 m, D = 7,04 m 38,907 = 3,14 r2
Bila bak berbentuk persegi, maka luasnya : A S = S2 = 6,237 m 38,907 = S2
Menghitung bak endapan lumpurC
Volume persegi = S3 = 6,2373 = 242,62 m3
h1
h2
Karena sudut kemiringan 45, maka h2 = 0,5 C = 0,5 6,237 = 3,1185 m Volume limas segiempat bagian bawah = Luas alas tinggi = S2 3,1185 = 6,2372 1,0395 = 40,44 m3
Volume lumpur = Luas alas (0,5 h2) = 0,25 A (0,5 3,1185) = 0,25 38,907 (1,55925) = 5,055 m3
C. Perhitungan Bak Pembubuh Tawas Tawas yang digunakan = 20 ml untuk 700 ml air sampel. Jika air sampel sebanyak 1000 ml maka jumlah tawas yang digunakan adalah 28,6 ml. Penentuan dosis 20 ml/700 ml 20.000 ml x = x/1000 ml = 700 x = 28,6 ml = 2,86 %
28,6 ml1000 ml x 100%
Kebutuhan tawas per liter = 2,86 % x 10 gr/L = 0,286 gr/L Dosis = dosis optimum Q = 0,286 gram/liter 101,162 liter/sekon = 28,93 gram/sekon Kebutuhan tawas/hari = dosis x 86400 sekon/hari = 28,93 gram/sekon 86400 sekon/hari = 2499522 gram/hari = 2499,552 kg/hari Volume bak tawas = kebutuhan tawas/hari td = 2499,552 kg/hari x 1 hari = 2499,522 kg = 2499,522 liter = 2,499 m3 2,5 m3 Dimensi bak jika h = 2 m dengan p = , maka V =pxxh 2,5 = x x 2 1,25 = 2 = 1,12 m, maka, dimensi bak pembubuh tawas p = 1,12 m ; = 1,12 m ; h = 2m D. Perhitungan Bak Koagulasi Volume bak koagulasi Q td = 8.740.368 liter/hari = 0,101162 m3/s = 720 sekon = Q td = 101,162 liter/s 720 s = 72836,64 liter = 72,836 m3 Dimensi bak jika h = 6 m dengan p = , maka dosis optimum
Volume tangki
V 12,14
=pxxh = 2 = 3,48 m p = 3,48 m ; = 3,48 m ; h = 6 m
72,836 = x x 6
maka, dimensi bak koagulasi Tenaga pengaduk P = G2 V
= 1000/s2 0,000890 N.s/m2 72,836 m3 = 64824,04 Nm/s = 64824,04 Watt = 64,824 kW Efisiensi Power Motor 80% P = 64,824 kW0,8 = 81,03 kW
Berdasarkan motor yang tersedia, dapat dipilih motor model Mix-1500 sebanyak 7 buah. Jadi, jumlah bak adalah 7 buah dengan debit air untuk satu bak adalah 14,45 L/s. Volume tiap bak berdasarkan power motor Spesifikasi motor = Model Mix-1500 ; n = 110-175 rpm ; power = 11,19 kW P = 11,19 kW x 80% = 8,952 kw = 8952 Watt V = 8952 watt1000/s2 0,000890 N.s/m2 = 10,06 10 m3 Dimensi Cek td = V bakQ p = = 2,2 m h=2m
= 10 m3101,162 L/s
= 10 m30,101162 m3/s = 98,85 sekonDesain alat pengaduk menggunakan tipe turbine, 6 flat blades, vaned disc dengan nilai KT = 5,75 ; n = 120 rpm = 2 rps D1 = PKT n3 15 = 11190 N.s/m25,75 23997 kg/m3 Nskgm15 = 0,753 m
E. Perhitungan Bak Flokulasi Dengan kanal bersekat (baffled channel) Bila G1 = 75/detik ( air waduk ) ; G2 = 35/detik ; G3 = 20/detik ; f = 0,3 Dengan p = 10 m ; h = 2 m Dengan Q = 101,162 liter/s = 0,101162 m3/s = 8740,4 m3/hari td keseluruhan = 30 menit td masing-masing kompartemen = 30 menit3 = 10 menit Flokulator G1 = 75/detik Total volume = Q td = 8740,4 m3/hari 30 menit 1 hari1440 menit = 182,1 m3 Total lebar flokulator = VL x H = 182,1 m310 x 2 = 9 m Lebar tiap kompartemen = 9 m3 = 3 m
Pada suhu 25C, nilai = 0,89 10-3 kg/msekon, = 997 kg/m3 Kompartemen pertama Dengan G = 75/detik ; td = 10 menitJumlah sekat (n)= 2t(1,44+f)HL GQ213 n= 2 0,0008910(60)997(1,44+0,3)210750,101162213 n=0,0006156219860749,6 13 n=51,35 51 buah Jarak antar sekat= 10 m51 buah=0,196 m Headloss pada flokulator= tgG2 Headloss pada flokulator= 0,000896009979,81752 Headloss pada flokulator= 0,307 m
Kompartemen kedua Dengan G = 35/detik ; td = 10 menitJumlah sekat (n)= 2t(1,44+f)HL GQ213 n= 2 0,0008910(60)997(1,44+0,3)210350,101162213 n=0,000615647880785,47 13 n=30,89 31 buah Jarak antar sekat= 10 m31 buah=0,322 m Headloss pada flokulator= tgG2 Headloss pada flokulator= 0,000896009979,81352 Headloss pada flokulator= 0,0668 m
Kompartemen ketiga Dengan G = 20/detik ; td = 10 menitJumlah sekat (n)= 2t(1,44+f)HL GQ213 n= 2 0,0008910(60)997(1,44+0,3)210200,101162213 n=0,000615615634542,19 13 n=21,27 21 buah Jarak antar sekat= 10 m21 buah=0,476 m Headloss pada flokulator= tgG2 Headloss pada flokulator= 0,000896009979,81202 Headloss pada flokulator= 0,022 m
F. Perhitungan Sedimentasi Tipe II Tabel nilai kekeruhan awal untuk perhitungan sedimentasi tipe II Pengambilan sampe ke- Nilai Kekeruhan (NTU) 1 2 3 Rata-rata 26,64 27,67 27,50 27,27
Tabel nilai kekeruhan untuk perhitungan sedimentasi tipe II Kedalaman (cm) 50 100 150 200 250 10 21,29 23,3 23,2 23,3 22,17 20 20,2 19,17 22,9 20,6 21,5 Waktu Sampling (menit) 30 16,2 17,7 20,4 19,5 21 40 15,8 13,9 16,4 19,1 19,5 50 12,1 18,6 15,8 13,9 15,7 60 5,67 12,8 13,6 13,3 14,4
% Removal = Kekeruhan awal-kekeruhan di tabelKekeruhan awal100%
Tabel nilai % removal untuk perhitungan sedimentasi tipe II Kedalaman (cm) 50 100 150 200 10 21,9 14,5 14,9 14,5 20 25,9 29,7 16 24,5 Waktu Sampling (menit) 30 40,3 35 25,2 28,3 40 42,2 49 40 30 50 55,7 31 41,8 49,1 60 79,2 53,2 50 51,3
250
18,7
21
23
28,4
42,4
47,3
Mengeplot tabel sehingga terbentuk grafik isoremoval
Menentukan waktu tertentu dan menghitung removal totalnya. t1 = 15 menit
Rt = RB + H1HRC- RB+H2HRD- RC+H3HRE- RD+H4HRF- RE Rt = 20+7525030- 20+5025040- 30+2725050- 40+2025070- 50 Rt = 20 + 3 + 2 + 1 + 1,6 = 27,6 %
t2
= 35 menit
Rt = RC +H2HRD- RC+H3HRE- RD+H4HRF- RE Rt = 30+17525040- 30+8025050- 40+2825070- 50 Rt = 30 + 7 + 3,2 + 2,24 = 42,44 %
t3
= 45 menit
Rt = RD+H3HRE- RD+H4HRF- RE Rt = 40+17525050- 40+7525070- 50 Rt = 40 + 7 + 6 = 53 %
t4
= 55 menit
Rt = RE+H4HRF- RE Rt = 50+17525070- 50 Rt = 50 + 14 = 64 %
Tabel % Removal Waktu (menit) 15 35 45 55 % Removal Total 27,6 42,44 53 64
Diplot hubungan antara waktu (t) dan % removal total Untuk mendapatkan 44 % pengendapan, diperlukan waktu 37 menit
Menghitung surface loading (overflow rate) pada waktu-waktu di atas dengan rumus SL = H/t, dimana SL adalah surface loading, H adalah tinggi kolom, dan t adalah waktu yang dipilih. Tabel surface loading Waktu (menit) 15 35 45 55 Surface loading (m3/hari-m2) 240 102,86 80 65,45 % RT 27,6 42,44 53 64
Grafik hubungan % removal total dan surface loading
Surface loading yang diperlukan untuk menghasilkan pengendapan 44 % adalah 81,82 m3/hari-m2. Berdasarkan pengolahan data dari hasil percobaan, diperoleh : td V0 = 37 menit = 81,82 m3/hari-m2
Untuk desain, nilai dari percobaan dikalikan dengan faktor scale up, jadi : td = 37 menit 1,75 = 64,75 menit
V0
= 81,82 m3/hari-m2 0,65 = 53,183 m3/hari-m2
Luas permukaan bakAS= QV0 AS= 8740,368 m3hari53,183 m3hari-m2= 164,48 m2
Kedalaman bak= Volume bakLuas permukaan bak Kedalaman bak= td QA Kedalaman bak= 37 menit 1 hari1440 menit 8740,368 m3hari164,48m2 Kedalaman bak=0,0257 hari53,14 mhari Kedalaman bak=1,366 m
Bila bak berbentuk lingkaran, maka luasnya : A r2 r = r2 = 52,38 = 7,24 m, D = 14,48 m 164,48 = 3,14 r2
Bila bak berbentuk persegi, maka luasnya : A S = S2 = 12,824 m 164,48 = S2
G. Perhitungan Bak Desinfeksi Kriteria desain : Kriteria desain untuk bak desinfeksi antara lain :1) Debit = 101,16 liter/sekon. 2) Kaporit yang digunakan mengandung 60 % chlor. 3) Konsentrasi larutan yang direncanakan = 4 %. 4) Berat jenis kaporit = 1,2 kg/liter. 5) Kapasitas pembubuhan maksimum = 600 cc/menit. 6) Daya pengikat chlor = 1,18 mg/liter.
7) Sisa chlor yang direncanakan = 0,4 mg/liter. 8) Efisiensi = 65 % Perhitungan Dosis chlor total = Daya pengikat chlor + sisa chlor = 1,18 mg/liter + 0,4 mg/liter = 1,58 mg/liter Kebutuhan kaporit per menit = 1,58 mg/liter 100/60 101,16 liter/s 60 s/1 menit = 15983,28 mg/menit = 15,983 gram/menit Kebutuhan kaporit per hari = (100/60) dosis chlor Q = (100/60) 1,58 mg/liter 101,16 liter/s = 266, 39 mg/s = 266,39 mg/s 86400 s/1 hari 1 kg/1000000 mg = 23,016 kg/hari Volume kaporit = kebutuhan kaporit/berat jenis kaporit
= 23,016 kg/hari / 1,2 kg/liter = 19,18 liter/hari Volume pelarut = (100 % - 4 %) / (4 %) 19,18 liter/hari = 4,603 liter/hari Volume larutan kaporit = Volume kaporit + volume pelarut = 19,18 liter/hari + 4,603 liter/hari = 23,783 liter/hari = 0,000275 liter/s Kapasitas bak = Q td = 101,16 liter/s 12 jam 3600 s/jam = 4.370.112 liter = 4370,112 m3 Volume = panjang lebar tinggi
4370,112 = panjang3 Panjang = lebar = tinggi = 16,35 m
H. Perhitungan Bak Filtrasi Debit (Q) = 8740368 liter/hari = 8740,368 m3/hari = 0,10116 m3/sekon Jumlah bak (n) = 12 Q0,5 = 12 (0,10116)0,5 = 12 0,318 = 3,816 4 bak + 1 bak cadangan = 5 bak Jika filtrasi menggunakan slow sand filter dengan nilai kekeruhan < 50 NTU, maka kriteria desainnya: a) Kedalaman media (L) = 1 mb) Prioritas () = 0,44 c) Kecepatan filtrasi (Vs) = 0,2 m/jam = 5,55 10-5 m/s d) Kecepatan gravitasi (g) = 9,81 m/s2 e) Faktor bentuk () berdasarkan nilai = 7,7 f) Viskositas dinamis () = 0,8363 10-2 kg/ms g) Densitas () = 1 kg/m3 h) Diameter media (d) = 0,3 mm = 3 10-4 m NRe= VSd NRe=7,71kgm35,5510-5(310-4)(0,836310-2kgms) NRe=1,5310-4
F=1501-NRe+1,75 F=1501-0,441,5310-4+1,75=5,4910-5 Hf=FL(1-)Vs22gd Hf=5,4910-511-0,44(3,0810-9m/s)(0,44)2(9,81 ms2)(3104m)=1,6610-10
Tinggi bak = Tinggi air maksimum + tinggi media = 90 cm + 100 cm = 190 cm = 1,9 m
Volume bak = Luas media tinggi bak = 2000 m2 1,9 m = 3800 m3
4.3
Pembahasan
Bendungan Lempake memiliki kemampuan untuk menampung air hujan yang berasal dari hulu sungai Karang Mumus. Luas DAS Karang Mumus sekitar 320 km2, bendungan lempake ini merupakan bangunan yang berada dalam system DAS Karang Mumus, dengan luas sub DAS nya, sebesar 195 km2 (195.000.000 m2). Menurut sumber, Dinas PU Pengairan Propinsi Kalimantan Timur, Luas Bendungan sekitar 180.000 m2, dengan kedalaman rata-rata 3 m, jadi kapasitasnya 540,000 m3 atau 540.000.000 liter air. Penampungan Air Bendung Lempake Dengan Kapasitas Setara 108.000 truck tangki air 5000 liter
Mercu Bendungan Lempake Pintu Pembilas Untuk Membersihkan Endapan Lumpur Pintu Pengatur Untuk Irigasi
Pintu Pembilas
Saat Kemarau Air Bendungan Lempake
Kualitas air di waduk Benanga, Lempake tidak tercemar berat, nilai kekeruhan tertingginya hanya sekitar 27,27 NTU dan kekeruhan rata-rata sebesar 13,514 NTU. Nilai kekeruhan yang rendah ini cukup beralasan karena di sekitar waduk tidak terdapat industri dan pertanian. Selain itu daerah di sekitar waduk masih berupa hutan sekunder, sehingga tingkat sedimentasi atau pendangkalan waduk dapat diminimalkan. Nilai kekeruhan yang rendah mengindikasikan bahwa pengolahan air waduk Benanga menjadi air bersih tidak memerlukan proses koagulasi-flokulasi. Proses koagulasi-flokulasi dilakukan apabila nilai kekeruhan melebihi 50 NTU. Sehingga air waduk yang diolah setelah melalui proses prasedimentasi akan langsung dialirkan ke bak filtrasi untuk pengolahan lebih lanjut. Hal ini akan berbeda bila air baku yang dipakai berasal dari sungai. Nilai kekeruhan air sungai yang cukup tinggi, contohnya sungai Mahakam yang memiliki nilai kekeruhan sekitar 100 NTU. Air baku tersebut memerlukan pengolahan koagulasi-flokulasi setelah melalui bak prasedimentasi. Setelah
pengolahan koagulasi-flokulasi, air sungai akan dialirkan ke bak sedimentasi II untuk mengendapkan flok-flok yang terbentuk. Selanjutnya, akan dialirkan menuju bak filtrasi. Pada proses pengolahan filtrasi, air dialirkan ke slow sand filter untuk diolah. Pemilihan jenis filter slow sand filter sebagai pengolahan lanjutan dikarenakan nilai kekeruhan yang tidak terlalu besar. Jenis filter ini memiliki rentang kecepatan penyaringan antara 2 sampai 5 liter/m2menit. Selanjutnya air yang telah difiltrasi dialirkan ke bak desinfeksi untuk proses klorinasi. Proses ini bertujuan menghilangkan bakteri patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Air yang telah diklorinasi ini kemudian ditampung dalam bak reservoir untuk dialirkan ke masyarakat.
BAB V PENUTUP
5.1
Kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain: Karakteristik sampel air waduk Benanga yang terletak di kelurahan
Lempake, Samarinda Utara memiliki nilai kekeruhan yang rendah, sekitar 13,514 NTU. Perencanaan pengolahan air waduk Benanga sebagai air baku dapat
dilakukan dengan pembangunan instalasi pengolahan air minum yang memanfaatkan proses prasedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Pada proses prasedimentasi (sedimentasi tipe I) air diolah untuk
dihilangkan padatannya yang mudah mengendap secara gravitasi. Pada tahap ini, air didiamkan agar setenang mungkin sehingga padatan tersuspensi di dalamnya dapat mengendap. Pada proses filtrasi, air dialirkan ke slow sand filter untuk dipisahkan
dengan
padatan
yang
tidak
dapat
diendapkan
pada
proses
prasedimentasi, sehingga air yang keluar terbebas dari kekeruhan. Selanjutnya pada proses desinfeksi, air diberi kaporit dengan dosis
yang telah disesuaikan dengan debit air, untuk membunuh bakteri patogen yang terdapat di dalam air.
DAFTAR PUSTAKA
A.
Buku Pustaka Kusnaedi. 2010. Mengolah Air Kotor Untuk Air Minum. Penebar Swadaya : Jakarta Tchobanoglous, George; Schroeder, Edward. 1987. Water Quality : Characteristics, Modeling, Modification. Addison Wesley Company Publishing : Canada
B.
Website Bhupalaka. 2010. Filtrasi. http://bhupalaka.files.wordpress.com Bhupalaka. 2010. Sedimentasi. http://bhupalaka.files.wordpress.com Eko, PU. 2010. Waduk Benanga, Lempake. http://kehidupan-
disamarinda.blogspot.com/ HMTL Unand. 2010. Koagulasi Flokulasi. http://rangminang.web.id Irfani, Achmad. 2007. Filtrasi. http://achmadirfani.files.wordpress.com Ismail. 2009. Kesetimbangan Air Sub DAS Karangmumus Di Kota Samarinda. http://journal.ui.ac.id Rachmawati; Iswanto, Bambang; Winarni. 2009. Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 5, No. 2: Pengaruh pH Pada Proses Koagulasi Dengan Koagulan Aluminium Sulfat Dan Ferri Klorida. http://puslit2.petra.ac.id