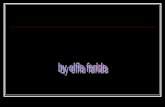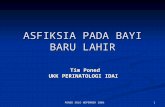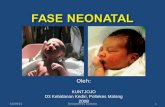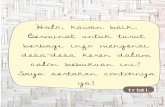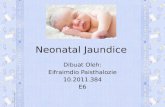DETERMINAN KEMATIAN NEONATAL DI DAERAH RURAL …
Transcript of DETERMINAN KEMATIAN NEONATAL DI DAERAH RURAL …

DETERMINAN KEMATIAN NEONATAL DI DAERAH RURAL INDONESIA TAHUN 2008-2012
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
Oleh:
Siti Malati Umah NIM: 1110101000040
PEMINATAN EPIDEMIOLOGI PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2014 M/1435 H

i
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 28 Agustus 2014
Siti Malati Umah

ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN
Skripsi dengan Judul
DETERMINAN KEMATIAN NEONATAL
DI DAERAH RURAL INDONESIA TAHUN 2008-2012
Telah disetujui dan diperiksa untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jakarta, 28 Agustus 2014
Oleh:
Siti Malati Umah
NIM: 1110101000040
Pembimbing I,
Ratri Ciptaningtyas, SKM, MHS
NIP. 198404042008122007
Pembimbing II,
Minsarnawati, SKM, M.Kes
NIP. 197502152009012003
PEMINATAN EPIDEMIOLOGI
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H/2014 M

iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul DETERMINAN KEMATIAN NEONATAL DI
DAERAH RURAL INDONESIA TAHUN 2008-2012 telah diujikan dalam
sidang skripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta pada 15 Agustus 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) pada Program Studi
Kesehatan Masyarakat.
Jakarta, 28 Agustus 2014
Sidang Skripsi,
Penguji I,
Raihana Nadra Al Kaff, SKM, MMA NIP. 197812162009012005
Penguji II,
Riastuti Kusuma Wardani, SKM, MKM NIP. 1980516200902005

iv
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI
Skripsi, 28 Agustus 2014
Siti Malati Umah, NIM: 1110101000040 Determinan Kematian Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
xviii + 156 halaman, 27 tabel, 6 gambar, 3 lampiran
ABSTRAK
Latar Belakang: Kematian neonatal merupakan penyumbang terbesar kasus kematian pada bayi di Indonesia sebanyak 59% kasus. Kematian neonatal lebih tinggi terjadi di daerah rural dibandingkan wilayah urban Indonesia. Pengetahuan tentang faktor yang berpengaruh terhadap kematian neonatal diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus kematian neonatal khususnya di daerah rural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kematian neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
Metode: Sumber data penelitian adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 dengan desain penelitian cross sectional study dan analisis statistik menggunakan uji chi square.
Hasil: Hasil penelitian didapatkan faktor yang berhubungan dengan kematian neonatal yaitu status pekerjaan ibu (p= 0,000), umur ibu (p=0,007), paritas (0,033), kunjungan antenatal (p=0,001) dan komplikasi kehamilan (p=0,002). Sedangkan pendidikan ibu (p=0,311), indeks kekayaan rumah tangga (0,375), jenis kelamin bayi (p=0,458), penolong persalinan (p=0,548), persalinan caesar (0,363) dan tempat persalinan (0,674) tidak berhubungan dengan kematian neonatal di daerah rural Indonesia.
Simpulan: Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan pada kelompok ibu umur >20 tahun dan >35 tahun serta kelompok ibu yang bekerja, peningkatan ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan tenaga pada layanan KB, pelayanan antenatal yang fokus pada terjaminnya ketersediaan, kelengkapan dan kualitas fasilitas dan tenaga kesehatan, pemantauan berkelanjutan bagi ibu yang mengalami komplikasi kehamilan dan peningkatan kualitas tenaga penolong persalinan.
Kata kunci: Determinan, Kematian Neonatal, Rural, Indonesia Daftar bacaan: 121 (1992-2014)

v
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCE PUBLIC HEALTH STUDY PROGRAM EPIDEMIOLOGY CONCENTRATION
Undergraduate Thesis, August 29th 2014
Siti Malati Umah, NIM: 1110101000040 Determinants of Neonatal Mortality in Rural Indonesia Year 2008-2012 xviii + 156 pages, 27 tables, 6 pictures, 3 attachments
ABSTRACT
Background: Neonatal mortality accounts for almost 59% of infant mortality in Indonesia. Neonatal mortality shows to be higher in rural area than in urban area. An understanding of the factors related to neonatal mortality in rural setting is needed to prevent neonatal death. This study aimed to identify the determinants of neonatal deaths in rural Indonesia year 2008-2012.
Method: The data source for the analysis was the 2012 Indonesia Demographic and Health Survey with cross sectional study design and statistic analysis was performed using chi square test.
Results: The results indicated that maternal occupation status (p= 0,000), maternal age (p=0,007), parity (0,033), antenatal care (p=0,001) and complications during pregnancy (p=0,002) were associated with neonatal death. While maternal education (p=0,311), household wealth index (0,375), sex of neonatus (p=0,458), birth attendants (p=0,548), cesarean delivery (0,363) dan place of delivery (0,674) were not associated with neonatal death in rural area of Indonesia.
Conclusion: Strategies on improving maternal knowledge needed to be focus on maternal age >20 and >35 years and maternal working group, provision of adequate health facilities both of the availability of health professionals and the completeness of equipments on family planning and antenatal care service, sustained monitoring on maternal complication group and improving skilled birth attendance towards providing quality service.
Keywords: Determinants, Neonatal Mortality, Rural, Indonesia Reading list: 121 (1992-2014)

vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS
A. Identitas Pribadi
Nama Lengkap : Siti Malati Umah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 26 Juli 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Pasirpanjang RT 006/002, Kecamatan Salem,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52275
Nomor telepon : 0857 4784 2313
Email : [email protected]
Website : elummah35.wordpress.com
B. Pendidikan Formal
1. 1997 - 2003 : SDN 03 Pasirpanjang, Salem, Brebes
2. 2003 - 2006 : MTs As Salam Salem, Brebes
3. 2006 - 2010 : MAN 2 Ciamis
4. 2010 - sekarang : S1-Peminatan Epidemiologi, Program Studi
Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang,
atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Mata Kuliah
Skripsi. Salawat dan salam senantiasa tecurahkan kepada Rasul tercinta yang telah
menjadi suri tauladan bagi umatnya.
Dengan bekal pengetahuan, pengarahan serta bimbingan yang diperoleh
selama perkuliahan, penulis menyusun skripsi mengenai “Determinan Kematian
Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012”. Skripsi ini disusun
dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa.
Masalah kematian pada neonatal dipilih sebagai topik penelitian mengingat
kematian neonatal menempati proporsi tertinggi kematian yang terjadi pada bayi.
Angka Kematian Bayi masih jauh dari target MDGs 2015. Target MDGs untuk
menurunkan Angka Kematian Bayi akan tercapai apabila penurunan Angka
Kematian Neonatal bisa dicapai. Sehingga diharapkan penelitian ini nantinya bisa
berkontribusi terhadap upaya penurunan angka kematian bayi serta balita di
Indonesia khususnya untuk daerah rural Indonesia.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. (hc). Dr. M. K. Tajudin, Sp. And selaku Dekan Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

viii
2. Ir. Febrianti, M.Si selaku Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat serta
penanggungjawab Mata Kuliah Skripsi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013-2014.
3. Ibu Fajar Ariyanti, Ph.D selaku kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014-2015.
4. Ibu Minsarnawati Tahangnacca, SKM, M.Kes selaku penanggungjawab
Peminatan Epidemiologi Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta serta dosen pembimbing skripsi atas arahan dan
bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ratri Ciptaningtyas, SKM, MHS selaku dosen pembimbing skripsi atas
konsultasi, arahan serta bimbingannya selama penyusunan skripsi.
6. Orang tua penulis, bagi Bapak (Ali Syamsuddin Alm) rasa terimakasih yang
sangat besar atas dukungan, do’a serta kepercayaannya yang diberikan
kepada penulis sehingga penulis semakin percaya diri dalam menghadapi
berbagai hal. Untuk Ibu (Syariah), dengan kelembutan dan kasih sayang serta
do’anya yang tak pernah berhenti dipanjatkan untuk penulis serta keteguhan
hati yang dicontohkannya sehingga semakin menguatkan penulis. Penulis
selalu mendo’akan, semoga Allah SWT menerima seluruh amal kebaikan
mereka dan mengampuni segala dosanya. Amiin.
7. A Irfan yang terus memberikan masukan, motivasi, semangat disaat penulis
menghadapi kesulitan-kesulitan. Ceu Ela, dengan kasih sayangnya yang
sangat tulus sehingga membuat penulis semakin semangat. Udin, adikku yang
paling santai menghadapi berbagai masalahnya. Ceu, A, Udin, semuanya
makasih atas dukungan semangat, motivasi dan do’anya. Buat Udin, Ayoo,

ix
segera menyusul 3.5 tahun selesai ya… Tidak lupa buat si bungsu Fuad yang
menjadi sponsor pulsa bagi penulis, makasih Uad bantuannya,, sangat
bermanfaat…
8. Buat Rizka sahabatku, teman sekosanku yang mau direpotkan, sering
dimintain tolong ini itu, De, makasih banget ya udah banyak ngebantu aku...
Buat Nida, Najah, Zata, makasih Nid, Jah, Ta, masukan dan do’a kalian saat
penyusunan proposal membuat semangatku bangkit kembali. Buat Wiwid,
kamu keren sis, aku banyak belajar dari kamu lho,,. Buat Luthfi, Fi.. makasih
ya, udah ngasih banyak masukan buat proposal dan skripsiku, skripsi kita
bener-bener mirip ya, tapi tetep berbeda. Buat Bebe, Tika, juga Karlin,
makasih ya kalian udah sering berbagi cerita, informasi, ngasih masukan,
saling nyemangatin, semoga ukhuwah kita tetap terjaga... Buat kalian
semuanya, makasih ya udah sering main ke kosan, refreshing banget buat
aku, skripsi jadi lebih menyenangkan (kapan lagi ya kita bisa kumpul di
kosan). Tidak lupa buat Ii, makasih ya udah ngasih semangat juga saat
proposal. Buat Putri, semangat selalu ya, semoga kita lulus tahun ini semua.
Terakhir buat dua cowok yang memang hanya dua cowok di peminatan
epidemiologi, Harun dan Bayu, Wong Palembang, cowok-cowok rajin yang
ngalahin cewek paling rajin di kelas, kalian bener-bener superrr, patut
dijadikan contoh. Peminatan Epidemiologi Pokoknya Tak Terlupakan (udah
kangen banget sama kalian...).
9. Teman-teman Kesehatan Masyarakat, Reka, Ifa, Bila, Nina, Angga, Anin,
Mawar, Sari, Nita terutama buat Eliza, Syifa, Qotrun, Dillah, Supri, Nia,

x
makasih ya buat kalian, kalian seru banget, bikin skripsi lebih seru, sekilas
ketegangan hilang, thanks banget Guys...
10. Teman-teman program studi lain, Keperawatan, Shulcha, Hilma, Alung;
teman-teman Farmasi Nia, Lina, Farida; adik kelas peminatan epidemiologi
Rini, Iis, Ila, Karim; teman-teman CSS MoRA UIN Jakarta, serta kakak
kelasku (Teh Eci) dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu.
Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian pada
skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis
dapat menyusun laporan penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Wassalamu‘alaikum Warohmatullah Wabarokatuh
Jakarta, 28 Agustus 2014
Siti Malati Umah

xi
MOTTO HIDUP
" ف إ ن س ع ال ع م ار س ی ر
اإ ر یس ر عس ع ال م .."ن “…Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada
kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan…” (Q.S. Al Insyiroh: 5-6)

xii
LEMBAR PERSEMBAHAN
Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapak (Alm)
dan Ibu tercinta…

xiii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ i
PERNYATAAN PERSETUJUAN .................................................................... ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ................................................................... iii
ABSTRAK ......................................................................................................... iv
RIWAYAT HIDUP PENULIS ......................................................................... vi
KATA PENGANTAR ...................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xix
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah.............................................................................. 4
1.3 Pertanyaan Penelitian ......................................................................... 5
1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................... 6
1.4.1 Tujuan Umum ........................................................................ 6
1.4.2 Tujuan Khusus ....................................................................... 6
1.5 Manfaat Penelitian ............................................................................. 8
1.5.1 Bagi Peneliti ........................................................................... 8
1.5.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat ............................ 8
1.5.3 Bagi Pemerintah ..................................................................... 8
1.5.4 Bagi Masyarakat..................................................................... 9
1.6 Ruang Lingkup Masalah .................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 10
2.1 Kematian Neonatal .......................................................................... 10
2.2 Angka Kematian Neonatal ............................................................... 11
2.3 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kematian Neonatal .......... 13

xiv
2.3.1 Faktor Sosial-ekonomi (Socioeconomic Factors) .................. 13
2.3.2 Determinan Terdekat (Proximate Determinants) .................. 20
2.3.2.1 Faktor Ibu (Maternal Factors) .................................. 20
2.3.2.2 Faktor Neonatal (Neonatal Factors) ......................... 24
2.3.2.3 Faktor Sebelum Melahirkan (Pre-Delivery Factors) . 38
2.3.2.4 Faktor Saat Melahirkan (Delivery Factors) .............. 47
2.3.2.5 Faktor Setelah Melahirkan (Post Delivery Factors) .. 61
2.4 Konsep Daerah Rural/Perdesaan ...................................................... 63
2.5 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 (SDKI 2012) ....... 68
2.6 Kerangka Teori ................................................................................ 75
BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL ........ 77
3.1 Kerangka Konsep ............................................................................ 77
3.2 Definisi Operasional ........................................................................ 80
3.3 Hipotesis Penelitian ......................................................................... 83
BAB IV METODE PENELITIAN .............................................................. 84
4.1 Desain Penelitian ............................................................................. 84
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian............................................................ 85
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian ....................................................... 85
4.3.1 Populasi Penelitian ............................................................... 85
4.3.2 Sampel Penelitian ................................................................. 85
4.4 Cara Pengambilan Sampel ............................................................... 86
4.5 Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 87
4.6 Pengolahan Data .............................................................................. 89
4.7 Analisis Data ................................................................................... 90
4.7.1 Analisis Univariat ................................................................. 91
4.7.2 Analisis Bivariat ................................................................... 91
BAB V HASIL ............................................................................................ 92
5.1 Distribusi Kematian Neonatal .......................................................... 92
5.2 Distribusi Tingkat Pendidikan Ibu .................................................... 92
5.3 Distribusi Status Pekerjaan Ibu ........................................................ 93
5.4 Distribusi Indeks Kekayaan Rumah Tangga ..................................... 93

xv
5.5 Distribusi Umur Ibu ......................................................................... 94
5.6 Distribusi Jenis Kelamin Bayi .......................................................... 94
5.7 Distribusi Paritas ............................................................................. 95
5.8 Distribusi Kunjungan Antenatal ....................................................... 95
5.9 Distribusi Komplikasi Kehamilan .................................................... 95
5.10 Distribusi Penolong Persalinan ........................................................ 96
5.11 Distribusi Persalinan Caesar ............................................................ 96
5.12 Distribusi Tempat Persalinan ........................................................... 97
5.13 Hubungan Pendidikan Ibu dengan Kematian Neonatal ..................... 97
5.14 Hubungan Pekerjaan Ibu dengan Kematian Neonatal ....................... 98
5.15 Hubungan Indeks Kekayaan Rumah Tangga dengan Kematian
Neonatal .......................................................................................... 99
5.16 Hubungan Umur Ibu dengan Kematian Neonatal ........................... 100
5.17 Hubungan Jenis Kelamin Bayi dengan Kematian Neonatal ............ 100
5.18 Hubungan Paritas dengan Kematian Neonatal ................................ 101
5.19 Hubungan Kunjungan Antenatal dengan Kematian Neonatal ......... 102
5.20 Hubungan Komplikasi Kehamilan dengan Kematian Neonatal....... 102
5.21 Hubungan Penolong Persalinan dengan Kematian Neonatal ........... 103
5.22 Hubungan Persalinan Caesar dengan Kematian Neonatal .............. 104
5.23 Hubungan Tempat Persalinan dengan Kematian Neonatal .............. 104
BAB VI PEMBAHASAN ........................................................................... 106
6.1 Keterbatasan Penelitian .................................................................. 106
6.2 Kematian Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 .. 107
6.3 Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kematian Neonatal di
Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ..................................... 111
6.3.1 Pendidikan Ibu ................................................................... 111
6.3.2 Pekerjaan Ibu ..................................................................... 115
6.3.3 Indeks Kekayaan Rumah Tangga........................................ 119
6.3.4 Umur Ibu ............................................................................ 123
6.3.5 Jenis Kelamin Bayi............................................................. 127
6.3.6 Paritas ................................................................................ 129
6.3.7 Kunjungan Antenatal .......................................................... 135

xvi
6.3.8 Komplikasi Kehamilan ....................................................... 142
6.3.9 Penolong Persalinan ........................................................... 145
6.3.10 Persalinan Caesar ............................................................... 152
6.3.11 Tempat Persalinan .............................................................. 154
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 161
7.1 Simpulan ....................................................................................... 161
7.2 Saran ............................................................................................. 162
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 164
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 175

xvii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Kriteria Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia............................... 67
Tabel 3.1 Definisi Operasional ...................................................................... 80
Tabel 4.1 Variabel dan Kode Variabel Penelitian Pada SDKI 2012 ............... 89
Tabel 4.2 Hasil Cleaning Data Daerah Rural Indonesia SDKI 2012 .............. 90
Tabel 5.1 Distribusi Kematian Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun
2008-2012 ..................................................................................... 92
Tabel 5.2 Distribusi Tingkat Pendidikan Ibu di Daerah Rural Indonesia Tahun
2008-2012 ..................................................................................... 92
Tabel 5.3 Distribusi Pekerjaan Ibu di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-
2012 .............................................................................................. 93
Tabel 5.4 Distribusi Indeks Kekayaan Rumah Tangga di Daerah Rural
Indonesia Tahun 2008-2012 .......................................................... 93
Tabel 5.5 Distribusi Umur Ibu di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 . 94
Tabel 5.6 Distribusi Jenis Kelamin Bayi di Daerah Rural Indonesia Tahun
2008-2012 ..................................................................................... 94
Tabel 5.7 Distribusi Paritas di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ..... 95
Tabel 5.8 Distribusi Kunjungan Antenatal di Daerah Rural Indonesia Tahun
2008-2012 ..................................................................................... 95
Tabel 5.9 Distribusi Komplikasi Kehamilan di Daerah Rural Indonesia Tahun
2008-2012 ..................................................................................... 96
Tabel 5.10 Distribusi Penolong Persalinan di Daerah Rural Indonesia Tahun
2008-2012 ..................................................................................... 96
Tabel 5.11 Distribusi Persalinan Caesar di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-
2012 .............................................................................................. 97
Tabel 5.12 Distribusi Tempat Persalinan di Daerah Rural Indonesia Tahun
2008-2012 ..................................................................................... 97

xviii
Tabel 5.13 Analisis Hubungan antara Pendidikan Ibu dengan Kematian
Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 .................. 98
Tabel 5.14 Analisis Hubungan antara Pekerjaan Ibu dengan Kematian Neonatal
di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................................. 98
Tabel 5.15 Analisis Hubungan antara Indeks Kekayaan Rumah Tangga dengan
Kematian Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 .. 99
Tabel 5.16 Analisis Hubungan antara Umur Ibu dengan Kematian Neonatal di
Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................................... 100
Tabel 5.17 Analisis Hubungan antara Jenis Kelamin Bayi dengan Kematian
Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................ 100
Tabel 5.18 Analisis Hubungan antara Paritas dengan Kematian Neonatal di
Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................................... 101
Tabel 5.19 Analisis Hubungan antara Kunjungan Antenatal dengan Kematian
Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................ 102
Tabel 5.20 Analisis Hubungan antara Komplikasi Kehamilan dengan Kematian
Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................ 102
Tabel 5.21 Analisis Hubungan antara Penolong Persalinan dengan Kematian
Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................ 103
Tabel 5.22 Analisis Hubungan antara Persalinan Caesar dengan Kematian
Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................ 104
Tabel 5.23 Analisis Hubungan antara Tempat Persalinan dengan Kematian
Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012 ................ 105

xix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tren Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal di
Indonesia Tahun 2002-2012 ........................................................ 13
Gambar 2.2 Bagan Alur Pengambilan Sampel Rumah Tangga dan Individu ... 69
Gambar 2.3 Kerangka Teori ........................................................................... 76
Gambar 3.1 Kerangka Konsep ........................................................................ 79
Gambar 4.1 Bagan Alur Pengambilan Sampel Penelitian ................................ 87
Gambar 4.2 Proses Pengambilan Data Penelitian ............................................ 88

1
1 BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berbagai laporan menunjukkan bahwa kematian neonatal menempati
proporsi kematian terbanyak yang terjadi pada bayi di dunia. Laporan
MDGs 2013 menunjukkan bahwa proporsi kematian neonatal pada kejadian
kematian balita di dunia mengalami peningkatan dari 36% pada tahun 1990
menjadi 43% pada tahun 2011 (United Nations, 2013). Data WHO juga
menunjukkan bahwa kematian neonatal memiliki proporsi sebesar 40%
kematian dari seluruh kematian yang terjadi pada balita di dunia (WHO,
2014).
Data SDKI 2012 menunjukkan kematian neonatal untuk periode 2008-
2012 di Indonesia sebesar 19 kematian per 1000 kelahiran hidup (KH).
Angka Kematian Neonatal ini merupakan proporsi kematian terbesar yang
terjadi pada bayi (59%) di Indonesia. Angka Kematian Bayi di Indonesia
yaitu sebesar 32 per 1000 KH untuk periode 2008-2012. Angka Kematian
Bayi ini menunjukkan masih cukup jauh untuk bisa mencapai target MDGs
menurunkan Angka Kematian Bayi sebesar 23 per 1000 KH pada tahun
2015 (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013).
Angka Kematian Neonatal berdasarkan wilayah rural dan urban di
Indonesia menunjukkan bahwa Angka Kematian Neonatal lebih tinggi di

2
daerah rural (perdesaan) Indonesia dibandingkan di daerah urban
(perkotaan) Indonesia. Angka Kematian Neonatal di daerah urban Indonesia
sebesar 15 per 1.000 KH. Sedangkan Angka Kematian Neonatal di daerah
rural Indonesia berdasarkan SDKI 2012 yaitu sebesar 24 per 1.000 KH
untuk periode 2003-2012 (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International,
2013). Angka Kematian Neonatal didaerah rural mengalami penurunan pada
hasil SDKI 2002-2003 (26 per 1000 KH) (BPS & ORC Macro, 2003),
namun Angka Kematian Neonatal di daerah rural Indonesia ini tetap konstan
berdasarkan hasil SDKI 2007 (24 per 1.000 KH) (BPS & Macro
International, 2008).
Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan kematian yang terjadi
pada dua puluh delapan hari pertama kehidupan dibagi jumlah bayi lahir
hidup. Pada SDKI 2012 AKN dihitung berdasarkan keterangan jumlah bayi
yang meninggal pada dua puluh delapan hari pertama kehidupan dibagi
dengan keterangan jumlah bayi yang bertahan hidup. Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dilaksanakan untuk mengetahui
informasi mengenai masalah kependudukan serta masalah kesehatan yang
fokus pada kesehatan ibu dan anak di Indonesia (BPS, BKKBN, Kemenkes
& ICF International, 2013).
Masa neonatal merupakan masa empat minggu pertama kehidupan
pada bayi setelah dilahirkan (WHO, 2006). Masa neonatal merupakan waktu
yang paling rentan untuk kelangsungan hidup anak. Upaya menurunkan
angka kematian neonatal menjadi semakin penting, bukan hanya karena
proporsinya yang semakin meningkat tetapi karena intervensi kesehatan

3
yang diperlukan untuk mengatasi penyebab utama kematian berbeda dengan
intervensi pada kematian balita secara umum (WHO, 2014).
Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor-faktor
yang berhubungan dengan kematian neonatal yaitu usia ibu (Prabamurti,
dkk., 2008), berat bayi lahir (Onwuanaku dkk., 2011), jarak kelahiran
(Mekonnen dkk., 2013), jenis kelamin bayi (Bashir dkk., 2013), paritas
(Singh dkk., 2013), pendidikan ibu (Upadhyay dkk., 2012), suntikan tetanus
toksoid pada ibu (Singh dkk., 2013), persalinan caesar (Chaman dkk.,
2009), umur kehamilan (Onwuanaku dkk., 2011), riwayat komplikasi
persalinan (Singh, dkk., 2013) dan fasilitas persalinan (Tura, dkk., 2013).
Penelitian yang dilakukan di beberapa daerah rural menunjukkan
bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian neonatal yaitu
kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, persalinan sesar, paritas, jarak
kelahiran, pendidikan ibu, usia ibu, pekerjaan ibu, komplikasi persalinan
(Mercer, dkk., 2006; Chaman, dkk., 2009; Upadhyay, dkk., 2012; Singh,
dkk., 2013). Penelitian lainnya menemukan bahwa penyebab utama
kematian pada neonatal di daerah rural yaitu asfiksia, infeksi (31%), lahir
prematur (26%), sepsis (45%) dan pneumonia (36%) (Baqui, dkk., 2006).
Penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa faktor risiko
yang paling berpengaruh adalah berat badan saat lahir (Efriza, 2007;
Fachlaeli, 2000). Penelitian lainnya yang menggunakan data SDKI 2003
menunjukkan bahwa status orang tua, status pekerjaan ayah, jarak
kelahiran, jenis kelamin bayi, ukuran bayi lahir dan riwayat komplikasi
persalinan memiliki hubungan dengan kematian neonatal di Indonesia

4
(Titaley, dkk., 2008). Umur ibu saat melahirkan dan umur kehamilan dapat
meningkatkan risiko terjadinya kematian neonatal (Fachlaeli, 2000). Pada
penelitian yang dilakukan (Yani & Duarsa, 2013) Yani dan Duarsa (2013)
menemukan bahwa pelayanan antenatal dan penolong persalinan memiliki
hubungan dengan kematian neonatal.
Target MDGs untuk menurunkan angka kematian bayi sebesar 23
kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 cukup berat bagi
Indonesia. Penurunana angka kematian bayi ini membutuhkan berbagai
upaya yang perlu ditingkatkan (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF
International, 2013) sedangkan waktu pencapaian hanya tersisa satu tahun.
Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang
berpengaruh terhadap kasus kematian neonatal di Indonesia dengan fokus di
daerah rural karena memiliki angka kematian neonatal yang lebih tinggi
dibandingkan di daerah urban serta memiliki angka kematian neonatal yang
tetap konstan dari tahun sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat
berkontribusi dalam upaya melakukan intervensi terkait faktor risiko
kematian neonatal sehingga bisa berdampak terhadap penurunan Angka
Kematian Neonatal di daerah rural Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan data SDKI 2012 untuk periode 2008-2012, diketahui
bahwa kematian neonatal menjadi penyumbang utama kematian yang terjadi
pada Bayi di Indonesia. Angka Kematian Bayi masih tinggi, sangat jauh
untuk bisa mencapai target MDGs. Angka Kematian Neonatal di daerah
rural Indonesia menunjukkan lebih tinggi dibandingkan di daerah urban

5
Indonesia. Kematian neonatal di daerah rural Indonesia tetap konstan
berdasarkan SDKI 2007 dan SDKI 2012. Sehingga perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan
kematian neonatal di daerah rural Indonesia agar bisa diketahui intervensi
yang diperlukan untuk menurunkan Angka Kematian Neonatal yang juga
diharapkan bisa berdampak pada penurunan Angka Kematian Bayi.
1.3 Pertanyaan Penelitian
Adapun pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut:
1) Bagaimana distribusi kematian neonatal, pendidikan ibu, pekerjaan ibu,
indeks kekayaan rumah tangga, umur ibu, jenis kelamin bayi, paritas,
kunjungan antenatal, komplikasi kehamilan, penolong persalinan,
persalinan caesar dan tempat persalinan di daerah rural Indonesia tahun
2008-2012?
2) Bagaimana hubungan pendidikan ibu dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?
3) Bagaimana hubungan pekerjaan ibu dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?
4) Bagaimana hubungan indeks kekayaan rumah tangga dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?
5) Bagaimana hubungan umur ibu dengan kematian neonatal di daerah
rural Indonesia tahun 2008-2012?
6) Bagaimana hubungan jenis kelamin bayi dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?

6
7) Bagaimana hubungan paritas dengan kematian neonatal di daerah rural
Indonesia tahun 2008-2012?
8) Bagaimana hubungan kunjungan antenatal dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?
9) Bagaimana hubungan komplikasi kehamilan dengan kematian neonatal
di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?
10) Bagaimana hubungan penolong persalinan dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?
11) Bagaimana hubungan persalinan caesar dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?
12) Bagaimana hubungan tempat persalinan dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan pada penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus
sebagai berikut:
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini yaitu diketahuinya determinan
kematian neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
1.4.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut:
1) Diketahuinya distribusi kematian neonatal, pendidikan ibu,
pekerjaan ibu, indeks kekayaan rumah tangga, umur ibu, jenis
kelamin bayi, paritas, kunjungan antenatal, komplikasi kehamilan,

7
penolong persalinan, persalinan caesar dan tempat persalinan di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
2) Diketahuinya hubungan pendidikan ibu dengan kematian neonatal
di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
3) Diketahuinya hubungan pekerjaan ibu dengan kematian neonatal
di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
4) Diketahuinya hubungan indeks kekayaan rumah tangga dengan
kematian neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
5) Diketahuinya hubungan umur ibu dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
6) Diketahuinya hubungan jenis kelamin bayi dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
7) Diketahuinya hubungan paritas dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
8) Diketahuinya hubungan kunjungan antenatal dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
9) Diketahuinya hubungan komplikasi kehamilan dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
10) Diketahuinya hubungan penolong persalinan dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
11) Diketahuinya hubungan persalinan caesar dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
12) Diketahuinya hubungan tempat persalinan dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.

8
1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1.5.1 Bagi Peneliti
Sebagai sarana menerapkan dan mengaplikasikan keilmuan
kesehatan masyarakat yang telah didapatkan di perkuliahan
mengenai metodologi penelitian, epidemiologi kesehatan reproduksi,
manajemen dan analisis data serta keilmuwan kesehatan masyarakat
lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.
1.5.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan bagi
kalangan akademisi sebagai informasi terhadap penelitian
selanjutnya.
1.5.3 Bagi Pemerintah
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bisa
mendapatkan hasil penelitian ini berupa Policy Brief mengenai
faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian neonatal di daerah
rural Indonesia. Sehingga diharapkan Policy Brief tersebut
selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upaya
penurunan Angka Kematian Neonatal di Indonesia terutama fokus di
daerah rural.

9
1.5.4 Bagi Masyarakat
Masyarakat bisa mengetahui faktor-faktor yang berhubungan
dengan kematian neonatal di daerah rural Indonesia setelah
membaca laporan hasil penelitian ini.
1.6 Ruang Lingkup Masalah
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan dengan kematian neonatal. Penelitian ini merupakan penelitian
epidemiologi analitik dengan variabel independen adalah pendidikan ibu,
pekerjaan ibu, indeks kekayaan rumah tangga, umur ibu, jenis kelamin bayi,
paritas, kunjungan antenatal, komplikasi kehamilan, penolong persalinan,
persalinan caesar dan tempat persalinan. Sedangkan variabel dependennya
adalah kematian neonatal. Desain penelitian yang digunakan adalah cross
sectional study, dimana variabel dependen maupun independen
dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Instrumen pada penelitian
berupa Kuesioner Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012.
Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2014. Populasi penelitian yaitu semua
neonatal di daerah rural Indonesia pada periode 2008-2012 dengan sampel
penelitian berjumlah 7.138 orang.

10
2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kematian Neonatal
Neonatus (bayi baru lahir) adalah bayi dari saat lahir sampai usia 4
minggu pertama kehidupan (Wong, 2004). Periode neonatal dimulai saat
bayi lahir sampai 28 hari setelah kelahiran (WHO, 2006). Periode neonatal
ini merupakan periode paling kritis untuk perkembangan dan pertumbuhan
bayi (Saifudin, dkk, 2009). Bayi sangat mudah terserang penyakit akibat
terjadi transisi dari kehidupan didalam kandungan ke kehidupan di luar
kandungan (ekstrauterus) yang memerlukan beberapa penyesuaian
fisiologi dan biokimia agar bayi bisa bertahan hidup. Pada masa transisi ini
sebagian besar masalah yang terjadi adalah lemahya adaptasi bayi akibat
aspiksia, kelahiran prematur dan efek yang terjadi akibat proses persalinan
(Kliegman, dkk., 2011).
Kematian neonatal menurut ICD10 adalah kematian yang terjadi
selama dua puluh delapan hari pertama kehidupan setelah bayi dilahirkan.
Kematian neonatal terbagi atas kematian neonatal dini dan kematian
neonatal lanjut. Kematian neonatal dini merupakan kematian seorang bayi
dari mulai setelah dilahirkan sampai 7 hari pertama kehidupan (0-6 hari).
Sedangkan kematian neonatal lanjut adalah kematian bayi setelah 7 hari
sampai sebelum 28 hari pertama kehidupan (7-27 hari) (WHO, 2006).

11
2.2 Angka Kematian Neonatal
Angka Kematian Neonatal merupakan jumlah kematian bayi
berumur kurang dari 28 hari pada periode tertentu biasanya pada periode
satu tahun (Timmreck, 1994). Walaupun Angka Kematian Balita di dunia
menunjukkan terjadi penurunan sebesar 41% dari 87 kematian per 1000
kelahiran hidup tahun 1990 menjadi 51 kematian per 1000 kelahiran hidup
tahun 2011, masih diperlukan upaya lebih serius untuk menurunkan dua
per tiga kematian balita pada tahun 2015. Selain itu, proporsi kematian
neonatal pada kematian balita di dunia justru mengalami peningkatan dari
36% pada tahun 1990 menjadi 43% pada tahun 2011 (United Nations,
2013).
Penurunan Angka Kematian Neonatal sangat penting untuk
mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 penurunan
Angka Kematian Balita. Target MDGs untuk penurunan Angka Kematian
Balita yaitu penurunan kematian sebesar dua per tiga kematian pada 2015
dari kematian balita yang terjadi pada tahun 1990 (United Nations, 2013).
Penurunan angka kematian balita ini secara lebih rinci yaitu dari 97
kematian per 1000 KH menjadi 32 kematian per 1000 KH pada tahun 2015
(Stalker, 2008). Angka Kematian Balita di Indonesia diketahui sebesar 40
per 1.000 KH pada periode 2008-2012, dimana kematian yang terjadi pada
bayi merupakan penyumbang kematian tertinggi (BPS, BKKBN,
Kemenkes & ICF International, 2013).
Angka Kematian Bayi di Indonesia yaitu sebesar 32 per 1000 KH
untuk periode 2008-2012. Sedangkan Angka Kematian Bayi di daerah

12
rural Indonesia sebesar 40 per 1000 KH untuk periode 2003-2012. Pada
kematian bayi tersebut diketahui kematian neonatal merupakan proporsi
kematian penyumbang paling banyak.
Angka Kematian Neonatal di Indonesia yaitu sebesar 19 per 1000
KH untuk periode 2008-2012. Angka kematian neonatal ini tidak
mengalami penurunan maupun peningkatan (konstan) dari hasil SDKI
sebelumnya (SDKI 2007). Namun, Proporsi kematian neonatal terhadap
kematian bayi mengalami peningkatan dari tahun 2007 ke tahun 2012
(58% menjadi 59%) (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International,
2013).
Angka kematian neonatal di daerah rural Indonesia berdasarkan
SDKI 2012 didapatkan sebesar 24 per 1000 KH. Angka kematian neonatal
ini mengalami penurunan berdasarkan SDKI 2002-2003, namun tetap
konstan berdasarkan SDKI 2007. Angka kematian neonatal di daerah rural
Indonesia berdasarkan SDKI 2002-2003 sebesar 26 per 1000 KH (BPS &
ORC Macro, 2003). Sedangkan berdasarkan SDKI 2007, angka kematian
neonatal di daerah rural Indonesia yaitu sebesar 24 per 1000 KH (BPS &
Macro International, 2008).

13
Gambar 2.1 Tren Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal
di Daerah Rural Indonesia Tahun 2002-2012
Sumber: (BPS & ORC Macro, 2003; BPS & Macro International, 2008;
BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013)
2.3 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kematian Neonatal
Determinan atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kelangsungan hidup neonatal menurut Titaley, dkk (2008) terdiri dari
faktor sosial-ekonomi (socioeconomic determinants) dan faktor terdekat
(proximate determinants). Determinan terdekat tersebut terdiri dari faktor
ibu, faktor bayi dan faktor pelayanan kesehatan.
2.3.1 Faktor Sosial-ekonomi (Socioeconomic Factors)
Faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh terhadap
kelangsungan hidup bayi terdiri dari pendidikan ibu, pekerjaan ibu,
indeks kekayaan rumah tangga dan wilayah tempat tinggal (Titaley,
dkk, 2008; Mekonnen dkk., 2013; Singh, dkk., 2013; Upadhyay,
dkk., 2012; Yi, dkk., 2011).
1) Pendidikan Ibu
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
52 4540
26 24 24
0
20
40
60
SDKI 2002-2003 SDKI 2007 SDKI 2012Ju
mla
h
Kematian Bayi Kematian Neonatal

14
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Adapun jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan
yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas
pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
Semakin meningkatnya level pendidikan ibu dapat
meningkatkan kemampuan ibu untuk memperoleh, memproses
dan memahami informasi dasar kesehatan tentang manfaat
pelayanan sebelum melahirkan dan informasi pelayanan
kesehatan reproduksi yang dibutuhkan. Informasi sangat
penting bagi ibu untuk membuat keputusan yang tepat. Ibu
dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih percaya diri
bertanya mengenai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh
dirinya (Karlsen, dkk., 2011).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan ibu berhubungan dengan kejadian kematian
neonatal (Mekonnen dkk., 2013; Upadhyay, dkk., 2012).
Tingkat pendidikan ibu memiliki hubungan dengan kejadian

15
kematian neonatal (Singh dkk., 2013). Semakin rendah tingkat
pendidikan ibu akan semakin besar peluang terjadinya kasus
kematian bayi (Ibu tidak pernah sekolah, OR: 2.48; ibu
berpendidikan rendah, OR: 1.57) (Faisal, 2010). Penelitian
lainnya juga menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat
pendidikan ibu dengan kematian bayi (Sugiharto, 2011).
Penelitian yang dilakukan Pertiwi (2010) juga menunjukkan
ada hubungan antara pendidikan dengan kematian neonatal.
Ibu yang tidak memiliki riwayat pendidikan lebih rentan
mengalami kejadian kematian pada neonatusnya (Manzar,
dkk., 2012).
Penelitian kualitatif pada masyarakat suku Dayak Siang
Murung Raya, menemukan bahwa terdapat remaja yang masih
duduk dibangku sekolah bahkan remaja yang belum
mengalami menstruasi yang sudah menikah. Hal tersebut
terjadi karena diketahui sebagian besar pendidikan masyarakat
setempat yang masih rendah (Kemenkes RI, 2012). Penelitian
pada masyarakat suku Gorontalo Desa Imbodu menemukan
bahwa sebagian besar masyarakat berpendidikan rendah.
Informasi yang didapatkan secara informal juga jarang
ditemukan di daerah perdesaan. Sebagian besar masyarakat
mendapatkan pengetahuan kesehatan berdasarkan penuturan-
penuturan orang tua. Para orang tua memiliki pengalaman
diobati oleh dukun saat mereka sakit. Selain itu, para remaja

16
sungkan untuk bertanya mengenai masalah kesehatan
reproduksi kepada orangtuanya. Biasanya para remaja tersebut
mendapatkan informasi dari teman-temannya (Kemenkes RI,
2012).
Namun, pada penelitian yang dilakukan Wijayanti
(2013) menunjukkan tidak ada hubungan antara pendidikan ibu
dengan kejadian kematian neonatal.
2) Pekerjaan Ibu
Apabila ibu melakukan pekerjaan saat hamil, ibu
memiliki kemungkinan terkena pajanan terhadap zat
fetotoksik, ketegangan fisik yang berlebihan, terlalu lelah serta
kesulitan yang berhubungan dengan keseimbangan tubuh. Ibu
yang sering beridiri di suatu tempat dalam jangka waktu lama
bisa berisiko mengalami varises vena, flebitis dan edema
(Ladewig, dkk., 2006).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara status pekerjaan ibu dengan kematian
neonatal (Singh, dkk., 2013). Status ibu bekerja memiliki
hubungan dengan kematian neonatal (Titaley, dkk., 2008). Ibu
yang bekerja mempunyai kecenderungan untuk mengalami
kejadian kematian bayi 1.52 kali lebih besar dibandingkan ibu
yang tidak bekerja (Faisal, 2010). Ada hubungan antara status
ibu bekerja dengan kematian neonatal dini (Nugraheni, 2013).

17
Ibu yang bekerja memiliki risiko 2.34 kali untuk mengalami
kematian neonatal dibandingkan ibu yang tidak bekerja (Dewi,
2010). Penelitian lainnya menunjukkan tidak ada hubungan
antara pekerjaan ibu dengan kejadian kematian neonatal
(Wijayanti, 2013).
Penelitian di daerah rural Etiopia menunjukkan bahwa
kematian bayi lebih tinggi terjadi pada ibu yang bekerja yang
merupakan usaha miliki sendiri. Bayi dari ibu tersebut
memiliki risiko 5.4 kali lebih besar untuk mengalami kematian
dibandingkan bayi dari ibu pada kelompok lainnya (petani,
IRT) (Andargie, dkk., 2013). Penelitian di daerah rural India
juga menemukan bahwa anak dari ibu yang tidak bekerja
(tinggal di rumah) memiliki risiko lebih rendah untuk
meninggal selama periode neonatal dibandingkan anak dari ibu
yang bekerja (Singh, dkk., 2013).
Penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Jrangoan
(Suku Madura) Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa
Timur, menemukan bahwa remaja putri telah menikah
umumnya pada usia 17 tahun. Remaja putri tersebut yang
kemudian menjadi nyonya-nyonya kecil harus bisa membantu
suami mengurus ladang yang merupakan tempat mereka
mencari nafkah. Ibu hamil tetap bekerja ke sawah walaupun
dalam kondisi hamil karena ingin membantu suaminya
mencari nafkah untuk keluarga. Kegiatan bertani yang

18
dilakukan oleh ibu hamil tersebut adalah menanam berbagai
jenis tanaman seperti padi, kacang-kacangan, singkong, ketela,
cabai, bawang dan tembakau (Kemenkes RI, 2012).
Kebiasaan ibu tetap bekerja juga ditemukan pada
masyarakat Etnik Manggarai Desa Waicodi Kecamatan Cibal
Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu
hamil usia muda maupun usia kehamilan tujuh bulan masih
selalu bekerja membantu suaminya di ladang. Pada saat
menjelang persalinan, ibu juga dianjurkan untuk turut bekerja
di kebun agar janin dalam kandungan tidak diganggu roh jahat
(Kemenkes RI, 2012).
Pada masyarakat Etnik Ngalum Distrik Oksibil
Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua juga diemukan
bahwa kebiasaan ibu saat hamil pada etnik ini yaitu dari mulai
menyiapkan sarapan untuk keluarga, memetik hasil kebun dan
kemudian menjualnya ke pasar, dimana jarak rumah ke pasar
cukup jauh. Ibu hamil dan ibu-ibu lainnya kemudian
menggunakan hasil penjualan dagangannya untuk membeli
keperluan keluarga yang telah habis. Selanjutnya ibu
menyiapkan makanan siang untuk keluarganya dan setelah
semua selesai ibu melakukan pekerjaan lain, mencuci pakaian,
mencuci piring, mengangkat air dan bahkan kembali lagi ke
kebun mengangkat kayu bakar untuk memasak di rumah.
Kebiasaan-kebiasaan melakukan pekerjaan berat ini berlaku

19
bagi seluruh ibu di Etnik Ngalum baik ibu tidak hamil maupun
tidak hamil (Kemenkes RI, 2012).
3) Indeks Kekayaan Rumah Tangga
Indeks kekayaan rumah tangga memiliki hubungan
dengan kejadian kematian neonatal. Rumah tangga dengan
indeks kekayaan rumah tangga terendah memiliki
kemungkinan 1,6 kali untuk mengalami kematian neonatal
dibandingkan rumah tangga dengan indeks kekayaan tinggi
(Bashir, dkk., 2013). Neonatus yang berasal dari ibu dengan
status sosial ekonomi dibawah rata-rata lebih rentan terhadap
kematian pada periode neonatal (Manzar, dkk., 2012; Gizaw,
dkk., 2014).
Penelitian yang dilakukan Mekonnen, dkk (2013) juga
menunjukkan terdapat hubungan antara indeks kekayaan
rumah tangga dengan kematian neonatal. Rumah tangga
miskin yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan memiliki
risiko yang meningkat terhadap kematian neonatal (Målqvist,
dkk., 2010). Ibu dan anak yang berasal dari keluarga miskin
memiliki risiko meningkat terhadap kematian neonatal dan
memiliki tantangan untuk mengakses pelayanan tepat waktu
dibandingkan keluarga yang lebih kaya (Lawn, dkk., 2009).

20
2.3.2 Determinan Terdekat (Proximate Determinants)
Menurut Titaley, dkk (2008), determinan atau faktor
terdekat terhadap kematian neonatal terdiri dari faktor ibu, faktor
neonatal, faktor sebelum melahirkan, faktor saat melahirkan dan
faktor setelah melahirkan.
2.3.2.1 Faktor Ibu (Maternal Factors)
Faktor ibu yang berpengaruh terhadap kelangsungan
hidup neonatal adalah umur ibu (Bashir, dkk., 2013;
Mekonnen, dkk., 2013; Upadhyay, dkk, 2012).
1) Umur Ibu
Pada umur dibawah 20 tahun, rahim dan panggul
sering kali belum tumbuh mencapai ukuran dewasa.
Akibatnya, ibu hamil pada usia itu mungkin mengalami
persalinan lama/macet atau gangguan lainnya karena
ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas dan
tanggungjawabnya sebagai orang tua. Ibu dianjurkan
hamil pada usia antara 20-35 tahun. Pada usia ini ibu
lebih siap hamil secara jasmani dan kejiwaan. Pada umur
35 tahun atau lebih, kesehatan ibu sudah menurun,
akibatnya ibu hamil pada usia itu mempunyai
kemungkinan lebih besar untuk mempunyai anak cacat,
persalinan lama dan perdarahan (Kemenkes RI, 2011).

21
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51%
kematian neonatal terjadi pada pada ibu usia muda (15-
24 tahun) (Yego, dkk., 2013). Umur ibu merupakan
faktor tidak langsung dan merupakan faktor confounding.
Ibu yang memiliki umur lebih dari 30 tahun bisa
mengalami kematian neonatal (Vandresse, 2008).
Terdapat hubungan antara variabel umur ibu saat
melahirkan dengan kejadian kematian bayi (Sugiharto,
2011) (Sugiharto, 2011; Mekonnen, dkk., 2013).
Penelitian yang dilakukan Bashir, dkk (2013)
menunjukkan bahwa kematian neonatal dipengaruhi oleh
umur ibu dengan OR sebesar 2.4 (≥ 40 tahun). Pada
penelitian Markovitz, dkk (2005) menunjukkan risko
kematian neonatal lebih tinggi pada ibu usia muda (12–
17 tahun) dari pada ibu usia lebih tua (18–19 tahun)
menunjukkan tidak ada perbedaan risiko kematian
neonatal.
Umur ibu memiliki pengaruh terhadap kematian
neonatal dengan nilai (Yani & Duarsa, 2013). Ibu yang
melahirkan pada kelompok umur <20 tahun dan
kelompok umur >30 tahun memiliki peluang lebih besar
untuk terjadinya kasus kematian bayi dibandingkan ibu
melahirkan umur 20-30 tahun (<20 tahun = OR: 1.53;
>30 tahun = OR: 1.46) (Faisal, 2010). Penelitian lainnya

22
juga menunjukkan bahwa ibu kelompok umur <20 tahun
dan >35 tahun memiliki risiko terjadinya kematian lebih
tinggi (OR: 1.595) dibandingkan dengan kelompok umur
antara 20-35 tahun (Wijayanti, 2013).
Namun hasil penelitian yang dilakukan
Onwuanaku dkk (2011) dan August, dkk., (2011)
menunjukkan bahwa umur ibu tidak memiliki hubungan
dengan kematian neonatal. Penelitian yang dilakukan
Pertiwi (2010) juga menunjukkan tidak ada hubungan
antara variabel umur ibu dengan kematian neonatal.
Tidak ada hubungan antara umur ibu kurang dari 20
tahun dengan kematian neonatal dini serta tidak ada
hubungan antara umur ibu lebih dari 35 tahun terhadap
kematian neonatal dini (Nugraheni, 2013).
Hasil penelitian kualitatif di salah satu daerah
rural Indonesia, yaitu pada masyarakat Etnik Madura
Jawa Timur, menemukan bahwa umumnya remaja putri
menikah sebelum menyelesaikan pendidikan pesantren,
yaitu sekitar usia 17 tahun (Kemenkes RI, 2012).
Penelitian kualitatif pada Etnik Nias, Sumatera Utara
juga menemukan bahwa masyarakat di Desa Hilifadölö
secara umum mentaati peraturan mengenai usia boleh
menikah yaitu minimal 18 tahun bagi perempuan dan 20
tahun bagi laki-laki. Selain itu, masih ditemukan

23
beberapa pasangan yang menikah sebelum umur
tersebut. Sebagian besar pasangan yang menikah
sebelum umur yang telah ditetapkan adalah pasangan
yang menikah di luar Pulau Nias (Kemenkes RI, 2012).
Bahkan hasil penelitian lainnya menemukan bahwa usia
perkawinan yang dianjurkan pada masyarakat Etnik
Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat yaitu minimal 16
tahun untuk perempuan dan minimal 18 tahun untuk
laki-laki (Kemenkes RI, 2012).
Pada masyarakat Etnik Ngalum, Provinsi Papua,
juga diketahui bahwa batasan usia boleh melakukan
pernikahan di Daerah Pegunungan Bintang adalah 18
tahun. Secara umum masyarakat yang benar-benar
memegang norma adat mematuhi aturan tersebut.
Namun, banyak juga masyarakat melanggar aturan
tersebut dengan melakukan perkawinan pada usia dini.
Diketahui, karena kurangnya pengetahuan para remaja
Etnik Ngalum mengenai kesehatan reproduksi, sehingga
banyak remaja yang hamil pada usia sangat muda yaitu
usia 13 tahun. Remaja tersebut melakukan aktivitas
belajar di sekolah dalam keadaan hamil dan pihak guru
tidak melarang mereka mengikuti kegiatan belajar karena
sudah memahami kondisi murid seperti itu di daerahnya.
Bahkan ada remaja yang telah memiliki anak, kemudian

24
menunggunya diluar kelas bersama ibunya. Selain itu,
para remaja tersebut cenderung tidak mengingat waktu
terakhir mengalami haid, sehingga mereka tidak
mengetahui berapa umur kandungannya. Kasus
kehamilan tidak hanya ditemukan pada anak dan remaja
tetapi juga terjadi pada ibu usia lebih dari 45 tahun.
Padahal kehamilan pada usia tersebut sangat berisiko
terhadap terjadinya komplikasi kehamilan. Apalagi
diketahui kasus anemia pada ibu hamil di Suku Ngalum
merupakan kasus yang paling tinggi di Papua (Kemenkes
RI, 2012).
2.3.2.2 Faktor Neonatal (Neonatal Factors)
Faktor neonatal yang berpengaruh terhadap
kelangsungan hidup neonatal yaitu infeksi/penyakit, paritas,
jarak kelahiran, jenis kelamin bayi, berat badan lahir,
inisiasi menyusu dini (Titalley, dkk., 2008; Debes, dkk.,
2013; Carlsen, dkk., 2013).
1) Infeksi/Penyakit
Penyakit tertentu dilihat sebagai indikator
biologi terhadap peranan determinan langsung
kematian neonatal (Mosley & Chen, 2003). Aspiksia,
kelahiran prematur, kelainan kongenital merupakan
penyebab terbanyak yang mengakibatkan buruknya
adaptasi bayi terhadap lingkungan diluar rahim

25
(Kliegman, dkk., 2011). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyebab utama kematian neonatal dini adalah
aspiksia (45%), infeksi (22%) dan kelainan kongenital
(11%) (Djaja, dkk., 2005).
Pada saat baru lahir, fungsi pernapasan yang
adekuat pada bayi sangat penting agar berhasil
beradaptasi dengan kehidupan diluar rahim. Pada janin,
organ pertukaran gas adalah plasenta sedangkan pada
saat lahir, paru-paru mengambil alih fungsi pernapasan.
Agar bayi bisa bertahan hidup, bayi harus mampu
mengembangkan fungsi paru-paru dengan udara,
melakukan pernapasan secara kontinu, dan
mempertahankan area kontak antara gas alveolus
dengan darah kapiler yang cukup besar agar efek
perpindahan gas dapat memenuhi kebutuhan metabolik
(Rudolph, dkk., 2007).
Infeksi yang relatif tidak membahayakan pada
orang dewasa bisa bersifat fatal jika terjadi pada bayi.
Gejala infeksi pada bayi sangat tidak jelas pada tingkat
awal kehidupan bayi, sehingga pengenalan terhadap
gejala infeksi pada bayi menjadi sangat penting. Pintu
masuk infeksi bisa melalui saluran pernapasan, saluran
pencernaan, saluran kemih, dan kulit (Price & Gwin,
2005).

26
Penelitian lainnya menunjukkan bahwa
pneumonia merupakan salah satu dari tiga penyebab
utama kematian neonatal yang berkontribusi terhadap
perbedaan kematian antara area rural dan urban pada
kematian neonatal (Yanping, dkk., 2010). Aspiksia,
infeksi dan kelainan kongenital merupakan faktor yang
berpengaruh terhadap kematian neonatal dini (Sriasih,
2012). Hasil penelitian Baqui, dkk (2006) menunjukkan
bahwa aspiksia, infeksi dan pneumonia merupakan
penyebab utama kematian pada neonatal selain.
Penelitian yang dilakukan Yego, dkk., (2013) juga
menunjukkan bahwa aspiksia merupakan salah satu
penyebab utama kematian neonatal.
Penelitian yang dilakukan Prabamurti, dkk
(2008) menunjukkan ada hubungan antara kondisi
usaha napas bayi dengan kematian neonatal.
Manajemen infeksi pada bayi baru lahir merupakan
salah satu intervensi yang dapat menurunkan kematian
pada neonatal (Khan, dkk., 2013).
2) Jenis Kelamin Bayi
Jenis kelamin merupakan karakteristik fisik
seseorang sebagai pria atau wanita (Andrews, 2009).
Bayi laki-laki cenderung lebih rentan terhadap penyakit
dibandingkan dengan bayi perempuan. Secara biologis,

27
bayi perempuan mempunyai keunggulan fisiologi pada
tubuhnya jika dibandingkan dengan bayi laki-laki
(Wells, 2000).
Hasil penelitian menunjukkan terdapat
hubungan antara jenis kelamin bayi dengan kematian
neonatal (Pertiwi, 2010). Penelitian yang dilakukan
Rahmawati (2007) juga menunjukkan bahwa jenis
kelamin secara statistik berhubungan dengan kematian
neonatal. Bayi laki-laki berisiko mengalami kematian
neonatal sebesar 1.4 kali dibandingkan dengan bayi
perempuan. Beberapa penelitian lainnya juga
menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin
dengan kematian neonatal (Pertiwi, 2010).
Namun penelitian lainnya menunjukkan tidak
terdapat hubungan antara jenis kelamin bayi dengan
kematian pada bayi (Faisal, 2010; Wijayanti, 2013).
Terjadi penurunan absolut kematian bayi yang lebih
tinggi pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan bayi
perempuan (Carlsen, dkk., 2013). Penelitian yang
dilakukan Dewi (2010) juga menunjukkan tidak
terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan
kematian neonatal.

28
Menurut penelitian kualitatif pada suku Nias
diketahui bahwa anak laki-laki (ono matua) dianggap
lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan.
Hal ini disebabkan karena suku Nias menganut sistem
patrilinear, yakni garis keturunan yang diikuti adalah
dari pihak laki-laki sehingga anak laki-lakilah yang
akan meneruskan keturunan/marga (ngaötö/mado)
keluarga dan juga mengurus harta atau warisan yang
dimiliki keluarga. Selain itu, sebagian besar anak laki-
laki yang sudah menikah tinggal bersama dengan orang
tua sehingga kelak ketika orang tua sudah tidak bisa
bekerja lagi maka anak laki-laki inilah yang akan
mengurus orang tuanya. Sehingga para ibu terus hamil
sampai akhirnya berhasil mendapatkan anak laki-laki
(Kemenkes RI, 2012).
3) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi
baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari
2500 gram (Saifuddin, dkk., 2009). BBLR sangat
terkait dengan kelahiran prematur dimana terjadi fungsi
organ belum matang, komplikasi akibat terapi dan
gangguan-gangguan tertentu (Kliegman, dkk., 2011).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian
menjadi lebih tinggi pada neonatus dengan berat lahir

29
kurang dari 2.5 kg (Onwuanaku dkk., 2011). Terdapat
hubungan antara berat bayi saat lahir dengan kematian
neonatal dini (Nugraheni, 2013). Anak lahir dengan
BBLR mempunyai kecenderungan untuk mengalami
kejadian kematian bayi sebesar 3.53 kali lebih besar
dibandingkan dengan ibu yang memiliki bayi lahir
BBLN (Faisal, 2010).
Pada beberapa penelitian lainnya juga
menunjukkan terdapat hubungan antara berat bayi lahir
dengan kematian neonatal (Schoeps, dkk., 2007;
Rahmawati, 2007; Dewi, 2010; Pertiwi, 2010;
Wijayanti, 2013). Namun, pada penelitian yang
dilakukan Sugiharto (2011) menunjukkan tidak terdapat
hubungan antara berat bayi lahir dengan kematian bayi.
2) Paritas
Menurut Kamus Saku Mosby (Kedokteran,
Keperawatan dan Kesehatan), paritas merupakan
klasifikasi perempuan berdasarkan jumlah bayi lahir
hidup dan lahir mati yang dilahirkannya pada umur
kehamilan lebih dari 20 minggu. Pada masa kehamilan,
rahim ibu teregang oleh adanya janin. Apabila terlalu
sering melahirkan, rahim akan semakin lemah. Apabila
ibu telah melahirkan 3 anak atau lebih, perlu

30
diwaspadai adanya gangguan pada waktu kehamilan,
persalinan dan nifas (Kemenkes RI, 2011).
Paritas lebih dari 3 menunjukkan ada hubungan
dengan kematian neonatal (Chaman, dkk., 2009).
Penelitian yang dilakukan Titaley, dkk (2008)
menunjukkan bahwa jarak kelahiran pendek
berhubungan dengan kematian neonatal. Hasil
penelitian lainnya menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara paritas dengan kematian neonatal
(Dewi, 2010). Penelitian yang dilakukan Sugiharto
(2011) menunjukan bahwa nomor urut kelahiran
memiliki hubungan dengan kematian bayi. Ibu yang
telah melahirkan lebih dari tiga anak mempunyai
kecenderungan untuk mengalami kejadian kematian
bayi sebesar 1.66 kali dibandingkan ibu yang telah
melahirkan 1-3 anak (Faisal, 2010). Penelitian lainnya
juga menyebutkan bahwa ibu yang memiliki paritas
lebih dari empat memiliki hubungan dengan kematian
neonatal (Rahmawati, 2007).
Namun, pada penelitian Rahmawati (2007)
menunjukkan bahwa ibu yang memiliki paritas satu
tidak menunjukkan adanya hubungan dengan kematian
neonatal. Penelitian lain yang dilakukan Nugraheni
(2013) juga menunjukkan tidak ada hubungan antara

31
urutan kelahiran pertama dengan kematian neonatal
dini. Pada penelitian yang dilakukan Wijayanti (2013)
menunjukkan tidak terdapat hubungan antara paritas
dengan kematian neonatal.
Hasil penelitian kualitatif lainnya menunjukkan
bahwa nilai anak bagi orang Toraja Sa’dan sangat
penting. Memiliki banyak anak masih menjadi
pandangan utama bagi sebagian besar penduduk
Sa’dan. Program Keluarga Berencana (KB) dari
pemerintah yang mengarahkan dua anak lebih baik
tidak berlaku bagi orang Toraja Sa’dan. Istilah KB bagi
orang Toraja Sa’dan diubah menjadi “keluarga besar”,
untuk menunjukkan banyaknya jumlah anak yang
mereka miliki. Bahkan seorang yang terpandang di
Toraja menceritakan bahwa dua bukan dua orang,
namun dua pasang (empat orang) untuk menunjukkan
anak yang beliau miliki. Ketiadaan seorang anak bagi
orang Toraja Sa’dan merupakan hal yang masiri’
(malu) dalam keluarga, dianggap lemah, dan dikasihani
oleh keluarga luas. Bahkan, sekalipun sudah memiliki
anak, tetapi baru satu, keluarga tersebut masih dianggap
belum lengkap (Kemenkes RI, 2012).
Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa
intervensi yang bisa dilakukan untuk mengontrol

32
jumlah kelahiran adalah penggunaan metode
kontrasepsi. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh,
menunjukkan bahwa penggunaan metode kontrasespi
berhubungan dengan kejadian kematian neonatal. Pada
ibu yang pernah menggunakan metode kontrasepsi
sekitar 39% lebih rendah terhadap kematian neonatal
dibandingkan ibu yang tidak pernah menggunakan
metode kontrasepsi (Chowdhury, dkk, 2013).
Pemakaian metode kontrasepsi (Contraceptive
Prevalence Rate) di Indonesia menurut hasil SDKI
2012 diketahui tidak ada perbedaan antara daerah
perdesaan dengan daerah perkotaan yaitu sebesar 62%.
Pemakaian kontrasepsi ini mengalami peningkatan dari
tahun 2007 sebelumnya yaitu sebesar 61%. Pemakaian
metode kontrasepsi modern juga mengalami
peningkatan dari 57% menjadi 58% (BPS, BKKBN,
Kemenkes & ICF International, 2013). Namun, angka
ini masih cukup jauh dari target MDGs 5 untuk
meningkatkan pemakaian metode kontrasepsi modern
sebesar 65% pada tahun 2015 (Kemenkes RI, 2014).
Diantara metode KB modern, metode KB yang
paling banyak digunakan wanita berstatus kawin adalah
suntikan dan pil (masing-masing 32 dan 14%). Peserta
KB suntikan mengalami peningkatan dari 12% tahun

33
1991 menjadi 32% tahun 2012. Sedangkan peserta KB
IUD mengalami penurunan dari 13% tahun 1991
menjadi 4% tahun 2012. Wanita di daerah perdesaan
cenderung lebih banyak menggunakan metode suntik
dibanding daerah perkotaan (masing-masing sebesar
28% dan 35%) sedangkan metode IUD,
MOW/sterilisasi wanita dan kondom lebih banyak di
gunakan di daerah perkotaan (BPS, BKKBN,
Kemenkes & ICF International, 2013).
Adapun total tingkat kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmetneed) wanita berstatus kawin 15-
49 tahun pada SDKI 2012 sebesar 11% (7% untuk
membatasi kelahiran dan 4% untuk menjarangkan
kelahiran). Walaupun unmetneed ini telah turun dari
13% pada SDKI 2007 menjadi 11% pada SDKI 2012
(BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013),
namun angka ini masih belum mencapai target MDGs 5
untuk menurunkan unmetneed menjadi 5% pada tahun
2015 (Kemenkes RI, 2014).
Hasil penelitian kualitatif di daerah Kalimantan
Tengah menemukan bahwa ibu hamil Suku Dayak
Siang Murung terpaksa tidak melakukan KB karena
alat di fasilitas kesehatan tidak tersedia (Kemenkes RI,
2012). Pada masyarakat suku lainnya diketahui bahwa

34
ibu sudah mengetahui tentang manfaat KB, namun ibu
tetap ingin memiliki anak lebih dari dua. Falsafah hidup
Banyak Anak Banyak Rezeki masih diyakini beberapa
warga hingga saat ini (Kemenkes RI, 2012).
4) Jarak Kelahiran
Apabila jarak kelahiran dengan anak
sebelumnya kurang dari 2 tahun, rahim dan kesehatan
ibu belum pulih dengan baik. Kehamilan dalam
keadaan ini perlu diwaspadai karena ada kemungkinan
pertumbuhan janin kurang baik, mengalami persalinan
yang lama atau perdarahan (Kemenkes RI, 2011). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jarak kelahiran kurang
dari 24 bulan (2 tahun) menunjukkan ada hubungan
dengan kematian neonatal (Chaman, dkk.,, 2009). Hasil
penelitian Titaley, dkk., (2008) juga menunjukkan
bahwa jarak kelahiran berhubungan dengan kematian
neonatal.
Penelitian yang dilakukan Smith, dkk (2003)
menunjukkan bahwa ibu yang memiliki jarak yang
pendek (<6 bulan) diantara kehamilannya memiliki
peluang lebih besar untuk mengalami komplikasi
pertama. Jarak antar kehamilan yang pendek
berhubungan peningkatan risiko kelahiran prematur dan
kematian neonatal. Penelitian lainnya menunjukkan

35
terdapat hubungan antara jarak antar kelahiran dengan
kematian bayi (Sugiharto, 2011). Namun, penelitian
lainnya menunjukkan tidak terdapat hubungan antara
jarak kelahiran dengan kematian neonatal dini
(Nugraheni, 2013). Jarak antar kelahiran tidak
berhubungan dengan kematian neonatal (Wijayanti,
2013).
5) Kelahiran Prematur
Persalinan prematur adalah persalinan yang
terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu (antara
20-37 minggu) (Saifuddin, dkk., 2009). Persalinan
prematur merupakan hal yang berbahaya karena
mempunyai dampak potensia terhadap kematian
perinatal (Wiknjosastro, dkk., 2002). Persalinan
prematur pada bayi dengan BBLR sangat tergantung
dengan usia kehamilan. Kelahiran prematur
berhubungan dengan kondisi kesehatan dimana terjadi
ketidakmampuan uterus untuk menahan janin akibat
ketuban pecah dini, pemisahan dini plasenta, kehamilan
ganda atau kondisi lain yang menyebabkan terjadinya
kontraksi uterus sebelum waktu persalinan (Kliegman,
dkk., 2011).
Hasil penelitian menunjukkan terdapat
hubungan antara umur kehamilan saat melahirkan

36
dengan kematian pada neonatal. Bayi yang dilahirkan
pada umur kehamilan kurang dari 37 minggu
menunjukkan angka kematian neonatal yang tinggi
dibandingkan dengan ibu melahirkan dengan umur
kehamilan 37 minggu atau lebih (Onwuanaku dkk.,
2011). Penelitian yang dilakukan Schoeps, dkk (2007)
menunjukkan terdapat hubungan antara kelahiran
prematur dengan kematian neonatal. Penelitian lainnya
menemukan bahwa kelahiran prematur pada minggu ke
32-36 memiliki risiko yang rendah terhadap kematian
neonatal dibandingkan kelahiran prematur kurang dari
32 minggu (Lisonkova, dkk., 2012).
6) Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
ASI dapat memberikan keuntungan imunitas,
gizi, dan psikososial. Jika dibandingkan dengan susu
sapi, ASI lebih banyak mengandung zat besi, gula,
vitamin A, C dan Vitamin B3. ASI memiliki protein
dan kalsium yang lebih rendah daripada susu sapi, tapi
jumlah tersebut lebih baik bagi bayi. ASI lebih mudah
dicerna karena gelembung lemak berukuran kecil serta
terbebas dari bakteri. Sehingga, bayi menjadi lebih
kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu pada anak-
anak. Bayi yang mendapatkan ASI lebih cenderung
tidak mengalami gangguan pencernaan (Price & Gwin,

37
2005). Jadi, manfaat selain menyediakan nilai gizi, ASI
juga memberikan perlindungan dalam melawan
sejumlah besar infeksi (Kliegman, dkk., 2011).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiasi
menyusu dini memberikan risiko yang rendah terhadap
kejadian kematian neonatal pada bayi dengan BBLR
(RR=0.580 dan bayi dengan infeksi yang berhubungan
dengan kematian neonatal (RR = 0.55) (Debes, dkk.,
2013). Penelitian yang dilakukan Pertiwi (2010)
menunjukkan bahwa inisiasi menyusu dini
berhubungan dengan penurunan risiko kematian
neonatal. Inisiasi menyusu setelah satu jam pertama
memiliki risiko dua kali lipat terhadap kematian
neonatal.
Penelitian lainnya menemukan bahwa ibu yang
tidak memberikan ASI pada bayinya mempunyai
kecenderungan untuk mengalami kematian bayi sebesar
10.67 kali lebih besar dibandingkan ibu yang
memberikan ASI pada waktu <1 jam (Faisal, 2010).
Penelitian yang dilakukan Sugiharto (2011) juga
menunjukkan terdapat hubungan antara waktu pertama
bayi mendapatkan ASI dengan kejadian kematian bayi.
Namun, pada penelitian yang dilakukan Dewi (2010)
dan Rahmawati (2007) menunjukkan tidak terdapat

38
hubungan antara pemberian Air Susu Ibu (ASI) dengan
kematian neonatal.
2.3.2.3 Faktor Sebelum Melahirkan (Pre-Delivery Factors)
Faktor sebelum melahirkan yang berpengaruh
terhadap kelangsungan hidup neonatal adalah kunjungan
antenatal dan komplikasi kehamilan (Singh, dkk., 2013,
Bashir, dkk., 2013; Singh, dkk 2014).
1) Kunjungan Antenatal
Pelayanan kesehatan neonatal harus dimulai
sebelum bayi dilahirkan melalui pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada ibu hamil. Berbagai bentuk upaya
pencegahan dan penanggulangan dini terhadap faktor-
faktor yang memperlemah kondisi seorang ibu hamil
perlu diprioritaskan seperti gizi rendah, anemia dan jarak
antar kelahiran dekat (Saifudin, dkk, 2009). Asuhan
antenatal merupakan upaya preventif program pelayanan
kesehatan obstetrik untuk optimalisasi kesehatan
maternal dan neonatal melalui serangkaian kegiatan rutin
selama kehamilan (Saifuddin, dkk., 2010). Adanya
manajemen yang baik saat bayi masih dalam kandungan,
selama persalinan, segera setelah dilahirkan dan
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setelahnya
akan menghasilkan bayi yang sehat (Saifudin, dkk.,
2009).

39
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan
akses ibu terhadap layanan antenatal adalah cakupan
kunjungan pertama (K1) dan cakupan kunjungan
minimal empat kali (K4) dengan tenaga kesehatan sesuai
standar. K1 sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada
trimester pertama sebelum minggu ke-8. Sedangkan K4
sebaiknya dilakukan minimal satu kali pada trimester
pertama (0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester
ke-2 (≥12-24 minggu) dan minimal 2 kali pada trimester
ke-3 (≥24 minggu sampai kelahiran) (Kemenkes RI,
2012).
Janin yang melakukan aktivitas secara aktif
menununjukkan janin berada dalam kondisi baik.
Adanya penurunan aktivitas janin menunjukkan janin
dalam kondisi bahaya dan membutuhkan penanganan
secepatnya (Ladewig, dkk., 2006). Kondisi seperti ini
bisa diketahui apabila ibu melakukan kunjungan
antenatal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara kunjungan antenatal dengan kematian
neonatal (<4, ≥4). Kunjungan ANC merupakan faktor
protektif yang berhubungan dengan kematian neonatal
pada minggu pertama (OR: 0.65) dan pada hari pertama
kehidupan (OR: 0.71) (Singh, dkk., 2014). Beberapa

40
penelitian lainnya yang dilakukan di Indonesia juga
menunjukkan terdapat hubungan antara kunjungan
antenatal dengan kematian neonatal (Rahmawati, 2007;
Dewi, 2010; Sukamti, 2011; Sugiharto, 2011).
Pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat
mencegah kematian neonatal (Sukamti, 2011). Ibu yang
tidak pernah melakukan kunjungan ANC mempunyai
kecenderungan untuk mengalami kematian bayi sebesar
.3.09 kali lebih besar dibandingkan ibu yang melakukan
kunjungan ANC sesuai standar minimal (Faisal, 2010).
Penelitian lainnya menemukan bahwa bayi yang
dilahirkan dari ibu dengan pelayanan antenatal tidak
lengkap berisiko mengalami kematian neonatal sebesar
16.32 lebih besar daripada bayi yang dilahirkan ibu
dengan pelayanan antenatal lengkap (Yani & Duarsa,
2013).
Ibu yang melakukan kunjungan ke fasilitas
kesehatan selama kehamilannya akan menerima
pemeriksaan dan pengidentifikasian kondisi-kondisi
yang berkaitan dengan komplikasi serta edukasi
mengenai tanda bahaya, potensi komplikasi dan tempat
untuk mencari pertolongan (Mahmood, 2002). Penelitian
lainnya oleh Hinderaker, dkk (2003) di wilayah rural
Tanzania menegaskan bahwa sekitar 62% kasus

41
kematian neonatal sebetulnya dapat dicegah melalui
kegiatan layanan antenatal di fasilitas layanan kesehatan.
Penyedia layanan kesehatan bertanggungjawab terhadap
lebih dari setengah dari faktor-faktor terhadap kematian
neonatal yang dapat dicegah, baik dari faktor kegagalan
klinik antenatal untuk merujuk ke fasilitas layanan
kesehatan yang lebih tinggi maupun kelalaian yang
terjadi di tingkat rumah sakit itu sendiri. Hal ini
mengindikasikan adanya potensi untuk melakukan
peningkatan layanan antenatal dan konsultasi rutin
termasuk layanan kehamilan di rumah sakit.
Kunjungan antenatal yang terlambat
kemungkinan menghambat ibu untuk mendapatkan
manfaat sepenuhnya dari strategi pencegahan pada
layanan antenatal misalnya suplementasi zat besi, asam
folat, pengobatan untuk infeksi cacing dan pengobatan
untuk pencegahan malaria pada kehamilan (Eijk, dkk.,
2006).
Penelitian yang dilakukan Titaley, dkk (2010) di
Indonesia menemukan bahwa yang berhubugan sangat
kuat dengan rendahnya kunjungan antenatal yaitu bayi
dari ibu yang tinggal di daerah rural, memiliki tingkat
indeks kekayaan rumah tangga rendah, berasal dari ibu
dengan berpendidikan rendah, jumlah kelahiran tinggi

42
dan jarak kelahiran kurang dari 2 tahun. Penelitian
kualitatif yang dilakukan di beberapa daerah rural
Indonesia menemukan bahwa ibu hamil suku Alifuru di
Provinsi Maluku baru akan memeriksakan kehamilannya
saat terlihat perubahan yang nyata pada tubuh ibu
(terlihat jelas ibu hamil). Kunjungan saat terakhir
menstruasi (K1) dan kunjungan pada trimester kedua
relatif kecil (Kemenkes RI, 2012).
Penelitian kualitatif lainnya menemukan bahwa
alasan ibu Etnik Dayak Siang Murung di Kalimantan
Tengah tidak melakukan pemeriksaan kehamilan yaitu
karena Puskesmas Pembantu yang ada di desa tidak
menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap seperti
obat-obatan, wilayah puskesmas pembantu cukup sulit
dijangkau oleh masyarakat di RT lain dan tenaga
kesehatan yang ditugaskan sering tidak berada di tempat
sehingga membuat masyarakat kesulitan saat
membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, sebagian
masyarakat memilih langsung melakukan pemeriksaan di
Rumah Sakit yang ada di Kabupaten. Rumah sakit
berada sangat jauh dari desa dan harus melewati jalan
yang cukup sulit terutama apabila terjadi hujan
disamping memerlukan biaya yang cukup besar.
Sehingga beberapa ibu hamil lainnya memilih tidak

43
memeriksakan kehamilannya dengan alasan petugas
kesehatan sering tidak ada di tempat (Kemenkes RI,
2012).
Penelitian lainnya pada ibu hamil Etnik
Gorontalo Provinsi Gorontalo menemukan bahwa
sebagian ibu hamil yang melakukan pemeriksaan
kehamilan kepada bidan tidak memakan vitamin yang
diberikan dengan alasan tidak diberi penjelasan manfaat
minum obat. Ibu juga tidak meminum vitamin penambah
darah dengan alasan vitamin rasanya pahit (Kemenkes
RI, 2012).
Namun, penelitian lainnya menunjukkan tidak
ada hubungan antara variabel antenatal dengan kematian
neonatal (Pertiwi, 2010). Penelitian yang dilakukan
Nugraheni (2013) juga menunjukkan tidak terdapat
hubungan antara kunjungan antenatal dengan kematian
neonatal dini (Nugraheni, 2013). Penelitian lainnya juga
menunjukkan tidak ada hubungan antara ANC dengan
kematian neonatal (Wijayanti, 2013).
2) Komplikasi Kehamilan
Menurut McCarthy & Maine (1992), komplikasi
kehamilan terdiri dari perdarahan, infeksi, pre-
eklampsia/eklampsia, persalinan lama/macet dan abortus.

44
Komplikasi kehamilan merupakan masalah kesehatan
yang sering terjadi selama kehamilan dan persalinan.
Masalah kesehatan ibu bisa saja terjadi sebelum
kehamilan yang pada akhirnya berdampak komplikasi
pada masa kehamilan. Komplikasi ini dapat berdampak
pada kesehatan ibu, kesehatan bayi ketika dilahirkan,
atau keduanya (Wiknjosastro, dkk., 2002).
Perdarahan yang terjadi pada kehamilan harus
selalu dianggap sebagai kelainan yang berbahaya.
Perdarahan setelah kehamilan dua minggu biasanya lebih
banyak dan lebih berbahaya daripada sebelum 22 minggu
sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda.
Perdarahan yang berbahaya umumnya bersumber pada
kelainan plasenta. Kejang merupakan salah satu gejala
pada wanita penderita eklampsia yang biasanya juga
diikuti dengan koma. Biasanya eklampsia terjadi
didahului pre-eklampsia, sehingga pengawasan antenatal
yang teliti dan teratur merupakan salah satu upaya untuk
mencegah timbulnya eklampsia (Wiknjosastro, dkk.,
2002).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara komplikasi kehamilan dengan kematian
neonatal dini. Prevalensi kematian neonatal dini lebih
besar pada kelompok komplikasi kehamilan

45
dibandingkan tidak mengalami komplikasi kehamilan
(Nugraheni, 2013). Penelitian lainnya menunjukkan ada
hubungan antara komplikasi selama kehamilan dengan
kejadian kematian neonatal (95% CI, 1.690-3.897)
(Wijayanti, 2013). Ibu yang mengalami komplikasi
kehamilan memiliki risiko 1.8 kali dibandingkan ibu
yang tidak mengalami komplikasi kehamilan
(Rahmawati, 2007). Hasil penelitian (Schoeps, dkk.,
2007) juga menunjukkan terdapat hubungan antara
komplikasi saat kehamilan dengan kematian neonatal.
Penelitian lainnya yang dilakukan di daerah rural
Bangladesh juga menunjukkan bahwa ibu yang
mengalami pendarahan selama kehamilannya
berhubungan kuat dengan adanya peningkatan risiko
terhadap kematian neonatal (Owais, dkk., 2013).
Penelitian yang dilakukan pada ibu hamil Etnik
Ngalum Provinsi Papua menemukan bahwa ibu yang
hamil tetap mengalami komplikasi walaupun telah
melakukan pemeriksaan kehamilan karena hamil pada
usia lebih dari 45 tahun dan memiliki anak rata-rata11-14
anak dengan jarak kelahiran yang berdekatan. Tingkat
anemia ibu hamil pada suku ini paling tinggi
dibandingkan etnik lainnya. Kondisi seperti ini
menyebabkan tingginya kejadian retensio plasenta saat

46
melahirkan. Padahal petugas kesehatan telah
memberikan tablet penambah darah yang seharusnya
diberikan tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali
karena tingginya kasus anemia. Namun, petugas
kesehatan tidak bisa memastikan apakah obat yang
diberikan rutin diminum oleh ibu hamil setiap hari
(Kemenkes RI, 2012). Hasil penelitian pada ibu hamil
Etnik Gorontalo Provinsi Gorontalo menemukan
sebagian ibu hamil yang melakukan pemeriksaan
kehamilan tidak memakan vitamin yang diberikan
dengan alasan tidak diberi penjelasan manfaat minum
obat. Ibu juga tidak meminum vitamin penambah darah
dengan alasan rasanya pahit (Kemenkes RI, 2012).
Anemia atau kadar Hb <11 g/dl yang salah
satunya bisa disebabkan karena defisiensi besi sehingga
perlu diberi obat penambah zat besi. Kondisi anemia
pada ibu hamil sangat berbahaya bisa menyebabkan
terjadinya perdarahan pasca persalinan (WHO;
Kemenkes RI; POGI; IBI, 2013). Perdarahan merupakan
penyebab terbanyak kematian pada ibu (Zakariah, dkk.,
2009). Berdasarkan hasil review bahwa dampak anemia
pada ibu hamil terhadap bayinya bervariasi sesuai tingkat
defisiensi Hb yang dialami oleh ibu. Defisiensi Hb <11
gr/dl berhubungan dengan peningkatan kematian pada

47
perinatal. Peningkatan 2-3 kali kematian perinatal pada
ibu dengan Hb <8.0 gr/dl dan peningkatan 8-10 kali
ketika kadar Hb <5.0 gr/dl. Selain itu, penurunan
terhadap berat bayi lahir dan lambatnya pertumbuhan
janin terjadi ketika kadar Hb ibu <8.0 gr/dl (Kalaivani,
2009).
Penelitian lainnya yang dilakukan Dewi (2010)
menunjukkan tidak ada hubungan antara komplikasi
kehamilan dengan kematian neonatal.
2.3.2.4 Faktor Saat Melahirkan (Delivery Factors)
Faktor saat melahirkan yang berpengaruh terhadap
kelangsungan hidup neonatal adalah penolong persalinan,
komplikasi persalinan, persalinan cesario dan tempat
persalinan (Titalley, dkk., 2008; Singh, dkk., 2013; Bashir,
dkk., 2013; Chaman, dkk 2009; Singh, dkk., 2014).
1) Penolong Persalinan
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
merupakan pelayanan persalinan yang aman yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (Depkes
RI, 2009). Penolong persalinan memiliki tugas untuk
mengawasi ibu yang sedang berada pada proses
persalinan dan mengecek apakah semua persiapan untuk
persalinan sudah lengkap serta member obat kepada ibu
jika terdapat indikasi bagi ibu maupun anaknya

48
(Wiknjosastro, dkk., 2002). Penanganan medis yang
tepat dan memadai selama melahirkan dapat menurunkan
risiko komplikasi yang bisa menyebabkan kesakitan
serius pada ibu dan bayinya (BPS, BKKBN, Kemenkes
& ICF International, 2013).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara penolong persalinan dengan kematian
neonatal. Penolong persalinan memiliki hubungan
dengan kematian neonatal pada minggu pertama
kehidupan yang terjadi di Asia (Singh, dkk., 2014).
Penelitian yang dilakukan di Indonesia juga
menunjukkan terdapat hubungan antara penolong
persalinan dengan kematian neonatal (Pertiwi, 2010;
Wijayanti, 2013). Ibu yang melahirkan dengan bantuan
tenaga bukan kesehatan mempunyai kecenderungan
untuk mengalami kejadian kematian bayi sebesar 2.01
kali lebih besar dibandingkan ibu yang melahirkan bayi
dengan bantuan tenaga kesehatan (Faisal, 2010).
Penelitian yang dilakukan Yani & Duarsa (2013) juga
menemukan bahwa penolong persalinan berhubungan
dengan kejadian kematian neonatal.
Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 83%
persalinan pada kurun waktu 2008-2012 ditolong oleh
tenaga kesehatan profesional (62% perawat/bidan/bidan

49
desa, 20% dokter kandungan dan 1% dokter). Proporsi
ini mengalami peningkatan dari hasil SDKI 2007 sebesar
73% persalinan yang ditolong tenaga kesehatan
profesional (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF
International, 2013).
Menurut Yego, dkk (2013) akses terhadap
penolong persalinan terampil termasuk dokter maupun
bidan penting untuk mencegah kematian maternal dan
neonatal. Penolong persalinan yang sebagian besar
dilakukan oleh penolong persalinan dengan keterampilan
yang rendah dapat berkontribusi terhadap kejadian
kematian neonatal dan kematian maternal. Pada
penelitian lainnya juga menemukan bahwa perlunya
pelatihan bagi penolong persalinan agar penolong
persalinan mampu menangani kasus infeksi yang
diketahui merupakan penyebab terbanyak kasus
kematian neonatal (Turnbull, dkk., 2011).
Pada penelitian yang dilakukan Kusiako, dkk
(2000) menunjukkan bahwa komplikasi pada saat
melahirkan merupakan penyebab sepertiga kematian
pada perinatal. Padahal peningkatan layanan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang terkualifikasi dan layanan
neonatus yang lebih baik seharusnya dapat menurunkan
kematian pada perinatal. Penelitian yang dilakukan di

50
Jawa Barat menemukan bahwa ibu yang mengakses
penolong persalinan terlatih atau melakukan persalinan
di fasilitas layanan kesehatan sebagian besar dilakukan
ketika ibu mengalami komplikasi kehamilan (Titaley,
dkk., 2010). Hasil penelitian kualitatif pada masyarakat
Suku Nias juga menemukan bahwa terkadang keluarga
alot dalam memutuskan merujuk ke rumah sakit atau
puskesmas. Hal tersebut menyebabkan ibu terlambat
mendapatkan pertolongan dari petugas kesehatan. Ibu
yang melakukan persalinan di rumah sakit biasanya ibu
yang sudah mengalami masalah pada persalinannya
(Kemenkes RI, 2012).
Review yang dilakukan Upadhyay, dkk (2012)
juga menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya yang
terampil merupakan salah satu penyebab kematian
neonatal yang terjadi di daerah rural India. Kurangnya
sumber daya manusia yang terampil berdampak pada
rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh
neonatus. Sehingga penyediaan tenaga kesehatan yang
terkualifikasi ke daerah rural merupakan tantangan yang
harus dilakukan untuk menghindari kematian pada
neonatal.
Pada penelitian Zimba, dkk (2012) juga
menemukan bahwa walaupun Malawi mengalami

51
peningkatan jumlah penolong persalinan terampil, tetapi
sebagian besar ibu dan bayi baru lahir yang mengalami
komplikasi masih belum mendapatkan penanganan
kesehatan yang diperlukan. Pada penelitian lainnya
diketahui bahwa peralatan dan kualitas layanan yang
tidak memadai juga merupakan tantangan di wilayah
Afrika dan Asia (Harvey, dkk., 2007). Menurut Singh,
dkk (2014) definisi tenaga penolong persalinan yang ada
saat ini, tidak mencakup unsur layanan yang memadai.
Walaupun sebagian besar negara di Afrika dan Asia
mengalami peningkatan jumlah tenaga penolong
persalinan terampil, sebagian besar setiap individu yang
disebut sebagai tenaga kesehatan terampil tidak memiliki
kompetensi yang diperlukan atau peralatan yang
dibutuhkan untuk mengatasi komplikasi pada ibu dan
bayi baru lahir. Berdasarkan tingginya kematian pada
minggu pertama kehidupan, pelatihan intervensi pada
masa intrapartum harus ditekankan.
Adapun penyebab masih tingginya kematian
neonatal pada penolong pesalinan non tenaga kesehatan
di daerah rural Indonesia kemungkinan terjadi karena
masih rendahnya akses ibu hamil terhadap tenaga
keseahatan.menurut. Seperti diketahui hasil penelitian
Titaley, dkk (2010) bahwa di beberapa daerah terpencil

52
di Indonesia, bidan desa yang pada beberapa wilayah
merupakan satu-satunya tenaga kesehatan penolong
persalinan yang tersedia, terkadang pergi keluar desa
(Titaley, dkk., 2010).
Masih tingginya kematian pada penolong
persalinan non tenaga kesehatan kemungkinan besar
karena pengetahuan dan keterampilan penolong
persalinan bukan tenaga kesehatan yang sangat kurang
tentang penanganan persalinan pada ibu bersalin,
maupun tentang penanganan bayi baru lahir. Apalagi
penanganan ibu dengan gejala eklampsia, akan sangat
sulit bagi penolong bukan tenaga kesehatan untuk dapat
melakukan tindakan yang tepat. Pengetahuan penolong
yang kurang tentang bagaimana melakukan upaya
pencegahan terhadap kemungkinan bayi aman dari risiko
terjadinya gangguan thermoregulasi, gangguan respirasi,
dan risiko lainnya yang biasa melekat pada bayi baru
lahir, sangat berpengaruh besar terhadap status kesehatan
neonatus. Jika penanganannya kurang tepat maka
kecenderungan terjadinya risiko kematian akan semakin
besar (Astuti, dkk., 2010).
Namun, pada beberapa penelitian lainnya
menunjukkan tidak ada hubungan antara penolong
persalinan dengan kematian bayi (Sugiharto, 2011;

53
Dewi, 2010). Penelitian yang dilakukan Nugraheni
(2013) juga menunjukkan tidak terdapat hubungan antara
penolong persalinan dengan kematian neonatal dini.
2) Komplikasi Persalinan
Komplikasi persalinan merupakan tanda bahaya
yang terjadi pada saat persalinan. Komplikasi yang
terjadi pada saat persalinan diantaranya adalah
perdarahan, ketuban pecah sebelum waktunya dan
persalinan lama (Kemenkes RI, 2011). Perdarahan yang
banyak segera atau dalam satu jam setelah melahirkan
sangat berbahaya dan merupakan penyebab kematian ibu
paling banyak. Ibu harus segera mendapatkan
pertolongan agar bisa diselamatkan (Kemenkes RI,
2011). Ketuban pecah dini merupakan keadaan pecahnya
selaput ketuban sebelum persalinan (WHO; Kemenkes
RI; POGI; IBI, 2013). Biasanya ketuban pecah saat
menjelang persalinan, setelah ada tanda awal persalinan
seperti mulas dan keluarnya lendir bercampur sedikit
darah. Bila ketuban pecah dan cairan ketuban keluar
sebelum ibu mengalami tanda-tanda persalinan, janin dan
ibu akan mudah terinfeksi (Kemenkes RI, 2011).
Kemudian, persalinan lama merupakan waktu
persalinan yang memanjang akibat kemajuan persalinan
yang terhambat (WHO; Kemenkes RI; POGI; IBI, 2013).

54
Biasanya persalinan berlangsung kurang dari 12 jam.
Apabila persalinan lebih dari 12 jam perlu ibu harus
segera mendapatkan pertolongan di rumah sakit untuk
menyelamatkan janin serta mencegah perdarahan dan
infeksi pada ibu (Kemenkes RI, 2011).
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan
antara komplikasi kelahiran dengan kematian neonatal
(Dewi, 2010). Ibu yang memiliki komplikasi persalinan
meningkatkan risiko kematian neonatal sebesar 1.5 kali
dibandingkan ibu yang tidak mengalami komplikasi
persalinan (Rahmawati, 2007). Penelitian lainnya yang
dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
komplikasi saat persalinan dengan kematian neonatal
(Schoeps, dkk., 2007). Penelitian lainnya yang dilakukan
di daerah rural Bangladesh juga menunjukkan bahwa ibu
yang mengalami pendarahan selama kehamilannya
berhubungan kuat dengan adanya peningkatan risiko
terhadap kematian neonatal (Owais, dkk., 2013).
Penelitian yang dilakukan pada ibu hamil Etnik
Ngalum Provinsi Papua menemukan bahwa ibu yang
hamil tetap mengalami komplikasi walaupun telah
melakukan pemeriksaan kehamilan karena hamil pada
usia lebih dari 45 tahun dan memiliki anak rata-rata11-14
anak dengan jarak kelahiran yang berdekatan. Tingkat

55
anemia ibu hamil pada suku ini paling tinggi
dibandingkan etnik lainnya. Kondisi seperti ini
menyebabkan tingginya kejadian retensio plasenta saat
melahirkan. Padahal petugas kesehatan telah
memberikan tablet penambah darah yang seharusnya
diberikan tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali
karena tingginya kasus anemia. Namun, petugas
kesehatan tidak bisa memastikan apakah obat yang
diberikan rutin diminum oleh ibu hamil setiap hari
(Kemenkes RI, 2012).
Hasil penelitian pada ibu hamil Etnik Gorontalo
Provinsi Gorontalo menemukan sebagian ibu hamil yang
melakukan pemeriksaan kehamilan tidak memakan
vitamin yang diberikan dengan alasan tidak diberi
penjelasan manfaat minum obat. Ibu juga tidak
meminum vitamin penambah darah dengan alasan
rasanya pahit (Kemenkes RI, 2012).
Anemia atau kadar Hb <11 g/dl yang salah
satunya bisa disebabkan karena defisiensi besi sehingga
perlu diberi obat penambah zat besi. Kondisi anemia
pada ibu hamil sangat berbahaya bisa menyebabkan
terjadinya perdarahan pasca persalinan (WHO;
Kemenkes RI; POGI; IBI, 2013). Perdarahan merupakan
penyebab terbanyak kematian pada ibu (Zakariah, dkk.,

56
2009). Berdasarkan hasil review bahwa dampak anemia
pada ibu hamil terhadap bayinya bervariasi sesuai tingkat
defisiensi Hb yang dialami oleh ibu. Defisiensi Hb <11
gr/dl berhubungan dengan peningkatan kematian pada
perinatal. Peningkatan 2-3 kali kematian perinatal pada
ibu dengan Hb <8.0 gr/dl dan peningkatan 8-10 kali
ketika kadar Hb <5.0 gr/dl. Selain itu, penurunan
terhadap berat bayi lahir dan lambatnya pertumbuhan
janin terjadi ketika kadar Hb ibu <8.0 gr/dl (Kalaivani,
2009).
Penelitian lainnya menunjukkan tidak ada
hubungan antara komplikasi selama persalinan dengan
kematian neonatal (Wijayanti, 2013).
3) Persalinan Caesar
Persalinan caesar merupakan tindakan untuk
melahirkan bayi melalui sayatan pada dinding uterus
yang masih utuh (Saifuddin, dkk., 2009). Persalinan
caesar merupakan operasi besar yang dilakukan pada
saat terdapat alasan kesehatan tertentu (Whalley, dkk.,
2008).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persalinan
dengan cara bedah caesar memiliki hubungan dengan
kematian neonatal (Bashir, dkk., 2013). Bayi dari ibu
yang kembali melakukan persalinan dengan cara caesar

57
memiliki angka kesakitan (penyakit pernapasan) lebih
tinggi dan tinggal di rumah sakit lebih lama
dibandingkan ibu yang melakukan persalinan per
vaginam yang sebelumnya melakukan persalinan caesar
(Kamath, dkk., 2009). Kematian neonatal meningkat
sejalan dengan tingginya persalinan caesar yang
dilakukan pada kondisi kegawatdaruratan. Selain itu
secara keseluruhan, persalinan caesar (kondisi
kegawatdaruratan maupun non kegawatdaruratan)
berhubungan dengan meningkatnya kesakitan pada
neonatal (Shah, dkk., 2009).
Hasil review literatur menyebutkan bahwa
persalinan caesar tanpa adanya alasan kesehatan
(kegawatdaruratan) juga bisa membahayakan kondisi ibu
dan janinnya baik dari segi pendek maupun lamanya
waktu yang diperlukan prosedur persalinan caesar
dibandingkan persalinan normal (Wiklund, dkk., 2012).
Penelitian lainnya menunjukkan tidak terdapat
hubungan antara persalinan caesar terhadap kematian
neonatal dini (Nugraheni, 2013). Penelitian yang
dilakukan Wijayanti (2013) juga menunjukkan tidak ada
hubungan antara riwayat operasi caesar dengan kejadian
kematian neonatal.

58
4) Tempat Persalinan
Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap
kematian ibu dan anak adalah terbatasnya tempat
persalinan yang memadai. Upaya untuk mengurangi
risiko kematian ibu dan anak adalah sangat penting
dengan cara meningkatkan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang profesional yang dilakukan di fasilitas
kesehatan (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF
International, 2013). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ibu yang melahirkan di fasilitas non kesehatan
mempunyai kecenderungan untuk mengalami kejadian
kematian bayi sebesar 1.35 kali lebih besar dibandingkan
ibu yang melahirkan bayi di fasilitas kesehatan (Faisal,
2010). Melahirkan diluar fasilitas layanan kesehatan
lebih memungkinkan untuk mengalami kematian
neonatal dibandingkan melahirkan dilakukan di fasilitas
layanan kesehatan (Ajaari, dkk., 2012).
Penelitian kualitatif pada Suku Mamasa,
Sulawesi Barat menemukan bahwa walaupun telah
terdapat program Jampersal (Jaminan Persalinan) namun
belum diketahui oleh ibu-ibu di wilayah tersebut. Selain
itu, mereka belum mempercayai sepenuhnya bahwa
bersalin di fasilitas kesehatan tidak dikenakan
biaya/gratis. Apalagi jika mereka harus di rujuk ke

59
Rumah Sakit, akan membutuhkan biaya yang lebih besar.
Selain itu, permasalahan juga terdapat pada tenaga
kesehatan dimana belum keluarnya pembayaran (klaim)
terhitung sejak 2011-2012. Padahal semua catatan dan
bukti telah terkumpul dengan rapi. Kejadian tersebut
terjadi pada semua bidan di desa dan kecamatan di
Kabupaten Mamasa. Meskipun demikian, bidan desa
tetap melayani dan menggratiskan persalinan yang
ditolong di fasilitas persalinan (Kemenkes RI, 2012).
Penelitian lainnya pada suku Toraja Sa’dan
menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan lain,
pertimbangan ekonomi untuk memenuhi biaya-biaya di
luar cakupan Jampersal, seperti transportasi, uang makan
keluarga yang menungguinya di sarana kesehatan, anak-
anak kecil yang ditinggalkan, hewan-hewan ternak
(pemeliharaan babi) yang menjadi tanggung jawab ibu.
Pendapatan sehari-hari menjadi pertimbangan lain
mengapa ibu memutuskan untuk melahirkan sendiri di
rumahnya. Selain itu, beberapa wilayah Toraja Sa’dan
memang berada jauh dari sarana pelayanan kesehatan.
Selain jarak yang jauh, akses warga terhadap pelayanan
kesehatan dipersulit dengan kondisi jalan yang rusak.
Sarana transportasi menjadi sulit dan mahal karena
kondisi jalan yang rusak parah (Kemenkes RI, 2012).

60
Hasil penelitian lainnya menunjukkan tidak ada
hubungan antara tempat persalinan dengan kematian bayi
(Sugiharto, 2011). Beberapa penelitian lainnya juga
menunjukkan tidak ada hubungan antara jenis tempat
persalinan dengan kematian neonatal (Pertiwi, 2010;
Nugraheni, 2013; Wijayanti, 2013). Penelitian yang
dilakukan di daerah rural Burkina Faso bahwa kematian
bayi lebih tinggi terjadi di fasilitas layanan kesehatan.
Adanya fasilitas pelayanan kesehatan tidak akan
memberikan perbedaan yang berarti jika fasilitas tersebut
tidak memiliki kelengkapan alat atau tenaga kesehatan
yang cukup terlatih (Diallo, dkk., 2012).
Menurut penelitian Singh, dkk (2012) juga
menunjukkan bahwa setelah adanya peningkatan
penggunaan rumah sakit bersalin di India berdampak
pada terjadinya penurunan kematian neonatal sebesar
2.5% namun penurunan kematian neonatal ini tidak
signifikan dimungkinkan terjadi karena masih rendahnya
kualitas layanan kesehatan. Seperti ditemukan juga pada
penelitian lainnya bahwa persalinan yang dilakukan di
rumah di daerah rural sebagian besar ditolong oleh
dokter atau bidan desa dengan tingkat pengetahuan dan
keterampilan masih tergolong cukup rendah (Yanping,
dkk., 2010).

61
2.3.2.5 Faktor Setelah Melahirkan (Post Delivery Factors)
Faktor setelah melahirkan yang berpengaruh
terhadap kelangsungan hidup neonatal adalah kunjungan
neonatal (Titalley, dkk., 2008; Kayode, dkk, 2014; Bashir,
dkk., 2013).
1) Kunjungan Neonatal
Pelayanan pada bayi baru lahir sangat penting
dilakukan untuk mengurangi kematian neonatal dan
mencegah komplikasi segera setelah ibu melahirkan
(BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013).
Sekitar dua per tiga bayi meninggal pada 4 minggu
pertama setelah kelahirannya (Pinem, 2009). Sehingga
untuk mencegah terjadinya kematian tersebut semua
bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan klinis
dalam 24 jam pertama kehidupan (Meadow & Newell,
2002).
Pada saat kelahiran, tubuh bayi baru lahir mulai
melakukan sejumlah adaptasi psikologik. Adanya
perubahan lingkungan yang dramastis menyebabkan
bayi memerlukan pemantauan ketat untuk menentukan
bagaimana bayi tersebut membuat suatu transisi yang
baik terhadap kehidupannya diluar rahim (Ladewig,
dkk, 2006). Pemeriksaan bayi baru lahir memiliki
tujuan untuk mendeteksi masalah penting sedini

62
mungkin sehingga dapat diobati secara tepat,
mempermudah adaptasi pada kehidupan ekstrauterus
dan melindungi bayi baru lahir dari proses berbahaya
seperti hipotermia dan infeksi (Rudolph, dkk., 2006).
Standar pelayanan kesehatan bagi neonatus
menetapkan bahwa setiap bayi baru lahir harus
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar oleh
tenaga kesehatan minimal tiga kali selama periode 0
sampai dengan 28 hari setelah lahir baik, di fasilitas
kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Adapun
kunjungan neonatus pertama (KN1) merupakan
pelayanan kesehatan terhadap neonatus sesuai standar
pada 6-48 jam setelah lahir. Kunjungan neonatal ini
diharapkan dapat meningkatkan akses neoantus
terhadap pelayanan kesehatan dasar dan mengetahui
sedini mungkin kelainan/masalah kesehatan yang
terjadi pada neonatus (Depkes RI, 2009).
Hasil penelitian menunjukkan terdapat
hubungan antara pemeriksaan bayi setelah melahirkan
dengan kejadian kematian neonatal (Pertiwi, 2010).
Kematian bayi lebih rendah pada bayi yang menerima
kunjungan pada hari pertama dibandingkan mereka
yang tidak menerima kunjungan. Bayi yang bertahan
hidup pada dua hari pertama dan menerima kunjungan

63
pertama pada hari kedua berhubungan dengan sebesar
64% kematian neonatal yang lebih rendah
dibandingkan mereka yang tidak menerima kunjungan.
Namun, kunjungan pertama setelah hari kedua
kehidupan pertama bayi tidak berhubungan dengan
penurunan kematian neonatal (Baqui, dkk., 2009).
Namun, pada penelitian yang dilakukan
Nugraheni (2013) menunjukkan tidak terdapat
hubungan antara kunjungan neonatal pertama dengan
kematian neonatal dini. Penelitian yang dilakukan
Singh, dkk (2012) juga menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan antara pemeriksaan bayi pada 24 jam setelah
kelahiran dengan kematian neonatal.
2.4 Konsep Daerah Rural/Perdesaan
Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun
2010 tentang klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Perkotaan
merupakan status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan
yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Sedangkan
perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat
desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah
perkotaan. Desa/Kelurahan merupakan wilayah administrasi terendah
dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah
kecamatan (BPS, 2010).

64
Adapun kriteria suatu desa/kelurahan dikategorikan sebagai
perkotaan atau perdesaan yaitu apabila suatu desa/kelurahan memiliki
persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah
tangga pertanian dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan (BPS,
2010). Fasilitas perkotaan tersebut yaitu (BPS, 2010):
1) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
2) Sekolah Menengah Pertama
3) Sekolah Menengah Umum
4) Pasar
5) Pertokoan
6) Bioskop
7) Rumah Sakit
8) Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon
9) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon
10) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik
Penentuan nilai/skor untuk menetapkan sebagai wilayah perkotaan
dan perdesaan atas desa/kelurahan yaitu sebagai berikut (BPS, 2010):
a. Wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase
rumah tangga, pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas
perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 10 (sepuluh)
atau lebih.
b. Wilayah perdesaan, apabila dari kepadatan penduduk,
persentase rumah tangga, pertanian, dan keberadaan/akses pada

65
fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor
dibawah 10 (sepuluh).
Nilai/skor kepadatan penduduk, persentase rumah tangga
pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki
dapat dilihat pada Tabel 2.1 (BPS, 2010).
Angka Kematian Neonatal di daerah rural berdasarkan SDKI 2012
menunjukkan kematian lebih tinggi di daerah rural dibandingkan di daerah
urban (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013). Penelitian
yang dilakukan di Bangladesh juga menemukan bahwa risiko kematian
neonatal di daerah rural menunjukkan lebih tinggi jika dibandingkan
dengan daerah urban (Chowdhury, dkk., 2013). Perbedaan antara wilayah
rural dan urban tersebut menggambarkan adanya perbedaan wilayah yang
mengalami perkembangan dan wilayah yang tidak mengalami
perkembangan (Yanping, dkk., 2010).
Penyebab kematian yang perlu mendapatkan perhatian serius di
daerah rural Indonesia yaitu masih tingginya pengaruh dari unsur budaya.
Hasil penelitian kualitatif pada ibu hamil Etnik Ngalum di Distrik Oksibil
Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat adat dimana pihak perempuan
harus membalas mas kawin kepada pihak laki-laki sebesar yang
dibayarkan kepada pihak perempuan. Apabila terjadi pelanggaran adat, ibu
tidak membayar mas kawin kepada pihak laki-laki, maka akan terdapat
korban dari keluarga tersebut. Salah satu kasus yang ditemukan, Ibu Tuti
seorang ibu hamil belum bisa membayar mas kawin sampai usia
kehamilannya 9 bulan. Pada saat melahirkan, bayi yang dilahirkan berada

66
dalam kondisi sehat namun keesokan harinya ditemukan bayi telah
meninggal. Keluarga menyadari betul, bahwa hal itu terjadi karena mereka
belum menyelesaikan pembayaran kembali mas kawin. Sehingga mereka
harus tunduk pada adat yang telah ada/turun-temurun dari nenek moyang
mereka (Kemenkes RI, 2012). Diketahui hasil SDKI 2012 menunjukkan
bahwa Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi dengan Angka
Kematian Neonatal yang tinggi di Indonesia yaitu sebesar 27 per 1.000
KH (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013).
Selain itu, kasus kematian bayi baru lahir yang masih tinggi pada
Etnik Ngalum Papua juga disebabkan karena bayi mengalami infeksi
pneumonia. Hasil pengamatan menemukan, ternyata pada beberapa
keluarga dapur perapian bukan hanya digunakan untuk memasak makanan
tetapi juga digunakan untuk menghangatkan badan pada saat malam hari
karena suhu yang cukup dingin (19-200C). Namun, perapian tersebut tidak
dilengkapi dengan cerobong asap, sehingga asap hasil pembakaran hanya
berputar didalam dapur (Kemenkes RI, 2012).

67
67
Tabel 2.1 Kriteria Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kriteria Keberadaan/Akses Pada Fasilitas Perkotaan
Kepadatan Penduduk per Km2 Nilai/Skor
Persentase Rumah Tangga
Pertanian Nilai/Skor Fasilitas Perkotaan Kriteria Nilai/Skor
>500 1 >70.00 1 a. Sekolah Taman Kanak-Kanak 1) Ada, atau ≤ 2.5 Km *)
2) > 2.5 Km *) 1 0 500-1249 2 50.00-69.99 2 b. Sekolah Menengah Pertama
1250-2499 3 40.00-49.99 3 c. Sekolah Menengah Umum 2500-3999 4 20.00-30.99 4 d. Pasar 1) Ada, atau ≤ 2 Km *)
2) > 2 Km *) 0 1 4000-5999 5 15-19.99 5 e. Pertokoan
6000-7499 6 10-14.99 6 f. Bioskop 1) Ada, atau ≤ 5 Km *)
2) > 5 Km *) 0 1 7500-8499 7 5.00-9.99 7 g. Rumah Sakit
>8500 8 <5.00 8 h. Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon
1) Ada
2) Tidak ada 1 0
i. Persentase RT Telepon 1) ≥ 8.00
2) < 8.00 0 1
j. Persentase RT listrik 1) ≥ 90.00
2) < 90.00 0 1
*) Jarak tempuh diukur dari Kantor Desa/Kelurahan

68
2.5 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 (SDKI 2012)
Survei demografi adalah survei yang menggambarkan rumah
tangga secara nasional. Survei ini menyediakan data dengan cakupan luas
terkait indikator monitoring dan evaluasi populasi, kesehatan dan gizi (ICF
International). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012
merupakan survei ketujuh yang dilakukan sebagai bagian dari proyek
internasional Demographic and Health Survey (DHS). Survei sebelumnya
dilakukan pada tahun 1987, 1991, 1994, 1997, 2002-2003, dan 2007.
SDKI 2012 dirancang bersama-sama oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes). SDKI 2012 bertujuan untuk
menyediakan informasi secara rinci tentang penduduk, keluarga berencana
dan bidang kesehatan (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International,
2013).
Pengambilan sampel yang dilakukan pada SDKI 2012 mengunakan
metode sampel tiga tahap. Pada tahap pertama dilakukan pemilihan
sejumlah Primary Sampling Unit (PSU) dari kerangka sampel PSU secara
Probability Proportional to Size (PPS). PSU adalah kelompok blok sensus
berdekatan yang menjadi wilayah tugas koordinator tim Sensus Penduduk
2010. Pada tahap kedua dilakukan pemilihan satu blok sensus secara PPS
disetiap PSU terpilih. Selanjutnya pada tahap ketiga dilakukan pemilihan
25 rumah tangga biasa di setiap blok sensus terpilih secara sistematik.
Rangkaian pengambilan sampel SDKI 2012 digambarkan pada Gambar
2.2 (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013).

69
Gambar 2.2 Bagan Alur Pengambilan Sampel Rumah Tangga dan Individu
Sumber: (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013) BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International (2013)
Sampel SDKI 2012 bertujuan untuk memberikan estimasi
karakteristik bagi perempuan usia 15-49 tahun dan laki-laki menikah usia
15-54 tahun di Indonesia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan di
setiap provinsi. Sehingga untuk mencapai tujuan ini, sebanyak 1.840 blok
sensus (874 di daerah perkotaan dan 966 di daerah pedesaaan) dipilih dari
daftar Blok sensus pada Primary Sampling Unit (PSU) yang terbentuk saat
sensus penduduk 2010. Pada setiap blok sensus, pemutakhiran dan
pemetaan daftar rumah tangga secara lengkap dilakukan pada bulan April
2012. Daftar lengkap rumah tangga dimasing-masing blok sensus
dijadikan dasar untuk pengambilan sampel tahap kedua. Sebanyak 25
rumah tangga dipilih secara sistematis dari setiap blok sensus. Semua
wanita usia 15-49 yang memenuhi syarat diwawancarai dalam komponen
Pemilihan Blok Sensus (Primary Sampling Unit) berdasarkan Daftar Blok Sensus
Penduduk 2010
Pemilihan 25 rumah tangga pada setiap Blok Sensus secara sistematis
Pemilihan wanita usia 15-49 yang memenuhi syarat di setiap rumah tangga
Wawancara wanita usia 15-49 yang memenuhi syarat

70
Remaja dari SDKI. Data wanita dan laki yang tidak pernah menikah usia
15-24 tahun merupakan dasar laporan ini. Selanjutnya 8 rumah tangga
dipilih secara sistematis dari 25 rumah tangga untuk mendapatkan
responden pria menikah usai 15-54 tahun (BPS, BKKBN, Kemenkes &
ICF International, 2013).
Hasil pendataan sampel rumah tangga didapatkan total rumah
tangga sebesar 46.024 untuk Indonesia dimana sebanyak 47.533 wanita
memenuhi syarat untuk diwawancarai. Total rumah tangga hasil pendataan
sampel untuk Provinsi Maluku adalah sebesar 1.077 rumah tangga.
Sedangkan total sampel wanita usia subur yang memenuhi syarat untuk
Indonesia didapatkan sebesar 1.291 wanita (BPS, BKKBN, Kemenkes &
ICF International, 2013).
SDKI 2012 menggunakan empat macam kuesioner yaitu kuesioner
rumah tangga, kuesioner wanita usia subur, kuesioner pria kawin dan
kuesioner remaja pria belum pernah kawin. Adanya perubahan cakupan
sampel individu wanita dari wanita pernah kawin (WPK) umur 15-49
tahun dalam SDKI 2007 menjadi wanita umur subur (WUS) 15-49 tahun
pada SDKI 2012, maka kuesioner WUS ditambahkan pertanyaan-
pertanyaan untuk remaja wanita belum pernah kawin umur 15-24 tahun.
Tambahan pertanyaan ini merupakan bagian dari kuesioner Survei
Kesehatan Reproduksi Remaja tahun 2007 (BPS, BKKBN, Kemenkes &
ICF International, 2013).

71
Kuesioner rumah tangga maupun kuesioner WUS SDKI 2012
sebagian besar mengacu pada versi terbaru (Maret 2011) kuesioner standar
yang digunakan program DHS VI. Model kuesioner tersebut disesuaikan
dengan kebutuhan di Indonesia. Beberapa pertanyaan di kuesioner standar
DHS tidak dicakup dalam SDKI 2012 karena kurang sesuai dengan
kondisi di Indonesia. Selain itu, kategori jawaban serta tambahan
pertanyaan disesuaikan dengan muatan lokal terkait program di bidang
kesehatan dan keluarga berencana di Indonesia (BPS, BKKBN, Kemenkes
& ICF International, 2013).
Kuesioner rumah tangga digunakan untuk mencatat seluruh
anggota rumah tangga dan tamu yang menginap di rumah tangga terpilih
sampel malam sebelum wawancara, dan keadaan tempat tinggal rumah
tangga terpilih. Pertanyaan dasar anggota rumah tangga yang dikumpulkan
adalah umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, dan hubungan
dengan kepala rumah tangga. Keterangan mengenai tempat tinggal yang
dikumpulkan meliputi sumber air minum, jenis kakus, jenis lantai, jenis
atap, jenis dinding, dan kepemilikan aset rumah tangga. Informasi
mengenai kepemilikan aset menggambarkan status sosialekonomi rumah
tangga tersebut. Kegunaan utama kuesioner rumah tangga adalah untuk
menentukan responden wanita dan pria yang memenuhi syarat untuk
wawancara perseorangan (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International,
2013).
Kuesioner WUS digunakan untuk mengumpulkan informasi dari
wanita umur 15-49 tahun. Topik yang ditanyakan kepada wanita tersebut

72
adalah latar belakang responden (status perkawinan, pendidikan, akses
terhadap media massa, dan lain-lain), riwayat kelahiran, pengetahuan dan
pemakaian kontrasepsi, perawatan kehamilan, persalinan, dan pemeriksaan
setelah melahirkan, pemberian air susu ibu dan makanan anak, kematian
anak, imunisasi dan kesakitan anak, perkawinan dan kegiatan seksual,
preferensi fertilitas, latar belakang suami/pasangan dan pekerjaan
responden, pengetahuan tentang HIV-AIDS dan infeksi seksual lain,
kematian saudara kandung, termasuk kematian ibu dan isu kesehatan
lainnya (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013).
Selanjutnya pada kuesioner wanita umur 15-24 tahun yang belum
pernah kawin, ditanyakan mengenai latar belakang tambahan yaitu
pengetahuan mengenai sistem reproduksi manusia, sikap tentang
perkawinan dan anak, peran keluarga, sekolah, masyarakat dan media,
rokok, minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, pacaran dan
perilaku seksual. Pada kuesioner pria kawin (PK), informasi yang
dikumpulkan dalam kuesioner PK hampir sama dengan kuesioner WUS
namun lebih pendek karena tidak mencakup riwayat kelahiran, dan
kesehatan ibu dan anak. Pada kuesioner untuk pria berstatus kawin juga
dikumpulkan informasi mengenai pengetahuan dan partisipasi mereka
dalam perawatan kesehatan anak. Kuesioner remaja pria (RP) mencakup
pertanyaan yang sama dengan kuesioner remaja wanita belum pernah
kawin umur 15-24 tahun (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International,
2013).

73
Sebelum memulai kegiatan di lapangan, kuesioner SDKI 2012
diujicobakan di Provinsi Riau dan Nusa Tenggara Timur untuk
memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan sudah jelas dan dapat dipahami
oleh responden. Uji coba penting dilakukan terkait dengan cakupan sampel
yang berbeda dengan SDKI sebelumnya. Pada SDKI sebelumnya
responden perempuan merupakan wanita yang pernah kawin umur 15-49
tahun berubah menjadi semua wanita umur 15-49 tahun terlepas dari status
perkawinan. Selain itu, terdapat pertanyaan baru dan format pertanyaan
yang disesuaikan dengan kuesioner standar DHS. Dua tim direkrut di
setiap provinsi. Uji coba dilakukan pada pertengahan Juli hingga
pertengahan Agustus 2011 di empat kabupaten terpilih, yang mencakup 4
blok sensus perkotaan dan empat blok sensus perdesaan. Kabupaten yang
dipilih untuk uji coba adalah Pekanbaru dan Kabupaten Kampar (Provinsi
Riau), serta Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Provinsi
Nusa Tenggara Timur). Berdasarkan temuan uji coba, dilakukan
penyempurnaan terhadap kuesioner rumah tangga dan individu (BPS,
BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013).
Kemudian dilakukan pelatihan kepada seluruh enumerator sebelum
survei dilakukan. Sebanyak 922 orang (376 pria dan 546 wanita) dilatih
sebagai pewawancara. Pelatihan berlangsung selama 12 hari pada bulan
Mei 2012 di sembilan pusat pelatihan yaitu Batam, Bukit Tinggi, Banten,
Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, Makasar, Manokwari dan Jayapura.
Pelatihan mencakup pembelajaran materi di kelas, latihan wawancara dan
tes. Pelatihan dibedakan menjadi tiga kelas yaitu kelas wanita (WUS),

74
kelas pria kawin (PK), dan kelas remaja pria (RP). Seluruh peserta dilatih
menggunakan kuesioner rumah tangga dan kuesioner perseorangan sesuai
jenis kelasnya. Pengumpulan data yang dilakukan pada SDKI 2012 yaitu
menggunakan metode wawancara terhadap responden penelitian
menggunakan kuesioner penelitian (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF
International, 2013).
Pengumpulan data SDKI 2012 dilakukan oleh 119 tim petugas.
Setiap tim terdiri dari delapan orang yaitu 1 orang pengawas pria, 1 orang
editor wanita untuk WUS dan PK, 4 orang wanita pewawancara WUS, 1
orang pria pewawancara PK yang merangkap sebagai editor RP, dan 1
orang pria pewawancara RP. Sedangkan untuk Provinsi Papua dan Papua
Barat setiap tim pengumpul terdiri dari dari lima orang, 1 orang pengawas
pria yang merangkap sebagai editor PK dan RP, 1 orang wanita editor
WUS, 2 orang wanita pewawancara WUS dan 1 orang pria pewawancara
PK dan RP. Kegiatan pengumpulan data SDKI 2012 di lapangan
berlangsung dari 7 Mei sampai 31 Juli 2012 (BPS, BKKBN, Kemenkes &
ICF International, 2013).
Hasil pengumpulan data dilapangan didapatkan sebesar 99%
sampel rumah tangga yang berhasil diwawancarai. Selanjutnya, sampel
wanita usia subur yang memenuhi syarat yang berhasil diwawancarai yaitu
sebesar 22.898 wanita (96%). Adapun rumah tangga yang berhasil
diwawancarai untuk Indonesia yaitu sebesar 97.4% (1.077 rumah tangga)
dan sampel wanita usia subur yang memenuhi syarat yang berhasil

75
diwawancarai sebesar 89% (1.149 wanita) (BPS, BKKBN, Kemenkes &
ICF International, 2013).
2.6 Kerangka Teori
Berdasarkan model faktor-faktor yang berhubungan dengan
kematian pada neonatal dari Titaley (2008) dapat diilustrasikan model
kerangka teori faktor-faktor yang mempengaruhi kematian neonatal pada
Gambar 2.3.

76
Gambar 2.3 Kerangka Teori
Sumber: Modifikasi Determinan Kelangsungan Hidup Bayi Titaley, dkk (1), 2008, Kayode, dkk, 2014 (2), Singh, dkk, 2013 (3), Bashir, dkk.
2013 (4), Mekonnen, dkk, 2013 (5), Upadhyay, dkk, 2012 (6), Onwuanaku, dkk 2011 (7), Chaman, dkk 2009 (8), Singh, dkk 2014
(9), Carlsen, dkk 2013 (10), Debes, dkk 2013 (11), Yego, dkk, 2013 (12), Yanping, dkk, 2010 (13)
Determinan Sosial-ekonomi:
Pendidikan Ibu3,5,6
Pekerjaan Ibu1,3
Indeks Kekayaan Rumah Tangga4
Hidup Meninggal
Faktor Ibu: Umur Ibu4,5,6
Faktor Sebelum Melahirkan:
Kunjungan Antenatal3,9 Komplikasi Kehamilan4
Faktor Neonatal:
Infeksi/Penyakit12,13
Jenis Kelamin Bayi1,3,4,5,10 Berat Bayi Lahir2,7,8
Paritas2,3,8
Jarak Kelahiran1,2,5,8
Kelahiran Prematur7
Inisiasi Menyusu Dini11
Determinan Terdekat (Proximate Determinants)
Faktor Saat Melahirkan:
Penolong Persalinan9
Komplikasi Persalinan1,3,4
Persalinan Caesar4,8
Tempat Persalinan1
Faktor Setelah Melahirkan:
Kunjungan Neonatal1,2,4

77
3 BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL
3.1 Kerangka Konsep
Berdasarkan teori penyebab kematian neonatal dari Titaley (2008),
faktor yang mempengaruhi kematian neonatal yaitu terdiri dari faktor
sosial ekonomi dan faktor terdekat (proximate determinants). Determinan
sosial-ekonomi tidak mempengaruhi secara langsung kematian neonatal,
namun hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat
pendidikan ibu, semakin besar peluang terjadinya kasus kematian bayi. Ibu
yang bekerja mempunyai kecenderungan untuk mengalami kejadian
kematian bayi lebih besar dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Ibu dan
anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki risiko meningkat
terhadap kematian neonatal. Sehingga peneliti ingin meneliti secara
langsung pengaruh faktor sosial-ekonomi tersebut terhadap kematian
neonatal.
Variabel berat bayi lahir, jarak kelahiran, kelahiran prematur,
inisiasi menyusu dini, komplikasi persalinan dan kunjungan neonatal tidak
dijadikan variabel penelitian karena sebagian besar data variabel missing
serta variabel infeksi/penyakit tidak dijadikan variabel penelitian karena
data tidak tersedia pada SDKI 2012. Adapun variabel lainnya yang dipilih
sebagai variabel penelitian adalah faktor terdekat yang terdiri dari variabel

78
umur ibu, jenis kelamin bayi, paritas, jarak kelahiran, kelahiran prematur,
kunjungan antenatal, komplikasi kehamilan, penolong persalinan,
persalinan caesar dan tempat persalinan.
Semakin tua umur ibu maka organ reproduksi ibu semakin
mengalami penurunan serta semakin muda umur ibu, organ reproduksi
yang ada belum cukup matang untuk menjalani proses kehamilan.
Sehingga pada umur terlalu muda dan terlalu tua kehamilan memiliki
risiko tinggi mengalami kematian bayi. Selain itu, apabila ibu terlalu
sering melahirkan rahim akan semakin lemah. Bayi pada ibu yang
mengalami komplikasi pada saat kehamilan memiliki kemungkinan untuk
mengalami komplikasi pada saat persalinan (perdarahan, persalinan sulit
atau lama) yang bisa menyebabkan terjadinya kematian pada bayi terutama
pada masa 28 hari pertama kehidupan.
Persalinan caesar dilakukan apabila terdapat indikasi kesehatan
tertentu, sehingga ibu lebih memiliki risiko kematian pada bayinya.
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan terampil akan membantu ibu
dan bayi tetap berada pada kondisi yang baik. Petugas kesehatan memiliki
keterampilan lebih baik dalam menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin
terjadi selama persalinan. Apabila ibu melangsungkan persalinan di
fasilitas kesehatan, kondisi yang memerlukan tindakan lebih lanjut bisa
dilakukan lebih cepat karena telah tersedianya alat-alat yang dibutuhkan.

79
Berikut kerangka konsep pada penelitian ini:
Gambar 3.1 Kerangka Konsep
Kematian Neonatal
Umur Ibu
Pekerjaan Ibu
Pendidikan Ibu
Indeks Kekayaan Rumah Tangga
Jenis Kelamin Bayi
Paritas
Kunjungan Antenatal
Komplikasi Kehamilan
Penolong Persalinan
Persalinan Caesar
Tempat Persalinan

80
3.2 Definisi Operasional
Tabel 3.1 Definisi Operasional
No Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur
Variabel Dependen 1. Kematian Neonatal Kematian yang terjadi selama dua
puluh delapan hari pertama kehidupan setelah bayi dilahirkan di Indonesia pada periode 2008-2012.
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-WUS Bagian
2 No. 216, 220, Bagian 4 No. 404
0 = meninggal 1 = tidak meninggal
(WHO, 2006)
Ordinal
Variabel Independen 2. Pendidikan Ibu Jenjang pendidikan tertinggi yang
pernah dijalani ibu. Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-WUS Bagian
1 No 105, 106
0 = rendah (SD atau SMP) 1 = tinggi (SMA, Diploma
atau Perguruan Tinggi) (Singh, dkk., 2013)
Ordinal
3. Pekerjaan Ibu Status pekerjaan yang dilakukan ibu baik dirumah maupun diluar rumah yang mendapat imbalan/penghasilan.
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-WUS Bagian
8 No. 807-814
0 = bekerja 1 = tidak bekerja
(Titaley, dkk., 2008)
Ordinal
4. Indeks kekayaan rumah tangga
Indeks kekayaan rumah tangga, yang didapatkan dengan mengukur karakteristik latar belakang rumah tangga (mengukur standar hidup rumah tangga dalam jangka panjang).
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-RT Bagian III
dan IV
1 = rendah 2 = menengah 3 = tinggi
(Bashir, dkk., 2013)
Ordinal
5. Umur Ibu Ulang tahun terakhir ibu saat dilakukan wawancara dikurangi umur
Observasi Data SDKI
Kuesioner SDKI 2012-WUS Bagian
0 = < 20 atau > 35 tahun 1 = 20-35 tahun
Ordinal

81
No Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur
anak terakhir pada periode 5 tahun sebelum survei (2008-2012).
2012 1 No. 102, 103 (Wijayanti, 2013)
6. Jenis Kelamin Jenis kelamin anak terakhir yang meninggal pada periode 2008-2012.
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-RT Bagian 2
No. 213
0 = laki-laki 1 = perempuan
(Titaley, dkk., 2008)
Ordinal
7. Paritas Jumlah bayi yang pernah dilahirkan ibu baik lahir hidup maupun lahir mati.
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-WUS Bagian
2 No. 224
0 = ≥ 4 1 = 1-3
(Titaley, dkk., 2008)
Ordinal
8. Kunjungan Antenatal
Jumlah kunjungan ibu memeriksakan kehamilan untuk anak terakhir pada periode 5 tahun sebelum survei (2008-2012).
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-Bagian 4 No.
408-412C
0 = tidak melakukan kunjungan atau kunjungan kurang dari empat kali
1 = kunjungan antenatal minimal empat kali
(Yani & Duarsa, 2013)
Ordinal
9. Komplikasi kehamilan
Riwayat terjadinya komplikasi pada kehamilan untuk kehamilan anak terakhir dengan tanda komplikasi mulas sebelum 9 bulan, perdarahan, demam yang tinggi, kejang-kejang dan pingsan.
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI-WUS Bagian 4 No.
414 C, 414 D
0 = komplikasi (minimal terdapat satu tanda komplikasi)
1 = tidak komplikasi (Nugraheni, 2013)
Ordinal
10. Penolong Persalinan Tenaga yang menjadi penolong persalinan untuk anak terakhir pada periode 5 tahun sebelum survei (2008-
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-WUS Bagian
4 No. 433
0 = non tenaga kesehatan 1 = tenaga kesehatan
(Titaley, dkk., 2008)
Ordinal

82
No Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala Ukur
2012). 11. Persalinan caesar Anak terakhir pada periode 5 tahun
sebelum survei (2008-2012) dilahirkan dengan cara perut dibedah untuk mengeluarkan bayi.
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-WUS Bagian
4 No. 435
0 = caesar 1 = tidak caesar
(Bashir, dkk., 2013)
Ordinal
12. Tempat persalinan Tempat ibu melangsungkan proses persalinan untuk anak terakhir pada periode 5 tahun sebelum survei (2008-2012).
Observasi Data SDKI
2012
Kuesioner SDKI 2012-WUS Bagian
4 No. 434
0 = non fasilitas layanan kesehatan
1 = fasilitas layanan kesehatan
(Titaley, dkk., 2008)
Ordinal

83
3.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kematian neonatal.
2. Ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan kematian neonatal.
3. Ada hubungan antara indeks kekayaan rumah tangga dengan kematian
neonatal.
4. Ada hubungan antara umur ibu dengan kematian neonatal.
5. Ada hubungan antara jenis kelamin bayi dengan kematian neonatal.
6. Ada hubungan antara paritas dengan kematian neonatal.
7. Ada hubungan antara kunjungan antenatal dengan kematian neonatal.
8. Ada hubungan antara komplikasi kehamilan dengan kematian neonatal.
9. Ada hubungan antara penolong persalinan dengan kematian neonatal.
10. Ada hubungan antara persalinan caesar dengan kematian neonatal.
11. Ada hubungan antara tempat persalinan dengan kematian neonatal.

84
4 BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi dengan
menggunakan desain cross sectional study dimana status paparan dan status
penyakit dikumpulkan dalam satu waktu (Gordis, 2004). Desain ini adalah
desain penelitian dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
2012 yang merupakan sumber data pada penelitian ini. Desain studi cross
sectional merupakan desain penelitian yang mudah dilakukan karena tidak
membutuhkan waktu follow up (Murti, 1997). Namun, desain cross sectional
memiliki kelemahan dimana tidak bisa membedakan antara faktor penyebab
dan akibat, karena pengumpulan data paparan dan efek dilakukan secara
bersamaan (Gerstman, 2003).
SDKI 2012 merupakan survei ketujuh yang dilakukan sejak tahun
1987 sebagai bagian dari proyek internasional Demographic and Health
Survey (DHS). Survei ini bertujuan untuk menyediakan informasi secara rinci
tentang penduduk, keluarga berencana dan kesehatan. Survei ini dirancang
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
(BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013).

85
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2014 dengan lokasi
penelitian adalah wilayah rural Indonesia. Adapun analisis data penelitian
dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian
4.3.1 Populasi Penelitian
Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang karakteristiknya
akan diduga (Hastono & Sabri, 2010). Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh neonatal di daerah rural Indonesia pada periode 2008-
2012 berdasarkan sampel SDKI 2012.
4.3.2 Sampel Penelitian
Sampel adalah bagian dari populasi yang ciri-cirinya akan
diteliti atau diukur (Hastono & Sabri, 2010). Sampel yang digunakan
pada penelitian ini yaitu wanita usia subur (15-49 tahun) di daerah
rural Indonesia dan pernah memiliki bayi pada rentang periode 2008-
2012. Besar sampel minimal pada penelitian ini ditentukan
berdasarkan rumus berikut (Dahlan, 2010):
n = Z1-α/2 2P(1-P)+Z1-β P1(1-P1)+ P2(1-P2)
2
(P1- P2)2 xDeff
Keterangan:
n1 = jumlah sampel minimal
Z1-α/2 = 1.96 (Nilai Z pada derajat kemakanaan α sebesar 5%
(0.05)

86
Z1-β = 0.84 (Nilai Z pada kekuatan uji 1-β dengan β sebesar
20%)
P = Proporsi total = (P1+P2)/2
P1 = proporsi kematian neonatal pada kelompok yang nilainya
merupakan judgement peneliti
P2 = proporsi kematian neonatal pada kelompok yang
bersumber dari kepustakaan
Deff = Desain efek
Berdasarkan nilai P2 hasil penelitian terdahulu sebesar 0.43
(Chaman, dkk., 2009), α = 5% (Z1-α/2 = 1.96); β = 20% (Zβ = 0.84), P1-
P2 = 3.5% dan Deff = 2 didapatkan jumlah sampel minimal yang
diperlukan untuk penelitian sebesar 6.327 sampel. Jumlah WUS yang
memililiki bayi pada periode 2008-2012 di daerah rural Indonesia
setelah proses cleaning data didapatkan sebesar 7.138 sampel.
Sehingga peneliti mengambil seluruh sampel tersebut (7.138 sampel)
karena telah memenuhi besar sampel minimal penelitian (6.327
sampel).
4.4 Cara Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih sampel WUS yang
memenui syarat dan berhasil diwawancarai di Indonesia. Jumlah sampel WUS
yang memenuhi syarat yang berhasil diwawancarai yaitu sebesar 45.607
wanita. Selanjutnya dipilih sampel WUS yang memiliki bayi pada periode
2008-2012. Jumlah sampel WUS yang memenuhi syarat dan berhasil
diwawancarai serta memiliki bayi pada periode 2008-2012 di Indonesia yaitu

87
sebesar 16.198 sampel. Selanjutnya dipilih WUS berdasarkan wilayah tempat
tinggal didaerah rural (perdesaan) yaitu sebesar 8.848 sampel. Kemudian
dilakukan proses cleaning data sehingga didapatkan jumlah sampel WUS
yang memiliki bayi pada periode 2008-2012 yaitu sebesar 7.138 sampel.
Berikut alur pengambilan sampel pada penelitian ini.
Gambar 4.1 Bagan Alur Pengambilan Sampel Penelitian
4.5 Teknik Pengumpulan Data
Sumber data pada penelitian ini adalah data hasil Survei Demografi
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Data yang dikumpulkan pada
Pemilihan sampel wanita usia 15-49 yang di wawancarai di Indonesia yaitu sebesar
45.607 sampel
Pemilihan sampel wanita usia 15-49 yang di wawancarai yang memiliki bayi di Indonesia
Tahun 2008-2012 yaitu sebesar 16.198 sampel
Pemilihan sampel wanita usia 15-49 yang di wawancarai yang memiliki bayi di daerah
rural Indonesia Tahun 2008-2012 yaitu sebesar 8.848 sampel
Pemilihan sampel hasil cleaning data wanita usia 15-49 yang di wawancarai yang memiliki
bayi di daerah rural Indonesia Tahun 2008-2012 yaitu sebesar 7.138 sampel

88
penelitian ini yaitu data hasil Kuesioner Wanita Usia Subur (WUS) dan
Kuesioner Rumah Tangga SDKI 2012 untuk Indonesia. Data hasil kuesioner
WUS yang dikumpulkan terdiri dari kematian neonatal, pendidikan ibu,
pekerjaan ibu, indeks kekayaan rumah tangga, wilayah tempat tinggal, umur
ibu, jenis kelamin bayi, paritas, kunjungan antenatal, komplikasi kehamilan,
penolong persalinan, persalinan caesar dan tempat persalinan.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis terlebih
dahulu terhadap Kuesioner WUS dan Kuesioner Rumah Tangga SDKI 2012.
Kemudian memilih variabel-variabel yang akan dijadikan sebagai variabel
penelitian berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.
Selanjutnya, peneliti meminta data mentah (row data) hasil Kuesioner WUS
dan Rumah Tangga ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) sebagai pemegang data SDKI 2012. Berikut ini gambaran
proses pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini:
Gambar 4.2 Proses Pengambilan Data Penelitian
Analisis Kuesioner Wanita Usia Subur (WUS) dan Kuesioner Rumah Tangga (RT), SDKI
2012
Pemilihan Variabel Penelitian Berdasarkan Penelitian-Penelitian Sebelumnya
Permintaan Data Mentah (Row Data) Hasil Kuesioner WUS dan RT, SDKI 2012 ke
BKKBN

89
4.6 Pengolahan Data
Adapun proses pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini
sebagai berikut:
1) Filter (Penyaringan), menyaring data yang tidak dibutuhkan dalam
penelitian. Peneliti sebelumnya mengidentifikasi pertanyaan pada
Kuesioner SDKI 2012 yang dianggap berkaitan dengan kematian
neonatal berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut kode
variabel penelitian pada row data SDKI 2012:
Tabel 4.1 Variabel dan Kode Variabel Penelitian Pada SDKI 2012
No. Variabel Kode Data Variabel Dependen 1. Kematian neonatal B5, B6, B7 Variabel Independen 2. Pendidikan ibu V106, V149 3. Pekerjaan ibu V714, V716, V731 4. Indeks kekayaan rumah tangga V190, V191 5. Umur ibu V012 6. Jenis kelamin bayi B4 7. Paritas V201 8. Kunjungan pelayanan antenatal M13, M14, S412BA-
S412BC 9. Komplikasi kehamilan S632HA-S632HX 10. Penolong persalinan M3A$1, M3B$1, M3C$1,
M3D$1, M3E$1, M3G$1, M3H$1, M3K$1, M3N$1
11. Persalinan Caesar V401, M17 12. Tempat persalinan M15
2) Cleaning (Pembersihan data), memeriksa kembali kemungkinan
adanya data tidak konsisten dan missing data dengan analisis frekuensi

90
terhadap masing-masing variabel penelitian. Berikut hasil cleaning
data pada penelitian ini:
Tabel 4.2 Hasil Cleaning Data Daerah Rural Indonesia SDKI 2012
No. Variabel Jumlah Awal
Data Valid Missing
1. Kategori anak hidup 8.848 8.848 0 2. Umur saat meninggal 8.848 8.848 0 3. Pendidikan ibu 8.848 8.368 480 4. Pekerjaan ibu 8.848 8.834 14 5. Indeks kekayaan rumah tangga 8.848 8.848 0 6. Wilayah tempat tinggal 8.848 8.848 0 7. Umur ibu 8.848 8.848 0 8. Jenis kelamin bayi 8.848 8.848 0 9. Paritas 8.848 8.848 0 10. Jarak kelahiran 8.848 5.722 3.126 11. IMD 8.848 7.226 1.622 12. Kunjungan antenatal 8.848 8.848 0 13. Komplikasi kehamilan 8.848 8.810 38 14. Penolong persalinan 8.848 8.784 64 15. Komplikasi persalinan 8.848 6.718 2130 16. Berat bayi lahir 8.848 6.652 2.196 17. Kelahiran prematur 8.848 585 8.263 18. Persalinan Caesar 8.848 8.769 79 19. Tempat persalinan 8.848 8.783 65 20. Kunjungan neonatal pertama 8.848 4.464 4.384
Jumlah Akhir Sampel 7.138 sampel
3) Recoding (pengkodean ulang), memberikan kode baru untuk setiap
variabel penelitian yang perlu diubah.
4.7 Analisis Data
Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari analisis
univariat dan analisis bivariat.

91
4.7.1 Analisis Univariat
Analisis univariat dilakukan untuk melihat distribusi variabel-
variabel yang akan diteliti. Variabel-variabel tersebut adalah kematian
neonatal, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, indeks kekayaan rumah
tangga, umur ibu, jenis kelamin bayi, paritas, kunjungan antenatal,
komplikasi kehamilan, penolong persalinan, persalinan caesar dan
tempat persalinan.
4.7.2 Analisis Bivariat
Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji statistik
chi square untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu adanya hubungan
antara variabel independen dengan variabel dependen penelitian.
Variabel independen penelitian terdiri dari pendidikan ibu, pekerjaan
ibu, indeks kekayaan rumah tangga, umur ibu, jenis kelamin bayi,
paritas, kunjungan antenatal, komplikasi kehamilan, penolong
persalinan, persalinan caesar dan tempat persalinan. Sedangkan
variabel dependennya adalah kematian neonatal.
Derajat signifikansi (α) pada penelitian ini ditetapkan sebesar
5% (0.05). Terdapat hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen apabila hasil perhitungan didapatkan nilai p lebih
kecil dari nilai α (P < α). Sebaliknya apabila nilai p didapatkan lebih
besar dari nilai α (P > α), maka tidak terdapat hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen.

92
5 BAB V HASIL
5.1 Distribusi Kematian Neonatal
Distribusi kematian neonatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada
Tabel 5.1 berikut ini:
Tabel 5.1 Distribusi Kematian Neonatal di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Kematian Neonatal n % Meninggal 79 1,1 Tidak meninggal 7059 98,9
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa dari 7.138 ibu yang memiliki
bayi, terdapat 1,1% (79 kasus) kematian neonatal yang terjadi pada bayi di
daerah rural Indonesia Tahun 2008-2012.
5.2 Distribusi Tingkat Pendidikan Ibu
Distribusi pendidikan ibu di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada
Tabel 5.2 berikut ini:
Tabel 5.2 Distribusi Tingkat Pendidikan Ibu di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Pendidikan Ibu n % Rendah 4911 68,8 Tinggi 2227 31,2
Total 7138 100

93
Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa sebagian besar ibu memiliki
tingkat pendidikan rendah (68,8%).
5.3 Distribusi Status Pekerjaan Ibu
Distribusi status pekerjaan ibu di daerah rural Indonesia dapat dilihat
pada Tabel 5.3 berikut ini:
Tabel 5.3 Distribusi Pekerjaan Ibu di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Status Pekerjaan Ibu n % Bekerja 3903 54,7 Tidak bekerja 3235 45,3
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa ibu yang memiliki status
bekerja yaitu sebesar 54,7% (3.903 orang).
5.4 Distribusi Indeks Kekayaan Rumah Tangga
Distribusi Indeks Kekayaan Rumah Tangga di daerah rural Indonesia
dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini:
Tabel 5.4 Distribusi Indeks Kekayaan Rumah Tangga di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Indeks Kekayaan Rumah Tangga n %
Rendah 4756 66,6 Menengah 1196 16,8 Tinggi 1186 16,6
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui bahwa sebagian besar ibu memiliki
indeks kekayaan rumah tangga rendah yaitu sebesar 66,6% (4.756 orang).

94
5.5 Distribusi Umur Ibu
Distribusi umur ibu di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel
5.5 berikut ini:
Tabel 5.5 Distribusi Umur Ibu di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Umur Ibu n % <20 tahun dan >35 tahun 1980 27,7 20-35 tahun 5158 72,3
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa sebagian besar ibu memiliki
umur 20-35 tahun yaitu sebesar 72,3% (5.158 orang).
5.6 Distribusi Jenis Kelamin Bayi
Distribusi jenis kelamin bayi di daerah rural Indonesia dapat dilihat
pada Tabel 5.6 berikut ini:
Tabel 5.6 Distribusi Jenis Kelamin Bayi di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Jenis Kelamin n % Laki-laki 3725 52,2 Perempuan 3413 47,8
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.6 diketahui bahwa bayi yang berjenis kelamin
perempuan lebih sedikit dibandingkan bayi berjenis kelamin laki-laki yaitu
sebesar 47,8% (3.413 bayi).

95
5.7 Distribusi Paritas
Distribusi paritas di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.7
berikut ini:
Tabel 5.7 Distribusi Paritas di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Paritas n % >=4 1368 19,1 1-3 5778 80,9
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.7 diketahui bahwa sebagian besar ibu memiliki
paritas 1-3 yaitu sebesar 80,9% (5.778 orang).
5.8 Distribusi Kunjungan Antenatal
Distribusi kunjungan antenatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat
pada Tabel 5.8 berikut ini:
Tabel 5.8 Distribusi Kunjungan Antenatal di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Kunjungan Antenatal n % Tidak ANC 2688 37,7 ANC 4450 62,3
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.8 diketahui bahwa ibu yang telah melakukan
kunjungan antenatal selama kehamilannya yaitu sebesar 62,3% (4.450 orang).
5.9 Distribusi Komplikasi Kehamilan
Distribusi komplikasi kehamilan di daerah rural Indonesia dapat dilihat
pada Tabel 5.9 berikut ini:

96
Tabel 5.9 Distribusi Komplikasi Kehamilan di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Komplikasi Kehamilan n % Komplikasi 427 6,0 Tidak komplikasi 6711 94,0
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.9 diketahui bahwa sebagian besar ibu tidak
mengalami komplikasi pada saat kehamilannya yaitu sebedar 94,0% (6.711
orang).
5.10 Distribusi Penolong Persalinan
Distribusi penolong persalinan di daerah rural Indonesia dapat dilihat
pada Tabel 5.10 berikut ini:
Tabel 5.10 Distribusi Penolong Persalinan di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Penolong Persalinan n % Non Nakes 1911 26,8 Nakes 5227 73,2
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.10 diketahui bahwa sebagian besar persalinan pada
ibu ditolong oleh tenaga kesehatan yaitu sebesar 73,2% (5.227 orang).
5.11 Distribusi Persalinan Caesar
Distribusi persalinan caesar di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada
Tabel 5.11 berikut ini:

97
Tabel 5.11 Distribusi Persalinan Caesar di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Persalinan Caesar n % Caesar 571 8,0 Tidak Caesar 6567 92,0
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.11 diketahui bahwa sebesar 8,0% (571 orang) ibu
yang melakukan persalinan caesar pada persalinannya.
5.12 Distribusi Tempat Persalinan
Distribusi tempat persalinan di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada
Tabel 5.12 berikut ini:
Tabel 5.12 Distribusi Tempat Persalinan di Daerah Rural Indonesia
Tahun 2008-2012
Tempat Persalinan n % Non Fasyankes 4276 59,9 Fasyankes 2862 40,1
Total 7138 100
Berdasarkan Tabel 5.12 diketahui bahwa ibu yang melakukan
persalinan di non fasilitas pelayanan kesehatan pada saat persalinannya yaitu
sebesar 59,9% (4.276 orang).
5.13 Hubungan Pendidikan Ibu dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara pendidikan ibu dengan kematian neonatal
di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.13 berikut ini:

98
Tabel 5.13 Analisis Hubungan antara Pendidikan Ibu dengan Kematian Neonatal di
Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Pendidikan Ibu Kematian Neonatal Total P
Value Meninggal Tidak meninggal n % n % n %
Rendah 59 1,2 4852 98,8 4911 100 0,311 Tinggi 20 0,9 2207 99,1 2227 100
Berdasarkan Tabel 5.13 diketahui bahwa dari 4.911 ibu yang
berpendidikan rendah terdapat 59 kematian neonatal (1,2%), sedangkan dari
2.227 ibu berpendidikan tinggi terdapat 20 kematian neonatal (0,9%).
Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,311 sehingga dapat diartikan
bahwa pada tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat hubungan antara
pendidikan ibu dengan kematian neonatal.
5.14 Hubungan Pekerjaan Ibu dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara pekerjaan ibu dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini:
Tabel 5.14 Analisis Hubungan antara Pekerjaan Ibu dengan Kematian Neonatal di
Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Status Pekerjaan Ibu
Kematian Neonatal Total P Value Meninggal Tidak meninggal
n % n % n % Bekerja 62 1,6 3841 98,4 3903 100 0,000 Tidak Bekerja 17 0,5 3218 99,5 3235 100
Berdasarkan Tabel 5.14 diketahui bahwa dari 3.903 ibu yang bekerja
terdapat 62 kematian neonatal (1,6%), sedangkan dari 3.235 ibu yang tidak
bekerja terdapat 17 kematian neonatal (0,5%). Berdasarkan hasil uji statistik
diperoleh nilai p = 0,000 sehingga dapat diartikan bahwa pada tingkat

99
kepercayaan 95% terdapat hubungan antara status pekerjaan ibu dengan
kematian neonatal.
5.15 Hubungan Indeks Kekayaan Rumah Tangga dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara indeks kekayaan rumah tangga dengan
kematian neonatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.15
berikut ini:
Tabel 5.15 Analisis Hubungan antara Indeks Kekayaan Rumah Tangga dengan
Kematian Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Indeks Kekayaan
Rumah Tangga
Kematian Neonatal Total P Value Meninggal Tidak meninggal
n % n % n % Rendah 47 1,0 4709 99,0 4756 100
0,375 Menengah 17 1,4 1179 98,6 1196 100 Tinggi 15 1,3 1171 98,7 1186 100
Berdasarkan Tabel 5.15 diketahui bahwa dari 4.756 ibu dengan status
indeks kekayaan rumah tangga rendah terdapat 47 kematian neonatal (1,0%),
dari 1.196 ibu dengan status indeks kekayaan rumah tangga menengah terdapat
17 kematian neonatal (1,4%) serta dari 1.186 ibu dengan status indeks
kekayaan rumah tangga tinggi terdapat 15 kematian neonatal (1,3%).
Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,375 sehingga dapat diartikan
bahwa pada tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat hubungan antara indeks
kekayaan rumah tangga dengan kematian neonatal.

100
5.16 Hubungan Umur Ibu dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara umur ibu dengan kematian neonatal di
daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.16 berikut ini:
Tabel 5.16 Analisis Hubungan antara Umur Ibu dengan Kematian Neonatal di
Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Umur Ibu Kematian Neonatal Total P
Value Meninggal Tidak meninggal n % n % n %
<20 tahun dan >35 tahun 33 1,7 1947 98,3 1980 100 0,007 20-35 tahun 46 0,9 5112 99,1 5158 100
Berdasarkan Tabel 5.16 diketahui bahwa dari 1.980 ibu yang berusia
<20 tahun dan >35 tahun terdapat 33 kematian neonatal (1,.7%), sedangkan dari
5.158 ibu yang berusia 20-35 tahun terdapat 46 kematian neonatal (0,9%).
Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,007 sehingga dapat diartikan
bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat hubungan antara umur ibu
dengan kematian neonatal.
5.17 Hubungan Jenis Kelamin Bayi dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara jenis kelamin bayi dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.17 berikut ini:
Tabel 5.17 Analisis Hubungan antara Jenis Kelamin Bayi dengan Kematian Neonatal
di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Jenis Kelamin Bayi
Kematian Neonatal Total P Value Meninggal Tidak meninggal
n % n % n % Laki-laki 45 1,2 3680 98,8 3725 100 0,458 Perempuan 34 1,0 3379 99,0 3413 100

101
Berdasarkan Tabel 5.17 diketahui bahwa dari 3.725 ibu dengan bayi
berjenis kelamin laki-laki terdapat 45 kematian neonatal (1,2%), sedangkan dari
3.413 ibu dengan bayi berjenis kelamin perempuan terdapat 34 kematian
neonatal (1,0%). Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,458
sehingga dapat diartikan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat
hubungan antara jenis kelamin bayi dengan kematian neonatal.
5.18 Hubungan Paritas dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara paritas dengan kematian neonatal di daerah
rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.18 berikut ini:
Tabel 5.18 Analisis Hubungan antara Paritas dengan Kematian Neonatal
di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Paritas Kematian Neonatal Total P
Value Meninggal Tidak meninggal n % n % n %
≥4 23 1,7 1342 98,3 1365 100 0,033 1-3 56 1,0 5717 99,0 5773 100
Berdasarkan Tabel 5.18 diketahui bahwa dari 1.365 ibu yang memiliki
paritas lebih dari empat terdapat 23 kematian neonatal (1,7%), sedangkan dari
5.773 ibu yang memiliki paritas 1-3 terdapat 56 kematian neonatal (1,0%).
Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,033 sehingga dapat diartikan
bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat hubungan antara paritas dengan
kematian neonatal.

102
5.19 Hubungan Kunjungan Antenatal dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara kunjungan antenatal dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.19 berikut ini:
Tabel 5.19 Analisis Hubungan antara Kunjungan Antenatal dengan Kematian Neonatal
di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Kunjungan Antenatal
Kematian Neonatal Total P Value Meninggal Tidak meninggal
n % n % n % Tidak ANC 45 1,7 2643 98,3 2688 100 0,001 ANC 34 0,8 4416 99,2 4416 100
Berdasarkan Tabel 5.19 diketahui bahwa dari 2.688 ibu yang tidak
melakukan kunjungan antenatal terdapat 45 kematian neonatal (1,7%),
sedangkan dari 4.416 ibu yang melakukan kunjungan antenatal terdapat 34
kematian neonatal (0,8%). Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p =
0,001 sehingga dapat diartikan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat
hubungan antara kunjungan antenatal dengan kematian neonatal.
5.20 Hubungan Komplikasi Kehamilan dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara komplikasi kehamilan dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.20 berikut ini:
Tabel 5.20 Analisis Hubungan antara Komplikasi Kehamilan dengan Kematian Neonatal
di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Komplikasi Kehamilan
Kematian Neonatal Total P Value Meninggal Tidak meninggal
n % n % n % Komplikasi 12 2,8 415 97,2 427 100 0,002 Tidak komplikasi 67 1,0 6644 99,0 6711 100

103
Berdasarkan Tabel 5.20 diketahui bahwa dari 427 ibu yang mengalami
komplikasi kehamilan terdapat 12 kematian neonatal (2,8%), sedangkan dari
6.711 ibu yang melakukan kunjungan antenatal terdapat 67 kematian neonatal
(1,0%). Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,002 sehingga dapat
diartikan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terdapat hubungan antara
komplikasi kehamilan dengan kematian neonatal.
5.21 Hubungan Penolong Persalinan dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara penolong persalinan dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.21 berikut ini:
Tabel 5.21 Analisis Hubungan antara Penolong Persalinan dengan Kematian Neonatal di
Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Penolong Persalinan
Kematian Neonatal Total P Value Meninggal Tidak meninggal
n % n % n % Non Nakes 24 1,3 1887 98,7 1911 100 0,548 Nakes 55 1,1 5172 98,9 5227 100
Berdasarkan Tabel 5.21 diketahui bahwa dari 1.911 ibu dengan
penolong persalinan bukan tenaga kesehatan terdapat 24 kematian neonatal
(1,3%), sedangkan dari 5.227 ibu dengan penolong persalinan oleh tenaga
kesehatan terdapat 55 kematian neonatal (1,1%). Berdasarkan hasil uji statistik
diperoleh nilai p = 0,548 sehingga dapat diartikan bahwa pada tingkat
kepercayaan 95% tidak terdapat hubungan antara penolong persalinan dengan
kematian neonatal.

104
5.22 Hubungan Persalinan Caesar dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara persalinan caesar dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.22 berikut ini:
Tabel 5.22 Analisis Hubungan antara Persalinan Caesar dengan Kematian Neonatal
di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Persalinan Caesar
Kematian Neonatal Total P Value Meninggal Tidak meninggal
n % n % n % Caesar 9 1,6 562 98,4 571 100 0,363 Tidak Caesar 70 1,1 6497 98,9 6567 100
Berdasarkan Tabel 5.22 diketahui bahwa dari 571 ibu yang melakukan
persalinan caesar pada persalinannya terdapat 9 kematian neonatal (1,6%),
sedangkan dari 6.567 ibu yang tidak melakukan persalinan caesar pada
persalinannya terdapat 70 kematian neonatal (1,1%). Berdasarkan hasil uji
statistik diperoleh nilai p = 0,363 sehingga dapat diartikan bahwa pada tingkat
kepercayaan 95% tidak terdapat hubungan antara persalinan caesar dengan
kematian neonatal.
5.23 Hubungan Tempat Persalinan dengan Kematian Neonatal
Hasil analisis bivariat antara jenis kelamin bayi dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.23 berikut ini:

105
Tabel 5.23 Analisis Hubungan antara Tempat Persalinan dengan Kematian Neonatal
di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Tempat Persalinan
Kematian Neonatal Total P Value Meninggal Tidak meninggal
n % n % n % Non Fasyankes 45 1,1 4231 98,9 4276 100 0,674 Fasyankes 34 1,2 2828 98,8 2862 100
Berdasarkan Tabel 5.23 diketahui bahwa dari 4.276 ibu dengan
persalinan dilakukan bukan di fasilitas pelayanan kesehatan terdapat 45
kematian neonatal (1,1%), sedangkan dari 2.862 ibu dengan persalinan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terdapat 34 kematian neonatal
(1,2%). Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,674 sehingga dapat
diartikan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% tidak terdapat hubungan antara
tempat persalinan dengan kematian neonatal.

106
BAB VI
PEMBAHASAN
6.1 Keterbatasan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang
berhubungan dengan kematian neonatal di daerah rural Indonesia.
Keterbatasan pada penelitian ini termasuk merupakan keterbatasan pada SDKI
2012 sebagai sumber data pada penelitian ini. Pertama, pelaporan kematian
terbatas pada wanita umur 15-49 tahun yang masih hidup. Oleh karena itu,
pelaporan anak yang meninggal dari wanita yang telah meninggal tidak
tersampaikan. Sehingga akan menghasilkan bias terhadap estimasi mortalitas
neonatal. Estimasi mortalitas akan berbeda dengan kenyataan sesungguhnya
di lapangan.
Kedua, responden cenderung kurang mengingat kejadian di masa
lampau, sehingga kemungkinan terjadi pelaporan tanggal kelahiran dan umur
saat meninggal yang berbeda yang bisa menghasilkan angka kematian yang
bias. Ketiga, kematian hanya dikumpulkan dari wanita usia 15-49 tahun,
sehingga wanita usia 50 tahun tidak dapat melaporkan kelangsungan hidup
anaknya pada periode survei yang dimaksud. Keempat, SDKI 2012 tidak
meneliti seluruh faktor yang berhubungan dengan kematian neonatal,

107
sehingga variabel pada penelitian terbatas pada variabel yang diteliti SDKI
2012. Kelima, terdapat hingga ribuan data yang missing pada variabel jarak
kelahiran, inisiasi menyusu dini, komplikasi persalinan, berat bayi lahir,
kelahiran prematur dan kunjungan neonatal pertama sehingga variabel
tersebut tidak bisa dianalisis.
6.2 Kematian Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Menurut WHO (2006) kematian neonatal adalah kematian yang terjadi
selama dua puluh delapan hari pertama kehidupan setelah bayi dilahirkan.
Kematian neonatal dibedakan menjadi kematian neonatal dini dan kematian
neonatal lanjut. Kematian neonatal dini yaitu kematian saat setelah bayi
dilahirkan sampai 7 hari pertama kehidupannya (0-6 hari) sedangkan kematian
neonatal lanjut yaitu kematian setelah hari ke tujuh sampai sebelum dua puluh
delapan hari (7-27 hari).
Pada penelitian ini ditemukan kematian neonatal sebesar 0.8% dari
total 7.138 bayi yang dilahirkan selama periode 2008-2012. Walaupun jumlah
kematian neonatal pada penelitian ini terlihat sangat kecil, tetapi hasil
perhitungan secara keseluruhan kasus kematian neonatal di daerah rural
Indonesia pada SDKI 2012 menghasilkan angka kematian neonatal di daerah
rural Indonesia sebesar 24 per 1000 KH. Adanya perbedaan yang cukup rumit
antara kematian neonatal dini dan lahir mati, sehingga SDKI menyarankan
untuk menggabungkannya pada penghitungan angka kematian. Angka
kematian neonatal di daerah rural tersebut tetap konstan berdasarkan hasil

108
SDKI pada periode sebelumnya. (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF
International, 2013).
Pada penelitian ini, didapatkan Angka Kematian Neonatal di daerah
rural Indonesia sebesar 11,19 per 1000 KH. Angka kematian neonatal di
daerah rural pada penelitian ini menunjukkan lebih kecil dari hasil SDKI 2012
sebelumnya dikarenakan pada penelitian ini terdapat ratusan variabel yang
tidak dianalisis sehubungan adanya missing data. Oleh karena itu, terdapat
beberapa kasus kematian neonatal yang tidak bisa masuk ke dalam penelitian
ini. Angka Kematian Neonatal di daerah rural berdasarkan SDKI 2012
menunjukkan kematian lebih tinggi di daerah rural dibandingkan di daerah
urban (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013). Hasil angka
kematian neonatal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Bangladesh
bahwa risiko kematian neonatal di daerah rural menunjukkan lebih tinggi jika
dibandingkan dengan daerah urban (Chowdhury, dkk., 2013). Perbedaan
antara wilayah rural dan urban tersebut menggambarkan adanya perbedaan
wilayah yang mengalami perkembangan dan wilayah yang tidak mengalami
perkembangan (Yanping, dkk., 2010).
Periode neonatal merupakan periode paling kritis untuk perkembangan
dan pertumbuhan bayi (Saifudin, dkk., 2009). Bayi pada periode ini sangat
mudah terserang penyakit akibat terjadi transisi dari kehidupan didalam
kandungan ke kehidupan di luar kandungan (ekstrauterus) yang memerlukan
beberapa penyesuaian baik fisiologi maupun biokimia sehingga bayi dapat

109
bertahan hidup. Asfiksia, kelahiran prematur, dan efek persalinan merupakan
salah satu penyebab lemahnya adaptasi bayi terhadap lingkungan barunya
(Kliegman, dkk., 2011). Penyebab langsung kematian neonatal pada
penelitian belum diketahui karena data tidak tersedia pada SDKI 2012.
Penelitian-penelitian di daerah rural yang telah dilakukan sebelumnya
menunjukkan bahwa penyebab langsung kematian neonatal adalah infeksi,
berat bayi lahir rendah, meningitis/sepsis, kelahiran prematur, asfiksia dan
pneumonia (Hinderaker, dkk., 2003; Baqui, dkk., 2006; Chowdhury, dkk.,
2010; Yanping, dkk., 2010; Turnbull, dkk., 2011; Owais, dkk., 2013).
Sebanyak 65% kasus kematian neonatal berdasarkan hasil identifikasi
terhadap penyedia pelayanan kesehatan sebetulnya dapat dicegah dan 51%
kasus dapat dicegah dari faktor pasien itu sendiri. Sebagian besar ibu yang
memiliki risiko terhadap kematian neonatal tidak menyadari keberadaan
faktor risiko tersebut. Kemudian sebagian besar pasien gagal untuk mencari
layanan kesehatan ketika mereka mengetahui tanda bahaya pada kehamilan.
Padahal sebetulnya apabila ibu mendapatkan pencegahan terhadap komplikasi
dan bayi mendapatkan pengobatan yang adekuat bisa mencegah terjadinya
kematian pada neonatal (Hinderaker, dkk., 2003).
Penyebab lain kematian yang perlu mendapatkan perhatian serius di
daerah rural Indonesia yaitu masih tingginya pengaruh dari unsur budaya.
Hasil penelitian kualitatif pada ibu hamil Etnik Ngalum di Distrik Oksibil
Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat adat dimana pihak perempuan

110
harus membalas mas kawin kepada pihak laki-laki sebesar yang dibayarkan
kepada pihak perempuan. Apabila terjadi pelanggaran adat, ibu tidak
membayar mas kawin kepada pihak laki-laki, maka akan terdapat korban dari
keluarga tersebut. Salah satu kasus yang ditemukan, Ibu Tuti seorang ibu
hamil belum bisa membayar mas kawin sampai usia kehamilannya 9 bulan.
Pada saat melahirkan, bayi yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat namun
keesokan harinya ditemukan bayi telah meninggal. Keluarga menyadari betul,
bahwa hal itu terjadi karena mereka belum menyelesaikan pembayaran
kembali mas kawin. Sehingga mereka harus tunduk pada adat yang telah
ada/turun-temurun dari nenek moyang mereka (Kemenkes RI, 2012).
Diketahui hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa Provinsi Papua merupakan
salah satu provinsi dengan Angka Kematian Neonatal yang tinggi di Indonesia
yaitu sebesar 27 per 1000 KH (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International,
2013).
Selain itu, kasus kematian bayi baru lahir yang masih tinggi pada
Etnik Ngalum Papua juga disebabkan karena bayi mengalami infeksi
pneumonia. Hasil pengamatan menemukan, ternyata pada beberapa keluarga
dapur perapian bukan hanya digunakan untuk memasak makanan tetapi juga
digunakan untuk menghangatkan badan pada saat malam hari karena suhu
yang cukup dingin (19-200C). Namun, perapian tersebut tidak dilengkapi
dengan cerobong asap, sehingga asap hasil pembakaran hanya berputar di
dalam dapur (Kemenkes RI, 2012).

111
Penurunan Angka Kematian Neonatal sangat penting agar bisa
mencapai target MDGs 4 penurunan angka kematian bayi sebesar 23 per 1000
KH pada tahun 2015. Namun penurunan angka kematian bayi menjadi cukup
berat mengingat waktu pencapaian target hanya tersisa satu tahun. Sehingga
perlu dilakukan upaya-upaya lebih giat lagi dalam melakukan intervensi
terhadap penurunan Angka Kematian Bayi.
6.3 Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kematian Neonatal di Daerah Rural Indonesia Tahun 2008-2012
Faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian neonatal pada
penelitian ini diuraikan pada bagian-bagian berikut:
6.3.1 Pendidikan Ibu
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No. 20 tahun 2003).
Pendidikan dapat mempengaruhi ibu dalam memperoleh, memproses
dan memahami informasi. Informasi sangat penting bagi ibu untuk
membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ibu dengan tingkat
pendidikan tinggi akan lebih percaya diri untuk bertanya mengenai

112
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi dirinya (Karlsen, dkk.,
2011).
Pada penelitian ini, pendidikan ibu dikategorikan menjadi
pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Pendidikan rendah terdiri
dari SD dan SMP. Ibu yang tidak sekolah tidak termasuk pendidikan
rendah karena data tidak ditemukan pada penelitian ini. Sedangkan
pendidikan tinggi terdiri dari SMA, diploma, atau perguruan tinggi.
Pengkategorian ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan
sebelumnya (Singh, dkk., 2013).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang memiliki
tingkat pendidikan rendah lebih banyak dibandingkan ibu yang
berpendidikan tinggi (68,8%). Hasil analisis statistik menunjukkan
bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan
kematian neonatal. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan Wijayanti (2013) namun berbeda dengan hasil penelitian
Mahmood, dkk (2002) bahwa pendidikan ibu berpengaruh terhadap
penurunan kematian bayi pada daerah rural Pakistan. Pendidikan
berhubungan dengan kematian neonatal dimana semakin rendah
tingkat pendidikan ibu semakin besar peluang terjadinya kematian
pada neonatal (Faisal, 2010).
Walaupun secara statistik hasil penelitian ini tidak
menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan ibu dengan

113
kematian neonatal, pada penelitian ini ditemukan bahwa jumlah
kematian neonatal lebih tinggi pada ibu dengan pendidikan rendah.
Hal ini sejalan dengan hasil Singh, dkk (2013) pada penelitiannya
bahwa bayi yang dilahirkan dari ibu yang sekolah lebih dari 10 tahun,
lebih sedikit bayi yang mengalami kematian neonatal (40%) jika
dibandingkan ibu yang buta huruf. Ibu dengan pendidikan rendah
merupakan kelompok berisiko dimana rendahnya tingkat pendidikan
dapat menurunkan kemampuan ibu untuk memahami informasi yang
diberikan (Karlsen, dkk., 2011).
Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang
dilakukan Andargie, dkk (2013) bahwa kematian bayi lebih tinggi
pada kelompok ibu pendidikan rendah (buta huruf). Sehingga ibu
dengan pendidikan tinggi merupakan harapan yang bisa memberikan
banyak manfaat dan peluang lebih baik untuk menurunkan kemiskinan
serta masalah kemiskinan yang berkaitan dengan masalah kesehatan.
Pada penelitian lainnya diketahui ibu yang tidak mengalami
pendidikan cenderung lebih banyak tinggal di daerah dengan waktu
tempuh lebih dari 1,5 jam ke fasilitas pelayanan kesehatan
dibandingkan ibu dengan pendidikan (Okwaraj, dkk., 2012). Hal ini
mengindikasikan bahwa kematian neonatal akan diperparah dengan
masalah waktu tempuh ke pelayanan kesehatan pada ibu dengan
pendidikan rendah.

114
Penelitian kualitatif lainnya menemukan bahwa pada
masyarakat suku Dayak Siang Murung Raya, terdapat remaja yang
masih duduk di bangku sekolah yang sudah menikah bahkan remaja
yang belum mengalami menstruasi. Hal tersebut terjadi karena
diketahui sebagian besar pendidikan masyarakat setempat yang masih
rendah (Kemenkes RI, 2012). Hal ini juga ditemukan bahwa sebagian
besar masyarakat suku Gorontalo Desa Imbodu berpendidikan rendah.
Selain itu, informasi yang didapatkan secara informal juga jarang
ditemukan di daerah perdesaan. Sebagian besar masyarakat
mendapatkan pengetahuan kesehatan berdasarkan penuturan-
penuturan orang tua. Para orang tua memiliki pengalaman diobati oleh
dukun saat mereka sakit. Selain itu, para remaja sungkan untuk
bertanya mengenai masalah kesehatan reproduksi kepada orangtuanya.
Biasanya para remaja tersebut mendapatkan informasi dari teman-
temannya (Kemenkes RI, 2012).
Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini, pemberian informasi
tentang kesehatan ibu dan anak perlu lebih ditingkatkan pada
kelompok ibu dengan tingkat pendidikan rendah. Peningkatan
pemberian informasi juga harus didukung oleh ketersediaan akses
yang memadai terhadap informasi tersebut.

115
6.3.2 Pekerjaan Ibu
Ibu yang melakukan pekerjaan pada saat hamil memiliki
kemungkinan terkena pajanan zat fetotoksik, ketegangan fisik
berlebihan, kelelahan serta kesulitan yang berhubungan dengan
keseimbangan tubuh. Kondisi lain, seperti ibu sering berdiri di suatu
tempat dalam jangka waktu lama juga bisa berisiko terhadap varises
vena, flebitis dan edema yang bisa membahayakan ibu (Ladewig, dkk.,
2006).
Pada penelitian ini, status pekerjaan ibu dibedakan menjadi
bekerja dan tidak bekerja. Ibu dikatakan bekerja apabila ibu berprofesi
sebagai tenaga ahli/teknisi, pemimpin, pejabat, industri, jasa, pertanian
dan tenaga produksi. Sedangkan ibu dikatakan tidak bekerja apabila
ibu mengatakan tidak memiliki profesi-profesi tertentu.
Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah ibu yang bekerja
lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak bekerja (54,7%). Ibu lebih
banyak bekerja pada bidang pertanian (19,5%), tenaga usaha jasa dan
penjualan (14%), dan pekerja industri (12,1%). Hasil uji statistik
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status pekerjaan dengan
kematian neonatal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
sebelumnya oleh Titaley, dkk (2008) bahwa status ibu bekerja
memiliki hubungan dengan kematian pada neonatal. Penelitian lainnya
yang dilakukan Faisal (2010) juga menunjukkan bahwa ibu yang

116
bekerja mempunyai kecenderungan untuk mengalami kejadian
kematian bayi 1,52 kali lebih besar dibandingkan ibu yang tidak
bekerja. Penelitian lainnya di wilayah rural India menunjukkan terjadi
penurunan risiko kematian neonatal sebesar 10% pada neonatus yang
dilahirkan dari ibu yang tidak bekerja dibandingkan neonatus yang
dilahirkan dari ibu yang bekerja (Singh, dkk., 2013).
Penelitian di daerah rural Etiopia juga menunjukkan bahwa
kematian bayi lebih tinggi terjadi pada ibu yang bekerja yang
merupakan usaha miliki sendiri. Bayi dari ibu tersebut memiliki risiko
5,4 kali lebih besar untuk mengalami kematian dibandingkan bayi dari
ibu pada kelompok lainnya (petani, IRT) (Andargie, dkk., 2013).
Penelitian di daerah rural India juga menemukan bahwa anak dari ibu
yang tidak bekerja (tinggal di rumah) memiliki risiko lebih rendah
untuk meninggal selama periode neonatal dibandingkan anak dari ibu
yang bekerja (Singh, dkk., 2013).
Pada penelitian ini menunjukkan ibu sebagian besar bekerja
sebagai petani. Hasil penelitian kualitatif yang dilakukan Pusat
Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Balitbangkes Kemenkes RI, di salah satu daerah rural Indonesia, Desa
Jrangoan (Suku Madura) Kecamatan Omben Kabupaten Sampang
Jawa Timur, menemukan bahwa remaja putri telah menikah umumnya
pada usia 17 tahun. Remaja putri tersebut yang kemudian menjadi

117
nyonya-nyonya kecil harus bisa membantu suami mengurus ladang
yang merupakan tempat mereka mencari nafkah. Ibu hamil tetap
bekerja ke sawah walaupun dalam kondisi hamil karena ingin
membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarga. Kegiatan bertani
yang dilakukan oleh ibu hamil tersebut adalah menanam berbagai jenis
tanaman seperti padi, kacang-kacangan, singkong, ketela, cabai,
bawang dan tembakau (Kemenkes RI, 2012).
Ibu-ibu muda tersebut akan istirahat hanya saat menjelang
persalinan. Setelah melahirkan, ibu juga hanya diminta untuk duduk
sementara pekerjaan lain yang biasanya dikerjakan seperti memasak,
mencuci pakaian dan membersihkan rumah dilakukan oleh sang
suami. Namun, hal ini terjadi jika sang suami tidak pergi ke luar kota
untuk bekerja. Bagi ibu yang suaminya bekerja di luar kota, ibu tetap
harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Selain itu,
mereka akan mulai bekerja setelah 35 hari dari persalinan dengan
alasan masa nifas telah selesai dan sudah mampu bekerja di ladang.
Pekerjaan di ladang yang dilakukan masyarakat suku madura ini
memang biasanya dilakukan oleh perempuan/ibu (Kemenkes RI,
2012). Kebiasaan ibu tetap bekerja juga ditemukan di Etnik Manggarai
Desa Waicodi Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa
Tenggara Timur, ibu hamil usia muda maupun usia kehamilan tujuh
bulan masih selalu bekerja membantu suaminya di ladang. Pada saat

118
menjelang persalinan, ibu juga dianjurkan untuk turut bekerja di kebun
agar janin dalam kandungan tidak diganggu roh jahat (Kemenkes RI,
2012).
Penelitian kualitatif lainnya pada masyarakat Etnik Ngalum
Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua
menemukan bahwa kebiasaan ibu saat hamil pada etnik ini yaitu dari
mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga, memetik hasil kebun dan
kemudian menjualnya ke pasar, dimana jarak rumah ke pasar cukup
jauh. Ibu hamil dan ibu-ibu lainnya kemudian menggunakan hasil
penjualan dagangannya untuk membeli keperluan keluarga yang telah
habis. Selanjutnya ibu menyiapkan makanan siang untuk keluarganya
dan setelah semua selesai ibu melakukan pekerjaan lain, mencuci
pakaian, mencuci piring, mengangkat air dan bahkan kembali lagi ke
kebun mengangkat kayu bakar untuk memasak di rumah. Kebiasaan-
kebiasaan melakukan pekerjaan berat ini berlaku bagi seluruh ibu di
Etnik Ngalum baik ibu tidak hamil maupun tidak hamil (Kemenkes
RI, 2012).
Kebiasaan bekerja pada ibu hamil juga ditemukan pada Etnik
Dayak Siang Murung di Kalimantan Tengah, ibu hamil tetap memilih
bekerja walaupun keluarga dan suami menganjurkan tidak bekerja. Ibu
hamil tetap melakukan mantat (menyadap karet) sebagai mata
pencaharian mereka bersama suaminya di ladang (Kemenkes RI,

119
2012). Kebiasaan tetap bekerja juga ditemukan pada ibu hamil Etnik
Alifuru di Provinsi Maluku, ibu tidak pernah berhenti melakukan
kegiatan yang harus dilakukannya sehari-hari walaupun usia
kehamilannya sekitar enam bulan. Ibu tetap pergi ke hutan, mencari
air, serta mengurus rumah dan anak-anak seperti biasanya. Ibu
menganggap bahwa kehamilan tidak boleh menghalanginya dari tugas
dan kewajiban sehari-hari (Kemenkes RI, 2012).
Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini dianjurkan
agar ibu hamil di daerah rural Indonesia menghindari pekerjaan yang
terlalu berat seperti melakukan pekerjaan tanpa jeda dari mulai pagi
sampai sore hari terutama pekerjaan berat seperti mengambil kayu di
hutan, menyadap getah karet dan membawa air dari hutan. Hal ini bisa
menyebabkan ibu hamil mengalami ketegangan atau kelelahan yang
bisa membahayakan kondisi kesehatannya serta janin yang
dikandungnya. Seperti diketahui hasil pada penelitian ini menunjukkan
bahwa ibu yang bekerja berhubungan dengan kejadian kematian
neonatal di daerah rural Indonesia.
6.3.3 Indeks Kekayaan Rumah Tangga
Indeks kekayaan rumah tangga pada SDKI 2012 dihitung
berdasarkan kepemilikan rumah tangga terhadap sejumlah aset yang
digunakan di rumah tangga seperti fasilitas sanitasi, sumber air minum,
barang tahan lama, bahan lantai rumah dan lain lain. Berdasarkan

120
keterangan kepemilikan atas sejumlah aset tersebut kemudian dihitung
menggunakan prinsip analisis komponen untuk mendapatkan skor
indeks kekayaan. Skor indeks kekayaan dibagi kedalam lima kuintil
kekayaan dari mulai skor indeks kekayaan terendah sampai tertinggi
yang terdiri dari 20% penduduk pada setiap kuintil. Lima kuintil
tersebut yaitu kuintil terendah, kedua, menengah, keempat dan
tertinggi. Hasil dari kepemilikan rumah tangga atas barang-barang
tertentu yang dibedakan kedalam lima kuintil tersebut digunakan untuk
mengukur status sosial ekonomi keluarga (BPS, BKKBN, Kemenkes
& ICF International, 2013).
Pada penelitian ini, indeks kekayaan rumah tangga dibedakan
menjadi tiga kategori yaitu rendah, menengah dan tinggi. Kategori
rendah terdiri dari kuintil terendah dan kuintil kedua, kategori
menengah terdiri dari kuintil menengah serta ketegori tinggi terdiri
dari kuintil keempat dan kuintil tertinggi. Pengelompokan ini
dilakukan karena jumlah kematian neonatal pada kuintil ke-2 dan ke-4
sangat kecil. Hal ini juga dilakukan pada penelitian sebelumnya
Bashir, dkk (2013) dimana kategori dibedakan menjadi rendah,
menengah dan tinggi karena jumlah kematian neonatal pada kuintil ke-
2 dan ke-4 sangat kecil.
Ibu dan anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki risiko
meningkat terhadap kematian neonatal karena memiliki tantangan

121
untuk mengakses pelayanan tepat waktu dibandingkan keluarga yang
lebih kaya (Lawn, dkk., 2009). Hasil penelitian ini menunjukkan ibu
yang memiliki indeks kekayaan rumah tangga rendah lebih banyak
dibandingkan ibu dengan indeks kekayaan menengah dan tinggi
(66,6%). Analisis statistik yang dilakukan pada penelitian ini
menemukan tidak terdapat hubungan antara indeks kekayaan rumah
tangga dengan kematian neonatal. Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan hasil penelitian Bashir, dkk (2013) bahwa indeks kekayaan
rumah tangga memiliki hubungan dengan kejadian kematian neonatal.
Pada penelitian Manzar, dkk (2012) dan Gizaw, dkk (2014) juga
menemukan bahwa neonatus yang berasal dari ibu dengan status sosial
ekonomi dibawah rata-rata lebih rentan mengalami kematian pada
periode neonatal.
Pada penelitian ini, jumlah ibu dengan indeks kekayaan rumah
tangga rendah lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Penelitian
kualitatif di salah satu daerah rural Indonesia juga menunjukkan bahwa
proporsi masyarakat kelompok miskin pada masyarakat Suku Mamasa
masih cukup besar (27,5%) (Kemenkes RI, 2012). Namun, pada
penelitian ini proporsi kematian neonatal lebih tinggi pada kelompok
lainnya. Kematian neonatal lebih tinggi pada kelompok indeks
kekayaan rumah tangga menengah dan tinggi. Hasil ini tidak konsisten
dengan hasil penelitian yang dilakukan di daerah rural Nepal bahwa

122
terjadi pengaruh faktor sosial-ekonomi yang lebih besar dibandingkan
pengaruh faktor biologi terhadap kelangsungan hidup bayi pada ibu
dengan usia muda (Sharma, dkk., 2009).
Sehingga kemungkinan penyebab kematian neonatal lebih
tinggi pada kelompok indeks kekayaan menengah dan tinggi karena
kelompok ibu usia berisiko lebih tinggi pada kelompok ini. Namun,
pada penelitian ini ditemukan bahwa ibu dengan usia berisiko, lebih
tinggi pada kelompok indeks kekayaan rendah. Kemungkinan faktor
lainnya berkontribusi terhadap hasil penelitian ini seperti status
pekerjaan ibu dan persalinan caesar. Pada penelitian ini diketahui
status ibu bekerja lebih tinggi pada kelompok ibu dengan indeks
kekayaan rendah dibandingkan kelompok lainnya. Hasil ini sesuai
dengan penelitian oleh Singh, dkk (2013) di daerah rural India bahwa
pada ibu yang bekerja menunjukkan ibu memiliki tingkat ekonomi
lebih rendah. Kemungkinan penyebab lainnya adalah tingginya
persalinan caesar, namun ternyata persalinan caesar menunjukkan
lebih tinggi pada ibu dengan indeks kekayaan rumah tangga rendah.
Penyebab lain tingginya kematian pada kedua kelompok
tersebut yaitu jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, menurut
Okwaraj, dkk (2012) efek dari jarak terhadap fasilitas layanan
kesehatan lebih berpengaruh di daerah dengan tingkat kemiskinan
tinggi dimana mereka tidak memiliki biaya untuk membayar

123
transportasi ke fasilitas layanan kesehatan dibandingkan keluarga yang
kaya. Pada penelitian ini diketahui kematian neonatal lebih tinggi pada
kelompok ibu dengan indeks kekayaan rumah tangga menengah dan
tinggi. Sehingga, masalah biaya untuk transportasi kemungkinan tidak
menjadi kendala bagi kedua kelompok ini. Sehingga perlu adanya
penelitian untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh terhadap
tingginya angka kematian neonatal pada kelompok indeks kekayaan
menengah dan atas.
6.3.4 Umur Ibu
Pada umur dibawah 20 tahun, rahim dan panggul sering kali
belum tumbuh mencapai ukuran dewasa. Akibatnya, ibu hamil pada
usia itu mungkin mengalami persalinan lama/macet atau gangguan
lainnya karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas dan
tanggungjawabnya sebagai orang tua. Ibu dianjurkan hamil pada usia
antara 20-35 tahun. Pada usia ini ibu lebih siap hamil secara jasmani
dan kejiwaan. Pada umur 35 tahun atau lebih, kesehatan ibu sudah
menurun, akibatnya ibu hamil pada usia itu mempunyai kemungkinan
lebih besar untuk mempunyai anak cacat, persalinan lama dan
perdarahan (Kemenkes RI, 2011).
Pada penelitian ini, ibu dikategorikan kedalam kelompok ibu
kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun dan kelompok ibu usia
20-35 tahun. Pengelompokkan ini didasarkan pada hasil penelitian

124
sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayanti (2013). Penelitian ini
menunjukkan, ibu yang memiliki umur kurang dari 20 tahun dan lebih
dari 35 tahun yaitu sebesar 27,7%. Hasil uji statistik umur ibu dengan
kematian neonatal diketahui terdapat hubungan antara umur ibu
dengan kematian neonatal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Yego, dkk
(2013) bahwa sebagian besar kematian neonatal terjadi pada ibu usia
muda. Umur ibu memiliki pengaruh terhadap kematian neonatal,
dimana semakin muda dan semakin tua umur ibu, maka semakin
tinggi juga kematian pada neonatal (Mekonnen, dkk., 2013; Bashir,
dkk., 2013; Markovitz, dkk., 2005). Pada penelitian ini menunjukkan
bahwa kematian neonatal lebih tinggi pada kelompok umur kurang
dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Penelitian oleh Sharma, dkk
(2009) juga menemukan bahwa kejadian yang merugikan bayi baru
lahir lebih tinggi pada kelompok ibu usia 12-15 dibandingkan ibu usia
20-24. Sekitar 51% bayi mengalami BBLR, 24% lahir prematur dan
73,5% usia kehamilan kecil. Bayi yang dilahirkan dari ibu usia 12-15
tahun memiliki risiko 2,24 kali lebih tinggi terhadap kematian neonatal
dibandingkan bayi yang dilahirkan dari ibu usia 20-24 tahun.
Penelitian lainnya berbasis rumah sakit di Nepal menemukan
bahwa kejadian BBLR, komplikasi pada neonatal dan komplikasi pada
ibu, lebih tinggi ditemukan pada ibu usia 15-19 tahun dibandingkan

125
ibu usia 20-24 tahun (Pun & Chauhan, 2011). Hasil ini juga didukung
oleh Chen, dkk (2007) bahwa kehamilan yang terjadi pada remaja
berhubungan dengan kejadian peningkatan risiko kematian pada
neonatal.
Hasil penelitian kualitatif di salah satu daerah rural Indonesia,
yaitu pada masyarakat Etnik Madura Jawa Timur, menemukan bahwa
umumnya remaja putri di daerah tersebut menikah sebelum
menyelesaikan pendidikan pesantren, yaitu sekitar usia 17 tahun
(Kemenkes RI, 2012). Penelitian kualitatif lainnya pada Etnik Nias,
Sumatera Utara juga menemukan bahwa masyarakat di Desa
Hilifadölö secara umum mentaati peraturan mengenai usia boleh
menikah yaitu minimal 18 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi
laki-laki. Selain itu, masih ditemukan beberapa pasangan yang
menikah sebelum umur tersebut. Sebagian besar pasangan yang
menikah sebelum umur yang telah ditetapkan adalah pasangan yang
menikah di luar Pulau Nias (Kemenkes RI, 2012). Bahkan hasil
penelitian lainnya menemukan bahwa usia perkawinan yang
dianjurkan pada masyarakat Etnik Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat
yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan minimal 18 tahun untuk
laki-laki (Kemenkes RI, 2012).
Pada masyarakat Etnik Ngalum, Provinsi Papua, juga diketahui
bahwa batasan usia boleh melakukan pernikahan di Daerah

126
Pegunungan Bintang adalah 18 tahun. Secara umum masyarakat yang
benar-benar memegang norma adat mematuhi aturan tersebut. Namun,
diektahui masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut
dengan melakukan perkawinan pada usia dini. Kurangnya
pengetahuan para remaja Etnik Ngalum mengenai kesehatan
reproduksi, sehingga banyak remaja yang hamil pada usia sangat muda
yaitu usia 13 tahun (Kemenkes RI, 2012).
Remaja tersebut melakukan aktivitas belajar di sekolah dalam
keadaan hamil dan pihak guru tidak melarang mereka mengikuti
kegiatan belajar karena sudah memahami kondisi murid seperti itu di
daerahnya. Bahkan ada remaja yang telah memiliki anak, kemudian
menunggunya diluar kelas bersama ibunya. Selain itu, para remaja
tersebut cenderung tidak mengingat waktu terakhir mengalami haid,
sehingga mereka tidak mengetahui berapa umur kandungannya. Kasus
kehamilan tidak hanya ditemukan pada anak dan remaja tetapi juga
terjadi pada ibu usia lebih dari 45 tahun. Padahal kehamilan pada usia
tersebut sangat berisiko terhadap terjadinya komplikasi kehamilan.
Apalagi diketahui kasus anemia pada ibu hamil di Suku Ngalum
merupakan kasus yang paling tinggi di Papua (Kemenkes RI, 2012).
Sehingga berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka perlu
adanya peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan ibu dan anak
bagi kelompok ibu usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun.

127
Peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu tersebut harus
ditingkatkan lebih serius di daerah rural Indonesia baik melalui
layanan antenatal di fasilitas layanan kesehatan maupun kegiatan yang
telah ada di masyarakat.
6.3.5 Jenis Kelamin Bayi
Jenis kelamin merupakan karakteristik fisik seseorang sebagai
laki-laki atau perempuan (Andrews, 2009). Bayi laki-laki cenderung
lebih rentan terhadap penyakit jika dibandingkan dengan bayi
perempuan. Secara biologis, bayi perempuan mempunyai fungsi
fisiologi tubuh lebih baik jika dibandingkan dengan bayi laki-laki
(Wells, 2000).
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa bayi berjenis kelamin
laki-laki lebih banyak dibandingkan bayi berjenis kelamin perempuan
(52,2%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat
hubungan antara jenis kelamin bayi dengan kematian neonatal. Hasil
penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan
Titaley (2008) dan Pertiwi (2010) yang menemukan bahwa terdapat
hubungan antara jenis kelamin bayi dengan kematian neonatal. Bayi
berjenis kelamin laki-laki memiliki risiko 1,49 kali lebih besar
terhadap kematian neonatal dibandingkan bayi perempuan (Titaley,
dkk., 2008). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian-

128
penelitian lainnya yang dilakukan sebelumnya (Dewi, 2010; Faisal,
2010; Wijayanti, 2013).
Namun, pada penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi
kematian neonatal lebih tinggi pada bayi berjenis kelamin laki-laki
dibandingkan bayi jenis kelamin perempuan. Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan di daerah rural Bangladesh yang
menunjukkan bahwa proporsi kematian neonatal lebih tinggi pada bayi
jenis kelamin laki-laki (60%) dibandingkan bayi jenis kelamin
perempuan (Owais, dkk., 2013). Keuntungan biologis yang dimiliki
bayi perempuan kemungkinan menyebabkan bayi perempuan lebih
mampu untuk bertahan hidup dibandingkan bayi laki-laki (Wells,
2000).
Seleksi alam diprediksi dapat meningkatkan kerentanan bayi
laki-laki terhadap kondisi-kondisi seperti penyakit infeksi, luka atau
gizi buruk. Fungsi fisiologi bayi laki-laki pada awal kehidupan tidak
sebaik fungsi fisiologi pada bayi perempuan. Perbedaan tersebut
diasumsikan semakin berkembang dengan munculnya masalah gizi
pada anak. Gizi memegang peranan penting sebagai etiologi penyakit
yang berkaitan dengan paru-paru pada neonatal. Bayi perempuan lebih
terlindungi karena memiliki tingkat kematangan paru-paru lebih baik
dibandingkan bayi laki-laki. Adanya interaksi antara penyakit infeksi
dengan masalah gizi menyebabkan kondisi yang semakin

129
membayakan bayi laki-laki. Selanjutnya, adanya pengaruh lingkungan
pada semua status gizi merupakan faktor yang lebih memperberat
kondisi laki-laki terhadap kasus kematian (Wells, 2000).
Selain itu, menurut penelitian kualitatif diketahui bahwa anak
laki-laki (ono matua) dianggap lebih berharga dibandingkan dengan
anak perempuan pada suku Nias. Hal ini disebabkan karena suku Nias
menganut sistem patrilinear, yakni garis keturunan yang diikuti adalah
dari pihak laki-laki sehingga anak laki-lakilah yang akan meneruskan
keturunan/marga (ngaötö/mado) keluarga dan juga mengurus harta
atau warisan yang dimiliki keluarga. Selain itu, sebagian besar anak
laki-laki yang sudah menikah tinggal bersama dengan orang tua
sehingga kelak ketika orang tua sudah tidak bisa bekerja lagi maka
anak laki-laki inilah yang akan mengurus orang tuanya. Sehingga para
ibu terus hamil sampai akhirnya berhasil mendapatkan anak laki-laki
(Kemenkes RI, 2012).
6.3.6 Paritas
Menurut Kamus Saku Mosby, paritas merupakan klasifikasi
perempuan berdasarkan jumlah bayi lahir hidup dan lahir mati yang
dilahirkannya pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Pada saat
hamil, rahim ibu teregang karena adanya janin. Apabila terlalu sering
melahirkan, rahim ibu akan semakin lemah. Jika ibu telah melahirkan

130
3 anak atau lebih, perlu diwaspadai adanya gangguan pada waktu
kehamilan, persalinan dan nifas (Kemenkes RI, 2011).
Pada penelitian ini, paritas dibedakan menjadi kelompok
paritas 1-3 dan paritas lebih dari 3. Pengkategorian ini didasarkan pada
hasil penelitian sebelumnya (Titaley, dkk., 2008) yang membagi
paritas kedalam dua kelompok. Pada penelitian ini menunjukkan
bahwa ibu yang telah melahirkan lebih dari tiga anak sebesar 19,1%.
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
paritas dengan kematian neonatal. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian Titaley, dkk (2008) bahwa paritas lebih dari tiga memiliki
hubungan dengan kematian neonatal. Hasil penelitian ini berbeda
dengan hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti (2013) yang
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara paritas dengan
kematian neonatal.
Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa kematian
neonatal lebih tinggi pada ibu dengan paritas lebih dari tiga. Hasil ini
konsisten dengan penelitian Titaley (2008) di Indonesia yang
menunjukkan bahwa kematian neonatal lebih tinggi terjadi pada bayi
dengan urutan kelahiran lebih dari empat dengan jarak kelahiran
kurang atau sama dengan dua tahun. Bayi dengan urutan kelahiran
lebih dari tiga merupakan faktor risiko potensial terhadap kematian
neonatal (Chaman, dkk., 2009). Tingginya paritas berkaitan dengan

131
semakin melemahnya rahim ibu akibat terjadinya peregangan rahim
karena keberadaan janin (Kemenkes RI, 2011).
Hasil peneilitian Faisal (2010) juga menunjukkan bahwa ibu
yang telah melahirkan lebih dari tiga anak mempunyai kecenderungan
untuk mengalami kejadian kematian bayi sebesar 1,66 kali
dibandingkan ibu yang telah melahirkan 1-3 anak. Pada penelitian
lainnya juga menunjukkan bahwa kematian neonatal semakin
meningkat pada ibu dengan paritas lebih dari tiga (Kozuki, dkk.,
2013). Kozuki, dkk (2013) juga menemukan bahwa kelahiran pertama
(nulipara) menunjukkan risiko kematian neonatal yang lebih tinggi.
Penelitian lainnya menunjukkan bahwa ibu dengan kelahiran pertama
memiliki risiko yang meningkat terhadap hipertensi, BBLR dan
persalinan caesar. Ibu dengan paritas tinggi namun tidak memiliki
riwayat komplikasi sebelumnya memiliki risiko yang rendah terhadap
terjadinya komplikasi (Majoko, dkk., 2004).
Pada penelitian ini, peneliti memasukan paritas satu kedalam
kelompok tidak berisiko berdasarkan pertimbangan terhadap
penelitian-penelitian yang telah dilakukan di Indonesia. Penelitian
tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara paritas satu dengan
kematian neonatal (Rahmawati, 2007; Nugraheni, 2013). Selain itu,
penelitian lainnya menunjukkan ada hubungan antara paritas lebih dari
tiga dengan kematian neonatal (Faisal, 2010). Penelitian yang

132
dilakukan di daerah rural Iran juga menunjukkan paritas lebih dari tiga
memiliki hubungan dengan kejadian kematian pada neonatal (Chaman,
dkk., 2009).
Hasil penelitian kualitatif pada Suku Ngalum Provinsi Papua
menemukan bahwa ibu yang hamil pada usia lebih dari 45 tahun
memiliki anak rata-rata11-14 anak dengan jarak kelahiran yang
berdekatan. Namun, dengan jumlah anak yang banyak dan tingkat
anemia tinggi/gizi kurang sehingga banyak ditemukan kasus retensio
plasenta (plasenta tertahan di dalam rahim tidak keluar bersama bayi).
Sehingga, ditemukan tingkat kematian ibu yang sangat tinggi pada
Suku Ngalum (Kemenkes RI, 2012).
Hasil penelitian kualitatif lainnya menunjukkan bahwa nilai
anak bagi orang Toraja Sa’dan sangat penting. Memiliki banyak anak
masih menjadi pandangan utama bagi sebagian besar penduduk
Sa’dan. Program Keluarga Berencana (KB) dari pemerintah yang
mengarahkan dua anak lebih baik tidak berlaku bagi orang Toraja
Sa’dan. Istilah KB bagi orang Toraja Sa’dan diubah menjadi “keluarga
besar”, untuk menunjukkan banyaknya jumlah anak yang mereka
miliki. Bahkan seorang yang terpandang di Toraja menceritakan
bahwa dua bukan dua orang, namun dua pasang (empat orang) untuk
menunjukkan anak yang beliau miliki. Ketiadaan seorang anak bagi
orang Toraja Sa’dan merupakan hal yang masiri’ (malu) dalam

133
keluarga, dianggap lemah, dan dikasihani oleh keluarga luas. Bahkan,
sekalipun sudah memiliki anak, tetapi baru satu, keluarga tersebut
masih dianggap belum lengkap (Kemenkes RI, 2012).
Padahal, hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang
bisa dilakukan untuk mengontrol jumlah kelahiran adalah penggunaan
metode kontrasepsi. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh,
menunjukkan bahwa penggunaan metode kontrasespi berhubungan
dengan kejadian kematian neonatal. Pada ibu yang pernah
menggunakan metode kontrasepsi sekitar 39% lebih rendah terhadap
kematian neonatal dibandingkan ibu yang tidak pernah menggunakan
metode kontrasepsi (Chowdhury, dkk, 2013).
Pemakaian metode kontrasepsi (Contraceptive Prevalence
Rate) di Indonesia menurut hasil SDKI 2012 diketahui tidak ada
perbedaan antara daerah perdesaan dengan daerah perkotaan yaitu
sebesar 62%. Pemakaian kontrasepsi ini mengalami peningkatan dari
tahun 2007 sebelumnya yaitu sebesar 61%. Pemakaian metode
kontrasepsi modern juga mengalami peningkatan dari 57% menjadi
58% (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013). Namun,
angka ini masih cukup jauh dari target MDGs 5 untuk meningkatkan
pemakaian metode kontrasepsi modern sebesar 65% pada tahun 2015
(Kemenkes RI, 2014).

134
Diantara metode KB modern, metode KB yang paling banyak
digunakan wanita berstatus kawin adalah suntikan dan pil (masing-
masing 32 dan 14%). Peserta KB suntikan mengalami peningkatan
dari 12% tahun 1991 menjadi 32% tahun 2012. Sedangkan peserta KB
IUD mengalami penurunan dari 13% tahun 1991 menjadi 4% tahun
2012. Wanita di daerah perdesaan cenderung lebih banyak
menggunakan metode suntik dibanding daerah perkotaan (masing-
masing sebesar 28% dan 35%) sedangkan metode IUD,
MOW/sterilisasi wanita dan kondom lebih banyak di gunakan di
daerah perkotaan (BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International,
2013).
Adapun total tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmetneed) wanita berstatus kawin 15-49 tahun pada SDKI 2012
sebesar 11% (7% untuk membatasi kelahiran dan 4% untuk
menjarangkan kelahiran). Walaupun unmetneed ini telah turun dari
13% pada SDKI 2007 menjadi 11% pada SDKI 2012 (BPS, BKKBN,
Kemenkes & ICF International, 2013), namun angka ini masih belum
mencapai target MDGs 5 untuk menurunkan unmetneed menjadi 5%
pada tahun 2015 (Kemenkes RI, 2014).
Hasil penelitian kualitatif di daerah Kalimantan Tengah
menemukan bahwa ibu hamil Suku Dayak Siang Murung terpaksa
tidak melakukan KB karena alat di fasilitas kesehatan tidak tersedia
(Kemenkes RI, 2012). Pada masyarakat suku lainnya diketahui bahwa

135
ibu sudah mengetahui tentang manfaat KB, namun ibu tetap ingin
memiliki anak lebih dari dua. Falsafah hidup Banyak Anak Banyak
Rezeki masih diyakini beberapa warga hingga saat ini (Kemenkes RI,
2012).
Sehingga upaya penurunan angka kematian neonatal dengan
mengunakan strategi peningkatan pemakaian metode kontrasepsi perlu
dilakukan. Startegi pemakaian metode kontrasepsi selain
memperhatikan aspek kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan juga
memperhatikan aspek budaya/adat masyarakat setempat.
6.3.7 Kunjungan Antenatal
Kunjungan antenatal merupakan pemeriksaan kesehatan yang
dilakukan ibu hamil selama masa kehamilannya minimal empat kali
yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (0-12 minggu),
minimal satu kali pada trimester ke-2 (≥12-24 minggu) dan minimal 2
kali pada trimester ke-3 (≥24 minggu sampai kelahiran) (Kemenkes
RI, 2012). Pelayanan kesehatan neonatal harus dimulai sebelum bayi
dilahirkan melalui pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu
hamil. Manajemen yang baik yang diperoleh bayi saat masih dalam
kandungan akan menghasilkan bayi yang sehat (Saifudin, dkk., 2009).
Pada penelitian ini, kunjungan antenatal dikategorikan menjadi
melakukan kunjungan antenatal dan tidak melakukan kunjungan
antenatal. Ibu dikategorikan melakukan kunjungan antenatal apabila

136
ibu melakukan kunjungan minimal satu kali pada trimester pertama,
minimal satu kali pada trimester kedua dan minimal dua kali pada
trimester ketiga. Pengkategorian ini dilakukan berdasarkan kriteria
kunjungan antenatal yang di rekomendasikan di Indonesia (Kemenkes
RI, 2012). Selain itu, pengkategorian ini juga didasarkan pada hasil
penelitian-penelitian sebelumnya (Yani & Duarsa, 2013; Singh, dkk.,
2014).
Pada penelitian ini diketahui bahwa tiga provinsi paling tinggi
yang telah melakukan kunjungan antenatal sesuai dengan rekomendasi
Kemenkes RI (1-1-2) di daerah rural Indonesia yaitu Provinsi DIY
(87,2%), Provinsi Bali (84%) dan Provinsi Jawa Tengah (82,6%).
Adapun tiga provinsi dengan jumlah kunjungan antenatal paling
rendah yaitu Provinsi Papua (31,7%), Provinsi Sulawesi Barat (33,8%)
dan Provinsi Gorontalo (43,4%). Angka cakupan tertinggi kunjungan
antenatal pada penelitian ini masih belum mencapai target rencana
strategis Kementerian Kesehatan RI yaitu sebesar 93% untuk target
kunjungan antenatal K4.
Pada penelitian ini, ibu yang tidak melakukan kunjungan
antenatal selama kehamilannya adalah sebesar 37,7%. Hasil uji
statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan antara kunjungan
antenatal dengan kematian neonatal. Hasil penelitian ini sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan Singh, dkk (2014) bahwa terdapat

137
hubungan antara kunjungan antenatal dengan kematian neonatal.
Penelitian lainnya menemukan bahwa ibu yang tidak melakukan
kunjungan antenatal memiliki risiko mengalami kematian neonatal
lebih tinggi dibandingkan ibu yang melakukan kunjungan antenatal
(Faisal, 2010; Yani & Duarsa, 2013). Namun, hasil ini tidak sesuai
dengan hasil pada penelitian-penelitian lainnya di Indonesia (Pertiwi,
2010; Nugraheni, 2013; Wijayanti, 2013).
Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa kematian
neonatal lebih tinggi pada kelompok ibu yang tidak melakukan
kunjungan antenatal dibandingkan ibu yang melakukan kunjungan
antenatal. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang menerima pemeriksaan
kesehatan selama kehamilan di daerah rural menunjukkan memiliki
peluang yang lebih tinggi untuk bertahan selama periode neonatal
(Mahmood, 2002).
Kondisi janin salah satunya dipengaruhi oleh adanya
komplikasi kehamilan, biasanya merupakan masalah yang sering
terjadi selama kehamilan. Komplikasi yang sering terjadi diantaranya
perdarahan, pre-eklampsia dan eklampsia. Eklampsia biasanya terjadi
didahului pre-eklampsia, sehingga pemeriksaan antenatal yang rutin
dan teliti merupakan salah satu upaya untuk mencegah eklampsia yang
bisa membahayakan kondisi ibu dan janin yang dikandungnya
(Wiknjosastro, dkk., 2002). Ibu yang melakukan kunjungan ke fasilitas

138
kesehatan selama kehamilannya akan menerima pemeriksaan dan
pengidentifikasian kondisi-kondisi yang berkaitan dengan komplikasi
serta edukasi mengenai tanda bahaya, potensi komplikasi dan tempat
untuk mencari pertolongan (Mahmood, 2002).
Penelitian lainnya oleh Hinderaker, dkk (2003) di wilayah rural
Tanzania menegaskan bahwa sekitar 62% kasus kematian neonatal
sebetulnya dapat dicegah melalui kegiatan layanan antenatal di
fasilitas layanan kesehatan. Penyedia layanan kesehatan
bertanggungjawab terhadap lebih dari setengah dari faktor-faktor
terhadap kematian neonatal yang dapat dicegah, baik dari faktor
kegagalan klinik antenatal untuk merujuk ke fasilitas layanan
kesehatan yang lebih tinggi maupun kelalaian yang terjadi di tingkat
rumah sakit itu sendiri. Hal ini mengindikasikan adanya potensi untuk
melakukan peningkatan layanan antenatal dan konsultasi rutin
termasuk layanan kehamilan di rumah sakit.
Pada penelitian Hinderaker, dkk (2003) juga ditemukan lebih
dari sepertiga kasus kematian neonatal tidak memiliki faktor risiko dan
kemungkinan tidak teridentifikasi pada layanan antenatal rutin. Hal ini
menjadi lebih membahayakan bagi ibu yang tidak menyadari adanya
faktor risiko pada dirinya. Sehingga ditegaskan bahwa setiap ibu hamil
merupakan kelompok yang berisiko. Pelayanan antenatal seharusnya
dapat berperan dalam melakukan skrining dan merujuk ibu hamil

139
dengan risiko atau komplikasi ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi.
Pelayanan antenatal harus fokus untuk mempersiapkan ibu untuk
persalinannya dan mengedukasi suaminya sehingga telah siap ketika
terjadi komplikasi yang tak terduga. Komunikasi yang baik antara
petugas kesehatan dan ibu hamil pada saat layanan antenatal perlu
ditekankan, harus dipastikan pesan yang disampaikan dimengerti oleh
ibu hamil maupun suaminya.
Kunjungan antenatal yang terlambat kemungkinan
menghambat ibu untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari strategi
pencegahan pada layanan antenatal misalnya suplementasi zat besi,
asam folat, pengobatan untuk infeksi cacing dan pengobatan untuk
pencegahan malaria pada kehamilan (Eijk, dkk., 2006). Adapun, hasil
pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 63,7% dari ibu yang
tidak melakukan kunjungan antenatal pada trimester pertama
melakukan kunjungan antenatal pada trimester ketiga. Sehingga,
kemungkinan hal ini menyebabkan ibu tidak menerima seluruh
manfaat layanan antenatal, dimana salah satunya dilakukan upaya
deteksi dini terhadap adanya komplikasi kehamilan maupun
persalinan.
Perilaku penggunaan layanan antenatal dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Hasil penelitian di daerah rural Kenya menunjukkan
bahwa ibu dengan status pernah mendapatkan pendidikan selama lebih

140
dari 8 tahun dan merupakan kelompok dengan tingkat sosial ekonomi
tinggi merupakan faktor paling berpengaruh terhadap kunjungan
antenatal. Walaupun terkadang persepsi mahalnya biaya yang
diperlukan untuk melakukan kunjungan antenatal dapat menghalangi
ibu untuk melakukan kunjungan. Biaya untuk transportasi, jarak ke
fasilitas layanan antenatal yang jauh bisa menjadi hambatan bagi ibu
untuk melakukan kunjungan antenatal begitu juga persepsi rendahnya
kualitas layanan antenatal menjadi salah satu hambatan ibu melakukan
kunjungan (Eijk, dkk. 2006).
Penelitian yang dilakukan Titaley, dkk (2010) di Indonesia
menemukan bahwa yang berhubugan sangat kuat dengan rendahnya
kunjungan antenatal yaitu bayi dari ibu yang tinggal di daerah rural,
memiliki tingkat indeks kekayaan rumah tangga rendah, berasal dari
ibu dengan berpendidikan rendah, jumlah kelahiran tinggi dan jarak
kelahiran kurang dari 2 tahun. Penelitian kualitatif yang dilakukan di
beberapa daerah rural Indonesia menemukan bahwa ibu hamil suku
Alifuru di Provinsi Maluku baru akan memeriksakan kehamilannya
saat terlihat perubahan yang nyata pada tubuh ibu (terlihat jelas ibu
hamil). Kunjungan saat terakhir menstruasi (K1) dan kunjungan pada
trimester kedua relatif kecil (Kemenkes RI, 2012).
Penelitian kualitatif lainnya menemukan bahwa alasan ibu
Etnik Dayak Siang Murung di Kalimantan Tengah tidak melakukan

141
pemeriksaan kehamilan yaitu karena Puskesmas Pembantu yang ada di
desa tidak menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap seperti obat-
obatan, wilayah puskesmas pembantu cukup sulit dijangkau oleh
masyarakat di RT lain dan tenaga kesehatan yang ditugaskan sering
tidak berada di tempat sehingga membuat masyarakat kesulitan saat
membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat
memilih langsung melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit yang ada
di Kabupaten. Rumah sakit berada sangat jauh dari desa dan harus
melewati jalan yang cukup sulit terutama apabila terjadi hujan
disamping memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga beberapa
ibu hamil lainnya memilih tidak memeriksakan kehamilannya dengan
alasan petugas kesehatan sering tidak ada di tempat (Kemenkes RI,
2012).
Penelitian lainnya pada ibu hamil Etnik Gorontalo Provinsi
Gorontalo menemukan bahwa sebagian ibu hamil yang melakukan
pemeriksaan kehamilan kepada bidan tidak memakan vitamin yang
diberikan dengan alasan tidak diberi penjelasan manfaat minum obat.
Ibu juga tidak meminum vitamin penambah darah dengan alasan
vitamin rasanya pahit (Kemenkes RI, 2012).
Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini bahwa ada hubungan
antara kunjungan antenatal dengan kematian neonatal di daerah rural
Indonesia, maka perlu memperhatikan aspek yang mempengaruhi

142
kunjungan antenatal tersebut. Seperti telah dijelaskan berbagai
penelitian, beberapa alasan ibu hamil tidak melakukan kunjungan
antenatal baik dari segi budaya, kurangnya ketersediaan fasilitas
kesehatan maupun kurangnya tenaga kesehatan. Pelayanan antenatal
perlu ditingkatkan dengan lebih mengutamakan kelengkapan fasilitas
kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan serta tetap menjamin kualitas
dari fasilitas dan tenaga kesehatan.
6.3.8 Komplikasi Kehamilan
Komplikasi kehamilan yaitu terdiri dari perdarahan, infeksi,
pre-eklampsia/eklampsia, persalinan lama/macet dan abortus
(McCarthy & Main, 1992). Komplikasi kehamilan merupakan masalah
kesehatan yang sering terjadi selama kehamilan dan persalinan.
Komplikasi kehamilan dapat berdampak pada kesehatan ibu, kesehatan
bayi ketika dilahirkan, atau pada keduanya (Wiknjosastro, dkk., 2002).
Pada penelitian ini, komplikasi kehamilan dikategorikan
menjadi komplikasi dan tidak komplikasi. Ibu masuk kedalam
kelompok komplikasi jika mengalami minimal satu bentuk komplikasi
(mulas sebelum 9 bulan, pendarahan, demam tinggi, kejang-kejang dan
pingsan). Sedangkan ibu masuk kedalam kelompok tidak komplikasi
jika ibu tidak mengalami satu pun bentuk komplikasi kehamilan.
Pengkategorian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya
(Nugraheni, 2013).

143
Pada penelitian ini diketahui ibu yang mengalami komplikasi
pada saat kehamilannya yaitu sebesar 6%. Hasil uji statistik
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara komplikasi kehamilan
dengan kematian neonatal. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil
penelitian yang dilakukan Nugraheni (2013) dan Wijayanti (2013)
bahwa ada hubungan antara komplikasi selama kehamilan dengan
kejadian kematian neonatal. Ibu yang mengalami komplikasi
kehamilan memiliki risiko lebih tinggi terhadap kematian neonatal
dibandingkan ibu yang tidak mengalami komplikasi kehamilan
(Rahmawati, 2007).
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kematian
neonatal lebih tinggi terjadi pada kelompok ibu dengan komplikasi
kehamilan. Bayi dari ibu yang mengalami komplikasi kehamilan
memiliki risiko 1,8 kali lebih tinggi terhadap kematian neonatal
dibandingkan bayi dari ibu yang tidak mengalami komplikasi selama
kehamilannya (Rahmawati, 2007). Penelitian lainnya yang dilakukan
di daerah rural Bangladesh juga menunjukkan bahwa ibu yang
mengalami pendarahan selama kehamilannya berhubungan kuat
dengan adanya peningkatan risiko terhadap kematian neonatal (Owais,
dkk., 2013).
Penelitian yang dilakukan pada ibu hamil Etnik Ngalum
Provinsi Papua menemukan bahwa ibu yang hamil tetap mengalami

144
komplikasi walaupun telah melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu
tersebut mengalami kehamilan pada usia lebih dari 45 tahun dan
memiliki anak rata-rata11-14 anak dengan jarak kelahiran yang
berdekatan. Tingkat anemia ibu hamil pada suku ini paling tinggi
dibandingkan suku lainnya. Kondisi seperti ini menyebabkan tingginya
kejadian retensio plasenta saat melahirkan. Padahal petugas kesehatan
telah memberikan tablet penambah darah yang seharusnya diberikan
tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali karena sangat tingginya
kasus anemia. Namun, petugas kesehatan tidak bisa memastikan
apakah obat yang diberikan rutin diminum oleh ibu hamil setiap hari
(Kemenkes RI, 2012).
Hasil penelitian pada ibu hamil Etnik Gorontalo Provinsi
Gorontalo juga menemukan bahwa sebagian ibu hamil yang
melakukan pemeriksaan kehamilan tidak meminum vitamin yang
diberikan dengan alasan tidak diberi penjelasan manfaat minum obat.
Ibu juga tidak meminum vitamin penambah darah dengan alasan
karena rasanya pahit (Kemenkes RI, 2012).
Anemia atau kadar Hb <11 g/dl yang salah satunya bisa
disebabkan karena defisiensi besi sehingga perlu diberi obat penambah
zat besi. Kondisi anemia pada ibu hamil sangat berbahaya bisa
menyebabkan terjadinya perdarahan pasca persalinan (WHO;
Kemenkes RI; POGI; IBI, 2013). Perdarahan merupakan penyebab

145
terbanyak kematian pada ibu (Zakariah, dkk., 2009). Berdasarkan hasil
review bahwa dampak anemia pada ibu hamil terhadap bayinya
bervariasi sesuai tingkat defisiensi Hb yang dialami oleh ibu.
Defisiensi Hb <11 gr/dl berhubungan dengan peningkatan kematian
pada perinatal. Peningkatan 2-3 kali kematian perinatal pada ibu
dengan Hb <8,0 gr/dl dan peningkatan 8-10 kali ketika kadar Hb <5,0
gr/dl. Selain itu, penurunan terhadap berat bayi lahir dan lambatnya
pertumbuhan janin terjadi ketika kadar Hb ibu <8,0 gr/dl (Kalaivani,
2009).
Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa terdapat
hubungan antara komplikasi kehamilan dengan kematian neonatal
maka perlu dilakukan peningkatan upaya deteksi dini di tingkat
layanan antenatal disertai pemantauan yang ketat terhadap kepatuhan
kelompok ibu yang dideteksi mengalami komplikasi kehamilan
(anemia, hipertensi, dan lain-lain) terhadap saran yang diberikan oleh
petugas kesehatan seperti dianjurkan mengonsumsi tablet penambah
darah.
6.3.9 Penolong Persalinan
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan
pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang kompeten (Depkes RI, 2009). Penanganan medis yang tepat dan
memadai saat ibu melahirkan dapat menurunkan risiko komplikasi

146
yang bisa menyebabkan kesakitan serius pada ibu dan bayinya (BPS,
BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013).
Pada penelitian ini, penolong persalinan dikategorikan menjadi
tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan. Penolong persalinan
dikategorikan sebagai tenaga kesehatan jika merupakan dokter, dokter
kandungan, perawat, bidan, atau bidan desa. Sedangkan penolong
persalinan dikategorikan sebagai non tenaga kesehatan jika penolong
persalinan adalah dukun, tetangga atau tanpa penolong persalinan.
Pengkategorian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang
dilakukan Titaley, dkk (2008) di Indonesia.
Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa 83% persalinan pada
kurun waktu 2008-2012 ditolong oleh tenaga kesehatan profesional
(62% perawat/bidan/bidan desa, 20% dokter kandungan dan 1%
dokter). Proporsi ini mengalami peningkatan dari hasil SDKI 2007
sebesar 73% persalinan yang ditolong tenaga kesehatan profesional
(BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International, 2013). Pada
penelitian ini diketahui ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan
profesional pada persalinannya di daerah rural Indonesia yaitu sebesar
73,2% (30,7% bidan, 24,1% bidan desa, 5,5% dokter kandungan, 1,3%
perawat, 0,4% dokter dan 11,2% lebih dari satu penolong tenaga
kesehatan). Angka ini masih cukup jauh dari target MDGs 5 tahun

147
2015, peningkatan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan
profesional menjadi 90% (Kemenkes RI, 2014).
Persalinan yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan pada
penelitian ini yaitu sebesar 26,8%. Hasil uji statistik menunjukkan
bahwa tidak terdapat hubungan antara penolong persalinan dengan
kematian neonatal. Artinya, tidak ada perbedaan antara penolong
persalinan oleh tenaga kesehatan maupun oleh non tenaga kesehatan.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Singh, dkk
(2014), Pertiwi, (2010) dan Wijayanti, (2013) yang menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara penolong persalinan dengan kematian
neonatal. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian
yang dilakukan Sugiharto (2011), Dewi (2010) dan Nugraheni (2013)
yang menunjukkan tidak terdapat hubungan antara penolong
persalinan dengan kematian neonatal.
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu
ditolong oleh tenaga kesehatan pada persalinannya, namun proporsi
kematian neonatal pada kedua kelompok tidak menunjukkan
perbedaan proporsi yang cukup jauh sehingga analisis statistik
menunjukkan tidak ada hubungan. Bahkan pada penelitian Titaley,
dkk (2011) yang dilakukan di Indonesia ditemukan kematian neonatal
dini justru lebih tinggi pada ibu yang bersalin di rumah yang ditolong
oleh tenaga yang terlatih. Penelitian lainnya menemukan bahwa

148
kematian neonatal lebih tinggi pada ibu tanpa penolong persalinan
(Neupane & Doku, 2014). Namun, pada penelitian ini hanya 0,4% ibu
yang melakukan persalinan tanpa adanya penolong persalinan.
Kemungkinan penyebab masih tingginya angka kematian
neonatal pada kelompok ibu dengan penolong persalinan tenaga
kesehatan adalah masih rendahnya kualitas penolong persalinan
tersebut. Seperti diketahui pada penelitian Yego, dkk (2013) bahwa
akses terhadap penolong persalinan terampil termasuk dokter maupun
bidan penting untuk mencegah kematian maternal dan neonatal.
Penolong persalinan yang sebagian besar dilakukan oleh penolong
persalinan dengan keterampilan yang rendah dapat berkontribusi
terhadap kejadian kematian neonatal dan kematian maternal (Yego,
dkk., 2013). Pada penelitian lainnya juga menemukan bahwa perlunya
pelatihan bagi penolong persalinan agar penolong persalinan mampu
menangani kasus infeksi yang diketahui merupakan penyebab
terbanyak kasus kematian neonatal (Turnbull, dkk., 2011).
Pada penelitian yang dilakukan Kusiako, dkk (2000)
menunjukkan bahwa komplikasi pada saat melahirkan merupakan
penyebab sepertiga kematian pada perinatal. Padahal peningkatan
layanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terkualifikasi dan
layanan neonatus yang lebih baik seharusnya dapat menurunkan
kematian pada perinatal. Pada penelitian ini, kemungkinan penyebab

149
lain masih tingginya kematian neonatal pada kelompok ibu dengan
persalinan oleh tenaga kesehatan adalah ibu memilih bersalin oleh
tenaga kesehatan ketika terjadi masalah serius pada persalinannya.
Seperti ditemukan pada penelitian yang dilakukan di Jawa Barat
bahwa ibu yang mengakses penolong persalinan terlatih atau
melakukan persalinan di fasilitas layanan kesehatan sebagian besar
dilakukan ketika ibu mengalami komplikasi kehamilan (Titaley, dkk.,
2010).
Review yang dilakukan Upadhyay, dkk (2012) juga
menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya yang terampil
merupakan salah satu penyebab kematian neonatal yang terjadi di
daerah rural India. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil
berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh
neonatus. Sehingga penyediaan tenaga kesehatan yang terkualifikasi
ke daerah rural merupakan tantangan yang harus dilakukan untuk
menghindari kematian pada neonatal.
Pada penelitian Zimba, dkk (2012) menemukan bahwa
walaupun Malawi mengalami peningkatan jumlah penolong persalinan
terampil, tetapi sebagian besar ibu dan bayi baru lahir yang mengalami
komplikasi masih belum mendapatkan penanganan kesehatan yang
diperlukan. Pada penelitian lainnya diketahui bahwa peralatan dan
kualitas layanan yang tidak memadai juga merupakan tantangan di

150
wilayah Afrika dan Asia (Harvey, dkk., 2007). Menurut Singh, dkk
(2014) definisi tenaga penolong persalinan yang ada saat ini, tidak
mencakup unsur layanan yang memadai. Walaupun sebagian besar
negara di Afrika dan Asia mengalami peningkatan jumlah tenaga
penolong persalinan terampil, sebagian besar setiap individu yang
disebut sebagai tenaga kesehatan terampil tidak memiliki kompetensi
yang diperlukan atau peralatan yang dibutuhkan untuk mengatasi
komplikasi pada ibu dan bayi baru lahir.
Adapun penyebab masih tingginya kematian neonatal pada
penolong pesalinan non tenaga kesehatan di daerah rural Indonesia
kemungkinan terjadi karena masih rendahnya akses ibu hamil terhadap
tenaga keseahatan.menurut. Hasil penelitian Titaley, dkk (2010) di
beberapa daerah terpencil di Indonesia menunjukkan bahwa bidan
desa yang pada beberapa wilayah merupakan satu-satunya tenaga
kesehatan penolong persalinan yang tersedia, terkadang pergi keluar
desa (Titaley, dkk., 2010). Hal ini semakin mempersulit akses ibu
terhadap tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan.
Masih tingginya kematian pada penolong persalinan non
tenaga kesehatan kemungkinan besar juga karena pengetahuan dan
keterampilan penolong persalinan bukan tenaga kesehatan yang sangat
kurang tentang penanganan persalinan pada ibu bersalin, maupun
tentang penanganan bayi baru lahir. Apalagi penanganan ibu dengan

151
gejala eklamsia, akan sangat sulit bagi penolong bukan tenaga
kesehatan untuk dapat melakukan tindakan yang tepat. Pengetahuan
penolong yang kurang tentang bagaimana melakukan upaya
pencegahan terhadap kemungkinan bayi aman dari risiko terjadinya
gangguan thermoregulasi, gangguan respirasi, dan risiko lainnya yang
biasa melekat pada bayi baru lahir, sangat berpengaruh besar terhadap
status kesehatan neonatus. Jika penanganannya kurang tepat maka
kecenderungan terjadinya risiko kematian akan semakin besar (Astuti,
dkk., 2010).
Hasil penelitian kualitatif pada masyarakat Suku Nias
menemukan bahwa terkadang keluarga alot dalam memutuskan
merujuk ke rumah sakit atau puskesmas. Hal tersebut menyebabkan
ibu terlambat mendapatkan pertolongan dari petugas kesehatan. Ibu
yang melakukan persalinan di rumah sakit biasanya ibu yang sudah
mengalami masalah pada persalinannya (Kemenkes RI, 2012).
Berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan upaya untuk
meningkatkan keterampilan penolong persalinan baik bagi tenaga
penolong persalinan. Peningkatan kualitas tenaga penolong persalinan
dilakukan dari mulai calon tenaga penolong persalinan di tingkat
akademik/universitas maupun bagi mereka yang telah berprofesi
sebagai tenaga penolong persalinan. Peningkatan kualitas tenaga

152
penolong persalinan ini terutama pada masalah penanganan
komplikasi pada ibu dan bayi baru lahir.
6.3.10 Persalinan Caesar
Persalinan caesar merupakan tindakan untuk melahirkan bayi
melalui sayatan pada dinding uterus yang masih utuh (Saifuddin, dkk.,
2009). Persalinan caesar merupakan operasi besar yang dilakukan
pada saat terdapat indikasi kesehatan tertentu (Whalley, dkk., 2008).
Pada penelitian ini, cara persalinan dibedakan menjadi persalinan
caesar dan bukan persalinan caesar. Ibu dikategorikan melakukan
persalinan caesar apabila ibu melakukan persalinan dengan cara perut
dibedah untuk mengeluarkan bayi. Sedangkan ibu dikategorikan tidak
melakukan persalinan caesar apabila ibu melakukan persalinan dengan
cara per vaginam/normal. Pengkategorian ini didasarkan pada
penelitian sebelumnya yang dilakukan Bashir, dkk (2013).
Pada penelitian ini diketahui ibu yang melakukan persalinan
caesar pada persalinannya yaitu sebesar 8%. Hasil uji statistik
menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara persalinan caesar
dengan kematian neonatal. Hasil pada penelitian ini tidak sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan Bashir, dkk (2013) yang
menunjukkan bahwa persalinan dengan cara bedah caesar memiliki
hubungan dengan kematian neonatal. Ibu dengan persalinan caesar
memiliki kemungkinan 1,6 kali lebih besar terhadap kematian neonatal

153
dibandingkan ibu yang melahirkan per vaginam. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugraheni (2013) dan
Wijayanti (2013) bahwa tidak ada hubungan antara persalinan caesar
dengan kematian neonatal. Namun, penelitian Owais, dkk (2013) di
daerah rural Bangladesh justru menemukan bahwa persalinan dengan
cara caesar menjadi faktor protektif terhadap kematian neonatal.
Walaupun uji statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan
antara persalinan caesar dengan kematian neonatal, pada penelitian ini
menunjukkan bahwa proporsi kematian neonatal lebih tinggi pada
kelompok ibu dengan persalinan caesar. Kemungkinan hal ini terjadi
karena persalinan caesar sebagian besar dilakukan karena ditemukan
adanya indikasi kesehatan tertentu pada ibu seperti ditunjukkan pada
hasil penelitian (Shah, dkk., 2009). Penelitian yang dilakukan di
daerah urban Ibadan Nigeria menunjukkan bahwa dari 21% ibu yang
melakukan persalinan caesar sebanyak 89% merupakan kasus
kegawatdaruratan (Adetola, dkk., 2011). Namun, pada penelitian
lainnya yang dilakukan di daerah Iran menemukan bahwa sebagian
besar persalinan caesar dilakukan bukan karena adanya indikasi
kesehatan (Bahadori, dkk., 2013).
Bayi dari ibu yang kembali melakukan persalinan dengan cara
caesar memiliki angka kesakitan (penyakit pernapasan) lebih tinggi
dan tinggal di rumah sakit lebih lama dibandingkan ibu yang

154
melakukan persalinan per vaginam yang sebelumnya melakukan
persalinan caesar (Kamath, dkk., 2009). Kematian neonatal meningkat
sejalan dengan tingginya persalinan caesar yang dilakukan pada
kondisi kegawatdaruratan. Selain itu secara keseluruhan, persalinan
caesar (kondisi kegawatdaruratan maupun non kegawatdaruratan)
berhubungan dengan meningkatnya kesakitan pada neonatal (Shah,
dkk., 2009).
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 571 persalinan
yang dilakukan secara caesar, 90,2% tidak mengalami komplikasi
selama kehamilannya. Sehingga, kemungkinan sebagian besar
persalinan caesar pada penelitian ini dilakukan bukan karena adanya
indikasi kesehatan. Hasil review literatur menyebutkan bahwa
persalinan caesar tanpa adanya alasan kesehatan (kegawatdaruratan)
juga bisa membahayakan kondisi ibu dan janinnya baik dari segi
pendek maupun lamanya waktu yang diperlukan prosedur persalinan
caesar dibandingkan persalinan normal (Wiklund, dkk., 2012).
6.3.11 Tempat Persalinan
Upaya untuk mengurangi risiko kematian ibu dan anak sangat
penting dengan cara meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang profesional yang dilakukan di fasilitas kesehatan (BPS, BKKBN,
Kemenkes & ICF International, 2013). Pada penelitian ini, tempat
persalinan dikategorikan menjadi non fasilitas layanan kesehatan dan

155
fasilitas layanan kesehatan. Ibu melakukan persalinan di fasilitas
layanan kesehatan jika persalinan dilakukan di rumah sakit, klinik,
dokter/perawat/bidan praktek, dan bidan desa. Sedangkan ibu
dikategorikan melakukan persalinan di non fasilitas layanan kesehatan
apabila ibu melakukan persalinan di rumahnya sendiri maupun rumah
dukun/tetangga. Pengkategorian ini didasarkan pada penelitian
sebelumnya yang dilakukan Titaley, dkk (2008).
Pada penelitian ini diketahui bahwa ibu yang melakukan
persalinan di non fasilitas pelayanan kesehatan yaitu sebesar 59,9%.
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara
tempat persalinan dengan kematian neonatal. Hasil ini berbeda dengan
hasil penelitian yang dilakukan Faisal (2010) menunjukkan bahwa ibu
yang melahirkan di fasilitas non kesehatan mempunyai kecenderungan
untuk mengalami kejadian kematian bayi lebih besar dibandingkan ibu
yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Namun, hasil penelitian ini
sama dengan penelitian yang dilakukan Sugiharto (2011), Pertiwi
(2010), Nugraheni (2013) dan Wijayanti (2013) bahwa tidak terdapat
hubungan antara tempat persalinan dengan kematian neonatal.
Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kematian
neonatal lebih tinggi terjadi di non fasilitas layanan kesehatan. Ibu
yang melakukan persalinan diluar fasilitas pelayanan kesehatan
memiliki risiko 1,85 kali lebih tinggi untuk mengalami kematian
neonatal dibandingkan ibu yang melahirkan di fasilitas layanan

156
kesehatan. Melahirkan diluar fasilitas layanan kesehatan lebih
memungkinkan untuk mengalami kematian neonatal dibandingkan
melahirkan dilakukan di fasilitas layanan kesehatan (Ajaari, dkk.,
2012).
Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah ibu yang
melahirkan di non fasilitas pelayanan kesehatan lebih tinggi
dibandingkan di fasilitas pelayanan kesehatan konsisten dengan hasil
penelitian Owais, dkk (2013). Namun, diketahui kematian neonatal
justru ditemukan lebih tinggi terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan.
Artinya, kasus kematian neonatal lebih tinggi terjadi di fasilitas
pelayanan kesehatan padahal penolong persalinan di fasilitas
pelayanan merupakan tenaga kesehatan. Hasil ini sesuai dengan hasil
penelitian Titaley (2011) bahwa terjadinya peningkatan risiko
kematian neonatal dini yang signifikan berhubungan dengan
persalinan yang dilakukan di rumah sakit di daerah rural Indonesia.
Hasil ini juga konsisten dengan penelitian lainnya yang
dilakukan di daerah rural Burkina Faso bahwa kematian bayi lebih
tinggi terjadi di fasilitas layanan kesehatan. Adanya fasilitas pelayanan
kesehatan tidak akan memberikan perbedaan yang berarti jika fasilitas
tersebut tidak memiliki kelengkapan alat atau tenaga kesehatan yang
cukup terlatih (Diallo, dkk., 2012). Hasil ini juga sejalan dengan hasil
penelitian Singh, dkk (2012) bahwa setelah adanya peningkatan
penggunaan rumah sakit bersalin di India terjadi penurunan kematian

157
neonatal sebesar 2,5% namun penurunan kematian neonatal ini tidak
signifikan dimungkinkan terjadi karena masih rendahnya kualitas
layanan kesehatan. Seperti ditemukan juga pada penelitian lainnya
bahwa persalinan yang dilakukan di rumah di daerah rural sebagian
besar ditolong oleh dokter atau bidan desa dengan tingkat pengetahuan
dan keterampilan masih tergolong cukup rendah (Yanping, dkk.,
2010).
Kemungkinan alasan lainnya yaitu sebagian besar persalinan
yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan persalinan
dengan komplikasi yang bisa berakibat pada kematian neonatal. Hal
ini terjadi karena perilaku mencari pelayanan kesehatan dilakukan
setelah awalnya persalinan akan dilakukan di rumah. Penolong
persalinan di rumah tidak akan merujuk ibu ke fasilitas layanan
kesehatan kecuali ibu telah mengalami komplikasi. Sehingga
lemahnya sistem layanan kesehatan juga akan berkontribusi terhadap
tingginya angka kematian neonatal di fasilitas layanan kesehatan
(Ajaari, dkk., 2012).
Pada penelitian ini didapatkan, hasil analisis antara komplikasi
kehamilan dengan tempat persalinan menunjukkan adanya hubungan.
Sebesar 49,2% persalinan yang dilakukan di fasilitas layanan
kesehatan merupakan kasus komplikasi kehamilan. Penelitian
kualitatif yang dilakukan pada masyarakat suku Mamasa Sulawesi
Barat juga menunjukkan bahwa beberapa kejadian kematian ibu dan

158
bayi saat bersalin di rumah sakit rujukan. Ibu hamil datang ke rumah
sakit tersebut dengan keadaan sangat parah (sakit berat) atau umur
kehamilan sudah terlalu tua (Kemenkes RI, 2012).
Penggunaan layanan kesehatan kemungkinan juga dipengaruhi
oleh jarak terhadap layanan kesehatan tersebut. Hasil penelitian di
daerah rural Etiophia ditemukan bahwa sekitar 90% anak tinggal di
wilayah dengan waktu tempuh lebih dari 1,5 jam ke fasilitas
kesehatan. Anak tersebut memiliki risiko 2 kali lebih besar terhadap
kematian dibandingkan anak yang tinggal dengan waktu tempuh 1,5
jam ke fasilitas kesehatan (Okwaraj, dkk., 2012). Penelitian lain di
daerah rural Burkina Faso menemukan bahwa terjadi 33% peningkatan
kematian bayi yang signifikan jika ibu tinggal dengan lokasi pusat
layanan kesehatan yang terdekat lebih dari 10 km (Becher, dkk.,
2004). Penelitian yang dilakukan di Jawa Barat menemukan bahwa
jarak dan keterbatasan biaya merupakan dua penyebab utama ibu tidak
mengakses penolong persalinan terlatih dan fasilitas layanan kesehatan
pada saat persalinannya (Titaley, dkk., 2010).
Walaupun 90% ibu telah melakukan kunjungan antenatal
namun hanya 2 dari 10 ibu yang melakukan persalinan di fasilitas
layanan antenatal. Hasil pengamatan diketahui bahwa persalinan
dilakukan di rumah berkaitan dengan adanya perkembangan persalinan
yang cepat, jarak, kesulitan transportasi pada malam hari dan biaya.
Jarak merupakan hambatan terhadap persalinan di fasilitas layanan

159
kesehatan bukan terhadap kunjungan antenatal. Hal ini dikarenakan
tidak semua fasilitas yang menyediakan layanan antenatal memiliki
layanan persalinan 24 jam. Sehingga jarak untuk mendapatkan fasilitas
kesehatan dengan layanan persalinan lebih sulit didapatkan
dibandingkan dengan layanan antenatal. Persalinan alami pada kondisi
gawat mungkin menjadi lebih baik untuk menyelesaikan masalah jarak
ke fasilitas layanan persalinan. Selain itu, ibu memilih tenaga
penolong persalinan tradisional karena lebih fleksibel dalam masalah
biaya. Bahkan masih ditemukan ibu tanpa tenaga penolong persalinan,
padahal ibu tanpa penolong persalinan akan kesulitan mendapatkan
penolong ketika terjadi komplikasi pada persalinannya (Eijk, dkk.,
2006).
Penelitian kualitatif pada Suku Mamasa, Sulawesi Barat
menemukan bahwa walaupun telah terdapat program Jampersal
(Jaminan Persalinan) namun belum diketahui oleh ibu-ibu di wilayah
tersebut. Selain itu, mereka belum mempercayai sepenuhnya bahwa
bersalin di fasilitas kesehatan tidak dikenakan biaya/gratis. Apalagi
jika mereka harus di rujuk ke Rumah Sakit, akan membutuhkan biaya
yang lebih besar. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada tenaga
kesehatan dimana belum keluarnya pembayaran (klaim) terhitung
sejak 2011-2012. Padahal semua catatan dan bukti telah terkumpul
dengan rapi. Kejadian tersebut terjadi pada semua bidan di desa dan
kecamatan di Kabupaten Mamasa. Meskipun demikian, bidan desa

160
tetap melayani dan menggratiskan persalinan yang ditolong di fasilitas
persalinan (Kemenkes RI, 2012).
Penelitian lainnya pada suku Toraja Sa’dan menunjukkan
bahwa terdapat pertimbangan lain, pertimbangan ekonomi untuk
memenuhi biaya-biaya di luar cakupan Jampersal, seperti transportasi,
uang makan keluarga yang menungguinya di sarana kesehatan, anak-
anak kecil yang ditinggalkan, hewan-hewan ternak (pemeliharaan
babi) yang menjadi tanggung jawab ibu. Pendapatan sehari-hari
menjadi pertimbangan lain mengapa ibu memutuskan untuk
melahirkan sendiri di rumahnya. Selain itu, beberapa wilayah Toraja
Sa’dan memang berada jauh dari sarana pelayanan kesehatan. Selain
jarak yang jauh, akses warga terhadap pelayanan kesehatan dipersulit
dengan kondisi jalan yang rusak. Sarana transportasi menjadi sulit dan
mahal karena kondisi jalan yang rusak parah (Kemenkes RI, 2012).
Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka perlu dilakukan
upaya peningkatan kualitas fasilitas layanan kesehatan baik dari segi
akses maupun kelengkapan alat dan ketersediaan tenaga kesehatan
profesional. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan peningkatan
perbaikan infrastruktur di wilayahnya agar akses terhadap fasilitas
kesehatan semakin meningkat.

161
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:
1) Sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan rendah (55,1%), berstatus
kerja (53,1%), memiliki indeks kekayaan rumah tangga rendah (47,7%),
tinggal diwilayah perdesaan (53,1%), memiliki umur antara 20-35 tahun
(74,3%), berjenis kelamin laki-laki (51,6%), memiliki paritas 1-3 (83,6%),
melakukan kunjungan antenatal (68,8%), mengalami komplikasi kehamilan
(93,5%), melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan (82,5%), melakukan
persalinan bukan caesar (87,3%) dan melakukan persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (57,9%).
2) Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
3) Terdapat hubungan antara status pekerjaan ibu dengan kematian neonatal
di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
4) Tidak terdapat hubungan antara indeks kekayaan rumah tangga dengan
kematian neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
5) Terdapat hubungan antara umur ibu dengan kematian neonatal di daerah
rural Indonesia tahun 2008-2012.

162
6) Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin bayi dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
7) Terdapat hubungan antara paritas dengan kematian neonatal di daerah rural
Indonesia tahun 2008-2012.
8) Terdapat hubungan antara kunjungan antenatal dengan kematian neonatal
di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
9) Terdapat hubungan antara komplikasi kehamilan dengan kematian neonatal
di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
10) Tidak terdapat hubungan antara penolong persalinan dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
11) Tidak terdapat hubungan antara persalinan caesar dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
12) Tidak terdapat hubungan antara tempat persalinan dengan kematian
neonatal di daerah rural Indonesia tahun 2008-2012.
7.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran
sebagai berikut:
7.2.1 Bagi Kementerian Kesehatan RI
1) Strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait
peningkatan pengetahuan ibu mengenai kesehatan ibu dan anak
perlu difokuskan pada kelompok ibu umur kurang dari 20 tahun

163
dan lebih dari 35 tahun dan kelompok ibu yang bekerja untuk
daerah rural Indonesia.
2) Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penggunaan metode
keluarga berencana yang didukung oleh ketersediaan dan
kelengkapan fasilitas dan tenaga yang perlukan serta
memperhatikan aspek budaya/adat masyarakat setempat.
3) Pelayanan antenatal perlu ditingkatkan dengan fokus pada
terjaminnya ketersediaan, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas
serta tenaga kesehatan di daerah rural Indonesia.
4) Upaya deteksi dini terhadap komplikasi pada kehamilan di daerah
rural Indonesia perlu diikuti dengan pemantauan yang
berkelanjutan pada kepatuhan ibu terhadap anjuran dari petugas
kesehatan.
5) Penyediaan tenaga penolong persalinan perlu difokuskan pada
peningkatan kualitas tenaga penolong persalinan terutama terkait
penanganan komplikasi pada ibu dan bayi baru lahir.
7.2.2 Bagi Pemerintah Daerah
Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki daerah dengan
karakteristik rural/perdesaan disarankan untuk melakukan peningkatan
ketersediaan, akses, kapasitas dan kualitas tenaga penolong persalinan
dan fasilitas persalinan di wilayahnya.

164
DAFTAR PUSTAKA
Adetola, A. O., Tongo, O. O., Orimadegun, A. E., & Osinusi, K. (2011). Neonatal Mortality in an Urban Population in Ibadan, Nigeria. Pediatrics and Neonatology , 244.
Ajaari, J., Masanja, H., Weiner, R., Abokyi, S. A., & Owusu-Agyei, S. (2012). Impact of Place of Delivery on Neonatal Mortality in Rural Tanzania. International Journal of MCH and AIDS , 52,.
Andargie, G., Berhane, Y., Worku, A., & Kebede, Y. (2013). Predictors of Perinatal Mortality in Rural Population of Northwest Ethiopia: A Prospective Longitudinal Study. BMC Public Health , 4.
Andrews, G. (2009). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Wanita Terjemahan Sari Kurnianingsih. Jakarta: EGC.
Astuti, W. D., Sholikhah, H. H., & Angkasawati, T. J. (2010). Estimasi Risiko Penyebab Kematian Neonatal di Indonesia Tahun 2007. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 306.
August, E., Salihu, H., Weldeselasse, H., Biroscak, B., Mbah, A., & Alio, A. (2011). Infant Mortality and Subsequent Risk of Stillbirth: a Retrospective Cohort Study. BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology , 1636-1645.
Bahadori, F., Hakimi, S., & Heidarzade, M. (2013). The Trend of Caesarean Delivery in The Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal , S69.
Baqui, A. H., Ahmed, S., Arifeen, S. E., Darmstadt, G. L., Rosecrans, A. M., Mannan, I., et al. (2009). Effect of Timing of First Postnatal Care Home Visit on Neonatal Mortality in Bangladesh: A Prospective Cohort Study. BMJ , 445-448.
Baqui, A., Darmstadt, G., Williams, E., Kumar, V., Kiran, T., Panwar, D., et al. (2006). Rates, Timing and Cause of Neontal Deaths in Rural India: Implication for Neonatal Health Programmes. Bulletin of The World Health Organization , 706-711.

165
Bashir, A. O., Ibrahim, G. H., Bashier, I. A., & Adam, I. (2013). Neonatal Mortality in Sudan: Analysis of the Sudan Household Survey, 2010. BMC Public Health , 1-9.
Becher, H., Muller, O., Jahn, A., Gbango, A., Kynast-Wolf, G., & Kouyate, B. (2004). Risk Factors of Infant and Child Mortality in Rural Burkina Faso. Bulletin of The World Health Organization , 270.
BPS & Macro International. (2008). Indonesia Demograhic and Health Survey 2007. Jakarta: BPS & Macro International.
BPS & ORC Macro. (2003). Indonesia Demographic and Health Survey. Jakarta: BPS & ORC Macro.
BPS. (2010). Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Jakarta: BPS.
BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International. (2013). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Jakarta: BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF International.
Carlsen, F., Grytten, J., & Eskild, A. (2013). Changes in Fetal and Neonatal Mortality during 40 Years by Offspring Sex: A National Registry-Based Study in Norway. BMC Pregnancy and Childbirth , 1-7.
Chaman, R., Naieni, K. H., Golestan, B., Nabavizadeh, H., & Yunesian, M. (2009). Neonatal Mortality Risk Factors in a Rural Part of Iran: A Nested Case-Control Study. Iranian Journal of Public Health , 48-52.
Chen, X.-K., Wen, S. W., Fleming, N., Demissie, K., Rhoads, G. G., & Walker, M. (2007). Teenage Pregnancy and Adverse Birth Outcomes: A Large Population Based Retrospective Cohort Study. International Journal of Epidemiology , 371.
Chowdhury, A. H., Islam, S. S., & Karim, A. (2013). Covariates of Neonatal and Post-Neonatal Mortality in Bangladesh. Global Journal of Human Social Science .
Chowdhury, H. R., Thompson, S., Ali, M., Alam, N., Yunus, M., & Streatfield, P. K. (2010). Causes of Neonatal Deaths in a Rural Subdistrict of Bangladesh Implications for Intervention. J. HEALTH POPUL NUTR , 375.

166
Dahlan, S. (2010). Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan. Jakarta: Salemba Medika.
Debes, A. K., Kohli, A., Walker, N., Edmond, K., & Mullany, L. C. (2013). Time to Initiation of Breastfeeding and Neonatal Mortality and Morbidity A Systematic Review. BMC Public Health , 1-14.
Depkes RI. (2009). Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA). Jakarta: Depkes RI.
Dewi, R. (2010). Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kematian Neonatal di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
Diallo, A. H., Meda, N., Sommerfelt, H., Traore, G. S., Cousens, S., & Tylleskar, T. (2012). The High Burden of Infant Deaths in Rural Burkina Faso A Prospective Community-Based Cohort Study. BMC Public Health , 12.
Djaja, S., Kosen, S., Fel, l. P., & Ariawan, I. (2005). Survei Kematian Neonatal (Studi Autopsi Verbal) di Kabupaten Cirebon, 2004. Buletin Penelitian Kesehatan , 41-52.
Efriza. (2007). Determinan Kematian Neonatal Dini Di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional , 104.
Eijk, A. M., Bles, H. M., Odhiambo, F., Ayisi, J. G., Blokland, I. E., Rosen, D. H., et al. (2006). Use of Antenatal Services and Delivery Care Among Women in Rural Western Kenya A Community Based Survey. Reproductive Health , 6.
Fachlaeli, E. (2000). Hubungan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dengan Kematian Neonatal Di Kabupaten DT II Majalengka Jawa Barat Tahun 1998. Universitas Indonesia .
Faisal, A. (2010). Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kematian Bayi di Indonesia Tahun 2003-2007 (Analisis Data SDKI 2007). Depok: Universitas Indonesia.
Gerstman, B. B. (2003). Epidemiology Kept Simple. New Jersey: Canada.
Gizaw, M., Molla, M., & Mekonnen, W. (2014). Trends and Risk Factors for Neonatal Mortality in Butajira District, South Central Ethiopia, (1987-2008): A Prospective Cohort Study. BMC Pregnancy and Childbirth , 1-6.
Gordis, L. (2004). Epidemiology Third Edition. Philadelphia: Elsevier Saunders.

167
Harvey, S. A., Blandón, Y. C., McCaw-Binns, A., Sandino, I., Urbina, L., Rodríguez, C., et al. (2007). Are skilled Birth Attendants Really Skilled? A Measurement Method, Some Disturbing Results and A Potential Way Forward. Bulletin of the World Health Organization .
Hastono, S. P., & Sabri, L. (2010). Statistik Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers.
Hinderaker, S. G., Olsen, B. E., Bergsjø, P. B., Gasheka, P., Lie, R. T., Havnen, J., et al. (2003). Avoidable Stillbirths and Neonatal Deaths in Rural Tanzania. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology , 616.
ICF International. (n.d.). DHS Overview. Retrieved Juny 27, 2014, from The DHS Program (Demographic and Health Surveys): http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm
Kalaivani, K. (2009). Prevalence & Consequences of Anaemia in Pregnancy. Indian J Med Res , 630.
Kamath, B. D., Todd, J. K., Glazner, J. E., Lezotte, D., & Lynch, A. M. (2009). Neonatal Outcomes After Elective Cesarean Delivery. The American College of Obstetricians and Gynecologists , 1231.
Karlsen, S., Say, L., Souza, J.-P., Hogue, C. J., Calles, D. L., Gülmezoglu, A. M., et al. (2011). The Relationship Between Maternal Education and Mortality Among Women Giving Birth in Health Care Institutions: Analysis of the Cross Sectional WHO Global Survey on Maternal and Perinatal Health. BMC Public Health , 1.
Kayode, G. A., Ansah, E., Agyepong, I. A., Amoakoh-Coleman, M., Grobbee, D. E., & Klipstein-Grobusch, K. (2014). Individual and Community Determinants of Neonatal Mortality in Ghana: A Multilevel Analysis. BMC Pregnancy and Childbirth , 1-12.
Kemenkes RI. (2011). Buku Pedoman Pengenalan Tanda Bahaya pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas Bagi Kader. Jakarta: Kemenkes RI.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012: Etnik Alifuru Seram Desa Waru Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Kemenkes RI , 59.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012: Etnik Dayak Siang Murung Desa Dirung Bakung Kecamatan Tanah Siang

168
Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kemenkes RI , 79-80.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012: Etnik Gorontalo Desa Imbodu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwoto Provinsi Gorontalo. Kemenkes RI , 88.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012: Etnik Madura Desa Jrangoan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Kemenkes RI , 14.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012: Etnik Mamasa Desa Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat . Kemenkes RI , 45.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012: Etnik Ngalum Distrik Oksibil Kabupaten Penggunungan Bintang Provinsi Papua . Kemenkes RI , 77-78.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012: Etnik Nias Desa Hilifadölö Kecamatan Lölöwa'u Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara . Kemenkes RI , 20.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012: Etnik Toraja Sa'dan Desa Sa'dan Malimbong Kecamatan Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemenkes RI , 2.
Kemenkes RI. (2012). Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak: Etnik Manggarai Desa Waicodi Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemenkes RI , 64.
Kemenkes RI. (2014). Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Kesehatan Ibu Tahun Anggaran 2013. Jakarta: Kemenkes RI.
Kemenkes RI. (2012). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Edisi Kedua. Jakarta: Kemenkes RI.
Khan, A. A., Zahidie, A., & Rabbani, F. (2013). Interventions to Reduce Neonatal Mortality from Neonatal Tetanus in Low and Middle Income Countries - A Systematic Review. BMC Public Health , 1-7.

169
Kliegman, R. M., Stanton, B. F., Schor, N. F., II, J. W., & Behrman, R. E. (2011). Nelson Text Book of Pediatrics 19th Edition International Edition. Philadelphia: Elsevier.
Kozuki, N., Lee, A. C., Silveira, M. F., Sania, A., Vogel, J. P., Adair, L., et al. (2013). The Associations of Parity and Maternal Age With Small-For-Gestational-Age, Preterm, and Neonatal and Infant Mortality A Meta-Analysis. BMC Public Health , 5.
Kusiako, T., Ronsman, C., & Paal, L. V. (2000). Perinatal Mortality Atributable to Complications of Childbirth in Matlab, Bangladesh. Bulletin of The World Health Organization , 623.
Ladewig, P. W., London, M. L., & Olds, S. B. (2006). Buku Saku Asuhan Ibu dan Bayi baru Lahir Terjemahan Salmiyatun. Jakarta: EGC.
Lawn, J., Kerber, K., Enweronu-Laryea, C., & Bateman, O. M. (2009). Newborn Survival in Low Resource Settings are We Delivering. BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology , 50.
Lisonkova, S., Sabr, Y., Butler, B., & Joseph, K. (2012). International Comparisons of Preterm Birth Higher Rates of Late Preterm Birth are Associated with Lower Rates of Stillbirth and Neonatal Death. BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology , 1630-1637.
Mahmood, M. A. (2002). Determinants of Neonatal and Post-neonatal Mortality in Pakistan. The Pakistan Development Review , 735, 739.
Majoko, F., LNyström, Munjanja, S., Mason, E., & Lindmark, G. (2004). Relation of Parity to Pregnancy Outcome in a Rural Community in Zimbabwe. African Journal of Reproductive Health , 205.
Målqvist, M., Sohel, N., Do, T. T., Eriksson, L., & Persson, L. Å. (2010). Distance Decay in Delivery Care Utilization Associated With Neonatal Mortality. A Case Referent Study in Northern Vietnam. BMC Public Health , 1-9.
Manzar, N., Manzar, B., Yaqoob, A., Ahmed, M., & Kumar, J. (2012). The Study of Etiological and Demographic Characteristics of Neonatal Mortality and Morbidity-A Consecutive Case Series Study from Pakistan. BMC Pediatrics , 1-6.

170
Markovitz, B. P., Cook, R., Flick, L. H., & Leet, T. L. (2005). Socioeconomic Factors and Adolescent Pregnancy Outcomes: Distinctions Between Neonatal and Post-Neonatal Deaths? BMC Public Health , 1-7.
McCarthy, J., & Maine, D. (1992). A Framework for Analyzing the Determinants of Maternal Mortality. Studies in Family Planning , 26.
Meadow, R., & Newell, S. (2002). Lectures Notes: Pediatrika. Terjemahan Kripti Hartini dan Asri Dwi Rachmawati. Jakarta: Erlangga.
Mekonnen, Y., Tensou, B., Telake, D. S., Degefie, T., & Bekele, A. (2013). Neonatal Mortality in Ethiopia: Trends and Determinants. BMC Public Health , 1-14.
Mercer, A., Haseen, F., Huq, N. L., Uddin, N., Khan, M. H., & Larson, C. P. (2006). Risk Factors for Neonatal Mortality in Rural Areas of Bangladesh Served by A Large NGO Programme. Oxford University Press , 432.
Mosley, W. H., & Chen, L. C. (2003). An Analytical Framework for The Study of Child Survival in Developing Countries. Geneva: World Health Organization.
Murti, B. (1997). Prinsip dan Metode Riset Epidemiologi. Yogyakarta: UGM Press.
Neupane, S., & Doku, D. T. (2014). Neonatal Mortality in Nepal A Multilevel Analysis of A Nationally Representative. Journal of Epidemiology and Global Health , 218.
Nugraheni, A. (2013). Pengaruh Komplikasi Kehamilan Terhadap Kematian Neonatal Dini di Indonesia (Analisis Data SDKI 2007). Depok: Universitas Indonesia.
Okwaraj, Y. B., Cousens, S., Berhane, Y., Mulholland, K., & Edmond, K. (2012). Effect of Geographical Access to Health Facilities on Child Mortality in Rural Ethiopia A Community Based Cross Sectional Study. Plos One , 3.
Onwuanaku, C. A., Okolo, S. N., Ige, K. O., Okpe, S. E., & Toma, B. O. (2011). The Effects of Birth Weight and Gender on Neonatal Mortality in North Central Nigeria. BMC Research Notes , 1-5.
Owais, A., Faruque, A. S., Das, S. K., Ahmed, S., Rahman, S., & Stein, A. D. (2013). Maternal and Antenatal Risk Factors for Stillbirths and Neonatal Mortality in Rural Bangladesh: A Case-Control Study. Plos One , 3.

171
Pertiwi, I. (2010). Hubungan Kematian Neonatal dengan Kunjungan ANC dan Perawatan Postnatal di Indonesia Menurut SDKI 2007-2008. Depok: Universitas Indonesia.
Pinem, S. (2009). Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi. Jakarta: CV. Trans Info Media.
Prabamurti, P. N., Purnami, C. T., Widagdo, L., & Setyono, S. (2008). Analisis Faktor Risiko Status Kematian Neonatal Studi Kasus Kontrol di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Tahun 2006. Semarang: Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia.
Price, D. L., & Gwin, J. F. (2005). Thompson's Pediatric Nursing An Introductory Text. Philadelphia: Elsevier Saunders.
Pun, K. D., & Chauhan, M. (2011). Outcomes of Adolescent Pregnancy at Kathmandu University Hospital, Dhulikhel, Kavre. Kathmandu University Medical Journal , 50.
Rahmawati, H. K. (2007). Hubungan Karakteristik Ibu, Karakteristik Bayi, Pelayanan Antenatal, dan Perawatan Persalinan dengan Kematian Neonatal di Indonesia Tahun 2003-2003 (Analisis Data SDKI 2002-2003). Depok: Universitas Indonesia.
Rudolph, A. M., Hoffman, J. I., & Rudolph, C. D. (2006). Buku Ajar Pediatri Rudolph Volume 1 Terjemahan A. Samik Wahab. Jakarta: EGC.
Rudolph, A., Hoffman, J. I., & Rudolph, C. D. (2007). Buku Ajar Pediatri Rudolph Volume 3 Terjemahan A. Samik Wahab. Jakarta: EGC.
Saifuddin, A. B., Rachimhadi, T., & Wiknjosastro, G. H. (2010). Ilmu Kebidanan Sarwono Prawiroharjo. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Saifudin, A. B., Adriaansz, G., Wiknjosastro, G. H., & Waspodo, D. (2009). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirodiharjo.
Schoeps, D., Almeida, M. F., Alenca, G. P., Jr., I. F., Novaes, H. M., Siqueira, A. A., et al. (2007). Risk Factors for Early Neonatal Mortality. Rev Saúde Pública , 1-8.
Shah, A., Fawole, B., M'Imunya, J. M., Amokrane, F., Nafiou, I., Wolomby, J.-J., et al. (2009). Cesarean Delivery Outcomes from The WHO Global Survey on

172
Maternal and Perinatal Health in Africa. International Journal of Gynecology and Obstetrics , 5.
Sharma, V., Katz, J., Mullany, L. C., Khatry, S. K., LeClerq, S. C., Shrestha, S. R., et al. (2009). Young Maternal Age and the Risk of Neonatal Mortality in Rural Nepal. Arch Pediatr Adolesc Med , 5.
Singh, A., Kumar, A., & Kumar, A. (2013). Determinants of Neonatal Mortality in Rural India, 2007–2008. PeerJ , 1-26.
Singh, A., Yadav, A., & Singh, A. (2012). Utilization of Postnatal Care for Newborns and Its Association with Neonatal Mortality in India: An Analytical Appraisal. BMC Pregnancy and Childbirth , 1-6.
Singh, K., Brodish, P., & Suchindran, C. (2014). A Regional Multilevel Analysis: Can Skilled Birth Attendants Uniformly Decrease Neonatal Mortality? Maternal Child Health Journal , 242-248.
Smith, G. C., Pell, J. P., & Dobbie, R. (2003). Interpregnancy Interval and Risk of Preterm Birth and Neonatal Death Retrospective Cohort Study. British Medical Journal , 313-315.
Sriasih, N. G. (2012). Determinan Faktor Risiko Yang Berpengaruh Terhadap Kematian Neonatal Dini. Jurnal Skala Husada , 129.
Stalker, P. (2008). Millenium Development Goals. New York: Bappenas dan UNDP.
Sugiharto, J. (2011). Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kematian Bayi di Indonesia Tahun 2007 (Analisis Data Sekunder SDKI 2007). Depok: Universitas Indonesia.
Sukamti, S. (2011). Pengaruh Pelayanan Kesehatan Terhadap Kematian Neonatal Anak Terakhir di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2010). Depok: Universitas Indonesia.
Timmreck, T. C. (1994). An Introduction to Epidemiology. London: Jones and Bartlett Publishers.
Titaley, C. R., Dibley, M. J., & Roberts, C. L. (2010). Factors Associated with Underutilization of Antenatal Care Services in Indonesia Results of Indonesia Demographic and Health Survey 2002 2003 and 2007. BMC Public Health , 9.

173
Titaley, C. R., Dibley, M. J., & Roberts, C. L. (2011). Type of Delivery Attendant, Place of Delivery and Risk of Early Neonatal Mortality Analyses of the 1994–2007 Indonesia Demographic and Health Surveys. Health Policy and Planning , 8, 9.
Titaley, C. R., Dibley, M. J., Agho, K., Roberts, C. L., & Hall, J. (2008). Determinants of Neonatal Mortality in Indonesia. BMC Public Health , 1-15.
Tura, G., Fantahun, M., & Worku, A. (2013). The Effect of Health Facility Delivery on Neonatal Mortality: Systematic Review and Meta-Analysis. BMC Pregnancy and Childbirth , 1-9.
Turnbull, E., Lembalemba, M. K., Guffey, M. B., Bolton-Moore, C., Mubiana-Mbewe, M., Chintu, N., et al. (2011). Causes of Stillbirth, Neonatal Death and Early Childhood Death in Rural Zambia by Verbal Autopsy Assessments. Tropical Medicine and International Health , 897.
United Nations. (2013). The Millennium Development Goals Report 2013. New York: United Nations.
Upadhyay, R., Dwivedi, P., Rai, S., Misra, P., Kalaivani, M., & Krishnan, A. (2012). Determinants of Neonatal Mortality in Rural Haryana: A Retrospective Population Based Study. Indian Pediatric , 291-294.
Vandresse, M. (2008). Estimation of a Structural Model of the Determinants of Neonatal Mortality in Hungary, 1984-88 and 1994-98. Population Studies , 85-111.
Wells, J. C. (2000). Natural Selection and Sex Differences in Morbidity and Mortality in Early Life. J. Theor. Biol. , 70, 71.
Whalley, J., Simkin, P., & Keppler, A. (2008). Panduan Praktis Bagi Calon Ibu: Kehamilan dan Persalinan. Jakarta: BIP.
WHO. (2014). Global Health Observatory (GHO): Neonatal Mortality. Retrieved Februari 5, 2014, from World Health Organization: http://www.who.int/gho/child_health/mortality/neonatal_text/en/index.html
WHO. (2006). Neonatal and Perinatal Mortality Country, Regional and Global Estimates. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
WHO; Kemenkes RI; POGI; IBI. (2013). Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan dan Rujukan. Jakarta: Kemenkes RI.

174
Wijayanti, A. C. (2013). Hubungan Jumlah Anak yang Dilahirkan Terhadap Kejadian Kematian Neonatal (Analisis Data SDKI 2007). Depok: Universitas Indonesia.
Wiklund, I., Andolf, E., Lilja, H., & Hildingsson, I. (2012). Indications for Cesarean Section on Maternal Request-Guidelines for Counseling and Treatment. Sexual & Reproductive Healthcare , 104.
Wiknjosastro, H., Saifuddin, A. B., & Rachimhadhi, T. (2002). Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
Wong, D. L. (2004). Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik. Terjemahan Monica Ester. Jakarta: EGC.
Yani, D. F., & Duarsa, A. B. (2013). Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kematian Neonatal. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional , 373.
Yanping, W., Lei, M., Li, D., Chunhua, H., Xiaohong, L., Mingrong, L., et al. (2010). A Study on Rural-Urban Differences in Neonatal Mortality Rate in China, 1996-2006. Journal Epidemiology Community Health , 935-936.
Yego, F., Williams, J. S., Byles, J., Nyongesa, P., Aruasa, W., & D'Este, C. (2013). A Retrospective Analysis of Maternal and Neonatal Mortality at A Teaching and Referral Hospital in Kenya. Reproductive Health , 1-8.
Yi, B., Wu, L., Liu, H., Fang, W., Hu, Y., & Wang, Y. (2011). Rural-Urban Differences of Neonatal Mortality in A Poorly Developed Province of China. BMC Public Health , 1-6.
Zakariah, A. Y., Alexander, S., Roosmalen, J. v., Buekens, P., Kwawukume, E. Y., & Frimpong, P. (2009). Reproductive Age Mortality Survey (RAMOS) in Accra, Ghana. Reproductive Health , 1-5.
Zimba, E., Kinney, M. V., Kachale, F., Waltensperger, K. Z., Blencowe, H., Colbourn, T., et al. (2012). Newborn Survival in Malawi: A Decade of Change and Future Implications. Oxford University Press , iii96.

175
LAMPIRAN-LAMPIRAN

176
KUESIONER

177
Pertanyaan Terkait Umur dan Pendidikan Ibu

178
Pertanyaan Terkait Status Pekerjaan Ibu

179
Pertanyaan Terkait Indeks Kekayaan Rumah Tangga

180

181

182

183
Pertanyaan Terkait Kematian Neonatal dan Jenis Kelamin Bayi
Pertanyaan Terkait Paritas

184
Pertanyaan Terkait Kunjungan Antenatal

185
Pertanyaan Terkait Komplikasi Kehamilan

186
Pertanyaan Terkait Penolong Persalinan
Pertanyaan Terkait Cara Persalinan
Pertanyaan Terkait Tempat Persalinan

187
HASIL UJI STATISTIK
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Tingkat Pendidikan Ibu * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%
Tingkat Pendidikan Ibu * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Tingkat Pendidikan Ibu
Rendah Count 59 4852 4911
% within Tingkat Pendidikan Ibu 1.2% 98.8% 100.0%
Tinggi Count 20 2207 2227
% within Tingkat Pendidikan Ibu .9% 99.1% 100.0%
Total Count 79 7059 7138 % within Tingkat Pendidikan
Ibu 1.1% 98.9% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 1.288a 1 .256 Continuity Correctionb 1.026 1 .311
Likelihood Ratio 1.338 1 .247 Fisher's Exact Test .274 .155
Linear-by-Linear Association 1.288 1 .256 N of Valid Casesb 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.65. b. Computed only for a 2x2 table
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent Pekerjaan Ibu * Kematian
Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%

188
Pekerjaan Ibu * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Pekerjaan Ibu Bekerja Count 62 3841 3903
% within Pekerjaan Ibu 1.6% 98.4% 100.0%
Tidak bekerja Count 17 3218 3235
% within Pekerjaan Ibu .5% 99.5% 100.0% Total Count 79 7059 7138
% within Pekerjaan Ibu 1.1% 98.9% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 18.263a 1 .000 Continuity Correctionb 17.304 1 .000
Likelihood Ratio 19.688 1 .000 Fisher's Exact Test .000 .000
Linear-by-Linear Association 18.260 1 .000 N of Valid Casesb 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.80. b. Computed only for a 2x2 table
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Indeks Kekayaan Rumah Tangga * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%
Indeks Kekayaan Rumah Tangga * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Indeks Kekayaan Rumah Tangga
Rendah Count 47 4709 4756
% within Indeks Kekayaan Rumah Tangga 1.0% 99.0% 100.0%
Menengah Count 17 1179 1196
% within Indeks Kekayaan Rumah Tangga 1.4% 98.6% 100.0%
Tinggi Count 15 1171 1186
% within Indeks Kekayaan Rumah Tangga 1.3% 98.7% 100.0%
Total Count 79 7059 7138 % within Indeks Kekayaan
Rumah Tangga 1.1% 98.9% 100.0%

189
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 1.963a 2 .375 Likelihood Ratio 1.885 2 .390
Linear-by-Linear Association 1.240 1 .265 N of Valid Cases 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.13.
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Umur Ibu * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%
Umur Ibu * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Umur Ibu 0 Count 33 1947 1980
% within Umur Ibu 1.7% 98.3% 100.0%
1 Count 46 5112 5158
% within Umur Ibu .9% 99.1% 100.0% Total Count 79 7059 7138
% within Umur Ibu 1.1% 98.9% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 7.848a 1 .005 Continuity Correctionb 7.157 1 .007
Likelihood Ratio 7.242 1 .007 Fisher's Exact Test .008 .005
Linear-by-Linear Association 7.847 1 .005 N of Valid Casesb 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.91. b. Computed only for a 2x2 table

190
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Jenis Kelamin * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%
Jenis Kelamin * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Jenis Kelamin Laki-Laki Count 45 3680 3725
% within Jenis Kelamin 1.2% 98.8% 100.0%
Perempuan Count 34 3379 3413
% within Jenis Kelamin 1.0% 99.0% 100.0% Total Count 79 7059 7138
% within Jenis Kelamin 1.1% 98.9% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square .730a 1 .393 Continuity Correctionb .550 1 .458
Likelihood Ratio .734 1 .392 Fisher's Exact Test .429 .230
Linear-by-Linear Association .730 1 .393
N of Valid Casesb 7138 a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.77. b. Computed only for a 2x2 table
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent Paritas * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%

191
Paritas * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Paritas >=4 Count 23 1342 1365
% within Paritas 1.7% 98.3% 100.0%
1-3 Count 56 5717 5773
% within Paritas 1.0% 99.0% 100.0% Total Count 79 7059 7138
% within Paritas 1.1% 98.9% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 5.156a 1 .023 Continuity Correctionb 4.523 1 .033
Likelihood Ratio 4.624 1 .032 Fisher's Exact Test .030 .020
Linear-by-Linear Association 5.155 1 .023 N of Valid Casesb 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.11. b. Computed only for a 2x2 table
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Kunjungan Antenatal * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%
Kunjungan Antenatal * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Kunjungan Antenatal Tidak Count 45 2643 2688
% within Kunjungan Antenatal 1.7% 98.3% 100.0%
Iya Count 34 4416 4450
% within Kunjungan Antenatal .8% 99.2% 100.0%
Total Count 79 7059 7138 % within Kunjungan
Antenatal 1.1% 98.9% 100.0%

192
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 12.681a 1 .000 Continuity Correctionb 11.863 1 .001
Likelihood Ratio 12.189 1 .000 Fisher's Exact Test .001 .000
Linear-by-Linear Association 12.679 1 .000 N of Valid Casesb 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29.75. b. Computed only for a 2x2 table
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Komplikasi Kehamilan * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%
Komplikasi Kehamilan * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Komplikasi Kehamilan Komplikasi Count 12 415 427
% within Komplikasi Kehamilan 2.8% 97.2% 100.0%
Tidak komplikasi Count 67 6644 6711
% within Komplikasi Kehamilan 1.0% 99.0% 100.0%
Total Count 79 7059 7138 % within Komplikasi
Kehamilan 1.1% 98.9% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 12.042a 1 .001 Continuity Correctionb 10.444 1 .001
Likelihood Ratio 8.687 1 .003 Fisher's Exact Test .002 .002
Linear-by-Linear Association 12.041 1 .001 N of Valid Casesb 7138
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.73. b. Computed only for a 2x2 table

193
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Penolong Persalinan * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%
Penolong Persalinan * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Penolong Persalinan Non Nakes Count 24 1887 1911
% within Penolong Persalinan 1.3% 98.7% 100.0%
Nakes Count 55 5172 5227
% within Penolong Persalinan 1.1% 98.9% 100.0%
Total Count 79 7059 7138 % within Penolong
Persalinan 1.1% 98.9% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square .530a 1 .466 Continuity Correctionb .361 1 .548
Likelihood Ratio .516 1 .472 Fisher's Exact Test .446 .270
Linear-by-Linear Association .530 1 .467 N of Valid Casesb 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.15. b. Computed only for a 2x2 table
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Persalinan Caesar * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%

194
Persalinan Caesar * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Persalinan Caesar Caesar Count 9 562 571
% within Persalinan Caesar 1.6% 98.4% 100.0%
Tidak caesar Count 70 6497 6567
% within Persalinan Caesar 1.1% 98.9% 100.0% Total Count 79 7059 7138
% within Persalinan Caesar 1.1% 98.9% 100.0%
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square 1.250a 1 .264 Continuity Correctionb .827 1 .363
Likelihood Ratio 1.117 1 .290 Fisher's Exact Test .291 .178
Linear-by-Linear Association 1.249 1 .264 N of Valid Casesb 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.32. b. Computed only for a 2x2 table
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Tempat Persalinan * Kematian Neonatal 7138 100.0% 0 .0% 7138 100.0%
Tempat Persalinan * Kematian Neonatal Crosstabulation
Kematian Neonatal
Total Meninggal Tidak meninggal
Tempat Persalinan Non Fasyankes Count 45 4231 4276
% within Tempat Persalinan 1.1% 98.9% 100.0%
Fasyankes Count 34 2828 2862
% within Tempat Persalinan 1.2% 98.8% 100.0% Total Count 79 7059 7138
% within Tempat Persalinan 1.1% 98.9% 100.0%

195
Chi-Square Tests
Value df
Asymp. Sig. (2-sided)
Exact Sig. (2-sided)
Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square .288a 1 .592 Continuity Correctionb .177 1 .674
Likelihood Ratio .286 1 .593 Fisher's Exact Test .645 .335
Linear-by-Linear Association .288 1 .592 N of Valid Casesb 7138
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.68. b. Computed only for a 2x2 table