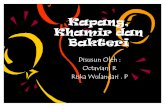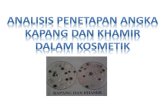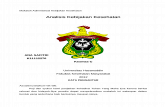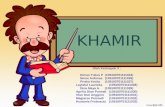Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang-Khamir (AKK ...
Transcript of Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang-Khamir (AKK ...

Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang-Khamir(AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau dari Perkebunan Rakyat
Boyolali Jawa Tengah
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)
Program Studi Ilmu Farmasi
Oleh :
Melissa
NIM : 068114093
FAKULTAS FARMASIUNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA2010

ii
Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang-Khamir(AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau dari Perkebunan Rakyat
Boyolali Jawa Tengah
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu SyaratMemperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)
Program Studi Ilmu Farmasi
Oleh :
Melissa
NIM : 068114093
FAKULTAS FARMASIUNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA2010

iii

iv

v
Hidup adalah
10 persen dari apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, dan
90 persen adalah bagaimana sikap kita menghadapinya.
Karya ini kupersembahkan dengan cinta teruntuk:
Mama, Papa, Ci Meti dan Oh Yohan atas semua dukungan, kasih sayang, dan doanya
Sonny tersayang atas segala cinta, semangat dan dukungan yang telah diberikan
Malaikat kecilku, dion, terima kasih atas senyummu yang selalu menyinari hariku
almamaterku tercinta

vi

vii

viii
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala
anugerah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang-Khamir (AKK) Ekstrak Kental
Teh Hijau dari Perkebunan Rakyat Boyolali Jawa Tengah”.
Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) di Fakultas Farmasi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya
bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini
penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Rita Suhadi M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata
Dharma.
2. Ibu Maria Dwi Budi Jumpowati, S.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah meluangkan banyak waktu untuk membantu penulis hingga
terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Erna Tri Wulandari, M.Si., Apt., selaku dosen penguji yang telah banyak
memberi masukan kepada penulis.
4. Ibu Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt., selaku dosen penguji yang telah banyak
memberi masukan kepada penulis.
5. Ibu Christine Patramurti, M.Si., Apt., selaku Kepala Program Studi atas batuan
yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.

ix
6. Ibu C.M. Ratna Rini Nastiti, M.Pharm., Apt., selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dosen Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma yang telah
memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Mas Wagiran, Mas Sarwanto, seluruh laboran dan karyawan Universitas Sanata
Dharma.
9. Orang tua, cici, koko tercinta, atas segala kasih sayang, dukungan, dan doanya
selama ini.
10. Sonny dan dion tersayang serta keluarga yang telah banyak membantu dan
selalu mendukung penulis selama pembuatan skripsi.
11. Teman-temanku tercinta Arum (mongkie), Riri, Micell, Dian (Mei2), Heni,
Vivin, Amel untuk semangat yang selalu diberikan hingga skripsi ini berhasil
terselesaikan, tengkyu very much. Teman-teman seperjuangan di laboratorium,
Ayu, Grace, Dini, dan Inge. Teman-teman KKN angkatan 39 kelompok 32,
terimakasih telah mau mengerti.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan laporan ini yang tidak
dapat disebutkan satu persatu.
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak
terlepas dari keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran
yang sifatnya membangun demi penyempurnaan laporan skripsi ini sangat penulis
harapkan.
Penulis

x
INTISARI
Teh (Camellia sinensis L.) telah diyakini memiliki banyak khasiat kesehatan,antara lain menurunkan tekanan darah, menghilangkan stress, dan lain-lain. Teh dariPerkebunan Rakyat Boyolali memiliki spesies yang sama dan bermutu tinggisehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Teh yang diolahdengan cara pemanasan disebut teh hijau. Ekstrak kental teh hijau merupakan salahsatu bentuk bahan baku obat tradisional yang harus memenuhi kualitas bahan bakuuntuk menjamin mutu dan keamanan penggunaan bahan baku tersebut denganstandarisasi bahan baku. Standarisasi bahan baku yang dilakukan dalam penelitian iniadalah pengujian cemaran mikroba yang meliputi Angka Lempeng Total (ALT) danAngka Kapang Khamir (AKK).
Pada penelitian ini dibuat ekstrak kental teh hijau dengan cara maserasimenggunakan pelarut etanol 70%. Kemudian dilakukan uji ALT dan AKK yangbertujuan untuk mengetahui nilai ALT dan AKK ekstrak kental teh hijau serta apakahALT dan AKK yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan Badan Penelitian Obatdan Makanan (BPOM) RI dalam Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia(Anonim, 2004), yaitu tidak melebihi 10 koloni/g.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ALT dan AKK yang terdapatdalam ekstrak kental teh hijau kurang dari 10 koloni/g. Hasil ini berarti tidak melebihibatas yang ditetapkan dalam Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat sehingga ekstrakkental teh hijau dari Perkebunan Rakyat Boyolali dapat diolah menjadi produk ObatTradisional yang aman untuk dikonsumsi berdasarkan nilai ALT dan AKK.
Kata kunci : Angka Lempeng Total bakteri (ALT), Angka Kapang/Khamir (AKK),ekstrak kental teh hijau

xi
ABSTRACT
Tea (Camellia sinensis L.) has been believed that it has many health benefits,including lowering blood pressure, relieveing stress, and others. Tea from Boyolaliplantation have the same species and high quality so it potentially used as rawmaterials of traditional medicine. Green tea was made by warm up the tea leaves.Green tea extract is one of traditional medicine raw materials that must fulfill the rawmaterials quality to ensure quality and safety of the use of these materials withstandardization of raw materials. Standardization of raw material in this study ismicrobiological test including microbial contamination Total Plate Count (ALT) andNumber of Mold / Yeast (AKK).
In this study, green tea extract was made by maceration using 70% ethanolsolvent. Then it was continued by microbiological tests of ALT and AKK were aimedto determine the value of ALT and AKK green tea extract exceed the limitation madeby Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI in the Monograph of MedicinalPlant Extracts In Indonesia (Anonim, 2004), which didn’t exceed 10 colonies / g.
The result indicated that the value of ALT and AKK contained in green teaextract was under 10 CFU / g and did not exceed the limit specified in the Monographof Medicinal Plant Extracts In Indonesia. It was proved that green tea extract fromBoyolali plantation could be processed into traditional medicine products were safetyfor consumption in terms of ALT and AKK.
Keywords: Total Plate Count (ALT), Numbers of Mold / Yeast (AKK), green teaextract

xii
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN JUDUL.................................................................................................. ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN................................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH......vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .................................................................. vii
PRAKATA .............................................................................................................viii
INTISARI...................................................................................................................x
ABSTRACT ...............................................................................................................xi
DAFTAR ISI............................................................................................................ xii
DAFTAR TABEL.................................................................................................... xv
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. xvi
DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... xviii
BAB I. PENGANTAR
A. Latar Belakang .............................................................................................. 1
1. Perumusan Masalah .......................................................................... 5
2. Keaslian Penelitian............................................................................ 5
3. Manfaat Penelitian ............................................................................ 6
B. Tujuan Penelitian........................................................................................... 6

xiii
BAB II. PENELAAHAN PUSTAKA
A. Teh (Camellia sinensis L.) ............................................................................ 8
1. Keterangan Botani............................................................................. 8
2. Deskripsi Tanaman Teh .................................................................... 8
3. Kandungan Kimia ............................................................................. 8
4. Khasiat................................................................................................9
B. Pembuatan Simplisia dan Serbuk Daun Teh................................................10
C. Ekstraksi Teh Hijau......................................................................................13
D. Uji Angka Lempeng Total (ALT) ............................................................... 15
E. Uji Angka Kapang Khamir (AKK)..............................................................18
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Dan Rancangan Penelitian ................................................................. 21
B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional ............................................ 21
1. Variabel Penelitian..................... ..................................................... 21
2. Definisi Operasional ....................................................................... 22
C. Bahan Dan Alat Penelitian ......................................................................... 23
D. Tatacara Penelitian ..................................................................................... 23
1. Determinasi Tanaman................... .................................................. 23
2. Pembuatan Simplisia dan Serbuk Daun Teh.............. ..................... 24
3. Ekstraksi Teh Hijau..........................................................................25
4. Pengujian Angka Lempeng Total (ALT).........................................25
5. Pengujian Angka Kapang Khamir (AKK).......................................27

xiv
6. Cara perhitungan berdasarkan Parameter Standar Umum Ekstrak
Tumbuhan Obat (Anonim,2000)......................................................29
E. Analisis Hasil................................................................................................32
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Determinasi Tanaman................... .............................................................. 35
B. Pembuatan Simplisia dan Serbuk Daun Teh.............. ................................. 36
C. Ekstraksi.......................................................................................................39
D. Pengujian Angka Lempeng Total (ALT)................... ................................. 41
E. Pengujian Angka Kapang Khamir (AKK)................................................... 46
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .... .............................................................................................53
B. Saran.............................................................................................................53
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 54
LAMPIRAN..............................................................................................................57
BIOGRAFI PENULIS ............................................................................................. 67

xv
DAFTAR TABEL
Tabel I. Angka Lempeng Total (ALT) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 24 Jam .............................................................................. 42
Tabel II. Angka Lempeng Total (ALT) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 48 Jam .............................................................................. 45
Tabel III. Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 5 Hari ……………............................................................ 47
Tabel IV. Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 6 Hari ………………….................................................... 48
Tabel V. Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 7 Hari .................................................................................49

xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Pohon teh............................................................................................. 58
Gambar 2. Daun teh ......................................................................................... .....59
Gambar 3. Daun, buah, dan bunga teh...................................................................59
Gambar 4. Ekstrak kental teh hijau........................................................................59
Gambar 5. Kontrol media (replikasi 1) ALT inkubasi 24 jam...............................60
Gambar 6. Kontrol pelarut (replikasi 1) ALT inkubasi 24 jam.............................60
Gambar 7. ALT 10-1 (replikasi 2) inkubasi 24 jam..............................................60
Gambar 8. ALT 10-2 (replikasi 2) inkubasi 24 jam...............................................60
Gambar 9. ALT 10-3 (replikasi 2) inkubasi 24 jam...............................................60
Gambar 10. ALT 10-4 (replikasi 2) inkubasi 24 jam...............................................60
Gambar 11. ALT 10-5 (replikasi 1) inkubasi 24 jam...............................................61
Gambar 12. ALT 10-6 (replikasi 2) inkubasi 24 jam...............................................61
Gambar 13. Kontrol media (replikasi 1) ALT inkubasi 48 jam..............................61
Gambar 14. Kontrol pelarut (replikasi 1) ALT inkubasi 48 jam.............................61
Gambar 15. ALT 10-1 (replikasi 1) inkubasi 48 jam...............................................61
Gambar 16. ALT 10-2 (replikasi 1) inkubasi 48 jam...............................................61
Gambar 17. ALT 10-3 (replikasi 1) inkubasi 48 jam...............................................62
Gambar 18. ALT 10-4 (replikasi 2) inkubasi 48 jam...............................................62
Gambar 19. ALT 10-5 (replikasi 1) inkubasi 48 jam...............................................62
Gambar 20. ALT 10-6 (replikasi 1) inkubasi 48 jam...............................................62

xvii
Gambar 21. Kontrol media (replikasi 1) AKK inkubasi 5 hari..............................62
Gambar 22. Kontrol pelarut (replikasi 1) AKK inkubasi 5 hari.............................63
Gambar 23. AKK 10-1 (replikasi 1) inkubasi 5 hari...............................................63
Gambar 24. AKK 10-2 (replikasi 2) inkubasi 5 hari...............................................63
Gambar 25. AKK 10-3 (replikasi 1) inkubasi 5 hari...............................................63
Gambar 26. AKK 10-4 (replikasi 1) inkubasi 5 hari...............................................63
Gambar 27. AKK 10-4 (replikasi 2) inkubasi 5 hari...............................................63
Gambar 28. Kontrol media (replikasi 2) AKK inkubasi 6 hari..............................64
Gambar 29. Kontrol pelarut (replikasi 1) AKK inkubasi 6 hari.............................64
Gambar 30. AKK 10-1 (replikasi 1) inkubasi 6 hari................................................64
Gambar 31. AKK 10-2 (replikasi 2) inkubasi 6 hari...............................................64
Gambar 32. AKK 10-3 (replikasi 1) inkubasi 6 hari...............................................64
Gambar 33. AKK 10-3 (replikasi 1) tampak depan inkubasi 6 hari........................64
Gambar 34. AKK 10-4 (replikasi 1) inkubasi 6 hari...............................................65
Gambar 35. AKK 10-4 (replikasi 2) inkubasi 6 hari...............................................65
Gambar 36. Kontrol media (replikasi 2) AKK inkubasi 7 hari..............................65
Gambar 37. Kontrol pelarut (replikasi 1) AKK inkubasi 7 hari.............................65
Gambar 38. AKK 10-1 (replikasi 2) inkubasi 7 hari...............................................65
Gambar 39. AKK 10-2 (replikasi 1) inkubasi 7 hari...............................................65
Gambar 40. AKK 10-3 (replikasi 1) inkubasi 7 hari...............................................66
Gambar 41. AKK 10-4 (replikasi 1) inkubasi 7 hari...............................................66
Gambar 42. AKK 10-4 (replikasi 2) inkubasi 7 hari...............................................66

xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Determinasi Tanaman.................................................................. ......57
Lampiran 2. Perhitungan Penimbangan Bahan.......................................................58
Lampiran 3. Foto Tanaman Teh .............................................................................58
Lampiran 4. Foto Ekstrak Kental Daun Teh Hijau ................................................ 59
Lampiran 5. Perhitungan Rendemen Ekstrak Kental Daun Teh Hijau...................59
Lampiran 6. Foto Angka Lempeng Total (ALT) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 24 Jam .............................................................................. 60
Lampiran 7. Foto Angka Lempeng Total (ALT) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 48 Jam .............................................................................. 61
Lampiran 8. Foto Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 5 Hari ……………............................................................ 62
Lampiran 9. Foto Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 6 Hari ………………….................................................... 64
Lampiran 10. Foto Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau Waktu
Inkubasi 7 Hari .................................................................................65

1
BAB I
PENGANTAR
A. Latar Belakang
Ekstrak kental teh hijau (Camellia sinensis L.) sebagai bahan baku obat
tradisional telah lama diyakini memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, antara lain
mencegah terjadinya penyakit jantung koroner (PJK), diabetes mellitus (DM),
menurunkan tekanan darah, menghilangkan stress, dan mempertahankan berat
tubuh ideal (Hartoyo, 2003). Tanaman teh dari Perkebunan Rakyat Boyolali
memiliki spesies yang sama dan digunakan oleh pabrik untuk memproduksi teh
seduh sehingga mutu tanaman teh terjamin. Perkebunan tersebut berada pada
ketinggian 1300-1500 m di atas permukaan laut, memiliki curah hujan yang tinggi
yaitu 3222 mm, dan memiliki tipe tanah andosol sehingga cocok sebagai tempat
tumbuh tanaman teh (Setyamidjaja, 2000). Diharapkan tanaman teh dari
Perkebunan Rakyat Boyolali, selain digunakan sebagai bahan baku produksi teh
seduh dapat pula digunakan sebagai bahan baku obat tradisional yaitu dalam
bentuk ekstrak kental teh hijau. Menurut Hartoyo (2003) teh hijau dibuat dengan
cara menginaktifasi enzim oksidase/fenolase yang ada dalam pucuk daun teh
segar dengan cara pemanasan atau penguapan menggunakan uap panas.
Bahan baku suatu obat tradisional, baik berupa simplisia maupun ekstrak,
harus memenuhi kualitas bahan baku untuk menjamin mutu, keamanan, dan
khasiat penggunaan bahan baku tersebut. Standarisasi bahan baku perlu dilakukan
untuk menjamin kualitas bahan baku (Anonim, 2005b). Obat tradisional
1

2
merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat
kandungannya sangat beragam sehingga untuk menjamin mutu obat tradisional
diperlukan cara pembuatan yang baik dengan lebih memperhatikan proses
produksi dan penanganan bahan baku. Keamanan dan mutu obat tradisional
bergantung salah satunya pada mutu bahan baku (Anonim, 2005a) sehingga mutu
bahan baku yang tinggi akan menjamin tingginya mutu obat tradisional dalam
upaya pengobatan.
Standarisasi bahan baku terdiri dari berbagai parameter standar umum dan
parameter standar khusus. Parameter standar umum ekstrak, meliputi : berat
kering dan berat jenis, kadar air, kadar abu, kadar sisa pelarut, residu pestisida, uji
batas logam berat, uji cemaran mikroba, kadar sari larut dalam pelarut tertentu,
kadar terlarut dengan spektrofotometer, sidik jari kromatogram, kadar total
golongan zat kandungan dan kadar zat aktif atau zat identitas (Anonim, 1999).
Parameter standar khusus ekstrak, meliputi penetapan organoleptik ekstrak
(meliputi bentuk, warna, bau dan rasa) dan penetapan kadar senyawa terlarut
dalam pelarut tertentu (meliputi kadar senyawa yang larut dalam air dan kadar
senyawa yang larut dalam etanol) (Anonim, 2004).
Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair, yang dibuat dengan
menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai (Anief, 2005).
Ekstrak kering memiliki konsistensi kering dan mudah digosokkan, ekstrak kental
bersifat liat dalam keadaan dingin, dan tidak dapat dituang. Ekstrak kental
mengandung air tidak lebih dari 30% sedangkan ekstrak cair dibuat sedemikian
hingga 1 bagian tumbuhan sesuai dengan 2 bagian ekstrak cair (Voigt, 1994).

3
Tujuan pembuatan ekstrak tumbuhan obat adalah untuk menstandarisasi
kandungannya sehingga menjamin keseragaman mutu, keamanan dan khasiat
produk akhir. Hasil standarisasi ekstrak tersebut diharapkan mampu menunjukkan
kualitas ekstrak tersebut, baik dalam hal kandungan bahan aktif, kadar air maupun
batas cemaran yang diperbolehkan (Anonim, 2005b). Jumlah cemaran mikroba
yang tinggi dapat mengubah karakter organoleptik dan dapat membahayakan bila
dikonsumsi. Jenis cemaran mikroba meliputi bakteri, kapang/fungi dan khamir
serta virus yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan
seperti penampilan, tekstur, rasa dan bau (Anonim, 2008). Dalam penelitian ini
dibuat ekstrak kental karena uji ALT dan AKK pada ekstrak kering teh hijau
pernah dilakukan. Hasil dari pengujian ALT dan AKK ekstrak kering tersebut
memenuhi syarat, yaitu tidak mengandung mikroba melebihi batas yang
ditetapkan. Ekstrak kental teh hijau dibuat dengan cara maserasi menggunakan
pelarut etanol 70%. Pemilihan pelarut dalam ekstraksi didasarkan pada kandungan
utama yang terdapat dalam teh hijau, yaitu flavonoid yang bersifat larut dalam
etanol 70%.
Dalam penelitian ini dilakukan uji cemaran mikroba sebagai salah satu
parameter standar umum ekstrak. Uji cemaran mikroba bertujuan memberikan
jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak
mengandung mikroba non patogen melebihi batas yang ditetapkan karena
berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya bagi kesehatan (Anonim,
2000). Adanya toksin bakteri yang terbentuk dalam ekstrak saat bakteri
bermultiplikasi, misalnya toksin botulin yang dihasilkan oleh Clostridium

4
botulinum atau adanya aflatoksin yang dihasilkan Aspergilus flavus akan sangat
berbahaya bila dikonsumsi (Anonim, 2008). Toksin botulin merupakan toksin
yang sangat kuat dan merupakan neurotoksin, yaitu menyerang sistem saraf dan
dapat menyebabkan kelumpuhan (Kusnandar, Hariyadi, dan Wulandari, 2006),
sedangkan aflatoksin selain meracuni organ tubuh juga bersifat karsinogenik
(Anonim, 1994). Uji cemaran mikroba yang dilakukan pada penelitian ini yaitu
Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Kapang Khamir (AKK).
Uji ALT bertujuan untuk menentukan jumlah atau angka bakteri aerob
mesofil yang mungkin mencemari ekstrak kental teh hijau yang merupakan bahan
baku suatu produk obat tradisional. Dalam Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat
Indonesia, batas ALT yang diperbolehkan untuk semua jenis ekstrak menurut
Badan POM RI tidak lebih dari 10 koloni/gram (Anonim, 2004). Berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 661/MENKES/SK/VII/1994 tentang
persyaratan obat tradisional, ALT harus ditekan sekecil mungkin karena meskipun
mikroba tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan, tetapi adanya toksin yang
terbentuk saat bakteri bermultiplikasi dapat menyebabkan keracunan.
Uji AKK digunakan untuk uji cemaran berupa kapang dan khamir.
Pencemaran khamir dan kapang terhadap produk meskipun sifat dan tingkatannya
tidak berpengaruh langsung pada kesehatan, namun sebaiknya dicegah sekecil
mungkin sampai dengan persyaratan batas AKK yang berlaku (Anonim, 2005a).
Kapang adalah kelompok mikroba yang tergolong dalam fungi multiseluler yang
mempunyai filamen, dan pertumbuhannya mudah dilihat karena penampakannya
yang berserabut seperti kapas (Fardiaz, 1993). Khamir adalah fungi uniseluler

5
yang mikroskopik dan tidak membentuk percabangan permanen (Jutono, Hartadi,
Siti Kabirun, Suhadi, dan Soesanto, 1980). Batas AKK yang ditetapkan oleh
Badan POM RI dalam Monografi Ekstrak Tumbuhan Indonesia untuk semua jenis
ekstrak tidak lebih dari 10 koloni/g (Anonim, 2004). Adanya jumlah kapang dan
khamir yang tinggi menunjukkan penurunan mutu obat tradisional karena jumlah
kapang dan khamir yang tinggi dapat mengubah karakter organoleptik dan
mengakibatkan perubahan kandungan zat aktif obat. Kapang dan khamir akan
berkembang biak bila tempat tumbuhnya cocok untuk pertumbuhan. Di samping
itu kapang tertentu ada yang menghasilkan zat racun (toksin) seperti jamur
Aspergilus flavus dapat menghasilkan aflatoksin yang berbahaya jika dikonsumsi
(Anonim, 1994). Sedangkan khamir dapat menyebabkan pembusukan ekstrak
yang disertai dengan pembentukan alkohol dan gas CO2 (Kusnandar, dkk., 2006).
Nilai ALT dan AKK yang terdapat dalam ekstrak kental teh hijau yang
diketahui menunjukkan salah satu parameter keamanan obat tradisional yaitu
keamanan penggunaan ekstrak sebagai bahan baku obat tradisional berdasarkan
nilai ALT dan AKK.
1. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Berapakah nilai ALT dan AKK yang terdapat dalam ekstrak kental teh hijau
dari Perkebunan Rakyat Boyolali?
2. Apakah nilai ALT dan AKK yang diperoleh melebihi batas yang
dipersyaratkan oleh Badan POM RI yaitu tidak lebih dari 10 koloni/g?

6
2. Keaslian Penelitian
Sejauh penelusuran pustaka dan jurnal yang dilakukan oleh penulis,
penelitian mengenai uji ALT dan AKK pada ekstrak kering teh hijau pernah
dilakukan namun pada ekstrak kental teh hijau yang berasal dari Perkebunan
Rakyat Boyolali belum pernah dilakukan.
3. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi
mengenai nilai ALT dan AKK dalam ekstrak kental daun teh hijau yang
diperoleh dari Perkebunan Rakyat Boyolali Jawa Tengah.
2. Manfaat praktis
Ekstrak kental teh hijau dari Perkebunan Rakyat Boyolali memenuhi
persyaratan mutu dan keamanan dari segi ALT dan AKK untuk digunakan
sebagai bahan baku obat tradisional.
B. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Mengetahui mutu dan keamanan penggunaan ekstrak kental teh hijau sebagai
bahan baku obat tradisional dilihat dari nilai ALT dan AKK.
2. Tujuan Khusus
a. Memperoleh nilai ALT dan AKK yang terdapat dalam ekstrak kental
teh hijau yang berasal dari Perkebunan Rakyat Boyolali

7
b. Membandingkan nilai ALT dan AKK yang terdapat dalam ekstrak
kental teh hijau apakah sesuai dengan persyaratan dari Badan POM RI
yaitu tidak lebih dari 10 koloni/g.

8
BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA
A. Teh (Camellia sinensis L.)
1. Keterangan Botani
Teh termasuk ke dalam suku : Theaceae, marga : Camellia, dan jenis :
Camellia sinensis (L.) O.K., dengan sinonim : Camellia bohea Griff, C. theifera
Dyer., Thea sinensis L., T. asamica Mast, T. cochinchinensis Lour., T.
cantoniensis, T. chinensis Sims., T. viridis L. Nama daerah untuk teh adalah Teh
(Melayu dan Jawa Tengah), Nteri (Sunda) (Tuminah, 2004).
2. Deskripsi Tanaman Teh
Pohon kecil, karena seringnya pemangkasan maka tampak seperti perdu.
Batang tegak, berkayu, bercabang-cabang, ujung ranting dan daun muda berambut
halus. Daun tunggal, bertangkai pendek, letak berseling, helai daun kaku seperti
kulit tipis, bentuk elips memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi
halus, pertulangan menyirip, panjang 6-18 cm, lebar 2-6 cm, warna hijau. Bunga
di ketiak daun, tunggal atau beberapa bunga bergabung menjadi satu, berkelamin
dua, garis tengah 3-4 cm, warna putih cerah dengan kepala sari berwarna kuning,
harum. Buah kotak, berdinding tebal, pecah menurut ruang, masih muda hijau,
setelah tua cokelat kehitaman (Dalimartha, 1999).
3. Kandungan Kimia
Daun teh mengandung kafein (2-3%), theobromin, theofilin, tanin,
xanthin, adenin, minyak atsiri, kuersetin, naringenin, dan natural fluoride. Setiap
8

9
100 g daun teh mengandung 75-80% air, polifenol 25%, protein 20%, karbohidrat
4%, kafein 2,5-4,5%, serat 27% dan pektin 6% (Dalimartha, 1999).
Zat bioaktif yang terdapat dalam teh, merupakan golongan flavonoid.
Flavonoid yang terdapat dalam teh terutama berupa flavanol dan flavonol. Katekin
teh merupakan flavonoid yang termasuk dalam kelas flavanol (Hartoyo, 2003).
Menurut Svobodova, Psotova, dan Walterova (2003), zat bioaktif utama
dalam teh merupakan polifenol golongan flavonoid yaitu flavonol tipe katekin,
antara lain (-)-Epicatechin, (-)-Epigallocatechin, (-)-Epicatechin 3-gallate, (-)-
Epigallocatechin 3-gallate (EC, EGC, ECG dan EGCG) serta flavonol seperti
kuersetin. EGCG merupakan antioksidan yang paling efektif sebagai
chemoprotective agent, jumlahnya sekitar 60-70% dari jumlah keseluruhan
katekin.
4. Khasiat
Khasiat teh bagi kesehatan antara lain mencegah terjadinya Penyakit
Jantung Koroner (PJK), Diabetes Mellitus (DM), menurunkan tekanan darah,
menghilangkan stress, dan mempertahankan berat tubuh ideal (Hartoyo, 2003).
Menurut Henning, dkk. (2004) polifenol dalam teh yang bertindak sebagai
antioksidan dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Aktivitas antioksidan
ini telah banyak dibuktikan melalui penelitian in vitro misalnya penelitian yang
dilakukan Vinson, Dabbagh, Serry, dan Jang (1995) yang membandingkan antara
berbagai antioksidan, baik yang bersifat alami maupun buatan, dalam
menghambat oksidasi LDL dan VLDL yang diinisiasi oleh ion Cu2+ menunjukkan

10
bahwa isomer katekin teh mempunyai aktivitas antioksidatif terkuat dibanding
antioksidan lain.
Berdasarkan cara pengolahannya, teh dapat diklasifikasikan menjadi tiga
jenis, yaitu teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Teh hijau dibuat dengan cara
menginaktifasi enzim oksidase/fenolase yang ada dalam pucuk daun tanaman teh
yang segar, dengan cara pemanasan atau penguapan menggunakan uap panas. Teh
hitam dibuat dengan cara memanfaatkan terjadinya oksidasi enzimatis terhadap
kandungan katekin sedangkan teh oolong dihasilkan melalui proses pemanasan
yang dilakukan segera setelah proses penggulungan daun dengan tujuan untuk
menghentikan proses fermentasi (Hartoyo, 2003).
B. Pembuatan Simplisia dan Serbuk Daun Teh
Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang
belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain, simplisia
merupakan bahan yang dikeringkan (Anonim, 1985). Pada umumnya pembuatan
simplisia melalui tahapan sebagai berikut :
1. Pengumpulan bahan baku
Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda antara lain
tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman, atau bagian
tanaman pada saat panen, waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuh.
Pengumpulan daun dilakukan dengan memetik bagian daun muda. Pada
bagian daun muda dari daun yang dipanen pada saat tanaman mengalami

11
pertumbuhan dari vegetatif ke generatif memiliki kandungan senyawa aktif tinggi,
ditandai dengan munculnya kuncup-kuncup bunga pada tanaman (Anonim, 1985).
2. Sortasi basah
Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-
bahan asing lainnya dari simplisia. Misalnya pada simplisia yang terbuat dari daun
suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, batang,
akar, daun yang telah rusak serta pengotor lainnya harus dibuang. Tanah
mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah tinggi, oleh karena itu
pembersihan simplisia dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba
awal (Anonim, 1985).
3. Pencucian
Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya
yang melekat pada simplisia. Pencucian dilakukan dengan air mengalir yang
bersih, misalnya air dari mata air, air dari sumur atau air PAM. Pencucian tidak
dapat membersihkan simplisia dari semua mikroba karena air pencucian yang
digunakan biasanya mengandung sejumlah mikroba. Jika air yang digunakan
untuk pencucian kotor, maka jumlah mikroba pada permukaan bahan tersebut
bertambah dan air yang terdapat pada permukaan bahan tersebut dapat
mempercepat pertumbuhan mikroba (Anonim, 1985).
4. Perajangan
Beberapa jenis simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan
simplisia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan
penggilingan. Biasanya dilakukan pada simplisia yang berasal dari akar, umbi,

12
rimpang, dan lain-lain (Anonim, 1985). Daun teh telah cukup tipis dan
mempunyai permukaan yang cukup luas sehingga tidak dilakukan perajangan.
5. Pengeringan
Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak
mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan
mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan mencegah
penurunan mutu dan perusakan simplisia. Pengeringan dihentikan apabila kadar
air yang terkandung dalam simplisia kurang dari 10% karena reaksi enzimatik
yang dapat menguraikan senyawa aktif sudah tidak berlangsung, maka akan
menekan terjadinya peruraian senyawa-senyawa kimia dalam daun oleh enzim-
enzim yang ada di dalamnya (Anonim, 1985). Menurut Katno (2008) daun teh
yang muda memiliki kandungan air yang lebih tinggi dan jaringan yang lebih
lunak dibandingkan daun tua sehingga hal tersebut membuat pengeringan daun
muda dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar daun tidak rusak. Tahap
pertama adalah simplisia diangin-anginkan dan tahap kedua adalah dengan
pemanasan yang lebih tinggi. Pengeringan menggunakan oven umumnya
didapatkan simplisia dengan mutu lebih baik karena pengeringan lebih merata dan
waktu yang diperlukan relatif cepat dan tidak tergantung cuaca. Selain itu kadar
air simplisia juga dapat ditekan serendah mungkin sehingga menekan kontaminasi
mikroba. Dari hasil proses pengeringan daun teh dengan cara pemanasan ini maka
diperoleh simplisia daun teh hijau.
Proses pembuatan serbuk bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel
sehingga akan memperluas permukaan partikel yang kontak dengan cairan penyari

13
sehingga diharapkan penyarian akan lebih efektif karena dapat mempermudah
penarikan senyawa aktif oleh cairan penyari.
C. Ekstraksi Teh Hijau
Ekstraksi merupakan perpindahan zat aktif yang semula berada di dalam
sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari
(Anonim, 1986). Ekstrak merupakan suatu bentuk bahan baku obat tradisional.
Menurut Anonim (2005a) bahan baku obat tradisional adalah simplisia, sediaan
galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang
tidak berkhasiat, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional. Ekstrak
adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati
atau hewani menurut cara yang sesuai, tanpa terkena cahaya matahari langsung.
Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional yang
belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain,
merupakan bahan yang dikeringkan. Sebagai cairan penyari digunakan air, eter,
atau campuran etanol dan air (Anonim, 1979).
Menurut Voigt (1994) pada ekstrak tumbuhan jika bahan pengekstraksinya
sebagian atau seluruhnya diuapkan, maka diperoleh ekstrak yang dikelompokkan
menurut sifat-sifatnya menjadi :
1. Ekstrak encer, yang memiliki konsistensi seperti madu dan dapat dituang.
2. Ekstrak kental, yang bersifat liat dalam keadaan dingin, dan tidak dapat
dituang. Ekstrak kental mengandung air tidak lebih dari 30%.

14
3. Ekstrak kering, memiliki konsistensi kering dan mudah digosokkan.
Melalui penguapan cairan pengekstraksi dan pengeringan sisanya
terbentuk suatu produk, yang mengandung air tidak lebih dari 5%.
4. Ekstrak cair, yang dibuat sedemikian, sehingga 1 bagian tumbuhan sesuai
dengan 2 bagian ekstrak cair.
Salah satu cara ekstraksi atau penyarian yaitu maserasi. Metode ekstraksi
dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat, daya
penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam
memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989).
Maserasi (macerare = merendam) merupakan proses penyarian yang
paling tepat di mana simplisia yang sudah halus memungkinkan untuk direndam
dalam cairan penyari sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-
zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 1989). Maserasi dilakukan dengan
merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus
dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel kemudian melarutkan zat aktif
dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam dan di
luar sel. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi
antara larutan yang di luar dan di dalam sel (Anonim, 1986).
Kelebihan cara ekstraksi ini adalah cara pengerjaan dan peralatan yang
digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kekurangan dari metode maserasi
ini adalah pengerjaan lama dan penyarian kurang sempurna (Anonim, 1986).
Cairan penyari atau pelarut yang biasa digunakan adalah air, eter, etanol,
atau campuran etanol-air (Anonim, 1986). Pemilihan penyari dalam penyarian

15
merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Cairan penyari untuk ekstrak
sebaiknya sesuai dengan zat aktif yang berkhasiat, dalam arti dapat memisahkan
zat aktif tersebut dari senyawa lainnya dalam bahan sehingga ekstrak mengandung
sebagian besar senyawa aktif berkhasiat yang diinginkan (Anonim, 2000). Pada
ekstraksi daun teh hijau ini digunakan cairan penyari berupa etanol 70% yang
merupakan campuran dua bahan pelarut yaitu etanol dan air dengan kadar etanol
70%. Menurut Voigt (1994) etanol 70% sangat efektif dalam menghasilkan
jumlah bahan aktif yang optimal. Hal ini dapat dikarenakan flavonoid yang
terdapat dalam ekstrak kental teh hijau larut dalam etanol 70% karena memiliki
polaritas yang sama. Adanya kandungan etanol dalam ekstrak kental dapat
mempengaruhi pertumbuhan mikroba karena etanol dapat menghambat
pertumbuhan mikrobia dengan cara merusak dinding sel sehingga mengakibatkan
lisis, mengubah permeabilitas membran sitoplasma yang menyebabkan kebocoran
nutrien dari dalam sel, mendenaturasi protein sel, dan menghambat sintesis asam
nukleat (Mazni, 2008).
Dalam proses pembuatan ekstrak dihitung rendemen ekstrak sebagai
perhitungan efektivitas prosedur (efektivitas pelarut mengekstrak komponen
senyawa aktif teh hijau) (Vogel, 1996).
D. Uji Angka Lempeng Total (ALT)
Uji Angka Lempeng Total (ALT) memiliki prinsip yaitu pertumbuhan
koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasikan pada lempeng agar
dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai yaitu 35-37oC. Pengujian
dilakukan secara duplo. Setelah diinkubasi, dipilih cawan petri dari satu

16
pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 30-300 koloni. Jumlah
koloni rata-rata dari kedua cawan dihitung lalu dikalikan dengan faktor
pengencerannya. Hasil dinyatakan sebagai ALT dalam tiap gram contoh bahan
(Anonim, 2000).
Pembuatan simplisia yang tidak sesuai standar dapat mempengaruhi hasil
ALT dan AKK. Pada saat sortasi basah, simplisia harus dipisahkan dari bahan-
bahan asing seperti kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah rusak, pengotor
lainnya harus dibuang, dan terutama tanah karena tanah mengandung bermacam-
macam mikroba dalam jumlah tinggi, oleh karena itu pembersihan simplisia dari
tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal. Pencucian pada
simplisia merupakan hal penting karena air pencucian yang kotor menyebabkan
jumlah mikroba pada permukaan bahan tersebut bertambah dan air yang terdapat
pada permukaan bahan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Selain
itu, pengeringan yang kurang sempurna (kadar air lebih dari 10%) akan
menyebabkan penurunan mutu atau perusakan simplisia karena air tersisa dapat
menjadi media pertumbuhan mikroba sehingga simplisia mengandung jumlah
mikroba yang cukup tinggi (Anonim, 1985). Menurut Voigt (1994) kadar air
dalam ekstrak kental tidak lebih dari 30%. Kadar air dalam ekstrak kental juga
turut menentukan banyaknya pertumbuhan mikroba di mana kadar air yang tinggi
dalam ekstrak kental dapat menjadi media pertumbuhan mikroba.
Sebelum pengujian ALT maupun AKK dilakukan persiapan sampel yang
meliputi penanganan kemasan, homogenisasi sampel dan pengenceran.
Penanganan kemasan dilakukan dengan membersihkan bagian wadah yang akan

17
dibuka menggunakan kapas beralkohol 70% kemudian dibuka secara aseptik di
dekat nyala api bunsen sehingga sampel tidak terkontaminasi oleh mikroba dari
lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Homogenisasi merupakan
pembebasan sel-sel mikroba yang masih terlindung oleh partikel sampel ekstrak
kental teh hijau dan untuk menggiatkan kembali sel-sel mikroba yang
viabilitasnya menurun akibat proses pembuatan ekstrak (Anonim, 2006a).
Menurut Lay (1994) pengenceran dilakukan untuk mempermudah perhitungan
koloni bakteri yang tumbuh. Dengan pengenceran diharapkan seluruh koloni
bakteri yang tumbuh dalam lempeng agar dapat terhitung.
Dalam pengujian ALT ini digunakan media PCA (Plate Count Agar) yang
mengandung trypton, ekstrak yeast, glukosa, dan agar yang berguna sebagai
nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. Trypton pada media adalah asam amino yang
merupakan sumber nitrogen yang diperlukan untuk metabolisme sel mikroba.
Ekstrak yeast juga mengandung asam amino yang lengkap dan vitamin. Glukosa
diperlukan mikroba sebagai sumber karbon dan energi, sedangkan agar digunakan
sebagai pemadat dalam pembuatan media (Sumarsih, 2007). Menurut Fardiaz
(1993) dalam media agar dapat ditambahkan komponen penghambat pertumbuhan
kapang-khamir misalnya asam sorbat, propionat dan asetat sehingga koloni yang
tumbuh dalam lempeng agar hanya berupa koloni bakteri.
Jumlah bakteri aerob mesofil dapat digunakan sebagai indikator bagi mutu
mikrobiologi. Jumlah yang tinggi dari bakteri tersebut seringkali sebagai petunjuk
bahan baku yang tercemar, sanitasi yang tidak memadai, kondisi (waktu dan atau
suhu) yang tidak terkontrol selama proses produksi atau selama penyimpanan

18
ataupun kombinasi dari berbagai kondisi tersebut (Anonim, 2008). Koloni bakteri
yang tumbuh dalam penentuan ALT dapat diamati secara langsung pada lempeng
agar. Setiap koloni dapat dianggap berasal dari satu sel yang membelah menjadi
banyak sel, meskipun juga mungkin berasal lebih dari satu sel yang letaknya
berdekatan (Lay, 1994).
ALT harus ditekan sekecil mungkin. Meskipun mikroba tersebut tidak
membahayakan bagi kesehatan, misal adanya toksin yang terbentuk saat bakteri
bermultiplikasi sehingga dapat menjadi mikroba yang membahayakan kesehatan
(Anonim, 1994). Bakteri yang mungkin tumbuh dan membahayakan kesehatan di
antaranya Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli.
Salmonella typhi menyebabkan demam tifoid karena endotoksin yang
dihasilkannya. Staphylococcus aureus menyebabkan peradangan dan
pembentukan abses. E. coli biasanya menyerang organ digesti manusia dan
menyebabkan infeksi pada traktus urinarius serta meningitis pada bayi.
Keberadaan bakteri-bakteri ini dikarenakan daya tahan yang tinggi dari bakteri
terhadap kekeringan, suhu tinggi dan pendinginan (Anonim, 2008). Batas nilai
ALT ekstrak kental teh hijau yang ditetapkan Badan POM RI yaitu tidak melebihi
10 koloni/g (Anonim, 2004).
E. Uji Angka Kapang Khamir (AKK)
Uji Angka Kapang Khamir (AKK) memiliki prinsip yaitu pertumbuhan
kapang dan khamir setelah cuplikan diinokulasikan pada media yang sesuai dan
diinkubasikan pada suhu 20-25 oC. Lempeng agar yang diamati adalah lempeng di

19
mana terdapat 40-60 koloni kapang/khamir. Jumlah koloni dari kedua cawan
dihitung lalu dikalikan dengan faktor pengencerannya. Hasil dinyatakan sebagai
AKK dalam tiap gram contoh bahan (Anonim, 2000).
Kapang adalah kelompok mikroba yang tergolong dalam fungi
multiseluler yang mempunyai filamen, dan pertumbuhannya mudah dilihat karena
penampakannya yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula akan
berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul akan terbentuk berbagai warna
tergantung dari jenis kapang (Fardiaz, 1993). Dalam media agar koloni kapang
berbentuk serabut karena kapang mempunyai filamen-filamen. Khamir adalah
fungi uniseluler yang mikroskopik dan tidak membentuk percabangan permanen.
Ukuran khamir 4-20 kali lebih besar daripada ukuran bakteri yaitu berkisar antara
1-9 µm x 2-20 µm tergantung pada spesiesnya. Bentuk khamir bermacam-macam
yaitu bulat (spheroid), bulat telur (elips), seperti silinder (silindris) dan
sebagainya. Khamir tidak mempunyai flagela sehingga tidak dapat bergerak aktif
(Jutono, dkk., 1980). Dalam media agar koloni khamir mirip dengan bakteri
namun memiliki ukuran yang lebih besar dari bakteri.
Pembuatan simplisia sesuai standar akan mempengaruhi hasil ALT dan
AKK yaitu akan mengurangi pertumbuhan mikroba dalam simplisia sehingga
mutu dan keamanan simplisia terjamin (Anonim, 1985). Kadar air dalam ekstrak
kental juga turut menentukan banyaknya pertumbuhan mikroba. Kadar air yang
tinggi dalam ekstrak kental dapat menjadi media pertumbuhan mikroba. Menurut
Voigt (1994) kadar air dalam ekstrak kental tidak lebih dari 30%.

20
Pada pengujian AKK ini digunakan media SDA (Saboraud Dextrose
Agar) yang mengandung casein, dextrose dan agar yang berguna untuk
pertumbuhan kapang dan khamir. Casein dalam media merupakan protein yang
digunakan sebagai sumber nitrogen untuk metabolisme sel mikroba. Dextrose
digunakan sebagai sumber karbon dan energi serta agar digunakan sebagai
pemadat dalam pembuatan media (Sumarsih, 2007). Media agar yang digunakan
ditambah dengan kloramfenikol sebagai antibakteri sehingga dapat menjamin
bahwa yang tumbuh dalam media agar adalah kapang dan khamir.
Adanya kapang dan khamir dalam suatu bahan pangan dalam jumlah yang
besar, menunjukkan penurunan mutu obat tradisional. Di samping itu, kapang
tertentu ada yang menghasilkan zat racun (toksin) yaitu Aspergillus flavus yang
dapat menghasilkan aflatoksin (Anonim, 1994), sedangkan khamir dapat
menyebabkan pembusukan yang disertai dengan pembentukan alkohol dan gas
CO2 (Kusnandar, dkk., 2006).
Batas nilai AKK ekstrak kental teh hijau (Camellia sinensis L.) yang
ditetapkan Badan POM RI yaitu tidak melebihi 10 koloni/g (Anonim, 2004).
Jumlah ALT dan AKK yang melebihi batas yaitu 10 koloni/g dapat mengubah
karakter organoleptik ekstrak, mengubah kandungan senyawa aktif tanaman yang
terdapat dalam ekstrak, dan adanya toksin yang dihasilkan mikroba dapat
menyebabkan keracunan (Anonim, 2008). Adanya cemaran mikroba
menyebabkan mutu dan khasiat ekstrak sebagai bahan baku obat tradisional
berkurang, bahkan penggunaan ekstrak menjadi berbahaya dan justru
menimbulkan penyakit.

21
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan rancangan
penelitian deskriptif komparatif. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium
Farmakognosi Fitokimia dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
a. Variabel bebas : ekstrak kental teh hijau.
b. Variabel tergantung : nilai Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka
Kapang Khamir (AKK).
c. Variabel pengacau terkendali : media pertumbuhan yaitu Saboraoud
Dextrose Agar (SDA) dan Plate Count Agar (PCA), suhu inkubasi 35C
untuk uji ALT dan 25oC untuk uji AKK, waktu inkubasi 24-48 jam untuk
uji ALT dan 5-7 hari untuk uji AKK, asal tanaman teh dari Perkebunan
Rakyat Boyolali Jawa Tengah, umur daun teh.
d. Variabel pengacau tak terkendali : kuantitas (jumlah) etanol yang terdapat
dalam ekstrak kental teh hijau.
21

22
2. Definisi Operasional
a. Daun teh adalah daun muda yang diperoleh dari tanaman teh (Camellia
sinensis L.) Perkebunan Rakyat Boyolali dengan memetik daun pada 3
percabangan daun dari ujung ranting.
b. Daun teh hijau diperoleh dari daun teh yang telah mengalami proses
pemanasan (pengeringan).
c. Ekstrak kental teh hijau adalah hasil ekstraksi daun teh hijau secara
maserasi selama 3 hari dengan pelarut etanol 70% di mana dilakukan
penggantian pelarut setiap harinya, kemudian dikentalkan dengan
evaporator dan waterbath hingga diperoleh ekstrak yang tidak dapat
dituang.
d. Cemaran mikroba merupakan tumbuhnya mikroba seperti bakteri, kapang
dan khamir yang dapat diketahui dengan pengujian mikrobiologis.
e. Homogenisasi merupakan pembebasan sel-sel mikroba yang masih
terlindung oleh partikel sampel ekstrak kental teh hijau dan untuk
menggiatkan kembali sel-sel mikroba yang viabilitasnya menurun akibat
proses pembuatan ekstrak.
f. Angka Lempeng Total (ALT) adalah salah satu uji cemaran mikroba yang
dilakukan dengan menghitung jumlah bakteri aerob mesofil yang terdapat
dalam ekstrak kental daun teh hijau.
g. Angka Kapang Khamir (AKK) adalah salah satu uji cemaran mikroba
yang dilakukan dengan menghitung jumlah kapang dan atau khamir yang
terdapat dalam ekstrak kental daun teh hijau.

23
C. Bahan dan Alat Penelitian
1. Bahan yang digunakan :
a. Daun teh (Camellia sinensis L.) dari Perkebunan Rakyat Boyolali yang
dipetik pada bulan Februari 2009
b. Kloramfenikol 1%, PCA (Plate Count Agar) (OXOID), BPW (Pepton
Dilution Fluid) (OXOID), SDA (Saboraud Dextrose Agar) (OXOID), ASA
(Air Suling Agar 0,05%) terbuat dari 0,05 gram agar dan 100 ml air suling
(aquadest), aquadest steril, etanol 70%.
2. Alat yang digunakan :
Vacuum rotary evaporator (Janke & Kunkel Ika Labortechnik), oven
(Merck. WTC Binder), timbangan analitik (Precition Balance Model AB-204,
Mettler Toledo), inkubator (Merck. Heraeus type B5050 Amsterdam), autoclave
(model: KT-40 No.108049 Midorigaoka Japan), Microbiological Safety Cabinet
(MSC), maserator, heater, vortex, bunsen, pipet ukur, cawan petri, tabung reaksi,
waterbath.
D. Tata Cara Penelitian
1. Determinasi Tanaman
Determinasi tanaman teh dilakukan secara makroskopis di Laboratorium
Farmakognosi Fitokimia, Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta. Determinasi tanaman dilakukan dengan mencocokkan habitus
tanaman teh secara keseluruhan mulai dari akar, batang, daun, dan bunga
dengan pustaka Flora of Java (Backer dan Bakhuizen, 1963).

24
2. Pembuatan Simplisia (Anonim, 1985) dan Serbuk Daun Teh
a. Pengumpulan daun teh
Daun teh diperoleh dari Perkebunan Rakyat Boyolali yang dipanen pada bulan
Februari tahun 2009. Daun teh yang digunakan adalah daun muda yang
berasal dari 3 percabangan ujung ranting, berwarna hijau.
b. Sortasi basah
Daun dipisahkan dari bagian tanaman lain dan dari bahan asing seperti tanah,
kerikil, dan rumput liar yang ikut saat pengumpulan sehingga hanya bagian
helaian daun saja yang digunakan.
c. Pencucian
Kotoran yang menempel pada bagian daun dibersihkan dengan cara dicuci
dengan air yang bersih dan mengalir.
d. Pengeringan
Pengeringan daun teh dilakukan secara bertahap yaitu dengan cara diangin-
anginkan terlebih dahulu selama kurang lebih 24 jam kemudian dikeringkan
dengan oven pada suhu 45 0C hingga daun kering dengan ciri mudah
diremukkan. Setelah daun kering, pengeringan dihentikan dan dilanjutkan
dengan penyerbukan (Anonim, 1985). Dari proses pengeringan ini diperoleh
simplisia daun teh hijau.
e. Penyerbukan
Daun teh hijau yang telah kering dikeluarkan dari oven kemudian diserbuk
dengan menggunakan mesin penyerbuk kemudian diayak dengan ayakan
nomor 12/50. Serbuk yang baik harus melewati ayakan nomor 4/18 (Anonim,

25
1989). Ayakan nomor 12/50 merupakan konversi dari ayakan 4/18. Serbuk
yang dihasilkan haruslah homogen (lolos ayakan nomor 12/50), kering atau
tidak lembab sehingga hasil perolehan ekstrak maksimal. Ukuran serbuk yang
kecil akan memperluas permukaan serbuk yang kontak dengan cairan penyari
sehingga cairan penyari dapat masuk ke dalam sel-sel tumbuhan dan menarik
senyawa aktif tumbuhan dengan maksimal.
3. Ekstraksi Teh Hijau
Ekstraksi dibuat dengan cara maserasi menggunakan etanol 70%. Satu
bagian (250 gram) serbuk kering daun teh hijau dimasukkan ke dalam
maserator ditambah 10 bagian etanol (2500 ml), ditutup dan dibiarkan selama
24 jam. Lalu maserat dipisahkan dan proses diulangi 2 kali dengan jenis dan
jumlah pelarut yang sama (Anonim, 2004). Semua maserat dikumpulkan dan
diuapkan dengan penguap vacuum dan diangin-anginkan di atas waterbath
hingga diperoleh ekstrak kental yang tidak dapat dituang.
4. Pengujian Angka Lempeng Total (ALT) (Anonim, 2000)
a. Pembuatan pengencer BPW (Buffered Peptone Water)
Menimbang 3,45 g BPW ke dalam 230 ml aquadest, diaduk
homogen, membaginya sebanyak 9 ml ke dalam 6 tabung reaksi (5 untuk
pengenceran ekstrak dan 1 sebagai kontrol pelarut) kemudian di-autoclave
15 menit.

26
b. Pembuatan Media PCA (Plate Count Agar)
Menimbang 7,05 g PCA ke dalam 300 ml aquadest, dipanaskan
hingga larutan jernih, kemudian di-autoclave 15 menit.
c. Persiapan Sampel (Penanganan Wadah/Kemasan)
Bagian wadah/kemasan ekstrak kental teh hijau (Camellia sinensis
L.) yang akan dibuka dibersihkan dengan kapas beralkohol 70% kemudian
dibuka secara aseptis di dekat nyala api bunsen.
d. Homogenisasi Sampel (SNI 01-2897-1992) (Anonim, 1992)
Secara aseptis, menimbang 10 g ekstrak kental daun teh hijau,
memasukkannya ke dalam labu ukur 100 ml kemudian menambahkan
larutan pengencer BPW (Buffer Pepton Water) hingga tanda batas
sehingga diperoleh pengenceran 1 : 10 (10-1). Dikocok dengan baik
kemudian dilanjutkan dengan pengenceran yang diperlukan.
e. Pengenceran Sampel
Menyiapkan 5 buah tabung reaksi yang masing-masing telah diisi
dengan 9 ml pengencer BPW. Pipet 1 ml pengenceran 10 -1 dari hasil
homogenisasi pada penyiapan sampel dan dimasukkan ke dalam tabung
pertama yang telah berisi 9 ml BPW hingga diperoleh pengenceran 10-2
dan dikocok sampai homogen dengan vortex. Kemudian dibuat
pengenceran selanjutnya hingga 10-6.
f. Uji Angka Lempeng Total (ALT)
Memipet 1 ml dari masing-masing pengenceran sampel dan
dituangkan pada cawan petri. Ke dalam tiap cawan petri dituangkan ± 15

27
ml media PCA (450 +10) kemudian segera cawan petri digoyang sambil
diputar agar suspensi sampel tersebar merata kemudian dibuat duplo.
Melakukan pula uji kontrol untuk mengetahui sterilitas media dan
pengencer. Untuk uji sterilitas media dilakukan dengan menuangkan
media PCA dalam suatu cawan petri dan biarkan memadat. Sedangkan
untuk uji sterilitas pengencer dilakukan dengan cara menuangkan media
PCA dan 1 ml pengencer (BPW) lalu dibiarkan memadat.
Seluruh cawan petri diinkubasi pada suhu 350C selama 24 hingga
48 jam dengan posisi terbalik, jumlah koloni yang tumbuh diamati dan
dihitung (Anonim, 2000).
5. Pengujian Angka Kapang Khamir (AKK)
a. Pembuatan Pelarut (ASA)
Menimbang 0,075 g agar dan melarutkannya dalam 150 ml
aquadest, panaskan hingga larutan jernih. Kemudian membaginya
sebanyak 9 ml ke dalam 4 tabung reaksi (3 untuk pengenceran ekstrak dan
1 sebagai kontrol pelarut), kemudian di-autoclave selama 15 menit.
b. Pembuatan Larutan Kloramfenikol
Menimbang 1 gram kloramfenikol kemudian dilarutkan dalam 100
ml aquadest steril. Berdasarkan Parameter Standar Umum Ekstrak
Tumbuhan Obat (Anonim, 2000) seharusnya ditimbang 100 mg/liter media
namun pada penelitian ini kloramfenikol yang digunakan sebanyak 1%

28
untuk meningkatkan efektivitas dalam menghambat tumbuhnya bakteri
pada media agar.
c. Membuat Media SDA
Menimbang 16,25 gram media SDA dan melarutkannya dalam 250
ml aquadest, dipanaskan hingga jernih, kemudian di-autoclave 15 menit.
d. Persiapan Sampel (Penanganan Wadah/Kemasan)
Bagian wadah/kemasan ekstrak kental teh hijau (Camellia sinensis
L.) yang akan dibuka dibersihkan dengan kapas beralkohol 70% kemudian
dibuka secara aseptis di dekat nyala api bunsen.
e. Homogenisasi Sampel (SNI 01-2897-1992) (Anonim,1992)
Secara aseptis, menimbang 10 g ekstrak kental daun teh hijau,
memasukkannya ke dalam labu ukur 100 ml kemudian menambahkan
larutan pengencer BPW (Buffer Pepton Water) hingga tanda batas
sehingga diperoleh pengenceran 1 : 10 (10-1). Dikocok dengan baik
kemudian dilanjutkan dengan pengenceran yang diperlukan.
f. Pengenceran Sampel
Menyiapkan 3 buah tabung reaksi yang telah diisi dengan 9 ml Air
Suling Agar (ASA). Memipet 1 ml pengenceran 10-1 dari hasil
homogenisasi pada penyiapan sampel dan memasukkannya ke dalam
tabung pertama yang telah berisi 9 ml ASA hingga diperoleh pengenceran
10-2 dan dikocok sampai homogen dengan vortex. Membuat pengenceran
selanjutnya hingga 10-4.
g. Uji Angka Kapang Khamir (AKK)

29
Memipet 1 ml dari masing-masing pengenceran sampel dan
dituangkan pada cawan petri. Ke dalam tiap cawan petri dituangkan ± 15
ml media SDA (450 +10) yang sebelumnya telah ditambah dengan 1 ml
larutan kloramfenikol kemudian segera cawan petri digoyang sambil
diputar agar suspensi sampel tersebar merata kemudian dibuat duplo.
Melakukan pula uji kontrol untuk mengetahui sterilitas media dan
pengencer. Untuk uji sterilitas media dilakukan dengan menuangkan
media SDA dalam suatu cawan petri dan biarkan memadat. Sedangkan
untuk uji sterilitas pengencer dilakukan dengan cara menuangkan media
SDA dan 1 ml pengencer (ASA) lalu biarkan memadat.
Seluruh cawan petri diinkubasi secara terbalik pada suhu 250C
selama 5 hingga 7 hari. Setelah 5 hari inkubasi, dicatat jumlah koloni
Kapang/Khamir yang tumbuh. Pengamatan terakhir dilakukan pada
inkubasi hari ke-7. Koloni khamir yang tumbuh dibedakan karena
bentuknya bulat kecil-kecil putih hampir menyerupai bakteri sedangkan
koloni kapang mempunyai filamen dan berserabut seperti kapas. Lempeng
Agar yang diamati adalah lempeng di mana terdapat 40-60 koloni
Kapang/Khamir (Anonim 2000).
6. Cara perhitungan ALT dan AKK berdasarkan Parameter StandarUmum Ekstrak Tumbuhan Obat (Anonim, 2000).
a. ALT
Dipilih cawan petri dari satu pengenceran yang menunjukkan jumlah
koloni antara 30-300. Jumlah koloni rata-rata dari kedua cawan dihitung lalu

30
dikalikan dengan faktor pengencerannya. Hasil dinyatakan sebagai Angka
Lempeng Total dalam tiap gram contoh. Bila ditemui jumlah koloni kurang
dari 30 atau lebih dari 300, maka diikuti petunjuk sebagai berikut :
1) Bila hanya satu di antara kedua cawan yang menunjukkan jumlah antara
30-300 koloni, dihitung rata-rata dari kedua cawan dan dikalikan dengan
faktor pengenceran.
2) Bila pada cawan petri dari dua tingkat pengenceran yang berurutan
menunjukkan jumlah antara 30-300 koloni, maka dihitung jumlah koloni
dan dikalikan faktor pengenceran kemudian diambil angka rata-rata. Jika
pada tingkat pengenceran yang lebih tinggi didapati jumlah koloni lebih
besar dari dua kali jumlah koloni yang seharusnya, maka dipilih tingkat
pengenceran terendah (misal pada pengenceran 10-2 diperoleh 140 koloni
dan pada pengenceran 10-3 diperoleh 32 koloni, maka dipilih jumlah
koloni pada tingkat pengenceran 10-2).
3) Bila dari seluruh cawan petri tidak ada satupun yang menunjukkan jumlah
antara 30-300 koloni, maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat
pengenceran terendah dan dihitung sebagai Angka Lempeng Total
Perkiraan.
4) Bila tidak ada pertumbuhan pada semua cawan dan bukan disebabkan
karena faktor inhibitor, maka Angka Lempeng Total dilaporkan sebagai
kurang dari satu dikalikan faktor pengenceran terendah.

31
5) Bila jumlah koloni per cawan lebih dari 3000, maka cawan dengan tingkat
pengenceran tertinggi dibagi dalam beberapa sektor (2,4, atau 8). Jumlah
koloni dikalikan dengan faktor pembagi dan faktor pengencerannya, hasil
dilaporkan sebagai Angka Lempeng Total Perkiraan.
6) Bila jumlah koloni lebih dari 200 pada 1/8 bagian cawan, maka jumlah
koloni adalah 200 x 8 x faktor pengenceran. Angka Lempeng Total
Perkiraan dihitung sebagai lebih besar dari jumlah koloni yang diperoleh
b. AKK
Misalkan pada pengenceran 10-4 terdapat sebanyak 40 koloni , maka angka
kapang khamir (bila terdapat) adalah 40 x 10-4 = 40.10-4 koloni per gram
contoh. Contoh untuk beberapa kemungkinan lain yang berbeda dari
pernyataan di atas, maka cara perhitungannya mengikuti petunjuk berikut :
1) Bila hanya salah satu di antara kedua cawan petri dan pengenceran yang
sama menunjukkan jumlah antara 40-60 koloni, dihitung jumlah koloni
dari kedua cawan dan dikalikan dengan faktor pengenceran.
2) Bila pada tingkat pengenceran yang lebih tinggi didapat jumlah koloni
lebih besar dari dua kali jumlah koloni pada pengenceran di bawahnya,
maka dipilih tingkat pengenceran terendah (misal pada pengenceran 10-2
diperoleh 60 koloni dan pada pengenceran 10-3 diperoleh 20 koloni, maka
dipilih jumlah koloni pada tingkat pengenceran10-2 yaitu 60 koloni.

32
3) Bila dari seluruh cawan tidak ada satupun yang menunjukkan jumlah
antara 40-60 koloni, maka dicatat angka sebenarnya dari tingkat
pengenceran terendah dan dihitung sebagai Angka Kapang Khamir
perkiraan
4) Bila tidak ada pertumbuhan pada semua cawan dan bukan disebabkan
karena faktor inhibitor, maka Angka Kapang Khamir dilaporkan sebagai
kurang dari satu dikalikan faktor pengenceran terendah.
E. Analisis Hasil
Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif yaitu membandingkan
data yang diperoleh dari penelitian dengan persyaratan yang ditetapkan Badan
POM RI dalam Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia (Anonim, 2004)
yaitu tidak melebihi 10 koloni/g untuk Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka
Kapang Khamir (AKK).
Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa nilai ALT dan nilai AKK
dengan satuan koloni per gram bahan. Dari nilai tersebut dapat diketahui apakah
nilai ALT dan AKK ekstrak kental teh hijau tidak melebihi batas sehingga akan
diperoleh informasi bahwa bahan baku ekstrak kental teh hijau ini dapat diolah
menjadi produk obat tradisional yang aman untuk dikonsumsi berdasar nilai ALT
dan AKK.

33
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyaknya khasiat bagi kesehatan yang dimiliki teh membuat tanaman teh
banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Tanaman teh dari
Perkebunan Rakyat Boyolali memiliki mutu yang terjamin dan digunakan oleh
pabrik untuk memproduksi teh seduh, namun belum digunakan sebagai bahan
baku obat tradisional berupa ekstrak. Dalam penelitian ini diharapkan tanaman teh
dari Perkebunan Rakyat Boyolali dapat pula digunakan sebagai bahan baku obat
tradisional.
Setiap bahan baku suatu obat tradisional, baik berupa simplisia maupun
ekstrak, harus memenuhi kualitas bahan baku untuk menjamin mutu dan
keamanan penggunaan bahan baku tersebut karena kualitas bahan baku yang baik,
misalnya kandungan kimia yang seragam, kadar air, dan bebas dari cemaran akan
menjamin mutu ekstrak dan keamanan dalam penggunaan ekstrak tersebut sebagai
bahan baku obat tradisional. Standarisasi bahan baku perlu dilakukan untuk
menjaga kualitas bahan baku obat alam. Salah satu standarisasi bahan baku yang
dilakukan adalah pengujian cemaran mikroba.
Bahan baku obat tradisional tidak boleh mengalami pencemaran fisik,
kimiawi atau mikroba yang dapat merugikan kesehatan atau mempengaruhi mutu
bahan baku. Pencemaran khamir, kapang dan atau bakteri terhadap produk
meskipun sifat dan tingkatannya tidak berpengaruh langsung pada kesehatan
33

34
hendaklah dicegah sekecil mungkin sampai dengan persyaratan batas yang
berlaku (Anonim, 2005b).
Uji cemaran mikroba bertujuan memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak
boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non patogen
melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan
berbahaya bagi kesehatan karena dapat mengubah karakter organoleptik,
mengakibatkan perubahan kandungan zat aktif dalam ekstrak, dan bahkan adanya
toksin yang dihasilkan saat bakeri multiplikasi dapat menyebabkan keracunan
(Anonim, 2000).
Uji yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji Angka Lempeng Total
(ALT) dan Angka Kapang Khamir (AKK) dari ekstrak kental teh hijau sebagai
bahan baku obat tradisional. Uji ALT dan AKK merupakan metode kuantitatif
yang umum digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang terkandung dalam
sampel (Anonim, 2008) sehingga dalam penelitian ini hanya uji ALT dan AKK
yang dilakukan. Uji ALT dan AKK ini merupakan metode kuantitatif karena
dilakukan perhitungan jumlah koloni sehingga memiliki nilai tertentu dan umum
dilakukan karena merupakan pengujian awal di mana dari pengujian ALT dan
AKK kemudian dapat diisolasi secara spesifik jenis koloni bakteri patogen yang
tumbuh, misalnya Staphylococcus aureus, Salmonella typi, E. coli, dan Aspergilus
flavus. Uji dilakukan dengan cara menghitung jumlah cemaran mikroba dalam
sampel ekstrak kental teh hijau kemudian dibandingkan dengan syarat jumlah
koloni mikroba yang terdapat dalam Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat
Indonesia (Anonim, 2004) yaitu 10 koloni/g untuk bahan baku berupa ekstrak.

35
1. Determinasi Tanaman Teh
Determinasi tanaman yaitu membandingkan suatu tumbuhan yang akan
diuji dengan satu tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya (dicocokkan atau
dipersamakan) (Anonim, 2006b). Determinasi tanaman teh (Camellia sinensis L.)
dilakukan untuk memastikan kebenaran tanaman yang akan digunakan dalam
penelitian. Determinasi tanaman dilakukan secara makroskopis dengan
mencocokkan tanda-tanda serta ciri-ciri yang ada pada tanaman dengan kunci
determinasi yang ada dalam panduan determinasi tumbuhan Flora of Java
(Backer dan Bakhuizen, 1963).
Tanaman teh diperoleh dari Perkebunan Rakyat Boyolali. Daerah Boyolali
merupakan tempat tumbuh yang cocok bagi tanaman teh. Selain itu teh yang
ditanam memiliki spesies yang sama dan digunakan oleh pabrik untuk
memproduksi teh seduh sehingga mutu tanaman teh terjamin. Teh merupakan
komoditas primer yang menjadi unggulan dari Perkebunan Rakyat Boyolali
sehingga mudah diperoleh dan lokasi perkebunan yang dekat dengan lokasi
penelitian mempermudah penelitian. Daun teh yang diperoleh dari Perkebunan
Rakyat Boyolali memiliki warna hijau, daun tunggal, bertangkai pendek dengan
letak berseling, helai daun kaku seperti kulit tipis, bentuk elips memanjang, ujung
dan pangkal runcing, tepi bergerigi halus, dan pertulangan menyirip. Foto daun
teh tersebut terdapat pada lampiran 3 (Gambar 2). Berdasarkan determinasi
tanaman yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanaman yang
digunakan benar-benar tanaman teh (C. sinensis L.). Hasil determinasi terlampir
pada lampiran 1.

36
2. Pembuatan Simplisia dan Serbuk Daun Teh
Pembuatan simplisia teh yang dilakukan pada penelitian telah didasarkan
pada Cara Pembuatan Simplisia (Anonim, 1985) sehingga menghasilkan simplisia
yang terstandar. Pembuatan simplisia ini meliputi pengumpulan daun teh, sortasi
basah, pencucian, perajangan, dan pengeringan. Dari hasil pengeringan akan
diperoleh simplisia daun teh hijau. Setelah dilakukan pembuatan simplisia
kemudian diserbuk sehingga menghasilkan serbuk simplisia daun teh hijau.
Penyerbukan dan serbuk yang diperoleh telah sesuai dengan Materia Medika
Indonesia (Anonim, 1989), di mana serbuk yang baik harus melewati ayakan
nomor 4/18.
Pembuatan simplisia teh yang tidak sesuai standar dapat memperbanyak
jumlah mikroba yang tumbuh sehingga memungkinkan tingginya nilai ALT dan
AKK pada ekstrak kental teh hijau. Pada saat sortasi basah, simplisia harus
dipisahkan dari bahan-bahan asing seperti kerikil, rumput, batang, daun, akar yang
telah rusak, pengotor lainnya harus dibuang, dan terutama tanah karena tanah
mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah tinggi, oleh karena itu
pembersihan simplisia dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba
awal. Pencucian pada simplisia merupakan hal penting karena air pencucian yang
kotor menyebabkan jumlah mikroba pada permukaan bahan tersebut bertambah
dan air yang terdapat pada permukaan bahan tersebut dapat mempercepat
pertumbuhan mikroba. Selain itu, pengeringan yang kurang sempurna (kadar air
lebih dari 10%) akan menyebabkan penurunan mutu atau perusakan simplisia
karena air tersisa dapat menjadi media pertumbuhan mikroba sehingga simplisia

37
mengandung jumlah mikroba yang cukup tinggi (Anonim, 1985). Menurut Voigt
(1994) kadar air dalam ekstrak kental tidak lebih dari 30%. Kadar air dalam
ekstrak kental juga turut menentukan banyaknya pertumbuhan mikroba di mana
kadar air yang tinggi dalam ekstrak kental dapat menjadi media pertumbuhan
mikroba.
Tanaman teh yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari
Perkebunan Boyolali. Dalam pengumpulan daun teh, bagian tanaman yang
digunakan adalah bagian daun muda yaitu 3 percabangan daun yang paling ujung
karena pada bagian daun muda daun teh memiliki kandungan senyawa aktif yang
tinggi. Daun teh hijau yang diperoleh kemudian dipisahkan dari bahan-bahan
pengotor yang tercampur di dalamnya seperti tanah, kerikil, rumput, daun yang
rusak. Proses ini dinamakan sortasi basah. Daun kemudian dicuci dengan air
mengalir agar tanah dan kotoran lain yang melekat pada tanaman dapat terlepas
serta tidak menempel lagi. Dalam penelitian ini, daun teh tidak mengalami proses
perajangan karena sudah cukup tipis.
Pengeringan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar air hingga
kurang dari 10% sehingga mencegah kapang ataupun fungi dan menghentikan
reaksi enzimatik, sehingga dapat mencegah penurunan mutu dan perusakan
simplisia. Dengan demikian, maka simplisia menjadi tidak mudah rusak dan dapat
disimpan dalam waktu yang lebih lama (Anonim, 1985). Daun dikeringkan
dengan dua tahap, pertama daun diangin-anginkan terlebih dahulu yang bertujuan
untuk mengurangi kandungan air, kemudian tahap kedua dilakukan pengeringan
dengan suhu yang lebih tinggi yaitu menggunakan oven dengan suhu 45 0C.

38
Pengeringan menggunakan oven umumnya mendapatkan simplisia dengan mutu
lebih baik karena pengeringan lebih merata dan waktu yang diperlukan relatif
cepat dan tidak tergantung cuaca. Selain itu kadar air simplisia juga dapat ditekan
serendah mungkin sehingga menekan kontaminasi mikroba (Katno, 2008).
Dengan pengeringan dua tahap ini proses pengeringan menjadi lebih optimal
karena dengan dua tahap pengeringan, kadar air dalam simplisia dapat lebih cepat
dan banyak berkurang. Dalam penelitian ini proses pengeringan dihentikan
apabila daun sudah dapat diremukkan dengan tangan karena tidak dilakukan
pengukuran kadar air yang terkandung dalam daun teh hijau. Daun yang kadar
airnya masih tinggi akan lebih sulit diremukkan dan terasa lembab. Apabila daun
mudah diremukkan dan sudah tidak terasa lembab, maka kemungkinan kadar
airnya sudah kurang dari 10% sehingga proses pengeringan sudah dapat
dihentikan.
Daun teh yang telah kering dikeluarkan dari oven kemudian diserbuk
dengan menggunakan mesin penyerbuk. Tujuan dari pembuatan serbuk adalah
untuk memperkecil ukuran partikel sehingga akan memperluas permukaan
partikel yang kontak dengan cairan penyari sehingga diharapkan penyarian akan
lebih efektif karena dapat mempermudah penarikan senyawa aktif oleh cairan
penyari. Pembuatan serbuk dilakukan dengan menggunakan alat penyerbuk
kemudian serbuk diayak dengan ayakan nomor 12/50 sehingga diperoleh serbuk
dengan derajat halus 12/50. Serbuk yang baik harus melewati ayakan nomor 4/18
(Anonim, 1989). Ayakan 12/50 merupakan konversi dari ayakan nomor 4/18
sehingga memiliki ukuran serbuk yang sama. Ayakan 12/50 memiliki arti bahwa

39
semua serbuk dapat melalui ayakan no. 12 dan tidak lebih dari 40% melalui
pengayak dengan no. 50. Serbuk daun teh hijau berhasil melewati ayakan 12/50
sehingga memiliki derajat halus yang baik.
3. Ekstraksi Teh Hijau
Ekstrak kental teh hijau diperoleh dengan mengekstraksi serbuk daun teh
hijau secara maserasi dengan penyari etanol 70%. Ekstraksi secara maserasi ini
dilakukan sesuai standar yang terdapat dalam Monografi Ekstrak
Tumbuhan Obat Indonesia (Anonim, 2004) yaitu satu bagian serbuk kering
dimasukkan ke dalam maserator dan ditambah dengan sepuluh bagian cairan
penyari. Pemilihan metode maserasi dikarenakan cara pengerjaan dan peralatan
yang digunakan pada metode maserasi sederhana dan mudah dilakukan. Selain itu
metode maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung
komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung
benzoin, tiraks dan lilin sehingga sesuai digunakan untuk mengekstraksi daun teh
karena kandungan kimia daun teh mudah larut dalam cairan penyari dan daun teh
tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin (Anonim, 1986). Pemilihan cairan
penyari untuk ekstrak sebaiknya sesuai dengan zat aktif yang berkhasiat, dalam
arti dapat memisahkan zat aktif tersebut dari senyawa lainnya dalam bahan
sehingga ekstrak mengandung sebagian besar senyawa aktif berkhasiat yang
diinginkan (Anonim, 2000). Penggunaan etanol 70% dalam ekstraksi teh hijau ini
dikarenakan kandungan kimia utama dari daun teh, yaitu flavonoid larut dalam
etanol.

40
Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan
penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar, di mana cairan penyari
akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya
perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang
konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan
konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi
keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama
proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari.
Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk
simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan
konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam dengan di luar sel
(Anonim, 1986). Penggantian cairan dilakukan untuk memperoleh hasil ekstraksi
yang maksimal dengan menghindari terjadinya kejenuhan cairan penyari. Endapan
yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan dengan vaccum evaporator
dan diangin-anginkan di atas waterbath hingga diperoleh ekstrak kental yang tidak
dapat dituang. Ekstrak yang dihasilkan memiliki warna cokelat kehitaman, berbau
khas dan rasa agak kelat, dan memiliki konsistensi kental (ekstrak tidak dapat
dituang). Foto ekstrak kental teh hijau terdapat pada lampiran 4.
Kadar etanol dalam ekstrak diasumsikan telah menguap dengan adanya
pemanasan dengan suhu kurang lebih 58oC. Namun tidak menutup kemungkinan
adanya etanol yang masih tersisa dalam ekstrak. Adanya sejumlah etanol yang
masih tersisa dalam ekstrak dapat mempengaruhi jumlah cemaran mikroba di
mana etanol dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Dari hasil ekstraksi 250

41
gram serbuk teh hijau diperoleh ekstrak kental teh hijau sebesar 58,63 gram
sehingga diperoleh rendemen ekstrak 23,45 %b/b.
4. Pengujian Angka Lempeng Total (ALT)
Pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dilakukan dengan
menginokulasikan sampel ekstrak kental teh hijau yang telah mengalami
homogenisasi dan pengenceran pada media lempeng agar dengan cara tuang (pour
plate) kemudian diinkubasi pada suhu 35-37oC. Sampel berupa ekstrak kental
daun teh hijau dihomogenisasi menggunakan larutan pengencer BPW (Buffered
Pepton Water). BPW mengandung peptone, sodium chloride, disodium
phosphate, dan potassium dihydrogen phosphate yang berfungsi sebagai media
pra pengayaan dan juga menyembuhkan atau menguatkan sel bakteri yang sangat
lemah atau sakit yang disebabkan proses pembuatan ekstrak sehingga bakteri
dapat tetap tumbuh dalam media pra pengayaan tersebut sebelum dilakukan
pengujian lebih lanjut (Sumarsih, 2007). Homogenisasi sampel memiliki prinsip
membebaskan sel-sel bakteri yang masih terlindung oleh partikel sampel dan
untuk menggiatkan kembali sel-sel bakteri yang mungkin viabilitasnya menurun
karena kondisi yang kurang memungkinkan selama proses pembuatan ekstrak
(Anonim, 2006a). Pengenceran sampel dilakukan dari pengenceran 10-1 hingga
10-6 yang bertujuan membantu untuk memperoleh perhitungan jumlah yang benar
karena seluruh koloni bakteri yang tumbuh dalam lempeng agar dapat terhitung.
Jumlah koloni bakteri yang terdapat dalam lempeng agar mencerminkan

42
pengenceran yang dilakukan (Lay, 1994), di mana makin tinggi pengenceran
maka jumlah mikroba yang diperoleh seharusnya semakin sedikit.
Dalam penelitian ini digunakan media PCA (Plate Count Agar) yang
mengandung trypton, ekstrak yeast, glukosa, dan agar yang berguna sebagai
nutrisi untuk pertumbuhan bakteri. Setelah media biakan disiapkan, media ini
harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan autoklaf dengan suhu 121oC
selama 20 menit karena bila media biakan yang disiapkan tidak disterilkan dan
dibiarkan selama beberapa hari, mikroba pencemar (mikroba kontaminan) akan
tumbuh dan menyebabkan kekeruhan media. Mikroba pencemar menyebabkan
tidak diketahui apakah perubahan yang terjadi dalam media disebabkan mikroba
yang ditumbuhkan atau mikroba pencemar (mikroba kontaminan) (Lay, 1994).
Setelah sampel diencerkan dan ditanam dalam media PCA, sampel diinkubasi
terbalik selama 24-48 jam pada suhu 35-37oC. Inkubasi terbalik dilakukan agar
uap air yang terbentuk selama inkubasi tidak menetes ke media biakan karena
akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba dan mempersulit pengamatan.
Tabel I. Angka Lempeng Total (ALT) Ekstrak Kental Teh Hijau WaktuInkubasi 24 Jam
Pengenceran Jumlah koloniReplikasi 1
Jumlah koloniReplikasi 2
Rata-ratajumlahkoloni
ALT(koloni/gekstrak)
Kontrol pelarut 0 0 0Kontrol media 0 0 010-1 0 0 010-2 0 0 010-3 0 0 0
10-4 0 5 2,510-5 1 0 0,510-6 0 0 0
<1 x 10

43
Tabel I menunjukkan bahwa pada cawan petri (1) dan (2) pengenceran 10-1
tidak terdapat adanya koloni bakteri. Hal yang sama juga terjadi pada pengenceran
10-2, 10-3, dan 10-6. Sedangkan pada pengenceran 10-4 terdapat pertumbuhan
bakteri sebanyak 5 koloni pada cawan petri (2) dan pada 10-5 hanya terdapat 1
koloni pada cawan petri (1). Berdasarkan Parameter Standar Umum Ekstrak
Tumbuhan Obat (Anonim, 2000) apabila dari seluruh cawan petri tidak ada
satupun yang menunjukkan jumlah antara 30-300 koloni, maka nilai ALT dicatat
angka sebenarnya dari tingkat pengenceran terendah dan dihitung sebagai Angka
Lempeng Total Perkiraan. Foto pengamatan ALT ekstrak kental teh hijau waktu
inkubasi 24 jam terdapat pada lampiran 6.
Dalam penelitian ini pengenceran yang digunakan sebagai acuan
perhitungan ALT yaitu pengenceran 10-1 karena merupakan pengenceran terendah
sedangkan pengenceran 10-2 hingga 10-6 merupakan hasil pengenceran dari
pengenceran 10-1. Rata-rata jumlah koloni dari pengenceran 10-1 yaitu 0 sehingga
diperoleh nilai ALT ekstrak kental teh hijau pada waktu inkubasi 24 jam sebesar
<1 x 10-1 yaitu kurang dari 10 koloni/gram. Batas nilai ALT ekstrak kental teh
hijau yang ditetapkan Badan POM RI yaitu tidak melebihi 10 koloni/g (Anonim,
2004). Sehingga diketahui bahwa nilai ALT ekstrak kental teh hijau tidak
melebihi batas yang ditetapkan.
Adanya koloni bakteri pada pengenceran 10-4 dan 10-5 dimungkinkan
merupakan kontaminasi atau adanya cemaran bakteri yang terjadi pada saat
pengujian ALT baik cemaran dari pelarut yang digunakan maupun cemaran
karena pengerjaan yang kurang aseptis. Untuk mengetahui sterilitas media dan

44
pelarut serta mengetahui keaseptisan dalam bekerja digunakan kontrol media
(PCA) dan kontrol pelarut (BPW). Pada pengamatan inkubasi 24 jam
menunjukkan tidak adanya koloni pada kontrol pelarut dan kontrol media
sehingga koloni bakteri yang terdapat pada pengenceran 10-4 dan 10-5 bukan
berasal dari pelarut maupun cara kerja pada saat pengujian ALT melainkan
berasal dari ekstrak kental teh hijau tersebut. Koloni bakteri tersebut hanya
muncul pada pengenceran 10-4 dan 10-5 sedangkan pada pengenceran 10-1 hingga
10-3 dan 10-6 tidak muncul koloni, hal ini mungkin terjadi karena adanya
kandungan etanol pada ekstrak kental teh hijau. Kandungan etanol yang terdapat
dalam ekstrak akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba karena etanol memiliki
sifat antimikroba. Kemungkinan banyaknya etanol pada pengenceran 10-1 hingga
10-3 lebih besar dibandingkan pengenceran 10-4 dan 10-5 karena semakin tinggi
pengenceran maka jumlah etanol yang terdapat dalam sampel ekstrak kental teh
hijau semakin berkurang sehingga pada pengenceran 10-4 dan 10-5 yang memiliki
jumlah etanol lebih sedikit, maka sifat antimikroba dalam sampel berkurang dan
mikroba lebih mudah tumbuh dalam sampel.
Kandungan etanol mungkin masih terdapat dalam ekstrak kental karena
pada ekstrak kental seluruh perlarut diasumsikan telah diuapkan dengan
pemanasan pada suhu sekitar 58oC dengan evaporator dan kemudian dikentalkan
di atas waterbath dengan suhu sekitar 58-60oC. Etanol memiliki titik didih sekitar
78oC sehingga dimungkinkan kandungan etanol masih terdapat dalam ekstrak.
Pemanasan dalam proses ekstraksi ini tidak melebihi 60oC karena dikhawatirkan
dapat merusak kandungan zat aktif dalam ekstrak. Kemungkinan adanya

45
kandungan etanol dalam ekstrak ini juga terlihat pada tabel II, yaitu adanya
pertumbuhan koloni bakteri pada pengenceran 10-6 yang meningkat dari
pengenceran sebelumnya.
Tabel II. Angka Lempeng Total (ALT) Ekstrak Kental Teh Hijau WaktuInkubasi 48 Jam
Pengenceran Jumlah koloniReplikasi 1
Jumlah koloniReplikasi 2
Rata-ratajumlahkoloni
ALT(koloni/gbahan)
Kontrol pelarut 0 0 0Kontrol media 0 0 010-1 0 0 010-2 0 0 010-3 0 0 010-4 0 7 3,510-5 1 0 0,510-6 24 0 12
<1 x 10
Pada tabel II terlihat adanya peningkatan jumlah koloni bakteri, yaitu 7
koloni pada pengenceran 10-4 pada cawan petri (2), 1 koloni pada cawan petri (1)
pengenceran 10-5, dan 24 koloni pada cawan petri (1) pengenceran 10-6. Adanya
kandungan etanol yang lebih sedikit pada pengenceran 10-6 menyebabkan mikroba
lebih mudah tumbuh pada lempeng agar karena tidak adanya penghambatan dari
etanol sehingga mikroba yang tumbuh juga lebih banyak. Foto pengamatan ALT
ekstrak kental teh hijau waktu inkubasi 48 jam terdapat pada lampiran 7.
Dalam pengujian diperlukan keaseptisan sehingga akan mencegah
tumbuhnya kontaminasi bakteri yang bukan berasal dari ekstrak karena dapat
membuat hasil penelitian menjadi bias. Hal ini dapat dilakukan dengan
menggunakan Microbiological Safety Cabinet (MSC) yang dilakukan di dalam
ruang tertutup dengan tekanan udara yang lebih positif daripada tekanan udara di
luar ruangan sehingga akan meminimalkan kontaminasi mikroba dari lingkungan.

46
5. Pengujian Angka Kapang Khamir (AKK)
Pengujian Angka Kapang Khamir (AKK) dilakukan dengan
menginokulasikan sampel ekstrak kental teh hijau yang telah dihomogenisasi dan
diencerkan pada media agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada 20-25 oC.
Sampel berupa ekstrak kental daun teh hijau dihomogenisasi dengan Air
Suling Agar 0,05% (ASA) yang berfungsi sebagai media pra pengayaan yang
terbuat dari 0,05 gram agar dalam 100 ml aquadest, kemudian dilakukan
pengenceran sampel. Menurut Lay (1994) pengenceran sampel bertujuan untuk
membantu dalam perhitungan jumlah koloni yang benar karena jika pada
pengenceran 10-1 jumlah koloni terlalu padat, dengan adanya pengenceran
diharapkan jumlah koloni pada pengenceran selanjutnya dapat dihitung.
Media agar yang digunakan dalam AKK yaitu SDA (Saboraud Dextrose
Agar) yang mengandung casein, dextrose dan agar yang berguna untuk
pertumbuhan kapang dan khamir. Dalam media agar juga ditambahkan
kloramfenikol sebagai agen antimikroba yang menghambat pertumbuhan bakteri
sehingga pengamatan pertumbuhan kapang dan khamir lebih mudah untuk
dilakukan. Kloramfenikol merupakan suatu antibiotik yang memiliki sifat
bakteriostatik yaitu menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara menghambat
pertumbuhan bakteri dengan cara bergabung dengan subunit ribosom 50S
sehingga mengganggu sintesis protein dan menghambat pengikatan asam amino
baru pada rantai polipeptida oleh enzim peptidiltransferase (Mazni, 2008).
Kloramfenikol ditambahkan 1 ml dalam 250 ml media. Pemberian kloramfenikol
ini sudah cukup efektif karena pada pengamatan tidak ditemukan adanya koloni

47
bakteri. Setelah media biakan disiapkan, media harus disterilkan terlebih dahulu
menggunakan autoklaf dengan suhu 121oC selama 20 menit untuk menghindari
terjadinya bias karena mikroba pencemar.
Setelah sampel diencerkan dan ditanam dalam media SDA, sampel
diinkubasi terbalik selama 7 hari pada suhu 20-25oC kemudian dihitung koloni
kapang dan khamir yang tumbuh pada hari ke 5 hingga ke 7. Inkubasi terbalik
dilakukan agar uap air yang terbentuk selama inkubasi tidak menetes ke media
biakan dan mempengaruhi pertumbuhan mikroba.
Tabel III. Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau WaktuInkubasi 5 Hari
Pengenceran Jumlah koloniReplikasi 1
Jumlah koloniReplikasi 2
Jumlahkoloni
AKK(koloni/gekstrak)
Kontrol pelarut 0 0 0Kontrol media 0 0 010-1 0 0 010-2 0 0 010-3 1 0 110-4 1 1 2
<1 x 10
Pada tabel III menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya koloni kapang
maupun khamir pada cawan petri (1) dan (2) pengenceran 10-1, 10-2. Sedangkan
pada pengenceran 10-3 terdapat pertumbuhan bakteri 1 koloni kapang pada cawan
petri (1) dan pada pengenceran 10-4 terdapat 1 koloni kapang masing-masing pada
cawan petri. Kapang yang diperoleh dalam pengamatan tampak berserabut dengan
warna tepi putih dan abu-abu kehitaman pada bagian tengah koloni, hal ini sesuai
dengan Fardiaz (1993) di mana kapang tergolong dalam fungi multiseluler yang
mempunyai filamen, dan pertumbuhannya mudah dilihat karena penampakannya

48
yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula akan berwarna putih,
tetapi jika spora telah timbul akan terbentuk berbagai warna tergantung dari jenis
kapang. Foto pengamatan AKK ekstrak kental teh hijau waktu inkubasi 5 hari
terdapat pada lampiran 8.
Tabel IV. Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau WaktuInkubasi 6 Hari
Pengenceran Jumlah koloniReplikasi 1
Jumlah koloniReplikasi 2
Jumlahkoloni
AKK(koloni/gekstrak)
Kontrol pelarut 0 0 0Kontrol media 0 1 110-1 0 0 010-2 0 0 010-3 1 0 110-4 1 1 2
<1 x 10
Tabel IV menunjukkan bahwa pada waktu inkubasi 6 hari tidak ada
perubahan jumlah koloni kapang/khamir pada pengenceran 10-1, 10-2, 10-3, 10-4
yaitu tidak adanya koloni kapang/khamir pada cawan petri (1) dan (2)
pengenceran 10-1, 10-2. Dan pada pengenceran 10-3 terdapat pertumbuhan kapang
1 koloni pada cawan petri (1) dan pada pengenceran 10-4 terdapat 1 koloni kapang
masing-masing pada cawan petri (1) dan (2). Namun pada kontrol media terdapat
pertumbuhan 1 koloni khamir pada cawan petri (2). Khamir yang terdapat dalam
pengamatan tampak seperti bakteri, berwarna putih dengan bentuk bulat namun
memiliki ukuran yang lebih besar dibanding bakteri, hal ini sesuai dengan Jutono,
dkk (1980) yaitu khamir merupakan fungi uniseluler yang mikroskopik dan tidak
membentuk percabangan permanen. Ukuran khamir 4-20 kali lebih besar daripada
ukuran bakteri. Bentuk khamir bermacam-macam yaitu bulat (spheroid), bulat

49
telur (elips), seperti silinder (silindris) dan sebagainya. Foto pengamatan AKK
ekstrak kental teh hijau waktu inkubasi 6 hari terdapat pada lampiran 9.
Tabel V. Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh Hijau WaktuInkubasi 7 Hari
Pengenceran Jumlah koloniReplikasi 1
Jumlah koloniReplikasi 2
Jumlahkoloni
AKK(koloni/gekstrak)
Kontrol pelarut 0 0 0Kontrol media 0 1 110-1 0 0 010-2 0 0 010-3 1 0 110-4 1 1 2
<1 x 10
Pada tabel V menunjukkan bahwa pengamatan pada waktu inkubasi 7 hari
tidak berbeda dengan waktu inkubasi 6 hari. Tidak ada perubahan jumlah koloni
kapang pada pengenceran 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 dan adanya 1 koloni khamir pada
kontrol media. Foto pengamatan AKK ekstrak kental teh hijau waktu inkubasi 7
hari terdapat pada lampiran 10.
Berdasarkan Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat (Anonim,
2000) apabila dari seluruh cawan petri tidak ada satupun yang menunjukkan
jumlah antara 40-60 koloni, maka nilai AKK dicatat angka sebenarnya dari
tingkat pengenceran terendah dan dihitung sebagai Angka Kapang Khamir
Perkiraan.
Dalam penelitian ini pengenceran terendah adalah pengenceran 10-1. Pada
pengenceran 10-1 waktu inkubasi 5 hingga 7 hari memiliki jumlah yang sama,
yaitu 0. Sehingga diperoleh nilai AKK ekstrak kental teh hijau pada waktu
inkubasi 5 hingga 7 hari sebesar < 1x 10-1 yaitu kurang dari 10 koloni/gram. Batas

50
nilai AKK ekstrak kental teh hijau yang ditetapkan Badan POM RI yaitu tidak
melebihi 10 koloni/g (Anonim, 2004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa AKK
dari ekstrak kental teh hijau tidak melebihi batas yang ditetapkan.
Adanya koloni bakteri pada pengenceran 10-3 dan 10-4 pada waktu
inkubasi 5, 6, dan 7 hari dimungkinkan merupakan kontaminasi atau adanya
cemaran bakteri yang terjadi pada saat pengujian AKK baik cemaran dari pelarut
yang digunakan maupun cemaran karena pengerjaan yang kurang aseptis. Untuk
mengetahui keaseptisan dalam bekerja digunakan kontrol media (SDA) sedangkan
untuk mengetahui adanya cemaran dari perlarut digunakan kontrol pelarut (ASA).
Pada pengamatan inkubasi 5 hari menunjukkan tidak adanya koloni pada kontrol
pelarut dan kontrol media sehingga koloni bakteri yang terdapat pada pengenceran
10-3 dan 10-4 bukan berasal dari pelarut maupun cara kerja pada saat pengujian
AKK melainkan berasal dari ekstrak kental teh hijau tersebut. Koloni bakteri
tersebut hanya muncul pada pengenceran 10-4 dan 10-5, hal ini mungkin terjadi
karena adanya kandungan etanol pada ekstrak kental teh hijau. Kandungan etanol
yang terdapat dalam ekstrak akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba karena
etanol memiliki sifat antimikroba. Kemungkinan jumlah etanol pada pengenceran
10-1 dan 10-2 lebih besar dibandingkan pengenceran 10-3 dan 10-4 karena semakin
tinggi pengenceran maka jumlah etanol semakin berkurang sehingga
kapang/khamir dapat tumbuh pada pengenceran 10-3 dan 10-4. Kandungan etanol
mungkin masih terdapat dalam ekstrak kental karena pada proses ekstraksi seluruh
pelarut diasumsikan telah diuapkan dengan pemanasan pada suhu sekitar 58oC
dengan evaporator dan kemudian dikentalkan di atas waterbath dengan suhu

51
sekitar 58-60oC namun karena etanol memiliki titik didih sekitar 78oC sehingga
dimungkinkan kandungan etanol masih terdapat dalam ekstrak.
Pada pengamatan AKK inkubasi hari ke 6 dan ke 7 menunjukkan adanya
pertumbuhan 1 koloni khamir pada kontrol media. Karena pada media telah
ditambahkan kloramfenikol sebagai antibakteri sehingga koloni yang tumbuh
pada media dapat dipastikan berupa khamir. Adanya koloni khamir pada kontrol
media menunjukkan adanya kontaminasi atau cemaran pada media dan kurangnya
keaseptisan dalam bekerja. Walaupun ada kontaminasi khamir dalam uji AKK ini,
namun dalam pengamatan tidak menunjukkan adanya perubahan jumlah koloni
dalam setiap pengenceran sampel dari waktu inkubasi 5 hingga 7 hari sehingga
kontaminasi khamir pada media tidak berpengaruh pada jumlah koloni kapang
yang tumbuh.
Nilai ALT dan AKK yang terdapat dalam ekstrak kental daun teh hijau
memenuhi batas persyaratan yang ditetapkan Badan POM RI dalam Monografi
Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia yaitu tidak melebihi 10 koloni/g untuk ALT
dan tidak melebihi 10 koloni/g untuk AKK. Sehingga dapat dinyatakan bahwa
ekstrak kental daun teh hijau dari Perkebunan Rakyat Boyolali berpotensi dan
dapat diolah menjadi produk obat tradisional yang aman untuk dikonsumsi dari
segi ALT dan AKK.
Selain pengujian ALT dan AKK, ekstrak juga harus memenuhi parameter
standarisasi lainya untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat ekstrak secara
menyeluruh yaitu parameter standar umum berupa berat kering dan berat jenis,
kadar air, kadar abu, kadar sisa pelarut, residu pestisida, uji batas logam berat,

52
kadar sari larut dalam pelarut tertentu, kadar terlarut dengan spektrofotometer,
sidik jari kromatogram, kadar total golongan zat kandungan dan kadar zat aktif
atau zat identitas (Anonim, 1999) dan parameter standar khusus ekstrak, meliputi
penetapan organoleptik ekstrak (meliputi bentuk, warna, bau dan rasa) dan
penetapan kadar senyawa terlarut dalam pelarut tertentu (meliputi kadar senyawa
yang larut dalam air dan kadar senyawa yang larut dalam etanol) (Anonim, 2004).
Penelitian lain mengenai standarisasi ekstrak selain dari segi mikrobiologi telah
dilakukan, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada aspek mikrobiologi,
khususnya ALT dan AKK.
Proses dan metode pembuatan ekstrak kental teh hijau ini cukup baik
dalam menghasilkan bahan baku berupa ekstrak kental teh hijau yang memenuhi
kualitas dari segi ALT dan AKK. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut
mengenai uji cemaran mikroba selain ALT dan AKK misalnya uji cemaran
mikroba patogen sehingga dapat diketahui pula keamanan penggunaan ekstrak
kental teh hijau dari Perkebunan Rakyat Boyolali sebagai bahan baku obat
tradisional dari segi mikroba patogennya.

53
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Nilai ALT dan AKK yang terdapat dalam ekstrak kental daun teh hijau
dari Perkebunan Rakyat Boyolali yaitu kurang dari 10 koloni/g.
2. Nilai ALT dan AKK yang terdapat dalam ekstrak kental daun teh hijau
tidak melebihi batas yang ditetapkan dalam Monografi Ekstrak Tumbuhan
Obat, yaitu 10 koloni/g sehingga ekstrak kental teh hijau dari Perkebunan
Rakyat Boyolali dapat diolah menjadi produk Obat tradisional yang aman
untuk dikonsumsi berdasarkan nilai ALT dan AKK.
B. SARAN
Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji mikroba patogen
untuk mengetahui keamanan penggunaan ekstrak kental teh hijau dari Perkebunan
Rakyat Boyolali sebagai bahan baku obat tradisional dari segi mikroba
patogennya.
53

54
DAFTAR PUSTAKA
Anief, 2005, Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik, 168-169, Gadjah MadaUniversity Press, Yogyakarta
Anonim, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, 4, Departemen Kesehatan RI,Jakarta
Anonim, 1985, Cara Pembuatan Simplisia, 4, 7-10, Departemen Kesehatan RI,Jakarta
Anonim, 1986, Sediaan Galenik, 1-16, Departemen Kesehatan RepublikIndonesia, Jakarta
Anonim, 1989, Materia Medika Indonesia, Jilid V, xxix, Departemen KesehatanRI, Jakarta
Anonim, 1992, Cara Uji Cemaran Mikroba, SNI (SNI 01-2897-1992), 4, 36,Jakarta
Anonim, 1994, Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo.661/MENKES/SK/VII/1994 tentang Persyaratan Obat tradisional,http://husinrm.files.wordpress.com/2008/02/persyaratan-_ot_edit.doc,diakses 18 Maret 2009
Anonim, 1999, dalam Hafid A.F., 2000, Penetapan Parameter Standar EkstrakEtanol Temulawak sebagai Bahan Baku Kapsul Temulawak,http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-res-2000-hafid2c-397-curcumma&q=uji+cemaran+mikroba, diakses tanggal 18 Maret 2009
Anonim, 2000, Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat, CetakanPertama, 24-25, 28-29, Departemen Kesehatan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal POM, Jakarta
Anonim, 2004, Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia, 1, BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta
Anonim, 2005a, Lampiran Pedoman Cara Pembuatan Obat tradisional yangBaik,http://www.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/LAMP_CPOTB.pdf,diakses tanggal, 18 Maret 2009
Anonim, 2005b, Standarisasi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia, Salah SatuTahapan Penting Dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia,

55
http://perpustakaan.pom.go.id/KoleksiLainnya/InfoPOM/0405.pdf, diaksestanggal, 30 September 2009
Anonim, 2006a, Metode Analisis PPOMN, 1, 5, Pusat Pengujian Obat danMakanan Nasional (Badan POM), Jakarta
Anonim, 2006b, Buku Ajar Taksonomi Tumbuhan Tinggi, http://e-course.usu.ac.id/content/biologi/taksonomi/textbook.pdf, diakses tanggal 28Desember 2009
Sumarsih, 2007, Nutrisi dan Medium Kultur Mikroba,http://sumarsih07.files.wordpress.com/2008/11/nutrisi-dan-medium-kultur-mikroba.pdf, diakses tanggal 28 Desember 2009
Anonim, 2008, Pengujian Mikrobiologi Pangan,http://perpustakaan.pom.go.id/KoleksiLainnya/InfoPOM/0208.pdf, diaksestanggal 20 Mei 2009
Ansel H.C., 1989, Introduction to Pharmaceutical Dosage Form, 164-165, Lea &Febiger, Philadelphia, USA
Backer, C.A and R.C. Bakhuizen Van Den Brink Jr, 1963, Flora of Java, Vol 1,3-6,29-34, 47, 318-320, N.V.P., Noordhoff, Groningen, The Netherlands
Dalimartha, S., 1999, Atlas Tumbuhan Obat Indonesia, 50-52, Trubus Agriwidya,Jakarta
Fardiaz, S. , 1993, Analisis Mikrobiologi Pangan, 182, P.T. Raja GrafindoPersada, Jakarta
Hartoyo, A., 2003, Teh dan Khasiatnya Bagi Kesehatan Sebuah Tinjauan Ilmiah,9-10, 23-30, Kanisius, Yogyakarta
Henning, S.M., Yantao, N., Lee, N.H., Thames, G.D., Minutti, R.R., Wang, H.,Go, V., dan Heber, D., 2004, Bioavailability and antioxidant activity of teaflavanols afterconsumption of green tea, black tea, or a green tea extractsupplement, http://www.ajcn.org/cgi/reprint/80/6/1558.pdf, diakses tanggal26 Desember 2009
Jutono, J. Soedarsono, S. Hartadi, Siti Kabirun S., Suhadi D., dan Soesanto, 1980,Pedoman Praktikum Mikrobiologi Umum Untuk Perguruan Tinggi, 28,Departemen Mikrobiologi Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada,Yogyakarta
Katno, 2008, Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat, 4, 23-24, 36, Balai BesarPenelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat tradisional

56
(B2P2TO-OT), Badan Penelitian dan Pengembangan KesehatanDepartemen Kesehatan RI, Jakarta
Kusnandar F., Hariyadi P., dan Wulandari N., 2006, Aspek Mikrobiologi MakananKaleng, http://www.nhas.ac.id/gdln/dirpan/pengalengan/topik/modul/sub-topik/karakteristikmikroba.pdf, diakses tanggal 26 Desember 2009
Lay, B. W., 1994, Analisis Mikroba di Laboratorium, 48, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta
Mazni, R., 2008, Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Umbi Bidara Upasterhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli,http://etd.eprints.ums.ac.id/4069/1/K100040158.pdf, diakses tanggal 26Desember 2009
Setyamidjaja, D., 2000, Teh Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen, 22-25,Kanisius, Yogyakarta
Svobodova, A., Psotova, J., dan Walterova, D., 2003, Natural Phenolics inprevention Of UV-Induced Skin Damage (A review), Biomed. Papers,147(2), 137
Tuminah, S., 2004, Teh [Camellia sinensis O.K. var. Assamica (Mast)] sebagaiSalah Satu Sumber Antioksidan,http://bebas.vlsm.org/v12/artikel/ttg_tanaman_obat/depkes/buku1/1-053.pdf, diakses tanggal 13 Mei 2009
Vinson, J.A., Dabbagh, Y.H., Serry, M.M., and Jang, J., 1995, Plant Flavonoids,Especially Tea Flavonols, Are Powerful Antioxidants Using an in VitroOxidation Model for Heart Disesase, Journal of Agriculture and FoodChemistry, Vol. 43, 2800
Voigt, R., 1994, Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Edisi V, 157, diterjemahkanoleh Soendari Noerono, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Vogel, A.I., Tatchell, A.R., Furnis, B.S., Hannaford, A.J. and P.W.G. Smith,1996, Practical Organic Chemistry, 53, Prentice Hall

LAMPIRAN

57
LAMPIRAN
Lampiran 1. Determinasi Tanaman Teh Hijau

58
Lampiran 2. Perhitungan Penimbangan Bahan
Pengujian Angka Lempeng Total (ALT)a. Pembuatan media PCA (300 ml)
ml
ml
1000
300x 23,5 g = 7,05 g PCA dalam 300 ml aquadest
b. Pembuatan larutan pengencer BPW (230 ml)
ml
ml
1000
230x 15 g = 3,45 g BPW dalam 230 ml aquadest
Pengujian Angka Kapang Khamir (AKK)a. Pembuatan media SDA (250 ml)
ml
ml
1000
250x 65 g = 16,25 g dalam 250 ml aquadest
b. Pembuatan larutan pengencer ASA 0,05%(150 ml)
ml
ml
100
150x 0,05 g = 0,075 g dalam 150 ml aquadest
c. Pembuatan larutan kloramfenikol1 g kloramfenikol dalam 100 ml aquadest steril
Lampiran 3. Foto Tanaman Teh Hijau
Keterangan gambar:
a.Daun
b.Batang
c.Akar
Gambar 1. Pohon teh hijau

59
Gambar 2. Daun teh hijau Gambar 3. Daun, buah, dan bunga teh hijau
Lampiran 4. Foto Ekstrak Kental Teh Hijau
Gambar 4. Ekstrak kental teh hijau
Lampiran 5. Perhitungan Rendemen Ekstrak Kental Teh Hijau
Serbuk teh hijau 250 gram dimaserasi dan dikentalkan, diperoleh 58,63 gram
ekstrak kental teh hijau.
Perhitungan rendemen = %100xkgramekstra
gramserbuk= %45,23%100
250
63,58x
gram
gram

60
Lampiran 6. Foto Angka Lempeng Total (ALT) Ekstrak Kental Teh HijauWaktu Inkubasi 24 Jam.
Gb.5 Kontrol media (replikasi 1) Gb.6 Kontrol pelarut (replikasi 1)Tidak terdapat koloni bakteri Tidak terdapat koloni bakteri
Gb.7 ALT 10-1 (replikasi 2) Gb.8 ALT 10-2 (replikasi 2)Tidak terdapat koloni bakteri Tidak terdapat koloni bakteri
Gb.9 ALT 10-3 (replikasi 2) Gb.10 ALT 10-4 (replikasi 2)Tidak terdapat koloni bakteri Terdapat 5 koloni bakteri

61
Gb.11 ALT 10-5 (replikasi 1) Gb.12 ALT 10-6 (replikasi 2)Tidak terdapat koloni bakteri Tidak terdapat koloni bakteri
Lampiran 7. Foto Angka Lempeng Total (ALT) Ekstrak Kental Teh HijauWaktu Inkubasi 48 Jam.
Gb.13 Kontrol media (replikasi 1) Gb.14 Kontrol pelarut (replikasi 1)Tidak terdapat koloni bakteri Tidak terdapat koloni bakteri
Gb.15 ALT 10-1 (replikasi 1) Gb.16 ALT 10-2 (replikasi 1)Tidak terdapat koloni bakteri Tidak terdapat koloni bakteri

62
Gb.17 ALT 10-3 (replikasi 1) Gb. 18 ALT 10-4 (replikasi 2)Tidak terdapat koloni bakteri Terdapat 7 koloni bakteri
Gb.19 ALT 10-5 (replikasi 1) Gb.20 ALT 10-6 (replikasi 1)Terdapat 1 koloni bakteri Terdapat 24 koloni bakteri
Lampiran 8. Foto Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh HijauWaktu Inkubasi 5 Hari.
Gb.21 Kontrol media (replikasi 1) Gb.22 Kontrol pelarut (replikasi 1)Tidak terdapat koloni kapang/khamir Tidak terdapat koloni kapang/khamir

63
Gb.23 AKK 10-1 (replikasi 1) Gb. 24 AKK 10-2 (replikasi 2)Tidak terdapat koloni kapang/khamir Tidak terdapat koloni kapang/khamir
Gb.25 AKK 10-3 (replikasi 1) Gb.26 AKK 10-4 (replikasi 1)Terdapat 1 koloni kapang Terdapat 1 koloni kapang
Gb. 27 AKK 10-4 (replikasi 2)Tidak terdapat koloni kapang/khamir

64
Lampiran 9. Foto Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh HijauWaktu Inkubasi 6 Hari.
Gb.28 Kontrol media (replikasi 2) Gb.29 Kontrol pelarut (replikasi 1)Terdapat 1 koloni khamir Tidak terdapat koloni kapang/khamir
Gb.30 AKK 10-1 (replikasi 1) Gb.31 AKK 10-2 (replikasi 2)Tidak terdapat koloni kapang/khamir Tidak terdapat koloni kapang/khamir
Gb.32 AKK 10-3 (replikasi 1) Gb. 33 AKK 10-3 (replikasi 1)Terdapat 1 koloni kapang Tampak depan koloni kapang

65
Gb.34 AKK 10-4 (replikasi 1) Gb.35 AKK 10-4 (replikasi 2)Terdapat 1 koloni kapang Terdapat 1 koloni kapang
Lampiran 10. Foto Angka Kapang Khamir (AKK) Ekstrak Kental Teh HijauWaktu Inkubasi 7 Hari.
Gb.36 Kontrol media (replikasi 2) Gb.37 Kontrol pelarut (replikasi 1)Terdapat 1 koloni khamir Tidak terdapat koloni kapang/khamir
Gb.38 AKK 10-1 (replikasi 2) Gb.39 AKK 10-2 (replikasi 1)Tidak terdapat koloni kapang/khamir Tidak terdapat koloni kapang/khamir

66
Gb.40 AKK 10-3 (replikasi 1) Gb.41 AKK 10-4 (replikasi 1)Terdapat 1 koloni kapang Terdapat 1 koloni kapang
Gb. 42 AKK 10-4 (replikasi 2)Terdapat 1 koloni kapang

67
BIOGRAFI PENULIS
Penulis lahir pada tanggal 10 Maret 1988 di
Purwokerto. Lahir dari Ayah bernama Hadi
Soedjatmiko dan Ibu bernama Yeni Setiawati, memiliki
dua saudara perempuan dan laki-laki. Penulis telah
menyelesaikan masa studinya di TK Santo Yoseph pada
tahun 1993 sampai tahun 1994, SD Santo Yoseph
Purwokerto pada tahun 1994 sampai dengan tahun
2000, SLTP Bruderan Purwokerto pada tahun 2000
sampai dengan tahun 2003, kemudian penulis
melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Purwokerto pada
tahun 2003 sampai dengan 2006 dan kuliah di Fakultas
Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada
tahun 2006 sampai tahun 2009.