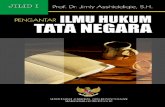2010_170210100035.docx
-
Upload
guntoro-chandra -
Category
Documents
-
view
42 -
download
0
description
Transcript of 2010_170210100035.docx
TUGAS AKHIR
KEJAHATAN TRANS-NASIONAL
“Peran ASEAN dalam Mengatasi Terorisme di Kawasan Asia Tenggara”
Disusun Oleh :
Annisa Chantika Irawan
170210100035
No. Telp/HP: 085624202008
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJAJARAN
JATINANGOR
2013
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahiim
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya dan ridlo-Nyalah penulisan
tugas akhir dengan judul “Peran ASEAN dalam Mengatasi Terorisme di Kawasan Asia
Tenggara” ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa pula dilimpahkan pada
baginda Rasulullah Muhammad SAW karena atas jasanyalah kita dibawa dari dunia
yang kelam ke dunia yang sekarang ini. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan
banyak rahmat-Nya pada kami, tetapi kami terkadang lupa untuk mensyukuri rahmat
dan nikmat tersebut.
Banyak tantangan yang dihadapi dalam menyusun makalah ini. Akan tetapi, berkat
dukungan dari berbagai pihak, akhirnya tugas ini terselesaikan. Mungkin tulisan ini
masih jauh dari sebutan mahakarya dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu,
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Mata Kuliah
Kejahatan Trans-Nasional.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan
agar makalah ini dapat berguna. Oleh karena itu untuk semakin menyempurnakan
makalah ini saya meminta saran dan kritik yang membangun dari para pembaca
sehingga di kemudian hari kami dapat membuat penulisan yang lebih baik dari ini.
Sesungguhnya yang benar hanya dari Allah SWT semata dan yang salah dari
kelemahan dan kekurangan kami.
Wabillahi Taufiq Wal Hidayah
Bandung, 29 Juli 2013
Penulis
2
DAFTAR ISI
Cover 1Kata Pengantar 2Daftar Isi 3
BAB I : PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang 41.2 Identifikasi Masalah 51.3 Tujuan Penulisan 51.4 Metodelogi Penulisan 5
1.4.1 Jenis Penelitian 51.4.2 Sumber Data61.4.3 Teknik Pengumpulan Data 6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA2.1 Teori Hubungan Internasional 72.2 Organisasi Internasional 92.3 Kesatuan Regional 102.4 Komunitas Keamanan 102.5 ASEAN Community 2015 132.6 Terorisme 132.7 Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention 15 on Counter Terrorism)
BAB III : PEMBAHASAN4.1 ASEAN Security Community 17
4.1.1 Ancaman Keamanan dan Kerawanan Bersama 184.1.2 Kesalingtergantungan Ekonomi dan Fungsional yang ber-Spill Over 19
dalam Menciptakan Hubungan Damai 4.2 Peran ASEAN dalam Mengatasi Terorisme di Asia Tenggara 25
4.2.1 Pentingnya Pemberantasan Terorisme di Asia Tenggara 254.2.2 Analisis Mengenasi ASEAN Convention on Counter Terrorism 29
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 345.2 Saran 36
Daftar Pustaka 38
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
ASEAN, pada dekade 1990-an, berhasil menunjukkan beberapa prestasinya
dalam bidang ekonomi, yaitu dalam mengatasi krisis ekonomi global pada tahun
1997-1998, dan dalam bidang konflik etnis terkait keanekaragaman budaya di
kawasan Asia Tenggara, melalui manajemen konflik yang dikenal
sebagai ASEANWays (Jones & Smith, 2002:93-94). Beberapa perjanjian pun telah
dilahirkan oleh ASEAN, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Free
Trade Association (AFTA) (Jones & Smith, 2002:95). Melalui keberhasilan ini,
para pemimpin ASEAN menghendaki adanya suatu hubungan kerjasama yang
lebih intens dan intim dan dirupakan dalam bentuk komunitas integrasi. Oleh
karenanya, ASEAN Community kemudian disepakati oleh para pemimpin
ASEAN melalui penandatanganan deklarasi Bali Concord II pada bulan Oktober
2003 (Cipto, 2007:80-81). Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang
dikembangkan dan diimplementasikan secara paralel dan seimbang, yakni ASEAN
Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) serta ASEAN
Sosial-Budaya Masyarakat (ASCC)1.
Secara khusus, makalah ini akan membahas mengenai peran dan juga usaha
ASEAN dalam mengatasi terorisme di kawasan Asia Tenggara. Sepert ASC yang
bertujuan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas antarnegara,
membangun sistem resolusi konflik multilateral, dan pemetaan kerangka kerja
sama untuk menangani ancaman keamanan, baik konvensional maupun yang
nonkonvensional2. ASC didasarkan pada norma bersama dan aturan perilaku yang
1 ASEAN Security Community Plan of Action. Dalam http://www.aseansec.org/16826.htm dikases2 Acharya, Amitav. (1998). “Collective Security and Conflict Management in Southeast Asia”. Dalam Emanuel Adler dan Michael Barnett, Security Community. Cambridge: Cambridge University Press.
4
baik dalam menjalin hubungan antar-negara serta pencegahan konflik secara
efektif dan adanya mekanisme resolusi3.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa
poin yang disimpulkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, ada pun
rinciannya sebagai berikut:
1. Bagaimana posisi ASEAN dalam mengatasi Terorisme di Asia Tenggara?
2. Apa yang dimaksud dengan Komunitas ASEAN dan Keamanan Regional?
3. Apa peran dan upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam mengatasi terorisme
di kawasan Asia Tenggara?
1.3 Tujuan Penulisan
Ada pun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:
1. Memenuhi tugas akhir semester antara mata kuliah KejahatanTransnasional.
2. Menambah khasanah ilmu khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang
lain.
3. Mencoba untuk menganalisis peran ASEAN dalam mengatasi terorisme di
Asia Tenggara.
1.4 Metodelogi Penulisan
1.4.1 Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Metode ini berupaya untuk menggambarkan
atau membuat lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta dan sifat-sifat serta fenomena-fenomena yang diteliti dan juga untuk
meneliti kedudukan suatu fenomena serta melihat hubungan antara satu
faktor dengan faktor lainnya. Dalam metode ini, data mula-mula disusun,
3 Cipto, Bambang. (2007). Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
5
dijelaskan, kemudian dianalisis. Dengan demikian, setelah dideskripsikan
maka data tersebut akan dianalisis kemudian.
Ukuran data kualitatif adalah logika dalam menerima atau menolak
sesuatu yang dinyatakan berupa kalimat, yang dirumuskan setelah
mempelajari sesuatu tersebut dengan cermat. Data kualitatif tidak
mempunyai pembanding yang pasti karena itu kebenaran yang akan adalah
dibuktikan bersifat relatif. Data dapat berupa pendapat, pandangan, konsep-
konsep keterangan, tanggapan, dan lain-lain yang berhubungan dengan
kehidupan manusia. (Nawawi dan Hadari, 1992: 209).
1.4.2 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang mendukung.
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu melalui
studi pustaka.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Hubungan Internasional
Berbicara mengenai terorisme yang ada di kawasan Asia Tenggara, pastinya
tak terlepas dari hubungan antar satu bangsa atau negara ke yang lainnya. akan
tetapi, pandangan tentang pemikiran Hubungan Internasional sendiri berawal dari
sebuah traktat atau Perdamaian Westphalia yang juga dikenal dengan
namaPerjanjian Munster dan Osnabruck pada tahun 1648, adalah serangkaian
perjanjian yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan secara resmi mengakui
Republik Belanda dan Konfederasi Swis ketika sistem negara modern mulai
dikembangkan.4
Sebelumnya, organisasi-organisasi otoritas politik abad pertengahan Eropa
didasarkan pada tatanan hirarkis yang tidak jelas. Dalam perdamaian Westphalia
terbentuk konsep legal tentang kedaulatan, yang pada dasarnya berarti bahwa para
penguasa, atau kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak
lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas
kedaulatan wilayah yang sama. Otoritas Yunani dan Roma kuno kadang-kadang
mirip dengan sistem Westphalia, tetapi keduanya tidak memiliki gagasan
kedaulatan yang memadai.
Sistem pemikiran Westphalia mendorong bangkitnya negara sampai bangsa,
institusionalisasi terhadap diplomasi dan tentara. Sistem pemikiran ini kemudian
‘diexpor’ ke Amerika, Afrika, dan Asia, lewat kolonialisme, dan standar-standar
peradaban. Sistem internasional kontemporer akhirnya dibentuk lewat
dekolonisasi selama Perang Dingin. Namun, sistem ini agak terlalu
disederhanakan, sementara sistem negara-bangsa dianggap modern, banyak 4 Global Search Teori-Teori Hubungan Internasional 2013 http://globalsearch1.blogspot.com/2013/06/teori-teori-hubungan-internasional.html
7
negara tidak masuk ke dalam sistem tersebut dan disebut sebagai pra-modern.
Lebih lanjut, beberapa telah melampaui sistem negara-bangsa dan dapat dianggap
pasca-modern. Kemampuan wacana HI untuk menjelaskan hubungan-hubungan
di antara jenis-jenis negara yang berbeda ini diperselisihkan. Level-level analisis
adalah cara untuk mengamati sistem internasional, yang mencakup level
individual, negara-bangsa domestik sebagai suatu unit, level internasional yang
terdiri atas persoalan-persoalan transnasional dan internasional level global.
Bersamaan dengan perkembangan peradaban dan pemikiran manusia, teori
tentang Hubungan Internasional berkembang berdasakan fase-fase yang kesemua
itu bermula dari5:
Current History: sebagai ladang penyelidikan intelektual yang sebagian besar
dipengaruhi fenomena abad ke-20. Akar-akar sejarah disiplin ini terletak pada
sejarah diplomatik yang merupakan salah satu pendekatan untuk memahami HI
yang berfokus pada deskripsi kejadian-kejadian sejarah, bukan eksplanasi teori.
Untuk kemudahan, aliran ini disebut pendekatanCurrent History terhadap studi
HI.
Idealisme Politik: Berawal setelah Perang Dunia I yang membuka pintu terhadap
revolusi paradigma dalam studi HI. Sejumlah perspektif HI berusaha menarik
perhatian para peminatnya pada periode ini. Meskipun demikian, aliran current
history masih memiliki pengikutnya. Aliran ini semakin kuat setelah Perang
Dunia II, terutama di Amerika Serikat. Pacuan senjata yang marak ketika Perang
Dingin semakin mengukuhkan perspektif Realisme.
Realisme Politik: perspektif Realisme lahir dari kegagalan membendung Perang
Dunia I dan II, terutama di Amerika Serikat. Pacuan senjata yang marak ketika
Perang Dingin semakin mengukuhkan perspektif Realisme.
5 Global Search Teori-Teori Hubungan Internasional 2013 http://globalsearch1.blogspot.com/2013/06/teori-teori-hubungan-internasional.html
8
The Behavior approach (pendekatan perilaku): aliran realism klasik menyiapkan
secara serius pemikiran teoritis mengenai kondisi global dan empiris. Namun
demikian ketidak-kuasaan karena kurangnya data, reaksi tandingan, kesuliran
dalam peristilahan dan metode, mendapatkan momentum pada tahun 1960-an dan
awal 1970-an. Disebabkan pendekatan perilaku terhadap studi Hubungan
Internasional maka banyak mempengaruhi pendekatan terhadap teori dan logika
serta metode penelitian.
The Neoralist Structural Approach (pendekatan Neoralisme Struktural):
pandangan ini membedakan antara eksplanasi peristiwa politik internasional di
tingkat nasional seperti negara yang diketahui sebagai politik luar negeri dengan
eksplanasi peristiwa di tingkat sistem internasional yang disebut sistem atau teori
sistem.
Institutionalisme Neoliberal: Seperti halnya neoliberal, institutionalis neoliberal
menggunakan teori structural politik internasional. Mereka terutama
berkonsentrasi kepada sistem internasional, bukannya karakteristik unit atau sub
unit di dalamnya, namun mereka member lebih banyak perhatian pada bagaimana
cara lembaga internasional dan aktor non negara lainnya mempromosikan kerja
sama internasional. Daripada halnya menggambarkan dunia di mana negara-
negara di dalamnya enggan bekerja sama karena masing-masing merasa tidak
aman dan terancam oleh yang lainya, Institusionalis Neoliberal membuktikan
syarat-syarat kerja sama yang mungkin dihasilkan dari kepentingan yang tumpang
tindih di antara entitas politik yang berdaulat.
2.2 Organisasi Internasional
ASEAN merupakan salah satu oganisasi internasional yang ada dalam
menjalankan usahanya mengatasi terorisme di kawasan Asia Tenggara. Menurut
Pasal 2 Konvensi Wina 1961, organisasi internasional: organisasi antar
pemerintah – pengertian sempit (karena membedakan antara organisasi
9
pemerintah/ inter-govermental organizations (IGO’s) dan organisasi non
pemerintah (NGO’s).
Organisasi internasional merupakan subjek buatan; subjek hukum yang
diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi internasional
melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu
perjanjian internasional; sehingga sangat dekata dan tergantung kepada negara-
negara anggotanya.6 Sehingga perannya dalam mengatasi terorisme di Asia
Tenggara seharusnya lebih mudah karena anggotanya merupakan bagian dari
organisasi internasional tersebut.
2.3 Kesatuan Regional
ASEAN memiliki peluang yang sangat besar dalam mengatasi terorisme
yang ada di Kawasan Asia Tenggara karena ASEAN merupakan kesatuan
regional dari anggota – anggota ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara.
Kesatuan regional ini dapat dijadikan sebagai kunci pokok dan utama dalam
menjadi batu loncatan menuju pemberantasan terhadap terorisme yang ada di
dalam kawasan tersebut.
2.4 Komunitas Keamanan
Komunitas keamanan ASEAN pada dasarnya cenderung melihat ke arah
internal, yakni diarahkan untuk pencegahan perang dan resolusi konflik dalam
kelompok. ASEAN mengakui bahwa kondisi pemberontakan yang berkelanjutan
di wilayah tersebut lebih berkaitan dengan kondisi internal sosial, ekonomi, dan
politik (Acharya, 1998). Oleh karenanya, ancaman internal dinilai lebih
mendesak. Solidaritas intra-ASEAN kemudian menjadi sangat dibutuhkan untuk
mengatasi permasalahan lintasnegara, melalui komunikasi dan sharing antar
intelijen, perjanjian ekstradisi bersama, patroli perbatasan bersama, dan operasi
kontra-pemberontakan. Komite perbatasan bilateral dibentuk untuk menangani
6 Sri Wahyuni Organisasi Internasional 2013 http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/pengertian-hukum-organisasi.html
10
pemberontakan, sebagai channel langsung untuk menangani sengketa teritori.
Pertumbuhan dari regionalisme dan pemecahan masalah kolektif membuktikan
klaim konstruktivis, bahwa terlepas dari keadaan eksogen, negara bisa
membentuk identitas kolektif dan kepentingan melalui integrasi yang
memungkinkan untuk mengatasi dilema keamanan (Acharya, 1998).
Dalam konteks ASEAN, eksistensi regional dibentuk untuk mengurangi
penggunaan paksaan dalam hubungan antarnegara. Dari sini kemudian
dimunculkan suatu identitas bersama yang dipahami sebagai sebuah proses dan
kerangka kerja yang mengarah kepada hubungan kerjasama mutual dan
menguntungkan. Ada empat faktor yang penting dalam kaitan pengembangan
identitas bersama ini, yaitu praktik multilateralisme, pengembangan aturan dasar
hubunga antarnegara, penciptaan dan penggunaan simbol, dan prinsip otonomi
regional (Acharya, 1998:209-214). ASEAN kemudian mampu mencegah
terjadinya perselisihan yang terjadi di luar kendali dengan menyelesaikannya
melalui penahanan dan pengelolaan isu-isu yang diperdebatkan, walaupun masih
terdapat beberapa konflik yang terjadi antaranggota ASEAN. Dalam hal ini,
eksistensi ASC dibutuhkan, dengan ciri utama dalah kemampuan untuk
mengatur segala konflik dalam regional secara damai. ASEAN talah bergerak
menuju interdependensi intraregional dan integrasi yang lebih baik. ASC juga
dapat berfungsi sebagai basis sebuah konsensus otoriter, yang diimplementasikan
melalui proliferasi bilateral kerjasama keamanan, perencanaan militer, dan
kepemilikan senjata.
Komunitas keamanan ASEAN ini menghadapi tentangan dan pesimisme dari
beberapa pihak, seperti kaum liberalis yang mengatakan bahwa komunitas
kemanan memerlukan sebuah lingkungan demokrasi-liberal dengan
interdependensi ekonomi yang signifikan serta pluralisme politik. Ekonomi
regional dan integrasi negara Dunia Ketiga pada kenyataannya belum cukup
berkembang karena tujuannya yang belum jelas. Perspektif liberal menyatakan
bahwa dosis tinggi dari politik otoritarian dan interdependensi ekonomi
11
intraregional yang relatif berada di level bawah menghalangi munculnya
komunitas kemanan regional (Acharya, 1998:199). Kritikan lain adalah adanya
label imitasi pada ASEAN. Permasalahan interpersonal yang tidak penting,
kurangnya kohesi dan legitimasi, serta tekanan-tekanan lain yang terjadi
terhadap hubungan antarnegara menjadi salah satu faktor yang menimbulkan
tanda-tanda imitatif (Jones & Smith, 2002:105). ASEAN hanya berperan untuk
mengelola dan mengurus konflik alih-alih menyelesaikannya. Peranan ASEAN
menjadi kurang efektif terhadap permasalahan internalnya, dan pada akhirnya
menjadi komunitas yang imitatif terhadap kelemahan-kelemahan kecil yang
dimilikinya. Khoo juga mengkritik ASEAN, terkait tautological nature, yaitu
pengulangan pernyataan dua kata yang berbeda namun memiliki kesamaan arti.
Dalam hal ini, Acharya (1998:1) menjelaskan bahwa komunitas keamanan dapat
didefinisikan sebagai sekelompok negara yang telah mengembangkan kebiasaan
jangka panjang terkait interaksi yang damai. Khoo (2004:43) berargumen bahwa
institusi dapat memperburuk ketegangan dengan mudah karena mereka dapat
memfasilitasi kerjasama sebagai hasil pemikiran realisme. ASEAN dipahami
sebagai institusi yang mengunci anggotanya dalam pola interaksi yang negatif,
namun dengan kondisi anggota ASEAN enggan meninggalkan keanggotaannya
karena akan meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekuatan eksternal.
Perkembangan komunitas keamanan ASEAN berupaya menjawab kritikan
ini. Adler dan Barnett (dalam Acharya, 1998:202) mengidentifikasi komunitas
keamanan ke dalam tiga fase, yaitu nascent (ditandai dengan persamaan persepsi
ancaman, ekspektasi mutual terhadap perdagangan, dan pembagian derajat
identitas), ascendant (ditandai dengan penguatan koordinasi militer,
pengurangan ketakutan antaraktor, pengadaan transisi kognitif, proses
intersubjektif, dan identitas kolektif terhadap peaceful change), dan mature
(ditandai dengan eksistensi kekuatan institusionalisasi dan supranasionalisme,
peningkatan derajat kepercayaan, dan minimalisasi konflik militer).
12
2.5 ASEAN Community 2015
Kerjasama internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan
dan politik luar negeri. Melalui kerjasama internasional, dapat memanfaatkan
berbagai peluang untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam
hal ini kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama
internasional, karena merupakan lingkaran konsentris terdekat di kawasan dan
menjadi pilar utama pelaksanaan politik luar negeri suatu bangsa. Dalam kurun
waktu 42 tahun sejak terbentuknya ASEAN, telah banyak capaiancapaian yang
diraih dan sumbangsih yang diberikan ASEAN bagi negara-negara anggotanya.
Salah satunya yang terpenting, adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di
kawasan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN juga terus
mengalami peningkatan.
Disamping itu, rasa saling percaya diantara negara-negara anggota ASEAN
dan juga antara ASEAN dengan negara-negara Mitra Wicara ASEAN, terus
tumbuh. ASEAN telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan positif
yang signifikan, dimana kerjasama ASEAN sekarang ini tengah menuju pada
tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan kedepan melalui
pembentukan dengan akan dibentuknya ASEAN Community pada tahun 2015.
Yaitu sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang
damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis
dan masyarakat yang saling peduli. Melalui ASEAN Community 2015 ini
seharusnya upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam memerangi terorisme
dapat menjadi lebih maksimal.
2.6 Terorisme
Terorisme kian menjadi hal yang dianggap paling mengancam stabilitas
keamanan global, hal ini didukung oleh terorganisirnya jaringan terorisme yang
menyebar di seluruh negara bagian yang dipengaruhi oleh semakin
berkembangnya globalisasi, teknologi, komunikasi, dan informasi. Selain itu,
13
persenjataan yang digunakan dalam tindak terorisme diduga mengalami
kemajuan yang sangat pesat, dan WMD (Weapon Mass Destruction) diduga
sebagai salah satu senjata yang tengah diupayakan dan dikembangkan oleh
sejumlah pelaku terorisme untuk melancarkan aksi terorismenya. Hal itu pula
yang pada akhirnya semakin memperkuat jaringan terorisme itu sendiri.
Teroris termasuk ke dalam salah satu aktor non-negara karena perannya yang
dapat mempengaruhi serta mengancam stabilitas keamanan global dan alur
sistem internasional. Tindak terorisme tidak hanya mengancam aspek keamanan
global, melainkan turut mengancam stabilitas pada aspek lain seperti politik,
lingkungan, maupun ekonomi.
Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak
kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan
bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat
luas. Realis melihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para teroris
tidak memiliki legitimasi untuk menggunakan senjata dalam mencapai tujuan
mereka. Pandangan ini percaya bahwa hanya negara yang memiliki legitimasi
untuk menggunakan senjata dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.
Critical theory melihat dan menglasifikasikan terorisme sebagai salah satu
aksi kekerasan politik. Maksudnya aksi yang dilakukan oleh teroris memiliki
tujuan-tujuan politis yang ingin dicapai. Pandangan ini melihat terorisme adalah
aktor politis layaknya pemberontakan, revolusi, atau insurgensi dimana tujuan
akhirnya adalah terjadinya perubahan politik yang sesuai dengan keinginan
mereka. Bedannya, dibandingkan dengan ketiga jenis kelompok lainnya,
terorisme adalah gerakan yang paling sedikit mendapatkan suppor dari
masyarakat. Mereka memiliki kesulitan untuk mendapat dukungan masyarakat.
Para teroris berharap aksi kekerasan yang mereka lakukan akan mendapat
reaksi yang tidak sepadan dari negara dan berharap hal tersebut akan
memberikan efek pada masyarakat untuk mengubah opini masyarakat dan untuk
14
mendapatkan support dari masyarakat. Menurut hukum internasional,
keberadaan pemberontak bisa diakui sebagai keberadaan yang setara dengan
negara karena mampu mempengaruhi dan mengubah sistem yang ada dengan
negara. Akan tetapi, terorisme tidak dapat digolongkan kedalam status
pemberontak.
2.7 Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on
Counter Terrorism)
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN)--Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik
Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik
Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam—selanjutnya
disebut sebagai ‘para Pihak’;
MENGINGAT Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum
internasional yang relevan, konvensi-konvensi dan protokol-protokol
internasional yang relevan berkaitan dengan pemberantasan terorisme, serta
resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan tentang langkah-
langkah yang dimaksudkan untuk memberantas terorisme internasional, dan
menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi hak asasi manusia,
perlakuan adil, aturan hukum, dan proses hukum semestinya serta prinsipprinsip
yang terkandung dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia
Tenggara yang dibuat di Bali pada tanggal 24 Februari 1976;
MENEGASKAN KEMBALI bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh
dihubungkan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau kelompok etnis
apa pun;
15
MENGINGAT juga Deklarasi ASEAN tentang Aksi Bersama Pemberantasan
Terorisme dan Deklarasi tentang Terorisme yang masing-masing diterima pada
Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tahun 2001 dan 2002;
MENEGASKAN KEMBALI komitmen kami pada Program Aksi Vientiane yang
dibuat di Vientiane pada tanggal 29 November 2004, khususnya penekanannya
dalam ‘membentuk dan berbagi norman-norma’,dan kebutuhan, antara lain, untuk
membantu penandatanganan suatu Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik
ASEAN, dan suatu Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, dan
pembentukan suatu Perjanjian Ekstradisi ASEAN, yang diamanatkan oleh
Deklarasi ASEAN Concord tahun 1976;
MEMPERHATIKAN DENGAN SAKSAMA atas bahaya serius yang
ditimbulkan oleh terorisme terhadap manusia-manusia tidak bersalah,
infrastruktur dan lingkungan, perdamaian dan stabilitas kawasan dan
internasional, serta pembangunan ekonomi;
MENYADARI pentingnya pengidentifikasian dan penyelesaian secara efektif
akar permasalahan terorisme dalam perumusan setiap langkah pemberantasan
terorisme;
MENYATAKAN KEMBALI bahwa terorisme, dalam segala bentuk dan
manifestasinya, yang dilakukan di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun,
merupakan suatu ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional
dan tantangan langsung bagi pencapaian perdamaian, kemajuan, dan
kesejahteraan ASEAN, dan perwujudan Visi ASEAN 2020;
MENEGASKAN KEMBALI komitmen kuat kami untuk meningkatkan kerja
sama dalam pemberantasan terorisme yang mencakupi pencegahan dan
penghentian segala bentuk tindakan teroris;
MENYATAKAN KEMBALI perlunya meningkatkan kerja sama kawasan dalam
pemberantasan terorisme dan mengambil langkah-langkah efektif dengan
16
mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum di ASEAN dan otoritas
yang relevan dalam memberantas terorisme;
MENDORONG para Pihak untuk menjadi pihak-pihak sesegera mungkin pada
konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang relevan berkaitan
dengan pemberantasan terorisme;
BAB III
PEMBAHASAN
4.1 ASEAN Security Community
ASEAN mempunyai potensi untuk menjadi komunitas keamanan di
kawasan Asia Tenggara. Hal ini diakui oleh para akademisi dan para pengambil
keputusan baik didalam maupun diluar kawasan. Salah satunya adalah kajian
bahwa ASEAN dianggap sebagai sebuah komunitas keamanan yang pluralistik,
dimana masing-masing anggotanya tetap mempertahankan
kedaulatannya (Acharya,1990). Pemahaman bahwa ASEAN menjadi komunitas
keamanan lebih didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada satupun anggotanya
yang menggunakan kekuatan bersenjata atau anggapan perlunya digunakannya
kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik di kawasan(Simon,
1999 :122). Sedangkan Michael Leifer sepakat bahwa ASEAN memang sebuah
komunitas keamanan karena kemampuannya untuk mencegah konflik intra-
mural dari kemungkinan eskalasi konfrontasi bersenjata untuk menjadi komunitas
politik (Leifer, 1995 : 129-132). Adalah kenyataan bahwa ketiadaan perang
diantara negara-negara anggota ASEAN sejak organisasi tersebut didirikan tahun
1967 merupakan prestasi terbesar ASEAN dalam mengatur interaksi damai
17
didalam kawasan. Ada tiga kekuatan utama menurut Amitav Acharya yang
menjadi prasyarat terbentuknya satu komunitas keamanan di kawasan, yaitu :
4.1.1 Ancaman Keamanan dan Kerawanan Bersama
Ancaman keamanan bersama adalah sumber ketidakamanan yang
berpotensi mengganggu secara nyata terhadap stabilitas negara-negara di
kawasan. Secara umum ancaman konvensional/tradisional merupakan salah
satu aspek keamanan yang sangat sensitif bagi negara-negara ASEAN,
karena berkaitan langsung dengan masalah kedaulatan, integritas dan
kelangsungan hidup suatu negara.
Yang menjadi ancaman keamanan bersama negara-negara ASEAN
secara konvensional hingga sekarang dan masih cukup relevan karena
memiliki potensi konflik yang lebih terbuka antar Negara anggota ASEAN
adalah permasalahan separatisme dan konflik perbatasan (Usman, 1996 :
159-164). Munculnya serangan terorisme di negara-negara ASEAN
atau transnational crimes yang terorganisasi telah merubah persepsi
ancaman bersama di kawasan Asia Tenggara menjadi tidak konvensional
lagi (keamanan non konvensional). Penyelundupan manusia secara ilegal,
pembajakan, penyelundupan narkotika, masalah lingkungan, pencucian
uang, terorisme, kejahatan ekonomi menjadi ciri tindak kejahatan lintas
batas yang terorganisir sebagai ancaman baru di kawasan (Dirjen
Kerjasama ASEAN Deplu RI, 2005 : Bab IV). Ancaman keamanan yang
bersumber dari adanya berbagai kerawanan domestik merupakan faktor
dominan dan menjadi motivasi dari pembentukan ASEAN. Kerawanan
bersama adalah celah/titik rawan yang telah terbuka sebagai akibat dari
ancaman nyata. Keamanan non tradisional, yang bersifat komprehensif dan
berorientasi pada manusia(human security) telah membuka celah kerawanan
bersama dan sekaligus menjadi ancaman nyata yang hadir dengan pola-pola
modifikasi dari sebelumnya dan telah memaksa (spin off) ASEAN untuk
18
menata kembali agenda kerjasama keamanannya. Hal paling penting di sini
adalah adanya kesamaan persepsi dari para pemimpin politik ASEAN akan
pentingnya ’comprehensive security’ untuk diadopsi ke dalam setiap bentuk
kerjasama keamanannya, sebagaimana yang telah dihasilkan di Vientiane,
Laos, 2004.
4.1.2 Kesalingtergantungan Ekonomi dan Fungsional yang ber-Spill Over
Dalam Menciptakan Hubungan Damai
Secara formal ASEAN adalah organisasi yang memfokuskan diri pada
upaya kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi
Deklarasi Bangkok merupakan komitmen politik untuk bersatu dan
bekerjasama dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas regional agar
negara-negara anggota dapat menikmati hidup merdeka tanpa campur
tangan asing serta dapat berkonsentrasi dalam memenuhi kepentingan
nasionalnya.
Kerjasama dibidang ekonomi dinilai sebagai pendorong utama
kerjasama antar negara karena bidang ini tidak sensitif dan tiap negara
menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai salah satu syarat
penunjang pembangunan nasionalnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa
sejak ASEAN berdiri, praktis tidak pernah terjadi konflik terbuka di antara
negara-negara yang bertetangga dengan ASEAN. Berbeda dengan situasi
sebelum ASEAN terbentuk, berbagai ketegangan, konflik maupun
konfrontasi; mewarnai kawasan ini. Dalam hal ini ASEAN telah berhasil
menata hubungan bertetangga dengan baik di antara sesama anggotanya.
Keberhasilan tersebut tentunya tidak berjalan dengan sendirinya, karena
ada faktor yang mendorongnya, yaitu faktor kerjasama ekonomi dan
fungsional yang ber-spill overdalam menciptakan hubungan damai.
Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun
1967, negara-negara anggota telah meletakan kerjasama ekonomi sebagai
19
salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya
kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian
preferensi perdagangan (preferential trade), usaha patungan (joint venture),
dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah
engara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti
ASEAN Industrial Projects Plan (1967), Preferential Trading Arrangement
(1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN
Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential
Trading Arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90an ketika negara-
negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk
menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota
ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan
saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi
ekonomi kawasan.
Pada KTT Ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani
Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic cooperation
menandai dicanangkannya ASEAN Free trade area (AFTA) dan pada
tanggal 1 Januari 1993 memberlakukan Common Effective Preferential
Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utamanya. Pendirian AFTA memberiksn
implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan
hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan
fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya
difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan
dan investasi. Ada anggapan bahwa dampak AFTA terhadap perdagangan
intra ASEAN sangat minimal, sebab selama 15 tahun terakhir perdagangan
intra ASEAN tetap saja berkisar antara 20-25 persen dari seluruh
perdagangan ASEAN. Tetapi penilaian seperti ini kurang tepat. Yang lebih
penting untuk diamati adalah tingkat pertumbuhan perdagangan ASEAN
secara keseluruhan yang mencapai 20-30 persen pertahun. Kawasan
20
ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang terbuka bagi dunia dan
mengandalkan pertumbuhannya pada pasar global dan bukan pasar
regional. AFTA memang tidak dimaksudkan untuk menciptakan pasar
regional bagi negara-negara ASEAN sendiri, tetapi untuk membuat
kawasan ASEAN menjadi yang menarik bagi produksi dunia (open
regionalism).Disamping AFTA, pada tahun 1995 ASEAN juga telah
menyepakati ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) untuk
membuka pasar jasa-jasa di kawasan ASEAN. Pada tahun 1996 ASEAN
mengembangkan skema kerjasama baru dibidang industri yaitu ASEAN
Industrial Cooperation (AICO), dimana insentif yang diberikan sebatas
pada pemberian preferensi tarif yang semakin berkurang, artinya karena
menurunnya tarif MFN. Selanjutnya pada tahun 1998 ASEAN
menandatangani kesepakatan baru, yaitu Framework Agreement on
ASEAN Investment Area (AIA), yang dimaksudkan untuk membuat
ASEAN menjadi suatu kawasan investasi yang kompetitif, terbuka dan
liberal melalui suatu persetujuan yang mengikat(Soesastro, 2007 : 316-
317). KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan
komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi
ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis
produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi,
tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih
bebas. (ASEAN Selayang pandang: 2007: 42).Kesepakatan ini dapat dilihat
sebagai perombakan baru dalam perjalanan kerjasama dan integrasi
ekonomi ASEAN. Ia bukan sekedar lanjutan logis (Logical extension) dari
AFTA, AFAS dan AIA, tetapi dengan jelas mengarah kepada pembentukan
pasar tunggal (Single Market) ASEAN. Dalam rumusan yang disepakati
para pemimpin ASEAN, tujuan dari AEC adalah untuk menciptakan a
single market and production base. Ini dapat diartikan sebagai integrasi
penuh, kecuali di bidang keuangan dan moneter.
21
Kerjasama ekonomi yang ber-spilover kepada penciptaan hubungan
damai (economic road towards peace and stability) diawali dengan
ditandatanganinya deklarasi ZOPFAN hingga munculnya dua dokumen
monumental yang menjadi tonggak dalam kerjasama keamanan (security
road towards peace and stability) pada KTT I di Bali 1976, dokumen
tersebut antara lain adalah ASEAN Concord 1 dan TAC (Treaty of Amity
and Cooperation) sebagai code of conduct. Pada kenyataannya kerjasama
dalam bidang keamanan diantara negara-negara anggota ASEAN
merupakan perpaduan antara kebijakan keamanan nasional masing-masing
negara anggota dalam satu pengaturan tatanan regional yang pada akhirnya
membentuk ketahanan regional (regional resilience). Komponen internal
dalam doktrin ketahanan regional pada prinsipnya merupakan upaya
membina rasa saling pengertian dan kepercayaan dalam kehidupan antar
negara (confidence building measures). Komponen eksternal yang
membentuk doktrin ketahanan regional adalah perwujudan dari semangat
kemandirian ASEAN dari campur tangan negara-negara luar kawasan.
Secara substansial doktrin ketahanan regional (regional resilience), pada
umumnya menganggap campur tangan pihak luar dalam urusan internal
kawasan sebagai faktor penyebab instabilitas (Anggoro, 1996 : 133-134).
Dibawah ini terdapat uraian dari bentuk-bentuk kerjasama ekonomi
dan fungsional yang pada perkembangannya ber-spill over dalam
kerjasama dalam menciptakan hubungan damai :
a) Deklarasi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)
Deklarasi ZOPFAN 1971 di Kuala Lumpur merupakan komitmen politik
dan kerjasama politik dan keamanan ASEAN untuk pertama kalinya dalam
sejarah ASEAN, meskipun ASEAN di design untuk wadah kerjasama
ekonomi, sosial dan budaya saja. Deklarasi ZOPFAN terdiri dari dua
bagian pokok, pendahuluan dan dua paragraf pokok. Pada paragraf pertama
22
menyatakan bahwa negara-negara ASEAN bertekad menjamin pengakuan
dan penghormatan atas suatu Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai,
bebas dan netral terlepas dari campur tangan kekuatan luar. Paragraf ke-2
menyatakan keinginan negara-negara Asia Tenggara memperluas bidang
kerjasama untuk memupuk kekuatan, solidaritas dan hubungan yang lebih
erat dengan sesama negara kawasan.
Dengan demikian ZOPFAN merupakan strategi besar untuk membina
ketahanan regional dan untuk membebaskan diri dari campur tangan pihak
luar, baik dengan menggalang kekuatan intra kawasan maupun mengatur
keterlibatan negara-negara luar kawasan di Asia Tenggara. Konsep
ZOPFAN sebenarnya merupakan kompromi dari berbagai pendapat negara
anggota ASEAN khususnya Indonesia dan Malaysia. Prakarsa netralitas
ASEAN oleh Malaysia dilatar belakangi dengan pertimbangan politik
domestik kerusuhan berdarah di Malaysia tahun 1969. Konflik rasial ini
dikhawatirkan akan mengundang perhatian China karena banyaknya warga
Malaysia keturunan Cina. Malaysia berharap agar prinsip netralitas tersebut
bisa menghalangi Cina melakukan campur tangan terhadap urusan dalam
negeri Malaysia. Sementara Indonesia menerjemahkan ZOPFAN sebagai
netralitas ASEAN dari kerjasama militer dengan negara-negara barat.
Adalah ironis kerjasama militer antara Malaysia, Singapura, Inggris,
Australia, dan Selandia Baru yang tergabung dalam Five Powers Defence
Arrangement (FPDA), ditandatangani pada tahun yang sama dengan
lahirnya konsep ZOPFAN pada tahun 1971 (Anwar, 1993 : 324). Di dalam
deklarasi ZOPFAN terdapat berbagai langkah prosedural dan strategis
untuk memenuhi tuntutan tersebut yang secara keseluruhan bukan hanya
memusatkan perhatiannya pada perlucutan senjata atau pencegahan
profilerasi nuklir melainkan meliputi juga kerjasama politik, ekonomi dan
fungsional lainnya. ZOPFAN bisa mengurangi kebutuhan akan intervensi
militer langsung negara-negara besar, dan yang lebih penting lagi,
23
menghindarkan negara-negara kecil mengundang atau mempropokasi
keterlibatan negara-negara besar dalam masalah-masalah bilateralnya
b) ASEAN Concord I
Perubahan situasi politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara yang
ditandai dengan penarikan tentara AS dari Vietnam Selatan mulai 1973 dan
kemenangan Vietnam Utara atas Vietnam Selatan pada tahun 1975 telah
mengubah konfigurasi politik dan keamanan di Asia Tenggara. Peristiwa
ini mendorong para pemimpin ASEAN untuk menilai kembali situasi Asia
Tenggara dan mempertegas maksud dan tujuan pembentukan ASEAN.
Para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengadakan KTT I di Bali, 23-25
Febuari 1976 untuk membahas perubahan tersebut dan merumuskan
langkah dan sikap strategis ASEAN. Pertemuan tersebut menjadi momen
penting dalam evolusi kerjasama keamanan ASEAN. KTT I yang
berlangsung di Bali dikemudian hari lebih dikenal sebagai Bali Concord I
melahirkan dua dokumen, yaitu; Deklarasi Kesepakatan ASEAN
(Declaration of ASEAN Concord) dan Perjanjian Persahabatan (Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast Asia).
Kedua dokumen tersebut mencerminkan penegasan kembali komitmen
negara-negara ASEAN terhadap; Deklarasi Bandung, Deklarasi Bangkok,
Deklarasi ZOPFAN, dan Piagam PBB, serta menegaskan tekad negara-
negara ASEAN untuk meningkatkan perdamaian, kemajuan, kemakmuran
dan kesejahteraan negara-negara ASEAN, melalui upaya stabilitasi politik
kawasan Asia Tenggara
4.2 Peran ASEAN dalam Mengatasi Terorisme di Asia Tenggara
24
4.2.1 Pentingnya Pemberantasan Terorisme di Asia Tenggara
Di Eropa, berbagai perbedaan masa lalu yang menjadi sumber konflik
semakin teratasi dan melenyap. Sebaliknya, di Asia Tenggara, masalah-
masalah warisan kolonialisme bermunculan dan berdampak pada stabilitas
dalam negara dan antar negara, seperti di Timor-Timur (Indonesia), di
Mindano (Filipina), dan Pathani (Thailand). Warisan kolonialisme yang
belum selesai juga telah mengakibatkan sulitnya penyelesaian masalah
perbatasan antar negara anggota ASEAN. Antara Indonesia-Malaysia,
misalnya, setelah selesai masalah Sipadan-Ligitan, masalah baru muncul
dan berpotensi dan menganggu hubungan bilateral, misalnya, soal
kepemilikan pulau Ambalat. Ini belum termasuk persoalan dari garis
perbatasan darat di sepanjang Pulau Kalimantan. Demikian pula, Indonesia
menghadapi masalah perbatasan dengan Singapura dalam soal garis
perbatasan laut di sekitar Riau, dan dengan Filipina dalam status pulau-
pulau di Utara Sulawesi, yang secara sepihak telah di klaim dalam konstitusi
Filipina sebagai miliknya. Kolonialisme selain meninggalkan konflik
domestik, yaitu konflik etnik dan agama dalam negara anggota ASEAN,
juga sangat rawan menimbulkan sengketa antar negara, yaitu sengketa
perbatasan. Kasus ambalat sempat berkembang ke arah yang
mengkhawatirkan. Hal ini terjadi karena negara-negara ASEAN yang
terlibat dalam konflik selama ini selalu berusaha menyimpan masalah yang
ada dan tidak berupaya menyelesaikannya secara tuntas di dalam forum
ASEAN (Acharya, 2001 : 6). Ini bisa terjadi akibat masih lemahnya
mekanisme resolusi konflik dalam ASEAN, sehingga selalu saja
penyelesaian konflik perbatasan antar negara anggotannya diserahkan pada
mediasi pihak asing, yang hasilnya belum tentu memuaskan semua pihak
yang bersengketa. Belum lagi ditambah kasus Myanmar dan penahanan
Aung San Suu Kyi, yang telah menghasilkan respon yang berbeda dari
anggota ASEAN. Respon yang bersikap keras dari Malaysia, Filipina, dan
25
Singapura sempat mengarah pada wacana pemberian sanksi pada Myanmar,
sekalipun mekanisme semacam itu belum pernah di atur. Dimasa depan,
perlu dipikirkanpemberian sanksi kepada negara-negara anggota ASEAN
yang dianggap tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati. ASEAN
bisa dinilai sebagai sebuah organisasi yang mendukung sebuah rezim yang
tidak menghormati HAM dan Demokrasi, karena tujuan ASEAN lebih
banyak ditentukan oleh keinginan untuk menjamin kelangsungan hidup
rezim non-demokratis. Hal ini diperparah ketika ASEAN justru menerima
Myanmar menjadi anggota pada tahun 1997. Sebaliknya, jika ada kewajiban
dan sanksi dan demokratisasi menjadi keharusan bagi setiap negara anggota,
maka setiap anggota yang tidak menjalankan dapat dikenakan sanksi, mulai
dari yang ringan yang berat. Sanksi itu bisa berupa pengucilan atau
harus menarik diridari keanggotaan (Sukma, 2006 : 53).
Prinsip non-interfence dan state soverignty adalah sumber dari
persoalan tersebut diatas. Diakui bahwa prinsip non intervensi dan integritas
kedaulatan nasional terhadap urusan domestik negara-negara anggota
ASEAN merupakan prinsip yang paling kontroversial dalam tubuh ASEAN,
dan oleh karenanya menjadikan perkembangan ASEAN sebagai organisasi
regional menjadi agak terhambat. Seharusnya apabila terdapat isu-isu yang
mempengaruhi hubungan bilateral, regional dan ekstra regional,
maka “prinsip non-interfence dapat diabaikan”, walaupun prinsip tersebut
telah melekat dalam tubuh ASEAN sejak awal pembentukannya(Pitsuwan,
2006 : 11). Masalah state sovereignty (kedaulatan nasional) yang
menghambat perkembangan ASEAN, tidak hanya terkait dengan persoalan
batas wilayah, tetapi juga masih beratnya negara anggota untuk dapat
menerima pemberlakuan atas azas supranasional dalam pengambilan
keputusan di ASEAN. Berbeda dengan Uni Eropa, didalam ASEAN
perbedaan-perbedaan identitas nasional semakin menguat dan menyulitkan
proses integrasi. Padahal, untuk dapat terciptanya ASC, setiap negara
26
anggota harus bersedia menanggalkan sebagian kedaulatan nasional dan
menukarkannya dengan kedaulatan bersama atau supranasional. Dengan
demikian, akan mudah bagi ASEAN untuk mengambil keputusan kolektif
secara efektif. Tidak seperti selama ini, setiap keputusan dalam resolusi
yang dihasilkan diserahkan atau tergantung kepada masing-masing
anggotanya untuk menjalankannya, tanpa kewajiban untuk menaatinya dan
sanksi yang diberikan, jika terjadi pelanggaran. ASEAN sering terperangkap
di antara retorika dan realita. Selama lebih dari 40 tahun usia ASEAN,
organisasi ini sudah banyak berbicara tentang kerjasama, tetapi ketika betul-
betul di butuhkan malah tidak terjadi. Dibalik semua sopan santun tentang
solidaritas dan kerjasama, semua persoalan yang dapat menegangkan daya
santai kelompok regional ini dan prinsip tidak saling mencampuri urusan
dalam negeri jelas harus dikaji ulang. Norma dan prinsip ASEAN yang
masih berlaku, yaitu memendam konflik dengan senyum di padang golf
sementara suasana di sekitarnya diselimuti oleh masalah kawasan lintas
batas yang tak kunjung padam karena mekanismenya tidak efektif dan
efisien. Apa yang disebut sebagai satu Asia Tenggara (One Southeast
Asia)tetaplah merupakan kumpulan dari banyak pusat
pengambilan keputusan dengan mekanismenya masing-masing. Minimnya
kepedulian rakyat ASEAN akan organisasi ASEAN jelas merupakan
kelemahan lain dari ASEAN yang dapat menghambat akselerasinya dalam
menuju integrasi komunitas ASEAN 2015. Dibenak mereka ASEAN hanya
berupa akronim organisasi di wilayah Asia Tenggara. ASEAN bukanlah
identitas mereka. Konsep We Feeling yang bermakna dalam bagi pemimpin
ASEAN ternyata bukanlah apa-apa bagi mereka. Amitav Acharya yang
seorang konstruktivist dan banyak diilhami oleh pemikiran Karl Dutsch
menyatakan bahwa membentuk suatu komunitas dalam bidang apapun,
maka We Feeling itu harus sudah ada. Tetapi jika kita lihat pada komunitas
yang ada di ASEAN, bahwa We Feeling itu tidak ada sama sekali, apalagi
jika disangkut pautkan dengan budaya dari masing-masing negara. We
27
Feelingitu hanya akan ada ketika memang terjadi ancaman yang dianggap
hal berbahaya secara bersama-sama. Identitas sebagai satu ASEAN saja
tidak dimiliki oleh masyarakat setiap negara anggota, karena didalam
internal negara-negara itu sendiri masih terjadi konflik antar ras, budaya
suku. Bagaimana mungkin mengakui bahwa kita sebagai suatu identitas
regional bersama, jika didalam negeri saja identitas nasional masih menjadi
masalah. Tradisi ASEAN yang telah berhasil melayani para anggotanya
selama lebih dari 40 tahun dalam mengambil keputusan bersama yang
berdasarkanmusyawarah untuk mencapai mufakat mungkin akan
menghadapi tantangan besar dimasa depan. Pemerintah negara anggota
ASEAN makin lama akan makin sering mendengarkan keluhan dan tuntutan
dari rakyat negaranya sendiri dan rakyat negara anggota lainnya. Jika ada
mekanisme untuk menyalurkan keluhan dan tuntutan tersebut maka slogan
satu Asia Tenggara akan benar-benar memiliki makna. Bukan menjadi
rahasia umum lagi bahwa masalah besar yang dihadapi ASEAN selama ini
adalah lemahnya implementasi dari berbagai prakarsa dan program yang
telah disepakati bersama, baik di tingkat para pemimpin ASEAN maupun di
tingkat pertemuan menteri-menteri ASEAN. Negara-negara ASEAN
memang pandai didalam merumuskan program-program kerjasama,
mengadakan seminar, konferensi, workshop, lokakarya, atau meeting
(rapat), tetapi senantiasa lemah dalam pelaksanaannya. Hal ini diakui dalam
laporan eminent persons groups (EPG) on the ASEAN Charter (Desember
2006) dan menjadi landasan bagi usulan untuk memperkuat kelembagaan
ASEAN, termasuk peran dari sekretaris Jenderal ASEAN. Selain
memperkuat peran Sekretariat ASEAN, kegiatan pemantauan (Monitoring)
diusulkan untuk melibatkan pihak-pihak non pemerintah agar dapat dibuat
penilaian yang obyektif dan dapat dikembangkan mekanisme yang dapat
mendorong proses pelaksanaan kesepakatan oleh masing-masing negara
ASEAN (Soesastro, 2007 : 321). Disini pemimpin negara-negara ASEAN
harus segera mengesampingkan basa basi khas ASEAN dan muncul dengan
28
langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah yang melintasi garis batas
kedaulatan negara.
4.2.2 Analisis Mengenasi ASEAN Convention on Counter Terrorism
Sungguhpun ada prospek bagi ASEAN didalam mewujudkan Security
Community, namun berbagai kendala tentu saja jelas ada. Secara mendasar
sejak awal pembentukan ASEAN jauh berbeda dengan Uni Eropa dalam
tingkat heterogenitasyang dihadapi. 10 negara Asia Tenggara mempunyai
berbagai keragaman baik dibidang budaya, ras, agama dan dipengaruhi
oleh aneka kekuatan serta berbeda tingkat pertumbuhan ekonomi, dan
beragam pandangan politik dan ideologi. Apalagi rakyat Asia Tenggara
belum terbiasa menjadi satu. Sejarah Asia Tenggara hampir selalu
terpecah-pecah dan diperburuk oleh kepentingan asing di kawasan.
Penduduk ASEAN sangat majemuk, baik dari segi etnis, bahasa, maupun
agama. Dalam sebuah negara Indonesia, misalnya, terdapat begitu banyak
kelompok etnis dan sub-etnisnya, yang juga hidup dengan bahasa lokal dan
kebudayaannya masing-masing. Berbeda dengan kondisi di Uni Eropa,
yang dalam setiap negara paling tidak terdapat satu atau tidak lebih dari
empat kelompok etnis asli sehingga juga tidak terdapat banyak bahasa yang
digunakan penduduknya dalam sebuah negara atau pun antar negara.
Dengan begitu, pembentukan negara bangsa Nation State anggota Uni
Eropa tidak sesulit pembentukan negara bangsa di negara anggota ASEAN,
mengingat tidak sulit untuk mencari bahasa komunikasi (Lingua franca)
yang bisa digunakan dalam kegiatan organisasi regional mereka. Anggota
Uni Eropa bisa dipersatukan oleh bahasa Inggris dan Latin karena mandala
Eropa pernah dikuasai Romawi. Sementara, ASEAN belum bisa menerima
kehadiran Bahasa Melayu sebagai Lingua franca, sebab pengaruh bahasa
ini tidak mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahasa resmi yang
dipakai dalam pertemuan-pertemuan ASEAN adalah bahasa Inggris,
29
sedangkan Kamboja dan Laos, misalnya, hampir tidak mampu berbahasa
Inggris. Bahasa asing yang mereka kuasai adalah Perancis.
Disamping itu, penyebaran agama yang homogen yang terjadi di
Eropa juga tidak dialami di Asia Tenggara. Secara realistis, agama Kristen
telah mempertemukan anggota Uni Eropa dalam bahasa dan budaya,
sedangkan di ASEAN di luar agama Hindu dan Budha yang telah lebih
dulu ada, masih ada agama Kristen dan Islam. Bisa dikatakan ASEAN
adalah satu-satunya organisasi regional yang bersifat
Multisivilisasional (Huntington, 1996 : 230-232). Heterogenitas yang
tinggi tidak hanya berimplikasi pada susahnya menyatukan anggota
ASEAN, namun juga lemahnya masing-masing negara anggota dalam
menyelesaikan agenda domestiknya. Tidak mungkin suatu negara dapat
menyepakati sebuah keputusan internasional, jika semua unsur dalam
negerinya belum memiliki persamaan persepsi dan kepentingan.
Heterogenitas kultur juga berdampak pada sulitnya membuat keputusan
yang efektif dan mengikat dalam setiap aktivitas ASEAN dimasa lalu.
Kultur Hinduisme, Budhisme, dan Islam yang mengakar kuat di kawasan
Asia Tenggara memiliki pengaruh atas disepakatinya musyawarah mufakat
dan konsensus sebagai ASEAN way dalam setiap penyelesaian masalah di
kawasan. Hal ini membuat absennya akuntabilitas dan sanksi terhadap
negara anggota, yang dikemudian hari ternyata tidak mematuhi keputusan
yang telah dihasilkan secara mengikat. Situasi yang berbeda tanpa di Uni
Eropa, yang selalu jelas keputusannya, dan mengikat, karena selalu
dilakukan lewat cara pemungutan suara (voting). Di masa depan
pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan
suara (voting) harus diintroduksi dalam berbagai kegiatan atau pertemuan
ASEAN (Sukma, 2006 : 53). Bila sebuah keputusan yang penting
didasarkan pada mekanisme voting, apalagi dalam situasi darurat
(Emergency), hal ini jelas lebih menciptakan good organization
30
governance, terutama untuk menumbuhkan akuntabilitas anggotanya.
Disini, negara-negara anggota ASEAN harus memiliki semangat
penghargaan atas HAM dan keniscayaan pada demokrasi. Mereka tidak
boleh ragu, apalagi menilai bahwa demokrasi adalah sumber masalah baru,
yang akan diciptakan disintegrasi dan instabilitas di tingkat domestik dan
kawasan. Mereka justru harus berpandangan sebaliknya, bahwa sikap anti
demokrasi merupakan kendala bagi terwujudnya ASEAN Security
Community (ASC). Menurut Amitav Acharya, di Eropa budaya politik
demokrasi terkait erat dengan munculnya kecenderungan akan
interdependensi ekonomi yang membantu negara-negara yang tergabung
dalam Uni Eropa untuk menciptakan masyarakat yang berkeamanan.
Sebaliknya ASEAN tidak mempunyai latar belakang kondisi budaya politik
seperti itu. (Acharya, 2001 : 195). Bahkan pada kenyataannya, banyak
kalangan menilai sebagian besar negara-negara anggota ASEAN tidak
demokratis sama sekali, karena mereka rata-rata mempunyai catatan buruk
dibidang HAM akibat masih kuatnya prinsip non interference dianut
negara anggotanya (Hofmann, 2006 : 58). Jelas bahwa yang dikatakan
sebagai sebuahSecurity Community adalah ketika didalam komunitas
keamanan tersebut mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-
nilai demokrasi. Jika ASEAN ingin tetap konsisten dengan komitmennya
mencapai komunitas keamanan pada 2015, maka pemerintah dari masing-
masing negara anggota jelas harus menghapuskan bentuk suksesi
kepemimpinan regional secara inkonstitusional seperti kudeta oleh junta
militer dengan menggulingkan kekuasaan legal seorang presiden atau
Perdana Menteri dengan cara-cara yang dapat menimbulkan aksi kekerasan
dan instabilitas nasional, seperti di Thailand. Komunitas Keamanan
ASEAN nantinya juga telah harus menghilangkan pergantian
kepemimpinan dengan cara-cara tidak demokratis. Melihat rencana aksi
komunitas keamanan ASEAN, jelas struktur politik kawasan ASEAN
diarahkan untuk semakin maju, terbuka, dan demokratis. Langkah
31
pembangunan politik melintasi isu-isu sensitif yang menyangkut demokrasi
layaknya di negara maju, penyelenggaraan pemilu yang bebas,
pemberantasan korupsi, pemeirntah yang bersih, penegakan dan supermasi
hukum, promosi pengembangan HAM hendaknya tidak menjadi retorika
politik. Bangunan ASEAN adalah rumah besar yang menggelindingkan
ASEAN shared-common value baru, yang menjunjung tinggi bahasa global
dunia, demokrasi di bawah pemeirntah yang baik. Elemen kemanusiaan
sudah pasti harus mendapat porsi yang lebih besar didalam konsep
komunitas keamanan ASEAN, dengan lebih menciptakan situasi kondusif
dalam hal kebebasan berpartisipasi dan menegakkan hak-hak asasi manusia
agar masyarakat ASEAN bisa melindungi dirinya sendiri. Memang
termasuk tanggung jawab pemerintah memberi perlindungan pada
rakyatnya tetapi perangkat terbaik dalam human security itu adalah
masyarakat itu sendiri. Itu memang tidak akan tercapai tanpa kebebasan
politik, partisipasi, dan pemenuhan hak individu. Semua harus
bersifat bottom up, bukan top down. Referensi model keamanan yang
berkisar pada prinsip non interfence yang mendasari ASEAN Way dewasa
ini ditantang oleh suatu model keamanan yang sangat luas (comprehensive
security) dan bersifat non konvensional, yaitu model keamanan
manusia (human security) dan upaya untuk melibatkan masyarakat luas
dalam kegiatan ASEAN. Model ini mengetengahkan kesejahteraan
perorangan yang harus dijamin oleh negara. Ia berpusat pada keamanan
atau ketidakamanan manusia sebagaimana ia terkait dengan negara atau
tatanan internasional. Masalah keamanan manusia ini memunculkan
perdebatan tentang intervensi dan non intervensi dalam masalah dalam
negeri negara anggota ASEAN. Kasus Myanmar dan Kamboja merupakan
tantangan pertama bagi kebijakan non intervensi dalam masalah dalam
negeri negara anggota ASEAN. (Kraft, 2006 : 26-28). Masalah Myanmar
bisa membuat ASEAN dinilai negatif karena ASEAN akan dianggap
mendukung sebuah rezim yang tidak menghormati HAM (Perwita, 2006 :
32
154), sehingga muncul kesan walaupun pembentukan ASEAN didasarkan
pada ikatan biografis, kesejarahan dan budaya di Asia Tenggara, pada
kenyataannya pendorong utama regionalisme ASEAN lebih banyak
ditentukan oleh keinginan untuk menjaminregime survival. Sampai
munculnya ASEAN Charter 2007, semua negara anggota ASEAN masih
menganggap bahwa prinsip non intervensi sangat penting bagi hubungan
antar bangsa. Oleh karena itu, bila penghargaan atas HAM dan Demokrasi
dapat dipatuhi oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai bagian dari
pemahaman baru keamanan non konvensional yaitu human security, maka
bisa dikatakan bahwa ASEAN bukanlah melulu Asosiasi pemerintahan,
politisi dan birokrat semata, melainkan juga akan menjadi komunitas yang
lebih luas dengan merangkul kalangan masyarakat sampai tingkat paling
bawah, karena selama ini ada anggapan bahwa ASEAN dianggap belum
mampu menciptakan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih luas
dalam memberikan kontribusi yang lebih bermakna sepanjang perjalanan
organisasi regional ini selama lebih dari 4 dasawarsa.
33
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Prinsip non-interfence dan state soverignty adalah sumber dari persoalan
tersebut diatas. Diakui bahwa prinsip non intervensi dan integritas kedaulatan
nasional terhadap urusan domestik negara-negara anggota ASEAN merupakan
prinsip yang paling kontroversial dalam tubuh ASEAN, dan oleh karenanya
menjadikan perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional menjadi agak
terhambat. Seharusnya apabila terdapat isu-isu yang mempengaruhi hubungan
bilateral, regional dan ekstra regional, maka “prinsip non-interfence dapat
diabaikan”, walaupun prinsip tersebut telah melekat dalam tubuh ASEAN sejak
awal pembentukannya(Pitsuwan, 2006 : 11). Masalah state
sovereignty (kedaulatan nasional) yang menghambat perkembangan ASEAN,
tidak hanya terkait dengan persoalan batas wilayah, tetapi juga masih beratnya
negara anggota untuk dapat menerima pemberlakuan atas azas
supranasional dalam pengambilan keputusan di ASEAN. Berbeda dengan Uni
Eropa, didalam ASEAN perbedaan-perbedaan identitas nasional semakin
menguat dan menyulitkan proses integrasi. Padahal, untuk dapat terciptanya ASC,
setiap negara anggota harus bersedia menanggalkan sebagian kedaulatan nasional
dan menukarkannya dengan kedaulatan bersama atau supranasional. Dengan
demikian, akan mudah bagi ASEAN untuk mengambil keputusan kolektif secara
efektif. Tidak seperti selama ini, setiap keputusan dalam resolusi yang dihasilkan
diserahkan atau tergantung kepada masing-masing anggotanya untuk
menjalankannya, tanpa kewajiban untuk menaatinya dan sanksi yang diberikan,
jika terjadi pelanggaran. ASEAN sering terperangkap di antara retorika dan
realita. Selama lebih dari 40 tahun usia ASEAN, organisasi ini sudah banyak
berbicara tentang kerjasama, tetapi ketika betul-betul di butuhkan malah tidak
terjadi. Dibalik semua sopan santun tentang solidaritas dan kerjasama, semua
34
persoalan yang dapat menegangkan daya santai kelompok regional ini dan prinsip
tidak saling mencampuri urusan dalam negeri jelas harus dikaji ulang. Norma dan
prinsip ASEAN yang masih berlaku, yaitu memendam konflik dengan senyum di
padang golf sementara suasana di sekitarnya diselimuti oleh masalah kawasan
lintas batas yang tak kunjung padam karena mekanismenya tidak efektif dan
efisien. Apa yang disebut sebagai satu Asia Tenggara (One Southeast
Asia)tetaplah merupakan kumpulan dari banyak pusat
pengambilan keputusan dengan mekanismenya masing-masing. Minimnya
kepedulian rakyat ASEAN akan organisasi ASEAN jelas merupakan kelemahan
lain dari ASEAN yang dapat menghambat akselerasinya dalam menuju integrasi
komunitas ASEAN 2015. Dibenak mereka ASEAN hanya berupa akronim
organisasi di wilayah Asia Tenggara. ASEAN bukanlah identitas mereka.
Konsep We Feeling yang bermakna dalam bagi pemimpin ASEAN ternyata
bukanlah apa-apa bagi mereka. Amitav Acharya yang seorang konstruktivist dan
banyak diilhami oleh pemikiran Karl Dutsch menyatakan bahwa membentuk
suatu komunitas dalam bidang apapun, maka We Feeling itu harus sudah ada.
Tetapi jika kita lihat pada komunitas yang ada di ASEAN, bahwa We Feeling itu
tidak ada sama sekali, apalagi jika disangkut pautkan dengan budaya dari masing-
masing negara. We Feelingitu hanya akan ada ketika memang terjadi ancaman
yang dianggap hal berbahaya secara bersama-sama. Identitas sebagai satu
ASEAN saja tidak dimiliki oleh masyarakat setiap negara anggota, karena
didalam internal negara-negara itu sendiri masih terjadi konflik antar ras, budaya
suku. Bagaimana mungkin mengakui bahwa kita sebagai suatu identitas regional
bersama, jika didalam negeri saja identitas nasional masih menjadi masalah.
Tradisi ASEAN yang telah berhasil melayani para anggotanya selama lebih dari
40 tahun dalam mengambil keputusan bersama yang
berdasarkanmusyawarah untuk mencapai mufakat mungkin akan menghadapi
tantangan besar dimasa depan. Pemerintah negara anggota ASEAN makin lama
akan makin sering mendengarkan keluhan dan tuntutan dari rakyat negaranya
sendiri dan rakyat negara anggota lainnya. Jika ada mekanisme untuk
35
menyalurkan keluhan dan tuntutan tersebut maka slogan satu Asia Tenggara akan
benar-benar memiliki makna. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa masalah
besar yang dihadapi ASEAN selama ini adalah lemahnya implementasi dari
berbagai prakarsa dan program yang telah disepakati bersama, baik di tingkat para
pemimpin ASEAN maupun di tingkat pertemuan menteri-menteri ASEAN.
Negara-negara ASEAN memang pandai didalam merumuskan program-program
kerjasama, mengadakan seminar, konferensi, workshop, lokakarya, atau meeting
(rapat), tetapi senantiasa lemah dalam pelaksanaannya. Hal ini diakui dalam
laporan eminent persons groups (EPG) on the ASEAN Charter (Desember 2006)
dan menjadi landasan bagi usulan untuk memperkuat kelembagaan ASEAN,
termasuk peran dari sekretaris Jenderal ASEAN. Selain memperkuat peran
Sekretariat ASEAN, kegiatan pemantauan (Monitoring) diusulkan untuk
melibatkan pihak-pihak non pemerintah agar dapat dibuat penilaian yang obyektif
dan dapat dikembangkan mekanisme yang dapat mendorong proses pelaksanaan
kesepakatan oleh masing-masing negara ASEAN (Soesastro, 2007 : 321). Disini
pemimpin negara-negara ASEAN harus segera mengesampingkan basa basi khas
ASEAN dan muncul dengan langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah
yang melintasi garis batas kedaulatan negara.
5.2 Saran
Pengembangan mekanisme yang terkait dengan masalah kelembagaan
ASEAN ini merupakan tantangan terbesar bagi ASEAN. Sejauh ini negara-negara
anggota ASEAN selalu enggan untuk mengembangkan kelembagaan ASEAN.
Sebagai akibatnya, kerja sama ASEAN kini melibatkan beberapa ratus pertemuan
dalam setahun dan bahkan mungkin secara riil hanya terjadi dalam pertemuan-
pertemuan itu. Lemahnya kelembagaan ASEAN adalah akibat dari kekhawatiran
negara-negara ASEAN mengenai pengaruh pengembangan kelembagaan regional
terhadap kedaulatan nasional mereka. Tetapi keinginan untuk mempertahankan
kedaulatan nasional secara absolut sebenarnya bertentangan dengan kesepakatan
untuk memperdalam integrasi ASEAN dan mewujudkan ASEAN Security
36
Community (ASC). Menurut hemat penulis, untuk bisa menjalankan rencana aksi
ASC yang lain terutama di bidang Political Development dan Conflict Resolution
jelas mutlak diperlukan ‘reintepretasi’ dan ‘revitalisasi’ atas prinsip non-
interference dan state sovereignty.
37
DAFTAR PUSTAKA
ASEAN Security Community Plan of Action. Dipetik pada tanggal 7 April
2011, dari: http://www.aseansec.org/16826.htm
Acharya, Amitav. (1998). “Collective Security and Conflict Management in
Southeast Asia”. Dalam Emanuel Adler dan Michael Barnett, Security
Community. Cambridge: Cambridge University Press.
Cipto, Bambang. (2007). Hubungan Internasional di Asia
Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen Pertahanan RI. 2003. Three Pillars of ASEAN. Dipetik pada
tanggal 7 April 2011, dari Bali Concord II Bisa Bawa ASEAN ke Arah Integrasi:
http://thainews.prd.go.th/newsenglish/14th_aseansummit_e/index.php?
option=com_content&task=view&id=16&Itemid=6
Jones, David M. & Smith, Michael L. R. (2002). ASEAN's Imitation
Community. Orbis, 46 1. Hal. 93-109.
Khoo, Nicholas. (2004). “Deconstructing The ASEAN Security Community:
A Review Essay”. International Relations of The Asia-Pasific, Volume 4. Oxford
University Press & Japan Association of International Relation. Hal. 35-46.
38