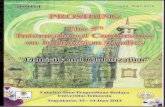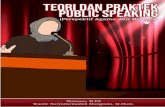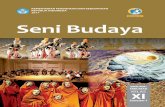Sendikraf - BBPPMPV Seni dan Budaya
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Sendikraf - BBPPMPV Seni dan Budaya
ISSN 27 46-3605
Analisis Tokoh Koyal dalam Mega,Mega Karya Arifin C. Noer: Konsep Subjek Slavoj Zizek Elyandra Widharta
Lantunan Eb Suku Yaghai Mappi Papua: Hubungan Makna, Bentuk, don Struktur Septina Rosalina Layan
Konsep Nyupak dalam Karawitan Jawa Sito Mardowo
Pandawa Lima: Perwujudan Nilai-Nilai Karakter Bangsa Purwadi
Pemanfaatan Kamera Lubang Jarum pada Pembelajaran Seni Budaya bagi Siswa Sekolah Dasar: lmplementasi Keterampilan Abad 21 Briliyan Syarifudin Ahmad
Peningkatan Kemampuan Peserta Didik dalam Mengidentifikasi Akor Musik dengan Teknik 'T upatma' Rus Endarti
Penggunaan Shapes Tools pada Microsoft Word untuk Meningkatkan Kemampuan Menggambar Comic Strips Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pacitan Ninik Setyawati
Volume 2 No 1 Mei 2021
�
..
.:-- :.
u.:v-w BBPPMPV SENIDANBUDAYA
BBPPMPV SENI DAN BUDAYA
DEWAN REDAKSI SENDIKRAF Jurnal Pendidikan Seni dan Industri Kreatif Penanggung Jawab
Dr. Dra. Sarjilah, M.Pd.
Penyunting Penyelia Dr. Rin Surtantini, M.Hum.
Penyunting Pelaksana Eko Santoso, S.Sn.
Tim Editor
Drs. Rahayu Windarto, M.M. Feti Anggraini, S.Ant., M.A Dr. I Gede Oka Subagia, M.Hum.
Dr. Diah Uswatun Nurhayati, M.Sn. Drs. Fajar Prasudi, M.Sn. Rohmat Sulistya, S.T., M.Si. Cahya Yuana, S.Sos., M.Pd. R. Haryadi Purnomo, S.T., M.Si. Dr. Wuryaningsih, S.Sos., M.Acc. Bagus Aries Sugiharta, S.S., M.A. Drs. Yoko Rimy, M.Si. Sigit Purnomo, S.Pd., M.Pd.
Mitra Bestari Prof. Drs. Triyono Bramantyo P.S., M.Mus.Ed., Ph.D. (Institut Seni Indonesia Yogyakarta) Prof. Dr. Sugeng Eko Putro Widoyoko, M.Pd. (Universitas Muhammadiyah Purworejo) Prof. Dr. Tri Hartiti Retnowati (Universitas Negeri Yogyakarta)
Sekretariat
Fatkhiyatun Jannah, S.H. Khumaidi Usman, S.E., M.Pd. Ambar Wahyu Astuti, S.H., M.Pd. Tri Widy Astuti, S.H., M.H. Aprilia Dwi Afsari, A.Md. Desain Grafis/Tata Letak
Budi Saptoto, S.Pd., M.Pd. Muhibbul Khoiri, S.Pd. Janu Riyanto, S.Sos., M.Sn.
Jurnal Sendikraf mulai terbit pada bulan November tahun 2020, terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Mei dan November, memuat artikel hasil penelitian atau hasil kajian maupun gagasan konseptual pada bidang pendidikan seni dan industri kreatif. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya Jl. Kaliurang Km. 12,5, Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY, Indonesia 55581 Pos-el: [email protected]
ISSN 2746-3605
ISSN 2746-3605
Volume 2 No 1 Mei 2021 Daftar Isi (Halaman i) Editorial (Halaman ii-iv)
Analisis Tokoh Koyal dalam Mega,Mega Karya Arifin C. Noer: Konsep Subjek Slavoj Žižek (Halaman 1-11) Elyandra Widharta
Lantunan Eb Suku Yaghai Mappi Papua: Hubungan Makna, Bentuk, dan Struktur (Halaman 12-23) Septina Rosalina Layan
Konsep Nyupak dalam Karawitan Jawa (Halaman 24-33) Sito Mardowo
Pandawa Lima: Perwujudan Nilai-Nilai Karakter Bangsa (Halaman 34-45) Purwadi Pemanfaatan Kamera Lubang Jarum pada Pembelajaran Seni Budaya bagi Siswa Sekolah Dasar: Implementasi Keterampilan Abad 21 (Halaman 46-54) Briliyan Syarifudin Ahmad Peningkatan Kemampuan Peserta Didik dalam Mengidentifikasi Akor Musik dengan Teknik ‘Tupatma’ (Halaman 55-63) Rus Endarti
Penggunaan Shapes Tools pada Microsoft Word untuk Meningkatkan Kemampuan Menggambar Comic Strips Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pacitan (Halaman 64-74) Ninik Setyawati Penulisan Artikel Jurnal Sendikraf (Halaman 75)
i
EDITORIAL
Volume kedua Jurnal Sendikraf yang terbit pada bulan Mei 2021 ini ditandai dengan tujuh artikel terseleksi yang dimuat sebagai isi pada nomor pertama ---dari rencana dua nomor edisi penerbitan pada tahun 2021. Dengan usianya yang masih sangat belia, edisi ini tetap lahir dengan spirit yang sama dengan edisi perdananya pada bulan November 2020 lalu, yaitu berbagi dan menerima dalam koridor akademis melalui proses belajar yang melibatkan terjadinya proses berpikir tanpa henti.
Ketujuh artikel pada edisi ini ---meskipun dalam konteks akademis maupun teknis sudah pasti tidak luput dari adanya keterbatasan dalam berbagai aspek--- telah diupayakan untuk dapat disajikan secara optimal melalui tahapan perjalanan yang hening dan panjang. Perjalanan sunyi ini bersama-sama ditempuh oleh pengelola jurnal, para penulis, tim editor, dan mitra bestari, dalam upaya memaknai dan mengembangkan cara pandang akademis yang konsisten. Kesabaran, ketekunan, kecermatan, ketelitian, dan berkonsentrasi juga merupakan nilai-nilai yang dijalani dalam proses penerbitan jurnal ini. Dalam edisi Mei 2021 ini tersaji tulisan yang merupakan hasil dari proses penelitian sesuai dengan jenis data yang diperoleh, terdapat pula hasil kajian atau gagasan konseptual dengan menggunakan pisau bedah atau pisau analisis tertentu. Semua ini dimaksudkan untuk memberi warna atau corak dari Jurnal Sendikraf ini. Dengan demikian, sebuah harapan akan terus terjaga, disepakati, dan dibangun, seiring dengan menyembulnya sebentuk bola kuning pada kaki langit di ufuk timur bumi setiap saat fajar tiba: Jurnal Sendikraf diharapkan dapat terus menyebarkan cahayanya bagi banyak pihak yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai akademis serta bidang seni (industri kreatif) dan pendidikan seni yang melingkupinya.
Artikel pertama disajikan oleh Elyandra Widharta; kajian ini menganalisis secara deskriptif tokoh Koyal dalam lakon Mega,Mega karya Arifin C. Noer (1966) berdasarkan konsep subjek Slavoj Žižek yang berpijak dari konsep psikoanalisis milik Lacan. Lakon yang masih memiliki relevansi dengan situasi sosial saat ini bercerita tentang dunia dan nasib para gelandangan yang termarjinalisasi dengan latar era pembangunan di Indonesia pada tahun 1960-an. Di dalam konsep subjek ini, tahapan yang dialami oleh manusia dalam eksistensinya dibagi menjadi tiga, yaitu The Real, The Imaginary, dan The Symbolic. Sebagai subjek, manusia memiliki caranya sendiri untuk dapat melanggengkan eksistensinya. Ia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh fantasi (imajinasi) dan ideologi. Menggerakkan fantasi untuk memenuhi hasrat ideologisnya menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh manusia. Analisis terhadap perjalanan laku Koyal dalam naskah lakon ini dapat menjadi refleksi pada laku hidup manusia, yaitu ketika seseorang dalam usahanya menolak The Real, ia melalui fase The Imaginary untuk mencapai eksistensi diri dalam The Symbolic. Yang terjadi, sebagai realitas baru, posisi The Symbolic atau The Real (yang sesungguhnya) selalu saja gagal karena munculnya faktor eksistensi manusia lain sebagai The Imaginary, tempat disandarkannya capaian eksistensi diri itu.
Dalam artikel kedua, Septina Rosalina Layan mengulas keterkaitan yang erat antara makna, bentuk, dan struktur pada lantunan atau nyanyian Eb, yang merupakan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap Eb sebagai tradisi lisan yang hidup, berkembang, dan diwariskan secara turun temurun pada kehidupan masyarakat suku Yaghai Mappi Papua. Kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan banyak dikisahkan melalui lantunan Eb yang menunjukkan bahwa Eb merupakan simbol dari nilai-nilai budaya lokal yang lahir secara alami dari gagasan serta berbagai perasaan manusia Suku Yaghai. Simbol-simbol ini memiliki makna sesuai dengan bentuk dan struktur lantunan Eb yang khas, yang juga menunjukkan terdapatnya jenis-jenis dari Eb itu sendiri, yaitu Eb Biasa, Eb Oghob, Nama Eb, dan Qaqau Eb. Pencatatan, pengkajian, dan analisis terhadap bentuk, struktur, serta makna Eb dari Papua ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya dokumentasi dan pemetaan budaya etnis yang masih hidup dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
ii
Artikel ketiga oleh Sito Mardowo mengetengahkan konsep nyupak dalam seni karawitan Jawa yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memeroleh formulasi pelarasan bumbungan gender dan pelarasan nada-nada gamelan. Pada kegiatan sehari-hari, istilah nyupak itu sendiri sebetulnya dapat ditemui berkaitan dengan kegiatan menyambung suatu benda yang terdiri dari dua elemen, yaitu benda yang disambung sebagai benda utama dan benda yang menyambung, sehingga benda utama dapat digunakan kembali sesuai dengan keperluannya. Tradisi pelarasan bumbungan dan nada-nada gamelan yang masih mengandalkan kepekaan telinga dalam menangkap frekuensi nada merupakan keterampilan yang sangat sulit untuk dipelajari karena memerlukan bakat dan pengalaman yang relatif lama agar telinga menjadi sangat peka terhadap frekuensi nada. Formulasi pelarasan berupa rentang frekuensi interval yang terdapat pada sistem pelarasan bumbungan dan nada gamelan sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesulitan pada kepekaan telinga dalam menangkap frekuensi nada, atau membantu kepekaan telinga terhadap frekuensi nada ketika melakukan pelarasan bumbungan gender dan pelarasan nada gamelan.
Beranjak ke sajian artikel keempat, Purwadi melakukan kajian terhadap karakter Pandawa Lima dari data kualitatif yang berupa ungkapan-ungkapan verbal yang dijumpai pada naskah lakon dan pementasan wayang kulit. Menggunakan lima nilai utama pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, analisis konten dilakukan terhadap tokoh-tokoh Pandawa (Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa). Hasil kajian atau analisis yang dilakukan menunjukkan terdapatnya kandungan nilai-nilai religius, nasionalis, mandiri, sikap gotong royong, dan integritas, yang muncul pada perwujudan kelima tokoh wayang kulit ini. Dalam pembahasan, nilai-nilai utama pendidikan karakter bangsa ini dikupas secara kontekstual untuk memperlihatkan representasi dari pengembangan nilai-nilai karakter yang lebih mendalam. Kajian ini menempatkan produk budaya etnis, khususnya wayang kulit, sebagai sumber gagasan, pengetahuan, wawasan, pandangan, maupun pemikiran manusia yang kaya dan tidak habis-habisnya untuk terus menerus digali.
Melalui artikel tentang pemanfaatan kamera lubang jarum yang merupakan artikel kelima pada edisi ini, Briliyan Syarifudin Ahmad mengingatkan pentingnya pendidik untuk selalu berkreasi dalam merancang alternatif materi dan media pembelajaran sebagai upaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Tak dapat dipungkiri bahwa keterampilan abad 21 juga menjadi pertimbangan atau basis yang penting dalam merancang pembelajaran pada masa kini. Pemanfaatan kamera lubang jarum pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya di sekolah dasar diyakini menjadi salah satu alternatif materi pembelajaran yang melatih murid-murid untuk berproses dan belajar menyelesaikan masalah, mengembangkan kreativitas, membangun kolaborasi, dan menjalin komunikasi. Lebih jauh lagi, materi ini memungkinkan pendidik untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai subjek pelajaran lain seiring dengan penerapan kurikulum tematik pada sekolah dasar.
Pada artikel keenam, Rus Endarti menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukannya untuk mencermati peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi akor musik yang merupakan salah satu tahapan dalam pembelajaran aransemen musik. ‘Tupatma” yang merupakan sebuah teknik untuk menentukan akor dengan menggunakan simbol angka Romawi I, IV, dan V, diperkenalkan kepada peserta didik melalui pembelajaran Seni Budaya. Efektivitas penerapan ‘Tupatma’ diukur melalui penelitian tindakan kelas dengan menggunakan materi lagu yang bertangga nada mayor untuk memberikan efek gembira dan semangat bagi peserta didik dalam mempelajari kompetensi baru yang mendasar. Hasil penelitian tindakan kelas sebanyak dua siklus yang dilakukan dengan model pembelajaran langsung dalam menerapkan teknik ‘Tupatma’ ini memberikan simpulan bahwa teknik ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap terjadinya peningkatan kemampuan peserta didik dalam melakukan identifikasi akor musik.
Edisi Sendikraf pada Mei 2021 ini diakhiri oleh tulisan Ninik Setyawati yang menguraikan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa SMP dalam
iii
menggambar comic strips dengan memanfaatkan shapes tools yang tersedia di aplikasi Microsoft Word dari Microsoft Office. Meskipun bukan merupakan aplikasi menggambar digital, kesederhanaan yang dimiliki oleh shapes tools pada aplikasi ini menawarkan alternatif menggambar komik yang mudah pada pembelajaran Seni Budaya. Serangkaian tahap pembelajaran yang dilakukan dalam kerangka penelitian tindakan kelas mulai dari pra siklus, siklus satu dan dua, serta refleksinya, memberikan gambaran bahwa shapes tools dan shapes style yang digunakan siswa dalam proses menggambar comic strips dapat menghasilkan karya menggambar yang menarik dan memiliki nilai lebih pada setiap siklus yang dilalui. Kreativitas dalam mengolah bentuk tokoh komik, warna, background antarpanel, efek gelap terang tokoh komik, efek bayangan, arah cahaya, dan keterbacaan teks pada balon kata, dinilai sebagai bentuk-bentuk peningkatan kemampuan menggambar yang dicapai oleh siswa.
Ketujuh artikel terseleksi dalam edisi ini tetaplah merupakan bagian dari serangkaian penerbitan Sendikraf ke depan. Permulaan-permulaan dari rangkaian ini diharapkan selalu berproses secara alami dalam menjawab kegelisahan akademis yang tak pernah berakhir. Dukungan dan partisipasi dari jiwa-jiwa yang berkobar dan terpanggil untuk terlibat dalam kegiatan publikasi ilmiah dalam konteks akademis ---yang merupakan wujud dari hasil penelitian, hasil kajian, gagasan konseptual, dan aplikasi teori yang bermuatan seni (industri kreatif) dan pendidikan seni--- akan tetap selalu dinanti. Dengan itu semua, nilai-nilai esensial yang konstruktif pada proses pengembangan Sendikraf semoga akan selalu lahir.
Yogyakarta, Mei 2021. Rin Surtantini
iv
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 1
ANALISIS TOKOH KOYAL DALAM MEGA,MEGA KARYA ARIFIN C. NOER: KONSEP SUBJEK SLAVOJ ŽIŽEK
CHARACTER ANALYSIS OF KOYAL IN ARIFIN C. NOER’S “MEGA,MEGA”:
CONCEPT OF SLAVOJ ŽIŽEK’S SUBJECT
Elyandra Widharta1 [email protected]
ABSTRACT
Slavoj Žižek describes concept of the subject based on Lacan’s psychoanalysis concept. Concept of the subject is divided into three, namely The Real, The Imaginary, and The Symbolic. The three subject concepts are the stages experienced by human beings in their existence. The current study attempts to analyze descriptively the character of Koyal in Arifin C. Noer's “Mega,Mega” employing the concept of Slavoj Žižek's subject. The purpose of analysis is to disclose the existence of Koyal as a paradoxical subject other than the dimensional side. The analysis brings about the conclusions that Koyal is present as a character with high level imagination. He is often considered abnormal by people around him like Hamung, Panut, Retno and Tukijan. Koyal apparently has experienced positions as the Real subject, The Imaginary, and The Symbolic along the plot of the play. However, Koyal has finally failed to reach the Real eventhough he has been reminded through the presence of another subject as The Imaginary. Subsequently, Koyal’s efforts to reach the Symbolic by setting up his existence in a certain position in the middle of the community has also failed.
Keywords: character analysis, subject, Arifin C. Noer, Žižek, “Mega,Mega”.
ABSTRAK
Slavoj Žižek mendeskripsikan konsep subjek yang berpijak dari konsep psikoanalisis milik Lacan. Konsep subjek tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu The Real, The Imaginary, dan The Symbolic. Ketiga konsep subjek ini merupakan tahapan yang dialami manusia dalam eksistensinya. Dalam kajian ini, Koyal sebagai tokoh dalam lakon Mega,Mega karya Arifin C. Noer dipilih untuk dianalisis secara deskriptif berdasarkan konsep subjek Slavoj Žižek. Tujuan analisis adalah untuk mengungkapkan eksistensi Koyal sebagai subjek paradoks selain sisi dimensional. Dari analisis yang dilakukan didapat simpulan bahwa Koyal hadir sebagai tokoh yang memiliki khayalan tingkat tinggi. Ia sering dianggap kurang waras oleh orang di sekitarnya seperti Hamung, Panut, Retno dan Tukijan. Koyal rupanya mengalami posisi sebagai subjek The Real, The Imaginary, dan The Symbolic sepanjang perjalanan lakon. Namun, Koyal akhirnya gagal mencapai The Real meskipun ia diingatkan melalui kehadiran subjek lain sebagai The Imaginary. Usaha Koyal untuk mencapai The Symbolic dengan mendudukkan eksistensi pada posisi tertentu di tengah komunitasnya juga mengalami kegagalan.
Kata kunci: analisis tokoh, subjek, Arifin C. Noer, Žižek, Mega,Mega.
1Elyandra Widharta adalah seorang praktisi teater, lulusan Dramaturgi S1 Seni Teater ISI Yogyakarta, 2007. Aktif berteater sejak tahun 2000 sampai hari ini. Aktor sandiwara berbahasa Jawa di Komunitas Sego Gurih sampai Kelompok Sedhut Senut. Pengalaman sampai saat ini masih aktif sebagai aktor, dramaturg, juri festival teater tradisi, dan kurator festival maupun parade teater. Pernah menulis buku “Pengetahuan Seni Rupa Indonesia, Asia, Eropa dan Amerika” (4 edisi buku pengayaan SMA/SMK, 2014); “Antologi Drama Liturgi” (2019); “Semiotika Lakon Wayang Beber Remeng Mangunjaya” pada Jurnal Tonil Teater ISI Yogyakarta, Vol 17, No 2, 2020. Pernah menjadi seniman undangan dari WCRC (World Communion of Reformed Churches) dalam kolaborasi performance di Leipzig Jerman tahun 2017.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 2
PENDAHULUAN
Mega,Mega merupakan lakon karya Arifin C. Noer yang bercerita mengenai dunia para gelandangan. Lakon ini berlatar kejadian pada era pembangunan di Indonesia tahun 1960-an. Para gelandangan tersebut antara lain Mae, Retno, Hamung, Panut, Koyal, dan Tukijan. Mae adalah gelandangan perempuan lanjut usia yang selalu menaruh rasa iri kepada Retno, tokoh perempuan lain yang masih berusia muda dan memiliki harapan dalam hidupnya meski ia seorang pekerja seks komersial. Hamung, di sisi lain, merupakan penyandang disabilitas yang kakinya cacat dan semasa hidupnya dibesarkan di panti asuhan. Sementara itu, Tukijan adalah seorang yang menyimpan harapan besar menjadi transmigran sukses di Sumatera. Sedangkan Panut, lebih memilih profesi sebagai pencopet. Koyal, tokoh yang akan dianalisis dalam artikel ini, berbeda dengan yang lain, karena memiliki daya fantasi kuat. Ia berkhayal mendapatkan lotre sehingga ia memiliki uang banyak.
Cerita bermula saat Koyal mendapatkan informasi nomor lotre yang keluar. Nomor tersebut hanya selisih satu angka pada bagian digit terakhir dengan nomor yang dibelinya. Lotre bernilai seratus juta rupiah itu jatuh pada nomor 432480, sedangkan milik Koyal bernomor 432488. Perbedaan satu angka inilah yang memicu munculnya konflik. Meski beda satu angka, namun Koyal sangat girang. Ia bersorak-sorak seolah menjadi jutawan. Selisih satu angka inilah yang membuat Koyal berkhayal sebagai pemenang dan hal itu ia ceritakan kepada Mae, Retno, Hamung, Panut, dan Tukijan.
Fantasi Koyal mulai muncul dan ia mengajak kawan-kawannya berfoya-foya. Pesta makan-makan di restoran paling enak, belanja pakaian di Toko Kim Sin, sampai bertamasya ke Tawangmangu. Hal paling di luar dugaan adalah ketika Koyal berkelakar untuk membeli Keraton Mataram.
Retno, Hamung, Panut, Tukijan turut hanyut dalam khayalan Koyal. Fantasi Koyal semakin menjadi-jadi ketika dirinya selalu mendapat dukungan dari Mae. Sebagai orang yang memberikan perlindungan kepada Koyal, Mae memang selalu memberikan dukungannya. Seluruh tindakan maupun perkataan Koyal selalu mendapatkan pembelaan. Namun, Tukijan berbeda, ia justru ingin menyadarkan pada yang lain bahwa itu hanyalah mimpi, tetapi Koyal selalu berhasil mempengaruhinya atas dukungan
dan pembelaan dari Mae. Ketidaksadaran yang menghampiri mereka disebabkan oleh pengaruh Koyal. Tukijan selalu berusaha melawan dunia fantasi Koyal, namun seringkali ia ikut hanyut di dalamnya.
Lakon Mega,Mega pernah dipentaskan oleh Teater Ketjil di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1969 disutradarai langsung oleh Arifin C. Noer. Tahun 1971, dipentaskan ulang di tempat yang sama dan di Surabaya. Mega,Mega yang diterjemahkan dalam bahasa Belanda pernah dipentaskan di Gedung Erasmus Huis Jakarta oleh mahasiswa Fakultas Sastra jurusan Bahasa Belanda Universitas Indonesia, juga dipentaskan di Gedung Schouwburg di Den Haag, Belanda dengan sutradara Rima Melati. Lakon Mega,Mega merupakan karya Arifin C. Noer yang ditulis pada tahun 1966 dan mendapat hadiah sebagai lakon terbaik 1967 dari Badan Pembina Teater Nasional Indonesia (C. Noer, 1999). Lakon ini juga pernah dipentaskan oleh sutradara Agus Imron pada tanggal 4 Mei 2007 di Auditorium Teater ISI Yogyakarta (Widharta, 2007). Selain itu, lakon ini pernah pula dipentaskan oleh mahasiswa Program Studi Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta 11-12 April 2015 di Teater Salihara (Nurjanah, 2015). Pementasan berikutnya oleh kelompok yang sama dilakukan di Malay Heritage Centre Singapore, pukul 20.00 waktu Singapura pada tanggal 23-24 Januari 2016 (Suhartadi, 2016). Meski telah berusia puluhan tahun, naskah Mega,Mega masih memiliki relevansi dengan situasi sosial hari ini. Nakah ini ditulis pada saat kondisi negara Republik Indonesia memasuki era pembangunan di segala bidang. Namun, maraknya pembangunan juga melahirkan dampak lain, salah satunya adalah kemiskinan. Menurut Ensiklopedia Sastra Indonesia (Sugono, 2021), Mega,Mega merupakan representasi atas realitas negara saat itu di mana kaum minoritas juga susah mendapatkan rumah tinggal maupun akses pekerjaan. Pada masa Orde Baru, kaum minoritas mengalami kesulitan mendapatkan tempat tinggal serta fasilitas yang layak. Mereka terpinggirkan dan hidup tanpa kepastian.
Tokoh Koyal merupakan representasi kaum minoritas yang menarik karena sering berada di luar batas kewajaran. Dia adalah manusia dengan fantasi dan ide-ide liar serta eksistensi yang terkadang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Pengaruh atas
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 3
kesenangan, megalomania, bahkan histeria kekuasaan dalam interaksi sosialnya.
Sampai hari ini, kemungkinan masih banyak dijumpai “Koyal” dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manusia yang memiliki ambisi dan dominasi dalam situasi sosial maupun politik, yang kemudian fantasinya mendominasi kuasa dan memberikan pengaruh luar biasa kepada orang lain. Manusia tidak lagi dikontrol oleh pikiran namun justru fantasi yang menjadi kendali bagi diri dan pengaruh pada orang di sekitarnya.
Analisis tokoh Koyal berdasarkan konsep subjek Slavoj Žižek dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran posisi eksistensi paradoks manusia. Fenomena manusia sebagai subjek paradoks rupanya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh fantasi (imajinasi) dan ideologi. Slavoj Žižek memiliki pemikiran relevan dan komprehensif untuk membaca fenomena manusia tersebut. Analisis ini penting bagi para pelaku teater untuk mendapatkan gambaran perwatakan tokoh secara komprehensif melengkapi kajian dimensi tokoh yang biasa dilakukan dalam tradisi teater.
Konsep subjek Slavoj Žižek tepat digunakan untuk menganalisis tokoh Koyal dalam lakon Mega,Mega karya Arifin C. Noer. Hal ini dikarenakan manusia sebagai subjek memiliki cara sendiri untuk melanggengkan eksistensinya. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan menggerakkan fantasi untuk memenuhi hasrat ideologisnya.
Slavoj Žižek adalah filsuf kelahiran Ljubljana Slovenia pada 21 Maret 1949 yang mendapat pengaruh dari Jacques Lacan. Ia mendapat gelar doktor dari Universitas Paris (Engelmann, 2018:129). Pemikiran Žižek cukup menarik dan kontekstual karena ia menggabungkan filsafat dan psikologi. Pemikiran Žižek memang unik, ia bisa membuat filsafat menjadi tampak menyenangkan dengan gayanya yang satir bahkan lelucon. Žižek banyak menulis pemikiran tentang manusia sebagai subjek yang rasional, otonom, atomistik, dan bebas dalam berhadapan dengan dunia (Wattimena, 2011:62).
Pemikiran mengenai subjek yang otonom sekaligus bebas itu sesuai dengan tokoh Koyal dalam lakon Mega,Mega. Sebagai subjek, ia menggiring tokoh-tokoh lainnya masuk ke dalam dunia fantasi. Kehadiran Koyal membawa dramatika lakon menjadi dinamis dan dapat lebih cair untuk masuk ke dalam ruang-ruang simbolik yang ia ciptakan melalui fantasi. Oleh
karena itu, konsep subjek Žižek relevan digunakan untuk menganalisis tokoh Koyal, terutama dari sisi perilaku berdasar hasrat ideologis yang berkaitan dengan fantasi.
Kajian mengenai konsep subjek Žižek pernah dilakukan sebelumnya oleh Nur Holis & Aprinus Salam tahun 2019 dengan judul “Posisi Subjek Tokoh Skeeter dalam Film The Help (2011) Karya Tate Taylor: Kajian Subjektivasi Slavoj Zizek”. Subjek tokoh Skeeter dikaji melalui data yang didapat dari menonton filmnya secara langsung. Sementara dalam kajian ini, konsep subjek digunakan untuk menganalisis tokoh dalam naskah lakon. Perbedaan dasarnya adalah pada data di mana kajian ini mengambil data langsung dari teks lakon sebelum dialihwahanakan menjadi pementasan sehingga belum mengalami sentuhan kreativitas dari bidang lainnya seperti penyutradaraan dan penataan artistik. Dengan demikian, teks lakon yang dikaji belum mengalami interpretasi atau ubahan artistik.
PEMBAHASAN
Tradisi teater mensyaratkan pembacaan teks secara seksama sebelum melakukan langkah kerja artistik berikutnya. Di dalam praktik teater, pembaca bereaksi atas teks lakon yang akan dimainkan. Hal ini merupakan bagian dari proses menghayati peran. Namun, analisis tokoh Koyal dalam lakon Mega,Mega dilakukan dengan tanpa melibatkan proses (praktik) penghayatan peran. Tafsir terhadap tokoh Koyal didapatkan setelah membaca keseluruhan teks lakon, reaksi yang timbul selepas pembacaan, dan kemudian tokoh dianalisis. Sebelum masuk pada tahap analisis deskriptif berdasar konsep subjek Slavoj Žižek, analisis dimensi tokoh perlu dilakukan untuk mendapatkan identifikasi dasar perwatakan tokoh Koyal.
Identifikasi Tokoh Koyal
Identifikasi seorang tokoh dalam teks lakon secara mendasar bisa dilacak melalui analisis dimensi tokoh. Dimensi tokoh tersebut adalah fisiologis, psikologis, dan sosiologis (Satoto, 2012). Harymawan (1988), mendeskripsikan dimensi fisiologis tokoh meliputi usia, jenis kelamin, keadaan tubuhnya, dan ciri-ciri fisik manusia. Dimensi psikologis meliputi mentalitas, ukuran moral, temperamen, perasaan pribadi, dan sikap. Dimensi sosiologis meliputi pendidikan, pekerjaan, peranan di masyarakat, aktivitas sosial, dan suku.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 4
Secara fisiologis, Koyal memiliki perawakan tinggi dan berkulit terang. Hal tersebut diperkuat oleh dialog Hamung berikut ini.
Hamung : Habis kau seperti orang yang kehilangan kepala, kalau kau terus begitu kau bisa jadi calon sinting. Tapi ya bagus juga. Kalau kau miring, si Koyal ada kawannya. Ya tentu ada bedanya. Kalau Koyal kesana-kemari pamer bahwa dia anaknya Belanda dan bangga akan badannya yang jangkung seperti opsir Belanda, sebaliknya kau tentu gembar-gembor bilang masih keturunan Jepang. (Tertawa).
(C. Noer, 1999:22)
Selain dalam dialog, ciri fisik Koyal juga dijelaskan melalui keterangan lakon sebagai berikut.
Lelaki Kurus Tinggi Berkulit Terang Meski Banyak Daki, Dan Berambut Lurus, Muncul Dengan Nafas Kacau. (C.Noer, 1999:27)
Gambar 1. Adegan Koyal (baju kuning) dengan Hamung. Pentas Mega,Mega di Auditorium Teater
ISI Yogyakarta, 2007. (Doc. Pribadi)
Secara sosiologis, Koyal digambarkan sebagai orang yang hidup dalam lingkungan gelandangan bersama Mae, Retno, Hamung, Panut, dan Tukijan. Mereka hidup di salah satu sudut dekat Keraton Yogyakarta. Pengertian gelandangan dalam lakon ini merupakan kaum minoritas yang tinggal berpindah-pindah. Saat peristiwa dalam lakon tersebut, mereka menempati salah satu sudut alun-alun di muka pagelaran keraton di Yogyakarta. Hal itu dapat dilihat dalam dialog berikut.
Mae : Tidak baik. Apalagi untuk malam ini. Aku bilang sekarang. Malam ini malam terang bulan. Sangat menyenangkan tidur di alun-alun ini. Di muka pagelaran. Berkat Sinuwun itu sakti.
Alangkah segarnya. Kita boleh melamun dengan sempurna di sini.
Panut : Tidak bau air kencing seperti di Musium.
(C. Noer, 1999:13)
Posisi Koyal sebagai seorang yatim piatu dan memilih hidup menjadi gelandangan, bergabung dengan tokoh lain, tampak dalam dialog berikut.
Koyal : Itu kau. Saya tetap ambil pusing. Habis saya punya orang tua. Hanya sayang mereka juga paman saya dan keluarganya, semuanya dicincang pemuda-pemuda waktu revolusi dulu. Mereka membantu Belanda dan Jepang. Bagaimana lagi? Kami perlu makan. Akhirnya tinggal saya seorang…
(C. Noer, 1999:34).
Sementara secara psikologis, Koyal digambarkan sebagai orang pintar yang memiliki bakat sejak kecil. Hal itu pernah diceritakan oleh ayahnya sendiri, seorang Kumico pada zaman pendudukan Jepang namun sudah meninggal. Kumico adalah ketua rukun tetangga pada zaman pendudukan Jepang (Moeljadi, 2016). Hal ini dapat dilihat dalam dialog berikut.
Koyal : (Berhenti) Itu sudah bakat. Pinter itu sudah bakat saya. Kau sendiri pernah dengar cerita saya tentang ayah saya yang dulu pernah jadi Kumico. Sudah lumrah kalau dia punya anak sepintar saya. Cuma sayangnya mereka terlampau cepet mati.
(C. Noer, 1999:31)
Namun demikian, oleh lingkungannya Koyal dianggap sebagai orang yang kurang waras. Hal ini bisa dilihat dalam dialog berikut.
Koyal : Kau lihat, Mung. Pada koran ini tertulis “Hadiah seratus juta jatuh pada nomer 432480, Solo”, sedangkan punyaku 432488. Ha, beda satu, kan? (tertawa senang). Hampir aku menang. Betul tidak?
Hamung : Belum menang sudah hilang ingatan. (C. Noer, 1999:28-29)
Di dalam lakon, hanya Mae yang bersedia mendukung Koyal sebagai seorang anak biasa saja seperti orang pada umumnya. Pembelaan Mae ini mungkin paradoks. Di satu sisi karena memang kesadaran Mae atas kondisi Koyal. Sementara di sisi lain Koyal sengaja didukung dan dibela agar ia tetap merasa memiliki kesadaran yang wajar seperti lainnya.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 5
Konsep Subjek menurut Slavoj Žižek Slavoj Žižek mengenalkan konsep subjek berpijak dari Lacan. Menurut Lacan, subjek mengalami tiga tahapan, yaitu fase The Real, fase The Imaginary, dan fase The Symbolic. Antara The Real dan The Symbolic mengalami kekurangan, tidak utuh dan terbelah. Untuk mencari kepastian diri, subjek mengacu pada The Imaginary dan mengkonstruksi dengan hasratnya (Manik, 2015:272-273).
Sementara itu, Žižek menjelaskan konsep subjek sebagai kritik terhadap subjek itu sendiri yang terkait dengan ideologi manusia. Ideologi lahir karena bentukan dari masyarakatnya, karena hasil dari interaksinya. Pada pengertian lain, ideologi menjadi bagian dari subjektivitas. Ideologi menjadi melebur bersama kemampuan pada diri subjek dan lingkungan masyarakat (Setiawan, 2016:2). Žižek membagi konsep subjek dalam tiga perbedaan berdasarkan dorongan (hasrat) ideologi yang dimilikinya. Dorongan ini tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan sekitar subjek atau lingkungan di luar subjek. Dalam The Sublime Object of Ideology (2008), ketiga subjek tersebut adalah (1) subject presumed to believe, (2) subject presumed to enjoy, dan (3) subject presumed to desire. Pertama, subject presumed to believe merupakan subjek yang menerima sistem kepercayaan berdasar informasi atas rumor yang diterimanya melalui kehidupan lingkungan sekitar. Subjek penerima kepercayaan memiliki pengaruh atas tindakan yang dilakukan. Subjek bergerak atas dasar rumor dan informasi yang ia dapatkan, namun subjek juga memiliki kesadaran bahwa rumor yang menyebar juga akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham terhadap situasi (Holis, 2019:526). Kedua, subject presumed to enjoy yaitu subjek yang memiliki rasa ketakutan atas hadirnya subjek lain. Subjek, oleh karenanya, menciptakan tindakan untuk segera memproteksi hal yang menjadi tujuannya atau kenikmatan yang sudah dicapainya. (Žižek, 2008:212) Ketiga, subject presumed to desire yaitu subjek yang memiliki peranan dalam tatanan histeria. Subjek ini beranggapan bahwa dirinya merupakan seorang yang paham tentang cara mengorganisasikan subjek lain demi memuaskan hasratnya. Selain itu, subjek rupanya memerlukan bantuan dari jenis subjek yang lain untuk mengendalikan hasratnya (Žižek, 2008:212).
Sementara di sisi lain, Slavoj Žižek juga menjelaskan konsep subjek sebagai The Real, The Imajinary, dan The Symbolic. Ketiga konsep tersebut memang diadopsi dari psikoanalisis Lacan namun memiliki perbedaan. Lacan memaknai hasrat sebagai “ingin menjadi” dan “ingin memiliki” (Manik, 2015), sementara Žižek memaknainya sebagai dorongan ideologi.
The Real bisa dipahami sebagai cita-cita subjek untuk melakukan sebuah tindakan. Cita-cita tersebut merupakan sesuatu yang utuh dan riil. The Real sejatinya merupakan hal yang tidak akan pernah bisa dibahasakan dan bersifat abstrak. Dalam usaha tersebut, subjek hanya akan bisa menerima enjoyment (subjektivitas) sebagai bentuk menghindarkan diri dari kegagalan abadi terhadap pencariannya. Subjek juga hanya akan mampu mengidentifikasi dirinya melalui the other yang sejatinya berada pada tatanan imajiner (Myers, 2003:25). The Imaginary lebih pada tahapan cerminan subjek melihat dirinya sendiri. Dalam tahapan ini subjek melihat dirinya membutuhkan subjek yang lain agar semakin jelas mengidentifikasi siapa dirinya. Bahkan pada tahapan ini subjek bisa saja tidak sesuai dengan identifikasi yang dilakukan melalui subjek lain, karena adanya sensasi yang timbul dalam dirinya (Myers, 2003:22). The Symbolic, merupakan tahapan ketika subjek sudah berinteraksi dengan hal lain yang mencakup bahasa, sistem, aturan, dan semua struktur dalam kehidupan sosial. Oleh karena yang simbolik ini dianggap baik, maka subjek dengan mudah menerima identitas dirinya bahkan bisa mendudukkan diri pada sebuah posisi dalam suatu kelompok atau komunitas, dan subjek bisa saja mendapat julukan (Žižek, 2008:22). Koyal menurut Konsep Subjek Slavoj Žižek Analisis tokoh Koyal berdasarkan konsep subjek melalui tahapan The Real, The Imaginary, dan The Symbolic dengan dorongan ideologi dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Koyal pada Tahapan The Real The Real merupakan tujuan yang ingin
dicapai oleh Koyal dalam hidup sesuai dengan yang dikehendaki melalui fantasinya. Koyal memberi pengaruh pada tokoh lain seperi Mae, Retno, Panut, Hamung, dan Tukijan dengan dunia khayalannya. Semua turut dalam alam pikiran Koyal. Dengan demikan, Koyal berhasil membangun satu tujuan bersama yaitu
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 6
bersenang-senang menghabiskan uang seratus juta hasil memenangkan lotre. Tokoh lainnya sebenarnya tahu bahwa angka lotre yang dibeli Koyal meleset satu angka dengan nomor lotre yang keluar secara resmi. Perbedaan satu digit angka inilah yang terus membersamai perjalanan Koyal sebagai subjek yang berusaha mewujudkan The Real.
Koyal merasa mampu mengendalikan situasi demi niatnya menuju The Real. Ia paham betul pada saat mengalami jalan buntu mempengaruhi orang lain dan bagaimana caranya bersiasat untuk menghindari sekaligus membuat orang lain percaya. Hal itu tampak dalam dialog dengan Hamung berikut.
Hamung : Belum menang sudah hilang ingatan. Koyal : Tak ambil pusing aku. Yang terang, aku
hampir menang. Artinya tak lama lagi aku pasti menang. Kau lihat, Mung. (Menunjuk Lotre Yang Lain) nih, aku sudah beli lagi. Tak Cuma itu malah. Baru saja aku Tanya pada tukang nujum. Burung glatik yang cerdik itupun menjanjikan kemenangan itu. Satu kartu dengan gambar bunga mawar, satu kartu dengan gambar sapi, satu kartu dengan gambar rumah. Kau pasti tidak percaya.
(C. Noer, 1999:29)
Dalam dialog tersebut, Koyal membuat siasat untuk mempertahankan soal kemenangan lotre itu dengan membeli lotre lagi dengan tujuan agar Hamung yakin padanya. Koyal memang membutuhkan dukungan orang lain untuk bersama-sama menyatakan bahwa semua ini nyata. Tindakan inilah yang terus dilakukan Koyal.
Koyal : Tidak. Tentu saya bisa mengembangkan bakat kepinteran saya. Lalu saya fikir...
Hamung : (memotong) Lalu saya melamun. (tertawa)
Mae : Hamung Retno : (tertawa) Koyal : (tidak peduli) Lalu saya fikir saya harus
punya banyak uang dulu. Malah akhir-akhirnya saya mencintai uang. Mengapa tidak? Saya telah melihat rumah yang bagus-bagus. Saya telah melihat mobil yang bagus-bagus. Saya telah melihat segala apa saja yang hanya didapat dengan uang. Lalu...
(C. Noer, 1999:35)
Upaya Koyal untuk mewujudkan The Real pada waktu tertentu dicoba untuk digagalkan oleh Tukijan. Tukijan, memiliki cita-
cita cukup realistis dibandingkan tokoh lain. Kehadiran Tukijan dalam alam fantasi Koyal sering menjadi kesadaran lain. Namun, hal ini seringkali tidak dihiraukan oleh tokoh lainnya. Sebenarnya, kehadiran Tukijan merupakan the other bagi Koyal. Hal itu bisa dijadikan cermin untuk menemukan identitas dirinya melalui cerminan orang lain (Myers, 2003:25).
Posisi Koyal terlihat paradoks karena selain memiliki upaya mewujudkan The Real, ia juga bisa berada dalam fase The Imaginary pada waktu bersamaan. Koyal sebenarnya sedang melihat dirinya melalui orang lain jika ia berada dalam kondisi sadar. Namun, kehadiran orang lain yaitu Tukijan dalam posisi sebagai cermin diri tetap tidak berlaku. Bagi Koyal, justru kehadiran subjek lain akan menghancurkan sensasi kenikmatan dalam dirinya. Dialog Tukijan yang hadir dengan sadar dalam alam khayalan Koyal dapat dilihat dalam cuplikan adegan berikut.
Tukijan : Kita ini mimpi. Koyal : Cerewet! Soalnya ‘kan kita cari
kenikmatan? Tukijan : (menantang) Apa? Koyal : (ketakutan) Tidak. Kenapa takut?
Bukankah malam ini saya yang jadi raja? (pada bulan) Bukankah begitu bulan? Harus? Baik. (seketika berubah sikap untuk meyakinkan dirinya ia bertolak pinggang) He, Jan! Dengar!
Tukijan : (takut) Ya, Yal! Koyal : Kamu jangan banyak cerewet, ya? Tukijan : Ya, Yal! Koyal : Malam ini kita akan makan kabut. Tukijan : Ya, Yal! Koyal : Dan menelan bulan. Tukijan : Ya, Yal!
(C. Noer, 1999:56)
Dialog Tukijan sebenarnya tepat dijadikan momentum bagi Koyal untuk mengidentifikasi siapa dirinya sehingga memasuki fase The Imaginary. Tukijan mengatakan semua hanya mimpi. Namun tidak berselang lama ia terpaksa turut dan patuh pada Koyal. Setiap kali Tukijan hadir sebagai the other, Koyal berhasil menampiknya sehingga ia tak beranjak dari fase The Real. Hal tersebut tampak dalam dialog dengan Retno dan Tukijan berikut ini.
(Tukijan diam saja) Koyal : Kau jangan diam saja, Retno. Retno : (Dengan genit) kau cemburu mas Jan? Tukijan : (Sekonyong-konyong meledak) Capek,
bangsat! Orang bisa cape oleh impian apapun! Lumpuh! Bajingan! Bajingan!
(Koyal menengadah)
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 7
Koyal : Bagaimana, bulan? Apakah saya masih berkuasa? Baik. (Bertolak pinggang) He, Jan. Kau jangan mentang-mentang ya!
Tukijan : (Ketakutan) Tidak, Yal. Sungguh mati saya tidak mentang-mentang.
Koyal : (Lebih bangga) Saya tahu. Kau cape. Ya?
Tukijan : Cape. Koyal : Ingin istirahat? Mengaso? Tukijan : Mengaso. Koyal : Katakan saja itu lebih baik. Ini
peringatan terakhir: ingat-ingat dengan baik perananmu malam ini.
(C. Noer, 1999:66-67)
Koyal seolah-olah tahu cara mengendalikan semua orang sesuai hasratnya. Akibatnya, fantasi Koyal semakin menggila. Ia terus berusaha mempengaruhi pikiran tokoh lain agar menyatu dalam perjalanan fantasinya yang liar. Pada sisi lain, kehadiran Panut juga sebagai the other bagi Koyal meskipun posisinya tidak dominan seperti Tukijan. Koyal pernah membuat siasat untuk mempertahankan khayalannya di depan Panut dan Hamung, meskipun Panut sempat membalas dialognya dengan cukup realistis. Dialog berikut menggambarkan posisi Koyal kembali dalam The Real.
Koyal : (Tertawa) orang-orang sepanjang jalan bersorak-sorak; hidup raja uang! Horee! Hidup raja uang! Saya tentu saja manggut-manggut. Dan dari koper saya hambur-hamburkan uang-uang itu. Pasti saya tertawa menyaksikan orang-orang berebutan uang seperti anak-anak ayam. Nah kalau sudah jam dua saya pulang. Uang habis sama sekali. Dalam gubuk ajaib itu saya tidur siang. Tidur di atas kasur yang berisi uang, berbantalkan bantal yang berisi uang, seraya memeluk guling yang berisi uang. (Tertawa) Sorenya saya keluar jalan-jalan dengan empat buah koper berisi uang. Tentu saja kali ini saya mesti menyewa mobil.... tiap-tiap rumah akan saya masuki dan saya taburi dengan uang. Terutama sekali rumah kau dan rumah Tukijan. (Tertawa) Dan kalau sudah habis...
Hamun : (Memotong)....Ngemis lagi. (Sekonyong-konyong muncul Panut dengan tergesa) Panut : Tidak usah, Yal. He, Yal. Dengan
gampang kau akan punya banyak uang asal kau mau nurut saya malam ini.
Koyal : Kemana?
Panut : Turut sajalah. (C. Noer, 1999:36-37)
Panut, dalam dialog tersebut, mengajak Koyal berangkat menyopet. Satu hal riil yang dapat dilakukan oleh Panut ketika tidak punya uang. Mae yang selalu memberikan perlindungan, memberikan nasehat kepada Koyal agar tidak usah pergi bersama Panut. Seolah Mae menjadi pendukung Koyal dalam melanggengkan kelangsungan fantasinya. Hal itu tampak dalam dialog di bawah ini.
Mae : Jangan. Ayo, Panut, kau membantah Ma’e. Jangan pergi! Disini saja! Koyal, kaupun tak usah pergi!
(C. Noer, 1999:37)
Selain mempertahankan khayalan menang lotre, Koyal rupanya menaruh hati pada Retno, pacar Tukijan. Cita-cita tindakan terhadap Retno yang benar-benar dilakukannya membuat Tukijan marah. Saat semua tokoh masih tidur, Koyal berencana untuk memegang betis Retno yang tersingkap. Upaya Koyal sekaligus kegagalannya tampak dalam dialog berikut.
Koyal : (Tertawa berdesis) Barangkali dia juga senang... (Dipegangnya kaki itu agak lama). Bulan, (Tertawa), Kau tidak ingin pegang?.... (Tertawa) Mana lebih enak, uang atau betis perempuan?... Saya jadi agak pusing. Pusing-pusing enak. (Tertawa berdesis)
(Sekonyong-konyong Tukijan bangkit melompat dan segera menangkap leher baju Koyal sehingga baju yang buruk itu tentu saja sobek sebagian. Karena sobek maka Tukijan menjambak lengan bajunya) Tukijan : Bajingan. (Diludahinya muka Koyal) Koyal : (Terkejut dan amat takut) Tidak, es,
tidak... Tukijan : Tidak? Kau kurang ajar. Kau bangsat.
Kau gila. Koyal : ...tidak....
(C. Noer, 1999:90-91)
Kemarahan Tukijan mulai tak terbendung dan alam fantasi Koyal mendapat ancaman. Ia bisa gagal mempertahankan alam khayalannya jika Tukijan tidak mempercayainya. Akibatnya, ia bisa gagal mewujudkan The Real.
Upaya Koyal membangun The Real sebenarnya terwujud di babak kedua. Saat semua beranjak tidur dan bermimpi. Alam mimpi adalah ruang simbolik yang dibangun Koyal secara mati-matian. Ia berdialog dengan lugasnya bisa memberi pengaruh kepada lainnya. Tokoh lain turut hanyut bersama histeria yang diciptakannya. Pada saat inilah sebenarnya
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 8
Koyal telah berada pada tahap The Symbolic bersama dengan lainnya meskipun di alam mimpi.
Namun di dalam kenyataan, posisi Koyal justru semakin terancam ketika mendapat kecaman dari Tukijan. Hal ini diperuncing oleh ikat pinggang Tukijan yang dipakai Koyal. Tukijan menuduh Koyal telah mencuri ikat pinggangnya.
Tukijan : Itu ikat pinggang saya. Bajingan. Setengah mati kemarin saya putar-putar mencari barang itu. Kembalikan!
Koyal : (Seraya terisak) Saya tidak mencurinya. Saya menemukannya.
Tukijan : Menemukannya di tempat saya. Koyal : Tidak. Tukijan : Lepaskan. Bangsat. Koyal : Saya tidak mencurinya. Saya
menemukannya. (C. Noer, 1999:93-94)
Pada bagian ini Koyal mulai kehilangan alam khayalannya. Sebagai subjek ia mulai lengah dalam mengendalikan The Real. Kehadiran berulang Tukijan sebagai the other beserta tuduhannya semakin memberi ancaman. Bahkan Tukijan terus berulang menyadarkan Koyal.
(Takut-takut Koyal mendekati Tukijan) Tukijan : Yal. (Curiga Koyal memandang Tukijan) Tukijan : Kau tahu.... Koyal : Tidak. Tukijan : Ya, kalau kau tahu artinya kau waras.
Yal, kau ingin sembuh? Koyal : Saya tidak sakit. Bagaimana?
(C. Noer, 1999:96)
Tukijan terus mendesak Koyal. Ia ingin mengatakan bahwa Koyal tidak waras. Namun, Koyal selalu menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak sakit. Ia merasa baik-baik saja. Apalagi ditambah dukungan dan pembelaan dari Mae bahwa Koyal juga seperti yang lainnya, yaitu bisa merasakan sakit hati.
Tukijan : Kau tidak sakit. Kau cuma tidak waras. Mae : Tukijan! Jaga bicaramu! Tak patut
kata-katamu. Tukijan : Biar dia sembuh, Ma’e. Mae : Tidak begitu caranya. Lagi dia masih
bisa merasa sakit hati seperti kata kau. Dia juga orang seperti kau. Dan apakah ada perlunya?
(C. Noer, 1999:96)
Pada akhirnya, kegagalan Koyal dalam mewujudkan The Real tampak jelas ketika Tukijan menyobek lembaran lotre itu. Koyal
mengalami kekalahan atas fantasi yang susah-payah dibangun sejak awal. Hasratnya hancur seketika melihat sobekan lotre miliknya di tangan Tukijan. Tukijan pun seolah ingin mengakhiri seluruh mimpi dan khayalan yang serba tidak jelas tersebut.
Tukijan : Saya kira kau nanti akan sembuh kalau saya berani melakukan sesuatu. Betul kau ingin uang banyak?
Koyal : Betul. Tukijan : Pasti satu ketika akan menjadi orang
kaya, kaya harta dan kaya segalanya. (Disobeknya lotre itu)
Koyal : Jangan! Ma’e, dia menyobek uang saya.
Mae : (Benci) Kau telah menyakiti hatinya. Tukijan : Ini lebih baik.
(C. Noer, 1999:98)
Begitu Tukijan membuang sobekan lotre dan diterbangkan angin, Koyal semakin sedih tak karuan, hatinya hancur. Mimpi yang dibangunnya sudah tidak ada artinya lagi.
Tukijan : Jangan menangis. Kau bukan anak kecil. Kalau kau tetap menangis kau tak akan pernah mendapatkan uang yang banyak itu kecuali angka-angka.
Koyal : Kau jahat. (Bangkit takut-takut mengancam Tukijan) Berikan lotre itu.
Tukijan : Tak ada gunanya. Koyal : Kau terlalu jahat. Berikan lotre itu. Tukijan : Lebih berguna untuk angin. (Dilemparkannya sobekan lotre itu tepat tatkala angin menderas) Koyal : Ma’e, dia jahat sekali. Oh, uang saya
diterbangkan angin. (Mengejar sobekan lotre) Tolong. Harta saya terbang semua! Semuanya terbang! Tolong....!
(C. Noer, 1999:98-99)
Kejadian ini membuat Koyal benar-benar tidak bisa lagi melanjutkan cita-cita tindakan karena sumber khayalannya telah hilang. Tanpa cita-cita tindakan, maka tidak ada The Real.
Gambar 2. Adegan Koyal (baju kuning), Mae, Retno dan Hamung. Pentas Mega-mega di Auditorium
Teater ISI Yogyakarta, 2007. (Doc. Pribadi)
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 9
2. Koyal pada Tahapan The Imaginary Koyal berada dalam The Imaginary saat
selalu berusaha meyakinkan subjek lainnya. Ia membuat pernyataan dengan bertanya pada tukang nujum meski jawaban yang ia peroleh berupa simbol burung gelatik, bunga mawar, sapi dan rumah (C. Noer, 1999:29). Simbol yang berkaitan erat dengan lotre dan kemenangan. Fase ini menjelaskan Koyal sebagai subjek mulai berinteraksi dengan simbol-simbol atas imajinasi di sekitarnya sekaligus mendorong fantasinya. Ia pun tidak segan-segan memaksakan imajinasinya kepada Retno, seorang yang disukainya.
Koyal : (Berhenti main suling) Ha, lihat. Aku menang, ya?
Retno : Tadi kau bilang hampir mau menang? Koyal : Sekarang bilanglah: Kau menang! Retno : Kau menang! Setan. Koyal : (Tertawa) Horeeee! Menang! Menang!
(C. Noer, 1999:45)
Retno dengan terpaksa akhirnya mengiyakan khayalan Koyal. Hal ini dibaca oleh Koyal sebagai sebuah kenyataan bahwa memang orang-orang percaya padanya.
Koyal selalu membuat siasat untuk mempertahankan khayalannya di saat kehadiran subjek lain berusaha menyadarkannya. Koyal menganggap dirinya raja atas kemenangan yang ia ciptakan. Ia berhak mengatur lainnya sesuai dengan hasratnya. Koyal juga tahu cara keluar dari kebuntuan sehingga kenapa siasat atas rayuan dan janji itu dilontarkan kepada tokoh-tokoh lain.
Koyal : Biar. Lezat. (Tertawa) Jangan terlampau sadar. Kita sibuk sekarang. Kita harus urus kemenangan kita. Jangan biarkan waktu terbuang. Kita harus punya rancangan. Jadi pertama-tama kita harus menukarkan lotre ini ke bank. Betul, Mung?
(C. Noer, 1999:49)
Dengan memengaruhi orang lain dan di saat yang sama semuanya percaya, maka eksistensi paradoks menghampiri Koyal karena berada secara bersamaan dalam fase The Imaginary dan fase The Real. Identifikasi diri berdasar pada cerminan orang lain tidak terjadi dengan baik karena orang lain percaya pada khayalan Koyal. Bahkan ketika Panut, dan terutama Tukijan mencoba untuk menyadarkan, Koyal selalu berusaha menampiknya. Apa yang disampaikan Panut dan Tukijan sesungguhnya adalah identitas diri Koyal dalam fase The Imaginary.
Namun Koyal rupanya terlalu menikmati The Real di mana cita-cita tindakan diwujudkan berdasar fantasi.
3. Koyal pada Tahapan The Symbolic Koyal dalam posisi The Symbolic terlihat ketika dirinya berinteraksi dengan Mae, Retno, Hamung, Panut, dan Tukijan. Subjek selain Koyal inilah yang menjadi bagian dari simbol sebuah struktur sosial dalam masyarakat, yaitu hidup berkelompok. Hal ini tampak dalam keterangan lakon berikut.
Terdengar suara seruling Koyal yang sumbang itu menyusup di sela-sela angin malam yang bergemuruh. Mae, Retno, dan Hamung sudah nyenyak tidur. Tukijan terbaring gelisah setengah tidur di atas tikar. Sedangkan Koyal masih asyik masuk di tengah impian-impiannya dengan serulingnya duduk di bawah tiang listrik.
(C. Noer, 1999:43)
Koyal menjadi bagian dari kelompok gelandangan tersebut dan diterima dengan baik. Meskipun subjek lain seringkali menganggap Koyal tidak waras, namun dirinya selalu mendapat pembelaan dari Mae. Apa yang dilakukan Mae merupakan proses penerimaan agar posisi eksistensi Koyal sama dengan yang lain.
The Symbolic, secara jelas menekankan sebuah relasi antarsubjek terjalin dengan wajar sebagai manusia sosial. Koyal diterima dalam kelompok sudah menjadi bukti bahwa dirinya bagian dari kelompok gelandangan tersebut. Kondisi ini semakin mengukuhkan eksistensi dirinya di dalam sebuah kelompok.
Interaksi antarsubjek yang menegaskan The Symbolic semakin kuat ketika Mae berani menyatakan sebagai ibu bagi semua orang dalam kelompok gelandangan tersebut. Jelas sekali bahwa Koyal tentu juga dianggap sebagai salah satu anaknya selain Hamung, Retno, Panut, dan Tukijan.
Mae : Siapa bilang? Mae tak pernah bertanggung jawab. Sekarang di sini Mae berusaha jadi ibu kalian.
(C. Noer, 1999:25)
Dalam perjalanannya, Koyal bahkan memiliki kedudukan khusus dalam kelompok tersebut. Ia memiliki peran besar dalam fase The Symbolic. Semua orang percaya padanya dan ia selalu mendapatkan pembelaan Mae. Hasrat ideologis Koyal terpenuhi dan ia merasa nyaman dengan itu. Namun demikian, eksistensi hidup berkelompok goyah ketika akhirnya Tukijan
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 10
menyobek lotre Koyal. Dunia khayalan yang dibangun Koyal hancur, semua orang tidak percaya. Satu-satunya harapan Koyal hanyalah Mae.
Namun demikian, tidak menunggu lama, Mae juga mulai meragukan Koyal. Ketika ia datang kembali lagi ke Mae karena ada tiga petugas yang memukul kepalanya sampai berdarah dan Mae meragukannya. Ketiga petugas keamanan itu menurut Koyal memukul kepalanya saat Koyal disuruh menyobek gambar partai di depan Kantor Pos.
Mae : Kenapa mereka memukul kepalamu? Koyal : Ada tiga orang laki-laki menyuruh saya
menyobeki gambar besar yang terpancang di muka kantor pos sana.
Mae : Gambar bioskop? Koyal : Bodoh. Gambar partai. Mae : Lalu? Koyal : Tiga laki-laki itu menyuruh saya
menguliti gambar itu. Mae : Siapa mereka? Koyal : Siapa. Bodoh. Mereka yang punya
gambar. Mereka perlu memperbaharui. Kalau sudah selesai nanti saya diberi upah.
(C. Noer, 1999:121-122)
Mae menunjukkan rasa tidak percaya dan Koyal memaksanya untuk memeriksa luka di kepalanya. Mae meraba dan tidak menemukan bekas luka tersebut.
Mae : (setelah meraba) Tidak ada. Koyal : Tadi ada. (tiba-tiba) Mae! Mereka
mengejar saya! Mereka mengejar saya! Mae : Mana mereka? Mana? Koyal : Mereka! Mereka datang! Mereka! Mae!
Masing-masing membawa kayu sangat besar. Tolong, Mae. Tolong! Kayu itu sangat besar!
Mae : Mana? Koyal : Jangan pukul kepala saya! Jangan!
Aduh! Sakit! Berdarah. Jangan! Tolong! Tolooong!
(seraya menjerit-jerit ia lari menyusup kabut yang biru itu, setelah berputar-putar menghindari pukulan-pukulan yang tak ada itu. Dengan sedih Mae mengikuti pusingan pusingan Koyal)
(C. Noer, 1999:123)
Ketidakpercayaan Mae sebagai satu-satunya orang yang selama ini mendukungnya, membuat Koyal kehilangan segalanya. Ia tidak lagi bisa meneguhkan posisi The Real sekaligus tidak lagi memiliki peluang berinteraksi dalam fase The Symbolic.
Koyal merupakan gambaran representasi manusia sebagai subjek yang kontekstual. Posisi
eksistensi manusia di tengah situasi yang terbatas pun selalu merasa kekurangan dan ada yang tidak utuh di dalam dirinya. Ia terus menggulirkan hasratnya untuk menjadi seseorang dalam impiannya, menutupi kekurangan, dan memiliki kekuasaan. Padahal setiap manusia selalu diingatkan melalui kehadiran subjek lain agar ia mau bercermin melihat eksistensi dirinya melalui orang lain.
Namun, ketika hasrat yang sudah terlanjur ideologis itu terlalu dominan, maka kedudukan eksistensi dirinyalah yang dianggap paling unggul dibanding yang lain. Sebelum kehadiran subjek lain menjadi ancaman, maka sebisa mungkin harus segera ditundukkan dengan berbagai cara demi kepuasan hasratnya. Itulah yang dilakukan oleh Koyal meski pada akhirnya ia tidak bisa lagi menikmati hasrat ideologis tersebut karena tidak mampu mempertahankan The Real dan kehilangan interaksi The Symbolic.
SIMPULAN
Koyal secara dimensi dapat dijabarkan sebagai seorang gelandangan yatim piatu berperawakan tinggi, berkulit terang, pintar, namun sedikit kurang waras. Ia menjalani kehidupan secara berkelompok dan berpindah-pindah bersama Mae, Retno, Hamung, Panut, dan Tukijan. Ia mampu mengarahkan dan bahkan menguasai pikiran orang di sekitarnya melalui fantasi yang ia bangun dengan mendapat dukungan dari Mae.
Berdasarkan konsep subjek Slavoj Žižek, posisi karakter dan eksistensi Koyal sebagai subjek telah mengalami fase The Real, The Imaginary, dan The Symbolic secara paradoks. Satu fase peneguhan identitas bertemu dengan fase lain yang akhirnya justru saling mengaburkan. Segala upaya sudah dilakukan Koyal untuk mewujudkan The Real sekaligus untuk mencapai The Symbolic, dua fase yang mampu memberikan kepuasan bagi hasrat ideologisnya. Namun demikian, Koyal akhirnya gagal meneguhkan identitas dirinya untuk mendudukkan eksistensi pada posisi tertentu di tengah komunitasnya. Mae, Panut, Retno, Tukijan, dan Hamung merupakan kelompok The Symbolic. Mereka adalah para subjek yang menjadi bagian dari aturan, bahasa, kultur, struktur sosial yang berada di sekitar Koyal. Retno, Hamung, Tukijan, dan Panut memiliki pengaruh tertentu meski tidak berhasil menundukkan eksistensi Koyal karena pembelaan yang dilakukan Mae.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 11
Kehadiran Panut, dan terutama Tukijan merupakan bagian kuat dari The Imaginary. Tukijan secara berulang-ulang menjadi bagian dari cermin kesadaran bagi Koyal yang justru ditolak. Kehadiran Tukijan akhirnya bisa menundukkan eksistensi khayalan Koyal sebagai The Real di akhir cerita. Tukijan terus menerus mendesak mengatakan kepada Koyal bahwa semua hanyalah mimpi. Sebagai the other, eksistensi Tukijan semakin mengancam posisi Koyal meskipun ada subjek lain yaitu Mae yang terus memberikan dukungan dan pembelaan. Mimpi kemenangan Koyal akhirnya hancur setelah kertas lotre disobek Tukijan. Keadaan ini membuat sumber khayalan Koyal sebagai cita-cita tindakan hilang. Dengan tidak adanya cita-cita tindakan, maka Koyal tidak lagi bisa berada dalam posisi The Real. Koyal kalah, ia mengalami histeria menjelang akhir cerita. Upaya terakhir dilakukan, sebagai replikasi tindakan dalam fase The Real untuk menuju fase berikutnya, dengan mengarang cerita tentang kedatangan tiga petugas yang memukul kepalanya sampai berdarah. Hal itu ia sampaikan pada Mae dengan harapan adanya pembelaan sebagaimana biasanya, satu syarat yang diperlukan Koyal untuk kembali berada pada fase The Symbolic. Namun, Mae terus berusaha memastikan bahwa tidak ada orang yang memukul kepalanya dan tidak ada darah di kepalanya. Koyal tetap beranggapan bahwa ketiga petugas itu datang mencari Koyal, tapi Mae tidak percaya. Akhirnya Koyal gagal dan berlari pergi meninggalkan Mae. Dengan tidak adanya kepercayaan Mae, maka peluang Koyal untuk kembali berinteraksi dalam fase The Symbolic menjadi sirna. Perjalanan laku Koyal dapat dijadikan refleksi laku hidup manusia secara umum. Seseorang dalam usahanya menolak The Real, mesti melalui fase The Imaginary untuk mencapai eksistensi diri dalam The Symbolic. Namun, posisi The Symbolic sebagai realitas baru atau The Real yang sesungguhnya selalu saja dirasa gagal karena faktor eksistensi manusia lain sebagai The Imaginary di mana capaian eksistensi diri itu disandarkan. REFERENSI
C. Noer, Arifin. (1999). Mega,Mega. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus.
Engelmann, Peter. (Ed). (2018). Filsafat di Masa Kini Alan Badiou dan Slavoj Žižek. Yogyakarta: Penerbit Basa-basi.
Harymawan, RMA. (1988). Dramaturgi. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosda Karya.
Holis, Nur & Salam, Aprinus. (2019). Posisi Subjek Tokoh Skeeter dalam Film The Help (2011) Karya Tate Taylor: Kajian Subjektivasi Slavoj Zizek. Jurnal NUSA, Vol. 14, No. 4 November 2019, pp 523-535.
Manik, Ricky Aptifive. (2015). Hasrat Nano Riantiarno dalam Cermin Merah: Kajian Psikoanalisis Lacanian. Jurnal Kandai, Vol.11 No 2, November 2015, 266-280.
Moeljadi, David dkk. (2016). KBBI V 0.4.0 Beta (40), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Myers, Tony. (2003). Slavoj Žižek. London: Routledge.
Nurjanah, Rina. (13 April 2015). Mega-Mega dalam Persembahan untuk Arifin C. Noer. Diakses dari https://www.liputan6.com/ citizen6/read/2212346/mega-mega-dalam-persembahan-untuk-arifin-c-noer
Satoto, Soediro. (2012). Analisis Drama dan Teater–Bagian 1. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Setiawan, R. (2016). Membaca Kritik Slavoj Žižek: Sebuah Penjelajahan Awal Kritik Sastra Kontemporer. Surabaya: Negasi Kritika.
Sugono, Dendy. (2021). Ensiklopedia Sastra Indonesia. Diakses dari http://ensiklopedia. kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Mega-Mega
Suhartadi, Imam. (24 Januari 2016). Mega-mega Karya Arifin C. Noer Dipentaskan di Singapura. Diakses dari https://www. beritasatu.com/hiburan/344186/megamega-karya-arifin-c-noer-dipentaskan-di-singapura
Wattimena, Reza A.A. (2011). Slavoj Žižek tentang Manusia sebagai Subjek Dialektis. Jurnal Orientasi Baru, Vol. 20 No. 1, 61-83.
Žižek, Slavoj. (2008). The Sublime Object of Ideology. New York: Verso.
Dokumentasi Pribadi: Elyandra Widharta tahun 2007 pada pementasan
Mega,Mega, sutradara Agus Imron, Jurusan Teater ISI Yogyakarta.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 12
LANTUNAN EB SUKU YAGHAI MAPPI PAPUA: HUBUNGAN MAKNA, BENTUK, DAN STRUKTUR
EB CHANT OF YAGHAI MAPPI PAPUA TRIBE:
THE RELATIONSHIP OF MEANING, FORM, AND STRUCTURE
Septina Rosalina Layan1
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
ABSTRACT
Eb is an oral tradition of singing that lives and develops in Yaghai tribe of Papua. Eb tells the story of human life in their relationship with other human beings, nature, and God. Eb tradition has been practiced and preserved up to now. The current study attempts to record, study, and analyse the form and structure of Eb and the relationship with its meaning. Sources of data are field observation notes, interviews, audio and video recordings, and photos, collected from participatory observation and interviews. The result of the study demonstrates that the chant forms of ordinary Eb and Oghob are without time signature, while the Qaqau Eb has a definite beat. Ordinary Eb is associated with universal joy, Qaqau Eb is associated with happy expression, while Oghob is associated with sorrow or sadness. The form and structure of Eb chant, such as the flow of melody, tempo, harmony, are closely related naturally to the meaning of the chant itself. Eb tradition has been inherited from generation to generation signifying cultural values of human ideas of the Yaghai Tribe.
Keywords: meaning, structural form, chant, Eb.
ABSTRAK
Eb merupakan tradisi lisan berupa nyanyian yang hidup dan berkembang pada masyarakat suku Yaghai Papua. Eb mengisahkan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan. Sampai saat ini, tradisi Eb masih terus dipraktikkan dan dipertahankan. Penelitian ini merupakan upaya untuk mencatat, mengkaji, dan menganalisis bentuk dan struktur Eb serta hubungannya dengan makna. Sumber data diperoleh dari catatan tertulis pengamatan lapangan, wawancara, rekaman audio, rekaman video, dan foto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk lantunan Eb Biasa dan Oghob bersifat misural (tanpa sukat), sedangkan Qaqau Eb memiliki ketukan yang pasti. Eb Biasa berkaitan dengan rasa sukacita yang bersifat universal, Qaqau Eb berkaitan dengan ungkapan bahagia, sedangkan Oghob berkaitan dengan dukacita atau kesedihan. Bentuk dan struktur lantunan Eb, seperti alur melodi, tempo, serta harmoni secara alamiah berkaitan erat dengan makna lantunan itu sendiri. Hal ini telah terjadi secara turun temurun sehingga Eb merupakan simbol dari nilai-nilai budaya yang lahir dari ide-ide manusia Suku Yaghai.
Kata kunci: makna, bentuk struktur, lantunan, Eb.
1Septina Rosalina Layan adalah seorang komponis, seniwati, dan pengajar di Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Seni di Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pendidikan S1 ditempuh pada Program Studi Penciptaan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Penulis aktif memproduksi karya komposisi kontemporer berbasis riset yang mengangkat isu lingkungan, perempuan, sosial, dan kemanusiaan di Papua sejak tahun 2014. Karya kontemporer yang diciptakan berbasis tradisi seni budaya Papua.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 13
PENDAHULUAN
Papua memiliki beragam lantunan sebagai bagian dari tradisi lisan yang biasanya disenandungkan atau dinyanyikan dalam suatu upacara ritual, misalnya berhasil dalam perang, perkawinan, kelahiran, kematian, mendapatkan hasil kebun yang berlimpah, dan sebagainya. Setiap suku di Papua menyebut nyanyian dengan berbagai istilah, misalnya nyanyian “Helaehili” dan “Ehabla” pada masyarakat Sentani. “Helaehili” (tangisan atau ratapan) merupakan salah satu bentuk puisi lisan yang dilantunkan ketika ada kematian. Lantunan tersebut mengisahkan kehidupan orang yang meninggal, sedangkan “Ehabla” merupakan bentuk puisi lisan yang dilantunkan dengan ekspresi kegembiraan (Yektiningtyas, 2010). Suku Hubula di Jayawijaya memiliki nyanyian yang disebut Etai. Nyanyian tersebut dilantunkan pada saat upacara perkawinan, membangun honai, membuka kebun baru, dan pada saat pesta babi yang disebut Mawek (Assa, 2012). Munaba pada suku Waropen dilantunkan pada situasi kedukaan untuk memberikan gambaran keberadaan, pengalaman hidup, dan jasa-jasa orang yang meninggal (Yenusi, 2016). Ada pula nyanyian adat Wor suku Biak yang dilantunkan dalam upacara adat, yaitu semacam puisi yang memiliki bentuk dan jenis beragam sesuai dengan makna upacara dan ritual (Rumansara, dkk., 2002). Dapat dikatakan bahwa nyanyian telah menjadi satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat Papua dan menjadi hal yang sangat penting untuk menjelaskan, menceritakan, bahkan menyampaikan nasehat kepada orang lain. Ada ungkapan dalam bahasa Biak yang berbunyi Ngo wor ba ido neri ngomar yang berarti kalau kami tidak bernyanyi kami akan mati (Rumansara dkk, 2002).
Eb merupakan tradisi lisan berupa nyanyian yang hidup dan berkembang pada masyarakat suku Yaghai Mappi yang terletak di selatan Papua. Suku Yaghai adalah salah satu suku yang tinggal di wilayah adat Anim-Ha, yaitu di wilayah pemerintahan kabupaten Mappi, yang merupakan salah satu pemekaran dari kabupaten Merauke Papua. Eb dilantunkan dalam bahasa sastra, untuk mengisahkan tentang sejarah kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, dengan alam dan dengan Tuhan. Eb memperdengarkan rangkaian bunyi atau melodi yang sama, namun berbeda sesuai maknanya. Eb mengalami pengulangan nada yang merupakan ciri khas darinya.
Kesederhanaan ini menjadi ciri utama dalam Eb, dan menjadi letak jati dirinya. Masyarakat pendukung Eb (suku Yaghai) sampai saat ini masih mempertahankan tradisi ini dalam lingkungannya. Orang tua yang terdiri dari laki-laki ataupun perempuan memiliki kelompok pelantun di kampungnya masing-masing. Mereka berkumpul di rumah adat ataupun di rumah ketua adat baik untuk keperluan upacara adat, sekedar berkumpul untuk berdiskusi, maupun bersilaturahmi dalam suasana kekeluargaan.
Pelantun Eb sebagian besar terdiri dari orang tua berusia 40-70 tahun. Kecenderungan ini terjadi selain karena Eb menggunakan bahasa sastra atau bahasa yang sulit diikuti oleh para remaja, tetapi juga karena tidak didukung dengan teks tertulis berupa kalimat syair lantunan, serta notasi dengan motif dan pengulangan yang khas. Ini yang menyebabkan Eb sulit dipelajari dan dilantunkan oleh kaum muda, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melantunkannya.
Dalam perkembangannya saat ini, Eb mengalami tantangannya tersendiri. Masyarakat pendukung Eb menghadapi situasi sosial berkaitan dengan budaya dari luar Papua yang berkembang, yaitu terjadinya asimilasi budaya yang terus menerus dan tidak dapat dihindari. Masyarakat dari luar Papua yang datang dan tinggal dengan berbagai kepentingan turut membawa budayanya masing-masing. Hal ini berdampak pada keberlangsungan Eb. Dengan situasi sosial yang demikian, tradisi lantunan Eb lambat laun akan semakin sulit dipelajari, dan semakin lama kemungkinan akan menjadi kenangan yang hanya dapat diceritakan saja dari generasi ke generasi. Dalam kondisi keberadaan Eb saat ini, penelitian sebagai usaha untuk mencatat, mengkaji, dan menganalisis bentuk dan struktur Eb serta hubungannya dengan makna menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah dihasilkannya literatur tertulis yang dapat digunakan sebagai bahan dan dokumentasi untuk mewariskan praktik Eb kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan, atau melalui sarana dan media lainnya dalam konteks pewarisan praktik dan nilai-nilai budaya lokal.
Lantunan Eb secara tidak langsung merupakan simbol makna yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, tentang kebahagiaan, sukacita, dan kesedihan. Makna musik tidak dikomunikasikan secara harfiah, namun menggunakan metafora, aliterasi, dan
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 14
pengulangan (Ehineni, 2017). Makna dalam lantunan Eb menjadi bagian terselubung dari bahasa metafora yang mengungkapkan berbagai peristiwa kehidupan suku Yaghai.
Pendokumentasian lantunan Eb yang dilakukan oleh Layan (2019) menunjukkan bahwa lantunan Eb sebagai tradisi turun temurun yang diwariskan secara lisan memiliki kekhasan musikal yang sederhana, bermakna, dan menunjukkan sebuah jati diri suku Yaghai. Berbeda dengan penelitian Eb pada suku Yaghai yang dilakukan ini, penelitian tentang suku Yaghai sendiri telah dilakukan oleh para misionaris MSC yang menyebarkan agama Katolik di selatan Papua dalam penelitian etnografi. Meskipun demikian, catatan etnografi dari para pastor misionaris MSC tidak membahas secara khusus tentang lantunan Eb. Pastor Cees Mauwese, pada tahun 1938, dengan bantuan para guru katekese yang ditugaskan di dusun tempat suku Yaghai berada, mencatat dan mengumpulkan informasi dengan baik tentang bagaimana kehidupan suku Yaghai yang memiliki tradisi mengayau. Suku tersebut juga memiliki sikap gotong royong dan memiliki hukum adat suku Yaghai, yaitu agho, erro, amar erro yang memiliki arti kebaikan hati, membagi, dan tukar menukar (Pongantung, 2019). Selain itu, pastor Mauwese juga mencatat tentang lantunan bunyian-bunyian sebagai ungkapan bahagia ketika suku Yaghai berhasil mendapatkan kepala manusia hasil pengayauan. Lantunan tersebut akan diperdengarkan dalam perjalanan pulang, pada saat penyambutan di dusun, sampai dengan perayaan pesta kepala. Dikatakan bahwa dengan menggunakan perahu, para pengayau yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa membunyikan air pada badan perahu kemudian melantunkan suara yang saling bersahut sahutan (nyame). Istri dari laki-laki yang berhasil memenggal atau mendapatkan kepala manusia akan berteriak dan bernyanyi lebih keras seperti memimpin lantunan. Hal ini juga terjadi ketika masyarakat mendengar kabar adanya kekalahan dalam pengayauan (situasi duka). Pada saat itu, lantunan akan terdengar dari segenap penduduk kampung untuk mengungkapkan perasaan sedih dan duka yang mendalam (Pongantung, 2019).
Penelitian etnografi yang dilakukan oleh Boelaars tentang Manusia Irian dahulu, sekarang, dan masa depan, mengungkapkan tentang pandangan hidup, kebiasaan sehari-hari, pengalaman beragama pada masa lampau dan perubahannya pada masa penyebaran Injil serta
pemerintahan. Boelaars mengungkapkan bahwa suku Yaghai dalam berbagai peristiwa, seperti ucapan rasa syukur atas kemenangan dalam perang (pengayauan) dan duka atas kekalahan dalam pengayauan, selalu menggunakan nyanyi-nyanyian adat dan tari-tarian (Boerlaars, 1986). Akan tetapi penelitian tersebut tidak menjelaskan lebih mendalam mengenai lantunan tradisi Eb dalam kebiasaan hidup masyarakat suku Yaghai. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berfokus pada proses yang terjadi, serta produk atau hasil. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti berupaya untuk memahami bagaimana sesuatu terjadi, kemudian melakukan analisis menggunakan teori-teori berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan (Creswell, 2015). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui catatan pengamatan lapangan, wawancara, rekaman audio, rekaman video dan foto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu handy recorder (zoom H6), kamera digital, dan alat tulis.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kurang lebih tujuh bulan, yaitu mulai tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 14 Februari 2019 di kampung Soba, kampung Linggua, kampung Mur, kampung Monana, dan kampung Agham. Di lokasi tersebut dilakukan pencatatan dan perekaman fakta yang disampaikan oleh informan. Pencatatan lirik setiap lantunan dan perekaman syair yang diucapkan kata demi kata oleh informan, dilakukan untuk mengetahui kisah dan makna yang terkandung dalam lantunan tersebut. Selain itu, dilakukan pula pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan cara masyarakat memulai dan mengakhiri Eb, waktu yang digunakan untuk melantunkan, berbagai hal yang terjadi pada saat Eb dilantunkan, siapa saja yang melantunkannya, serta keterlibatan perempuan dalam lantunan Eb.
Wawancara dilakukan secara sederhana, tidak formal, serta dengan menggunakan dialek sehari-hari, agar data yang diperoleh relevan dengan hasil yang diinginkan. Pertanyaan dalam wawancara berkembang dan mengalir sesuai jawaban awal setiap subjek. Pada penelitian ini, dilakukan wawancara dengan kepala suku, pelantun Eb, seniman, dan budayawan suku Yaghai, yaitu Bapak Selus Ribamogoin, Bapak
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 15
Williams Waimu, Bapak Noorbertus Yagoyemu, Bapak Esebius Emogoin, Bapak Simon Yadohamang, Bapak Pollynus Yermogoin dan Ibu Dafrosa Kaimu.
Kegiatan analisis data diawali dengan mengubah catatan lapangan hasil pengamatan menjadi catatan pengamatan, kemudian mentranskripsikan hasil rekaman wawancara secara detail sesuai dengan audio wawancara. Catatan pengamatan dari hasil catatan lapangan dijabarkan secara rinci dan kemudian dianalisis melalui proses coding, yang bertujuan untuk menemukan dan menandai informasi-informasi penting. Disebut penting atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut memiliki kemampuan untuk membangun sebuah titik fokus yang jelas, sehingga proses analisis dapat berlangsung secara terarah.
Pada catatan pengamatan dilakukan sistem coding dalam dua tahap. Tahap pertama, yaitu dengan membaca catatan pengamatan untuk menentukan tema atas kejadian, kemudian memberikan istilah atau meringkas penjelasan tersebut menjadi beberapa kata yang mewakili penjelasan. Kata tersebut seterusnya disebut sebagai kode. Selanjutnya, kode tersebut diletakkan di samping penjelasan tema kejadian. Jika penjelasan mengalami kesamaan, maka akan mendapatkan kode yang sama; jika tidak, maka akan menghasilkan kode yang berbeda. Hal ini dilakukan secara menyeluruh pada semua catatan pengamatan. Kode-kode tersebut dituliskan dalam daftar kode beserta penjelasannya.
Pada hasil wawancara, dilakukan proses pembacaan kembali transkrip wawancara dan pembuatan kode terhadap segmen wawancara. Kode dibuat berdasarkan hal esensial yang disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan kisah yang diceritakan dalam lantunan Eb. Pembuatan kode dilakukan pada setiap transkrip wawancara dari masing-masing narasumber. Pembuatan kode yang dilakukan pada catatan pengamatan dan transkrip wawancara akan menghasilkan kode dalam jumlah banyak. Pengkodean tahap awal ini akan kembali dibaca dan dikelompokkan, kemudian dilakukan reduksi untuk melihat kembali kode-kode sebelumnya. Kode-kode yang telah direduksi dibaca kembali secara menyeluruh untuk dilakukan reduksi tahap kedua.
Selanjutnya, lantunan Eb hasil perekaman didengarkan kembali dan dilakukan pembagian rekaman sesuai kisah lantunan yang berkaitan dengan rasa bahagia, ucapan syukur, dan kesedihan (penyesalan, ratapan). Setelah itu
dilakukan proses editing (memotong dan merapikan) audio rekaman tersebut, mencocokkannya dengan catatan pengamatan dan hasil wawancara, dengan tujuan untuk mempermudah proses transkripsi bunyi ke teks notasi. Dalam proses tersebut dilakukan perekaman sebanyak empat puluh lantunan yang dua puluh diantaranya ditranskripsikan ke dalam teks notasi. Selanjutnya, hasil reduksi dari pengamatan, wawancara, serta hasil transkripsi audio diolah menjadi data yang akan dianalisis berdasarkan makna, bentuk, dan struktur lantunan Eb. Selain melalui pengamatan dan wawancara, data penelitian juga diperoleh dari dokumen dan arsip catatan sejarah yang berkaitan dengan suku Yaghai. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Bentuk musik dalam karya musik dapat dibagi menjadi dua, yaitu bentuk tertutup (closed form) dan bentuk terbuka (open form). Closed form merupakan karya musik baku, seperti perioda, lagu dua dan tiga bagian, classic sonata allegro, dan passacaglia, sedangkan open form merupakan bentuk musik terbuka dan bebas (tidak termasuk dalam kategori closed form). Bentuk terbuka diklasifikasikan menjadi dua, yakni bentuk terbuka seperti bentuk abad dua puluh, toccata, rhapsody dan fantasy yang memiliki karakter tertentu, serta bentuk bebas atau free forms yang lebih programatik, judulnya lebih opsional dan tidak berhubungan dengan karakter tertentu. Salah satu yang termasuk dalam bentuk terbuka adalah musik programa yang bentuk dan isinya dipengaruhi oleh extra musical references atau faktor lain dari luar musik (Leon Stein, 1979). Teori ini digunakan sebagai acuan untuk menganalisis bentuk dan struktur yang ditemukan pada lantunan Eb. Kisah atau cerita yang terkandung dalam Eb mengarahkan pada asumsi bahwa Eb memiliki bentuk musik programatik yang di dalamnya terkandung extra musical references atau faktor lain dari luar musik itu sendiri.
Teori yang digunakan dalam proses analisis data mengenai hubungan makna dengan bentuk dan struktur Eb adalah teori interpretasi budaya. Budaya lahir dari ide-ide manusia seperti suatu dokumen publik, berasal dari publik dan berada di ranah publik. Analisis budaya bukan ilmu eksperimental yang mencari hukum umumnya, melainkan ilmu interpretatif yang mencari makna dari aksi simbol, seperti susunan kata, pigmen dalam lukisan, baris dalam
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 16
tulisan, suara dalam musik yang berpola dan penuh makna (Geertz, 1973).
Bentuk dan Struktur Lantunan Eb
Bentuk dan struktur lantunan Eb memiliki keterkaitan atau hubungan dengan makna yang ditemukan dalam kisah-kisah lantunan Eb. Kisah-kisah yang terdapat dalam lantunan Eb menghasilkan jenis-jenis lantunan yang telah hidup dalam tradisi ini. Dari hasil analisis bentuk dan struktur Eb berdasarkan jenis-jenisnya, ditemukan adanya bentuk dan struktur yang hampir sama. Kekhasan dari lantunan Eb secara keseluruhan terdapat pada alur melodi, tempo, dan harmoni yang merupakan bentuk terbuka. Pelantun akan mengulang nyanyian tergantung kesepakatan dan ‘seperti’ bergaya nyanyian resitatif. Terdapat empat jenis lantunan Eb, yaitu Eb Biasa, Eb Oghob, Nama Eb dan Qaqau Eb.
Bentuk Eb Biasa dan Oghob terkadang bersifat misural (tanpa sukat), sedangkan Qaqau Eb memiliki ketukan yang pasti, sehingga dapat menggunakan tanda sukat 4/4 atau 2/4, serta tidak ada nada dasar yang ditentukan. Pelantun akan mencari nada dasar yang tepat untuk dinyanyikan dengan cara membunyikan nada awal pada suara bawah, kemudian dinaikkan lagi sampai pelantun merasa bahwa nada itu tepat untuk dipakai. Hal ini merupakan cara alami yang dilakukan. Terkadang para pelantun dengan nada dasar awal telah menyelesaikan satu bagian lagu. Akan tetapi jika ada pelantun yang merasa nada tersebut tidak tepat, maka ia akan mengulangi dari awal atau tengah-tengah lagu dengan menggunakan nada dasar baru. Selanjutnya, semua akan mengikuti lagu tersebut sehingga akan terdengar seperti adanya modulasi. Untuk mempermudah peletakan lirik dan penulisan notasi, digunakan sukat 4/4 untuk semua jenis Eb dengan menggunakan nada dasar berdasarkan rekaman audio yang telah diperoleh di lapangan.
1. Eb Biasa Lantunan ini memiliki gaya yang hampir
sama dengan nyanyian resitatif abad pertengahan pada sejarah musik barat. Resitatif merupakan istilah yang dipakai sejak tahun 1600 di Italia untuk gaya nyanyian solois yang diiringi dengan instrumen dengan lagu sederhana, agar syairnya dapat menonjol (bicara sambil bernyanyi). Hal ini berkaitan dengan awal opera Italia sebagai usaha menirukan drama klasik Yunani yang diperkirakan dibawakan dengan cara resitatif, yang menyanyikan kalimat dialog yang
pemberhentiannya ditentukan oleh satu kalimat/ frase lagu (Prier, 2009). Meskipun demikian, istilah resitatif di sini tidak digunakan untuk menyebut gaya yang sama dengan Eb Biasa. Hal ini dikarenakan resitatif dinyanyikan oleh solo lalu diikuti dengan kelompok, sedangkan Eb Biasa dinyanyikan oleh kelompok. Meskipun demikian, terkadang ada suara solo yang terdengar dengan tempo yang berbeda dari kelompok suara yang dapat memimpin jalannya lantunan, seperti mempercepat tempo, memperlambat, ataupun mengubah nada dasar. Tempo lantunan dimulai dengan tempo sedang sampai sedikit lebih cepat.
Lantunan ini memperdengarkan bunyi yang beragam seperti harmoni, tetapi tidak seperti bunyi harmonisasi yang dibentuk dengan mengikuti teori musik Barat. Jika harmoni Barat tidak memperbolehkan adanya pendobelan nada terts atau nada ketiga dari rangkaian melodi yang membentuk harmoni, maka lantunan Eb Biasa ini justru dengan jelas memperdengarkan pendobelan nada terts, sehingga kesan harmoni yang ditimbulkan akan berbeda dari harmonisasi yang dibentuk menggunakan teori Barat. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam pada penelitian selanjutnya, karena lantunan Eb Biasa ini memiliki kekhasan bunyi lantunan harmoni yang beragam dan sangat khas.
Gambar 1. Suasana di Kampung Mondau/Linggua
saat Melantunkan Eb
(Dokumentasi Pribadi)
Dari analisis yang dilakukan, Eb Biasa menggunakan enam nada (heksatonis) yang terdiri dari la, sol, fa, mi, re, do. Nada tersebut memiliki skala nada diatonis atau alur melodi yang didominasi oleh dua nada saja, yaitu sol dan mi, sedangkan nada la, fa, re, dan do merupakan nada sisipan. Pada bagian akhir frase atau akhir melodi lantunan, terdapat nada re dan do yang dibunyikan dengan tempo yang diperlambat sedikit demi sedikit, atau dalam
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 17
istilah musik Barat dikenal dengan istilah ritardando (rit).
Gambar 2. Contoh 1-Eb Biasa
Gambar 2 merupakan salah satu Eb Biasa dari kampung Linggua Yaghai Barat. Pada birama kelima dan keenam, terdapat pengulangan nada sol, mi, dan di akhir frase lantunan (birama enam), ditutup dengan nada sisipan re, do.
Gambar 3. Contoh 2-Eb Biasa Gambar 3 merupakan salah satu Eb Biasa
dari kampung Linggua, Yaghai Barat. Skala nada diatonis atau alur melodi didominasi oleh dua nada, yaitu sol dan mi, sedangkan nada la, fa, re dan do merupakan nada sisipan.
Gambar 4. Contoh 3-Eb Biasa
Gambar 4 merupakan salah satu Eb Biasa dari kampung Soba Yaghai Timur. Pada birama kelima ketukan pertama, terdapat nada la sebagai sisipan, terjadi repetisi atau pengulangan, dan di akhir frase akan ditutup dengan nada la, sol. Pengulangan dilakukan sesuai kesepakatan. Untuk mengakhiri nyanyian, nada terakhir pada frase akan dibunyikan lebih panjang sesuai kesepakatan. Nada-nada yang digunakan adalah skala nada diatonis atau alur melodi yang didominasi oleh dua nada saja, yaitu nada sol dan mi, tanpa sisipan re dan do di akhir lantunan.
2. Qaqau Eb Lantunan ini berbeda dengan Eb Biasa
yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada tempo lantunan, ragam bunyi nada, dan alur melodi yang digunakan. Jika Eb Biasa dilantunkan dengan tempo sedang sampai sedikit lebih cepat, maka Qaqau Eb dilantunkan dengan tempo sedang sampai cepat penuh semangat. Berdasarkan ragam nada yang dimiliki, jika Eb Biasa menggunakan enam nada (heksatonis) dengan skala nada tritonis, maka Qaqau Eb menggunakan lima nada pentatonis, yaitu nada si, la, sol, fa dan mi dengan skala nada tritonis yang tentunya berbeda dengan alur melodi pada Eb Biasa. Jika Eb Biasa menggunakan alur melodi yang didominasi oleh dua nada yaitu sol dan mi, maka Qaqau Eb menggunakan alur melodi yang didominasi oleh tiga nada, yaitu nada la, sol dan mi, sedangkan nada fa dan si merupakan nada sisipan. Berdasarkan cara menyelesaikan lantunan, Eb Biasa akan diakhiri dengan nada sisipan re dan do pada akhir frase dan keseluruhan lantunan, sedangkan pada Qaqau Eb akan terdengar suara kindho dengan pola pukulan cepat disambut teriakan manggar yang panjang sesuai kesepakatan, ditandai oleh tangan penabuh tifa yang diangkat tinggi.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 18
Selanjutnya, semua pelantun akan menutup dengan teriakan hu.
Gambar 5. Contoh 1-Qaqau Eb
Gambar 5 merupakan salah satu contoh
Qaqau Eb dari kampung Linggua Yaghai Barat dengan skala nada tritonis tanpa nada sisipan. Qaqau Eb memiliki tempo dan ketukan yang statis, namun setelah terjadi pengulangan dari awal, tempo akan semakin cepat dari tempo sebelumnya atau dalam istilah musik barat dikenal dengan accelerando (accel).
Gambar 6. Suasana di Kampung Soba saat
Melantunkan Eb
(Dokumentasi Pribadi)
Gambar 7. Contoh 2-Qaqau Eb
Gambar 7 merupakan Qaqau Eb dari kampung Soba Yaghai Timur, yang memiliki skala nada tritonis dengan nada si sebagai sisipan. Ini adalah salah satu Eb yang dilantunkan dengan bernyanyi dan menari.
3. Eb Oghob Lantunan ini berbeda dengan lantunan Eb
Biasa dan Qaqau Eb. Jika Eb Biasa menggunakan enam nada (heksatonis) dan Qaqau Eb menggunakan lima nada (pentatonis), maka Eb Oghob hanya menggunakan empat nada tetratonis yaitu fa, re, do, dan si dengan skala nada diatonis yang didominasi oleh nada fa dan re. Pada bagian akhir lagu akan ditutup dengan nada do dan si. Tempo lantunan ini adalah lambat-sedang, memiliki kesan sedih, mendayu-dayu, dan meratap. Ada beberapa kesamaan antara Eb Biasa dan Eb Oghob yang terletak pada tempo lantunan saat mengakhirinya. Nada do dan si yang dibunyikan tersebut akan diperlambat sedikit demi sedikit (ritardando) dan nada si akan ditarik lebih panjang.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 19
Gambar 8. Contoh Eb Oghob
Gambar 9. Suasana di Kampung Mur dan Monana saat Melantunkan Eb
Hubungan Makna, Bentuk, dan Struktur Eb
Nyanyian Eb memiliki kisah yang beragam dan menyimpan cerita sejarah suku Yaghai, antara lain kisah masa lalu, dinamika perkembangan budaya, kisah kelompok masyarakat dalam marga, nama kebesaran kampung, kisah tentang seorang pemimpin yang disegani, kisah tentang dusun, hak wilayah adat, kisah pernikahan, serta kisah hidup seseorang
yang telah meninggal. Semua kisah ini diceritakan secara lisan dalam lantunan Eb.
Suku Yaghai terbagi atas wilayah Yaghai barat, tengah, dan timur. Wilayah tengah dan timur memiliki kesamaan bahasa dan dialek, sedangkan wilayah barat memiliki sedikit perbedaan bahasa dan dialek. Namun demikian, orang Yaghai barat dapat mengerti bahasa dari wilayah Yaghai tengah dan timur. Istilah Eb digunakan untuk menjelaskan nyanyian tradisi pada suku Yaghai secara keseluruhan, namun ada istilah khusus untuk penyebutan jenis Eb di wilayah Yaghai timur. Jenis nyanyian Eb berkaitan dengan kisah-kisah yang terdapat di dalamnya. Nada-nada yang telah tersusun dari setiap jenis, bentuk, skala nada, frase, alur melodi, serta tempo, telah membentuk kisah dan makna yang berbeda. Jika alur melodi, frase dengan nada dan tempo tertentu didengarkan, maka akan langsung mengerti Eb apa yang sedang dilantunkan. Bentuk dan struktur Eb memiliki kisahnya sendiri, yakni kebahagiaan, sukacita, dan dukacita. Ketiga hal ini berkaitan dengan kisah Eb yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan. Bapak Noorbertus Yagoyemu adalah salah satu pelantun Eb yang juga merupakan kepala adat kampung Monana Yaghai Barat. Ia menjelaskan bahwa Eb adalah nyanyian Adat suku Yaghai yang memiliki kisah tentang kehidupan masa lampau suku Yaghai yang pergi mengayau atau memenggal kepala manusia (musuh). Pada saat para pemimpin akan pergi berperang, maka masyarakat akan melantunkan Eb untuk mengantarkan mereka. Setelah perang selesai dan anggota berhasil membawa hasil (kepala manusia), maka seluruh kelompok masyarakat akan menyambut dengan lantunan Eb bahagia, bersemangat dan penuh energi. Keberhasilan ini disambut meriah oleh seluruh masyarakat dengan memukul kindho atau tifa, memegang tombak, serta salawaku, sambil bernyanyi serta menari. Kisah tentang nyanyian ini kini telah beralih fungsi mengisahkan para pemimpin yang berwibawa, memiliki pengaruh kuat, dan membawa kemakmuran bagi masyarakat. Kisah tersebut antara lain menceritakan tentang para misionaris agama Katolik di wilayah Mappi, tentang pembaptisan pertama masyarakat suku Yaghai, serta tentang guru-guru katekese yang membantu para misionaris. Ia menjelaskan bahwa lantunan Eb menceritakan tentang hubungan manusia dengan
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 20
manusia atau hubungan sosial antara sesama manusia yang memiliki nilai adat budaya sangat tinggi, saling kerja sama, menghargai, memberikan semangat, serta memiliki rasa kebersamaan yang terwujud dalam suatu pesta ungkapan rasa syukur, sukacita, bahagia, maupun dukacita. Jika ada manusia yang menunjukkan sikap acuh tak acuh, tidak sesuai dengan kebaikan, kasih sayang, serta hal-hal baik lainnya, maka mereka akan dibunuh karena dipercaya memiliki bibit kejahatan yang dapat merusak kehidupan bersama masyarakat suku Yaghai.
Bapak Selus Ribamogoin, seorang pelantun Eb yang merupakan kepala Adat kampung Linggua/Mondau Yaghai Barat menjelaskan bahwa Eb adalah warisan turun temurun dari tete-nenek moyang suku Yaghai. Eb itu bernyanyi, memukul kindho atau tifa untuk menceritakan kisah kehidupan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa Eb mengisahkan kebahagiaan karena berhasil menemukan pohon sagu, kemudian memangkurnya dengan hasil yang banyak. Selain itu, Eb juga menggambarkan kebahagiaan atas kemurahan Tuhan yang telah menyediakan makanan, serta kebahagiaan karena dapat melihat burung-burung bermain bebas di hamparan rawa luas yang indah. Eb merupakan nyanyian untuk memuji kebesaran Tuhan (Aghme). Penjelasan ini juga disampaikan oleh seorang pelantun Eb dari kampung Piay dan Wanggate (tengah dan timur), Bapak Williams Waimu, yang mengatakan bahwa Eb menceritakan kisah hidup yang dilantunkan dalam nyanyian.
Masyarakat pendukung adat dan budaya suku Yaghai memeluk kepercayaan adat sebelum mengenal agama. Mereka berkeyakinan bahwa Tuhan suku Yaghai adalah Matahari. Matahari dalam bahasa Yaghai barat adalah Hapaq, sedangkan untuk suku Yaghai tengah dan timur disebut Tapaq. Eb dilantunkan untuk memuji kebesaran Tuhan yang terbentuk dalam wujud matahari. Dalam keyakinannya, Tuhan yang berwujud mataharilah yang menciptakan alam beserta segala isinya, manusia pria dan wanita yang hidup berkelompok dalam marga-marga. Matahari sangat menentukan kehidupan manusia Yaghai. Matahari memberikan aturan-aturan atau hukum adat sebagai menjadi prinsip dasar yang harus dijalani, ditaati, diikuti, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari aturan-aturan atau hukum adat tersebut adalah untuk mengatur kehidupan bersama yang
damai, aman, tenteram dan bahagia. Setelah agama Katolik mulai disebarkan, yang diikuti dengan kehadiran para pastor misionaris dan para katekese di wilayah Mappi, masyarakat pendukung budaya Yaghai kemudian menyerahkan diri dengan cara dibaptis untuk mengikuti Kristus sesuai ajaran Agama Katolik. Eb yang sebelumnya dilantunkan untuk memuji kebesaran matahari, kini beralih fungsi sebagai nyanyian untuk memuji dan memberikan kehormatan bagi Aghme atau Tuhan Yesus. Kisah ini diceritakan dalam lantunan yang penuh sukacita dan bahagia.
Bapak Williams Waimu juga menjelaskan bahwa selain mengisahkan kebahagiaan dan sukacita, Eb juga mengisahkan duka cita. Ketika seseorang mendengarkan berita duka dari keluarga atau kerabat, mereka secara spontan akan menangis sambil bercerita mengenai seseorang yang baru saja dipanggil Tuhan, menyesali, dan meratapinya dalam lantunan. Lantunan ini dinyanyikan secara spontan pada saat mendengar berita duka tersebut. Setelah bertahun-tahun, untuk mengenang keluarga yang telah meninggal, akan dilantunkan nyanyian yang berkisah tentang kematian, rasa penyesalan, rasa haru, serta mengenang kebahagiaan saat bersama. Kisah-kisah yang diceritakan dalam lantunan Eb yang telah dijelaskan ini menghasilkan jenis-jenis nyanyian Eb yang telah ada sejak tete-nenek moyang suku Yaghai. Penjelasan mengenai jenis-jenis Eb dianalisis berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam kepada informan.
1. Eb Biasa Eb Biasa merupakan istilah yang dipakai
oleh masyarakat Yaghai untuk menjelaskan lantunan yang berbeda dengan lantunan Qaqau Eb, Oghob, atau Nama Eb. Lantunan ini, cenderung mengisahkan sesuatu hal yang lebih universal mengenai hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Eb Biasa mengungkapkan sesuatu yang universal dan biasanya tidak secara spesifik menjelaskan perasaan seseorang atau kelompok pada suatu peristiwa, misalnya lantunan yang berkisah tentang batas-batas wilayah tanah kampung. Kisah tersebut akan diceritakan dalam lantunan Eb dengan tujuan agar orang yang mendengar akan mengetahui batas-batas wilayah kampung atau marganya. Lantunan ini tidak menjelaskan perasaan seseorang maupun kelompok, yang memiliki ataupun tidak memiliki wilayah tersebut, tidak
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 21
pula menjelaskan perasaan khusus, misalnya rasa bahagia dan terhormat karena memiliki tanah yang luas ataupun sebaliknya.
Kisah lain dalam konteks lantunan Eb Biasa, misalnya kisah tentang seorang anak yang akan pergi merantau. Lantunan ini akan menjelaskan bagaimana seseorang tersebut datang dan meminta doa restu dari orang tua, kemudian orang tua akan mendoakan serta memberikan nasehat. Kisah dalam lantunan ini tidak secara spesifik menjelaskan tentang perasaan seseorang yang akan meninggalkan keluarga dan keluarga yang ditinggalkan, namun cenderung mengisahkan apa yang dilakukan seseorang dan suatu keluarga ketika akan pergi merantau.
Eb Biasa secara tidak langsung memberikan pesan dan informasi kepada orang lain yang mendengar lantunan tentang suatu peristiwa. Contoh lain dari Eb Biasa, yaitu kisah tentang laki-laki dan perempuan pergi memangkur sagu. Lantunan dalam kisah ini akan menjelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan pergi mencari pohon sagu, menemukan pohon tersebut, kemudian memangkurnya. Pohon sagu yang ditemukan merupakan petunjuk dari Tuhan. Lantunan Eb Biasa sebatas menyampaikan informasi bahwa karena petunjuk dan kebaikan Tuhan, maka mereka dapat menemukan pohon sagu. Dalam lantunan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tentang bagaimana perasaan mereka setelah menemukan pohon sagu, memangkur, dan menghasilkan makanan. Lantunan Eb Biasa juga mengisahkan tentang iman dan kepercayaan akan Tuhan, salah satunya kisah tentang kebangkitan Tuhan. Kisah ini dilantunkan untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit ke surga, membuka kubur batu, dan bangkit mengalahkan maut. Lantunan Eb Biasa tidak menjelaskan perasaan bahagia karena Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut, tetapi sebatas menyampaikan pesan dan informasi kepada yang mendengar. Kisah dalam Eb Biasa cenderung mengisahkan hal yang universal dan pada akhirnya dikatakan sebagai rasa syukur dan sukacita.
2. Qaqau Eb Jika Eb Biasa cenderung mengisahkan hal-hal yang universal, Qaqau Eb mengisahkan hal-hal yang lebih spesifik dari hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Contoh kisah dalam Qaqau Eb, antara lain kisah tentang masyarakat
kampung yang akan mengantarkan para pemimpin dan anggotanya pergi berperang (mengayau), dan saat pulang mereka membawa hasil (kepala manusia) yang disambut dengan kebahagiaan besar. Kisah ini menjelaskan bagaimana lantunan Qaqau Eb mengantar dan menyambut seorang pemimpin perang. Dalam konteks saat ini, Qaqau Eb digunakan untuk mengantar dan menyambut seorang pemimpin yang memiliki peran penting dalam masyarakat, sosok yang dikagumi dan disanjung, serta menjadi panutan masyarakat. Sebagai contoh, yaitu pemimpin daerah, pemimpin gereja, camat, bupati, uskup, pastor, biarawati, serta tamu kehormatan. Contoh lain, yaitu kisah tentang kebahagiaan seseorang yang melihat alam yang indah, melihat burung ayam rawa yang sedang mengumpulkan rumput kering dan membuat sarang, menari-nari dengan lincah. Kisah ini menjelaskan suatu rasa kegembiraan. Selanjutnya kisah lain dalam Qaqau Eb berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kisah tersebut menceritakan bagaimana masyarakat kampung Linggua menyerahkan tengkorak kepala hasil perangnya kepada para pastor. Mereka bersedia dibaptis dan meninggalkan tradisi mengayau sebagai ungkapan rasa bahagia karena telah menerima terang, menerima Injil dan diangkat menjadi anak Allah. Ungkapan kebahagiaan ini dilantunkan dengan penuh semangat dan bahagia. Qaqau Eb cenderung mengisahkan hal yang bahagia, bersemangat, menggebu-gebu dan penuh energi.
3. Eb Oghob Dalam penyebutan sehari-hari, nyanyian
Eb di wilayah Yaghai timur dikenal dengan istilah Nama-Eb dan Oghob. Nama berarti menangis. Nama-Eb yang mengisahkan tentang seseorang yang telah meninggal ini diciptakan di saat ada kematian. Keluarga atau orang yang mendengar seseorang telah meninggal secara spontan akan menangis dan menceritakan kehidupan seseorang tersebut dalam lantunannya. Ratapan penyesalan dan rasa haru serta tangisan disampaikan lewat lantunan nyanyian. Nama-Eb jarang dinyanyikan karena nyanyian ini bersifat spontanitas. Namun demikian, tidak jarang bahwa lantunan Nama-Eb dapat dinyanyikan kembali untuk mengenang seseorang yang telah pergi, meskipun sedikit berbeda dengan nyanyian awal. Seseorang dapat membuat kembali nyanyian tersebut untuk mengenang seseorang yang telah pergi baik itu
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 22
meninggal dunia ataupun pergi untuk sementara. Nyanyian yang dilantunkan untuk mengenang seseorang yang telah meninggal, yang menggambarkan kesedihan, dukacita, ratapan, maupun kepedihan disebut dengan istilah Oghob.
Nyanyian Eb dibawakan secara komunal, bersama-sama atau kelompok. Pengulangan nyanyian tergantung kesepakatan bersama. Alat musik yang digunakan adalah kindho atau tifa dan pup yaitu alat musik yang terbuat dari bambu, berbentuk tabung dan terdapat lubang kecil pada salah satu ujung bambu. Nyanyian Eb memberikan pesan kebersamaan, gotong royong, saling membantu.
Eb dilantunkan oleh pria maupun wanita dewasa. Perempuan mendapat tempat yang setara untuk bernyanyi bersama, memukul kindho, memimpin nyanyian dan memiliki kelompok nyanyian Eb yang anggotanya terdiri dari mama-mama dan anak perempuan dewasa. Situasi ini telah berlangsung dari tete-nenek moyang. Hal ini berarti bahwa perempuan pada suku Yaghai sangat dihormati, dihargai dan memiliki peranan penting, meskipun sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah tentang hal tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan suku Yaghai mengambil bagian dalam pekerjaan seperti mencari ikan di rawa, memangkur sagu, mencari kayu bakar di hutan, menjaga anak dan mengurus keluarga. Meskipun perempuan bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga, namun dalam kaitannya dengan tradisi nyanyian Eb, tampak bahwa perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Peradaban suku Yaghai memberikan bukti akan sebuah pemikiran yang maju, terbuka, serta berkembang. Hal ini juga disampaikan oleh para misionaris Katolik dalam catatan etnografi bahwa kerja sama antara laki-laki dan perempuan sangat terlihat pada suku Yaghai dalam berbagai pekerjaan, seperti membangun rumah, membuat perahu, berkelahi, dan pergi mengayau. Tampak bahwa telah terjadi kerja sama antara laki-laki dan perempuan yang disertai pembagian tugas masing-masing dengan jelas (Boerlaars, 1986).
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dari hasil penelitian, ditemukan adanya hubungan antara makna, bentuk, dan struktur nyanyian Eb. Makna yang terkandung dalam kisah Eb berbeda-beda sesuai dengan
bentuk dan struktur yang tidak terlepas dari jenis-jenis Eb. Sebagai contoh, ketika nada-nada diperdengarkan dengan skala tritonis, dengan satu nada sisipan, tempo cepat, pengulangan, dan teriakan, maka orang akan mengerti bahwa Eb yang dilantunkan adalah Qaqau Eb dengan perasaan bahagia dan gembira. Hal ini berlaku untuk Eb Biasa dan Oghob.
Makna memiliki hubungan erat dengan bentuk dan struktur nyanyian Eb itu sendiri. Eb Biasa berkaitan dengan sukacita yang bersifat universal, Qaqau Eb berkaitan dengan ungkapan bahagia, Oghob berkaitan dengan dukacita yaitu kesedihan. Begitu pula sebaliknya bahwa bentuk dan struktur nyanyian Eb berkaitan erat dengan makna nyanyian itu sendiri. Keterkaitan antara bentuk, struktur, dan makna Eb ini telah terjadi secara turun temurun. Hasil analisis dan interpretasi terhadap tradisi lantunan ini menunjukkan bahwa Eb merupakan simbol dari nilai-nilai budaya lokal yang kaya yang lahir dari ide-ide manusia suku Yaghai. Nilai-nilai budaya lokal berupa tradisi lisan ini diharapkan akan dapat terus hidup dan dihidupkan sebagai kekayaan budaya Indonesia melalui upaya dokumentasi dan pemertahanan praktiknya dalam kehidupan suku Yaghai Mappi Papua.
Gambar 10. Mama-mama dari Kampung Soba
Memukul Kindho/Tifa saat Melantunkan Eb
REFERENSI
Assa, Veibe Rhibka. (2012). Fungsi dan Makna Etai pada Ritus Mawek Orang Hubula di Kabupaten Jayawijaya. Dalam Dumatubun, E.A. (Ed.) Perspektif Budaya Papua. Jakarta: CV Ihsan Mandiri.
Boelaars, Jan. (1986). Manusia Irian Dahulu Sekarang dan Masa Depan. Jakarta: PT. Gramedia.
Creswell, John W. (2015). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 23
Ehineni, Taiwo Oluwaseun. (2017). From Conceptual Methapors to Cultural Methapors: Methaporical Language in Proverbs and Praise Poems. Language Matters Journal. Volume 48:3, 130-144.
Geertz, Clifford. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc.
Layan, Septina. (2019). Nyanyian Tradisi Eb Suku Yaghai Mappi Papua Selatan. Yogyakarta: Penerbit SAE.
Pongantung, Herman. (2019). Tanah-Tanah Rawa. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Prier, Karl-Edmund. (2009). Kamus Musik. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi.
Rumansara, Enos., Rumbiak, Trisna., Tawayop, Emanuel., Pahabol, Ayub., dan Ambarwati. (2012). Tradisi WOR di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Jakarta: Konsultan Media.
Stein, Leon. (1979). Structure & Style Expanded Edition: The Study and Analysis of Musical Forms. Florida: Summy-Bichard Music.
Yektiningtyas-Modouw, Wigati. (2010). Helaihili dan Ehabla Fungsinya dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Sentani Papua. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
Yenusi, Bilgita. (2016). Relasi Sosial dalam Nyanyian “Munaba” Etnik Waropen- Papua: Kajian Sosiologi Sastra. Melanesia Jurnal Ilmiah. Vol. 1 No.1.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 24
KONSEP NYUPAK DALAM KARAWITAN JAWA
THE CONCEPT OF ‘NYUPAK’ IN JAVANESE TRADITIONAL MUSIC INSTRUMENT
Sito Mardowo1
Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
ABSTRACT
The word ‘nyupak’ is a Javanese term which is often used in daily events or activities. ‘Nyupak’ is simply an activity of joining two objects so that the main object joined with another object can be used again according to its function. As a matter of fact, the term ‘nyupak’ is also used in karawitan organology in the process of (1) the tuning of ‘gender bumbungan’ (‘gender’ resonance) and (2) the tuning of gamelan, both in the form of blades and in the form of ‘pencon’. The current study aims at exploring the concept of ‘nyupak’ in Javanese traditional music instrument from acoustic perspective. The results of the study demonstrate that ‘nyupak’ in the tuning on ‘gender bumbungan’ (‘gender’ resonance) ranges from the intervals of 2 cents up to 12 cents, or written as 2 ≤ x ≤ 12 cents, and ‘nyupak’ in the tuning on gamelan ranges from the intervals of 10 cents up to 33 cents, or written as 10 ≤ x ≤33 cents. The result of the study provides a referential formulation for the tuning process of ‘gender bumbungan’ and gamelan, particularly to cope with ear sensitivity in capturing the tone frequency.
Keywords: karawitan, nyupak, tuning, interval.
ABSTRAK
Kata nyupak merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang sering digunakan pada peristiwa atau kegiatan sehari-hari. Secara sederhana kegiatan nyupak dapat diartikan sebagai kegiatan menyambung dua buah benda sehingga benda yang tersambung dapat berfungsi lagi sesuai dengan keperluannya. Istilah nyupak ternyata digunakan juga pada organologi karawitan yang diterapkan pada (1) pelarasan bumbungan gender dan (2) pelarasan gamelan, baik yang berbentuk bilah maupun yang berbentuk pencon. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep nyupak yang diterapkan pada karawitan Jawa dari perspektif ilmu akustika. Hasil pengukuran yang dilakukan pada studi lapangan menunjukkan bahwa nyupak pada pelarasan bumbungan gender berkisar pada interval 2 cent sampai dengan 12 cent, atau dapat dituliskan 2 ≤ ᵡ ≤ 12 cent, dan nyupak pada pelarasan gamelan berkisar pada interval 10 cent sampai dengan 33 cent atau 10 ≤ ᵡ ≤ 33 cent. Formulasi pelarasan ini dapat menjadi acuan untuk mengatasi kesulitan pada kepekaan telinga dalam menangkap frekuensi nada, atau membantu kepekaan telinga terhadap frekuensi nada ketika melakukan pelarasan bumbungan gender dan pelarasan nada gamelan.
Kata kunci: karawitan, nyupak, pelarasan, interval.
1Sito Mardowo adalah widyaiswara di BBPPMPV Seni dan Budaya yang menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Program Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis berminat pada bidang seni karawitan, seni budaya, dan pendidikan.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 25
PENDAHULUAN
Istilah nyupak atau nyopak sering ditemukan pada percakapan sehari-hari dalam bahasa Jawa. Nyupak atau nyopak berasal dari kata dasar supak atau sopak yang secara sederhana berarti ‘sambung’. Apabila mendapat imbuhan, maka kata nyupak berarti ‘menyambung’, dan supakan berarti ‘sambungan’ (Sudarmanto, 2008:317).
Pada masa ekonomi sulit pascakemerdekaan, istilah nyupak dikenal oleh anak-anak sekolah pada masa itu. Alat tulis pensil yang pada saat itu relatif mahal bagi anak sekolah terpaksa harus digunakan seefisien mungkin sampai pada rautan yang sangat pendek. Apabila pensil sudah mulai pendek (kurang lebih tinggal 5 cm), maka cara memegang pensil menjadi sulit. Untuk mengantisipasi kesulitan tersebut, pensil tersebut di-supak (disambung) dengan bambu sehingga menjadi panjang dan nyaman untuk digunakan lagi sampai pada rautan yang terakhir. Hastanto, peneliti dan ahli organologi gamelan, melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014, mengatakan bahwa bambu yang digunakan untuk menyambung pensil yang pendek harus dipilih sesuai dengan ukuran pensil yang akan disambung. Diameter lingkaran luar pensil harus tepat atau sesuai dengan diameter lingkaran dalam bambu, sehingga ketika disambung menjadi kuat dan ketat.
Istilah nyupak juga ditemukan pada kegiatan sehari-hari di kalangan para tukang bangunan rumah, misalnya pada saat membuat usuk2 yang terbuat dari bambu. Apabila bambu tersebut kurang panjang, maka dilakukan kegiatan nyupak dengan cara menyambung dua buah potongan bambu sehingga bambu tersebut menjadi lebih panjang. Begitu juga pada peristiwa menyambung dua buah paralon air agar menjadi panjang, para tukang biasa menyebut kegiatan tersebut dengan istilah nyupak.
Menyimak arti kata dan ilustrasi peristiwa yang disajikan, maka kata atau istilah nyupak dapat dimaknai sebagai kegiatan menyambung suatu benda yang minimal terdiri dari dua elemen, yaitu (1) benda yang disambung, dan (2) benda yang menyambung. ‘Benda yang disambung’ merupakan benda utama atau benda
2Usuk atau juga biasa dikenal dengan istilah ‘kasau’ adalah balok kayu atau bambu yang diletakkan melintang di atas penyangga atap rumah. Usuk memiliki bentuk yang memanjang, mulai dari balok dinding hingga keluar bagian dinding.
pokok yang akan digunakan untuk keperluan tertentu, sedangkan ‘benda yang menyambung’ merupakan sebuah benda sekunder yang difungsikan untuk mendukung benda utama atau benda pokok agar benda utama dapat digunakan sesuai dengan keperluannya.
Istilah nyupak ternyata juga digunakan dalam dunia karawitan, terutama pada sistem pelarasan gamelan Jawa. Istilah nyupak ini digunakan pada saat seorang penglaras gamelan melakukan pelarasan bumbungan3 gender dan pelarasan nada-nada gamelan. Sampai saat ini para ahli pelarasan gamelan maupun para ahli bidang organologi karawitan belum pernah menggali konsep nyupak dengan pendekatan ilmu akustika yang membahas tentang frekuensi gamelan. Analisis pengukuran frekuensi nada-nada gamelan yang menghasilkan konsep embat dalam karawitan Jawa dilakukan oleh Hastanto (2010). Yang dikupas dalam penelitian Hastanto ini adalah frekuensi gamelan Jawa yang dikaitkan dengan embat4. Studi dilakukan dengan cara mengukur frekuensi nada gamelan Jawa, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan karakter Larasati5 atau Sundari6. Penelitian Hastanto secara detail menganalisis frekuensi gamelan, tetapi tidak menyinggung permasalahan nyupak yang terdapat pada sistem pelarasan gamelan Jawa. Di sisi lain, Rahayu (2013) melakukan penelitian kontroversi slendro keroncong, yang mengungkap komparasi frekuensi tangga nada slendro pada gamelan Jawa dengan frekuensi tangga nada slendro pada alat musik keroncong. Menurut analisisnya, para seniman karawitan beranggapan bahwa slendro yang dimainkan dengan alat musik keroncong dirasa fals atau blero, sedangkan para seniman keroncong beranggapan bahwa tangga nada slendro gamelan tetap enak didengarkan ketika mengiringi lagu-lagu langgam Jawa. Penelitian ini tidak mengupas tentang peristiwa nyupak yang terdapat pada gamelan Jawa dan frekuensi resonator pada instrumen gamelan Jawa.
Penelitian terkait yang dilakukan oleh Seno (2008) membahas daya kreativitas AL. Suwardi dalam menciptakan alat musik baru,
3Bumbungan adalah sebuah resonator yang terbuat dari bambu maupun galvalum yang berfungsi sebagai penguat frekuensi nada. Agar bumbungan dapat berfungsi sebagai penguat nada, maka perlu dilakukan pelarasan. 4Embat adalah pengaturan frekuensi nada gamelan sehingga memiliki karakter tertentu. 5Larasati adalah embat gamelan yang memiliki karakter halus, lembut (Jawa: luruh). 6Sundari adalah embat gamelan yang memiliki karakter lincah, genit (Jawa: mbranyak).
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 26
yang salah satunya adalah gender jangkung yang merupakan paduan antara gender Jawa dengan vibraphone. Gender jangkung menggunakan bumbungan sebagai resonator dengan bentuk yang panjang menyerupai bumbungan yang terdapat pada alat musik vibraphone. Bumbungan tersebut juga dilaras sesuai dengan frekuensi yang diinginkan tetapi tidak secara detail membahas bagaimana cara melaras dan bagaimana konsep nyupak itu diterapkan. Penelitian Seno ini lebih berfokus pada bagaimana daya kreativitas AL. Suwardi dalam menciptakan alat musik baru untuk memenuhi tuntutan kebutuhan karya komposisi baru. Hardjito dalam bukunya, ‘Melaras Getar Bilah’ (1977) menuliskan cara menghitung getaran, menetapkan frekuensi, dan cara mengukur frekuensi dari sudut pandang ilmu fisika dan akustika. Dalam tulisannya, Hardjito menjelaskan kerja melaras dengan cara merendahkan-meninggikan frekuensi instrumen gamelan, tetapi tidak menyinggung peristiwa nyupak pada pelarasan bumbungan maupun menetapkan sejauh mana frekuensi nyupak pada pelarasan nada-nada gamelan.
Telaah yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait konteks pelarasan gamelan Jawa telah mendorong dilakukannya penelitian tentang pelarasan bumbungan gender dan pelarasan nada-nada gamelan. Oleh karena itu, penelitian untuk menemukan formulasi nyupak yang diterapkan pada pelarasan bumbungan gender dan pelarasan nada-nada gamelan perlu untuk dilakukan.
Sampai saat ini tradisi pelarasan bumbungan dan pelarasan nada-nada gamelan masih mengandalkan kepekaan telinga dalam menangkap frekuensi nada. Keterampilan tersebut pada saat ini sangat sulit dipelajari karena membutuhkan bakat dan pengalaman yang relatif lama agar menjadi peka terhadap frekuensi nada. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memformulasikan konsep nyupak yang ditinjau dari rentang frekuensi interval yang terdapat pada sistem pelarasan bumbungan dan gamelan. Apabila rentang tersebut sudah diketahui, maka dengan mudah seseorang dapat melakukan pelarasan dengan alat bantu frekuensi meter. METODE PENELITIAN
Fokus dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan rumusan rentang frekuensi pada pelarasan bumbungan dan pelarasan nada-nada
gamelan yang menurut para pengalaras gamelan disebut dengan istilah ‘nyupak’. Data-data frekuensi yang diarahkan pada penemuan rumusan rentang frekuensi diperoleh melalui (1) studi pustaka untuk mencari data yang berkaitan dengan organologi gamelan Jawa, ilmu akustika, pengukuran frekuensi, dan data-data frekuensi gamelan, (2) proses wawancara dengan penglaras gamelan dan peneliti organologi karawitan untuk mendapatkan informasi tentang pengertian nyupak dan penerapannya, dan (3) studi lapangan untuk mendapatkan data-data frekuensi bumbungan dan nada-nada gamelan dengan cara melakukan perekaman bunyi nada gamelan dan bumbungan dengan menggunakan aplikasi Adobe Audition 1.0. Setelah perekaman bunyi ini dilakukan, dilakukan juga editing agar hasil suara menjadi lebih jernih. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran frekuensi dengan menggunakan aplikasi G-String dan aplikasi Da Tuner yang terdapat pada Smartphone yang berbasis Android.
Analisis data yang diperoleh pada penelitian ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah membandingkan frekuensi bilah dengan bumbungan untuk menemukan formulasi nyupak pada bumbungan gender. Rentang antara frekuensi bilah dan bumbungan dicatat mulai dari rentang terkecil sampai dengan rentang terbesar. Rentang terkecil dan rentang terbesar kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan formulasi atau konsep nyupak bumbungan gender. Analisis yang kedua dilakukan untuk menemukan konsep nyupak pada pelarasan nada-nada gamelan dengan cara membandingkan data interval pada beberapa perangkat gamelan. Interval nada diidentifikasi dari mulai interval terpendek sampai dengan interval terpanjang. Setelah diketahui interval terpendek dan interval terpanjang, data tersebut digunakan sebagai acuan untuk menemukan formulasi atau konsep nyupak pada pelarasan gamelan Jawa.
HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Istilah nyupak pada lingkup karawitan Jawa sering ditemui pada peristiwa pelarasan bumbungan gender dan pelarasan nada-nada gamelan, baik yang berbentuk bilah maupun yang berbentuk pencon7. Pelarasan bumbungan gender adalah kegiatan pelarasan yang dilakukan
7Pencon adalah instrumen gamelan yang berbentuk seperti panci. Pada bagian tengah dibuat menonjol yang berfungsi sebagai letak atau titik yang dipukul.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 27
antara bilah gender dengan bumbungan gender. Bilah gender yang digunakan sebagai sumber bunyi harus dilaras sesuai dengan frekuensi yang diharapkan, sedangkan bumbungan juga perlu dilaras menyesuaikan bilah yang sudah dilaras. Dengan demikian, peristiwa nyupak dalam konteks pelarasan ini merupakan keterkaitan antara bilah dengan bumbungan.
Sebagai penguat suara, bumbungan gender harus dilaras lebih tinggi daripada bilah gender yang terletak di atasnya, tetapi rentang frekuensi yang ditetapkan pada bumbungan tidak boleh terlalu jauh. Apabila terlalu jauh, bumbungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagai penguat suara. Begitu juga pada pelarasan frekuensi nada-nada gamelan. Sistem pelarasan nada-nada dalam satu perangkat gamelan dibuat berbeda dengan selisih frekuensi dalam rentang frekuensi yang masih nyupak.
Selain berkaitan dengan bilah-bumbungan gender, peristiwa nyupak juga terdapat pada waktu dilakukannya pelarasan gamelan yang berkaitan dengan interval gamelan. Pengertian interval dalam konteks ini adalah jarak antara nada satu dengan nada lainnya. Pada populasi gamelan Jawa yang relatif banyak, tidak ada satupun gamelan yang sistem pelarasannya sama antara gamelan yang satu dengan lainnya. Perbedaan sistem pelarasan gamelan tersebut disengaja agar masing-masing gamelan memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan keinginan pemilik gamelan (misalnya apakah pelarasan gamelan cenderung menghasilkan karakter Larasati atau Sundari). Munculnya karakter gamelan dapat dilakukan dengan cara menggeser interval nada-nada yang terdapat pada tangga nada. Peristiwa menggeser nada-nada tersebut bisa dilakukan, namun harus dalam koridor masih nyupak. Dalam hal ini, peristiwa nyupak pada pelarasan bumbungan gender dan pelarasan gamelan memiliki konsep yang berbeda.
Konsep Nyupak pada Pelarasan Bumbungan Gender
Istilah nyupak pada dunia pelarasan gamelan dinyatakan sudah lama diketahui, namun sampai sekarang belum ada pustaka maupun informan yang menyatakan secara pasti kapan istilah tersebut digunakan (Hastanto, 2014). Meskipun tidak terdapat informasi yang menjelaskan kapan istilah nyupak digunakan pada pekerjaan pelarasan gamelan, setidaknya sedikit informasi tentang nyupak pada syair tembang ‘Sekar Macapat Kinanthi’ berikut ini dapat diketahui.
Sekar Macapat Kinanti
Kendhang teteh anarunthung,
suwarane lin-sumalin, jejeg ajeg wiramanya,
gender gumlendheng-gumlindhing, nyupak sumruwung bumbungnya,
gambang mblebeg banyu mili.
(http://www.sastra.org, diunduh tanggal 1 April 2021)
Terjemahan secara sederhana dari sekar
atau tembang ‘Kinanthi’ tersebut adalah sebagai berikut.
Sekar Macapat Kinanti
Kendhang jelas nyaring suaranya,
suaranya berganti-ganti, (macam-macam warna suaranya),
irama lagu konsisten dan teguh iramanya, gender bergaung mengalir,
nyupak nyaring suara bumbungnya, gambang nyaring mengalir.
Pupuh atau bait ‘Sekar Kinanthi’ yang
diunduh dari laman www.sastra.org di atas tidak diketahui siapa penciptanya. Pada akhir tembang diberikan identitas tahun penciptaan tembang, yaitu pada tahun 1938. Berdasarkan identitas penciptaan tembang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 1938 istilah nyupak sudah digunakan pada pelarasan gamelan.
Syair tembang ‘Sekar Macapat Kinanthi’ tersebut menyatakan bahwa kata nyupak yang ada di dalamnya ditujukan pada (1) instrumen gender, (2) bumbungan, dan (3) kualitas suara nyaring. Secara sederhana dapat dianalisis bahwa instrumen gender dapat memiliki suara yang nyaring ketika terdapat bumbungan yang nyupak. Antara instrumen gender dengan sumber bunyi bilah dan bumbungan harus terjadi peristiwa nyupak.
Kata nyupak pada kegiatan sehari-hari, sebagaimana contoh kegiatan menyambung pensil, memberikan pemahaman bahwa nyupak merupakan kegiatan menyambung dua elemen yang berbeda ukuran, dan ketika disambung harus dengan ukuran yang tepat. Apabila dua hal tersebut diterapkan dalam permasalahan nyupak yang terlihat pada tembang Kinanti di atas, maka makna yang diperoleh adalah (1) nyupak merupakan kegiatan menyambung dua elemen,
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 28
yaitu elemen suara bilah gender dan elemen suara bumbungan. Bilah gender apabila dipukul akan menghasilkan suara tetapi tidak berlangsung lama, atau pendek durasinya. Oleh sebab itu dibutuhkan bumbungan yang berfungsi untuk memperpanjang suara yang ditimbulkan bilah, sehingga (2) dua elemen yaitu bilah dan bumbungan berbeda ukurannya, tetapi ketika disambungkan haruslah memiliki presisi atau ketepatan.
Pada kegiatan nyupak ini, frekuensi bumbungan harus lebih tinggi daripada frekuensi bilah agar suara yang dihasilkan lebih nyaring, lebih kuat dan lebih jelas. Pengertian presisi dalam konteks ini adalah frekuensi bumbungan harus lebih tinggi, tapi tidak terlalu signifikan supaya bumbungan dapat berfungsi memperkuat dan memperjelas nada. Hal ini diungkapkan oleh
Miskan, seorang pengrajin dan penglaras gamelan yang tinggal di Kemalang, Klaten, melalui wawancara pada tanggal 15 Desember 2014.
Pernyataan Miskan pada wawancara tersebut digunakan sebagai pijakan awal untuk melakukan analisis konsep nyupak pada bumbungan gender. Data frekuensi bilah dan bumbungan gender diambil dari instrumen gender barung laras Slendro gamelan gaya Surakarta milik Studio Karawitan BBPPMPV Seni dan Budaya Yogyakarta. Alat ukur frekuensi menggunakan aplikasi Da-Tuner lite dan G-string yang terdapat pada aplikasi mobile phone android.
Tabel 1. Frekuensi Nada Bilah-Bumbungan Gender
Register II III IV V
Nada nm pn gl dd lm nm pn gl dd lm nm pn gl dd
Frekuensi Bilah 116 135 154 178 204 235 272 309 358 409 469 543 619 713
Frekuensi Bumbungan 118 137 159 189 210 247 276 317 363 412 479 548 623 722
Keterangan: nm = nem pn = penunggul gl = gulu
dd = dada lm = lima
Pada Tabel 1 di atas dapat disimak bahwa seluruh data frekuensi bilah lebih rendah dari pada bumbungan. Perbedaan tinggi-rendah frekuensi bilah dan bumbungan memang disengaja untuk meningkatkan kualitas suara yang ditimbulkan dari sumber bunyi bilah gender. Perbedaan tersebut membentuk jarak nada atau interval antara frekuensi bilah dengan frekuensi bumbungan. Namun jarak nada tersebut harus masih dalam rasa ‘nyupak’, yang maksudnya masih dalam koridor toleransi rasa pelarasan gamelan Jawa. Untuk mengetahui toleransi jarak nada frekuensi bilah dan bumbungan dapat dilakukan dengan cara nilai frekuensi bumbungan dikurangi dengan nilai frekuensi bilah. Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Data pada Tabel 2 berikut ini menunjukkan bahwa konsep nyupak yang diterapkan pada pelarasan gender barung berada pada toleransi jarak nada antara frekuensi nada bilah dengan nada bumbungan, yaitu berada pada kisaran 2 cent sampai dengan 12 cent, atau dapat dituliskan sebagai 2 ≤ ᵡ ≤ 12 cent.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 29
Tabel 2. Toleransi Jarak Nada Frekuensi Bumbungan-Bilah
Register Nada Frekuensi
Bumbungan (FBu)
Frekuensi Bilah (FBi)
FBu -
FBi II nm 118 116 2
III
pn 137 135 2 gl 159 154 5 dd 189 178 11 lm 210 204 6 nm 247 235 12
IV
pn 276 272 4 gl 317 309 8 dd 363 358 5 lm 412 409 3 nm 479 469 10
V pn 548 543 5 gl 623 619 4 dd 722 713 9
Pelarasan bumbungan yang menggunakan
konsep nyupak pada instrumen gender ternyata selaras dengan hukum Doppler yang menyatakan bahwa frekuensi bunyi yang didengar atau ditangkap oleh pendengar atau penangkap akan lebih tinggi daripada frekuensi sebenarnya dari bunyi yang dihasilkan sumber bunyi (Charmahina, https://independent. academia. edu).
Pada instrumen gender, bilah menjadi sumber suara atau bunyi, sedangkan bumbungan digunakan sebagai penangkap sumber bunyi. Bilah gender yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Agar hasil suara tersebut dapat ditangkap dan dapat diperkuat, frekuensi penangkap
gelombang (bumbungan) harus berada di atas frekuensi bilah sebagai sumber suara.
Konsep Nyupak pada Pelarasan Nada Gamelan
Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penggeseran frekuensi pada interval nada-nada gamelan sengaja dilakukan dengan tujuan agar gamelan tersebut memiliki karakter yang unik sesuai dengan keinginan pemilik gamelan. Penggeseran frekuensi nada tersebut akan berdampak pada interval yang tidak flat atau datar tetapi interval yang meluas. Untuk memperjelas penerapan konsep tersebut, dibahas terlebih dahulu tentang frekuensi dan interval atau jangkah pada musik diatonis sebagai bahan bandingan.
Tangga nada diatonis mempunyai tujuh nada dalam satu oktaf yang jarak nadanya dibedakan menjadi dua, yakni (1) jarak nada satuan (tones), yang maksudnya adalah jarak nada antara nada satu dengan nada yang lainnya bernilai satu satuan utuh dengan ukuran 200 cent, dan (2) jarak nada tengahan laras (semitones), yang maksudnya adalah jarak nada satu dengan nada lainnya bernilai setengah dengan ukuran 100 cent (Banoe, 2003:114). Jumlah interval atau jarak nada satuan (tones) adalah lima buah dalam satu oktaf, sedangkan jarak nada tengahan laras (semitones) adalah dua buah dalam satu oktaf. Skema pada Gambar 1 berikut menjelaskan hal ini.
Gambar 1. Tangga Nada Diatonis (Rahayu, 2013: 37) Ditinjau dari sisi interval, tangga nada diatonis memiliki 1200 cent dalam satu oktaf yang merupakan penjumlahan dari nada pertama: C1 sampai dengan nada C2. Ukuran 1200 cent dalam satu oktaf ini merupakan standar yang sudah dibakukan secara internasional sehingga tidak
ada penafsiran lain selain ukuran tersebut. Dampak dari pembakuan interval tersebut adalah frekuensi tiap nada dalam tangga nada diatonis menjadi baku pula seperti terlihat dalam Gambar 2 berikut.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 30
Gambar 2. Frekuensi Nada Diatonis (Ishafit, dkk., https://www.researchgate.net/publication/326143127. Diunduh 10 April 2021)
Pembakuan interval yang memiliki jumlah
1200 cent secara tepat berdampak pada frekuensi nada pertama yang bernilai separuh dari nada oktafnya. Apabila di dalam gambar nada C4
bernilai 262 Herzt, maka nada oktafnya adalah C5 yang bernilai 524. Hal ini dapat dirumuskan menjadi:
F1 = Frekuensi nada bawah F2 = Frekuensi nada tinggi, 1 oktaf dari nada F1
Karawitan Jawa tidak menganut konsep absolute pitch seperti yang terdapat pada tangga nada diatonis. Secara teoretis satu oktaf atau satu gembyang senilai 1200 cent, tetapi pada kenyataannya pelarasan semacam itu tidak dilakukan pada karawitan Jawa. Satu gembyang dalam karawitan Jawa tidak mutlak 1200 cent, tetapi cenderung bernilai lebih. Sebagai contoh pada Tabel 3 berikut ini disajikan pelarasan gender barung gamelan Ageng Kabupaten Karanganyar.
Tabel 3. Pelarasan Gender Barung Gamelan Ageng
Register II III IV
Nada nm pn gl dd lm Nm pn gl dd lm nm pn gl dd
Frekuensi 119 136 156 180 209 239 274 316 363 418 481 551 632 726
Interval N 245 237 247 250 240 230 247 240 244 247 235 240 237
Interval G 1219 cent
Interval G 1204 cent
Interval G 1207 cent
Interval G 1207 cent
Interval G 1201 cent
(Sumber: Hastanto, 2012: 42)
Keterangan: N = Nada G = Gembyang atau satu oktaf
nm = nem pn = penunggul gl = gulu
dd = dada lm = lima
Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa satu gembyangan: nm2 ke nm3
senilai 1219, pn3 ke pn4 senilai 1204, gl3 ke gl4
senilai 1207, dd3 ke dd4 senilai 1207, dan lm3 ke lm4 senilai 1201. Tidak terdapat satu pun jangkah satu gembyang pada deretan nada-nada
tersebut yang bernilai tepat pada nilai 1200 cent, tetapi cenderung lebih di atas 1200 cent. Nilai kecenderungan kelebihan tersebut disengaja oleh para penglaras agar pelarasan memiliki karakter, tidak datar, dan tidak hambar (Hastanto, 2012: 43).
F2 = 2 x F1
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 31
Proses ‘kesengajaan’ dalam menggeser frekuensi agar interval satu gembyang melebihi 1200 cent tersebut ternyata menggunakan konsep nyupak yang memiliki pengertian frekuensi nada digeser meluas atau melebar. Satu gembyang yang seharusnya memiliki interval 1200 cent diperluas melebihi nilai tersebut dengan cara menurunkan frekuensi nada (F1) atau meninggikan frekuensi pada (F2). Namun penggeseran tersebut juga tidak boleh terlalu lebar atau luas supaya nada yang digeser tidak menjadi blero atau fals.
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana tingkat penggeseran frekuensi yang dilakukan sehingga tidak melebihi batas toleransi yang berdampak nada menjadi blero atau fals. Dalam sistem pelarasan di Jawa dikenal istilah ‘toleransi rasa pelarasan slendro atau pelog’, yang maksudnya adalah nada-nada
yang terdapat dalam laras pelog atau slendro dapat ‘digoyang8’ sesuai selera pemilik gamelan atau penglaras gamelan, tetapi harus masih dalam lingkup nuansa ‘rasa’ pelarasan slendro atau pelog (Rahayu, 2013:54). Pernyataan tersebut masih bersifat abstrak, karena untuk menentukan ‘rasa’ slendro atau pelog dibutuhkan pengalaman-empiris dalam sistem pelarasan gamelan Jawa.
Berdasarkan studi yang pernah dilakukan, Rahayu (2013) mendapatkan data tentang frekuensi laras gamelan-gamelan babon9 (Gamelan RRI Surakarta, Gamelan Wayangan Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, Gamelan Kyai Slamet Tamtaman Baluwarti Surakarta, dan Gamelan Gedhong Gede ISI Surakarta) yang terdapat di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Data-data tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Skala 1 Frekuensi Nada Gamelan Babon10 Surakarta
(Sumber: Rahayu, 2013)
Skala 1 menunjukan interval nada dari beberapa gamelan yang menyatakan bahwa dari nada Nem ke Ji memiliki interval terpendek 230 cent dan interval terjauh 263, dari nada Ji ke Ro interval terpendeknya adalah 227 cent dan interval terjauhnya adalah 237, dari nada Ro ke Lu interval terpendeknya adalah 215 cent dan interval terjauhnya adalah 240, dari nada Lu ke Ma interval terpendeknya adalah 240 cent dan interval terjauhnya adalah 260, dan dari nada Ma ke Nem memiliki interval terpendek 210 cent dan interval terjauh 230.
8 Menggeser frekuensi nada ke atas atau ke bawah. 9 Pelarasan gamelan yang dijadikan acuan gamelan-gamelan yang lain.
Tabel 4. Interval Terpendek dan Terpanjang
JARAK NADA
TERPENDEK (cent)
TERPANJANG (cent)
Nem ke Ji 230 263 Ji ke Ro 227 237 Ro ke Lu 215 240 Lu ke Ma 240 260 Ma ke Nem 210 230
Data interval terpendek dan terpanjang
dalam ukuran cent yang disajikan pada Tabel 4 di atas dapat digunakan sebagai acuan untuk memaknai batas toleransi interval yang dinyatakan tidak blero atau fals. Berdasarkan data-data tersebut, dicari toleransi jarak nada
10 Babon adalah gamelan yang digunakan sebagai acuan pelarasan.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 32
dengan cara interval terpanjang dikurangi interval terpendek di setiap jarak nada (Nem ke Ji, Ji ke Ro, Ro ke Lu, Lu ke Ma, Ma ke Nem).
Tabel 5. Interval Terpanjang Dikurangi Terpendek
JARAK NADA
TER-PANJANG
TER-PENDEK
TERPANJANG DIKURANGI TERPENDEK
Nem ke Ji 263 230 33 Ji ke Ro 237 227 10 Ro ke Lu 240 215 25 Lu ke Ma 260 240 20 Ma ke Nem
230 210 20
Tabel 5 menunjukkan bahwa jarak nada
atau jangkah nada Nem ke Ji memiliki nilai terbanyak, yaitu sebesar 33 cent, sedangkan yang lain berkisar antara 10 sampai dengan 25 cent. Makna dari hasil pengukuran ini adalah bahwa toleransi ‘rasa’ jarak nada yang dinyatakan tidak fals atau blero versi gamelan Jawa adalah 10 cent sampai dengan 33 cent, atau dapat dituliskan sebagai 10 ≤ ᵡ ≤ 33 cent.
Pernyataan serupa juga pernah ditulis oleh Hastanto (2010:62), yang menyatakan bahwa toleransi pergerseran jarak yang masih dirasakan kêpénak11 dalam bingkai interval panjang adalah di atas 260 cent dan di bawah 290 cent. Apabila disejajarkan dengan cara menyimpulkan toleransi ‘rasa’ jarak nada seperti pada Tabel 3, maka akan didapatkan nilai interval adalah 290 – 260 = 30 cent. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran 33 cent pada penelitian ini dengan pernyataan Hastanto (2010), karena hasil pengukuran hanya terpaut 3 cent saja.
SIMPULAN
Konsep nyupak atau nyopak yang biasa dilakukan pada kegiatan hidup sehari-hari ternyata dapat diterapkan dalam ranah karawitan. Penerapan tersebut berangkat dari esensi dari makna kata nyupak, yaitu bahwa (1) nyupak merupakan kegiatan menyambung dua elemen, dan (2) dua elemen tersebut berbeda ukurannya tetapi ketika disambung harus presisi atau memiliki ketepatan ukuran.
11 Kêpénak adalah sesuatu yang dirasakan enak (appropriate), dan ora kêpénak adalah situasi yang sebaliknya. Keduanya merupakan parameter rasa dalam karawitan Jawa yang juga termasuk nada-nadanya.
Dalam konteks ini, konsep nyupak dalam karawitan Jawa diterapkan pada cara kerja instrumen gender yang menggunakan dua elemen, yaitu (1) bilah gender sebagai sumber bunyi, dan (2) bumbungan sebagai resonator yang berfungsi sebagai penguat nada. Frekuensi nada bilah harus lebih rendah dibandingkan dengan bumbungan gender, dengan toleransi 2 sampai dengan 12 cent atau 2 ≤ ᵡ ≤ 12 cent. Konsep ini selaras dengan hukum gelombang Doppler yang menyatakan bahwa frekuensi gelombang suara yang memancar dari sebuah sumber bunyi akan diterima lebih tinggi.
Konsep nyupak juga diterapkan pada sistem pelarasan gamelan Jawa yang nada oktaf pada register bawah atau atas secara sengaja akan di ‘goyang’, atau frekuensi nada digeser ke bawah atau ke atas agar nada yang ditimbulkan tidak ‘terasa’ datar atau flat. Tingkat toleransi penggeseran nada berkisar pada 10 sampai dengan 33 cent atau dapat diformulasikan menjadi 10 ≤ ᵡ ≤ 33 cent. Formulasi pelarasan yang ditemukan dari penelitian ini dapat diterapkan sebagai acuan untuk mengatasi kesulitan pada kepekaan telinga dalam menangkap frekuensi nada, atau membantu kepekaan telinga terhadap frekuensi nada ketika melakukan pelarasan bumbungan gender dan pelarasan nada gamelan. REFERENSI
Banoe, Pono. (2003). Kamus Musik. Yogyakarta: Kanisius.
Charmahina, Ancas. Pengertian Efek Doppler. Diakses dari https://independent. academia. edu. 10 April 2021.
Hardjito, Driadi Dwi. 1977. Melaras Getar Bilah. Bandung: ITB Press.
Hastanto, Sri. (2010). Konsep ‘Embat’ dalam Karawitan Jawa. Laporan Penelitian Program Hibah Kompetisi Seni B-Seni Tahun 2009-2010. Surakarta: ISI Press.
Hastanto, Sri. (2012). Ngeng dan Reng: Persandingan Sistem Pelarasan Gamelan Ageng Jawa dan Kebyar Bali. Surakarta: ISI Press Surakarta.
Ishafit, Khairil Anwar, dan Muh. Toifur. (2018). Pengukuran Frekuensi Tangga Nada Instrumen Musik dengan Sistem ‘Microcomputer Based Laboratory’. Diakses dari https://www.researchgate.net/ publication/326143127. 10 April 2021.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 33
Rahayu, TAP. (2013). Kontroversi Slendro Keroncong. Tesis S2 Pengkajian Musik ISI Surakarta.
Seno, Galih Naga. (2018). Kreativitas AL. Suwardi dalam Penciptaan Instrumen Baru. Tesis S2 Pengkajian Musik ISI Surakarta.
Sudarmanto. (2008). Kamus Lengkap Bahasa Jawa. Semarang: Widya Karya.
Webtografi: http://www.sastra.org/katalog/judul. Diunduh 1
April 2021. Informan: Miskan, 56 tahun, pengrajin dan penglaras
gamelan, tinggal di Kemalang, Klaten. Wawancara pada tanggal 15 Desember 2014.
Sri Hastanto, 75 tahun, peneliti, Guru Besar dalam bidang Etnomusikologi di ISI Surakarta, dan ahli Organologi Karawitan. Wawancara pada tanggal 13 Juli 2013.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 34
PANDAWA LIMA: PERWUJUDAN NILAI-NILAI KARAKTER BANGSA
PANDAWA LIMA: REPRESENTATION OF NATION CHARACTER VALUES
Purwadi1 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
ABSTRACT
Leather puppet or classical Javanese ‘wayang’ contains rich moral teaching practiced in human life. The current article aims at describing and analyzing Pandawa Lima characters reflecting five principal nation character values designed by the government. Content analysis is employed to study verbal expressions obtained from the narration of play scripts and ‘wayang kulit’ performance. The result of the study demonstrates that the characters of Pandawa reinforce five principal nation character values, namely (1) Puntadewa completely represents religious character values with sub-values of belief in God, being pious and absolutely obedient to God, care to others, and being harmonious with environment; (2) Werkudara fully represents character values of nationalism with sub-values of love to the homeland, spirit of nationality, devotion to the country, and pluralism; (3) Arjuna partly represents the character values of being independent with sub-values of lifelong learners, hardworkers, and being resilient; (4) Nakula partly represents the character values of working together with the sub-values of collaboration, helping each other, and doing things in a voluntary way; (5) Sadewa partly represents integrity character values with sub-values of being keen on the truth, moral commitment, responsibility, and respecting others.
Keywords: Pandawa, character values, nation character.
ABSTRAK
Wayang kulit mengandung banyak ajaran moral yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji perwujudan karakter Pandawa Lima yang mencerminkan 5 (lima) nilai utama karakter bangsa yang dicanangkan oleh pemerintah. Analisis konten dilakukan untuk mengkaji data berupa ungkapan-ungkapan verbal yang diperoleh dari narasi naskah lakon dan pementasan wayang kulit. Hasil kajian menunjukkan bahwa perwujudan Pandawa memberikan penguatan kepada 5 (lima) nilai utama karakter bangsa, yaitu (1) Puntadewa merupakan perwujudan sepenuhnya dari nilai karakter religius dengan subnilai karakter beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintah-Nya, peduli sosial, dan menjaga keselarasan dengan alam semesta; (2) Werkudara merupakan perwujudan sepenuhnya dari nilai nasionalisme dengan subnilai rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, semangat rela berkorban, dan semangat kebhinekaan; (3) Arjuna merupakan perwujudan sebagian dari nilai kemandirian dengan subnilai pembelajar sepanjang hayat, kerja keras, dan tahan banting; (4) Nakula merupakan perwujudan sebagian dari nilai gotong royong dengan subnilai kerja sama, tolong-menolong, dan sikap kerelawanan; serta (5) Sadewa merupakan perwujudan sebagian dari nilai integritas dengan subnilai cinta pada kebenaran, komitmen moral, tanggung jawab, dan menghargai martabat individu.
Kata kunci: Pandawa, nilai-nilai, karakter bangsa.
1Purwadi adalah widyaiswara di BBPPMPV Seni dan Budaya, menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP), Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011. Penulis berminat dan menggeluti bidang Seni Pedalangan dan Evaluasi Pendidikan. Karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan adalah “Pengembangan Instrumen Penilaian Kompetensi Siswa SMK Seni dan Budaya dalam Mendalang Gaya Surakarta” (2011).
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 35
PENDAHULUAN
Pertunjukan wayang kulit purwa merupakan lambang dari kehidupan manusia yang berisi kebiasaan hidup, tingkah laku, dan pengorbanan, baik secara individu maupun kelompok (Sastroamidjojo, 1964). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya—seperti nilai filosofis, agamis, pedagogis, etis dan estetis—bersifat universal, mudah dicerna, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Murtiyoso, 1996). Dalam cerita Mahabharata, keluarga Pandawa merupakan simbol dari etos kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; sedangkan keluarga Kurawa sebagai simbol keangkara murkaan, kenistaan, kedengkian, ketamakan, dan ketidakteraturan (Achmadi, 2004).
Berdasarkan catatan sejarah, wayang pernah berhasil digunakan untuk mendakwahkan agama Islam di Jawa karena keberadaannya membantu mengajarkan ketauhidan, akhlak mulia, dan pesan-pesan sesuai tata aturan hukum Islam yang disampaikan melalui cerita dan tokoh-tokohnya (Zarkasi, 1977). Wayang sebagai alat adalah benda mati. Berhasil dan tidaknya wayang untuk mengajarkan sesuatu tergantung dari cara menyampaikannya. Sebagai sarana penyampaian suatu ajaran, wayang mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, wayang dapat diterima oleh semua kalangan. Kedua, cerita wayang banyak mengandung nilai-nilai ajaran moral yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan. Ketiga, cerita wayang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman (Widadi, 2016).
Kajian tentang karakter wayang telah banyak ditulis oleh para ahli di bidangnya. Akan tetapi, belum terdapat kajian yang berfokus pada pembahasan mengenai karakter wayang tokoh Pandawa yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk menggali dan mendeskripsikan perwujudan karakter Pandawa yang sesuai dengan 5 (lima) nilai utama karakter bangsa.
Nilai-nilai karakter dalam pertunjukan wayang terdapat pada keseluruhan isi cerita maupun perilaku tokoh-tokohnya, baik secara tersirat maupun tersurat. Karakter wayang dalam kajian ini menggunakan rumusan karakter tokoh Pandawa yang ditulis oleh Wirastodipura dalam bukunya Ringgit Wacucal, Wayang Kulit, Shadow Puppet (2006), sedangkan 5 (lima) nilai
utama karakter bangsa akan menggunakan rumusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
Kelima nilai utama karakter bangsa tersebut adalah (1) religius: mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta; (2) nasionalisme: menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya nilai nasionalisme ini meliputi rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, semangat rela berkorban, dan semangat kebinekaan; (3) kemandirian: tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita nilai kemandirian ini meliputi kerja keras, pembelajar sepanjang hayat, dan tahan banting; (4) gotong royong: mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama nilai gotong royong ini meliputi kerja sama, solidaritas, kekeluargaan, bersahabat, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama; serta (5) integritas: upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan nilai integritas ini meliputi kejujuran keteladanan, tanggung jawab, komitmen moral, dan cinta pada kebenaran (Kemendikbud, 2017).
Kajian wayang kulit tentang Pendidikan Karakter Bangsa masih terbatas. Dalam artikel hasil penelitiannya, Tri Ratna Herawati (2014) membahas tentang karakter tokoh dalam lakon Puspita Manik yang terintegrasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tulisan ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai karakter tokoh-tokoh Pandawa sebagai perwujudan karakter bangsa. Widadi dalam bukunya Membaca Wayang dengan Kacamata Islam (2016) membahas tentang arti nama wayang dan perangkat pertunjukannya yang dihubungkan dengan ajaran agama Islam. Tulisan ini tidak membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam tokoh wayang secara rinci. Karya tulis hasil penelitian dari Aulia Fajri Purnamasari (2013) yang berjudul Upaya Penanaman Nilai-nilai Karakter melalui Tokoh-tokoh Wayang: Dampaknya terhadap Perilaku Keagamaan Siswa di SMPN 18 Purwareja
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 36
membahas tentang penanaman karakter melalui wayang, faktor penghambat, dan dampaknya terhadap perilaku keagamaan. Uraiannya difokuskan pada kemungkinan dampak yang disebabkan oleh karakter tokoh wayang terhadap akhlak siswa. Tulisan tersebut tidak menjelaskan tentang nilai religius salah satu tokoh wayang. Dalam beberapa kajian tersebut belum terdapat pembahasan mengenai Pandawa sebagai perwujudan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa.
PEMBAHASAN
Menurut Mahabharata versi India, Pandawa adalah lima bersaudara yang semuanya putra dari raja Kerajaan Astina Pura, Prabu Pandu Dewanata. Puntadewa, Werkudara, dan Arjuna adalah putra Prabu Pandu Dewanata dengan Dewi Kunthi Talibrata, sedangkan Nakula dan Sadewa yang lahir kembar adalah putra Prabu Pandu Dewanata dengan Dewi Madrim (Poedjosoebroto, 1978). Cerita Mahabharata masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Hindu, sehingga cerita tentang tokoh-tokoh Pandawa banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu, semisal berupa pemujaan terhadap para dewa, pemujaan terhadap arwah leluhur, pembagian tingkatan manusia dalam berbagai kasta, serta ajaran lainnya.
Bersamaan dengan berkembangnya ajaran agama Islam, wayang pun kemudian digubah dengan memasukkan ajaran Islam dalam rangka untuk berdakwah. Gubahan-gubahan yang dikerjakan tersebut selalu disesuaikan dengan budaya dan kehidupan bangsa Indonesia sampai sekarang. Penyesuaian dengan perkembangan zaman tersebut ditampilkan dalam cerita dan tokoh-tokohnya. Karakter tokoh-tokohnya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tujuannya. Fokus kajian ini adalah membahas karakter tokoh Pandawa yang disesuaikan dengan program pemerintah, yaitu penguatan 5 (lima) nilai utama pendidikan karakter.
Puntadewa sebagai Perwujudan Karakter Religius
Karakter Puntadewa dalam tulisan Wirastodipura (2006) adalah gemar memberi, sabar dan menerima keadaan, mencintai sesama makhluk hidup, adil, serta taat beragama. Puntadewa merupakan Pandawa yang pertama, anak sulung dari Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Kunthi Talibrata. Para dalang, seperti Ki
Nartosabdo, Ki Anom Suroto, Ki Manteb Sudarsana, Ki Timbul Hadi Prayitno, dan Ki Hadi Sugito, menceritakan bahwa Prabu Puntadewa mempunyai karakter yang mencerminkan kehidupan religius. Sifat-sifat yang dimilikinya adalah sabar, menerima segala keadaan, disiplin, peduli sesama, cinta damai, selalu bersikap adil, ramah, selalu memberi tanpa mengharap kembali, suka menolong, dan tidak mau berbohong.
1. Beriman dan Bertakwa Prabu Puntadewa terkenal mempunyai
darah putih karena kebaikan, keikhlasan, dan keyakinannya terhadap kekuasaan Tuhan. Ia sangat percaya (beriman) adanya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Semua yang terjadi di alam dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Manusia hidup di dunia hanyalah sakdrema hanglakoni atau sekadar menjalankan kehidupannya. Apapun yang diminta oleh orang lain pasti diberikannya. Jangankan istrinya, seandainya nyawanya yang diminta pun akan ia berikan. Hal ini karena Prabu Puntadewa percaya kekuasaan Tuhan (Harghana, 2003).
Prabu Puntadewa mempunyai pusaka yang sangat terkenal kehebatan dan keistimewaannya, yaitu jamus kalimasada. Pusaka tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan apapun sesuai dengan kehendak pemiliknya, sejauh dapat membawa ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan dalam negara Amarta. Oleh karena itu, banyak negara-negara lain yang berusaha merampas, mencuri, dan ingin melenyapkan jimat kalimasada karena iri dan dengki. Apabila pusaka kalimasada hilang maka akan terjadi kekacauan di Amarta. Diceritakan bahwa suatu waktu Dewa Srani ingin menguasai dunia. Ibunya memberi saran agar ia mencuri pusaka jamus kalimasada milik Prabu Puntadewa. Rencana tersebut dilaksanakan oleh Dewa Srani dan berhasil, sehingga ia menjadi orang hebat yang dapat menguasai dunia. Pada akhirnya, pusaka jamus kalimasada dapat direbut kembali oleh Puntadewa (Zarkasi, 1977).
Pusaka jamus kalimasada berwujud sebuah surat berhuruf Arab, sehingga disebut juga layang kalimasada. Prabu Puntadewa tidak akan mati sebelum mampu membaca tulisan yang terdapat dalam layang tersebut. Walaupun semua adiknya telah mati dalam lakon Pandawa Muksa, Prabu Puntadewa masih hidup lama sekali sampai beberapa zaman. Setelah bertahun-tahun,
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 37
pada akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang dapat mengajarinya cara membaca tulisan Arab tersebut. Ia belajar membacanya. Adapun bunyi tulisan dalam jamus kalimasada itu adalah asyhadu anla illaha ilallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rosululah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah (Haq, 2010).
Setelah Prabu Puntadewa dapat membaca dan mengucapkan tulisan Arab dalam jamus kalimasada, pada akhirnya ia menemui ajalnya. Kematiannya dalam keadaan husnulkhatimah. Lafal tulisan tersebut dalam ajaran agama Islam disebut syahadat, yaitu mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah rasul dan utusan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia tentang cara menyembah Tuhan yang benar. Orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat (kalimasada) berarti menjadi Islam. Keislamannya menjadi hilang jika syahadatnya (kalimasadanya) hilang (Zarkasi, 1977).
Suatu saat keluarga Pandawa yang dipimpin oleh Prabu Puntadewa membangun Candi Sapta Arga, yaitu suatu makam atau kuburan nenek moyang untuk dipuja. Oleh karena perhatian Puntadewa tertuju pada pemujaan dan pembangunan, kalimasada miliknya hilang dicuri oleh Mustakaweni. Hal ini merupakan lambang atau gambaran bahwa apabila orang Islam memuja-muja dan menyembah atau memohon sesuatu kepada nenek moyangnya maka kalimasada-nya (syahadatnya) hilang karena telah menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Hilangnya kalimasada menimbulkan banyak bencana dan kekacauan yang menyengsarakan rakyat Amarta. Sebaliknya, orang yang kuat memegang syahadatnya (kalimasada-nya), sekalipun ia adalah seorang rakyat jelata, akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya.
Kekacauan di Amarta akibat hilangnya kalimasada membuat Prabu Puntadewa mengutus Bambang Priyambada untuk menangkap pencurinya dan merebut kembali kalimasada. Pada saat peperangan Mustakaweni melawan Bambang Priyambada, kalimasada selalu berpindah tangan. Kadang berada di tangan Priyambada, ada kalanya berada di tangan Mustakaweni. Keduanya sama-sama sakti dan banyak tipu muslihat. Pada saat kalimasada berhasil direbut Priyambada, ia berikan jimat tersebut kepada Petruk dan berpesan kepadanya
untuk berhati-hati dalam menjaga kalimasada supaya tidak dicuri lagi oleh Mustakaweni. Setelah menerima kalimasada, Petruk meninggalkan peperangan dan menjadi sakti mandraguna. Dengan senjata jamus kalimasada, Petruk berhasil menjadi raja di negara Sonya Wibawa. Hal ini menggambarkan bahwa dengan memegang kalimasada, seorang yang hina seperti Petruk pun akan diangkat derajatnya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan (Asmoro, Agustus 2020).
2. Menjalankan Segala Perintah-Nya Nama lain dari Puntadewa adalah
Yudhistira, yang berasal dari kata yu-dhi-istira. Yu singkatan dari kata rahayu, dhi dari adhi, dan istira dari esti nira. Rahayu artinya selamat, adhi berarti baik, dan esti nira artinya tujuan hidupnya. Yudhistira bermakna keselamatan dan kebaikan menjadi tujuan dalam kehidupannya. Keselamatan dan kebaikan yang menjadi tujuan hidupnya tersebut hanya dapat dicapai dengan berperilaku sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Pencipta Alam, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Nama yang melekat dalam dirinya tidak hanya merupakan sebuah panggilan tetapi juga selalu diaplikasikan dalam kehidupannya, sehingga orang-orang yang ada di dekatnya selalu merasa aman, nyaman, dan bahagia (Widadi, 2016). Pusaka jamus kalimasada milik Prabu Puntadewa selalu dibawa dan ditempatkan di sumpingnya. Hal ini bermakna bahwa dalam hidupnya Puntadewa selalu memegang teguh keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang terjadi selalu diserahkan dan dipasrahkan kepada Tuhan. Itulah beberapa karakter yang melekat dalam diri Prabu Puntadewa. Selalu menyembah pada Tuhan yang menciptakan dirinya dan alam semesta dengan selalu menjalankan ajaran-ajaran suci yang telah dinasihatkan oleh ibunya, yaitu Dewi Kunthi Talibrata dan kakeknya, Begawan Abiasa.
3. Peduli Sosial Nama lain yang melekat dalam diri Prabu
Puntadewa adalah Samiaji. Sami berarti sama atau tidak berbeda, dan aji artinya nilai atau kedudukan. Samiaji bermakna kedudukan yang sama (Poedjosoebroto, 1978). Menurut ajaran Islam, kedudukan manusia di hadapan Tuhan adalah sama dan tidak berkasta, sedangkan yang membedakan adalah ketakwaan atau ketaatannya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Tuhan yang sebagaimana
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 38
tertulis dalam Alquran surah Alhujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut.
Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu (Alhujurat: 13).
Menurut Widadi (2016), banyaknya orang
Jawa yang berbondong-bondong masuk Islam salah satunya disebabkan karena semua manusia sama kedudukannya, tidak berkasta, bahkan sesama orang Islam bagaikan satu keluarga atau satu saudara. Hal ini dijelaskan dalam Alquran surah Alhujurat ayat 10 yang artinya sebagai berikut.
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (Alhujurat:10).
Prabu Puntadewa suka menolong
rakyatnya yang sedang membutuhkan pertolongan tanpa diminta, sehingga ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Kepedulian sosialnya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari uraian yang disampaikan dalang dalam janturan (narasi dalang) pada saat jejer pertama, yaitu paring sandhang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, tulung teken wong kalunyon, asung kudhung wong kepanasan aweh banyu wong kasatan, hamaluyakaken wong kang nandang sakit kinaryo suka wong kang nedheng nandhang prihatin (Suroto, Maret 2021). Terjemahannya adalah memberi busana orang yang telanjang karena tidak mempunyai pakaian, memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, memberi tongkat kepada orang yang sedang berjalan di jalan yang licin, memberi payung kepada orang yang sedang kepanasan, memberi air kepada masyarakat yang sedang kekeringan, memberi kesembuhan kepada yang sakit, dan memberi kebahagiaan kepada orang yang sedang menderita kesusahan. Itulah sifat dan karakter Pandawa yang pertama, Prabu Puntadewa, yang merepresentasikan nilai-nilai karakter religius.
4. Selaras dengan Alam Semesta Dalam lakon Babad Wanamarta
diceritakan bahwa Pandawa diberi hutan bernama Wanamarta untuk dibuka menjadi sebuah negara. Pandawa menerima pemberian dari Raja Astina, Destarastra. Pandawa membabati Hutan Wanamarta bersama-sama. Dengan menggunakan tenaga dan kekuatannya, Werkudara atau Bratasena mulai menebangi pohon-pohon yang ada di hutan tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak hewan yang lari ketakutan meninggalkan Wanamarta. Melihat banyak hewan yang lari menyelamatkan diri karena terganggu ketenteramannya, Puntadewa menasihati agar dalam membuka hutan sebaiknya memperhatikan dan melindungi hewan-hewan di dalamnya agar tetap hidup dan tidak teraniaya (Wirastodipura, 2006).
Dalam lakon Pandawa Dadu, Ki Nartosabdo menceritakan bahwa Pandawa diusir dari negaranya setelah kalah dari Kurawa dalam permainan dadu. Mereka harus tinggal dan hidup di hutan selama menjalani hukuman. Suatu saat, Kunthi merasa kehausan dan meminta untuk dicarikan air bersih. Sadewa, Nakula, Arjuna, dan Werkudara pergi mencarikan air. Mereka tidak pernah kembali karena mati di pinggir telaga setelah meminum airnya. Puntadewa mencari keberadaan adik-adiknya tersebut. Baru belakangan Puntadewa mengetahui bahwa kematian adik-adiknya disebabkan oleh air beracun di telaga. Puntadewa bertemu dengan penunggu telaga dan memohon kepadanya untuk dapat menghidupkan kembali adik-adiknya serta menawarkan racun pada air telaga. Setelah semua persyaratan dari penunggu telaga dipenuhi oleh Puntadewa, keempat adiknya dapat hidup kembali dan air telaga pun menjadi tidak beracun (Nartosabdo, Juni 2020). Hal ini membuktikan bahwa karakter individu yang menjaga keselarasan dengan alam semesta terwujud pada tokoh Puntadewa. Werkudara sebagai Perwujudan Karakter Nasionalisme
Mengacu kepada kebijakan Kemendikud (2017), nasionalisme adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Subnilai nasionalisme antara lain adalah mengapresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, serta menghormati keragaman budaya, suku, dan
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 39
agama. Nilai-nilai ini tergambarkan pada karakter Pandawa yang kedua, Werkudara.
Dalam tulisannya, Wirastodipura (2006) menggambarkan Werkudara sebagai tokoh Pandawa yang berkarakter kuat pemberani, cinta tanah air, dan tidak takut menghadapi bahaya. Raden Werkudara adalah putra dari Prabu Pandu Dewanata dengan Dewi Kunthi Talibrata dan merupakan adik dari Prabu Puntadewa. Werkudara berasal dari kata wreka dan udara. Wreka berarti hidup, dan udara artinya angin. Werkudara bermakna hidup dari inti sarinya angin atau udara. Nama lain dari Werkudara adalah Bratasena. Brata artinya setia, dan sena berarti kuat. Bratasena bermakna orang yang kuat kesetiaannya terhadap bangsa dan negaranya serta cinta tanah air dengan semangat kebangsaannya (Suroto, September 2016). Selain Bratasena, nama lain Werkudara adalah Wijasena. Wija berarti buah, dan sena adalah kesetiaan. Wijasena bermakna buah dari kesetiaan, yaitu rasa nasionalisme yang ada dalam dirinya.
Senjata Werkudara adalah kuku pancanaka. Kuku ini terletak di kedua ibu jari tangannya. Ketajamannya melebihi tombak dan panah. Senjata Werkudara yang lain adalah gada rujak pala atau gada lukitasari atau disebut juga gada lambita muka, yang merupakan gada terbesar dan tersakti dalam dunia pewayangan. Gada rujak pala berasal dari kata rujak dan pala. Rujak adalah buah yang dilembutkan dengan cara diulek, dan pala artinya otak. Gada rujak pala bermakna sebelum melakukan sesuatu, baik dalam perkataan maupun perbuatan, seharusnya diolah dalam otak atau dipikirkan terlebih dahulu agar yang akan dilakukan dapat bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, terdapat gada lukitasari yang berasal dari kata lukita dan sari. Lukita artinya surat, dan sari berarti enak rasanya. Lukitasari bermakna semua perbuatannya selalu nyaman dirasakan oleh orang lain sebab sebelum melakukan perbuatan dipikirkan terlebih dahulu (rujak pala) agar membuahkan hasil yang bermanfaat bagi orang lain (wijasena), yaitu sebuah kesetiaan (bratasena) terhadap bangsa dan negara (Widadi, 2016).
1. Rasa Cinta Tanah Air Werkudara mempunyai rasa cinta kepada
tanah air yang sangat besar. Ki Manteb Sudarsono dalam lakon Sesaji Rajasuya menceritakan bahwa sewaktu Amarta diserang oleh Prabu Jarasandha yang sakti madraguna,
Werkudara dengan gagah berani menghadapi raja angkara yang sangat kejam tersebut. Kekejaman Prabu Jarasandha ditunjukkan dengan pembunuhan atas orang tuanya sendiri, yaitu Prabu Bhrihadatta. Tidak sekadar dibunuh, orang tuanya tersebut juga dikuliti. Kulitnya dijadikan tambur dan dipasang di perbatasan negara Giribajra. Tambur Bhrihadatta akan berbunyi jika ada orang dari negara lain yang melewati perbatasan. Oleh karena itu, bunyi tambur tersebut dijadikan pertanda bahwa ada orang mancanegara yang memasuki Giribajra. Pada saat Kresna, Werkudara, dan Arjuna ke Giribajra untuk menumpas kejahatan yang dilakukan oleh Jarasanda, Arjuna diperintahkan untuk memanah tambur tersebut. Tujuannya adalah supaya tambur tersebut tidak berbunyi, sehingga kedatangan mereka tidak diketahui.
Kekejaman Prabu Jarasandha lainnya adalah ia berencana membunuh para raja dari 100 (serratus) negara, termasuk Amarta, sebagai tumbal dalam sesaji rudra untuk pemujaan kepada Sanghyang Rudra sebagai dewa sesembahannya. Para raja dari negara-negara sahabat Amarta seperti Astina, Wiratha, Mandura, Mandraka, Plasajenar, Widarbo, Kumbina, dan lainnya ditangkap oleh Prabu Jarasandha. Rasa cinta tanah air yang melekat di hati Werkudara telah mendorongnya untuk melakukan pembelaan terhadap negaranya yang akan diserang oleh Prabu Jarasandha. Atas bantuan Kresna dan Arjuna, Werkudara dapat membunuh Prabu Jarasandha dan membebaskan semua raja yang telah ditangkap oleh Prabu Jarasandha (Soedarsono, Juni 2020). Rasa cinta tanah air Werkudara sangat besar. Ancaman apapun yang akan mengganggu ketenteraman dan keamanan Amarta akan senantiasa ia hadapi, sekalipun dengan mengorbankan nyawa.
2. Semangat Kebangsaan Semangat kebangsaan dan jiwa ksatria
Werkudara terlihat jelas dalam lakon Jagal Abilawa. Setelah menjalani pembuangan di hutan selama 12 (dua belas) tahun karena kalah bermain dadu, Pandawa harus bersembunyi di suatu negara selama satu tahun lamanya agar keberadaannya tidak diketahui oleh para Kurawa. Apabila dalam jangka waktu setahun keberadaan Pandawa terbongkar maka harus mengulangi hukuman pembuangannya selama 12 (dua belas) tahun lagi. Pandawa menentukan tempat persembunyian mereka di negara Wirata dengan menyamar sebagai abdi atau pembantu. Puntadewa menyamar sebagai Kangka, seorang
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 40
lurah pasar Wirata. Werkudara menyamar sebagai Abilawa, seorang tukang penjual daging atau jagal. Arjuna menyamar sebagai Kedhi Wrahatnala, seorang banci dengan pekerjaan pelatih tari. Si kembar Nakula dan Sadewa menyamar sebagai Tantripala dan Darmagranti, sepasang tukang rumput.
Pada saat negara Wirata diserang Prabu Susarma dari negara Trigarta yang dibantu oleh Prabu Duryudana dari negara Astina, Werkudara dengan penyamarannya sebagai Abilawa datang membantu. Terdorong semangat kebangsaannya yang tinggi, walaupun tidak diperintahkan oleh pejabat Wiratha, Abilawa berusaha menyelamatkan Raja Wiratha yang sedang disiksa dengan cara ditarik kereta mengelilingi negara. Setelah berperang sekuat tenaga, Abilawa berhasil menyelamatkan Prabu Matswapati dan mengalahkan Prabu Susarma dan Duryudana. Kedua raja yang menyerang tersebut pada akhirnya dapat kembali ke negaranya masing-masing dan penyamaran Pandawa tidak terbongkar oleh Prabu Duryudana (Nugroho, November 2019). Itulah semangat kebangsaan yang dimiliki Werkudara, yang tanpa diminta atau diperintah pun ia membela negara tempat persembunyian sekaligus penyamarannya yang sedang diserang negara lain, sekalipun itu bukan negara asalnya sendiri.
3. Menghargai Kebhinekaan Raden Werkudara sangat menghargai
kebhinekaan karena ia menyadari bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dengan beraneka macam ragam bentuk dan warna. Semua yang diciptakan Tuhan pasti tidak sama atau berbeda antara satu dan lainnya. Satu tubuh saja bermacam-macam nama dan bentuknya. Perbedaan-perbedaan tersebut akan saling mengisi dan melengkapi. Makhluk dalam dunia wayang juga berbeda-beda, yaitu ada dewa, manusia, raksasa, jin, setan, dan sebagainya. Raden Werkudara sangat menghargai keanekaragaman ciptaan Tuhan dengan tidak membedakan antara raksasa, dewa, dan manusia. Semua adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dan dihargai keberadaannya.
Menurut Poedjosoebroto (1978), Raden Werkudara mempunyai tiga istri yang berbeda-beda. Istri pertama adalah Dewi Nagagini, anak seekor dewa ular yang bernama Batara Antaboga. Dari perkawinannya dengan Dewi Nagagini lahirlah anak pertama yang diberi nama Raden Antareja. Kesaktian dari Antareja
ini adalah dapat masuk ke dalam bumi dan berjalan di dalam seperti layaknya di atas bumi. Istri Werkudara yang kedua adalah Dewi Arimbi, yaitu seorang raseksi adik dari raksasa yang bernama Arimba. Perkawinannya dengan Arimbi melahirkan Raden Gatutkaca. Semasa bayi, Raden Gatutkaca berwujud raksasa. Setelah berhasil mengalahkan Patih Sekipu dan Prabu Naga Pracona dari negara Giling Wesi, Raden Gatutkaca diubah menjadi ksatria tampan oleh Batara Guru. Kesaktian Raden Gatutkaca adalah dapat terbang tinggi di awan tanpa menggunakan sayap. Istri ketiga dari Raden Werkudara adalah Dewi Urang Ayu, putri Batara Baruna yang merupakan dewa penguasa samudera di dunia. Perkawinannya dengan Dewi Urang Ayu melahirkan anak yang diberi nama Raden Antasena yang mempunyai kesaktian dapat berjalan di dalam lautan seperti halnya di daratan. Ketiga ksatria yang merupakan putra-putra dari Werkudara tersebut selalu menjaga keamanan dan ketenteraman bangsa dan negara, baik di darat, laut, maupun udara.
Antareja menjaga keamanan di darat, Gatutkaca menjaga keamanan di udara, dan Antasena menjaga keamanan di lautan. Walaupun terlahir dari ibu yang berbeda, mereka selalu menjaga kasih sayang, kerukunan, dan kedamaian untuk mempertahankan keutuhan amarta (Poedjosoebroto, 1978). Meskipun berbeda-beda, Raden Werkudara sangat menyayangi ketiga putranya. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai karakter menghargai kebhinekaan dan keberagaman.
4. Semangat Rela Berkorban Werkudara mempunyai sifat rela
berkorban demi kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman umat manusia. Ia rela berkorban tidak hanya untuk rakyatnya, tetapi juga untuk sesama manusia pada umumnya. Dalam lakon Sang Bima yang disajikan oleh MPP Bayu Aji (Oktober 2020), putra dari Ki Anom Suroto, diceritakan bahwa rakyat negara Ekacakra sangat menderita karena raja Ekacakra, Prabu Baka, gemar memakan daging manusia. Rakyat Ekacakra setiap harinya diwajibkan untuk menyerahkan makanan untuk sang raja berupa nasi segerobak dengan lauk manusia yang satu per satu secara bergiliran dimakan olehnya. Banyak rakyat Ekacakra yang melarikan diri ke negara lain. Apabila dalam pelariannya tertangkap, mereka akan diserahkan untuk menjadi makanan sang raja.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 41
Para punggawa Ekacakra tertular sifat rajanya yang gemar memakan manusia, sehingga rakyat Ekacakra setiap hari tidak hanya satu tetapi juga bisa menyediakan sampai lima orang. Suatu saat tibalah giliran Demang Ijrapa dari Desa Manahilan yang berkewajiban menyediakan makanan untuk Prabu Baka. Pada saat itu, Dewi Kunthi Talibrata dan putra-putranya, yaitu Pandawa, sedang menginap di rumah Demang Ijrapa. Mengetahui tuan rumahnya dalam keadaan susah, Dewi Kunthi menanyakan sebabnya. Demang Ijrapa pun menceritakan keadaan Ekacakra yang sesungguhnya.
Sudah menjadi kewajiban bagi para Pandawa untuk menyelamatkan rakyat Ekacakra dari kekejaman rajanya. Werkudara yang masih bernama Bratasena rela mengorbankan dirinya dengan bersedia untuk dimakan oleh Prabu Baka. Demang Ijrapa dipersilakan untuk menyajikan Bratasena kepada Prabu Baka sebagai ganti dari anggota keluarganya untuk dijadikan santapan sang raja. Demang Ijrapa sebetulnya menolak pengorbanan Werkudara ini. Akan tetapi, setelah ia mengetahui bahwa mereka itu adalah Pandawa dan Bratasena pernah berhasil membunuh Prabu Arimba maka pada akhirnya Demang Ijrapa bersedia menyerahkan Bratasena kepada sang raja sebagai santapan. Prabu Baka sangat senang karena Demang Ijrapa memenuhi kewajibannya menyerahkan satu manusia untuk dimakan. Setelah Bratasena diserahkan, terjadilah perang tanding antara Bratasena dan Prabu Baka. Perang ini dimenangkan oleh Bratasena dengan terbunuhnya Prabu Baka (Aji, Oktober 2020). Semangat rela berkorban demi kepentingan rakyat selalu ada dalam diri Werkudara atau Bratasena. Nilai nasionalisme terwujud dalam tokoh ini.
Arjuna sebagai Perwujudan Karakter Kemandirian
Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain serta mempergunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai kemandirian, antara lain, etos kerja (kerja keras), tangguh, tahan banting, berdaya juang, profesional, kreatif, berani, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nilai-nilai ini tergambarkan pada karakter Pandawa yang ketiga, Arjuna.
Raden Arjuna terkenal karena ketampanan wajahnya, lemah lembut tutur katanya, dan
banyak mempunyai senjata sakti pemberian para dewa. Kesaktian yang dimilikinya bisa menandingi para dewa dari kahyangan, sehingga ia sangat percaya pada kemampuannya, bakat dalam dirinya, dan tidak bergantung kepada orang lain. Menurut Wirastodipura (2006), karakter tokoh Arjuna adalah berbelas kasihan, suka menolong, cerdik pandai, lemah lembut, dan suka melindungi yang lemah. Menurut Anom Suroto dalam pergelarannya berjudul Wahyu Tohjali, sifat-sifat Raden Arjuna, antara lain, (1) made wiku haldaka, (2) payo katiuping rana, dan (3) wanita jinatu krama. Made wiku haldaka berarti apabila mendengar ada seorang guru sakti yang berada di gunung maka ia pasti berkeinginan menjadi siswanya untuk menambah ilmu di segala bidang kehidupan. Payo katiuping rana berarti apabila mendengar ada kekejaman, ketidakadilan, perampokan, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan oleh seseorang maka ia pasti segera menumpas dan membinasakannya. Sifat yang ketiga, wanita jinatu krama, berarti apabila mendengar ada wanita cantik maka ia pasti melamar dan mempersuntingnya (Suroto, Februari 2021).
1. Kerja Keras Arjuna selalu berusaha untuk berhasil
mewujudkannya keinginannya. Keberhasilannya didapat melalui kerja keras tanpa mengenal lelah. Semua senjata yang dimilikinya adalah anugerah dewa atas jasa-jasa dan hasil kerja kerasnya. Arjuna pernah bertapa di sebuah gua bernama Mintaraga yang terletak di Gunung Indrakila. Ia bersumpah tidak akan mengakhiri bertapa sebelum keinginannya tercapai, yaitu mendapatkan sebuah pusaka sakti mandraguna untuk mencapai kemenangan pada saat Perang Bharatayuda.
Tapa Arjuna tersebut menyebabkan terjadinya bencana di kahyangan Suralaya. Batara Guru penguasa kahyangan memerintahkan para bidadari untuk menggoda Arjuna supaya membatalkan tapanya. Para bidadari gagal dalam tugasnya. Sebaliknya, para bidadari tersebut justru yang tergoda oleh Arjuna. Pada akhirnya, Batara Guru memberikan sebuah senjata berupa panah yang bernama pasopati. Pusaka tersebut kesaktiannya luar biasa dan menjadi syarat untuk kemenangan para Pandawa di Tegal Kurusetra dalam Perang Bharatayuda.
Selain itu, atas kerja kerasnya Arjuna dapat mengalahkan raja angkara murka, yaitu seorang raja raksasa dari Kerajaan Manimantaka
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 42
yang bernama Prabu Niwata Kawaca. Raja raksasa tersebut berkeinginan mempersunting bidadari kahyangan yang bernama Dewi Supraba. Oleh karena dewa tidak mengizinkan, kahyangan dirusak Prabu Niwata Kawaca. Para dewa menderita kekalahan dan lari menyelamatkan diri. Para dewa meminta bantuan Arjuna untuk menumpas Prabu Niwata Kawaca. Terjadilah perang tanding yang sangat dahsyat antara Prabu Niwata Kawaca dan Arjuna. Perang ini dimenangkan oleh Arjuna. Niwata Kawaca terbunuh di tangan Arjuna dengan menggunakan panah pasopati. Atas kemenangannya tersebut, Arjuna diberi hadiah menjadi raja di kahyangan Tinjomaya dengan gelar Prabu Kiritin (Soetarno, 2005).
Proses perjalanan Arjuna dalam mendapatkan senjata dan kemenangan ini merupakan perwujudan dari sifat kerja keras yang melekat dalam dirinya. Banyak sekali pusaka Arjuna yang merupakan pemberian para dewa atas hasil kerja kerasnya, antara lain, gendewa (dari Bathara Indra), panah ardadadali (dari Bathara Kuwera), dan panah cundamanik (dari Bathara Narada). Arjuna juga memiliki pusaka-pusaka sakti lainnya, antara lain, keris kyai kalanadah, panah sangkali (dari Resi Durna), panah candranila, panah sirsha, keris kyai sarotama, keris kyai baruna, keris pulanggeni (diberikan pada Abimanyu), trompet dewanata, cupu berisi minyak jayengkaton (pemberian Bagawan Wilawuk dari Pertapaan Pringcendani) dan kuda ciptawilaha dengan cambuk kyai pamuk (Wirastodipuro, 2006).
2. Pembelajar Sepanjang Hayat Made wiku haldaka merupakan salah satu
dari sifat Arjuna. Artinya adalah senang belajar dan menuntut ilmu kepada guru yang arif, bijaksana, dan sakti mandraguna. Apabila Arjuna mendengar bahwa di suatu tempat ada seorang guru yang sakti dan cerdik pandai, ia pasti segera mencari dan menimba ilmu darinya. Sejak kecil Arjuna telah berguru kepada Begawan Durna di Pertapaan Sokalima untuk mempelajari keterampilan memanah (Asmoro, November 2020). Arjuna juga pernah berguru kepada Begawan Padmanaba di Padepokan Untarayana. Di sana ia belajar bersama kakak sepupu dari garis ibu yang bernama Narayana (Nartosabdo, Juni 2020).
Selain itu, Arjuna berguru kepada Begawan Wilawuk di Pedepokan Pringcendani. Sang guru memberikan pusaka lisah jayengkaton. Dengan mengusapkan minyak
jayengkaton ke alis mata, Arjuna dapat melihat semua makhluk yang tidak bisa dipandang dengan mata telanjang. Arjuna juga pernah berguru kepada Begawan Bima Suci di Pertapaan Arga Kelasa. Dari begawan tersebut Arjuna mendapatkan wejangan atau uraian tentang ilmu kasampurnan, yaitu manunggaling kawula Gusti (Teguh, 2007). Di Pertapaan Andong Sumiwi, Arjuna juga menjadi siswa Begawan Siddikara. Karena kepandaiannya, Arjuna diberi hadiah berupa putri kesayangan sang begawan yang bernama Endang Pariyawati untuk dijadikan istri (Asmoro, Agustus 2020). Dari perkawinan tersebut lahirlah anak yang diberi nama Bambang Priyambada. Itulah sifat dan karakter Arjuna yang senang menuntut ilmu dan sesuai dengan karakter pembelajar sepanjang hayat.
3. Tahan Banting Arjuna bersama keluarga Pandawa selalu
mengalami kepahitan hidup. Banyak penderitaan yang dialaminya sejak kecil hingga dewasa. Keadaan tersebut menjadikan Arjuna dan Pandawa menjadi manusia yang kuat, hebat, bermartabat, dan tahan banting dari penderitaan apapun. Saat remaja, Arjuna dan Pandawa lainnya ditipu dan dibakar hidup-hidup di Bale Sigala-gala, yaitu sebuah istana yang terbuat dari kardus dan mudah terbakar yang berlokasi di Hutan Waranawata. Pelaku pembakaran adalah para Kurawa yang selalu iri atas keberhasilan Arjuna dan Pandawa dalam segala hal. Di tengah malam yang sunyi, saat Pandawa tidur nyenyak di Bale Sigala-gala, Pandawa dibakar oleh Purucana atas perintah para Kurawa. Pandawa selamat dari maut karena pertolongan seekor garangan putih yang menuntunnya lewat terowongan yang telah dipersiapkan oleh Widura, yaitu paman Pandawa yang mengetahui rencana keji Kurawa (Nartosabdo, Juli 2020).
Saat dewasa, Arjuna dan Pandawa harus mengalami perjalanan hidup menjadi orang buangan dengan tinggal di hutan selama 12 (dua belas) tahun karena ditipu Sangkuni dalam permainan dadu. Setelah 12 (dua belas) tahun berlalu, Arjuna dan Pandawa harus bersembunyi di Kerajaan Wirata dengan menyamar sebagai rakyat jelata (Wirastodipuro, 2006). Penderitaan demi penderitaan yang dialami membuat Arjuna menjadi ksatria yang tahan banting, yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai karakter kemandirian.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 43
Nakula sebagai Perwujudan Karakter Gotong Royong
Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Subnilai gotong royong, antara lain, menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, antidiskriminasi, antikekerasan, dan sikap kerelawanan (Kemendikbud, 2017). Nilai-nilai ini tergambarkan pada karakter Pandawa yang keempat, Nakula.
Raden Nakula terlahir kembar bersama adiknya yang bernama Raden Sadewa. Sejak bayi ia diasuh oleh ibu tirinya, Dewi Kunthi Talibrata, yang merupakan ibu dari Puntadewa, Werkudara, dan Arjuna. Ibu kandung Nakula bernama Dewi Madrim meninggal bersama dengan Prabu Pandu Dewanata. Nakula selalu mengikuti kakak-kakaknya dengan setia. Sifat kegotongroyongan melekat dalam dirinya.
Nama kecil Nakula adalah Pinten, yang berasal dari kata pin dan ten. Pin singkatan dari pinter (Jawa), dan ten singkatan dari telaten (Jawa). Pinter artinya pandai, dan telaten artinya tekun. Pinten adalah orang yang pandai dan memiliki ketekunan, sehingga apa yang diinginkan dapat dicapai dengan mudah. Seseorang yang pandai tetapi tidak memiliki ketekunan akan menemukan banyak kegagalan dalam hidupnya, sehingga terasa tidak ada manfaat dan kegunaannya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (Poedjosoebroto, 1978).
Solidaritas Nakula dapat dilihat pada saat menjalani penyamaran di Wirata. Setelah menjalani masa pembuangan selama 12 tahun di hutan, Nakula menyamar sebagai tukang rumput yang bernama Tantripala. Nakula bersama-sama dengan saudaranya yang lain bekerja sama ikut berjuang menyelamatkan negara Wirata yang sedang di ambang kehancuran atas serangan Prabu Duryudana dari Astina dan Prabu Susarmo dari Trigarta (Sudarsono, Mei 2020).
Dalam lakon Salya Gugur yang disajikan oleh dalang Ki Nartosabdo (Oktober 2020), peran Nakula sangat penting karena dapat menentukan kemenangan di pihak Pandawa. Diceritakan bahwa Prabu Salyapati, raja Kerajaan Mandaraka, sangat sakti karena mempunyai kesaktian bernama candabirawa. Wujud candabirawa adalah raksasa kecil atau buta bajang yang apabila terbunuh satu maka
akan menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi enam belas, dan seterusnya sampai arena pertempuran Tegal Kurusetra penuh dengan candabirawa. Dengan kesaktiannya tersebut, Prabu Salya mustahil dapat dikalahkan oleh Pandawa.
Demi kemaslahatan para Pandawa dan keselamatan para prajuritnya, Nakula bersama adiknya, Sadewa, menghadap Prabu Salya dengan memegang keris untuk melakukan bunuh diri karena merasa tidak akan bisa menang melawan Prabu Salya. Melihat apa yang dilakukan Nakula dan Sadewa tersebut, Prabu Salya merasa iba karena Nakula dan Sadewa adalah keponakannya sendiri, yaitu anak dari Dewi Madrim yang merupakan adiknya. Prabu Salya akhirnya memberikan rahasianya agar bisa dikalahkan oleh para Pandawa (Nartosabdo, Oktober 2020). Inilah peran Nakula dalam Perang Bharatayuda yang selalu berorientasi kepada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, karakter gotong royong terwujud dalam tokoh Nakula.
Sadewa sebagai Perwujudan Karakter Integritas
Nilai karakter integritas adalah upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, yang terdiri dari kejujuran keteladanan, tanggung jawab, komitmen moral dan cinta pada kebenaran. Subnilai integritas, antara lain, kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, berkomitmen moral, antikorupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (Kemendikbud, 2017). Nilai-nilai ini tergambarkan pada karakter Pandawa yang kelima, Sadewa.
Menurut Wirastodipura, Sadewa mempunyai watak jujur, setia, bertanggung jawab, berkomitmen moral, dan cinta pada kebenaran. Di pedalangan gaya Surakarta, tokoh Sadewa jarang tampil sebagai tokoh utama. Sebaliknya, Sadewa sering menjadi tokoh utama di pedalangan gaya Yogyakarta. Menurut Widadi (2016) nama kecil Sadewa adalah Tangsen, yang berasal dari kata tang dan sen, artinya tanggung jawab dan risen. Tanggung jawab adalah orang yang selalu berusaha menunaikan amanah dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Risen berasal dari kata risi (Jawa) yaitu malu melakukan perbuatan yang tercela (Widadi, 2016).
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 44
Sadewa memiliki kemampuan analisis yang cermat serta sikap kritis yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari lakon Semar mBangun Kayangan yang disajikan oleh dalang Ki Seno Nugroho pada bulan Desember 2019. Dalam lakon tersebut, Puntadewa meminta saran kepada keempat adiknya tentang niat Kresna palsu yang ingin meminjam jimat kalimasada sebagai tumbal negara Dwaraka yang terkena bencana. Bima, Arjuna, dan Nakula menyetujui dengan alasan Kresna adalah penasihat Pandawa yang berjasa besar. Dalam hal ini, Sadewa mempunyai pemikiran lain. Ia berpendapat bahwa seharusnya Kresna tidak perlu meminjam jamus kalimasada sebagai tumbal untuk mengatasi masalah di Dwarawati karena Kresna merupakan titisan Wisnu, sedangkan kalimasada adalah dasar dan pedoman hidup bagi rakyat Amarta. Meminjamkan kalimasada kepada Kresna sama saja mencederai nilai-nilai yang ada dalam jimat tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, Sadewa menolak keinginan Kresna. Ia menerima apapun konsekuensinya, sekalipun diusir dari istana. Sadewa teguh dengan pendiriannya karena merasa kebenaran ada pada dirinya (Nugroho, Desember 2019).
Dalam lakon Wirata Parwa disebutkan bahwa Sadewa menyamar sebagai Darmagranti yang hidup di pedesaan sebagai tukang rumput, peternak, dan petani yang mengelola lumbung pangan negara Wirata. Suatu ketika, lumbung tersebut diserang oleh banyak hama. Kerusakan lahan mengakibatkan penurunan hasil panen. Sebagai petani yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, Sadewa dan Nakula bersama Bilawa atau Bima bekerja sama untuk membasmi hama dan membenahi lahan tersebut.
Sadewa merupakan anak dari dewa pengobatan yaitu Batara Aswin, sehingga ia pun pandai mengobati segala macam penyakit. Dalam Perang Bharatayuda, Sadewa yang berkomitmen moral tidak tega melihat para prajurit yang sangat menderita karena luka terkena senjata. Ia berada di belakang layar untuk mengobati para prajurit yang nahas tersebut. Dalam lakon Sudamala atau Durgo Ruwat, Raden Sadewa dapat meruwat Batari Durga dari raseksi kembali menjadi wanita cantik bernama Batari Uma. Batari Durga adalah ratunya segala macam makhluk halus yang sering menggoda kebahagiaan manusia. Tempat tinggalnya di Hutan Dandang Mangore atau Setra Ganda Mayit. Semula Batari Durga adalah
seorang bidadari yang sangat cantik dan merupakan istri Batara Guru di kahyangan Suralaya. Kesalahan yang dilakukan Batari Durga membuat Batara Guru marah dan mengutuknya menjadi raseksi dan diberi kekuasaan untuk memimpin semua makhluk halus. Sadewalah yang dapat meruwat Batari Durga ke wujud semula (Nugroho, September 2018). Sifatnya yang jujur, memberi teladan, tanggung jawab, berkomitmen moral, dan cinta kebenaran inilah wujud karakter integritas dalam diri Sadewa.
SIMPULAN
Seluruh penguatan 5 (lima) nilai utama pendidikan karakter bangsa, yang terdiri dari (1) religius, (2) nasionalisme, (3) kemandirian, (4) gotong royong, dan (5) integritas, terwujud dalam karakter tokoh Pandawa, baik sepenuhnya maupun sebagian subnilainya. Nilai karakter religius terwujud sepenuhnya dalam karakter tokoh Pandawa yang pertama, Prabu Puntadewa, terutama untuk subnilai beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, peduli sosial, serta individu menjaga keselarasan dengan alam semesta (lingkungannya). Nilai nasionalisme terwujud sepenuhnya dalam karakter tokoh Pandawa yang kedua, Raden Werkudara, terutama untuk subnilai rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebhinekaan, dan semangat rela berkorban.
Nilai kemandirian terwujud sebagian dalam karakter tokoh Pandawa yang ketiga, Raden Arjuna, terutama untuk subnilai kerja keras, pembelajar sepanjang hayat, dan tahan banting. Subnilai berdaya juang, profesional, kreatif, dan keberanian tidak tampak perwujudannya pada berbagai referensi penokohannya (lakon, dalang, buku, dan pertunjukan). Nilai gotong royong terwujud sebagian dalam karakter tokoh Pandawa yang keempat, Raden Nakula, terutama untuk subnilai kerja sama, tolong-menolong, dan sikap kerelawanan. Subnilai menghargai, inklusif, berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, solidaritas, empati, antidiskriminasi, dan antikekerasan tidak tampak perwujudannya pada berbagai referensi penokohannya. Nilai integritas terwujud sebagian dalam karakter tokoh Pandawa yang kelima, Raden Sadewa, terutama untuk subnilai cinta pada kebenaran, komitmen moral, tanggung jawab, dan menghargai martabat individu. Subnilai kejujuran, setia, antikorupsi,
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 45
keadilan, dan keteladanan tidak tampak perwujudannya pada berbagai referensi penokohannya.
Nilai-nilai karakter bangsa yang direpresentasikan oleh tokoh karakter Pandawa menunjukkan bahwa wayang kulit merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus dirawat dan dijaga keberadaannya. Pemaknaan terhadap lima nilai utama pendidikan karakter melalui kajian terhadap tokoh karakter Pandawa memberikan kemungkinan dilakukannya kajian kontekstual serupa terhadap budaya-budaya lokal lain yang masih hidup dalam masyarakat.
REFERENSI
Achmadi, Asmoro. (2004). Filsafat dan Kebudayaan Jawa: Upaya Membangun Keselarasan Islam dan Budaya Jawa. Surakarta: CV Cenderawasih.
Haq, Muhammad Zaairul. (2010). Tasawuf Pandawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harghana SW, Bondhan. (2003). Janturan Jangkep Wayang Purwa. Surakarta: CV Cenderawasih.
Herawati, Tri Ratna. (2014). Pendidikan Karakter yang Terintegrasi dalam Wayang Kulit dengan Lakon ‘Puspito Manik’. Diakses dari http://repository.upy.ac.id/446/
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kemendikbud.
Murtiyoso, Bambang. (1996). Pengungkapan Nilai-nilai Islam dalam Pertunjukan Wayang Kulit. Makalah disampaikan pada Seminar Pergelaran Wayang Kulit dan Sarasehan Budaya LSMI/HMI Cabang Surakarta di Taman Budaya Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1996.
Poedjosoebroto. (1978). Wayang Lambang Ajaran Islam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Purnamasari, Aulia Fajri. (2013). Upaya Penanaman Nilai-Nilai Karakter melalui Tokoh Wayang dan Dampaknya terhadap Perilaku Keagamaan Siswa di SMP Negeri 18 Purworejo. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses dari https://fdokumen.com/document/upaya-penanaman-nilai-nilai-karakter-melalui-i-iv-daftar-pustakapdf-lingkungan.html
Sastroamidjojo, Seno. (1964). Renungan tentang Pertunjukan Wayang Kulit. Yogyakarta: Percetakan Republik Indonesia.
Soetarno. (2005). Pertunjukan Wayang dan Makna Simbolisme. Surakarta: STSI Press.
Teguh. (2007). Moral Islam dalam Lakon Bima Suci. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widadi, Subur. (2016). Membaca Wayang dengan Kacamata Islam. Sukoharjo: CV Farishma Indonesia.
Wirastodipuro. (2006). Ringgit Wacucal, Wayang Kulit, Shadow Puppet. Surakarta: ISI Press.
Zarkasi, Effendi. (1977). Unsur Islam dalam Pewayangan. Bandung: Al-Ma’arif.
Peraturan Pemerintah: Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter.
Youtube: Aji, MPP Bayu. (Oktober 2020). Sang Bima.
https://youtu.be/zl6y-AdSviw Asmoro, Purbo. (Agustus 2020). Lakon
Mbangun Candi ngantos Petruk dadi Ratu. https://youtu.be/gPxnOB9uSGw
Asmoro, Purbo. (November 2020). Pendadaran Siswa Sokalima. https://youtu.be/kzEVBNqEp1U
Nartosabdo. (Juni 2020). Kresno Kembang. https://youtu.be/K7AIVS_AZaI
Nartosabdo. (Juni 2020). Pandawa Dadu. https://youtu.be/OIdnqogdtqc
Nartosabdo. (Juli 2020). Bale Golo-golo. https://youtu.be/A4-S1lbqFxI
Nartosabdo. (Oktober 2020). Salyo Gugur. https://youtu.be/JQkSG4g4LBc
Nugroho, Seno. (September 2018). Durgo Ruwat. https://youtu.be/Uci7VzwC8_4
Nugroho, Seno. (November 2019). Wiratha Parwa. https://youtu.be/uX8Fyrjn4bk
Nugroho, Seno. (Desember 2019). Semar mBangun Kahyangan. https://youtu.be/uy5WcCZjAp4
Soedarsono, Manteb. (Mei 2020). Wiratha Parwa/Bima Labuh. https://youtu.be/nQF2rryrYC0
Soedarsono, Manteb. (Juni 2020). Sesaji Raja Suya. https://youtu.be/aUDiIiaLzCs
Soedarsono, Manteb. (Januari 2021). Arjuna Wiwaha. https://youtu.be/BpotoEG0wR4
Suroto, Anom. (September 2016). Bima Bungkus. https://youtu.be/8ED1HyeETiE
Suroto, Anom. (Februari 2021). Wahyu Tohjali. https://youtu.be/aYbIo9nmWqQ
Suroto, Anom. (Maret 2021). Semar mBangun Kahyangan. https://youtu.be/cuBEYGz9bRg
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 46
PEMANFAATAN KAMERA LUBANG JARUM PADA PEMBELAJARAN SENI BUDAYA BAGI SISWA SEKOLAH DASAR:
IMPLEMENTASI KETERAMPILAN ABAD 21
THE UTILIZATION OF PINHOLE CAMERA IN ARTS AND CULTURE LEARNING FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS:
IMPLEMENTATION OF 21 ST CENTURY SKILLS
Briliyan Syarifudin Ahmad 1 Homeschooling Primagama Yogyakarta
ABSTRACT
This article aims to present the results of a study on the utilization of pinhole camera as an alternative media of learning to implement 21st century skills in arts and culture learning in the primary schools through-the activities of making cameras, decorating cameras, taking pictures, and presenting pictures. Literature review is carried out to collect information on 21st century skills and the utilization of pinhole camera in the process of learning arts and culture in primary schools. The discussion puts forward students’ activities in the process of making pinhole camera, using the camera, and doing collaboration with other learning subjects. The result of the study comes up with the ideas of creating alternative learning materials and media through the utilization of pinhole camera which enables teachers to design contented and meaningful learning for students. Subsequently, this may remarkably substantiate the implementation of 21st century skills at schools in actual practices of problem solving, developing creativity, collaboration, and communication, to successfully achieve the learning objectives.
Keywords: pinhole camera, 21st century skills, arts and culture learning, primary school.
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk memaparkan hasil kajian mengenai pemanfaatan kamera lubang jarum sebagai alternatif media pembelajaran yang digunakan untuk menerapkan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya pada siswa di sekolah dasar melalui aktivitas pembuatan kamera, menghias kamera, pengambilan foto, dan presentasi hasil foto. Kajian literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang keterampilan abad 21 serta pemanfaatan kamera lubang jarum pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya di sekolah dasar. Pembahasan menyajikan aktivitas belajar siswa dalam mempelajari proses pembuatan kamera lubang jarum, menggunakan kamera, dan melakukan kolaborasi berbagai subjek pelajaran. Hasil kajian memberikan pandangan bahwa pemanfaatan kamera lubang jarum dalam pembelajaran di kelas merupakan alternatif materi sekaligus media pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Hal ini sangat mendukung penerapan keterampilan abad 21 di sekolah dalam tindakan nyata melalui aktivitas penyelesaian masalah, pengembangan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai.
Kata kunci: kamera lubang jarum, keterampilan abad 21, pembelajaran seni budaya, sekolah dasar.
1Briliyan Syarifudin Ahmad adalah guru sekolah dasar di lembaga pendidikan non formal Homeschooling Primagama yang menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Pendidikan Dasar (S-2) Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis berminat/menggeluti bidang cerita anak dan pendidikan seni di sekolah dasar. Penelitian yang pernah dibuat berfokus pada pengembangan inovasi literasi dan seni rupa di sekolah dasar.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 47
PENDAHULUAN
Data dari Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2009 menunjukkan bahwa meskipun model pendidikan transmisi yang dilakukan para guru dengan melakukan transfer pengetahuan kepada siswa melalui ceramah dan buku teks sudah ketinggalan zaman, hal tersebut masih dominan diterapkan sebagai pendekatan pembelajaran di berbagai belahan dunia. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengubah praktik pendidikan model industri bagi peserta didik abad ke-21 (Zhao, 2012; Hargreaves, 2009; Hammond, 2009). Penelitian-penelitian tersebut mengetengahkan bahwa praktik pembelajaran abad 21 harus dapat menciptakan pembelajaran yang membantu siswa terhubung dengan dunia dan memahami masalah yang dihadapi dunia saat ini.
Pembelajaran abad 21 mengharuskan guru dan sekolah mengolah dan mempertahankan minat siswa terhadap materi yang terhubung dengan dunia nyata. Hal ini karena keterampilan abad 21 dalam kurikulum tidak hanya bermanfaat bagi siswa dan guru, namun juga berguna untuk mempersiapkan karir masa depan siswa (Alismail & McGuire, 2015). Oleh karena itu, guru harus berusaha meningkatkan keingintahuan siswa, meningkatkan keterampilan mengajar secara fleksibel, memanfaatkan berbagai media, serta menyediakan sumber-sumber belajar bagi siswa baik di dalam kelas maupun di luar sekolah.
Pengembangan keterampilan di sekolah dasar diperoleh melalui berbagai subjek pelajaran, antara lain muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP). Hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru sekolah dasar memberikan gambaran bahwa pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya dibelajarkan berdasarkan keterampilan yang dimiliki guru atau bersumber dari buku pelajaran, padahal materi di buku pelajaran kadang tidak sesuai dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya memiliki tantangan tersendiri untuk diterapkan dalam pembelajaran abad 21 di sekolah.
Penelitian yang dilakukan Saavedra & Opfer (2012) menunjukkan bahwa beberapa pembelajaran abad 21 berfokus pada jenis keterampilan berpikir dan komunikasi yang kompleks. Pembelajaran bukan sekedar hafalan namun juga disertai pengembangan keterampilan siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan
kreativitas, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Faktanya, keterampilan tersebut sering dilakukan secara terpisah di sekolah, padahal keterampilan ini perlu dibelajarkan secara bersamaan dalam satu tema. Rochmawati, Wiyanto, dan Ridlo (2019) menyatakan bahwa pembelajaran abad 21 di sekolah dasar masih belum optimal mengembangkan semua keterampilan abad 21 karena keterampilan itu dikembangkan secara terpisah.
Idealnya, pembelajaran abad 21 mengha-silkan siswa-siswa yang mampu berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi serta mampu melakukan komunikasi dengan baik. Miftah (2014) menyatakan bahwa selain berfokus pada pengembangan keterampilan pembelajaran abad 21, keberhasilan pembelajaran juga ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengupayakan pemanfaatan media dalam aktivitas pembelajaran sebagai sumber belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pemanfaatan kamera lubang jarum sebagai media pembelajaran SBdP di dalam kelas. Kamera lubang jarum biasanya terbuat dari kotak dengan "lubang jarum" kecil di salah satu sisi kotak dan layar di sisi lainnya. Lubang jarum sangat kecil sehingga hanya sejumlah kecil sinar cahaya yang bisa melewatinya. Kamera ini sangat mudah dibuat dan dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar (Zitzewitz, 2011). Pembelajaran yang dapat dilakukan dengan media ini pun sangat beragam. Siswa dapat berkreasi dengan membuat kameranya sendiri sekaligus mengomunikasikan hasil foto yang diambil tersebut. Pembelajaran seperti ini melibatkan siswa belajar secara aktif dan memunculkan motivasi belajar siswa. Siswa terpacu untuk terus belajar, baik di sekolah maupun di rumah bahkan di masa libur sekalipun. Hal tersebut dikarenakan siswa-siswa memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk terus belajar di mana pun mereka berada.
Berdasarkan hasil observasi pada beberapa sekolah di Kabupaten Sleman, diketahui bahwa guru kelas belum pernah menggunakan kamera lubang jarum dalam pembelajaran. Padahal, materi ini terdapat dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi optik dan pencahayaan. Aktivitas membuat kamera lubang jarum ini dapat dimanfaatkan guru untuk memaksimalkan pembelajaran abad 21.
Penelitian yang dilakukan oleh Button Clare (2007) berkaitan dengan pelajaran
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 48
menggunakan kamera lubang jarum menunjuk-kan bahwa kegiatan siswa dalam membuat kamera lubang jarum secara mandiri, mengambil foto, dan mengembangkan gambar, memberikan siswa pengalaman pendidikan yang luar biasa dan menarik. Sayangnya aktivitas belajar menggunakan kamera lubang jarum hanya berfokus pada kegiatan fotografi. Padahal kegiatan tersebut dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan kegiatan belajar Seni Budaya dan Prakarya dan subjek pelajaran lainnya yang mendukung implementasi keterampilan abad 21 dalam pembelajaran.
Penelitian Syaifudin (2013) menyimpul-kan bahwa pemanfaatan media kamera lubang jarum dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan melalui kompetensi mengekspre-sikan diri melalui gambar dengan mengandalkan cahaya. Berkaitan dengan ini, Asep, Djumhana, & Hendriani (2018) menyatakan bahwa pembe-lajaran dengan menggunakan metode eksperimen mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa.
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsi-kan pemanfaatan kamera lubang jarum sebagai alternatif media pembelajaran yang digunakan untuk menerapkan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya pada siswa di sekolah dasar. Pemanfaatan kamera lubang jarum sebagai media dan materi pembelajaran di dalam kelas memungkinkan guru untuk mendesain suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan abad 21. Keterampilan yang dimaksud mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. PEMBAHASAN
Keterampilan Abad 21 Era informasi menciptakan kebutuhan
akan keterampilan yang harus dimiliki individu, yang membuat setiap orang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang disebut sebagai keterampilan belajar abad 21 untuk memecahkan masalah baru di dunia baru. Siswa diharapkan dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan abad 21 adalah seperangkat kemampuan yang perlu dikembangkan siswa agar berhasil di era informasi. Crockett (2011) menjelaskan beberapa keterampilan penting
yang dibutuhkan oleh siswa pada abad ke-21 meliputi keterampilan penyelesaian masalah, kreativitas, berpikir analitis, kolaborasi, dan komunikasi.
Trilling & Fadel (2009) menjelaskan struktur dan komponen (keterampilan, pengetahuan, dan keahlian) yang dibutuhkan siswa untuk dapat sukses dalam pekerjaan dan kehidupan di masyarakat pada abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 merupakan seperangkat kemampuan yang perlu dikembangkan siswa agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada era informasi. Berdasarkan pelangi pengetahuan dan keterampilan abad 21 Trilling & Fadel (2009) tersebut, terdapat tiga jenis keterampilan abad 21 yang sangat diperlukan pada era informasi. Keterampilan tersebut meliputi learning and innovation skills (keterampilan belajar dan berinovasi), information, media, and technology skills (keterampilan informasi, media, dan teknologi), dan life and career skill (keterampilan hidup dan karir).
Ketiga keterampilan ini diperlihatkan pada Gambar 3 berikut ini.
Gambar 1. Pelangi Pengetahuan dan Keterampilan
Abad 21 Sumber: Trilling & Fadel (2009)
Learning and innovation skills menjadi
inti dari terwujudnya pemelajar yang mandiri sepanjang hayat untuk memenuhi kebutuhan keterampilan abad 21. Selanjutnya, kunci dari learning and innovation skills ini dikenal dengan sebutan 4C, yaitu berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), berkomunikasi (communicating), dan berkolaborasi (collaborating). Keempat keterampilan tersebut diharapkan dapat membantu siswa belajar, berinovasi, menguasai IPTEK untuk sukses baik di sekolah maupun bagi masa depannya.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 49
1. Keterampilan berpikir kritis Keterampilan berpikir kritis merupakan
cara berpikir reflektif dan masuk akal, yang berfokus pada penentuan apa yang harus dipercaya atau dilakukan (Ennis, 2015). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya berpikir kritis berfokus pada analisis yang cermat terhadap sebuah pemecahan masalah. Siswa membutuhkan kemampuan membandingkan, menerapkan, mengevaluasi, dan melakukan sintesis agar mampu menyelesaikan masalah secara kritis.
Berpikir kritis dan pemecahan masalah dianggap oleh banyak orang sebagai dasar baru pembelajaran abad ke-21 (Trilling & Fadel, 2009). Jenis keterampilan ini sangat berharga karena memungkinkan siswa untuk berurusan secara praktis dengan masalah-masalah sosial, matematika, dan ilmiah. Hal ini akan memberdayakan siswa dalam membuat keputusan yang efektif dan berkepala dingin dalam kehidupan sosialnya.
2. Kreativitas Berpikir kreatif dapat dimaknai sebagai
upaya mencari sebanyak mungkin alternatif. Solusi yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan atau penyelesaian masalah yang lainnya (Precourt, 2013). Siswa harus dapat berpikir dan belajar secara kreatif baik di lingkungan digital maupun nondigital untuk mengembangkan solusi yang unik dan berguna. Meskipun keaslian dan imajinasi kreatif bersifat pribadi, tapi bimbingan dan pelatihan secara substansial dapat meningkatkan output belajar bagi siswa.
Trilling & Fadel (2009) menyatakan bahwa fokus pendidikan tradisional adalah pada fakta, hafalan, keterampilan dasar, dan uji coba, yang tidak mendukung pengembangan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dapat didorong dengan membangun lingkungan kelas yang menerima dan memperkuat gagasan baru. Aktivitas melakukan proyek yang bermanfaat dan tugas akan memberikan tantangan bagi siswa untuk mengatasinya dengan cara yang imajinatif.
3. Komunikasi Komunikasi yang efektif membutuhkan
perhatian pada keseluruhan proses, bukan hanya isi pesan (Wachs, 2008). Siswa harus dapat berkomunikasi dengan teks, ucapan, dan beberapa format multimedia lainnya. Mereka harus dapat berkomunikasi secara visual melalui video seefektif yang mereka lakukan dengan teks
dan ucapan. Komunikasi adalah istilah luas yang menggabungkan tingkat interaksi dan berbagi informasi multi-faceted. Fakta yang diperoleh dari pembelajaran di kelas menunjukkan bahwa siswa menyukai berkomunikasi dengan memanfaatkan berbagai teknologi untuk berkomunikasi.
Trilling & Fadel (2009) menemukan bahwa siswa dapat berkomunikasi dengan bebas saat memanfaatkan teknologi. Namun, sebuah studi tentang komunikasi menunjukkan bahwa pesan online tidak mampu menunjukkan adanya aksen. Komunikasi secara langsung lebih memungkinkan adanya interaksi yang bermakna dalam pembelajaran sehingga merangsang siswa berkomunikasi secara aktif.
4. Kolaborasi Pembelajaran kolaboratif adalah pembela-
jaran secara berkelompok dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau menciptakan sebuah produk (Laal & Ghodsi, 2012). Pembelajaran abad 21 menuntut siswa untuk memiliki kemampuan berkolaborasi baik di lingkungan sekitar maupun berkolaborasi secara virtual. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kerjasama dan interaksi antar siswa. Lebih luas lagi siswa dapat meminta bantuan berbagai pihak berdasarkan tema masalah yang ada untuk memberikan solusi dari masalah tersebut.
Bentuk keterhubungan dan kolaborasi sangat penting untuk pembelajaran, kesehatan mental dan emosional siswa. Ini adalah keterampilan yang perlu dilatih secara kontinyu oleh guru kepada siswa. Beberapa pendapat tersebut pada dasarnya menekankan pentingnya keterampilan yang harus dimiliki siswa agar sukses dalam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Keterampilan mendasar yang harus dikuasai siswa meliputi keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Keterampilan abad 21 memerlukan pendekatan dan metode baru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satunya adalah pemanfaatan media yang dapat membantu guru dalam mengembangkan keterampilan abad 21 pada siswa. Kamera lubang jarum (pinhole camera) menjadi alternatif yang mendukung hal tersebut.
Kamera Lubang Jarum
Kamera lubang jarum tidak akan lepas dari sejarah perkembangan kamera. Lewis & Lewis (2009) mengatakan bahwa foto dimulai
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 50
sekitar abad ke sebelas, saat kamera pertama obscura pada Gambar 2 (yang secara harfiah berarti "ruangan gelap"), dikembangkan. Kamera seukuran ruangan seperti itu pertama kali digunakan untuk mempelajari gerhana. Dengan mencegah semua cahaya memasuki ruangan dan kemudian memotong lubang kecil di bawah naungan jendela, seseorang dapat memproyeksikan bayangan matahari yang terbalik ke dinding yang berlawanan.
Gambar 2. Bentuk Obscura/Pinhole Camera (Wikipedia.org)
Membuat kamera lubang jarum tidak
membutuhkan banyak waktu dan biaya. Siswa dapat membangun sendiri kamera lubang jarum karena prinsip kamera ini sangat sederhana (Hirsch, 2009). Prinsip yang sederhana ini dapat diterapkan untuk merangsang kreativitas siswa dalam mengembangkan sendiri bentuk kamera yang mereka inginkan.
Peres (2007) mengatakan bahwa kamera lubang jarum menggunakan lubang kecil (dibuat dengan jarum) dengan bahan buram tipis dan bukan menggunakan lensa untuk menyampaikan gambar ke bidang fokus. Lensa yang bukan berasal dari lensa optik membuat gambar foto kamera lubang jarum tidak tajam. Waktu memfoto yang relatif lama dibutuhkan untuk mencegah hasil foto kamera lubang jarum bergerak (blur).
Banyak fotografer merasa senang membuat sendiri hasil fotonya, dan lebih bermakna jika fotografer membuat kameranya sendiri (Hirsch, 2009). Kamera lubang jarum dapat dibuat dari kardus, karton, triplek, paralon, bahkan tempurung kelapa. Pada dasarnya kamera ini dibuat dari bahan-bahan yang tertutup
dan tidak ada celah cahaya. Kamera lubang jarum menggunakan negatif paper (kertas peka cahaya) untuk merekam bayangan yang masuk ke dalam kamera.
Kamera lubang jarum membentuk sebuah gambar melalui lubang cahaya yang sempit sebesar lubang jarum. Sinar cahaya yang melintasi lubang jarum ini diteruskan sebagai garis lurus dan membentuk gambar terbalik di sisi berlawanan dalam kotak, di mana sepotong kertas peka cahaya ditempatkan untuk merekam gambar (Peres, 2007). Selanjutnya proses cuci cetak hasil pengambilan gambar dapat dilakukan di ruang gelap.
Camera obscura atau kamera lubang jarum merupakan prinsip dasar kerja kamera yang digunakan sekarang. Kamera ini dapat dibuat dari bahan sederhana yang ada di sekitar. Prinsip kerjanya adalah “kamar gelap”, yaitu ruang yang tidak terdapat celah cahaya untuk masuk. Selanjutnya kamera ini diberikan lubang sebesar jarum untuk memberi celah cahaya masuk dan membentuk bayangan. Bayangan tersebut kemudian direkam menggunakan kertas peka cahaya hingga muncul gambar. Proses ini dilanjutkan melalui kegiatan cuci cetak hasil gambar di ruang gelap.
Karakteristik Siswa SD
Sesuai dengan perkembangannya, peserta didik pada usia 7 hingga 12 tahun berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap ketika kemampuan berpikir peserta didik sudah mulai terstruktur secara keseluruhan. Namun struktur ini masih lemah dan hanya memungkinkan penalaran secara perlahan karena tidak adanya kombinasi-kombinasi yang tergeneralisasi (Piaget & Inhelder, 2016).
Slavin (2011) mengungkapkan perkem-bangan peserta didik pada tahap operasional konkret mengalami kesulitan dengan pemikiran yang abstrak. Peserta didik pada tahap operasional konkret ini sudah dapat membentuk suatu konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah, akan tetapi hanya sejauh jika mereka melibatkan objek atau situasi yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Oleh karena itu, dalam tahap operasional konkret, siswa akan membentuk suatu konsep yang menghubungkan pengetahuan yang mereka miliki dengan cara memecahkan masalah yang sederhana. Dalam hal ini, guru dapat membantu siswa dalam aktivitas belajar menggunakan kamera lubang jarum.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 51
Pembelajaran Menggunakan Kamera Lubang Jarum pada Siswa Sekolah Dasar
Kamera lubang jarum biasanya dibuat dari kaleng yang berbentuk tabung. Kaleng tersebut kemudian dilubangi dengan bor dan diberi lensa yang dibuat dari alumunium yang diberi lubang dengan jarum. Setelah membuat kamera, siswa dapat melakukan observasi berdasarkan hasil yang telah mereka kerjakan. Pertanyaan yang diajukan pada saat observasi ini misalnya: Apakah gambar yang dihasilkan terbalik? Atau: apa pengaruh dari besarnya lubang pada kamera? (Samuel & James, 2005)
Kamera lubang jarum merupakan media yang sering digunakan pada materi sifat-sifat cahaya dan optik dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IV sekolah dasar. International Curriculum Program (ICP) Cambridge memanfaatkan kamera lubang jarum dalam tema invention. Siswa dibelajarkan proses penemuan kamera dan diberikan aktivitas untuk mengembangkan kamera buatannya sendiri. Aktivitas ini juga mengajarkan siswa untuk memanfaatkan barang-barang di sekitar untuk dikembangkan menjadi kamera.
Siswa akan dapat merekam pengamatan, menjelaskan pembentukan gambar dengan kamera lubang jarum, membangun kamera lubang jarum, dan menarik kesimpulan berdasarkan observasi (Margolin, 2009). Pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada lingkungan sekitar dapat menambah ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran.
Keunggulan kamera lubang jarum dalam pembelajaran siswa SD adalah digunakan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Keterampilan kolaboratif yang dimaksud adalah bekerjasama antarsiswa, bahkan dengan orang-orang di sekitar siswa yang memiliki kapasitas dalam pemecahan masalah yang diberikan pada saat pembelajaran. Siswa dapat melakukan pembelajaran secara mandiri di luar kelas karena media ini dapat dibuat dengan mudah dan murah. Penerapan Keterampilan Abad 21 melalui Pemanfaatan Kamera Lubang Jarum pada Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya
Pembelajaran dengan menggunakan kamera lubang jarum dimulai dari proses pembuatan kamera lubang jarum. Siswa dan guru mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya siswa membuat kamera
berdasarkan arahan guru. Setelah siswa memahami prinsip pembuatan kamera ini, mereka dapat mengembangkan sesuai kreativitas yang mereka miliki. Dari aktivitas pembuatan kamera ini, siswa memiliki kesempatan untuk berpikir kritis.
Selanjutnya ketika siswa diajak untuk menghias kamera, guru merangsang kreativitas siswa. Siswa memeroleh kesempatan dan pengalaman untuk mendesain dan memanfaatkan keterampilan yang didapatkan pada pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Setelah siswa dapat memotret dengan menggunakan kamera lubang jarum, mereka dapat diberikan pengalaman untuk mengomunikasikannya dalam bentuk pameran dengan bimbingan guru. Siswa juga dapat berkolaborasi dengan siswa-siswa lain untuk mengembangkan ragam jenis kamera atau hasil gambar. Aktivitas yang menyenangkan dapat meningkatkan keinginan siswa untuk selalu belajar dan mengembangkan kreativitasnya. Penerapan keempat keterampilan pada learning and innovation skills atau 4C diuraikan berikut ini melalui pemanfaatan kamera lubang jarum pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya.
1. Critical thinking Aktivitas dalam menerapkan keterampilan
berpikir kritis pada siswa sekolah dasar adalah melalui kegiatan pembuatan kamera. Kegiatan ini melatih siswa untuk menalar proses terjadinya gambar dengan menghubungkan pengetahuan siswa tentang bayangan dan prinsip cahaya. Selain itu siswa dapat menganalisis proses terjadinya gambar dengan kamera yang hanya terbuat dari bahan sederhana. Aktivitas tersebut membuat siswa belajar beberapa subjek pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Integrasi beberapa subjek pelajaran membuat tujuan belajar lebih efisien.
Gambar 3. Rasa Ingin Tahu Siswa ketika Memperhatikan Penjelasan Guru/Trainer
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 52
Siswa juga diajak berlatih menyelesaikan masalah, sehingga mereka harus memperhitung-kan berapa lama waktu yang digunakan untuk mengambil gambar dan apa yang memengaruhi hasil foto. Gambar 3 di atas menunjukkan siswa dalam proses ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat bertanya untuk dapat menghasilkan gambar dari kamera yang mereka buat sendiri.
2. Creativity Aktivitas merakit dan menghias kamera
dapat mengembangkan kreativitas siswa. Siswa dapat berpikir kreatif menggunakan berbagai ide atau gagasan dalam membuat kamera. Selain itu konsep dasar pembuatan kamera ini dapat dikembangkan siswa dengan menciptakan variasi jenis kamera yang terbuat dari berbagai macam bahan. Bahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kamera lubang jarum misalnya berupa triplek, karton, kardus, bambu, kaleng, dan berbagai media lainnya. Bahan yang sederhana membuat media ini mudah dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya di sekitar siswa.
Gambar 4. Kreativitas Siswa dalam Membentuk Kamera
Proses menghias kamera dapat dilakukan
dengan kertas stiker. Siswa dapat memberikan gambar dan mewarnai sesuka hati mereka. Selain itu, aktivitas ini merangsang mereka untuk dapat mendesain dan memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki. Kegiatan ini memungkinkan siswa untuk membuat desain batik, gambar lukisan, atau gambar kolase sebagai hiasan kamera yang mereka buat.
3. Communication Hasil gambar yang dibuat oleh siswa
dapat digunakan untuk mengadakan pameran siswa. Melalui kegiatan pameran, siswa dapat mengomunikasikan proses dan hasil pembuatan karya mereka kepada banyak orang. Guru dapat memajang hasil karya siswa melalui website atau media sosial. Siswa dapat memberikan caption
pada foto yang mereka buat. Hal ini dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam menulis berdasarkan gambar.
Gambar 5. Siswa Memamerkan Hasil Foto dan Kamera Buatannya Sendiri
Melalui kegiatan pameran baik secara
online atau offline, siswa mendemonstrasikan cara membuat kamera pada khalayak umum dan dari proses tersebut mereka dapat memperoleh respon atau komentar terhadap karya yang sudah mereka buat. Aktivitas ini membantu siswa untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
4. Collaboration Kegiatan kolaborasi dapat dilakukan di
dalam dan di luar sekolah. Siswa dapat berkolaborasi dengan siswa lain untuk membuat karya foto atau bahkan menciptakan model kamera. Hal tersebut dapat mendukung siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Proses ini melatih siswa untuk terbiasa bekerjasama menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Gambar 6 berikut ini adalah contoh model kamera dan hasil foto berdasarkan kolaborasi siswa dengan pengrajin bambu di sekitar rumahnya.
Gambar 6. Hasil Foto Menggunakan Kamera yang Terbuat dari Bambu
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 53
SIMPULAN
Pemanfaatan kamera lubang jarum dalam pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya di Sekolah Dasar menjadi salah satu alternatif bagaimana keterampilan berpikir kritis, kreativitas, berkomunikasi, dan berkolaborasi dikembangkan melalui sebuah proses belajar yang meliputi aktivitas pembuatan kamera, menghias kamera, pengambilan foto, dan presentasi hasil foto siswa. Aktivitas pembelajaran ini seyogianya dilakukan dengan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan agar tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan abad 21 dapat dicapai.
Berdasarkan aktivitas dalam pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya, terdapat beberapa keuntungan yang mendukung implementasi pembelajaran abad 21 di sekolah dasar. Keuntungan menggunakan kamera lubang jarum dalam pembelajaran antara lain (1) tujuan belajar dapat diintegrasikan dalam berbagai subjek pembelajaran secara lebih efisien; (2) guru dapat menyesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki siswa; (3) memudahkan siswa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain; dan (4) pembelajaran lebih bermakna, karena siswa mengalami secara langsung proses pembelajaran di kelas.
REFERENSI
Alismail, H. A., & McGuire, P. (2015). 21st Century Standards and Curriculum: Current Research and Practice. Journal of Education and Practice, VI(6), 150–155.
Asep, S., Djumhana, N., & Hendriani, A. (2018). Penerapan Metode Eksperimen untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, III(2), 22-29.
Clare, B. (2007). Pinhole Cameras: For Science, Art, and Fun! Tech Directions, 67(5), 21-24.
Crockett, L., Jukes, I., & Churches, A. Literacy is NOT Enough: 21st Century Fluencies for the Digital Age. Newbury Park, CA: Corwin.
Ennis, R. H. (2015). Critical Thinking: A Streamlined Conception. In The Palgrave Handbook of Critical Thinking in Higher Education (hal. 31–47).
Hammond, L. D. (2009). Teaching and the change wars. A. Hargreaves & M. Fullan (Eds.), Changes wars (pp. 45-68). Bloomington, IN: Solution Tree.
Hargreaves, A. (2009). The fourth way of
change. A. Hargreaves & M. Fullan (Eds.) , Change wars (pp. 11-43). Bloomington, IN: Solution Tree.
Hirsch, R. (2009). Photographic Possibilities: The Expressive Use of Equipment, Ideas, Material, and Processes. Burlington: Focal Press.
Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. In Procedia - Social and Behavioral Sciences (Vol. 31, hal. 486–490).
Lewis, R. L., & Lewis, S. I. (2009). Cengage Advantage Books: The Power of Art. Belmont: Clark Baxter.
Margolin, M. (2009). Light & Color. Portland: J. Weston Walch.
Miftah, M. (2014). Pemanfaatan Media Pembelajaran untuk Peningkatan Kualitas Belajar Siswa. Jurnal KWANGSAN, 2(1), 1-11.
Organization of Economic Cooperation and Development. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Paris: OECD.
Peres, M. R. (2007). The Focal Encyclopedia of Photography. Burlington: Elsevier Inc.
Piaget, J., & Inhelder, B. (2016). Psikologi Siswa. The Psychology of the Child. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Precourt, G. (2013). What we know about creativity. Journal of Advertising Research, 53(3), 238–239.
Rochmawati, A., Wiyanto, W., & Ridlo, S. (2019). Analysis of 21st Century Skills of Student on Implementation Project Based Learning and Problem Posing Models in Science Learning. Journal of Primary Education, 8(4), 58-67.
Saavedra, A. R., & Opfer, V. D. (2012). Learning 21st-Century Skills Requires 21st-Century Teaching. Phi Delta Kappan, 94(2), 8–13.
Samuel, A., & James, E. D. (2005). Physics VI. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
Slavin, R. E. (2011). Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik. Jakarta: Permata Puri Media.
Syaifudin, M. (2013). Pemanfaatan Media Kamera Lubang Jarum pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Melukis pada Siswa Kelas V SDI Darut Taqwa Surabaya. Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan, IV(2), 1-7.
Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills. Jossey-Bass, 256.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 54
https://doi.org/10.1145/1719292.1730970 Wachs, S. (2008). Strategies for Career Success.
Journal of Oncology Practice, 4(1), 37–40. Zhao, Y. (2012). World class learners:
Educating creative and entrepreneurial students. New York: Sage Publication.
Zitzewitz, P. W. (2011). The Handy Physics Answer Book. Canton, MI: Visible Ink Press.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 55
PENINGKATAN KEMAMPUAN PESERTA DIDIK DALAM MENGIDENTIFIKASI AKOR MUSIK DENGAN TEKNIK ‘TUPATMA’
THE IMPROVEMENT OF STUDENTS’ ABILITY
TO IDENTIFY MUSIC CHORDS USING ‘TUPATMA’ TECHNIQUE
Rus Endarti1 SMKN 2 Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRACT
Identifying music chords is one of the students’ abilities in developing their creativity when learning Cultural Arts as the school subject. The mostly encountered problem at school is that students are less motivated to develop their ability to create music arrangement since they consider Cultural Art as a school subject proposed for only talented students. The current research aims at increasing the students’ ability to identify music chords using the technique of ‘Tupatma’ through direct instruction model. The classroom action research was carried out in two cycles including the stages of planning, implementation, observation, and reflection in each cycle. Subjects were tenth graders of Food Technology Class 1 in SMKN 2 Godean in the academic year of 2017/2018. Data collection techniques included observation, questionnaire, documentation, and field notes, while data analysis employed the technique of quantitative descriptive analysis. The result of the study demonstrates that the use of ‘Tupatma’ technique through direct instruction model can improve the average score of students’ learning completion rate in each cycle. Students’ average score in cycle 1 is 76.72 with the mastery percentage of 72%; and in cycle II students’ average score becomes 81.75 with the mastery percentage of 100 %.
Keywords: to identify, music chords, ‘Tupatma’, classroom action research.
ABSTRAK
Mengidentifikasi akor musik merupakan salah satu kemampuan peserta didik dalam mengembangkan kreativitas pada mata pelajaran Seni Budaya. Masalah yang terjadi adalah rendahnya motivasi peserta didik untuk menguasai kemampuan ini karena mereka beranggapan bahwa mata pelajaran Seni Budaya diperuntukkan bagi peserta didik berbakat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi akor musik dengan teknik ‘Tupatma’ melalui model pembelajaran langsung. Penelitian tindakan kelas dilakukan sebanyak dua siklus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi pada setiap siklusnya. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas X Boga 1 di SMKN 2 Godean pada tahun pelajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, dokumentasi, dan catatan lapangan. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik ‘Tupatma’ dengan model pembelajaran langsung dapat meningkatkan nilai rerata ketuntasan peserta didik pada setiap siklus. Nilai rerata siswa pada siklus I adalah 76,72 dengan persentase ketuntasan 72%, dan nilai rerata siswa pada siklus II meningkat menjadi 81,75 dengan persentase ketuntasan 100 %.
Kata kunci: mengidentifikasi, akor musik, ‘Tupatma’, penelitian tindakan kelas.
1 Rus Endarti adalah guru di SMKN 2 Godean Sleman Yogyakarta dengan pendidikan terakhir Magister Manajemen Pendidikan dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan adalah “Pembelajaran Seni Budaya melalui Model Pembelajaran Team Assissted Individualization/Bantuan Individual dalam Kelompok (BidaK)” pada Jurnal Wuny Vol. 1 No. 2/2019. Karya lagu yang sudah dipublikasi dan digunakan di lembaga/instansi adalah “Mars Kosudgama”, “Himne SMPN 2 Sleman”, “Mars SMKN 1 Kalasan”, “Mars Sidoagung”, dan “Mars SMKN 2 Godean”.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 56
PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 mengamanatkan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan pula dalam Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Inilah fungsi utama pendidikan secara nasional dalam upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rambu-rambu yang diberikan pemerintah dalam mengembangkan kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan harus mengarah pada tujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Seiring dengan ini, Seni Budaya yang digolongkan dalam kelompok mata pelajaran estetika diarahkan pada tujuan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.
Pembelajaran Seni Musik merupakan salah satu aspek dari pembelajaran Seni Budaya selain Seni Rupa, Seni Tari, dan Seni Teater yang diberikan di sekolah. Pelajaran Seni Budaya penting untuk diberikan karena keunikan perannya yang tak mampu diemban oleh mata pelajaran lain. Keunikan tersebut terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam kegiatan berekspresi, berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan: belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni. Amanat BSNP menyebutkan bahwa guru Seni Budaya setidaknya mengajarkan dua aspek seni sesuai dengan kemampuan dan sumber daya manusia serta fasilitas yang tersedia (BSNP, 2006).
Dalam pelaksanaan pembelajaran Seni Musik ditemukan suatu permasalahan mendasar yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam menentukan akor lagu sebagai dasar mengolah
aransemen. Kesulitan dirasakan ketika peserta didik tidak memiliki kecukupan bekal kemampuan awal yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya ataupun pengalaman musik yang didapat dari lingkungan sosialnya.
Kenyataan ini menarik dan mendorong untuk dilakukannya perumusan mengenai strategi pembelajaran aransemen musik melalui identifikasi akor musik yang mudah dipahami dan dilakukan oleh peserta didik yang kemampuan awalnya masih kurang. Dalam buku ‘Metode Edutainment’ dijelaskan bahwa strategi merupakan sebuah rencana, rancangan, dan plot bagi dibangunnya sebuah metode pembelajaran yang selanjutnya akan dijabarkan dalam teknik dan gaya pembelajaran (Moh. Sholeh Hamid, 2013).
Kegiatan mengidentifikasi akor musik dapat menumbuhkan kemampuan dalam membuat aransemen. Aransemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) diartikan sebagai nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama saat menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi. Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengaransemen musik memiliki tahapan dan proses kompleks. Salah satu tahapannya adalah mengidentifikasi akor musik.
Kegiatan mengidentifikasi akor musik sebagai bagian dari proses aransemen akan membuahkan hasil penataan atau penuangan ide-ide musikal, di antaranya adalah pengembangan melodi, filler yang berupa isian ritmik ataupun melodi bebas sebagai usaha untuk memperindah sajian musik dengan tidak mengubah melodi utama lagu. Aransemen juga dapat diartikan sebagai gubahan lagu untuk orkes atau kelompok paduan musik, baik vokal maupun instrumental (Banoe, 2003a). Dengan demikian keterampilan mengaransemen musik dapat diartikan sebagai kecakapan teknik untuk memproses atau mengolah suatu karya lagu menjadi sajian musik yang bernilai artistik.
Prinsip akor adalah triad atau trinada, yaitu susunan trinada yang secara vertikal dibentuk atas unsur nada alas (tonika), ditambah tert (nada ketiga), dan ditambahkan kwint (nada kelima). Berdasarkan prinsip tersebut maka dapat dipastikan bahwa setiap nada akan dapat disusun menjadi suatu akor.
Dalam analisis harmoni dipergunakan dasar dua macam tangga nada sebagai landasan pembentukan akor, yaitu tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor yang
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 57
dikenal dalam jajaran tangga nada autentik Gregorian sebagai ionis (ionian mode) dan aeolis (aeolian mode) (Banoe, 2003b). Lagu yang mendasarkan pada tangga nada diatonik mayor umumnya memiliki suasana gembira, semangat, tegas, atau optimis. Sedangkan lagu dengan tonalitas minor dapat menciptakan suasana sedih, sayu, pesimis atau tenang. Baik dalam tangga nada mayor maupun minor, penerapan teknik tupatma dalam proses aransemen tetap memiliki prinsip yang sama.
Untuk memudahkan pemahaman peserta didik dalam meningkatkan kemampuan mengidentifikasi akor musik, guru menggunakan istilah ‘Tupatma’ yang merupakan sebuah teknik untuk menentukan akor dengan menggunakan simbol angka Romawi I, IV, dan V. Teknik ‘Tupatma’ dalam tangga nada mayor memiliki unsur nada seperti terlihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Unsur Akor ‘Tupatma’
Akor I IV V
Unsur nada 5 3 1
1 6 4
2 7 5
Dalam menerapkan teknik ‘Tupatma’,
peserta didik setidaknya harus memiliki bekal kemampuan awal, yaitu tangga nada yang kemudian dikembangkan menjadi akor. Akor adalah paduan nada yang mengandung tiga nada atau lebih, baik dengan menambahkan ataupun mengulangi salah satu nada yang terkandung dalam triad (Banoe, 2003b).
Langkah-langkah untuk menentukan akor dengan teknik ‘Tupatma’ dimulai dengan menentukan satu lagu yang hendak diaransemen. Satu komposisi lagu biasanya terangkai atas ruas-ruas birama, dan pada setiap ruas birama berisi notasi dengan sejumlah hitungan tertentu. Langkah-langkah penerapannya adalah dengan mencermati kecenderungan notasi pada tiap-tiap birama lagu: 1. Notasi yang memiliki kecenderungan pada
nada do (1), mi (3), dan atau sol (5) diberikan akor I.
2. Notasi yang memiliki kecenderungan pada nada fa (4), la (6), dan atau do (1) diberikan akor IV.
3. Notasi yang memiliki kecenderungan pada nada sol (5), si (7), dan atau re (2) diberikan akor V.
4. Menuliskan simbol tingkatan akor I, IV, atau V tersebut di atas melodi lagu, pada birama yang terkait.
Berikut ini adalah contoh mengidentifikasi akor dengan Teknik ‘Tupatma’.
IBU KITA KARTINI
D = 1, 4/4 WR. Supratman
Gambar 1. Notasi Lagu “Ibu Kita Kartini” (Siagian, 1976).
Apabila seluruh melodi lagu telah ditentukan akornya secara tepat maka hasilnya akan dapat dimainkan dengan alat musik harmonis, seperti gitar atau piano. Cara mengaplikasikannya adalah dengan cara mengubah simbol tingkatan akor tersebut dengan simbol huruf. Misalnya, jika lagu menggunakan tangga nada mayor natural (C=1) maka akor I adalah C, akor IV adalah F, dan akor V adalah G. Langkah selanjutnya akor tersebut dimainkan sesuai bentuk tekanan akor pada alat musiknya. Gambar 2 dan 3 menunjukkan bentuk tekanan akor pada gitar dan piano.
C F G
Gambar 2. Bentuk Tekanan Akor pada Gitar
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 58
C
F
G
Gambar 3. Bentuk Tekanan Akor pada Piano Untuk melihat sejauh mana efektivitas
metode ‘Tupatma’, diadakan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas ini dipilih materi lagu menggunakan tangga nada mayor. Hal ini sengaja dilakukan agar memberikan efek gembira dan semangat bagi peserta didik dalam mempelajari kompetensi baru yang mendasar. Selain itu juga untuk menyempurnakan muatan materi yang tidak hanya bersifat konseptual, faktual, dan prosedural, namun juga sampai pada tataran metakognitif dalam unsur nilai rasa.
Kemampuan mengidentifikasi akor musik merupakan hal esensial dalam mengembangkan kreativitas di bidang seni musik. Akan tetapi, justru pada aspek inilah peserta didik banyak mengalami masalah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan kompetensi pedagogik maupun profesional guru dalam memfasilitasi pengembangan kreativitas dan soft skill peserta didik melalui bidang seni yang diharapkan bermanfaat bagi kehidupannya.
Keseluruhan proses kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini dibingkai atau didesain dengan menggunakan model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction Model). Model pembelajaran langsung merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu peserta didik dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Jadi sifat model pembelajaran langsung menempatkan peran guru yang sangat dominan. Untuk itu, guru harus bisa menjadi model yang menarik bagi peserta didik. Hunaepi, dkk. (2014) menyatakan bahwa model pembelajaran langsung merupakan salah satu model yang berorientasi pada peran guru yang aktif, baik sebagai mediator, motivator ataupun fasilitator.
Meskipun berpusat pada guru, untuk keberhasilan pembelajaran tetap dituntut keterlibatan secara aktif peserta didik secara fisik dan mental. Karena itu guru harus menjamin terjadinya keterlibatan aktif peserta didik terutama pada setiap langkahnya. Model
pembelajaran langsung menurut Trianto (2007) memiliki 5 (lima) tahap yaitu (1) menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik; (2) mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan; (3) membimbing pelatihan; (4) mengecek pemahaman dan umpan balik; dan (5) memberi kesempatan pelatihan lanjutan dan penerapan.
Penelitian tindakan kelas ini mengambil subjek peserta didik kelas X Boga 1 SMK Negeri 2 Godean. Sleman, DIY. Pemilihan peserta didik kelas ini didasarkan pada pertimbangan kurangnya kemampuan awal yang dimiliki peserta didik dalam bidang seni musik serta rendahnya kemampuan mengidentifikasi akor musik walaupun sudah dapat bermain musik.
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik Kelas X Boga 1 SMK Negeri 2 Godean dalam mengidentifikasi akor musik dengan teknik ‘Tupatma’ yang memiliki kesan mudah dan sederhana melalui model Pembelajaran Langsung. Dalam konteks ini, kemampuan untuk mengidentifikasi akor musik merupakan hal penting dan mendasar dalam proses kreatif aransemen agar dapat menyajikan permainan musik yang bernilai estetis.
METODE PENELITIAN
Subjek pada penelitian penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Godean Sleman pada bulan Febuari 2018 sampai dengan April 2018 adalah peserta didik kelas X Boga 1 yang berjumlah 32 orang. Subjek peserta didik kelas ini dipilih karena capaian hasil belajarnya rendah serta lemahnya motivasi belajar. Identifikasi penyebab pemasalahan ini ada beberapa faktor, yaitu (1) kurangnya pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik dari jenjang pendidikan sebelumnya; (2) terbatasnya alat bantu untuk mendukung proses pembelajaran seni musik; serta (3) kurangnya pengalaman bermusik peserta didik sehingga perlu tahapan proses menyamakan persepsi untuk belajar berkreasi dalam seni musik.
Model penelitian tindakan kelas ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart (1988). Pelaksana-annya direncanakan berlangsung paling sedikit dua siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan prosedur masing-masing siklus melalui 4 (empat) tahap, yaitu tahap perencanaan
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 59
(planning), pelaksanaan (acting), observasi (observating), dan refleksi (reflecting).
Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis campuran (mixed methods) antara kuantitatif dan kualitatif. Karenanya analisis bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran, serta aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran serta fenomena untuk mengurai permasalahan pembelajaran (Sugiyono, 2014).
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi (1) observasi yang melibatkan asesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang bertindak sebagai kolaborator. Perannya adalah untuk membantu dalam pencatatan fenomena yang terjadi selama proses pembelajaran, serta mengawasi perubahan pada diri peserta didik yang meliputi keaktifan, hasil belajar, suasana proses pembelajaran, dan perubahan pada guru selama proses kegiatan pembelajaran; (2) angket berisi tanggapan peserta didik terhadap aktivitas pembelajaran; (3) dokumentasi berupa foto aktivitas peserta didik dan guru sebagai salah satu satu bukti keaktifan pembelajaran; dan (4) lembar penilaian unjuk kerja untuk mendeteksi perubahan kemampuan peserta didik; serta (5) catatan lapangan untuk mendukung data.
Pengolahan data dengan menggunakan statistik sederhana rerata. Proses perhitungan dilakukan dengan menjumlah nilai yang diperoleh peserta didik, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh nilai rata-rata. Hasil rerata ini dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan SMKN 2 Godean kelas X, yaitu 75.
HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Data penelitian berupa hasil tes unjuk kerja, data hasil observasi berupa pengamatan pengelolaan penerapan teknik Tupatma dengan model pembelajaran langsung yang dilakukan pada setiap siklus.
Siklus I Kegiatan pada Siklus I dimulai dari tahap
perencanaan yang meliputi persiapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran, penyusunan materi, persiapan media, alat evaluasi pembelajaran yang berupa soal tes unjuk kerja, dan alat-alat pengajaran yang mendukung berupa instrumen musik
harmonis. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi aktivitas guru dan peserta didik.
Langkah-langkah yang dilakukan pada model pembelajaran langsung diuraikan berikut ini. 1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan mempersiapkan peserta didik dengan mempelajari materi sebagai prasyarat belajar akor sebagai bagian dari proses identifikasi dengan alat musik minimal pianika untuk berlatih penjarian akor.
2. Guru mempresentasikan pengetahuan peserta didik dalam menerapkan teknik ‘Tupatma’, yaitu menempatkan akor I, IV, dan V dalam melodi lagu dan mendemonstrasikan keterampilan dalam menerapkan akor dalam alat musik harmonis piano. Untuk tujuan efektivitas, pada tahap ini peserta didik turut mencoba di tempat masing-masing menggunakan alat musik bantu pianika.
3. Guru membimbing pelatihan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pembimbingan dalam aspek kognitif dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menentukan simbol akor dalam lagu model secara bergilir. Aspek afektif ditanamkan melalui tahap memperdengarkan keselarasan bunyi harmoni alat musik sesuai progres akor hasil pekerjaan peserta didik. Untuk merangsang keaktifan, dalam proses pembimbingan pada aspek kognitif diberikan penghargaan bonus skor nilai kepada setiap peserta didik yang maju ke depan kelas untuk menentukan akor lagu model di papan tulis, dengan mempertimbangkan ketepatan akor yang diberikan. Pembimbingan dalam aspek psikomotorik dilaksanakan dengan memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk memainkan lagu model yang telah diberi simbol akor menggunakan alat musik harmonis piano atau gitar. Hasil capaian keterampilannya dituliskan pada catatan peserta didik sebagai umpan balik dan catatan guru untuk kepentingan penilaian.
4. Guru mengecek pemahaman peserta didik dan pemberian umpan balik. Dalam hal ini peserta didik diminta mengidentifikasi akor lagu ‘Ibu Kita Kartini’ ciptaan WR. Supratman dengan cara membubuhkan simbol akor I, IV atau V pada setiap birama lagu. Hasil penentuan akor tersebut dimainkan pada alat musik piano secara individu dengan bimbingan guru.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 60
5. Guru memberi kesempatan pelatihan lanjutan dan penerapan. Pada tahap terakhir ini peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan latihan secara mandiri di luar waktu kegiatan belajar mengajar. Bagi peserta didik yang sudah menguasai, diberikan pengayaan berupa latihan lagu Nusantara lainnya.
Pengamatan keaktifan peserta didik dan guru dilaksanakan bersamaan selama proses belajar mengajar berlangsung. Hasil pengamatan mengindikasikan adanya keaktifan dan respon yang baik pada diri peserta didik serta semangat guru dalam memfasilitasi pembelajaran.
Pada tahap akhir, peserta didik diberi tes unjuk kerja yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mereka dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan.
Hasil pembelajaran pada Siklus I digambarkan dalam Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Distribusi Nilai Tes pada Siklus I
No N No N No N No N 1 72 9 76 17 78 25 78
2 78 10 78 18 74 26 78 3 72 11 81 19 78 27 72 4 78 12 76 20 76 28 78 5 80 13 76 21 74 29 78 6 76 14 78 22 72 30 84 7 80 15 78 23 74 31 82 8 78 16 72 24 70 32 80
Jumlah total nilai: 2455 Jumlah Skor Maksimal Ideal: 3200
Rata-rata Skor Tercapai: 76,72 (72 % mencapai Ketuntasan Belajar Minimal)
Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa dengan
penerapan teknik ‘Tupatma’ melalui model pembelajaran langsung diperoleh nilai rata-rata hasil belajar peserta didik sebesar 76,72. Dalam pra-siklus, capaian rerata hasil belajar peserta didik adalah 64,31. Dengan demikian terjadi kenaikan nilai rerata sebesar 12,41 dari kondisi pra-siklus.
Bila dilihat dari persentase ketuntasan belajar, nilai rerata hasil belajar peserta didik belum mencapai 75%. Hal ini berarti masih diperlukan adanya perbaikan dengan tindakan lanjutan (siklus 2) agar tercapai Ketuntasan Belajar Minimalnya. Kondisi tidak ideal ini terjadi karena kurangnya kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi baru dengan level kognitif tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Selain itu, ditemukan adanya kelemahan lain dalam hal pembimbingan
keterampilan, yaitu tidak semua peserta didik dapat terlayani dengan baik karena satu guru harus melayani praktik secara individu terhadap 32 peserta didik dengan keterbatasan waktu.
Siklus II Tahap perencanaan pada Siklus II
dipersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran 2, penyusunan materi, persiapan media, alat evaluasi pembelajaran yang berupa soal tes unjuk kerja dan alat-alat pengajaran pendukung berupa instrumen musik harmonis. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi aktivitas guru dan peserta didik.
Tahap kegiatan dan pelaksanaan Siklus II dilaksanakan dengan tetap mengacu pada rencana pembelajaran dan memperhatikan revisi dari Siklus I sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus sebelumnya tidak terulang kembali. Kerjasama dengan kolaborator lebih ditingkatkan untuk menemukan solusi bagi perbaikan proses pembelajaran pada Siklus II. Pengamatan oleh kolaborator dilaksanakan selama berlangsungnya proses belajar mengajar.
Langkah-langkah pembelajaran pada Siklus II masih tetap sama dengan Siklus I. Perbedaannya terletak pada materi lagu dan teknik pelatihan yang diuraikan berikut ini. 1. Guru menyampaikan tujuan pembejaran dan
mempersiapkan peserta didik. Guru mengajak peserta didik mempersiapkan diri dengan mempelajari materi sebagai prasyarat belajar dalam mengidentifikasi akor musik sebagai bagian dari proses aransemen, serta mempersiapkan alat musik harmonis pendukung termasuk pianika untuk berlatih teknik penjarian akor.
2. Guru mempresentasikan pengetahuan teknik ‘Tupatma’, yaitu menempatkan akor I, IV, dan V pada setiap birama lagu serta mendemonstrasikan keterampilan dalam menerapkan akor pada alat musik piano. Agar optimal pemahamannya, pada tahap ini peserta didik turut mencoba di tempat masing-masing menggunakan alat musik bantu pianika.
3. Guru membimbing pelatihan yang meliputi aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Pembimbingan dalam aspek kognitif dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menentukan simbol akor pada lagu model secara bergilir. Untuk merangsang keaktifan, setiap peserta didik yang berkontribusi
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 61
menentukan akor dengan simbol yang tepat pada lagu model di papan tulis diberikan bonus skor nilai sebagai penghargaan. Untuk pembimbingan pada aspek afektif diberikan dalam bentuk mencocokkan bersama keharmonisan bunyi yang dihasilkan melalui alat musik piano berdasarkan progres akor hasil pekerjaan peserta didik. Sedangkan untuk bimbingan aspek psikomotor dilaksanakan dengan memberi kesempatan kepada peserta didik memainkan lagu model yang telah diberi simbol akor dengan tepat. Setiap progres keterampilannya dicatat pada buku peserta didik sebagai umpan balik dan catatan guru untuk kepentingan penilaian.
4. Guru mengecek pemahaman peserta didik dan pemberian umpan balik. Dalam hal ini peserta didik diminta untuk mengidentifikasi akor lagu ‘Satu Nusa Satu Bangsa’ ciptaan L. Manik dengan cara membubuhkan simbol akor I, IV atau V pada setiap birama lagu. Hasil penentuan akor tersebut dimainkan pada alat musik piano secara individu dengan bimbingan guru.
5. Guru memberi kesempatan pelatihan lanjutan dan penerapan. Pada tahap terakhir ini peserta didik diberi kesempatan melakukan latihan secara mandiri di luar waktu kegiatan belajar mengajar dengan mentor teman yang lebih menguasai.
Pengamatan keaktifan peserta didik dan guru dilaksanakan selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pada tahap akhir, peserta didik diberi tes unjuk kerja yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Hasil pembelajaran pada Siklus II digambarkan dalam Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Distribusi Nilai Tes pada Siklus II No N No N No N No N 1 81 9 77 17 82 25 83 2 84 10 81 18 82 26 82 3 82 11 92 19 80 27 79 4 82 12 85 20 81 28 81 5 82 13 82 21 81 29 79 6 84 14 83 22 76 30 85 7 82 15 82 23 79 31 83 8 81 16 80 24 81 32 82
Jumlah total nilai: 2616 Jumlah Skor Maksimal Ideal: 3200
Rata-rata Skor Tercapai: 81,75 (100 % mencapai Ketuntasan Belajar Minimal)
Hasil pembelajaran pada Siklus II menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata prestasi belajar peserta didik adalah 81,75 yang berarti angka ini berada di atas kriteria ketuntasan belajar minimal SMKN 2 Godean untuk mata pelajaran Seni Budaya dengan standar nilai 75. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan belajar tercapai 100%.
Skor yang diperoleh menggambarkan tingginya tingkat penguasaan peserta didik dalam mengidentifikasi akor lagu menggunakan teknik ‘Tupatma’, yaitu prestasi belajar peserta didik lebih mengalami peningkatan pada Siklus II dari pada Siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dimungkinkan karena peserta didik mulai terbiasa dengan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru.
Pada tahap ini dilakukan juga pengkajian terhadap proses dan tingkat keberhasilannya. Refleksi dan diskusi dilakukan guru dengan kolaborator berkaitan dengan keefektifan keseluruhan proses belajar mengajar. Kelemahan yang terjadi dalam Siklus I telah diatasi dengan baik. Jika dalam Siklus I tidak semua peserta didik terlayani dengan baik oleh satu guru karena keterbatasan waktu. maka dalam Siklus II ditambahkan strategi pelatihan model mentoring. Dalam proses pelatihan keterampilan dipilih 2 (dua) orang peserta didik mahir piano dan 2 (dua) peserta didik mahir gitar untuk menjadi mentor bagi peserta didik yang lain. Istilah ‘mahir’ di sini diartikan peserta didik telah menguasai permainan alat musik harmonis pada lagu terkait.
Berdasarkan hasil observasi, selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, persentase pelaksanaan untuk masing-masing aspek cukup besar. Peserta didik aktif dan tampak antusias selama proses belajar mengajar berlangsung. Kekurangan pada siklus sebelumnya sudah diperbaiki sehingga terjadi peningkatan nilai.
Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik dalam mengidentifikasi akor musik dengan teknik ‘Tupatma’ memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Peningkatan hasil belajar peserta didik antarsiklus yang menggambarkan capaian berdasarkan katagori prestasi belajar dan nilai ketuntasan belajar berdasarkan rata-rata pada masing-masing siklus terlihat dalam Tabel 4 berikut.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 62
Tabel 4. Interval Nilai Antarsiklus
NO INTER- VAL
KATE- GORI
FREKUENSI & PERSENTASE
SIKLUS I SIKLUS II 1 90 – 100 Amat
Baik 0
(0 %) 1
(0.031 %) 2 75 – 89 Baik 23
(0.719 %) 31
(0.969 %) 3 60 – 74 Cukup 9
(0.281 %) 0
(0 %) 4 0 - 59 Kurang 0
(0 %) 0
(0 %) Capaian nilai hasil belajar bila disajikan
dalam bentuk grafik ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Capaian Nilai Hasil Belajar
Dari grafik di atas terlihat bahwa terdapat
peningkatan prestasi belajar peserta didik dalam memahami materi pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada Siklus I dan Siklus II. Peningkatan prestasi tersebut tidak hanya berupa peningkatan dalam nilai rerata namun juga pada ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal. Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal SMK Negeri 2 Godean ditetapkan dengan nilai 75. Nilai ketuntasan belajar berdasarkan nilai rerata pada tiap-tiap siklus disajikan dalam Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Ketuntasan Belajar Berdasarkan Nilai Rerata
Siklus Nilai
Rerata Ketun-tasan Keterangan
I 76,72 72 %
Menunjukkan adanya peningkatan dalam nilai rerata dari sebelum metode diterapkan, namun ketuntasan masih di bawah standar, yaitu 75
II 81,75 100 %
Menunjukkan adanya peningkatan dari siklus sebelumnya baik dari nilai rata-rata maupun ketuntasan.
Ketuntasan belajar berdasarkan nilai rata-rata pada Siklus I dan Siklus II ditunjukkan dalam bentuk grafik pada Gambar 4 berikut.
Gambar 4. Ketuntasan Belajar
Berdasarkan analisis data, aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar mengidentifikasi akor musik dengan teknik ‘Tupatma’ pada setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar peserta didik yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata peserta didik pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik dalam mengidentifikasi akor musik dengan teknik ‘Tupatma’ memberi dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
Sebagaimana tujuan penelitan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi akor musik dengan teknik ‘Tupatma’, maka pendekatan penelitian ini menggunakan perpaduan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan campuran ini menggambarkan data prestasi belajar, perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak menghubungkan perilaku yang diteliti dengan variabel lainnya ataupun menguji atau menjelaskan penyebab sistematisnya, namun berusaha menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat.
Aktivitas peserta didik yang paling dominan adalah mengikuti proses belajar dengan antusias, keaktifan dalam mengerjakan tugas mengidentifikasi akor musik, dan meningkatnya motivasi untuk mencoba hasil penentuan akor lagu dalam alat musik harmonis piano. Guru juga aktif dalam menerapkan teknik ‘Tupatma’ melalui model pembelajaran langsung.
Analisis data yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 63
terhadap hasil pembelajaran. Pengalaman estetis yang ditawarkan guru sebagai umpan balik terhadap hasil mengidentifikasi akor musik menjadi nilai tambah dari proses belajar mengajar ini, sehingga pelajaran seni budaya langsung menyentuh pada esensinya, dan bukan hanya menjadi pelajaran teori semata.
Selama penelitian berlangsung terdapat pula beberapa hal yang perlu diperhatikan. Secara keseluruhan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran baik. Namun karena keterbatasan waktu dan ketersediaan alat, guru masih kurang leluasa dalam memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Merujuk pada Endarti (2019) yang menyarankan penerapan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) untuk mengatasi masalah ini, maka peserta didik dapat tetap terlayani semua, yaitu dengan cara mengefektifkan mentoring dalam kelas.
SIMPULAN
Fenomena rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran Seni Budaya khususnya pada aspek musik perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang intensif. Inovasi pembelajaran mutlak diperlukan untuk menemukan strategi, model dan teknik pembelajaran yang tepat, efektif dan kreatif. Penerapan teknik ‘Tupatma’ dalam mengidentifikasi akor musik diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh guru Seni Budaya khususnya dalam aspek musik untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang berdampak pada hasil belajar mereka.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan atau sumbangan terhadap pengembangan pembelajaran seni budaya di sekolah untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada pendidik untuk dapat mengembangkan inovasi
pembelajaran dalam bentuk-bentuk lain sebagai bagian penting dalam perjalanan pengembangan profesi guru.
REFERENSI
Banoe, Pono. (2003a). Kamus Musik. Yogya-karta: Kanisius.
Banoe, Pono. (2003b). Pengantar Pengetahuan Harmoni. Yogyakarta: Kanisius.
BSNP (2006). Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Depdiknas, 2003. Undang-undang R.I Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
Endarti, Rus (2019). Pembelajaran Seni Budaya Melalui Model Pembelajaran Team Assissted Individualization/Bantuan Individual dalam Kelompok (BidaK). Jurnal Wuny. Vol. 1, No.
2/2019. Diakses dari: https://journal.uny.ac.id/index.php/wuny/article/view/27581
Hamid, Moh. Soleh (2013). Metode Edutainment. Yogyakarta: Diva Press.
Hunaepi, dkk. (2014). Model Pembelajaran Langsung “Teori dan Praktik”. Mataram: Duta Pustaka Ilmu.
Kemmis, S. and McTaggart, R. (1988). The Action Research Reader. Victoria: Deakin University Press.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016.
Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Siagian, M.P. (1976). Indonesia yang Kucinta. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Sugiyono (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Edisi ke-5. Bandung: Alfabeta.
Trianto. (2007). Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 64
PENGGUNAAN SHAPES TOOLS PADA MICROSOFT WORD UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGAMBAR COMIC STRIPS
SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 PACITAN
THE USE OF SHAPES TOOLS IN MICROSOFT WORD TO IMPROVE THE EIGHTH GRADERS’ ABILITY IN DRAWING COMIC STRIPS
IN SMP NEGERI 1 PACITAN
Ninik Setyawati1 SMP Negeri 1 Pacitan [email protected]
ABSTRACT
Students’ boredom of drawing comic strips using manual techniques and the constraining condition of digital drawing devices are the results of problem identification that bring about the conduct of the current research. Hence, the research question proposed is how students’ ability in drawing comic strips can be improved by introducing them the ‘shapes tools’ available in Microsoft Word. Classroom action research of Kemmis and McTaggart model (1990) is employed to answer the research question with the research subjects of the eighth graders of SMP Negeri 1 Pacitan involved in two research cycles for three months comprising four steps in each cycle, namely (1) planning, (2) implementing, (3) observing, and (4) reflecting. Research results demonstrate that in pre-cycle condition, the average score of comic strips drawing skill is below the score of minimum mastery criteria. Having been introduced with shapes tools of Microsoft Word in research cycle 1 and 2, the average score of students’ drawing skill and the classical mastery score increase significantly. The use of ‘shapes’ and ‘shapes styles’ offers some good points in color processing: the work resembles a three-dimensional form, the process is fast, the work is easy to edit and to duplicate, the file size is small, and the work is relatively equivalent to graphic applications.
Keywords: shapes, drawing skill, Microsoft Word, comic strips.
ABSTRAK
Kejenuhan siswa dalam menggambar komik dengan teknik manual dan keterbatasan spesifikasi perangkat menggambar digital merupakan hasil identifikasi masalah yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana kemampuan siswa dalam menggambar comic strips ditingkatkan melalui pengenalan shapes tools yang tersedia pada Microsoft Word. Masalah ini dijawab melalui penelitian tindakan kelas model Kemmis dan McTaggart (1990), dengan tujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam menggambar comic strips menggunakan shapes tools pada Microsoft Word. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Pacitan. Penelitian dilaksanakan pada 2 (dua) siklus selama 3 (tiga) bulan dengan empat tahap pada setiap siklus, yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi prasiklus, rata-rata nilai keterampilan menggambar comic strips berada di bawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimal. Setelah shapes tools dikenalkan kepada siswa pada siklus 1 dan 2, nilai rata-rata keterampilan siswa dan ketuntasan klasikal naik secara signifikan. Kelebihan yang diperoleh dari penggunaan shapes dan shapes style
1 Ninik Setyawati adalah pengajar di SMPN 1 Pacitan yang menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada Pendidikan Seni Rupa, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis berminat/menggeluti bidang Seni Budaya cabang Seni Rupa yang dipadukan dengan teknologi informasi komunikasi. Karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan antara lain “Peningkatan Prestasi melalui Belajar Mandiri Menggunakan Model ‘Forte’ pada Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 1 Pacitan” Tahun Pelajaran 2017/2018”.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 65
dalam mengolah warna adalah karya menjadi berkesan tiga dimensi, prosesnya cepat, mudah untuk diedit maupun digandakan, ukuran file kecil, dan hasil karya relatif setara dengan aplikasi grafis.
Kata kunci: shapes, kemampuan menggambar, Microsoft Word, comic strips.
PENDAHULUAN
Pembelajaran Seni Budaya dalam kurikulum 2013 dirumuskan mencakup studi karya yang terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang pembelajarannya dirancang berbasis aktivitas dan apresiasi terhadap hasil karya dari studi dan praktik seni budaya. Sesuai dengan Permendikbud No.24 Tahun 2016, materi yang diterapkan salah satunya adalah menggambar komik, termasuk kompetensi cabang seni rupa yang diajarkan pada semester 2 kelas VIII terdapat pada kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik, dan pada kompetensi dasar 4.4, yaitu menggambar komik dengan berbagai teknik. Pencapaian pembelajaran comic strips yang diharapkan adalah memahami konsep komik, unsur-unsur komik, jenis komik, media, teknik, dan prosedur menggambar komik, dan menerapkan pengetahuan praktis dan teoretis tersebut dalam praktik menggambar komik dengan teknik digital.
Menggambar komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dalam bentuk buku, cerita pendek, bahkan ada yang dibuat dalam selembar kertas saja (Kemdikbud, 2017:138). Komik merupakan gambar-gambar dan lambang lain yang saling terjukstaposisi (bersebelahan) dalam urutan tertentu yang bertujuan memberikan informasi dan tanggapan estetika dari pembaca, dan komik memanfaatkan ruang dalam media gambar untuk meletakkan gambar demi gambar sehingga membentuk alur cerita (McCloud, 2008). Berdasarkan bentuknya, komik terdiri dari lima jenis, yaitu (1) komik strips (comic strips), komik yang hanya terdiri dari beberapa panel saja dan biasanya muncul di surat kabar atau majalah; (2) buku komik (comic book), komik yang disajikan dalam bentuk buku yang tidak merupakan bagian dari media cetak lainnya; (3) novel grafis (graphic novel), komik yang memiliki tema-tema yang lebih serius dengan panjang cerita hampir sama dengan novel dan ditujukan bagi pembaca dewasa, bukan anak-anak; (4) komik kompilasi, merupakan
kumpulan beberapa judul komik dari komikus yang berbeda; dan (5) komik online (web comic), komik yang menggunakan media internet dalam publikasinya (Maharsi, 2011). Materi gambar komik yang dipelajari siswa berupa gambar comic strips. Menurut Nurgiyantoro (2013), comic strips merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja namun sudah menampilkan suatu gagasan utuh. Comic strips merupakan komik pendek yang terdiri dari beberapa panel dan biasanya muncul di surat kabar, bertema humor, dan bergaya kartun karikatur. Dalam menggambar komik, elemen-elemen yang perlu dipelajari adalah (1) panel; (2) sudut pandang; (3) parit; (4) balon kata; (5) efek; (6) ilustrasi; (7) ukuran gambar; (8) cerita; (9) splash; dan (10) garis gerak (Tim Abdi Guru, 2017).
Teknik menggambar komik bisa dilakukan melalui teknik manual, teknik digital, maupun penggabungan antara teknik manual dan digital. Langkah-langkah atau prosedur kerja dalam menggambar komik adalah (1) menentukan gagasan/tema cerita; (2) merancang karakter tokoh komik; (3) mendeskripsikan watak tokoh; (4) merancang alur cerita; dan (5) menggambar sesuai alur cerita (Tim Abdi Guru, 2017). Untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam menggambar dengan teknik manual, guru dapat mengenalkan siswa dengan menggunakan teknik digital dalam menggambar komik. Melalui teknik digital, diharapkan siswa tertarik dalam berkarya sehingga menghasilkan karya yang lebih baik daripada sebelumnya. Akan tetapi, untuk menggambar dengan teknik digital diperlukan aplikasi khusus dan spesifikasi komputer lebih besar, seperti program coreldraw, adobe photoshop, adobe illustrator, dan program-program grafis lainnya. Hal ini menjadi kendala bagi guru dalam mengajarkan teknik digital kepada siswa terutama pengadaan aplikasinya, yang membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi, sementara laptop siswa maupun komputer sekolah tidak mendukung untuk dilakukan penginstalan aplikasi grafis. Di sisi lain, jika menggunakan aplikasi pada handphone tidak memungkinkan karena
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 66
peraturan sekolah melarang siswa menggunakan dan membawa handphone ke sekolah.
Berkaitan dengan permasalahan di atas, salah satu gagasan terkait pemanfaatan aplikasi yang sudah ada dan dimiliki oleh siswa adalah penggunaan shapes tools yang tersedia pada aplikasi Microsoft Office, yaitu aplikasi pengolah kata (Microsoft Word), pengolah angka (Microsoft Excel), dan aplikasi presentasi (Powerpoint). Ketiga aplikasi ini sangat mudah dioperasikan siswa dalam mengolah data, angka, laporan, dan mengerjakan berbagai tagihan tugas pembelajaran di sekolah. Dalam penelitian tindakan kelas ini, shapes tools yang dimanfaatkan oleh siswa dalam menggambar comic strips adalah yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word.
Shapes merupakan berbagai gambar berbentuk kurva yang dapat disisipkan dalam dokumen. Langkah-langkah dalam menentukan shapes adalah (1) menempatkan titik sisip di lokasi di mana shapes akan ditempatkan; (2) mengklik tab insert; (3) mengklik shapes pada group illustrations; (4) menentukan bentuk shapes yang diinginkan; dan (5) mengklik dan menarik mouse ke arah tertentu sehingga membentuk shapes sesuai dengan bentuk yang diinginkan (Fauzi & Arifin, 2007).
Penggunaan shapes dalam menggambar komik strips merupakan pemanfaatan media shapes tools yang terdapat pada Microsoft Office, khususnya Microsoft Word yang sebelumnya hanya digunakan sebagai media untuk menyisipkan bentuk geometris seperti bentuk garis lurus (lines), persegi (rectangle), lingkaran (curve), segitiga (triangle), anak panah (arrow), berdasarkan kebutuhan dalam pengetikan, pembuatan laporan, dan sebagainya. Icon-icon shapes yang digunakan dalam pembuatan gambar antara lain: (1) lines, yaitu berbagai jenis garis, curve, freeform, dan sebagainya; (2) basic shapes, yaitu icon bentuk dasar seperti bentuk lingkaran, segitiga, persegi, kubus, tabung, dan sebagainya; (3) block arrow, yaitu berbagai icon anak panah; (4) flowchart, yaitu bentuk alur bagan; (5) callouts, yaitu berbagai bentuk balon dialog; dan (6) star and banner, yaitu berbagai bentuk bintang dan banner.
Shapes yang sudah disisipkan ke dalam dokumen masih dapat dimodifikasi dengan berbagai macam pilihan. Pemilihan warna pada shapes adalah dengan memilih salah satu fitur pada shapes styles, yaitu (1) picture; (2) gradient; (3) texture; dan (4) pattern. Untuk
memperbaiki garis atau outline di sekitar shape, dapat dilakukan dengan memilih warna, ketebalan, atau tanda hubung. Beberapa pilihan dapat mempercantik shape, banyak juga pilihan yang memberi efek 3D yang dapat disesuaikan dengan mengklik “3-D Options” di bagian bawah menu (Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi, 2017:22).
Identifikasi terhadap macam-macam shapes icon menemukan adanya dua icon yang menyerupai icon freehand pada aplikasi Coreldraw, yaitu icon curve dan freeform. Setelah dilakukan uji coba dalam menggambar, dan kedua icon tersebut bisa digunakan untuk membuat objek tokoh komik, maka shapes dimanfaatkan sebagai aplikasi alternatif kebaruan dalam menggambar komik, walau dikenal umum bukan sebagai aplikasi menggambar digital. Penggunaan shapes ini diharapkan dapat menjadi pengalaman baru bagi siswa dalam menggambar komik digital, dan sebagai aplikasi alternatif menggambar yang prosesnya cepat, mudah diedit, mudah digandakan, ukuran file-nya kecil, dan hasil karyanya relatif setara dengan aplikasi grafis.
Penggunaan shapes dalam menggambar comic strips juga merupakan perwujudan dari keinginan untuk mencoba perangkat lunak yang bersifat sederhana tetapi dapat menghasilkan karya gambar yang relatif setara dengan perangkat lunak untuk menggambar digital yang sebenarnya. Jenis comic strips dipilih karena merupakan salah satu jenis komik yang disukai anak-anak. Selain itu, comic strips merupakan karya komik yang terdiri dari beberapa bagian, memiliki jalinan cerita singkat, bisa bersambung dengan mengambil cerita yang menghibur.
Prosedur atau langkah dalam menggambar comic strips menggunakan shapes meliputi langkah-langkah (1) menulis ide cerita dari pengalaman pribadi atau imajinasi sendiri; (2) merancang cerita dalam bentuk sketsa (storyboard) menjadi 3-6 panel atau lebih; (3) memindahkan storyboard pada icon pengolah gambar; (4) membuat bagian atau panel cerita; (5) membuat judul dan teks dialog pada panel; dan (6) menggabungkan panel cerita sesuai jalan cerita yang dibuat. Pembuatan comic strips dimulai dari pembuatan storyboard yang diaplikasikan pada Microsoft Word. Pembuatan sketsa bisa dilakukan secara manual dan outline-nya dijiplak dengan teknik digital.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 67
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis dan McTaggart (1990) dengan perangkat yang terdiri dari empat komponen, yaitu plan (perencanaan), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Keempat komponen berupa untaian tersebut dipandang sebagai satu siklus, yang merupakan putaran kegiatan dari keempat komponen tersebut. Hanya saja, komponen tindakan dan pengamatan dijadikan satu kesatuan waktu, karena pada kenyataannya ketika tindakan dilaksanakan, pengamatan juga harus dilaksanakan (Kusumah & Dwitagama, 2010).
Mengacu kepada model Kemmis dan McTaggart tersebut, kegiatan action dan observation dilaksanakan dalam waktu yang sama dan merupakan dua kegiatan yang tidak dipisahkan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, catatan lapangan, dan angket. Sumber data untuk teknik pengumpulan data ini adalah hasil menggambar siswa, catatan kejadian pada saat pembelajaran, dan respon atau jawaban yang diberikan oleh siswa terhadap angket yang dibagikan terkait pembelajaran.
Pada teknik observasi, dikembangkan instrumen yang berisi ceklis daftar pengamatan, yaitu keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, gagasan, atau pendapat dan sikap dalam melakukan proses menggambar. Hasil akhir gambar dengan teknik digital terutama difokuskan kepada pengolahan warna, efek gelap terang, dan bayangan. Refleksi guru dilakukan setelah observasi dengan melihat video rekaman selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan video tutorial yang dibuat oleh guru dalam menggambar komik menggunakan shapes tools.
Pada Gambar 1 terlihat model penelitian tindakan kelas oleh Kemmis & McTaggart (1990) dengan langkah (1) melakukan perencanaan (planning) tindakan yang meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu melaksanakan (2) tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Jika siklus 1 belum berhasil, maka dilakukan proses tahapan perencanaan yang direvisi (revised plan) hingga refleksi (reflection) pada siklus 2 dan seterusnya sampai tercapai ketuntasan dan peningkatan hasil belajar.
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII
E pada SMP Negeri 1 Pacitan yang berjumlah 31 siswa, terdiri dari 17 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Dari 9 (sembilan) kelas VIII yang ada, kelas VIII E memperoleh nilai terendah dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, siswa pada kelas ini dipilih sebagai subjek penelitian. Di samping itu, identifikasi masalah yang dilakukan juga merujuk pada adanya kejenuhan siswa dalam menggambar komik dengan teknik manual yang berdampak pada nilai rendah yang diperoleh siswa. Kurang mendukungnya spesifikasi komputer untuk praktik menggambar dengan teknik digital turut pula menyumbang munculnya masalah. Pengenalan pemanfaatan shapes tools pada Microsoft Word sebagai aplikasi yang digunakan untuk menggambar comic strips merupakan tindakan yang dipilih untuk dilakukan oleh guru untuk mengatasi permasalahan di kelas ini.
Penelitian dilakukan selama tiga bulan mulai dari pertengahan bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan April 2020. Tahapan kegiatan penelitian terdiri dari prasiklus, siklus 1, dan siklus 2, seperti terlihat pada jadwal kegiatan penelitian pada Tabel 1.
Gambar 1. Siklus PTK Kemmis & McTaggart
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 68
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian
HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Prasiklus Pada observasi prasiklus ditemukan
adanya kelemahan siswa dalam hal membaca buku siswa dan sumber belajar lain (literasi), keaktifan dalam mengajukan pertanyaan, pendapat atau gagasan, dan penyelesaian hasil akhir gambar comic strips dengan teknik manual. Refleksi diri juga yang dilakukan guru pada tahap ini menunjukkan adanya kelemahan guru dalam menyediakan media belajar yang menarik bagi siswa dan dalam pengelolaan kelas.
Pada tahap prasiklus, hasil belajar 31 siswa pada aspek pengetahuan melalui penilaian harian menunjukkan nilai terendah 60, nilai tertinggi 86 dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 78. Rinciannya adalah 22 orang siswa tuntas (70,97%), 9 orang siswa tidak tuntas (29,03%). Perolehan nilai rata-rata ketuntasan klasikal 80,10. Penilaian harian pada aspek pengetahuan dilakukan dengan bentuk soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Kisi-kisi soal meliputi konsep komik; unsur-unsur komik (panel, sudut pandang, parit, balon kata, efek, ilustrasi, ukuran gambar, cerita, splash, dan garis gerak); jenis komik (comic strips, buku komik, novel grafis, komik kompilasi, dan komik online); teknik menggambar (manual dan
digital); media (alat, bahan); dan prosedur menggambar komik.
Rubrik penilaian keterampilan berbasis produk meliputi rancangan storyboard, kreativitas (penguasaan media dan alat), teknik, dan finishing atau penyelesaian akhir. Nilai keterampilan berbasis produk pada tahap prasiklus menunjukkan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 60, sedangkan nilai tertinggi adalah 82. Dalam hal ini, 22 orang siswa tuntas (70,97%) dengan rincian nilai di atas KKM 19,36% sebanyak 6 orang siswa, dan nilai sesuai KKM 51,61% sebanyak 16 orang siswa dengan perolehan nilai rata-rata ketuntasan klasikal 75,16. Persentase siswa yang tidak tuntas sebesar 29,03% untuk 9 orang siswa. Secara ringkas, hal ini terlihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Kompetensi Siswa Kelas VIII E dalam Menggambar Komik pada Tahap Prasiklus
Perolehan Nilai Siswa Prasiklus Pengetahuan 80,10 Keterampilan 75,16 Ketuntasan Klasikal (KKM 78) 70,97%
Dari uraian di atas, dijumpai kelemahan-
kelemahan dalam pembelajaran pada tahap prasiklus, baik pada aktivitas siswa, hasil refleksi diri dari guru, maupun hasil perolehan nilai aspek pengetahuan dan keterampilan. Tindakan revisi perencanaan (revised plan) dilakukan untuk kelanjutan tindakan pada siklus 1.
Siklus 1 Kegiatan siklus 1 dilakukan dengan
langkah (1) Plan, dilaksanakan pada minggu ke-5 bulan Januari 2020 dengan langkah sebagai berikut: penyusunan perangkat RPP, pembuatan lembar observasi, penyusunan soal tes formatif, pembuatan video tutorial dasar menggambar menggunakan shapes, pembuatan rambu-rambu penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan; (2) Action, pelaksanaannya pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan Februari 2020 dengan kegiatan pembelajaran dan penilaian; (3) Observation, dilakukan bersamaan dengan action dengan kegiatan mengumpulkan data selama 2 (dua) kali pertemuan, meliputi data observasi aktivitas siswa, refleksi diri dari guru, dokumentasi, angket, hasil perolehan nilai pengetahuan dan keterampilan.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 69
Hasil observasi siklus 1 pada aktivitas siswa ditemukan kelemahan seperti kurangnya keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, pendapat atau gagasan, dan ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan hasil akhir gambar dengan teknik digital terutama dalam mengolah warna, efek gelap terang, dan bayangan. Refleksi diri juga dilakukan guru terkait kelemahan dalam membuat video tutorial dasar menggambar menggunakan shapes, dan perlunya peningkatan bimbingan kepada siswa.
Hasil belajar pada penilaian harian untuk aspek pengetahuan pada siklus 1 menunjukkan bahwa nilai terendah 76, nilai tertinggi 88, siswa tuntas sebesar 82,16% (pada 26 orang siswa), siswa tidak tuntas 16,13% (pada 5 orang siswa), dengan perolehan nilai rata-rata ketuntasan klasikal 83,87%. Pada penilaian keterampilan berbasis produk, diperoleh nilai terendah 62, nilai tertinggi 82, siswa tuntas 83,87% (sebanyak 26 orang siswa) dengan rincian nilai di atas KKM 67,74% (sebanyak 21 orang siswa) dan nilai sesuai KKM 16,13% (sebanyak 5 orang siswa), dengan perolehan nilai rata-rata ketuntasan klasikal 78,16. Persentase siswa yang tidak tuntas sebesar 16,13% (untuk 5 orang siswa). Hal itu terlihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Kompetensi Siswa Kelas VIII E dalam Menggambar Komik pada Siklus 1
Berdasarkan Tabel 3, pada siklus 1, tercapainya ketuntasan klasikal yang diharapkan pada indikator keberhasilan ada di bawah 85%, yaitu 83,87%, sehingga diperlukan tindakan siklus 2.
Refleksi Siklus 1 Refleksi siklus 1 menemukan kelemahan
dari proses dan hasil menggambar siswa terutama dalam pengolahan warna menggunakan shapes style yang belum maksimal, baik mengolah warna, memberi sentuhan gelap terang, dan bayangan, termasuk pemahaman dan pengolahan elemen-elemen komik yang banyak tidak dikerjakan oleh siswa, sehingga hasil berupa nilai yang sesuai dengan kriteria rubrik penilaian produk masih rendah.
Siklus 2 Kegiatan siklus 2 yang dilakukan meliputi
(1) Plan, yang dilaksanakan pada minggu ke-4
bulan Februari 2020. Berdasarkan kelemahan tindakan siklus 1, langkah yang dilakukan adalah perbaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pembuatan lembar observasi, perbaikan video tutorial menggambar shapes dengan menambah shapes style, dan penyusunan soal tes formatif; (2) Action, pelaksanaannya pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan Maret 2020 dengan kegiatan pembelajaran dan penilaian; (3) Observation, yang pelaksanaannya dilakukan pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan Maret 2020, dengan kegiatan mengumpulkan data yang dilaksanakan pada 2 (dua) kali pertemuan berupa penilaian harian, penilaian keterampilan berbasis produk, penilaian diri, data observasi, catatan lapangan, dokumentasi, maupun angket; (4) Reflection, yang pelaksanaannya dilakukan pada minggu ke-3 bulan Maret 2020 dengan kegiatan mengolah data pada siklus 2.
Hasil observasi siklus 2 pada aktivitas siswa ditemukan terjadinya peningkatan dalam kegiatan literasi. Siswa terlihat aktif bertanya kepada guru, aktif berpendapat atau mengungkapkan gagasan, dan menyelesaikan hasil akhir gambar comic strips dengan teknik digital terutama dalam mengolah warna, efek gelap terang, dan bayangan menggunakan shapes style. Hal ini terjadi setelah siswa mengamati video tutorial menggambar komik menggunakan shapes yang ditayangkan oleh guru. Video yang dirancang oleh guru berisi cara membuat bentuk tokoh komik menggunakan icon curve, mengolah warna dengan shapes fill, membuat background panel, memberi efek gelap terang menggunakan shapes effect dengan menentukan arah cahaya, memberi efek bayangan yang termasuk shapes style, dan memberikan balon percakapan menggunakan callout pada kumpulan icon shapes. Hasil refleksi diri guru pada siklus 1 juga dilaksanakan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus 2 dengan cara lebih meningkatkan bimbingan langsung kepada siswa dalam mengolah warna, efek gelap terang dan bayangan menggunakan shapes style.
Angket minat menggambar comic strips dengan menggunakan shapes terdiri dari 20 (dua puluh) pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa sebagai responden. Pengolahan data kuesioner yang dijawab oleh 31 responden menghasilkan skor terendah 75, skor tertinggi 100, skor mean (rata-rata) sebesar 95, median sebesar 95, dan modus sebesar 95.
Perolehan Nilai Siswa Siklus 1
Pengetahuan 82,16
Keterampilan 78,16
Ketuntasan Klasikal (KKM 78) 83,87%
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 70
Hasil belajar pada penilaian harian untuk aspek pengetahuan pada siklus 2 dari 31 siswa yang mengerjakan diperoleh nilai terendah 77, nilai tertinggi 94, siswa tuntas sebesar 93,55% (29 siswa) dan siswa belum tuntas 6,45% (2 siswa) dengan perolehan nilai rata-rata ketuntasan klasikal 87,55. Nilai terendah keterampilan berbasis produk adalah 76, sedangkan nilai tertinggi 92, kemudian siswa tuntas sebanyak 29 orang atau sebesar 93,55%, siswa belum tuntas sebesar 6,45% untuk 2 orang siswa, dan perolehan nilai rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 88,16. Pada siklus 2 juga dilaksanakan penilaian diri yang telah dikerjakan oleh 31 siswa setelah mereka selesai mengerjakan kompetensi keterampilan berbasis produk. Penilaian diri terdiri dari 10 pertanyaan dengan perolehan modus nilai B (Baik). Tabel 4 menunjukkan hasil belajar siswa pada siklus 2.
Tabel 4. Kompetensi Siswa Kelas VIII E Menggambar Komik pada Siklus 2
Perolehan Nilai Siswa Siklus 2 Pengetahuan 87,55 Keterampilan 88,16 Ketuntasan Klasikal (KKM 78) 93,55% Refleksi Siklus 2
Berdasarkan Tabel 4, persentase ketuntasan belajar aspek pengetahuan dan keterampilan telah mencapai indikator keberhasilan sebesar 93,55%. Penelitian ini dikatakan berhasil karena indikator keberhasilan hasil belajar secara klasikal minimal 85% dari jumlah siswa yang mencapai KKM. KKM telah tercapai, bahkan hasilnya melebihi dari batas minimal ketuntasan klasikal hasil belajar.
Diskusi Pada tahap prasiklus, ditemukan
kelemahan pada aktivitas siswa kelas VIII E dalam melakukan kegiatan literasi membaca buku siswa dan sumber belajar lain. Selain itu, siswa juga pasif dalam bertanya, mengajukan pendapat atau gagasan, dan ada beberapa siswa yang hanya mengerjakan storyboard komik saja tanpa menyelesaikan hasil akhir gambar komik dengan teknik manual. Selain aktivitas siswa, hasil dari refleksi guru juga menunjukkan adanya kelemahan dalam menyediakan media ajar yang menarik bagi siswa, termasuk peranan guru yang kurang dalam pengelolaan kelas.
Prosedur kerja dalam menggambar komik yang dilakukan pada kegiatan prasiklus setelah siswa memahami konsep komik, elemen, jenis, dan tekniknya, adalah memulai kegiatan dengan menulis cerita untuk beberapa adegan, membuat karakter tokoh, dilanjutkan dengan membuat storyboard pada kertas A3, dan proses pewarnaan menggunakan media mix atau campuran antara media basah dan media kering. Cerita ditulis berdasarkan pengalaman siswa sendiri dan mengilustrasikan cerita dalam bentuk storyboard setiap panel sesuai rancangan panel yang dibuat. Rubrik penilaian berupa rancangan storyboard, kreativitas (penguasaan media dan alat), teknik, dan finishing/hasil akhir.
Gambar 2 di atas merupakan karya salah
satu siswa kelas VIII E yang menggunakan teknik manual dengan media mix atau campuran antara media basah dan media kering pada kegiatan prasiklus. Faktor yang menjadi kelemahan pada teknik manual adalah proses pendetailan warna rumit dilakukan karena objek gambar comic strips setiap panel berukuran kecil, terjadi kesulitan dalam memberikan elemen-elemen komik seperti efek, garis gerak, dan pendetailan tokoh sehingga gambar belum maksimal, serta perlu kehati-hatian dalam menuliskan teks pada balon kata. Ukuran balon kata kecil, sedangkan tulisan teks menggunakan tangan harus menyesuaikan dengan area balon kata. Pada praktiknya, ditemukan beberapa siswa dalam membuat storyboard komik tidak
Gambar 2. Karya Siswa dengan Teknik Manual
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 71
melanjutkan dengan proses mewarna, sehingga penilaian hasil akhir (finishing) tidak dilakukan, yang berakibat nilai yang diperoleh kurang.
Respon siswa yang diungkapkan dalam kuesioner (angket) berkaitan teknik manual dalam menggambar komik. Hasilnya menunjukkan 95% siswa memilih alasan bosan dalam mewarna objek dan 95% memilih teknik digital. Dari hasil observasi, siswa mengungkapkan kebosanan, kejenuhan dalam proses mewarna dengan teknik manual, karena merasakan kesamaan teknik pada praktik pembelajaran seni rupa sebelumnya. Alasan lain adalah terjadinya kesulitan dalam membuat dialog komik, karena tulisan harus menyesuaikan area balon kata, besar kecilnya panel, dan ukuran huruf yang ditulis secara manual. Hasil penilaian diri juga sama dengan angket, yaitu siswa lebih senang memilih shapes dalam kegiatan menggambar komik daripada teknik manual. Dari hasil analisis data yang diperoleh dari angket, observasi, dan penilaian diri, dapat disimpulkan bahwa rata-rata siswa lebih senang menggambar comic strips dengan teknik digital daripada dengan teknik manual. Dengan menggunakan shapes, siswa mudah memahami karena dari awal sudah mengenal berbagai shapes icons dan terbiasa menggunakannya, misalnya menyisipkan shapes icons untuk mendukung pemenuhan tugas. Dari kumpulan shapes icons, belum semua dipelajari dan digunakan siswa dalam menyisipkan bentuk dalam teks. Ada dua shapes icons yang belum dipelajari dan dipraktikkan siswa, yaitu icon curve dan freeform. Mengidentifikasi kumpulan shapes icons dan mencoba masing-masing icon telah dilakukan siswa pada siklus 1. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan membuktikan icon mana yang bisa digunakan untuk menggambar bentuk-bentuk bebas, tokoh komik, background, layaknya pada aplikasi grafis.
Untuk memudahkan pemahaman materi dan praktik siswa, tayangan video tutorial menggambar menggunakan shapes dan shapes style disertai demonstrasi langsung dilakukan oleh guru untuk memudahkan siswa dalam praktik menggambar. Tindakan ini dilakukan untuk membangun keingintahuan siswa dan menciptakan suasana senang dalam berkarya sehingga meningkatkan minat belajar dan kemampuan menggambar. Minat belajar yang meningkat diharapkan akan diiringi dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dipelajari. Minat belajar perlu mendapatkan perhatian khusus karena merupakan salah satu
faktor penunjang keberhasilan proses belajar. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat (Slameto, 2010). Winkel (1999) mendefinisikan minat sebagai kecenderungan yang menetap dalam diri subjek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu. Minat pada dasarnya adalah timbulnya keinginan dan kemauan seseorang yang menyatu sehingga gigih dan semangat melakukan sesuatu. Rasa lebih suka dan ketertarikan akan direspon oleh pikiran seseorang untuk melakukan aktivitas sesuai jenis kesukaan tanpa adanya pengaruh atau paksaan, karena dilandasi kesenangan. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Siswa yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut.
Kemampuan dalam belajar berkaitan dengan minat belajar. Kemampuan atau ability adalah bakat yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan secara fisik atau mental yang diperoleh sejak lahir, melalui belajar dan pengalaman (Soehardi, 2003). Menurut Syah (2000) dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kemampuan (kompetensi) merupakan sekumpulan kecakapan yang harus dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas fungsionalnya sehingga menggambarkan hakikat kualitatif dan perilaku yang tampak sangat berarti (Mulyasa, 2003). Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau ability adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang diperoleh sejak lahir yang pada dasarnya bisa diasah. Kemampuan merupakan potensi yang ada berupa kecakapan berusaha dengan diri sendiri. Kemampuan menggambar adalah kapasitas siswa agar bisa menggambar tentang apa yang telah dipelajari untuk mendapatkan pengalaman.
Anak akan belajar dengan baik apabila mempunyai minat belajar dan kemampuan yang besar. Dalam pembelajaran Seni Budaya, ketika menggambar komik dengan menggunakan shapes, siswa yang memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi akan cepat mengingat dan mengerti apa yang ia pelajari. Siswa dengan
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 72
minat yang tinggi dalam menggambar komik menggunakan shapes, akan mendorong dirinya untuk mengetahui secara mendalam kemampuan atau kompetensi yang didapatnya. Siswa yang memiliki minat tinggi terhadap suatu kemampuan, sudah tentu akan selalu berupaya memperbaiki hasil belajarnya. Siswa tersebut akan aktif bertanya jika menemukan kesulitan dalam memahami apa yang dipelajari. Sebaliknya, seorang siswa yang memiliki minat yang rendah pada kemampuan, akan mengikuti proses kegiatan belajar dengan kurang aktif dan akan berdampak pada hasil belajar yang diperolehnya. Dengan demikian siswa dengan minat belajar yang tinggi akan mencapai hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang minat belajarnya rendah. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan mencurahkan perhatiannya secara maksimal. Keaktifan bertanya, mencurahkan gagasan dalam membuat storyboard komik memerlukan minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran menggambar komik. Pengolahan warna pada tokoh dan background panel, memberikan efek gelap terang, efek bayangan dalam mengolah storyboard komik dengan teknik digital menggunakan shapes tools dan shapes style membutuhkan kemampuan menggambar dan minat belajar yang tinggi agar hasil produk komik yang dibuat sesuai dengan rancangan, seperti terlihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3 merupakan salah satu karya produk comic strips dari salah satu siswa kelas VIII E. Kemampuan menggambar menggunakan shapes tools dan shapes style yang telah dipelajari siswa menghasilkan karya yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya, menghasilkan pewarnaan dan efek gambar yang berbeda, sehingga pengalaman yang didapat akan memberikan perasaan senang, minat belajar dan kemampuan menggambar meningkat. Peningkatan minat belajar dan kemampuan menggambar comic strips dengan menggunakan shapes tools dan shapes style menjadikan karya siswa lebih menarik dari storyboard sebelumnya, kreativitas lebih terlihat dari segi pengolahan bentuk tokoh komik, warna, background antarpanel, efek gelap terang tokoh komik, efek bayangan, arah cahaya, dan keterbacaan teks pada balon kata. Dengan demikian, minat belajar dan kemampuan dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal yang belum pernah dilakukan dan akan menghasilkan sesuatu yang baru sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Nasution (1989) mendefinisikan bahwa prestasi belajar merupakan kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Kemampuan menggambar dan minat belajar yang tinggi dalam menggambar comic strips menggunakan shapes akan menghasilkan karya original dari hasil berpikir, merasa, dan berbuat dengan langkah berikut ini, yaitu (a) menulis ide cerita; (b) merancang cerita (storyboard) dalam 3-6 panel; (c) memindahkan storyboard pada icon pengolah gambar; (d) membuat panel cerita; (e) membuat judul dan teks dialog; dan (f) menggabungkan panel cerita sesuai jalan cerita yang dibuat.
Beberapa faktor keunggulan menggambar komik menggunakan shapes tools pada Microsoft Word hingga berdampak dapat meningkatkan kemampuan siswa diidentifikasikan berikut ini. 1. Segi teknik: shapes dikenal siswa sebagai
tools untuk menyisipkan bentuk-bentuk geometris pada aplikasi Microsoft Office. Seluruh siswa belum pernah menggambar bebas menggunakan shapes apalagi mengenal icon curve dan freeform, sehingga pada awal proses menggambar, timbul rasa ingin tahu siswa, dan hampir seluruh siswa merasa senang karena ada pengalaman baru, dan rasa percaya diri timbul setelah bisa menggambar komik dengan teknik digital. Gambar 3. Karya Siswa dengan Teknik Digital
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 73
2. Segi ide cerita: pengalaman bebas dalam menentukan gagasan, ide, atau imajinasi dalam menyusun alur cerita komik menjadikan imajinasi siswa bebas mengalir hingga menghasilkan cerita yang menarik dan original.
3. Segi hasil gambar: proses gambar mudah digandakan, diedit, dan hasil gambar setiap adegan variatif, dapat diberi efek gelap terang pada tokoh, efek bayangan, background pada panel, efek pencahayaan, sebagai proses penyelesaian hasil akhir gambar (finishing). Kelancaran proses menggambar komik yang dilakukan siswa mulai dari pembuatan storyboard manual yang dijiplak dalam teknik digital sampai menghasilkan kompetensi menghasilkan nilai rata-rata baik bahkan sangat baik.
4. Segi tulisan/teks dialog: keterbacaan teks pada balon kata jelas walaupun dengan ukuran font kecil dengan berbagai jenis font baku.
5. Segi pembagian panel: bentuk panel menyesuaikan dengan desain, mudah diedit melalui editpoints, dan jumlah panel mudah dikembangkan.
6. Segi pewarnaan: shapes style membantu mendapatkan warna yang diinginkan, memberi kesan gelap terang, maupun bayangan.
7. Segi waktu: proses pengerjaannya lebih cepat dibandingkan menggunakan teknik manual.
8. Segi pengembangan karya: hasil karya comic strips bisa dicetak, digandakan, dipajang, dipublikasikan pada media surat kabar, majalah, media sosial, dan sebagainya. Hasil karya bisa dipindah atau diaplikasikan ke Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, serta dapat dikembangkan pada gambar lain seperti poster, iklan, ragam hias, dan sebagainya.
SIMPULAN
Kemampuan menggambar comic strips siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Pacitan menjadi meningkat setelah para siswa dikenalkan dengan penggunaan shapes tools pada Microsoft Office. Peningkatan kemampuan ini terlihat dari nilai yang diperoleh siswa pada pra siklus dan dua siklus yang dilalui pada penelitian tindakan kelas. Teknik manual yang selama ini digunakan dalam menggambar komik pada tahap tertentu telah menimbulkan rasa jenuh siswa. Di sisi lain, keterbatasan spesifikasi perangkat menggambar digital juga
membuat proses menggambar comic strips tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan mudah dan menyenangkan. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam menggambar comic strips dapat ditingkatkan melalui pengenalan shapes tools. Fasilitas sederhana dari Microsoft Office ini meskipun tidak untuk menggambar digital, dapat memberikan kemudahan dan kesenangan tersendiri bagi siswa dalam menghasilkan karya comic strips mereka.
Penelitian tindakan kelas selanjutnya seyogianya dapat dilanjutkan dengan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam kegiatan observasi aktivitas siswa dan guru, karena kegiatan observasi pada penelitian ini hanya mengandalkan rekaman video kegiatan pembelajaran dan foto kegiatan penelitian. Penggunaan shapes tools dalam menggambar digital untuk comic strips tetap perlu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menghasilkan karya-karya siswa yang lebih kreatif. REFERENSI
Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi Institut Pertanian Bogor. (2017). Panduan Teknis Microsoft Word 2013 – Bagian 1. Diakses dari http://dsitd.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Modul-Pelatihan-Microsoft-Word-2013.pdf.
Fauzi, A. & Arifin, Johar. (2007). Mengupas Tuntas Microsoft Word 2007. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Kemdikbud. (2017). Seni Budaya SMP/MTs Kelas VIII Edisi Revisi 2017. Jakarta: PT Intan Pariwara.
Kemmis, S. & Mc.Taggart, R. (1990). The Action Research Planner. Victoria: Deakin University Press.
Kusumah, W. & Dwitagama, D. (2010). Mengenal Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT Indeks.
Maharsi, Indiria. (2011). Komik Dunia Kreatif Tanpa Batas. Yogyakarta: Kata Buku.
McCloud, Scott. (2008). Understanding Comics- Memahami Komik (terjemahan S. Kinanti). Jakarta: KPG.
Mulyasa. (2003). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021 | 74
Nasution, S. (1989). Kurikulum dan Pengajaran. Jakarta: PT Bina Aksara.
Nurgiyantoro, Burhan. (2013). Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Permendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta.
Soehardi, Sigit. (2003). Esensi Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Lukman Offset.
Syah, Muhibbin. (2000). Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Tim Abdi Guru. (2017). Seni Budaya untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga.
Winkel, W.S. (1999). Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Jurnal Sendikraf, Volume 2 No 1 Mei 2021| 75
PENULISAN ARTIKEL JURNAL SENDIKRAF
Tim Editorial Jurnal Sendikraf yang terbit dua kali dalam setahun (Mei dan November) mengundang penulis
artikel untuk mempublikasikan tulisan ilmiah sebagai hasil penelitian dan/atau hasil kajian, gagasan
konseptual, aplikasi teori, yang memuat substansi seni, pendidikan seni, dan industri kreatif. Ketentuan
umum yang ditetapkan untuk penulisan diuraikan berikut ini.
1. Artikel belum pernah dipublikasikan sebelumnya oleh media atau jurnal manapun dengan
memberikan pernyataan tertulis bahwa artikel yang dikirimkan tidak mengandung aspek
plagiarisme.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan kaidah yang
berlaku.
3. Artikel ditulis dengan menggunakan Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Sendikraf dan Template
Artikel Jurnal Sendikraf yang memuat ketentuan penulisan artikel secara umum dan khusus yang
dapat diunduh di http://gg.gg/PedomanSendikraf
4. Artikel yang telah memenuhi ketentuan pada pedoman penulisan dan template dapat dikirimkan ke
alamat [email protected]
5. Penulis akan menerima pemberitahuan berkaitan dengan proses yang akan dilalui untuk kepastian
dimuat atau ditolaknya artikel dengan catatan tertentu.
6. Penulis yang mendapatkan pemberitahuan untuk melalukan revisi artikel wajib untuk melakukan
revisi sesuai dengan masukan dan anjuran dari mitra bestari dan tim editorial pada batas waktu yang
diberitahukan sebelum dapat dimuat dalam jurnal.