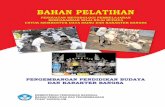radikalisme agama dan tantangan ideologi bangsa
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of radikalisme agama dan tantangan ideologi bangsa
RADIKALISME AGAMA DAN TANTANGAN IDEOLOGI BANGSA
INDONESIA
Studi Wacana Pendirian Negara Islam (Khilafah Islamiyah) di Indonesia pada
Kalangan Mahasiswa Islam FISIP Unhas
RELIGION RADICALISM AND THE CHALLENGES OF INDONESIAN’S
IDEOLOGY
A Study on Islamic State (the Chalipate of Islamiyah) Discourse in Indonesia
among Islamic Student of FISIP Unhas
SKRIPSI
ACHMAD FAIZAL
E41113309
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
RADIKALISME AGAMA DAN TANTANGAN IDEOLOGI BANGSA
INDONESIA
Studi Wacana Pendirian Negara Islam (Khilafah Islamiyah) di Indonesia pada
Kalangan Mahasiswa Islam FISIP Unhas
SKRIPSI
ACHMAD FAIZAL
E41113309
SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN
SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :
NAMA : ACHMAD FAIZAL
NIM : E41113309
JUDUL : RADIKALISME AGAMA DAN TANTANGAN IDEOLOGI BANGSA
(STUDI PANDANGAN MAHASISWA ISLAM TERHADAP WACANA
PENDIRIAN NEGARA ISLAM (KHILAFAH ISLAMIYAH) DI
INDONESIA)
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil
karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila
dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil
karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
Makassar, 01 Januari 2018
Yang menyatakan
ACHMAD FAIZAL
HALAMAN PERSEMBAHAN
Tiada insan yang paling berhak menerima persembahan ini pertama kali melainkan dia adalah
kedua orang tua penulis ; Alm.Zubair Ali & ST.Aminah. Terutama untuk sang Ibu yang tak
pernah jemu menyelipkan doa di sela – sela rutinitas dunianya. Dukungan moril dan materil yang
diberikan selama ini hanyalah bagian terkecil dari wujud kasih sayangnya. Semoga Allah
senantiasa merahmati dan melindungimu.
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmani rahim
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Tiada kata agung yang patut keluar dari lisan ini selain ucapan puji dan syukur atas segala
limpahan Rahmat-Nya yang mewujud kepada tubuh yang sehat, waktu yang sempat serta ilmu
yang bermanfaat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini di
waktu yang tepat. Salam dan taslim tak lupa juga penulis kirimkan kepada baginda Muhammad
SAW, sang pembebas, sang pencerah dan sang tauladan bagi segenap umat manusia, serta
kepada para Sahabat, Tabi’in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah berada di jalan-
Nya.
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik di tingkat kesarjanaan
(S-1) pada Departemen Sosiologi FISIP Unhas. Adapun judul skripsi ini adalah “Radikalisme
dan Tantangan Ideologi Bangsa (studi pandangan mahasiswa islam terhadap wacana pendirian
negara islam (khilafah islamiyah) di Indonesia)”.
Maka melalui kalimat pengantar ini, penulis hendak mengucapan terima kasih yang tiada tara
kepada pihak – pihak yang selama ini berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
Ucapan terima kasih ini terutama penulis berikan kepada Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU,
selaku pembimbing I dan Dr. Mansyur Radjab, M.Si, selaku pembimbing II. Terima kasih atas
segala arahan dan masukannya selama proses penyelesaian naskah skripsi ini.
Ucapan terima kasih juga penulis berikan yang sebesar besarnya kepada :
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Alimuddin Unde, M,Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
3. Dr. Mansyur Radjab, M.Si, selaku Ketua Departemen Sosiologi dan Dr. Ramli AT,
M.Si selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh staf akademik Departemen Sosiologi yang sedikit banyak telah mewariskan ilmu
dan pengalamannya kepada penulis selama kurang lebih 4 tahun penulis menyelami
samudera ilmu di kampus Unhas.
5. Terima kasih kepada saribattang angkatanku SATGAS 13 yang sedikit banyak telah
menjadi wadah bagi pemenuhan kebutuhan ekonomis, psikologis dan biologis penulis
selama menelusuri rimba ilmu pengetahuan di kampus Unhas.
6. Terima kasih kepada KEMASOS yang telah menjadi rumah persinggahan perdana bagi
penulis untuk mengisi bekal pengetahuan dan pengalaman di kampus Unhas. Amanah
menjadi salah satu nahkoda organisasi ini merupakan bekal tak berharga bagi penulis
sebelum mengarungi kehidupan “nyata” kedepannya. Juga kepada para anggota –
anggotanya (senior dan junior) yang menjadi teman berdialektika penulis dalam
mengembangkan wacana - wacana sosiologis, proud of you.
7. Terima kasih buat para ikhwan dan akhwat di KAMMI UNHAS yang menjadi wadah
bagi penulis untuk mengembangkan wawasan keislaman yang progresif, solid dan kritis.
8. Terima kasih juga buat saudara - saudara seiman dalam lingkaran MUJAHID
MULTIDIMENSI yang telah menjadi ruang muhasabah diri bagi penulis selama
menapaki lika – liku kehidupan dunia yang fana ini.
9. Terima kasih buat kawan – kawan MIANGERS 96 yang sedikit banyak mewarnai
kondisi psikologis penulis dalam beberapa bulan terkahir ini. Meskipun secara kuantitas,
usia hubungan kita belum lama, tetapi secara kualitas, sudah cukup disandingkan dengan
hubungan Romeo dan Juliet.
10. WIRA sebagai tangan kanan, SULAIMAN GIBRAN sebagai diplomat ulung dalam
urusan pragmatis, IBNU sebagai konsultan cakar yang handal, BUNG FAISAL & ILO’
sebagai kawan onani pengetahuan, HERMAN sebagai tangan kiri, WISNUR sebagai
konsultan IT, ARI yang bapaknya sebagai pembimbing I ku, UGI sebagai tuan rumah
mazhab BTP Blok 1, AHYA yang menjadi “the others” bagi SATGAS 13, dan terakhir
IVAN sebagai tetua SATGAS 13. TERIMA KASIH SODARA.
11. Yang terakhir, skripsi ini saya dedikasikan untuk KAMU yang semoga senantiasa berada
dalam penjagaan-Nya. Ini sekaligus sebagai salah satu indikator pembuktian bahwa
keseriusanku itu memang nyata. Terima kasih atas segala perhatian dan kasihnya yang
menjadi salah satu pemantik semangat buat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
Semoga kita tetap istiqamah untuk saling menjaga dan bertukar doa hingga hari yang
dinanti – nanti itu telah tiba.
Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh
Achmad Faizal
ABSTRAK
Achmad Faizal. E41113309. Radikalisme Agama dan Tantangan Ideologi Bangsa
Indonesia (Studi Wacana Pendirian Negara Islam (Khilafah Islamiyah) di Indonesia pada
Kalangan Mahasiswa Islam FISIP Unhas). Dibimbing oleh Tahir Kasnawi dan Mansyur
Radjab.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan
mahasiswa islam terhadap wacana pendirian negara islam (Khilafah Islamiyah) di Indonesia
serta bagaimana penafsiran mahasiswa islam terhadap kedudukan syariat islam dan pancasila
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Subjek dalam penelitian ini berjumlah enam puluh orang mahasiswa Fisip Unhas yang terdiri
dari setiap departemen dan angkatan yang ada di lingkup fakultas. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian adalah penelitian deskriptif - kuantitatif yaitu sebuah pendekatan yang mencoba
menggambarkan kecendrungan pandangan mahasiswa islam tatkala diperhadapkan oleh wacana
pendirian negara islam di Indonesia serta bagaimana mereka menafsirkan kedudukan syariat
islam dan pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas responden berpendapat tidak setuju
terhadap wacana pendirian negara islam di Indonesia yang disertai dengan berbagai alasan yang
melatarinya. Meskipun mayoritas responden tidak setuju terhadap wacana tersebut, tetapi hampir
setengah dari jumlah keseluruhan responden mendukung formalisasi syariat islam serta
penegakannya secara tegas. Kemudian mengenai pandangan mahasiswa islam tentang
kedudukan syariat islam dan pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
sebagian besar tidak setuju jika syariat islam dikesampingkan meskipun tidak sesuai dengan
hukum negara yang berlaku. Tetapi sebagian besar dari responden masih mengakui eksistensi
pancasila sebagai ideologi bangsa dan menilai masih relevan untuk kondisi Indonesia hari ini.
Kata kunci : Radikalisme Agama, Mahasiswa Islam, Ideologi Bangsa.
ABSTRACT
Achmad Faizal. E41113309. Religion Radicalism and the Challenges of Indonesian’s
Ideology (a Study on Islamic State (the Caliphate Islamiyah) Discourse in Indonesia among
Islamic Student of FISIP Unhas). Supervised by Tahir Kasnawi and Mansyur Radjab.
This research aims to describe in terms of how islamic student' perspective on the establisment of
islamic state discourse (the caliphate Islamiyah) in Indonesia and also to explain how Islamic
student' perspective on Islamic rules and Pancasila within the context of nationhood and
statehood.
The amount of respondents on this research is sixty islamic students which consists of each
departemen and grade at ISIPOL Faculty. This research uses a quantitative – descriptive method
which is aim to describes Islamic student's perspective against the establisment of islamic state
discourse (the Caliphate islamiyah) in Indonesia as well as to explains how Islamic student's
interpretation on Islamic rules and Pancasila within the context of nationhood and statehood.
The result of this research revealed that the majority of respondents are disagree with the
establishment of an islamic state in Indonesia with a variety of reasons following. Although the
majority of respondents are disagree with it, but almost half of the total respondents support the
formalization of islamic rules and want to upholding it firmly. Then, in terms of islamic student'
perspectives against islamic rules and pancasila within the context of nationhood and statehood,
most of them are disagree if islamic rules is sidelined even if not conforming to the state law
prevailing. However, most of them still acknowledge Pancasila as nation ideology and declare
that Pancasila is still relevant for today.
Keyword : Religion Radicalism, Islamic Student, Nation Ideology
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN……………………………………………………………………… i
HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………… ii
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………….. iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI…………………………………….….
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI……………………………….… iv
HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………………… v
KATA PENGANTAR……………………………………………………………..... vi
ABSTRAK………………………………………………………………………..….. vii
ABSTRACT………………………………………………………………..…..…..…. ix
DAFTAR ISI…………………………………………………………………..…..….. x
DAFTAR TABEL……………………………………………………………………. xii
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………. xiii
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………………. xiv
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN……………………….…..…..….. xv
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………….…..…..….. 1
A. Latar Belakang Masalah……………………………………………………..…..….. 1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………..…..….. 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…………………………………………..…..…... 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………..…..…..… 10
A. Definisi Operasional………………………………………………….…..…..…... 10
B. Deskrips Teori…………………………………………………………..…..…..….. 26
C. Hasil Penelitian yang Relevan……………………………………………..…..….. 31
C. Kerangka Konseptual.………………………………………………… …..…..….. 33
BAB III METODE PENELITIAN…………………………………………..…..…..…... 35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian………………………………………..…..…..……. 35
B. Tipe dan Dasar Penelitian…………………………………………………..…..…... 38
C. Populasi dan Sampel Penelitian…………………………..…..…..………………… 39
D. Teknik Pengumpulan Data……………………………………………..…..…..…… 45
E. Teknik Analisis Data…………………………………………………..…..…..……. 46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN……………………..…..….. 50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………..…..…..…………… 61
BAB VI PENUTUP…………………………………………………………..…..….... 90
A. Kesimpulan……………………………………………………..…..…..………….. 90
B. Saran-saran………………………………………………………………..…..….... 90
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..…..…..………….. 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN……………………………………………….…..…..…... 94
RIWAYAT HIDUP PENULIS…………………………………..…..…..…………… 110
DAFTAR TABEL
NOMOR HALAMAN
1. Perbandingan Definisi Negara Islam …………………………… 22
2. Rangkaian Jadwal Penelitian …………………………………… 37
3. Daftar Distribusi Responden ……………………………………. 42
4. Daftar Jumlah Mahasiswa Setiap Departemen di Fisip Unhas
Semester 2017/2018 ……………………………………………… 58
5. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ………………. 60
6. Distribusi Responden Berdasarkan Departemen ………………… 61
7. Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan …………………… 62
8. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pendirian
Negara Islam di Indonesia Ditinjau dari Jenis Kelaminnya . …….. 65
9. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pendirian
Negara Islam di Indonesia Ditinjau dari Departemennya ………... 66
10. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pendirian
Negara Islam di Indonesia Ditinjau dari Angkatannya……………. 67
11. Distribusi Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengesampingan
Syariat Islam Apabila Tidak Sesuai dengan Hukum Negara yang
Ditinjau dari Jenis Kelaminnya …………………………..……….. 73
12. Distribusi Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengesampingan
Syariat Islam Apabila Tidak Sesuai dengan Hukum Negara yang
Ditinjau dari Departemennya ……………………………………... 75
13. Distribusi Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengesampingan
Syariat Islam Apabila Tidak Sesuai dengan Hukum Negara yang
Ditinjau dari Angkatannya……………………………………… 76
DAFTAR GAMBAR
NOMOR HALAMAN
1. Skema Kerangka Pemikiran ……………………………………… 35
2. Ilustrasi Proses Pengumpulan dan Pengelolahan Data…………. 45
3. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pendirian Negara Islam
di Indonesia ……………………………………………………...... 64
4. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pembubaran Ormas
yang Menganut Paham Radikalisme di Indonesia…………………. 68
5. Distribusi Pandangan Responden Terhadap Penerapan Syariat Islam
secara Kaffah……………………………………………………..... 69
6. Distribusi Pandangan Responden Terhadap Formalisasi Syariat Islam…70
7. Distribusi Pandangan Responden Terhadap Penegakan Syariat Islam
dengan Sikap Tegas ……………………………………………. 71
8. Distribusi Jawaban Mahasiswa Terhadap Upaya Pengesampingan
Syariat Islam Apabila Tidak Sesuai dengan Hukum Negara
yang Berlaku………………………………………………………. 72
9. Distribusi Jawaban Mahasiswa Terhadap Relevansi Pancasila
dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial…………. 77
10. Distribusi Jawaban Mahasiswa Terhadap Ketidaksesuaian
antara Nilai – Nilai Islam dan Pancasila ………………………….. 78
11. Distribusi Jawaban Mahasiswa Terhadap Upaya Penafsiran
Syariat Islam sesuai Konteks Zaman dan Masyarakat……………... 79
DAFTAR LAMPIRAN
NOMOR HALAMAN
1. Dokumentasi Pengisian Kuesioner …………………………………. 94
2. Daftar Nama Responden Beserta Identitasnya………………………. 95
3. Kuesioner penelitian ………………………………………………... 98
4. Hasil pengelolahan data SPSS ………………………………………. 102
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN
LAMBANG/SINGKATAN ARTI
BALITBANG Badan Penelitian dan Pengembangan
FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FPI Front Pembela Islam
FUI Forum Umat Islam
HTI Hizbut Tahrir Indonesia
IM Ikhwanul Muslimin
JAT Jamaah Ansharit Tauhid
KAMM Kesatuan Aksi Mahasiswa MuslimIndonesia
LJ Laskar Jundullah
MMI Majelis Mujahidin Indonesia
NII Negara Islam Indonesia
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU Nahdhatul Ulama
ORMAS Organisasi Masyarakat
PERPU Peraturan Pengganti Undang - Undang
PKS Partai Kesejahteraan Sosial
PNI Partai Nasional Indonesia
POLRI Polisi Republik Indonesia
SDI Sarekat Dagang Islam
TNI Tentara Nasional Indonesia
TII Tentara Islam Indonesia
UUD Undang – Undang Dasar
UNY Universitas Negeri Yogyakarta
UNHAS Universitas Hasanuddin
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara dengan teritori terbesar dengan tingkat
keberagaman tertinggi di dunia. Ia terdiri atas berbagai suku, adat, ras dan agama.
Memiliki penduduk dengan jumlah yang tak kurang dari 250 juta jiwa, dengan total
penggunaan bahasa lebih dari 700 bahasa lokal serta Agama-agama mayoritas dunia
(Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) turut serta mendiami Bumi
Pertiwi Indonesia (www.cia.gov).
Keberagaman tersebut tidak serta merta membuka kran disintegrasi bangsa, sebab
Indonesia yang sedari awal kemerdekaan hingga kini telah diikat oleh simpul pererat
bangsa bernama Pancasila dengan semboyannya yang khas Bhinneka Tunggal Ika. Ia
memiliki daya untuk menundukkan berbagai perbedaan kedalam satu konsep negara –
bangsa (nation state) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya merupakan falsafah hidup (way of
life) yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia jauh sebelum ia merdeka. Bahkan
menurut para ahli sejarah bahwasanya sejak kerajaan Kutai, Sriwijaya dan Majapahit
berdiri di bumi Nusantara, mereka telah mengamalkan unsur-unsur pembentukan
Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai sosial-politik, nilai kesejahteran dan lain-lain.
Nilai-nilai kehidupan tersebutlah yang menjadi bahan baku yang kemudian diramu
sedemikian rupa hingga melahirkan Pancasila (http://www.learniseasy.com).
Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi serangkaian perjalanan panjang,
setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk
mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia
sebagai kode kebangsaan bersama (civic nationalism). Proses ini ditandai oleh
kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan nasional (seperti Boedi Oetomo,
SDI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia dan lain-lain), Partai Politik (Indische
Partij, PNI, Partai-Partai Sosialis), dan Sumpah Pemuda. (Pimpinan dan Tim Sosialisasi
MPR, 2016).
Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan,
dan kelompok masyarakat di Indonesia (Pimpinan dan Tim Sosialisasi MPR, 2016).
Namun kini ia dirundung berbagai ancaman dan tantangan kebangsaan baik yang berasal
dari internal maupun eksternal bangsa.
Salah satu ancaman dan tantangan terbesar Pancasila yang sejak era kemerdekaan
hingga kini konsisten menghantui bangsa adalah hadirnya gerakan gerakan
fundamentalisme atau radikalisme berbasis agama yang ingin mengubah ideologi bangsa
bahkan bentuk negara Indonesia (www.lib.lemhannas.go.id).
Secara sederhana, gerakan radikalisme/fundamentalisme yang selalu ditautakan
dengan konteks keagamaan dapat dipahami sebagai sebuah gerakan yang berusaha
memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar (Abdullah,2016). Dalam
konteks Indonesia, gerakan tersebut bercita-cita ingin melakukan perubahan besar dalam
politik kenegaraan dengan menggunakan cara-cara kekerasan maupun nir kekerasan
(indoktrinisasi). Perubahan besar dalam politik yang dimaksud adalah mengubah bentuk
NKRI menjadi Negara Islam Indonesia.
Salah satu memoar gerakan pendirian negara Islam di awal-awal kemerdekan
Indonesia yang sempat menimbulkan kegaduhan bangsa adalah dengan berdirinya
Negara Islam Indonesia (NII). Kelahiran negara baru tersebut yang diproklamirkan oleh
Imam Kartosuwirdjo pada tahun 1949 yang kemudian diperkuat oleh basis militernya
bernama Tentara Islam Indonesia (TII) hampir saja menghapus NKRI dari jajaran bangsa
besar di dunia. Terlepas dari wacana pro dan kontra terkait tindakan tersebut
diklasifikasikan sebagai tindakan makar atau pahlawan bagi bangsa Indonesia
(www.lensaindonesia.com).
Upaya pendirian negara Islam atau dengan kata lain formalisasi syariat islam
kedalam institusi pemerintahan masih berlanjut hingga kini. Gerakan Islam tersebut
secara khusus disebut dengan istilah “Gerakan Islam Syari’at”. Menurut Haedar Nashir,
gerakan tersebut merupakan suatu gerakan yang berusaha dengan gigih memperjuangkan
formalisasi syari’at Islam ke dalam institusi negara (pemerintahan), dan konstruksi dari
Islam syariat hanya mengambil 10 persen dari kandungan ayat Al-Quran. Namun 10
persen ini yang menjadi sangat mengatur kehidupan masyarakatnya.
Hadirnya gerakan formalisasi syariat islam atau pendirian negara Islam di Indonesia
diprakarsai oleh aktor-aktor baru. Gerakan mereka berada diluar
kerangka mainstream proses politik maupun wacana dalam gerakan Islam dominan
seperti yang telah dilakukan oleh organisasi islam pendahulu mereka (NU,
Muhammadiyah, Al–Irsyad dan Persis). Fenomena munculnya aktor baru ini sering
disebut “Gerakan Islam Baru” (new Islamic movement). Kelompok- kelompok tarbiyah
(yang kemudian menjadi PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ) dan sebagainya
merupakan representasi baru gerakan Islam di Indonesia (Wahid, 2009).
Munculnya gerakan-gerakan islam baru tersebut yang memiliki pijakan
transnasional kini menjadi kekuatan sosial yang tak terduga. Beberapa di antaranya
bahkan menyatakan sebagai golongan yang anti-Pancasila karena menganggap Pancasila
sebagai thaghut (sesembahan) yang berarti menyembah ideologi syirik, sehingga mereka
bercita - cita agar umat Islam bersatu dan tunduk pada hukum Allah yang hanya dapat
diterapkan dalam satu sistem kekhalifahan dunia (Khilafah Islamiyah) (www.voa-
islam.com).
Berbagai organisasi islam transnasional yang bercita cita ingin mendirikan negara
Islam memiliki pijakan sendiri dalam mengimplementasikan konsep tersebut. Sehingga
beragam definisi hadir dan hingga saat ini belum ada konsep yang jelas dan baku
mengenai kerangka negara Islam seperti apa. Sehingga alih- alih mendirikan negara
islam, paling tidak umat islam harus menuntaskan dua masalah paling mendasar terlebih
dahulu. Pertama tafsiran untuk mendirikan negara islam apakah dihukumi wajib atau
tidak, kedua, rumusan bentuk negara islam sekaligus model kepemimpinanya seperti apa.
Misalnya konsep negara Islam versi Hizbut Tahrir sebagaimana dikutip dalam pasal
2 kitab Masyrû’ Dustûr li ad-Dawlah al-Islâmiyyah menyebutkan negara Islam adalah
daerah yang di dalamnya diterapkan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan,
termasuk dalam urusan pemerintahan.
Konsep Darul Islam yang dibawa oleh Hizbut Tahrir berangkat dari keyakinan
bahwa Islam adalah sebuah agama dan daulah yang mengatur semua aspek kehidupan
mulai dari hukum, budaya, ekonomi, sosial dan politik. Konsep ini diilhami dari “Negara
Madinah” pada zaman Rasul abad ke 7 M dengan sistem khilafah sebagai bentuk negara
dan syariat Islam sebagai ideologinya (http://hizbut-tahrir.or.id).
Sementara bagi golongan Ahmadiyah bahwa khilafah bukanlah berbentuk politis
(negara) tetapi hanya bercorak agamis. Menurut pemahaman mereka, khilafah ‘ala
minhajul nubuwah telah berdiri yang terwujud dalam khilafah Ahmadiyah yang mana
semata- mata hanya untuk melaksanakan tugas risalah an- Nubuwah Muhammad SAW
yakni “memenangkan agama (islam) diatas semua agama (Ash- Shaf, 61:9)”. Dengan
kata lain, bagi Jemaah Ahmadiyah penerapan Khilafah Islamiyah tidak perlu dengan
mendirikan sebuah negara, tetapi cukup dengan memperjuangkan syariat- syariat Islam
(Hudori, 2009).
Terlepas dari perdebatan konseptual tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana mereka melakukan proses infiltrasi atau persuasi wacana kepada masyarakat
Indonesia agar mengaminkan wacana tersebut. Faktual, organisasi islam transnasional
tersebut memiliki underbouw atau minimal afiliasi dengan organisasi yang sevisi
dengannya di berbagai negara di dunia. Misalnya HTI yang memiliki underbouw
bernama “Gema Pembebasan”, Ikhwanul Musliminin dengan KAMMI. Maka kelompok
tersebutlah yang akan bertugas melakukan proses infiltrasi pemikiran ke berbagai lapisan
masyarakat mulai dari kalangan intelektual, pekerja hingga masyarakat awam.
Namun bagi penulis, hal yang menarik adalah tatkala mereka hendak menebar benih
- benih pemikirannya ke dalam dunia kampus atau kalangan mahasiswa. Sebagaimana
lazim diketahui bahwasanya dunia kampus yang menawarkan mimbar akademik yang
relatif bebas untuk bergulat dengan beragam pemikiran – baik kiri maupun kanan -
dengan sendirinya membawa konsekuensi logis berupa tersedianya ladang yang subur
untuk ditanami benih – benih ideologis. Sehingga sangat sulit rasanya untuk menampik
jika mahasiswa tidak tersentuh oleh ideologi radikal sekalipun.
Sebagai komparasi, untuk kalangan siswa/pelajar sendiri terdapat riset yang
menyatakan bahwa benih - benih radikalisme/fundamentalisme telah tumbuh mekar di
tubuh siswa. Menurut riset terbaru yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Makassar
tahun 2016 di 5 kota besar Indonesia Timur menyebutkan bahwa, sebanyak 9,2 % (101
siswa) yang menganggap Pancasila tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, sebanyak
2,1% (23 siswa) sangat bersedia untuk melakukan aksi bom bunuh diri dan 8,3% (91
siswa) bersedia untuk melakukan bom bunuh diri (Laporan Tim BLA, 2016).
Sementara hasil penelitian yang dilaksanakan oleh LIPI tahun 2016 di berbagai
sekolah di Indonesia, menunjukkan bahwa 25 % siswa dan 21 % guru menyatakan
pancasila tidak lagi relevan. Sementara 84,8 % siswa dan 76,2 % guru menyatakan setuju
dengan penerapan syariat islam (www.lipi.go.id).
Kemudian untuk kalangan mahasiswa sendiri, pada tahun 2010 Balai Litbang
Agama Makassar juga telah melakukan penelitian tentang “paham dan sikap keagamaan
mahasiswa muslim” di beberapa kota di kawasan Indonesia Timur dimana hasilnya
menunjukkan bahwa sebanyak 63,5 % mahasiswa setuju bentuk negara khilafah dan 17,1
% sangat setuju. Kemudian ada 59,3 % sepakat terhadap formalisasi syariat islam dan
14,8% sangat setuju. Selanjutnya, ada 47,9% yang menyatakan tidak bersedia dipimpin
oleh yang bukan beragama islam dan 18,3% sangat tidak bersedia (Laporan Tim BLA,
2010).
Kemudian penelitian selanjutnya tentang “Pergeseran Paham Keagamaan
Mahasiswa Islam” yang juga diadakan oleh Balitbang Agama Makassar pada tahun 2015
terhadap empat perguruan tinggi besar di Makassar menujukkan bahwa pemikiran dan
sikap berpikir moderat dari kalangan anak muda terdidik ini telah bergeser ke arah
radikalisme dengan corak berfikir lebih radikal dan fanatik ekstrem (Laporan Tim BLA,
2015).
Jika ingin membandingkan sejauh mana kematangan berfikir dan bersikap antara
siswa dan mahasiswa, idealnya mahasiswa sebagai agen intelektual telah dianggap
memiliki independensi dan kecakapan nalar. Sehingga sejatinya mereka mampu memilih
dan memilah atau dengan kata lain tidak mudah menerima begitu saja (taken for granted)
informasi ataupun ihwal pengetahuan yang ia peroleh.
Meskipun telah lahir kebijakan pemerintah (PERPU) tentang pembubaran ormas
yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, tetapi hal itu hanya dapat mematikan
organisasinya bukan ideologinya sebab mencegah penyebaran ideologi hanya mungkin
dilakukan dengan upaya counter - hegemony. Kemudian fenomena yang peneliti amati
adalah antusiasme beragama dari kalangan muda terdidik cukup meningkat drastic
belakangan ini. Gejala – gejala yang ditemui adalah semakin maraknya kelompok studi
keislaman (tarbiyah) di masjid – masjid kampus.
Olehnya, berangkat dari situ, penulis menganggap penting untuk melacak kembali
sejauh mana ideologi kebangsaan berupa Pancasila masih terpatri dalam tubuh
mahasiswa hari ini. Hal ini juga sebagai upaya untuk memproyeksikan kemana arah
kebijakan ideologis bangsa kedepannya yang mana notabenya kursi - kursi kekuasaan
tersebut niscaya akan diisi oleh pemuda yang hidup hari ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti
tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pandangan mahasiswa Islam terhadap wacana pendirian negara Islam
(Khilafah Islamiyah) di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa Islam terhadap kedudukan Pancasila dan
syariat islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas,
maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa islam terhadap wacana
pendirian negara Islam (Khilafah Islamiyah) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan mahasiswa islam terhadap kedudukan
Pancasila dan syariat islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
D. Manfaat Penelitian
Selain tujuan, tentunya penulis berharap dalam penelitian ini terkandung manfaat ke
depannya. Adapun manfaat yang mungkin dapat diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis/Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan setetes pengetahuan tentang
sejauh mana perkembangan ihwal gerakan radikalisme di indonesia yang ditinjau secara
sosiologis, serta memberikan gambaran sekilas bagi yang berminat untuk meneliti lebih
lanjut mengenai perkembangan gerakan radikalisme islam di kalangan mahasiswa maupun di
masyarakat secara umum.
2. Manfaat Praktis
Dengan bertambahnya wawasan tentang implikasi laten dari gerakan radikalisme
terhadap integrasi bangsa, semoga dengannya dapat menumbuhkan sikap toleransi, pikiran
yang jernih dan terbuka, serta juga memantik kepedulian dalam merawat keutuhan bangsa.
Diharapkan pula menjadi informasi tambahan dan sekaligus sebagai pertimbangan bagi
pemangku kebijakan seperti rektor, dekan atau stakeholders terkait dalam merumuskan
kebijakan teknis seperti menghadirkan ruang – ruang kajian ilmiah dan mata kuliah yang
khusus membahas fenomena radikalisme secara ilmiah.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. AGAMA DALAM WAWASAN KEBANGSAAN
1. RADIKALISME AGAMA (ISLAM)
Secara etimologi (akar kata), radikalisme berasal dari bahasa latin radix yang
berarti ; mendasar, pokok, asas, dan pondasi. Sementara secara terminologi
(istilah), penggunaan kata radikalisme memiliki makna serupa dengan istilah
fundamentalisme yakni sebagai sebuah paham yang berusaha memperjuangkan
atau menerapkan apa yang dianggap mendasar (Anzar Abdullah, 2016).
Terminologi fundamentalisme atau radikalisme dalam agama, apabila
dihubungkan dengan istilah dalam kamus bahasa Arab, sampai saat ini belum
ditemukan. Istilah ini adalah murni produk Barat yang sering dihubungkan
dengan fundamentalisme dalam Islam. Dalam tradisi Barat istilah
fundamentalisme dalam Islam sering ditukar dengan istilah lain, seperti:
“ekstrimisme Islam” oleh Gilles Kepel, atau “Islam Radikal” menurut Emmanuel
Sivan, dan ada juga istilah “integrisme, “revivalisme”, atau “Islamisme”.
Dibandingkan dengan istilah lainnya tersebut, “Islam radikal”, yang paling
sering disamakan dengan “Islam fundamentalis”. Sebab istilah fundamentalisme
lebih banyak berangkat dari literalisme dalam menafsirkan teks-teks keagamaan,
dan berakhir pada tindakan dengan wawasan sempit, yang sering melahirkan aksi
destruktif dan menyalahkan orang lain (Junaidi Abdullah, 2014 : 283-284).
John. L Esposito, seorang pakar tentang Islam, melakukan elaborasi
mengenai istilah “fundamentalisme” dengan mengasosiasikan dengan tiga hal
sebagai berikut: Pertama, dikatakan beraliran fundamentalis, apabila mereka
menyerukan panggilan untuk kembali ke ajaran agama yang mendasar atau
fondasi agama yang murni; Kedua, pemahaman dan persepsi tentang
fundamentalisme sangat dipengaruhi oleh kelompok Protestan Amerika, yaitu
sebuah gerakan Protestan abad ke-20 yang menekankan penafsiran Injil secara
literal yang fundamental bagi kehidupan ajaran agama Kristen; Ketiga, istilah
fundamentalisme dan anti Amerika. Esposito kemudian berpendapat bahwa istilah
fundamentalisme ini sangat bermuatan politis Kristen dan stereotype Barat, serta
mengindikasikan ancaman monolitik yang tidak eksis. Oleh karena itu, Esposito
tidak sependapat dengan kalangan Barat mengenai istilah “fundamentalisme
Islam”, ia lebih cenderung untuk memakai istilah “revivalisme Islam” atau
“aktivisme Islam” yang menurutnya tidak berat sebelah dan memiliki akar dalam
tradisi Islam.
Senada dengan Esposito, Al-Asymawi (1998), menyatakan bahwa
penggunaan istilah fundamentalisme tiada lain bertujuan untuk menjelaskan
adanya tindakan ekstrimisme religius dalam Islam, bukan Islamnya yang
fundamentalis. Oleh karena itu, tidak bisa disamakan atau diidentikkan atau
disetarakan dengan ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam tidak
mereferensikan adanya tindakan kejahatan, radikalisme, ekstrimisme dengan cara-
cara anarkis, seperti bom dan bunuh diri (Anzar Abdullah, 2016 : 4).
Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi memberikan istilah radikalisme dengan
istilah al-Tatarruf ad-Dini. Dalam bahasa yang lugas, radikalisme adalah bentuk
mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktikkan
ajaran agama dengan mengambil posisi tarf atau pinggir. Jadi jauh dari substansi
ajaran agama Islam, yaitu ajaran moderat di tengah-tengah (wasathan). Biasanya
posisi pinggir ini adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan, yang
tidak sewajarnya. Sehingga menimbulkan sikap kaku dan keras. Lebih lanjut,
Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa posisi praktik agama seperti itu
mengandung tiga kelemahan, yaitu: pertama, tidak disukai oleh tabiat kewajaran
mansia; kedua, tidak bisa berumur panjang, dan yang ketiga, sangat rentan
mendatangkan pelanggaran atas hak orang lain. Apa makna dari implikasi cara
beragama seperti ini, ialah bahwa dalam praktik pengalaman beragama terdapat
orang-orang berperilaku ekstrim sehingga melebihi kewajaran yang semestinya
(Junaidi Abdullah, 2014 :284).
Jikalau kita membuka lembaran sejarah Islam di masa masa awal
perkembangan islam khususnya pasca sepeninggal Nabi SAW, akan ditemukan
fakta bahwa radikalisme sebagai suatu gerakan bukanlah fenomena baru dalam
dunia Islam kontemporer.
Dalam perspektif sejarah, gerakan radikalisme dalam Islam telah muncul di masa
Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan munculnya golongan Khawarij yang
memberontak atas ketidaksetujuannya dengan tahkim (arbitrase) yang
memenangkan musuh, yakni dari kelompok Muawiyah. Kelompok Khawarij ini
digolongkan sebagai gerakan radikalisme Islam klasik (Anzar Abdullah, 2016 :
5).
Memasuki fase pra-modern, dunia islam kembali diwarnai dengan aksi-aksi
radikal. Gerakan tersebut muncul disemenanjung Arab di bawah pimpinan
Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (1703-1792). Dengan mengusung visi
pemurnian agama islam (purisasi), para pengikutnya melakukan tindakan
kekerasan dengan membunuh orang-orang yang dianggap melakukan
penyimpangan terhadap islam seperti amalan bid’ah, tahayyul, dan khurafat serta
menghancurkan monument-monumen historis di Mekkah dan Madinah (Junaidi
Abdullah, 2014 : 287).
Kemudian memasuki fase modern, dunia islam juga tidak luput dari aksi
fundamentalisme agama bahkan telah menjadi isu global terutama
fundamentalisme islam berwujud terorisme dan peperangan. Jika membandingkan
gerakan fundamentalisme klasik dan pra-modern dengan gerakan
fundamentalisme kontemporer , yang pertama disebut berangkat dari landasan
teologis dan ideologis fundamental dalam kaitannya dengan ihwal ibadah
(ukhrawi) dengan membawa semangat kebangkitan islam (revivalisme of islam).
Sementara yang kedua disebut - fundamentalisme kontemporer - lebih banyak
dipengaruhi oleh respon Islam atas modernisme Barat sebagaimana yang telah
dilakukan oleh para penganut Kristen orthodox (fundamentalist Kristen) demi
memproteksi kitab bible dari pengaruh sekulerisme - modernisme
(www.cliffnotes.com).
Paling tidak ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok
fundamentalis islam hari ini ;
• Pertama, mereka menolak sekularisme masyarakat Barat yang memisahkan
agama dan politik, gereja, dan masjid dari Negara. Kesuksesan Barat
melakukan sekularisasi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, karena
dapat mengancam Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurusi
persoalan akhirat saja, tetapi sekaligus duniawi.
• Kedua, banyak umat Islam yang menginginkan agar masyarakat mereka
diperintah sesuai dengan al-Qur’an dan syari’at Islam sebagai aturan
bernegara. Oleh krena itu, dewasa ini tidak mengherankan, apabila muncul
gerakan bawah tanah yang bercita-cita membangun Khilafah Islamiyah
dengan mengusung tema-tema kedaulatan Tuhan, jihad, revolusi Islam,
keadilan sosial, dan sebagainya.(Junaidi Abdullah, 2014).
Menurut Pontoh (2016) bahwa dalam konteks Indonesia terkait gerakan
fundamentalisme islam, paling tidak dalam 15 tahun terakhir pasca reformasi
1998, lanskap politik di Indonesia diramaikan oleh menguatnya gerakan-gerakan
Islam dalam berbagai variannya. Yang paling mencolok, tentu saja, adalah
gerakan Islam generasi baru yang mengusung aspirasi politik Islam, baik yang
berjuang di jalur parlementer maupun ekstra parlementer. Nama-nama seperti
Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Forum Umat Islam (FUI),
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Laskar Jundullah dan sekian jenis aliansi-aliansi
temporer untuk merespon isu-isu tertentu ramai menghiasi pemberitaan media
konvensional, media sosial, dan sekian bentuk hasil riset. Aksi-aksi mereka, baik
yang berbentuk kekerasan fisik maupun persuasif diperbincangkan secara luas.
(Kumar, 2016 : 2)
2. NEGARA ISLAM (KHILAFAH ISLAMIYAH)
Para pengusung ide formalisme Islam dalam negara menggunakan istilah
yang berbeda-beda mengenai masalah ini. Tiga istilah yang paling sering
digunakan adalah “Khilafah Islamiah”, “Daulah Islamiah”, dan “Negara Islam”.
Istilah Khilafah berasal dari tradisi pemerintahan Islam masa-masa awal yang
dikomandani Khalafa’ al- Rasyidun; istilah daulah dipinjam dari Daulah
Umayyah dan Daulah Abbasiah yang waktu itu diartikan sebagai “putaran
pemerintahan dinasti”; sedang istilah negara sebagai terjemahan dari nation-state
yang baru diperkenalkan belakangan oleh Nicolo- Machiavelli (1469-1527).
Dalam dunia Islam, istilah “Negara Islam” dikenal baru abad 20. Ketiga istilah itu
sebenarnya menunjuk pada maksud yang sama, yakni keharusan adanya bentuk
Negara resmi yang berbasis Islam, entah itu khilafah Islamiah atau Negara Islam
(Wijaya, 2012).
Namun mengenai konsep negara Islam yang baku, belum ditemukan hingga
hari ini. Bahkan bagi Arkoun, Khilāfah merupakan sebuah gagasan yang sangat
utopis. Arkoun berargumen bahwa isu khilāfah ini tidak ada kesepakatan di
kalangan umat, karena berbeda penafsiran teks agama serta latar belakang sosial
budaya masing-masing negara muslim (Muqtada, 2017 : 139-140).
Menurut Gus Dur bahwa Islam sebagai jalan hidup tidak memiliki konsep
yang jelas tentang negara. Paling tidak ada dua alasan yang mendasarinya.
Pertama, bahwa Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti
tentang pergantian kepemimpinan. Itu terbukti ketika Nabi SAW wafat dan
digantikan oleh Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah
SAW dilakukan melalui ba’iat oleh para kepala suku dan wakil-wakil kelompok
umat yang ada pada waktu itu. Sedangkan Abu Bakar sebelum wafat menyatakan
kepada kaum muslimin, hendaknya Umar Bin Khattab diangkat menggantikan
posisinya. Ini berarti sistem yang dipakai adalah penunjukkan. Sementara Umar
menjelang wafatnya meminta agar penggantinya ditunjuk melalu sebuah dewan
ahli yang terdiri dari tujuh orang. Lalu dipilihlah Utsman bin Affan untuk
menggantikan Umar. Selanjutnya Utsman digantikan Ali bin Abi Thalib. Pada
saat itu Abu Sufyan juga telah menyiapkan anak cucunya untuk menggantikan
Ali. Sistem ini kelak menjadi acuan untuk menjadikan kerajaan atau marga yang
menurunkan calon-calon raja dan sultan dalam sejarah islam.
Kedua, besarnya Negara yang idealisasikan oleh islam, juga tak jelas
ukurannya. Nabi Muhammad meninggalkan madinah tanpa ada kejelasan
mengenai bentuk pemerintahan kaum muslimin. Tidak kejelasan misalnya,
Negara islam yang diidealkan bersifar mendunia dalam konteks Negara-bangsa
(nation-state) ataukah hanya Negara-kota (city- state) (Wahid, 2006: xviii-xix).
Namun untuk kebutuhan penelitian ini, maka peneliti menggunakan konsep
negara islam yang dipahami secara umum atau dengan kata lain peneliti
mengambil pengertian dari beberapa ahli ataupun tokoh/aktivis organisasi
pengusung negara Islam, baik yang klasik maupun kontemporer seperti Hizbut
Tahrir, ISIS, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah, Ahmadiyah dan lain
sebagainya, lalu meramunya menjadi satu definisi umum.
Menurut Taqiyuddin an- Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir bahwa negara Islam
(Khilafah Islamiyah) adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di
dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban risalah
Islam ke seluruh penjuru dunia (Yusalina, 2016 : 139).
Kemudian negara Islam (Khilafah Islamiyah) dibangun di atas delapan
struktur yaitu: Khalifah, Mu’awin Tafwidh, Mu’awin Tanfidz, Amirul Jihad, para
Wali, Qadha, Aparatur Administrasi Negara, dan Majelis Umat. Jika Negara
telah memiliki kedelapan struktur tersebut, berarti strukturnya sudah sempurna.
Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka struktur Negara kurang sempurna,
tetapi masih terkategori sebagai Daulah Islam. Berkurangnya salah satu dari
struktur tersebut tidak membahayakan negara, selama khalifah masih ada, karena
struktur ini adalah asas dalam negara. Adapun kaidah-kaidah pemerintahan dalam
Daulah Islam ada empat yaitu: pengangkatan seorang khalifah, kekuasaan adalah
milik umat, kedaulatan berada di tangan syara’ dan hanya khalifah yang
berwewenang untuk mentabani hukum-hukum syara’ dengan kata lain
menjadikannya sebagai perundang-undangan. Jika salah satu dari kaidah-kaidah
ini hilang, maka pemerintahannya menjadi tidak Islami, bahkan harus
menyempurnakan seluruh kaidah yang empat itu seluruhnya. Asas Daulah Islam
adalah khalifah, sedangkan selainnya adalah wakil dari khalifah atau tim
penasihat baginya. Dengan demikian, Daulah Islam adalah khalifah yang
menerapkan sistem Islam. Khilafah atau Imamah adalah pengaturan tingkah laku
secara umum atas kaum Muslim (an- Nabhani, 2012 : 300).
Menurut Imam Al – Mawardi dalam karyanya al- ahkam al- sultaniyah bahwa
imamah atau khalifah adalah penggantian posisi Nabi untuk menjaga
kelangsungan agama dan urusan dunia. Secara tersirat bahwa bentuk Negara yang
ditawarkan Al-Mawardi lebih kepada teokrasi, menjadikan agama dan Tuhan
sebagai pedoman dalam bernegara. Bahwa pemerintahan merupakan sarana untuk
menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga pelaksanaannya pun berdasar dan
dibatasi oleh kekuasaan Tuhan (Riyadi, 2008).
Menurut Abul a’la Al- Maududi bahwa islam adalah agama paripurna yang
memuat prinsip-prinsip lengkap tentang semua segi kehidupan moral, etika, serta
petunjuk dibidang politik, sosial dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya
sebagai satu keyakinan tetapi sebagai sistem yang lengkap yang menjawab semua
persoalan manusia. Semua itu tidak bisa diwujudkan dalam tindakan praktis tanpa
adanya negara Islam yang menjamin pelaksanaannya (Naki, 1999).
Menurut Hasan Al-Banna bahwa wajib hukumnya bagi umat islam untuk
memikirkan upaya tegaknya eksistensi khilafah. Menurutnya, khilafah adalah
simbol persatuan umat islam. Khilafah menurut konsepnya bersifat kolektif, yaitu
berupa perserikatan antar negara (Khoiriya, 2016).
Menurut Muhammad Abduh Islam menghendaki pemerintahan yang
demokratis. Namun, soal bentuk atau sistem pemerintahan, kata Abduh, tidak ada
ketentuannya dalam Islam. Hal tersebut diserahkan kepada kehendak dan ijtihad
kaum muslimin sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi (Pulungan, tt : 20)
Kemudian menurut Rashid Ridha bahwa Khilafah Islamiyah adalah wajib
syar’i dan eksistensi khilafah sangat penting dalam rangka penerapan hukum
syari’at Islam. Baginya Islam adalah agama untuk kedaulatan, politik dan
pemerintahan (Yusalina, 2016 : 144).
Adapun menurut golongan Ahmadiyah bahwa khilafah bukanlah berbentuk
politis (negara) tetapi hanya bercorak agamis. Menurut pemahaman mereka,
khilafah ‘ala minhajul nubuwah telah berdiri yang terwujud dalam khilafah
Ahmadiyah yang mana semata- mata hanya untuk melaksanakan tugas risalah an-
Nubuwah Muhammad SAW yakni “memenangkan agama (islam) diatas semua
agama (Ash- Shaf, 61:9)”. Dengan kata lain, bagi Jemaah Ahmadiyah,penerapan
Khilafah Islamiyah tidak perlu dengan mendirikan sebuah negara, tetapi cukup
dengan memperjuangkan syariat- syariat Islam (Hudori, 2009).Untuk
perbandingan definisi yang lebih rinci, berikut peneliti sajikan dalam bentuk tabel
berikut :
Tabel 1.1. Perbandingan Definisi Negara Islam
NAMA PANDANGAN KETERANGAN
Taqiyuddin an
Nabhani
Negara Islam adalah kepemimpinan umum bagi seluruh
kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum - hukum
syariat Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh
penjuru dunia.
Pendiri/ Tokoh
Hizbut Tahrir
Abul a’la al Maududi
Islam dipahami bukan hanya sebagai satu keyakinan tetapi
sebagai sistem yang lengkap yang menjawab semua
persoalan manusia. Semua itu tidak bisa diwujudkan dalam
tindakan praktis tanpa adanya negara Islam yang menjamin
pelaksanaannya
Imam Al Mawardi
Imamah atau khalifah adalah penggantian posisi Nabi untuk
menjaga kelangsungan agama dan urusan dunia. Bentuk
negara lebih kepada teokrasi, menjadikan agama dan Tuhan
sebagai pedoman dalam bernegara.
Hasan al Banna
Wajib hukumnya bagi umat islam untuk memikirkan upaya
tegaknya eksistensi khilafah. Khilafah adalah simbol
persatuan umat islam. Konsepnya bersifat kolektif, yaitu
berupa perserikatan antar negara.
Pendiri Ikhwanul
Muslimin
Rashid Ridha
Khilafah Islamiyah adalah wajib syar’i dan eksistensi
khilafah sangat penting dalam rangka penerapan hukum
syari’at Islam. Islam adalah agama untuk kedaulatan, politik
dan pemerintahan
Jamaluddin al
Afghani
Islam menghendaki bentuk republik. Sebab di dalamnya
terdapat kebebasan berpendapat
dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang
dasar.
Pendiri
Al - Hizb al-
Wathan
Muhammad Abduh
Islam menghendaki pemerintahan yang demokratis. Bentuk atau
sistem pemerintahan, tidak ada ketentuannya dalam Islam, tetapi
diserahkan kepada kehendak dan ijtihad kaum muslimin sesuai
dengan kondisi yang mereka hadapi.
Mufti Mesir
Tabel 1.1. Data diolah dari berbagai sumber
3. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA & DASAR NEGARA
Ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata ; ideos artinya
pemikiran, dan logis artinya logika, ilmu, pengetahuan. Menurut Ali Syariati
(1982), ideologi adalah ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat
diberbagai subyek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk
direalisasikannya. Olehnya, Ideologi tidak hanya dimiliki oleh Negara, dapat juga
berupa keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam Negara, seperti partai
politik atau asosiasi politik, kadang hal ini sering disebut sub-ideologi atau bagian
dari ideologi (Sayyid Santoso, 2015).
Menurut Frans Magnis Suseno (1991) (dalam Santoso, 2015), ideologi
adalah sebagai system berfikir, nilai-nilai, dan sikap dasar rohaniah sebuah
gerakan, kelompok sosial atau individu. Sementara menurut Antonio Gramsci
(dalam Simon, 1999 dikutip oleh Santoso, 2015), ideologi lebih sekedar system
ide, ia secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya
ideologi mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak,
mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya.
Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika
rumusan kepentingan hidup-bersama di wilayah nusantara diuji dan didewasakan
sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan
Indonesia memuncak ketika mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan
kepentingan ideologi (awal abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme,
Islamisme, Sosialisme – Indonesia dan komunisme, yang diakhiri secara yuridis
ketatanegaraan tanggal 18 agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya
Pancasila oleh PPKI sebagai dasar NKRI.
Menurut Notonegoro (1967) bahwa lima unsur yang terdapat pada Pancasila
bukanlah hal yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya
dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat Indonesia yang nyata ada dan
hidup dalam jiwa masyarakat (Pimpinan MPR dan Tim, 2016 : 87).
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara
adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan pula sebagai ideologi Negara serta
sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap materi muatan
peraturan perundang-undagan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila (Pimpinan MPR dan TIM, 2016 : 90-91).
4. SYARIAT ISLAM
Syariat adalah segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Qur’an dan sunah.
Semula kata ini berarti, jalan menuju kesumber air, yakni jalan kearah sumber
kehidupan. Kata kerjanya adalah syara’a yang berarti ‚menandai atau mengambar
jalan yang jelas menuju sumber air.
Pengertian syariat Islam ini dapat dibagi menjadi dua pengertian: pertama
dalam pengertian luas, kedua dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas,
syariat Islam ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur
oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa
mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil
dalil-dalilnya langsung dari al-Qur’an dan al-Hadith, atau sumber pengambilan
hukum seperti: ijma’, qiyas, istihsan, istish-hab, dan mashlahlh mursalah.
Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang
berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur’an, hadis yang sahih, atau yang
ditetapkan oleh ijma’.
B. DESKRIPSI TEORI
Ada beragam teori ataupun pendekatan yang telah digunakan untuk menganalisis
fenomena gerakan fundamentalisme atau gerakan kebangkitan islam secara umum.
Setidaknya ada 3 pendekatan yang paling banyak dikutip seperti dikatakan oleh Syafii
Maarif (2009) dalam Wahid (2009) sebagai berikut :
- Pertama, kegagalan umat islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah
sangat menyudutkan islam. Karena ketidakberdayaan menghadapi arus panas itu,
golongan fundamentalis mencari dalil-dalil agama untuk “menghibur diri” dalam
sebuah dunia yang dibayangkan belum tercemar.
- Kedua, membesarnya gelombang fundamentalisme di berbagai Negara muslim
terutama didorong oleh rasa kesetiakawanan terhadap nasib yang menimpa saudara-
saudara di Palestina, Kashmir, Afganistan dan Iraq.
- Ketiga, maraknya fundamentalisme khususnya di Nusantara lebih disebabkan oleh
kegagalan Negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya rasa keadilan
sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang
masih menggurita adalah bukti nyata kegagalan itu.
Namun pada tulisan ini, peneliti mencoba menguraikan 2 teori atau pendekatan
dalam mengupas fenomena gerakan fundamentalisme islam, bukan dari sisi gerakan
sosial organisasinya tetapi dari sudut pandang sasaran gerakan organisasi tersebut.
Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan dalam poin rumusan masalah bahwa
penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan sikap atau pandangan objek atau target
gerakan fundamentalisme islam, dalam hal ini mahasiswa.
1. STRUKTURAL FUNGSIONAL
Salah satu tokoh fungsionalisme struktural yang memberikan sumbangsi
pemikiran teoritis terhadap perkembangan kajian/analisis struktur-fungsional
adalah Robert K. Merton. Diantara sumbangsih tersebut, yang paling terkenal
terhadap fungsionalisme struktural dan terhadap sosiologi pada umumnya adalah
analisisnya mengenai hubungan kultur, struktur dan anomi.
Merton mendefinisikan kultur sebagai “seperangkat nilai normatif yang
terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota
kelompok. Struktur sosial adalah seperangkat hubungan sosial yang teroganisir,
yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di
dalamnya. Anomi terjadi bila ada keterputusan hubungan antara norma kultural
dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok
untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural (Ritzer, 2008:142-143 ).
Dengan ketiga konsep tersebut, peneliti mencoba menganalisis fenomena
gerakan fundamentalisme islam di Indonesia dalam bentuk pendirian negara islam
yang kemudian dibenturkan dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara
Indonesia. Pertama, kultur berislam masyarakat Indonesia yang terbangun selama
ini adalah kultur moderat, toleran dan tidak kaku. Pola atau corak beragama
(islam) di Indonesia juga dibangun diatas perpaduan tradisi/budaya masyarakat
setempat sehingga mereka tidak mengenal istilah bid’ah, tahayyul dan khurafat ,
sebuah istilah yang sering dilontarkan oleh sekolompok muslimin yang menganut
islam garis keras. Kedua, oleh karena pola atau corak ber- islam masyarakat
Indonesia yang moderat, toleran dan tidak kaku maka pola hubungan sosial
(struktur sosial) yang terbangun antara sesama pemeluk agama/kepercayaan
minoritas (Nasrani, Buddha, Hindu maupun agama - agama adat) yang ada di
Indonesia dapat dikata harmonis. Ketiga, anomi dapat terjadi manakala pola
berislam masyarakat Indonesia berubah menjadi kaku, intoleran dan radikal.
Untuk analisis tingkat struktur, Merton menambahkan konsep baru yakni
akibat yang tidak diharapkan (unanticapted consequences). Tindakan mempunyai
akibat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, analisis sosiologi
diperlukan untuk menemukan akibat yang tidak diharapkan ini (Ritzer, 2008:
141). Apabila pola beragama (islam) masyarakat Indonesia berubah menjadi
radikal, intoleran dan kaku maka dapat menimbulkan perpecahan di antara sesama
pemeluk agama dan hal ini sebagai sesuatu yang tidak diharapkan dalam
pandangan struktural fungsional.
Untuk analisis anomi sendiri, Merton menghubungkannya dengan istilah
penyimpangan yang berarti penolakan terhadap konsekuensi disfungsional dalam
kesenjangan antara kebudayaan dan struktur yang mengarah pada penyimpangan
dalam masyarakat (Ritzer, 2008 : 143).
2. FAKTA SOSIAL
Agama adalah institusi sosial yang khusus. Kekhususannya ialah bahwa
dalam agama manusia mempermasalahkan hidupnya dalam dimensi yang tidak
empiris. Sehingga ia berbeda dengan institusi- institusi lainnya seperti keluarga,
pendidikan, ekonomi dan sebagainya (Veeger, 1986 : 164).
Menurut Durkheim bahwa agama adalah suatu system kepercayaan praktik
yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus (suci).
Kepercayaan dan praktik tersebut diturunkan kedalam 2 unsur penting yakni sifat
kudus, sakral, suci (sacred) dan ritual dari agama (Upe, 2010 : 104).
Agama menjadi sebuah fakta sosial yang mampu mengikat, mengontrol dan
mengatur para pemeluknya karena dalam setiap agama mengandung sesuatu yang
dianggap kudus (sacred) oleh masyarakat sehingga sulit rasanya bagi seorang
individu melepaskan diri dari kontrol agamanya.
Dalam konsepsi Durkheim tentang dasar agama, ia merumuskan bahwa
terdapat tata sakral dan tata profan. Tata sakral merujuk kepada sesuatu yang
dianggap sacral, suci, atau kudus seperti Tuhan, Roh, Binatang, Tumbuhan.
Sementara Tata Profan merujuk kepada sesuatu yang menyangkut kehidupan
sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan seterusnya.
Meminjam konsepsi Durkheim tersebut, peneliti mencoba menganalisis dalam
kaitannya dengan bagaimana pemeluk Islam memandang konsepsi negara islam.
Pertama, bahwa seluruh muslim sepakat menjadikan Allah berserta wahyuNya
(Al-Qur’an & Hadist) sebagai tata sakral, suci, atau sesuatu yang wajib diimani
kebenarannya. Namun untuk sistem kehidupan bernegara atau pemerintahan,
peneliti melihat timbul dua arus pemikiran utama, ada yang menganggap sistem
kehidupan bernegara sebagai sesuatu yang juga sakral, dengan kata lain harus
sesuai dengan syariat islam yang diejawantahkan kedalam pendirian negara Islam
dan formalisasi syariat, ada pula yang menafsirkan bahwa sistem bernegara atau
pemerintahan hanya sebagai tata profane atau dengan kata lain, umat islam diberi
ruang untuk merumuskan sendiri sistem negara apa yang paling terbaik tanpa
menanggalkan syariat islam atau tanpa melakukan formalisasi syariat.
Dengan demikian, dalam penelitian ini, kita dapat mengidentifikasi bagaimana
pandangan mahasiswa terhadap kedudukan antara Pancasila dan UUD 1945 dan
syariat islam didalam konteks kehidupan bernegara. Dengan kata lain, yang mana
dijadikan tata sakral dan tata profan diantara keduannya.
C. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN
Dari hasil proses studi pustaka, peneliti menemukan beberapa hasil
penelitian yang membahas tentang fenomena gerakan fundamentalisme islam
terkhusus penelitian yang membahas tentang wacana pendirian Negara Islam
(Khilafah Islamiyah).
Pertama, hasil penelitian dari Miftahul Ilmi (2008) tentang “Persepsi Ulama
NU terhadap Sistem Khilafah (studi kasus ulama NU kota Semarang)”. Hasilnya
bahwa menurut ulama NU kota Semarang, khilafah merupakan sistem
pemerintahan yang bersifat universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang
mengintegrasikan agama dan politik, sehingga Negara merupakan lembaga politik
sekaligus agama. Sistem khilafah tersebut tidak pas diterapkan di Indonesia,
bahkan sudah tidak relevan untuk kondisi sekarang. Sebab negara-negara Islam
atau yang berpenduduk mayoritas muslim sudah mapan dengan nation state.
Meskipun sistem khilafah ideal karena dapat mempersatukan dunia Islam, tetapi
sulit diwujudkan atau sebagai konsep ideal utopis. Menurut ulama NU, Islam
tidak mewajibkan untuk menerapkan sistem khilafah. Tidak terdapat satu pun ayat
al-Qur’an maupun hadis yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan khilafah.
Yang diperintahkan oleh Islam adalah mendirikan imamah (kepemimpinan), dan
imamah bentuknya tidak harus khilafah, tetapi disesuaikan dengan situasi dan
perkembangan politik yang ada sehingga relevan.
Kedua, hasil penelitian dari Mastur (2010) tentang “Respon Mahasiswa
Muslim UNY Terhadap Pemikiran Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia” bahwa ada
yang menganggap perlu mendirikan negara Islam sebagai solusi di tengah krisis
yang menempa umat islam belakangan ini, tetapi konsep khilafah yang digagas
HTI bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena dasar negara Indonesia
tidak mengenal sistem khilafah. Indonesia sudah memiliki dasar negara dan
perundang-undangan yang final.
D. KERANGKA KONSEPTUAL
Bergulirnya wacana pendirian negara Islam di Indonesia sejak kemerdekaan
hingga hari ini menimbulkan sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan. Yang pro
dapat dipastikan datang dari sang pengusung negara islam serta umat islam yang
memahami teks kitab suci secara literal - skriptual, sementara yang kontra datang dari
terutama penjaga keutuhan NKRI – Pemerintah – TNI – Polri serta umat islam
moderat (kalangan NU dan Muhammadiyah).
Menurut Imam Jauhari (2012 : 187) bahwa hubungan negara dan Islam tidak
dapat dimengerti sebagai sebuah hubungan yang statis. Artinya keharusan adanya
negara Islam tidak sekuat keharusan adanya agama Islam. Misalnya kalau dari segi
historis ditemukan adanya negara Islam dalam arti sebagaimana yang pernah terjadi
pada zaman nabi SAW, tidak dapat dimutlakkan bahwa tatanan negara islam itu
diwujudkan pada masa sekarang ini. Hal ini serupa dengan pencarian demokraasi
yang memimpikan demokrasi asli ; demokrasi Athena.
Oleh karenya, peneliti menganggap penting untuk diketahui sejauh mana
ideologi radikal telah menggerogoti anak bangsa. Hal demikian dapat diidentifikasi
dari respon yang diberikan tatkala wacana pendirian Negara Islam digulirkan. Berikut
peneliti sajikan skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini :
Gambar 1.1. SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN
PENDIRIAN
NEGARA ISLAM
PANCASILA PENERAPAN
SYARIAT
ISLAM
PANCASILA
KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN
BERNEGARA NKRI
BAB III
METODE PENELITIAN
A. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN
1. Waktu penelitian
Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi jadwal kegiatan yang akan
dilaksanakan. Dalam jadwal tersebut berisi keterangan kegiatan dan berapa lama
penelitian akan dilakukan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanankan pada bulan
September 2017 hingga bulan November 2017 yang juga masuk dalam kalender
akademik Unhas untuk semester ganjil tahun ajaran 2017-2018.
Uraian tentang penggunaan waktu penelitian dimaksudkan untuk: (1)
perencanaan kerja peneliti sendiri; (2) untuk menentukan alokasi dana yang
dibutuhkan selama penelitian; (3) agar dapat diperkirakan jumlah tenaga lapangan
yang akan dibutuhkan.
Berdasarkan penjelasan diatas, maksud utama dari kebutuhan mengelola
waktu pelaksanaan penelitian ini agar penelitian dapat dikendalikan terutama dari
segi waktu dan yang terpenting adalah dengan waktu penelitian yang terkendali,
anggaran penelitian pun bisa diproyeksikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya sehingga semua kegiatan penelitian dapat dikoordinasikan. Jadwal
penelitian biasanya juga memuat hal yang harus dikerjakan, kapan pelaksanaan
dan selesainya suatu kegiatan, serta berapa banyak waktu (jam, hari, minggu,
bulan, dan tahun) yang dibutuhkan.
Berikut peneliti sajikan lini masa atau rangkaian jadwal penelitian ini kedalam
tabel yang lebih rinci:
Tabel 1.2. RANGKAIAN JADWAL PENELITIAN
No Kegiatan Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1
Penyusunan
Proposal
2
Seminar
Proposal
3
Persiapan
Administrasi
dan Persuratan
Izin Penelitian
4
Observasi
Langsung ke
Lokasi
Penelitian
5
Penentuan
Populasi dan
Sampel
Penelitian
6
Pengumpulan
Data
7 Analisis Data
8
Pembuatan Draf
Skripsi
9
Penyempurnaan
Skrispi
10
Ujian Meja
untuk Strata 1
Tabel 1.2 : Sumber data diolah oleh peneliti
2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penentuan lokasi ini didasari atas
pertimbangan bahwa mahasiswa atau responden yang akan diteliti menjalankan
aktivitas perkuliahannya di lokasi tersebut sehingga memudahkan peneliti
menemukan responden yang bersangkutan.
B. TIPE DAN DASAR PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis memilih tipe penelitian kuantitatif untuk
menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengelolah, dan menganalisis data hasil
penelitian. Hal ini senada dengan topik atau judul penelitian ini yang ingin
menggambarkan secara umum bagaimana respon mahasiswa islam terhadap wacana
pendirian Negara Islam di Indonesia.
Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti sebuah populasi atau sampel tertentu, kemudian pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian tertentu, analisis data bersifat kuantitatif statistik
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Dalam penelitian kuantitatif, metode penelitian yang dapat digunakan adalah
metode survey, expost facto, eksperimen, evaluasi, action research, policy research.
Kemudian dalam penelitian kuantitatif setidaknya ada dua strategi yang paling sering
diterapkan dalam ilmu sosial yakni penelitian survey dan eksperimen. Namun dalam
penelitian ini, peneliti memilih penelitian survey untuk menjawab rumusan masalah
yang ajukan.
Lebih lanjut, penelitian survey pada dasarnya berusaha memamparkan secara
kuantitatif kecendrungan, sikap, opini dari suatu populasi tertentu dengan meneliti
satu sampel dari populasi tersebut. Penelitian survey adalah penelitian yang tidak
melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel-variabel yang
diteliti. Hal ini senada dengan rumusan masalah penelitian ini yang hanya ingin
menggambarkan (deskripsi) respon mahasiswa islam secara umum terhadap wacana
pendirian Negara islam di Indonesia dan bagaimana mereka menafsirkan kedudukan
pancasila dan syariat islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa
islam FISIP Unhas yang masih aktif atau terdaftar pada semester akademik yang
sedang berlangsung saat penelitian ini dilaksanakan.
Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua
yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti
dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
Untuk menentukan sample dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
sampel kouta (kouta sampling). Teknik sampel kouta (kouta sampling ) adalah teknik
untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai
jumlah kouta yang diinginkan.
Asumsi dasar peneliti menggunakan teknik sampel kouta per angkatan adalah
untuk melihat kecendrungan jawaban responden pada setiap angkatan responden.
Walaupun peneliti menggunakan teknik sampling kouta, namun didalam memilih
responden di lapangan, peneliti menggunakan teknik acak. Adapun kriteria responden
diantaranya ; mahasiswa angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016. Pertimbangan peneliti
menetapkan mahasiswa angkatan 2013 sebagai batas atas karena untuk mahasiswa
angkatan 2012 dan 2011 dianggap sulit lagi ditemukan di areal kampus. Sementara
untuk mahasiswa angkatan 2016 sebagai batas bawah karena untuk mahasiswa
angkatan 2017 dianggap masih baru dan belum terlalu mengenal dinamika kampus.
Maka untuk masing-masing angkatan, peneliti telah menetapkan sebanyak 5% dari
total seluruh mahasiswa per-angkatan yang ditaksir berjumlah 300-350 mahasiswa
yang masuk setiap tahunnya di FISIP Unhas. Sehingga didapatkan jumlah responden
sebanyak 15 mahasiswa untuk setiap angkatan dan total keseluruhan sebanyak 60
mahasiswa.
Selain karakteristik angkatan, peneliti juga telah menetapkan karakter responden
berikutnya berupa menjadi aktivis lembaga kemahasiswaan dengan asumsi bahwa
mereka yang aktif terlibat dalam lembaga kemahasiswaan dinilai memiliki kapasitas
pengetahuan yang lebih tentang wacana organisasi, gerakan, dan ideologi
sebagaimana topik penelitian ini yang membahas tentang gerakan ideologis. Karakter
terakhir yakni beragama islam, dengan pertimbangan bahwa mereka yang beragama
islam dinilai lebih paham akan agamanya sendiri ketimbangan mahasiswa yang non-
muslim karena topik penelitian yang diangkat seputar gerakan radikalisme dalam
islam.
Daftar responden beserta identitasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 1.3 DAFTAR DISTRIBUSI RESPONDEN
DEPARTEMEN JUMLAH ANGKATAN JUMLAH
Antropologi 8 2013 15
Hubungan Internasional 8 2014 15
Ilmu Politik 7 2015 15
Ilmu Komunikasi 10 2016 15
Ilmu Administrasi Negara 6
Ilmu Pemerintahan 8
Sosiologi 13
JUMLAH 60 orang 60 orang
Tabel 1.3 : Sumber data primer 2017
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Secara teoritis, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil
penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data.
Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrument
sementara kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang
digunakan untuk mengumpulkan data.
Lebih lanjut, jika dilihat dari segi cara mendapatkan data, terdapat 3 teknik
pengumpulan data yaitu interview (wawancara), kuesioner (angket) dan observasi
(pengamatan) serta gabungan ketiganya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket/kuesioner untuk
mengumpulkan data. Teknik ini dilakukan dengan cara membagikan daftar
pertanyaan kepada responden yang kemudian ia memberikan jawaban pada setiap
pertanyaan yang ada.
E. SUMBER DATA PENELITIAN
Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi
atau keterangan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan
fakta. Juga dapat didefinisikan data adalah kumpulan fakta, angka, atau sesuatu yang
dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu
kesimpulan.
Syarat – syarat data yang baik adalah :
1. Data harus akurat
2. Data harus relevan
3. Data harus up to date
Secara garis besar, data dibagi kedalam beberapa kelompok. Jika dilihat dari cara
memperoleh data, maka terdiri dari 2 jenis, diantaranya ;
1. Data primer
Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama
atau tempat objek penelitian dilakukan. Adapun data primer dalam penelitian ini
yakni responden (mahasiswa) yang akan diteliti.
2. Data sekunder
Yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan
pengolahnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni buku, jurnal
maupun sumber internet.
F. TEKNIK ANALISIS DATA
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari
seluruh responden atau sumber data terkumpul. Dalam penelitian kuantitatif kegiatan
analisis datanya meliputi; pengelolahan data dan penyajian data, melakukan
Gambar 1.2 Ilustrasi Proses Pengumpulan dan Pengelolahan Data
perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan
menggunakan uji statistik. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis,
langkah terakhir tidak dilakukan.
a. Pengelolahan Data
Sebelum data dianalisis, maka langkah pertama yang ditempuh peneliti
adalah pengelolahan data. Setalah data berhasil dikumpul melalui kuesioner, data
kemudian diolah melalui beberapa tahap. Berikut peneliti sajikan ilustrasi
proses pengelolahan data mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi data.
Dalam melakukan proses pengelolahan dan analisis data, ada beberapa
langkah atau tahap yang mesti ditempuh. Tahapan- tahapan tersebut sebagai
berikut :
Pengelolahan data :
- Editing data
- Coding data
- Tabulasi data
Pengumpulan data
(kuesioner)
Analisis data :
- Penyajian data
- Uji statistik
Interpretasi data
1. Editing (pemeriksaan data)
Langkah ini dilakukan untuk memeriksa data yang telah berhasil
dikumpulkan dari lapangan. Tujuan dilakukannya editing adalah untuk
mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada
catatan lapangan. Pada proses ini, peneliti menemukan beberapa kekurangan
yang dilakukan oleh responden pada saat pengisian kuesioner seperti tidak
mengisi kolom pertanyaan secara lengkap, uraian jawaban yang ditulis
kurang jelas sehingga sulit dibaca.
2. Coding (pengkodean data)
Setelah tahap editing selesai dikerjakan dan jawaban responden dalam
kuesioner dipandang cukup memadai, maka langkah berikutnya adalah
pemberian kode (coding). Coding data merupakan suatu proses penyusunan
secara sistematis data mentah (yang ada dalam kuesioner) ke dalam bentuk
yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data seperti komputer. Pada proses
ini, peneliti melakukan pengkodean data pada variabel – variabel yang ada
dalam kuesioner seperti identitas responden, variabel Negara islam, variabel
pancasila dan variabel syariat islam.
3. Pemindahan Data Ke Komputer (Data Entering)
Pada langkah ini, peneliti memindahkan data yang telah dikode ke
dalam mesin pengolah data dengan menggunakan salah satu pengelolahan
data yaitu aplikasi SPSS (Statistical Package For Sosial Science).
Pemindahan data ke komputer dilakukan setelah semua kuesioner selesai
diberi kode.
4. Pembersihan data (Data Cleaning)
Data Cleaning adalah memastikan bahwa seluruh data yang telah
dimasukkan ke dalam mesin pengolah data sudah sesuai dengan sebenarnya.
Pembersihan data dilakukan untuk pengecekan keseluruhan data yang
dimasukkan dalam komputer untuk mengetahui apakah seluruh data telah
sesuai dengan yang ada dalam kuesioner.
b. Analisis Data
Setelah data diolah menggunakan SPSS, peneliti kemudian melanjutkan ketahap
selanjutnya yaitu analisis data yang meliputi penyajian data (data output) dan uji
statistik.
1. Penyajian Data (Data Output)
Data output adalah hasil pengolahan data. Dalam menyajikan data, peneliti
menggunakan beberapa model penyajian data seperti penggunaan tabel,
diagram maupun grafik.
2. Penganalisaan Data (Data Analyzing)
Pada tahap ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif. Hal ini sesuai
dengan judul dan rumusan masalah penelitian ini yang hanya
mendeskripsikan pandangan mahasiswa islam terhadap wacana pendirian
Negara islam di Indonesia.
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. SEJARAH SINGKAT UNIVERISTAS HASANUDDIN
Universitas Hasanuddin atau yang disingkat Unhas secara resmi didirikan pada
tanggal 10 september tahun 1956. Jika ditelusuri, embrio lahirnya Unhas berasal dari
Fakultas Ekonomi cabang Universitas Indonesia (UI) Jakarta yang telah berdiri di
Makassar sejak tahun 1947. Kemudian sejak dikeluarkannya SK. Menteri PP dan K No.
3369/s tanggal 11 juni 1956 terhitung mulai 1 September 1956 dan dengan PP No. 23
tanggal 8 September 1956, Unhas telah dipimpin oleh sejumlah Rektor mulai dari Prof.
Mr.A.G. Pringgodigdo sebagai Rektor pertama hingga Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu,
M.A yang tengah menjabat sekarang (www.unhas.ac.id).
Kemudian pada tanggal 3 Maret 1953, fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masyarakat cabang Fakultas Hukum UI resmi dibuka. Disusul oleh fakultas Kedokteran
pada Oktober 1953, fakultas Teknik pada 1963, fakultas Sastra pada 1960, fakultas Sosial
Politik pada 1961, fakultas Pertanian 1962, fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA)
1963, fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan 1963, Fakultas Kedokteran Gigi 1983,
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) 1982, dan Fakultas ilmu Kelautan 1996
(www.unhas.ac.id).
Adapun Visi dari Unhas adalah Pusat Unggulan Dalam Pengembangan Insani, Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Budaya Berbasis Benua Maritim Indonesia.
Sedangkan Misi dari Unhas sebagai berikut ;
• Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas
pembelajar yang inovatif dan proaktif.
• Melestarikan, mengembangkan, menemukan dan menciptakan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya.
• Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
Selain itu, unhas juga memiliki nilai sebagai berikut ;
• Integritas: mewakili jujur, berani, bertanggung jawab dan teguh dalam pendirian.
• Inovatif: merupakan kombinasi dari kreatif, berorientasi mutu, mandiri dan kepeloporan.
• Katalitik: mewakili sifat berani, keteguhan hati, dedikatif dan kompetitif.
• Arif: manifestasi kepatutan, adil dan beradab, holistik dan asimilatif.
B. SEKILAS TENTANG FISIP UNHAS
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebelum resmi berdiri sebagai bagian dari salah
satu Fakultas di Universitas Hasanuddin (UNHAS), pada awalnya merupakan perguruan
tinggi swasta yang bernama Fakultas Tata Praja Universitas 17 Agustustur 1945, yang
didirikan oleh Mr. Tjia Kok Tjiang (Alm.) di Ujung Pandang. Dapat dicatat disini bahwa
Fakultas Tata Praja (Public Administration) tersebut, merupakan yang pertama ketika itu
didirikan di Kawasan Timur Indonesia.
Dalam perkembangannya, Fakultas Tata Praja tersebut oleh para pendirinya
diusahakan akan dilebur ke dalam Fakultas Ekonomi UNHAS, yang direncanakan
menjadi salah satu jurusan yang ada dan dapat dibuka pada tahun kuliah 1959 – 1960.
Namun disebabkan berbagai kesulitan teknis yang dihadapi sehingga realisasinya tidak
dapat dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut (follow up), dari rencana itu diupayakan lagi
pelaksanaannya agar fakultas ini dimasukkan ke dalam lingkungan UNHAS sebagai
fakultas yang berdiri sendiri sesuai keinginan semula dari pelopor pendirinya.
Dalam rencana penegeriannya itu, semula diharapkan agar dapat terealisasi pada
tanggal 10 September 1960 bertepatan dengan perayaan Dies Natalis IV UNHAS pada
waktu yang mana direncanakan pula peresmian berdirinya Fakultas Sastra dan Filsafat
serta Teknik. Namun karena adanya berbagai kesulitan teknis kembali yang dihadapi,
maka rencana tersebut barulah terlaksana melalui SK Menteri P.P & K dengan Surat
Keputusan tertanggal 30 Januari 1961 No. : A.4692/U.U.41961, terhitung mulai tanggal 1
Februari 1961. Dengan peresmiannya itu, maka mahasiswanya pun dialihkan menjadi
mahasiswa negeri dengan beberapa ketentuan (syarat) yaitu harus menempuh ujian
Negara yang diselenggarakan oleh satu panitia yang dibentuk oleh Menteri P.P & K yang
beranggotakan terdiri atas dosen-dosen UNHAS.
Perlu diketahui bahwa dalam rangka usaha peresmian/penegerian perguruan
tinggi dan perkembangan UNHAS pada umumnya dan FISIP pada khususnya, telah turut
serta memberikan bantuan yang besar sekali artinya bagi perkembangan pendidikan dapat
disebutkan antara lain Pagdam XIV Hasanuddin (sekarang bernama Pangdam VII
Wirabuana) waktu itu Bapak Brigjen. M. Yusuf (mantan Menhankam Pangab dan Ketua
Bapeka RI), Bapak Andi Pangeran Pettarani (Gubernur pada saat itu), dan beberapa
pejabat tinggi lainnya.
Pada saat setelah penegerian itu, maka datanglah pimpinan fakultas yaitu Mr. Tjia
Kok Tjiang sebagai pejabat Ketua, sedangkan Sekretaris diserahkan kepada Mr. Soekanto
sebagai pejabat. Namun Mr. Tjia Kok Tjiang hanya sempat memimpin dan membina
perguruan tinggi ini selama kurang lebih 5 (lima) bulan, berhubung karena beliau
meninggal dunia secara tiba-tiba pada tanggal 3 Mei 1961 pada saat sementara
berlangsung ujian negara bagi mahasiswa dalam rangka persyaratan penegerian fakultas
ini, dan selanjutnya sepeninggal beliau, pimpinan Perguruan Tinggi ini dipegang
langsung oleh Presiden UNHAS (Arnold Monotutu) sebagai pejabat Ketua.
Jumlah tenaga pengajar pada saat penegeriannya sebanyak 16 orang termasuk
asisten, sedangkan jumlah mahasiswa seluruhnya 228 orang yang terdiri dari tingkat
persiapan 91 orang, tingkat (B.A)-I sebanyak 61 orang, dan 32 orang ditingkat (B.A)-II
guna pengurusan/penyelenggaraan administrasinya, dipindahkan 2 (dua) orang tenaga
dari pegawai kantor UNHAS dengan dibantu oleh tenaga pegawai harian, sedangkan
bendaharawan dipegang langsung oleh Mr. Soekanto.
Perubahan selanjutnya Perguruan Tinggi Tata Praja sesudah penegeriannya itu,
diubah statusnya menjadi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hasanuddin
berdasarkan Surat Keputusan Menteri P.P & K RI tanggal 30 Januari 1961 No. :
A/4692/U.U/5/1961 dengan 2 jurusan di dalamnya, yaitu Jurusan Tata Praja (Public
Administration) dan Jurusan Publisistik. Adapun Jurusan Publisistik ini merupakan
peralihan dari Perguruan Tinggi Pers dan Publisistik Sulawesi yang sebelumnya didirikan
di Makassar oleh sebuah Yayasan atas dorongan dan bantuan penuh Panglima Brigjen M.
Yusuf dalam rangkan mempertinggi mutu dan kemampuan tenaga “Policy Man”.
Dalam perkembangannya, Jurusan Tata Praja mengalami lagi perubahan atau
penyempurnaan. Hal tersebut disebabkan kesalahan pengertian sementara pihak yang
beranggapan bahwa Tata Praja dihubungkan atau diasosiasikan dengan pengertian
Perguruan Tinggi Pamong Praja. Namun setelah Lembaga Administrasi Negara (LAN)
diresmikan oleh Pemerintah dimana dengan resmi pula istilah “Public Administration”,
diterjemahkan menjadi Administrasi Negara, barulah nama Tata Praja disesuaikan pula
dan diubah menjadi Jurusan Administrasi Negara. Sedangkan Jurusan Publisistik tetap
dipergunakan karena telah mendapat persetujuan dari Menteri P.P & K. Selain itu juga
digunakan sebagai nama Jurusan pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan
Kemasyarakatan Universitas Indonesia di Jakarta dan Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Gajah Mada.
Tanggal 15 November 1962, Mr. Soekanto diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu
Sosial Politik Universitas Hasanuddin, sedangkan kedudukan sekretaris dipercayakan
kepada Abdullah Amu. Selanjutnya Prof. Arnoal Mononutu kembali yang menjabat
sebagai Dekan, sedangkan E. A. Mokodompit, MA dipercaya sebagai Kuasa Dekan I
bersama Drs. Jonathan Salusu sebagai Kuasa Dekan II. Tanggal 1 Januari 1964 struktur
pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Politik kembali berubah dengan diangkatnya E. A.
Mokodompit sebagai dekan, dengan didampingi oleh Pembantu Dekan I Drs. Jonathan
Salusu (untuk Bidang Akademik), Pembantu Dekan II G.R. Pantow (untuk Bidang
Administrasi dan Kesejahteraan), dan Pembantu Dekan III Drs. Hasan Walinono (untuk
Bidang Kemahasiswaan). Teaching Staff pada saat itu terdapat 20 orang Dosen Tetap,
dosen LB 25 dan Asisten LB 15 orang.
Pada tahun 1967 keadaan mahasiswa tercatat sejumlah 1.338 orang terdiri atas :
309 orang tingkat persiapan, 348 orang tingkat Sarjana Muda I, 135 orang Tingkat Muda
II, 93 orang Tingkat Sarjana I, dan 135 orang Tingkat Sarjana II, jumlah Sarjana yang
dihasilkan saat itu sebanyak 81 orang diantaranya 2 orang Sarjana Publistik. Selanjutnya,
dalam usia perkembangannya selama 7 tahun FISIP – UNHAS mengalami pergantian
pimpinan yang silih berganti. Tahun 1965 s/d 1969 pimpinan Fakultas dijabat oleh Drs.
Hasan Walinono, dan kemudian tahun 1970 – 1971 dijabat kembali oleh Drs Jonathan
Salusu dengan sekretaris Drs. Sadly AD. Tahun 1971-1972 jabatan Dekan Fakultas
kembali dipegang oleh Drs. Hasan Walinono, sedangkan sekretarisnya adalah Drs. A. S.
Achmad.
Sejalan dengan usaha renaca penataan Kampus UNHAS Baraya, maka Fakultas
Ilmu Sosial Politik sebagai satu-satunya Fakultas yang berlokasi di luar kampus juga
direncanakan berpindah lokasi ke kampus Baraya. Hal mana baru dapat terlaksana pada
tahun 1974 setelah terjadi pergantian pimpinan Universitas dari Prof. Dr. A. Hafied
kepada Prof. Dr. A. Amiruddin (mantan Gubernur Sulawesi Selatan, sekarang Wakil
Ketua MPR RI) saat itu.
Dengan pindahnya Fakultas Ilmu Sosial Politik ke Kampus Baraya dan
menempati salah satu gedung di belakang Fakultas Teknik, maka gedung Fakultas ini
yang berlokasi di jalan Dr. Ratulangi 93 dijual kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan, dan meruapakan modal pertama dalam pembelian tanah di Tamalanrea
yang dewasa ini telah dibangun menjadi Kampus Baru UNHAS. Sehubungan dengan itu,
pada tahun 1975 Drs. A. S. Achmad berangkat ke negeri Belanda untuk memperdalam
studi bidang Komunikasi Pembangunan, maka jabatan sekretaris yang dipegangnya untuk
sementara waktu dijabat oleh Drs. M. Ashar Ahmad, dan pada tahun 1978 dijabat
kembali oleh Drs. A. S. Achmad sampai dengan tahun 1977.
Dengan ditunjuknya UNHAS sebagai Proyek Perintis Pembangunan Perguruan
Tinggi untuk jangka waktu lima tahun sesuai SK Menteri P dan K RI No. : 08/U/1977
tanggal 10 Januari 1977, UNHAS mencoba melakukan usaha mencari bentuk dan sistem
organisasi perguruan tinggi yang lebih efektif dan efisien dalam perkembangan
pembangunan. Untuk itu, sejak 1 Februari 1977 diberlakukan sistem organisasi matriks
dimana fakultas mengalami perubahan pengertian. Fakultas hanya merupakan wadah
pengembangan sumber daya ilmu, saran dan pelaksana pendidikan sehingga berada pada
aliran sumber daya.
Sedangkan untuk pengembangan program, monitoring dan evaluasi pendidikan,
penelitian dan pengabdian masayarakat dikelola oleh pusat kajian. Sebagai tindak lanjut
Surat Keputusan tersebut, maka Fakultas Ilmu Sosial Politik yang tadinya berdiri sendiri
sebagai salah satu wadah fakultas dalam jajaran 9 fakultas yang ada di Universitas
Hasanuddin, selanjutnya digabung bersama Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sastra
menjadi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan BUDAYA (FIISBUD) dengan dekannya yang
pertama dijabat oleh Drs. La Tanro pada masa bakti 1977-1980 dan Dr. Kustiah Kristanto
pada masa bakti 1980-1982. Sedangkan untuk pengelolaan dan pengembangan program
pendidikan ilmu-ilmu sosial dan sastra ditunjuk Drs. M. Syukur Abdullah sebagai Dekan
Kajian, keadaan ini berlangsung hingga awal tahun 1983.
Patut dicatat bahwa dalam tahun 1977, sistem kurikulum yang diterapkan sekian
lama untuk penyelesaian dua jenjang pendidikan, yaitu Program Sarjana Muda selama 3
tahun dan Program Sarjana selama 5 tahun diubah menjadi kurikulum sistem kredit yang
memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinyalebih cepat. Langkah inilah
yang merupakan persiapan pelaksanaan Program Pendidikan Strata Satu (S1) yang mulai
dibuka secara serentak dalam lingkungan UNHAS sejak tahun 1980, termasuk dalam
Fakultas Ilmu Sosial Politik, juga pada tahun 1980 dengan selesainya pembangunan
gedung induk Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya di Kampus Baru Tamalanrea, maka
secara bertahap kegiatan akademik dan administrasi fakultas dipindahkan dari Kampus
Baraya ke Kampus Baru Tamalanrea.
Dalam perkembangannya, setelah terjadi pergantian pimpinan Universitas
Hasanuddin dari Prof. Dr. A. Amiruddin kepada Prof. Dr. Hasan Walinono pada akhir
tahun 1982, organisasi fakultas kembali mengalami perubahan sejalan dengan
diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. : 5 tahun 1982 yang mengatur tentang
Struktur Organisasi Perguruan Tinggi di Indonesia. Terhitung 1 Januari 1983 sejalan
dengan perubahan Struktur UNHAS yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 5 Tahun 1980 dan KEPRES. No. : 62/1982, Program Pendidikan Ilmu-
Ilmu Sosial yang dahulu bersumber dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dikembangkan
dalam satu fakultas dengan nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Hal
mana merupakan nama yang sama dipakai pada perguruan tinggi umumnya di Indonesia
(www.fisip.unhas.ac.id).
Adapun visi, misi dan tujuan dari FISIP Unhas dibawah kepemimpinan Dekan
Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si sebagai berikut :
Visi : Sebagai pusat unggulan ilmu sosial dan ilmu politik di Asia Tenggara
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis benua maritim
tahun 2020.
Misi :
• Mengoptimalkan proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang
memiliki kompetensi yang bisa diandalkan, mampu bekerja mandiri, dan
adaptif terhadap kondisi aktual masyarakat.
• Mengembangkan kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan
masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.
• Mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset sesuai
kondisi objektif dan kebutuhan masyarakat melalui kemitraan dengan
berbagai pemangku kepentingan.
• Meningkatkan mutu pengelolaan fakultas yang profesional, akuntabel,
transparan dan partisipatif.
Tujuan : Menghasilkan luaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja dan memiliki akhlaq terpuji yang mampu memberikan kontribusi
bagi pengembangan dunia kerja dan masyarakat baik pada tingkat nasional
maupun internasional (www.fisip.unhas.ac.id).
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari 7 departemen diantaranya:
Tabel 1.4. DAFTAR JUMLAH MAHASISWA FISIP UNHAS SEMESTER 2017/2018
NO DEPARTEMEN JUMLAH
MAHASISWA
1 ANTROPOLOGI 182
2 HUBUNGAN INTERNASIONAL 272
3 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 370
4 ILMU KOMUNIKASI 317
5 ILMU PEMERINTAHAN 232
6 ILMU POLITIK 204
7 SOSIOLOGI 193
TOTAL 1770
Tabel 1.4 Sumber data bidang akademik FISIP UH 2017
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana masalah yang peneliti angkat yaitu “radikalisme agama dan masa depan
ideologi bangsa : studi pandangan mahasiswa islam terhadap wacana pendirian negara Islam
(khilafah islamiyah) di Indonesia”, maka pendekatan yang peneliti gunakan yakni analisis
deskriptif - kuantitatif guna melihat bagaimana kencendrungan pandangan mahasiswa Islam
terhadap wacana pendirian negara Islam di Indonesia serta bagaimana mahasiswa Islam
menafsirkan kedudukan Pancasila dan syariat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Berikut peneliti paparkan hasil penelitian tersebut kedalam dua bagian utama sesuai dengan
rumusan masalah yang ditawarkan dalam penelitian ini. Bagian pertama mendeskripsikan
bagaimana pandangan mahasiswa tentang negara Islam dan bagian kedua mendeskripsikan
bagaimana pandangan mahasiswa tentang pancasila dan syariat islam.
A. HASIL PENELITIAN
1. Identitas Responden
Berdasarkan metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini yakni
metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel berupa teknik kouta sampling,
maka peneliti telah menetapkan total sampel sebanyak 60 responden mahasiswa. Adapun
karakteristik responden diantaranya; beragama islam, aktivis lembaga kemahasiswaan
serta terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016. Alasan
peneliti menetapkan mahasiswa angkatan 2013 sebagai batasan atas kriteria responden
dikarenakan untuk mahasiswa angkatan 2012 dan 2011 dianggap relatif sulit untuk
ditemui lagi di areal kampus, sementara untuk batasan bawah dipilih mahasiswa angkatan
2016 dikarenakan untuk mahasiswa angkatan 2017 diasumsikan masih tergolong
mahasiswa baru yang belum terlalu mengenal dinamika kehidupan kampus.
Untuk penjabaran data identitas responden yang lebih lengkap, berikut peneliti
sajikan ke dalam bentuk tabel :
a. Jenis kelamin
Tabel 1.5. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 1.5.Sumber data primer 2017
Dapat dilihat pada tabel 1.5 tersebut dimana dari total 60 responden mahasiswa,
hasil jumlah responden untuk jenis kelamin laki- laki sebanyak 32 orang (53,3%),
sementara untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 28 orang (46,7%).
b. Departemen
Tabel 1.6. Distribusi Responden Berdasarkan Departemen
NO DEPARTEMEN
JUMLAH
RESPONDEN
1 Antropologi 8
NO JENIS KELAMIN JUMLAH RESPONDEN
1 LAKI LAKI 32
2 PEREMPUAN 28
60
2 Hubungan Internasional 8
3 Ilmu Politik 7
4 Ilmu Komunikasi 10
5 Ilmu Administrasi Negara 6
6 Ilmu Pemerintahan 8
7 Sosiologi 13
60
Tabel 1.6 Sumber data primer 2017
Untuk kategori departemen, dapat dilihat pada tabel 1.6 dimana jumlah responden
yang didapatkan untuk Departemen Antropologi sebanyak 8 orang (13,3%),
Departemen HI sebanyak 8 orang (13,3%), Departemen Ilmu Politik sebanyak 7
orang (11,7%), Departemen Ilmu Komunikasi sebanyak 10 orang (16,7%),
Departemen Ilmu Administrasi Negara sebanyak 6 orang (10%), Departemen Ilmu
Pemerintahan sebanyak 8 orang (13,3%) dan untuk Departemen Sosiologi sebanyak
13 orang (21,7%).
c. Angkatan
Tabel 1.7. Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan
Tabel 1.7 Sumber data primer 2017
Untuk kategori angkatan, dapat dilihat pada tabel 1.7 tersebut dimana jumlah
responden untuk masing – masing angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016 sebanyak 15
orang (25%).
Dalam penentuan sampel, peneliti mengolaborasikan beberapa teknik pengambilan
sampel yakni random sampling dan kouta sampling. Hal ini bertujuan untuk menyaring
dan menjaring secara tepat siapa saja yang nanti akan mendapatkan kuesioner.
Pada tabel 1.7 dapat dilihat distribusi responden yang merata dengan masing masing
angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 berjumlah 15 responden dimana asumsi dasarnya
adalah rata – rata populasi mahasiswa setiap angkatannya untuk setiap tahun berkisar 300
– 350 mahasiswa sehingga teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah
kouta sampling dengan proporsi sampel setiap angkatan yang diambil sebesar 5% dari
total mahasiswa setiap angkatan yang bersangkutan.
NO ANGKATAN JUMLAH
1 2013 15
2 2014 15
3 2015 15
4 2016 15
60
Sementara pada tabel 1.5 terlihat distribusi responden yang tidak merata dikarenakan
peneliti menggunakan teknik penarikan sampel secara acak dengan asumsi bahwa
perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi esensi jawaban yang ingin dicari oleh
peneliti. Begitu juga dengan kategori departemen pada tabel 1.6 juga terlihat distribusi
responden yang tidak merata dikarenakan peneliti menggunakan teknik pengambilan
sampel secara acak. Asumsi dasarnya adalah proporsi jumlah mahasiswa untuk setiap
departemen/himpunan mahasiswa jurusan tidak merata.
2. Hasil Jawaban Responden
Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ajukan berupa 1) bagaimana pandangan
mahasiswa islam terhadap wacana pendirian Negara Islam di Indonesia, 2) Bagaimana
pandangan mahasiswa islam terhadap kedudukan Pancasila dan syariat islam, berikut
hasil yang didapatkan ;
a. Pandangan Mahasiswa Islam terhadap Wacana Pendirian Negara Islam
Untuk rumusan masalah ini, hasil yang peneliti dapatkan adalah dari 60
responden mahasiswa, sebanyak 9 orang (15 %) menjawab setuju apabila negara
Islam didirikan di Indonesia dan 51 orang (85 %) yang tidak setuju atas wacana
tersebut. Data dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut ;
Diagram 1.1. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pendirian Negara
Islam di Indonesia
Diagram 1.1. Sumber data primer 2017
Kemudian peneliti mencoba melakukan persilangan data beberapa variabel identitas
responden seperti jenis kelamin, departemen dan angkatan dengan beberapa variabel
rumusan masalah seperti negara islam, pancasila dan syariat islam. Hal ini bertujuan
untuk melihat kecendrungan jawaban responden jika dilihat dari identitasnya.
Untuk hasil persilangan antara variabel jenis kelamin dengan variabel negara
islam, didapatkan hasil bahwa jumlah laki laki yang menjawab setuju sebanyak 5
orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Adapun yang menjawab tidak setuju,
laki laki sebanyak 27 orang dan perempuan sebanyak 24 orang. Data dapat dilihat
pada tabel 1.8 berikut ;
15%
85%
Setuju = 9 orang
Tidak setuju = 51orang
Tabel 1.8. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pendirian Negara Islam di
Indonesia Ditinjau dari Jenis Kelaminnya
JENIS KELAMIN SETUJU TIDAK JUMLAH
Laki – laki 5 27 32
Perempuan 4 24 28
Jumlah 9 51 60
Tabel 1.8 Sumber data primer 2017
Untuk hasil persilangan variabel departemen dengan variabel negara islam
didapatkan hasil bahwa pada Depertemen Antropologi yang setuju sebanyak 3 orang
dan tidak setuju 5 orang, Departemen Hubungan Internasional yang setuju
sebanyak 1 orang dan tidak setuju 7 orang, Departemen Ilmu Administrasi Negara
yang setuju sebanyak 1 orang dan tidak setuju 5 orang, Departemen ilmu
Komunikasi yang setuju sebanya 2 orang dan tidak setuju 8 orang, Departemen Ilmu
Pemerintahan yang setuju sebanyak 1 orang dan tidak setuju 7 orang, Departemen
Ilmu Politik yang setuju tidak ada dan tidak setuju 7 orang, Departemen Sosiologi
yang setuju sebanyak 1 orang dan tidak setuju sebanyak 12 orang. Hasil data yang
lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut ;
Tabel 1.9. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pendirian Negara Islam di
Indonesia Ditinjau dari Departemennya
DEPARTEMEN SETUJU TIDAK JUMLAH
Antropologi 3 5 8
Hubungan internasional 1 7 8
Ilmu Administrasi Negara 1 5 6
Ilmu Komunikasi 2 8 10
Ilmu Pemerintahan 1 7 8
Ilmu Politik 0 7 7
Sosiologi 1 12 13
Jumlah 9 51 60
Tabel 1.9 Sumber data primer 2017
Kemudian untuk hasil persilangan variabel angkatan dengan variabel negara
islam didapatk hasil bahwa pada angkatan 2016 yang setuju sebanyak 4 orang dan
tidak setuju sebanyak 11 orang, angkatan 2015 yang setuju sebanyak 1 orang dan
tidak setuju 14 orang, angkatan 2014 yang setuju sebanyak 2 orang dan tidak setuju
13 orang, angkatan 2013 yang setuju sebanyak 2 orang dan tidak setuju 13 orang.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut ;
Tabel 1.10. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pendirian Negara Islam di
Indonesia Ditinjau dari Angkatannya
ANGKATAN SETUJU TIDAK JUMLAH
2016 4 11 15
2015 1 14 15
2014 2 13 15
2013 2 13 15
JUMLAH 9 51 60
Tabel 1.10 Sumber data primer 2017
Kemudian untuk konteks Indonesia sebagai negara demokratis, maka
menyuarakan gagasan atau pendapat adalah hak bagi setiap warga negara yang telah
dijamin oleh UU. Namun bagaimana jika terdapat kelompok/organisasi masyarakat
(ormas) yang hendak menyuarakan gagasan atau wacana untuk mendirikan negara
Islam di Indonesia yang secara konstitusional dianggap sebagai tindakan makar
terhadap negara atau dicap sebagai ormas yang menganut paham radikalisme ?.
Jika ditinjau dari PERPU Ormas tahun 2017, maka sanksi yang paling ringan
bagi ormas yang dianggap melakukan tindakan radikalisme adalah peneguran dan
sanksi yang paling berat adalah pembubaran. Lalu bagaimana pendapat aktivis
mahasiswa yang beragama islam tentang pembubaran ormas di negara demokrasi ini
?.
Dari 60 responden mahasiswa, sebanyak 40 orang (66,7 %) menjawab setuju
jika kelompok/ormas Islam yang menganut paham radikalisme dibubarkan oleh
pemerintah, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 20 orang (33,3%).
Untuk sajian data dapat dilihat dalam diagram berikut :
Diagram 1.2. Distribusi Pandangan Responden terhadap Pembubaran Ormas
yang Menganut Paham Radikalisme di Indonesia
Diagram 1.2. Sumber data primer 2017
Selain itu, dengan menggunakan teknik pengukuran data skala likert, beberapa buah
pertanyaan yang menjadi turunan dari variabel negara Islam juga didapat hasil
sebagai berikut ;
i. Negara Islam adalah perwujudan Islam secara kaffah
Hasil yang peneliti dapatkan dari 60 responden mahasiswa, sebanyak 4 orang
(6,7 %) yang sangat setuju dan 20 orang (33,3 %) yang setuju bahwa penerapan
negara islam adalah bentuk pengamalan islam secara kaffah (totalitas). Sedangkan
sebanyak 4 orang (6,7%) yang sangat tidak setuju dan 14 orang (23,3%) yang
tidak setuju bahwa penerapan negara islam adalah bentuk pengamalan islam
secara kaffah. Sementara yang menjawab netral sebanyak 18 orang (30%).
Grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :
66.70%
33.30% Setuju = 40 orang
Tidak Setuju = 20orang
Diagram 1.3. Distribusi Pandangan Responden Terhadap Penerapan Syariat
Islam secara Kaffah
Diagram 1.3 Sumber data primer 2017
ii. Formalisasi Syariat Islam
Dari hasil penelitian yang didapatkan menyatakan bahwa dari 60 responden
mahasiswa, sebanyak 3 orang (5%) sangat setuju dan 20 orang (33,3%) setuju
terhadap formalisasi syariat Islam atau dibuatkan undang-undang syariah.
Sedangkan sebanyak 5 orang (8,3%) sangat tidak setuju dan 18 orang (30%) tidak
setuju terhadap formalisasi syariat islam atau undang – undang syariah.
Sementara sebanyak 14 orang (23,3%) menjawab netral. Grafiknya dapat dilihat
berikut :
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
SangatSetuju
Setuju Netral TidakSetuju
SangatTidakSetuju
4
20
18
14
4
Frekuensi Mahasiswa
Diagram 1.4. Distribusi Pandangan Responden Terhadap Formalisasi
Syariat Islam
Diagram 1.4. Sumber data primer 2017
iii. Syariat Islam dan Cara Penegakannya
Hasil yang peneliti dapatkan adalah dari 60 responden mahasiswa, 9 orang
(15%) menjawab sangat setuju dan 23 orang (38,3%) menjawab setuju jika syariat
islam ditegakkan secara tegas (tanpa konpromi). Sedangkan 4 orang (6,7%)
menjawab sangat tidak setuju dan 8 orang (13,3%) tidak setuju jika syariat islam
ditegakkan secara tegas. Sementara 16 orang (26,7%) menjawab netral.
3
20
14
18
5
0
5
10
15
20
25
SangatSetuju
Setuju Netral TidakSetuju
SangatTidakSetuju
Frekuensi Mahasiswa
Diagram 1.3. Distribusi Pandangan Responden Terhadap Penegakan Syariat
Islam dengan Sikap Tegas
Diagram 1.5. Sumber data primer 2017
b. Pandangan Mahasiswa Islam tentang Kedudukan Syariat Islam dan Pancasila
Untuk rumusan masalah kedua, hasil yang didapatkan oleh peneliti menyebutkan
bahwa dari 60 responden mahasiswa, sebanyak 1 orang (1,7%) menjawab sangat
setuju dan 7 orang (11,7%) menjawab setuju jika syariat islam dikesampingkan
apabila tidak sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Sedangkan sebanyak 10
orang (16,7%) menjawab sangat tidak setuju dan 25 orang (41,7%) menjawab
tidak setuju apabila syariat islam dikesampingkan meskipun bertentangan dengan
hukum negara yang berlaku. Sementara sebanyak 17 orang (28,3%) menjawab
netral. Grafiknya ditampilkan sebagai berikut :
9
23
16
8
4
0
5
10
15
20
25
SangatSetuju
Setuju Netral TidakSetuju
SangatTidakSetuju
Frekuensi Mahasiswa
Diagram 1.6. Distribusi Jawaban Mahasiswa Terhadap Upaya Pengesampingan
Syariat Islam Apabila Tidak Sesuai dengan Hukum Negara yang Berlaku
Diagram 1.6. Sumber data primer 2017
Sebagaimana pada rumusan masalah pertama, peneliti juga mencoba
menyilangkan variabel identitas responden dengan variabel rumusan masalah kedua
yaitu kedudukan pancasila dan syariat islam.
Untuk hasil persilangan data antara variabel jenis kelamin dengan variabel
kedudukan pancasila dan syariat islam didapatkan hasil bahwa untuk kelompok
jawaban setuju sebanyak 6 orang laki – laki dan sebanyak 2 orang perempuan.
Sementara untuk kelompok jawaban netral, sebanyak 11 orang laki – laki dan 6
orang perempuan. Adapun untuk kelompok jawaban tidak setuju, sebanyak 15 orang
laki – laki dan perempuan sebanyak 20 orang. Untuk data lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 2.1 berikut;
2%12%
28%
41%
17%
Sangat Setuju = 1 orang
Setuju = 7 orang
Netral = 17 orang
Tidak Setuju = 25 orang
Sangat Tidak Setuju =10 orang
Tabel 2.1. Distribusi Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengesampingan Syariat
Islam Apabila Tidak Sesuai dengan Hukum Negara yang Ditinjau dari Jenis
Kelaminnya
JENIS KELAMIN SS S N TS STS JUMLAH
Laki – laki 1 5 11 10 5 32
Perempuan 0 2 6 15 5 28
Jumlah 1 7 17 25 10 60
Tabel 2.1 Sumber data primer 2017
Kemudian untuk hasil persilangan data antara variabel departemen dengan
variabel kedudukan pancasila dan syariat islam didapatkan hasil bahwa Departemen
Antropologi sebanyak 1 orang yang masuk kelompok setuju, 3 orang menjawab
netral dan 4 orang masuk kelompok tidak setuju. Departemen Hubungan
Internasional sebanyak 2 orang masuk kelompok setuju, 2 orang netral dan 4 orang
masuk kelompok tidak setuju. Departemen Ilmu Komunikasi, sebanyak 2orang
masuk kelompok setuju, 1 netral dan 7 orang masuk kelompok tidak setuju.
Departemen Ilmu Administrasi Negara tidak ada yang menjawab setuju dan netral,
6 orang yang menjawab tidak setuju. Departemen ilmu Pemerintahan sebanyak 1
orang masuk kelompok setuju, 2 orang netral dan 5 orang masuk kelompok tidak
setuju. Departemen Ilmu Politik sebanyak 1 orang masuk kelompok setuju, 5 orang
netral dan 1 orang masuk kelompok tidak setuju. Departemen Sosiologi sebanyak 1
orang masuk kelompok setuju, 4 orang netral dan 8 orang masuk kelompok tidak
setuju. Untuk data lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut;
Tabel 2.2. Distribusi Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengesampingan Syariat
Islam Apabila Tidak Sesuai dengan Hukum Negara yang Ditinjau dari
Departemennya
DEPARTEMEN SS S N TS STS JUMLAH
Antropologi 0 1 3 3 1 8
Hubungan Internasional 0 2 2 1 3 8
Ilmu Administrasi Negara 0 0 0 6 0 6
Ilmu Komunikasi 1 1 1 5 2 10
Ilmu Pemerintahan 0 1 2 4 1 8
Ilmu Politik 0 1 5 1 0 7
Sosiologi 0 1 4 5 3 13
Jumlah 1 7 17 25 10 60
Tabel 2.2 Sumber data primer 2017
Untuk hasil persilangan data antara variabel angkatan dengan variabel kedudukan
pancasila dan syariat islam didapatkan hasil bahwa untuk angkatan 2016 sebanyak 1
orang masuk kelompok jawaban setuju, 5 orang netral, dan 9 orang masuk kelompok
tidak setuju. Angkatan 2015 sebanyak 1 orang masuk kelompok jawaban setuju, 4
orang netral dan 10 orang masuk kelompok tidak setuju. Angkatan 2014 sebanyak 4
orang masuk kelompok setuju, 3 orang netral dan 8 orang masuk kelompok tidak
setuju. Angkatan 2013 sebanyak 2 orang masuk kelompok setuju, 5 orang netral dan
8 orang masuk kelompok tidak setuju. Untuk data lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel 2.3 berikut;
Tabel 2.3. Distribusi Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengesampingan Syariat
Islam Apabila Tidak Sesuai dengan Hukum Negara yang Ditinjau dari
Angkatannya
ANGKATAN SS S N TS STS JUMLAH
2016 1 0 5 8 1 15
2015 0 1 4 8 2 15
2014 0 4 3 3 5 15
2013 0 2 5 6 2 15
JUMLAH 1 7 17 25 10 60
Tabel 2.3 Sumber data primer 2017
Selain pertanyaan utama diatas, berikut peneliti sajikan hasil penelitian dari
beberapa pertanyaan turunan terkait hubungan antara kedua variabel tersebut yakni
variabel syariat islam dan variabel Pancasila.
i. Pancasila dan Relevansinya
Hasil yang peneliti dapatkan bahwasanya dari 60 responden mahasiswa,
sebanyak 6 orang (10%) menjawab sangat tidak setuju dan 25 orang (41,7%)
menjawab tidak setuju jika Pancasila tidak mampu lagi menjamin keadilan dan
kesejahteraan sosial bagi segenap rakyat Indonesia. Sedangkan yang menjawab
sangat setuju sebanyak 4 orang (6,7%) dan yang menjawab setuju sebanyak 5
orang (8,3%) jika Pancasila tidak mampu lagi menjamin keadilan dan
kesejahteraan sosial bagi segenap rakyat Indonesia. Sementara yang menjawab
netral sebanyak 20 orang (33,3%). Grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :
Diagram 1.6. Distribusi Jawaban Mahasiswa Terhadap Relevansi Pancasila
dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
Diagram 1.7. Sumber data primer 2017
ii. Ketidaksesuaian Nilai - Nilai Pancasila dan Syariat Islam
Hasil yang peneliti dapatkan adalah dari 60 responden mahasiswa, sebanyak
1 orang (1,7%) yang menjawab sangat setuju dan 2 orang (3,3%) menjawab setuju
jika nilai-nilai pancasila bertentangan dengan syariat islam. Sedangkan sebanyak
17 orang (28,3%) menjawab sangat tidak setuju dan 20 orang (33,3%) tidak setuju
jika nilai- nilai pancasila dikatakan bertentangan dengan syariat islam. Sementara
20 orang (33,3%) menjawab netral. Grafiknya dapat dilihat sebagai berikut :
Diagram 1.8. Distribusi Jawaban Mahasiswa Terhadap Ketidaksesuaian
antara Nilai – Nilai Islam dan Pancasila
0
5
10
15
20
25
sangatsetuju
setuju netral tidaksetuju
sangattidak
setuju
4 5
20
25
6
Frekuensi Mahasiswa
Diagram 1.8. Sumber data primer 2017
iii. Syariat Islam dan Peluang Penafsirannya
Hasil yang peneliti dapatkan adalah dari 60 responden mahasiswa, sebanyak
10 orang (16,7%) menjawab sangat setuju dan 16 orang (26,7%) menjawab setuju
apabila syariat islam ditafsirkan sesuai dengan konteks zaman dan masyarakatnya.
Sedangkan yang menjawab sangat setuju 5 orang (8,3%) dan tidak setuju 12
orang (20%) apabila syariat islam ditafsirkan sesuai konteks zaman dan
masyarakatnya. Sementara sebanyak 17 orang (28,3%) menjawab netral.
Grafiknya dapati dilihat sebagai berikut :
Diagram 1.9. Distribusi Jawaban Mahasiswa Terhadap Upaya Penafsiran
Syariat Islam sesuai Konteks Zaman dan Masyarakat
02468
101214161820
SangatSetuju
Setuju Netral TidakSetuju
SangatTidakSetuju
12
20 20
17
Frekuensi Mahasiswa
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Pendirian Negara Islam dan Eksistensi Pancasila
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural
Robert Merton dalam menganalisis wacana pendirian negara islam di Indonesia yang
kemudian dibenturkan oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara
Indonesia yang telah diangggap final.
Asumsi dasar dari pendekatan fungsionalisme struktural Merton adalah sebagai
berikut : a) masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian bagian
atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. b) Setiap
struktur dalam sistem sosial selalu melahirkan sisi fungsional dan disfungsional bagi
masyarakat (Ritzer, 2013 : 22).
Hadirnya wacana untuk mendirikan negara islam di Indonesia jika dilihat dari
pendekat fungsionalisme Merton tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai hal yang
fungsional sekaligus disfungsional. Fungsional bagi golongan/kelompok umat islam
yang mengusung wacana tersebut tetapi disfungsional bagi eksistensi bangsa dan
negara Indonesia. Asumsi dasarnya adalah bahwa dalam konteks hidup berbangsa dan
bernegara, masyarakat Indonesia telah diwariskan oleh satu sistem yang baku dan
final yaitu Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan
NKRI sebagai bentuk negara. Oleh karena itu, dengan digulirkannya wacana untuk
mendirikan negara islam di Indonesia maka secara teoritis akan bertentangan dan
mengancam eksistensi ideologi, dasar dan bentuk negara sebagai sesuatu yang telah
terberi (given).
Lalu bagaimana jika ditinjau dari sisi pandangan warga negaranya terutama para
pemudanya yang didaku sebagai pelanjut generasi bangsa dan calon pemimpin masa
depan ini jika diperhadapkan dengan wacana tersebut ?.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 60 responden
mahasiswa FISIP Unhas, diperoleh hasil yang menyebutkan bahwa sebanyak 9 orang
(15 %) menjawab setuju terhadap wacana pendiri negara islam di Indonesia,
sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 51 orang (85%).
Melihat hasil tersebut, terdapat berbagai alasan yang dituliskan oleh responden
baik yang setuju maupun tidak setuju. Misalnya dari pihak yang setuju, menurut JN
mahasiswa angkatan 2013 mengemukakan :
“sebagai umat islam, tentu cita-cita tertinggi adalah segala lini kehidupan
berbasis islam. Tentunya prinsip saling menghargai juga penting untuk agama
lain”
Kemudian menurut OS mahasiswa angkatan 2014 yang juga setuju dengan
pendirian negara islam di indonesia berpendapat bahwa :
“karena hukum dan pedoman hidup kita berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Qur’an
merupakan kitab suci dari umat islam”
Terlepas dari kedalaman dan keluasan pengetahuan yang dimiliki oleh
masing - masing responden yang setuju terhadap wacana negara Islam, peneliti
melihat kecendrungan berbagai alasan yang dikemukakan oleh responden
bahwasanya mereka yang pro akan wacana negara islam dilandasi oleh sebuah
keyakinan (iman) untuk menjalankan seluruh dimensi kehidupan ini berdasarkan
Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup umat islam, termasuk didalam
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun.
Sementara yang tidak setuju terhadap wacana pendirian negara Islam di
Indonesia juga memiliki alasan tersendiri. Misalnya menurut TS mahasiswa
angkatan 2015 menyatakan :
“ karena untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul, Indonesia tidak harus
menjadi negara islam. Banyak peraturan pemerintah yang bisa dibilang baik dan
tidak menyalahi aturan Al-Qur’an dan As-Sunnah”
Lalu pendapat lain yang berasal dari ZZ maahsiswa angkatan 2014 menyatakan
ketidaksetujuannya dengan alasan :
“karena untuk konteks hari ini, konsepsi pancasila masih sangat relevan di
Indonesia”
Adapun menurut AI mahasiswa angkatan 2016 mengatakan :
“karena Indonesia merdeka bukan hanya di tangan orang islam, tapi Indonesia
merdeka dengan beragam agama”
Dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh 51 responden yang kontra
terhadap wacana negara islam tersebut, peneliti melihat kecendrungan respoden
bahwa mereka masih menganggap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
Indonesia yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan suku, agama, ras
dan golongan/kelompok masyarakat Indonesia kedalam sebuah wadah bernama
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sehingga kehendak untuk mendirikan negara islam (Khilafah Islamiyah) di
Indonesia patut untuk dipertimbangkan secara matang, meskipun islam sebagai
agama mayoritas di Indonesia. Tanpa itu, hanya mengantarkan Indonesia kedepan
pintu gerbang perpecahan bangsa.
Selain itu, karakter islam yang terbangun di Indonesia berasal dari iklim yang
moderat dan berwarna kultural sebagaimana menurut pandangan Gus Dur (2006)
bahwa Islam di Indonesia muncul dalam keseharian kultural yang tidak berbaju
ideologis serta tidak mengabaikan pluralitas masyarakat. Sehingga hadirnya
wacana untuk mendirikan negara islam yang sarat akan kepentingan ideologis
dinilai tidak sesuai dengan wajah umat islam Indonesia.
Meskipun mayoritas responden tidak setuju terhadap wacana pendirian
negara Islam di Indonesia, tetapi sebagian besar responden mengharapkan apabila
syariat Islam ditegakkan secara tegas sebagaimana pada diagram 1.5.
menunjukkan sebanyak 32 responden (53,3%) berada pada posisi setuju. Serta
pada diagram 1.4 juga menunjukkan sebanyak 23 orang (38,5%) yang berada
pada posisi setuju apabila syariat islam diformalkan atau dibuatkan perda syariah.
Menurut peneliti, dari angka tersebut menunjukkan adanya indikasi untuk
mengamalkan ajaran islam secara formal atau mengikat pemeluknya secara
konstitusional. Artinya, apabila umat islam melakukan tindakan yang menyalahi
aturan agama maka perlu diberikan sanksi/hukuman kepada yang bersangkutan
sesuai hukum islam, seperti hukuman mati, cambukan, pemotongan tangan dan
seterusnya.
2. Penafsiran Syariat Islam dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Untuk rumusan masalah yang kedua ini, peneliti menggunakan pendekatan fakta
sosial dalam menganalisis bagaimana mahasiswa islam memposisikan dan
menafsirkan dua sumber hukum yang mengikatnya yakni Pancasila dan UUD 1945
sebagai sumber hukum dalam bernegara dan syariat Islam sebagai sumber hukum
dalam beragama.
Dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, ada yang menafsirkan bahwa
agama (Islam) dan negara adalah entitas yang tak terpisah dan adapula yang
menafsirkan sebaliknya bahwa urusan agama (Islam) dan urusan negara harus
dipisah. Dengan kata lain, jika terdapat sebuah persoalan yang dihadapi oleh individu
atau kelompok masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,
maka hukum yang harus digunakan adalah hukum negara yang berlaku, dalam hal ini
Pancasila dan UUD 1945.
Bila ditinjau dari aspek pemikiran, menurut Munawir Sjadzali (dalam Suyuti
Pulungan, tt, h. 2-3), pemikiran politik Islam kontemporer dapat digolongkan ke
dalam tiga aliran. Aliran pertama berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata
dalam pengertian sarjana Barat, yakni hanya mengatur hubungan manusia dengan
Tuhan. Sebaliknya, Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap yang
mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk sistem politik atau
ketatanegaraan. Oleh karena itu, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan
Barat, sejatinya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam yang dipraktikkan oleh
Rasulullah dan Khulafaurrasyidin.
Aliran kedua berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat
yang tidak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad, menurut
aliran ini, adalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya. Tugasnya tidak
dimaksudkan untuk mendirikan negara dan memimpinnya. Ia hanya mempunyai
tugas tunggal, yaitu mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan
menjunjung tinggi budi pekerti luhur.
Aliran ketiga berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang serba lengkap dan
bahwa di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan. Namun bagi aliran ini, walaupun
dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi ia mengandung seperangkat
tata nilai yang lengkap bagi kehidupan bernegara.
Selain kategorisasi berdasarkan kecendrungan pemikiran tersebut, dalam konsepsi
Durkheim tentang fakta sosial, ia merumuskan bahwa terdapat tata sakral dan tata
profan. Tata sakral merujuk kepada sesuatu yang dianggap sakral, suci, atau kudus
seperti Tuhan, Roh, Binatang, Tumbuhan. Sementara Tata Profan merujuk kepada
sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan
seterusnya.
Maka dengan meminjam konsep Durkheim tersebut, peneliti melihat terdapat dua
kubu dalam masalah ini. Ada yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945 hanya
sebagai tata profan sedangkan syariat islam sebagai tata sakral. Dengan kata lain,
kedudukan syariat islam lebih tinggi dibanding Pancasila dan UUD 1945. Adapula
sebaliknya, Pancasila dan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding
syariat islam.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti menyebutkan bahwa
dari 60 responden mahasiswa, sebanyak 1 orang (1,7%) menjawab sangat setuju dan
7 orang (11,7%) menjawab setuju apabila syariat islam boleh dikesampingkan jika
tidak sesuai dengan hukum negara yang berlaku. Sedangkan sebanyak 10 orang
(16,7%) menjawab sangat tidak setuju dan 25 orang (41,7%) menjawab tidak setuju
apabila syariat islam dikesampingkan meskipun bertentangan dengan hukum negara
yang berlaku.
Jadi dapat dikatakan bahwa kecendrungan responden masih menjadikan syariat
islam (Al-Quran dan Hadist) sebagai tata sakral meskipun dalam konteks kehidupan
berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain, kedudukan syariat islam dianggap
lebih tinggi dari Pancasila dan UUD 1945.
3. Eksistensi Pancasila dan Ancaman Radikalisme
Gagasan untuk mendirikan negara Islam oleh sebagian pemikir islam
dikategorikan sebagai gerakan radikalisme/fundamentalisme agama. Sebagaimana
definisi radikalisme adalah sebuah paham yang berusaha memperjuangkan atau
menerapkan apa yang dianggap mendasar. Mereka menginginkan agar masyarakat
islam diperintah sesuai dengan al-Qur’an dan syari’at Islam sebagai aturan bernegara.
Jika ditinjau dari tingkatannya, maka upaya mendirikan negara islam dapat
digolongkan sebagai radikalisme tingkat sedang. Adapun tingkat tertinggi adalah
tindakan- tindakan terorisme seperti bom bunuh diri, penjarahan, dan perusakan
tempat- tempat umum. Adapun radikalisme yang tegolong tingat rendah seperti
gerakan takfiri atau upaya saling mengkafirkan atau penuduhan sesat antara sesama
umat islam.
Dengan melihat hasil penelitian ini yang menunjukkan sebanyak 9 orang setuju
jika negara islam didirikan di Indonesia, maka secara teoritis mereka dapat
digolongkan telah menganut atau paling tidak sevisi dengan kelompok/paham
radikalisme.
Meskipun populasi penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan, tetapi paling tidak
telah menggambarkan kenyataan sosial yang ada bahwa gerakan radikalisme islam
sedikit banyak telah berpengaruh di kalangan aktivis mahasiswa sekalipun.
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian ini, terdapat dua poin utama yang dapat penulis
paparkan, diantaranya ;
• Mayoritas responden tidak setuju terhadap wacana pendirian negara islam
(khalifah Islamiyah) di indonesia yang disertai dengan berbagai alasan yang
melatarinya terutama alasan keberagaman (SARA) yang menjadi karakter bangsa.
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia dianggap masih mampu
mengakomodasi seluruh kepentingan suku, agama, ras dan golongan/kelompok
masyarakat Indonesia kedalam sebuah wadah bersama bernama Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Sehingga kehendak untuk mendirikan negara islam
(Khilafah Islamiyah) di Indonesia patut untuk dipertimbangkan secara matang,
meskipun islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.
Meskipun demikian, sebagian responden cenderung setuju apabila syariat islam
diformalkan atau diwujudkan kedalam Undang – Undang/Perda Syariah demi
penegakan islam secara kaffah.
• Kemudian terkait kedudukan syariat islam dan hukum negara dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara, mayoritas responden cenderung tidak setuju
apabila syariat islam dikesampingkan meskipun itu berbenturan dengan aturan
hukum (UU) negara yang berlaku. Terlepas dari itu, mayoritas responden masih
mengakui relevansi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan menganggap masih
mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh, ada beberapa buah saran
yang hendak penulis usulkan, diantaranya ;
• Pertama, penulis melihat bahwa formalisasi syariat islam jauh lebih realistis dan
lebih relevan diwacanakan di indonesia ketimbang menggagas pendirian negara
islam. Meskipun wacana formalisasi syariat islam masih menimbulkan pro dan
kontra, tetapi dari segi tujuan, hal ini sebagai sarana atau upaya untuk
mengakomodasi kepentingan umat islam dalam menjalankan nilai –nilai
agamanya serta sebagai alternatif hukum formal bagi hukum indonesia yang
dinilai tumpul.
• Kedua, Untuk lingkup akademis atau dunia kampus dimana penelitian ini
diadakan maka penulis mengusulkan agar pemangku kepentingan (Rektor, Dekan
atau stakeholder terkait) dapat merumuskan kebijakan teknis yang sehat berupa
mengadakan forum – forum kajian/seminar ilmiah atau dalam bentuk mata kuliah
ketimbang mengeluarkan kebijakan hukum berupa pelarangan secara
organisasional/ideologis sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh pemerintah
pusat.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Anzar (2016). “ Gerakan Radikalisme dalam Islam Perspektif Historis”. ADDIN, 10
(1).
Abdullah, Junaidi (2014). “Radikalisme Agama (dekonstruksi tafsir ayat-ayat kekerasan dalam
al-quran)”. Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 8 (2).
An- Nabhani, Taqiyuddin. (2006). Daulah Islam.. Jakarta Selatan : HTI Press
Armando, Nina M (2005). “Ensiklopedi Islam”. Ichtiar Baru Van Hoeve. 6 (301).
Berger, Peter L dan Thomas Luckmann (2012). Tafsir Sosial Atas Kenyataan (risalah tentang
sosiologi pengetahuan). Jakarta: LP3ES.
Creswell, J.W (2014). Research Design (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan mixed).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hudori, Ahmad (2009). Khilafah Islamiyah perspektif Ahmadiyah. Jakarta : UIN Syarif
Hidayatullah. http;//repository.uinjkt.ac.id
Ilmi, Miftahul. (2008). Persepsi Ulama NU tentang Sistem Khilafah. Surabaya : IAIN
Walisongo. library.walisongo.ac.id/digilib/download
Jauhari, Imam.B (2012). Teori Sosial (proses islamisasi dalam system ilmu pengetahuan).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Khoiriyah, Nuriana (2016). Konsep Khilafah Islamiyah Gerakan Ikhwanul Muslimin menurut
Pemikiran Hasan al Banna. Surakarta : Perpustakan,uns.ac.id.
Kumar, Deepa (2016). Islam dan Politik (sebuah analisis marxis). IndoPROGRESS.
Mardalis (2006). Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal). Jakarta: Bumi Aksara.
Mastur (2010). Respon Mahasiswa Islam UNY tentang Pemikiran Khilafah HTI. Yogyakarta :
UIN SUKA. digilib.uin-suka.ac.id
Muqtada, Muhammad Rikza (2017). “Utopia Khilafah Islamiyah : Studi Tafsir Politik
Muhammad Arkoun”. Jurnal Theologia, 28 (I). http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1410
Naki, Ridwan (1999). Konsep Khilafah menurut Abul a’la Al - Maududi dan Ali Syariati.
Surabaya : IAIN Sunan Ampel. http://digilib.uinsby.ac.id/17777/
Pulungan, Suyuti (2013). “Ide Jamaluddin Al – Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha
tentang Negara dan Pemerintahan dalam Islam.
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI (2016). Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI.
Ritzer, George. Douglas J Godman (2008). Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana.
Riyadi, Dedi Slamet (2008). Analisis terhadap Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir.
Semarang : IAIN Walisongo.
Santoso Kristeva, Sayyid (2015). Sejarah Ideologi Dunia (kapitalisme, sosialisme, komunisme,
fasisme, anarkisme, anarkisme-marxisme, konservatisme). Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
Syamsulrijal (2017). “Radikalisme Kaum Muda Islam Terdidik di Makassar”. Al-Qalam. 23 (2).
Siregar, Sofyan (2011). Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Upe, Ambo (2010). Tradisi Aliran dalam Sosiologi (dari filosofi positivistic ke post positivistic).
Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Veeger, K..J (1986). Realitas Sosial (refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-masyarakat
dalam cakrawala sejarah sosiologi). Jakarta: PT Gramedia.
Wahid, Abdurahman (2006). Islamku, Islam Anda, Islam Kita (agama masyarakat negara
demokrasi). Jakarta : The Wahid Institute.
Wahid, Abdurahman (Editor) (2009) . Ilusi Negara Islam (ekspansi gerakan islam transnasional
di Indonesia ). Jakarta: The Wahid Institute.
Wijaya, Aksin (2012). Negara islam Indonesia ? (menguji otentitas argument hukum khilafah
islamiyah dalam konteks berislam Indonesia). Conference Proceeding AICIS XII.
digilib.uinsby.ac.id
Yamani, Ahmad Zaki (1977). “Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini”. Intermasa.
14.
Yusalina, Henny (2016). “Dinamika Penerapan Khilafah (Sebuah Tinjauan Sosio-Historis)”.
Wardah. 17( 2).
INTERNET
www.voa-islam.com (Diakses pada 23 April 2017).
https://www.kemenag.go.id/berita/431981/terima-hti-menag-berpesan-soal-pancasila-dan-
konsensus-bangsa ( Diakses pada 30 April 2017)
http://seputarsulawesi.com/berita-riset-litbang-agama-makassar-temukan-potensi-radikalisme-di-
sekolahsekolah-indonesia-timur.html (Di akses pada2 mei 2017)
http://lipi.go.id/berita/single/Radikalisme-Ideologi-Menguasai-Kampus/15082 (Diakses pada 2
mei 2017)
https://www.cliffsnotes.com/study-guides/sociology/religion/religious-fundamentalism (Diakses
pada 25 april 2017)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html (Diakses pada 21 april
2017)
(http://www.learniseasy.com/sejarah-nilai-pancasila.html Diakses pada 22 april 2017).
http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010594/swf/5058/files/basic-
html/page16.html (Diakses pada 22 april 2017)
LAMPIRAN 2
Daftar responden beserta identitasnya
NO NAMA DEPARTEMEN ANGKATAN JENIS KELAMIN
1 Ghifafari Ramadhan Ilmu Politik 2013 L
2 Ilham Alfais Sosiologi 2013 L
3 Fachrul Rozy Ilmu komunikasi 2013 L
4 Yusriah amaliah Ilmu pemerintahan 2013 P
5 Mikhail M Ilmu politik 2013 L
6 Fahmi sulthoni Ilmu politik 2013 L
7 Adnan Najib Ilmu pemerintahan 2013 L
8 Thorgib zulfikar Hubungan internasional 2013 L
9 Rustam Antropologi 2013 L
10 Rahmad hidayat Antropologi 2013 L
11 Sulaeman Sosiologi 2013 L
12 Jabal Nur Hubungan internasional 2013 L
13 Achmad Hubungan internasional 2013 L
14 Fuad hidayat Antropologi 2013 L
15 Hasyim asari Ilmu pemerintahan 2013 L
16 Orisya Ilmu komunikasi 2014 P
17 Dirwan kalam Ilmu politik 2014 L
18 Y Ilmu politik 2014 L
19 Nur haeriya Ilmu komunikasi 2014 P
20 Intan Firdausi Ilmu komunikasi 2014 P
21 Zulfah Ilmu komunikasi 2014 P
22 Annisa lutfiah Ilmu komunikasi 2014 P
23 Nursandrawali Sosiologi 2014 P
24 Marlina rajab Ilmu pemerintahan 2014 P
25 Nur azizah raja Ilmu pemerintahan 2014 P
26 Supriadi Ilmu pemerintahan 2014 P
27 Jannah Ilmu pemerintahan 2014 L
28 Aulia hardina hakim Hubungan internasional 2014 P
29 Zulmi zuliansyah Hubungan internasional 2014 L
30 Arbi hamzah Hubungan internasional 2014 L
31 Fathimah shiddiqah Sosiologi 2015 P
32 Zulfadli muchisyam Administrasi Negara 2015 L
33 Ari Administrasi Negara 2015 L
34 Princess Administrasi Negara 2015 P
35 Andi teri sangka Administrasi Negara 2015 P
36 Eka apriliyanti Administrasi Negara 2015 P
37 Abdul masli Antropologi 2015 L
38 Muhammad ardan Antropologi 2015 L
39 Citra Sosiologi 2015 P
40 Andi nuramina Sosiologi 2015 P
41 Syahrul syam Sosiologi 2015 L
42 Abdurahman Sosilogi 2015 L
43 Barbie Hubungan internasional 2015 P
44 Amiliyah arief Hubungan internasional 2015 P
45 Nurhikmah Sosiologi 2015 P
46 Rostina oktavia Ilmu komunikasi 2016 P
47 Arini widyastuti Antropologi 2016 P
48 Wahyu ramadhan Antropologi 2016 L
49 Rangga Antropologi 2016 L
50 Nurul mufidah Administrasi Negara 2016 P
51 Saddam husaen Ilmu komunikasi 2016 L
52 Tasa Ilmu komunikasi 2016 P
53 Ramdhan syahroni Sosiologi 2016 L
54 Andi annisa Ilmu pemerintahan 2016 P
55 Hajarullah Sosiologi 2016 L
56 Wilda yanti Ilmu komunikasi 2016 P
57 Haslina Sosiologi 2016 P
58 Nadhira humairah Sosiologi 2016 P
59 Widya astute Ilmu politik 2016 P
60 Muh agung Ilmu politik 2016 L
TOTAL 60
Tabel : Sumber data primer 2017
LAMPIRAN 3
KUESIONER PENELITIAN
RADIKALISME AGAMA DAN MASA DEPAN IDEOLOGI BANGSA
“STUDI PANDANGAN MAHASISWA ISLAM TERHADAP WACANA PENDIRIAN NEGARA
ISLAM (KHILAFAH ISLAMIYAH) DI INDONESIA”
Responden yang terhormat,
Bersama dengan ini, mohon kiranya agar Anda dapat bersedia meluangkan waktu untuk mengisi
kuesioner penelitian ini yang berjudul “Studi Pandangan Mahasiswa Islam terhadap Wacana
Pendirian Negara Islam (Khilafah Islamiyah) di Indonesia”. Informasi yang anda berikan adalah
bantuan yang sangat berharga dalam menunjang proses penyelesaian skripsi kami yang juga
menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S-1 di Departemen Sosiologi FISIP
Unhas..
Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Salam Hormat,
Achmad Faizal
E411 13 309
I. IDENTITAS RESPONDEN
a. Nama :
b. Jenis kelamin :
( ) Laki- Laki ( ) Perempuan
c. Departemen :
( ) Antropologi ( ) Hubungan Internasional ( ) Ilmu Politik
( ) Ilmu Komunikasi ( ) Ilmu Administrasi Negara
( ) Ilmu Pemerintahan ( ) Sosiologi
d. Angkatan :
( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015 ( ) 2016
e. No telp/HP :
f. Organisasi :
1. ………………………………………..…….
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
Petunjuk Pengisian Kuesioner
1. Sebelum menjawab, responden diharap agar membaca setiap pertanyaan dengan
seksama.
2. Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda centang (√) pada salah
satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang diperlukan untuk setiap
pertanyaan.
3. Isilah secara singkat apabila ada pertanyaan yang membutuhkan penjelasan.
4. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada
teknik skala Likert, yaitu:
• Sangat Setuju (SS) = 5
• Setuju (S) = 4
• Netral (N) = 3
• Tidak Setuju (TS) = 2
• Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
5. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya,
oleh sebab itu mohon kiranya untuk mengisi kuesioner dengan data yang sebenarnya.
II. DAFTAR PERTANYAAN
1. Apa pendapat Anda tentang wacana pendirian Negara islam di Indonesia ?
a. Setuju b. Tidak
Alasannya?
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Sebutkan ormas Islam di Indonesia yang menurut Anda menganut paham radikalisme
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
3. Apa pendapat Anda tentang pembubaran ormas Islam yang dianggap menganut paham
radikalisme ?
a. Setuju b. Tidak
Alasannya ?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Variabel Negara Islam
PERNYATAAN SS S N TS STS
4. Pendirian Negara islam di Indonesia tidak cocok dengan
karakter Islam Nusantara yang moderat
5. Pendirian Negara islam tidak cocok dengan sistem
demokrasi yang berlaku Indonesia
6. Pendirian Negara islam tidak cocok dengan karakter
bangsa Indonesia yang beragam/multicultural
7. Kepercayaan/Agama minoritas di Indonesia yang
dianggap sesat perlu dihilangkan
8. Pendirian Negara Islam adalah bagian dari pengamalan
islam secara kaffah (totalitas)
9. Sistem ekonomi islam cocok diterapkan di Indonesia
menggantikan sistem ekonomi kapitalisme
10. Syariat islam (Al-Quran & Hadist) perlu diformalkan/
dibuatkan undang-undang syariah
11. Syariat islam (Al-Quran & Hadist) perlu diperjuangkan
oleh partai politik yang berasaskan islam
12. Syariat islam (Al-Quran & Hadist) perlu ditegakkan
secara tegas/ tanpa kompromi
Variabel Pancasila
13. Pancasila boleh diganti dengan ideologi lain
14.
Pancasila mampu menaungi segala bentuk
kepercayaan/agama yang dianut oleh masyarakat
Indonesia
15. Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa Indonesia
16. Pancasila tidak mampu lagi menjamin keadilan dan
kesejahteraan sosial bagi segenap rakyat Indonesia
17. Pancasila adalah sumber segala sumber hukum bagi
bangsa Indonesia
18. Nilai nilai Pancasila bertentangan dengan syariat islam
(Al-Quran & Hadist)
Variabel Syariat Islam
19. Syariat islam (Al-Quran & Hadist) adalah sumber hukum
utama bagi umat islam dalam konteks hidup berbangsa
dan bernegara
20. Hukum islam dapat dikesampingkan jika tidak sesuai
dengan Pancasila/UUD 1945
21. Syariat islam (Al-Quran & Hadist) boleh ditafsirkan
sesuai konteks zaman dan masyarakatnya
22. Nilai-nilai islam telah terkandung di dalam Pancasila
LAMPIRAN 4
PENGELOLAHAN DATA SPSS
A. IDENTITAS RESPONDEN
DEPARTEMEN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Antropologi 8 13.3 13.3 13.3
HI 8 13.3 13.3 26.7
Politik 7 11.7 11.7 38.3
komunikasi 10 16.7 16.7 55.0
administrasi negara 6 10.0 10.0 65.0
pemerintahan 8 13.3 13.3 78.3
sosiologi 13 21.7 21.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
JENIS KELAMIN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
laki laki 32 53.3 53.3 53.3
Perempuan 28 46.7 46.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
ANGKATAN
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2013 15 25.0 25.0 25.0
2014 15 25.0 25.0 50.0
2015 15 25.0 25.0 75.0
2016 15 25.0 25.0 100.0
Total 60 100.0 100.0
T1
Frequenc
y
Perce
nt
Valid
Perce
nt
Cumulativ
e Percent
Vali
d
setuj
u
9 15.0 15.0 15.0
Tida
k
51 85.0 85.0 100.0
Total 60 100.0 100.0
T3
Frequenc
y
Perce
nt
Valid
Perce
nt
Cumulativ
e Percent
Vali
d
setuj
u
40 66.7 66.7 66.7
tidak 20 33.3 33.3 100.0
Total 60 100.0 100.0
X4
Frequenc
y
Percen
t
Valid
Percen
t
Cumulativ
e Percent
Vali
d
1 4 6.7 6.7 6.7
2 3 5.0 5.0 11.7
3 26 43.3 43.3 55.0
4 21 35.0 35.0 90.0
5 6 10.0 10.0 100.0
Tota
l
60 100.0 100.0
x5
Frequenc
y
Percen
t
Valid
Percen
t
Cumulativ
e Percent
Vali
d
1 3 5.0 5.0 5.0
2 13 21.7 21.7 26.7
3 8 13.3 13.3 40.0
4 25 41.7 41.7 81.7
5 11 18.3 18.3 100.0
Tota
l
60 100.0 100.0
x7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 12 20.0 20.0 20.0
2 16 26.7 26.7 46.7
3 6 10.0 10.0 56.7
4 16 26.7 26.7 83.3
5 10 16.7 16.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
x8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 4 6.7 6.7 6.7
2 14 23.3 23.3 30.0
3 18 30.0 30.0 60.0
4 20 33.3 33.3 93.3
5 4 6.7 6.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
x9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 4 6.7 6.7 6.7
2 7 11.7 11.7 18.3
3 24 40.0 40.0 58.3
4 18 30.0 30.0 88.3
5 7 11.7 11.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
x10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 5 8.3 8.3 8.3
2 18 30.0 30.0 38.3
3 14 23.3 23.3 61.7
4 20 33.3 33.3 95.0
5 3 5.0 5.0 100.0
Total 60 100.0 100.0
x11
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 4 6.7 6.7 6.7
2 7 11.7 11.7 18.3
3 19 31.7 31.7 50.0
4 23 38.3 38.3 88.3
5 7 11.7 11.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
x12
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 4 6.7 6.7 6.7
2 8 13.3 13.3 20.0
3 16 26.7 26.7 46.7
4 23 38.3 38.3 85.0
5 9 15.0 15.0 100.0
Total 60 100.0 100.0
y13
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 17 28.3 28.3 28.3
2 22 36.7 36.7 65.0
3 10 16.7 16.7 81.7
4 10 16.7 16.7 98.3
5 1 1.7 1.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
y14
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 1 1.7 1.7 1.7
2 3 5.0 5.0 6.7
3 7 11.7 11.7 18.3
4 30 50.0 50.0 68.3
5 19 31.7 31.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
y15
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2 1 1.7 1.7 1.7
3 5 8.3 8.3 10.0
4 32 53.3 53.3 63.3
5 22 36.7 36.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
y16
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 6 10.0 10.0 10.0
2 25 41.7 41.7 51.7
3 20 33.3 33.3 85.0
4 5 8.3 8.3 93.3
5 4 6.7 6.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
y17
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 2 3.3 3.3 3.3
2 6 10.0 10.0 13.3
3 13 21.7 21.7 35.0
4 26 43.3 43.3 78.3
5 13 21.7 21.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
y18
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 17 28.3 28.3 28.3
2 20 33.3 33.3 61.7
3 20 33.3 33.3 95.0
4 2 3.3 3.3 98.3
5 1 1.7 1.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
z20
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 10 16.7 16.7 16.7
2 25 41.7 41.7 58.3
3 17 28.3 28.3 86.7
4 7 11.7 11.7 98.3
5 1 1.7 1.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
z21
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 5 8.3 8.3 8.3
2 12 20.0 20.0 28.3
3 17 28.3 28.3 56.7
4 16 26.7 26.7 83.3
5 10 16.7 16.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
z22
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 2 3.3 3.3 3.3
2 2 3.3 3.3 6.7
3 14 23.3 23.3 30.0
4 29 48.3 48.3 78.3
5 13 21.7 21.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
93
RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : Achmad Faizal
Tempat & Tanggal Lahir : Makassar, 9 Juni 1995
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Alamat : Jl. Satando Komp TNI – AL Dewa Kembar C/1 233
Riwayat Pendidikan :
a. SD HANG TUAH MAKASSAR 2001 - 2007
b. SMP NEGERI 7 MAKASSAR 2007 – 2010
c. SMA NEGERI 4 MAKASSAR 2010 – 2013
d. S/1 SOSIOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN 2013 – 2017
Riwayat Organisasi :
a. KETUA BIDANG ROHANI OSIS SMA NEGERI 4 MAKASSAR PERIODE
2011/2012
b. KORDINATOR KEBIJAKAN PUBLIK KAMMI UNHAS PERIODE 2014/2015
c. INTERNAL OVERSIGHT MUN UNHAS PERIODE 2015/2016
d. MAKES (Al Markaz For Khudi Enlightening Studies) PERIODE 2015/2016
e. KETUA UMUM KEMASOS FISIP UNHAS PERIODE 2016/2017
f. JARINGAN AKTIVIS FILSAFAT ISLAM CABANG MAKASSAR BARAT 2017