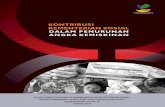PUISI ARAB DAN PROTES SOSIAL
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of PUISI ARAB DAN PROTES SOSIAL
Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
Hak Cipta ©2016 pada PenulisCetakan 1, Rajab 1437/April 2016
PenulisAndri Ilham
Penata Letak TeksNi’am Masykuri
Perancang SampulAlan Zuhri
Diterbitkan OlehTranspustaka
Lini Penerbitan Transinstitute
Puri Kartika A5/17 RT. 01/RW. 08 Tajur-Ciledug-Tangerang 15152Telp: 021-97161983; 021-74701906; SMS: 0838 7699 1249; Fax: 021-74701906
Email: [email protected]
Katalog Dalam Terbitan (KDT)Ilham, Andri ―Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-IslamJakarta: Transpustaka, 2016xii + 198 halaman; 17.6 x 25 cmISBN: 978-979-3907-48-2
Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam buku ini berdasarkan ALA-LC Romanization Tables.
Konsonan
NamaHuruf LatinNamaHuruf Arab
tidak dilambangkantidak dilambangkanalifأbebbā’بtettā’ت
te dan haththā’ثjejjīmج
ha [titik di bawah]ḥḥā’حka dan hakhkhā’خ
deddālدde dan hadhdhālذ
errrā’رzetzzāyزesssīnس
iv Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
es dan hashshīnشes [titik di bawah]ṣṣādصde [titik di bawah]ḍḍādضte [titik di bawah]ṭṭā’طzet [titik di bawah]ẓẓā’ظkoma terbalik di atas‘‘aynع
ge dan haghghaynغefffā‘فqiqqāfقkakkāfكelllāmل
emmmīmمennnūnنwewwāwوhahhā’ـه
apostrof’hamzahءyeyyā’ي
Vokal
Vokal Tunggal
NamaHuruf LatinNamaTandaaafatḥahَـ ــiikasrahِـ ــuuḍammahُـ ــ
vPedoman Transliterasi Arab-Latin
Vokal Rangkap
NamaGabungan HurufNamaTanda dan Huruf
a dan weawfatḥah dan wāwـَ و ــa dan yeayfatḥah dan yā’ـَ ي ــ
Contoh:Imru’ al-Qays = امرؤ الَقيْس Shawqī Ḍayf = َشْويق ضيف
Mad
Mad (maddah) merupakan tanda bunyi panjang dalam bahasa Arab (bunyi pendek menjadi bunyi panjang).
NamaHurufNamaTanda dan Huruf
a dan garis di atasāfatḥah dan alifـَ ا ــmad dan alifآ
i dan garis di atasīkasrah dan yā’ـِ ي ــu dan garis di atasūḍammah dan wāwـُ و ــ
Contoh:Ādāb = آداب ’Khula‘ā = خلَعاء
Ṣu‘lūk = صعلُوك Banī = بن
Alif Maqṣūrah
Alif maqṣūrah (ى) digunakan sebagai (ا ـَ ) untuk menunjukkan vokal panjang, dan ditransliterasikan dengan (á). Contoh: الّشنفَرى = al-Shanfará
Kata Sandang
Kata sandang (ال) dilambangkan dengan huruf (al), baik yang diikuti dengan huruf shamsīyah (huruf yang dapat menyebabkan peleburan huruf lām sebagai artikel menjadi bunyi yang sama dengan bunyi huruf tersebut), maupun yang diikuti huruf qamarīyah (huruf yang tidak menyebabkan peleburan huruf lām sebagai artikel). Kata sandang ini ditulis dengan tanda (-) terpisah dari kata yang mengikuti. Contoh:
(al) diikuti huruf shamsīyah, الّصعايلك = al-Ṣa‘ālīk
(al) diikuti huruf qamarīyah, اـهيلْal-Jāhilī = ال
vi Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
Tā’ Marbūṭah
1. Jika kata diakhiri dengan tā’ marbūṭah (ة), atau kata tersebut diikuti oleh kata sandang (ال), serta bacaan keduanya dipisah, maka ditransliterasikan dengan (h). Contoh:
qabīlah = قبيلة
al-ṣa‘lakah = الّصعلكة
al-mu‘āraḍah al-siyāsīyah = املعارضة السياسّية
2. Jika kata yang berakhiran (ة) dikonstruksi (iḍāfah), maka ditransliterasikan dengan (t). Contoh: أغربة العرب = aghribat al-‘Arab
Tashdīd
Tashdīd atau shaddah ( ـّ ) merupakan tanda pada tulisan Arab untuk menyatakan huruf rangkap.
1. Tashdīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang ber-tashdīd tersebut. Contoh: ا Ta’abbaṭa Sharran = تأبَّط رشًّ
2. Tashdīd dengan huruf juga digunakan untuk vokal rangkap (aw) dan (ay) yang diikuti huruf konsonan, maka transliterasinya menjadi (aww) dan
(ayy). Contoh: شوَّال = Shawwāl أيَّام = ayyām
3. Tashdīd dilambangkan dengan (īy) atau (ūw), jika hurufnya adalah huruf vokal panjang (ī) dan (ū) yang diikuti huruf konsonan sesudahnya. Contoh:
adūw‘ = عُدّو aṣabīyah qabalīyah‘ = عصِبّية قبِلّية
Prakata
Buku yang berjudul “Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam” ini pada awalnya merupakan tesis untuk memperoleh gelar magister yang diajukan pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesis tersebut telah dipertahankan pada Sidang Ujian Pendahuluan Tesis, 1 Oktober 2015, dan pada Sidang Ujian Promosi Magister, 4 Januari 2016.
Buku ini berupaya menyajikan tren lain dalam diskursus puisi Arab pra-Islam (al-shi‘r al-Jāhilī). Memang benar bahwa tema kesukuan merupakan citra yang dominan dalam puisi Arab pra-Islam. Namun, benar pula jika dikatakan bahwa citra seperti itu bukanlah satu-satunya. Faktanya dalam puisi Arab pra-Islam ditemukan kecenderungan lain, yaitu puisi-puisi yang menyimpang dan memberontak terhadap suku (baca: kabilah) dan nilai-nilainya yang dominan.
Kecenderungan tersebut khususnya seperti yang ditunjukkan dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk; sekelompok masyarakat pinggiran yang memberontak kabilah, seperti orang-orang khula‘ā’ yang terusir dari kabilah, dan identitas kesukuan mereka dicabut; para aghribat al-‘Arab yang terdiskriminasi akibat perbedaan rasial dan nasab; atau orang-orang miskin yang semata-mata hidup sebagai Ṣa‘ālīk sebagai akibat dari munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan kabilah. Tidak seperti puisi-puisi para penyair kabilah yang mencerminkan bentuk fanatisme individu terhadap kabilahnya (al-shakhṣīyah al-qabalīyah), puisi-puisi yang dipresentasikan kelompok Ṣa‘ālīk mencerminkan bentuk independensi individual (al-shakhṣīyah al-fardīyah) yang memberontak dan bertendensi protes, khususnya disparitas sosial yang meliputi kemiskinan dan kesenjangan dalam hubungan nasab dan kekerabatan suku.
viii Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
Demikianlah, pada akhirnya kajian tersebut dapat diselesaikan, meskipun masih sangat jauh dari memuaskan. Segala puji dan syukur kepada Allah, SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Kepada Rasulullah, SAW. penulis haturkan salawat dan salam.
Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih kiranya patut diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan atas terselesaikannya tesis ini. Kepada Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. Kepada Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, beserta Dr. JM. Muslimin, M.A. selaku Ketua Program Studi Magister, dan Prof. Dr. Didin Saepudin, M.A. selaku Ketua Program Studi Doktor. Juga tak lupa kepada Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., beserta Dr. Yusuf Rahman, M.A., dan Prof. Dr. Suwito, M.A., yang telah memberikan tambahan waktu studi kepada penulis. Meskipun ketika studi ini berakhir, mereka telah menyelesaikan masa jabatannya di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Ibu Dr. Yeni Ratna Yuningsih, M.A. selaku pembimbing yang telah dengan tekun membaca dan memberikan kritik dan arahan kepada penulis selama proses penulisan tesis. Kepada para dosen penguji Sidang Promosi Magister, Prof. Dr. Sukron Kamil, M.A. dan Dr. Muhbib Abdul Wahab, M.A., terima kasih atas input dan saran yang diberikan untuk perbaikan tesis. Selanjutnya, penulis juga perlu menyampaikan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika; para dosen, staf akademik, dan staf Perpustakaan Riset Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada penulis dalam mengurus segala hal yang menyangkut perkuliahan.
Kepada Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Dinas Pendidikan, terima kasih atas bantuan dana pendidikan yang tentunya sangat membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi di kampus. Kepada teman-teman di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Lalu M. Ariadi, Fauzani, Husen, Juhar Mukhlas, Zamrizal, Lestari, Lukman, Ahmad, Pratama, Yasril, Wahyudi, Bapak Dr. Ibnu Ansori, M.A., dan lainnya, yang telah banyak meluangkan waktu untuk diskusi-diskusi cerdasnya. Untuk teman-teman seperantauan dari Kuala Tungkal-Jambi di Jakarta; Omzho, Huda, Hanafi, Apay, Iwan, dan Muis, yang bersama kalian seolah mengingatkan kembali betapa indahnya kampung halaman. Juga kepada teman-teman di Kosan Pak Borju; Tio, Ni’am, Alan, Haizam, Qusairi, Mawardi, Marom, Habibah, dan lainnya, terima kasih atas pertemanannya. Tak lupa pula, ucapan terima kasih juga penulis
ixPrakata
haturkan kepada Iin, Muthi, Asih, Suci, Syehab, Ican, Maman, dan teman-teman di komunitas Relawan Nusantara Jaya (RNJ). Khusus kepada Rima dan Mantri, terima kasih atas motivasi dan pelajaran berharga tentang arti persahabatan. Tetaplah menjadi bagian dari “bertiga”.
Last but not least, rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga tentunya wajib penulis sampaikan kepada almarhum kedua orang tua penulis; ayahanda Drs. H. M. Saad Sanusi dan ibunda Hj. Maimunah. Meskipun tak dapat melihat keberhasilan anaknya dalam menyelesaikan kuliah Pascasarjana, namun keduanya telah banyak berjasa dalam membesarkan dan mendidik penulis. Doa dan nasehat yang mereka berikan semasa hidup kiranya dapat menjadi kekuatan dan rasa optimis bagi penulis untuk dapat menatap kehidupan yang lebih baik. Tentunya karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan, semoga menjadi amal jariyah untuk keduanya. Juga kepada saudara-saudara penulis; Fauzan Anugrah, S.S., Rahmi, Syukran Habibi, S.Pd., dan keponakan-keponakan tersayang; Ismi Bikilmi Hawa dan M. Fakhri Ramadhan, serta sanak famili dan kerabat di Kuala Tungkal–Jambi, terima kasih atas bantuan dan dukungan moralnya. Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan untuk para guru dan ustaz di Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) Kuala Tungkal–Jambi yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis. Semoga Allah, SWT. membalas segala amal baik mereka dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya.
Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk dapat menghasilkan temuan-temuan yang ideal. Atas segala kekurangan, kedangkalan analisis, penerjemahan puisi yang belum sempurna, dan kesimpulan dalam buku ini, tentunya menjadi tanggung jawab penulis. Kiranya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diperlukan untuk kesempurnaan buku ini. Namun demikian, besar harapan semoga karya yang sangat sederhana ini dapat menjadi amal baik bagi penulis dan bermanfaat bagi yang lain. Āmīn.
Ciputat, 10 April 2016
Andri Ilham
Daftar Isi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ― iiiPrakata ― viiDaftar Isi ― xi
Bab 1Pendahuluan ― 1
Bab 2Sastra dan Realitas Sosial: Potret Puisi Arab pra-Islam ― 231. Sastra sebagai Konstruksi Realitas Sosial ― 232. Puisi: Cerminan Sosial, Politik, dan Budaya Arab pra-Islam ― 34
a. Kesukuan: Citra Dominan Puisi Arab pra-Islam ― 40b. Kecenderungan Puisi yang Menyimpang dan Memberontak:
Potret dari Sisi Lain Kehidupan Arab pra-Islam ― 46
Bab 3Ṣa‘ālīk dalam Diskursus Puisi Arab pra-Islam ― 591. Ṣa‘ālīk: Potret Masyarakat Pinggiran Masa pra-Islam ― 592. Karakteristik Puisi Ṣa‘ālīk: Penyimpangan Struktur Formal ― 68
a. Struktur Bentuk ― 69Bait-bait Pendek ― 69Karakteristik Bahasa ― 71Prosodis ― 71
xii Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
b. Struktur Isi ― 75Kesatuan Tema ― 75Puisi Epik ― 77 Realis ― 78Bebas dari Unsur Fanatisme Kesukuan ― 80 Muatan Protes Sosial ― 81
Bab 4Protes terhadap Diskirminasi dalam Hubungan Nasabdan Kekerabatan Suku ― 871. Nasab dan Kekerabatan Suku: Simbol Identitas Sosial Masyarakat
Arab pra-Islam ― 872. Terasing dari Kehidupan Kabilah: Konstruksi Protes Sosial ― 101
a. Khula‘ā’: Terusirnya Individu dari Kekerabatan Suku ― 102b. Marginalisasi Individu Akibat Perbedaan Rasial dan Nasab:
Pengalaman Aghribat al-‘Arab dan Hujanā’ ― 117
Bab 5Kemiskinan sebagai Masalah Utama Kehidupan Ṣa‘ālīk ― 1371. Kabilah dan Problem Ekonomi: Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial ― 1372. Ṣa‘ālīk dan Kemiskinan ― 1463. Perampokan sebagai Protes Sosial ― 154
Bab 6Kesimpulan ― 167
Daftar Pustaka ― 171Glosarium ― 185Indeks ― 191Tentang Penulis ― 197
Bab 1Pendahuluan
Karya sastra selalu terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Faktor sejarah dan lingkungan (milieu) ikut membentuknya karena ditulis oleh pengarang sebagai anggota masyarakat. Walaupun menyajikan kualitas
estetis, karya sastra juga menyediakan berbagai informasi mengenai fakta-fakta sosial dan mempunyai kesempatan yang luas untuk membicarakan pelbagai hal; politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Luasnya kesempatan ini sebanyak fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui karya sastra seorang pengarang juga mengungkapkan problema kehidupan yang pengarang sendiri ikut berada di dalamnya. Dengan demikian, masalah sosial dan kejadian yang dialami, dirasakan, dan dilihat oleh pengarang, melahirkan ide atau gagasan yang dituangkan dalam karyanya.
Relevansi sastra dan realitas sosial asumsi dasarnya adalah bahwa sastra tidak bisa lepas dari kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya. Pengarang memanfaatkan kekayaan faktual yang ada dalam masyarakat, dan kemudian dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa karya sastra juga dibentuk, dan berada dalam posisi di antara jaringan dan sistem nilai dalam masyarakatnya. Menurut Albert William Levi, juga Shawqī Ḍayf, setiap karya sastra merupakan ciptaan manusia, diproduksi dalam waktu dan mengambil tempat dan konteks tradisi yang lebih luas, yaitu pranata sosial, ideologi, dan gagasan-gagasan. Karya sastra tidak hadir dalam ruang kosong, ia merupakan refleksi kehidupan, dan merupakan kegelisahan individual ketika berinteraksi dengan masyarakatnya. Seorang pengarang hadir tidak semata-mata turun dari langit, tetapi ia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tumbuh dari pemikiran, perasaan, dan pendengaran. Dengan kata lain, tidak
2 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
benar jika seorang pengarang mampu memisahkan dirinya dari masyarakat yang melingkupinya.1 Oleh karenanya dalam pandangan Étienne Balibar dan Pierre Macherey, juga seperti yang dikatakan oleh K. Satchidanandan, sastra menjadi tidak ada di luar kondisi-kondisi sosial dan sejarahnya.2
Sebagai medium komunikasi, karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi individual, melainkan juga memiliki fungsi sosial. Komunikasi yang bermakna ditunjukkan melalui relevansinya dalam hubungan antara pengarang dan pembaca; subjek dan objek. Selain itu, karya sastra juga memungkinkan memiliki tujuan, sekaligus mekanisme obsesi subjek dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu yang mempersoalkan hal-hal konkret yang menjadi masalah masyarakat.3 Di banyak karya sastra, misalnya, terdapat beberapa pengarang yang menggunakan karya sastra sebagai salah satu media untuk memperjuangkan ide-ide kemasyarakatannya. Kasus Indonesia setidaknya dapat dikemukakan beberapa pengarang yang juga gigih memperjuangkan ide pengembangan tata kemasyarakatan Indonesia baru, seperti Sutan Takdir Alisjahbana dengan roman Layar Terkembang (1936) yang bercerita tentang emansipasi wanita; Achdiat Kartamihardja dengan romannya Atheis (1949) yang mengetengahkan pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia sejak permulaan abad ke-20 yang tradisional ke gaya hidup modern di mana pergeseran itu membawa serta perselisihan dan bentrokan antara paham-paham lama dengan yang baru, khususnya di wilayah sosial, budaya, dan politik; Pramoedya Ananta Toer dengan karyanya Midah Si Manis Bergigi Emas (1954) yang bercerita tentang upaya perlawanan tokoh wanita terhadap budaya patriarkat di masa penjajahan; juga seperti kumpulan puisi pamflet W.S. Rendra, Potret Pembangunan dalam Puisi (1993), dan Wiji Thukul dalam kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru (2004) yang bermuatan protes sosial, dan lain sebagainya. Semua karya sastra tersebut adalah rekaman kehidupan dalam masyarakat, dan refleksi dari apa yang pernah dialami oleh pengarangnya.
Dalam pandangan Marxisme, bahkan karya sastra dianggap sebagai alat yang pada gilirannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu.4 Jika karya sastra digunakan sebagai media untuk
1Albert William Levi, “Literature as a Humanity,” Journal of Aesthetic Education, Vol. 10, No. 3/4, Bicental Issue (July-October 1976): 50; Shawqī Ḍayf, al-Baḥth al-Adabī: Ṭabī‘atuh, Manāhijuh, Uṣūluh, Maṣādiruh (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1997), 96.
2Étienne Balibar dan Pierre Macherey, “On Literature as an Ideological Form,” dalam Untying the Text: A Post-Structuralist Reader, ed. Robert J.C. Young (London & Boston: Routledge & Kegan Paul, 1981), 80-84; K. Satchidanandan, “Poetry, Against Violence,” Indian Literature, Vol. 53, No. 1/249 (January/February 2009): 6.
3Nyoman Kutha Ratna, Sastra dan Cultural Studies (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 361-4.4Nyoman Kutha Ratna, Sastra dan Cultural Studies, 373; Raman Selden, Peter Widdowson, dan
3Pendahuluan
menyampaikan protes terhadap realitas sosial yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, maka karya sastra sesungguhnya memiliki kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ini misalnya diwujudkan dengan cara memberikan respon terhadap fungsi-fungsi kekuasaan yang dilakukan oleh para pemimpin yang tidak membela kepentingan masyarakat. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan melalui karya sastra memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah menyalahgunakan kekuasaan. Pada akhirnya fungsi sosial karya sastra diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada manusia untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.
Kecenderungan sastra sebagai alat yang berkaitan erat dengan kepentingan kelompok tertentu dalam kesusastraan Marxis dikenal dengan istilah “sastra bertendensi” (littérature engagée). Karya sastra dianggap sebagai kritik sosial, serta melihat pengarang sebagai penyuluh masyarakat. Oleh karena itu, sastra bertendensi sering disejajarkan dengan sastra untuk masyarakat, dan dipertentangkan dengan seni untuk seni (l’art pour l’art).5 Asumsinya, tidak ada karya sastra yang diciptakan untuk kepentingan seni itu sendiri. Sebaliknya, karya sastra menduduki posisi penting dalam masyarakat. Dengan adanya intensitas pada tujuan-tujuan tertentu, maka terkadang aspek-aspek lain seperti estetika kurang mendapat perhatian.6
Dalam melihat hubungan antara sastra dan kekuatan sosial yang terkandung dalam masyarakat, teori sastra Marxis didasarkan pada gagasan bahwa sastra adalah produk kekuatan sosial dan ideologi. Menurut Terry Eagleton, untuk alasan historis apa pun karya sastra diketengahkan sebagai medium dari keprihatinan yang secara mendalam berakar dalam kehidupan kultural dan politik dari suatu masa. Oleh karena itu, selain sebagai cerminan realitas sosial, sastra juga dapat berfungsi sebagai media ekspresi ideologi. Sebaliknya, juga dapat berfungsi sebagai konter ideologi pada masanya. Inilah kemudian yang mendasari pandangan Eagleton memberikan usulan kritik politik terhadap sastra, karena politik merupakan tatanan kehidupan masyarakat dengan melibatkan kekuasaan di dalamnya. Sedangkan karya sastra merupakan faktor yang dipengaruhi oleh unsur-unsur di luarnya, seperti ras, lingkungan, dan momen, termasuk juga politik.7 Sastra, dengan demikian, secara vital terlibat dalam kehidupan konkret
Peter Brooker, A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory (Edinburgh: Pearson, 2005), 82-84.5Gerakan seni untuk seni ini dimulai sebagai reaksi terhadap kecenderungan atau tendensi nilai
seni yang terpengaruh dari aktivitas manusia. Lihat A.H. Hannay, “The Concept of Art for Art’s Sake,” Philosophy, Vol. 29, No. 108 (January 1954): 44.
6Nyoman Kutha Ratna, Sastra dan Cultural Studies, 361-63.7Terry Eagleton, Fungsi Kritik, terj. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 111, 121. Tentang
4 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
manusia, dan bukan sekedar gambaran abstrak.
Tema tentang sastra dan protes sosial tentu bukan sesuatu yang baru. Mungkin karena seni atau sastra juga dipahami sebagai kritik atas kenyataan sosial ataupun politik yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai humanisme, maka sastrawan pun menjadikan seni dan tulisannya sebagai media untuk menyampaikan aspirasi.8 Dalam konteks kesusastraan Indonesia, misalnya, kelompok sosial tertentu seperti Lembaga Kedaulatan Rakyat (Lekra) yang muncul sekitar tahun 1960-an, bahkan memanfaatkan sastra untuk kepentingan yang sangat praktis, yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Para seniman Lekra dan simpatisannya menganut paham realisme sosialis yang tegas berpihak pada rakyat atas dasar paham “seni untuk rakyat”, serta menolak aliran “seni untuk seni”, khususnya sebagaimana yang diusung oleh kalangan Manifes Kebudayaan. Oleh karena itu, kelompok ini menempatkan sastra sebagai alat politik, dan sebagai sumber protes dan ideologi.9
Lebih jauh ketika melihat hubungannya dalam konteks kesusastraan Arab, sastra sebagai sarana protes sosial bahkan telah dikenal pada masa pra-Islam (Jāhilīyah). Menurut Muḥammad Aḥmad al-‘Azb, bahkan kecenderungan tema-tema yang mencerminkan pemberontakan dan protes sosial dalam kesusastraan Arab modern, seperti karya-karya Jubrān Khalīl Jubrān ‘Kahlil Gibran’ (w. 1931),10 Ma‘rūf al-Ruṣāfī (w. 1945),11 dan lainnya, bukanlah sesuatu yang baru dalam diskursus kesusastraan Arab, akan tetapi memiliki akar historis yang jauh sebelumnya telah ditunjukkan dalam puisi-puisi Arab pra-Islam, khususnya puisi-puisi Ṣa‘ālīk.12
Teori ini juga bisa dijadikan sebagai penolakan atas pandangan kritik sastra Arab klasik, bahkan kritik sastra Arab modern, yang umumnya menampilkan puisi Arab pra-Islam dengan citra kesukuan (baca: kabilah). Dalam perkataan
usulan kritik politik dalam sastra, lihat Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Oxford: Blackwell, 1996), 169-89.
8Narendre Mohan, “Protest and Literature,” Indian Literature, Vol. 18, No. 1 (January-March, 1975): 92-95.
9A. Teeuw, Sastra Baru Indonesia, Jilid. 1 (Ende-Flores: Nusa Indah, 1980), 186-87.10Lihat Muḥammad Najm al-Ḥaq al-Nadwī, “Jubrān fī Ḍaw’i Mu’allafātih al-‘Arabīyah: Dirāsah
Taḥlīlīyah,” Majallat al-Qism al-‘Arabī, no. 16, 2009, 157-92; Daniela Rodica Firanescu, “Renewing Thought from Exile: Gibran on the New Era,” Synergies Monde Arabe, no. 8 (2011): 67-80.
11Lihat Salma Khadra Jayyusi, “Ma‘rūf al-Ruṣāfī and the Poetics of Anti-Colonialism,” dalam The Poetics of Anti-Colonialism in the Arabic Qaṣīdah, ed. Hussein N. Kadhim (Leiden-Boston: Brill, 2004), 85-130; Md. Joynul Hoque, “Ma‘ruf al-Rusafi: His Live and Works,” Pratidhwani–A Journal of Humanities and Social Science, Vol. I, Issue II (October 2012): 27-34.
12Muḥammad Aḥmad al-‘Azb, “Ẓawāhir al-Tamarrud fī al-Shi‘r al-‘Arabī al-Mu‘āṣir” (Disertasi., Jāmi‘at al-Azhar, 1976), 17-18.
5Pendahuluan
lain, kritik tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan organik antara puisi dengan struktur kesukuan.13 Diakui oleh Muḥammad Aḥmad Jād al-Mawlá Bek, ‘Alī Muḥammad al-Bajāwī, dan Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, bukti nyata adanya keterkaitan tersebut adalah sebagaimana yang tercermin dalam sejarah pertikaian bangsa Arab (ayyām al-‘Arab) pada masa pra-Islam. Ketika mengkaji kisah-kisah pertikaian tersebut, maka yang tergambarkan adalah kesatuan antara puisi dengan kabilahnya di satu sisi, dan kesatuan antara apa yang dipraktikkan oleh kabilah dengan apa yang dikatakan oleh penyair di sisi yang lain. Oleh karena itu, melihat puisi-puisi para penyair kabilah, seperti al-A‘shá, ‘Antarah ibn Shaddād, al-Ḥārith ibn Ḥillizah, ‘Āmir ibn Ṭufayl, Abī Qays ibn al-Aslat, Qays ibn al-Ḥātim, ‘Abd Yaghūth ibn Ṣalā’ah, al-Muhalhil ibn Rabī‘ah, al-Khansā’, Ṣakhr dan Mu‘āwiyah ibn ‘Amr, Ḥassān ibn Thābit, dan lainnya, maka terlihat jelas kecenderungan tersebut.14
Dalam tradisi kesukuan, selama hubungan antara penyair dengan kabilahnya terikat secara sosial (al-‘aqd al-ijtimā‘ī), maka secara otomatis akan membentuk sebuah ikatan puitika (al-‘aqd al-fannī) bahwa ia berbicara sebagai representasi dari suara kolektivitas kabilahnya. Dengan kata lain, secara artistik puisi-puisi yang dihasilkan diwarnai oleh kepentingan kabilahnya, bukan pribadinya.15 Mengenai hal ini Ira M. Lapidus dan Mohammed A. Bamyeh mengatakan, kesukuan merupakan tema dominan yang digunakan oleh para penyair Arab pra-Islam dalam puisi-puisi yang mereka ciptakan. Puisi merupakan media propaganda sistem kesukuan yang mengekspresikan sebuah perjuangan untuk nama baik kabilah, dan tidak menawarkan kesempatan untuk mengekspresikan individualitas. Seorang penyair dengan keterampilan yang dimilikinya mampu melukiskan kebaikan dan kemenangan kabilahnya dalam puisi-puisi yang ia ciptakan, sebagaimana ia juga mampu mendeskripsikan kejelekan dan kekalahan perang yang diderita oleh kabilah lain.16
13Lihat di antaranya: Ibn Sallām al-Jumaḥī, Ṭabaqāt Fuḥūl al-Shu‘arā’, Jilid. 1, ed. Maḥmūd Muḥammad Shākir (Jeddah: Dār al-Madanī, t.t); al-Jāḥiẓ, al-Bayān wa-al-Tabyīn, Jilid. 1, ed. ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn (Kairo: Maktabat al-Khānjī, 1998); Aḥmad Amīn, Fajr al-Islām (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1969), 59; Muṣṭafá Ṣādiq al-Rāfi‘ī, Tārīkh Ādāb al-‘Arab, Jilid. 2, ed. ‘Abd Allāh al-Minshāwī dan Mahdī al-Baḥqīrī (Kairo: Maktabat al-Aymān, 1997), 24-26; ‘Alī Muṣṭafá ‘Ashshā, “Jadalīyat al-‘Aṣabīyah al-Qabalīyah wa-al-Qiyam fī Namādhij min al-Shi‘r al-Jāhilī,” Majallat Majma‘ al-Lughah al-‘Arabīyah bi-Dimishq 83 (t.t): 1-26.
14Lihat pada bab pendahuluan (muqaddimah), Muḥammad Aḥmad Jād al-Mawlá Bek, ‘Alī Muḥammad al-Bajāwī, dan Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Ayyām al-‘Arab fī al-Jāhilīyah (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣrīyah, t.t). Tentang penjelasan adanya keterkaitan organik antara struktur puisi dan struktur kesukuan, lihat Adonis, al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil: Baḥth fī al-Ibdā‘ wa-al-Ittibā‘ ‘inda al-‘Arab, Jilid. 2 (Beirut: Dār al-Sāqī, 1994), 45.
15Yūsuf Khulayf, Dirāsāt fī al-Shi‘r al-Jāhilī (Kairo: Maktabat Gharīb, t.t), 174.16Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, 2nd ed (Cambridge: Cambridge University Press,
6 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
Dalam hubungan ini, tentu saja kita tidak menolak citra dominan tersebut. Namun, juga keliru jika menganggap bahwa gambaran seperti itu adalah citra satu-satunya dalam menggambarkan kehidupan pra-Islam. Faktanya dalam puisi Arab pra-Islam sendiri ditemukan benih-benih kreatif yang menyimpang dan memberontak terhadap kabilah dan nilai-nilainya yang dominan. Sebagaimana yang diakui oleh Yūsuf Khulayf dan Adonis, kecenderungan menyimpang dan memberontak dalam puisi Arab pra-Islam ini khususnya seperti yang ditunjukkan dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk; sekelompok masyarakat marginal yang memberontak kabilah, seperti Qays ibn al-Ḥidādīyah, Abū al-Ṭamaḥān al-Qaynī, Ḥājiz al-Azdī, Ta’abbaṭa Sharran, al-Sulayk ibn al-Sulakah, al-Shanfará, ‘Urwah ibn al-Ward, dan lain sebagainya.17 Selain juga dibuktikan dalam sebagian puisi-puisi Imru’ al-Qays dan Ṭarafah ibn al-‘Abd.18 Dalam puisi-puisi tersebut tercerminkan kecenderungan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kesukuan.19
Tidak seperti puisi-puisi para penyair kabilah yang mencerminkan bentuk fanatisme individu terhadap kabilahnya, puisi-puisi yang dipresentasikan oleh kelompok Ṣa‘ālīk khususnya, merupakan puisi-puisi yang memberontak dan menyimpang. Demikian, sebagaimana yang diakui oleh Roger Allen,20 Muḥammad al-Nuwayhī,21 Muhsin J. al-Musawi,22 dan Leila Khani.23 Menurut Adel Sulaiman Gamal, puisi-puisi Ṣa‘ālīk menunjukkan sikap anti sosial,24 atau dalam istilah Yūsuf Khulayf, puisi-puisi Ṣa‘ālīk mencerminkan sikap independensi individual (al-shakhṣīyah al-fardīyah) yang lepas dari kabilahnya. Hilangnya semangat
2002), 13; Mohammed A. Bamyeh, The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1999), 281.
17Lihat Shawqī Ḍayf, al-‘Aṣr al-Jāhilī (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2003), 375-87; Yūsuf Khulayf, al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-‘Aṣr al-Jāhilī (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1978); ‘Abd al-Ḥalīm Ḥifnī, Shi‘r al-Ṣa‘ālīk: Manhajuhu wa-Khaṣā’iṣuh (Kairo: al-Hay’ah al-Miṣrīyah al-‘Āmmah li-al-Kitāb, 1987); Ḥasan Ja‘far Nūr al-Dīn, Mawsū‘at al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk: al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk min al-‘Aṣr al-Jāhilī ḥattá al-‘Aṣr al-Ḥadīth, Jilid 2 (Beirut: Rashād Bars, 2007).
18Tentang penyimpangan dalam puisi-puisi Imru’ al-Qays, lihat Adonis, al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil, Jilid. 1, 208-11, 258-63. Tentang Ṭarafah ibn al-‘Abd, lihat Yūsuf Khulayf, Dirāsāt fī al-Shi‘r al-Jāhilī, 182-83; ‘Abd al-Razzāq al-Khushrūm, al-Ghurbah fī al-Shi‘r al-Jāhilī (Damaskus: Ittiḥād al-Kitāb al-‘Arab, 1982), 233-40.
19Yūsuf Khulayf, Dirāsāt fī al-Shi‘r al-Jāhilī, 180-89; Adonis, al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil, Jilid. 1, 143.
20Roger Allen, An Introduction to Arabic Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 68.
21Muḥammad al-Nuwayhī, al-Shi‘r al-Jāhilī: Manhaj fī Dirāsatihi wa-Taqwīmih, Jilid. 1 (Kairo: al-Dār al-Qawmīyah, t.t), 886.
22Muhsin J. al-Musawi, Arabic Poetry: Trajectories of Modernity and Tradition (London & New York: Routledge, 2006), 238.
23Leila Khani, “Investigating the Aspects of Social, Political, and Economic Life between Different Groups Saalik,” AENSI Journals: Journal of Applied Science and Agriculture 8/4 (September 2013): 361.
24Dikutip oleh Jonathan A.C. Brown, “The Social Context of pre-Islamic Poetry: Poetic Imagery and Social Reality in the Mu‘allaqāt,” Vol. 25, No. 3 (2012): 29-50.
7Pendahuluan
kesukuan ini merupakan konsekuensi dari munculnya disparitas sosial dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa itu.25
Disparitas sosial merupakan problem yang dihadapi oleh kelompok Ṣa‘ālīk pra-Islam. Adanya kesenjangan antarindividu dalam kabilah, seperti munculnya diskriminasi dalam hubungan nasab dan kekerabatan suku, kesenjangan antara kelas kaya dan miskin, atau masalah-masalah lainnya yang diakibatkan oleh kondisi tersebut. Kasus para Ṣa‘ālīk dari golongan khula‘ā’ yang terusir dan identitas kesukuan mereka dicabut, atau pada pengalaman hidup orang-orang aghribat al-‘Arab dan hujanā’ yang termarginalkan akibat perbedaan rasial dan nasab, adalah potret bagaimana nasab dan identitas kesukuan menjadi ukuran dalam penentuan kedudukan sosial seseorang dalam kabilah. Maka jika identitas kesukuan mereka dicabut, atau memiliki ras dan nasab yang berbeda, mereka tidak dianggap sebagai bagian dari kabilahnya.
Di sisi lain, faktor kemiskinan juga merupakan masalah utama bagi kehidupan kelompok Ṣa‘ālīk pada masa pra-Islam. Selain karena kondisi kehidupan Jazirah Arab yang sulit, kemiskinan bahkan muncul dari akibat munculnya kesenjangan ekonomi dalam kabilah di mana terpusatnya kekayaan di tangan kelas tertentu. Sehingga dengan perbedaan yang tajam dalam hal material inilah kemudian yang menjadi pemicu terjadinya jurang pemisah antara orang-orang kaya dan miskin. Sesuatu yang memberikan dampak pada terkikisnya hubungan antarindividu dalam kabilah, dan menjadikan orang-orang miskin lari dari kesatuan masyarakatnya (kabilah).26
Dari konteks ini, yang menjadi perhatian dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk adalah bahwa puisi-puisi tersebut muncul dari pemikiran dan pandangan tertentu tentang kehidupan. Dari sisi muatan, puisi-puisi mereka menggambarkan potret disparitas sosial dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Tidaklah mengherankan jika puisi-puisi Ṣa‘ālīk umumnya mengekspresikan penolakan terhadap perbedaan kelas, dan menggambarkan situasi ekonomi mereka yang buruk, serta persoalan-persoalan lainnya.27 Sebagaimana yang dikatakan oleh Burhān al-Dīn Dallū, cerita-cerita Ṣa‘ālīk dan puisi-puisinya mencerminkan kesadaran pahit karena kemiskinan yang melilit kehidupan mereka, kegelisahan atas kezaliman sosial, dan kehinaan tempat tinggal mereka, serta penolakan
25Yūsuf Khulayf, Dirāsāt fī al-Shi‘r al-Jāhilī, 187-89.26Tentang golongan-golongan yang dikategorikan sebagai Ṣa‘ālīk dan faktor-faktor yang
melatarbelakangi munculnya pada masa pra-Islam, lihat Yūsuf Khulayf, al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-‘Aṣr al-Jāhilī, 57-58, 63-150.
27Khalīl ‘Abd al-Karīm, Quraysh min al-Qabīlah ilá al-Dawlah al-Markazīyah (Beirut & Kairo: Mu’assasat al-Intishār al-‘Arabī & Sīnā, 1997), 287.
8 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
terhadap perbudakan dan diskriminasi etnis.28
Di sisi lain, puisi-puisi Ṣa‘ālīk juga memiliki kecenderungan menyimpang–dalam arti melakukan perubahan–dari struktur formal puisi Arab pra-Islam. Kecenderungan tersebut khususnya seperti yang terlihat dalam bentuk, tema, bahkan karakteristik diksi dan musikalitas dalam matra (wazn) yang pendek.29 Jika umumnya puisi-puisi para penyair kabilah melontarkan pemikiran, mempertahankan dan melestarikan, serta mengikuti pola dan tradisi yang sudah ada, maka puisi-puisi Ṣa‘ālīk lahir dari pengalaman dan pemikiran mereka dengan menempuh jalan baru yang boleh jadi belum ada sebelumnya. Namun demikian, puisi-puisi seperti yang diusung oleh kelompok Ṣa‘ālīk yang dalam istilah Khalīl ‘Abd al-Karīm disebut sebagai “al-shi‘r al-siyāsī ṭarīf” (puisi politik pinggiran),30 atau dalam istilah Adonis disebut sebagai “al-shi‘r al-madhhabī” (puisi sektarian) ini tidak memiliki arti penting dari sisi seni untuk seni, akan tetapi makna pentingnya lebih terkait dengan transformasi puisi dari wilayah ekspresi intuisi menuju ekspresi nalar yang berdasarkan pada realitas.31
Dari perspektif inilah kemudian mengapa mengkaji puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam menjadi penting untuk dikembangkan lebih jauh. Makna pentingnya tidak hanya bagi diskursus puisi Arab, tetapi juga bagi peradaban Arab secara umum. Dalam hubungan ini, makna pentingnya terkait dengan beberapa alasan:
Pertama, kecenderungan berbeda seperti yang ditunjukkan oleh puisi-puisi Ṣa‘ālīk, selain puisi-puisi dalam kecenderungan para penyair kabilah tentunya, memperlihatkan sebuah perspektif yang dapat dijadikan titik tolak dalam berbagai fakta dan kesimpulan dalam mengkaji puisi Arab pra-Islam, bahkan peradaban Arab secara umum. Perspektif tersebut menyiratkan makna bahwa sejatinya peradaban Arab tidaklah tunggal, akan tetapi beragam. Dengan kata lain, asal-usul tersebut mengandung benih-benih dialektis antara yang menerima dan menolak. Meminjam teori yang dikemukakan oleh Adonis, yang “al-thābit” (mapan-statis) dan “al-mutaḥawwil” (berubah-dinamis).
Al-Thābit khususnya terkait dengan kabilah dan nilai-nilainya yang dominan, sementara al-mutaḥawwil terkait dengan penyimpangan dan pemberontakan terhadapnya. Tidak adanya sistem yang mencairkan seluruh kabilah, serta
28Burhān al-Dīn Dallū, Jazīrat al-‘Arab qabl al-Islām: al-Tārīkh al-Iqtiṣādī, al-Ijtimā‘ī, al-Thaqāfī, wa-al-Siyāsī (Beirut: Dār al-Fārābī, 2004), 163.
29Tentang karakteristik puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, lihat ‘Abd al-Ḥalīm Ḥifnī, Shi‘r al-Ṣa‘ālīk: Manhajuhu wa-Khaṣā’iṣuh, 406-21; Yūsuf Khulayf, al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-‘Aṣr al-Jāhilī, 259-319.
30Khalīl ‘Abd al-Karīm, Quraysh, 289.31Adonis, al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil, Jilid. 1, 308-14.
9Pendahuluan
menyatukan kehidupan dan pemikirannya, memiliki peran mendasar yang menyebabkan dialektika ini tetap memiliki kadar kebebasan dan keterbukaan. Dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk khususnya, selain juga dalam sebagian puisi-puisi Imru’ al-Qays dan Ṭarafah ibn al-‘Abd, ada benih bagus yang mendorong terjadinya transformasi puisi menuju dimensi dan perspektif baru. Oleh karena itu, jika memang benar pernyataan yang mengatakan bahwa puisi merupakan dokumen sosial (dīwān) dan sumber pengetahuan paling otoritatif yang dimiliki oleh bangsa Arab, maka dapat dikatakan bahwa puisi merupakan sumber pertama bagi peradaban Arab yang terbagi sesuai dengan tingkatan dan sumbernya. Tentunya puisi tidaklah tunggal dengan satu pola, akan tetapi beragam, baik dari sisi ekspresi (al-ta‘bīr) maupun muatannya (al-muḥtawá).32
Kedua, puisi-puisi Ṣa‘ālīk telah memberikan corak tersendiri bagi diskursus puisi Arab. Kecenderungan dalam puisi-puisi tersebut mencerminkan makna dan dimensi lain dari kehidupan pra-Islam. Dimensi tersebut tidak hanya tampak pada muatan puisi yang mencerminkan pemberontakan dan protes terhadap kabilah dan nilai-nilainya yang dominan, akan tetapi juga tampak pada struktur formal puisi yang menyimpang dari kecenderungan umum puisi Arab pra-Islam. Kesimpulan ini paling tidak menguatkan teori yang dikemukakan oleh Yūsuf Khulayf dan Adonis.
Ketiga, fenomena Ṣa‘ālīk bukan saja dapat dilihat sebagai fakta sejarah, tetapi juga sebagai bagian integral dari pertumbuhan peradaban Arab. Dalam kaitan ini menarik untuk disinggung beberapa pendapat–meskipun bersifat spekulatif–seperti Ṣaghīr ibn Gharīb ‘Abd Allāh al-‘Anazī yang mengatakan bahwa mengkaji berbagai macam kemungkinan munculnya berbagai sekte oposan dalam sejarah bangsa Arab tentu tidak bisa dilepaskan dari implikasi oposisional (al-mu‘āraḍah al-siyāsīyah) kelompok Ṣa‘ālīk.33 Demikian pula, munculnya gerakan oposisi Khawārij juga tidak bisa dilepaskan dari kelompok Ṣa‘ālīk. Sebagaimana diakui oleh Aḥmad Sulaymān Ma‘rūf dalam pernyataannya bahwa kelompok Ṣa‘ālīk merupakan genealogi dari munculnya kelompok Khawārij (wa-anna al-Ṣa‘ālīk, Ṣa‘ālīk al-Jāhilīyah hum ajdād al-Khawārij).34 Namun demikian, fakta sejarah semacam ini setidaknya kurang mendapat perhatian. Karenanya perlu ada kajian lebih lanjut mengenai hal ini.
32Adonis, al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil, Jilid. 1, 258-9.33Ṣaghīr ibn Gharīb ‘Abd Allāh al-‘Anazī, “Ru’yat al-‘Ālam fī Shi‘r al-Ṣa‘ālīk ḥattá Nihāyat al-
Qarn al-Thālith al-Hijrī” (Disertasi., Jāmi‘at Umm al-Qurá, 2010/1431 H), 4.34Aḥmad Sulaymān Ma‘rūf, Qirā’ah Jadīdah fī Mawāqif al-Khawārij, wa-Fikrihim, wa-Adabihim
(Damaskus: Dār al-Ṭallās, 1988), 21-23.
10 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
Keempat, kajian tentang puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam merupakan bidang kajian yang belum mendapatkan perhatian yang cukup. Terlebih lagi kajian tentang kritik dan sejarah sastra Arab klasik, khususnya puisi Arab pra-Islam, selama ini didominasi oleh kajian-kajian tentang puisi-puisi para penyair “top”. Meminjam terminologi yang digunakan oleh al-Aṣma‘ī, “fuḥūlat al-shu‘arā’”,35 seperti puisi-puisi para penyair mu‘allaqāt (untuk menyebut sebagiannya saja), ketimbang puisi-puisi para penyair marginal, seperti puisi-puisi Ṣa‘ālīk.
Argumen-argumen yang telah dikemukakan tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk mengkaji puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, yang dalam hal ini mengambil fokus pada muatan protes yang dikandungnya. Tentunya, kajian terhadap konteks sosial yang melingkupi puisi-puisi tersebut tidak dapat dipalingkan. Oleh karena itu, upaya eksplorasi puisi melalui tinjauan sosiologis menjadi cukup beralasan untuk dilakukan. Tujuannya agar dapat menyajikan berbagai fakta sosial yang terkandung dalam puisi-puisi tersebut. Apalagi dikatakan bahwa meskipun kesempurnaan bentuk sebagai tanda keunggulan ciptaan puisi Arab pra-Islam, namun jika kembali pada tradisi puisi pada masa itu, kita dapat melihat bahwa puisi hampir tidak pernah meninggalkan peranannya sebagai bahasa pencatat dan pengungkap kecenderungan sosial dan intelektual zamannya.36 Dengan begitu, menganalisis puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam dengan perspektif sosiologi sastra merupakan sesuatu yang relevan, bahkan signifikan.
Fokus Kajian
Kritik sastra Arab klasik, bahkan kritik sastra Arab modern, umumnya menampilkan puisi Arab pra-Islam dengan citra kesukuan. Dalam perkataan lain, kritik tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan organik antara struktur puisi dengan struktur kesukuan. Padahal, di sisi lain terdapat puisi-puisi yang mencerminkan penyimpangan dan pemberontakan terhadap kabilah dan nilai-nilainya yang dominan. Meminjam teori yang dikemukakan oleh Yūsuf Khulayf, puisi Arab pra-Islam memiliki kecenderungan dengan apa yang ia sebut sebagai “al-shi‘r al-Jāhilī bayn al-qabalīyah wa-al-fardīyah,” (puisi Arab pra-Islam: cerminan kesukuan vis-à-vis independensi individual),37 atau dalam istilah Adonis, “al-thābit wa-al-mutaḥawwil” (yang mapan-statsis dan yang berubah-dinamis).38
35al-Aṣma‘ī, Kitāb Fuḥūlat al-Shu‘arā’, ed. Ṣalāḥ al-Dīn al-Munajjad (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1980).
36Muhsin J. al-Musawi, Arabic Poetry, 1.37Lihat Yūsuf Khulayf, Dirāsāt fī al-Shi‘r al-Jāhilī, 171-89.38Adonis, al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil, Jilid. 1, 258-9.
11Pendahuluan
Pertama, puisi-puisi para penyair kabilah (aṣḥāb al-madhhab al-qabalī), yaitu puisi-puisi yang menyuarakan kepentingan kabilah atau kekuasaan. Kedua, puisi-puisi para penyair independen (aṣḥāb al-madhhab al-fardī), yaitu puisi-puisi yang menyimpang dan memberontak dari tradisi kesukuan dan nilai-nilainya yang dominan. Kecenderungan ini, baik yang muncul dari pengalaman subjektif (al-tajribah al-dhātīyah) seperti puisi-puisi Imru’ al-Qays dan Ṭarafah ibn al-‘Abd, ataupun yang muncul dari pengalaman politik ideologis (al-tajribah al-siyāsīyah al-īdiyūlūjīyah) seperti yang tercermin dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk dan kehidupan mereka.
Dari dua kecenderungan tersebut, buku ini memfokuskan kajian pada puisi-puisi Ṣa‘ālīk. Kajian tentang kelompok Ṣa‘ālīk pra-Islam secara umum memiliki kemungkinan berbagai macam permasalahan yang dapat dijadikan sebagai objek kajian, seperti latar belakang sejarah, tokoh-tokoh, karakteristik kehidupan, maupun puisi. Namun, terkait dengan puisi-puisi yang menjadi kecenderungan kelompok Ṣa‘ālīk, secara umum dapat diidentifikasi dalam dua hal:
Pertama, dari struktur formal, puisi-puisi Ṣa‘ālīk memiliki kecenderungan berbeda, baik dari sisi bentuk, tema, maupun karakteristik bahasa dan seni yang menyimpang dari umumnya puisi Arab pra-Islam. Kedua, dari sisi muatan. Jika umumnya puisi-puisi para penyair kabilah mencerminkan bentuk fanatisme individu terhadap kabilah, maka puisi-puisi Ṣa‘ālīk mencerminkan pemberontakan dan protes, khususnya disparitas sosial dalam kehidupan kabilah. Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah muatan protes sosial dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam.39
Muatan protes yang terkandung dalam puisi-puisi tersebut tentunya dipahami dengan mengaitkan konteks sosialnya, atau yang dalam istilah René Wellek dan Austin Warren disebut sebagai sisi ekstrinsik, sebagaimana yang menjadi objek kajian sosiologi sastra.40 Secara lebih spesifik, masalah utama kajian ini setidaknya diuraikan dengan mempertanyakan bagaimana puisi-puisi Ṣa‘ālīk menggambarkan protes terhadap disparitas sosial dalam masyarakat Arab pra-Islam?
Lebih lanjut, buku ini juga memuat beberapa batasan: pertama, kelompok Ṣa‘ālīk pra-Islam yang menjadi fokus kajian–sebagaimana klasifikasi yang
39Protes/pro.tes/protés/n adalah pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal, dan sebagainya. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1107.
40René Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, terj. Melani Budianta (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 79.
12 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
dilakukan oleh Yūsuf Khulayf dalam bukunya al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-‘Aṣr al-Jāhilī–terdiri dari tiga golongan, yaitu: khula‘ā’, individu-individu yang terusir dari kekerabatan suku; aghribat al-‘Arab, individu-individu yang termarginalkan akibat perbedaan rasial dan kualitas nasab; dan ṣa‘ālīk fuqarā’, golongan masyarakat miskin.41
Kedua, objek protes yang dijadikan fokus kajian adalah disparitas sosial, khususnya dengan menitikberatkan pada dua hal: pertama, protes terhadap diskriminasi dalam hubungan nasab dan kekerabatan suku. Kedua, protes terhadap kemiskinan dan kesenjangan sosial. Jika dapat diklasifikasikan, yang pertama merupakan identifikasi dari tendensi protes sosial puisi-puisi Ṣa‘ālīk dari golongan khula‘ā’ dan aghribat al-‘Arab. Sedangkan yang kedua merupakan identifikasi dari protes sosial puisi-puisi ṣa‘ālīk fuqarā’; golongan masyarakat miskin.
Beberapa Kajian Terdahulu
Kajian tentang sejarah, tokoh-tokoh, dan karakteristik puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, setidaknya telah menjadi tema kajian dalam buku-buku sejarah kesusastraan Arab (tārīkh al-adab al-‘Arabī) pada umumnya, meskipun terkadang hanya sebatas uraian-uraian singkat. Sebagian di antaranya seperti: Jurjī Zaydān, Tārīkh Ādāb al-Lughah al-‘Arabīyah;42 Jawwād ‘Alī, al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab qabl al-Islām,43 Shawqī Ḍayf, al-‘Aṣr al-Jāhilī;44 Ḥasan Ja‘far Nūr al-Dīn, Mawsū‘at al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk: al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk min al-‘Aṣr al-Jāhilī ḥattá al-‘Aṣr al-Ḥadīth;45 Roger Allen, An Introduction to Arabic Literature;46 Ignaz Goldziher, A Short History of Classical Arabic Literature;47 dan lain sebagainya.
Kajian yang lebih komprehensif tentang puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam pertama kali dilakukan oleh Yūsuf Khulayf dalam karyanya al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-‘Aṣr al-Jāhilī (1958). Paling tidak ada dua hal pokok yang menjadi fokus kajian
41Yūsuf Khulayf, al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-‘Aṣr al-Jāhilī, 57-58.42Jurjī Zaydān, Tārīkh Ādāb al-Lughah al-‘Arabīyah, Jilid. 1, ed. Shawqī Ḍayf (Kairo: Dār al-Hilāl,
t.t), 141-44.43Jawwād ‘Alī, al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab qabl al-Islām, Jilid. 9 (Baghdād: Jāmi‘at Baghdād,
1993), 601-53.44Shawqī Ḍayf, al-‘Aṣr al-Jāhilī (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2003). 375-87.45Ḥasan Ja‘far Nūr al-Dīn, Mawsū‘at al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk: al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk min al-‘Aṣr al-Jāhilī
ḥattá al-‘Aṣr al-Ḥadīth, Jilid 2 (Beirut: Rashād Bars, 2007).46Roger Allen, An Introduction to Arabic Literature (Cambridge: Cambridge University Press,
2003), 67-68.47Ignaz Goldziher, A Short History of Classical Arabic Literature, terj. Joseph Desomogyi
(Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1966), 13-17.
13Pendahuluan
Khulayf, yaitu: pertama, latar belakang munculnya fenomena Ṣa‘ālīk pada masa pra-Islam. Kedua, tema dan karakteristik puisi yang menjadi kecenderungan mereka. Kajian ini juga diakhiri dengan ulasan biografis tentang dua tokoh Ṣa‘ālīk pra-Islam, yakni ‘Urwah ibn al-Ward dan al-Shanfará. Khusus mengenai puisi-puisi yang menjadi kecenderungan kelompok Ṣa‘ālīk pra-Islam, Khulayf lebih membincangkan tentang karakteristik umum puisi, seperti bentuk, tema, maupun karakteristik bahasa dan seni, yang menurutnya memiliki kecenderungan berbeda dari umumnya puisi Arab pra-Islam.48
Kajian serupa juga telah menarik perhatian ‘Abd al-Ḥalīm Ḥifnī dalam Shi‘r al-Ṣa‘ālīk: Manhajuhu wa-Khaṣā’iṣuh (1987). Kajian Ḥifnī sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Khulayf, yakni fokus pada sejarah dan karakteristik puisi-puisi Ṣa‘ālīk. Perbedaannya, jika Khulayf hanya fokus pada kelompok Ṣa‘ālīk pra-Islam, Ḥifnī lebih mengembangkan kajiannya terhadap kelompok Ṣa‘ālīk dari masa pra-Islam sampai pada masa Islam.49 Kajian yang dilakukan oleh ‘Abd al-Ḥalīm Ḥifnī, selain juga studi Yūsuf Khulayf, meskipun lebih bercorak sejarah sastra (tārīkh al-adab), namun paling tidak merupakan kajian yang komprehensif dan sangat informatif tentang puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam.
Kajian penting lainnya adalah tulisan Ḥasan Muḥammad Rabāba‘ah dengan judul “al-Ghārah ‘inda al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-Jāhilīyah” (1998/1418 H). Dibandingkan dengan dua kajian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Khulayf dan Ḥifnī, kajian Rabāba‘ah lebih spesifik, yakni fokus pada tema perampokan (al-ghārah) dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam. Menurutnya, sebagaimana yang tercermin dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk, terdapat dua motif perampokan yang menjadi karakteristik mereka: pertama, motif material (al-dāfi‘ al-jasadī). Motif ini merupakan bentuk perampokan yang umumnya dilakukan oleh kelompok Ṣa‘ālīk sebagai orang-orang miskin yang hidup dalam kelaparan dan membutuhkan makanan. Kedua, latar belakang individual (al-dāfi‘ al-nafsī). Perampokan ini dilatarbelakangi oleh masalah-masalah individual yang dialami oleh para Ṣa‘ālīk, seperti terusirnya mereka dari kabilahnya, diskriminasi akibat perbedaan rasial dan nasab, masalah kemiskinan, dan lain sebagainya. Karenanya, perampokan dalam pengalaman ini dapat dilihat sebagai bentuk protes terhadap kabilah yang telah merampas hak-hak sosial mereka.50
48Yūsuf Khulayf, al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-‘Aṣr al-Jāhilī (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1978).49‘Abd al-Ḥalīm Ḥifnī, Shi‘r al-Ṣa‘ālīk: Manhajuhu wa-Khaṣā’iṣuh (Kairo: al-Hay’ah al-Miṣrīyah
al-‘Āmmah li-al-Kitāb, 1987).50Ḥasan Muḥammad Rabāba‘ah, “al-Ghārah ‘inda al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-Jāhilīyah,” Majallat
Jāmi‘at al-Malik Su‘ūd – al-Ādāb 1, 1998/1418 H, 53-92.
14 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
Ṣaghīr ibn Gharīb ‘Abd Allāh al-‘Anazī, di pihak lain, dalam disertasinya di Universitas Umm al-Qurá Saudi Arabia dengan judul “Ru’yat al-‘Ālam fī al-Shi‘r al-Ṣa‘ālīk ḥattá Nihāyat al-Qarn al-Thālith al-Hijrī (2010/1431 H). Jika kajian Rabāba‘ah fokus pada tema perampokan, maka kajian al-‘Anazī lebih fokus pada pandangan dunia (worldview) dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk. Terlebih lagi kajian al-‘Anazī ini tidak hanya membincangkan tentang worldview dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, tetapi membandingkannya dengan puisi-puisi Ṣa‘ālīk pada masa Islam, Umayyah, dan ‘Abbāsīyah. Dalam pandangan al-‘Anazī, worldview yang ditunjukkan dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, seperti gambaran tentang memisahkan diri dari kehidupan kabilah (al-infiṣāl ‘an al-qabīlah), protes terhadap kemiskinan dan kesenjangan sosial (al-iḥtijāj ‘an al-faqr wa-ghiyāb al-‘adālah al-ijtimā‘īyah), dan kebebasan (faḍā’ al-ḥurrīyah).51
Leila Khani, “Investigating the Aspects of Social, Political, and Economic Life between Different Groups Saalik” (2013). Kajian ini pada dasarnya fokus pada perbincangan tentang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kelompok Ṣa‘ālīk. Dalam pandangan Khani, masalah-masalah sosial seperti diskriminasi rasial, disparitas ekonomi antara kelas kaya dan miskin, merupakan sebagian dari faktor-faktor yang menyebabkan mereka memberontak dan memisahkan diri dari kehidupan kabilah. Gambaran tentang kondisi ini seperti yang banyak terekam dalam puisi-puisi yang mereka ciptakan. Dalam kajiannya, Khani membandingkan karakteristik kehidupan kelompok Ṣa‘ālīk pada masa pra-Islam dan Umayyah. Jika pada masa pra-Islam, mereka keluar dan memberontak terhadap kabilah, maka pada masa Umayyah mereka memberontak terhadap khalifah.52
Kajian tentang puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam juga menarik perhatian Adonis dalam al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil: Baḥth fī al-Ibdā‘ wa-al-Ittibā‘ ‘inda al-‘Arab (1994). Kajian Adonis ini pada dasarnya merupakan kajian tentang epigonisme (ittibā‘) dan inovasi (ibdā‘) dalam pemikiran bangsa Arab (teologi, politik, budaya, hukum, termasuk bahasa-sastra-puisi), yang menurutnya bahwa aspek ittibā‘ lebih menguat dan dominan daripada ibdā‘. Ibdā‘ menempuh jalan baru yang belum pernah ada sebelumnya, sedangkan ittibā‘ mengikuti pola yang sudah ada. Yang menarik dari kajian mengenai puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, Adonis berpendapat bahwa puisi-puisi yang dipresentasikan oleh kelompok Ṣa‘ālīk merupakan
51Ṣaghīr ibn Gharīb ‘Abd Allāh al-‘Anazī, “Ru’yat al-‘Ālam fī Shi‘r al-Ṣa‘ālīk ḥattá Nihāyat al-Qarn al-Thālith al-Hijrī” (Disertasi., Jāmi‘at Umm al-Qurá, 2010/1431 H).
52Leila Khani, “Investigating the Aspects of Social, Political, and Economic Life between Different Groups Saalik,” AENSI Journals: Journal of Applied Science and Agriculture 8/4 (September 2013): 361.
15Pendahuluan
wajah lain dari puisi Arab pra-Islam. Jika umumnya puisi-puisi yang menjadi kecenderungan para penyair kabilah melontarkan pemikiran yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikannya, maka puisi-puisi Ṣa‘ālīk melahirkan pemikiran baru yang boleh jadi bertujuan untuk dapat menggantikan warisan pemikiran yang dominan. Oleh sebab itu, menurutnya, para penyair kabilah dapat disebut sebagai penyair konservatif yang mendukung sistem (status quo), sedangkan kelompok Ṣa‘ālīk merupakan penyair yang memberontak sistem. Kajian Adonis ini dengan menjadikan puisi ‘Urwah ibn al-Ward; salah seorang tokoh Ṣa‘ālīk pra-Islam, sebagai contoh kajian.53
Khalīl ‘Abd al-Karīm, Quraysh min al-Qabīlah ilá al-Dawlah al-Markazīyah (1997). Studi ‘Abd al-Karīm ini pada dasarnya fokus pada kajian tentang pemikiran, pelacakan, dan penelusuran terhadap sejarah kabilah Quraysh dan Islam sekaligus yang telah membangun kekuasaan secara sistematis dengan meramu agama dan budaya dengan segala variannya. Yang menarik di sini, Abd al-Karīm juga mengulas tentang puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam. Bahkan, ia sampai pada pemikiran bahwa puisi-puisi Ṣa‘ālīk memiliki signifikansi yang tercermin dalam dua hal: pertama, mengilustrasikan kondisi masyarakat miskin yang diakibatkan oleh munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan kabilah. Kedua, puisi-puisi Ṣa‘ālīk merupakan media ekspresif dalam mendorong masyarakat miskin untuk menolak hukum-hukum diskriminatif dan tidak toleran, serta bertujuan untuk melakukan perubahan.
Dalam hubungan ini, yang dimaksud oleh ‘Abd al-Karīm adalah bahwa puisi-puisi Ṣa‘ālīk bukanlah puisi yang hanya mengekspresikan kekesalan dan kekecewaan atas kemiskinan yang melanda kehidupan mereka. Namun, lebih dari itu bahwa puisi-puisi tersebut merupakan puisi politik pinggiran (al-shi‘r al-siyāsī ṭarīf) yang memiliki peran penting dalam membangun premis-premis sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, yang dengan intens mewacanakan egaliterianisme dan keadilan sosial. Dengan begitu, puisi-puisi tersebut mempunyai pengaruh tersendiri di kalangan masyarakat miskin. Sesuatu hal yang dalam pandangan ‘Abd al-Karīm turut memberikan jalan bagi masyarakat miskin dalam merespon dakwah yang disebarkan oleh Muhammad melalui wacana keadilansosialnya.54
53Adonis, al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil: Baḥth fī al-Ibdā‘ wa-al-Ittibā‘ ‘inda al-‘Arab, Jilid. 1 (Beirut: Dār al-Sāqī, 1994). Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Adonis, Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, Vol. 1, terj. Khairon Nahdiyyin (Yogyakarta: LKIS, 2007).
54Khalīl ‘Abd al-Karīm, Quraysh min al-Qabīlah ilá al-Dawlah al-Markazīyah (Beirut & Kairo: Mu’assasat al-Intishār al-‘Arabī & Sīnā, 1997). Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi
16 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
Lebih jauh ketika materi kajian tentang muatan protes sosial dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam sedikit disinggung, sehingga dalam konteks inilah setidaknya penelitian ini patut diangkat dan dipertajam lagi dari kajian-kajian terdahulu. Karena bagaimanapun, kajian dengan tema ini penting dilakukan untuk dapat dijadikan argumentasi bahwa puisi-puisi Ṣa‘ālīk mencerminkan tren lain dalam diskursus puisi Arab pra-Islam, yaitu puisi-puisi yang menyimpang dan memberontak terhadap kabilah dan nilai-nilainya yang dominan. Namun demikian, tanpa bermaksud mengecilkan kajian-kajian terdahulu, harus diakui bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh Yūsuf Khulayf, Adonis, Khalīl ‘Abd al-Karīm, Leila Khani, dan lainnya, secara implisit juga telah menyinggung kecenderungan tersebut.
Sosiologi Sastra sebagai Pendekatan
Kajian ini memusatkan perhatian pada fenomena sosial dalam karya sastra, dalam hal ini puisi. Oleh karena itu, studi ini merupakan jenis penelitian kritik sastra. Namun demikian, sejauh memiliki relevansinya dengan penelitian ini, sejarah sastra pun ditelaah pula, terutama untuk mengetahui situasi sosial dan ideologi yang turut memengaruhi puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam. Penelitian sejarah sastra lebih menekankan pada perkembangan karya sastra, tokoh-tokoh, ciri-ciri, aliran-aliran, yang semuanya berpengaruh terhadap perkembangan karya sastra. Sedangkan kritik sastra lebih membincangkan tentang pemahaman, penghayatan, dan penilaian terhadap karya sastra.55 Dalam aplikasinya meski berbeda dalam penekanannya, kedua model kajian tersebut tidak benar-benar dapat dipisahkan.
Sebagaimana telah dirumuskan dalam ruang lingkup permasalahan, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada pemahaman terhadap puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam yang berkaitan dengan konteks sosial, atau sisi ekstrinsiknya. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam hubungan ini, upaya eksplorasi puisi melalui tinjauan sosiologis menjadi cukup beralasan untuk dilakukan dalam upaya menyajikan berbagai informasi mengenai fakta-fakta sosial dalam puisi-puisi tersebut.56
Khalil Abdul Karim, Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan, terj. M. Faisol Fatawi (Yogyakarta: LKIS, 2002).
55Atmazaki, Ilmu Sastra: Teori dan Terapan (Padang: Angkasa Raya, 1990), 9.56Secara umum dapat dikatakan bahwa fakta sastra menyiratkan adanya pencipta, karya, dan
publik. Kehadiran individu pencipta menimbulkan masalah interpretasi psikologis, moral, dan filsafat. Media karya menimbulkan masalah estetika, gaya bahasa, dan teknik. Sedangkan adanya kolektivitas-publik menimbulkan masalah dari segi historis, politik, sosial, bahkan ekonomi. Lihat Robert Escarpit, Sosiologi Sastra, terj. Ida Sundari Husen (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 3.
17Pendahuluan
Sosiologi sastra sebagai suatu cara pandang terhadap karya sastra,57 memiliki paradigma dan asumsi epistemologis yang berbeda dari apa yang telah digariskan oleh teori sastra berdasarkan pada prinsip otonomi sastra, seperti Formalisme dan Strukturalisme murni yang sama-sama menganggap karya sastra pada dasarnya bersifat otonom, sehingga yang menjadi perhatian keduanya adalah teks sastra itu sendiri.58 Sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan keterlibatan struktur sosialnya, seperti hubungan antara pengarang dengan kelas sosialnya, status sosial dan ideologinya, kondisi ekonomi dalam profesinya, dan segmen pembaca yang ditujunya. Dengan demikian, penelitian sosiologi sastra dilakukan dengan cara mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan unsur-unsur karya sastra dalam kaitannya dengan perubahan struktur sosial yang terjadi di sekitarnya.59
Menurut Diana Laurenson dan Alan Swingewood, setidaknya terdapat tiga perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu: pertama, penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan situasi pada masa karya sastra tersebut diciptakan. Kedua, penelitian yang mengungkap karya sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya. Dan ketiga, penelitian yang mengungkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Seorang peneliti dapat mengungkap salah satu atau secara keseluruhan dari ketiga perspektif tersebut, tergantung dengan kemampuannya. Namun, semua itu juga tergantung pada sasaran atau tujuan penelitian. Jika ingin mengungkap fakta sejarah masyarakat pada masa lalu, memang tepat menggunakan perspektif ketiga. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Elizabeth dan Toms Burn, karya sastra memang seringkali tampak terikat dengan momen khusus dalam sejarah masyarakat.60
Penelitian ini berusaha memahami sejauhmana puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam mengungkap fakta sejarah masyarakat Arab pada masa itu. Apalagi jamak diketahui bahwa puisi Arab pra-Islam tidak hanya sebagai seni verbal yang
57Teori sosiologi sastra muncul dari konsep mimesis (tiruan) Plato yang menganggap karya seni sebagai tiruan dari kenyataan. Jadi, karya seni merupakan tiruan dari tiruan. Sebaliknya, filsafat ide Plato yang semata-mata bersifat praktis tersebut ditolak oleh Aristoteles. Menurutnya, karya seni tidak semata-mata tiruan dari kenyataan. Dalam memahami kenyataan, seni didominasi oleh penafsiran. Oleh karena itu, seniman tidak semata-mata meniru kenyataan, tetapi menciptakan dunianya sendiri. Lihat Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4-5.
58Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 133-34, 182-83.
59Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, 25-26.60Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi
(Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), 79.
18 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
terbentuk sebagai seni itu sendiri, dan terlepas dari fungsi sosialnya. Salah satu fungsi sosial puisi Arab pra-Islam adalah sebagai sumber informasi sejarah. Puisi merupakan gambaran nyata dari potret kehidupan masyarakat Arab pada masanya. Karenanya, mengkaji kehidupan masyarakat Arab pra-Islam tidak akan sempurna tanpa merujuk puisi. Dengan begitu, menganalisis puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam dengan perspektif sosiologi sastra merupakan sesuatu yang relevan.
Dalam aplikasinya sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, khususnya protes sosial puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, maka perspektif yang digunakan adalah gagasan tentang keterlibatan sastra, pengarang, politik, dan ideologi. Dalam kritik sastra Marxis dikenal dengan sebutan “sastra bertendensi” (littérature engagée).61 Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan littérature engagée menurut Max Adereth adalah pentingnya menempatkan atau melihat politik dan ideologi sebagai latar belakang sastra, tidak sebagai sesuatu yang dipaksakan. Bagaimanapun tegasnya secara tersurat maupun tersirat, sastra harus menempatkan kritik terhadap zamannya.62 Pendekatan ini juga sebagaimana yang diusulkan oleh Fredric Jameson,63 Terry Eagleton,64 dan Ariel Haryanto,65 tentang apa yang mereka istilahkan dengan kritik politik dalam sastra.
Sumber dan Cara Membacanya
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data yang dikategorikan primer adalah antologi puisi para penyair Ṣa‘ālīk pra-Islam, di antaranya: Dīwān ‘Urwah ibn al-Ward;66 Dīwān
61Nyoman Kutha Ratna, Sastra dan Cultural Studies, 360. Ada beberapa bentuk relasi sastra dan politik, di antaranya: 1). Patronasi negara, baik untuk kepentingan politik (hegemoni), maupun untuk kepentingan sastra itu sendiri. Teori ini khususnya sebagaimana yang diusung oleh Diana Laurenson, Raymond Williams dan dibuktikan oleh Tony Davies; 2). Sastra yang menggambarkan praktik politik yang terjadi; 3). Sastra sebagai etika politik; 4). Sastra sebagai kritik demi terjadinya transformasi politik yang dalam bahasa Max Adereth disebut littérature engagée. Lihat Sukron Kamil, Najīb Maḥfūẓ, Sastra, Islam, dan Politik: Studi Semiotik terhadap Novel Awlād Ḥāratinā (Ciputat: UIN Jakarta Press), 83-86.
62Dikutip oleh Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, 117.63Raman Selden, Peter Widdowson, dan Peter Brooker, A Reader’s Guide to Contemporary Literary
Theory, 98.64Terry Eagleton, Literary Theory, 169-89.65Ariel Haryanto, “Sastra dan Politik: Sebuah Upaya Memahami Persoalan Kesusastraan
Mutakhir di Indonesia,” dalam Perdebatan Sastra Kontekstual, ed. Ariel Haryanto (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 39-40.
66Terdapat beberapa versi terkait antologi puisi ‘Urwah ibn al-Ward, di antaranya: ‘Abd al-Mu‘īn al-Malūḥī, ed. Dīwān ‘Urwah ibn al-Ward, Syarah oleh Ibn Sikkīt (Damaskus: Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Qawmī, 1966); Asmā’ Abū Bakr Muḥammad, ed. Dīwān ‘Urwah ibn al-Ward Amīr al-Ṣa‘ālīk (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1992); Sa‘dī Ḍannāwī, ed. Dīwān ‘Urwah ibn al-Ward (Beirut: Dār al-Jīl, 1996).
19Pendahuluan
al-Shanfará, wa-Yalīhi Dīwānā al-Sulayk ibn al-Sulakah, wa-‘Amr ibn Barrāq;67 Dīwān Ta’abbaṭa Sharran;68 Dīwān al-Luṣūṣ fī al-‘Aṣrayn al-Jāhilī wa-al-Islāmī oleh Muḥammad Nabīl Ṭarīfī; Dīwān al-Hudhalīyīn karya al-Sukkarī; dan Dīwān al-Mufaḍḍalīyāt karya Abū al-‘Abbās al-Mufaḍḍal ibn Muḥammad al-Ḍabbī.
Adapun sumber sekunder yang digunakan adalah sumber-sumber dari berbagai disiplin yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan, seperti: Kitāb al-Aghānī karya Abū al-Faraj al-Iṣfahānī, al-Shi‘r wa-al-Shu‘arā’ karya Ibn Qutaybah, Yūsuf Khulayf, al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-‘Aṣr al-Jāhilī; ‘Abd al-Ḥalīm Ḥifnī, Shi‘r al-Ṣa‘ālīk: Manhajuhu wa-Khaṣā’iṣuh, Aḥmad Amīn, al-Ṣa‘lakah wa-al-Futūwah fī al-Islām; Ḥasan Muḥammad Rabāba‘ah, “al-Ghārah ‘inda al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk fī al-Jāhilīyah”; Ṣaghīr ibn Gharīb ‘Abd Allāh al-‘Anazī, “Ru’yat al-‘Ālam fī al-Shi‘r al-Ṣa‘ālīk ḥattá Nihāyat al-Qarn al-Thālith al-Hijrī”; Ḥasan Ja‘far Nūr al-Dīn, Mawsū‘at al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk: al-Shu‘arā’ al-Ṣa‘ālīk min al-‘Aṣr al-Jāhilī ḥattá al-‘Aṣr al-Ḥadīth; ‘Abduh Badawī, al-Shu‘arā’ al-Sūd wa-Khaṣā’iṣuhum fī al-Shi‘r al-‘Arabī; Adonis, al-Thābit wa-al-Mutaḥawwil: Baḥth fī al-Ibdā‘ wa-al-Ittibā‘ ‘inda al-‘Arab; Khalīl ‘Abd al-Karīm, Quraysh min al-Qabīlah ilá al-Dawlah al-Markazīyah; dan sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan.
Dalam aplikasinya, dari sumber-sumber data yang ada mengenai puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, penulis tidak bertujuan untuk menetapkan otentisitas teks orisinal. Argumen dan diskusi penulis di sini berdasarkan pada resensi puisi-puisi yang dianggap otentik dan otoritatif oleh para kritikus. Sedangkan dalam konteks biografi, hikayat, atau riwayat-riwayat (akhbār) yang mendampingi puisi, diasosiasikan dengan puisi-puisi tersebut.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti asumsi yang dikembangkan dalam paradigma sosiologi sastra yang pada dasarnya berangkat dari pemikiran bahwa karya sastra merupakan refleksi masyarakat pada masa karya tersebut ditulis. Oleh karena itu, untuk memenuhi paradigma tersebut, penelitian ini memanfaatkan pula data eksternal yang melatarbelakangi lahirnya puisi-puisi Ṣa‘ālīk yang diteliti, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
67Ṭalāl Ḥarb, ed. Dīwān al-Shanfará, wa-Yalīhi Dīwānā al-Sulayk ibn al-Sulakah, wa-‘Amr ibn Barrāq (Beirut: Dār Ṣādir, 1996). Khusus antologi puisi al-Shanfará, lihat Imīl Badī‘ Ya‘qūb, ed. Dīwān al-Shanfará (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1996).
68Beberapa versi antologi puisi-puisi Ta’abbaṭa Sharran, di antaranya: ‘Alī Dhū al-Faqār Shākir, ed. Dīwān Ta’abbaṭa Sharran wa-Akhbāruh (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1984); Ṭalāl Ḥarb, ed. Dīwān Ta’abbaṭa Sharran (Beirut: Dār Ṣādir, 1996); ‘Abd al-Raḥmān al-Muṣṭāwī, ed. Dīwān Ta’abbaṭa Sharran (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2003).
20 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
Sumber data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ada dalam karya sastra, dalam hal ini adalah fakta-fakta sosial yang terefleksikan dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap fakta-fakta tersebut. Metode ini tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan.69 Dengan metode ini penulis berusaha menjelaskan dan memaknai fakta-fakta sosial seputar pandangan protes kelompok Ṣa‘ālīk pra-Islam. Setelah itu, dilakukan formulasi dan interpretasi sosiologis sehingga diperoleh pemahaman tertentu mengenai masalah yang menjadi fokus kajian.
Dalam interpretasi sosiologis sekurang-kurangnya terdapat tiga model analisis, yaitu: pertama, dengan menganalisis sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat, dan sebaliknya. Teks biasanya dipotong-potong, diklasifikasikan, dan dijelaskan makna sosiologisnya. Kedua, perspektif biografis, yaitu menganalisis pengarang. Perspektif ini akan berhubungan dengan life history seorang pengarang dengan latar belakang sosialnya. Ketiga, perspektif reseptif, yaitu dengan menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra.70 Dari ketiga perspektif tersebut, penelitian ini lebih memprioritaskan kecenderungan pertama, yaitu terbatas pada penafsiran teks secara sosiologis. Meski demikian, untuk kepentingan penelitian ini kecenderungan kedua juga dipertimbangkan. Dengan begitu, pandangan tentang realitas objektif yang melatarbelakangi puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam akan dapat dipahami.
Ringkasnya, kerangka kerja analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: pertama, korpus data yang telah dipilih, diklasifikasikan sesuai dengan objek kajian. Kedua, setelah data diklasifikasikan, selanjutnya dilakukan kajian isi atau fakta-fakta dalam struktur puisi-puisi tersebut. Ketiga, fakta objektif dalam puisi-puisi tersebut dipahami dalam konteks sosio-historisnya. Ini berarti bahwa teks puisi diutamakan sebagai bahan penelaahan, kemudian dipergunakan lebih dalam lagi gejala sosial yang terdapat di luar puisi. Dan terakhir, membuat kesimpulan terkait dengan rumusan masalah, dan/atau jawaban dari permasalahan yang timbul.
69Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 53.
70Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, 80-81.
21Pendahuluan
Struktur Buku
Secara umum buku ini sepenuhnya mengacu pada sistem penulisan kutipan dan bibliografi model Turabian Style Citation, dan pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan ALA-LC Romanization Tables. Pada bab kesatu merupakan pendahuluan sebagai gambaran umum buku ini. Selanjutnya, bab kedua membicarakan tentang diskursus sastra dan realitas sosial dalam kaitannya dengan puisi Arab pra-Islam. Ada dua isu yang dikedepankan dalam pembahasan di bab ini: pertama, membicarakan tentang sastra sebagai konstruksi realitas sosial. Tujuan pembahasan ini dimaksudkan sebagai kerangka teoritis dalam melihat sastra yang tidak dilihat sebagai sesuatu yang otonom dan terlepas dari fungsi sosialnya, melainkan dikonstruksi oleh realitas sosial yang melatarbelakanginya. Kedua, membicarakan tentang diskursus puisi sebagai cerminan sosial, politik, dan budaya Arab pra-Islam. Tujuannya untuk melihat puisi yang tidak hanya dipandang sebagai produksi kebahasaan (al-intāj al-lughawī) yang mementingkan aspek estetis, namun di sisi lain juga memiliki signifikansi historis, yaitu sebagai bahan utama untuk mengkaji perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat Arab pra-Islam.
Penyajian dalam subbab ini juga didasari oleh teori Adonis yang disebut “al-thābit wa-al-mutaḥawwil.” Dari penyajian ini nantinya akan diperoleh pemahaman bahwa puisi Arab pra-Islam memperlihatkan kecenderungan dialektis antara puisi-puisi kabilah sebagai citra dominan puisi Arab pra-Islam yang secara organik terikat dengan kesukuan, dan kecenderungan puisi-puisi penyair independen yang menyimpang dan memberontak terhadap kesukuan. Penyimpangan tersebut khususnya seperti yang ditunjukkan dalam sebagian puisi Imru’ al-Qays dan Ṭarafah ibn al-‘Abd yang muncul dari pengalaman subjektif (al-tajribah al-dhātīyah), maupun puisi-puisi yang muncul dari pengalaman politik ideologis (al-tajribah al-siyāsīyah al-īdiyūlūjīyah), seperti yang tercermin dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk dan kehidupan mereka.
Bab ketiga membincangkan tentang Ṣa‘ālīk dalam diskursus puisi Arab pra-Islam. Uraian dalam bab ini secara khusus bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang kelompok Ṣa‘ālīk dan karakteristik puisi-puisi mereka. Pertama, menguraikan secara deskriptif fenomena Ṣa‘ālīk sebagai potret masyarakat pinggiran pada masa pra-Islam, baik menyangkut terminologi Ṣa‘ālīk itu sendiri, latar belakang kemunculannya, maupun karakteristik kehidupan mereka. Kedua, menjelaskan karakteristik puisi-puisi Ṣa‘ālīk dari struktur bentuk dan muatannya yang memiliki kecenderungan berbeda dari umumnya puisi Arab pra-Islam,
22 Puisi Arab dan Protes Sosial: Kajian atas Puisi Pinggiran Ṣa‘ālīk pra-Islam
seperti penggunaan bait-bait pendek yang lebih dominan ketimbang qaṣīdah yang panjang, karakteristik bahasa dan pemilihan diksi, prosodis, maupun muatan puisi yang bebas dari unsur fanatisme kesukuan dan bertendensi protes sosial.
Bab keempat, pembicaraan difokuskan pada uraian tentang protes sosial terhadap diskriminasi dalam hubungan nasab dan kekerabatan suku sebagai salah satu kecenderungan yang tercermin dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk pra-Islam. Ada dua hal yang dibicarakan dalam bab ini: pertama, deskripsi awal dalam membicarakan tentang nasab dan kekerabatan suku sebagai simbol identitas sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kedua, membicarakan tentang marginalisasi dari kehidupan kabilah sebagai konstruksi protes sosial kelompok Ṣa‘ālīk. Uraian dalam bab ini secara khusus merupakan identifikasi dari tendensi protes sosial sebagaimana yang tercermin dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk dari golongan khula‘ā’ dan aghribat al-‘Arab. Kasus orang-orang khula‘ā’ yang terusir dan identitas kesukuan mereka dicabut, atau seperti pada pengalaman hidup orang-orang aghribat al-‘Arab dan hujanā’ yang termarginalkan karena perbedaan rasial dan kualitas nasab, kondisi itulah kemudian yang melatarbelakangi memberontaknya mereka dan keluar dari kehidupan kabilah.
Bab kelima membincangkan tentang protes terhadap kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai masalah utama bagi kehidupan kelompok Ṣa‘ālīk pada umumnya. Ini ditunjukkan tidak hanya dalam puisi-puisi Ṣa‘ālīk dari golongan masyarakat miskin, tetapi juga puisi-puisi golongan khula‘ā’ dan aghribat al-‘Arab. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika perampokan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menuntut hak-hak sosial mereka terhadap orang-orang kaya. Perampokan yang menjadi karakteristik kehidupan kelompok Ṣa‘ālīk ini tidak semata-mata dipandang sebagai kejahatan, tetapi sebagai sebuah bentuk protes sosial.
Bab keenam ditutup dengan kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan, serta rekomendasi sebagai implikasi dari capaian penelitian ini. Dari kesimpulan dibicarakan hasil temuan utama, sedangkan rekomendasi menjelaskan keterbatasan dan kekurangan penelitian ini sehingga memberi gambaran dari sisi mana yang perlu dilanjutkan dengan penelitian lebih lanjut, baik oleh penulis sendiri atau oleh peneliti lainnya.