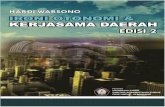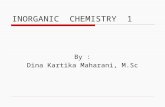Politik Lokal dan Otonomi: Sebuah Perbincangan Singkat
Transcript of Politik Lokal dan Otonomi: Sebuah Perbincangan Singkat
1.
2.
3.
DAFTAR ISI
Masa Depan Otonomi Khusus Papua
Djohermansyah Djohan
Esensi dan Peran Pamong PrajaAries Djaenuri
Penguatan Satuan Polisi Pamong PrajaDalam Penyeleng garaan Pemerintahan DaerahHyronimus Rowa
Menimbang Kembali Pemilihan Kepala DaerahTak Langsung, Respon Terhadap MekanismeDemokrasi Langsung Di IndonesiaMuhadam Labolo
Politik Lokal dan Otonomi, Sebuah Perbincangan SingkatLeo Agustino
Implementasi Kebij akan Pendelegasian WewenangDari Bupati Kepada Camat Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah dan KependudukanAndi Pitono
Realitas dan Upaya Reformasi BirokrasiRahman Hadi
Rencana Pembentukan Kota Maumere, Dintinjau dariAspek Politik dan AdministratifHelianus Rudianto
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonom Baru(Studi Kasus Pada Kabupaten Pemekaran di Indonesia)Bambang Supriyadi, Arya Hadi Dharmatvan, Setia Hadi dan Akhmad Fauzi
l-5
6-12
t3-21
22-30
3t-42
43-49
69-76
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Politik Lokal Dan OtonomioSebuah Perbincangan Singkat
LEO AGUSTINO
Dosen di Program Sains Politik, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Shategi (PPSPS)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia(uKM), Bangi, Malaysia E-mail: [email protected]
Abstrak: Artikel ini mendiskusikan dan menganalisis mengenai politik lokal secarakonseptual dan aplikasinya di beberapa negara berkembang. Hal ini menjadi pentingkarena pelajaran yang dapat dipetik darinya berguna bagi penyempurnaan sistemotonomi di Indonesia. Beberapa hal yang digariskan dalam artikel ini ialah mengenaimanfaat dan kekurangan yang dapat ditimbulkan oleh otonomi, makna dasar otonomidan perbincangan yang menyertainya serta implementasi otonomi di beberapa negara.Pelajaran apa yang bisa di petik dari ketiga perkara ini? Satu yang pasti, otonomitidak selalu mengantar daerah ke arah positif, terkadang justru ia membawa ekonomi-politik daerah ke arah yang negatif. Ini karena otonomi tidak dijalankan secara efeltifsehingga menguncupkan makna dan tujuan asas otonomi daerah itu sendiri danpengalaman beberapa negara menunjukkan hal ini semua. Artikel ini memfokuskanpada perbincangan konseptual mengenai politik lokal dan otonomi serta aplikasinya dibeberapa negara. Ini dilatari oleh satu hal yaitu terkait dengan perubahan sosiopolitiksejak tahun 1970-an, dari rejim otokratik yang sentralistik ke demokrasi politik yangterdesentralisasi.
Keyword : Politik Lokal, Otonomi, Implementasi
Demokrasi dirasa banyak pihak memberikanierempatan pada pelembagaa\ kewenangan yanghb'ih mandiri dan luas kepada pemerintahan daerahhrsusnya), yang berbeda dengan rejim otokratik,ffi mana segala hal ditentukan oleh pemerintah pusat
1 g acap kali tidak rasional dengan kebutuhanmasyarakat di level lokal. Persoalannya, mengapahita mesti mendukung demokrasi atau desentralisasiErutama di aras lokal? Apa keuntungan yang dapat,diperoleh darinya? Dan, bagaimana desentralisasi.ilTnt mendorong dan memperkuat demokrasi di leveluasional?
Untuk membahasnya, artikel ini dibagikanke dalam empat bagian. Pertama, menganalisismanfaat pembangunan demolaasi politik bagidesentralisasi politik. Kedua, menguraikan perdebatan$mgkat mengenai politik lokal yang terkait denganmonomi. Ketiga, (terkait dengan hal sebelumnya)membincangkan kerangka konseptual mengenai,xonomi daerah yang berkait erat dengan desentralisasi
folitik. Dan keempat, sebagai bahasan terakhir,nenilai beberapa aplikasi otonomi atau desentralisasidi beberapa negara. Untuk menghasilkan analisis yang
kaya perdebatan dan perbincangan, pengumpulan
data dilakukan dengan cara studi literatur. Sumberliteratur dipilih secara selektif agar dapat menjelaskanfokus analisis artikel ini, dengan berlandaskansumber literatur yang otoritatif dan tepat, makahasilnya memberikan'warna' terhadap analisis yang
berkualitas. Dengan merujuk pada kerangka sepertiini, maka artikel ini mendapat pondasi yang kukuhuntuk memulai perbincangannya pada bagian-bagianseterusnya.
I\'I{NIIAAT DAN KEKURANGAN OTONOMIDAERAH
Merujuk pertanyaan di atas, setidaknya ada
beberapa argumen di mana otonomi atau desentralisasibermanfaat bagi pembangunan demokrasi politik di aras
lokal. Pertama, menumbuhkembangkan akuntabilitasdan responsivitas. Desentralisasi mendorongpemerintah daerah untuk lebih bertanggungjawab dan
responsif atas keperluan warganya. Dalam konteksdemokrasi lokal, akuntabilitas perlu diartikan sebagai
kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi
31
32 Politik Lokal Dan Otonomi, Sebuah Perbincangan Singkat
kebutuhan untuk pemerataan ekonomi dan politik.
Sebab, sejalan dengan istilah desentralisasi itu sendiri,
logika penyebaran wewenang dan kekuasaan menjadi
landasan dalam pemerintahan. Sedangkan responsivitas
bukan hanya dimaknai sebagai kemampuan pemerintah
lokal untuk menanggapi kebutuhan dan keperluan
warga setempat, tetapi lebih jauh dari itu adalah
adanya kemauan untuk mendishibudikan pelayanan
publik tidak pernah terlaksana secara optimal selama
sistem sentralisasi berkuasa.
Kedua, mengembangakan warga sebagai
masyarakat sipil dalam arti yang sejati. Desentralisasi
di level lokal sedikit banyaknya turut mendorong kadar
partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan
daerah, selain juga menanamkan kemampuan
kewargaan sesama mereka. Hal ini dimungkinkan
oleh satu keyakinan bahwa masyarakat setempat lebih
mengetahui masalah yang mereka rasakan berbanding
pemerintah pusat. Untuk menyelesaikan masalah,
masyarakat akan saling berinteraksi satu sama lainmengembangkan komitmen bersama yang pada
akhirnya menumbuhkan sifat saling percaya, toleransi,
kerjasama dan solidaritas. Dari sifat inilah kemudian
keterlibatan masyarakat dalam penyelanggaraan
pelayanan publik di tingkat lokal mencetuskan
keterampilan masyarakatnya sehingga menjadi
modal sosial yang bermanfaat bagi pelembagaan
desentralisasi. Ujung dari itu semul adalah tumbuh
dan matangnya organisasi dan jaringan masyarakat
sipil di daerah. Ini semua pada gilirannya melindungi
sistem demokrasi dari alienasi masyarakatnya terhadap
kehidupan politik di aras lokal.Ketiga, melembagakan mekanisme checks and
b al ances (pengawasan dan penyeimbangan). Dengan
berkembangnya antitesis sentralisasi dalam bentuk
otonomi daerah, pemerintah daerah diberi peluang
untuk bertindak sebagai pengawal dan pengawas
struktural bagi pemerintah pusat dari tindakan-tindakan yang mengarah pada tumbuhnya rejimotokratik. Ini karena kekuasaan pemerintah daerah
dapat hadir secara lugas dalam mekanisme checks
and balances atas penerapan kekuasaan pusat;
misalnya dengan membuat kebijakan-kebijakanyang berorientasi publik manakala pemerintah pusat
berkebalikan dengannya, sehingga warga terlindungi
oleh implementasi peraturan tersebut.
Keempat, memantapkan legitimasi politikpemimpin-pemimpin daerah. Karenapemerintah daerah
berangkat dari ketulusan warga untuk mengangkat
pimpinan formal lokal melalui mekanisme pemilihan
secara langsung, maka secara otomatis keadaan initurut mencetuskan legitimasi politik yang lebh tinggibagi pimpinan daerah. Atau jika tidak pemilihan itutidak dilakukan secara langsung, paling tidak, logika
desentralisasi dapat memberikan kesempatan kepada
kelompok minoritas dan pengakuan sosiopolitik
kepada mereka untuk aktif dalam kancah politik lokalmelalui kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
Selain itu, keempat hal di atas ada beberapa
lagi kategori yang dapat dituliskan di sini mengenai
manfaat desentralisasi seperti memberi peluang
kepada pemerintah daerah untuk berinovasi tanpa
perlu menjustifikasi kepada daerah lain, menciptakan
kestabilan politik dengan memberi peluang kepada
masyarakat dalam skop teritori yang tidak terlalu
luas, meningkatkan pembangunan secara berprioritas
sehingga menekan biaya dan lainnya. Namun paling
tidak, empat hal di ataslah yang sering kali menjadi
alasan mengapa desentralisasi menjadi penting jikadibanding dengan logika politik sentralisasi.
Walaupun demikian, perlu diingat bahwa
dampak desentralisasi tidak semuanya bersifat positif(memberikan manfaat) terhadap demokrasi di level
subnasional. Kendati sistem sentralisasi sudah tidakada, tetapi perlu diingat bahwa warisannya dalam
bentuk intoleransi dan diskriminasi antara kelompokpendatang dan pribumi sangat mungkin (semakin)
menguat, ini yang pertama. Logika 'keputradaerahan'
atau apapun namanya sering digunakan untuk
menjustifikasi perihal sebegini. Dengan menggunakan
label 'putra (asli) daerah', terutama untuk kasus
di Indonesia, setiap orang kini dapat menciptakan
peluangnya masing-masing ke arah sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang berimplikasi pada pemasukan
ekonomi bagi mereka. Kedua, terjadinya pemborosan
keuangan atau anggaran daerah. Pemindahan
kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada
pemerintah yang lebih rendah tingkatannya secara
otomatis mendorong terciptanya banyak posisi baru
dalam birokrasi daerah. Meski hal ini menguntungkan
dari aspek akses dan pelayanan yang diterima warga,
tetapi realitas ini juga mencetuskan jumlah biaya yang
turut membengkak. Satu yang pasti ialah kadar belanja
daerah menjadi (amat) besar. Tanggungan sebegini
bukan hanya diletakkan pada pundak pemerintah
daerah semata, tetapi juga dikalungkan pada
pemerintah pusat dan juga rakyat selaku pembayar
pajak kepada pemerintah. Akibatnya anggaran belanja
nasional melonjak dan dapat mendatangkan utang-
utang baru. Ketiga, kekhilafan dalam mengidentifikasi
Gcara saksama otoritas pekerjaan pusat ataupun{rErah dapat menghadirkan duplikasi pekerjaan, ataudaliknya kegagalan kerja karena masing-masingErganggap pihak lain telah mengerjakan pekerjaantrsebut. Duplikasi ini (mungkin) dirasa tidakkmasalah walaupun dana yang keluar besar, sebab
lmrerintah telah melalcukan pekerjaan utamanya yakniclaksanan pembangunan daerah. Yang bermasalahgbila pembangunan itu tidak dilakukan karena*riap pemerintah mengharapkan dari yang lain,nmlm dana tetap habis keluar. Hal ini terkait seperti&rgan perkara kedua di atas yang memboroskanha baik di aras pusat maupun daerah. Keempat,mcul dan menguatnya kantong-kantong kekuasaanmiter baru di tangan-tangan kelompok tertentu*bd s trongman). Kelompok ini boleh j adi kelompok-ldompok yang benar-benar baru atau juga kelompokha yang telah berubah owarna' dengan cara menata&i sedemikian rupa sehingga kehadirannya di masahh 1.ang dekat dengan rejim otokratik tidak dilffitikC mesa sekarang ini. Siapa mereka? Menurut Vedif flarliz (2003:124) (mereka) adalah: "... ambitiousplitrcal fixers and entrepreneurs, wily and still-pfuory state bureaucrats, and aspiring and newlywtdant business groups, aswell as wide range ofplitical gangsters, thugs and civil militia."
Mengikut pada dua pandangan di atas, terdapathfrat' dan 'kurafat' otonomi daerah, maka uraianr&el ini menumpukan analisisnya pada perkara yang&hrkan terakhir. Mengapa? Setidaknya ada tigarlmen yang melatarbelakangi tulisan ini. Pertama,mbahas'manfaat' desentralisasi sangat mungkinmrbrrat kita terbuai bahwa segala berjalan sesuai*q--.io. Padahal bisa jadi apa yang sedang terjadi:rr hi adalah perjalanan yang mengarah pada tanggap benar dalam bangunan yang salah. Maknanya,
ffirrfan yang terjadi di sana-sini, jangan-janganhqdah upaya restrukturisasi atau reformat sifat dan
1deku otoritarianisme rejim sebelumnya ke dalamh=s*n baru oleh aktor-aktor tertentu. Kedua, denganhFerhatikan peristiwa, mengurai fakta dan menelitih. bisa sangat mungkin terbit suatu pola, arah
ry kebiasaan yang sangat pekat dengan aktivitasrH aktor-aktor lokal. Sesuatu hal yang tidak mustahiltr pola arah ataupun kebiasaan yang terekam dalamftr{ ini menjadi alternatif atau modal jalan keluarlhi perbaikan desentralisasi di masa depan. Ketiga,rQrakat kita terlalu gandrung dengan penemuann barang baru yang mengarah diskontinuitas.'[fibfberlanjutan
pada satu hal mungkin baik, tetapi
Jurnal PamongPraja, Vol. I Thhun 2011 : 31-42 33
dalam konteks desentralisasi ia berarti kesalahan fatal.Sebagai contoh, partai politik secara teoritik diyakinisebagai institusi demokrasi yang berperan melakukanagregasi dan artikulasi, tetapi pada kenyataannya padamasa lalu dan sekarang mereka hanya bisa mengobraljanji, memobilisasi massa dan tidak mendidikkonstifuen. Dengan format baru pemilihan umum didaerah, masyarakat kembali tidak mampu menjadibenteng pengawas dan penyeimbang kekuatan partaipolitik sehingga warga kembali terjerembab pada
money politics, barter politik, negosiasi kepentingandan lainnya. Oleh karena itulah, 'sisi gelap' kerapmuncul daripada'sisi terang'nya.
Berdasarkan pada beberapa alasan di atas
terutama tiga bagian terakhir, artikel ini mengajakpembaca untuk saling mengingatkan akan adanyahal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam lanskappolitik lokal maupun pelaksanaan otonomi daerah.Untuk menambah matangnya pemahaman mengenaisisi gelap otonomi daerah, maka bagian selanjutnyamendiskusikan dulu mengenai kerangka konseptualmengenai politik lokal.
POLITIK LOKAL : SATU PERDEBATAN KONSEPTUAL
Pada dasarnya membicarakan politik lokal danotonomi daerah adalah membicarakan hubunganpemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena,membicarakan dua entitas dalam level yang berbedaini merupakan inti untuk mengukur praktik otonomi,di mana hubungan tersebut juga dapat mengungkapkankedudukan dan autoritas masing-masing skoppemerintahan. Bagi para sarjana beraliran Marxis,membahas hubungan pusat-daerah tidaklah relevankarena pemerintah pusat dan pemerintah daerahdianggap sebagai satu kesatuan aparatus negara.Pemerintah daerah hanya merupakan institusi yangmenghadirkan negara di daerah. Dalam arti katalain, pemerintah daerah merupakan instrumen bagipemerintah pusat, ini satu hal.
Hal lain, adalah politik lokal itu sendiri. Politiklokal dalam artikel ini diartikan sebagai interaksiantar aktor dalam satu wilayah sehingga mencetuskandinamika politik di dalamnya. Namun sebelum jauhberdialektika mengenai interaksi tersebut, terlebihdahulu perlu dipahami apa itu pemerintah? Daripadanya nanti, dapat dibedakan antara'pemerintahpusat' dan 'pemerintah daerah,' yang berkorelasidengan 'politik pusat' dan 'politik lokal.' Perkara iniperlu dimunculkan agar tidak menimbulkan perbedaan
34 Politik Lokal Dan Otonomi, Sebuah Perbincangan Singkat
pemahaman. Oleh karena itu, hal yang mesti dibahas
sekarang adalah apa itu negara danapa itu pemerintah?
Dan di mana letak perbedaan keduanya sehingga
analisis artikel ini bisa memastikan bahwa yang
dibahas adalah mengenai politik lokal dan otonomidaerah yang berhubungan dengan interaksi pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah, bukan hubungan
negara pusat dengan negara lokal?Pada umumnya sarjana ilmu sosial sepakat
bahwa negara dan pemerintah adalah dua entitas yang
berbeda. Walaupun demikian, keduanya tidak dapat
dipisahkan. Berkaitan dengan hubungan negara dan
pemerintah ini, Maclver (1964) menyatakan bahwa
negara merupakan sistem organisasi yang memilikikedaulatan tertinggi dan mampu menciptakan hukumyang bersifat mengikat dan memaksa sehingga dapat
mengatur serta mengendalikan interaksi masyarakat
dalam wilayahnya. Sedangkan pemerintah adalah
organisasi yang melaksanakan peranan negara ini,urainya The state is an association which, actingthrough law os promulgated by a govbrnment endowed
to this end with coercive power maintains within acommunity teruitorially demarcated the universolexternal conditions of social order (MacIver 1964:22).
Dalam perspektif yang tidak berbeda, Kousoulass(197 5) menyetujui uraian Maclver. Beliau menegaskan
bahwa pemerintah adalah badan yang berkuasa untukmembuat aturan yang mengikat, mengimplementasikan
kebijakan, menyelesaikan konflik dalam masyarakat
dan menggunakan kekuasaan koersif apabila
otoritasnya digugat (Kousoulass 1975:6). Dalampraktik kekuasaan pusat, pemerintah dipandang sebagai
badan yang memiliki kaitan dengan manajemen publikdalam rangka menjaga kepentingan negara yang lebihbesar, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan
memperkuatkan legitimasi negara. Dalam arti kata
lain, pemerintah merupakan bagian dari usaha untukmemaksimumkan kekuatan negara.
Kajian klasik Miliband dalam bukunya The
state in capitalist society (1969) sejalan dengan
argumen kedua sarjana di atas. Menurutnya, negara
dan pemerintah adalah dua entitas yang berbeda dan
tidak bisa dipisahkan. Lebih lanjut menurut Miliband(1969:50): "It is not very surprising that government
and the state should often appear as synonymous. ForI Argumen ini sejalan dengan kajian klasik Poulantzas (1913) yangmengatakan bahwa otonomi negara merupakan bentuk kemampuan negara untuk
merumuskan kepentingannya secara bebas, terutamanya dari tekanan klas dominan atau klas kapitalis. Walaupun terkadang negara perlu mengakomo-
dasi kepentingan satu kelompok, tetapi karena otonomi negara inilah negara dapat menjaga dan mencipta keseimbangan kepentingan semua kelompok
dalam masyarakat yang diwamai oleh beraneka persaingan. Dalam konteks ini negara memiliki kecendenrngan 'bebas dari kendali klas dominan,'teru-tamanya dalam melayani kepentingan mereka. Inilah yang dimaksudkan sebagai otonomi negara Elaborasi Poulantzas (1973) sejalan dengan analisis
Offe & Ronge (1975) yang bertajuk 'Theses on the theory of the state.' Menurut mereka, negra memiliki pandangan yang bebas unhrk rnemformulasi
kebijakan bagi menciptakan stabilitas dalam sistem kapitalis, dan bukan (untuk) melayani kepentingan klas tefientu.
it is the governmentwhich spealcs on the stateb behalf."Tambahnya lagi, negan adalah pemilik monopolilegitimasi yang dapat menggunakan kekuatan fisikuntuk memaksa rakyat taat atas pelbagai kebijakanyang telah diformulasi dalam teritorinya. Penggunaan
kekuatan tersebut menurutnya hanya dapat dilakukanoleh pemerintah; karena pemerintahlah yang dapat
mewujudkan kekuatan tersebut.
Elaborasi Miliband (1969) di atas boleh
dikata tidak setarikan nafas dengan kajian Skocpol
(1979\ yang menyatakan bahwa tidak selamanya
tujuan negara sejalan dengan langkah yang diambiloleh pemerintah. Argumen ini dilandaskan pada
pemahaman akan termanipulasinya pemerintah
oleh (berbagai) kepentingan elit berkuasa sehingga
membuatnya tidak dapat mencapai'kebaikan bersama.'
Pandangan Skocpol ini dapat dirunut akarnyapada argumen Stepan (1978) yang melihat negara
sebagai organisasi yang otonom dan dominan dalam
menjalankan kekuasaannya. Menurut Stepan, negara
adalah organic-statism yang memiliki fungsi yang
terpusat terutamanya dalam menciptakan kestabilan
dan ketertiban. Kembali pada Skocpol, menurutnya,
negara itu bersifat otonom karena ia bebas menentukan
caranya sendiri dalam menjalankan kekuasaan, kedap
dari intervensi klas kapitalis, sehingga ketertiban dan
kestabilan politik dalam wilayahnya dapat diwujudkan(Skocpol 1979:11).1 Lebih lanjut beliau menyatakan,
otonomi negara adalah sifat asli negara yang wujudbersama dengan kemunculan negara. Ia bukan
diciptakan dan dimanipulasi oleh klas dominan sepertiyang dituduhkan oleh pengikut Marxis. Karena itu,dalam analisis Skocpol (1985:13) dinyatakan bahwa
otonomi negara dapat dilihat dari adanya dominasiyang dilakukan oleh agensi rregara, yaitu birokrasisebagai pelaksana fungsi negara yang bersifatsentralistik.
Pandangan Skocpol (1979;1985) tentang negara
ditentang oleh Shively (1999) yang menyatakan
bahwa entitas negara dan pemerintah adalah
berbeda. Perbedaan paradigma ini dilandaskan pada
pendefinisian yang cair atas kedua entitas tersebut.
Menurut Shively (1999:49) pemerintah sebagai
adalah: "... a group of people within the state who
have the ultimate authority to act on behalf of the
ffie." Pendapat Shively ini menunjukkan bahwa
Fcmerintah adalah sekumpulan orang yang memilikimitas paling tinggi dalam negara untuk bertindakres nama negara. Takrifan ini menjustifikasirctaligus menegaskan bahwa hanya pemerintahlah
1ug dapat bertindak melaksanakan kekuasaan atas
ofina negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara.
lLebih jauh Shively (1999) menerangkan bahwa negara
mupakan organisasi pemilik kekuasaan tertinggi danpemilik legitimasi sah, sedangkan pemerintah hanyapelaksana kekuasaan tersebut.
Studi terkini yang dilakukan oleh Migdal &Schlichte (2005) berusaha untuk menengahi perbedaan
iua pandang di atas. Menurut mereka, otonomiocgara yang ditelurkan oleh aliran pemikiran neo-llanris bersurnber dari: "... ability of state to transcendrie power of these organizations and their interest ande-frame them in terms of the stateb territory, whichrculated space" (Migdal & Schlichte 2005:4). Karenamlleh, otonomi neigara ini haruslah didukung olehnmber daya yang memadai, terutamanya birokrasirutuk melaksanakan fungsi negara. Melalui birokrasimL tembah mereka lagi, "... the state exhibits its ownvzferences and has the strength to act the preferences.sd to change the behavior of others" (Migdal &i-hlichte 2005:5). Berkaitan dengan ketersediaanc.nmber daya inilah, maka politik negara dilaksanakan:nieh pemerintah. Hal ini menjustifikasi bahwa negarar"ielah entitas yang lebih besar dan lebih tinggi.aurpada pemerintah.
Setelah secara sepintas lalu mengelaborasirefinisi negara dan pemerintah, maka tepatlah saatnyamnrk membicarakan pengertian 'politik pusat' dan
rulitik lokal' yang dilandaskan pada pengertian-Rosertian di atas. Istilah 'politik pusat'dan 'politikr'rriral'menurut Wolman (1990) adalah kurang tepat..m karena apa yang dinamakan 'politik lokal' adalahtaresentasi dari 'politik pusat.' Atau dalam bahasaffixn p€ran pemerintah pusat dalam memformulasir.ei"Uakan politik tujuannya amat luas, termasukmciiputi hal ihwal yang berkait dengan kepolitikanm level lokal (Wolman 1990:29). Sejalan denganmr- Johnson (1997:138) mengidentifikasi dua bentukman pemerintah pusat dalam 'politik lokal'dalam hal
Jurnal PamongPraja, Vol. I Tahun 2011 : 31-42 35
ini berkait erat dengan pembangunan daerah. Pertama,pemerintah pusat membuat keputusan pembangunan
secara langsung melalui kementerian di tingkat pusatdan mengawal projek tersebut untuk kepentingan rakyatdi daerah. Kedua, pemerintah pusat mengembangkanmodel pengatwan sebagai pemegang kekuasaan negara
terhadap isu-isu yang berkembang di aras lokal. Untukmemastikan peranan tersebut berjalan, kajian Wolmandan Johnson dikukuhkan oleh studi Mann (2008) yang
menjelaskan perbedaan jenis kekuasaan pemerintah
dalam dua matra, yaitu: (i) kekuasaan infrastruktur dan(ii) kekuasaan despotik. Menurut Mann (2008:356,passim), kekuasaan infrastruktur adalah kekuasaanatau kemampuan negara untuk masuk dalam aktivitaskelompok masyarakat yang bertujuan mengawasidan mengendalikan pelbagai aktivitas dan kegiatanmereka. Sedangkan kekuasaan despotik adalah bentukkehendak elit negara untuk memaksakan keinginannyadalam masyarakat demi kepentihgan tertentu.
Dalam konteks unitary state seperti di Indonesia,upaya untuk mencapai tujuan negara sangat tergantungkepada sejauhmana pemerintahnya menyerahkansebagian kekuasaan itu kepada daerah. Jika kekuasaan
itu terlalu disentralisasi, maka akan membuatnyamenjadi despotik. Agar hal ini tidak terjadi,pemerintah pusat harus mempunyai strategi dalammengaplikasikannya, misalnya melalui penerapanotonomi daerah. Tujuannya adalah menghadirkankekuasaan infrastruktur di aras lokal.2 Tetapi, merujukpada lanskap politik Orde Baru Soeharto yangantipolitik, kekuasaan despotik lebih ditonjolkansehingga pencederaan demokrasi berlaku, pelecahanhak asasi manusia terjadi, pemarginalan masyarakatwujud, yang pada intinya rejim Orde Baru despotikmerujuk pada kerangka Mann (2008).
Untungnya, pada tahun 1998 terjadi transformasipolitik yang tercetus dari adanya tuntutan dan desakanmasyarakat untuk turut terlibat langsung dalam proses
politik dan pemerintahan di aras lokal. Dalam Jiwazaman' yang tengah bertransformasi, pemerintahIndonesia merespons tuntutan tersebut denganmenerbitkan undang-undang pemerintahan daerahyang menjamin partisipasi dan penyertaan publikdalam pelbagai proses politik dan pemerintahan.
l:ss dalam artikel ini berargumen bahwa dominasi yang dilalcukan negara dalam konteks otonomi bukanlah bagian dari hegemoni negara, tetapiicr€liktya bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara itu sendiri. Otonomi daerah atau desentralisasi diimplementasikan dengan tujuan unnrkumJorong agar rakyat setia kepada negara, bukannya kepada pemerintah yang berkuasa seperti yang tedadi dalam konteks hegemoni negara. Mengikut-t-osci(1971:57),hegemonimerupakan:"...thesupremacyofasocialgroupmanifestitselfintwoways,as'dorninotion'andasintellectualandmoralea*rship." Dalam praktiknya, kekuasaan hegemoni ini cenderung diamalkan dengan cara consenti kendati demikian, pada umumnya ia dilalarkanr€'n cana paksaan, manipulasi, dan bahkan tindakan represif (coercion). Singkatnya, hegemoni merujuk kepada proses di mana negara berusaham:apertahankan kekuasaannya dan kendalinya terhadap masyarakat melalui paksaan dan dominasi. Ililah yang te{adi di Indonesia pada masa Orde3'r-r Soeharto dalam hal ini mengutamakan hegemoni daripada otonomi dalani pemerintahannya dengan tujuan mengekalkan stdtus quo.
36 Politik Lokal Dan Otonomi, Sebuah Perbincangan Singkat
Implikasi dari penyerahaan dan penyertaan ini ternyatamendatangkan masalah seperti muncul semangat
kedaerahan dan konflik efrik yang sampai saat inimasih mengancam stabilitas politik di Indonesia(Holtzappel & Ramstedt 2010; Leo Agustino2011). Hal ini dikarenakan adanya realignment ataupenyesuaian baru atas interaksi berbagai aktor di diaras lokal. Berlandaskan realignments inilah, artikelini memposisikan 'politik lokal' bersandar. Selainitu, dengan teras seperti ini pulalah perbincanganselanjutnya menempatkan diri untuk mengurai 'sisigelap'politik lokal dan otonomi di beberapa negarapaling tidak sebagai pelajaran bagi otonomi diIndonesia. Namun sebelum hal ini diutarakan, terlebihdahulu dianalisis kerangka konsep otonomi (secara
ringkas) di bagian seterusnya.
URAIAN SINGKAT MENGENAI KONSEP OTONOMI
Setelah membahas secara singkat mengenaipolitik lokal yang diawali dengan perdebatan idetentang negara dan pemerintah yang kemudiandiakhiri dengan perbedaan level pemerintah pusatdan daerah sehingga menghadirkan politik pusat danpolitik lokal, maka bagian ini melanjutkan diskusinyadengan menguraikan secilra ringkas mengenai konsep
perintah. Merujuk pada dua perkataan tersebut, makasecara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai'peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan)tersendiri', atau menurut Leo Agustino (2011:11)berarti 'memerintah sendiri.' Kajian klasik milikHoggart (1981) menyatakan otonomi harus dipahamisebagai sebuah interaksi antara pemerintah yangberada lebih tinggi kedudukannya dengan pemerintahyang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut,otonomi mesti dipahami sebagai independence oflocalities yang kedap dari adanya campur tanganpemerintah di aras atas. Senalar dengan uraian Hoggart,Samoff (1990:26) pula menyatakan otonomi sebagaitransferred power and authoriry over decision makingto local units are the core of autonomy. Berbagaiargumen di depan tidak disanggah oleh Rosenbloom(1993) yang menjelaskan otonomi sebagai wujudpenyerahan suatu kuasa kepada pemerintah yanglebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayahsecara bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintahpusat. Bahkan Kirby (dalam Leo Agustino 2011:ll)memberi definisi otonomi daerah seperti berikut The
freedom to sctwithout being controlled directly orindirectly by others. Local autonomy is perceived as
the capacity of local units to oct based on thetr owninterestwithout considering the reaction of upper levelagencies. Autonomous local units are self-sfficientand have the obility to determined local needs, goals,and resourcers allocations. r
Jikamerujukpadabeberapa definisi di atas, otonomidaerah dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah
daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan,kebijakan dan membuat keputusan pembangunan didaerah berdasarkan keperluan masyarakat tempatan.Tidak jauh berbeda, Escobar-Lemmon (2004:20)menyatakan otonomi sebagai pemindahan otoritas,fungsi dan tanggung jawab untuk memformulasikebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah. Atas dasar konsep tersebut, makaada bidang kuasa pemerintah daerah untuk membuatprogram dan peraturan sesuai keadaan wilayahnya.Karena itu, dalam artikata lain, otonomi merupakanantitesis dari sentralisasi kekusaan politik pemerintahpusat. Oleh karena itu, otonomi seringkali dipadankandengan desentralisasi. Karena keduanya menyiratkanpelembagaan kekuasaan dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah, maka beberapa sarjana sepertiSmith (1985:18) menyatakan desentralisasi sebagai
may be clearly distinguished from the dispersal ofheadquareters'branchesfrom the capital city, as whenpart of a national ministry is moved to provincial cityto provided employment there.
Inti dari uraian di atas adalah pendelegasianwewenang dari pemerintah yang lebih tinggi levelnyakepada pemerintahan yang lebih rendah bidangkuasanya. Menguntit uraian Smith, Bird & Wallich(1993) membuat argumentasi untuk merealisasikanotonomi melalui desentralisasi. Yang manamenurutnya, desenfralisasi mesti dibagi ke dalamtiga matra yakni dekonstrasi, delegasi dan devolusi.Tulisnya Deconcentration refers to dispersionof responsibilities within the central governmentstructure ftom the center to regional branch fficers,and difersfrom delegation in which local governmentmay execate certain functions on behalf of thecentral governt]tstl (otd accountable to it for theirperformare\ od bolution in which.full decisionmaking ad itryIatotaion anthority is transferred tolocal govwtuut,which is accountable only to its owncortsfiMios-
']tFTIIIrFHEIt:kh
f.-&
otonomi. Otonomi secara etimologi berasal dari kata ... involves the delegation of power to lower levelsauto dannomos yang berarti sendiri dan peraturan atau in a tenitorial hierarchy;.......... Decentralization
EbEEthrq:flEdH!qhCl:hh',b
f"
Ih
ttiL
Dqsi
hCA
atamrhmmdaItigal
Eftbnof
bneit_v
firnFyamglichkan
llnailam
hrsi.
surn
I
I
l
tentrers,
nent' the
theirisioned totown
Seabright (1996) mengambil sudut lain dalammemahami otonomi atau desentralisasi khususnyadalam konteks keterkaitan antara otonomi daerahdengan pengembangan otoritas pemerintah daerah.Ini menjadi penting karena hanya otoritas pemerintahdaerah yang dapat menjamin dilaksanakannya otonomidengan baik, di mana pemerintah daerah dapatmenentukan keputusan-keputusan yang bersifat lokal.Sejalan dengan pendapat tersebut, Lambright (2003 :3 1)
menegaskan semula bahwa kewajiban pemerintahpusat hanyalah to inspect, monitori and wherenecessary offer technical advice, support supervision,and training within their respective sectors;tidak lebih.Atas dasar pengertian ini, keputusan dan tindakanpimpinan daerah diarahkan pada pilihan-pilihan yangberkembang di daerah berdasarkan keperluan bagimengembangkan kemampuan politik dan ekonomimasyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwaotonomi daerah adalah instrumen bagi mematangkandemokrasi politik, ekonomi, dan partisipasi rakyat dilevel lokal.
Jika melihat srudi Seabright (1996) danLambright (2003), maka kajian klasik Rondinelli &Chemma (1983) mendapatkan tempatnya. Karenamenurut mereka, otonomi akan menyediakan ruangbagi 'kebaikan bersama' apabila pemerintahan daerahmemiliki otoritasnya sendiri dalam otonomi daerah.Beberapa kebaikan otonomi menurut Rondinelli& Chemma (1983:14) adalah: (i) mengatasi\.eterbatasan dana dan masa serta sesuai denganirepentingan masayarakat setempat, (ii) mengurangisit-at prosedural dan berbelit-belit dari birokrasi, (iii)nerumuskan kebijakan-kebijakan publik dengan lebih:ealistik, (iv) memberi layanan yang lebih baik dantpat kepada daerah-daerah terpencil, (v) melibatkan-nasyarakat luas dalam pemerintahan dan lainnya.Selaras dengan Rondinelli & Chemma, Leo Agustinol0ll:13) menyatakan bahwa 'kebaikan bersama'
"ken lebih efektif dan efisien apabila didukung olehkemampuan daerah dalam aspekteknis, fiskal, institusi,Sm implementasi. Kemampuan teknis, lanjutnya,rs*"leh kemahiran pemerintah daerah merurnuskanh-msep untuk kemudian drgunakan dalam mencapaiptmbangunan daerah, berdasarkan keperluanrakyatnya. Kedua, kemampuan fiskal, adalahadanya kecukupan sumber dana dan daerah bebasdalam mencari sumber-sumber pendapatan dalammenjalankan fungsi pemerintah. Ketiga, kemampuaninstitusi, dimengerti sebagai adanya kemudahaninteraksi semasa organisasi pemerintah daerah guna
Jurnal Pamong Praja, VoL I Tahun 2011 : 31-42 37
merealisasikan perancangan dan pembangunandaerah. Keempat, kemampuan implementasi, yaitukesanggupan pemerintah daerah untuk mengatasiimplikasi dari setiap kebijakan yang diterapkannya.
Wafiupun pelbagai kebaikan dapat hadir melaluikebijakan otonomi, namun beberapa implikasi negatifselalu ada. Misalnya, penyalahgunaan kekuasaan
oleh elit lokal (sehingga menghadirkan para localstrongmen atau greatmen), berkembangnya politikpatron-clienl di tingkat daerah, menyebarnya kasus
KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di level lokal,perampokan kekayaan daerah baik berupa :uang cash
maupun dalam bentuk sumber daya alam dan lainnya.B eberapa temuan tersebut dibuktikan oleh kaj ian B land(1997) di Chile dan Venezuela, Harriss-White (1999)di India, Escobar-Lemmon (2000) di Colombia danCosata Rica, Clarke (200i) di Ghana, Edmonds (2001)di Mexico, Falleti (2003) di Argentina, Colombia danMexico seperti dibahas dalam bagian selanjutnya.
GAMBARAN OTONOMI DI BEBERAPA NEGARA
Hingga sejauh ini sudah banyak sarjana yangmelakukan penelitian dan menulis tentang praktikdesentralisasi dan otonomi daerah di berbagai negaraberkembang, terutama dalam kaitannya denganpelaksanaannya yang pelbagai. Antaranya dilakukanoleh Bland (1997), Escobar-Lemmon (2000), Clarke(2001), Edmonds (2001) dan Mahakanjana (2004).Bland (1997) mengkaji mengenai pemerintah lokaldan hubungan antartingkat pemerintahan dalamprogram desentralisasi di Chile dan Venezuela. Blandmenyatakan otonomi yang diimplementasikan di keduanegara berkenaan terlaksana secara beda khususnyadari segi pembagian otoritas antara pemerintah lokaldengan pemerintah pusat. Antara perbedaan tersebutialah kepala daerah di Chile tidak dipilih melaluipemilihan umum karena gubernur dilantik langsungoleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan anggotaparlemen daerah dan pemerintah provinsi hanyaberfungsi dalam hal administratif saja, dan tidakmempunyai otoritas dalam menenflrkan rancanganpembangunan. Karena itu, lanjut Bland, politik lokaldi Chile menjadi kurang bekembang. Hal ini sejalandengan bahasan Jackson (2005) tentang politik lokaldi Chile yang menemukan bahwa pemerintah daerahtidak diberikan otonomi yang luas dalam menjalankanpemerintahannya sehingga menyebabkan banyakfungsi dan tanggungjawab pemerintah daerah tidakdapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini
38 Politik Lokal Dan Otonomi, Sebuah Perbincangan Singkat
karena kebijakan publik tidak sekehendak dengan
tuntutan dan keperluan masyarakat.
Sebaliknya di Venezuela, merujuk Bland(1997), gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan
diselenggarakan seperti Pilkada atau pemilukadadi Indonesia, dan separuh anggota parlemen daerah
dipilih langsung, manakala sisanya ditetapkan olehelit partai di tingkat pusat. Dari perbedaan tersebut,pemerintah lokal di Venezuela berkembang dengan
baik, ia mempunyai kekuasaan dan sumber keuanganyangjelas bagi pembangunan di aras lokal sebagai hasilpembagian kekuasaan antara pusat dengan daerah.
Pada arah sebaliknya, pemerintah daerah di Chilemenjalankan pembangunan berdasarkan peruntukan
otoritas dan keuangan yang dikehendaki olehpemerintah pusat (terhadap suatu daerah). Implikasinyatanggungjawab pemerintahan daerah di Chile menjadisesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan kepadapemerintah pusat bukan kepada rakyat setempat.
Kendati demikian, konflik kepentingan elit politiklokal justru banyak terjadi di Venezuela berbandingdi Chile. Ini disebabkan oleh pelimpahan kekuasaanyang besar pada daerah yang justru digunakan olehpara elit politik lokal untuk melakukan tawar menawardalam hal desentralisasi fiskal.
Berbeda dengan kajian Bland, elaborasi Escobar& Alvarez (1992) tentang otonomi daerah menarikdiperhatikan karena melihat konsep ini dalamperspektif pelibatan rakyat dalam mensukseskandesentralisasi itu sendiri. Di samping itu, kajianEscobar& Alvarez menumpukan perhatiannya di Boliviabukan di Chile ataupun Venezuela. Selain itu, Escobar& Alvarez menyatakan, meskipun Bolivia merupakannegara yang tergolong sebagai negara berkembangdan mempunyai sumber daya yang terbatas, tetapidesentralisasinya dapat dikatakan sukses karenadidukung oleh rakyat dan organisasi masyarakatsipil di negara bersangkutan. Dukungan inilah yang
menjadi 'ramuan' penting bagi kesuksesan programsosial diselenggarakan secara amat baik. Tidak hanyaitu, bahkan pengelolaan pemerintah di tingkatan lokalsangat berdampak positif sehingga memberi pelayananpada rakyat secara tulus yang menyertakan empatidi dalamnya. Hasilnya, pelaksanaan desentralisasi
di Bolivia berhasil membawa perubahan besar yang
amat progresif, dan daerah berkembang dengan
cukup pesat. Pencapaian ini menyebabkan Boliviamendapat pengesahan oleh dunia internasional dan
pelaksanaannya kemudian dikenal sebagai Bolivianmodel of decentralization. Bank Dunia (World Bank)
malah menganjurkan supaya Costa Rica, Panama,
Haiti dan Republik Dominica untuk mempelajarisertarmengikuti jejak otonomi di Bolivia (PopulorParticipation Bolivia\ untuk dijalankan di negara
mereka masing-masing (Escobar & AIv arez 1992:1 83).
Kelebihan kajian Escobar & Alvarez ialahbeliau mampu menunjukkan kekuatan pelaksanaan
desentralisasi di Bolivia yakni desentralisasi mampu
mengembangkan proses demokratisasi dalam
formulasi kebijakan daerah. Selain itu, karena ada
pembagian kuasa yang jelas antara pusat dengan
lokal, capaian pemerintah daerah menjadi jauh lebihefektif dan efisien. Tetapi malangnya, kajian Escobar
& Alvarez (1992) terdapat kelemahan, misalnya,
beliau tidak menjelaskan mekanisme yang berkaitan
dengan dimensi ekonomi-politik dan keuangan yang
menyebabkan tercapainya pemerintahan yang efisien
berdasarkan pendemokrasian formulasi kebijakan ditingkat lokal. Bagaimanapun, fokus kajian Escobar &Alvarez telah menjelaskan kepada pembaca mengenai
keberhasilan suatu negara memperluas partisipasi
rakyat sehingga tercapai pemerintahan yang efektifdan efisien.
Kajian mengenai proses desentralisasi diColombia dan Costa Rica sebagai negara kesatuan, dan
Venezuela sebagai negara federal diurai oleh Escobar-
Lemmon (2000). Perbincangannya sangat menarikkarena membandingkan otonomi daerah di dua sistemyang berbeda. Hasil kajiannya mendapati bahwa
otonomi di Colombia lebih maju dalam desentralisasipolitik dan keuangan karena pemilihan pimpinandaerah dilakukan secara langsung dan demokratis.
Di samping itu, pemerintah daerah di Colombiajuga diberi tanggungiawab besar untuk mengelola
pelayanan yang cocok dan sesuai dengan kehendak
rakyat di daerah otonom masing-masing. Bahkanpemerintah daerah mempunyai hak terhadap berbagai
macam pajak dan cukai sehingga mempermudah
mereka untuk menetapkan rancangan pembangunan
daerah. Dan, pembagian hasil pajak tersebut antara
pemerintah daerah dengan pusat dilakukan berdasarkanpersentase.
Sebaliknya di Costa Rica, otonomi tidak berjalan
dengan mulus karena pemerintah daerah hampir tidakmemptrnyai otonomi sebab semuanya ditentukandan dikuasai oleh pusat. Selanjutnya di Venezuela
pula, walaupun negara tersebut menjalan sistem
federalisme, namun pemerintahan di negara bagian
tidak mempunyai kekuasaan untuk menarik pajak
l,,LHr-*hrlln3rn
-ITrh--Eq
IqrdrEtFcrbarrhbiFtirH.qFElrtHfrEFI
DqFrlle
hE!rrxFiETh
liIiI!IItF
k
IIFtpI!
:tFbItI
lrena ihwal ini dikendalikan oleh pemerintah pusat.
&€i Lemmon(2000:235), hal ini menjadi penghalanghrgi kesuksesan otonomi daerah. Kajian Escobar-lgnmon ini menyita perhatian karena ia berhasilmrgilustrasikan bahwa negara yang berbentukbc$atuan lebih sukses melaksanakan otonomihbanding negara federal. Kajiannya pada tahun 2000o diperkukuh lagi oleh analisis Mohammad Aguslbotr & Leo Agustino (2011) yang menjelaskan&deralisme di Malaysia dalam konteks hubunganrrsat dengan daerah di Malaysia tidak mencerminkanrrl*n1'n otonomi di tingkat lokal karena adanyasekatandm halangan dalam aspek politik dan ekonomi dirstiap negara bagian. Oleh karena itu, MohammadAgus Yusoff dan Leo Agustino (2011) menyebut&derali sme Malaysia sebagai qu as i -fe der al i s me.
Merujuk pada uraian Escobar-Lemmon (2000)dn Mohammad Agus Yusoff dan Leo Agustino (201 I )t[ atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa kesuksesand.smtralisasi ataupun otonomi bukanlah terletaknda bentuk negara, tetapi lebih pada political willm& saling berbagi kekuasaan dan melaksanakan
gg"rngjawab masing-masing di tingkat pusat@il+rrn daerah.
Elaborasi mengenai desentralisasi dan politik lokaly g diselenggarakan di Amerika Selatan diuraikanp&a oleh Edmonds (2001). Edmonds membahas
mgenai hal tersebut di Mexico, studinya mendapati
mcapaian pembangunan setiap daerah berbeda-hda karena tiga faktor. Pertama, terdapat persaingannrrsetiap pemerintah daerah untuk membuatHijakan publik yang dapat mendukung aspirasi danptisipasi masyarikat dalam pelaksanaan otonomillni&nl Kedua, terdapat pertentangan di kalangan
m kong partai politik sehingga menyebabkannsryulitkan partai politik untuk mengontrol kepala{h:rah (chief government) dalam melaksanakanmmi lokal di Mexico. Ketiga, kemampuanmintah daerah dalam mencari sumber-sumber
- iT\atan berbeda di daerahnya masing-masing.Dalam perspektifyang berbeda dengan beberapa
qpa di atas, khususnya dalam konteks skop
Jurnal Pamong Praja, Vol. I Tahun 20II : 3I-42 39
analisisnya, Clarke (2001) membahas desenfralisasidan demokrasi lokal di Ghana. Kajian Clarkemendiskusikan struktur desentralisasi di Ghana danmenganalisis kompleksitas jaringan relasi dan interaksiyang mempengaruhi pemerintah daerah. Beliaumembagi struktur desentralisasi di Ghana ke dalamempat tingkatan, yaitu dewan koordinator nasional,dewan daerah, majelis daerah, dan unit jawatan kuasa
lainnya.3 Clarke selanjutnya menyatakan meskipunGhana melaksanakan desentralisasi, tetapi pemerintahpusat tetap melakukan pengawalan dan pengawasan
terhadap pembagian keuangan kepada pemerintahdaerah. Walau pemerintah pusat mengawal danmengawasi keuangan pemerintah daerah, namundesentralisasi di Ghana mencapai keberhasilan karenakebijakan pembangunan negaranya berlandaskanpada partisipasi lokal. Implikasi dari realitas inimenghasilkan pemerintah daerah yang mempunyaiprosedur perancangan yang baik, dan daerah berhasilmenjalankan projek dan pelayanan pembangunankarena aspirasi publik di tingkat lokal dipenuhi,kerjasama dengan NGO dijalankan dan pemerintahdaerah mengakfifkan pertemuan-pertemuan bagipembangunan desa sesuai dengan keperluan mereka.
Temuan Clarke di atas selaras dengan kajianNyendu setahun sebelumnya. Nyendu (dalam LeoAgustino 2011) dalam konteks ini meneliti partisipasirakyat dalam program desentralisasi politik di Ghana.
Beliau menyimpulkan bahwa otonomi di Ghanaberhasil memperluas ruang publik yang berfungsidalam proses dan penentuan kebijakan di aras lokal.Kendati demikian, kajian Nyendu dan Clarke (2001)tidak saling melengkapi dan kurang menerka sisi gelapdesentralisasi di Ghana.
Lambright (2003) pula mengkaji politik lokal diAfrika tepatnya di Uganda. Kajiannya menjelaskankaitan antara politik pemerintah pusat dengandaerah dalam menjalankan desentralisasi. Lambrightmenemukan bahwa dukungan politik yang kuat daridaerah kepada pemerintah pusat berdampak pada
pencapaian pembangunan di daerah. Ini karenasokongan dari pemerintah daerah dapat mewujudkan
s iryi<mal Coordinating Councils (RCCs) adalah jawatan yang diketuai oleh Regional Chief Executive yang dipilih olehhsiden sebagai Regional Coordinating Directors. RCCs mengkoordinasi dan mengintegrasikan rencana District As-nblies (DAs) dan mengesahkan anggaran belanja mereka dan sekaligus melakukan pemeriksaan atas kesesuaian peng-
Faan anggaran. Selanjutnya DAs menempatkan lagi ke District Council apabila kuasa DAs jauh lebih luas daripadal[Ci karena menurut undang-undang DAs memiliki otoritas dalam hal mengawal dekonsentrasi yang berkait denganrfotrkatan pajak dan pelayanan publik lainnya yang dijalankan masing-masing kota (District Council). DAs juga
iliki otoritas dalam hal menetapkan kategori jumlah warga untuk sebuah Metropolitan (warga lebih dari 250.000),hcipal (warga lebih dari 95.000), atau 75.000 warga untuk setiap District Council (Clarke 2001:79).
.ro Politik Lokal Dan Otonomi, Sebuah Perbincangan Singkat
hubungan yang harmonis dengan pemerintah
pusat berbanding pemerintah daerah yang terus-
menerus membangkang terhadap kebijakan pusat.
Pembangkangan kepada pusat, lanjut Lambright,
disebabkan oleh (i) strategi elit pemerintah daerah
untuk menguasai (kekuasaan) politik di tingkat lokalsupaya pusat tidak banyak melakukan intervensi
dalam urusan daerah dan (ii) supaya pemerintah pusat
memberi perhatian pada daerah dalam melaksanaan
pembangunan (Lambright 2003 :430, 432).
Nakano (dalam Leo Agustino 201 1) pula mengkaj itentang desentralisasi dan politik lokal di Prancis dan
Jepang. Nakano menemukan bahwa desentralisasi
di Perancis berjalan lebih baik berbanding dengan
pelaksanaan hal yang sama di Jepang. Ini karena di
Prancis masyarakat awam mempunyai'suara langsung'
dalam proses formulasi kebijakan nasional melalui
cumul des mandats yang diamanatkan oleh undang-
undang desentralisasi Prancis, sedangkan di Jepang
tidak mempunyai model politik desentralisasi seperti
itu. Hal lain yang berbeda antara kedua negarayaflgditeliti oleh Nakano adalah pemilihan anggota senat
yang dipilih langsung oleh parlemen lokal (Nakano
2006:247), sedangkan di Jepang pemilihannya
dilakukan melalui minister of home affair. Selain itu,
konstitusi Prancis mensyaratkan pembagian bidang
kuasa antara pemerintah daerah dan pusat berdasar
pada kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing
pemerintah daerah, sedangkan di Jepang tidak.
Kendati demikian, untuk mengawal dan memperkokohpelaksanaan desentralisasi di Jepang pemerintah pusat
membentuk decentr al iz ation c o mmis s ion yangbekerj a
untuk memberdayakan dan menguatkan otonomilokal berdasarkan isu dan masalah publik utama yang
terdapat dalam masyarakat.
Uraian di atas menunjukkan otonomi tidak selalu
berjalan mulus. Kadang jalan berliku, menanjak, terjaldan lainnya. Sebab itulah, ramai para penyelenggara
yang kemudian mengambil jalan pintas dalam
menyelenggarakan pemerintahan secara serampangan.
Perbedaan hasil akhir dalam impelementasi misalnya
dapat ditunjukkan dalam kasus Chile dan Venezuela
yang dikaji oleh Bland, Prancis dan Jepang yang
dijelaskan Nakano serta Colombia dan Costa Rica yang
dinilai oleh Escobar-Lemmon. Merujuk pada seluruh
uraian dalam bagian ini satu yang dapat disimpulkan
otonomi selalu menghasilkan wajah gandanya; di satu
saat ia bisa menghadirkan karunia, tetapi di saat yang
lain (karena pelaksanaannya yang dilaksanakan tanpa
pengelolaan dan komitmen yang kuat) ia dapat menjadi
kutuk bagi semesta ekonomi-politik di aras lokal.
PENUTUP
Artikel ini telah menunjukkan manfaat daripelaksanaan otonomi daerah di banyak negara.
Antaranya menumbuhkembangkan akuntabilitas
dan responsivitas, mengembangakan warga sebagai
masyarakat sipil dalam arti yang sejati, melembagakan
mekanisme checlcs and balances (pengawasan dan
penyeimbangan), memantapkan legitimasi politikpemimpin-pemimpin daerah, memberi peluang
kepada pemerintah daerah untuk berinovasi tanpa
perlu menjustifikasi kepada daerih lain, menciptakan
kestabilan politik dengan memberi peluang kepada
masyarakat dalam skop teritori yang tidak terlalu luas
dan meningkatkan pembangunan secara berprioritas
sehingga menekan biaya. Walau begitu, otonomi
tidak jarang mencetuskan pembusukan pembangunan
politik yang justru hendak dibangunnya. Ini misalnya
ditunjukkan dengan adanya intoleransi dan diskriminasi
antara kelompok pendatang dan pribumi sangat
mungkin (semakin) menguat, terjadinya pemborosan
keuangan atau anggaran daerah, kekhilafan dalam
mengidentifikasi secara saksama otoritas pekerjaan
pusat ataupun daerah sehingga menghadirkan
duplikasi pekerjaan dan juga muncul dan menguabrya
kantong-kantong kekuasaan otoriter baru di tangan-
tangan kelompok tertentu (local strongman).
Realitas tersebut misalnya ditunjukkan dengan
realitas yang terjadi di beberapa negara seperti yang
ditunjukkan oleh Bland di Chile dan Venezuela
yang dikajinya, Nakano di Prancis dan Jepang dan
Escobar-Lemmon di Colombia dan Costa Rica. Satu
kecenderungan yang muncul dari bahasan artikelini adalah keberhasilan otonomi diperoleh dari
pemberian kekuasaan yang penuh dari pemerintah
pusat kepada daerah untuk menentukan kebijakanpungutan daerah bagi memenuhi anggaran belanja
daerah. Keadaan ini menjayakan setiap daerah untuk
mengembangkan sumber keuangannya masing-
masing bagi pencapaian ekonomi yang dikehendaki.
Tetapi, hal ini juga menyebabkan pemerintah daerah
membuat pelbagai kebijakan yang bersifat pungutan
kepada rakyat sehingga mencetuskan peraturan-
peraturan bermasalah. Akibatnya, kebijakan pungutan
yang diformulasi oleh pemerintah daerah menjadi
kontraproduktif dengan kehendak rakyat untuk
tI
fiIII
.sa
(lo
nryIIl!i(
na.
as
pian
an
riknglpa(an
ada
uas
itas
omi
mperluas kegiatan ekonomi mereka. Di luar ituslua, kondisi ini menyebabkan timbulnya perbedaan
mis belanja pembangunan antara daerah. Akibatnya,
Fengeluaran pemerintah daerah kerap dimanipulasiffi elit lokal, sehingga mencetuskan otonomi yang
fihk efektif. Pelajaran otonomi yang tidak efektifinilah yang justru ditonjolkan dalam artikel ini dalam
rmgka memperbaiki dan menyempumakan otonomidrrah yang sedang dilaksanakan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Btrd R. & Wallich, C. 1993. Fiscal decentralizationand intergovernmental relation in transitioneconomies: toward a systemic frameworkof analysis. Washington D.C.: World BankInstitute.
Bland, G. 1997. Political broker revisited: localgovernment, decentralization, and
democracy in Chile andVenezuela. DisertasiPhD. University of Baltimore.
Clarke, V.B. 2001. In search of good governance:
decentralization and democracy in Ghana.
Disertasi PhD. Northern Illinois University.Edmonds, E. 2001. Decentralization and local
autonomy in Mexico. Disertasi PhD.
University of Colorado.
Escobar, A., & Alvarez, S.E. 1992. The makingof social movements in Latin America:identity, strategl, and democracy. Boulder:Westview.
Escobar-Lemmon, M.C. 2000. The causes and
process of decentralization. Disertasi PhD.
The Univrsity ofArizona.Falleti, T.G. 2003. Governing govemors: coalitions
and sequences of decentralization inArgentina, Colombia, and Mexico. Disertasi
PhD. Northwestern University.Harriss-White, B. 1999. How India works: the
character of the local cconomy. Cambridge:
Cambridge University Press.
Hure-girrt, K. 1981. Local decision-making autonomy:
a review.of conceptual and methodologicalissues. London: King's College Press.
Holuappel, C.J.G. & Ramstedt, M. (eds.). 2010.
Decentralization and regional autonomy inIndonesia. Singapore: ISEAS.
,lncLson, S.M. 2005. Identity matters: politicalidentity construction and the process of
Jurnal PamongPraja, Vol. I Tahun 20ll : 31-42 41
identity influence. Disertasi PhD. Universityof Minnesota.
Johnson, W.C. 1997. Urban planning and politics.Chicago: Planners Press.
Kousoulass, G.D. 1975. On government and politics.Califomia: Duxburry Press.
Lambright, G.M.S. 2003. The dillema ofdecentralization: a study of local politics inUganda. Disertasi PhD. Michigan State
University.Leo Agustino. 2011. Sisi gelap otonomi daerah.
Bandung: Widya Padjadj aran.
Maclver, R.M. 1964. The modern state. London:Oxford University Press.
Mann, M. 2008. Infrastuctural powerrevisited. Study
of Comparative International Development
43:355-365.Migdal, J.S. & Schlichte, K. 2005. Rethinking the
state. Dlm. K. Schlichte.(ed.). The dynamics
ofstates: theformation and crises of the state
domination, 1-40. Burlington: Ashgate.
Milliband, R. 1969. The state in capitalist society.
New York: Basic Books.
Mohammad Agus Yusoff & Leo Agustino. 2011.
Federalisme di Malaysia: potret hubungan
pusat-daerah. Analisis CSIS 42(2): 193-216.
Offe, C. & Ronge, V.H. 1975. Theses on the theory ofthe state. New German Critique 6: 137-147.
Poulantzas, N. 1973. Political power and socialclasses. Ted. London: Verso.
Rondinelli, D.A., & Cheema. 1983. Decentralizationin developing countries. California: Sage
Publications.
Rosenbloom, D.H. 1993. Public administrastion:understanding management, politics, and law
in the public sector. New York: McGraw-Hill.
Sammoff, J. 1990. Decentralization: the politics ofintervention. Development and Change 2l:5 13-530.
Seabright, P. I 996. Accountability and decentralizationin government: an incomplete contracts
model. European Economics Review 40:
6l-89.Shively, W.P. 1999. Power and choice: an introduction
to political science. Boston: McGraw-Hill.Skocpol, T. 1979. State and revolution: old regime
and revolutionary crises in France, Rusia,
and China. Theory and Society 7(l):7-95.
man
lnya
nasi
ngat
osan
alam
rjaan
irkan
rtnya
rgan-
:ngan
yang
ntela
! dan
Satu
utikeldari
rintah
'ijakanrclartja
untuk
rasing-
ndaki.daerah
ngutan
aturan-
mgutan
nenjadiuntuk
42 Politik Lokal Dan Otonomi, Sebuah Perbincangan Singkart
Skocpol, T. 1985. Bringing the state back in: strategiesof analysis in current research. Dlm. PeterB. Evans, Dietrich Rueschemeyer & ThedaSkocpol (eds.). Bringing the state back in,3-44. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
Smith, B.C. 1985. Decentralization: the tenitorialdimension ofthe state. London: Allen & Unwin.
St€pan, A. 1978. The state and society: Perucomparative perpective. Princeton:Princeton University Press.
Wolman, H. 1990. Decentralization: what it is andwhywe should care. Dlm. R.J. Bennett (ed.).Decentralization, local government, andmarkets : towards a post-welfare agenda, 29-42. Oxford: Oxford University Press.
iSu*
iffitll$&;1
;&*,
f,ihehhttEi-hiltDr.tqErprp,bh,
tanftft,,!|-