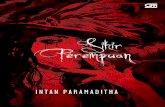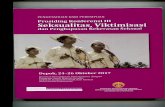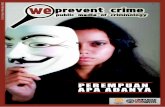Perlawanan Perempuan terhadap Kekerasan dalam ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Perlawanan Perempuan terhadap Kekerasan dalam ...
1
Perlawanan Perempuan terhadap Kekerasan dalam Berpacarandi Video Musik K-Pop
Koko Sadewo & Rina Sari KusumaUniversitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162 Email: [email protected]
Abstract: Women often become victims of violence in dating relationship and are just likely accept it. However, women depicted as victims dare against the perpetrators in some music videos. Through qualitative content analysis, this study aims to find forms of violence and women’s resistance toward it in dating in K-pop music videos. The results show that there are two forms of violence experienced by women, i.e. physical and psychic violence. In addition, victims can break down the stereotype that women are weak. It is showed by the attitude of women who dare to do revenge by hurting, even killing the perpetrators.
Keyword: dating violence, K-pop music, video clip, women’s resistance
Abstrak: Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam berpacaran dan cenderung menerima begitu saja kekerasan tersebut. Namun demikian, perempuan yang digambarkan menjadi korban berani bertindak melawan pelaku dalam beberapa video klip musik. Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan serta perlawanan perempuan terhadap kekerasan dalam berpacaran di video klip musik K-pop. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua bentuk kekerasan yang diterima perempuan, yaitu kekerasan fisik dan psikis. Selain itu, korban dapat mendobrak stereotip yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap perempuan yang berani melawan dengan cara membalas dendam, melukai, hingga membunuh pelaku.
Kata Kunci: kekerasan dalam berpacaran, musik K-pop, perlawanan perempuan, video klip
Kekerasan merupakan persoalan pelanggaran kondisi manusia yang selalu menarik untuk dikaji. Kekerasan sering terjadi karena orang-orang atau lembaga yang dominan dan kuat tidak ingin wewenang mereka dilanggar atau tidak dipatuhi, sehingga kekerasan bisa dilakukan dan terjadi pada siapa saja, tanpa memandang kelas sosial, umur, maupun jenis kelamin. Menurut Fakih (1999, h. 9), kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun
integritas mental psikologi seseorang. Mahardika (2010, h. 1) menambahkan bahwa kekerasan memiliki arti sebagai hal atau sifat yang keras, paksaan, dan kekuatan.
Kekerasan masuk dalam perilaku agresi dan merupakan salah satu tipe agresi yang merujuk pada bentuk-bentuk agresi fisik ekstrem. Perilaku agresif tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan kepada
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
2
orang lain. Kebutuhan laki-laki untuk mendominasi atau menguasai perempuan dan ketidakmampuan untuk berempati menyebabkan laki-laki lebih senang mengandalkan kekerasan (Khaninah & Widjanarko, 2017, h. 151). Menurut Awuy (dalam Tisyah & Erna, 2013, h. 2) perempuan merupakan makhluk yang pasif (objek), sedangkan laki-laki merupakan makhluk yang aktif (subjek), sehingga kekuasaan ada di tangan laki-laki. Laki-laki sering menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan karena laki-laki hanya sekadar ingin menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kuasa dan perempuan harus tunduk. Perempuan selama ini selalu dianggap lemah dan mereka tidak dapat melawan saat terjadi kekerasan, sehingga kaum perempuan masih banyak mengalami kekerasan.
Seiring perkembangan zaman, pelaku kekerasan tidak hanya laki-laki. Kini perempuan dapat menjadi pelaku kekerasan dan laki-laki menjadi korban. Kekerasan biasanya terjadi pada laki-laki dalam konteks hubungan persaudaraan, pertemanan, per-cintaan, hingga hubungan suami istri.
Berpacaran adalah proses perkenalan atau pendekatan antara dua insan manusia yang saling tertarik untuk saling mengenal serta menjalin hubungan yang lebih serius dan pribadi. Tujuan akhir berpacaran adalah untuk melanjutkan hidup bersama dalam ikatan yang resmi. Berpacaran merupakan perilaku yang negatif karena berpacaran merupakan bagian dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hal buruk apabila tidak sesuai aturan. Orang-orang sering kali
lupa bahwa di balik indahnya berpacaran terdapat hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan. Pasangan yang sedang berpacaran tidak sadar bahwa hubungan mereka dapat berubah menjadi mengerikan, tidak sehat, dan dipenuhi kekerasan (Putri, 2012, h. 2).
American Psychological Association (1996) menyatakan bahwa kekerasan dalam berpacaran (KDP) memiliki pengertian sebagai kekerasan fisik dan emosional yang dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya dalam hubungan berpacaran dan ditujukan untuk memperoleh kekuasaan, kekuatan, dan kontrol atas pasangannya. Sugarman dan Hotaling (1989, h. 1035) mendefinisikan kekerasan berpacaran sebagai penggunaan atau ancaman kekuatan fisik dalam hubungan kencan. Perilaku yang termasuk sebagai tindakan kekerasan dalam berpacaran adalah salah satu pihak merasa tersakiti secara fisik dan emosi oleh pasangannya dan menimbulkan kesengsaraan dan kerugian. Beberapa faktor penyebab kekerasan dalam berpacaran, yaitu perdebatan, keinginan yang tidak terpenuhi, rasa cemburu, depresi, dan perilaku yang tidak dikehendaki. Sementara itu, dampak kekerasan adalah rasa tertekan, cemas, takut, sedih, dendam, timbulnya perspektif negatif terhadap pasangan, luka di tubuh, dan dampak paling fatal, yaitu kematian (Warkentin, 2008, h. 17).
KDP terdiri dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, emosional, paksaan seksual, pelecehan verbal, menguntit, atau perilaku yang mengancam. Data Centers for Disease
Koko Sadewo & Rina Sari Kusuma. Perlawanan Perempuan terhadap ...
3
Control and Prevention (2020) menyatakan bahwa pada tahun 2013 sekitar 10 persen siswa sekolah menengah atas di Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka telah mengalami kekerasan fisik oleh pasangan mereka dan 10 persen lainnya mengalami kekerasan seksual. Data penelitian Richards, Branch, dan Ray (2014, h. 323) menunjukkan bahwa 22 persen remaja telah melakukan kekerasan fisik terhadap pasangan mereka, sedangkan 16 persen remaja melaporkan bahwa mereka menjadi korban kekerasan pasangan mereka. Sementara itu, 34 persen remaja melaporkan terlibat dalam kekerasan emosional dan 39 persen remaja melaporkan bahwa mereka menjadi korban kekerasan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa kekerasan dalam berpacaran merupakan masalah yang serius dan memiliki beragam dampak yang merugikan korban. Bentuknya dapat berupa cedera fisik, gangguan stres pascatrauma, depresi, kecemasan, penyalahgunaan obat-obatan, dan bunuh diri. Selain itu, kekerasan dalam berpacaran di masa datang dapat menyebabkan pelaku terlibat kekerasan dalam rumah tangga (Park & Kim, 2018, h. 19).
Khaninah dan Widjanarko (2017, h. 154) menjelaskan bahwa Youth Centre SeBAYA-PKBI Jawa Timur, pada bulan Agustus 2010, di Surabaya, mengadakan survei mengenai kekerasan dalam berpacaran terhadap 100 remaja. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 12 persen responden diputus oleh pacarnya karena menolak ketika diajak berhubungan badan (seks), 13 persen responden pernah
dipukul hingga ditendang saat tidak menuruti sang pacar. Selain itu, sejumlah 17 persen responden pernah dikatakan tidak cinta apabila menolak ajakan pacar untuk berhubungan badan dan sebanyak 33 persen responden pernah dimarahi pacar karena menolak untuk berciuman. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Semarang pada 2011 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berjumlah 95 kasus dan kekerasan dalam berpacaran menempati peringkat kedua tertinggi setelah kekerasan dalam rumah tangga (Khaninah & Widjanarko, 2017, h. 153). Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengenai kekerasan dalam berpacaran menunjukkan sejumlah 4.304 kasus kekerasan fisik, 3.325 kasus kekerasan seksual, 2.607 kasus kekerasan psikis, dan 971 kasus kekerasan ekonomi (Saroh, 2016).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prabowo (2012, h. 9) menggambarkan perempuan sebagai pelaku tunggal tindak kekerasan dan juga sebagai penentu akhir cerita. Di dalam cerita, tokoh Dara digambarkan sebagai perempuan yang melakukan KDP secara sengaja yang dibuktikan ketika dirinya menjadwal dating para korban-korbannya dan menyiapkan berbagai senjata untuk dapat menghabisi para korbannya. Prabowo (2012) menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisis video musik Korean pop (K-pop) dengan objek dan metode yang berbeda.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
4
Video klip merupakan tampilan visual dari hasil penggabungan musik sebuah grup musik atau penyanyi yang diciptakan tidak hanya untuk mempromosikan lagu atau penyanyinya, melainkan untuk menyampaikan pesan pembuatnya (Effendy, 2002, h. 14). Selain itu, sebuah video klip juga menjadi media komunikasi untuk menggambarkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika sebuah video klip sudah disebarluaskan untuk disaksikan khalayak, pembuat video klip tersebut memiliki tanggung jawab atas tersebarluasnya nilai, prasangka, hingga keyakinan tertentu (Mahardika, 2010, h. 8).
Musik K-pop dipilih karena sekarang ini Korean Wave (hallyu) sedang tren. Hal ini menyebabkan mulai tersebarnya kebudayaan Korea ke berbagai negara, termasuk Indonesia. K-pop merupakan kepanjangan dari Korean pop. Musik pop Korea adalah musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Sejumlah artis dan kelompok musik pop Korea sudah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara, serta mengikuti jejak Korean Wave (Poriskova, 2012, h. 17). K-pop baru-baru ini memasuki leksikon budaya populer global terkait standar baru dalam musik populer. Daya tarik visual dari idola, pertunjukkannya, dan tingkat konservatisme musik yang signifikan telah memikat jutaan penggemar di seluruh dunia dan menarik perhatian media internasional. Antara akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an, sejumlah grup K-pop membuat debut internasional yang sukses. Fokus dari kelompok tersebut adalah presentasi visual dan koreografi mereka di atas maupun di luar
panggung. Sejak awal 2000-an, ruang lingkup keterlibatan internasional dalam produksi K-pop telah melebar secara bertahap. Frekuensi mengadakan konser K-pop di negara-negara asing dan jumlah lagu yang dinyanyikan dalam bahasa asing meningkat (Choi & Maliangkay, 2014, h. 3).
Kemunculan boyband dan girlband menjadi salah satu faktor kesuksesan musik K-pop. Girlband juga menjadi contoh bahwa perempuan juga dapat berkarya. Menurut Bancin dan Nurani (2018), ada beberapa musik girlband K-pop yang liriknya berbicara mengenai perlawanan perempuan. Pertama, CL (anggota girlband 2NE1) dengan lagu “The Baddest Female” yang liriknya mengajak perempuan menjadi tangguh dan tidak dapat dimanfaatkan oleh kaum laki-laki. Kedua, Miss A dengan lagu “I Don’t Need A Man” yang liriknya mengajak kaum perempuan menjadi mandiri tanpa harus bergantung pada laki-laki. Ketiga, Girls Day dengan lagu “Female President” yang liriknya mengajak kaum perempuan mendapatkan hal yang diinginkan tanpa harus menunggu laki-laki lebih dahulu.
Fenomena berpacaran yang telah dibahas sebelumnya masuk dalam salah satu konteks ilmu komunikasi, yaitu komunikasi antarpribadi atau interpersonal. DeVito (dalam Wulandari, 2016, h. 5) menyatakan bahwa komunikasi antarpribadi adalah hubungan timbal balik yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan jelas. Komunikasi antarpribadi menyebabkan seseorang dapat membangun, menjaga, dan meningkatkan
Koko Sadewo & Rina Sari Kusuma. Perlawanan Perempuan terhadap ...
5
hubungan sosial dengan orang di sekitarnya, baik itu anggota keluarga, teman, maupun orang-orang yang dianggap penting dalam kehidupannya. Berger (dalam Wulandari, 2016, h. 5) menambahkan bahwa komunikasi yang paling sering digunakan oleh orang-orang untuk saling berinteraksi adalah komunikasi antarpribadi. Menurut Hardjana (2003, h. 85) komunikasi interpersonal antara dua orang yang baru kenal akan berbeda dengan yang sudah kenal lama. Bahkan, hubungan antara pacar dengan teman biasa pun berbeda karena masing-masing orang berbeda tingkat kedalaman komunikasinya. Dalam berpacaran, kita dapat mengungkapkan maksud kita secara lebih khusus, tetapi juga dapat saling memiliki komitmen khusus (Hardjana, 2003, h. 85).
Komunikasi antarpribadi memuat hubungan romantis, yaitu hubungan antarindividu yang berasumsi bahwa mereka menjadi dasar dari dan terus-menerus menjadi bagian hidup orang lain. Hubungan romantis yang berkomitmen memiliki ikatan I-thou, yaitu ketika kita menginvestasikan banyak hal dan setiap orang mengetahui partner mereka seutuhnya sebagai seorang individu. Terdapat tiga dimensi dalam hubungan romantis, yaitu hasrat, komitmen, dan keintiman (Febriani, 2016, h. 30).
Sementara itu, Kistler dan Lee (2009, h. 79) telah melakukan penelitian tentang efek jangka pendek dari paparan video music hiphop dengan jumlah konten seksual yang bervariasi. Hasilnya menunjukkan bahwa khalayak laki-laki yang terpapar
video musik dengan konten seksual yang tinggi melaporkan adanya objektivitas perempuan yang lebih besar dan lebih banyak menerima perkosaan dibandingkan dengan mereka yang menonton video musik dengan konten seksual yang rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa video musik dapat memengaruhi persepsi tentang kesesuaian kekerasan dalam hubungan. Video musik dapat memengaruhi persepsi hubungan melalui penciptaan narasi atau cerita yang digambarkan dalam lagu dan gambar visual yang menyertainya (Rhodes, Potocki, & Masterson, 2018, h. 4).
Media juga berkontribusi pada pemahaman tentang berpacaran yang sehat dan tidak sehat. Hal tersebut tercermin ketika media mencirikan hubungan berpacaran yang kasar atau tidak sehat melalui rasa memiliki dan kecemburuan sebagai tindakan cinta dan pengabdian yang romantis. Selain itu, media membombardir khalayak dengan memberikan gambaran bahwa laki-laki selalu memecahkan masalah mereka melalui cara-cara kekerasan. Lebih jauh, perilaku agresif, bersifat fisik, dan misoginis ini dikagumi sebagai maskulinitas heroik, sehingga pada akhirnya perempuan dan laki-laki akan memasukkan kekerasan dalam definisi mereka tentang kedewasaan (Soroptimist International of the Americas, 2013, h. 7).
Media juga merupakan salah satu agen yang ikut melanggengkan ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang beredar, salah satu contohnya berita mengenai perkosaan. Pemberitaan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
6
mengenai perkosaan menggambarkan bahwa pihak perempuan yang menjadi korban dan pihak laki-laki selalu memberikan dalih bahwa pihak perempuan juga ikut andil menyebabkan perkosaan itu terjadi. Pola pemberitaan yang mendiskreditkan perempuan biasanya tidak sensitif gender, sehingga tidak heran apabila perempuan akan selalu menjadi bahan eksploitasi yang muncul dalam bentuk-bentuk pengalamiahan, ketimpangan, subordinasi, dan marginalisasi (Setiansah, 2009, h. 143-145).
Samadani (dalam Armando, 2015, h. 3) menjelaskan empat bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pertama, kekerasan fisik, yaitu kekerasan dengan memukul, menampar, menendang, mendorong, dan serangkain tindakan fisik lain, yang dilakukan menggunakan anggota badan pelaku (misalnya tangan dan kaki) atau menggunakan alat (misalnya balok kayu dan batu). Kedua, kekerasan psikologis/emosional, yaitu kekerasan dengan mengancam, menghina, mempermalukan pasangan di depan umum, dan menjelek-jelekkan, yang berdampak pada perasaan korban. Ketiga, kekerasan ekonomi, yaitu kekerasan dengan memaksa pasangan memberikan uang, selalu minta dibelikan sesuatu, meminta pasangan mencukupi segala keperluan hidupnya, serta meminjam uang dan tidak mengembalikan, yang berhubungan dengan masalah perekonomian (barang dan uang). Keempat, kekerasan seksual, yaitu kekerasan dengan meraba, memeluk, mencium, hingga melakukan hubungan seksual atas dasar ancaman dan paksaan, atau penyerangan seksual.
Laki-laki mendominasi pemberitaan di media dan media ikut andil dalam mengonstruksi realitas kehidupan sosial. Media membentuk realitas yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak mendominasi kehidupan bermasyarakat. Secara tidak langsung, media sering kali memberi makna bahwa khalayak perempuan adalah konsumsi laki-laki dan khalayak laki-laki identik dengan kekuasaan laki-laki terhadap khalayak perempuan. Khalayak laki-laki di media adalah penguasa khalayak perempuan (Farnisari & Sudrajat, 2013, h. 10).
Perempuan sering kali dikisahkan dalam sebuah televisi atau film sebagai sosok yang tertindas. Namun demikian, sosok perempuan dalam film “Perempuan Berkalung Sorban” digambarkan sebagai korban yang tidak menyerah dan melawan balik. Annisa, tokoh utama film tersebut, belajar melawan diskriminasi gender yang hadapinya sejak kanak-kanak. Annisa juga memiliki keberanian seksual yang hebat karena selama bertahun-tahun menderita dan bertahan dari siksaan dan hinaan suami serta anggota keluarganya sendiri. Pada suatu ketika, saat Annisa dan Khudori, teman masa kecil Annisa, berduaan saja, Annisa melepaskan jilbabnya dan mengundang Khudori untuk bercinta, lalu bergegas memeluknya (Heryanto, 2018, h. 95).
Kedudukan perempuan di negara lain pun cukup memprihatinkan. Di Korea Selatan, pada abad ke-18, keberadaan perempuan selalu dinomorduakan di segala hal dan tunduk pada laki-laki menjadi kewajiban perempuan. Menurut adat dalam
Koko Sadewo & Rina Sari Kusuma. Perlawanan Perempuan terhadap ...
7
masyarakat tradisional Korea Selatan, anak laki-laki lebih disukai daripada anak perempuan. Menurut ajaran Konfusianisme, perempuan dilarang untuk melakukan banyak peran. Hal tersebut menyebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan hingga saat ini. Kondisi tersebut hampir sama dengan Indonesia, perempuan Korea Selatan dilarang untuk keluar rumah, harus menetap di dalam rumah, dan berurusan dengan keperluan rumah saja. Dalam masyarakat tradisional, mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di tengah masyarakat dan hanya diperbolehkan melakukan kegiatan domestik saja, yaitu sebagai istri dan ibu. Kedudukan perempuan pada masa tersebut sangat merosot akibat diskriminasi gender. Bahkan, mereka tidak boleh memperoleh kedudukan yang setara maupun lebih tinggi dari laki-laki (Farnisari & Sudrajat, 2013, h. 10-11).
Situasi di Korea Selatan mulai berubah di akhir abad ke-19 dengan mulai didirikannya sekolah modern yang bertujuan khusus mendidik perempuan. Perempuan-perempuan yang bersekolah mulai terlibat dalam seni, pengajaran, pekerjaan keagamaan, dan pencerahan perempuan lain. Para perempuan telah mengalami perubahan sosial yang besar setelah Perang Korea (1950-1953) yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Korea Selatan pun berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Status sosial perempuan telah meningkat secara signifikan dalam tiga puluh tahun terakhir karena modernisasi dibandingkan Korea Selatan pada masa lalu yang terikat pada ajaran Konfusianisme (Khairani, 2018, h. 2).
Kesadaran akan gender pada tahun 2000-an terus meningkat. Pengaruh pendidikan yang terus berkembang dan isu hak asasi manusia yang dilandasi semangat feminisme menyebabkan peran perempuan di Korea Selatan semakin meningkat. Perempuan di Korea Selatan sampai saat ini belum bisa menikmati status yang setara dengan laki-laki, meskipun perempuan di sana sudah banyak memainkan peran penting dalam setiap bagian kehidupan bermasyarakat (Farnisari & Sudrajat, 2013, h. 11).
Latar belakang masalah dan tinjauan pustaka di atas mendorong tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui bentuk kekerasan dan perlawanan perempuan terhadap kekerasan dalam hubungan berpacaran di video klip musik K-pop.
METODE
Penelitian ini dilakukan dengan meng-gunakan pendekatan kualitatif dan berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menjelaskan atau men deskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Sifat dari penelitian ini ialah subjektif karena peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan (Kriyantono, 2006, h. 196).
Objek penelitian ini ialah video klip K-pop yang bercerita tentang kekerasan dalam berpacaran. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan nonprobability sampling dan teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah video-video klip K-pop tentang hubungan berpacaran yang dirilis antara
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
8
tahun 2010-2017. Sampel diambil berdasarkan kriteria, yaitu terdapat tindakan kekerasan dalam hubungan berpacaran dalam video klip tersebut. Setelah itu, peneliti mengambil sampel secara acak dan mendapatkan tiga sampel yang sesuai dengan kriteria. Video klip yang dipilih diambil dari YouTube, yaitu video klip dari girlband 2NE1 berjudul “Go Away” (Park & Taek, 2010), Dalshabet berjudul “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012), dan Sistar berjudul “One More Day” (Moroder & Hong, 2016).
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dokumentasi. Selain itu, analisis data didukung dengan literatur dari sumber lain berupa buku dan jurnal penelitian terdahulu, yaitu buku karya Heryanto (2018) dan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2012).
Analisis data yang digunakan ialah analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif banyak digunakan untuk meneliti dokumen yang berupa simbol, gambar, dan teks untuk memahami suatu konteks sosial tertentu. Dalam analisis isi kualitatif, jenis data atau dokumen yang dianalisis berupa simbol, tanda, maupun gambar, yang disebut dengan istilah teks. Analisis isi kualitatif secara konseptual digunakan untuk mengidentifikasi, mengolah, menemukan, dan menganalisis dokumen untuk memahami maknanya (Bungin, 2017, h. 203). Analisis isi kualitatif dilakukan dengan pendekatan deduktif guna mengkategorikan objek yang diteliti. Pendekatan deduktif dilakukan dengan cara menurunkan analisis teori dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan hal yang akan diteliti. Isi dari tiga
video klip yang sudah dipilih dianalisis dengan melihat penggambaran bentuk-bentuk kekerasan dalam berpacaran dan sikap perlawanan yang dilakukan perempuan.
Sebuah penelitian memerlukan uji validitas agar teruji kebenarannya. Uji validitas penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber data dan triangulasi peneliti. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan hasil yang diteliti dari tiga video klip yang sudah dipilih dengan data-data yang diperoleh dari proses dokumentasi kepustakaan. Sedangkan triangulasi peneliti dilakukan dengan membandingkan temuan peneliti dengan peneliti lainnya.
HASIL
Hasil analisis isi tiga video klip tersebut menunjukkan bentuk kekerasan yang diterima dan perlawanan perempuan terhadap kekerasan yang diterima dalam hubungan berpacaran. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.
Kekerasan fisik adalah perilaku yang mengakibatkan korban terluka secara fisik. Kekerasan ini paling mudah dilihat akibatnya, tetapi banyak korban yang sengaja menutupinya. Pelaku biasanya menggunakan anggota tubuhnya atau alat tertentu untuk melukai korban (Manjorang & Aditya, 2015, h. 11). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terdapat dalam ketiga video klip tersebut adalah (1) mengguncangkan tubuh, (2) menghempaskan, (3) menarik, (4) melemparkan barang, (5) menjambak, dan (6) menampar.
Koko Sadewo & Rina Sari Kusuma. Perlawanan Perempuan terhadap ...
9
Bentuk kekerasan fisik berupa “mengguncangkan tubuh” di dalam video klip ditunjukkan saat pelaku memegang pundak atau lengan korban dan kemudian menggoyangkannya secara maju mundur. Hal ini menyebabkan tubuh korban menjadi tidak nyaman. Bahkan, pegangan yang sangat kencang dapat menyebabkan rasa sakit di daerah yang dipegang pelaku. Kekerasan ini terdapat dalam video klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012) yang menggambarkan pelaku memegang kedua bahu korban dan kemudian mengguncang tubuh korban. Hal ini menyebabkan tubuh korban merasa tidak nyaman, meskipun tidak menimbulkan luka yang fatal.
Bentuk kekerasan fisik berupa “menghempaskan” di dalam video klip ditunjukkan saat korban memegang tangan pelaku untuk mencegah supaya tidak pergi, tetapi pelaku melepaskan pegangan tersebut dengan kasar. Akibatnya, tubuh korban terpental dan terjatuh. Kekerasan ini terdapat di tiga video klip tersebut, namun terdapat perbedaan. Di video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010), saat korban memegang tangan pelaku, pelaku menghempaskan pegangan tersebut, sehingga tubuh korban terguncang. Di video klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012), saat korban menahan agar pelaku tidak pergi dengan cara memegang tangan pelaku, pelaku menghempaskan pegangan korban yang mengakibatkan korban terjatuh. Di dalam video klip “One More Day” (Moroder & Hong, 2016), saat pelaku hendak mendekati teman korban, korban tiba-tiba naik ke pundak pelaku dan mencoba untuk menghentikan pelaku dan
kemudian pelaku menghempaskan tubuh korban ke kasur.
Bentuk kekerasan fisik berupa “menarik” di dalam video klip terlihat ketika pelaku dengan paksa menarik anggota tubuh korban untuk mengikutinya. Hal ini tentu saja menyebabkan rasa sakit di daerah yang dipegang dan juga rasa tidak nyaman. Kekerasan ini terdapat dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010) yang menggambarkan pelaku menarik tangan korban agar korban mengikutinya pergi ke suatu tempat.
Bentuk kekerasan fisik berupa “melemparkan barang” di dalam video klip nampak ketika pelaku melemparkan jaket yang dikenakan ke arah korban. Hal tersebut menyebabkan timbulnya rasa sakit pada tubuh yang terkena lemparan jaket tersebut. Kekerasan ini terdapat dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010) dan “One More Day” (Moroder & Hong, 2016). Ada sedikit perbedaan dari dua video tersebut terkait arah lemparan. Video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010) menunjukkan bahwa pelaku melemparkan jaket ke arah korban dan tidak mengenai korban. Angin dari lemparan jaket tersebut yang mengenai korban. Sedangkan video klip “One More Day” (Moroder & Hong, 2016) menunjukkan bahwa pelaku melemparkan jaket ke arah korban dan mengenai korban.
Bentuk kekerasan fisik berupa “menjambak” di dalam video klip terlihat saat pelaku tiba-tiba datang dari belakang dan menarik rambut korban. Hal ini menyebabkan korban kaget dan tubuhnya tertarik ke belakang. Selain itu, korban juga
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
10
merasakan rasa sakit di bagian kepalanya. Kekerasan ini terdapat dalam video klip “One More day” (Moroder & Hong, 2016), saat korban sedang berjalan dengan temannya, tiba-tiba pelaku datang dari arah belakang dan menarik rambut korban.
Bentuk kekerasan fisik berupa “menampar” di dalam video klip ditunjukkan saat pelaku menampar pipi korban. Hal ini tentu saja menyebabkan rasa sakit di pipi hingga luka memar. Kekerasan ini terdapat dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010) dan “One More Day” (Park & Taek, 2010). Dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010), pelaku menampar korban secara berurutan hingga empat kali, sehingga menyebabkan luka memar di pipi korban. Sedangkan dalam video klip “One More Day” (Moroder & Hong, 2016), pelaku hanya menampar korban sebanyak satu kali dan tidak menyebabkan luka memar di pipi korban.
Kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap korban dalam contoh-contoh di atas berawal dari bentuk-bentuk yang kecil hingga besar. Kekerasan dalam bentuk kecil dapat berupa mengguncangkan tubuh, menghempas, dan menarik yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada korban dan rasa sakit di bagian tertentu. Kekerasan dalam bentuk besar dapat berupa menjambak dan menampar yang menyebabkan rasa sakit dan luka di daerah yang diserang.
Sementara itu, kekerasan emosional adalah kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan perkataan maupun mimik wajah. Hal ini bisa juga disebut juga kekerasan psikologis karena akibat dari kekerasan ini bukan luka fisik, namun
memengaruhi emosi atau psikis korban (Manjorang & Aditya 2015, h. 7). Bentuk-bentuk kekerasan psikologis dalam ketiga video klip tersebut adalah (1) berbicara dengan nada tinggi, (2) membentak, dan (3) mempermalukan orang di depan umum.
Bentuk kekerasan psikologis berupa “berbicara dengan nada tinggi” di dalam video klip memang tidak didengarkan melalui suara pelaku saat berbicara dengan nada tinggi, namun hal ini dapat terlihat dari mimik dan ekspresi wajah pelaku. Hal tersebut membuat korban merasa tidak nyaman karena berbicara dengan nada tinggi identik dengan ekspresi marah. Kekerasan ini dapat ditemukan di dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010) dan “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012). Di dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010), suara pelaku yang berbicara dengan nada tinggi dapat terdengar dengan jelas karena musik latar di awal video belum dimulai. Pelaku berbicara dengan korban saat di kafe dan menggunakan nada tinggi, sehingga menjadi perhatian orang di sekitarnya. Sementara itu, di dalam video klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012), adegan pelaku berbicara dengan nada tinggi tidak dapat terdengar, namun hal ini dapat terlihat dari ekspresi wajah pelaku. Pelaku berbicara menggunakan nada tinggi bersamaan dengan pelaku mengguncangkan tubuh korban. Dalam video klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012), pengambilan gambar difokuskan pada wajah pelaku dengan teknik medium close up untuk membuat adegan terlihat lebih riil, sehingga terlihat dengan jelas pelaku sedang berbicara dengan nada tinggi.
Koko Sadewo & Rina Sari Kusuma. Perlawanan Perempuan terhadap ...
11
Gambar 1 Ekspresi Pelaku saat Berbicara dengan Nada Tinggi
Sumber: Video Klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012)
Bentuk kekerasan psikologis berupa “membentak” di dalam video klip juga tidak didengarkan melalui suara pelaku saat membentak, tetapi hal ini dapat terlihat dari ekspresi wajah, mimik, dan bentuk mulut. Orang yang membentak identik dengan mulut terbuka lebar. Akibat yang ditimbulkan dari bentuk kekerasan ini adalah korban kaget dan takut karena pelaku sudah dapat dipastikan sedang marah. Kekerasan ini terdapat dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010) dan “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012). Di dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010), pelaku membentak korban sesaat setelah menampar korban. Hal ini dapat terdengar dengan jelas karena musik latar berhenti saat adegan tersebut. Dalam video klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012), pelaku membentak korban saat korban hanya diam saja ketika diajak berbicara dan suara pelaku membentak korban tidak diperdengarkan, tetapi dapat terlihat dari ekspresi wajah dan postur tubuh pelaku. Dalam video klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012), pengambilan gambar difokuskan dari samping dan long shoot sehingga dapat terlihat ekspresi dan postur tubuh pelaku yang menunjukan sedang membentak dan marah terhadap korban.
Gambar 2 Ekspresi dan Postur Tubuh Pelaku saat Membentak Korban
Sumber: Video Klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012)
Bentuk kekerasan psikologis berupa “mempermalukan orang di depan umum” di dalam video klip terlihat saat pelaku sedang berkelahi atau menyerang korban di tempat terbuka. Hal ini tentu saja menjadi perhatian orang di sekitarnya dan menyebabkan korban merasa tidak nyaman karena malu menjadi tontonan orang. Kekerasan ini terdapat dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010) dan “One More Day” (Moroder & Hong, 2016). Di dalam video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010), kekerasan ini terlihat saat pelaku dan korban duduk berhadapan di sebuah kafe dan kemudian pelaku memukul meja serta berbicara dengan nada tinggi, sehingga hal ini menyebabkan korban dan pelaku menjadi pusat perhatian orang di sekitar mereka. Setelah pelaku pergi, orang-orang membicarakan korban dan membuat korban menjadi malu, grogi, dan salah tingkah. Hal ini terlihat saat korban gemetar mengambil kacamatanya serta menabrak pelayan dan pintu saat akan keluar. Sedangkan di dalam video klip “One More Day” (Moroder & Hong, 2016), pelaku membuat korban merasa malu saat korban sedang berjalan di luar ruangan dengan temannya. Pelaku tiba-
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
12
tiba datang dari belakang dan menjambak rambut korban. Hal ini membuat korban malu karena pelaku menyerang di tempat terbuka dan saat bersama teman korban.
Tiga video klip tersebut menggambarkan dua sikap yang ditunjukkan perempuan (korban) terhadap kekerasan fisik dan kekerasan psikologis, yaitu menangis dan balas dendam. Tiga video klip tersebut menunjukkan adegan korban menangis setelah mendapatkan kekerasan karena korban merasa sedih dan menerima tindak kekerasan dari pelaku. Korban menangis karena rasa sedih, rasa sakit akibat kekerasan dari pelaku, maupun rasa sakit hati atau emosi. Sementara itu, adegan balas dendam ditunjukkan saat korban berniat membalas pelaku dengan cara korban. Tiga video klip tersebut menunjukkan bahwa balas dendam korban dilampiaskan dengan membunuh pelaku melalui cara yang berbeda-beda.
Video klip “Go Away” (Park & Taek, 2010) menggambarkan korban yang keesokannya bertemu dengan pelaku di lintasan balap mencoba balas dendam dengan cara menabrakkan mobilnya ke mobil pelaku. Hal ini memicu kecelakaan antara mereka berdua, sehingga mobil mereka berdua saling bertabrakan dan meledak. Korban berhasil membalaskan dendamnya meskipun korban juga kehilangan nyawanya. Selanjutnya, dalam video klip “Hit U” (E-Tribe & Hong, 2012), korban melakukan pembalasan dengan cara menembak pelaku menggunakan senjata api, bahkan korban tidak segan membunuh teman-teman pelaku yang menghalangi jalannya. Pada saat bertemu dengan pelaku, korban berpura-pura memeluknya lebih
dahulu, lalu menembak pelaku hingga tewas. Sementara itu, dalam video klip “One More Day” (Moroder & Hong, 2016), balas dendam korban dibantu oleh temannya. Awalnya, teman korban memukul menggunakan batu dan pelaku masih bisa bertahan. Setelah itu, pukulan kedua yang dilakukan teman korban tepat di kepala menyebabkan pelaku mulai lemah dan korban pun memukul kepala pelaku menggunakan botol. Teman korban pun kembali memukul kepala pelaku menggunakan botol hingga akhirnya pelaku tewas. Perempuan yang selama ini dianggap lemah oleh masyarakat ternyata dapat menjadi pelaku tindak kekerasan, hingga tidak segan untuk membunuh.
PEMBAHASAN
Ketiga video klip tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan adalah pihak laki-laki yang berperan sebagai pacar korban. Berpacaran merupakan bentuk hubungan di antara dua orang yang saling bersepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius dan intim. Keduanya memutuskan untuk saling bertemu, beraktivitas, dan mencurahkan perasaan bersama (Manjorang & Aditya, 2015, h. 2). Hal ini dapat dilihat pada setiap adegan dalam tiga video tersebut yang menunjukkan adegan flashback. Adegan tersebut menceritakan korban dan pelaku sedang mengadakan pertemuan, berduaan, menghabiskan waktu bersama hingga bermesraan. Adegan-adegan ini ditampilkan sesaat setelah kekerasan terjadi.
Ketiga video klip tersebut menunjukkan pula bahwa kekerasan psikologis memang terjadi lebih sedikit
Koko Sadewo & Rina Sari Kusuma. Perlawanan Perempuan terhadap ...
13
daripada kekerasan fisik, namun akibat yang dirasakan sama beratnya. Kekerasan psikologis dalam video klip tersebut terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik. Jadi, selain melakukan kekerasan fisik, pelaku juga melakukan kekerasan psikologis di saat yang sama.Kekerasan dalam Berpacaran
Kekerasan dalam berpacaran tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, selebritas pun mengalaminya. Hal ini ditunjukkan dengan beredarnya beberapa berita mengenai kekerasan dalam berpacaran, seperti artis Korea, Goo Hara, yang dilaporkan kekasihnya karena melakukan tindak kekerasan (Abeba, 2018). Sementara itu, di Indonesia, kekerasan dalam berpacaran juga pernah dialami oleh artis Ardina Rasti. Kasus ini terjadi saat Ardina Rasti menjadi pacar Eza Gionino. Tindakan kekerasan tersebut berlangsung setelah empat bulan mereka berpacaran (Elizabeth, 2018).
Kekerasan dalam video klip tersebut juga ditemukan dalam beberapa film di Indonesia. Film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” menunjukkan kaum perempuan menjadi korban kekerasan serta menerima kekerasan fisik dan psikis (Suharmanto, 2013, h. 76). Selain itu, Fabriar (2013, h. 39) menemukan bahwa Annisa, tokoh perempuan dalam film “Perempuan Berkalung Sorban”, mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari orang tua dan suaminya.
Penelitian tentang kekerasan dalam pacaran di Korea Selatan pernah dilakukan oleh Gover, Park, Tomsich, dan Jennings (2011). Studi tersebut mengambil
mahasiswa di Korea Selatan sebagai sampel. Gover, dkk. (2011, h. 1238) menemukan bahwa 24,3 persen perempuan dan 34,7 persen laki-laki melakukan serangan kecil terhadap pasangan mereka pada tahun sebelumnya serta 19,3 persen perempuan dan 8,1 persen laki-laki melakukan serangan berat. Selain itu, 34,3 persen responden melakukan penyerangan terhadap pasangan mereka di tahun sebelumnya.
Laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat akan dikecam apabila menangis. Sementara itu, masyarakat memperbolehkan perempuan menangis karena masyarakat menganggap bahwa perempuan lebih lemah dan emosional dibanding laki-laki. Perempuan pada umumnya dicitrakan sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah, pasif, lemah, dan subjektif. Akibatnya, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak penting dan tidak sempurna, sehingga perempuan selalu dieksploitasi, tidak dianggap, dan diposisikan sebagai pihak yang hanya perlu mengurusi permasalahan domestik saja. Perempuan sering kali menghadapi tindakan kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan ekonomi) karena laki-laki memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan perempuan. Budaya patriarki ini membuat perempuan tidak memiliki kedaulatan atas dirinya (Nurhayati, 2012, h. 148).
Sementara itu, penelitian Kusuma (2017, h. 56) menunjukkan bahwa tokoh perempuan mendapatkan agresi-agresi (verbal, fisik, psikis, dan seksual) dari tokoh laki-laki. Laki-laki yang melakukan tindak perkosaan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
14
dan pelecehan terhadap perempuan lebih menunjukkan kekuasaan dan dominasinya, bukan hanya terkait persoalan seksual semata. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan adalah representasi dari sistem kapitalistik. Perempuan menjadi budak proletar yang tidak berdaya dan tidak dapat mengubah situasi.
Penelitian Veridiana (2013, h. 117) menunjukkan bahwa munculnya suku perempuan merupakan salah satu wujud gerakan feminis yang menentang patriarki. Bentuk perlawanan dari perempuan dalam film “Lost in Papua” ditunjukkan dengan cara melakukan tindakan pelecehan seksual hingga kekerasan fisik. Pandangan yang menunjukkan bahwa kaum perempuan dilihat sebagai kanibal membuktikan perempuan dapat menjadi pelaku kekerasan dan lebih kuat daripada laki-laki. Sedangkan penelitian Prabowo (2012, h. 9) menunjukkan bahwa perempuan menjadi pelaku tunggal tindak kekerasan dan penentu akhir cerita. Perempuan dalam film “Dara” digambarkan melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap laki-laki yang dikencaninya.
Kekerasan di media atau video klip berbeda dengan kekerasan di dunia nyata. Di media, kekerasan yang terjadi hanya rekaan untuk menunjang jalan cerita yang diperankan oleh beberapa tokoh melalui alur ceritanya. Adegan terlihat nyata karena sudut pengambilan gambar dan efek-efek lain. Luka yang dihasilkan pun bukan luka sebenarnya, melainkan luka buatan atau tata rias. Namun demikian, jika khalayak sering terpapar hal tersebut, maka ada dampak yang negatifnya, yaitu khalayak
menjadi terbiasa melihat tindak kekerasan serta menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa dan ikut menirunya. Lebih jauh, dampak paling buruk adalah kepedulian terhadap korban tindakan kekerasan semakin luntur dan sirna karena kekerasan dianggap sebagai hal yang pantas dilakukan (Mahmudah, 2013, h. 58).Sikap Perempuan terhadap Kekerasan
Perempuan dapat menyikapi kekerasan fisik dan psikologis dengan menangis dan membalas dendam. Menangis adalah proses mengeluarkan air mata. Menangis dapat menenangkan pikiran setelah adanya kekecewaan atau masalah (Simbolon, 2015, h. 34). Menurut Nelson (dalam Robinson, Hill, & Kivlighan, 2015, h. 382), ada tiga tipe menangis. Pertama, inhibited cry, yaitu tangisan yang tidak ingin dikeluarkan atau seseorang menahan air mata mereka agar tidak keluar. Kedua, protest cry, yaitu tangisan yang muncul untuk menghindari atau membatalkan kehilangan yang dirasakan, menunjukkan penolakan untuk menerima kerugian, kemarahan atas kehilangan, atau menyalahkan orang lain atas kehilangan. Ketiga, despair cry, yaitu tangisan yang mewakili kesedihan dan penerimaan kerugian, menunjukkan penerimaan, kesedihan, atau pengakuan kesedihan. Ketiga video klip tersebut menunjukkan adegan korban menangis setelah mendapatkan kekerasan. Tangisan korban tersebut masuk dalam jenis despair cry karena korban merasa sedih dan menerima tindakan kekerasan dari pelaku.
Chaplin (dalam Dewiana, 2011, h. 26) mengartikan dendam sebagai perlawanan untuk membalas ketidakadilan, baik nyata
Koko Sadewo & Rina Sari Kusuma. Perlawanan Perempuan terhadap ...
15
maupun khayalan. Balas dendam merupakan sebuah siklus yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan. Korban melakukan pembalasan untuk mencapai kebahagian mereka atau membalas perbuatan pelaku, tetapi di sisi lain pelaku juga akan menjadi korban ketika mendapatkan pembalasan dari korban. Selain berdampak negatif, balas dendam memiliki dampak positif, yaitu mengembalikan harga diri, mengembalikan perasaan pelaku balas dendam yang terluka, memberi pembelajaran kepada pelaku penyerangan, mengembalikan rasa keadilan, dan mengembalikan harga diri pelaku pembalasan (Matanggaran, 2015, h. 11-12).
Ketiga video klip yang menjadi sumber data menunjukkan bahwa balas dendam dilakukan untuk mengembalikan rasa keadilan karena pelaku melakukan kekerasan secara sewenang-wenang. Pelaku juga telah membuat harga diri korban hilang karena korban hanya bisa diam dan menerima perlakuan dari pelaku. Kekerasan ini terjadi ketika pelaku berbuat kekerasan secara fisik dan menggunakan ancaman dalam rangka melukai, mengintimidasi, dan mengontrol korban (Martha, 2013, h. 3).
Media membuat kekerasan menjadi biasa karena terlalu sering menghadirkan sesuatu yang umum dan normal dalam dunia tontonan. Media mengatur pesannya sedemikian rupa, sehingga penonton terbiasa untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Keyakinan pemirsa mengenai kekerasan menjadi lebih kuat karena semua gambar dan teks diatur sedemikian rupa. Tujuan utama penayangan adegan kekerasan dalam media adalah untuk memperoleh rating
program tinggi dan sukses di pasaran. Sedangkan aspek pendidikan dan efek traumatis penonton tidak dipertimbangan oleh media yang menampilkan adegan kekerasan (Haryatmoko, 2011, h. 121).
Kaum perempuan selain melakukan perlawanan secara fisik juga melakukan perlawanan dengan cara melaporkan pelaku kekerasan. Hal ini terjadi pada artis Indonesia Ardina Rasti yang melaporkan Eza Gionino ke pihak kepolisian dan Eza Gionino pun sudah dinyatakan bersalah. Dalam kasus tersebut, Ardina Rasti melengkapi laporannya dengan bukti-bukti lengkap, seperti foto-foto luka yang dialaminya dan rekaman suara saat terjadinya penyerangan (Elizabeth, 2018). Selain itu, artis Korea, Goo Hara, melaporkan kekasihnya karena pengancaman dan kejahatan seksual. Dalam kasus ini, Goo Hara mengakui kesalahannya, namun dia juga ingin pelaku dihukum atas kesalahannya. Goo Hara pun melaporkan pelaku atas paksaan dan ancaman, serta pelanggaran atas kasus kejahatan seksual (Abeba, 2018).
Video klip menampilkan pesan berupa ekspresi berbagai fenomena yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat. Kekerasan dalam hubungan berpacaran merupakan kekerasan yang terjadi antarindividu melalui hubungan yang intim. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga video klip tersebut memuat pesan tertentu. Pesan tersebut adalah tindakan kekerasan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terjadi dalam ranah rumah tangga saja, tetapi juga dalam hubungan berpacaran. Pelaku tindak kekerasan masih didominasi oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
16
menjadi korbannya. Meskipun demikian, perempuan sebagai korban juga berani melakukan perlawanan terhadap pihak laki-laki dengan cara balas dendam. Oleh karena itu, kekerasan saat ini dapat terjadi kapan pun dan perempuan yang dianggap lemah dapat memberikan sikap untuk melawan.
SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua bentuk kekerasan dalam berpacaran yang diterima oleh perempuan selaku korban, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik yang ditemukan berupa guncangan, hempasan, tarikan, lemparan barang, jambakan, dan tamparan. Kekerasan psikologis atau emosional dapat berupa perilaku berbicara dengan nada tinggi, bentakan, dan mempermalukan orang di depan umum.
Stereotip yang berkembang di masyarakat menganggap perempuan lemah dan mudah menangis, namun tokoh perem-puan dalam penelitian ini selaku korban ternyata dapat mendobrak stereotip tersebut dan bertindak membela diri atas kekerasan yang menimpanya. Pada mulanya, dalam video klip, sikap perempuan yang ditunjukkan hanya diam, menerima kekerasan dari pelaku, dan menangis. Namun, selanjutnya mereka bertindak sebagai penentu akhir cerita dan berhasil melakukan perlawanan kepada pelaku dengan cara balas dendam. Mereka tidak hanya melukai, tetapi juga sampai membunuh pelaku. Perempuan berhasil membuktikan bahwa mereka tidak lemah. Mereka menerima kekerasan, namun mereka juga bisa bertindak menjadi pelaku kekerasan.
Video Musik K-pop menggambarkan bahwa kaum perempuan melakukan perlawanan hingga menjadi lebih unggul dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan oleh mulai lunturnya pengaruh Konfusianisme di Korea yang sangat lekat dengan budaya patriarki. Kaum perempuan Korea melalui K-pop pun mulai menunjukkan dominasinya. Ketiga pesan video klip tersebut disampaikan melalui girlband dari Korea. Mereka ingin menunjukkan bahwa sekarang kaum perempuan berani melawan kekerasan.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat pandangan khalayak menggunakan pendekatan resepsi penonton tentang perlawanan perempuan terhadap kekerasan dalam hubungan berpacaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat khalayak mengenai perlawanan perempuan terhadap kekerasan dalam hubungan berpacaran berdasarkan cara pandang yang beragam dari masyarakat.
DAFTAR RUJUKAN
Abeba, R. A. (2018). Goo Hara blak-blakan soal tudingan menganiaya pacar. tabloidbintang.com. <https://www.tabloidbintang.com/asia/korea/read/112597/goo-hara-blakblakan-soal-tudingan-menganiaya-pacar>
American Psychological Association. (1996). Violence and the family: Report of the American Psychological Association presidential task force on violence and the family. <http://www.nnflp.org/apa/APA_task_force.htm>
Armando, G. (2015). Upaya jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
Bancin, E. L., & Nurani, N. (2018, Maret 8). 9 lagu k-pop yang berbicara soal girls power. kumparan.
Koko Sadewo & Rina Sari Kusuma. Perlawanan Perempuan terhadap ...
17
com. <https://kumparan.com/kumparank-pop/9-lagu-k-pop-yang-berbicara-soal-girls-power/full>
Bungin, B. (2017). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Depok, Indonesia: Rajawali Pers.
Centers for Disease Control and Prevention (2020). Preventing Teen Dating Violence. <https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html>
Choi, J. B., & Maliangkay, R. (Eds). (2014). K-pop–the international rise of the Korean musik industry. London, UK: Routledge.
Dewiana, R. A. (2011). Analisis trauma dan dendam Hannibal Lecter dalam novel Hannibal Rising karya Thomas Harris. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
E-Tribe (Produser), & Hong, W. K. (Sutradara). (2012). Hit U [Music Video]. Korea Selatan: Happyface Entertainment. <https://www.youtube.com/watch?v=fj1pw5pdexU>
Effendy, H. (2002). Mari membuat film: Panduan menjadi produser. Jakarta, Indonesia: Yayasan Konfiden.
Elizabeth, J. (2018, April 22). Pernah trauma, 7 artis ini sempat alami kekerasan saat pacaran. POPBELA.com. <https://today.line.me/id/pc/article/Pernah+Trauma+7+Artis+Ini+Sempat+Alami+Kekerasan+Saat+Pacaran-w5j09R>.
Fabriar, S. R. (2013). Potret perempuan dalam film Perempuan Berkalung Sorban. SAWWA, 9(1), 27-44.
Fakih, M. (1999). Analisis gender & transformasi sosial. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
Farnisari, M., & Sudrajat, A. (2013). Bias gender dalam film seri Korea “Sungkyunkwan Scandal”. Paradigma, 1(2), 8-15.
Febriani, A. R. N. (2016). Analisis komunikasi interpersonal pacaran jarak jauh. Skripsi. Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia.
Gover, A. R., Park, M. R., Tomsich, E. A., & Jennings, W. G. (2011). Dating violence perpetration and victimization among South Korean college
students: A focus on gender and childhood maltreatment. Journal of Interpersonal Violence, 26(6), 1232-1263.
Hardjana, A. M. (2003). Komunikasi intrapersonal & interpersonal. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
Haryatmoko. (2011). Etika komunikasi: Manipulasi media, kekerasan, dan pornografi. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
Heryanto, A. (2018). Identitas dan kenikmatan: Politik budaya layar Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.
Khaninah, A. N., & Widjanarko, M. (2017). Perilaku agresif yang dialami korban kekerasan dalam pacaran. Jurnal Psikologi, 15(2), 151-160.
Khairani, I. (2018). Perempuan Korea dalam film serial drama Korea “jewel in the palace”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
Kistler, M. E., & Lee, M. J. (2009). Does exposure to sexual hip-hop music videos influence the sexual attitudes of college students? Mass Communication and Society, 13(1), 67–86.
Kriyantono, R. (2006). Teknis praktis riset komunikasi. Jakarta, Indonesia: Pancaran Prenadamedia Group.
Kusuma, R. S. (2017) Gender in Asian movie: Narrative deconstruction analysis of rashomon. Asian Journal of Media and Communication, 1(1), 51-62.
Mahardika, T. F. (2010). Representasi kekerasan terhadap laki-laki dalam video klip lagu “janji janji” (Studi semiotik tentang representasi kekerasan terhadap laki-laki dalam video klip lagu “janji janji” dipopulerkan oleh Agnes Monica). Skripsi. Universitas Pembangungan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.
Mahmudah, D. (2013). Tayangan kekerasan di televisi dan terpaannya pada khalayak masyarakat. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, 4(1), 53-60.
Manjorang, A. P., & Aditya I. (2015). The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia. Jakarta, Indonesia: VisiMedia.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 1-18JurnalILMU KOMUNIKASI
18
Martha, A. E. (2013). Proses pembentukan hukum kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta, Indonesia: Aswaja Pressindo.
Matanggaran, V. (2015). Balas dendam pada suku Bugis dan Makassar. Skripsi. Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia.
Moroder, G. (Produser), & Hong, W. K. (Sutradara). (2016). One More Day [Music Video]. Korea Selatan: Starship Entertainment. <https://www.youtube.com/watch?v=E4TygUpWUTQ>
Nurhayati, E. (2012). Psikologi perempuan dalam berbagai perspektif. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
Park, S., & Kim, S. H. (2018). The power of family and community factors in predicting dating violence: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 40, 19-28.
Park, T. (Produser), & Taek, C. E. (Sutradara). (2010). Go Away [Music Video]. Korea Selatan: YG Entertainment. <https://www.youtube.com/watch?v=3yW13T2sfKg>
Poriskova, V. K. (2012). Pengaruh terpaan Soompi.com terhadap sikap komunitas Jogja K-pop Family (studi deskriptif-kuantitatif pengaruh terpaan Soompi.com terhadap sikap komunitas Jogja Kpop Family tentang budaya pop Korea). Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
Prabowo, T. L. (2012). Penggambaran perempuan sebagai pelaku kekerasan dalam film Dara. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
Putri, R. R. (2012). Kekerasan dalam berpacaran. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
Richards, T. N., Branch, K. A., & Ray, K. (2014). The impact of parental and peer social support on dating violence perpetration and victimization among female adolescents: A longitudinal study. Violence and Victims, 29(2), 317–331.
Rhodes, N., Potocki, B., & Masterson, D. S. (2018). Portrayals of intimate partner violence in music videos: Effects on perceptions of IPV warning signs. Media Psychology, 21(1), 137-156.
Robinson, N., Hill, C. E. & Kivlighan, D. M. (2015). Crying as communication in psychotherapy: The influence of client and therapist attachment dimensions and client attachment to therapist on amount and type of crying. Journal of Counseling Psychology, 62(3), 379-392.
Saroh, M. (2016, September 5): Kekerasan dalam pacaran. tirto.id. <https://tirto.id/kekerasan-dalam-pacaran-bGQf>
Setiansah, M. (2009). Politik media dalam membingkai perempuan (Analisis framing pemberitaan kasus video porno Yahya Zaini dan Maria Eva di harian umum Kompas dan Suara Merdeka). Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(2), 137-154.
Simbolon, I. (2015). Gejala stres akademis mahasiswa keperawatan akibat sistem belajar blok di fakultas ilmu keperawatan X Bandung. Jurnal Skolastik Keperawatan. 1(1), 29-37.
Soroptimist International of the Americas. (2013). Teen dating violence: Learn about teen dating violence, its risk-factors and consequences, as well as preventative efforts. Philadelphia, USA: Soroptimist International of the Americas.
Sugarman, D. B., & Hotaling, G. T. (1989). Violent men in intimate relationships: An analysis of risk markers. Journal of Applied Social Psychology, 19(12), 1034-1048.
Suharmanto, A. (2013). Representasi kekerasan dalam rumah tangga pada film 7 hati 7 cinta 7 wanita. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.
Tisyah, D. W., & Erna, R. (2013). Analisis kekerasan pada masa pacaran (dating violence). Sociologie, 1(1), 1-9.
Warkentin, J. B. (2008). Dating violence and sexual assault among college men: Co-occurrence, predictors, and differentiating factors. Disertasi. Ohio University, Ohio.
Wulandari, O. (2016). Pemeliharaan hubungan antara orang tua yang bercerai dan anak (Studi kualitatif deskriptif komunikasi antarpribadi antara orang tua yang memiliki hak asuh dengan anaknya). Komuniti, 8(1), 3-18.
19
Analisis Semiotika Kritik Sosial dalam Balutan Humorpada Komik Faktap
Alifia Hanifah LuthfiUniversitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57196Email: [email protected]
Abstract: Komik Faktap as strip comics take stories about social issues that occur in society using humorous stories. This study uses Roland Barthes’s semiotic analysis method with the theory of social criticism and humor in the media, which aims to find humor as a social critique of Indonesian Parliament (DPR RI). The research objects consist of six episodes which divided into two categories, namely: criticism of members of the Indonesian Parliament and criticism of the policies of the Indonesian Parliament. The result shows that humor is conveyed with allusion techniques, satire, parody of events, analogies, and apologism.
Keywords: humor, semiotics, social criticism, strip comic
Abstrak: Komik Faktap merupakan komik strip yang mengangkat cerita mengenai isu sosial yang terjadi di masyarakat dan dikemas menggunakan cerita humor. Penelitian ini memakai metode analisis semiotika Roland Barthes dan menggunakan teori kritik sosial dan humor dalam media, serta bertujuan untuk mengetahui humor sebagai kritik sosial terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Komik yang menjadi objek penelitian terdiri atas enam episode yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu: kritik terhadap anggota DPR RI dan kritik terhadap kebijakan DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humor disampaikan dengan teknik allusion, satire, parodi kejadian, analogi, dan apologisme.
Kata Kunci: humor, komik strip, kritik sosial, semiotika
Kritik di Indonesia pada era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru memiliki sejarah kelam. Seseorang yang mengkritik pemerintah akan dipidanakan, dicekal, bahkan diasingkan dari lingkungan sosial. Kasus pencekalan juga menimpa para seniman di masa Orde Baru, seperti intimidasi yang dialami W. S. Rendra, pembubaran pementasan Teater Koma, dan pembubaran pementasan “Marsinah Menggugat” karya Ratna Sarumpaet (Apriyono, 2015). Tindakan-tindakan
pencekalan tersebut disebabkan oleh kandungan kritik terhadap pemerintah dalam karya para seniman dan hal tersebut dianggap dapat mengancam kekuasaan pemerintah.
Situasi berbeda terjadi saat Orde Baru berakhir. Masyarakat memiliki kebebasan dalam menyampaikan gagasan berupa saran maupun kritik yang ditujukan kepada pemerintah melalui berbagai medium komunikasi. Sanjaya (2013, h. 189) mengemukakan bahwa kritik sosial
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
20
merupakan praktik komunikasi yang bertujuan mengontrol jalannya suatu sistem di masyarakat. Wujudnya berupa pendapat dalam bentuk tulisan, simbol, lisan, maupun gambar.
Informasi mengalir sangat cepat pada era multimedia. Pergeseran praktik komunikasi sebagai akibat dari konvergensi media membuat media sosial menjadi wadah baru bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi mengenai isu sosial. Hal tersebut mengakibatkan industri media saling berlomba dalam menghasilkan informasi terbaru (Haryanto, 2014, h. 211-212).
Konvergensi media juga membuat komik bergeser dari media cetak ke media digital. Komik digital lebih dikenal dengan istilah webcomics. Webcomics merupakan media baru yang bersifat dua arah, sehingga mendorong pembentukan opini publik dalam wujud kritik maupun saran yang disampaikan melalui cerita komik strip. Kritik dalam komik digital tidak hanya berfokus pada masalah politik, tetapi juga memberikan kritik terhadap masalah sosial, seperti ekonomi, budaya, dan ketimpangan sosial (Putri, 2018, h. 2).
Komik, seperti halnya televisi dan radio, juga merupakan salah satu medium yang dapat memberikan berbagai macam informasi kepada pembacanya (Augereau, Iwata, & Kise, 2018, h. 1-2). Hal ini membuat komikus lebih bebas mengungkapkan ide pada komiknya. Di sisi lain, komik juga berfungsi sebagai medium penyampai kritik terhadap permasalahan sosial.
Komik dikelompokkan menjadi dua, yaitu comic-strip dan comic-books. Gibbons dan Varnum (dalam Tatalovic,
2009, h. 2) mengungkapkan bahwa komik strip merupakan rangkaian cerita bergambar yang disusun secara berseri. Sedangkan comic-books atau buku komik merupakan kumpulan cerita bergambar yang memuat satu atau lebih judul dan tema cerita (Sobur, 2013, h. 137). Awalnya, komik strip merupakan media hiburan. Teks dan gambarnya dikemas secara sederhana. Komik pun berkembang dalam wacana, narasi, dan gambar, serta mengalami peningkatan kualitas cerita. Komik strip yang awalnya diterbitkan di majalah dan surat kabar sering kali membatasi kebebasan berekspresi komikus untuk menuangkan imajinasinya. Hal tersebut terjadi karena proses produksinya sarat kepentingan pemilik media, terutama saat komik mengangkat permasalahan sosial.
Sementara itu, komik yang beredar melalui internet memiliki karakter yang berbeda dibanding komik yang didistribusikan di majalah dan surat kabar. Komik-komik tersebut menjadi ajang bagi komikus untuk menuangkan ide (Iliescu, 2016, h. 21). Komik digital pun mampu membuat komikus menjangkau segmen pembaca lebih luas.
Webcomics yang sedang populer saat ini adalah Line Webtoon. Line Webtoon merupakan komik dalam jaringan (daring) yang berasal dari Korea Selatan. Kehadiran Line Webtoon disambut baik oleh pasar Indonesia. Agnes (2016) mencatat bahwa pada tahun 2015 Indonesia menjadi pasar terbesar dengan enam juta pengguna aktif yang sudah mengunduh Line Webtoon dari total 35 juta pengguna di seluruh dunia.
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
21
Konten Line Webtoon sangat beragam, mulai dari genre untuk remaja hingga konten cerita yang bermuatan dewasa.
Salah satu komik strip dari Indonesia yang cukup populer adalah Komik Faktap. Komik yang bergenre komedi ini dirilis pada 8 Oktober 2016 dengan jadwal publikasi setiap Kamis dan Minggu. Distribusi komik ini dilakukan melalui Line (lewat Line Webtoon) dan Instagram. Komik strip ini telah mempunyai lebih dari 250 episode dengan rating cukup tinggi, yaitu 9,03 (Komik Faktap, 2019).
Tema dalam komik strip tersebut adalah isu sosial yang terjadi di kalangan masyarakat biasa, tokoh terkenal, seperti selebritas, hingga pejabat pemerintahan. Komikus pada komik strip ini tidak jarang menyisipkan kritik dalam isu yang dibahasnya. Pesan yang berupa kritik sosial pada Komik Faktap disampaikan melalui cerita humor.
Kritik sosial merupakan sebuah inovasi sosial yang dapat menjadi sarana komunikasi gagasan baru sekaligus mengevaluasi gagasan lama untuk perubahan sosial. Walzer dalam Qusairi (2017, h. 206) mengemukakan bahwa kritik sosial merupakan aktivitas sosial berupa pengamatan dan upaya membandingkan dengan cermat tentang perkembangan kualitas masyarakat. Tujuan dari kritik sosial adalah mewujudkan perubahan sosial, emansipasi, dan pencerahan (Supraja, 2018, h. 93).
Kritik sosial dapat diungkapkan melalui beberapa media, misalnya menggunakan media tradisional, seperti ungkapan sindiran
antarindividu, pertunjukan yang berkonteks komunikasi publik, seni dalam sastra, maupun media massa. Seiring perkembangan zaman, media baru, seperti media sosial dan blog, juga dapat dimanfaatkan sebagai medium kritik.
Masyarakat pada era digital meman-faatkan media sosial untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk mengungkapkan kritik atas kejadian yang dianggap menyimpang atau tidak wajar. Horkheimer (dalam Suseno, 2013, h. 209) mengemukakan bahwa tindakan manusia dapat membuat dan mengubah realitas sosial. Teori kritis mampu memberikan kritik terhadap realitas sosial karena teori kritis dapat memahami kemungkinan untuk dapat mengubah keadaan melalui pengamatan terhadap dinamika yang sedang terjadi.
Humor merupakan salah satu cara yang dapat dipakai seseorang untuk menyampaikan gagasan dan pikirannya. Humor juga digunakan untuk mengungkapkan ajakan yang dapat menghibur dan menimbulkan simpati. Humor merupakan kegiatan yang identik dengan lelucon untuk merangsang seseorang agar tertawa (Krissandi & Setiawan, 2018, h. 47). Humor tidak memutuskan benar atau salah karena humor tidak memerlukan pembuktian. Hal terpenting dalam humor adalah lucu dan tidak lucu (Sudarmo, 2014, h. 192). Humor yang telah menyebar di masyarakat mempunyai berbagai bentuk dan fungsi. Fungsi humor antara lain sebagai sarana hiburan, pendidikan, dan protes sosial.
Humor merupakan salah satu seni kritik yang melibatkan pembaca untuk mengenali peristiwa yang diangkat dalam ceritanya. Humor dianggap berhasil jika pembaca dapat menertawakan cerita yang
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
22
disajikan (Colletta, 2009, h. 859-864). Cerita humor dapat menggambarkan suatu kejadian sosial yang sering kali berbentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan penguasa (Arslan, 2014, h. 96-98). Salah satu bentuk humor yang digunakan untuk menyampaikan kritik adalah humor satire. Humor satire merupakan humor yang digunakan oleh penulis untuk mengkritik dengan cara mengejek atau mempermalukan seseorang atau sesuatu (Berger dalam Sugiarto, 2016, h. 6). Kritik dalam bentuk humor pada komik diekspresikan melalui parodi karakter yang mudah dikenali oleh pembacanya. Dialog yang menggunakan bahasa santai dan mengundang tawa membuat kritik lebih mudah diterima.
Penelitian ini menganalisis fenomena Komik Faktap menggunakan semiotika. Semiotika merupakan ilmu yang mengkaji tanda (Sobur, 2013, h. 15). Semiotika mempelajari tanda dan semua yang berhubungan dengannya, termasuk fungsi dan hubungannya dengan tanda lain (Kriyantono, 2006, h. 265). Van Zoest (1993) mengungkapkan bahwa tanda bukan hanya berupa suatu benda saja, tetapi juga suatu kejadian, tidak adanya kejadian, kebiasaan, dan segala sesuatu yang dapat diamati. Semiotika merupakan sebuah kerangka analisis yang membedah tanda atau kata-kata dalam bahasa yang berkaitan dengan tanda-tanda lain. Tanda adalah objek fisik yang memiliki makna. Setiap tanda terdiri dari penanda (signifier) dan petanda (signified) (Fiske, 2012, h. 73-76).
Sementara itu, Barthes (dalam Sobur, 2013, h. 46) mengemukakan bahwa semiotika merupakan pengembangan dari tingkatan dua tataran makna, yaitu tingkat denotatif dan konotatif. Denotatif merupakan tingkatan pertama yang biasanya dimaknai secara harfiah. Denotatif terdiri dari penanda (signifier) dan petanda (signified). Hal ini menyebabkan tataran denotatif merupakan makna yang paling jelas dan nyata dari sebuah tanda. Sedangkan konotatif merupakan tingkatan kedua yang menggambarkan proses interaksi yang terbentuk ketika tanda bersatu dengan emosi dan perasaan pembaca beserta nilai budaya yang dianutnya (Wibowo, 2013, h. 213).
Kerangka pemikiran Barthes menun-jukkan bahwa konotasi berkaitan erat dengan operasi ideologi. Barthes menyebutnya dengan istilah mitos. Level konotasi menjelaskan praktik mitos tersebut. Mitos merupakan gambaran dari budaya tertentu yang menjelaskan atau memahami beberapa aspek yang ada pada realitas atau alam. Barthes menganggap mitos sebagai budaya yang menyangkut cara berpikir atau memahami sesuatu (Fiske, 2012, h. 144). Barthes memandang mitos dan ideologi bekerja sama untuk menginterpretasikan hal tertentu dari individu yang khas dengan menaturalkannya secara historis (Sobur, 2013, h. 183).
Eksistensi sebuah tanda terjaga jika pengguna memakai tanda tersebut saat berkomunikasi dan memelihara mitos nilai-nilai yang dikonotasikan dari budaya mereka. Hubungan tanda dengan mitos dan konotasi bersifat ideologis. Oleh karena itu, ketika tanda membuat suatu mitos dan
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
23
nilai dalam bentuk konkret yang dikenal secara luas, penggunaan tanda tersebut memberikan kehidupan pada ideologi. Di sisi lain, ideologi juga dapat membentuk persepsi suatu kelompok terhadap sebuah tanda (Fiske, 2012, h. 276-280).
Teori Barthes mengenai semiotika secara harfiah merupakan pengembangan dari teori bahasa Ferdinand de Saussure. Inti dari teorinya adalah ide tentang dua tatanan signifikasi. Signifikasi tahap pertama mengkaji tentang hubungan antara signifier dan signified yang disebut dengan istilah denotatif, yaitu makna harfiah dari tanda itu. Signifikasi tahap kedua adalah konotasi, yaitu makna yang subjektif. Pada tahap selanjutnya, tanda bekerja melalui mitos yang merupakan lapisan signified dan mempunyai makna paling dalam (Vera, 2014, h. 27-28).
Penelitian terdahulu yang membahas mengenai komik dengan kerangka analisis semiotika adalah “Politisasi dalam Ragam Bahasa Komik Mice Cartoon (Analisis Semiotika Roland Barthes)” oleh Nursalim (2015, h. 62-78). Penelitian tersebut membahas komikus Mice Cartoon yang menggunakan aspek politik dalam komik yang dibuatnya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa komikus dalam dialog kartun yang dibuatnya menyampaikan pandangan tentang kehidupan sekitar dan memberikan sindiran terhadap pemerintah melalui bahasa politik. Oleh karena itu, pendekatan semiotika Barthes diperlukan guna mengetahui secara mendalam hubungan yang terjadi antara komik dan realitas kehidupan.
Penelitian lain mengenai kritik sosial dilakukan oleh Sugiwardana (2014, h. 86-96). Penelitian yang berjudul “Pemaknaan Realitas serta Bentuk Kritik Sosial dalam Lirik Lagu Slank” tersebut menjelaskan kritik sosial dalam lirik lagu Slank yang ditujukan untuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lirik lagu merupakan hasil interpretasi pengarang saat melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Lirik lagu “Seperti Para Koruptor” karya Slank merupakan salah satu bentuk esensi dari kritik sosial.
Sementara itu, penelitian ini memilih cerita yang memiliki kategori kritik terhadap anggota DPR RI. Komikus pada Komik Faktap menggambarkan beberapa tokoh yang memiliki pengaruh terhadap orang lain. Tokoh tersebut merupakan gambaran dari anggota DPR RI yang merasa berkuasa. Beberapa tokoh lain merupakan gambaran dari tokoh masyarakat dan imajinasi komikus yang melakukan kritik terhadap DPR RI. DPR RI dipilih karena anggota lembaga tersebut merupakan wakil rakyat yang seharusnya berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan tidak memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.
Kinerja DPR RI periode 2014-2019 dianggap tidak mengalami perubahan dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Hal tersebut diketahui dari kurang produktifnya anggota DPR RI dalam mengambil inisiatif membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
24
menyejahterakan masyarakat (Solihah & Witianti, 2016, h. 292-301). Selain itu, menurut Fajar (2018), kebijakan DPR RI menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan pada pembuatan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3. Pelaksanaan kebijakan tersebut dianggap membuat anggota DPR RI kebal terhadap hukum, sekalipun mereka tersandung kasus korupsi. Hal tersebut membuat perilaku dan kebijakan DPR RI sering kali menjadi sorotan masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi kinerja mereka.
Komik Faktap, sebagai objek penelitian ini, merupakan media hiburan yang menyampaikan kritik terhadap kondisi sosial di atas. Kritik yang dikemas melalui gambar dan dialog tersirat tersebut tidak menampilkan secara langsung pihak yang menjadi sasaran kritik. Hal yang dimaksud dapat diketahui melalui berita mengenai kejadian yang sedang dibahas dalam episode tersebut.
METODE
Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode semiotika Roland Barthes. Semiotika merupakan cabang ilmu yang mengkaji tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya (Zoest dalam Lantowa, Marahayu, & Khairussibyan, 2017, h. 1). Semiotika Barthes menggunakan dua tahap pemahaman. Tahap pertama adalah hubungan petanda dan penanda dalam denotasi. Sedangkan tahap kedua
adalah konotasi yang menggambarkan proses interaksi yang terjalin antara emosi dan perasaan dari pembaca serta nilai budaya yang dianutnya.
Objek penelitian ini adalah Komik Faktap yang dipublikasikan melalui Line Webtoon dan diunggah pada kurun waktu Januari 2017 hingga April 2018. Kurun waktu tersebut dipilih karena memiliki episode yang sesuai dengan kriteria peneliti, yaitu episode dengan cerita humor yang mengandung kritik terhadap DPR RI.
Kriteria tersebut telah menuntun peneliti mendapatkan enam episode. Pertama, episode 35 yang berjudul “Ngemis” (28 Januari 2017). Kedua, episode 105 yang berjudul “Mukjizat” (30 September 2017). Ketiga, episode 115 yang berjudul “Lapor” (4 November 2017). Keempat, episode 119 yang berjudul “Papa” (18 November 2017). Kelima, episode 146 yang berjudul “Kritik” (21 Februari 2018). Keenam, episode 163 yang berjudul “Untung” (25 April 2018).
Peneliti menggunakan sumber data primer, yaitu Line Webtoon sebagai penerbit Komik Faktap. Pada tahap konotatif, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder, yaitu referensi dari berbagai studi pustaka. Objek yang dianalisis adalah dialog dan gambar pada Komik Faktap. Analisis dilakukan dengan memilah data yang telah dikategorikan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Analisis dilakukan dengan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk menginterpretasikan data secara denotatif dan konotatif, serta mengungkapkan mitos keenam episode Komik Faktap tersebut.
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
25
HASIL
Episode 35: “Ngemis”
Gambar 1 Episode “Ngemis”Sumber: Komik Faktap (2017a)
Episode “Ngemis” tersebut menun-jukkan seorang tokoh laki-laki sedang menelepon di sebuah ruangan. Hal ini terlihat dari balon teks “Apa iya gue sampe harus ngemis juga jadi babu ke rumah elo? Kayak kata siapa itu di Twitter. Hahahaha!” Sementara itu, seorang perempuan berada di belakang laki-laki yang menjadi tokoh utama tersebut. Perempuan yang memakai baju hijau dan rok cokelat itu sedang membawa nampan dan sebuah cangkir berada di atasnya. Perempuan itu membelalakkan mata dan membuka mulutnya dengan lebar saat mendengar perkataan yang diucapkan tokoh laki-laki lewat telepon.
Tokoh laki-laki itu majikan dan perempuan di belakangnya adalah pem-bantu. Penggambaran tokoh laki-laki berbadan gemuk menandakan bahwa keadaan hidupnya sejahtera (Boedhijono,
Santiko, Maulana, Wuryantoro, & Rahardjo, 2008, h. 45). Orang yang dimaksud oleh komik ini sebagai pihak yang menulis “ngemis jadi babu” di Twitter pada balon teks panel kedua adalah wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri Hamzah menuliskan penyataan “Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela” di akun @Fahrihamzah pada 24 Agustus 2017 (BBC, 2017). Hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan pengguna Twitter karena pemakaian kata “ngemis” yang ditujukan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Fenomena mengemis identik dengan kemiskinan dan orang pinggiran yang mencari nafkah dengan cara merendah dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Saleh, Riyanto, & Mustaqim, 2014, h. 24). Hal tersebut membuat penggunaan kata “ngemis”
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
26
dalam tulisan di akun Twitter @Fahrihamzah mengungkapkan makna bahwa TKI yang bekerja di luar negeri dianggap memohon dan mengharap belas kasih lebih dahulu, tetapi pekerja asing di Indonesia banyak yang berdatangan dari berbagai negara.
Pernyataan Fahri Hamzah ini menjadi perdebatan di kalangan pengguna Twitter karena dianggap telah meremehkan perjuangan seseorang agar lolos seleksi menjadi TKI. Sementara itu, keputusan menjadi TKI dipilih oleh sebagian tenaga kerja di Indonesia karena dianggap sebagai salah satu solusi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran (Haryanti, 2009, h. 389).Episode 105: “Mukjizat”
Episode “Mukjizat” menunjukkan seorang tokoh laki-laki memakai kacamata serta kemeja berwarna abu-abu dan jas putih sedang berbicara di depan beberapa
mikrofon. Panel ketiga menunjukkan seorang tokoh laki-laki yang terbaring di tempat tidur dengan memakai masker oksigen. Sebuah televisi terlihat sedang menyiarkan siaran langsung. Siaran tersebut menampilkan seorang hakim yang sedang membacakan pengumuman. Hal tersebut terlihat dari balon teks “Dalam perkara dugaan korupsi … status pemohon sebagai tersangka ....”
Panel keempat melanjutkan teks panel ketiga dengan balon teks “Dinyatakan tidak sah.” Panel keempat menggambarkan tokoh laki-laki membuka mata kiri dan menaikkan alisnya setelah hakim membacakan pengumuman. Panel kelima menunjukkan tokoh laki-laki berkemeja biru dan jas abu-abu, yaitu tokoh yang sama dengan tokoh laki-laki pada panel kedua, kembali berbicara di depan beberapa mikrofon dan sebuah alat perekam.
Gambar 2 Episode “Mukjizat”Sumber: Komik Faktap (2017b)
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
27
Tokoh laki-laki yang memakai jas berwarna putih dan sedang melakukan wawancara adalah seorang dokter. Hal ini diketahui dari jas putih yang dipakainya. Jas putih merupakan pakaian yang identik dengan profesi dokter ketika sedang bekerja di rumah sakit (Chandra, 2013, h. 7). Dokter tersebut sedang melakukan wawancara dengan beberapa reporter. Dokter tersebut dalam wawancara yang sedang dilakukannya memberikan keterangan kepada media dengan menyatakan bahwa pasiennya mengalami komplikasi penyakit. Wawancara yang dilakukan oleh tokoh dokter digambarkan melalui beberapa mikrofon yang berada di depannya. Mikrofon merupakan aspek penting bagi reporter saat hendak melakukan wawancara (Junaedi, 2013, h. 77).
Sementara itu, tokoh laki-laki yang terbaring di atas tempat tidur itu merupakan pasien di sebuah rumah sakit. Hal tersebut dapat diketahui melalui masker oksigen yang dipakainya. Masker oksigen merupakan alat bantu pernapasan pasien yang dirawat inap di rumah sakit (Nursanto, Rizal, & Hadiyoso, 2015, h. 2192). Siaran televisi yang sedang berlangsung membahas sidang praperadilan kasus dugaan korupsi dan menghasilkan suatu putusan, yaitu status pemohon yang dinyatakan sebagai tersangka dianggap tidak sah. Tokoh laki-laki yang menjadi pasien dan sedang tertidur tersebut adalah Setya Novanto. Setya Novanto dianggap telah mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus yang menjeratnya dengan alasan
sakit dan menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit (Mustafa, 2017, h. 233-234).
Tokoh tersebut tiba-tiba tersadar serta membuka satu mata dan mengerutkan dahinya saat siaran langsung di televisi menggambarkan hakim telah selesai membacakan hasil putusan sidang praperadilan. Mata terbuka dan dahi berkerut dipercayai sebagai micro gesture suatu kebohongan. Tokoh laki-laki yang digambarkan sedang tersenyum dengan menarik mulut ke arah telinga merupakan penggambaran senyum palsu yang ditujukannya kepada media saat kembali melakukan klarifikasi (Gunandi & Hartanti, 2013, h. 42).
Komikus pada episode ini mengonstruksi ketua DPR RI, Setya Novanto, sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Berita berjudul “Menang Praperadilan, Setya Novanto Akhirnya Keluar dari Rumah Sakit” (Batubara, 2017) memuat foto Setya Novanto memakai kaos putih, terbaring di tempat tidur, serta menggunakan masker oksigen dan selang infus. Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) oleh KPK pada 18 Juli 2017.
Setya Novanto kemudian mengajukan banding pada 4 September 2017, namun tepat tiga pekan sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur dengan alasan sebagian besar fungsi jantungnya mengalami gangguan. Hal tersebut membuat Setya Novanto tidak menghadiri pemeriksaan yang telah
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
28
dijadwalkan oleh KPK. Hakim tunggal yang menangani kasus tersebut menjatuhkan putusan praperadilan, yaitu menolak status tersangka terhadap Setya Novanto. Dengan demikian, status Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah (Batubara, 2017).
Penyampaian kritik tersebut dikemas dalam bentuk cerita yang memiliki persamaan dengan kejadian sebenarnya dan memberi tekanan pada situasi yang ditargetkan atau sering disebut dengan humor analogi (Sudarmo, 2014, h. 15). Hal tersebut disampaikan pada panel keempat dengan penggambaran Setya Novanto yang sebelumnya memejamkan mata tiba-tiba membuka mata kiri dan mengerutkan dahinya. Selain itu, penggambaran tokoh dokter yang melakukan wawancara dengan telapak tangan terbuka juga mengartikan bahwa dokter itu memberikan informasi palsu mengenai kondisi pasiennya (Pease, 2003, h. 47-48). Sedangkan pada panel kelima, tokoh yang berperan sebagai dokter kembali melakukan wawancara dengan ekspresi alis terangkat yang menandakan bahwa dokter tersebut ragu-ragu ketika mengklarifikasi kondisi pasiennya yang tiba-tiba terbangun, setelah sebelumnya dikabarkan bahwa pasien tersebut mengidap komplikasi penyakit (Amelia, 2017, h. 7).
Selain itu, tokoh laki-laki tersebut juga digambarkan sedang memberi senyum palsu. Mulut yang ditarik secara horizontal atau ke arah telinga menandakan bahwa di pernyataan sebelumnya, tokoh tersebut telah berbohong (Gunandi & Hartanti, 2013, h. 42). Penggambaran kamar pasien yang berfasilitas single bed dan televisi merupakan kamar
pasien very important person (VIP) yang hanya dipesan oleh orang-orang kaya (Tedja & Tanuwidjaja, 2015, h. 944). Episode ini menyampaikan kritik melalui penggambaran orang kaya yang dapat melakukan semua keinginannya menggunakan uang mereka. Salah satu keinginan itu adalah meminta dokter yang merawatnya agar memberikan informasi palsu mengenai kondisi kesehatannya untuk menghambat kasus hukum yang sedang menjeratnya.Episode 115: “Lapor”
Episode “Lapor” menunjukkan sebuah ruangan penjara dengan jeruji besi dan pakaian penjara berwarna jingga. Percakapan di ruangan tersebut dilakukan oleh beberapa tokoh laki-laki berbaju jingga yang bertanya kepada lelaki lain di ruangan itu mengenai alasan sang tokoh dapat masuk penjara. Panel kedua menunjukkan orang tersebut menjawab, “Gara-gara bikin meme ngeledek pejabat tersangka korupsi, Bang. Saya dilaporin orangnya”. Tokoh laki-laki lainnya pada panel ketiga juga angkat bicara, “Lah, kita semua juga!” Kemudian panel kelima menunjukkan seseorang berkata, “Itu yang ngelaporin kita!” sambil menunjuk orang yang membelakanginya dengan menggunakan ibu jari.
Beberapa narapidana dalam satu sel yang sama mendengarkan penjelasan dari salah satu tokoh narapidana yang memakai kacamata. Tokoh tersebut menceritakan bahwa dirinya dipenjara karena membuat meme yang mengejek pejabat pemerintahan yang menjadi tersangka kasus korupsi, “Gara-gara bikin meme ngeledek pejabat tersangka korupsi, Bang. Saya dilaporin
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
29
orangnya”. Narapidana lain juga dilaporkan oleh orang yang sama dan dalam kasus yang sama pula. Sedangkan seorang narapidana yang berada dalam sel penjara yang berbeda adalah pejabat yang terlibat kasus korupsi. Pejabat tersebut adalah Setya Novanto yang melaporkan narapidana lainnya sekaligus telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP (Rahayu, 2018, h. 21-22).
Drama mengenai kecelakaan dan komplikasi penyakit yang dialami Setya Novanto dijadikan bahan candaan oleh pengguna media sosial dalam bentuk meme. Berbagai meme dan konten lain yang mengandung sindiran dan ditujukan untuk ketua DPR RI banyak beredar di media sosial. Setya Novanto pun melaporkan 32 akun media sosial karena telah membuat meme tentang dirinya (Aziz, 2017). Setya Novanto melaporkan akun-akun tersebut karena dianggap telah mencemarkan nama
baiknya. Tokoh laki-laki yang berada dalam sel penjara berbeda di panel kelima komik tersebut adalah Setya Novanto. Setya Novanto memidanakan orang-orang yang membuat meme tentang dirinya karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Namun, Setya Novanto juga dipidanakan atas kasus korupsi e-KTP.
Penyampaian kritik dalam episode ini ditunjukkan melalui humor satire. Humor satire merupakan humor yang digunakan untuk menyindir dengan cara mengejek sesuatu atau seseorang (Sudarmo, 2014, h. 14). Humor tersebut ditunjukkan pada panel kelima yang digambarkan melalui salah satu tokoh laki-laki menunjuk menggunakan ibu jari yang ditujukan kepada orang yang berada di sel penjara sebelahnya. Menunjuk menggunakan ibu jari kepada orang lain merupakan sinyal ejekan yang ditujukan kepada orang tersebut (Pease, 2003, h.
Gambar 3 Episode “Lapor”Sumber: Komik Faktap (2017c)
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
30
71-73). Hal ini juga didukung dengan adanya balon teks, “Itu yang ngelaporin kita” yang mengartikan bahwa orang yang melaporkannya juga menjadi narapidana akibat kasus yang menjeratnya.Episode 119: “Papa”
Episode ini diawali dengan panel yang menggambarkan adegan mobil menabrak tiang listrik. Panel keempat menggambarkan seorang perawat perempuan menoleh ke arah kanan karena ada seseorang menanyakan kepadanya, “Suster, suami saya baik-baik saja? Kasian anak-anak kalo papa mereka sampai kenapa-kenapa. Soalnya papa mereka adalah ….” Panel kelima menggambarkan empat tiang lampu. Tiang lampu berwarna biru sedang terbaring di tempat tidur dan memakai masker oksigen. Dua tiang lampu berukuran lebih pendek dan berwarna hijau dan cokelat, serta tiang lampu berwarna merah muda sedang berdiri di samping tempat tidur. Mereka merupakan keluarga dari tiang lampu.
Tiang lampu yang berada di tempat tidur adalah ayah, sedangkan tiang lampu berwarna merah muda adalah ibu dan dua tiang lampu lain yang berwarna hijau dan cokelat adalah anak-anaknya.
Penggambaran sebuah mobil hitam menabrak tiang lampu di pinggir jalan merupakan peristiwa kecelakaan mobil yang dialami oleh ketua DPR RI Setya Novanto (Mustafa, 2017, h. 233). Masyarakat Indonesia pada kejadian tersebut lebih peduli kepada keadaan tiang lampu daripada kondisi Setya Novanto yang saat itu juga menjadi korban kecelakaan.
Kecelakaan mobil menabrak tiang listrik itu terjadi dari arah Jalan Permata Berlian menuju Pertama Hijau, Jakarta Selatan pada Kamis, 16 November 2017, pukul 18.35 WIB. Salah satu penumpangnya adalah ketua DPR RI Setya Novanto. Keesokan harinya, kecelakaan tersebut ramai diberitakan di berbagai
Gambar 4 Episode “Papa”Sumber: Komik Faktap (2017d)
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
31
media massa (Sariah, 2018, h. 89-91). Tiang lampu yang dirawat di sebuah rumah sakit pada panel keempat dan kelima merupakan penggambaran protes masyarakat yang lebih peduli kepada tiang lampu yang ditabrak oleh Setya Novanto daripada kondisi Setya Novanto setelah mengalami kecelakaan tersebut. Masyarakat merasa bahwa peristiwa kecelakaan yang menimpa Setya Novanto merupakan sandiwara untuk menghindari jerat hukum KPK karena sebelumnya Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP (Mustafa, 2017, h. 233).
Kritik sosial pada potongan panel di atas merupakan rekonstruksi dari peristiwa kecelakaan yang menimpa Setya Novanto. Kritik tersebut disampaikan menggunakan humor berbentuk plesetan atau sering juga disebut sebagai parodi. Pada episode ini, komikus memelesetkan korban kecelakaan sebenarnya. Salah satu korban kecelakaan pada peristiwa sesungguhnya adalah Setya Novanto. Komikus memberikan penggambaran yang tidak terduga pada korban kecelakaan, yaitu sebuah tiang lampu sekaligus kepala keluarga dalam sebuah keluarga tiang lampu.Episode 146: “Kritik”
Episode “Kritik” menggambarkan tokoh laki-laki membawa selembar kertas dan membacakan pengumuman untuk warga yang berkumpul di depannya. Pengumuman tersebut dapat diketahui melalui balon teks “Mulai hari ini berlaku aturan baru. Yang mengkritik saya bisa dipidana!” Panel kedua menggambarkan tokoh laki-laki lain memberikan sanggahan
terhadap pengumuman yang disampaikan “Kok begitu, Pak? Kalo kerjanya ga becus pantas dikritik”. Panel ketiga menunjukkan tokoh laki-laki pertama memberikan tanggapan balik “Saya kan petinggi. Hormati dong!” Panel kelima menunjukkan seorang tokoh laki-laki yang sama sedang diikat di tiang bendera. Warga yang berkumpul di depan tokoh laki-laki tersebut memberikan hormat kepadanya. Balon teks dari warga menunjukkan pernyataan “Tadi minta dihormati, sekarang minta diturunkan.”
Tokoh yang membacakan pengumuman di atas merupakan pegawai pemerintahan. Wacana peraturan pemerintah yang baru menggambarkan bahwa mereka antikritik. Masyarakat harus menghormati dan tidak diizinkan mengkritik semua hal yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan serta peraturan yang dikeluarkannya (Nurrahma, 2018, h. 109).
Kritik pada episode ini disampaikan melalui dialog yang terdapat pada balon teks, “Kok begitu, Pak? Kalo kerjanya ga becus pantas dikritik.” Sanggahan berupa penolakan langsung tersebut merupakan bentuk protes dari masyarakat Indonesia mengenai UU MD3 yang ditetapkan oleh DPR RI. Penetapan UU MD3 dinilai tidak sebanding dengan kinerja DPR RI selama ini. Anggota DPR dianggap pantas menerima kritikan agar kinerjanya maksimal. Komikus menyampaikan kritiknya menggunakan humor satire sebagai ejekan yang ditujukan kepada tokoh pejabat pemerintahan (Sugiwardana, 2014, h. 92). Ejekan tersebut digambarkan melalui warga yang mengikat tokoh pejabat pemerintahan di tiang bendera.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
32
Episode 163: “Untung”
Episode “Untung” menceritakan per-bincangan dua laki-laki di sebuah ruangan yang terdapat tumpukan barang. Panel yang menggambarkan tokoh laki-laki berbaju hijau juga memuat balon teks “Ini bos koruptor kena 15 tahun. Kalo dibandingkan sama hasil korupsinya masih untung”. Tokoh tersebut sedang menghitung kerugian yang diperoleh koruptor ketika ditangkap dan didenda sesuai hukuman yang dijatuhkan. Tokoh laki-laki lain yang memakai baju biru merupakan bos dari tokoh laki-laki yang memakai baju hijau. Tokoh tersebut mengatakan, “Jadi maksud lo?”
Panel keempat memuat balon teks “Daripada kerja sama, Bos, mending saya k-“. Panel kelima menunjukkan tokoh bos mengejar tokoh karyawan sambil mengangkat ember merah. Tokoh bos memuat balon teks “Mau korupsi maksud lo?! Mabok bir oplosan ya?” Sedangkan tokoh karyawan memuat balon teks “Yeee, bercanda, Bos!”
Panel tersebut menunjukkan tokoh yang berperan sebagai karyawan sedang membicarakan vonis hukum yang diterima koruptor. Koruptor yang dimaksud adalah Setya Novanto yang telah melakukan korupsi e-KTP. Pengadilan dalam vonis terakhir memutuskan bahwa Setya Novanto dihukum 15 tahun penjara (Faisal, 2018, h. 161). Di Indonesia, koruptor dihukum lebih ringan daripada kejahatan korupsi yang telah dilakukannya. Para koruptor ini masih memiliki banyak harta dan dapat melakukan semua hal yang mereka inginkan menggunakan hartanya meskipun vonis telah diberikan (Tanuwijaya, 2014, h. 265-266).
Cerita episode ini menggambarkan bahwa masyarakat menganggap putusan hukuman yang diberikan kepada Setya Novanto tidak sebanding dengan uang yang telah dikorupsinya. Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Setya Novanto mencapai 2,3 triliun rupiah, sedangkan
Gambar 5 Episode “Kritik”Sumber: Komik Faktap (2018a)
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
33
denda yang harus dibayar oleh Setya Novanto sebesar 7,3 juta dolar Amerika atau setara dengan 100 miliar rupiah (Faisal, 2018, h. 161).
Kritik pada episode kali ini disampaikan melalui balon teks “Ini bos koruptor kena 15 tahun. Kalo dibandingkan sama hasil korupsinya masih untung.” Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa koruptor di Indonesia tidak merasa rugi kehilangan hartanya, walaupun hakim menjatuhkan hukuman denda dan penjara. Harta dari hasil korupsi lebih banyak daripada denda yang harus dibayarkan. Mereka masih bisa melakukan kegiatan yang diinginkan, seperti menyuntikkan dana untuk partai politik dan membayar mahal pengacara untuk membelanya (Tanuwijaya, 2014, h. 266).
PEMBAHASAN
Kritik yang digambarkan Komik Faktap merupakan kritik terhadap ketimpangan sosial yang terjadi antara
masyarakat dan para penguasa negara. Penelitian ini memilih enam episode Komik Faktap sebagai objek penelitian. Komik pertama yaitu episode yang berjudul “Ngemis”. Fenomena mengemis identik dengan kemiskinan dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Saleh, Riyanto, & Mustaqim, 2014, h. 24). Dialog dalam balon teks tokoh laki-laki di epsisode tersebut memuat kritik dalam bentuk humor allusion, yaitu humor yang menyindir secara tidak langsung dan ditujukan kepada pihak lain yang dikenal, walaupun tidak akrab (Sudarmo, 2014, h. 14). Sindiran tersebut menyasar tulisan yang diunggah oleh akun Twitter @Fahrihamzah mengenai anak bangsa atau masyarakat Indonesia yang mengemis agar bisa menjadi TKI di luar negeri. Padahal program transmigrasi dengan menjadi tenaga kerja di negara lain diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia (Wafirotin, 2013, h. 17).
Gambar 6 Episode “Untung”Sumber: Komik Faktap (2018b)
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
34
Sementara itu, komikus pada episode yang berjudul “Mukjizat” mengonstruksi ketua DPR RI, Setya Novanto, sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Penyampaian kritik dikemas dalam bentuk cerita yang memiliki persamaan dengan kejadian sebenarnya dan memberi tekanan pada situasi yang ditargetkan. Hal ini sering disebut sebagai humor analogi (Sudarmo, 2014, h. 15).
Setya Novanto yang sebelumnya digambarkan memejamkan mata, tiba-tiba membuka mata kiri dan mengerutkan dahinya. Tokoh dokter yang melakukan wawancara dengan telapak tangan terbuka juga mengartikan bahwa dokter tersebut memberikan informasi palsu mengenai kondisi pasiennya (Pease, 2003, h. 47-48). Dokter tersebut kembali melakukan wawancara dengan ekspresi alis terangkat yang menandakan bahwa dirinya ragu-ragu ketika mengklarifikasi kondisi pasiennya (Amelia, 2017, h. 7).
Dokter tersebut juga digambarkan sedang menunjukkan senyum palsu. Hal ini terindikasi dari mulut ditarik secara horizontal atau ke arah telinga yang menandakan bahwa pada pernyataan sebelumnya dokter tersebut telah berbohong (Gunandi & Hartanti, 2013, h. 42). Penggambaran kamar pasien berfasilitas single bed dan televisi menunjukkan kamar pasien VIP yang hanya dipesan oleh orang-orang kaya (Tedja & Tanuwidjaja, 2015, h. 944). Episode ini juga menyampaikan kritik melalui penggambaran orang kaya yang dapat melakukan semua keinginannya dengan menggunakan uang mereka. Salah
satu keinginan tersebut adalah meminta dokter yang merawatnya memberikan informasi palsu mengenai kondisi kesehatannya untuk menghambat kasus hukum yang sedang menjeratnya.
Episode yang berjudul “Lapor” men-jadikan drama kecelakaan dan komplikasi penyakit yang dialami Setya Novanto yang menjadi bahan candaan oleh pengguna media sosial dalam bentuk meme. Penyampaian kritik dalam episode ini ditunjukkan melalui humor satire. Humor satire merupakan humor yang digunakan untuk menyindir dengan cara mengejek sesuatu atau seseorang (Sudarmo, 2014, h. 14).
Humor tersebut ditunjukkan pada panel kelima melalui salah satu tokoh laki-laki yang menunjuk menggunakan ibu jari dan ditujukan kepada orang yang berada di sel penjara sebelahnya. Menunjuk menggunakan ibu jari kepada orang lain merupakan sinyal ejekan yang ditujukan kepada orang tersebut (Pease, 2003, h. 71-73). Balon teks bertuliskan “Itu yang ngelaporin kita” mengartikan bahwa orang yang melaporkannya juga menjadi narapidana akibat kasus korupsi yang dilakukannya.
Komik keempat yang berjudul “Papa” menceritakan kecelakaan mobil Setya Novanto yang menabrak tiang listrik pada Kamis, 16 November 2017. Keesokan harinya, kecelakaan tersebut ramai diberitakan di berbagai media massa (Sariah, 2018, h. 89-91). Tiang lampu yang dirawat di sebuah rumah sakit pada panel keempat dan kelima merupakan penggambaran dari bentuk protes masyarakat. Masyarakat
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
35
merasa bahwa peristiwa kecelakaan yang menimpa Setya Novanto merupakan sandiwara untuk menghindari jerat hukum KPK karena sebelumnya Setya Novanto sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP (Mustafa, 2017, h. 233). Kritik sosial pada potongan panel di atas merupakan rekonstruksi dari peristiwa kecelakaan yang menimpa Setya Novanto.
Kritik tersebut disampaikan menggunakan humor berbentuk plesetan atau sering juga disebut sebagai parodi. Isi dari humor plesetan adalah memelesetkan segala sesuatu dan biasanya cerita yang menggunakan humor ini cukup mengandung kejutan (Sudarmo, 2014, h. 50). Episode tersebut memelesetkan korban kecelakaan sebenarnya. Korban kecelakaan peristiwa sebenarnya adalah Setya Novanto, namun komikus memberikan penggambaran yang tidak terduga pada korban kecelakaan, yaitu sebuah tiang lampu sekaligus kepala keluarga dari keluarga tiang lampu.
Episode “Kritik” berkaitan dengan pengumuman peraturan terbaru mengenai hak imunitas anggota parlemen yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang lebih dikenal sebagai UU MD3. Pengumuman disampaikan melalui tokoh laki-laki sebagai salah satu pejabat pemerintahan. Hal tersebut dapat diketahui dari pakaian yang dikenakannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 memuat aturan yang menyatakan bahwa pakaian dinas dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri salah satunya berwarna cokelat khaki (warna cokelat seperti jerami kering).
Tokoh yang melakukan protes adalah gambaran dari respons penolakan masyarakat Indonesia mengenai undang-undang yang ditetapkan oleh DPR RI. Undang-undang tersebut dianggap membuat anggota parlemen kebal terhadap hukum sekalipun mereka melakukan kesalahan, serta menghalangi kebebasan pendapat dan partisipasi dalam pemerintahan (Katharina, 2018, h. 26).
Episode tersebut menyampaikan kritik melalui dialog yang terdapat pada balon teks, “Kok begitu, Pak? Kalo kerjanya ga becus pantas dikritik”. Sanggahan berupa penolakan langsung tersebut merupakan bentuk protes dari masyarakat Indonesia mengenai UU MD3 yang ditetapkan oleh DPR RI. Kinerja DPR RI dalam merevisi undang-undang yang berasal dari inisiatif para anggota dewan dinilai sangat rendah dan tidak produktif (Solihah & Witianti, 2016, h. 292-295).
Penetapan UU MD3 dinilai tidak sebanding dengan kinerja DPR RI selama ini. Anggota DPR dianggap pantas menerima kritikan agar kinerjanya maksimal. Komikus menyampaikan kritiknya melalui humor satire sebagai ejekan yang ditujukan kepada tokoh pejabat pemerintahan (Sugiwardana, 2014, h. 92). Ejekan tersebut digambarkan melalui warga yang mengikat tokoh pejabat pemerintahan di tiang bendera.
Episode yang berjudul “Untung” menunjukkan anggapan masyarakat atas putusan hukum yang diberikan kepada Setya Novanto tidak sebanding dengan uang yang telah dikorupsinya. Kerugian
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
36
negara akibat korupsi yang dilakukan Setya Novanto mencapai 2,3 triliun rupiah, sedangkan denda yang harus dibayarkan Setya Novanto sebesar 7,3 juta dolar Amerika atau setara dengan 100 miliar rupiah (Faisal, 2018, h. 161).
Humor ditunjukkan melalui dialog pada balon teks tokoh laki-laki yang berperan sebagai karyawan. Tokoh tersebut mengatakan kepada bosnya bahwa dirinya ingin melakukan korupsi saja karena vonis hukumnya lebih ringan daripada nominal uang korupsinya, namun keinginan tersebut hanya sebagai candaan. Humor tersebut merupakan humor apologisme, yaitu humor yang digunakan untuk berlindung di balik lelucon karena tokoh yang melontarkan pernyataan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mempunyai dasar argumen (Sudarmo, 2014, h. 15).
Komikus menyampaikan kritik sosialnya melalui beberapa teknik humor. Pertama, allusion, yaitu humor yang digunakan untuk menyindir seseorang. Teknik ini tidak secara langsung meng-gambarkan kondisi asli dari fenomena yang terjadi. Hal ini ditunjukkan melalui panel komik dengan adegan seorang laki-laki sedang berbicara melalui telepon, padahal kondisi asli dari kejadian adalah cuitan di Twitter. Kedua, analogi, yakni kritik yang dikemas dalam bentuk cerita dan memiliki persamaan dengan kejadian sebenarnya, serta memberi tekanan pada situasi yang ditargetkan (Sudarmo, 2014, h. 15).
Ketiga, satire, yaitu humor melalui ejekan atas situasi yang terjadi. Teknik ini
memberikan gambaran tidak terduga di akhir komik. Keempat, plesetan, yaitu humor yang ceritanya mengandung plesetan dan kejutan. Komik ini menggambarkan korban kecelakaan adalah tiang lampu, bukan Setya Novanto. Kelima, apologisme, yaitu humor yang digunakan untuk berlindung di balik lelucon karena tokoh yang melontarkan pernyataan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mempunyai dasar argumen (Sudarmo, 2014, h. 15). Komik tersebut mengangkat isu mengenai koruptor di Indonesia yang masih kaya dan tidak merasa dirugikan, walaupun telah divonis penjara dan denda. Gambaran tersebut ditunjukkan melalui dialog tokoh karyawan yang ingin melakukan korupsi, tetapi dirinya menyangkal ketika bosnya memarahinya.
Pembahasan pada level mitos mengindikasikan bahwa kritik Komik Faktap tentang DPR RI memiliki dua sasaran, yaitu tokoh DPR RI dan kebijakan DPR RI. Kritik terhadap tokoh DPR RI yang diangkat pada komik tersebut merupakan kritik atas kejadian kecelakaan dan perawatan di rumah sakit yang dialami oleh Setya Novanto pada kasus korupsi e-KTP. Kecelakaan dan perawatan di rumah sakit itu disebut-sebut sebagai upaya Setya Novanto untuk mangkir dari proses hukum yang menjeratnya. Selain itu, kritik atas rendahnya denda yang diberikan kepada koruptor ditampilkan melalui gambaran tokoh yang sedang berhitung untung-rugi.
Kritik kepada Setya Novanto juga disampaikan melalui komik berjudul “Lapor”. Komik tersebut mengkritik Setya Novanto atas laporannya terhadap 32
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
37
akun media sosial yang membuat meme mengenai dirinya setelah kecelakaan. Selain itu, kritik juga ditujukan atas cuitan Fahri Hamzah yang menyebutkan bahwa TKI adalah orang yang mengemis di luar negeri. Hal ini mendapat kritik karena TKI merupakan penyumbang devisa negara dan tidak mengandalkan belas kasihan.
Kebijakan yang menguntungkan posisi DPR RI juga dikritik oleh Komik Faktap. Komikus menggambarkan seorang pejabat pemerintahan yang mengumumkan bahwa setiap orang yang mengkritik akan dipidana. Tokoh tersebut juga mengemukakan bahwa dirinya harus dihormati. Panel selanjutnya menunjukkan bahwa pejabat tersebut diikat di tiang bendera dan diberi hormat. Komik ini menunjukkan kritik atas kebijakan UU MD3 yang membuat lembaga tersebut kebal hukum dan dapat memidanakan setiap orang yang melakukan kritik kepada pemerintah.
SIMPULAN
Enam episode Komik Faktap melakukan kritik dalam dua kategori, yaitu kritik terhadap anggota DPR RI dan kritik terhadap kebijakan DPR RI. Mitos yang ditemukan pada masing-masing episodenya merupakan kejadian yang dialami oleh anggota DPR RI dan menjadi kontroversi atau perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya pengguna media sosial.
Peneliti menemukan lima teknik humor yang digunakan untuk menyampaikan kritik tersebut, yaitu allusion, satire, plesetan, analogi, dan apologisme. Peneliti berharap ada penelitian lain yang membahas
mengenai analisis wacana dari komentar pembaca di Line Webtoon.
DAFTAR RUJUKAN
Agnes, T. (2016). Pembaca line webtoon Indonesia terbesar di dunia. detik.com. <https://hot.detik.com/art/d-3274551/pembaca-line-webtoon-indonesia-terbesar-di-dunia>
Amelia, C. (2017). Pesan sosial dan bentuk pesan pada komik “hai, miiko!” (Studi analisis isi). JOM FISIP, 4(2), 1-13.
Apriyono, A. (2015). Catatan kelam dunia seni di masa orde baru. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2399984/catatan-kelam-dunia-seni-di-masa-orde-baru#>
Arslan, H. (2014). Exposition of spontaneous humor in digital environment especially in social media after social events. Journal of Media Critiques, 1(3), 95-106.
Augereau, O., Iwata, M., & Kise, K. (2018). A survey of comics research in computer science. Journal of Imaging, 4(7), 1-15.
Aziz, A. (2017). Akun medsos penyebar meme Setya Novanto dilaporkan ke polisi. tirto.id. <https://tirto.id/32-akun-medsos-penyebar-meme-setya-novanto-dilaporkan-ke-polisi-cztn>
Batubara, P. (2017). Menang praperadilan, setya novanto akhirnya keluar dari rumah sakit. okezone.com. <https://news.okezone.com/read/2017/10/03/337/1787660/menang-praperadilan-setya-novanto-akhirnya-keluar-dari-rumah-sakit>
BBC. (2017). Menyebut TKI ‘mengemis jadi babu’, fahri hamzah jadi bulan-bulanan. bbc.com. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38728106>
Boedhijono, S. K., Santiko, H., Maulana, R., Wuryantoro, E., & Rahardjo, W. (2008). Dinamika kehidupan anak-anak pada masa Jawa kuna abad viii – xv masehi. Makara Sosial Humaniora, 12(1), 39-55.
Chandra, M. (2013). Representasi dokter dalam film “7 hati 7 cinta 7 wanita”. Jurnal e-Komunikasi, 1(1). 1-12.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 19-40JurnalILMU KOMUNIKASI
38
Colletta, L. (2009). Political satire and postmodern irony in the age of Stephen Colbert and Jon Stewart. The Journal of Popular Culture, 42(5), 856-874.
Faisal. (2018). Analisis yuridis pencabutan hak politik terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 155-163.
Fajar, A. (2018). Revisi UU MD3 tuai kontroversi, ini kata millennials. idntimes.com. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ardiansyah-fajar/revisi-uu-md-3-tuai-kontroversi-ini-kata-millennials/full>
Fiske, J. (2012). Pengantar ilmu komunikasi (edisi ketiga). Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada.
Gunandi, I. G. A., & Hartanti, S. (2013, Juni). Manual assessment derajat kebohongan pada adegan video klip berdasarkan Naïve Bayesian. Makalah dipresentasikan di Seminar Aplikasi Nasional Teknologi Informasi, Yogyakarta, Indonesia.
Haryanti, E. (2009). Remitansi tenaga kerja Indonesia: Dampaknya terhadap inflasi dan konstribusinya terhadap kualitas hidup masyarakat. Ekuitas, 13(3), 388-405.
Haryanto, I. (2014). Jurnalisme era digital tantangan industri media abad 21. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
Iliescu, A. (2016). The comic strip – a weapon for social criticism. Irregular, 1(1), 17-28.
Junaedi, F. (2013). Jurnalisme penyiaran dan reportase televisi. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.
Katharina, R. (2018). Polemik perubahan atas UU MD3 dalam perspektif kebijakan publik. Jurnal Pusat Penelitian, X(5), 25-30.
Komik Faktap. (2017a). Ngemis. webtoons.com. <https://m.webtoons.com/id/comedy/komik-faktap/ep-35gemis/viewer?title_no=798&episode_no=36>
------------------. (2017b). Mukjizat. webtoons.com. <https://m.webtoons.com/id/comedy/komik-faktap/ep-105 mukjizat/viewer?title_no=798&episode_no =106>
------------------. (2017c). Lapor. Webtoons.com. <https://www.webtoons.com/id/comedy/komik-faktap/ep-115-lapor/viewer?title_no=798&episode_no=116>
------------------. (2017d). Papa. webtoons.com. <ht tps : / /m.webtoons .com/id/comedy/komik-faktap/ep-119-papaviewer?title_ o= 798&episode_no=120>
------------------. (2018a). Kritik. webtoons.com. <ht tps : / /m.webtoons .com/id/comedy/komik-faktap/ep-146kritik/viewer? title_no=798&episode_no=148>
------------------. (2018b). Untung. webtoons.com. <https://m.webtoons.com/id/comedy/komik-faktap/ep-163-untung/viewer?title_no=798&episode_no=165>
------------------. (2019). Komik Faktap. webtoons.com. <https://www.webtoons.com/id/comedy/komik-faktap/list?title_no=798&page=1&webtoon-pla t form-redirect=true>
Krissandi, A. D. S., & Setiawan, K. A. C. (2018). Kritik sosial stand up comedy Indonesia dalam tinjauan prakmatik. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 7(2), 46-59.
Kriyantono, R. (2006). Teknik praktis riset komunikasi. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.
Lantowa, J., Marahayu, N. M., & Khairussibyan. (2017). Semiotika: Teori, metode, dan penerapannya dalam penelitian sastra. Yogyakarta, Indonesia: Deepublish.
Mustafa. (2017). Citra Setya di jagat maya (Analisis semiotika dan etika komunikasi Islam gambar Setya Novanto pada akun instagram detik.com). Jurnal Pemikiran Islam, 41(2), 213-239.
Nurrahma. (2018). Implikatur ujaran kebencian warga net pada sosial media instagram (Isu politik Indonesia 2017). Paper presented at Seminar Nasional Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.
Nursalim, M. P. (2015). Politisasi dalam ragam bahasa komik Mice Cartoon (Analisis
Alifia Hanifah Luthfi. Analisis Semiotika Kritik ...
39
semiotika Roland Barthes). Jurnal Sasindo, 2(2), 62-78.
Nursanto, N., Rizal, A., & Hadiyoso, S. (2015). Perancangan dan implementasi regulator oksigen otomatis berdasarkan tingkat pernapasan. e-Proceeding of Engineering, 2(2), 2192-2198.
Pease, A. (2003). Bahasa tubuh menguak pikiran lawan bicara melalui gerak bahasa isyarat. Jakarta, Indonesia: Prestasi Pustaka.
Putri, D. M. (2018). Pengaruh media sosial line webtoon terhadap minat membaca komik pada mahasiswa Universitas Riau. JOM FISIP, 5(1), 1-15.
Qusairi, W. (2017). Kritik sosial pada lirik lagu merdeka karya grup musik Efek Rumah Kaca. eJurnal Komunikasi, 5(4), 202-216.
Rahayu, S. (2018). Konstruksi teks pada media Kompas dalam pemberitaan kasus Setya Novanto. Resolusi, 1(1), 17-35.
Saleh, K., Riyanto, & Mustaqim, M. (2014). Tradisi mengemis: Pergulatan antara ekonomi dan agama (Studi perilaku mengemis masyarakat di Demak). Jurnal Penelitian, 8(1), 23-44.
Sanjaya, B. A. (2013). Makna kritik sosial dalam lirik lagu “Bento” karya Iwan Fals (Analisis semiotika Roland Barthes). eJournal Ilmu Komunikasi, 1(4), 183-199.
Sariah. (2018). Ekspresi kritik melalui disfemisme pada pemberitaan kasus Setya Novanto di media massa daring. Metalingua, 16(1), 79-93.
Sobur, A. (2013). Semiotika komunikasi. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. Jurnal Pemerintah, 2(2), 291-307.
Sudarmo, D. M. (2014). Anatomi lelucon di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kombat Publishers.
Sugiarto, V. D. (2016). Teknik humor dalam komedi yang dibintangi oleh stand up comedian. Jurnal E-Komunikasi, 4(1), 1-12.
Sugiwardana, R. (2014). Pemaknaan realitas serta bentuk kritik sosial dalam lirik lagu slank. Skriptorium, 2(2), 86-96.
Supraja, M. (2018). Pengantar metodologi ilmu sosial kritis Jurgen Habermas. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
Suseno, F. M. (2013). Dari Mao ke Marcuse percikan filsafat marxis pasca-lenin. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
Tanuwijaya, F. (2014). Vonis hakim yang memiskinkan koruptor. Masalah-Masalah Hukum, 43(2), 263-272.
Tatalovic, M. (2009). Science comics as tools for science education and communication: A brief, exploratory study. Journal of Science Communication, 8(4), 1-17.
Tedja, P., & Tanuwidjaja, G. (2015). Efektivitas desain kamar dan nurse station pada paviliun penderita stroke di rumah sakit Y di Surabaya. Paper presented at Seminar Nasional Teknologi 2015, Institut Teknologi Nasional Malang, Indonesia.
Van Zoest, A. (1993). Semiotika tentang tanda, cara kerjanya dan apa yang kita lakukan dengannya. Jakarta, Indonesia: Yayasan Sumber Agung.
Vera, N. (2014). Semiotika dalam riset komunikasi. Bogor, Indonesia: Penerbit Ghalia Indonesia.
Wafirotin, K. Z. (2013). Dampak migrasi terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga TKI di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ekuilibrium, 11(2), 15-33.
Wibowo, I. S. H. (2013). Semiotika komunikasi: Aplikasi praktis bagi penelitian dan skripsi komunikasi (edisi 2). Jakarta, Indonesia: Penerbit Mitra Wacana Media.
41
Penggambaran Perempuan di Majalah Popular 1988-2018
Formas Juitan LaseUniversitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta 13630Email: [email protected]
Abstract: This paper aims to look at the depiction of women on the Popular magazine’s covers since published in 1988 to 2018. The concept of post-feminism is used as a theoretical framework and semiotic as the method of analysis. The result shows that women are represented in two ways: sexual objects and sexual subjects. Sexual objects are marked through the sexualized women body with sexual-passive poses. Furthermore, the depiction of sexual subjects is marked through sexual-active poses. Provocative and sexually active poses with the pretense of “girl power” are actually a form of exploitation.
Keywords: feminine body, Popular magazine, post-feminism, sexualization of women
Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk melihat penggambaran perempuan di sampul majalah Popular dari tahun 1988 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan konsep pascafeminisme dan metode semiotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan direpresentasikan dalam dua cara, yaitu objek seksual dan subjek seksual. Objek seksual ditandai melalui tubuh perempuan dengan pose seksual pasif, sedangkan subjek seksual ditandai melalui pose seksual aktif. Penggambaran perempuan sebagai subjek seksual tidak lebih baik daripada objek seksual yang diobjektifikasi. Bentuk-bentuk penggambaran secara provokatif dan seksual aktif dengan pretensi “girl power” sebenarnya adalah eksploitasi.
Kata Kunci: majalah Popular, objek seksual, pascafeminisme, perempuan, subjek seksual
Majalah Popular menggunakan perempuan sebagai materi majalahnya sejak edisi perdana pada 18 Februari 1988. Pada edisi tersebut, model Camelia Malik masih ditampilkan dengan pakaian yang sopan. Pada tahun 1991, majalah Popular memunculkan konsep model dan pakaian renang yang dianggap vulgar dan porno. Modelnya tersegmentasi pada kalangan selebritas, yaitu aktris sinetron dan film, pedangdut, penyanyi, dan model. Mereka ditampilkan setengah telanjang dengan pose yang seksi. Pose seksi itu dikuatkan
dengan teks seksual di sampul majalah tersebut, seperti: “Seks Multi Partner”, “Order ABG Virgin”, “Seks Macan Wanita EsTeWe”, dan “Seks Tukar Tambah”.
Brenner (1999, h. 21) mengatakan bahwa telah terjadi perubahan yang menunjukkan gerakan-gerakan berbeda pada sampul majalah Femina tahun 1970-an. Seorang ibu, anak perempuan, atau model yang sebelumnya ditampilkan dalam pakaian yang sopan dengan tatapan mata jauh ke depan dan senyum manis di bibir berubah menjadi provokatif dan seksi di sekitar tahun 1990-an.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 41-56JurnalILMU KOMUNIKASI
42
Hal yang sama juga ditemukan pada majalah Popular. Model-model perempuan ditampilkan percaya diri dengan pose yang lebih seksi dan provokatif. Perasaan malu-malu dengan senyum manis tidak ada lagi dan digantikan dengan tatapan mata yang tajam. Menurut Gill (2003, h. 102), pergeseran penggambaran perempuan ini menunjukkan perempuan sebagai orang yang aktif, mandiri, dan memiliki otonomi seksual. Perubahan tersebut merupakan respons terhadap gerakan feminism. Gejala ini disebut dengan istilah pascafeminisme. Katie dan Danfield (dalam Sulistyani, 2011, h. 20-21) menyatakan bahwa pascafeminisme sebagai power feminism, yaitu pandangan feminisme yang mengedepankan emansipasi perempuan untuk meraih kuasa dengan cara mengeluarkan perempuan dari dominasi patriarki yang selama ini menempatkannya sebagai objek. Gerakan pascafeminisme ini telah mengilhami perempuan untuk mendobrak tatanan-tatanan lama dalam masyarakat dan berani keluar menjadi seseorang yang diinginkannya.
Menurut McRobbie (2009, h. 84-85), salah satu bentuk dari gerakan pascafeminisme yang membebaskan diri dari dominasi laki-laki adalah kebebasan seksual. Perempuan kini merayakan tubuh dan seksualitasnya menurut pilihannya sendiri. Perempuan yang dahulu ditampilkan malu-malu dan cenderung menjadi objek tatapan laki-laki, kini telah berubah dengan tampilan provokatif melalui penonjolan tubuh yang seksi (Goldman dalam Gill, 2007, h. 147). Hal ini mendorong perempuan untuk menjadi sosok yang diinginkannya, termasuk tampil seksi dan provokatif.
Gill (2007, h. 148) menyatakan bahwa penggambaran perempuan dari objek seks menjadi subjek yang berhasrat seksual telah menjelma menjadi sumber kekuatan dan identitas lewat tubuh yang seksi. Tubuh perempuan yang diseksualkan di media massa menjadi tak terhindarkan dan menjadi instrumen yang powerful, di mana perempuan bisa menjadi apa saja yang diinginkannya, termasuk memilih untuk punya dada implan, tampil telanjang di sampul majalah, atau memaksa diri mereka kelaparan untuk memperoleh tubuh yang kurus (Hatton & Trautner, 2013, h. 73).
Menurut Goldman (dalam Gill, 2007, h. 148-150), penggambaran perempuan yang terobjektifikasi menjadi tersamarkan karena perempuan tersebut ditampilkan sebagai subjek seksual yang aktif dan berhasrat, sesuai dengan keinginan mereka untuk terbebaskan. Ketika perempuan seolah-olah berkuasa atas tubuhnya, pada saat yang sama media menggunakan bahasa feminis itu untuk menjual tubuh perempuan kepada pembaca dan pengiklan. Media massa beroperasi berdasarkan logika kapitalistik (Hatton & Trautner, 2013, h. 74).
Gill (2003, h. 103-105) menyatakan bahwa perubahan penggambaran perem-puan menjadi subjek seksual ini perlu dicermati secara kritis. Pertama, representasi perempuan sebagai subjek seksual hanya berlaku bagi kategori perempuan tertentu, yakni perempuan yang menarik secara seksual: berkulit putih, langsing, dan cantik. Mereka yang bertubuh gemuk, keriput, dan lebih tua tidak berada pada posisi yang sama sebagai subjek seksual.
Juitan Lase. Penggambaran Perempuan di ...
43
Kedua, perempuan yang menjadi subjek seksual selalu takut kehilangan hal-hal yang menjadikannya superior, yakni wajah cantik, kulit putih, dan kemudaan. Hal yang paling menakutkan bagi perempuan adalah penuaan dan berat badan. Perempuan terjebak dalam mitos kecantikan itu sendiri ketika menjadi subjek. Mitos kecantikan ini menyerang perempuan secara fisik dan psikologis.
Ketiga, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih dan memuaskan diri sendiri ketika menjadi subjek seksual. Perempuan menjadi agen yang mengobjektifikasi secara bebas diri mereka sendiri dalam media. Otonomi yang dimiliki perempuan membebaskan dirinya dari ketidaksetaraan atau ketimpangan kekuasaan dan perempuan pun dapat menggunakan kecantikannya untuk membuat mereka merasa nyaman. Kecantikan menjadi bentuk pendisiplinan baru terhadap tubuh perempuan ketika perempuan merasa bebas dari ketidaksetaraan melalui kecantikan. Perempuan harus putih, cantik, dan langsing agar bisa tetap merasa menjadi subjek yang berkuasa.
Kekuasaan yang dimiliki perempuan melalui kecantikan adalah lingkaran penindasan dan pendisiplinan baru terhadap tubuh perempuan itu sendiri. Menurut Gill (2003, h. 106) perubahan perempuan dari objek seksual ke subjek seksual adalah perubahan “from an external male judging gaze to a self-policing narcissistic gaze”, di mana seharusnya perempuan membebaskan diri dari objektifikasi tatapan laki-laki, namun justru menjebak dirinya pada pendisiplinan baru yang datang dari dirinya sendiri.
Van Zoonen (1994) mengatakan bahwa media massa mampu mengonstruksi dunia imajinasi melalui mitos-mitos yang diciptakan oleh masyarakat, menjadikan realitas tertentu yang diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran, serta memproduksi dan mereproduksi ideologi dominan. Media massa tidak bisa dipisahkan dari agenda politik, ekonomi, dan sosiokultural masyarakat sebab media massa memiliki relasi sepadan dengan elemen-elemen tersebut. Media mampu mendorong perempuan meraih kekuasaan dan mengakomodasi kesadaran itu di ruang-ruang media dan di sisi lain berpretensi sebagai agen modernisasi feminis alih-alih eksploitasi (Gill, 2007, h. 147-149).
Artikel ini menganalisis penggambaran perempuan di sampul majalah Popular sejak diterbitkan tahun 1988 hingga 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan penggambaran perempuan dari tahun ke tahun, sehingga pembaca bisa memahami penggambaran perempuan sebagai representasi perempuan ideal dalam masyarakat.
METODE
Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang digunakan adalah sampul majalah Popular sejak tahun 1988 hingga 2018. Pemilihan edisi sampul majalah Popular ini dilakukan menggunakan teknik purposive atau judgemental sampling. Menurut peneliti, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampul sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu melihat penggambaran tubuh
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 41-56JurnalILMU KOMUNIKASI
44
perempuan dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengamatan, sejak tahun 1988-2018 majalah Popular telah mengubah tagline majalahnya sebanyak lima kali, yaitu “Mereka Yang Berprestasi” (1988-1990), “Sport Wear Fashion” (1991-2001), “Entertainment For Men” (2002-2008), “Talk About Men’s World” (2009-2011), “#1 Men’s Magazine in Indonesia” (2011-2014), dan “Every Man Needs a Breaks” (2015-sekarang). Perubahan tagline ini menjadi kriteria bagi peneliti untuk memilih sampel dari sampul secara purposive. Sampel yang dipilih dapat mewakili tren yang ditampilkan tiap tagline majalah. Alasan peneliti adalah untuk mengantisipasi tren yang mengemuka dalam sampul majalah dan bergantung pada jenjang waktu penerbitan edisi majalah tersebut.
Peneliti menggunakan metode semiotika sebagai metode analisis untuk membongkar makna tanda pada tubuh perempuan dalam sampul majalah ini. Metode semiotika (dalam bahasa Pierce) dan semiologi (dalam bahasa de Saussure dan Barthes) adalah kajian tentang makna sebuah tanda yang merupakan hasil produksi sosial sebuah komunitas tertentu (Barthes, 1967, 1973; Fiske, 1990; Hartley, 2002; O’Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery, & Fiske, 1994). Menurut van Zoonen (1994, h. 74) metode ini populer dalam kajian media feminis karena memfasilitasi peneliti untuk membongkar struktur tanda atas tubuh perempuan yang ditampilkan dalam media massa. O’Sullivan, dkk. (1994, h. 287) menyatakan bahwa salah satu hal yang menarik dalam menganalisis struktur tanda adalah “the processes of significations.
Ada tiga tahap proses signifikasi. Tahap pertama adalah tahap denotasi, yakni tahap identifikasi relasi penanda (signifier) dan petanda (signified) dari sebuah tanda tertentu. Tahap denotasi ini menjelaskan hubungan tanda-tanda yang relevan dan aspek-aspek dominan yang merujuk pada tanda yang dianalisis dari sampul majalah Popular. Menurut van Zoonen (1994, h. 75), hubungan penanda dan petanda ini tidak sembarang (less arbitrary) karena penjelasan hubungan tersebut dapat menggunakan semiotika Pierce (ikon, indeks, simbol).
Ikon adalah tanda yang dibuat mirip dengan objek yang dirujuk. Foto dapat dikatakan sebagai tanda ikonik karena mereka mensimulasikan referen yang sama (Sebeok, 2001, h. 10). Sedangkan indeks adalah tanda yang merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain. Indeks ini, misalnya, tanda asap berhubungan dengan tanda api. Asap dan api ini disebut sebagai tanda indeks. Sementara itu, simbol adalah tanda yang berasal dari mana pun dan menjadi rujukan apa pun. Ia bisa terdiri dari kata, gerakan yang disepakati dalam komunitas masyarakat tertentu, dan menjadi konvensi sosial budaya tertentu.
Tahap kedua adalah tahap konotasi dan mitos. Tahap konotasi adalah tahap setelah tanda denotatif. Tahap ini menghubungkan makna tanda yang ditemukan dari hasil identifikasi penanda dan petanda sebelumnya dengan makna tanda dari hasil interaksi dengan pengguna tanda berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang saat tanda diproduksi. Nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang berkembang pada saat majalah
Juitan Lase. Penggambaran Perempuan di ...
45
Popular terbit dapat diamati dari peralihan pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi hingga sekarang ini. Penciptaan realitas tubuh perempuan di sampul majalah Popular tentu tidak bisa dilepaskan dari tren yang mengemuka pada masa itu. Tahap konotasi ini memberikan ruang untuk memahami bagaimana realitas itu tidak sebatas ditangkap atau dimediasi, tetapi juga diseleksi oleh awak media dan ditampilkan di sampul majalah.
O’Sullivan, dkk. (1994, h. 288) menjelaskan bahwa mitos adalah tingkatan kedua dari tahap konotasi. Mitos tidak kasat mata dan tidak mudah dideteksi. Mitos tumbuh subur dalam bentuk wicara melalui wacana. Mitos memiliki fungsi ganda, yakni selain menunjukkan, menjelaskan, dan membuat kita paham makna tanda, di saat yang sama mitos juga memaksakan keberadaannya kepada kita (Barthes, 1973). Mitos adalah sebuah upaya menaturalisasi suatu hal kepada kita, sehingga kita menerimanya sebagai sesuatu yang nyata dan benar, padahal hal tersebut sebenarnya merupakan sistem semiologis. Mitos akan berubah seiring dengan sejarah perkembangan manusia karena tidak statis
dan abadi. Hal yang diyakini dalam wicara hari ini, belum tentu memiliki wicara yang sama pada era berikutnya.
Tahap ketiga adalah tahap ideologi. Fiske dan Hartley (dalam O’Sullivan, dkk., 1994, h. 289) menyebutkan bahwa hasil dari pemaknaan konotasi dan mitos juga mengandung ideologi. Menurut Barthes (1967, h. 90), “ideology while connotation becomes natural”. Ideologi tercipta ketika konotasi menjadi sesuatu yang diterima, dianggap normal, dan lumrah oleh masyarakat. Hartley (2002, h. 106) menyatakan bahwa makna alami itu tidak hanya inheren pada sebuah peristiwa atau objek tertentu. Makna peristiwa dan benda yang dibangun selalu berorientasi sosial dan selaras dengan kelas, gender, ras, atau kepentingan lainnya. Ideologi yang termanifestasi itu tidak mudah terlihat. Fiske (1990, h. 176) mengatakan bahwa ideologi bekerja dengan cara menciptakan anggapan umum (common sense) pada tanda yang dimunculkan, sehingga masyarakat dengan mudah menerimanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada niat untuk mempertanyakannya.
Gambar 1 Proses SignifikasiSumber: O’Sullivan, dkk. (1994, h. 288)
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 41-56JurnalILMU KOMUNIKASI
46
HASIL
Salah satu hal yang dominan ditemukan pada sampul majalah Popular periode 1988-1991 adalah penggambaran perempuan dalam pose yang menunjukkan lekuk tubuh yang seksi, namun berpakaian sopan. Majalah ini menampilkan perempuan-perempuan muda seperti Paramita Rusady, Nike Ardilla, dan Ayu Azhari yang sedang populer pada masa itu. Kepopulerannya ini diafirmasi pada tulisan dalam kotak merah di sudut kanan bawah dalam majalah Popular edisi Desember 1990 tentang “Nominasi Artis Terpopular 1990/1991”. Nike Ardilla, misalnya, tampak tersenyum dengan mata yang sayu saat melihat ke kamera. Ayu Azhari pun tampak tersenyum lebar dan menunjukkan gigi. Ketiganya mengenakan baju yang cukup sopan, namun sama-sama membentuk lekukan, sehingga menonjolkan bagian tubuh mereka yang seksi.
Kesopanan tampaknya digunakan untuk mengafirmasi tagline “Mereka yang Berprestasi” yang diusung majalah Popular. Tagline ini diidentikkan oleh majalah Popular dengan kesuksesan, baik secara kepopuleran maupun materi, dan tetap menjaga kesopanan. Makna berprestasi selain berpakaian sopan adalah menjadi perempuan bermoral. Hal ini ditunjukkan dengan teks, “Paramitha Rusady: Itu Bukan Ciuman Birahi” (edisi Juli 1988), “Kathleen Turner: Saya Bukan Perempuan Jalang” (edisi Juli 1988), “Nike Ardilla Ogah Ciuman, Takut Hamil” (edisi Desember 1990). Citra berprestasi adalah citra yang positif, sedangkan berciuman, perempuan jalang, birahi, dan hamil adalah citra yang negatif. Berciuman tentu tidak
akan membuat orang hamil. Mengasosiasikan berciuman sama dengan bersenggama adalah mitos. Dalam sampul ini, orang yang berprestasi dikonstruksi sebagai orang yang tabu melakukan tindakan seksual, seperti berciuman dan hamil. Perempuan berprestasi adalah perempuan yang bermoral.
Pada periode 1992 hingga 1999, penggambaran perempuan di sampul majalah Popular mulai bergeser dari bermoral dan seksi ke sensual. Perempuan ditampilkan dengan pose tubuh yang seksi, postur badan yang tegak atau meliuk, mukanya sedikit menunduk, wajahnya tegas, dan tatapan melirik atau menoleh ke kamera dan dari kamera. Pada periode ini, ekspresi tersenyum mulai memudar. Penggunaan pakaian renang cukup dominan dan ikut membentuk lekuk tubuh, kulit, dan ketiak perempuan.
Salah satu tanda yang menarik pada penggambaran ini adalah bulu ketiak yang dibiarkan muncul dalam sampul. Bulu ketiak yang ditampilkan Djenar Maesa Ayu pada sampul edisi Oktober 1993, memediasi tren sejak 1970 hingga 1990-an yang turut dipopulerkan oleh salah satu aktris film Indonesia, Eva Arnaz, dalam filmnya berjudul “Maju Kena Mundur Kena”. Bulu ketiak kemudian dikenal pada massa itu sebagai simbol gairah seksual.
Menurut Hooper (2014), seorang fotografer asal Inggris, bulu ketiak pada tubuh perempuan menegaskan kecantikan yang alami. Dalam perkembangan tren kecantikan menjelang tahun 2000-an, bulu ketiak mulai dianggap mengganggu penampilan perempuan. Bulu ketiak diharamkan muncul dan dipamerkan di muka umum. Sampul-
Juitan Lase. Penggambaran Perempuan di ...
47
Gambar 2 Ragam Sampul Majalah PopularSumber: Majalah Popular Berbagai Edisi
Paramitha Rusady Juli 1988
Nike Ardilla Desember 1990
Ayu AzhariNovember 1991
Djenar Maesa AyuOktober 1993
Keke SuryoMaret 1995
Sophia LatjubaJuli, 1999
Sarah AzhariJanuari 2004
Novi Billgie Purwono Agustus 2009
Ayu AuliaAgustus 2015
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 41-56JurnalILMU KOMUNIKASI
48
sampul majalah yang muncul belakangan itu sudah tidak pernah lagi menampilkan model dengan bulu ketiak, termasuk model yang ditampilkan di majalah Popular.
Penekanan pada bentuk tubuh yang langsing, tatapan tajam, bulu ketiak, dan latar laut semakin memperjelas makna bahwa perempuan ideal memiliki bentuk tubuh dan seksualitas yang aktif, modern, dan alami. Tubuh yang alami adalah penanda tradisi yang dianggap sebagai tubuh yang tunduk dan patuh. Menurut Said (1978), alami adalah sebuah mitos eksotis dan tradisional yang ditujukan kepada perempuan pribumi yang disebut exotic other, untuk menandai oposisi biner dari kecantikan ideal perempuan Barat. Hal ini ditemukan pada sampul edisi Mei 1999 yang menampilkan Sophia Latjuba. Sophia Latjuba dalam sampul tersebut digambarkan tampak telanjang dan tidak ada penonjolan bagian tubuh yang provokatif dibandingkan pada sampul-sampul majalah Popular di era 2000-an. Ideologi yang diciptakan oleh majalah Popular adalah ketelanjangan Sophia Latjuba sebagai perempuan berdarah Eropa (indo) yang menawarkan kompleksitas tentang budaya representasi dalam citra positif. Rubrik editorial majalah Popular edisi September 1997 menyebutkan bahwa model yang ditampilkan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu:
Tidak semua model berwajah cantik bisa dan memenuhi syarat untuk foto dengan pakaian renang, sebab tubuhnya harus proporsional dan punya rasa percaya diri yang besar. “Susahnya, struktur tubuh Asia, pada umumnya kurang bagus. Belum lagi memelihara tubuh belum jadi bagian hidup,” kata Cintya Lumanauw, pengarah
gaya yang sering menangani pemotretan popular (pop). Karena itulah, Anda tak perlu heran, jika model-model yang bagus, umumnya wanita indo. (Rubrik Editorial, majalah Popular, 1997)
Tubuh yang proporsional, wajah cantik, dan punya rasa percaya diri adalah tiga kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang model yang tampil di sampul majalah Popular. Kriteria ini juga semakin mengerucutkan pilihan ideal kepada perempuan indo yang dianggap sebagai representasi ideal itu sendiri. Majalah Popular menanamkan bahwa tubuh perempuan ideal adalah tubuh yang seksi, menonjolkan seksualitasnya, dan indo. Ketika tampil sebagai model sampul, Sophia Latjuba menjadi simbol perempuan ideal. Majalah Popular melalui representasi indo menanamkan ideologi dominan yang mengagungkan Barat sebagai ras yang superior dan ideal.
Penggambaran perempuan pada edisi 2000-2018 tidak berbeda jauh dari sebelumnya. Perbedaannya adalah penonjolan bagian-bagian tubuh yang tidak hanya dimaknai secara sensual, tetapi lebih berani dan tegas sebagai perempuan seksual. Sarah Azhari pada edisi Januari 2004, misalnya, secara konotatif menampilkan ekspresi percaya diri, provokatif, dan sensual. Rasa percaya diri ditandai oleh ekspresi wajah yang tegas, tatapan mata yang tinggi, dan tubuh yang condong ke depan. Sikap tubuh yang provokatif dan sensual ditandai dengan bibir yang terbuka, menonjolkan bagian dada, perut, lengan dan rambut yang basah.
Penggambaran perempuan dalam rentang edisi tersebut juga menampilkan Novi Billgie
Juitan Lase. Penggambaran Perempuan di ...
49
Purwono pada edisi Agustus 2009. Bagian tubuhnya terbentuk karena penggunaan pakaian renang yang menonjolkan payudara, bahu, perut, dan paha. Rambutnya yang hitam bergelombang diurai ke sisi kanan hingga menutupi sebagian payudara kanannya. Tatapan matanya tajam mengarah pada mata kamera. Bibirnya sedikit terbuka dengan gincu berwarna nude peach. Tubuhnya agak menonjolkan bagian dada ke depan. Bagian wajah, tatapan mata yang tajam, dan bibir yang sedikit terbuka mengarah pada pemaknaan tegas akan perempuan yang seksi.
Pada edisi Desember 2012, penggam-baran perempuan ditunjukkan melalui gaya Tina Toon. Tina Toon tampil dengan busana kimono berwarna merah dan gaya rambut yang mirip perempuan tradisional Tiongkok. Kimono berwarna merah tampak kontras dengan latar hitam sampulnya, sehingga me-nonjolkan tubuh Tina Toon, terutama bagian tulang selangka, dada, dan paha. Gerakan tangannya tampak sedang menarik bagian kerah kimononya, sehingga menghasilkan performa seksual yang menggoda.
Gambar 3 Pose Tina ToonSumber: Sampul Majalah Popular Edisi Desember 2012
Sementara itu, Ayu Aulia yang tampil pada edisi Agustus 2015 ditampilkan maskulin. Hal ini ditandai dengan tato rajah pada bagian tubuh. Terdapat empat tato di tubuh sang model: dua berada pada lengan kanan, satu pada lengan kiri, dan satu lagi pada bagian dada kiri atas. Tanda maskulin lain yang ditunjukkan adalah sebuah tongkat yang dipegang oleh Ayu Aulia.
Secara konotatif, ekspresi percaya diri, provokatif, dan seksual menggiring pemaknaan pada citra tubuh yang tak hanya seksi, tetapi juga sensual. Penggambaran subjek seksual ini juga semakin ditegaskan melalui teks-teks majalah tersebut. Majalah Popular edisi Januari 2004, misalnya, menampilkan teks “Sex in the water: Dari Variasi, Kenikmatan & Kesehatan”, “Seks Tanpa Status”, dan “Mami-mami Online”; edisi Agustus 2009 menampilkan teks “Selingkuh Awas Mengintai”, “Mengintip Bisnis Mucikari Kakap”, serta “Do You Have A Unique ‘Bird’ Tentukan Posisi Bercinta Anda”; dan edisi Agustus 2015 yang menampilkan teks “Sensasi No Bra di Teras little Tokyo” dan “Durasi, Irama, dan Waktu Terbaik Bercinta”.
Tanda perempuan dan teks-teks seksual yang muncul di sampul ini adalah tanda yang mengarah pada mitos kenikmatan laki-laki. Perempuan dan seks adalah dua hal yang menjadi objek hiburan laki-laki. Dalam sampul majalah Popular, Sarah Azhari, Novi Billgie Purwono, Tina Toon, dan Ayu Aulia tidak ditampilkan dalam pose yang pasif melainkan aktif, berani, provokatif, dan maskulin. Asumsinya adalah ada upaya membalikkan anggapan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 41-56JurnalILMU KOMUNIKASI
50
umum yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa seks dan perempuan. Seksualitas perempuan dijadikan sebagai kekuatan dan senjata. Seksualitas perempuan adalah milik perempuan itu sendiri. Tabu-tabu seksual yang dipelihara masyarakat pada periode sebelumnya yang menyebut perilaku tersebut sebagai perilaku tidak bermoral tampaknya tidak berlaku lagi.
PEMBAHASAN
Hasil analisis terhadap sampul majalah Popular periode tahun 1988-2018 menunjukkan bahwa perempuan di-gambar kan sebagai objek dan subjek seksual. Sampul-sampul yang menunjukkan perempuan sebagai objek seksual ditemukan pada edisi 1988-1999, sementara edisi 2000-an menampilkan perempuan sebagai subjek seksual. Penggambaran perempuan sebagai objek seksual ditandai melalui representasi pose seksual pasif, penonjolan lekuk tubuh, tatapan mata malu-malu, dan bibir yang tersenyum. Ekspresi tersenyum dominan ditemukan pada model yang ditampilkan pada sampul edisi 1988-1991. Hal ini, misalnya, ditemukan pada sampul yang menampilkan Nike Ardilla pada edisi Desember 1990 dan Ayu Azhari pada edisi November 1991.
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perempuan dalam sampul majalah Popular tetap diobjektifikasi kendati mereka tidak ditampilkan secara seksual. Objektifikasi ini terlihat melalui penonjolan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti belahan dada, paha, dan lekukan tubuh, sehingga menciptakan citra perempuan seksi dan menjadi objek sasaran moral bangsa.
Perempuan pada periode ini diharapkan menjadi perempuan yang berprestasi dan bermoral, bukan sebaliknya.
Implikasi menjadi perempuan tidak bermoral cukup pelik pada periode ini (Brenner 1999, h. 33). Perempuan diberi beban tanggung jawab untuk menjaga moral bangsa, mendidik anak, serta menjaga martabat suami dan keluarga. Pandangan ini termanifestasi melalui ideologi konco wingking yang dilegitimasi melalui organisasi perempuan, seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Rahayu, 2004, h. 426; Suryakusuma, 1998, h. 113). Media mereproduksi ideologi ini untuk mengontrol perempuan sebagai objek sasaran kebijakan dan menjadi objek kenikmatan seksual.
Penggambaran perempuan pada edisi 1992-an menunjukkan penonjolan tubuh seksual perempuan yang berbeda daripada periode sebelumnya. Berdasarkan pengamatan, konsep pakaian renang mulai digunakan oleh majalah Popular sejak 1991. Konsep ini juga telah digunakan sejumlah majalah pria yang terbit pada 1980-an (Junaedhie, 1995; Lesmana, 1995). Konsep ini masih menjadi tren di majalah-majalah pria hingga saat ini. Penggunaan pakaian renang telah mendorong perubahan pemilihan latar gambar yang banyak mengambil lokasi di kolam renang atau pantai. Hal ini untuk menghindari teguran dari Departemen Penerangan (istilah yang digunakan pada masa Orde Baru) yang menginstruksikan pengelola majalah agar tidak memublikasikan materi pornografi.
Juitan Lase. Penggambaran Perempuan di ...
51
Sejak model-model sampul tampil di majalah Popular dengan pakaian renang, pakaian renang telah menjadi penanda properti tubuh perempuan (Gill 2007, h. 150). Ada sebuah proses internalisasi dan naturalisasi pakaian renang terhadap tubuh perempuan yang kemudian menciptakan mitos perempuan bikini. Masyarakat pun mengarahkan pandangan dan penilaiannya pada sosok perempuan seksual dengan payudara yang besar, bokong padat, perut langsing, tubuh semampai, kulit putih, dan rambut panjang. Citra semacam inilah yang dibangun oleh majalah Popular sebagai pandangan umum tentang tubuh perempuan yang ideal.
Penggambaran Djenar Maesa Ayu pada edisi Oktober 1993 dan Keke Suryo pada edisi Maret 1995 menunjukkan bagian tubuh seksual, namun tidak ditunjukkan dalam ekspresi yang mandiri, provokatif, dan percaya diri. Bentuk pose tubuh, ekspresi wajah, dan tatapan yang tidak tegas mengarahkan pada posisi ditatap daripada menatap mata kamera. Hal ini kemudian dimaknai sebagai bentuk penggambaran perempuan sebagai objek seksual daripada subjek seksual.
Hal yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh Sophia Latjuba yang tampil telanjang pada edisi Mei 1999. Secara awam, ketelanjangan dapat dimaknai sebagai objektifikasi, namun pada sampul ini, ketelanjangan dapat di maknai sebaliknya. Menurut Berger (1972, h. 54), ketelanjangan dibedakan menjadi dua: nakedness dan nudity. Nakedness dan nudity adalah dua terminologi yang mengandung makna yang berbeda.
To be naked is to be oneself. To be nude is to be seen naked by others and yet not recognized for oneself. A naked body has to be seen as an object in order to become a nude (the sight of it as an object stimulates the use of it as an object). Nakedness reveals itself. Nudity is placed on display. To be naked is to be without disguise. To be on display is to have the surface of one’s own skin, the hairs of one’s own body, turned into a disguise which, in that situation, can never be discarded. The nude is condemned to never being naked. Nudity is a form of dress. (Berger, 1972, h. 54)
Argumen Berger berangkat dari analisisnya terhadap lukisan Old Master (genre bagi pelukis Eropa yang melukis sebelum tahun 1800) yang melukis tubuh perempuan dalam kondisi telanjang. Menurut Berger (1972, h. 51), perempuan ditampilkan telanjang karena laki-laki memang ingin melihatnya telanjang. Dalam sampul majalah Popular, Sophia Latjuba menyadari ketelanjangannya. Ketelanjangan itu diguna kan untuk menunjukkan kekuasaannya. Ketika seorang model difoto, model juga turut berkontribusi memengaruhi bagaimana model tersebut hendak ditangkap kamera. Sophia Latjuba pun tidak kehilangan kekuasaan atas tubuhnya. Sophia Latjuba tampil dengan percaya diri, menatap langsung pada lensa kamera, serta tidak mengeksploitasi bagian dada, perut, dan tulang selangka. Kesan ketelanjangan yang ditampilkan Sophia Latjuba mengarah pada tubuh yang aktif dan berkuasa atas tubuhnya.
Setelah Sophia Latjuba, penggambaran perempuan semakin menonjolkan bagian-bagian tubuh, seperti buah dada yang besar, tulang selangka yang menonjol, paha yang kurus, dan tatapan mata
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 41-56JurnalILMU KOMUNIKASI
52
seksual dan provokatif sebagai bagian dari properti tubuh (Gill 2003; 2007) melalui maskulinitas tubuh feminin (McRobbie 2004; 2009). Ekspresi semacam inilah yang mengarah pada pemaknaan tubuh seksual yang merujuk pada penciptaan perempuan sebagai subjek seksual (Gill, 2003, h. 101-103).
Terkait maskulinitas tubuh feminin, istilah maskulin biasanya diasosiasikan dengan laki-laki (Rubin, 1997). Identitas gender maskulin mendefinisikan laki-laki sebagai makhluk yang perkasa, sensual, dan rasional. Maskulinitas dalam analisis ini disimbolkan lewat aksi survival, tato, perang, dan senjata (tongkat). Tanda-tanda ini memitoskan identitas gender feminin yang selama ini dikonstruksikan kepada perempuan dan membentuk identitas perempuan maskulin.
McRobbie (2009, h. 85) menyebutnya fallic girl, yakni perempuan yang berani menonjolkan seksualitasnya dan mem-pertahankan feminitasnya sebagai bentuk kekuasaan untuk menaklukkan laki-laki yang mereka inginkan. Menurut McRobbie (2009, h, 85), perilaku fallic girl ini menyebarkan nilai-nilai yang menantang dominasi patriarki yang mengonstruksi perempuan dalam dikotomi perempuan nakal dan perempuan baik-baik. Resistensi terhadap dominasi patriarki dalam sampul ini ditegaskan lewat tanda-tanda tato, tongkat, dan sensualitas sang model. Namun, teks “Swimsuit Survivor” menandai perempuan seksual yang maskulin.
Majalah Popular menawarkan ideologi tentang dunia laki-laki melalui
tagline “Entertainment For Men”, “Talk About Men’s World”, “#1 Men’s Magazine in Indonesia”, serta “Every Man Needs a Breaks” dan perempuan menjadi bagian dari dunia tersebut. Menurut Laura dalam Handajani (2010, h. 160), “man cannot bear the burden of objectification”. Handajani (2010, h. 160-161) berargumen karena laki-laki tidak mampu menanggung beban objektifikasi tersebut, maka laki-laki memerlukan bentuk ekspresi kekuasaan dan dominasinya terhadap perempuan.
Representations of sexualized women in these magazines contribute to a discourse of male agency in the Indonesia socio-political context. Male agency in this case is a reaction from a subordinated group of men to express their male power by using women as the tokens of their power. (Handajani, 2010, h. 160-161)
Laki-laki membutuhkan seksualitas perempuan untuk memperkuat ideologi maskulinitas dalam majalah Popular. Menguasai secara seksual sama halnya dengan meletakkan perempuan di bawah kekuasaannya. Menurut Bourdieu (2001, h. 20-21), tindakan menguasai atau menaklukkan perempuan tidak selalu bertujuan untuk kepemilikan seksual, tetapi dapat mengarah pada penguasaan secara singkat untuk mengafirmasi dominasi laki-laki terhadap perempuan.
Penggambaran perempuan sebagai subjek seksual di sampul majalah Popular ini menjadi penting dipertanyakan. Hatton & Trautner (2013) menyatakan bahwa perempuan yang menjadi subjek seksual memiliki kesadaran gender (choice feminism). Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan sebagai subjek seksual masih terbatas pada kelompok perempuan
Juitan Lase. Penggambaran Perempuan di ...
53
tertentu. Perempuan yang menjadi subjek seksual dalam sampul majalah Popular terbatas pada mereka yang berprofesi sebagai model dan aktris. Mereka memiliki kecantikan ideal, yakni berkulit putih, bertubuh langsing, dan muda. Tidak ditemukan satu pun model yang bertubuh gemuk, berkeriput, dan tua. Hal ini akan terus menjadi lingkaran penindasan bagi perempuan karena kekuasaan lewat kecantikan tidak akan bertahan selamanya. Hal ini pun mampu mendorong perempuan pada upaya-upaya mempertahankan kecantikan dengan cara yang menyakiti tubuh seperti operasi plastik.
Penggambaran perempuan sebagai subjek seksual di media massa hanya memberikan perempuan kekuasaan semu dalam menampilkan dirinya sendiri sesuai keinginannya. Namun, kekuasan perempuan melalui kecantikan, tubuh langsing, dada dan pantat yang besar, kulit putih, dan muda justru menjadi rezim pendisiplinan baru terhadap tubuh perempuan (Gill, 2003, h. 106). Pendisiplinan baru ini bukan berasal dari luar, tetapi dari dirinya yang terperangkap dalam mitos sebagai subjek seksual itu sendiri.
SIMPULAN
Penggambaran perempuan di sampul majalah Popular dilakukan melalui dua bentuk, yaitu sebagai objek dan subjek seksual. Temuan ini menjawab tujuan penelitian, yaitu ada pergeseran penggambaran perempuan dari tahun ke tahun berdasarkan sampel analisis. Pergeseran tersebut ditandai dengan
penggambaran perempuan sebagai objek seksual yang dominan ditemukan pada sampul edisi 1988 hingga 1999, sedangkan sampul majalah pada edisi 2000-2018 dominan menggambarkan perempuan sebagai subjek seksual. Implikasi dari penggambaran tersebut adalah perempuan yang digambarkan sebagai objek seksual diobjektifikasi sebagai objek melalui pose seksual pasif. Saat perempuan digambarkan sebagai subjek seksual, perempuan seolah-olah berkuasa atas dirinya sendiri, mandiri, dan dominan.
Media tampak telah berlaku adil bagi perempuan, padahal penggambaran perempuan sebagai subjek seksual ini mengalami persoalan. Pertama, hanya perempuan dengan kriteria tertentu yang diberikan tempat demikian, yakni mereka yang masih menarik secara seksual, seperti berkulit putih, langsing, dan cantik. Mereka yang bertubuh gemuk, keriput, dan lebih tua tidak berada pada posisi yang sama sebagai subjek seksual. Tidak semua perempuan bisa direpresentasikan sebagai subjek. Majalah Popular seolah-olah memberikan pilihan bagi perempuan untuk berkuasa atas dirinya, namun terbatas pada perempuan yang memenuhi standar kecantikan ideal tertentu.
Kedua, perempuan yang ditampilkan sebagai subjek seksual ini semakin terjebak dalam mitos kecantikan itu sendiri. Tubuh yang ideal adalah tubuh yang sensual, maka bentuk tubuh, seperti payudara, pantat, berat badan hingga warna kulit menjadi momok yang mati-matian dijaga oleh perempuan. Dalam kondisi ini, mitos
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 41-56JurnalILMU KOMUNIKASI
54
tubuh ideal akan terus menghantui, baik secara fisik maupun psikologis perempuan. Ketiga, jebakan mitos kecantikan lewat tubuh seksual tersebut merupakan bentuk pendisiplinan baru bagi tubuh perempuan.
Penggambaran perempuan sebagai subjek seksual bukan untuk memperjuangkan perempuan menjadi berkuasa dan mandiri. Media tidak benar-benar memberikan kekuasaan bagi perempuan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara kerja media yang berdasarkan logika kapitalistik-patriarki. Majalah Popular sebagai majalah pria yang masih bertahan di Indonesia perlu mengevaluasi dan melakukan autokritik pada pilihan-pilihan penggambaran perempuan di sampulnya. Majalah Popular tidak hanya mengobjektifikasi, tetapi menampikan bentuk-bentuk penggambaran secara provokatif dan seksual aktif dengan pretensi girl power yang sebenarnya adalah eksploitasi.
DAFTAR RUJUKAN
Barthes, R. (1967). Elemens of semiology. London, UK: Jonathan Cape.
-------------. (1973). Mythologies. London, UK: Paladin Grafton.
Berger, J. (1972). The ways of seeing. London, UK: British Broadcasting Corporations.
Bourdieu, P. (2001). Masculine domination. Standford, California: Stanford University Press.
Brenner, S. (1999). On public intimacy of the New Order: Images of women in the popular Indonesian print media. Indonesia, 67, 13-37.
Fiske, J. (1990). Introducation to communication studies. London & New York, NY: Rotledge.
Gill, R. (2003). From sexual objectification to sexual subjectification: The resexualisation of women’s bodies in the media. Feminist Media Studies, 3(1), 100-106.
----------. (2007). Postfeminist media culture: Elements of a sensibility. European Journal of Cultural Studies, 10(2), 147-166.
Handajani, S. (2010). Selling alternative masculinities: Representations of masculinities in Indonesia men’s lifestyle magazine. Disertasi Doktoral. Tidak Diterbitkan. Universitas Western Australia, Australia.
Handajani, S. (2014). Let’s judge a magazine by its cover: A textual analysis of the covers of Gadis. Jurnal Wacana, 15(1), 87-103.
Hatton, E., & Trautner, M. N. (2013). Images of powerful women in the age of ‘choice feminism’. Journal of Gender Studies, 22(1), 65–78.
Hartley, J. (2002). Communication, cultural and media studies, the key concept (3rd). London, UK: Routledge.
Hooper, B. (2014). Natural beauty new photo project. Therealbenhopper.com. <http://blog.therealbenhopper.com/2014/04/08/natural-beauty-new-photo-project/>
Junaedhie, K. (1995). Rahasia dapur majalah di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
Lesmana, T. (1995). Pornografi dalam media massa. Jakarta, Indonesia: Penebar Swadaya.
McRobbie, A. (2004). Postfeminism and popular culture. Feminist Media Studies, 4(3), 255-264.
----------------. (2009). The aftermath of feminism: Gender, culture and cocial change. London, UK: Sage Publication Ltd.
O’Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., Montgomery, M, & Fiske, J. (1994). Key concepts in communication and cultural studies (eds). London, UK: Routledge.
Rahayu, R. I. (2004). Politik gender Orde Baru: Tinjauan organisasi perempuan sejak 1980-an. Dalam Liza Hadiz, Perempuan dalam wacana politik Orde Baru (h. 421-449). Jakarta, Indonesia: LP3ES.
Rubin, G. (1997). The traffic in women. Dalam Linda Nicholson, The second wave. A reader in feminist theory (p. 157-210). New York, NY: Routledge.
Juitan Lase. Penggambaran Perempuan di ...
55
Said, E. W. (1978). Orientalism. London and Henley, UK: Routledge & Kegan Paul.
Sebeok, T. A. (2001). Signs: An introduction to semiotics (2nd). New York, NY: Random House Inc.
Sulistyani, H. D. (2011). Korban dan kuasa di dalam kajian kekerasan terhadap perempuan. Jurnal Forum, 39 (2), 20-24.
Suryakusuma, J. (1998). Beban muskil majalah wanita. Dalam Idi Subandi Ibrahim dan Hanif Suranto, Wanita dan media: Konstruksi ideologi gender dalam ruang publik Orde Baru (h. 112-115). Bandung, Indonesia: Remaja Rosda Karya.
Van Zoonen, L. (1994). Feminist media studies. London, UK: Sage Publication Ltd.
57
Komunikasi Partisipatif Panda CLICK! di Bunut Hilir
Mario Antonius BirowoUniversitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 6, Yogyakarta 55281Email: [email protected]
Abstract: It is often difficult for people at the grassroots level to gain access to public sphere due to limited access to bottom-up voices. Participatory communication put people as subjects in the communication process. This research uses a case study method to understand participatory communication using photovoice. To empower community in Bunut Hilir, Kapuas Hulu Regency, photovoice of Panda CLICK! is used by WWF West Kalimantan to enable community to express their ideas, especially on environmental issues. Kapuas Hulu Regency is known as a conservation area. Community uses digital pocket cameras because its ease of use to express their ideas with photos.
Keywords: environment, Panda CLICK!, participatory communication, photovoice
Abstrak: Sering kali masyarakat di tingkat akar rumput sulit mendapatkan akses ke ruang publik karena akses yang terbatas bagi partisipasi masyarakat bawah. Komunikasi partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tujuan memahami komunikasi partisipatif dengan menggunakan photovoice yang bernama Panda CLICK!. WWF Kalimantan Barat memberdayakan masyarakat Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan photovoice. Kabupaten Kapuas Hulu dikenal sebagai wilayah konservasi lingkungan. Photovoice bertujuan agar masyarakat memiliki akses untuk menyatakan gagasan atau pikirannya, khususnya tentang isu lingkungan. Masyarakat difasilitasi kamera saku digital sederhana untuk berekspresi.
Kata Kunci: komunikasi partisipatif, lingkungan, Panda CLICK!, photovoice
Persoalan lingkungan semakin mengemuka pascabencana alam akibat degradasi kondisi lingkungan. Berbagai cuaca ekstrem bermunculan, seperti hujan sangat deras yang mendatangkan longsor atau banjir; kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen, kebakaran hutan serta krisis air bersih; angin kencang atau topan yang merusak rumah-rumah dan bangunan lainnya; peningkatan suhu yang menyebabkan naiknya permukaan laut; serta kerusakan lingkungan di seputar
pantai karena abrasi dan intrusi air laut ke daratan. Intrusi air laut/asin membuat kerusakan pada keragaman hayati. Perubahan iklim yang menimbulkan ketidakpastian dan munculnya cuaca ekstrem merupakan akibat dari efek rumah kaca yang disebabkan meningkatnya gas tertentu, antara lain karbon dioksida (CO2), metana (CH2), dan nitrous oksida (N2O) di atmosfer bumi (Benson, 2008, h. 210).
Hutan merupakan salah satu penentu pengaturan iklim, sehingga perubahan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 57-74JurnalILMU KOMUNIKASI
58
kondisi hutan akan berpengaruh pada keadaan iklim di dunia. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan isu pelestarian lingkungan sebagai salah satu tujuan dari Millennium Development Goals (MDGs) (UN, 2008, h. 2). Penetapan tersebut menyatakan sudah waktunya dunia menaruh perhatian pada peningkatan kualitas lingkungan.
Luasan hutan tropis Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. Indonesia memiliki posisi penting di mata dunia mengingat manfaat hutan sebagai gudang keanekaragaman hayati dan bank lingkungan global karena menyerap CO2 dan menghasilkan O2 (Sumargo, Nanggara, Nainggolan, & Apriani, 2011, h. 1; WWF, 2013).
Kalimantan memiliki kawasan yang dikenal dengan sebutan The Heart of Borneo. Kawasan seluas 22 juta hektar tersebut mencakup tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kawasan ini merupakan tempat bagi hutan khatulistiwa yang kaya keanekaragaman hayatinya. Hutan di Pulau Kalimantan saat ini terancam. Forrest Watch Indonesia mencatat bahwa laju deforestasi di Kalimantan antara tahun 2000-2009 adalah 550.586,39 hektar/tahun. Hal ini merupakan deforestasi terbesar di Indonesia (Sumargo, dkk., 2011). Catatan lain menunjukkan bahwa deforestasi yang tinggi ini diperkirakan mencapai 1,17 juta hektar/tahun antara tahun 2003-2006 di seluruh wilayah Indonesia (Indrarto, dkk., 2012, h. 3).
Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, misalnya, World Wide Fund for Nature-Indonesia (WWF-Indonesia) mencatat pertambahan areal perkebunan kelapa sawit dari 931,84 hektar pada tahun 1990 menjadi 67.729,35 hektar pada tahun 2016 (Albertus Tjiu, Program Manajer WWF Kalimantan Barat, wawancara, 11 Maret 2018). Penebangan hutan di Kalimantan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal dan dunia karena dampaknya pada perubahan iklim global. Tercatat 12 juta jiwa masyarakat lokal bergantung pada kelestarian hutan Kalimantan (ADB, 2013). Pemerintah Indonesia menetapkan adanya hutan konservasi seluas 27.429.555,99 hektar agar kawasan hutan tetap terjaga (BPS, 2017).
Kerusakan hutan semakin parah karena adanya kebakaran hutan yang merupakan suatu bencana dominan akibat ulah manusia. Indonesia mengalami kebakaran hutan setiap tahun dan para pelaku pembakaran terkesan tidak memiliki efek jera. Pada tahun 2019, persoalan kebakaran hutan meningkat bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Data pada Januari-September 2019, wilayah yang terbakar mencapai 328.000 hektar. Dampak kebakaran hutan meliputi kerugian sekitar US$ 5.000.000 pada lahan seluas 8.000.000 hektar. Asap kebakaran dirasakan sampai beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina (Tobing, 2019).
Masyarakat lokal berada di posisi paling rentan karena dampak kerusakan
Mario Antonius Birowo. Komunikasi Partisipatif Panda ...
59
lingkungan langsung mengimbas mereka. Mereka tinggal di wilayah terpencil yang jauh dari perhatian pemerintah dan pusat-pusat forum ilmiah. Padahal, partisipasi mereka sangat penting dalam pemecahan masalah kerusakan lingkungan.
Salah satu upaya membangun partisipasi masyarakat adalah melalui penggunaan media foto (photovoice). Mereka dapat menyuarakan idenya dengan menampilkan foto-foto yang direkam berdasarkan kacamata mereka. Photovoice untuk pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di berbagai tempat dan isu, seperti climate change di Australia (Baldwin & Chandler, 2010), peran perempuan di bidang pertanian di Rwanda (Gervais & Rivard, 2013), kesehatan seksual dan reproduksi pekerja seks di Bali (Lestari, Sulistiowati, & Natalya, 2016), serta masalah kesehatan dan lingkungan di Kenya (Bisung, Elliott, Abudho, Karanja, & Schuster-Wallace, 2015). Persoalan lingkungan juga diangkat dalam laporan penelitian kaum muda di Lebanon mengenai konservasi (Mattouk & Talhouk, 2017).
Penelitian ini memiliki kebaruan karena belum ada studi tentang penggunaan photovoice untuk program penyelamatan lingkungan di wilayah hutan Kalimantan. Photovoice merupakan metode berbasis partisipasi masyarakat yang hanya bisa dijalankan pada sistem demokratis. Kesadaran kritis juga dapat didorong dengan photovoice melalui proses reflektif (Wang & Pies, 2004; Bendell & Sylvestre, 2016; Carroll, Garroutte, Noonan, & Buchwald, 2018). Photovoice adalah
konsep public sphere karena membahas perspektif demokrasi dan komunikasi (Fuller, 2007; Howley, 2005; Liebenberg, 2018). Habermas menyatakan bahwa konsep public sphere memerlukan adanya akses masyarakat ke ruang publik di mana mereka bisa mendiskusikan gagasan-gagasannya, membangun kesamaan pengertian tentang masalah-masalah bersama, dan memperoleh posisi yang sama di dalam proses komunikasi (Habermas, 1989).
Sementara itu, Freire (1983) menawarkan pendekatan kesadaran kritis bagi masyarakat. Menurut Freire (1983), aktivitas pemberdayaan masyarakat harus mampu membangun kesadaran masyarakat atas situasi yang menindas atau tidak menguntungkan. Pembangunan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan komunikasi partisipatif di mana masyarakat ditempatkan pada posisi subjek dalam proses komunikasi. Pemikiran Freire tersebut memberi inspirasi pada pendekatan yang digunakan dalam photovoice (Wang & Pies, 2004).
Program pemberdayaan bagi kelompok marginal harus membuka peluang bagi pergeseran posisi mereka sebagai konsumen menjadi produsen pesan, sehingga mengubah struktur komunikasi yang bersifat satu arah menjadi dua arah (Rennie, 2006). Salah satu media alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berekspresi adalah media foto (Royce, Parra-Medina, & Messias, 2006). Kekuatan foto sebagai pengangkat isu-isu sosial sudah dikenal sejak abad ke-
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 57-74JurnalILMU KOMUNIKASI
60
19 (Chandler & Baldwin, 2010). Foto digunakan untuk memperkuat kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari perhatian pemerintah. Kegiatan komunikasi dengan menggunakan foto dikenal sebagai photovoice atau photonovela. Photovoice digunakan antara lain pada aspek lingkungan, kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, dan community building (Berbés-blázquez, 2012; Cornwall, Capibaribe, & Gonçalves, 2010; Nowell, Berkowitz, Deacon, & Foster-fishman, 2006; Teti, Murray, Johnson, & Binson, 2012; Wang, Susan, Hutchison, Bell, & Pestronk, 2004).
METODE
Photovoice merupakan bagian dari participatory action research yang melibatkan subjek penelitian (masyarakat) dalam proses pengumpulan data hingga menggunakan hasil penelitian untuk ditindaklanjuti dengan aksi. Metode ini berorientasi pada perspektif masyarakat dalam memahami lingkungannya (Nowell, Berkowitz, Deacon, & Foster-fishman, 2006; Teti, Murray, Johnson, & Binson, 2012; Wang & Pies, 2004; Bendell & Sylvestre, 2016). Pengumpul data adalah masyarakat dengan menggunakan kamera. Kamera digunakan untuk merekam kondisi lingkungan dan menampilkan realitas hidup sehari-hari di lingkungannya. Photovoice menyediakan data berbasis bukti-bukti foto yang dibuat oleh komunitas untuk merefleksikan realitas kehidupannya (Wang & Pies, 2004; Engle, 2013). Metode studi kasus digunakan untuk memahami
penerapan program photovoice serta melihat dinamika partisipasi masyarakat secara mendalam (Gervais & Rivard, 2013; Engle, 2013). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara. Pertama, wawancara informan, baik warga maupun staf WWF Kalimantan Barat. Kedua, observasi lapangan di lokasi pelaksanaan program Panda CLICK! di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dengan melibatkan diri dalam program pelatihan, pameran, dan proses pelaksanaan di masyarakat. Ketiga, menggali berbagai data sekunder untuk memahami penggunaan photovoice dalam upaya konservasi lingkungan di Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimatan Barat.
Kabupaten Kapuas Hulu terkenal sebagai kabupaten konservasi karena kekayaan alamnya. Sebagian besar wilayahnya masuk sebagai wilayah Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum. Di wilayah ini, hidup subspesies orang utan Pongo pygmaeus pygmaeus. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan subspesies orang utan ini dalam daftar yang paling terancam. Orang utan Kalimantan berkurang drastis hingga 60% antara tahun 1950 dan 2010, serta diperkirakan akan turun 22% antara tahun 2010 dan 2025 (IUCN, 2016).
Status sebagai kabupaten konservasi menuntut Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tanggung jawab khusus. Kawasan konservasi ini memiliki tugas dalam pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa,
Mario Antonius Birowo. Komunikasi Partisipatif Panda ...
61
serta ekosistemnya (Statistik Kehutanan Indonesia, 2011, h. 3). Bukanlah hal mudah menyandingkan pembangunan dan pelestarian alam di Kalimantan karena lahan hutan berubah menjadi areal pertambangan dan perkebunan. Di sisi lain, usaha pertambangan dan perkebunan dengan cepat dapat mendegradasi kualitas lingkungan. Degradasi lingkungan berpengaruh bagi masyarakat setempat karena hutan merupakan sumber kehidupan bagi mereka.
HASIL
Hasil studi ini memperkaya metode penelitian di bidang komunikasi, khusus-nya pada penyediaan data yang berbasis masyarakat. Perspektif masyarakat men-jadi hal utama karena mereka dapat menceritakan lingkungan kehidupannya sehari-hari melalui foto dan proses pen-ciptaan foto.
Proses penciptaan foto bermula dari pandangan mata yang notabene merupakan indra yang ajaib (Efransjah, 2013). Keajaiban tersebut ditandai dengan kemampuan mata menangkap stimulus visual, di mana mata menjadi bagian sensor tubuh manusia yang bermanfaat dalam pemaknaan dan respons terhadap situasi lingkungan. Segala sesuatu yang berada di seputar dirinya akan dipersepsi secara visual atau diberi pemaknaan. Pemaknaan tersebut akan menentukan tindakan seseorang.
Memotret dengan kamera merupakan kegiatan yang terkait art karena melibatkan keterampilan dan rasa dalam menangkap objek. Semua orang bisa melihat benda
yang sama dengan kamera, namun akan berbeda sudut pandang dan pemaknaannya. Perbedaan pemaknaan inilah yang terkait dengan ekspresi individu pemotret (fotografer). Foto bisa menjadi ekspresi atau pernyataan dari gagasan-gagasan yang dipikirkan pemotret.Sejarah Panda CLICK!
Panda CLICK! adalah program pendidikan lingkungan bagi masyarakat berbasis foto yang diinisiasi oleh WWF Kalimantan Barat sejak 2010 (Syahirsyah, Technical Support Unit WWF Kalimantan Barat, wawancara, 11 Februari 2018). Nama “Panda” diambil dari maskot WWF, yaitu beruang panda dari Tiongkok yang sedang terancam punah. Sedangkan kata “CLICK” berasal dari singkatan Communications Learning towards Innovative Change and Knowledge. Panda CLICK! dimaknai sebagai proses pembelajaran untuk perubahan dan penambahan pengetahuan dengan media foto. Kamera dan kegiatan memotret dipadukan untuk menggali data dan pengetahuan lokal yang berfokus pada isu lingkungan.
Program ini bermula ketika WWF Kalimantan Barat melihat areal di Desa Teluk Aur yang menjadi jalur migrasi orang utan dan keberadaan ikan arwana yang hampir punah. Hutan di sana masih terjaga dengan baik dan harus dijaga karena menjadi tempat hidup flora dan fauna. Wilayah tersebut dikenal sebagai The Heart of Borneo, yaitu jantungnya Pulau Kalimantan yang sangat kaya kenanekaragaman hayati. Kekayaan wilayah tersebut dilindungi dan masuk dalam wilayah Taman Nasional Danau Sentarum
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 57-74JurnalILMU KOMUNIKASI
62
(TNDS). Sebagian wilayah TNDS terletak di Kecamatan Bunut Hilir (Taman Nasional, 2013). Sejalan dengan upaya perlindungan kekayaan alam tersebut, WWF Kalimantan Barat meluncurkan Panda CLICK! yang bertujuan untuk menyediakan sarana komunikasi bagi masyarakat setempat. Fachrizal (2013, h. 12) menyatakan bahwa penyampaian sebuah pesan tidak melulu hanya dilakukan melalui bahasa lisan atau tulisan.
Panda CLICK! menjadi program pemberdayaan masyarakat yang diandalkan oleh WWF Kalimantan Barat. Program ini diminta untuk diterapkan di daerah-daerah lain, seperti di Sebangau, Kalimantan Tengah (2014-2016) (Fachrizal, 2016) dan tahun 2019 di Kapit, Serawak, Malaysia (Jengging, 2019). Panda CLICK! dilakukan bertahap karena pendekatan visual sudah dimulai sejak tahun 2000 dengan menggunakan dokumentasi video. Masyarakat menjadi aktor dalam dokumentasi tersebut, kemudian hasilnya didiskusikan pula oleh masyarakat. Teknologi penggunaan dokumentasi video terasa kompleks, meskipun memudahkan penyampaian pesan. Pada tahun 2008, melalui pendekatan antropologi visual, diperkenalkan photovoice. Albertus Tjiu (Program Manajer WWF Kalimantan Barat, wawancara, 2 September 2016) menyatakan bahwa WWF bekerja sama dengan Photovoice International melakukan photovoice di kawasan Danau Sentarum, Kapuas Hulu. Kawasan ini masuk dalam Taman Nasional Betung Kerihun–Taman Nasional Danau Sentarum (Fachrizal, 2013, h. 13). Program ini kemudian menjadi cikal bakal Panda CLICK! di beberapa
wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Panda CLICK! dilaksanakan di tiga dusun di Desa Teluk Aur, yaitu Dusun Puring, Dusun Jaung I, dan Dusun Jaung II. Dusun Puring dipilih karena dihuni oleh mayoritas etnik Melayu, sedangkan Dusun Jaung I dan II merupakan wilayah pemukiman etnik Dayak Iban. Jumlah penduduk di Dusun Puring 879 jiwa, Dusun Jaung I 138 jiwa, dan Dusun Jaung II 166 jiwa (Arman, 2013). Menurut Syamsuni Arman (Guru Besar Antropologi Universitas Tanjungpura Pontianak, wawancara, 26 April 2013), ada informasi menarik tentang lokasi tinggal para penduduk. Etnik Melayu lebih memilih tinggal di tepi Sungai Kapuas, sedangkan etnik Dayak Iban lebih memilih tinggal di pedalaman, yaitu di tepi Danau Pengelang dan di bukit di belakang Danau Pengelang.
Panda CLICK! menjadikan kamera sebagai alat masyarakat melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan. Mereka berkomunikasi tidak hanya menggunakan bahasa lisan dan tulisan, namun juga menggunakan foto. Proses pelaksanaan Panda CLICK! dibagi menjadi tiga kegiatan, yaitu pelatihan, praktik lapangan, dan pameran.Pelatihan
Pelatihan Panda CLICK! tahap I dilakukan tahun 2010 dengan melibatkan 30 masyarakat lokal dari empat desa, yaitu Desa Teluk Aur, Desa Empangau, Desa Meliau, dan Desa Kelawik. Evaluasi terhadap pelatihan ini menunjukkan keberhasilan karena dihasilkan foto
Mario Antonius Birowo. Komunikasi Partisipatif Panda ...
63
sebanyak 58.181 foto (Rizky & Widjaya, 2011). Foto-foto ini merupakan kekayaan berharga bagi komunitas karena foto-foto tersebut merekam berbagai macam data tentang flora dan fauna, serta aktivitas sosial budaya masyarakat.
Panda CLICK! diadakan kembali pada tahun 2011. Pelatihan dilakukan di Nanga Bunut, Ibu Kota Kecamatan Bunut Hilir, karena merupakan wilayah tinggal peserta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan beberapa alasan. Pertama, peserta tidak perlu meninggalkan pekerjaannya sehari-hari, terutama saat mencari nafkah. Seusai pelatihan peserta dapat melanjutkan pekerjaannya. Kedua, membangun kondisi pelatihan yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari karena peserta berada di wilayah yang dikenalinya. Situasi pelatihan pun tidak mengalami kesenjangan dengan kehidupan sehari-hari karena praktik memotret dapat dilakukan kapan pun. Kondisi tersebut relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengangkat isu lingkungan lokal sebagai milik bersama. Hal ini mempermudah warga untuk mengembangkan keterampilan yang diperoleh dari latihan. Peserta menghasilkan 229.181 foto dalam rentang satu tahun setelah pelatihan.
Peserta pelatihan sebanyak 26 orang dengan latar belakang profesi, usia, etnik, dan jenis kelamin yang berbeda. Mereka berasal dari tujuh desa, yakni Desa Bunut Hilir, Desa Bunut Tengah, Desa Etibab, Desa Kapuas Raya, Desa Ujung Pandang, Desa Teluk Aur, Desa Bunut Hulu (Rizky & Widjaya, 2011). Pemilihan peserta ini dilakukan agar karya
foto yang dihasilkan dapat bervariasi dan ide tentang konservasi alam dapat segera tersebar semakin luas. Profesi peserta antara lain nelayan, guru, perangkat desa, dan pengurus adat. Tiga peserta yang sudah dilatih pada tahap I akan dipilih sebagai fasilitator lokal untuk memudahkan konsultasi, koordinasi, dan diskusi hasil. Para fasilitator akan bertanggung jawab mengumpulkan karya foto peserta.
Pelatihan singkat dilaksanakan selama empat hari, yakni tanggal 30 Mei hingga 2 Juni 2011 dan terdiri dari materi di kelas dan lapangan. Pelatihan di hari pertama diawali dengan pengantar dari fasilitator WWF Kalimantan Barat mengenai situasi lingkungan, program kerja WWF di Kapuas Hulu, serta pengetahuan konservasi orang utan. Materi selanjutnya adalah penggunaan kamera sebagai alat perekam informasi lingkungan (alam dan sosial budaya). Pelatihan berpusat pada materi dasar-dasar fotografi dan teknik penggunaan kamera. Peserta mengembangkan keterampilannya berdasar pengalaman praktik langsung di lapangan.
Saat pelatihan, peserta Panda CLICK! tahap I ikut berbagi pengalaman. Mereka menjadi fasilitator pendamping lokal. Fasilitator lokal menampilkan hasil foto mereka yang berisi informasi kekayaan alam, mata pencaharian masyarakat, kehidupan sosial budaya, serta kekurangan/problem dan harapan pembangunan wilayah mereka. Semua presentasi menggunakan bahasa lokal dan bahasa Indonesia, serta diawali dan diakhiri dengan pantun yang merupakan kekhasan budaya mereka.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 57-74JurnalILMU KOMUNIKASI
64
Presentasi tersebut bagai men-demonstrasi kan pengetahuan yang mendalam, kepercayaan diri, serta kebanggaan atas tanah hidup mereka. Ungkapan kebanggaan tersebut terlihat pada pernyataan Suratno, salah satu peserta Panda CLICK! tahap I.
Sungai Kapuas beralur-alurBergelombang setiap hari Selamat datang di Teluk AurDesa permai kebanggaan kami
Pantun di atas menjadi pembuka untuk menyelami Desa Teluk Aur. Ada nuansa syukur atas keelokan alam Teluk Aur. Kekayaan alam merupakan anugerah bagi masyarakat yang bergantung pada alam. Pantun tersebut juga berfungsi sebagai ice breaking. Suasana kelas pun mencair. Ungkapan-ungkapan spontan berhamburan dari peserta dan suasana keakraban tampak di sana. Situasi ini merupakan salah satu keunggulan ketika pelatihan dilakukan di tempat dan bersama peserta yang tidak asing.
Presentasi dari fasilitator lokal lainnya mengajak peserta untuk menjaga kelestarian alam karena jika alam lestari maka penghidupan masyarakat pun lestari. Perhatian terhadap lingkungan nampak pula pantun yang dinyatakan Sudarso, salah satu peserta Panda CLICK! tahap I.
Indah warna burung kenari Terbang tinggi ke sana-sini Kami ingin arwana tetap lestari Karena itu adalah kebanggaan kami
Pantun di atas berangkat dari realitas ikan arwana yang merupakan salah satu andalan penghasilan masyarakat.
Sejak ditetapkan sebagai satwa pesona nasional bernilai ekonomi tinggi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional, ikan arwana menghadapi bahaya kepunahan karena banyak diburu. Karakteristik ikan arwana yang mudah stres dapat menjadi salah satu indikator kelestarian lingkungan sungai dan danau di wilayah mereka.
Tahap selanjutnya, peserta diajak hunting untuk memotret di sekitar area pelatihan. Peserta mencoba mempraktikkan materi yang didapatkan di kelas. Awalnya mereka saling memotret sesama peserta dengan berbagi pose. Tawa pun tak luput menjadi sasaran bidikan mereka. Pengalaman ini nampak menggembirakan bagi peserta karena proses belajar tersebut seperti halnya bermain. Perlahan-lahan beberapa peserta mulai mengalihkan perhatian pada objek di sekitar mereka. Ada yang mencoba berbagai fasilitas kamera, seperti macro untuk bunga-bunga kecil, dan landscape untuk pemandangan yang lebih luas. Sejak itu, keberanian memotret dari berbagai posisi semakin tampak. Beberapa peserta bertiarap memotret tanaman di bawah gertak (jalanan setapak terbuat dari kayu sebagai penghubung rumah-rumah).
Proses kreatif untuk mendapatkan foto unik pun berkembang. Mereka mulai asyik mengeksplorasi segala benda di sekitarnya sesuai minat masing-masing. Mereka segera memotret ketika ada anak-anak sekolah lewat. Beberapa peserta mulai beranjak menelusuri kampung Nanga Bunut dan memotret berbagai perilaku
Mario Antonius Birowo. Komunikasi Partisipatif Panda ...
65
dan aktivitas masyarakat. Peserta secara tidak sadar ikut melakukan pengumpulan data. Data-data tersebut berupa foto tentang berbagai aktivitas kehidupan sosial manusia dan kehidupan alam lingkungan. Data tidak disimpan atau dinikmati sendiri, namun didiskusikan di antara peserta. Awalnya diskusi membahas tentang teknik fotografi, dan berkembang menjadi forum untuk menautkan data dengan konteks lokal mereka.Praktik Lapangan
Fasilitator WWF-Indonesia melihat peserta mampu mengeksplorasi berbagai fasilitas kamera secara autodidak, sehingga dapat menghasilkan foto yang beragam tentang lingkungannya. Identifikasi tersebut didasarkan pada pengalaman pendampingan peserta pelatihan Panda CLICK! tahap I.
Sering kali peserta juga mencoba untuk menggunakan teknik-teknik fotografi yang tidak dilatihkan. Kepercayaan diri peserta akan kemampuan fotografi semakin meningkat ketika mereka sering melakukan praktik. Mereka mulai memberanikan diri untuk mengambil objek dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi, seperti memotret burung enggang dan orang utan di pucuk pohon tinggi. Beberapa foto dipamerkan di Nanga Bunut dan di buku Crystal Eye yang menunjukkan cara kerja ulet dari peserta dalam mengejar objek foto mereka. Buku Crystal Eye yang diluncurkan pada pertengahan 2013 tersebut berisi 346 foto karya mereka. Buku ini secara resmi diluncurkan di dua tempat, yaitu Putusibau untuk edisi bahasa Indonesia dan Jakarta untuk edisi bahasa Inggris.
Gambar 1 Karya Foto Zulkarnaen: Warga sedang Menjala Ikan di Sungai AurSumber: Putera, dkk. (2013)
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 57-74JurnalILMU KOMUNIKASI
66
Gambar 2 Karya Foto Edi Suhadi: Orangutan di Teluk Aur
Sumber: Putera, dkk. (2013)
Pengenalan lingkungan yang baik membantu para peserta untuk menghasilkan foto-foto yang unik. Foto tentang gotong royong oleh anak-anak saat mengangkat perahu dapat menjadi salah satu contohnya. Foto tersebut bercerita tentang lokasi tempat tinggal mereka di pedalaman yang mendorong masyarakat untuk menjaga kerja sama satu sama lain. Kehidupan yang keras di pedalaman dapat diatasi jika ada semangat saling mendukung. Soliditas masyarakat tersebut ternyata juga berperan penting saat mereka merumuskan aturan-aturan yang melindungi kelestarian Danau Pengelang, Desa Teluk Aur.
Peserta memiliki kemampuan penge-nalan medan yang baik berdasarkan foto-foto flora dan fauna yang dihasilkan. Ada peserta yang berhasil memotret anggrek kupu-kupu yang cukup jarang ditemukan, kucing hutan, buaya, dan ular. Beberapa foto memamerkan hasil tangkapan ikan, serta proses pengolahan yang men jadikan-nya kerupuk basah dan kering. Proses pengolahan tersebut dirangkai dalam photo essay, sehingga foto seperti bercerita tentang kegiatan ibu-ibu melakukan kegiatan ekonomi berbasis bahan baku lokal.
Kamera saku digital dipinjamkan ke para peserta selama satu tahun untuk memberi ruang eksplorasi identifikasi lingkungan. Peserta bebas menggunakannya untuk mengumpulkan berbagai objek foto. Pemilihan kamera saku disengaja karena kesederhanaan operasinya. Kamera yang sederhana memudahkan peserta untuk belajar. Mereka pun tidak perlu dipusingkan dengan masalah teknis, sehingga dapat berfokus pada objek foto. Pelatihan mendorong peserta mengamati, merekam, dan mendiskusikan kondisi alam dan situasi sosial-budaya di lingkungannya.Pameran
Setelah masa satu tahun melakukan program Panda CLICK! tahap I, peserta diajak untuk memublikasikan karya-karya mereka lewat pameran yang difasilitasi WWF-Indonesia. Pameran foto diselenggarakan di Gedung Pertemuan Nanga Bunut agar mudah diakses oleh masyarakat setempat. Sebanyak 138 dari 58.181 foto karya peserta pelatihan tahap I ditunjukkan ke publik. Foto-foto
Mario Antonius Birowo. Komunikasi Partisipatif Panda ...
67
tersebut terbagi ke dalam dua tema besar, yaitu lingkungan alam dan sosial-budaya. Kesempatan pameran merupakan peristiwa yang menarik untuk para fotografer karena mereka bisa menunjukkan hasil kerja setahun ke publik. Displai foto dibuat menarik dengan ukuran poster dan diberi sorot lampu kecil. Persiapan dilakukan gotong royong oleh tim WWF-Indonesia dan masyarakat setempat, khususnya para peserta program.
Pameran terasa meriah dengan melihat antusiasme pengunjung dan para fotografer. Catatan panitia menunjukkan bahwa terdapat 563 pengunjung memadati ruang pameran, meskipun peneliti memperkirakan jumlahnya lebih dari itu. Pengunjung datang dari beragam usia, jenis kelamin, dan profesi. Anak-anak sekolah berbondong-bondong hadir di siang dan malam hari, sementara orang-orang dewasa
datang bersama keluarga. Pameran menjadi forum publik karena menjadi acara bersama. Tampaknya, masyarakat di Nanga Bunut haus akan hiburan. Mereka biasa hidup terpencil dan sepi, sehingga kehadiran sebuah acara segera disambut dengan antusias. Hal ini juga disambut antusias oleh tim Panda CLICK!, khususnya para peserta yang karya-karyanya dipamerkan.
Pengunjung antusias bertanya kepada para fotografer dan karyanya. Antusiame tersebut terlihat misalnya saat pengunjung bertanya tentang sebuah foto orang utan. Fotografer pun menjelaskan bagaimana proses bisa menemukan orang utan dan keberhasilan memotretnya. Mendapatkan foto orang utan di alam liar merupakan prestasi luar biasa, apalagi ketika pemotretan dilakukan dengan kamera saku. Hal ini berarti fotografer memotret sedekat mungkin dengan orang utan.
Gambar 3 Pameran Foto di Gedung Pertemuan Nanga BungutSumber: Dokumentasi Peneliti
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 57-74JurnalILMU KOMUNIKASI
68
Dialog pun terjadi di antara pengunjung dan fotografer. Bermula dari salah satu foto dan berlanjut ke foto-foto lainnya. Di dalam proses dialog, ingatan pengunjung disegarkan kembali tentang situasi lingkungannya. Semua flora dan fauna yang ada di foto bukanlah objek asing karena ada di seputar tempat tinggal mereka, hanya terkadang masyarakat luput memperhatikannya. Mereka pun bercerita bahwa dahulu mereka mudah menemukan flora dan fauna yang ada di foto tersebut. Mereka tersadarkan bahwa flora dan fauna tertentu mulai terancam keberadaannya di wilayah mereka. Dialog tersebut memberikan ruang bagi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta membantu masyarakat mengidentifikasi persoalan. Dialog itu pun memunculkan kesadaran tentang kondisi lingkungan yang mulai berubah, flora dan fauna yang menghilang, serta munculnya kekaguman mereka akan kekayaan alam wilayahnya.
PEMBAHASAN
Dialog menjadi forum bagi terciptanya kesadaran warga atas situasi lingkungannya. Kesadaran tersebut memunculkan harapan berikutnya, yaitu aksi bersama dari warga. Proses ini disebut sebagai conscientisation (Freire, 1983). Proses dialog menjadi kunci program Panda CLICK! untuk membuka kesadaran peserta. Pada proses pemotretan orang utan misalnya, fotografer bercerita tentang kesulitan-kesulitan yang harus ditempuh untuk menemukan orang utan. Kesulitan ini kemudian menjadi bahan refleksi bahwa keberadaan orang utan sudah semakin jarang. Hal ini menjadi ironi bagi mereka karena wilayah Kalimantan dikenal sebagai rumah bagi orang utan. Foto lain berkisah tentang gotong royong saat memindahkan suatu mesin. Foto tersebut seolah-olah menjadi penangkap memori sekaligus harapan tetap terjaganya kehidupan yang saling membantu di lingkungan sosial masyarakat pedalaman.
Gambar 4 Salah Satu Partisipan Menerangkan Karya Fotonya kepada PengunjungSumber: Dokumentasi Peneliti
Mario Antonius Birowo. Komunikasi Partisipatif Panda ...
69
Pameran foto menjadi bagian dari aktivitas refleksi di mana foto memancing masyarakat menanggapi lingkungannya. Komunikasi horizontal dua arah di antara masyarakat telah terjadi, seperti terlihat dalam pameran. Mereka saling bertukar pengalaman tentang isu lingkungan. Secara alamiah mereka melakukan proses pendidikan secara bersama-sama.
Sisi lain yang menarik dalam pameran tersebut adalah munculnya raut muka bangga di wajah para fotografer. Mereka bagai menjadi selebritas di ruang publik karena dikerumuni dan diberi pertanyaan oleh banyak orang. Kepercayaan diri pun terbangun dan menjadi nilai penting bagi proses pemberdayaan masyarakat. Kesempatan masyarakat untuk berperan sebagai aktor dalam proses komunikasi membantunya memperoleh kepercayaan diri. Hal ini adalah sesuatu yang penting untuk proses pemberdayaan diri (Stuart & Bery, 1996).
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa foto membantu warga untuk meng-ekspresikan idenya. Mereka dapat bercerita dengan lancar tentang apa yang ditampilkan dalam foto serta proses pengambilan fotonya. Fenomena tersebut menunjukkan fungsi foto yang mampu membantu masyarakat mengekspresikan gagasannya. Foto menjadi media testimoni warga terkait dengan lingkungan sosial maupun alam. Penyampaian gagasan melalui foto menjadi alternatif dari kebiasaan terdahulu dalam berkomunikasi. Masyarakat dipermudah mendapat akses untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya melalui foto. Ketika ada kesempatan dan kemampuan mengekspresikan gagasannya,
maka gagasan tersebut memiliki peluang untuk mendapat perhatian.
Panda CLICK! mendorong masyarakat setempat untuk mengidentifikasi ke-butuhan nya melalui dokumentasi foto berbagai aspek di lingkungannya. Hal ini sesuai dengan temuan para akademisi yang mendalami photovoice. Photovoice dapat dilihat sebagai salah satu bentuk media alternatif yang digunakan untuk membantu masyarakat melakukan pengumpulan data, identifikasi masalah, atau mengangkat isu yang terjadi di lingkungan mereka. Hal inilah yang dialami oleh warga Teluk Aur. Mereka mengalami cara-cara pengenalan lingkungan mereka dengan partisipatif. Mereka menentukan apa yang menjadi hal penting bagi mereka melalui lensa kamera. Dasar penggunaan photovoice adalah masyarakat setempat memiliki pengetahuan yang baik tentang diri dan lingkungannya (Wang, Susan, Hutchison, Bell, & Pestronk, 2004).
Pengetahuan yang dimiliki menjadikan mereka dapat aktif mendiskusikan masalah mereka sendiri. Foto yang mereka hasilkan menjadi representasi dari ekspresi kumpulan pengetahuannya. Masyarakat setempat dapat terlibat berdiskusi karena memiliki kapasitas untuk berekspresi, serta akses yang terbuka ke ruang publik. Akses ini menandai adanya sistem demokrasi, di mana ruang publik menjadi milik bersama (Habermas, 1989; Hill & Sen, 2005). Fraser memaknai konsep public sphere dari Habermas berbasis pada forum di mana para partisipan dapat menyuarakan pendapatnya tanpa kekangan (Fraser, 2003).
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 57-74JurnalILMU KOMUNIKASI
70
Dalam konteks partisipan Panda CLICK!, mereka belajar meningkatkan kemampuan berekspresi dan mengapresiasi pendapat orang lain. Kondisi tersebut penting untuk menciptakan ruang dialog bersama (Pusey, 1987). Mengacu pada Freire (1983), pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Panda CLICK! bermanfaat membangun kesadaran masyarakat, khususnya pada kesadaran atas situasi yang menindas atau tidak menguntungkan, dalam hal ini persoalan degradasi lingkungan hidupnya.
WWF-Indonesia mendukung proses penyebaran gagasan masyarakat Bunut ke publik yang lebih luas dengan melihat hasil yang menggembirakan tersebut. Salah satunya melalui peluncuran buku Crystal Eye. Buku ini juga dilengkapi oleh tulisan yang menjelaskan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya. Upaya mereka menjaga sungguh-sungguh kelestarian lingkungan melalui Peraturan Desa (Perdes) Danau Lindung Pengelang Desa Teluk Aur tanggal 24 Januari 2008 menjadi salah satu contohnya. Perdes ini antara lain mengatur cara penangkapan ikan, pelanggaran, dan sanksinya. Hal ini dilakukan agar ikan-ikan tetap terjaga keberadaannya dan tidak habis karena eksploitasi yang berlebihan.
SIMPULAN
Panda CLICK! membantu masyarakat mengumpulkan data dan mengekspresikan kepentingannya melalui foto. Masyarakat menjadi aktor utama di dalam proses pendidikan lingkungan. Foto membantu mereka bercerita tentang kekayaan alam yang mereka miliki, serta berefleksi
tentang kondisi terkini lingkungan mereka. Pengetahuan lokal masyarakat menjadi modal ketika mereka mencoba membingkai realitas kehidupan sehari-hari ke dalam foto. Proses pembingkaian ini sebenarnya telah mengajak mereka untuk sungguh-sungguh mengenali kembali lingkungannya.
Foto hanya mampu merekam sebagian dari realitas, walaupun ada ribuan foto yang dihasilkan. Ada begitu banyak objek, namun hanya sedikit yang bisa terekam dalam foto. Dalam konteks inilah diperlukan pembingkaian. Pembingkaian tidak terjadi tiba-tiba, namun erat dengan frame of references dan field of experiences fotografer. Proses tersebut menjelma menjadi ide dan ide inilah yang dikonstruksikan oleh fotografer. Setiap foto yang mereka hasilkan selalu mengandung sesuatu yang ingin dikatakan. Mereka ingin berbicara melalui foto.
Program Panda CLICK! yang telah dijalankan di Kecamatan Bunut Hilir terbagi dalam tiga rangkaian kegiatan, yaitu pelatihan, praktik lapangan, dan pameran. Rangkaian kegiatan tersebut berjalan dengan mengedepankan masyarakat sebagai subjek. Photovoice yang digunakan di dalam program Panda CLICK! secara partisipatif telah merangsang masyarakat untuk mendialogkan problem lingkungannya. Sementara itu, efek dalam bentuk aksi masih perlu dilihat seiring berjalannya waktu. Penelitian perlu dilakukan untuk melihat dampak jangka panjang atas program ini karena aksi berikutnya menjadi aktivitas penting dalam program Panda CLICK!. WWF-Indonesia
Mario Antonius Birowo. Komunikasi Partisipatif Panda ...
71
diharapkan tetap mendampingi masyarakat untuk melihat apakah program ini selanjutnya dapat mendorong masyarakat mengalami perubahan sosial, khususnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan.
DAFTAR RUJUKAN
ADB. (2013, 27 Februari). ADB bantu pelestarian hutan yang terancam di Kalimantan. Adb.org. <http://www.adb.org/news/adb-help-conserve-threatened-forests-borneo-bahasa>
Arman, S. (2013). Kehidupan komunitas di Bunut Hilir. Dalam Abroorza Ahmad Yusra, Andi Fachrizal, Mario Antonius Birowo, Muhlis Suhaeri, & Syamsuni Arman, Crystal Eye (h. 50-52). Jakarta, Indonesia: WWF-Indonesia.
Baldwin, C., & Chandler, L. (2010). At the water’s edge: Community voices on climate change. Local Environment, 15(7), 637-649.
Bendell, K., & Sylvestre, J. (2016). How different approaches to taking pictures influences participation in a photovoice project. Action Research, 15(3), 357-372.
Benson, N. (2008). Climate change, effects. Dalam S. George Philander (ed), Encyclopedia of global warming and climate Change (p. 210-214). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
Berbés-blázquez, M. (2012). A Participatory assessment of ecosystem services and human Wellbeing in Rural Costa Rica using photo-voice. Environmental Management, 49(4), 862-875.
Bisung, E., Elliott, S. J., Abudho, B., Karanja, D. M., & Schuster-Wallace, C. J. (2015). Using photovoice as a community based participatory research tool for changing water, sanitation, and hygiene behaviours in Usoma, Kenya. BioMed Research International, 2015, 1-10.
BPS. (2017). Luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia menurut provinsi berdasarkan SK Menteri Kehutanan SK.76/MenLHK0II/2015. Bps.go.id. <https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan-dan-kawasan-konservasi-perairan-
indonesia-menurut-provinsi-berdasarkan-sk-menteri-kehutanan.html>
Carroll, C., Garroutte, E., Noonan, C., & Buchwald, D. (2018). Using photovoice to promote land conservation and indigenous well-being in Oklahoma. EcoHealth 15, 450-461.
Chandler, L., & Baldwin, C. Y. F. Q. (2010). Reflections from the water’s edge: Collaborative photographic narratives addressing climate change. Social Alternatives, 29(4), 30-36.
Cornwall, A., Capibaribe, F., & Gonçalves, T. Y. (2010). Revealed cities: A photovoice project with domestic workers in Salvador, Brazil. Development, 53(2), 299-300.
Engle, L. (2013). Photovoice case study and toolkit. Ihconline.org. <https://www.ihconline.org/filesimages/Tools/Pop Health/SIM/SDOH Toolkit/PhotoVoice.pdf>
Efransjah. (2013). Kata Pengantar WWF-Indonesia. Dalam Abroorza Ahmad Yusra, Andi Fachrizal, Mario Antonius Birowo, Muhlis Suhaeri, & Syamsuni Arman, Crystal Eye (h. 8-9). Jakarta, Indonesia: WWF-Indonesia.
Fachrizal, A. (2013). Sekilas tentang Panda CLICK! Dalam Abroorza Ahmad Yusra, Andi Fachrizal, Mario Antonius Birowo, Muhlis Suhaeri, & Syamsuni Arman, Crystal Eye (h. 12-13). Jakarta, Indonesia: WWF-Indonesia.
Fachrizal, A. (2016, 7 Maret). Pesan menggetarkan dari kampung nelayan Sebangau. Mongabay.co.id <https://www.mongabay.co.id/2016/03/07/pesan-menggetarkan-dari-kampung-nelayan-sebangau/>
Fraser, N. (2003). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. Dalam C. Elliot (ed), Civil society and democracy (p. 83-105). New Delhi, India: Oxford University Press.
Freire, P. (1983). Pedagogy of the oppressed. Harmondsworth, London: Penguin.
Fuller, L. (2007). Introduction. Dalam L. Fuller (Ed.), Community media: International perspectives (p. 1-17). New York, NY: Palgrave Macmillan.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 57-74JurnalILMU KOMUNIKASI
72
Gervais, M., & Rivard, L. (2013). Smart photovoice agricultural consultation: Increasing Rwandan women farmers’ active participation in develop ment. Development in Practice, 23(4), 496-510.
Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge, UK: The MIT Press.
Hill, D., & Sen, K. (2005). The internet in Indonesia’s new democracy. Oxon, England: RoutledgeCurzon.
Howley, K. (2005). Community media: Peoples, places and communication technologies. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Indrarto, G. B., dkk. (2012). The context of REDD+ in Indonesia: Drivers, agents, and institutions. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
IUCN. (2016). Pongo pygmaeus. Iucnredlist.org. <http://www.iucnredlist.org/details/17975/0>
Jengging, A. N. (2019, 14 Mei). Panda CLICK! gave opportunities to the kapit communities to share stories through pictures. Panda.org. <http://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/borneo_forests/?347616/Panda-CLICK-Gave-Opportunities-To-The-Kapit-Communities-to-Share-Stories-Through-Pictures>
Liebenberg, L. (2018). Thinking critically about photovoice: Achieving empowerment and social change. International Journal of Qualitative Methods, 17(1), 1-9.
Lestari, M. D., Sulistiowati, N. M. D., & Natalya, N. P. (2016). Kesehatan seksual dan reproduksi serta fasilitas kesehatan di lokasi prostitusi: Community based participatory research dengan photovoice pada pekerja seksual di Gunung Lawu, Bali. Jurnal Psikologi Undip, 15(1), 77-91.
Mattouk, M., & Talhouk, S. N. (2017). A content analysis of nature photographs taken by Lebanese rural youth. PLoS ONE, 12(5), 1-14.
Nowell, B. L., Berkowitz, S. L., Deacon, Z., & Foster-fishman, P. Y. (2006). Revealing the cues within
community places: Stories of identity, history, and possibility. American Journal of Community Psychology, 37(1/2), 29-46.
Pusey, M. (1987). Jurgen Habermas. London, UK: Routledge.
Putera, M. H., Yursa, A. A., Fachrizal, A., Arman, S., Tjiu, A., Wulffraat, S., Widjaya, I., Syahirsyah, J. , Hendratno, S. (eds). (2013). Crystal Eye. Jakarta, Indonesia: WWF-Indonesia.
Rennie, E. (2006). Community media: A global introduction. New York, NY: Rowman & Littlefield Publishers.
Rizky, C., & Widjaya, I. (2011, 7 Juni). Program fotografi komunitas, Panda CLICK! kembali digelar. Wwf.or.id. <http://www.wwf.or.id/?22661/Program-fotografi-komunitas-Panda-CLICK-kembali-digelar>
Royce, S., Parra-Medina, D., & Messias, D. (2006). Using photovoice to examine and initiate youth empowerment in community-based program: A picture of process and lessons learned. Californian Journal of Health Promotion, 4(3), 80-91.
Statistik Kehutanan Indonesia. (2011). Jakarta, Indonesia: Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
Stuart, S., & Bery, R. (1996). Powerful grass-roots women communicators: Participatory video in Bangladesh. Dalam J. Servaes, T. Jacobson & S. White (eds), Participatory communication for social change. New Delhi, India: Sage.
Sumargo, W., Nanggara, S. G., Nainggolan, F. A., & Apriani, I. (2011). Potret keadaan hutan Indonesia periode tahun 2000-2009. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia.
Taman Nasional. (2013). Taman nasional. Kapuashulukab.go. id . <https: / /web.kapuashulukab.go.id/page/taman-nasional>
Teti, M., Murray, C., Johnson, L., & Binson, D. Y. (2012). Photovoice as a community-based participatory research method among women living with HIV/AIDS: Ethical opportunities and challenges. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 7(4), 34-43.
Mario Antonius Birowo. Komunikasi Partisipatif Panda ...
73
Tobing, S. (2019, 20 September). Darurat kabut asap kebakaran hutan setiap tahun. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/telaah/2019/09/20/darurat-kabut-asap-kebakaran-hutan-setiap-tahun/1>
UN. (2008). Official list of MDG indicators. <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/OfficialList2008.pdf>
Wang, C. C., Susan, M-S., Hutchison, P. M., Bell, L., & Pestronk, R. M. (2004). Flint Photovoice:
Community building among youths, adults, and policymakers. American Journal of Public Health, 94(6), 911-913.
Wang, C. C., & Pies, C. A. (2004). Family, maternal, and child health through photovoice. Maternal and Child Health Journal, 8(2), 95-102.
WWF. (2013). Kehutanan. Wwf.or.id. <http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/>
75
Tinjauan Konstruksi Sosial Atas Nasionalisme Net Generation
Ana Nadhya AbrarUniversitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281Email: [email protected]
Abstract: Net Generation is an age-group that is familiar with the internet and actively using it. This generation is viewed as a group whose sense of nationalism questioned. This paper aims to evaluating the nationalism embraced by the Net Generation. The data are the results of an evaluative study to five students of the Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada, class of 2014. The result shows that their understanding of nationalism is different from what has been transmitted by historians. They love Indonesia in a unique way that is different from how the older generations express their love to the motherland.
Keywords: internet, nationalism, net generation
Abstrak: Net generation adalah generasi yang akrab dengan teknologi dan aktif menggunakannya. Generasi ini dipandang sebagai generasi yang diragukan rasa nasionalismenya. Tulisan ini bertujuan untuk menilai nasionalisme yang dianut oleh net generation. Pengambilan data dilakukan sebagai hasil studi evaluatif terhadap lima orang mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, angkatan 2014 yang aktif mengakses internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang nasionalisme berbeda dengan pemahaman yang ditularkan oleh para sejarawan. Mereka mencintai Indonesia dengan cara yang unik, terutama jika dibandingkan dengan ekspresi cinta tanah air yang ditunjukkan oleh generasi tua.
Kata Kunci: internet, nasionalisme, net generation
Net generation atau generasi internet merupakan generasi yang sangat adaptif dengan teknologi. Generasi ini terbiasa menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah, dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Net generation juga terbiasa menggunakan internet dan berkelana dari satu situs ke situs lain untuk mencari berbagai informasi melalui Google, serta berkomunikasi melalui surat elekronik (surel) dan media sosial. Mereka pun menjadi terhubung dengan dunia di luar tanah air mereka. Hal ini membuat net
generation dapat dengan mudah mengetahui kejadian yang ada di luar negaranya.
Akses internet membuat cakrawala pengetahuan net generation terbuka lebar. Tapscoot (dalam Dheny, 2017, h. 8) menyebutkan bahwa generasi yang akrab dengan teknologi komunikasi dan informasi ini sebagai generasi Z. Karakteristik generasi Z berbeda dengan generasi lainnya. Oblinger dan Oblinger (2005, h. 29) mengidentifikasi perbedaan karakteristik antargenerasi tersebut seperti terlihat pada tabel 1.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 75-90JurnalILMU KOMUNIKASI
76
Tabel 1 menunjukkan bahwa net generation menyukai teknologi terbaru dan terbiasa berkomunikasi menggunakan wahana komputer (computer mediated communication). Mereka memanfaatkan semua sumber daya di dalam internet untuk belajar. Mereka pun sangat familier dengan Google Scholar, Microsoft Academic, dan Library Genesis. Mereka menghabiskan banyak waktunya untuk berselancar di internet.
Generasi Z disebut juga sebagai digital natives. Partini (2017, h. 4), dalam pidato pengukuhan guru besarnya yang berjudul “Perubahan Peranan Perempuan: Peluang dan Tantangan”, mengemukakan bahwa digital natives merupakan generasi muda yang tumbuh dengan dikelilingi berbagai perangkat yang selalu terhubung dengan jaringan internet. Kehadiran digital natives menggeser nilai budaya yang sebelumnya telah berlaku, mengubah tatanan sosial, profesional, dan etika, termasuk saat menjalankan peran yang berbasis jenis kelamin.
Pengertian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kondisi yang kini sedang manaungi net generation.
Joesoef (2006, h. 199) menyatakan bahwa mereka mempunyai ide lain tentang nasionalisme. Mereka pun memiliki pendapat lain tentang patriot. Pendapat tersebut, menurut sinyalemen generasi tua, berbeda dengan pendapat yang umum. Tidak jarang generasi tua menganggap net gereration tidak memiliki rasa cinta tanah air. Apabila sinyalemen ini benar, hal tersebut merupakan akibat dari penyebab yang sudah berlangsung lama. Pencarian terhadap penyebab ini dihadapkan pada pertanyaan lain mengenai respons net generation terhadap masa depan.
Sementara itu, beberapa ahli ilmu sosial menilai bahwa globalisasi merusak nasionalisme. Anderson (2016, h. 197) menyebutkan bahwa globalisasi merupakan racun penghancur nasionalisme. Tidak berlebihan kiranya apabila Anderson menentang globalisasi, terutama globalisasi ala Amerika Serikat. Terlepas dari setuju atau tidak dengan pendapat Anderson tersebut, pendapat itu memperkuat keinginan peneliti untuk memahami nasionalisme net generation. Pada satu sisi, mereka sudah terbiasa dengan globalisasi atau paling tidak pikiran mereka sudah mengglobal.
Tabel 1 Perbedaan Antara Generasi Baby Boomers, Generasi X, dan Net GenerationAspek Generasi Baby Boomers Generasi X Net Generation
Tahun Lahir 1946-1964 1965-1982 1982-1991Deskripsi Me generation Latchkey generation MilenialAtribut/sifat dasar Optimis, gila kerja Bebas dan skeptis Penuh harapan, penuh
determinasiKesukaan Tanggung jawab, etika kerja,
dapat melakukan pekerjaan ter-tentu
Kebebasan, multitasking, keseimbangan kehidupan kerja
Aktivisme publik, tek-nologi terbaru, orang tua
Hal-hal yang tidak disukai Kemalasan di usia 50 tahun Birokrasi dan sensasi Segala sesuatu yang lam-ban dan hal-hal negatif
Sumber: Oblinger dan Oblinger (2005, h. 29)
Ana Nadhya Abrar. Tinjauan Konstruksi Sosial ...
77
Kesadaran mengenai kebutuhan internet sudah tumbuh di kalangan net generation sejak satu dasa warsa terakhir. Kesadaran ini menggolongkan mereka sebagai anggota masyarakat yang tidak lagi menggantungkan sumber informasi dari media massa arus utama. Mereka pun dengan sigap mengumpulkan berbagai informasi dari internet. Informasi yang mereka peroleh tersebut membuat mereka mempunyai pendapat berbeda tentang dunia ini.
Pendapat mereka tersebut pada hakikatnya muncul karena konstruksi sosial. Menurut Leeds-Hurwitz (2009, h. 891), konstruksi sosial adalah proses manusia mengonstruksi pengertian tentang dunia. Leeds-Hurwitz (2009, h. 891), meminjam pendapat Peter Berger dan Thomas Luckman, menyatakan bahwa ada dua syarat yang diperlukan agar manusia dapat mengonstruksi pengertian tentang dunia. Pertama, manusia mempunyai pengalaman bersinggungan dengan dunia itu. Kedua, bahasa.
Berdasarkan pendapat tersebut, kita dapat melihat bahwa net generation mempunyai pengalaman bersinggungan dengan dunia luar melalui internet. Sekalipun hanya melalui internet, mereka mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Mereka pun menyaksikan dorongan ke satu dunia tanpa batas dan adaptasi peradaban industri barat.
Pada sisi lain, net generation melihat dunia mengglobal. Dalam dunia seperti ini, setiap orang yang berasal dari belahan bumi mana pun secara proaktif menggunakan teknologi komunikasi. Apabila tidak demikian, maka orang
tersebut akan ketinggalan. Perasaan tidak ingin ketinggalan ini mendorong net generation mengalokasikan banyak waktu untuk berkelana di internet.
Kelancaran berkelana di internet meng haruskan net generation dapat meng-gunakan bahasa dengan baik, terutama bahasa Inggris. Mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami hal-hal yang mereka akses tanpa keterampilan berbahasa Inggris yang baik, walaupun sifatnya pasif. Setelah memahami hal-hal yang diperoleh tersebut, mereka pun terampil berbahasa untuk merekonstruksi dunia yang mereka lihat. Sebenarnya, konstruksi sosial terjadi dalam suasana tersebut.
Penulis memiliki dua asumsi ber-dasarkan pengamatan terhadap konstruksi sosial pada net generation. Pertama, net generation akan merasa ketinggalan apabila tidak berkelana di internet. Kedua, net generation mempunyai keterampilan berbahasa Inggris yang memadai. Bertolak dari kedua asumsi inilah, peneliti melihat gambaran perjumpaan net generation dengan internet.
Salah satu penelitian yang membahas perjumpaan manusia dan internet dilakukan oleh Lee dan Sundar (2014). Lee dan Sundar (2014, h. 743) menjelaskan bahwa interaksi manusia dengan internet perlu digalakkan, sekalipun meniru suasana penelitian media tradisional. Perjumpaan manusia dengan internet tentu saja berbeda dengan perjumpaan manusia dengan televisi. Menurut Sylado (2000, h. xxiii), televisi telah alpa menuntun masyarakat ke arah tujuan edukatif yang
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 75-90JurnalILMU KOMUNIKASI
78
dapat membuat masyarakat berpikir kritis dan sehat. Namun, perjumpaan manusia dengan internet justru merangsang mereka untuk mencari informasi ke mana-mana dan mengembarakan pikiran mereka sesuai dengan keinginan mereka.
Selanjutnya, peneliti memilih model efek kumulatif untuk melihat efek internet pada net generation. Menurut Werder (2009, h. 633), model ini memberikan efek yang konsisten dan berulang kali dari pesan yang ditangkap pengakses media. Model ini berbeda dengan model efek langsung (direct effect model) dan model efek terbatas (limited effect model). Model ini mempunyai titik tekan pada frekuensi penggunaan media sosial. Semakin banyak waktu yang dialokasikan seorang individu untuk menggunakan media sosial, semakin banyak pula individu tersebut mengadopsi realitas yang dibawa media sosial itu. Itulah sebabnya aktivitas mengakses internet dan menggunakan telepon seluler (ponsel) menjadi penting dalam penelitian ini. Sekalipun Werder (2009) berbicara dalam konteks media massa, peneliti berasumsi bahwa model ini bisa juga digunakan untuk melihat efek pesan yang diterima melalui media interaktif (internet).
Peneliti melihat nasionalisme dalam mengidentifikasi dunia yang akan dikonstruksi oleh net generation. Pemilihan nasionalisme ini peneliti lakukan karena ingin mengonfirmasi pernyataan Joesoef (2006) di awal tulisan ini. Sementara itu, Abdullah (2005, h. vii) mengemukakan bahwa nasionalisme berasal dari patriotisme. Patriotisme disebut
sebagai awal sekaligus menjadi landasan emosional nasionalisme. Patriotisme sendiri merupakan struktur kesadaran yang lahir dari renungan sejarah masyarakat dan pergulatan pemikiran tentang masa depan. Berdasarkan pernyataan Abdullah (2005) di atas, patriotisme merupakan syarat mutlak dari nasionalisme. Sementara itu, patriotisme bisa diperlihatkan melalui rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air ini, mengutip pendapat Muhammad Yamin, merupakan petunjuk masa depan yang penuh harapan (Abdullah, 2016, h. 5). Maka, peneliti menjadikan cinta tanah air sebagai indikator patriotisme dan menjadikan patriotisme sebagai indikator nasionalisme.
Oleh karena itu, melihat nasionalisme dari kacamata net generation sangat diperlukan. Penilaian net generation terhadap nasionalisme tersebut akan terus menjadi beban untuk mereka apabila tidak diselesaikan. Tulisan ini mencoba membahas nasionalisme net generation yang gemar berkelana di internet dari segi konstruksi sosial, khususnya lima mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada (UGM), angkatan 2014. Data yang dipakai untuk tulisan ini didasarkan pada hasil studi evaluatif terhadap subjek penelitian.
METODE
Peneliti menggunakan metode deskriptif yang menuntun peneliti untuk dapat mendeskripsikan hasil konstruksi informan tentang nasionalisme. Deskripsi tersebut peneliti lakukan dengan ukuran kualitatif.
Ana Nadhya Abrar. Tinjauan Konstruksi Sosial ...
79
Sementara itu, dari sisi kegunaan, penelitian ini tergolong penelitian evaluatif. Metode ini berupaya memberikan umpan balik terhadap keadaan, program, atau kegiatan apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Slamet, 2013, h. 8).
Peneliti menggunakan wawancara mendalam dengan semua informan sebagai teknik pengumpulan data. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat kualitatif atau lebih tepatnya kualitatif interaktif karena data yang dihimpun berasal dari interaksi peneliti dengan informan. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk teks dan tidak dianalisis dengan statistik. Peneliti mengerahkan segala fungsi indrawi untuk menganalisis data agar bisa menjawab pertanyaan penelitian.
Informan penelitian ini adalah lima mahasiswa Fakultas Psikologi, UGM, angkatan 2014 yang mengakses internet sedikitnya tiga jam sehari. Kriteria lain juga ditambahkan oleh peneliti, yaitu informan berkomunikasi menggunakan WhatsApp Messenger sedikitnya dua jam sehari. Pemilihan informan bertolak dari asumsi bahwa alokasi waktu sekian banyak untuk media sosial dan internet menjadikan mereka tenggelam dalam beragam informasi. Mereka pun tanpa
sadar telah menjadi “manusia global”. Dalam posisi ini, semua informasi yang mereka peroleh memengaruhi mereka dalam mengonstruksi rasa cinta tanah air. Para informan tersebut adalah Riski Amelia, Yasminnuha Jauharini, Dyah Utari Hastrarini, Rizqi Karomatul Khoiroh, dan Omar Syarief Natasubagyo. Keterangan lebih lengkap mengenai kelima informan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.
Reliabilitas data dihasilkan dari triangulasi melalui pengecekan informan kepada teman dekat mereka di Fakultas Psikologi, UGM, yakni Zafira Ayusti Abrar, untuk mengonfirmasi kebiasaan mereka saat menggunakan internet. Di samping itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan semua informan. Pengecekan dan diskusi tersebut membuat peneliti yakin bahwa semua narasumber tidak bias dalam menjawab semua pertanyaan penelitian ini.
HASIL
Data yang masuk melalui wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa net generation mengartikan pemahaman mereka mengenai cinta tanah air dalam beragam wujud. Ragam wujud cinta tanah air tersebut akan dijelaskan lebih lengkap melalui beberapa subbab pada bagian ini.
Tabel 2. Informan PenelitianNama Usia Hobi
Riski Amelia (Kiki) 21 tahun Membaca, mendengarkan musik, menontonYasminnuha Jauharini (Yasmin) 21 tahun Menggambar, membaca, memasakDyah Utari Hastrarini (Utari) 22 tahun Membaca, surfing di internet, memasak, mendengarkan musikRizqi Karomatul Khoiroh (Karom) 21 tahun TravellingOmar Syarief Natasubagyo (Omar) 21 tahun Bermain game, membaca novel, bercerita dan mendengarkan cerita,
berdiskusi
Sumber: Olahan Peneliti
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 75-90JurnalILMU KOMUNIKASI
80
Hafal Lagu-Lagu Wajib Nasional
Informan pertama adalah Riski Amelia (Kiki) yang berusia 21 tahun. Menurut Kiki, pembahasan mengenai nasionalisme merupakan pemikiran yang unik. “Menurut saya, nasionalisme itu sikap kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ia lebih merupakan pemahaman terhadap bangsa dan Negara” (Riski Amelia, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi Kiki nasionalisme itu baru sebatas sikap, belum sampai pada perilaku. Berdasarkan pernyataan tersebut, Kiki pun menjelaskan mengenai posisinya.
Kalau disuruh menilai diri saya sendiri, saya merasa pemahaman saya sudah dapat, sikap saya juga sudah dapat. Namun, saya belum seperti para aktivis itu yang berdemo untuk menunjukkan kecintaannya pada tanah air. Saya hanya tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai nasionalisme. (Riski Amelia, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017)
Selanjutnya, Kiki pun menjelaskan asal atau sumber informasi yang diterimanya mengenai nasionalisme.
Dari sejak menjadi murid SMA .... Kebetulan saya ikut banyak organisasi sejak dari SMA. Saya ikut pasukan khusus pengibaran bendera merah putih. Saya juga dapat bimbingan dari guru terkait nasionalisme. Kegiatan ini berlangsung tiap minggu. Ada kegiatan kelas yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Ada juga kegiatan di luar kelas yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip kepahlawanan. Terus saat kuliah, pemikiran saya tentang nasionalisme menjadi lebih terbuka, terutama setelah saya menjadi anggota BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Psikologi. (Riski Amelia, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017)
Aktivitas diskusi dengan teman-teman di BEM Fakultas Psikologi UGM menyebabkan Kiki harus mengakses
internet lebih dahulu. “Kalau tidak begitu, tidak nyambung saat berdiskusi” (Riski Amelia, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017).
Persoalan yang kemudian muncul adalah durasi waktu yang digunakan Kiki untuk mengakses internet dalam sehari. Kiki mengemukakan bahwa durasi waktu yang digunakannya mengakses internet sekitar 18 jam per hari, termasuk akses yang dilakukannya di hari Minggu. Pada saat berkelana di internet, Kiki mengaku bahwa dirinya cukup membuang waktu dan merasa rugi karena telah menghabiskan banyak waktu dengan berselancar di internet. Kiki juga mengemukakan bahwa dirinya berupaya mengurangi akses internet karena banyak distraksi di internet (Riski Amelia, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017).
Kiki menyatakan bahwa informasi adalah sumber inspirasi untuk melancarkan tugasnya sebagai mahasiswa. Awalnya, Kiki perlu berselancar untuk mencari informasi atau menerjemahkan sesuatu melalui google translate, tetapi selama berselancar Kiki pun tergoda untuk membuka tautan yang tidak ada hubungannya dengan niatan awal dirinya mengakses internet. Kiki mengemukakan bahwa dirinya mendapatkan banyak informasi dari tautan-tautan yang diaksesnya tersebut (Riski Amelia, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017).
Kiki mengakui bahwa dirinya mudah kehilangan fokus apabila sedang mengakses internet. Kiki pun masih belum dapat memperbaiki kebiasaan
Ana Nadhya Abrar. Tinjauan Konstruksi Sosial ...
81
tersebut, misalnya, dengan mengurangi akses melalui hyperlink agar tetap fokus. Kiki menceritakan bahwa saat dirinya ingin menulis artikel dan berselancar di internet karena membutuhkan informasi dari beberapa sumber untuk memperkaya tulisan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan beberapa situs internet lainnya, muncul beberapa distraksi, seperti notifikasi dari Instagram dan tautan berita lain, seperti berita pernikahan Raisa dan Hamish Daud. Pada momen ini, Kiki tergoda untuk menggali informasi tersebut lebih jauh sampai tiga jam lamanya.
Kiki pun mengaku bahwa dirinya belum dapat disiplin dan fokus. Kemampuan untuk bisa memperoleh banyak informasi tentang kejadian di negara lain jelas menyenangkan untuk Kiki. Pengetahuan baru mengenai bagaimana sebuah negara memajukan rakyatnya juga menjadi inspirasi bagi Kiki. Itulah sebabnya, Kiki akan terus mengakses internet.
Namun demikian, rasa nasionalisme tidak banyak terganggu oleh informasi yang diakses oleh Kiki melalui internet. Kiki pun menambahkan keterangannya mengenai kaitan antara nasionalisme dan patriotisme, “Cinta tanah air dulu, terus dia paham nasionalisme, baru dia berbuat patriotisme” (Riski Amelia, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017). Pendapat Kiki tentang nasionalisme dan patriotisme berbeda dengan keterangan Abdullah (2005, h. vii) yang mengatakan bahwa “Patriotisme adalah awal, tetapi sekaligus pula landasan emosional dari nasionalisme”.
Menurut Kiki, contoh orang yang cinta tanah air itu antara lain orang yang hafal lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional lainnya. Persoalan menghafal lagu wajib nasional dinilai Kiki sebagai hal yang langka di era sekarang ini. Kiki menilai bahwa di generasinya hanya sedikit orang yang bisa menyanyikan lagu wajib nasional. Hal inilah yang menyebabkan Kiki menyebutkan bahwa salah satu indikator cinta tanah air adalah kemampuan menghafal lagu wajib nasional.For What It Is dan No Matter What It Is
Yasminnuha Jauharini (Yasmin) telah lama berpikir tentang nasionalisme. Nasionalisme yang besar dan berkobar-kobar. Yasmin membayangkan bahwa nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air. Jawaban yang dikemukakan Yasmin cukup sederhana, tetapi Yasmin mengelaborasi pemaknaan cinta tanah air dengan beragam ekspresi yang dipakai untuk menunjukkan nasionalisme. Salah satunya melalui sebuah ilustrasi ketika seorang atlet Indonesia pindah ke negara lain dan menjadi atlet yang bergaji besar di sana. Ada pula periset Indonesia pindah ke Jepang dan menjadi periset bergaji besar pula di sana. Ada yang berkomentar bahwa atlet dan periset itu tidak nasionalis. Bagi Yasmin, keputusan atlet dan periset tersebut tidak dapat serta-merta diartikan sebagai sikap yang tidak nasionalis. Persoalan ekonomi, dalam hal ini gaji, tidak bisa linier dengan rasa nasionalisme. Yasmin juga menyebutkan bahwa ada banyak dinamika yang terjadi sebelum mereka pindah ke luar negeri (Yasminnuha Jauharini, mahasiswa
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 75-90JurnalILMU KOMUNIKASI
82
Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 8 September 2017).
Yasmin juga mengemukakan bahwa dirinya memiliki rasa cinta tanah air Indonesia, meskipun Yasmin merasa sulit mengungkapkannya. Yasmin menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa diterimanya secara pribadi, misalnya situasi warga negara Indonesia yang tidak peduli dengan negaranya sendiri (Yasminnuha Jauharini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 8 September 2017).
Yasmin juga menyatakan bahwa hal yang penting adalah mengakui dan menyadari manusia Indonesia bagian dari bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, rakyatnya mempunyai identitas, mempunyai kewarganegaraan dan mempunyai nilai-nilai yang dianut dari suku asalnya. Menurut Yasmin, selama seseorang mengakui dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, hal tersebut sudah menjadi dasar lahirnya nasionalisme. Yasmin pun menjelaskan bahwa nasionalisme berkaitan dengan hak dan kewajiban.
Menurut pandangan saya, nasionalisme itu adalah identitas. Identitas itu dibentuk oleh banyak hal. Ia tidak hanya dibangun oleh nilai-nilai saja, tetapi juga oleh hak dan kewajiban. Jadi nasionalisme itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Contohnya, sebagai orang Indonesia, kewajiban saya adalah berperilaku selayaknya yang baik berbudaya Indonesia. (Yasminnuha Jauharini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 8 September 2017)
Sebagai bagian dari net generation, Yasmin mengemukakan bahwa dirinya mulai menyalakan ponselnya jam enam pagi dan mematikannya jam sepuluh malam setiap hari. Yasmin pun siap memulai hari
dengan ponsel yang menyala. Yasmin sudah membiasakan pola aktivitas seperti itu sejak duduk di kelas tiga Sekolah Menengah Atas (SMA). Yasmin dapat dengan mudah berkomunikasi dengan kawan-kawannya menggunakan ponsel. Yasmin juga merasa terbantu untuk mencari informasi yang dibutuhkannya (Yasminnuha Jauharini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 8 September 2017).
Namun demikian, kadang-kadang Yasmin merasa stres juga mengetahui banyaknya informasi yang masuk ke ponselnya. Yasmin menghabiskan waktu sepuluh jam dengan ponsel dan laptopnya dalam satu hari. Yasmin sudah berupaya untuk mengontrol pemakaian ponsel dan laptop karena sering kali kedua gawai ini memberinya beban tersendiri, terutama jika ada banyak pesan yang harus dijawabnya. Di sisi lain, Yasmin mengemukakan bahwa ada hal positif yang didapatkannya melalui penggunaan gawai. Yasmin merasa tidak teralienasi secara sosial dan tidak mengalami kecemasan informasi.
Saya mengerti bahwa dunia menjadi semakin global. Saya merasa harus siap bersaing dan berkompetisi di dunia yang global. Tantangannya adalah memilah apa yang baik buat saya. Bagian mana dari globalisasi itu yang baik untuk saya dan apa yang harus saya pertahankan sebagai warga negara Indonesia. Mana pula yang harus saya kembangkan saat masuk ke dunia global. (Yasminnuha Jauharini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 8 September 2017)
Pengalaman menggunakan laptop dan ponsel membuat Yasmin memperoleh pemahaman bahwa nasionalisme bukan merupakan wujud kesetiaan tertinggi individu terhadap negara.
Ana Nadhya Abrar. Tinjauan Konstruksi Sosial ...
83
Nasionalisme tidak sama dengan menyerahkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara. Soalnya, nasionalisme hanya sebatas identitas saja. Padahal kesetiaan kadang-kadang mengandung istilah actions speak louder than word. Kalau saya bilang saya orang Indonesia, itu hanya permukaannya saja. Nasionalisme harus dilihat melalui usaha yang saya lakukan untuk menunjukkan itu. Maka, implementasi nasionalisme itu adalah patriotisme. Berarti patriotisme lebih tinggi dari nasionalisme karena sudah ada action-nya, sudah ada perilakunya. (Yasminnuha Jauharini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 8 September 2017)
Pendapat Yasmin ini bertentangan dengan pendapat Kohn (dalam Daliman, 2006, h. 58) yang mengatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Namun, pendapat Yasmin tersebut dikondisikan oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam berinteraksi dengan internet. Yasmin sudah memiliki kesadaran sendiri tentang nasionalisme. Bertolak dari kesadaran tersebut, Yasmin kemudian mengatakan bahwa to love once country for what it is dan to love a country no matter what it is merupakan pengejawantahan rasa cinta tanah air. Dalam konteks Indonesia, pernyataan tersebut berarti: mencintai Indonesia adalah to love Indonesia for what it is dan to love Indonesia no matter what it is (Yasminnuha Jauharini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 8 September 2017).Bangga dengan Kekayaan Fauna Indonesia
Informan lain, Dyah Utari Hastarini (Utari), mengemukakan dengan penuh keyakinan bahwa nasionalisme adalah rasa cinta serta bangga pada tanah air dan
bangsanya. Jika pada era terdahulu rasa cinta tanah air berwujud reaksi terhadap kolonialisme, maka kini rasa cinta tanah air tetap diperlukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing. Utari mengatakan bahwa kesadaran (sense) itu diperolehnya dari berbagai kesempatan, mulai dari saat bersekolah di SMA, berkuliah di Fakultas Psikologi UGM, hingga surfing di internet. Utari pun mengaku bahwa setiap hari dirinya mengakses internet paling kurang sepuluh jam.
Aduh banyak banget, lebih dari sepuluh jam. Sekitar berapa ya, karena saya tidur lima jam. Pahitnya 17 jam. Hari libur sama aja. Itu sudah saya mulai sejak saya bersekolah di SMA. (Dyah Utari Hastarini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017)
Kutipan ini menunjukkan bahwa Utari mengakses internet 17 jam per hari selama tujuh tahun. Utari merasa bahwa aktivitas tersebut tidak ideal. Utari pun mengemukakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, meskipun belum sampai kecanduan. Utari juga menyebutkan bahwa ada waktu-waktu tertentu saat Utari merasa lelah memegang ponsel dan ingin mengurangi waktu mengakses internet. Utari juga mengemukakan bahwa ada implikasi internet pada dirinya. Utari tidak dapat membayangkan bahwa dirinya akan mengalami perubahan pandangan tentang Indonesia. Utari merasa bahwa ada yang tidak baik tentang Indonesia setelah sering mengakses internet.
Kok Indonesia itu jelek banget sih? Saya merasa mau pindah saja dari Indonesia. Banyak banget berita jelek tentang Indonesia. Saya malu jadi warga Indonesia. Sempet juga sih kayak gitu. (Dyah Utari Hastarini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017)
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 75-90JurnalILMU KOMUNIKASI
84
Menurut Utari, tidak hanya dirinya yang pernah berniat pindah ke negara asing. Beberapa temannya juga pernah mempunyai niat yang sama.
Teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Mereka bilang, ya ampun jeleknya kondisi Indonesia zaman sekarang. ‘Kayaknya enak tinggal di Singapura’, tambah mereka. Apalagi mereka mengerti tentang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Berkat MEA, tentu gampang bekerja di Singapura. (Dyah Utari Hastarini, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 6 September 2017)
Niat Utari untuk pindah ke negara lain tidak bertahan lama. Niat itu segera sirna saat Utari teringat bahwa bagaimanapun dirinya harus mempunyai kebanggaan terhadap Indonesia. Kebanggaan Utari pada Indonesia disebabkan oleh kekayaan fauna Indonesia, seperti harimau sumatera dan orang utan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh aktivitasnya mengikuti gerakan World Wide Fund for Nature (WWF) yang kemudian menjadi perwujudan cinta tanah air. Utari membangun nasionalismenya dari kebanggaan pada fauna Indonesia. Akhirnya, Utari merasa bahwa nasionalisme adalah panggilan hati. Menurut Utari, nasionalisme tidak linier dengan persoalan hak dan kewajiban sebagai warga negara karena ada juga warga negara asing yang mampu mewujudkan kecintaannya terhadap Indonesia.
Utari menyatakan bahwa patriotisme adalah rela berkorban untuk negara, baik harta, jiwa, maupun raga. Patriotisme lahir setelah adanya nasionalisme. Demikianlah pendapat Utari mengenai kaitan antara nasionalisme dengan patriotisme. Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat
Abdullah (2005, h. vii) yang mengatakan bahwa patriotisme adalah awal sekaligus landasan emosional dari nasionalisme. Utari merasa bahwa kebanggaan terhadap kekayaan fauna Indonesia merupakan manifestasi dari rasa cinta pada Indonesia. Artinya, rasa cinta tanah air ditunjukkan melalui keberadaan hal-hal materiel yang menjadi milik suatu negara.Mengalahkan Ego
Rizqi Karomatul Khoiroh (Karom), dalam usia 21 tahun lebih, merasa belum memiliki nasionalisme yang kuat. Karom merasa tertinggal dibandingkan dengan generasi sebelumnya pada saat mereka seusianya. Namun, Karom sudah memberikan kontribusi kepada negara ini dalam bentuk pikirannya. Karom menyebutkan bahwa dirinya bergabung dengan organisasi yang cenderung kritis dalam menilai isu-isu yang muncul di Indonesia. Karom tidak dibesarkan di kota besar. Karom mengenal nasionalisme sejak kecil dari gurunya, seperti kebanyakan orang-orang di kampungnya.
Namun, pandangan saya sudah berbeda ketika saya semakin besar karena saya juga belajar dari lingkungan, dari kampus, dari internet, dari orang sekitar, dan tentu dari organisasi yang saya ikuti (Rizqi Karomatul Khoiroh, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 12 September 2017).
Karom mengemukakan bahwa nasionalisme adalah kesadaran di dalam diri mengenai rasa cinta tanah air. Kadar cinta tanah air setiap individu berbeda-beda, namun paling tidak setiap individu harus memilikinya. Pandangan seperti itu lebih banyak diperolehnya dari organisasi ekstra yang diikutinya (Rizqi Karomatul
Ana Nadhya Abrar. Tinjauan Konstruksi Sosial ...
85
Khoiroh, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 12 September 2017).
Karom mengakses internet minimal empat jam sehari dengan menggunakan ponsel dan laptop. Laptop dipakai Karom terutama untuk mengerjakan tugas per-kuliahan, sedangkan ponsel dipakai untuk meng akses media sosial. Karom pun merasa bahwa dirinya mulai bergantung pada ponsel.
Penggunakan laptop dan ponsel untuk mengakses internet guna memenuhi kebutuhan informasi selama 4-5 jam per hari tidak membuat Karom merasa membuang-buang waktu. Karom merasa biasa-biasa saja karena dirinya memiliki banyak waktu luang. Karom juga tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa mengakses gawai. Kendati begitu, Karom punya kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama terhadap mereka yang terkena bencana. Karom mengalahkan egonya demi membantu mereka. Menurut Karom, sikap semacam itu adalah wujud patriotisme.
Patriotisme itu sikap. Misalnya, rela melakukan sesuatu yang konkret sebagai perwujudan rasa nasionalisme. Untuk itu, setiap individu harus mengalahkan egonya agar bisa berkontribusi lebih besar kepada Negara .... Nasionalisme dan cinta tanah air itu basic menuju patriotisme. (Rizqi Karomatul Khoiroh, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 12 September 2017)
Pandangan Karom ini tentu berbeda dengan pandangan Abdullah (2005, h. vii) yang melihat bahwa patriotisme sebagai landasan emosional dari nasionalisme. Meskipun demikian, Karom mengemukakan bahwa cinta tanah air hanya bisa terwujud apabila setiap warga negera dapat mengalahkan egonya untuk bisa berkontribusi pada Indonesia.
Menjadi Nasionalis Dahulu
Nasionalisme, bagi Omar Syarief Natasubagyo (Omar), merupakan idealisme yang menempatkan negara di posisi paling atas. Omar sependapat dengan Kohn (dalam Daliman, 2006, h. 58) yang mengatakan bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dalam bahasa lain, Omar mengatakan bahwa inti nasionalisme adalah mencintai negara. Omar sendiri menyimpulkan bahwa dirinya dapat disebut nasionalis jika dirinya mencintai Indonesia. Omar pun mengakui bahwa nasionalismenya masih kurang.
Intinya kan mencintai negara. Sementara saya sendiri, seperti katakanlah pengetahuan tentang negara Indonesia, juga tidak terlalu luas. Mungkin juga kurang mencintai produk dalam negeri. Bahkan sampai sekarang pun, produk dalam negeri yang saya suka hanya batik dan gamelan. (Omar Syarief Natasubagyo, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 12 September 2017)
Omar juga mengakui bahwa wawasan-nya tentang nasionalisme tersebut banyak diperolehnya dari orang tuanya, bukan dari internet.
Dari orang tua karena orang tua saya berasal dari lingkungan tentara. Bapak saya bukan tentara, namun dia dibesarkan di lingkungan tentara. Jadi, dia menanamkannya kepada saya seperti itu: harus mencintai tanah air. (Omar Syarief Natasubagyo, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 12 September 2017)
Nasionalisme Omar, secara praktis, lebih terfokus pada lingkungan asalnya. Omar pun menjadikan lingkungannya sebagai pihak yang harus menerima manfaat.
Kalau lingkungan saya memang membutuhkan itu, apakah itu produk barang atau makanan,
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 75-90JurnalILMU KOMUNIKASI
86
entah itu dari luar atau dalam, asal itu bisa membuat saya bertahan, ya sudah. Jadi, saya tidak terlalu menekankan harus begini dan begitu. (Omar Syarief Natasubagyo, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 12 September 2017)
Sikap nasionalisme sering kali dihubungkan dengan persoalan penjajahan yang membutuhkan nasionalisme untuk membangun kekuatan melawan penjajah. Omar mengatakan bahwa bukan berarti nasionalisme tidak berguna ketika tidak ada lagi penjajahan fisik di Indonesia. Saat ini, nasionalisme diperlukan untuk melawan korupsi dan konflik.
Sekalipun menimba nasionalisme dari orang tua, Omar tetap saja menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengakses internet. Omar mengakses internet selama delapan jam per hari. Omar menyebutkan bahwa dirinya mengakses informasi dengan menggunakan laptop. Sedangkan media sosial diaksesnya menggunakan ponsel. Omar mengakui bahwa dirinya lebih banyak menghabiskan waktu mengakses internet daripada membaca buku. Omar juga mengakui bahwa dirinya mulai kecanduan mengakses internet. Namun demikian, Omar tidak merasa ada persoalan.
Saya bisa dibilang kecanduan internet, tapi bukan dalam hal yang negatif. Kalau orang-orang yang kecanduan, selalu negatif. Misalnya sering mengakses pornografi dan pornoaksi atau terlalu banyak main online game. Kalau saya kecanduan karena lihat Facebook dan membaca sumber-sumber berita lain. Bukankah informasi di internet lebih cepat daripada informasi yang disiarkan koran. (Omar Syarief Natasubagyo, mahasiswa Fakultas Psikologi UGM, wawancara, 12 September 2017)
Walapun demikian, Omar tidak pernah mengalami kecemasan informasi
(information anxiety) dengan semua informasi yang diperolehnya melalui internet. Omar juga tidak pernah khawatir dengan hoaks di internet karena dirinya sendiri cukup selektif saat memilah informasi yang baik dan benar di internet.
Di tengah kenyataan itu, Omar berpendapat bahwa cinta tanah air merupakan salah satu komponen nasionalisme. Pendapat ini sesuai dengan penjelasan yang termuat dalam kerangka pemikiran teoritik, yaitu cinta tanah air merupakan wujud patriotisme dan patriotisme merupakan indikator nasionalisme. Namun, ketika bicara soal patriotisme, Omar mengatakan bahwa patriotisme merupakan aplikasi atau penerapan nasionalisme.
Pernyataan seperti ini berbeda dengan penjelasan Abdullah (2005, h. vii) yang mengatakan bahwa patriotisme adalah awal dan sekaligus landasan emosional dari nasionalisme. Namun, seseorang harus menjadi nasionalis dahulu sebelum dapat disebut mencintai Indonesia.
PEMBAHASAN
Beberapa pengamat berharap internet membawa pencerahan salah satunya Mohamad (2016, h. 170). Informasi diharapkan semakin sulit dimonopoli dan dialog akan berlangsung dengan seru. Harapan Mohamad ini agaknya terjadi pada kelima informan penelitian ini. Mereka menjadikan informasi yang diperoleh melalui internet ibarat air pasang yang mengangkat perahu ke level ketinggian yang memadai untuk berlayar. Mereka tidak hanya melihat kemajuan di negara
Ana Nadhya Abrar. Tinjauan Konstruksi Sosial ...
87
lain, tetapi juga ketimpangan di negara sendiri.
Dalam konteks ini, agaknya kita sering mendengar ungkapan: right or wrong is my country. Artinya, benar atau salah kita harus membela negara kita. Apabila informan dalam penelitian ini menganut doktrin tersebut, mereka dapat disebut kaum ultranasionalis. Apabila tidak, pertanyaan yang menyusul kemudian adalah mengenai setuju atau tidaknya mereka dengan semboyan right is right, wrong is wrong.
Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita melihat pendapat Susilo Bambang Yudhoyono tentang penganut sikap yang terakhir.
Aplikasinya, mereka merasa tidak harus membela negaranya, bangsanya, dan tanah airnya, manakala di mata mereka Indonesia salah. Kelompok ini dianggap lebih setia pada masyarakat dunia ketimbang bangsanya sendiri. Kerap kali mereka disebut kaum ultranasionalis. (Yudhoyono, 2014, h. 701-702)
Informan dalam penelitian ini ternyata tetap mencintai bangsanya sendiri. Namun, mereka tidak tutup mata dengan kesalahan yang terjadi di negaranya. Mereka protes apabila terjadi kesalahan yang sangat mendasar, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka tidak mau membela negaranya secara membabi buta. Mereka bahkan ingin berkontribusi menyelesaikan masalah yang terjadi di negaranya sendiri.
Pertanyaan yang mencuat kemudian adalah mengenai kecewa atau tidaknya mereka dengan tanah airnya—yang diliputi banyak masalah—dan mereka memiliki atau tidak keinginan menjadi warga
negara lain. Salah satu informan, Kiki misalnya, sama sekali tidak ingin menjadi warga negara lain. Namun, Kiki ingin mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di negara lain. Kiki ingin memperoleh inspirasi tentang bagaimana sebuah negara memajukan rakyatnya.
Informan penelitian ini pun tidak pernah ragu menilai dirinya. Omar, misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa dirinya belum mencintai Indonesia secara menyeluruh. Di samping belum punya pengetahuan yang luas tentang Indonesia, Omar juga kurang mencintai produk dalam negeri.
Pada saat mengakses internet, informan dalam penelitian ini tidak hanya sekadar mengikuti rasa ingin tahu mereka saja. Mereka menimba informasi itu dan menyesuaikannya dengan kebutuhan mereka. Mereka tidak sekadar berpuas diri, melainkan juga menilai dirinya sendiri. Karom, misalnya, tidak ingin menjadi generasi yang egois. Sebaliknya, Karom merasa harus mengalahkan egonya agar bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk Indonesia.
Cara informan berpikir ini sesungguhnya adalah produk dari zaman mereka, yaitu zaman yang antusias menggunakan internet. Kenyataan ini, sesuai dengan pendapat Kuntowijoyo (1993, h. 279) yang mengemukakan bahwa setiap zaman memiliki sistem pengetahuan dan simbol tersendiri. Sistem pengetahuan dan simbol yang dimiliki masyarakat sangat ditentukan oleh teknologi yang tersedia pada era tersebut. Hal ini memengaruhi cara berpikir, mengelola pengetahuan, dan menciptakan simbol.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 75-90JurnalILMU KOMUNIKASI
88
Penjelasan ini menjadikan kita maklum apabila net generation mempunyai pendapat yang berbeda dengan generasi sebelumnya tentang nasionalisme. Generasi sebelumnya menganggap patriotisme adalah awal mula dan sekaligus landasan emosional dari nasionalisme, sedangkan net generation memandang nasionalisme sebagai wawasan atau kesadaran tentang cinta tanah air; patriotisme merupakan perwujudan nyata dari nasionalisme; dan nasionalisme dan cinta tanah air menjadi prasyarat bagi lahirnya patriotisme. Semua perbedaan ini bertolak dari cara mereka mengonstruksi nasionalisme sesuai dengan pengetahuan yang mereka peroleh dari aktivitas berkelana di internet.
Namun demikian, kita tidak dapat begitu saja menyederhanakan nasionalisme.
Nasionalisme dan globalisasi memang punya kecenderungan untuk membatasi pandangan kita. Itu sebabnya yang kian diperlukan adalah percampuran serius dan canggih dari kemungkinan-kemungkinan emansipatif nasionalisme dan internasionalisme. (Anderson, 2016, h. 197)
Bersamaan dengan itu, agaknya kita perlu menggarisbawahi pendapat Liem Sioe Siet, salah seorang pendiri Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang nasionalisme.
Nasionalisme harus dilandasi humanisme. Nasionalisme yang kelewatan, itu chauvinisme. Itu masih mending atau lumayan. Namun, bila sampai membabi buta, melebihi chauvinisme, menjelma menjadi negara Nazi fasis, rasis, dan ekspansionisme yang jelas-jelas menginjak-injak kemanusiaan, tak seorang pun yang waras pikirannya akan menyetujuinya. (Siet, 2019, h. 192)
Kehadiran internet dan pemakaian gawai oleh net generation mengonstruksi nasionalisme berdasarkan ragam informasi
yang diakses melalui internet. Di sisi lain, lingkungan fisik tempat net generation bertumbuh juga memiliki andil besar dalam menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Hal ini ditunjukkan oleh Omar yang tumbuh di lingkungan tentara dan Karom yang ikut berorganisasi. Kedua informan tersebut mengonstruksi nasionalisme melalui tindakan nyata di lingkungannya atau melalui pemikiran-pemikiran kritis yang dilatih dengan keterlibatan di organisasi. Pada tahap ini, bukan hal yang mustahil nasionalisme yang berlandaskan humanisme seperti yang dikemukakan Siet (2019, h. 192) terwujud. Kuncinya adalah keterlibatan aktif net generation di lingkungan sosial.
Di sisi lain, perwujudan nasionalisme akan diaplikasikan berbeda dengan pengalaman Kiki, Yasmin, dan Utari yang cenderung membandingkan Indonesia dengan negara lain. Konsumsi internet melalui pemakaian gawai tentu membuka kesempatan bagi net generation untuk melihat kondisi global. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana net generation tetap mampu melihat ke dalam, bersikap kritis pada negaranya, dan mengambil sikap proaktif untuk membangun Indonesia.
Pendapat net generation ini tentu saja sah. Soal salah-benarnya, mari kita serahkan kepada sejarah. Redana (2013, h. 136) mengemukakan bahwa seseorang yang membaca buku dan internet memiliki kecenderungan yang berbeda. Membaca melalui internet cenderung menjadikan manusia semakin dangkal karena setiap informasi di internet akan terhubung
Ana Nadhya Abrar. Tinjauan Konstruksi Sosial ...
89
dengan tautan ke informasi lain atau malah memberikan distraksi tertentu kepada pembacanya.
Hal ini juga yang membentuk pe-mahaman net generation tentang nasio-nalisme yang unik dan berbeda dengan generasi lain. Konstruksi nasionalisme me nurut net generation bertumpu pada hal-hal yang materiel, seperti keberadaan kekayaan fauna dan kemampuan menghafal lagu wajib nasional. Di sisi lain, masih terdapat pula net generation yang memiliki pemahaman bahwa rasa nasionalisme diwujudkan melalui kontribusi kepada lingkungan sekitar. Net generation yang memiliki pandangan seperti ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatannya secara sosial melalui organisasi dan mendapat pemahaman mengenai nasionalisme dari orang tua.
Hal ini menunjukkan bahwa sintesis tentang nasionalisme perlu dibentuk melalui kegiatan-kegiatan di luar berinternet. Van Dijk (2012, h. 9) menyatakan bahwa pemahaman dan makna memerlukan interaksi antara komunikasi melalui internet dan komunikasi langsung, kecuali jika seseorang lebih percaya diri dengan interaksi yang diarahkan oleh kecerdasan buatan. Pernyataan Van Dijk ini dapat menggambarkan situasi yang perlu diwaspadai oleh net generation, yaitu situasi ketika bentuk pemahaman mereka dikontrol oleh media internet.
Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai nasionalisme net generation perlu diagendakan. Dalam penelitian lanjutan tersebut, salah satu persoalan nasionalisme
yang perlu dibahas adalah ungkapan “NKRI adalah harga mati”. Ungkapan ini, bagi generasi tua merupakan ungkapan yang harus dipraktikkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
SIMPULAN
Penjelasan pada uraian di atas menegaskan sinyalemen yang menyatakan bahwa net generation mempunyai ide lain tentang nasionalisme. Mereka punya pendapat yang lain pula tentang aksi patriot. Bahkan, mereka mempunyai cara lain untuk mencintai Indonesia. Net generation menegaskan bahwa nasionalisme dapat diekspresikan dengan beragam cara, misalnya mampu menghafal lagu nasional, bangga pada kekayaan fauna, hingga mengikuti organisasi yang mampu melatih daya pikir kritis. Internet memberikan dampak yang besar bagi net generation, salah satunya dalam mengonstruksi nasionalisme dan patriotisme.
Simpulan ini merupakan hasil tinjauan konstruksi sosial terhadap kegemaran net generation berkelana di internet. Simpulan ini dapat pula menjadi pembuka untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang cara lain tersebut: apakah masuk akal atau tidak; apakah perlu ditularkan kepada orang lain atau tidak; dan apakah dapat dipakai sebagai pegangan untuk menjadikan Indonesia di masa depan yang lebih adil atau tidak.
DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, T. (2005). Pengantar. Dalam Restu Gunawan. Muhammad Yamin dan cita-cita persatuan. Yogyakarta, Indonesia: Ombak.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 75-90JurnalILMU KOMUNIKASI
90
-----------. (2016, Januari). Historiografi dalam denyut sejarah bangsa. Tulisan ini dipresentasikan dalam ceramah Historiografi Indonesia dalam Perspektif Sejarah di Teater Salihara, Jakarta, Indonesia.
Anderson, B. (2016). Hidup di luar tempurung. Serpong, Indonesia: Marjin Kiri.
Daliman. (2006). Harmonisasi hubungan nasionalisme dan agama menuju Indonesia baru. Dalam M. Todhi As’ad (ed). Kearifan profesor bersuku-suku untuk kenal mengenal. Yogyakarta, Indonesia: UNY Press.
Dheny, N. H. R. (2017). Lahirnya generasi baru: The net-generation. Jurnal Ilmiah Stikosa-AWS. 3(2), 1-23.
Joesoef, D. (2006). Dia dan aku: Memoar pencari kebenaran. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
Kuntowijoyo. (1993). Paradigma islam: Interpretasi untuk aksi. Bandung, Indonesia: Penerbit Mizan.
Lee, E. J., & Sundar, S. S. (2014). Interaksi manusia-komputer. Dalam Charles R. Berger, Michael E. Roloff, & David R. Roskos-Ewoldsen, Handbook ilmu komunikasi. Bandung, Indonesia: Nusamedia.
Leeds-Hurwitz, Wendy. (2009). Social construction of reality. Dalam Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss (eds), Encyclopedia of communication theory (h. 891-894). Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
Mohamad, G. (2016, November 13). Dusta. Majalah Tempo, h. 170.
Oblinger, D., & Oblinger, J. (2005). Is it age or IT: First steps toward understanding the net generation. Dalam Diana G. Oblinger & James L. Oblinger (eds), Educating the net generation (h. 2.1-2.20). Washington, DC, USA: Educause.
Partini. (2017). Perubahan peranan perempuan: Peluang dan tantangan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Gadjah Mada, 10 Oktober.
Redana, B. (2013). Mind body spirit: Aku bersilat, aku ada. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
Siet, A. J. L. S. (2019). Untaian mutiara dalam kehidupan sehari-hari. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Slamet, Y. (2013). Metode penelitian sosial. Surakarta, Indonesia: UNS Press.
Sylado, R. (2000). Belajar peri kecendekiaan dari Stephen Hawking. Dalam Stephen Hawking, Stephen Hawking on writing. Bandung, Indonesia: Qanita.
Werder, O. H. (2009). Media effects theories. Dalam Stephen W. Littlejohn and Karen A. Foss (eds), Encyclopedia of communication theory (h. 632-634). Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
Van Dijk, J. (2012). The Network Society (3rd edition). London, UK: Sage.
Yudhoyono, S. B. (2014). Selalu ada pilihan: Untuk pencinta demokrasi dan para pemimpin Indonesia mendatang. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
91
Wacana Komunikasi Lingkungan dalam Iklan Properti Meikarta
Christina Arsi LestariUniversitas Mercu Buana Jakarta
Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650Email: [email protected]
Abstract: This article discusses the environmental communication discourse through Meikarta advertisements. Using the critical discourse analysis (CDA) method and based on the concept of environmental communication in the field of media studies which focused on advertising, it can be concluded that Meikarta advertisement is still in the agenda setting stage. Based on the environmental communication function, the existence of Meikarta advertisement can be classified as a technical function that provides information on the effects of the damage to the natural and social environment in Jakarta.
Keywords: advertising, discourse analysis, environmental communication, meikarta
Abstrak: Studi ini membahas wacana komunikasi lingkungan dalam iklan Meikarta dengan menggunakan konsep komunikasi lingkungan yang berfokus pada kajian terhadap iklan. Metode yang dipakai adalah analisis wacana kritis. Hasilnya menunjukkan bahwa iklan Meikarta masih dalam tahap agenda setting. Iklan tersebut mampu memersuasi khalayak dengan gambaran fakta-fakta lingkungan Jakarta yang kumuh, serta memiliki beragam polusi dan kriminalitas. Tinjauan terhadap fungsi komunikasi lingkungan menggolongkan iklan Meikarta dalam fungsi teknis yang memberikan informasi dampak kerusakan lingkungan alam dan sosial Jakarta.
Kata kunci: analisis wacana, iklan, komunikasi lingkungan, meikarta
Studi komunikasi sudah tidak asing lagi bagi khalayak. Beberapa ruang lingkupnya, seperti komunikasi korporasi, komunikasi pemasaran, dan komunikasi politik, menjadi populer. Namun, ruang lingkup studi komunikasi yang multidisiplin, seperti komunikasi lingkungan, komunikasi kesehatan, komunikasi pariwisata, dan komunikasi pembangunan, belum mendapat perhatian khusus.
Komunikasi lingkungan merupakan studi komunikasi dari tradisi retorika yang muncul pertama kali di Amerika pada tahun
1980-an. Studi ini mengkaji keterkaitan antara komunikasi dan human-nature relation. Premis dasar studi ini menyatakan bahwa cara manusia berkomunikasi sangat memengaruhi persepsinya tentang kehidupan di bumi. Persepsi ini membentuk cara individu mendefinisikan hubungannya dengan alam (Littlejohn & Foss, 2009, h. 344-346).
Isu lingkungan membutuhkan komunikasi yang efektif agar pesan mengenai dampak lingkungan dapat menggugah kesadaran masyarakat. Hal ini selaras dengan laporan Kompas
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 91-106JurnalILMU KOMUNIKASI
92
(Ariestya, 2017) yang mengemukakan bahwa permasalahan lingkungan memiliki kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut memerlukan pengaktifan fungsi komunikasi lingkungan.
Salah satu fenomena media yang berhubungan erat dengan isu komunikasi lingkungan adalah iklan properti Meikarta. Sejak bulan Mei 2017, televisi, surat kabar, dan media dalam jaringan (daring) menyuguhkan iklan dan pemberitaan mengenai hal tersebut. Mega proyek Meikarta menjanjikan kepada masyarakat kemudahan interaksi yang dapat diraih dengan teknologi terkemuka yang disediakan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan perpindahan secara fisik.
Iklan Meikarta menampilkan sosok anak perempuan sebagai modelnya dan menyampaikan narasi tentang kondisi lingkungan yang sangat tidak nyaman. Anak perempuan itu sedang berada di dalam mobil dan melihat ketidakteraturan kota yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kondisi tersebut digambarkan dengan kemacetan, banjir, dan tindak kriminal. Iklan tersebut menyuguhkan sebuah tagline yang muncul dari pernyataan sang model, “Aku ingin pindah ke Meikarta”.
Isi iklan Meikarta ini menimbulkan pro dan kontra. Lokasi properti tersebut sampai hari ini masih tidak jelas dan ganjil. Salah satu keganjilan yang muncul adalah ketidaksesuaian luas area tahap pertamanya. Proyek yang dipromosikan oleh PT. Lippo Cikarang Tbk. sebagai pengembang proyek Meikarta itu dikabarkan memiliki luas 100 hektare. Hal ini tidak sesuai dengan pemberian izin penggunaan lahan yang diberikan
Pemerintah Provisi Jawa Barat kepada proyek Meikarta yang luasannya hanya 84,6 hektare (Fauzan & Pamungkas, 2018).
Di sisi lain, promosi properti ini cukup massal. Perusahaan memakai seluruh ruang iklan yang ada, seperti ruang iklan di surat kabar, televisi, radio, portal berita digital, dan billboard, pada kurun waktu empat bulan sejak Mei 2017 (Detik, 2017). Hal yang sama juga dapat temukan di mal, khususnya mal milik Lippo Group, dan sejumlah perkantoran. Konter-konter properti di Jakarta dengan staf penjualan yang rajin menawarkan barang dagangannya juga semakin banyak terlihat. Penawaran yang dijanjikan oleh pihak Lippo Group adalah membangun sebuah kota baru yang akan menjadi kota terindah, terlengkap, paling modern, dan tercanggih se-Asia Tenggara (Budi, 2017).
Keganjilan pada proses pemasaran proyek Meikarta sepanjang tahun 2017 menggiring kecurigaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proyek pembangunannya. KPK sebelumnya telah mengindikasikan bahwa perizinan proyek Meikarta bermasalah sejak awal. Salah satu indikasinya yaitu lokasi peruntukan proyek yang tidak memungkinkan dipakai untuk membangun seluruh proyek seluas 500 hektare tersebut. Selain itu, terdapat pula kasus suap yang dilakukan oleh pihak Lippo Group kepada beberapa oknum pejabat pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Masalah lain yang muncul adalah perizinan Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Tarigan, 2019).
Christina Arsi Lestari. Wacana Komunikasi Lingkungan ...
93
Di tengah berbagai kontroversi proyek pembangunan Meikarta tersebut, proses pembangunan masih berlangsung hingga 2019. Pada bulan Januari 2019, konstruksi dua apartemen di Central Business District (CBD) Meikarta telah selesai dibangun. Dua menara yang bernama Glendale Park dan Newport Park itu merupakan menara kelima dan keenam di Orange County dengan total 1.094 unit apartemen. Perusahaan mengaku apartemen di CBD Meikarta itu telah laku hingga 95 persen sejak penjualan perdananya pada tahun 2016 (Sugianto, 2019).
Penelitian terdahulu yang mengangkat iklan Meikarta dan berfokus pada komunikasi lingkungan belum ada. Penelitian yang sudah ada berfokus pada konstruksi pemberitaan perizinan pembangunan Meikarta di portal beritasatu.com dan kompas.com (Yusman, 2018, h. 23-28). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada pemberitaan tentang perizinan pembangunan Meikarta, beritasatu.com cenderung memihak kepada Meikarta dan menyalahkan wakil Gubernur Jawa Barat. Unsur kepemilikan media memengaruhi cara pemberitaan di media ini. Di sisi lain, pemberitaan kompas.com mendukung pembangunan Meikarta, tetapi kompas.com sangat berhati-hati dalam menyampaikan fakta dan berusaha mengajak pembaca untuk melihat bahwa pengembang swasta tidak seharusnya dihambat perizinannya dalam melakukan pembangunan daerah.
Sedangkan penelitian terdahulu yang membahas mengenai isu komunikasi lingkungan, seperti penelitian yang
dilakukan oleh Ardian (2018, h. 1), menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan dan metode analisis wacana memiliki peran penting pada pembahasan isu lingkungan dan pemetaan pemegang kepentingan. Komunikasi lingkungan merupakan sebuah sarana yang dapat memfasilitasi pertukaran infomasi antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada sisi metode, analisis wacana dipakai untuk mengidentifikasi peran dan posisi pemangku kepentingan yang terlibat pada tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Sementara itu, tulisan ini berbeda dengan dua penelitian di atas karena membahas wacana komunikasi lingkungan dalam iklan properti Meikarta. Iklan yang berdurasi satu menit tersebut diawali dengan hujan di tengah kota dengan warna-warna gelap yang digunakan untuk visualisasikan suasana suram. Di tengah kemacetan kota, seorang anak perempuan duduk di kursi penumpang bagian belakang sebuah mobil. Anak perempuan yang sedang melamun menghadap jalan itu dikagetkan dengan hentakan di kaca mobilnya hingga wajahnya berubah sedih dan muram.
Visualisasi selanjutnya adalah pemandangan buruk kota, seperti sungai yang kotor, orang berjalan di tanah yang becek, kemacetan, penjambretan terhadap seorang perempuan paruh baya, serta kota yang kotor dan jorok. Pada bagian ini terdengar suara narator laki-laki dewasa, “Terkadang kita lupa, kehidupan yang kita jalani menjadi seperti ini.” Kemudian visual mobil yang ditumpangi anak perempuan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 91-106JurnalILMU KOMUNIKASI
94
tadi bergerak menyusuri terowongan dan seolah-olah memasuki “dunia yang baru”. Di dalam terowongan inilah terdengar suara si anak perempuan, “Bawa aku pergi dari sini”. Suasana seketika beralih menjadi terang, berwarna, dan hidup, yaitu suasana perkotaan yang teratur, modern, dan lebih “manusiawi”. Kemudian tulisan Welcome to Meikarta 5 minutes to destination muncul mengikuti suasana tersebut.
Selanjutnya, suara narator terdengan kembali, “Kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara mudah untuk menggapai cita. Kita lupa semua ini dapat menjadi milik kita”. Visualisasi dilanjutkan dengan tulisan Polution Index: Low. Anak perempuan tersebut lalu disuguhkan dengan pemandangan yang modern dan serba canggih. Hal ini terlihat dengan adanya Closed Circuit Television (CCTV) yang akan memantau seluruh kota, papan digital bertuliskan Polution Index: Low, serta bangunan yang mewah. Di tempat itu, si anak perempuan berkumpul dengan keluarganya, yaitu ayah, ibu, dan seorang adik laki-laki. Iklan berlanjut dengan gambaran kemajuan Meikarta dengan kereta cepat bawah tanah, aktivitas memilih baju dengan virtual reality, serta taman bermain yang ramah anak dan perempuan.
Narator laki-laki kembali berkata di tengah keceriaan si anak perempuan menikmati kebersamaan dengan keluarganya, “Kita lupa semua ini bisa jadi milik kita.” Si anak perempuan lalu mengatakan, “Aku ingin pindah ke Meikarta”. Iklan diakhiri dengan logo Meikarta.
Tulisan ini membahas fenomena iklan Meikarta di atas berdasarkan perspektif komunikasi lingkungan. Atmakusumah (2000, h. 58) mengemukakan bahwa komunikasi lingkungan merupakan proses komunikasi yang terjalin antara individu dengan alam. Hal ini mencakup persepsi individu terhadap lingkungan alam. Pesan yang terkandung pada komunikasi lingkungan bertujuan memecahkan permasalahan lingkungan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Eksistensi komunikasi lingkungan juga diharapkan dapat membangun kesadaran mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Komunikasi lingkungan terdiri dari dua cakupan. Pertama, Komunikasi Lingkungan Pragmatis. Cakupan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengedukasi, memperingatkan, dan memersuasi masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan (Atmakusumah, 2000, h. 58). Kedua, Komunikasi Lingkungan Konstitutif. Cakupan ini lebih mengarah pada proses pemaknaan kita terhadap alam. Fakta yang didapatkan bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda, sehingga kita dapat lebih mengetahui kebenaran yang ada (Atmakusumah, 2000, h. 58).
Konsep mengenai komunikasi lingkungan tersebut menunjukkan dua fungsi komunikasi lingkungan. Pertama, fungsi strategis. Aktivitas utama komunikasi lingkungan pada fungsi ini adalah kampanye dan peningkatan kesadaran
Christina Arsi Lestari. Wacana Komunikasi Lingkungan ...
95
khalayak untuk peduli terhadap lingkungan. Tujuannya adalah mengajarkan, mengajak, dan mendorong pihak-pihak terkait (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk berpartisipasi mengatasi permasalahan lingkungan. Partisipasi dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye sosial terkait isu lingkungan, penyuluhan, dan advokasi untuk mendorong kebijakan yang pro terhadap isu lingkungan (Ariestya, 2017).
Kedua, fungsi teknis. Fungsi ini dilakukan untuk mengumpulkan, memu-blikasikan, dan menyebarkan informasi tentang isu-isu lingkungan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada khalayak tentang permasalahan-permasalahan ling-kungan. Bentuk kegiatan nya meliputi publikasi, liputan media, tulisan di portal, media sosial, dan iklan (Ariestya, 2017).
Komunikasi lingkungan yang menjadi fokus tulisan ini adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam yang menjadi sorotan utama adalah penggambaran dari visual iklan Meikarta yang menunjukkan ruang terbuka hijau dan pengelolaan limbah rumah tangga yang baik, sehingga tidak menimbulkan polusi. Pembahasan berikutnya adalah terkait lingkungan sosial yang menyoroti visualisasi iklan Meikarta melalui sudut pandang si tokoh anak kecil yang melihat kemacetan, banjir, kawasan kumuh, hingga aksi kriminal.
Tulisan ini berupaya mengeksplorasi penggunaan bahasa yang menggambarkan pesan komunikasi lingkungan dalam iklan properti Meikarta, serta membedah ideologi yang ingin ditanamkan pengiklan pada masyarakat melalui iklan tersebut.
METODE
Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting. Bahasa digunakan untuk melihat terjadinya ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Fairclough dan Wodak (dalam Badara, 2012, h. 29), analisis wacana kritis berusaha menyelidiki penggunaan bahasa oleh kelompok-kelompok sosial yang saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. Fairclough (1989, h. 26) mengemukakan bahwa wacana merupakan sebuah praktik sosial. Fairclough membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi, yakni teks, praktik wacana (discourse practice), dan praktik sosial (social practice). Dimensi teks berhubungan dengan aspek-aspek linguistik, misalnya kosakata, semantik dan tata kalimat, koherensi dan kohesivitas, serta proses pembentukan pengertian antarsatuan tersebut (Fairclough dalam Badara, 2012, h. 25).
Sementara itu, proses pengolahan data dan analisis pada tulisan ini menggunakan metode analisis wacana kritis yang dikemukakan Teun A. van Dijk. Kerangka analisis wacana van Dijk terdiri atas tiga struktur utama (Eriyanto, 2001, h. 227-229). Pertama, struktur makro. Struktur makro merupakan makna global/umum dari sebuah teks yang dapat dipahami melalui topiknya. Dengan kata lain, struktur makro merupakan analisis sebuah teks yang dipadukan dengan kondisi sosial di sekitarnya untuk memperoleh satu tema sentral.
Tema sebuah teks tidaklah terlihat secara eksplisit di dalam teks, melainkan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 91-106JurnalILMU KOMUNIKASI
96
tercakup di dalam keseluruhan teks dalam satu kesatuan bentuk yang koheren. Jadi, tema sebuah teks dapat ditemukan dengan cara membaca teks tersebut secara keseluruhan sebagai sebuah wacana sosial, sehingga dapat ditarik satu ide pokok/topik/gagasan yang dikembangkan dalam teks tersebut (Imam, 2012, h. 4).
Kedua, superstruktur. Superstruktur merupakan kerangka dasar sebuah teks yang meliputi susunan atau rangkaian struktur atau elemen sebuah teks dalam membentuk satu kesatuan yang koheren. Dengan kata lain, superstruktur merupakan analisis skema atau alur sebuah teks. Ibarat sebuah bangunan, sebuah teks juga tersusun atas berbagai elemen, seperti pendahuluan, isi, dan penutup, yang harus dirangkai sedemikian rupa supaya membentuk sebuah teks yang utuh dan menarik. Dalam sebuah iklan, superstruktur merupakan struktur pembentuk iklan yang meliputi kepala iklan (headline), ilustrasi iklan, isi iklan (body copy), logo produk (signature line), dan penutup iklan (standing details) (Leech dalam Brata, 2017, h. 19).
Ketiga, struktur mikro. Struktur mikro merupakan bagian analisis teks yang didasarkan pada empat unsur intrinsiknya. Unsur pertama adalah semantik. Unsur ini dikategorikan sebagai makna lokal dan terbentuk dari kata, klausa, kalimat, dan paragraf. Semantik membentuk makna dari hubungan antarkata, antarklausa, antarkalimat, dan antarparagraf yang membangun satu kesatuan makna dalam satu kesatuan teks (Imam, 2012, h. 4).
Unsur kedua adalah sintaksis. Unsur ini membantu pembuat teks memanipulasi
keadaan dengan cara memberikan penekanan tematik pada tatanan kalimat. Manipulasi tersebut dapat berupa pemilihan penggunaan kata, kata ganti, preposisi, dan konjungsi, serta pemilihan bentuk-bentuk kalimat, seperti kalimat pasif atau aktif (Imam, 2012, h. 4).
Unsur ketiga adalah stilistik. Unsur ini mengidentifikasi ragam tampilan sebuah teks dengan menggunakan bahasa sebagai sarananya. Teks bisa memilih berbagai ragam tampilan, seperti puisi, drama, atau narasi. Berdasarkan gaya bahasanya, sebuah teks bisa menampilkan gaya melalui diksi atau pilihan kata, pilihan kalimat, majas, matra, atau ciri kebahasaan lainnya (Imam, 2012, h. 4).
Unsur keempat adalah retoris. Unsur ini berhubungan dengan gaya penekanan sebuah topik dalam teks. Gaya penekanan yang berhubungan erat dengan cara pesan dari sebuah teks akan disampaikan ini dapat meliputi hiperbola, repetisi, dan aliterasi (Imam, 2012, h. 4).
HASIL
Struktur Wacana Iklan
Visualisasi iklan Meikarta tidak menyebutkan secara jelas bahwa kota pertama yang serba kelam tersebut adalah Jakarta. Namun, ciri-ciri kondisi yang digambarkan dalam iklan tersebut, seperti kemacetan, banjir, banyak sampah, kriminalitas, dan warga yang individualistis, mengarahkan kita ke sebuah kota metropolitan seperti Jakarta.
Tema iklan tersebut adalah pindah dari kota yang kumuh dan padat ke kota modern
Christina Arsi Lestari. Wacana Komunikasi Lingkungan ...
97
yang bernama Meikarta. Iklan tersebut menceritakan seorang anak perempuan yang sedang berada di dalam mobil bersama keluarganya. Mobil yang ditumpanginya terjebak di suatu lingkungan kota yang kumuh, banjir saat hujan dan menimbulkan kemacetan. Bahkan kota tersebut dipandang tidak aman karena terlihat aksi penjambretan dari sudut pandang si anak.
Iklan tersebut menggambarkan kondisi Jakarta sesuai kondisi yang sering terjadi, yaitu kepadatan penduduk, kumuh, adanya kemacetan, polusi, serta kriminalitas. Hal ini didukung pula dengan data mengenai beberapa permasalahan Jakarta. Pertama, kepadatan penduduk. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Akbar, 2020) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk DKI Jakarta di wilayah perkotaan sebesar 16.882 jiwa/km2. Hal ini kontras dengan angka kepadatan penduduk Indonesia yang hanya mencapai 141 jiwa/km2.
Kedua, area kumuh. Area kumuh di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 445 Rukun Warga (RW). Baru 200 RW dari jumlah tersebut yang ditata hingga tahun 2019 (Sari, 2019). Ketiga, kemacetan. Pada tahun 2018, Jakarta menduduki posisi ketujuh dari sepuluh kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan sebesar 53% (Ikhsanudin, 2019). Keempat, polusi udara. Polusi udara di Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat keenam dari sepuluh kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dan membahayakan kesehatan (Kurnia, 2020). Kelima, kriminalitas. Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mencatat sejumlah 32.614 kasus kejahatan
yang terjadi di wilayah Jakarta sepanjang tahun 2019. Intensitas kejahatan setidaknya terjadi setiap 16 menit (Sidik, 2019).
Visualisasi selanjutnya beralih ke gambaran kota yang disebut-sebut sebagai kota impian dan menjadi solusi dari permasalahan tempat tinggal yang kumuh dan sarat tindak kriminal tersebut. Konstruksi pesan tentang kota impian yang cerah, hijau, modern, bebas macet, aman, dan nyaman menjadi salah satu bentuk persuasi kepada masyarakat Jakarta agar mau menanamkan investasinya pada produk Meikarta. Penekanan mengenai kota impian juga dapat dilihat melalui logo produk Meikarta. Pada logo tersebut, terdapat slogan The Future is Here Today. Tampilan logo tersebut menunjukkan bahwa produk properti Meikarta adalah masa depan Jakarta.Superstruktur
Superstruktur merupakan proses identifikasi struktur pembentuk wacana. Superstruktur mengenal adanya unsur skematik yang mengacu pada isi wacana secara keseluruhan. Wacana dalam hal ini adalah iklan Meikarta. Cerita dalam iklan tersebut diawali dengan kondisi kota yang padat, macet, berpolusi, dan adanya tindak kriminal. Kemudian ada seorang anak kecil perempuan di dalam mobil bersama keluarganya sedang terkena macet. Si anak merasa sedih melihat kondisi kota tersebut hingga berkata dalam hati, “Bawa aku pergi dari sini.”
Adegan selanjutnya adalah mobil yang ditumpangi anak perempuan tersebut keluar dari kemacetan dan melewati terowongan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 91-106JurnalILMU KOMUNIKASI
98
panjang hingga sampai di sebuah kota bernama Meikarta. Kota ini membuat si anak tersenyum kagum dan gembira karena si anak tinggal di kota yang bersih, tanpa kemacetan, tanpa polusi, aman, dan didukung pula dengan teknologi penunjang aktivitas yang canggih.
Iklan Meikarta yang tayang dalam bentuk audio visual memuat tiga hal yang dapat dianalisis berdasarkan strategi penyampaian pesan, tindakan dan gerakan, serta naskah atau cerita iklan. Naskah cerita iklan ini diperkuat dengan unsur emosi, demonstrasi, unsur visual dan suara, unsur-unsur pembentuk iklan, serta proses produksi iklan (Effendi, 2009, h. 4).
Iklan Meikarta menggunakan tipe iklan bercerita (storytelling). Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa iklan Meikarta memiliki jalinan cerita untuk tujuan tertentu, yaitu promosi produk properti. Jalinan cerita pada iklan Meikarta bersifat mengkritik kondisi lingkungan fisik maupun sosial yang sering terjadi di kota-kota besar, seperti kemacetan, banjir, banyak sampah, polusi, kriminalitas, dan sikap warganya yang individualistis. Pengiklan menciptakan bentuk-bentuk narasi dengan jalinan cerita yang bertujuan untuk menyentuh unsur-unsur emosional khalayak, seperti rasa marah, rasa takut, rasa senang, maupun rasa kecewa yang semuanya dapat langsung tampak di layar televisi.
Penampilan anak sebagai tokoh utama dalam iklan menggambarkan kejujuran karena anak-anak biasanya tampil apa adanya, polos, dan spontan dalam mengekspresikan dirinya. Sosok seorang anak perempuan dalam iklan tersebut digunakan sebagai penguat unsur
storytelling yang akan menunjukkan jalinan cerita dengan menghadirkan rasa bosan, kesal, dan takut dari seorang anak perempuan saat dia berada di lingkungan yang penuh masalah sosial. Narasi pun berujung pada perubahan emosi anak perempuan tersebut yang menunjukan rasa bahagia melalui ekspresi wajahnya saat memasuki suatu kawasan dengan lingkungan yang bersih, bebas polusi, modern, dan aman untuk anak-anak bermain.
Pengiklan Meikarta memanfaatkan unsur audio dan visual. Kombinasi yang sempurna dari unsur audio dan visual dapat menjadi alat jual yang cukup potensial bagi produk yang diiklankan. Produk properti Meikarta telah didemonstrasikan melalui iklan. Visualisasi dari kondisi lingkungan yang disajikan juga dekat dengan kehidupan khalayak yang tinggal di perkotaan, sehingga situasi yang dirasakan oleh anak perempuan dalam iklan tersebut turut pula dirasakan oleh penontonnya.Struktur Mikro
Struktur mikro adalah analisis struktur wacana secara tekstual. Analisis tekstual ini meliputi analisis semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Semantik bertujuan mengamati makna yang ingin ditekankan pada praktik wacana. Media biasanya akan memberikan detail pada satu sisi atau menggambarkan suatu hal secara eksplisit, kemudian mengurangi detail di sisi lainnya. Semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna dan arti dalam suatu bahasa (Kusuma, 2009, h. xix).
Banyak makna akan terbentuk dalam suatu kode bahasa, apalagi jika telah menjadi rangkaian kode. Unsur semantik
Christina Arsi Lestari. Wacana Komunikasi Lingkungan ...
99
dalam analisis wacana model van Dijk memiliki beberapa elemen, seperti latar, detail, maksud, praanggapan, dan nominalisasi. Bahasa merupakan alat untuk merepresentasikan realitas melalui pilihan kata-kata dan cara penyajiannya. Bahasa juga dapat menciptakan realitas, menentukan corak dari realitas yang ditampilkannya, dan menentukan makna yang muncul darinya. Bahasa dapat memberikan aksen tertentu terhadap suatu peristiwa atau tindakan dengan cara mempertajam, memperlembut, atau mengaburkan suatu peristiwa (Kholisoh, 2015, h. 313).
Unsur semantik pada iklan Meikarta menggambarkan perubahan kondisi lingkungan yang sehat dan hal tersebut menjadi pesan utama iklan. Makna yang ditekankan dalam wacana iklan tersebut adalah Meikarta sebagai bentuk Jakarta yang lebih cantik dapat terwujud dengan kerja sama semua warga Jakarta, bahkan warga Indonesia, untuk menanamkan investasinya pada proyek pembangunan “kota” Meikarta tersebut.
Sementara itu, sintaksis pada iklan merupakan unsur yang mempelajari hubungan antarkata, antarkalimat, maupun antarparagraf. Sintaksis memuat elemen koherensi yang memberi tekanan pada kontinuitas makna dalam teks. Unsur wacana dalam bentuk dialog pada iklan Meikarta mengandung koherensi untuk membentuk alur cerita yang jelas dan dialog yang memiliki kontinuitas makna, khususnya tentang kampanye komunikasi lingkungan yang memersuasi khalayak agar sadar dan mau
bekerja sama dalam membangun kota impian, yaitu “Jakarta Baru yang Cantik”. Gambaran tersebut sesuai dengan visualisasi kota yang modern, canggih, aman, dan nyaman untuk ditinggali.
Iklan kerap menjual mimpi untuk menarik perhatian khalayaknya. Harapan iklan Meikarta untuk membangun kota modern bertajuk “Jakarta Baru yang Cantik” menyiratkan bahwa kota atau lingkungan tempat tinggal modern yang aman, nyaman, dan indah hanya diperuntukkan bagi khalayak yang memiliki modal (uang) saja. Iklan tersebut sering memunculkan dialog “kita lupa” yang mengisyaratkan sebuah ironi bahwa keberadaan khalayak di kondisi lingkungan yang kumuh dan semrawut disebabkan oleh ketidaksadaran khalayak. Pembuat iklan Meikarta berusaha menarik sisi psikologis khalayak pada ironi yang diciptakan, sehingga khalayak dipersuasi untuk sadar bahwa khalayak dapat keluar, bahkan harus keluar, dari rumahnya sekarang juga dan pindah ke Meikarta. Seolah-olah kegiatan pindah rumah semudah membalikkan telapak tangan atau semudah berkata “kita lupa, semua ini bisa menjadi milik kita”.
Unsur stilistik digunakan untuk melihat pilihan kata (diksi) yang dipakai dalam suatu wacana. Pilihan kata dalam struktur wacana ini berkaitan dengan penggunaan kode/bahasa dalam membentuk suatu wacana. Dalam penelitian ini, unsur stilistik lebih ditekankan melalui wacana komunikasi lingkungan di iklan Meikarta.
Iklan Meikarta bertemakan mobilitas khalayak dari tempat tinggal yang kumuh
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 91-106JurnalILMU KOMUNIKASI
100
dan semrawut ke tempat yang modern, indah, aman, dan nyaman. Iklan ini lebih banyak menggunakan pilihan kata “terkadang kita lupa”. Kata “kita lupa” diulang hingga tiga kali dalam dialog iklan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa iklan memberi tekanan pada penyadaran terhadap khalayak agar mulai berpikir tentang lingkungan timpat tinggalnya yang sudah benar-benar tidak layak untuk dijadikan “rumah” lagi. Oleh karena itu, iklan tersebut mengonstruksi gambaran kota modern yang canggih, indah, aman, dan nyaman dengan tajuk “Jakarta Baru yang Cantik”.
Pemilihan nama Meikarta sebagai brand juga memiliki konsep mendalam dalam proyek pembangunan ini. Brand tersebut menyiratkan bahwa khalayak tidak perlu pindah dari Jakarta dan hanya perlu bekerja sama membangun “Jakarta Baru yang lebih Cantik”. Konsep pindah atau mobilitas tidak menjadi momok karena seakan-akan tetap berada di wilayah Jakarta.
Sedangkan retoris dipakai untuk mengetahui cara penekanan makna/pesan dilakukan dalam suatu wacana. Wacana berbentuk dialog dalam iklan ini disertai dengan ekspresi, seperti bosan, jenuh, dan cemberut memandang kemacetan, kesemrawutan, serta kriminalitas di kota dari balik kaca mobilnya sambil berkata dalam hati, “bawa aku pergi dari sini”.
Ekspresi si anak begitu ceria saat memasuki gedung apartemen yang penuh fasilitas canggih dan modern, serta berbarengan dengan munculnya dialog,
“cara mudah untuk menggapai cita”. Si anak begitu kagum dan tersenyum bahagia.
Kedua ekspresi yang ditunjukkan si tokoh pada iklan Meikarta menggambarkan tingkat stres yang tinggi pada ekspresi si anak pada bagian sebelumnya hingga si anak berkata dalam benaknya untuk dibawa pergi dari tempat tersebut. Ekspresi setelahnya menunjukkan kelegaan dan kenyamanan, bahkan rasa kagum, karena terbebas dari segala masalah yang ada pada lingkungan sebelumnya dan tinggal di lingkungan yang sehat secara fisik maupun mental.Struktur Makro
Tematik merupakan struktur makro pada elemen wacana van Dijk, yaitu merupakan tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu wacana. Tema yang diangkat dalam iklan tersebut adalah “Pindah dari kota yang kumuh dan padat ke kota modern yang bernama Meikarta”. Iklan tersebut menceritakan seorang anak perempuan yang sedang berada di dalam mobil bersama keluarganya. Mobilnya terjebak di suatu lingkungan kota yang kumuh, banjir saat hujan, dan menimbulkan kemacetan. Bahkan kota tersebut dipandang tidak aman karena si anak melihat ada aksi penjambretan dari sudut pandangnya. Hal tersebut ditampilkan melalui beberapa narasi, yaitu “bawa aku pergi dari sini”, “kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup”, dan “aku ingin pindah ke Meikarta”.
Permintaan untuk “pergi dari sini” diucapkan oleh sosok anak kecil perempuan yang mengisyaratkan rasa bosan atau jenuh. Narasi tersebut diperkuat dengan visualisasi pemandangan dua kota yang sangat bertolak
Christina Arsi Lestari. Wacana Komunikasi Lingkungan ...
101
belakang. Kota pertama yang didatangi si anak dan keluarganya adalah kota yang kumuh, penuh polusi udara, kemacetan karena banjir, bahkan tindak kriminal. Namun, kota kedua yang menjadi tujuan si anak dengan keluarganya merupakan kota modern dengan polusi udara yang rendah karena ada taman kota yang indah, sistem keamanan yang canggih, kondisi kota yang tertata, bebas macet, dan ditunjang dengan teknologi yang mempermudah aktivitas berbelanja maupun bekerja.
Narasi “cara lain untuk hidup” merupakan gambaran dari kota modern dalam iklan tersebut. Kota terstruktur semacam itu akan hadir di Jakarta ini, sehingga diberi istilah “pindah ke Meikarta”. Meikarta terdiri dari dua suku kata, yaitu “mei” dan “karta”. “Mei” memiliki arti “cantik” dan “karta” diambil dari nama kota Jakarta. Jadi, Meikarta berarti Jakarta baru yang cantik.
Makna tersebut menyiratkan mimpi untuk membangun Jakarta yang lebih cantik dari Jakarta sekarang. Mimpi tersebut juga dimaksudkan untuk menghilangkan berbagai macam polusi yang ada di Jakarta, seperti polusi udara, polusi air kali, “polusi” macet, dan “polusi” kriminalitas. Tema tersebut menempatkan fokus penelitian ini pada wacana tentang nama Meikarta itu sendiri. Dalam konteks komunikasi lingkungan, Meikarta telah menjadi bentuk kampanye lingkungan, walaupun bermain dalam ranah yang terlalu hiperbol atau berlebihan apabila dipandang oleh masyarakat Jakarta saat ini.
Iklan Meikarta berusaha meng-gambarkan kondisi Jakarta sesuai
kenyataan tentang kepadatan penduduk, kekumuhan dan kesemrawutan kota, kemacetan, polusi, serta kriminalitas. Oleh karena itu, konstruksi sebuah tempat yang indah, nyaman, dan modern menjadi solusi dari keadaan Jakarta yang buruk tersebut. Meikarta bukan lagi menjadi mimpi akan “Jakarta Baru yang Cantik”. Meikarta juga menjadi bentuk agenda setting media periklanan untuk memperoleh modal dan keuntungan dari proses pembangunannya. Meikarta hanyalah produk yang dikonstruksi dalam kampanye komunikasi lingkungan terwujudnya “Jakarta Baru yang Cantik” dan dipersuasikan kepada khalayak agar “dibeli” dengan alasan investasi. Hal ini berujung pada keuntungan jangka panjang bagi pihak pembangun Meikarta.
PEMBAHASAN
Penelitian ini mengkaji wacana iklan Meikarta dari perspektif komunikasi lingkungan. Keberadaan iklan Meikarta dapat digolongkan sebagai fungsi teknis komunikasi lingkungan sebab iklan tersebut memberikan informasi tentang kerusakan lingkungan alam dan lingkungan sosial di Jakarta. Iklan Meikarta mencoba memberikan informasi kepada khalayak tentang permasalahan-permasalahan ling-kungan di Jakarta, kemudian menyuguhkan gambaran tempat tinggal dengan ling-kungan yang bersih dan sehat.
Iklan Meikarta mengangkat tema “Pindah dari kota yang kumuh dan padat ke kota modern yang bernama Meikarta”. Tema tersebut dibangun oleh visualisasi anak perempuan yang jenuh dan sedih
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 91-106JurnalILMU KOMUNIKASI
102
dengan kondisi kota yang kumuh, serta narasi “pergi dari sini” yang diucapkan oleh anak perempuan tersebut. Narasi dan visualisasi iklan saling memperkuat pesan mengenai kontrasnya pemandangan dua kota. Kota pertama yang didatangi si anak bersama keluarganya adalah kota yang kumuh, penuh polusi udara, kemacetan karena banjir, bahkan tindak kriminal. Kota kedua yang menjadi tujuan si anak bersama keluarganya merupakan kota modern dengan polusi udara yang rendah karena ada taman kota yang indah, sistem keamanan yang canggih, kondisi kota yang tertata, bebas macet, dan ditunjang dengan teknologi yang mempermudah aktivitas berbelanja maupun bekerja.
Efek desain grafis iklan ini menciptakan visualisasi hunian dengan lingkungan fisik dan sosial yang sangat ideal. Kondisi lingkungan fisik dan sosial yang ideal dalam iklan Meikarta tersebut merupakan bentuk imajinasi pengiklan. Imajinasi tersebut berupa harapan terwujudnya hunian yang nyaman dan bersih di masa depan, seperti tagline Meikarta.
Analisis superstruktur iklan Meikarta menunjukkan konsistensi pengiklan pada rancangan promosinya yang salah satunya memanfaatkan televisi. Bentuk audio-visual iklan televisi dinilai efektif karena memiliki unsur message strategy (strategi penyampaian pesan), action (tindakan), motion (gerakan), dan storytelling (naskah ataupun cerita iklan). Storytelling diperkuat dengan unsur emotion (emosi), demonstration (demonstrasi), sight (unsur pandangan visual), sound (unsur audio/
suara), elements (unsur-unsur iklan), serta filming and taping (proses produksi iklan) (Effendi, 2009, h. 4).
Message Strategy telah digunakan oleh pengiklan Meikarta dengan mengiklankan produk Meikarta di televisi. Televisi sebagai media massa konvensional menampilkan unsur visual beserta audio secara bersamaan, sehingga iklan Meikarta dapat menampilkan unsur audio-visual secara utuh. Sementara itu, action dan motion juga telah digunakan oleh pengiklan Meikarta. Keduanya juga terkait pada televisi yang merupakan media visual bergerak. Inilah yang membuat televisi lebih memikat dibanding media cetak dan radio.
Storytelling pun sangat digunakan dalam naskah atau jalinan cerita iklan Meikarta yang mengkritik kondisi lingkungan fisik dan sosial yang sering terjadi di kota-kota besar, seperti kemacetan, banjir, sampah, polusi, kriminalitas, dan warga yang individualistis. Iklan Meikarta menggunakan media televisi untuk menyentuh emosi khalayak dengan memainkan emosi tokoh anak perempuan. Tokoh seorang anak digunakan untuk menggambarkan kejujuran karena anak-anak biasanya tampil apa adanya, polos, dan spontan dalam mengekspresikan diri.
Sosok seorang anak perempuan juga digunakan sebagai penguat unsur storytelling yang menunjukkan jalinan cerita dengan menghadirkan rasa bosan, kesal, hingga takut si anak perempuan tersebut. Narasi pun berujung pada perubahan emosi dari si anak yang ditunjukkan dengan ekspresi bahagia si
Christina Arsi Lestari. Wacana Komunikasi Lingkungan ...
103
anak saat memasuki kawasan yang bersih, bebas polusi, modern, dan aman untuk anak-anak bermain.
Iklan Meikarta telah mendemonstrasi-kan bentuk dan suasana lingkungan melalui iklan televisi. Iklan Meikarta di televisi termasuk sering tayang saat awal kejayaannya. Visualisasi dari kondisi lingkungan yang disajikan juga dekat dengan kehidupan khalayak yang tinggal di perkotaan. Seolah-olah hal yang dirasakan oleh si anak dalam iklan Meikarta juga turut dirasakan oleh penontonnya.
Iklan Meikarta juga menggunakan unsur elements berupa video dan audio. Unsur ini dibentuk melalui ekspresi tokoh iklan yang ditampilkan dalam sosok anak perempuan, pencahayaan yang kontras antara suram dan cerah, dan proses dramatisasi melalui permainan warna-warna gelap saat setting lokasi berada di kepadatan kota besar. Efek cahaya terang pun mulai muncul saat setting lokasi bertuliskan Meikarta.
Iklan ini membandingkan Meikarta dengan kota metropolitan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Jakarta. Meikarta divisualisasikan lebih megah dibandingkan kota pertama. Kota pertama digambarkan sebagai kota dengan berbagai masalah sosial. Pengiklan menunjukkan tidak adanya kehidupan yang manusiawi pada kota pertama tersebut. Kemudian Meikarta hadir sebagai jalan keluar melalui penggambaran Meikarta sebagai kota yang terang, cerah dengan lingkungan yang sehat, fasilitas yang modern, dan keceriaan keluarga saat berkumpul.
Suasana Meikarta sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan kota pertama. Meikarta juga menawarkan kenyamanan bagi anak dan perempuan melalui ruang terbuka hijau yang luas, tempat piknik bersama keluarga, dan bebasnya anak-anak saat bermain tanpa dihantui kekhawatiran terhadap tindak kriminal. Visualisasi iklan Meikarta juga menawarkan kehidupan yang bebas macet, alam yang bersih, sehat, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern.
Selain itu, pengiklan Meikarta tampaknya juga menawarkan sesuatu yang belum ada sebelumnya, yaitu fasilitas virtual reality untuk berbelanja dan menonton televisi. Fasilitas lain yang juga muncul dalam iklan tersebut adalah Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) berkecepatan tinggi. Seluruh penggambaran tersebut ditawarkan Meikarta sebagai bentuk imajinasi, mimpi, dan harapan. Pembuat iklan sangat mengetahui keresahan warga kota metropolitan.
Fokus pesan iklan Meikarta adalah kritik sosial melalui visualisasi kondisi lingkungan fisik dan sosial. Adegan dalam iklan Meikarta menunjukkan kondisi tata bangunan di perkotaan yang tidak tersusun rapi, kemacetan, banjir, serta realitas sosial dalam wujud kriminalitas dan sifat individualis yang digambarkan dengan ketidakpedulian warga pada tindak kriminal yang dialami orang lain.
Konstruksi makna yang dibangun oleh pengiklan menggiring khalayak untuk menyadari kondisi lingkungan yang
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 91-106JurnalILMU KOMUNIKASI
104
buruk, penuh polusi, serta menimbulkan kepenatan dan tingkat stres yang tinggi. Sementara itu, adegan selanjutnya menggambarkan kondisi lingkungan Meikarta yang menyuguhkan solusi dengan sebuah ilustrasi yang belum nyata. Deskripsi kota impian ini menunjukkan peran pengiklan sangat krusial dalam pemasaran Meikarta. Iklan Meikarta membandingkan superioritasnya dengan kota metropolitan lain seperti Jakarta. Iklan ini tidak hanya menggunakan narasi, tetapi juga memvisualkannya menggunakan teknik pencahayaan yang kontras sebagai pembanding antara Meikarta dengan kota besar lainnya.
Iklan Meikarta ini menggunakan koherensi repetisi atau pengulangan untuk menanamkan pengaruhnya, seperti narasi “kita lupa”. Narasi tersebut digunakan sebagai bentuk kampanye yang dilakukan pihak Lippo Group dengan gencar melalui media massa cetak dan elektronik. Kegiatan pemasaran yang dilakukan secara perlahan namun pasti memersuasi khalayak untuk percaya pada produk Meikarta. Hal ini dibuktikan pihak Lippo Group yang berhasil menyelesaikan pembangunan dua Apartemen di CBD Meikarta pada Januari 2019. Kedua menara yang bernama Glendale Park dan Newport Park itu merupakan menara kelima dan keenam di Orange County dengan total 1.094 unit apartemen. Perusahaan mengaku bahwa apartemen di CBD Meikarta itu telah laku hingga 95 persen sejak penjualan perdananya pada tahun 2016 (Sugianto, 2019).
Iklan Meikarta menempatkan wacana lingkungan pada ranah agenda setting. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadi simbol utama yang dipakai untuk memengaruhi khalayak dan mengonstraskannya dengan kondisi lingkungan yang buruk dan tidak baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Hal ini membingkai makna melalui angan-angan tentang lingkungan modern dan sehat. Bentuk pembingkaian yang sesuai dengan definisi di atas merupakan solusi atau hasil yang ditawarkan dalam setiap iklan. Hal inilah yang sering disebut sebagai konstruksi makna.
Gambaran Iklan Meikarta telah mampu memengaruhi khalayaknya. Iklan menjadi sarana bagi Meikarta memengaruhi khalayaknya untuk percaya pada produk Meikarta dan seakan-akan khalayak menutup mata pada kasus-kasus yang diberitakan media terkait proses pembangunannya.
Selain itu, iklan Meikarta tidak ditujukan untuk golongan masyarakat menengah ke bawah. Iklan ini menyasar kalangan menengah ke atas karena mengambil sudut pandang seorang anak perempuan. Si anak perempuan diperankan oleh tokoh berwajah indo. Si anak juga berada di dalam mobil dan menciptakan jarak dengan masyarakat kota. Si anak tersebut tidak digambarkan berada di tepi jalan, di dalam angkutan umum, atau sedang bersepeda motor sebagai gambaran yang lebih lekat dengan kondisi kaum menengah ke bawah.
Oleh karena itu, ideologi yang tampaknya berusaha ditanamkan dalam iklan Meikarta adalah kota besar yang ada saat ini, seperti Jakarta, merupakan kota
Christina Arsi Lestari. Wacana Komunikasi Lingkungan ...
105
yang jelek, tidak nyaman, dan tidak aman untuk ditinggali. Meikarta sebagai kota yang masih dalam tahap pembangunan hadir dan memosisikan diri sebagai Jakarta yang baru, serta menjadi solusi dari semua permasalahan kota besar yang sudah ada sebelumnya. Konsep kebaruan dan modernitas yang ditawarkan pada iklan Meikarta menjadi janji dari pengiklan kepada calon pembeli tentang hunian dan hidup baru yang lebih berkualitas.
Iklan Meikarta, ditinjau dari fungsi komunikasi lingkungan, menunjukkan dampak kerusakan lingkungan alam dan lingkungan sosial di Jakarta. Iklan Meikarta mencoba memberikan informasi kepada khalayak tentang permasalahan-permasalahan lingkungan di kota Jakarta dan menyuguhkan gambaran tempat tinggal dengan lingkungan yang bersih dan sehat.
SIMPULAN
Wacana yang ditampilkan iklan Meikarta menyajikan agenda setting dan pembingkaian sebagai kunci utama keberhasilannya. Ideologi yang tampaknya berusaha ditanamkan dalam iklan Meikarta adalah kota besar yang ada saat ini, seperti Jakarta, merupakan kota yang jelek, tidak nyaman, dan tidak aman untuk ditinggali. Meikarta sebagai kota yang masih dalam tahap pembangunan hadir dan memosisikan diri sebagai Jakarta yang baru, serta menjadi solusi dari semua permasalahan kota besar yang sudah ada sebelumnya.
Keberadaan iklan Meikarta, ditinjau dari fungsi komunikasi lingkungan, dapat digolongkan sebagai fungsi teknis karena
memberikan informasi mengenai dampak kerusakan lingkungan alam dan lingkungan sosial di Jakarta. Identifikasi lanjutan mengenai dampak iklan Meikarta dapat dikaji melalui penelitian yang berbeda di masa depan.
DAFTAR RUJUKAN
Akbar, A. (2020). Berapa kepadatan penduduk DKI Jakarta saat ini? www.jakarta.go.id. <http://statistik.jakarta.go.id/berapa-kepadatan-penduduk-dki-jakarta-saat-ini/>
Ardian, H. Y. (2018). Kajian teori komunikasi lingkungan dalam penelitian pengelolaan sumber daya alam. Perspektif Komunikasi, 2(1), h. 1-20.
Ariestya. A. (2017). Mempertanyakan eksistensi komunikasi lingkungan di Indonesia. www.kompas.com. <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/08220681/mempertanyakan-eksistensi-komunikasi-l ingkungan-di-indonesia?page=all>
Atmakusumah. (2000). Mengangkat masalah lingkungan ke media massa. Jakarta, Indonesia: Obor.
Badara, A. (2012). Analisis wacana: Teori, metode, dan penerapannya pada wacana media. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
Brata, I. (2017). Analisis iklan rumah spa dan salon kecantikan di kecamatan ubud. Retorika, 3(1), 16-29.
Budi, K. (2017). Banyaknya penjualan meikarta buktikan tingginya minat masyarakat. www.kompas.com. <https://sorot.kompas.com/meikarta/read/2017/11/25/171600428/banyaknya-penjualan-meikarta-buktikan-tingginya-minat-masyarakat>
Detik. (2017). Dampak iklan meikarta munculkan animo besar masyarakat. www.detik.com.
<https://finance.detik.com/advertorial-news-block/d-3631437/dampak-iklan-meikarta-munculkan-animo-besar-masyarakat>
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 91-106JurnalILMU KOMUNIKASI
106
Effendi, M. A. (2009). The power of corporate governance: Teori dan implementasi. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
Eriyanto. (2001). Analisis wacana: pengantar analisis teks media. Yogyakarta, Indonesia: LKiS.
Fairclough, N. (1989). Language and power. London, United Kingdom: Longman.
Fauzan, R., & Pamungkas, W. W. (2018). Izin proyek meikarta beda luas lahan garapan. www.bisnis.com. <https://surabaya.bisnis.com/read/20181025/440/852949/izin-proyek-meikarta-beda-luas-lahan-garapan>
Ikhsanudin, A. (2019). Pemprov DKI banggakan tingkat kemacetan Jakarta turun 8% di 2018. www.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4589136/pemprov-dki-banggakan-tingkat-kemacetan-jakarta-turun-8-di-2018>
Imam, A. F. (2012). Analisis wacana van Dijk pada lirik lagu irgaa tani (my heart will go on). Journal of Arabic Learning and Teaching, 1(1), 1-8.
Kholisoh, N. (2015). Konstruksi peran politik perempuan di media. Jurnal Wacana, 14(4), 297-400.
Kurnia, T. (2020). Kualitas udara Jakarta terburuk nomor 5 di dunia, Tangsel terpolusi se-Indonesia. www.liputan6.com. <https://www.liputan6.com/global/read/4187320/kualitas-udara-jakarta-terburuk-nomor-5-di-dunia-tangsel-terpolusi-se-indonesia>
Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Encyclopedia of communication theory. Thousand Oaks, CA: Sage.
Sari, N. (2019). Ada 445 rw kumuh di Jakarta, hanya 200 yang ditata dengan konsep cap. www.kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/06/08101031/ada-445-rw-kumuh-di-jakarta-hanya-200-yang-ditata-dengan-konsep-cap?page=all>
Sidik, F. M. (2019). Kejahatan di Jakarta selama 2019 terjadi setiap 16 menit 11 detik. www.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4837676/kejahatan-di-jakarta-selama-2019-terjadi-setiap-16-menit-11-detik>
Sugianto, D. (2019). Konstruksi 2 apartemen di cbd meikarta rampung. www.detik.com. <https://finance.detik.com/properti/d-4398686/konstruksi-2-apartemen-di-cbd-meikarta-rampung>
Tarigan, S. (2019). Meikarta terkini: Temuan kpk terbaru kasus meikarta hingga terkuak biaya anggota dprd ke luar negeri. www.tribunnews.com. <http://medan.tribunnews.com/2019/01/09/meikarta-terkini-temuan-kpk-terbaru-kasus-meikarta-hingga-terkuak-biaya-anggota-dprd-ke-luar-negeri>
Yusman, R. (2018). Konstruksi media online tentang pemberitaan perizinan meikarta di www.beritasatu.com dan www.kompas.com edisi september 2017. Jurnal Mediakom, 8(1), 15-30.
107
Literasi Privasi dan Perilaku Proteksi Konsumen Belanja Daring Generasi Y
Ananda Dwitha Yuniar & Alan Sigit FibriantoUniversitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang 65145Email: [email protected]
Abstract: Inhibited conditions in communication process of the online shopping have led to privacy concerns. Some previous studies show privacy paradox. Measurements of online privacy literacy play an important role to fill the paradoxical privacy gaps. Moderated regression analysis (MRA) is used to measure causality between these variables with privacy breach experiences as the moderate variables. The total number of respondents is 283. The research finding shows that the higher the level of online privacy literacy, the user will be aware of the violation of privacy and able to be protective. However, violations of privacy cannot be considered as a trigger for consumers’ protective behavior.
Keywords: online shopping, privacy literacy, privacy paradox
Abstrak: Kondisi yang terbatas dalam proses komunikasi belanja daring memunculkan perdebatan mengenai isu privasi. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kekhawatiran konsumen terhadap privasi tidak memiliki konsistensi terhadap perilaku (paradoks privasi). Pengukuran literasi privasi memiliki peran yang cukup penting untuk mengisi gap paradoks privasi tersebut. Pengukuran kausalitas antarvariabel ini menggunakan moderated regression analysis (MRA) dengan pengalaman pelanggaran privasi sebagai variabel moderasi. Total responden yang berpartisipasi berjumlah 283 orang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi daring pengguna, semakin sadar pula pengguna tersebut terhadap pelanggaran privasi dan memiliki kemampuan bersikap protektif. Namun, pelanggaran privasi tidak bisa dianggap sebagai pemicu tindakan protektif konsumen.
Kata Kunci: belanja online, literasi privasi, paradoks privasi
Belanja online atau dalam jaringan (daring) bukan semata-mata kegiatan ekonomi tentang pertukaran uang dan barang. Belanja daring merupakan kegiatan komunikasi, interaksi, dan transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan jaringan internet yang dimediasi layar komputer atau smartphone. Proses komunikasi dalam belanja daring meliputi hubungan interpersonal antara penjual dan pembeli hingga terjadi pertukaran
informasi. Berdasarkan karakteristiknya, belanja daring memiliki aturan dan kondisi yang terbatas dalam proses komunikasi maupun transaksinya, serta berbeda dengan proses belanja konvensional (brick mortal) yang dapat diselesaikan dalam satu waktu (Trepte, dkk., 2015, h. 336). Keterbatasan komunikasi dalam belanja daring menyebabkan komunikasi antara penjual dan pembeli berbasis pada kepercayaan (trust).
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 107-122JurnalILMU KOMUNIKASI
108
Keterbatasan serta perbedaan karak-teristik antara belanja daring dengan belanja konvensional ini membuat konsumen harus mampu mengatasi segala tantangan, termasuk risiko privasi. Platform belanja daring yang memiliki fungsi utama sebagai marketplace dan menyumbang pertumbuhan perekonomian digital suatu negara dikenal dengan sebutan e-commerce. Menurut Metzger (2007, h. 336), privasi memiliki implikasi terhadap e-commerce karena melibatkan pengungkapan informasi pribadi, seperti nomor telepon seluler (ponsel), alamat rumah, alamat surat elektronik (surel), dan nomor kartu kredit. Mooney (2015, h. 8) menyatakan bahwa informasi privasi merupakan kerahasiaan pemikiran dan perlu dilindungi dari berbagai pelanggaran privasi, seperti doxing dan hacking. Pengungkapan informasi pribadi dalam proses belanja daring memunculkan isu penting mengenai privasi bagi konsumen karena konsumen diharuskan mengungkapkan informasi pribadi saat melakukan transaksi.
Proses pengungkapan informasi pribadi menimbulkan kepedulian konsumen ter-hadap privasi (privacy concern). Dalam transaksi e-commerce, kepedulian terhadap privasi muncul ketika konsumen berpotensi kehilangan kendali atas informasi pribadinya (Metzger, 2007, h. 336). Beberapa penelitian menaruh perhatian mengenai privacy concern konsumen dalam konteks belanja daring, khususnya e-commerce (Vasileiadis, 2014; Gupta & Dubey, 2016; Fortes & Rita, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian terhadap privasi tidak memiliki konsistensi terhadap perilaku. Hal tersebut
berarti bahwa konsumen telah memiliki kepedulian dan kekhawatiran terhadap ancaman dan risiko privasi ketika mereka mengungkapkan informasi pribadi melalui internet, tetapi mereka tidak melakukan tindakan proteksi terhadap privasi mereka.
Tidak adanya konsistensi antara kekhawatiran konsumen terhadap privasi dengan perilaku konsumen ini disebut sebagai privacy paradox atau paradoks privasi (Kokolakis, 2015, h. 2). Paradoks privasi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce karena semakin paradoksnya perilaku konsumen terhadap privasi memudahkan pihak e-commerce mengumpulkan informasi pribadi dan preferensi konsumen sebanyak-banyaknya (Büchi, Just, & Latzer, 2016, h. 3). Informasi pribadi konsumen yang dihimpun dapat menjadi big data atau e-commerce database (basis data) yang memiliki nilai bisnis tinggi dan juga menyebabkan potensi pelanggaran privasi informasi lebih besar (Shinta, 2009, h. 53). Pelanggaran privasi ini disebabkan oleh penjualan informasi pribadi konsumen oleh e-commerce yang bersangkutan kepada perusahaan lain tanpa izin untuk kepentingan tertentu.
Perlindungan informasi pribadi konsumen merupakan salah satu isu penting dalam e-commerce di Indonesia (Kearney, 2015, h. 11) karena belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus perlindungan informasi pribadi konsumen oleh pemerintah. Padahal di negara maju informasi maupun data pribadi konsumen mendapatkan perlindungan undang-undang.
Ananda Dwitha Yuniar & Alan Sigit Fibrianto. Literasi Privasi dan ...
109
Selain itu, data Google & Temasek (2016) menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh e-commerce Indonesia adalah sentimen konsumen yang buruk akibat adanya kecurangan dalam memanfaatkan informasi pribadi konsumen tanpa izin. Memanfaatkan, menghimpun, dan menyalahgunakan infor-masi privadi konsumen merupakan bentuk pelanggaran hukum, tetapi kesadaran ini belum menjadi perhatian khusus di Indonesia karena kurangnya peer group yang mewadahi dan mendukung perdebatan mengenai perlindungan privasi.
E-commerce yang beroperasi di Indonesia telah membangun pendekatan untuk melindungi informasi pribadi atau privasi konsumen melalui fitur kebijakan privasi. Namun pada kenyataannya, sistem keamanan dan kebijakan privasi yang digunakan di situs e-commerce tidak sesuai dengan standar keamanan digital (Jumiati, Rosdiana, & Kusumastuti, 2017, h. 60). Pada tahun 2016, sistem keamanan yang tidak sesuai standar ini dibuktikan dengan terjadinya cyber crime pada platform besar di Indonesia, yakni Tokopedia dan BukaLapak. Kedua platform e-commerce tersebut diretas. Bahkan pelaku menyatakan bahwa mereka dengan leluasa dapat mengambil data penting konsumen, seperti alamat surel, kata sandi, nomor rekening, hingga nomor kartu kredit (Nistanto, 2016). Kejadian ini membuktikan bahwa kedua platform e-commerce besar sekelas BukaLapak dan Tokopedia pun tidak sepenuhnya dapat menjamin keamanan informasi pribadi konsumen. Melalui kejadian ini, tidak dapat dipungkiri bahwa
potensi distorsi informasi pribadi konsumen dapat terjadi pada e-commerce baru.
Problem paradoks atau ketidaksesuaian yang dimiliki oleh konsumen mendorong peneliti berasumsi bahwa konsumen belum melek penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam penelitiannya, Trepte, dkk. (2015, h. 362) menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang tata cara melindungi privasi pengguna membuat tidak adanya kesesuaian dengan perilaku. Pengguna sebenarnya telah berusaha untuk mengontrol informasi mereka, tetapi mengalami masalah dalam praktiknya karena kurangnya literasi privasi daring. Park (2013, h. 217) menyatakan bahwa literasi privasi daring merupakan prinsip yang mendorong, mendukung, dan memberdayakan pengguna untuk melakukan kontrol atas informasi pribadi mereka. Selain itu, literasi privasi daring dipahami sebagai bagian dasar yang penting dalam domain perdebatan privasi digital (Park, Campbell, & Kwak, 2012, h. 1019).
Kegunaan internet dapat dirasakan oleh pengguna ketika mereka melakukan pengungkapan informasi pribadi. Pengguna sering tidak menyadari bahwa jejak aktivitas penjelajahan internet maupun pembelian daring tersimpan oleh sistem (Acquisti, Brandimarte, & Loewenstein, 2015, h. 510). Jejak dan informasi pribadi konsumen, mulai dari alamat surel, informasi akun bank, history, cookie, hingga alamat Internet Protocol (IP), dapat dijadikan aset data untuk kepentingan bisnis melalui sistem algoritma (Latzer, Hollnbuchner, Just, & Saurwein, 2014). Begitu pula dalam konteks belanja daring, informasi pribadi yang diberikan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 107-122JurnalILMU KOMUNIKASI
110
sebagai ketentuan transaksi dapat menjadi big data yang menguntungkan. Memanfaatkan basis data konsumen dianggap sebagai strategi pemasaran baru yang dapat memiliki pengaruh besar pada peningkatan perekonomian digital (Agustiyanti, 2017) dan meningkatnya potensi pelanggaran privasi.
Kini, konsumen belanja daring mulai peduli dengan distorsi privasi mereka. Survei Mastel dan APJII (2016) menyatakan bahwa 98 persen konsumen daring membutuhkan perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah mengenai data pribadi. Namun demikian, beberapa penelitian menyatakan bahwa privacy concern tidak memiliki konsistensi terhadap perilaku. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Fortes dan Rita (2016) yang menyatakan bahwa konsumen merasakan tingkatan risiko ketika melakukan belanja daring, namun konsumen tetap melakukan keterbukaan berulang. Sementara itu, penelitian Vasileiadis (2014) menyatakan bahwa risiko konsumen terkait keamanan informasi privasi tidak menghalangi mereka untuk mengadopsi mobile commerce. Sedangkan penelitian Carrascal, Riederer, Erramilli, Cherubini, dan Oliveira (2013) menunjukkan bahwa individu menyadari informasi pribadi mereka tidak terlindungi, namun mereka tetap bersedia memberikannya.
Secara konseptual, elemen pengukuran literasi privasi ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan, namun ada perbedaan dengan penelitian Trepte, dkk. (2015), yaitu penelitian tersebut lebih mengedepankan pengetahuan tentang aspek hukum dan regulasi. Sementara itu, literasi privasi daring yang digunakan dalam penelitian di
ranah ilmu komunikasi ini adalah aspek-aspek yang mampu mengukur pengetahuan mengenai penggunaan media daring.
Secara singkat, literasi privasi merupa-kan kombinasi dari penerangan fakta (knowing that) dan prosedural (knowing how) pengetahuan tentang privasi daring. Dalam penelitian ini, aspek penerangan fakta literasi privasi mengacu pada pengetahuan pengguna mengenai kesadaran tentang praktik kerja institusi dan pemahaman terhadap kebijakan privasi. Sedangkan pengetahuan prosedural mengacu pada kemampuan pengguna dalam melakukan kontrol atau proteksi atas informasi pribadi ketika melakukan belanja daring.
Salah satu alasan utama yang mendorong konsumen memilih berbelanja daring adalah faktor kenyamanan yang memungkinkan aktivitas tersebut dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Faktor lain yang juga menjadi pendorong adalah ketersediaan dan keberagaman produk, komparasi harga, dan penghematan biaya (Rose, Clark, Samouel, & Hair, 2012). Namun, berbelanja daring juga tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Lissitsa dan Kol (2016, h. 310) menjelaskan bahwa salah satu kekurangan paling riskan dalam berbelanja daring adalah adanya ancaman atau risiko terhadap informasi pribadi konsumen yang datang dari pihak e-vendor, sehingga konsumen harus memiliki kemampuan proteksi untuk menghindari hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Trepte, dkk. (2015, h. 339), yaitu pengetahuan prosedural sebagai elemen literasi privasi daring mengacu pada kemampuan pengguna melakukan kontrol atau proteksi atas informasi pribadi mereka.
Ananda Dwitha Yuniar & Alan Sigit Fibrianto. Literasi Privasi dan ...
111
Kemampuan pengguna dapat diukur menggunakan basis Protection Motivation Theory (PMT). Rogers menyatakan bahwa ‘protecting motivation’ merupakan faktor yang mengarahkan individu untuk mencegah ancaman/risiko (Youn, 2009, h. 397). PMT disusun sebagai dua subproses perantara yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi ancaman (threat-appraisal process) dan memilih alternatif (coping appraisal). Dalam konteks privacy behavior, konsumen dapat mendorong motivasi proteksi mereka dan terlibat dalam perilaku pengurangan risiko (Youn, 2009, h. 399).
Strategi yang dapat diterapkan oleh pengguna meliputi penghindaran, yakni mengabaikan ancaman hingga memilih untuk tidak menggunakan internet. Menurut Youn (2009, h. 399), ada dua indikator untuk mengukur kemampuan penghindaran pengguna, yakni fabricate dan refrain. Fabricate merupakan tanggapan konsumen untuk memalsukan informasi pribadi mereka. Sedangkan refrain adalah kemampuan konsumen meningkatkan kontrol dalam melakukan interaksi dengan website (e-commerce). Cho, Sánchez, dan Lim (2009, h. 407) menyatakan bahwa semakin besar kepedulian individu tentang pengumpulan informasi oleh para pemasar dan praktik pengambilan informasi lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang mencoba mengadopsi privacy protection behaviour.
Penelitian terbaru oleh Büchi, Just, dan Latzer (2016) menyatakan bahwa privacy protection behaviour berfokus pada self-help dalam tindakan proteksi. Self-help berkaitan
dengan kemampuan pengguna dalam menggunakan internet. Dengan kata lain, self-help dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pengguna untuk melawan distorsi privasi. Self-help meliputi aspek teknis termasuk privacy-enhancing technologies, cookie management, hingga do-not-track technologies. Kemampuan self-help proteksi privasi ini penting karena organisasi/platform mendapat keuntungan dari pengumpulan dan pertukaran data pribadi konsumen (Saurwein, Just, & Latzer, 2015). Selain itu, Büchi, Just, dan Latzer (2016, h. 12) juga menambahkan bahwa kemampuan perilaku proteksi tersebut juga didukung adanya pengalaman pelanggaran privasi (privacy breaches). Perilaku proteksi didukung oleh sikap pengguna untuk melindungi informasi pribadi mereka dan menjadi penguat perilaku karena adanya pengalaman atau kecurigaan pelanggaran privasi.
Artikel ini menyajikan hasil penelitian yang mengukur literasi privasi konsumen dalam belanja daring. Hasil tersebut merupakan jawaban terhadap dua pertanyaan. Pertama, seberapa besar pengaruh literasi privasi daring konsumen generasi Y (gen Y) urban terhadap kemampuan bersikap proteksi ketika melakukan belanja daring? Kedua, sejauh mana pengaruh variabel pengalaman pelanggaran privasi mampu memoderasi elemen literasi privasi daring terhadap kemampuan bersikap proteksi?
Penelitian terdahulu yang terkait dengan literasi privasi dalam media daring serta kemampuan individu dalam melindungi informasi privasi mereka dapat ditelusuri dari tiga penelitian. Pertama, penelitian Park
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 107-122JurnalILMU KOMUNIKASI
112
(2013) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dari literasi digital terhadap kemampuan kontrol terhadap informasi pribadi pengguna media daring. Variabel bebas dalam penelitian Park adalah literasi yang mencakup tiga hal, yaitu keakraban dengan aspek teknis, kesadaran terhadap praktik institusi (e-commerce), dan pemahaman terhadap kebijakan privasi. Variabel terikatnya adalah perilaku kontrol atas informasi yang meliputi dimensi sosio-teknis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengguna yang terliterasi dengan baik lebih mempraktikkan kontrol informasi dibandingkan dengan pengguna yang kurang terliterasi. Faktor sosio-demografi, seperti tingkat pendapatan dan pendidikan juga berpengaruh positif terhadap kemampuan mengontrol informasi.
Kedua, penelitian Trepte, dkk. (2015) yang bertujuan untuk mengelaborasi peran dari literasi privasi dalam menjelaskan perilaku konsumen dan sikap (attitude) pengguna tentang privasi. Metode yang digunakan adalah analisis isi. Literasi privasi dalam penelitian ini mengacu pada pengetahuan dan strategi data protection. Mereka membuat konsep untuk mengetahui dan menganalisis tingkat literasi privasi yang disebut online privacy literacy scale (OPLIS) yang terdiri dari lima elemen, yaitu pengetahuan tentang praktik organisasi, pengetahuan tentang aspek teknis, pengetahuan tentang aspek hukum dan legal, pengetahuan tentang European directives on privacy, dan pengetahuan tentang regulasi informasi pribadi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu yang peduli terhadap privasi sebenarnya ingin
bertindak sesuai dengan kepeduliannya, tetapi kurangnya literasi privasi menghambat mereka berperilaku konsisten.
Ketiga, penelitian Büchi, Just, dan Latzer (2016) yang lebih berfokus pada kemampuan pengguna media daring dalam melakukan proteksi diri terhadap informasi pribadi mereka. Pendekatan pada fenomena ini didasarkan pada asumsi bahwa protective behaviour tergantung pada sikap terhadap privasi, pengalaman, dan tingkat keterampilan menggunakan internet. Ada beberapa elemen pengukur kemampuan self-protection, antara lain pengaturan, penyamaran, hingga penghapusan. Studi tersebut menerangkan bahwa perilaku proteksi didasarkan pada pengalaman pelanggaran terhadap privasi mereka. Seharusnya individu yang memiliki keahlian dan keterampilan digital dapat menghindari pelanggaran privasi dan tidak menyebabkan individu merasakan ancaman yang lebih besar.
Ketiga penelitian tersebut tidak menyebutkan secara spesifik konteks yang mereka gunakan, baik dalam media sosial maupun belanja daring. Masing-masing penelitian juga memiliki perspektif, variabel, metode, dan wilayah generalisasi yang berbeda, meskipun berada dalam satu topik pembahasan yang sama, yaitu peran literasi privasi dalam media daring. Penelitian Büchi, Just, dan Latzer (2016) di atas menunjukkan adanya paradoks privasi, yaitu keterampilan (skills) dalam mengoperasikan media digital tidak berpengaruh terhadap perilaku proteksi, sehingga perlu adanya peran literasi media daring untuk mengukur sejauh mana
Ananda Dwitha Yuniar & Alan Sigit Fibrianto. Literasi Privasi dan ...
113
pengetahuan (knowledge) pengguna, bukan sebatas kemampuannya saja.
Penelitian ini menggunakan literasi privasi dalam konteks belanja daring, sehingga terlihat perbedaan dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini pun berbeda karena mengisi kekosongan penelitian di Indonesia yang mengkaji tentang literasi privasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya tentang literasi dalam media digital.
METODE
Survei daring dilakukan untuk mengukur dan menganalisis sejauh mana tingkat literasi privasi konsumen belanja daring memengaruhi kemampuan berperilaku protektif atas informasi pribadi. Survei daring tersebut menggunakan Google Forms yang disebarkan selama dua bulan dengan perhitungan jumlah sampel minimum yang harus terkumpul
menggunakan formula Lemeshow, yaitu sebanyak 270 responden. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik, sehingga pengumpulan data dan interpretasi data bersifat objektif. Peneliti diposisikan terpisah dari objek penelitian, sehingga tidak ada intervensi jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Responden yang menjadi objek penelitian memiliki dua karakteristik. Pertama, konsumen belanja daring di Surabaya dan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Kedua wilayah tersebut dipilih karena memiliki jumlah pelaku belanja daring tertinggi di Indonesia (MARS Indonesia, 2016). Kedua, pelaku belanja daring berusia milenial atau biasa disebut sebagai generasi Y (gen Y), yaitu orang dalam rentang usia 18-30 tahun. Generasi ini disebut sebagai digital natives dan berada pada rentang usia yang menjadi target utama e-commerce dalam memasarkan produk maupun jasa.
Tabel 1 Pengukuran Variabel Literasi Privasi Daring
No Variabel Indikator Pengukuran Sumber1. Literasi Privasi
DaringKeakraban dengan aspek teknis
Keakraban dengan aspek teknis yang terdapat pada e-commerce, mulai dari aspek yang bersifat generik hingga teknis yang berbasis keamanan digital.
Likert:Tidak sama sekali – Sangat familier
Park (2013); Gupta dan Dubey (2016)
Kesadaran terhadap praktik institusi
Kesadaran terhadap praktik yang dilakukan e-commerce, seperti promosi dan iklan.
True – False Park (2013)
Pemahaman mengenai kebijakan yang berlaku di Indonesia
Pemahaman mengenai kebijakan, legalitas, dan aturan yang berkaitan dengan privasi yang berlaku.
True – False
2. Kemampuan berperilaku protektif
Kemampuan pengabaian dan kemampuan teknis
Kemampuan mengabaikan,menahan diri, mengatur, memonitor, memalsukan, dan menghapus informasi pribadi daring.
Likert:Tidak sama sekali – Sangat sering
Youn (2009); Park, (2013); Büchi, Just, dan Latzer (2016)
3. Pelanggaran Privasi
Pengalaman pelanggaran privasi
Pelanggaranpenyalahgunaan
Binary (0-1) Büchi, Just, dan Latzer (2016)
Sumber: Olahan Peneliti
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 107-122JurnalILMU KOMUNIKASI
114
Kuesioner daring yang digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian telah diuji coba. Data awal yang diuji validitasnya adalah pretest kuesioner yang disebarkan kepada konsumen urban di kedua lokasi penelitian. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan cara mengorelasikan setiap skor item dengan skor total menggunakan teknik korelasi Pearson (Product Moment). Tingkat signifikansi 10 persen menghasilkan r
tabel 0,288. Pengukuran reliabilitas dikatakan memberikan hasil yang konsisten atau reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.
HASIL
Pengujian validitas masing-masing variabel penelitian menunjukkan adanya satu item pertanyaan instrumen yang tidak valid atau rtabel > riT, yakni variabel Technology Familiarity (X1), item pertanyaan (TF2), mengenai tingkat keakraban responden pada kegunaan utama dari surel pribadi, sehingga item
pertanyaan tersebut dibuang dan tidak digunakan sebagai alat ukur. Selain itu, semua nilai koefisien korelasi item atau sebanyak 48 item pertanyaan menghasilkan skor total (riT) > dari nilai korelasi tabel (rtabel). Dengan demikian, item kuesioner pada variabel X1, X2, X3, Y, dan moderasi Z dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian. Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini menggunakan one shot, yaitu pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan sekali penyebaran kuesioner pada responden. Selanjutnya, hasil skor tersebut diukur korelasinya. Berdasarkan ringkasan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian diketahui bahwa semua nilai Cronbach’s Alpha > 0.6. Dengan demikian, item pertanyaan kuesioner pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel atau konsisten dalam pengukuran masing-masing variabel.
Setelah mengukur dan menghitung hasil penelitian dalam bentuk data statistik dengan menggunakan SPSS 20, peneliti
Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas One Shot
Variabel Koefisien Validitas (M)
Korelasi Tabel Keterangan
X1 0.738 > 0.288 ValidX2 0.538 > 0.288 ValidX3 0.580 > 0.288 ValidY 0.650 > 0.288 ValidZ 0.922 > 0.288 Valid
Variabel Koefisien Reliabilitas Batas Toleransi Keterangan
X1 0.915 < 0.6 ReliabelX2 0.643 < 0.6 Reliabel
X3 0.701 < 0.6 Reliabel
Y 0.925 < 0.6 Reliabel
Z 0.822 < 0.6 Reliabel
Sumber: Olahan Peneliti
Ananda Dwitha Yuniar & Alan Sigit Fibrianto. Literasi Privasi dan ...
115
melakukan pembahasan dengan tujuan menginterpretasikan, memperjelas makna, dan secara lebih detail menjabarkan gambaran nyata variabel yang diteliti dengan pembuktian teori-teori yang digunakan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang akan digambarkan secara objektif sesuai data empirik.
Penelitian ini menggunakan dua tahap analisis. Pertama, menggunakan deskriptif statistik agar pembaca memahami kondisi garis besar objek dan variabel penelitian. Kedua, data penelitian diolah dengan analisis regresi moderasi (MRA) untuk memoderasi variabel pengetahuan tentang aspek teknis (X1), pengetahuan tentang praktik institusi (X2) (dalam penelitian ini berkaitan dengan belanja daring), dan pengetahuan tentang kebijakan privasi (X3) terhadap variabel Y, yaitu kemampuan pengguna untuk bersikap protektif terhadap informasi pribadi mereka ketika melakukan belanja daring pada e-commerce. Pembahasan lebih lengkap terlihat dalam tabel 3.
Sebagian besar responden generasi Y yang berpartisipasi dalam penelitian
ini berumur antara 22-25 tahun sebesar 57,6 persen dari total 283 responden dan didominasi oleh responden perempuan, yaitu sebesar 60,8 persen. Selain itu, responden yang berdomisili di Jabodetabek dan Surabaya memiliki persentase yang hampir seimbang.
Tabel 4 menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen tentang privasi dalam belanja daring di Indonesia berada pada rata-rata. Hal ini terlihat pada elemen keakraban dengan aspek teknis yang memiliki M=3.13 dan SD=0.95. Konsumen belanja daring lebih familier dengan aspek-aspek teknis yang bersifat generik, seperti HTML, IP Address, Cookies, dan Firewalls, serta dianggap sebagai aspek teknis yang mampu melindungi informasi pribadi ketika belanja pada platform e-commerce.
Sementara itu, pada elemen kesadaran dengan praktik e-commerce, seperti iklan, spam, dan phising, konsumen Indonesia telah memiliki pengetahuan karena mampu menjawab dengan benar M=0.72 dan SD=0.45. Namun, sebagian konsumen masih memiliki pengetahuan yang terbilang lemah, sehingga mereka belum menyadari informasi pribadi mereka disalahgunakan.
Tabel 3 Statistik Deskriptif Demografi Responden (N = 283)
% %
Umur Gender
18 – 2122 – 2526 – 29
6.7 PerempuanLaki-laki
60.857.6 39.235.3 Frekuensi Belanja Daring
Domisili Cukup SeringSeringSering Sekali
32.9JabodetabekSurabaya
47.3 50.552.7 16.6
Sumber: Olahan Peneliti
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 107-122JurnalILMU KOMUNIKASI
116
Sedangkan pada elemen ketiga, pemahaman terhadap kebijakan privasi M=0.69 dan SD=046 menyatakan bahwa konsumen belanja daring cukup paham tentang kebijakan privasi, namun banyak juga responden yang belum mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan informasi pribadi. Sebagian besar responden menyatakan pernah mengalami pelanggaran privasi dan mereka kini sedang mengalami pelanggaran privasi. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen Indonesia telah memiliki ke sadaran bahwa privasi mereka dapat disalahgunakan ketika melakukan belanja daring, khususnya pada platform e-commerce.
Tabel 4 Distribusi Pengetahuan Responden (N=283)
Variabel M SDLiterasi Privasi Daring
Keakraban dengan aspek teknis
Kesadaran terhadap praktik e-commerce
Pemahaman terhadap kebijakan privasi
3.13 0.95
0.72 0.45
0.69 0.46
Kemampuan Proteksi Privasi 2.85 1.17
Variabel ZPersepsi Responden
MTidak Ya
Z1 % 44.2 55.8 0.56
Z2 % 47.3 52.7 0.53
Sumber: Olahan Peneliti
Tabel 5 Regresi Moderasi *Sig < 0.1
Variabel β t value
X1 .308* .000X2 .157* .002X3 .091* .006Z .300 .301
X1 X Z .208* .002
X2 X Z -.100* .023X3 X Z -.023 .461
Sumber: Olahan Peneliti
PEMBAHASAN
Hasil literasi privasi menunjukkan regresi tahap pertama, kedua, dan ketiga mengindikasikan bahwa keakraban terhadap aspek teknis (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan proteksi privasi (Y). Hal ini berarti semakin tinggi keakraban pada aspek teknis cenderung dapat meningkatkan kemampuan proteksi privasi. Hasil ini mendukung hipotesis (1a) bahwa konsumen dengan tingkat keakraban tinggi dengan aspek teknis akan memiliki kemampuan bersikap protektif terhadap privasi. Hal ini sejalan dengan Park (2013) dan Trepte, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang aspek teknis merupakan bagian penting yang memiliki
Ananda Dwitha Yuniar & Alan Sigit Fibrianto. Literasi Privasi dan ...
117
pengaruh positif terhadap kemampuan mengontrol hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan informasi privasi. Dengan kata lain, aspek teknis merupakan elemen penting untuk mengukur pengetahuan konsumen dalam konteks literasi privasi daring. Aspek teknis Platform Privacy Preference (P3P) atau dikenal sebagai kebijakan privasi dan phising merupakan item yang paling berkaitan langsung dengan keamanan privasi pada platform e-commerce. Namun demikian, persentase keakrabannya tidak tinggi dan responden lebih memiliki keakraban dengan aspek teknis yang bersifat generik, seperti HTML, IP Address, Cookies, dan Firewalls. Hal ini sesuai dengan istilah digital natives yang dikemukakan oleh Hershatter dan Epstein (2010, h. 212) bagi generasi Y yang memiliki keakraban dan pengetahuan tentang aspek teknis.
Penelitian ini tidak bisa menggali lebih dalam responden yang mengaku memiliki pengetahuan tentang aspek teknis. Misalnya, ketika responden menjawab familier tentang fungsi cookies, hal ini akan semakin terbukti ketika responden diberikan pertanyaan tambahan mengenai pengetahuan seperti apa yang mereka ketahui tentang cookies. Cookies merupakan perangkat lunak yang dapat merekam preferensi konsumen dan melalui perangkat lunak ini data dapat dilacak oleh platform. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa konsumen cukup sering menggunakan perangkat lunak berbasis teknis, seperti memblokir dan menghapus cookies. Hal ini membuktikan bahwa generasi Y memiliki kemampuan bersikap protektif
terhadap privasi mereka. Dengan kata lain, antara keakraban dengan aspek teknis dan kemampuan proteksi berbanding lurus. Berbeda dengan penelitian Park (2013) yang menyatakan bahwa responden jarang menggunakan perangkat lunak berbasis privacy enhancing technologies (PET), responden pada penelitian ini tidak mengarah pada karakteristik umur tertentu.
Kesadaran terhadap praktik institusi merupakan pengetahuan konsumen tentang pelacakan, pengumpulan, dan penggunaan informasi pribadi konsumen secara ilegal (Trepte, dkk., 2015, h. 362). Regresi tahap pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan bahwa kesadaran praktik institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan proteksi privasi. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran konsumen mengenai praktik institusi cenderung dapat meningkatkan kemampuan proteksi privasi. Hasil ini mendukung hipotesis (1b) bahwa konsumen dengan tingkat kesadaran tinggi mengenai praktik institusi memiliki kemampuan bersikap protektif terhadap privasi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Park (2013) yang menyatakan bahwa responden dengan pengetahuan dan kesadaran mengenai praktik institusi, baik di Social Networking Sites (SNS) maupun platform e-commerce, memiliki pengaruh terhadap kemampuan kontrol dalam media digital, walaupun tidak signifikan.
Kesadaran konsumen akan praktik pengumpulan data merupakan indikator pengetahuan faktual yang dibutuhkan dalam privasi daring (Hoofnagle, King, Li, & Turow, 2010, h. 17). Sebagian
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 107-122JurnalILMU KOMUNIKASI
118
besar responden generasi Y cenderung memilih jawaban yang benar dan memiliki pengetahuan serta kesadaran terhadap praktik yang dilakukan e-commerce mulai dari promosi hingga adanya phising. Kesadaran ini mengindikasikan bahwa konsumen generasi Y menyadari informasi pribadi mereka dapat bernilai ekonomis. Mereka pun dapat melakukan penyesuaian dengan memiliki bekal kemampuan bersikap protektif terhadap privasi untuk tidak memberikan informasi pribadi mereka secara lengkap.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi strategi perlindungan privasi tidak hanya pengetahuan mengenai aspek teknis dan praktik institusi, tetapi juga tentang pemahaman terhadap kebijakan privasi yang mencakup aturan, legalitas, dan undang-undang (Trepte, dkk., 2015). Pemahaman terhadap aturan yang berlaku merupakan bentuk sikap pengendalian pengguna terhadap aturan karena ruang daring semakin tidak terbatas dan kompleks. Jika konsumen mengetahui hak dan batasan mereka melalui aturan atau kebijakan, maka mereka pun dapat melindungi informasi pribadi sekaligus dapat bertanggung jawab terhadap optimalisasi pengungkapan informasi pribadi (Turow, Hennessy, & Bleakley, 2008, h. 422).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada regresi tahap pertama, kedua, dan ketiga kesadaran praktik institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan proteksi privasi. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran praktik institusi cenderung dapat meningkatkan kemampuan proteksi privasi. Hasil
ini mendukung hipotesis (1c) bahwa konsumen dengan tingkat pengetahuan tinggi terhadap kebijakan privasi memiliki kemampuan bersikap protektif terhadap privasi. Pengukuran pemahaman konsumen terhadap kebijakan privasi didasarkan pada pertanyaan spesifik tentang kebijakan dan aturan yang berlaku di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Park (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap kebijakan privasi dalam menggunakan media digital memberikan pengaruh terhadap kemampuan kontrol informasi, walaupun hasilnya tidak signifikan.
Kausalitas ketiga elemen literasi privasi daring memainkan peran cukup penting. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dan signifikan dari semua elemen pengetahuan tentang aspek teknis (X1), pengetahuan tentang praktik institusi (dalam penelitian ini berkaitan dengan belanja daring) (X2), dan pengetahuan tentang kebijakan privasi (X3), baik pada regresi tahap pertama, kedua, dan ketiga, terhadap variabel kemampuan pengguna untuk bersikap protektif (Y). Kausalitas ini tidak mudah untuk diartikan dan dijabarkan karena sifat cross-sectional data survei. Penggunaan metode eksperimental atau Focus Group Discussion dapat menutupi kekurangan penelitian ini karena penelitian yang mencakup tingkat pengetahuan akan lebih dapat diambil kesimpulan apabila peneliti dapat terlibat langsung di lapangan menemui responden.Pengalaman Pelanggaran Privasi
Penelitian ini menggunakan pengalaman pelanggaran privasi sebagai variabel moderasi. Hal ini berbeda dengan
Ananda Dwitha Yuniar & Alan Sigit Fibrianto. Literasi Privasi dan ...
119
penelitian Park (2013) yang menggunakan moderasi umur, gender, dan pendidikan sebagai variabel yang memoderasi tingkat literasi privasi daring terhadap kemampuan kontrol. Efek moderasi pengalaman pelanggaran privasi diadopsi dari penelitian Buchi, dkk. (2016) yang menggunakan variabel pengalaman pelanggaran privasi (privacy breach) mampu memoderasi (strong predictor) variabel keahlian menggunakan internet dan secara signifikan memengaruhi kemampuan pengguna bersikap protektif terhadap privasi.
Melalui kuesioner, peneliti memberikan dua pertanyaan mengenai pengalaman pelanggaran privasi ini. Pertama, “Apakah ketika melakukan kegiatan belanja daring privasi Anda pernah dilanggar?” Pertanyaan ini didasarkan pada pengalamanan yang pernah mereka alami (past experience). Sebagian besar responden gen Y urban atau sebesar 55.8 persen mengaku pernah mengalami pelanggaran privasi. Kedua, “Apakah Anda merasa informasi pribadi Anda sedang disalahgunakan oleh e-commerce terkait?” Pertanyaan ini didasarkan pada pengalaman yang sedang terjadi. Sebagian besar responden atau 52.7 persen mengaku privasi mereka sedang dilanggar oleh platform e-commerce. Persentase tersebut memunculkan pemahaman bahwa konsumen gen Y urban di Indonesia telah memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap pelanggaran privasi yang mereka alami.
Hasil penelitian pada regresi kedua menunjukkan bahwa pengalaman pelanggaran privasi konsumen (Z)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan proteksi privasi konsumen (Y). Hasil ini mendukung hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa konsumen yang memiliki pengalaman pelanggaran privasi ketika belanja melalui e-commerce akan semakin kuat bersikap protektif terhadap privasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buchi, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa pengalaman pelanggaran privasi menjadi strong predictor kemampuan proteksi privasi pengguna. Dienlin dan Trepte (2015, h. 286) juga menyatakan bahwa pengalaman pelanggaran dan gangguan privasi, baik yang telah terjadi maupun yang saat ini sedang dialami konsumen, akan meningkatkan kesadaran individu dan memungkinkannya bersikap defence.
Uji pada regresi tahap ketiga menunjukkan bahwa interaksi antara keakraban pada aspek teknis (X1) dan pengalaman pelanggaran privasi konsumen (Z) signifikan terhadap kemampuan proteksi privasi. Hasil ini mendukung hipotesis (2a) yang menyatakan bahwa pengalaman pelanggaran privasi mampu memoderasi keakraban dengan aspek teknis terhadap kemampuan bersikap protektif terhadap privasi.
Pada regresi ketiga diperoleh informasi bahwa interaksi antara kesadaran praktik institusi (X1) dan pengalaman pelanggaran privasi konsumen signifikan terhadap kemampuan proteksi privasi. Pengalaman pelanggaran privasi konsumen dinyatakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran praktik institusi terhadap kemampuan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 107-122JurnalILMU KOMUNIKASI
120
proteksi privasi. Hasil ini mendukung hipotesis (2b) yang menyatakan bahwa pengalaman pelanggaran privasi mampu memoderasi kesadaran terhadap praktik institusi terhadap kemampuan bersikap protektif. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel moderasi (pengalaman pelanggaran privasi konsumen) bersifat semu.
Selanjutnya, pada regresi ketiga diperoleh informasi bahwa interaksi antara pemahaman terhadap kebijakan privasi dan pengalaman pelanggaran privasi konsumen tidak signifikan terhadap kemampuan proteksi privasi. Hasil ini tidak mendukung hipotesis (2c) yang menyatakan bahwa pengalaman pelanggaran privasi mampu memoderasi pengetahuan mengenai kebijakan privasi terhadap kemampuan bersikap protektif. Dengan demikian, hasil negatif dan tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pelanggaran privasi konsumen tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman mengenai kebijakan privasi terhadap kemampuan konsumen gen Y urban untuk bersikap protektif terhadap privasi. Hal ini berarti bahwa variabel moderasi (pengalaman pelanggaran privasi konsumen) bersifat independen (exogenous moderator).
Hasil dari regresi ketiga ini terlihat paradoks sebab seharusnya konsumen yang memahami dan memiliki kebijakan privasi, serta menyadari adanya pelanggaran privasi akan memiliki signifikansi kemampuan bersikap proteksi terhadap privasi. Dienlin dan Trepte (2015, h. 290) menyatakan bahwa pengalaman pelanggaran dan gangguan privasi, baik yang telah terjadi maupun yang saat ini sedang dialami
konsumen, akan meningkatkan kesadaran individu dan memungkinkannya bersikap protektif. Namun, hasil penelitian ini tidak demikian. Hal ini terjadi karena pelanggaran privasi yang dialami konsumen milenial di Indonesia belum memicu tindakan tertentu, sehingga penelitian ini tidak dapat menggali hal tersebut.
Hal di atas dapat terjadi juga karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengenai pelaporan pelanggaran yang dialami oleh konsumen belanja daring. Konsumen urban gen Y yang tidak memiliki kemampuan beraktivitas dengan internet secara memadai di antara terpaan berbagai macam bentuk platform e-commerce dapat menjadi kemungkinan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Trepte, dkk. (2015, h. 362) bahwa sikap tertentu individu dipengaruhi oleh tiga aspek, yakni kemauan, kemampuan, dan pengalaman yang memicu tindakan bahwa privasi mereka harus dilindungi.
SIMPULAN
Privasi merupakan sesuatu yang begitu mudahnya diabaikan, khususnya dalam konteks belanja daring di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya peer group yang memfasilitasi dan mendukung perdebatan mengenai privasi yang wajib untuk dilindungi dan penyalahgunaan informasi privasi tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hukum. Berbagai macam risiko privasi yang dapat mengganggu keamanan informasi pribadi konsumen ketika berbelanja daring
Ananda Dwitha Yuniar & Alan Sigit Fibrianto. Literasi Privasi dan ...
121
melalui e-commerce meliputi risiko penyalahgunaan informasi pribadi, risiko privasi teknologi, risiko privasi platform e-commerce, dan risiko transaksi.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dari total tujuh hipotesis atau dugaan penelitian yang telah disusun, enam hipotesis terjawab melalui regresi hierarki tiga tahap dan menunjukkan bahwa semakin tingginya keakraban pada aspek teknis cenderung dapat meningkatkan kemampuan proteksi privasi. Berikutnya, semakin tingginya kesadaran konsumen mengenai praktik institusi cenderung dapat meningkatkan kemampuan proteksi privasi. Selanjutnya, semakin baiknya kesadaran praktik institusi cenderung dapat meningkatkan kemampuan proteksi privasi. Hasil ini menjelaskan bahwa pemahaman terhadap kebijakan privasi berpengaruh terhadap kemampuan proteksi privasi. Peran dari variabel moderasi pengalaman pelanggaran privasi pada hipotesis kedua (H2) menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan proteksi privasi. Hal ini berarti semakin banyaknya pengalaman pelanggaran privasi konsumen cenderung dapat meningkatkan kemampuan proteksi privasi, meskipun peningkatannya tidak signifikan.
DAFTAR RUJUKAN
Acquisti, A., Brandimarte, L., & Loewenstein, G. (2015). Privacy and human behavior in the age of information [review]. Science, 347(6221), 509–514.
Agustiyanti. (2017, Juni 5). OJK minta fintech lindungi konsumen dan data negara. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170604230717-78-219392/ojk-
minta-fintech-lindungi-konsumen-dan-data-negara>
Büchi, M., Just, N., & Latzer, M. (2016). Caring is not enough: The importance of internet skills for online privacy protection. Information, Communication & Society, 20(8), 1-18.
Carrascal, J. P., Riederer, C., Erramilli, V., Cherubini, M., & Oliveira, R. (2013, May). Your browsing behavior for a big mac: Economics of personal information online. Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web, Rio de Janeiro, Brazil, 189-200.
Cho, H., Sánchez M. R., & Lim, S. S. (2009). A multinational study on online privacy: Global concerns and local responses. Journal of New Media & Society, 11(3), 395–416.
Dienlin, T. & Trepte, S. (2015). Is the privacy paradox a relic of the past? An in-depth analysis of privacy attitudes and privacy behaviors. European Journal of Social Psychology, 45(3), 285–297.
Fortes, N. & Rita, P. (2016). Privacy concerns and online purchasing behaviour: Towards an integrated model. European Research on Management Business Economic, 22(3), 167–176.
Google & Temasek. (2016). E-conomy sea: Unlocking the $200 billion digital opportunity in Southeast Asia. <https://www.thinkwithgoogle.com/_qs /documents /4859/e-conomy_handout_1_20160525_eXq5Gdl. pdf>
Gupta, P., & Dubey, A. (2016). E-commerce study of privacy, trust and security from consumer’s perspective. International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 5(6), 224-232.
Hershatter, A., & Epstein, M. (2010). Millennials and the world of work: An organization and management perspective. Journal of Business and Psychology, 25(2), 211-223.
Hoofnagle, C., King, J., Li, S., & Turow, J. (2010). How different are young adults from older adults when it comes to information privacy attitudes and policies? SSRN Electronic Journal, 1-20.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 107-122JurnalILMU KOMUNIKASI
122
Jumiati, Rosdiana, H., & Kusumastuti, R. (2017). Why a policy is needed to protect privacy information in Indonesia’s e-commerce. Paper presented at IAPA International Conference 2016, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
Kearney, A. T. (2015). Lifting the barriers to e-commerce in ASEAN. ASEAN Research Institute. <https://www.atkearney.co.uk/documents/10192/Lifting+the+Barriers+to+ECommerce+in+ASEAN.pdf/>
Kokolakis, S. (2015). Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon. Computers & Security, 1-29.
Latzer, M., Hollnbuchner, K., Just, N., & Saurwein, F. (2014). The economics of algorithmic selection on the Internet. Working Paper–Media Change & Innovation Division. University of Zurich, Zurich. <http://www.mediachange.ch/media/pdf/publications/economics_of_algorithmic_selection.pdf>
Lissitsa, S., & Kol, O. (2016). Generation X vs. generation Y–A decade of online shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 304-312.
MARS Indonesia. (2016). Studi e-commerce Indonesia 2016. <http://www.marsindonesia.com/products/business-reports/studi-e-commerce-indonesia-2016>
Mastel & APJII. (2016). Infografis konklusi survey ekosistem DNA (device, network & apps). <https://apjii.or.id/content/read/39/282/Hasil-Survey-Ekosistem-DNA-Nasional-APJII-dan-MASTEL>
Metzger, J. M. (2007). Communication privacy management in electronic commerce. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 335-361.
Mooney, C. (2015). Online privacy and business. San Diego, CA: Reference Point Press, Inc.
Nistanto, R. K. (2016, Juli 20). Begini cara Herdian membobol server bukalapak dan tokopedia.
KOMPAS.com. <http://tekno.kompas.com/read/2016/07/20/22030007/begini.cara.herdian.membobol.server.bukalapak.dan.tokopedia>
Park, J. Y. (2013). Digital literacy and privacy behavior online. Communication Research, 40(2), 215-236.
Park, J. Y., Campbell W. S., & Kwak, N. (2012). Affect, cognition and reward: Predictors of privacy protection online. Computers in Human Behavior, 28(3), 1019–1027.
Rose, S., Clark, M., Samouel, P., & Hair, N. (2012). Online customer experience in e-retailing: An empirical model of antecedents and outcomes. Journal of Retailing, 88(2), 308-322.
Saurwein, F., Just, N., & Latzer, M. (2015). Governance of algorithms: Options and limitations. Info, 17(6), 35–49.
Shinta, D. 2009. Cyber law: Perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam e-commerce menurut hukum internasional. Bandung, Indonesia: Widya Padjajaran.
Trepte, S., Teutsch, D., Masur, P. K., Eicher, C., Fischer, M., Hennhöfer, A., & Lind, F. (2015). Do people know about privacy and data protection strategies? Towards the “online privacy literacy scale” (OPLIS). Dalam S. Gutwirth, R. Leenes, & P. de Hert (eds), Reforming european data protection law (Vol. 20, h. 333–365). Dordrecht, Belanda: Springer.
Turow, J., Hennessy, M., & Bleakley, A. (2008). Consumers’ Understanding of Privacy Rules in the Marketplace. Journal of Consumer Affairs, 42(3), 411–424.
Vasileiadis. (2014). Privacy concerns and trust in the adoption of m-commerce. Social Technologies, 4(1), 179–191.
Youn, S. (2009). Determinants of online privacy concern and its influence on privacy protection behaviors among young adolescents. The Journal of Consumer Affairs, 43(3), 389-418.
123
Spasialisasi Sony Music Entertainment Indonesia
Ahmad Khairul NuzuliUniversitas Amikom Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta 55283Email: [email protected]
Abstract: Changes in production process are made in line with the approach of political economy and market. This study aims to find out how the practice of political economy, especially spatialization in Sony Music Entertainment Indonesia. This is a descriptive qualitative research with case study approach. Primary data were obtained through interview, while secondary data were obtained from documentation, literature studies, and the media. The result showed that Sony Music Entertainment Indonesia conducted a spatialization practice supported by digitalization, so that the company became easier to integrate horizontally and vertically and its music products dominate Indonesian market.
Keywords: music, political economy of media, recording industry, spatialization
Abstrak: Perubahan dalam proses produksi dilakukan agar sejalan dengan pendekatan ekonomi politik dan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik ekonomi politik, khususnya spasialisasi di Sony Music Entertainment Indonesia. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi, studi pustaka, dan media. Hasilnya menunjukkan bahwa Sony Music Entertainment Indonesia melakukan praktik spasialisasi yang didukung oleh digitalisasi, sehingga hal tersebut mempermudah integrasi perusahaan secara horizontal dan vertikal agar produk musiknya mendominasi pasar Indonesia.
Kata Kunci: ekonomi politik media, industri rekaman, musik, spasialisasi
Musik merupakan karya budaya yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Musik juga dijadikan media hiburan anak-anak hingga orang dewasa. Musik dalam ilmu komunikasi dikategorikan sebagai media komunikasi massa karena kemampuannya menyampaikan pesan kepada komunikan yang jumlahnya relatif besar. Menurut Yuliarti (2015, h. 191), mengonsumsi lagu bisa dikategorikan sebagai proses komunikasi karena terjadi pengiriman pesan melalui teks dan lirik, serta umpan balik dari pendengarnya, baik berupa sikap maupun perasaan.
Kemajuan teknologi internet juga menjadi penunjang perkembangan industri musik. Kondisi ini membuat format musik bergeser ke ranah digital. Dellyana, Hadiansyah, Hidayat, dan Asmoro (2015, h. 18) mengatakan bahwa era 2000-an, tepatnya tahun 2006, merupakan titik perkembangan musik digital yang memberikan dampak signifikan untuk industri musik di Indonesia. Kehadiran internet mempermudah para penikmat musik mendapatkan musik. Orang dapat mengakses musik dengan genre apapun dan di manapun selama terhubung dengan internet.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 123-138JurnalILMU KOMUNIKASI
124
Penelitian yang dilakukan oleh Dewatara dan Agustin (2019, h. 8-9) menemukan bahwa pemasaran musik di era digital melalui internet mempermudah proses distribusi dan konsumsi. Selain itu, peraturan dan regulasi yang mampu mengurangi pembajakan melalui internet dapat membantu perusahaan rekaman dalam melindungi kekayaan intelektual mereka. Menurut Ayyubi (2016), aplikasi JOOX menguasai 34,7 persen pasar musik digital di Indonesia dan disusul oleh SoundCloud (10,2 persen), LangitMusik (10,1 persen), dan Spotify (9,8 persen).
Data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia/ASIRI (2019) menunjukkan bahwa 80 persen perusahaan rekaman dari 80 anggota ASIRI masih aktif mendistribusikan karya-karya musik rekaman di Indonesia. Di antara perusahaan-perusahaan rekaman tersebut, Sony Music Entertainment Indonesia (SME Indonesia) merupakan salah satu perusahaan rekaman besar di Indonesia dan menjadi bagian dari Sony Music Entertainment Inc. (SME) yang memiliki market share produk global sebesar 21 persen (Stassen, 2019). SME Indonesia merupakan salah satu anak perusahan Sony Corporation of America yang aktif memproduksi karya-karya rekaman di Indonesia. SME Indonesia juga mengorbitkan beberapa penyanyi dan grup musik, seperti Cokelat, Gita Gutawa, Nindy, The Changcuters, Sheila on 7, Duo Maia, Cinta Laura, dan Anggun C. Sasmi.
SME Indonesia sebagai bagian dari industri musik tidak terlepas dari kepentingan ekonomi (economic interest),
terutama kepentingan pemilik modal. Kemudahan dalam era digitalisasi ini juga dimanfaatkan oleh industri musik untuk mentransformasikan rekamannya dari manual ke digital. Bhaskoro (2013) menuliskan bahwa SME Indonesia memperoleh keuntungan terbesarnya melalui layanan unduh lagu via iTunes, yakni sebuah situs unduh lagu legal yang dimiliki oleh Apple.
Proses transformasi tidak terjadi begitu saja. Proses ini melibatkan strategi pemilik modal yang mengikuti tekanan pasar. Hal ini sejalan dengan pendekatan utama ekonomi politik media mengenai perubahan industri media di bawah tekanan pasar dan kepentingan ekonomi politik pemilik modal yang membuat kebijakan (Garnham dalam McQuail, 2011, h. 255). Perubahan itu dilakukan karena berbagai tekanan kepentingan ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sebagai akibat dari kecenderungan monopolistik dan proses integrasi, baik secara vertikal maupun horizontal.
Mosco (2009, h. 159) menyebut spasialisasi sebagai proses perpanjangan institusional sebuah perusahaan media untuk mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. Spasialisasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu spasialisasi vertikal dan spasialisasi horizontal. Spasialisasi vertikal merupakan penguasaan atas proses produksi hingga distribusi agar terintegrasi. Sedangkan spasialisasi horizontal merupakan penguasaan pasar melalui berbagai upaya pembelian dan kerja sama dengan perusahaan lain (Mosco, 1996, h. 5).
Ahmad Khairul Nuzuli. Spasialisasi Sony Music ...
125
Spasialisasi dipilih karena pada era digital perusahaan musik tidak menganggap jarak dan waktu sebagai hambatan untuk mempraktikkan ekonomi politiknya. Hal ini berada dalam konteks kekuasaan dapat memengaruhi proses produksi, distribusi, hingga konsumsi produk industri musik. Digitalisasi jutru membantu indutri musik melakukan praktik spasialisasi untuk mengembangkan usaha dan mencari ke-untungan sebanyak-banyaknya. Spasia lisasi dalam konteks penelitian ini menekankan pada proses digitalisasi yang membantu penyebaran produk SME Indonesia tanpa terhalang jarak dan waktu. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya jaringan yang dibuat oleh SME Indonesia untuk tujuan integrasi perusahaan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Fokus penelitian ini adalah praktik ekonomi politik khususnya spasialisasi yang dilakukan oleh SME Indonesia untuk mengembangkan perusahaan dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Industri musik menjadi institusi kapitalis yang mencetak keuntungan, sedangkan media adalah perangkat ideologis yang melanggengkan kekuasaan kaum kapitalis yang menjadikan masyarakat hanya sebagai konsumen.
Hal ini dipertegas oleh pendapat Adorno dan Horkheimer (2002, h. 95) yang mengatakan bahwa konsumen adalah pihak yang tidak mempunyai kekuatan. Konsumen akan patuh kepada pemilik industri yang memproduksi produk budaya, dalam konteks penelitian ini adalah industri musik. Konsumen yang
pasif akan cenderung hanya menjadi alat kaum kapitalis dalam mencari keuntungan semata.
Adorno & Horkheimer (2002, h. 95) juga mengatakan bahwa terdapat proses standardisasi dan pseudo-individualism dalam industri budaya. Praktik menunjukkan tetap ada kekuatan dan otoritas yang terstandardisasi, walaupun dalam prosesnya seolah-olah terdapat demokratisasi, individualisasi, dan keberagaman. Akibatnya, seolah-oleh kaum kapitalis menawarkan keberagaman kepada konsumen, padahal sebetulnya tawaran-tawaran tersebut hanyalah sebuah hegemoni.
Hegemoni yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penggiringan konsumsi konsumen terhadap produk musik menuju satu titik seragam, yaitu ketika penikmat/konsumen musik digiring untuk menyukai musik-musik tertentu dan hanya cenderung menikmati dan menggemari salah satu genre musik saja. Konsumen yang hanya menerima akan terhegemoni dan menganggap hal tersebut sebagai kondisi yang lumrah dan wajar. Gramsci (dalam Sugiono, 1999, h. 31) mengatakan bahwa hegemoni adalah bentuk dominasi kelompok lain yang ditopang oleh kekuasaan. Masyarakat akan cenderung taat pada produk-produk kesenian karena adanya dominasi dan masyarakat pun cenderung tidak memiliki banyak pilihan. Hegemoni tidak harus dalam bentuk pemaksaan, tetapi dapat berupa upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 123-138JurnalILMU KOMUNIKASI
126
Penelitian ini berparadigma kritis. Paradigma tersebut dipilih karena ekonomi politik tidak pernah lepas dari kontrol kepemilikan media (McQuail, 2011, h. 43). Kekuatan kontrol terhadap konten dan perluasan pasar sangat ditentukan oleh kekuatan kepentingan-kepentingan pemilik kebijakan. McQuail (2011, h. 43) juga mengatakan bahwa ekonomi politik media adalah bagian dari teori kritis media yang menganggap perusahaan media adalah alat bantu kelas dominan dalam melakukan kontrol kepada masyarakat untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, media hanyalah perpanjangan tangan orang-orang yang berkuasa dalam menyebarkan kekuasaannya (Littlejohn & Foss, 2011, h. 432).
Sementara itu, Golding dan Murdock (dalam Curran & Gurevitch, 1991, h. 15-32) menyatakan bahwa perspektif ekonomi politik terletak pada dominasi perusahaan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Sedangkan Mosco (1996, h. 74-75) berpendapat bahwa ekonomi politik selalu membahas persoalan sosial dan keuntungan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi sumber-sumber yang berhubungan dengan komunikasi. Pendekatan ekonomi politik memberi wadah bagi peneliti untuk melakukan studi media sebagai institusi ekonomi yang sudah mapan dalam perluasan kontrol terhadap produksi dan relasi.
METODE
Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kriyantono (2014, h. 6) mengatakan bahwa riset kualitatif
bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sedangkan riset deskriptif mendorong periset mendeskripsikan detail topik yang terjadi melalui sebuah narasi (Kriyantono, 2014, h. 65-66). Topik yang dideskripsikan penelitian ini adalah bentuk dan proses terjadinya spasialisasi SME Indonesia.
Sementara itu, pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena pen dekatan ini mampu menggambarkan situasi di sebuah institusi pada kasus tertentu. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Alex Sancaya (managing director SME Indonesia) dan Sundari Mardjuki (senior marketing and communication SME Indonesia). Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu mempertimbangkan kriteria spesifik untuk dijadikan sumber data. Contoh pertimbangan tersebut adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan paling tahu kebijakan dalam sebuah intitusi atau perusahaan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi informasi yang dibutuhkan untuk penelitian (Sugiyono, 2016, h. 214). Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi, studi pustaka, dan media untuk menjelaskan sebuah peristiwa secara komprehensif.
Sugiyono (2016, h. 241) mengatakan bahwa keabsahan data penelitian kualitatif bisa dilihat dari teknik triangulasinya, yakni pengumpulan data-data melalui berbagai cara berbeda yang bertujuan memperoleh kebenaran dengan standar tinggi. Cara-cara pengumpulan data tersebut dapat berupa
Ahmad Khairul Nuzuli. Spasialisasi Sony Music ...
127
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi secara saksama. Oleh karena itu, kebenaran yang diperoleh dapat saja berasal dari berbagai sudut pandang, sehingga data-data tersebut dapat dibandingkan dan kebenaran dapat dilihat secara utuh.
HASIL
SME Indonesia dipimpin oleh Alex Sancaya sebagai managing director sejak 2013. Di Indonesia, SME Indonesia juga menjadi pemilik dari perusahaan rekaman: Musica Studios, Trinity Optima Music, Suara Sangkar Emas, dan Keci Musik. SME Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan Sony Corporation of America (Sony). Sony merupakan perusahan raksasa yang didirikan oleh Morita pada 7 Mei 1946 dan bergerak di bidang media, hiburan, elektronik, dan jasa keuangan.
Anak-anak perusahaannya tersebar hampir di seluruh dunia. Di sektor produksi film, Sony menguasai sebelas rumah produksi, yaitu Columbia Pictures, TriStar Pictures, Mandalay Entertainment, Phoenix Pictures, Sony Pictures Classics, Sony Pictures Entertainment, Columbia-Tri Star Home Video, Triumph Films, Metro-Goldwyn-Mayer, United Artist, dan Screen Gems. Sedangkan di sektor bisnis industri musik, Sony mempunyai dua anak perusahaan, yaitu Sony/ATV Music Publishing dan Sony BMG Music Entertainment yang juga tersebar di negara-negara lain, tak terkecuali Indonesia. Di sektor telepon seluler (ponsel), Sony mempunyai Sony Mobile. Di sektor elektronik, Sony mempunyai produk
terkenal seperti PlayStasion, televisi, kamera, proyektor, komputer, dan printer.
Selain itu, Sony juga melakukan joint venture dengan Bertelsmann AG. Bertelsmann AG adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang produksi konten televisi dan radio. Bertelsmann AG juga memiliki percetakan buku musik. Pada divisi musik, Bertelsmann AG bekerja sama dengan Sony untuk melakukan distribusi konten musik yang ada di radio dan televisi di berbagai negara (Bertelsmann, 2006, h. 61-62).
Sony tidak hanya bergerak di industri media hiburan, elektronik, dan jasa keuangan. Sony memperluas bidang usahanya dengan spasialisasi horizontal. Hal ini dilakukannya melalui kerja sama dengan perusahan lain yang bergerak di luar industri media, terutama industri musik, misalnya melalui pemasaran produk berplatform digital dalam jaringan (daring), seperti Spotify, YouTube, dan iTunes. Sedangkan secara vertikal, Sony melakukan monopoli antara induk perusahaan dan anak perusahaannya dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi jenis dan genre produk, terutama produk musik pop.
Kondisi di atas mengindikasikan bahwa konten memperoleh kontrol dalam proses produksi (Mosco, 2009, h. 175-176). Hal ini pun terlihat dari aktivitas SME yang ada di Amerika dan Indonesia yang sama-sama memproduksi artis bergenre pop Amerika, seperti One Direction, Adele, dan Shakira. Sedangkan di Indonesia ada Cokelat, Gita Gutawa, Nindy, Sheila on 7, Duo Maia, Cinta Laura, dan Anggun C. Sasmi yang
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 123-138JurnalILMU KOMUNIKASI
128
memiliki genre mayoritas pop. SME yang menguasai perusahaan musik di berbagai negara, termasuk Jepang, Amerika, Korea, dan Indonesia, menyebabkan standardisasi dan homogenisasi produk musik, yaitu pop.
Digitalisasi mengubah pengalaman industri dalam membuat dan memasarkan produk musiknya. Hal ini sejalan dengan pengalaman khalayak dalam menikmati dan mendengarkan musik yang tidak lepas dari media sosial dengan layanan musik streaming (Wikström, 2014, h. 423-443). Littejohn dan Foss (2011, h. 686) mengatakan bahwa digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari ketika segala sesuatu yang manual bertransformasi menjadi serba otomatis dan segala sesuatu yang bersifat rumit bertransformasi menjadi serba ringkas. Tentunya hal ini sejalan dengan Mosco (2009, h. 159) yang menyebut spasialisasi sebagai proses mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mentransformasi perusahaan, baik dalam produksi maupun pemasaran produk, agar lebih efisien.
Digitalisasi dilakukan untuk mengikuti selera pasar yang lebih menyukai musik berformat digital dan dapat dibawa ke mana pun tanpa produk fisik. Pasar pun lebih menyukai proses jual beli secara digital. Hal ini sejalan dengan hasil riset International Federation of the Phonographic Industry (2016, h. 15) yang mengatakan bahwa peningkatan jumlah pengguna ponsel dan internet menyumbangkan dukungan yang cukup besar dalam perkembangan industri musik, termasuk dalam layanan musik streaming yang lebih disukai pasar.
SME Indonesia dituntut mampu bangkit menghadapi tantangan digitalisasi tersebut. Langkah transformasi musik ke arah digital pun diambil sebagai bentuk efisiensi, baik dari segi produksi maupun penjualan. Musik digital merupakan bagian dari format musik dari masa ke masa. Musik digital akhirnya menjadi tren musik saat ini setelah era piringan hitam, kaset, Video Compact Disc (VCD), dan Digital Video Disc (DVD). Format file musik digital yang paling populer adalah MP3, WAV, AAC, dan juga WMA.
Alex Sancaya mengatakan bahwa tantangan utama dalam perkembangan musik di era globalisasi adalah digitalisasi. Digitalisasi membuat perubahan dalam proses produksi rekaman musik.
Proses produksi rekaman musik digital tentu lebih mudah dibanding analog. Mulai dari studio yang lebih sederhana, bahkan bisa dilakukan di kamar pribadi musisi itu, hingga proses penyuntingan, perekaman musik digital memang tidak serumit pada perekaman analog. (Alex Sancaya, managing director SME Indonesia, wawancara, 15 Februari 2015)
Selain itu, dalam penjualannya, SME Indonesia juga telah bekerja sama dengan platform penjualan digital yang memanfaatkan internet, seperti YouTube, iTunes, Google Music, Spotify, JOOX, dan Deezer. Pemilihan platform ini juga dianggap dapat mengurangi pembajakan yang menjadi keluhan banyak musisi. Proses digitalisasi pun dapat menyelamatkan berbagai file musik lama karya para musisi.
Sementara itu, Sundari Mardjuki mengatakan bahwa di era digital dan globalisasi, hadirnya media sosial mempermudah industri musik dalam
Ahmad Khairul Nuzuli. Spasialisasi Sony Music ...
129
mempromosikan dan menjual produknya, “Globalisasi menjadi wadah bagi era keterbukaan, sehingga hal ini bisa menjadi peluang bagi industri untuk mempromosikan produknya melalui media sosial” (Sundari Mardjuki, senior marketing and communication SME Indonesia, wawancara, 26 Januari 2016).
Proses digitalisasi dalam produksi dan penjualan ini tidak terlepas dari prinsip ekonomi politik yang berorientasi pada pasar. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghapus jarak dan waktu dalam proses produksi dan penjualan antara penjual dan pembeli, serta mencari keuntungan sebanyak-banyaknya (Mosco, 2009, h. 159). Selain itu, digitalisasi juga sejalan dengan prinsip ekonomi. Menurut Dewatara dan Agustin (2019, h. 8), proses digitalisasi musik membuat para pencipta lagu dapat memproduksi musik dengan murah dan para pendengar pun dapat membeli produk musik dengan harga yang murah juga.
Sementara itu, efisiensi di bidang pencegahan pembajakan juga menjadi pertimbangan SME Indonesia, sehingga kegiatan menggunggah musik gratis tanpa seizin perusahaan rekaman dan artis bisa dikurangi.
Munculnya musik streaming membuat label dan artis tidak begitu khawatir masalah pembajakan. Perusahaan musik bisa terus berinovasi, walaupun produk musik berupa fisik berkurang. Musik streaming juga membuat pelanggan tetap dan pendapatan iklannya bisa membuat industri musik tetap berjalan. (Alex Sancaya, managing director SME Indonesia, wawancara, 15 Februari 2015)
Bachdar (2016) mengatakan bahwa pembajakan musik di era digital tidak
pernah surut karena ring back tone (RBT) bisa menjadi penyelamat dengan mem-berikan pemasukan 194 miliar rupiah bagi perusahaan rekaman. Benny Ho dalam Bachdar (2016) mengatakan bahwa munculnya musik streaming menjadi harapan baru dalam pemberantasan pem bajakan dan meningkatkan market size industri musik di Indonesia. Platform penjualan digital yang tersedia secara efisien membuat pembajakan dapat ditanggulangi, sehingga perusahaan rekaman dan musisi pun tidak begitu khawatir akan haknya (Alex Sancaya, managing director SME Indonesia, wawancara, 15 Februari 2015).
PEMBAHASAN
Bentuk spasialisasi horizontal terlihat pada perluasan perusahaan Sony dalam mengakuisisi perusahaan lain. Bahkan pada tahun 2018, SME mengakuisisi EMI Music Publishing yang memiliki artis-artis ternama, seperti Drake, Sam Smith, dan Queen (Sebayang, 2018). Hal ini dilakukan untuk mengurangi saingan pasar SME dan tetap mendominasi pasar industri musik secara internasional. Sedangkan pada spasialisasi vertikal, SME fokus melakukan produksi dan penjualan secara digital.Spasialisasi Vertikal SME Indonesia
Pandangan Marxisme melihat bahwa ideologi-ideologi budaya, seperti seni, merupakan hasil sampingan yang ditentukan oleh basis ekonomi. Marxisme, sebagai bentuk aliran kritis, selalu mempunyai ketertarikan terhadap produk seni. Aliran ini percaya bahwa masyarakat kapitalis sangat mahir menyebarkan
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 123-138JurnalILMU KOMUNIKASI
130
ideologi melalui produk budaya, terutama seni. Musik sebagai salah satu produk budaya yang berupa kesenangan menjadi penting untuk dikritisi karena rentan disetir dan dimanipulasi oleh kapitalis sebagai pemilik perusahaan dan pemegang modal (Woodfin & Zarate, 2008, h. 131).
Perkembangan internet dan berbagai vendor jual musik daring mengubah kondisi. Batasan jarak, ruang, dan waktu sudah tidak menjadi halangan dalam distribusi produk musik dari perusahaan rekaman kepada pendengar selaku konsumen. Globalisasi menghapus hambatan ruang dan waktu. Kondisi tersebut membantu kegiatan spasialisasi (Mosco, 2009, h. 157). Hal inilah yang diaplikasikan oleh SME Indonesia dalam mendistribusikan musiknya ke masyarakat dan sekaligus menjadi cara SME Indonesia mengendalikan distribusi musiknya, yaitu melalui kerja sama dengan vendor jual musik daring untuk mempermudah penjualan produk.
Mosco (2009, h. 24) menyatakan bahwa ekonomi politik adalah kajian tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan, yang bersama-sama dalam interaksinya menentukan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber-sumber yang ada. Globalisasi menjadikan dunia tanpa batas dan membuat penyeragaman di pasar secara global dalam sistem, pola, dan budaya, serta berubah ke arah digital. Digitalisasi dan globalisasi mengubah proses produksi, distribusi, dan konsumsi industri musik.
Konten lagu yang dominan diproduksi oleh SME Indonesia bergenre pop. Hal
ini dilakukan untuk mempertahankan dan mendominasi pasar. Lagu pop merupakan genre yang menjadi standar dan memberi pengaruh pada komoditas lain, contohnya SME Indonesia dan SME sama-sama dominan memproduksi lagu yang bergenre pop. Hal ini tentunya akan menjadi komoditas pasar yang menyebar melalui globalisasi dan menjadi gaya hidup. Musik pop akan menjadi mesin pengeruk uang bagi SME Indonesia.
Perspektif Marxis melihat musik sebagai bagian dari alat ideologi yang berhubungan dengan seni. Musik juga menjadi alat penghibur dan komoditas bisnis yang laku di pasaran. Hal ini menjadi sasaran empuk para pemilik modal untuk mencari keuntungan. Khadavi (2014, h. 53) menyatakan bahwa industri musik membuat standardisasi dan homogenisasi, terutama industri musik pop yang berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian, proses penciptaan lagu, upaya produksi, pemasaran, pendistribusian, orientasi konsumsi, karakter lagu, dan sifat kebutuhan masyarakat telah diarahkan oleh pemilik modal yang berorientasi pada pasar. Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan kapitalis dalam menguasai industri musik sebagai budaya dan ideologi.
Spasialisasi merupakan sebuah sistem konsentrasi yang memusat dan berkaitan dengan cara subsistem-subsistem disentralkan, sehingga hal-hal yang muncul di media merupakan wujud dominasi para pemilik media. Sistem konsentrasi tersebut mempunyai pengaruh pada konten media. Di Indonesia, SME Indonesia
Ahmad Khairul Nuzuli. Spasialisasi Sony Music ...
131
menjadi pemilik perusahaan rekaman Musica Studios, Trinity Optima Music, Suara Sangkar Emas, dan Keci Musik. Menurut Devereux (2013, h. 63), salah satu bentuk kekuatan politik dari individu adalah ketika individu tersebut menguasai industri media. Konsentrasi dominan berimbas pada tidak adanya independensi konten genre lagu yang menyebabkan standardisasi dan homogenisasi. Hal ini kemudian menjadi fenomena yang lazim karena berorientasi pasar dan berstruktur liberal yang menghalangi keberagaman konten (diversity of content). Musik pop menjadi genre yang dominan dan oposisi dari genre lain yang menjadi minoritas.
Adorno (dalam Stone, 2016, h. 79-80) mengatakan bahwa musik pop adalah salah salah satu genre yang telah mengalami standardisasi, yaitu lirik dan musiknya mempunyai satu kesamaan dengan yang lain. Selain itu, Adorno (dalam Stone, 2016, h. 80) menyebut hal itu sebagai pseudo-individualism, yakni pelanggengan kekuasaan kapitalis dengan membuat khalayak tidak menyadari bahwa hal-hal yang mereka dengarkan telah diperdengarkan dan disederhanakan sebelumnya.
Pramudyanto (2013, h. 80) mengatakan bahwa dominasi lagu pop merupakan bentuk pseudo-individualism yang memiliki kekuatan untuk menjaga khalayak tetap menjadi pendengar yang pasif. Khalayak telah mengikuti logika industri karena musik pop merupakan hasil standar industri yang memengaruhi kualitas musik. Kekuasaan yang mapan akan
memengaruhi proses penciptaan musik dan pendengar musik.
Proses menjadikan musik pop sebagai genre dominan tidak terlepas dari hegemoni kelompok berkuasa. Masyarakat patuh pada kehendak penguasa dan secara tidak sadar telah berpartisipasi dalam rangka kepatuhan tersebut. Hegemoni merupakan istilah yang menggambarkan proses kekuasaan menundukkan masyarakat untuk mengikuti standar yang dibuatnya. Hal ini menciptakan ketidakberdayaan khalayak untuk kritis terhadap konten genre musik akibat adanya hegemoni kepentingan ekonomi industri musik. Sayangnya, belum ada hukum di Indonesia yang mengatur tentang konsentrasi kepemilikan di industri musik. Hal ini sejalan dengan pendapat Muis (2001, h. 65) yang mengatakan bahwa aturan hukum mengenai aturan main selalu mempunyai hubungan erat dengan masalah politik (kontrol dan kekuasaan) serta budaya (simbolisasi, komodifikasi, spasialisasi, dan strukturisasi) perekonomian nasional. Kontrol terhadap konten bertujuan untuk melanggengkan selera pasar yang sesuai dengan tujuan pemilik perusahaan.
Prasetiyo (2013, h. 80) mengatakan bahwa musik pop adalah genre yang paling banyak digandrungi dan didengar oleh kalangan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa musik pop adalah preferensi teratas yang didengarkan kalangan remaja. Ayyubi (2016) menambahkan bahwa pada tahun 2017, genre pop diprediksi menjadi genre yang paling banyak didengar, yaitu sekitar 81,4 persen, dan disusul oleh R&B sekitar 34,9 persen, serta Jazz 34,1 persen.
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 123-138JurnalILMU KOMUNIKASI
132
Theodore Adorno, salah satu pemikir Sekolah Frankfurt, ahli teori musik, musisi, dan komposer, berpandangan bahwa musik sebagai bagian dari industri budaya mengalami proses standardisasi dan pseudo-individualism (Adorno & Horkheimer, 2002, h. 95). Standardisasi selalu berhubungan dengan keseragaman genre musik. Sedangkan pseudo-individualism berhubungan dengan upaya menjaga penikmat musik dengan membuat pendengarnya tidak kritis melalui suguhan konten-konten yang menghibur.
Sumahar (2014, h. viii) mengatakan bahwa di Indonesia ada upaya perusahaan rekaman arus utama menyeragamkan tema dan jenis musik sebagai bentuk dominasi dan hegemoni terhadap pendengar musik. Kondisi tersebut dikendalikan oleh para pemilik modal yang melakukan eksploitasi pada genre musik pop dan menawarkannya pada masyarakat sebagai standar budaya dan selera dominan. Konten yang diproduksi oleh musik pop selalu bertemakan cinta atau diistilahkan “cinta melulu”. Istilah “cinta melulu” berasal dari lagu buatan band Efek Rumah Kaca sebagai bentuk sindiran dan perlawanan terhadap konten lagu hasil dominasi dan hegemoni perusahaan rekaman arus utama.
Leavis (dalam Barker, 2000, h. 47) mengatakan bahwa budaya musik pop adalah hasil budaya berbasis komoditas dengan tujuan utama dibeli dan mudah dikonsumsi, namun gagal memperkaya pengetahuan konsumen. Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa pemilihan musik pop sebagai genre dominan dalam
lagu-lagu yang diproduksi oleh SME Indonesia bertujuan untuk mempertahankan konsumen sebagai komoditas. Musik pop yang umumnya memuat konten percintaan mematikan sikap kritis dan selera pendengar. Musik tidak lagi dianggap sebagai karya intelektual, melainkan hanya sebuah produk industri yang berperan sebagai hiburan semata.
Hal yang perlu dikritisi dari praktik kontrol terhadap konten produksi musik adalah munculnya standardisasi. Hal ini jelas merupakan praktik tidak sehat yang membuat konsumen harus tunduk pada jenis konten yang diberikan oleh perusahaan besar, semacam SME Indonesia. Sentralisasi genre musik merupakan bentuk monopoli pemilik perusahaan terhadap selera musik masyarakat. Hal ini tentunya berdampak terhadap terbatasnya pilihan genre musik yang diterima masyarakat. Ketidakseimbangan antara genre musik pop dan musik lain merupakan salah satu dampak dari konten produksi musik yang diatur oleh kekuatan dominasi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari agenda dan kepentingan pemilik SME Indonesia yang menganggap musik pop adalah genre yang paling banyak penggemarnya dan menguntungkan secara ekonomi.
Konsumen dan para penyanyi merupakan salah satu aspek yang tidak lepas dari bagian produksi. Pemilihan aliran musik yang diproduksi pun dipengaruhi oleh permintaan konsumen yang tidak independen. Hal ini terlihat dari keberadaan musik pop yang menjadi genre utama dari produksi musik SME Indonesia. Kondisi
Ahmad Khairul Nuzuli. Spasialisasi Sony Music ...
133
tersebut menunjukkan adanya standarisasi atau penyeragaman yang membuat konsumen tunduk terhadap produk yang dihasilkan. Adorno dan Horkheimer (2002, h. 95) berpendapat bahwa konsumen adalah pihak yang lemah dan tidak berdaya. Kekuasaan dalam industri musik membuat konsumen menyesuaikan diri dan sepakat pada kepatuhan yang dibuat oleh otoritas.
Konsumen dan genre musik terus dieksploitasi demi menjaga dominasi. Publik yang pasif pun menjadi tergantung dan tunduk pada musik pop yang sudah dimonopoli oleh SME Indonesia. Mental atau cara berpikir publik seolah-olah dianggap mendukung sistem kapitalis dalam industri budaya dan konsumen dianggap sebagai bagian dari sistem yang tidak terpisahkan (Adorno & Horkheimer, 2002, h. 95-96). Hal ini memperluas anggapan bahwa ideologi industri budaya sangat manipulatif dalam mendominasi pasar. Mereka seolah-olah menyediakan hiburan dengan menyenangkan hati masyarakat dan menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap konten atau produk mereka. Hal ini semata-mata dilakukan demi kesenangan pada ideologi bisnis kapitalis yang mereka jalankan melalui pengambilalihan kesadaran dan perhatian masyarakat (Adorno & Horkheimer, 2002, h. 144).
Standardisasi menghapus autentisitas dan orisinalitas, sehingga meniadakan tantangan dalam proses produksi musik. Standardisasi inilah yang memengaruhi bagian lirik dan chorus yang merupakan inti lagu, sehingga hal tersebut
membuat adanya individualitas semu yang seolah-olah menawarkan variasi, walaupun sebenarnya tidak demikian. Hal ini membuat pelaku industri musik menjadikannya sebagai alat untuk memperluas dominasi, walaupun awalnya standardisasi musik adalah bentuk strategi kompetitif yang terbilang sukses. Mereka melakukan kontrol dan mendisiplinkan tiap-tiap elemen dalam proses produksi dan distribusi, lalu melanggengkan hegemoni dan mengekalkan dominasi kapitalis mereka.
Hegomoni adalah sebuah kontrol sosial yang dilakukan oleh pihak dominan melalui penggunaan media dan selalu erat kaitannnya dengan proses ekonomi politik media (Gramsci dalam Strinati, 2004, h. 148). Proses ekonomi politiknya bisa berupa upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual (Sugiono, 1999, h. 31). Hal ini menyebabkan individu sebagai konsumen secara suka rela menerima dan menyerap pandangan dominan dan melakukan asimilasi terhadap pandangan terebut. Gramsci (dalam Strinati, 2004, h. 148) juga menjelaskan bahwa musik sebagai produk budaya adalah salah satu tempat hegemoni diproduksi, direproduksi, dan diubah.
Selain proses produksi, proses memperkenalkan artis ke masyarakat juga dipengaruhi oleh era digitalisasi dan globalisasi. Era digitalisasi memengaruhi rantai produksi dan distribusi produk. Penguasa industri pun harus mengambil keputusan untuk masuk ke ranah digital. Pemanfaatan internet pun menjadi sarana yang mempermudah penjualan produk
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 123-138JurnalILMU KOMUNIKASI
134
industri musik karena pola konsumsi masyarakat juga berubah. Masyarakat menjadi lebih suka melakukan transaksi dengan aplikasi digital dan internet. Globalisasi dan digitalisasi tenyata tidak bebas kepentingan ekonomi dan politik. Globalisasi juga tidak membuat kita bebas memilih karena adanya kekuasaan yang membuat standardisasi.Spasialisasi Horizontal SME Indonesia
Spasialisasi horizontal berhubungan dengan aktivitas SME Indonesia bekerja sama dengan perusahaan lain dalam memasarkan produknya. Chaffey dan Smith (2008, h. 339) mengatakan bahwa pemasaran digital merupakan aktivitas pemasaran dengan menggunakan internet (media digital) untuk memberikan pelayanan bagi pelanggan dalam kegiatan jual beli.
SME Indonesia memilih media sosial untuk memasarkan produk dan memperkenalkan artisnya. Media sosial yang dipakai SME Indonesia adalah YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. YouTube tidak hanya menjadi media promosi, tetapi juga media pemasaran karena apabila video tertentu memiliki banyak viewer, maka para pengiklan akan tertarik mengiklankan produknya melalui layanan YouTube AdSense.
Pemasaran musik digital juga bisa bekerja sama dengan vendor jual musik daring, seperti iTunes, Google Music, Spotify, JOOX, dan Deezer, dengan biaya yang minim dan murah, yakni 10 dolar selama satu tahun. Vendor-vendor tersebut akan mengelola hingga royalti lagunya.
Bhaskoro (2013) mengatakan bahwa SME memperoleh keuntungan besar melalui layanan unduh lagu via iTunes, yaitu sebuah situs unduh lagu legal yang dimiliki oleh Apple. Hal ini membuktikan bahwa SME memilih pasar daring untuk memudahkan dan mengefektifkan penjualan produknya.
Sementara itu, SME Indonesia mencoba menghilangkan batas ruang antara produk yang ditawarkannya dengan konsumen ketika teknologi pemasaran secara digital dapat melakukan proses transaksi tanpa terhalang ruang dan waktu. Pendistribusiannya dapat menggunakan internet dengan bantuan vendor jual musik daring, seperti iTunes, Google Music, Spotify, JOOX, dan Deezer, tanpa terkendala perbedaan letak geografis. Kontrak dengan Spotify membuat SME Indonesia memiliki lima puluh juta pelanggan berbayar di dunia dan memengaruhi market presence SME Indonesia. Kanal SME Indonesia sudah memiliki 972 ribu pelanggan di YouTube dan video-videonya telah ditonton oleh lebih dari sembilan ratus juta penonton.
SME Indonesia melalui full digital right dapat leluasa menyebarkan produk musiknya dengan aplikasi jual musik gratis. Jaringan distribusi digital menambah efektivitas karena sarana tersebut dapat memasarkan produk dengan cepat dan luas. Ketiadaan Compact Disc (CD) dapat meminimalkan risiko barang rusak dan data penjualan dapat terhitung secara digital dan otomatis. Musik pun dapat diakses dan diunduh selama terhubung dengan internet.
SME Indonesia yang telah mentransformasikan produk musiknya ke
Ahmad Khairul Nuzuli. Spasialisasi Sony Music ...
135
ranah digital tetap memproduksi VCD. Alex Sancaya mengatakan bahwa produksi VCD merupakan bentuk penghargaan pada para musisi untuk dapat tetap mempunyai bentuk fisik dari karya-karya mereka. SME Indonesia dalam penjualan VCD bekerja sama dengan Kentucky Fried Chicken (KFC) Indonesia, salah satu perusahaan restoran. Sementara itu, Sundari Mardjuki mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan serangkaian strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan SME Indonesia karena melalui kemitraan tersebut produk VCD SME Indonesia dapat diperoleh melalui gerai-gerai KFC di seluruh Indonesia. SME Indonesia juga menghadirkan penyanyi-penyanyinya ke gerai-gerai KFC untuk menyapa penggemarnya di berbagai kota.
SME Indonesia dalam memasarkan VCD-nya juga bekerja sama dengan lapak jual beli daring, seperti lazada.co.id, anak perusahaan Jerman Rocket Internet. Lazada.co.id dipilih sebagai mitra karena memiliki jangkauan pemasaran sampai ke seluruh Indonesia dan fasilitas multiple payment, termasuk cash-on-delivery (COD), yang memberi kemudahan pada konsumen SME Indonesia mendapatkan produk VCD yang diinginkan. Selain itu, promo yang dilakukan lazada.co.id tentunya akan mampu menarik konsumen untuk membeli produk tersebut.
SME Indonesia juga menjadi pemilik dari produsen musik Musica Studios, Trinity Optima Music, Suara Sangkar Emas, dan Keci Musik. SME Indonesia mendominasi produksi musik di Indonesia
untuk meminimalkan persaingan. Persaingan penjualan mengakibatkan munculnya kontrol konten. Penjualan pun harus dipilih dengan risiko yang minimal.
Spasialisasi menghapus ruang dan waktu melalui penggunaan kekuasaan. Pola pikir untuk mengefektifkan segala lini penjualan menjadi poin utama terbentuknya spasialisasi. Efektivitas selalu menitikberatkan pada cara memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminim-minimnya. Regulasi yang belum ada pun menjadi celah bagi SME Indonesia untuk mempraktikkan ekonomi politiknya. SME Indonesia tumbuh dan langgeng menjadi perusahaan rekaman besar di Indonesia.
SIMPULAN
Integrasi vertikal dan horizontal industri musik merupakan bagian dari proses spasialisasi. SME Indonesia mengalami perkembangan dan keuntungan pesat berkat dukungan globalisasi dan digitalisasi. Selain itu, SME Indonesia menerapkan spasialisasi dengan melakukan perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi, baik vertikal maupun horizontal. Proses spasialisasi yang bersifat vertikal dilakukan dengan membuat konten mayoritas lagu bergenre pop dan melakukan digitalisasi pada produknya untuk memperoleh kontrol dalam produksi musik. Sedangkan pada spasialisasi horizontal, SME Indonesia bekerja sama dengan para vendor, seperti iTunes, Google Music, Spotify, JOOX, dan Deezer, untuk menjual produk musik digitalnya. Selain
VOLUME 17, NOMOR 1, Juni 2020: 123-138JurnalILMU KOMUNIKASI
136
itu, lazada.co.id dan KFC dipilih menjadi mitra untuk memasarkan produk VCD-nya. Media sosial pun dipakai untuk mengenalkan para artisnya.
Konsentrasi media mempunyai pengaruh pada konten. SME Indonesia menjadi pemilik perusahaan musik Musica Studios, Trinity Optima Music, Suara Sangkar Emas, dan Keci Musik. Hal ini berimbas pada ketiadaan independensi konten dan genre lagu. Standardisasi dan homogenisasi pun terjadi dan berimbas menjadi fenomena yang lazim karena berorientasi pasar dan berstruktur liberal. Praktik ini tidak sehat karena menghalangi keberagaman konten.
Di Indonesia, kondisi ini didukung oleh ketiadaan regulasi yang mengatur tentang konsentrasi kepemilikan di industri musik. Pemerintah seharusnya berperan aktif menjadi regulatory body, meskipun ada pertentangan mengenai fungsi pengaturan pemerintah yang sering dikaitkan dengan intervensi pemerintah pada industri media. Poin pentingnya adalah pemerintah harus dapat berperan aktif sebagai pengatur kepentingan publik.
DAFTAR RUJUKAN
Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002) Modernitas dialectic of enlightenment. California, CA: Stanford University Press.
Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. (2019). About ASIRI. asiri.co.id. <http://asiri.co.id/about/>
Ayyubi, S. A. (2016, November 30). Industri musik digital diprediksi jadi tren 2017. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161130/105/607764/industri-musik-digital-diprediksi-jadi-tren-2017>
Bachdar, S. (2016, December 1). Mampukah streaming musik menghapus pembajakan?. Marketeers.com. <https://marketeers.com/mampukah-streaming-musik-menghapus-pembajakan/>
Barker, C. (2000). Cultural Studies: Teori dan praktik. Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
Bhaskoro, A. T. (2013, Juni 7). Sony Musik Indonesia: Raih pendapatan dari iTunes sudah melampaui pendapatan dari ringback tone. Dailysocial.id. <https://dailysocial.id/post/sony-music-indonesia-raih-pendapatan-melalui-itunes>
Bertelsmann. (2006) Bertelsmann annual report 2005. <https://www.bertelsmann.com/media/investor-relations/annual-reports/annual-report-2005.pdf>
Chaffey, D., & Smith, P. R. (2008). Emarketing excellence: Planning and optimizing your digital marketing (3rd ed). Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
Curran, J., & Gurevitch, M. (eds). (1991). Mass media and society. London, UK: Edward Arnold.
Devereux, E. (2013). Understanding the media. London, UK: Sage Publications.
Dellyana, D., Hadiansyah, F., Hidayat, A., & Asmoro, W. (2015). Ekonomi kreatif: Rencana pengembangan industri musik nasional 2015-2019. Jakarta, Indonesia: PT. Republik Solusi.
Dewatara, G. W., & Agustin, S. M. (2019). Pemasaran musik pada era digital: Digitalisasi industri musik dalam industri 4.0 di Indonesia. WACANA, 18(1), 1-10.
International Federation of the Phonographic Industry. (2016). Global music report 2016: State of the industry. IFPI. <https://www.ifpi.org/downloads/GMR2016.pdf>
Khadavi, M. J. (2014). Dekonstruksi musik pop Indonesia dalam perspektif industri budaya. Jurnal Humanity, 9(2), 47-56.
Kriyantono, R. (2014). Teknik praktis riset komunikasi. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.
Ahmad Khairul Nuzuli. Spasialisasi Sony Music ...
137
Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). Teori komunikasi. Jakarta, Indonesia: Salemba Humanika.
McQuail, D. (2011). Teori komunikasi massa McQuail (edisi 6). Jakarta, Indonesia: Salemba Humanika.
Mosco, V. (1996). The political economy of communication: Rethinking and renewal. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc.
--------- (2009). The Political economy of communication (2th ed). London, UK: Sage Publications Ltd.
Muis, A. A. (2001). Indonesia di era dunia maya: Teknologi informasi dalam dunia tanpa batas. Bandung, Indonesia: PT. Remaja Rosdakarya.
Pramudyanto, A. B. (2013). Media baru dan peluang counter-hegemony atas dominasi logika industri musik (studi kasus perkembangan netlabel di Indonesia). Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(1), 63-82.
Prasetiyo, A. (2013). Preferensi musik di kalangan remaja. Promusika, 1(1), 75-92.
Sebayang, R. (2018, Mei 22). Sony gelontorkan dana Rp 32,2 t untuk kuasai EMI Music. cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180522110454-4-15977/sony-gelontorkan-dana-rp-322-t-untuk-kuasai-emi-music/2>
Stassen, M. (2019, Maret 13). The global record industry generated $18.8bn last year – With 31% going to Universal Music Group. Music Business Worldwide. <https://www.
musicbusinessworldwide.com/the-global-record-industry-generated-18-8bn-last-year-with-31-going-to-universal-music-group/>
Stone, A. (2016). The value of popular music: An approach from post-kantian aesthetics. Cham, Swiss: Palgrave Macmillan.
Strinati, D. (2004). An introduction to theories of popular culture (2nd ed). London, UK: Routledge.
Sugiono, M. (1999). Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d. Bandung, Indonesia: PT Alfabeta.
Sumahar, M. P. (2014). Analisis wacana dominasi major label pada industri musik Indonesia di dalam lirik lagu “cinta melulu” dan “pasar bisa diciptakan, cipta bisa dipasarkan (biru)” dari band efek rumah kaca. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
Yuliarti, M. S. (2015). Komunikasi musik: Pesan nilai-nilai cinta dalam lagu Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi, 12(2), 189-198.
Woodfin, R., & Zarate, O. (2008). Marxisme untuk pemula. Yogyakarta, Indonesia: Resist Book.
Wikström, P. (2014). The music industry in an age of digital distribution. Dalam Jonathan Fox (ed), Change: 19 key essays on how the internet is changing our lives (h. 423-443). Madrid, Spanyol: BBVA-Turner.