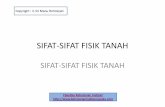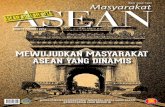Perancangan interior pusat pemberdayaan & konservasi wayang di ...
penerapan teknik konservasi tanah dan air oleh masyarakat di ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of penerapan teknik konservasi tanah dan air oleh masyarakat di ...
PENERAPAN TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN
AIR OLEH MASYARAKAT DI DESA BONTO
SOMBA HULU DAS MAROS
Oleh :
RAHMADANI
M111 14 025
PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
ii
ABSTRAK
Rahmadani (M 111 14 025). Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air
Oleh Masyarakat di Desa Bonto Somba Hulu DAS Maros. di bawah
bimbingan Usman Arsyad dan Daud Malamassam
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan teknik konservasi tanah
dan air oleh masyarakat di Desa Bonto Somba serta hubungannya dengan tipologi
masyarakat yang mempengaruhi tindakan konservasi tanah dan air. Penelitian ini
dilakukan pada bulan Januari sampai dengan hingga bulan Maret 2018 di Desa
Bonto Somba Hulu DAS Maros. Pengambilan data dilakukan dengan observasi
langsung di lapangan dan wawancara kepada petani dengan menggunakan daftar
pertanyaan (kuisioner) berdasarkan teknik purposive sampling. Data yang
dikumpulkan dari tipologi masyarakat berupa umur, tingkat pendidikan,
pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan luas lahan garapan. Data tersebut
diolah dengan teknik kontingensi kemudian diklasifikasikan dan diuji chi square.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan yang dilakukan
masyarakat di Desa Bonto Somba adalah metode vegetatif berupa tanaman
penutup tanah, kebun campuran dan pekarangan sedangkan metode mekanik
berupa pengolahan tanah dan teras bangku. Hubungan tipologi sosial ekonomi
masyarakat dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air tidak memiliki
hubungan yang nyata dikarenakan masyarakat menggunakan teknik konservasi
tanah dan air secara turun-temurun.
Kata kunci : Teknik Konservasi Tanah dan Air, Tipologi Masyarakat, Desa Bonto
Somba
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillaahirabbil „aalamiin.
Puji dan syukur kepada Allah SWT atas anugerah, rahmat, karunia dan
izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dan
penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan
Air Oleh Masyarakat di Desa Bonto Somba Hulu DAS Maros”.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis
mendapat berbagai kendala. Tanpa bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak,
penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Untuk itu, dengan penuh
kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.Ir. H. Usman
Arsyad dan Prof. Dr.Ir. Daud Malamassam M.Agr selaku pembimbing yang
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan mengarahkan
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa
memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau.
Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih dan
penghargaan kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si, Ibu Ira Taskirawati, S.Hut.,
M.Si., Ph. D dan Wahyuni, S.Hut,. M.Hut selaku penguji yang telah
membantu dalam memberikan saran, guna perbaikan skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Kehutanan Bapak Dr. Ir. Syamsuddin Millang, M.S dan
sekretaris Jurusan Bapak Dr. Ir. Baharuddin, M.P, serta Bapak/Ibu Dosen
dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
3. Partner penelitian Andi Rismayanti Kakanda-kakandaku yang membantu
selama penelitian Muh Syafiq, Zulqadri, Dian Dirga Priatna, Ilham Hairul
dan Gufriadi, serta teman-teman seperjuangan DAS 22 di Laboratorium
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang senantiasa mendukung.
4. Dg Rowa sekeluarga selaku Ketua RT Dusun Cindakko, Desa Bonto Somba,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Terima kasih atas jamuannya
selama penelitian.
5. Sahabatku yang senantiasa membantu Afni Arfiah Ramli, Siti Melinda
Pristiyanti Puteri, Nurhikmah Usbar, Sitti Hardianti Suaib, Made Sawitri
iv
Dewayani, Putri Khairunnisa, Mutmainna Dwi Lestari, Nur Indah
Jasmin, Nurfadhilah Mansyur, dan Sri Wahuni Muzhar serta teman-teman
seperjuangan AKAR 2014, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang
telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Kakanda Andi Irwan Amrullah yang selalu bisa jadi tempat berbagi
cerita, berkeluh kesah serta banyak memberikan semangat dan dukungan
selama penyelesaian skripsi.
7. Teman – teman KKN Reguler UNHAS Gelombang 96 di Kelurahan Galung
Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Nur Wahyuni Utami dan
Andi Magfira Akhmad.
8. Semua pihak yang telah turut membantu dan bekerjasama setulusnya dalam
pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.
Akhirnya kebahagiaan ini kupersembahkan kepada Ayahanda H.M. Dahlan
B, S.E dan Ibunda Hj. Nurwana serta Saudara-saudaraku Dzuljalali,
Nurhikmah, Hardiyanti Dahlan dan Mutmainna Dahlan terima kasih telah
mencurahkan doa, kasih sayang, cinta, perhatian pengorbanan, motivasi yang
sangat kuat yang tak akan putus dan tak terhingga di dalam kehidupan penulis
selama ini.
Kekurangan dan keterbatasan pada dasarnya ada pada segala sesuatu yang
tercipta di alam ini, tidak terkecuali skripsi ini. Untuk itu dengan penuh
kerendahan hati penulis terbuka menerima segala saran dan kritik dari pembaca
dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.
Makassar, Mei 2018
Rahmadani
v
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii
ABSTRAK ..................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................. vi
DAFTAR TABEL .......................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. x
I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2. Tujuan dan Kegunaan .................................................................. 2
II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 4
2.1. Daerah Aliran Sungai ................................................................. 4
2.2. Konservasi Tanah dan Air ........................................................... 5
2.2.1 Konservasi Tanah ................................................................. 6
2.2.2 Konservasi Air ..................................................................... 7
2.2.3 Teknik Konservasi Tanah dan Air ....................................... 8
2.3. Tipologi sosial ekonomi masyarakat ........................................... 15
2.3.1 Pendidikan ............................................................................ 15
2.3.2 Pendapatan ........................................................................... 16
2.3.3 Umur .................................................................................... 17
2.3.4 Jumlah anggota keluarga ...................................................... 17
2.3.5 Luas lahan garapan ............................................................... 18
III. METODE PENELITIAN ................................................................. 19
3.1. Waktu dan Tempat ...................................................................... 19
3.2. Alat dan Bahan ........................................................................... 19
3.3. Metode pengumpulan data
3.4. Prosedur Penelitian ...................................................................... 20
3.4.1. Penetapan lokasi penelitian .................................................... 20
3.4.2. Observasi lapangan ................................................................ 20
3.4.3. Wawancara ........................................................................... 20
3.5 Populasi dan sampel ...................................................................... 20
3.6 Analisis data .................................................................................. 20
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 22
4.1. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air .............................. 22
4.2. Metode vegetatif ............................................................................ 23
vi
4.2.1 Tanaman Penutup Tanah ..................................................... 23
4.2.2 Kebun Campuran ................................................................. 24
4.2.3 Pekarangan .......................................................................... 25
4.3. Metode Mekanik .......................................................................... 26
4.3.1 Pengolahan tanah menurut kontur ....................................... 26
4.3.2 Teras Bangku ....................................................................... 27
4.3.3 Saluran drainase .................................................................. 28
4.4. Tipologi Masyarakat .................................................................... 29
4.4.1 Uji chi square antara penerapan teknik konservasi tanah dan
air dengan tipologi masyarakat ........................................... 29
V. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 38
5.1. Kesimpulan .................................................................................. 38
5.2. Saran ............................................................................................ 38
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 39
LAMPIRAN ................................................................................................... 41
vii
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Halaman
Tabel 1. Metode Konservasi Tanah dan Air di Desa Bonto Somba ............ 22
Tabel 2. Klasifikasi Responden berdasarkan Umur Petani ......................... 30
Tabel 3. Tabel Kontingensi Penerapan Teknik KTA dan Umur petani ........ 30
Tabel 4. Tipologi Masyarakat berdasarkan Pendidikan Formal ................... 31
Tabel 5. Perincian responden berdasarkan Penghasilan/pendapatan ........... 33
Tabel 6. Tabel Kontingensi Penerapan Teknik KTA dan Pendapatan ....... 33
Tabel 7. Perincian Responden berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga . 34
Tabel 8. Tabel Kontingensi Penerapan Teknik KTA dan Jumlah
Tanggungan Keluarga ..................................................................... 34
Tabel 9. Perincian Responden Berdasarkan Luas Lahan Garapan ............... 35
Tabel 10. Tabel Kontingensi Penerapan Teknik KTA dan Luas Lahan
Garapan ............................................................................................ 36
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Judul Halaman
Gambar 1. Teknik Vegetatif dengan Tanaman Penutup Tanah. ................. 23
Gambar 2. Penerapan Teknik Konservasi (Metode Vegetatif ) Kebun
campuran ..................................................................................... 24
Gambar 3. Bentuk Wanatani Pada Pekarangan ............................................ 25
Gambar 4. Pengolahan Tanah dan Penanaman Menurut Kontur ............... 26
Gambar 5. Teras Bangku pada Penggunaan Lahan Sawah .......................... 27
Gambar 6. Saluran Drainase ......................................................................... 28
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Judul Lampiran
Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian ............................................................ 43
Lampiran 2. Peta Titik Pengamatan............................................................ 44
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan (kuisioner) ................................................ 45
Lampiran 4. Tabel Tipologi Masyarakat Berdasarkan Latar Belakang
Sosial Ekonomi ...................................................................... 49
Lampiran 5. Perhitungan Uji Chi Square ................................................... 51
Lampiran 6. Tabel X2 Chi Square ............................................................. 53
Lampiran 7. Dokumentasi .......................................................................... 54
1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan nasional dewasa saat ini memiliki peningkatan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat diupayakan secara terus menerus di segala bidang.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari era globalisasi yang ditandai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dan pada
akhirnya membawa tantangan, ancaman serta peluang bagi masyarakat. Demikian
pula halnya pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan yang harus
mengikuti era tersebut sehingga harus di kelola secara bersinergi dan berwawasan
lingkungan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada agar dapat
memperoleh hasil yang maksimal.
Pemanfaatan lahan yang terus menerus mengalami peningkatan akibat dari
pembangunan nasional, tidak bisa ditunda lagi. Hal ini harus disesuaikan dengan
konsep pembangunan yang merata dan berkesinambungan. Karena tanpa
diimbangi dengan asas kelestarian hutan khususnya dalam penerapan teknik
konservasi tanah dan air (KTA) dapat menjadi faktor utama penyebab terjadinya
bencana banjir, longsor, dan kekeringan yang pada akhirnya akan menimbulkan
kerugian terhadap masyarakat bahkan akan mengancam keselamatan manusia.
Dampak khusus dari kondisi tersebut menyebabkan lahan kritis semakin
bertambah.
Pertambahan penduduk yang terus meningkat umumnya tidak sejalan
dengan laju penyediaan sumber daya alam sehingga akan menyebabkan
ketersediaannya terutama lahan menjadi semakin langka dan terbatas. Hal ini
diperparah lagi apabila masyarakat memanfaatkan lahan pada daerah yang curam
dan sangat curam terutama di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) tanpa diikuti
dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air yang benar. Jariyah (2014),
permasalahan DAS tumbuh seiring dengan pertambahan penduduk. Daerah Aliran
Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh bagian hulu, kondisi biofisik daerah
tangkapan dan daerah resapan air. Pada umumnya kondisi di daerah hulu rawan
terhadap gangguan manusia. Pengelolaan DAS bagian hulu sering menjadi fokus
2
perhatian, mengingat kawasan DAS bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan
biofisik melalui daur hidrologi, sehingga kesalahan penggunaan lahan daerah hulu
akan berdampak pada masyarakat di daerah hilir (Jariyah, 2014).
Pemanfaatan lahan di setiap daerah berbeda karena memiliki karakteristik
yang khas disebut tipologi. Tipologi diartikan sebagai pengelompokkan wilayah
berdasarkan karakteristik tertentu yang dibangun berdasarkan karakteristik
biofisik dan sosial ekonomi masyarakat. Tipologi merupakan suatu
pengklasifikasian atau pengelompokan obyek berdasarkan kesamaan sifat-sifat
dasar menjadi tipe-tipe tertentu (Rijal, dkk. 2016).
Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Bonto Somba Hulu DAS
Maros umumnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal penerapan
konservasi tanah dan air. Karakter sosial ekonomi ini merupakan salah satu
indikator yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan teknik konservasi tanah
dan air berbasis tipologi masyarakat di Desa Bonto Somba Hulu DAS Maros.
Asdak (2010) menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi, tingkat kesadaran dan
kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, cenderung lebih mendahulukan
kebutuhan primer dan sekunder, sehingga sering terjadi perambahan hutan di
daerah hulu DAS, penebangan liar, dan praktik-praktik pertanian lahan kering di
perbukitan yang mengakibatkan kerusakan DAS.
Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang
“Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air berbasis Tipologi Masyarakat
di Desa Bonto Somba Hulu DAS Maros”.
1.2. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengidentifikasi penerapan teknik konservasi tanah dan air yang dilakukan
oleh petani.
2. Menggambarkan tipologi sosial ekonomi masyarakat dan hubungannya
dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air.
Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
bahan pertimbangan bagi instansi-instansi terkait dalam melakukan sosialisasi dan
3
penyuluhan kepada petani, tentang teknik konservasi tanah yang baik untuk
diaplikasikan sehingga pengetahuan masyarakat dalam mengelola lahan bisa
meningkat dan kesejahtraannya dapat lebih baik kedepan.
4
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Daerah Aliran Sungai (DAS)
Istilah Daerah Aliran Sungai (DAS) banyak digunakan oleh beberapa ahli
dengan makna atau pengertian yang berbeda-beda, ada yang menyamakan dengan
catchment area, watershed atau drainage basin. Daerah Aliran Sungai (DAS)
merupakan keseluruhan kawasan pengumpul suatu sistem tunggal, sehingga dapat
disamakan dengan catchment area (Sudaryono, 2002).
Asdak (2010) menyatakan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah
daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang
berfungsi menerima, menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan untuk
kemudian disalurkan ke danau, waduk dan ke laut sebagai muara akhir melalui
sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan Daerah Tangkapan Air (DTA
atau Catchment area) yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya
terdiri atas sumber daya alam (tanah, air dan vegetasi) dan sumberdaya manusia
sebagai pemanfaat sumber daya alam.
Setiap DAS mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang mempengaruhi
proses pengaliran air hujan yang jatuh di dalamnya sampai keluar ke muara dan
masuk ke laut atau danau. Karakterikstik DAS terutama ditentukan oleh faktor
lahan (topografi, tanah, geologi, geomorphologi) dan faktor vegetasi dan tata
guna/penggunaan lahan itulah yang akan mempengaruhi debit sungai dan
kandungan lumpurnya. Kondisi DAS dikatakan bertambah baik apabila
perbandingan debit maksimum dan minimum bertambah kecil atau dapat
dikatakan pula bahwa air sungai mengalir sepanjang tahun secara lebih merata, air
sungai menjadi lebih bersih karena lumpur yang terkandung berkurang. Menurut
Dapertemen Kehutanan (2009), untuk mengetahui perkembangan kondisi DAS
perlu dilakukan pengamatan terhadap perbandingan debit sungai beserta
lumpurnya.
Jariyah (2014) menyatakan bahwa permasalahan DAS tumbuh seiring
dengan pertambahan penduduk dan waktu. DAS sangat dipengaruhi oleh bagian
hulu, kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air. Pada umumnya
5
kondisi di daerah hulu rawan terhadap gangguan manusia. Jariyah (2014)
pengelolaan DAS bagian hulu sering menjadi fokus perhatian, mengingat kawasan
DAS bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi,
sehingga kesalahan penggunaan lahan daerah hulu akan berdampak pada
masyarakat di daerah hilir.
2.2. Konservasi Tanah dan Air
Tanah dan air sebagai sumberdaya alam terbarukan harus dikelola dan
dimanfaatkan secara bijaksana agar diperoleh manfaat yang berkelajutan dan
produktifitasnya tetap lestari. Setiap macam penggunaan tanah serta aliran
permukaan. Teknologi yang digunakan dalam pengelolaan lahan akan diperoleh
pemanfaatan dan produktifitas yang berkelanjutan atau sebaliknya (Mawardi,
2013).
Upaya penyelamatan bumi dalam bentuk Konservasi Tanah dan Air, sangat
mendesak untuk mengembalikan ekosistem tanah dan air demi keselamatan
kehidupan yang menyertainya. Konservasi Tanah dan Air adalah dua hal yang
saling berkaitan. Tindakan konservasi atau perlindungan alam terhadap tanah,
berdampak pada ketersediaan kuantitas dan kualitas air yang berkelanjutan. Usaha
konservasi atau perlindungan alam terhadap air, akan melibatkan suatu tindakan
untuk pengelolaan daerah tangkapan air secara terpadu, yang berarti juga tindakan
konservasi tanah (Susilawati, 2006). Berhubungan adanya hubungan yang erat
sekali antara tanah dan air, bahwa setiap perlakuan yang diberikan kepada
permukaan sebidang tanah akan mempengaruhi pula tata air ditempat itu dan
hilirnya, maka masalah konservasi tanah dan air merupakan dua hal yang
berhubungan erat sekali (Triwanto, 2012).
Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air bertujuan: (a) melindungi
permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatan kapasitas
infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konservasi aliran permukaan: (b)
menjamin fungsi tanah pada lahan agar mendukung kehidupan masyarakat; (c)
mengoptimalkan fungsi tanah pada lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi,
sosial dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari; (d) meningkatkan daya
6
dukung Daerah Aliran Sungai; (e) meningkatkan kemampuan kapasitas untuk
mengembangkan dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara
partisipatif; dan menjamin kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan
merata untuk kepentingan masyarakat (UU No. 37 Tahun 2014).Lahan menurut
Siswomartono (1989) adalah lingkungan alami dan kultural tempat berlansungnya
produksi; suatu istilah yang lebih luas dari pada tanah. selain tanah, sifat-sifat
meliputi kondisi fisik lainnya, seperti : Deposit mineral, iklim, dan pasok air,
lokasi yang bertalian dengan pusat-pusat kegiatan, populasi dan lahan lain; ukuran
masing-masing daerah; dan penutup tanaman yang ada, pekerjaan perbaikan, dan
sebagainya.
2.2.1. Konservasi Tanah
Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada
cara penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan
memperlakukannya seuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi
kerusakan tanah. Sifat-sifat fisik dan kimia tanah serta keadaan topografi lapangan
menentukan kemampuan tanah untuk suatu penggunaan dan perlakuan yang
diperlukan (Arsyad, 2010).
Konservasi tanah dapat dikategorikan sebagai perpaduan ilmu pengetahuan
yang mengembangkan teknologi pengawetan sumber daya alam khususnya
sumber daya tanah dan air sebagai faktor penentu kualitas lingkungan hidup.
Konservasi tanah dan air itu sendiri adalah usaha-usaha untuk menjaga dan
menigkatkan produktivitas tanah, kualitas, kuantitas air. Problem yang mendasari
saat ini adalah pertambahan penduduk yang selalu meningkat dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi di era industrialisasi yang membutuhkan
sejumlah tanah satu lahan yang cukup luas untuk aktivitas kehidupan dan
pembangunan dalam mensejahterakan umat manusia.
Junaidi (2009) mengemukakan tujuan umum konservasi tanah saat ini ada 3,
yaitu: (1) untuk melindungi fungsi tanah dari kerusakan yang diakibatkan oleh
faktor alami dan campur tangan manusia, (2) untuk memperbaiki fungsi tanah
yang telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alami dan campur
tangan manusia dan (3) untuk memelihara sekaligus meningkatkan kemampuan
7
tanah agar dapat digunakan secara lestari. Berdasarkan ketiga tujuan tersebut,
konsep konservasi tanah telah berkembang yang semula hanya bertujuan
pencegahan menjadi perbaikan bahkan peningkatan kemampuan tanah dalam
fungsinya.
2.2.2. Konservasi Air
Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah
seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi
banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim
kemarau. Konservasi air dapat dilakukan dengan (a) meningkatkan pemanfaatan
dua komponen hidrologi, yaitu air permukaan, dan air tanah dan (b) meningkatkan
efisiensi pemakaian air irigasi (Arsyad, 2010).
Winarto, (2006) mengatakan bahwa konservasi sumberdaya air adalah
upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan, keadaan sifat dan fungsi
sumberdaya air, agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang
memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk, baik dalam waktu sekarang
maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan yang berhubungan
dengan pengendalian dan pengelolaan aliran permukaan dapat diformulasikan
dalam strategi konservasi air. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah
sebanyak-banyaknya di daerah-daerah cekungan atau lembah, sehingga dapat
digunakan sebagai sumber air untuk pengairan dimusim kemarau maupun pada
periode pendek saat dibutuhka oleh tanaman pada musim hujan. Konservasi air
juga dapat meningkatkan penutupan permukaan tanah dengan mulsa dan
teknologi ini sudah sangat popular dikalangan petani (Kurnia, dkk. 2003).
Asdak (2010) setiap perlakuan yang diberikan pada sebidang tanah akan
mempengaruhi tata air tempat itu dan tempat-tempat hilirnya. Oleh karena itu,
maka konservasi tanah dan air merupakan dua hal yang berhubungan erat sekali,
berbagai tindakan konservasi tanah merupakan juga tindakan konservasi air.
Arsyad (2010) Secara garis besar, metode konservasi tanah dan air dibagi menjadi
3 yaitu : metode vegetatif, mekanik dan kimia. Konservasi tanah dalam arti luas
adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan
kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya dengan syarat-syarat yang
8
diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sifat fisik, kimia dan biologi
menentukan kemampuan tanah (soil copability) untuk suatu penggunaan dan
perlakuan yang diperlukan agar tanah tidak rusak dan dapat digunakan secara
berkelanjutan (sustainable). Sifat-sifat tanah tersebut juga menentukan tanah
untuk tererosi. Konservasi tanah pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan
jatuh ke tanah unuk pertanian seeffisien mungkin, dan mengatur aliran air agar
tidak terjadi banjir yang merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim
kemarau.
2.2.3. Teknik Konservasi Tanah dan Air
Teknik konservasi tanah di Indonesia diarahkan pada tiga prinsip utama
yaitu perlindungan permukaan tanah terhadap pukulan butir-butir hujan,
meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah seperti pemberian bahan organik atau
dengan cara meningkatkan penyimpanan air, dan mengurangi laju aliran
permukaan sehingga menghambat material tanah dan hara terhanyut (Agus, dkk,
1999). Ketiga teknik konservasi tanah secara vegetatif, mekanis dan kimia pada
prinsipnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengendalikan laju erosi, namun
efektifitas, persyaratan dan kelayakan untuk diterapkan sangat berbeda. Oleh
karena itu pemilihan teknik konservasi yang tepat sangat diperlukan (Kasdi, dkk,
2003).
Metode konservasi tanah dapat dibagi dalam tiga golongan utama, yaitu (1)
metode vegetatif, (2) metode mekanik dan (3) metode kimia.
a. Metode Vegetatif
Teknik konservasi tanah secara vegetatif adalah setiap pemanfaatan
tanaman/vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dari
erosi, penghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan lengas tanah,
serta perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia maupun biologi. Pada
dasarnya konservasi tanah secara vegetatif adalah segala bentuk pemanfaatan
tanaman ataupun sisa-sisa tanaman untuk mengurangi erosi. Tanaman ataupun
sisa-sisa tanaman berfungsi sebagai pelindung tanah terhadap daya pukulan butir
9
air hujan maupun terhadap daya angkut air aliran permukaan (runoff), serta
meningkatkan peresapan air ke dalam tanah (Kasdi, dkk, 2003).
Teknik vegetatif dalam konservasi tanah adalah :
Penanaman dengan tanaman penutup tanah (permanent plant cover)
Tumbuh-tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai penutup tanah dapat
digolongkan dalam tiga jenis :
1) Tumbuhan penutup tanah tinggi atau tanaman pelindung, seperti Albizzia
falcata Backer dan Leucaena leucocephala
2) Tumbuhan penutup tanah sedang, berupa semak seperti beberapa tumbuhan
leguminosa (kacang-kacangan), yaitu Cro talaria anagyroides, C. juncea L,
C.striata
3) Tumbuhan penutup tanah rendah, seperti Colopogonium muconoides Desv,
Sentrosema pubescens Benth, Ageratum conizoides L (babadotan), dan
beberapa jenis rumput-rumputan, misalnya akar wangi, rumput gajah, dan
rumput benggala.
Penanaman dalam strip ( Strip Cropping)
Penanaman dalam strip (strip cropping) adalah suatu sistem bercocok tanam
yang beberapa jenis tanaman ditanam dalam satu strip yang berselang-seling pada
sebidang tanah pada waktu yang sama dan disusun memotong lereng atau
menurut garis kontur. Biasanya tanaman yang digunakan adalah tanaman pangan
atau tanaman semusim lainnya diselingi dengan strip-strip tanaman yang tumbuh
rapat berupa tanaman penutup tanah pupuk hijau. Penanaman dalam strip cukup
efektif untuk lahan yang kemiringannya tidak terlalu curam, biasanya digunakan
pada lereng 3-8,5%.
Pemakaian mulsa
Pembenaman sisa-sisa tumbuhan ke dalam tanah selain dibenamkan ke
dalam sisa-sisa tumbuhan dapat pula diletakkan di atas tanah sebagai serasah
(mulsa) yang dapat mempertahankan kelembaban tanah. Dengan mulsa maka
penguapan air tanah dapat diperkecil sehingga tumbuhan yang terdapat pada tanah
tersebut dapat tetap hidup.
10
Watani (agroforestry)
Praktek watani (agroforestry) merupakan sistem perladangan berpindah,
hanya tanaman kehutanan yang dapat ditanam beragam dari tanaman buah hingga
jenis kayu yang diharapkan untuk dipanen kayunya bukan buahnya, program
watani ini tergantung pada kebiasaan setempat.
Menurut Agus dkk (1999), sistem watani telah lama dikenal di masyarakat
Indonesia dan berkembang menjadi beberapa macam seperti pertanaman sela,
pertanaman lorong, talun hutan rakyat, kebun campuran, pekarangan dan tanaman
pelindung/multistrata.
1) Pertanaman sela, adalah pertanaman campuran antara tanaman tahunan dan
tanaman musiman. Sistem ini banyak dijumpai di daerah hutan atau kebun
yang dekat dengan lokasi pemukiman.
2) Pertanaman lorong, adalah suatu sistem dimana tanaman pagar pengontrol
erosi berupa barisan tanaman yang ditanam rapat mengikuti garis kontur,
sehingga membentuk lorong-lorong dan tanaman semusim berada diantara
tanaman pagar tersebut. Sistem ini sesuai untuk diterapkan pada lahan
kering dengan kelerangan 3-40%.
3) Talun hutan rakyat adalah lahan diluar wilayah pemukiman penduduk yang
ditanami tanaman tahunan yang dapat diambil kayu maupun buahnya.
Sistem ini tidak memerlukan perawatan intensif dan hanya dibiarkan begitu
saja sampai saatnya panen. Karena tumbuh secara spontan, maka jarak
tanam sering tidak seragam, jenis tanaman sangat beragam dan kondisi
umum lahan seperti hutan alami.
4) Kebun campuran, adalah lahan diluar pemukiman penduduk yang ditanami
tanaman tahunan maupun musiman yang dapat diambil kayu, daun maupun
buahnya.
5) Pekarangan, adalah kebun disekitar rumah dengan berbagai jenis tanaman
baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Lahan tersebut
mempunyai manfaat tambahan bagi keluarga petani, dan secara umum
11
merupakan gambaran kemampuan suatu keluarga dalam mendayagunakan
potensi lahan secara optimal
6) Tanaman pelindung, adalah tanaman tahunan yang ditanam disela-sela
tanaman pokok tahunan. Tanaman pelindung ini dimaksudkan untuk
mengurangi intensitas penyinaran matahari, dan tempat melindungi tanaman
pokok dari bahaya erosi terutama ketika tanaman pokok masih muda.
7) Silvipastur adalah bentuk lain dari tumpang sari, tetapi yang ditanam disela-
sela tanaman tahunan bukan tanaman pangan melainkan tanaman pakan
ternak seperti rumput gajah (Pennisetum purpureum), rumput raja
(Pennisetum pupoides), dan lain-lain.
b. Metode Mekanik
Metode fisik atau mekanis adalah tindakan atau perilaku yang ditunjukan
kepada tanah agar dapat memperkecil aliran air permukaan, sehingga dapat
mengalir dengan kekuatan tidak merusak.
Pengolahan Tanah
Pada pengolahan tanah, pembajakan dilakukan menurut kontur atau
memotong lereng, sehingga terbentuk jalur tumpukan tanah dan alur diantara
tumpukan tanah yang terbentang menurut kontur. Pengolahan menurut kontur
akan lebih efektif jika diikuti dengan penanaman menurut kontur, yaitu barisan
tanaman diatur sejalan dengan garis kontur (Arsyad, 2010).
Keuntungan utama dari pengelolaan tanah menurut kontur adalah
terbentuknya penghambatan aliran permukaan dan terjadinya penampungan air
sementara, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya erosi. Untuk
daerah dengan curah hujan yang rendah, sistem ini sekaligus sangat efektif bagi
konsentrasi air (Suripin, 2004).
Teras
Sukartaatmadja (2004), mengemukakan bahwa teras adalah bangunan
Konservasi Tanah dan Air secara mekanis yang dibuat untuk memperpendek
panjang lereng dan atau memperkecil kemiringan lereng dengan jalan penggalian
dan pengurugan tanah melintang lereng. Tujuan pembuatan teras adalah untuk
12
mengurangi kecepatan aliran permukaan (run off) dan memperbesar peresapan air,
sehingga kehilangan tanah berkurang.
1) Teras bangku, merupakan teras yang dibuat dengan cara memotong lereng
dan meratakan tanah dibidang oleh sehingga terjadi deretan menyerupai
tangga (Wajudi, 2014). Teras bangku adalah bangunan teras yang dibuat
sedemikian rupa sehingga bidang olah miring ke belakang (reverse back
slope) dan dilengkapi dengan bangunan pelengkap lainnya untuk
menampung dan mengalirkan air permukaan secara aman dan terkendali
(Sukartaatmadja, 2004). Teras bangku memang cukup efektif dalam
mengurangi erosi, bila tanah (solum) cukup dalam. Pada tanah yang dangkal
teras bangku cenderung menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan
tanaman, dan bila tanah mempunyai permeabilitas lambat, teras bangku
dapat mempercepat terjadinya longsor. Pada daerah dengan jenis tanah yang
berstruktur lepas, tampaknya penerapan teras bangku kurang baik dan sering
rusak, untuk itu diperlukan penanaman tanaman penguat teras.
2) Teras datar biasanya dibuat pada tanah-tanah dengan kemiringan lereng
<3%, dengan tujuan untuk menahan dan menyerap air. Teras ini dibuat tetap
menurut garis kontur terutama pada tanah-tanah yang mempunyai
permeabilitas cukup besar sehingga tidak terjadi penggenangan atau luapan
air melalui guludan (Triwanto, 2012). Pembuatan teras-teras tersebut agar
dapat berfungsi dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya pada sisa-sisa
(tebing) hanya ditanami dengan rumput-rumputan yang dapat mendorong
daya tahan penebingannya seandainya pada tempat itu terdapat banyak batu-
batuan, pemanfaatan batu-batuan untuk maksud tersebut adalah lebih baik.
Selanjutnya untuk melindungi tebing teras dapat dimanfaatkan tanaman
penutup tanah yang rendah (Kartasapoetra, 2010).
3) Teras gulud, merupakan sistem pengendalian erosi secara mekanis yang
berupa barisan gulud yang dilengkapi rumput penguat gulud dan saluran air
dibagian lereng atas (Wajudi, 2014).
Drainase
Drainase yang berasal dari bahasa inggris dranage mempunyai arti
mengalirkan, menguras, membuang atau mengalirkan air. Secara umum dapat
13
didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik
yang berasal dari air hujan, rembesan maupun kelebihan air irigasi dari suatu
kawasan/lahan sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu. Drainase juga
dapat diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya
dengan salinitas. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga
air tanah (Suripin, 2004).
Arsyad (2010) mengemukakan bahwa drainase berarti keadaan dan cara
keluarnya air lebih. Air lebih adalah air yang tidak dapat ditahan atau dipegang
atau ditahan oleh butir-butir tanah dan memenuhi pori-pori tanah. Fasilitas
drainase atau sistem drainase dapat berupa sistem drainase di permukaan tanah
(surface drainase) dan di dalam tanah atau dibawah permukaan tanah (subsurface
atau undergraound drainase). Sistem drainase di permukaan tanah dapat berupa
(a) peralatan tanah (b) guludan dan (c) saluran terbuka. Kebutuhan akan sistem
drainase ini umumnya terdapat pada tanah-tanah datar yaitu lerengnya kurang dari
2% sebabian besar berlereng kurang dari 1%.
Saluran pembuangan air
Suripin (2004), menyatakan bahwa saluran pembuangan air berfungsi untuk
menghindari terkonsentrasinya aliran permukaan di sembarang tempat yang akan
membahayakan dan merusak tanah yang dilewatinya. Tujuan utama pembangunan
saluran pembuangan air adalah untuk mengarahkan dan menyalurkan aliran
permukaan dengan kecepatan yang tidak tererosive ke lokasi pembuangan air
yang sesuai.
Bangunan Stabilisasi
Bangunan stabilisasi sangat penting artiya dalam rangka reklamasi
parit/selokan dan pengendalian erosi parit/selokan. Bangunan stabilisasi yang
umum berupa dam penghambat (check dam), balok dan rorak. Bangunan-
bangunan tersebut berfungsi untuk mengurangi volume dan kecepatan aliran
permukaan, disamping juga untuk menambah masukan air tanah dan air bawah
tanah (Suripin, 2004).
Dam penghambat dibuat dengan memasang papan, balok kayu, bata atau
tumpukan tanah untuk mengurangi erosi pada parit atau selokan untuk
mengurangi erosi pada parit atau selokan untuk menghambat kecepatan air, dan
14
tanah terendapkan pada tempat tersebut. Untuk mengatasi erosi parit (gully
erosion) digunakan juga dam penghambat yang terdiri atas tumpukan cabang dan
ranting (Arsyad, 2010).
c. Metode Kimia
Metode kimia merupakan salah satu sifat tanah yang sangat menguntungkan
kepekaan tanah terhadap erosi. Oleh karena itu sejak tahun 1950-an telah dimulai
adanya usaha-usaha untuk memperbaiki kemantapan struktur tanah melalui
pemberian preparat-preparat kimia yang secara umum disebut pemantap tanah
(Soil conditioner). Suripin (2004) mengemukakan bahwa usaha pemantapan tanah
yang bertujuan untuk sifat fisik tanah dengan menggunakan preparat-preparat
kimia baik secara buatan maupun alami.
Bahan pemantapan tanah yang baik harus mempunyai sifat-sifat sebagai
berikut dalam (Suripin, 2004):
1) Mempunyai sifat yang adhesif serta dapat bercampur dengan tanah secara
merata
2) Dapat merubah sifat hidrophobik tanah, yang dengan demikian dapat
merubah kurva penahanan air tanah
3) Dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, yang berarti
mempengaruhi kemampuan tanah dalam menahan air
4) Daya tahan sebagai pemantap tanah cukup memadai, tidak terlalu singkat
dan tidak terlalu lama
5) Tidak bersifat racun (phytotoxic) dan harganya terjangkau.
Salah satu teknik konservasi tanah yang dapat diterapkan guna
mengendalikan erosi dan aliran permukaan, sekaligus menambah bahan organik
tanah adalah teknik mulsa vertikal. Teknik ini memanfaatkan limbah organik, baik
yang berasal dari serasah gulma, cabang, ranting, batang maupun daun-daun
bekas tebangan atau pembersih lahan dengan memasukkannya kedalam saluran
atau alur yang dibuat sejajar kontur pada bidang tanah yang diusahakan. Penerpan
mulsa vertikal pada dasarnya selalu dikombinasikan dengan pembuatan guludan.
Secara ekologis teknik ini terbukti dapat menurunkan laju aliran permukaan, erosi
dan kehilangan unsur hara. Aliran permukaan akan masuk ke dalam saluran yang
berisi mulsa (limbah hutan), kemudian meresap kedalam profil tanah. Bahan
15
organik yang berupa mulsa ini merupakan media yang dapat menyerap dan
memegang massa air dalam jumlah besar, sehingga penyimpanan air dalam tanah
dapat berjalan efesien (Pratiwi dan Nahendra, 2012).
2.3. Tipologi Sosial Ekonomi Masyarakat
Tipologi adalah pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik tertentu
yang dibangun berdasarkan keadaan biofisik, sosial, dan ekonomi maupun
kebijakan politik. Tipologi juga diartikan sebagai suatu pengklasifikasian atau
pengelompokkan obyek berdasarkan kesamaan sifat-sifat dasar menjadi tipe-tipe
tertentu (Rijal, dkk, 2016). Sosial ekonomi setiap daerah diyakini berbeda karena
memiliki karakteristik sendiri. Karakteristik yang khas ini disebut dengan tipologi.
Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian
sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Kata sosial
sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat
(KBBI,1996:958). Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani
yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu
peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai
aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga (Koentjaraningrat,1981).
Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun
material. Kebutuhan pokok dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat
penting guna kelangsungan hidup manusia. Untuk melihat kondisi sosial ekonomi
keluarga atau masyarakat yaitu Pendidikan, luas lahan, jumlah tanggungan
keluarga dan penghasilan. Berdasarkan hal ini maka keluarga atau kelompok
masyarakat itu dapat digolongkan memiliki sosial ekonomi rendah, sedang, dan
tinggi (Koentjaraningrat, 1981). Penelitian ini menambahkan satu kriteria
penentuan sosial ekonomi masyarakat yaitu umur, dimana umur dapat melihat
tingkat produktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam bekerja.
2.3.1. Pendidikan
Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak harus dipenuhi sebagai
pengalaman belajar yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi
dasar dalam perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Pendidikan diartikan
16
sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang
memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai
dengan kebutuhan (Syah, 2006). Seorang anak normal yang tumbuh dewasa maka
secara otomatis pemikirannya pun akan berkembang dan lebih bijak dalam
mengambil suatu keputusan, jika dalam pertumbuhan menuju kedewasaannya
diimbangi dengan Pendidikan yang baik.
Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia ditinjau dari
tumbuhnya rasa percaya diri serta memiliki sikap yang inovatif dan kreatif untuk
mengembangkan daerahnya. Dan semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang
memungkinkan seseorang tersebut mencapai tingkat Pendidikan yang tinggi.
Undang – Undang RI No.20 Tahun 2003, jalur pendidikan dibagi menjadi:
1. Jalur Formal
a. Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah
atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk yang lebih sederajat.
b. Pendidikan Menengah
Pendidikan Menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan
pendidikan menengah jurusan, seperti: SMA, MA, SMK, MAK atau
bentuk lain yang sederajat.
c. Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,
institute, dan universitas.
2. Jalur Nonformal
3. Jalur Formal
2.3.2. Pendapatan
Kartono Wirosuharja, (1985) menyatakan bahwa “pendapatan adalah arus
uang atau barang yang didapat oleh perseorangan, kelompok orang, perusahaan
atau suatu perekonomian pada suatu periode tertentu”. Berdasarkan pendapat di
atas maka dalam kehidupan usaha rumah tangga tersebut untuk memenuhi segala
17
kebutuhannya sehingga sebagian besar dan kecilnya pendapatan suatu rumah
tangga akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan rumah tangganya.
Pendapatan adalah jumlah keseluruhan dari hasil yang diperoleh baik dari
pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan yang dapat dilihat dan diukur
dengan rupiah dalam waktu tertentu. Sehubungan dengan tingkat pendapatan,
berikut kriteria golongan pendapatan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012:
a. Pendapatan golongan rendah jika penghasilan di bawah 1.500.000 per bulan
b. Pendapatan golongan menengah jika penghasilan 1.500.000 – 2.500.000 per
bulan
c. Pendapatan golongan tinggi jika penghasilan 2.500.000 – 3.500.000 per
bulan
Jika pendapatan suatu rumah tangga tinggi, maka sudah pasti kebutuhan
pokok rumah tangga tersebut akan terpenuhi.
2.3.3. Umur
Umur merupakan salah satu karakteristik individu yang sangat berperan
dalam menentukan kemam puan kerja dan produktivitas kerja (Handoko, 2001).
Petani yang berumur muda biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa
yang belum mereka ketahui, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk
lebih cepat melakukan anjuran dari kegiatan penyuluhan. Umur juga dapat
menentukan tingkat produktifitas dalam melakukan suatu pekerjaan. Umur yang
dianggap produktif menurut Badan Pusat Statistik yaitu 15 – 64 tahun (BPS,
2016).
Ekasari (2014) mengemukakan adanya hubungan yang positif antara umur
petani dengan pengambilan keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi. Dikatakan
bahwa semakin tua usia petani maka cenderung akan bersifat positif terhadap
inovasi.
2.3.4. Jumlah Anggota Keluarga
Jumlah anggota keluarga sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan untuk menerima suatu inovasi. Hal ini dapat
dimengerti karena konsekuensi penerimaan inovasi akan berpengaruh terhadap
18
keseluruhan sistem keluarga petani (Ekasari, 2014). Dalam kaitan ini Monsher
(1991) menjelakan bahwa keputusan mengenai perairan masih diambil oleh petani
sebagai individu, akan tetapi keputusan itu diambil dalam kedudukannya sebagai
anggota keluarga.
2.3.5. Luas Lahan Garapan
Ekasari (2014) luas lahan garapan petani dapat mempengaruhi tingkat
adopsi mereka terhadap inovasi. Dalam kaitan ini beberapa hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan teknologi baru akan dapat respon dari petani bila
mempunyai lahan luas, sebaliknya pada lahan yang sempit maka dianggap oleh
petani tidak efesien.
19
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Januari hingga
Maret 2018 di Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros,
Hulu DAS Maros.
3.2. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Positioning System
(GPS), Kamera Digital dan Alat Tulis Menulis. Sedangkan bahan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Pertanyaan (kuisioner) dan Peta Lokasi Penelitian.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi
pada penelitian ini adalah:
3.3.1. Data Primer
Data primer merupakan data yang langsung diperoleh di lapangan melalui
observasi. Observasi dilakukan dengan mengidentifikasi teknik konservasi tanah
dan air yang diterapkan oleh petani. Melakukan wawancara di lokasi penelitian
berdasarkan karakteristik tipologi sosial ekonomi masyarakat.
3.3.2. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai instansi atau lembaga
terkait berupa: Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros, Peta Administrasi
Kabupaten Maros, serta Data kependudukan (BPS).
20
3.4. Prosedur Penelitian
3.4.1. Penetapan lokasi penelitian
Pengambilan data dilapangan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan
lokasi yang dianggap mewakili daerah Hulu DAS Maros berdasarkan
penampakan citra google earth tahun 2016.
3.4.2. Observasi Lapangan (Ground Check)
Observasi lapangan bertujuan untuk melihat penerapan teknik konservasi
tanah dan air yang dilakukan oleh petani.
3.4.3. Wawancara
Wawancara dilakukan pada masyarakat (responden) untuk mengetahui
penerapan teknik konservasi tanah dan air berdasarkan tipologi masyarakat yang
meliputi karakteristik sosial ekonomi masyarakat, umur, pendidikan, penghasilan,
jumlah tanggungan keluarga, dan luas lahan garapan.
3.5. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bonto Somba Hulu
DAS Maros. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik
purposive sampling dengan pertimbangan aksesbilitasi .
3.6. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan teknik konservasi tanah dan air
yang diterapkan masyarakat digunakan analisis deskriptif .
2. Untuk menjelaskan hubungan antara tipologi sosial ekonomi masyarakat
dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air, dilakukan analisis uji chi
square (Hubungan kontengensial).
21
Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :
H0 = Tidak ada hubungan yang nyata antara penerapan teknik konservasi dengan
sosial ekonomi masyarakat
H1 = Ada hubungan yang nyata antara penerapan teknik konservasi tanah dan air
dengan sosial ekonomi masyarakat
Kriteria pengambilan keputusan
“tolak hipotesis nol (H0) apabila nilai signifikan chi squre <0.05 atau nilai
chi square hitang lebih besar dari (>) nilai chi square tabel.”
Statistik uji chi square yang dihitung dengan rumus :
X2= Ʃ
Dimana :
X2 = nilai chi kuadrat
Ʃ = jumlah keseluruhan
fo = frekuensi observasi/pengamatan
fe = frekuensi ekspektasi/harapan
22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap penerapan teknik konservasi tanah
dan air yang dilakukan masyarakat di Desa Bonto Somba adalah teknik
konservasi tanah secara vegetatif dan mekanik. Teknik vegetatif yang diterapkan
berupa tanaman penutup tanah, kebun campuran dan pekarangan sedangkan
teknik mekanik yang diterapkan adalah berupa pengolahan tanah menurut kontur,
dan teras bangku. Tanaman penutup tanah ditemukan hanya di areal persawahan
terutama di pematang sawah. Kebun campuran ditemukan di luar area pemukiman
warga. Pekarangan yang di dapat berada di sekitar rumah warga yang mempunyai
manfaat tambahan bagi keluarga. Pengolahan menurut kontur di temukan pada
area perladangan. Teras bangku ditemukan di areal persawahan warga. Bentuk-
bentuk dari metode konservasi tanah tersebut disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Metode Konservasi Tanah dan Air di Desa Bonto Somba Hulu DAS
Maros
No.
Metode KTA
Bentuk-bentuk Teknik KTA
Jumlah
Responden
(orang)
1. Metode Vegetatif
Kebun Campuran 4
Pekarangan 2
2. Metode Mekanik
Pengolahan tanah menurut
kontur 2
Tanaman penutup tanah, teras
bangku 15
3. Metode Vegetatif dan
Mekanik
Tanaman penutup tanah, teras
bangku, kebun campuran 3
Tanaman penutup tanah, teras
bangku, pekarangan 4
Jumlah 30
Berdasarkan data di atas diperoleh dari hasil penelitian bahwa dari 30
responden yang di teliti terdapat 6 orang yang menerapkan teknik konservasi
tanah dan air secara vegetatif, 17 orang yang menerapkan metode mekanik,
selebihnya 7 orang menerapkan teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif
dan mekanik.
23
4.2 Metode Vegetatif
4.2.1. Tanaman Penutup Tanah
Tanaman penutup tanah yang terdapat di Desa Bonto Somba kebanyakan
ditemukan pada areal persawahan khususnya pada pematang sawah berupa
rumput-rumputan yaitu rumput australia (Paspalum dilatatum) seperti yang
terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Tanaman Penutup Tanah yaitu rumput Australia
Petani di Desa Bonto Somba memanfaatkan tanaman penutup tanah dengan
tujuan agar permukaan tanah dapat terhindar dari ancaman erosi karena kecepatan
jatuh setiap butir hujan telah dilemahkan sehingga kemampuannya untuk
mengerosi tanah semakin kecil. Selain itu, pertumbuhan jenis rumput-rumputan
ini juga dapat tumbuh dengan cepat dan membantu meminimalkan daya tumbuk
air hujan ketika bersentuhan dengan daun rumput-rumputan. Tanaman penutup
tanah rendah terdiri dari jenis rumput-rumputan dan tumbuhan merambat atau
menjalar yang banyak terdapat pada talud dan tampingan teras bangku yang
berfungsi untuk melindungi tanah dari butir-butir air hujan, mengurangi kecepatan
aliran permukaan dan memperbesar infiltasi kedalam tanah sehingga mengurangi
erosi. Kemampuan teras bangku sebagai pengendali erosi akan meningkat bila
ditanami dengan tanaman penguat teras seperti rerumputan. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Kertasapoetra (2010) bahwa tanaman rumput-rumputan selalu
diutamakan dalam usaha pengawetan tanah dan atau pencegahan erosi karena : (a)
tanaman rumput-rumputan dapat tumbuh dengan cepat sehingga dalam waktu
24
yang pendek tanah telah dapat tertutupi oleh tanaman tersebut secara rapat dan
tebal, (b) bagian atas tanaman mampu untuk melindungi permukaan tanah dari
tumbukan butir-butir air hujan dan memperlambat aliran permukaan dan (c)
bagian bawah tanaman dapat memperkuat resistensi tanah dan membantu
melancarkan infiltrasi air ke dalam tanah.
4.2.2. Kebun Campuran
Kebun campuran merupakan lahan di luar wilayah pemukiman penduduk
yang ditanami tanaman tahunan maupun musiman. Adanya kombinasi tanaman
tahunan dan tanaman musiman akan menghasilkan variasi tajuk yang akan
berdampak pada kondisi tanah dibawahnya. Jenis tanaman yang terdapat di lokasi
penelitian yaitu bambu, jati, kakao, jati putih, mangga, jagung, pisang, ubi kayu,
nangka, jabon putih, jambu biji, jambu monyet dan gamal.
Gambar 2. Penerapan Teknik Konservasi (Metode Vegetatif ) Kebun campuran
Kebun campuran seperti yang terlihat pada Gambar 2 dapat dilihat dari
strata tajuknya yang memiliki 4 strata tajuk, dimana pada lapisan tingkat strata
tajuk 1 banyak ditemukan jenis tanaman jati, dan jabon, strata 2 banyak
ditemukan jenis tanaman bambu, pisang, coklat, gamal, mangga, jambu biji,
nangka, dan jambu monyet, strata 3 banyak ditemukan jenis tanaman jambu
biji,pisang, ubi kayu dan strata 4 banyak ditutupi oleh rumput-rumput. Kondisi
kebun campuran dilapangan hampir seluruh permukaan tanah tertutup oleh
25
vegetasi yang ada diatasnya sehingga tanah dapat resisten terhadap daya butir-
butir hujan yang dapat melakukan penghancuran agregat tanah agar lahan tersebut
mudah tererosi, selain itu banyaknya air hujan yang masuk ke dalam tanah
dibandingkan air yang mengalir melalui aliran permukaan.
Pada kebun campuran di areal datar maupun berlereng mempunyai jarak
tanam yang tidak teratur. Meskipun demikian tanaman tersebut memiliki kondisi
penutupan tajuk yang rapat dan berlapis sehingga dapat mengurangi laju aliran
permukaan, mencegah erosi dan banjir. Jadi semakin rapat dan banyak lapisan
tajuk suatu tanaman, maka semakin besar kemampuannya mengurangi energi
potensial air hujan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asdak (2010) menyatakan
bahwa vegetasi terhadap erosi yaitu melindungi permukaan tanah dari tumbukan
air hujan (memperkecil kecepatan air hujan) sehingga dapat mengurangi
kemungkinan terjadinya erosi.
4.2.3. Pekarangan
Pekarangan adalah kebun di sekitar rumah dengan berbagai jenis tanaman
baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Pemanfaatan pekarangan oleh
masyarakat yang bermukim di lokasi penelitian merupakan salah satu upaya
masyarakat dalam menerapkan metode konservasi tanah secara vegetatif dalam
bentuk wanatani. Pekarangan di lokasi penelitian pada umumnya di tanami
dengan jagung, pisang, ubi kayu, nangka, kakao, sukun, seperti yang terlihat pada
Gambar 3.
Gambar 3. Bentuk Wanatani pada Pekarangan
26
Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat memanfaatkan tanaman
yang ada di pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada pula yang
memanfaatkannya untuk kebutuhan ekonomi dengan cara dijual ke pasar. Dari
segi konservasi tanah, pemanfaatan pekarangan baik untuk melindungi tanah yang
ada dibawahnya. Jenis vegetasi yang bervariasi serta tersusun atas beberapa strata
akan menciptakan penutupan lahan yang baik sehingga tanah terhindar dari
pukulan langsung air hujan. Penutup tanah juga menambah kandungan bahan
organik tanah yang meningkatkan resistensi terhadap erosi yang terjadi. Fungsi
pekarangan tersebut sesuai dengan pernyataan Fitriadi R, dkk. (1997) dalam Sari
(2015) bahwa pekarangan merupakan campuran antara tanaman tahunan, tanaman
umur panjang, dan ternak (termasuk sapi) di pekarangan sekitar rumah berupa
suatu sistem ekonomis, biofisik, dan sociocultural yang mempunyai struktur
terpadu dengan batas-batas jelas memenuhi yang sama dari tahun ke tahun,
walaupun ada sedikit variasi musiman.
4.3 Metode Mekanik
4.3.1 Pengolahan Tanah Menurut Kontur
Pengolahan tanah menurut kontur adalah penanaman mengikuti garis kontur
yang dilakukan pada lahan miring untuk mengurangi erosi dan aliran permukaan.
Selain itu pengolahan tanah menurut kontur pembajakannya dilakukan menurut
kontur atau memotong lereng, sehingga terbentuk jalur tumpukan tanah dan alur
di antara tumpukan tanah yang terbentang menurut kontur seperti yang terlihat
pada Gambar 4.
Gambar 4. Pengolahan Tanah dan Penanaman Menurut Kontur
27
Berdasarkan pengamatan dilapangan tentang pengolahan tanah dan
penanaman menurut kontur. Tanaman yang seharusnya diatur searah kontur akan
tetapi setelah hasil wawancara masih ada warga yang menerapkan searah lereng.
Hasil wawancara oleh petani yang menerapkan searah lereng mengatakan bahwa
sudah biasa melakukan budidaya menurut arah lereng (dari atas ke bawah) dengan
melakukan peralatan tangan seperti cangkul. Menurut Arsyad, (2010) pengolahan
tanah menurut kontur lebih efektif jika diikuti dengan penanaman menurut kontur,
yaitu barisan tanaman yang diatur searah kontur. Keuntungan utama pengolahan
menurut kontur adalah terbentuknya penghambat aliran permukaan yang
meningkatkan penyerapan air oleh tanah dan menghindari pengangkutan tanah.
4.3.2 Teras Bangku
Teras bangku adalah timbunan tanah yang dibuat melintang atau memotong
kemiringan lereng dengan cara menggali tanah pada lereng dan meratakan tanah
di bagian bawah sehingga terjadi suatu deretan tangga atau bangku (Arsyad,
2010). Berdasarkan pengamatan dilapangan, metode konservasi tanah dengan
bentuk teras bangku banyak ditemukan pada penggunaan lahan berupa sawah
seperti yang terlihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Teras Bangku pada Penggunaan Lahan Sawah
28
Hasil pengamatan terhadap penerapan teknik konservasi tanah yang
umumnya berupa teras bangku dapat dilihat pada Gambar 5. Teras bangku seperti
ini sudah diterapkan oleh masyarakat secara turun temurun karena mereka sadar
bahwa cara seperti itu dilakukan agar tidak mudah tererosi. Hal ini sejalan dengan
pernyataan Arsyad (2010) tentang efektifitas teras bangku sebagai pengendali
erosi dan akan semakin meningkat efektifitasnya bila ditanami dengan tanaman
penguat teras. Selain itu rerumputan yang ditanam pada pematang sawah juga
dapat meningkatkan efektifitas teras bangku karena dapat memperkecil daya
tumbuk butiran hujan. Pada musim kemarau masyarakat mengganti pola tanam
padi pada areal persawahan tersebut dengan pola tanam palawija (jagung, umbi-
umbian dan kacang-kacangan). Hal ini dilakukan guna meningkatkan pendapatan
ekonomi petani pada pergantian musim dan lahan masyarakat tetap produktif.
4.3.3 Saluran Drainase
Saluran drainase yang teridentifikasi di lapangan dibuat searah dengan
lereng. Pembuatan saluran drainase tersebut merupakan salah satu usaha petani
untuk membuang air lebih dari permukaan tanah sehingga tidak menggenangi
tanah secara berlebihan yang dapat merugikan tanaman sehingga tanah tersebut
dapat difungsikan secara optimal seperti yang terlihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Saluran drainase
Sesuai yang terlihat pada Gambar 6 kondisi saluran drainase yang
diidentifikasi di lapangan sudah baik untuk mencegah terjadinya erosi karena
sudah banyak terlihat tanaman penguat di tepi saluran drainase. Penerapan
drainase di lokasi penelitian dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya
erosi karena sudah memiliki tanaman penguat tepi di saluran drainase. Tanaman
29
penguat akan menyebabkan tanah-tanah pada tepi saluran tidak tererosi karena
adanya akar yang dapat mengikat partikel-partikel tanah serta bagian tanaman lain
yang dapat mengurangi kecepatan aliran.
4.4 Tipologi Masyarakat
Untuk menganalisis data hasil penelitian tentang penerapan teknik
konservasi tanah dan air dalam kaitannya dengan tipologi masyarakat di Desa
Bonto Somba dapat dianalisis berdasarkan latar belakang sosial ekonomi
responden. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu uji chi square (X2)
untuk mengetahui hubungan antara penerapan teknik konservasi tanah dan air
dengan tipologi masyarakat
4.4.1 Uji Chi Square Hubungan antara Penerapan Teknik Konservasi Tanah
dan Air
a. Umur Petani
Umur merupakan salah satu karakteristik yang sangat berpengaruh terhadap
semangat kerja dan meningkatkan produktifitas bekerja, kemampuan nalar dalam
menerima perkembangan teknologi pertanian. Adapun penggolongan umur
responden dapat dibagi menjadi 3 kelompok yang didasarkan pada umur produktif
dan non produktif, umur produktif dibagi lagi menjadi umur produktif muda dan
umur produktif tua. Kelompok umur produktif muda adalah umur 15-34 tahun.
Kelompok umur produktif tua adalah umur 35-54 tahun. Kelompok umur non
produktif adalah umur 55 tahun ke atas (Radja R, 2000) dalam Gautama (2007).
Berdasarkan informasi pada Tabel 2, umur respoden di Desa Bonto Somba
yang bekerja di sektor pertanian (petani) berada pada kisaran umur 35-54 tahun
atau dapat digolongkan ke dalam kisaran produktif tua untuk bekerja.
30
Tabel 2. Klasifikasi responden berdasarkan umur di Desa Bonto Somba
Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 30 responden 9 orang atau 30%
memiliki umur yang produktif muda, 19 orang atau 63% produktif tua dan 2 orang
atau 7 % memiliki umur non produktif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
masyarakat di Desa Bonto Somba berada pada kisaran umur produktif tua.
Analisis hubungan tipologi masyarakat dengan teknik konservasi tanah
dan air yang diterapkan berdasarkan tingkatan umur dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Tabel Kontingensi antara penerapan Teknik KTA dan umur petani
Umur
Teknik Konservasi Tanah dan Air
Total Persentase (%) Vegetatif Mekanik
Vegetatif dan
Mekanik
15-34 4 3 2 9 30
>35 2 14 5 21 70
Jumlah 6 17 7 30 100
Berdasarkan Tabel 3 selanjutnya diuji dengan uji chi square (X2) untuk
mengetahui taraf signifikan antara umur petani dengan penerapan teknik
konservasi tanah dan air. Uji Chi Square (X2) dilakukan dalam taraf nyata (α) =
0,05 pada derajat bebas = 2 sehingga diperoleh hasil X2 hitung = 5,083
(Lampiran 5) yang lebih kecil dari X2 tabel yaitu sebesar 5,99 (Lampiran 6). Dari
hasil analisis ini menunjukkan bahwa hipotesis null diterima yang berarti tidak
ada hubungan yang nyata antara umur petani dan penerapan teknik konservasi
tanah dan air. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa yang menerapkan teknik
konservasi tanah dan air antara umur produktif muda dan yang produktif tua
dianggap sama. Hal ini menunjukkan bahwa umur petani tidak berpengaruh
terhadap penerapan teknik konservasi tanah dan air dilokasi penelitian. Menurut
Ekasari (2014) tidak ada hubungan yang nyata antara umur petani dengan
penerapan teknik Konservasi Tanah dan Air karena anggota keluarga biasanya
No Umur Jumlah (orang) Persentase (%)
1. produktif muda 15-34 9 30
2. produktif tua 35-54 19 63
3. non produktif > 55 2 7
Jumlah 30 100
31
mencari pekerjaan di luar daerahnya yang mereka anggap yang dapat memberi
sejumlah pendapatan yang layak dibanding jika mereka mengolah lahan. Berbeda
dengan penelitian Lesmana, dkk (2011) yang mengatakan bahwa umur akan
mempengaruhi kemampuan fisik bekerja dan cara berpikir responden. Umur
yang lebih muda biasanya cenderung lebih agresif dan lebih dinamis dalam
berusaha bila dibandingkan dengan umur yang lebih tua. Disamping itu, umur
juga mempengaruhi kinerja responden dalam mengelola usaha taninya.
b. Pendidikan Formal
Hasil pengamatan terhadap tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bonto
Somba diperlihatkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Tipologi masyarakat berdasarkan pendidikan formal
No. Parameter Jumlah (orang) Persentase (%)
1. Tidak Tamat SD 26 87
2. SD 3 10
3. SMP - -
4. SMA - -
5. Perguruan Tinggi 1 3
Jumlah 30 100
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden yang
diwawancarai terdapat 26 orang atau 87% yang tidak tamat SD, tiga orang atau
10% yang berpendidikan tamat SD dan hanya satu orang atau 3% yang
berpendidikan tinggi (S1). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknik
konservasi tanah dan air dengan tipologi masyarakat berlatar belakang pendidikan
tidak berkaitan langsung terhadap pendidikan petani responden. Rata-rata
responden yang diwawancarai telah melakukan teknik konservasi tanah dan air
secara turun menurun dan juga berdasarkan pengalaman yang didapatkan dari
perilaku masyarakat petani di desa lain.
Pendidikan khususnya pendidikan formal merupakan modal yang sangat
berharga untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang layak, pendidikan juga
sangat berpengaruh pada pola kehidupan setiap individu, baik cara berfikir dan
32
bersikap maupun dalam hal penggunaan peralatan yang berteknologi canggih
mayoritas pendidikan petani adalah tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Hal ini
disebabkan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Bonto Somba belum
memadai terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan hanya terdapat satu sekolah
(SD) yang ada di Dusun Bonto-Bonto yang berjarak kurang lebih 20 km dari
Dusun Cindakko dan Dusun Bara dengan akses jalan yang tidak bisa dijangkau
roda empat bahkan roda dua sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor
rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas
turut menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki petani.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan pengetahuan yang
dimiliki masyarakat juga rendah. Hal ini sangat berkaitan terhadap pekerjaan yang
dimiliki masyarakat di Desa Bonto Somba yang sebagian besar bekerja sebagai
petani. Pengetahuan yang sangat minim menyebabkan masyarakat hanya
mengelolah lahan yang dimiliki secara turun temurun atau secara tradisional,
sehingga hasil yang diperoleh juga sangat minim. Pendidikan merupakan hal yang
paling penting dan mendasar dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dalam rangka menghadapi era globalisasi dan
perkembangan teknologi. Pendidikan memiliki peranan penting dalam
menciptakan tenaga-tenanga yang terampil dalam pembangungan khususnya
pembangunan di sektor pertanian.
c. Penghasilan/pendapatan
Pada umumnya masyarakat di Desa Bonto Somba bekerja di sektor
pertanian (petani) yang merupakan sumber penghasilan utama. Di samping itu
mereka juga mempunyai penghasilan tambahan dari pekerjaan sebagai buruh
bangunan dan ada juga yang bekerja pada industri pengolahan gula aren secara
tradisional. Untuk lebih jelasnya data penghasilan masyarakat petani di Desa
Bonto Somba dapat disajikan pada Tabel 5.
33
Tabel 5. Perincian responden berdasarkan penghasilan/pendapatan
No. Pendapatan/bulan Jumlah
(orang) Persentase (%)
1. < 1.500.000 23 77
2. 1.500.000 – 2.500.000 5 17
3. > 2.500.000 2 6
Jumlah 30 100
Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 30 responden 23 orang atau 77%
berpenghasilan rata-rata dibawah Rp.1.500.000 per bulan, lima orang atau 17%
yang berpendapatan Rp 1.500.000- 2.500.000 dan selebihnya 2 orang atau 6%
yang berpengasilan di atas Rp. 2.500.000,-. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa sebagaian besar masyarakat di Desa Bonto Somba masih berada pada
golongan berpendapatan rendah.
Analisis hubungan tipologi masyarakat dengan teknik konservasi tanah dan
air yang diterapkan berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Tabel Kontingensi antara penerapan Teknik KTA dan pendapatan
Pendapatan
Teknik Konservasi Tanah dan Air
Total Vegetatif Mekanik
Vegetatif
dan Mekanik
Rendah 4 14 5 23
Tinggi 2 3 2 7
Jumlah 6 17 7 30
Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa hasil analisis dengan menggunakan
chi square (X2) dalam taraf nyata α = 0,05 dan derajat bebas = 2 diperoleh hasil
X2 tabel pada derajat bebas = 2 diperoleh hasil X2 hitung = 0,742 (Lampiran 5)
sedangkan X2 tabel sebesar 5,99 maka hasilnya dinyatakan tidak signifikan pada
taraf signifikasi 5% dengan demikian hipotesis null diterima sehingga
disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata antara pendapatan petani
dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata
antara pendapatan petani dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air. Hal
34
ini terjadi karena petani yang berpenghasilan rendah maupun tinggi masing-
masing sama dalam menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa pematang
sawah. Menurut penelitian Ekasari (2014), mengatakan bahwa pendapatan petani
dalam kaitannya dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air menunjukkan
bahwa faktor pendapatan petani antara petani yang berpendapatan rendah dan
berpendapatan tinggi tidak jauh berbeda. Faktor pendapatan petani tidak
berpengaruh terhadap penerapan teknik konservasi.
d. Jumlah Tanggungan Keluarga
Hasil penelitian terhadap jumlah tanggungan keluarga petani dalam hal
penerapan teknik konservasi tanah dan air disajikan pada Tabel 7. Tabel tersebut
menunjukkan banyaknya jumlah tanggungan keluarga dari responden. Dapat
dilihat sebagian besar responden memiliki jumlah tanggungan keluarga yaitu 3-4
orang.
Tabel 7 Sebaran responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga
No. Tanggungan Keluarga Jumlah Persentase (%)
1. 1 – 2 orang 6 20
2. 3 – 4 orang 20 67
3. > 5 orang 4 13
Jumlah 30 100
Hubungan petani dengan tanggungannya secara umum adalah hubungan
sebagai suami/istri dan anak. Responden yang tidak memiliki tanggungan
disebabkan karena belum berumah tangga, baru membangun rumah tangga, atau
telah ditinggal mati. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7 bahwa dari 30 orang
responden terdapat 20 orang atau 67% yang menanggung biaya hidup 3-4 orang, 6
orang atau 20% yang menanggung 1-2 orang dan 4 orang atau 13% yang
menanggung di atas 5 orang. Jumlah tanggungan keluarga menunjukkan besarnya
beban petani yang harus dipikul dalam hal pembiayaan hidup sehari-hari. Selain
itu, berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga. Menurut
Gafur (2009), semakin besar jumlah tanggungan keluarga yang ditanggung petani,
maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi
35
kebutuhan sehari-hari, namun di sisi lain akan menghemat jumlah tenaga kerja
dalam pengelolaan usaha tani di luar keluarga, apabila tanggungan tersebut dapat
membantu mengelola usaha taninya.
Analisis hubungan tipologi masyarakat dengan teknik konservasi tanah dan
air yang diterapkan berdasarkan tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Tabel Kontingensi antara penerapan Teknik KTA dan jumlah tanggungan
keluarga
Jumlah Tanggungan
Keluarga
Teknik Konservasi Tanah dan Air
Total Vegetatif Mekanik
Vegetatif
dan Mekanik
Rendah 3 2 1 6
Tinggi 3 15 6 24
Jumlah 6 17 7 30
Berdasarkan hasil penelitian terhadap jumlah tanggungan keluarga petani
dalam kaitan dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air selanjutnya
dilakukan analisis uji chi square untuk mengetahui tingkat signifikan antara
jumlah tanggungan keluarga dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air.
Analisis pada Tabel 8 dengan menggunakan uji Chi Square (X2). Uji Chi Square
(X2) dalam taraf nyata (α) = 0,05 dan derajat bebas = 2 diperoleh hasil X2 hitung
= 4,237 (Lampiran 5) lebih kecil dari X2 tabel yaitu sebesar 5,99 (Lampiran 6).
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa hipotesis null diterima yang berarti
tidak ada hubungan yang nyata antara umur petani dan penerapan teknik
konservasi tanah dan air. Hal ini disebabkan karena jumlah tanggungan keluarga
responden bervariasi, mulai dari yang memiliki tanggungan keluarga sedikit
hingga banyak. Tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor yang
mendorong petani untuk berusaha dalam bertani. Menurut Lesmana, dkk (2011)
mengatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga merupakan aset tenanga kerja
yang dapat dimanfaatkan petani dalam mengelola usaha taninya. Besarnya jumlah
tanggungan keluarga akan mendorong petani bersifat dinamis dalam mencoba
menerapkan suatu teknologi untuk meningkatkan produktivitas guna memenuhi
kebutuhan hidup.
36
e. Luas Lahan Garapan
Luas lahan garapan yang dimiliki petani untuk berusaha tani di Desa Bonto
Somba rata-rata mengelola sawah kurang dari satu hektar (Tabel 9). Keterbatasan
lahan pertanian disebabkan karena wilayah tersebut berada di dataran tinggi.
Selain itu, akses jalan di Desa Bonto Somba kurang memadai sehingga sawah
yang di kelola tidak sampai satu hektar.
Tabel 9. Perincian responden berdasarkan luas lahan garapan
No. Luas Lahan Garapan Jumlah Persentase (%)
1. < 0.50 ha 21 70
2. 0.50 – 1 ha 7 23
3. > 1 ha 2 7
Jumlah 30 100
Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa dari 30 responden terdapat 21
orang atau 70% yang luas lahan garapannya <0.50 ha, 9 orang atau 30% luas
lahan garapannya > 0.50 ha. Analisis hubungan tipologi masyarakat dengan teknik
konservasi tanah dan air yang diterapkan berdasarkan luas lahan garapan dapat
dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Tabel Kontingensi antara penerapan Teknik KTA dan luas lahan
garapan
Luas lahan garapan
Teknik Konservasi Tanah dan Air
Total Vegetatif Mekanik
Vegetatif dan
Mekanik
Rendah 3 14 4 21
Tinggi 3 3 3 9
Jumlah 6 17 7 30
Berdasarkan hasil penelitian terhadap luas lahan garapan dalam kaitan
dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air selanjutnya dilakukan analisis
uji chi square untuk mengetahui tingkat signifikan antara tanggungan keluarga
dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air. Hasil analisis dengan
menggunakan uji Chi Square (X2), dalam taraf nyata (α) = 0,05 dan derajat bebas
= 2 diperoleh hasil X2 hitung = 2,926 (Lampiran 5) lebih kecil dari X2 tabel
37
sebesar 5,99 (Lampiran 6). Dari analisis uji Chi Square (X2) menunjukkan bahwa
hipotesis null diterima yang berarti tidak ada hubungan yang nyata antara luas
lahan garapan dengan penerapan teknik konservasi tanah dan air. Hal ini
menunjukkan bahwa luas lahan yang digarap baik lahan berkategori luas atau
sempit sama sekali tidak berpengaruh bagi petani dalam menerapkan teknik
konservasi tanah dan air. Petani yang memiliki lahan sempit menerapkan teknik
konservasi tanah dan air yang sama dengan petani yang memiliki lahan luas.
Luas lahan garapan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat
penting dalam pengembangan usaha tani. Luas lahan berdampak pada upaya
transfer dan penerapan teknologi. Pengetahuan dan keterampilan petani yang
diperoleh melalui kegiatan pelatihan dapat diterapkan dan dikembangkan oleh
petani di lahannya. Lahan yang cukup luas akan memudahkan petani dalam
menerapkan teknologi tanpa takut akan adanya resiko kegagalan, hal ini terkait
pula dengan biaya produksi yang dikeluarkan, output yang dihasilkan, serta
pendapatan yang diperoleh petani (Gafur 2009).
38
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Teknik konservasi tanah dan air yang di terapkan di Desa Bonto Somba
berupa metode vegetatif diantaranya tanaman penutup tanah, kebun
campuran dan pekarangan, metode mekanik yaitu teras bangku dan
pengolahan tanah dan tanaman menurut kontur.
2. Secara umum masyarakat di Desa Bonto Somba tidak tamat SD (87%),
berpenghasilan <Rp.2.500.000/bulan (94%), memiliki tanggungan keluarga
antara 3-4 orang (67%) dan memiliki luas lahan garapan <1 ha.
3. Hasil uji chi square menunjukkan tidak terdapat hubungan yang nyata antara
penerapan teknik konservasi tanah dan air dengan unsur tipologi sosial
ekonomi masyarakat yang meliputi umur, pendidikan, tingkat pendapatan,
luas lahan garapan dan jumlah tanggungan keluarga.
5.2. Saran
Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penerapan teknik
konservasi tanah dan air berbasis tipologi masyarakat maka disarankan
pemerintah (instansi) terkait senantiasa memberikan bimbingan arahan dan
penyuluhan tentang arti pentingnya penerapan teknik konservasi tanah dan air
agar mereka mempunyai pemahaman dalam hal penerapannya. Dalam upaya
meningkatkan pendapatan petani diharapkan dapat melakukan kegiatan atau
penambahan jenis tanaman dalam hal ini agroforestry yang juga dapat berfungsi
sebagai konservasi.
.
39
DAFTAR PUSTAKA
Agus F. A Abdurrachman, A. Rachman, S.H. Talaohu, A. Dariah, B.R.
Prawiradiputra, B. Hafif, dan Wiganda S. 1999. Teknik Konservasi Tanah
dan Air. Sekretariat Tim Pengendali Bantuan Penghijauan dan Reboisasi
Pusat. Jakarta
Arsyad, S. 2010. Konservasi Tanah dan Air. Institut Pertanian Bogor Press.
Bogor
Asdak, C. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.Gadjah Mada
University Press. Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik. 2016. Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2011-2015.
Jakarta.
Dapertemen Kehutanan. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-
DAS). Jakarta
Ekasari, F.Y. 2014. Hubungan Penerapan Konservasi Tanah dan Air dengan
Faktor Sosial Ekonomi di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi
moncong, Kabupaten Gowa. Fakultas Kehutanan. UNHAS.
Gafur S. 2009. Motivasi petani dalam menerapkan taknologi produksi kakao
(kasus kecamatan sirenja kabupaten Donggala Sulawesi Tengah) [tesis].
Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Gautama, Iswara. 2007. Studi Sosial Ekonomi Masyarakat pada Sistem
Agroforestry Di Desa Lasiwala Kabupaten Sidrap. Jurnal Hutan dan
Masyarakat. 2( 3 ): 319 – 328.
Handoko, T. 2001. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta:
BPFE.
Jariyah, Nur Ainun. 2014. Karakteristik Masyarakat Sub DAS Pengkol dalam
Kaitannya dengan Pengelolaan DAS. Balai Penelitian Teknologi
Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. JURNAL Penelitian Sosial
dan Ekonomi Kehutanan Vol. 11 No. 1 Maret 2014, Hal. 59 – 69
Junaidi, E. 2009.Peningkatan Produktivitas Hutan Rakyat Melalui Penerapan
Teknik Konservasi Tanah Lokal Spesifik (Studi Kasus pada DAS
Cisadene. Balai Penelitian Kehutanan Ciamis.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 1996. Jakarta: Balai Pustaka 958
40
Kartasapoetra, A. G., dan Sutedjo, M.M. 2010. Teknologi Konservasi Tanah dan
Air. Edisi Kedua. Cetakan Keenam. Rineka Cipta. Jakarta
Kasdi Subagyono, Setiari Marwanto, dan Undang Kurnia. 2003. TEKNIK
KONSERVASI TANAH SECARA VEGETATIF. Seri Monograf No. 1.
Sumber Daya Tanah Indonesia. BALAI PENELITIAN TANAH. Pusat
Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
Koentjaraningrat. 1981. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta:
Gramedia.
Lesmana, D., Ratina R., Jumriani.2011. Hubungan Presepsi Dan Faktor-Faktor
Sosial Ekonomi Terhadap Keputusan Petani Mengembangkan Pola
Kemitraan Petani Plama Mandiri Kelapa Sawit di Kelurahan Bantuas
Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Universitas Mulawarman.
Samarinda. Vol.8 No.2 Hal 10-13.
Mawardi. 2013. Analisis Faktor Konservasi Kombinasi Teras Nikolas dan
Tanaman Kacang (Faktor CP untuk Teras Nikolas + Kacang Tanah).
Jurnal Wahan Teknik Sipil Vol. 18 No. 2.
Monsher, A.T. 1991. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. CV Yasaguna.
Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai. Jakarta.
Prasantyawati, W.A.D. 2014. Aspek Sosial Ekonomi Teknik Konservasi Tanah
dan Air Studi Kasus Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Bogor.
Institut Pertanian Bogor. Bogor
Pratiwi dan Nahendra, B.H. 2012. Pengaruh Penerapan Teknik Konservasi Tanah
Terhadap Pertumbuhan Pertanaman Mahoni (Swietenia macrophylla King
di Hutan Penelitian Carita. Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi.
Bogor
Presiden Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Sekretariat RI. Jakarta
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
Rijal, S., Saleh, M., Jaya, I., & Tiryana, T. (2016). Deforestation Profile of
Regency Level in Sumatera. Internation Jurnal of Science, 385-402.
Sari, Resky Amalia. 2015. Identifikasi Teknik Konservasi Tanah dan Air di
Dusun Benteng Rajayya Desa Bilalang Kecamatan Manuju (DAS
41
Jeneberang) Kabupaten Gowa.Skripsi.Fakultas Kehutanan.Universitas
Hasanuddin.
Sudaryono. 2002. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu, konsep
Pembangunan Berkelanjutan. BPPT. Jakarta
Sukartaatmadja. 2004. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press. Bogor.
Suripin. 2004. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Edisi Kedua. Penerbit
ANDI. Yogyakarta.
Susilawati, 2006. Konservasi Tanah dan Air di Daerah Semi Kering Propinsi
Nusa Tenggara Timur. Jurnal Teknik Sipil Vo. III No. 1
Syah, M. (2006). Psikologi Belajar. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
Triwanto J, 2012. Konservasi Lahan Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai. UMM Press. Malang
Wajudi, 2014. Konservasi Tanah Air. www.ksdasulsel.org/konservasi/139-
konservasi-tanah-air. [Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017].
Winarto, B. 2006. Kamus Rimbawan. Yayasan Bumi Indonesia Hijau. Bogor
45
Lampiran 3. Daftar Kuisioner
DAFTAR PERTANYAAN
(QUISIONER)
“STUDI PENERAPAN TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR
BERBASIS TIPOLOGI MASYARAKAT DI DESA BONTO SOMBA HULU
DAS MAROS‟
RESPONDEN
KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
BULAN/TAHUN :
46
A. Identitas responden
1. Nama responden :
2. Latar belakang responden :
a. Nama responden :
b. Umur :
c. Jenis kelamin : laki-laki/perempuan
d. Agama : Islam/Kristen protestan/46ending katolik/
e. Tingkat pendidikan*:
(1) Belum pernah sekolah
(2) SD (Tamat / Tidak Tamat, s.d kelas…....................)
(3) SMP (Tamat / Tidak Tamat, s.d kelas…....................)
(4) SMA (Tamat / Tidak Tamat, s.d kelas…....................)
(5) Lainnya (sebutkan) …......... (Tamat / Tidak Tamat, s.d kelas…....)
f. Suku bangsa :
g. Pekerjaan :
- Pokok
- Sampingan `
h. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan
(1) Tidak (2) Ya
Jika jawaban YA, sebutkan jenis pelatihan atau penyuluhan usaha tani
yang pernah Bapak/Ibu ikuti
Nama Pelatihan/Penyuluhan Tahun Penyelenggara Lamanya
(hari/jam) Ket
B. informasi mengenai keluarga
No. Nama Jumlah anggota
keluarga
Keterangan
Bekerja sendiri Sekolah Lainnya*
1 Laki-laki dewasa
(>12 tahun)
2 Perempuan dewasa
(>12 tahun)
3 Anak laki-laki
(5-12 tahun)
4 Anak perempuan
(5-12 tahun)
5 Balita
Jumlah
47
Catatan : - keluarga adalah orang tinggal serumah maupun tidak serumah tetapi
secara penuh dibiayai oleh kepala keluarga.
- *a) membantu usaha, b) tidak bekerja
C. Tingkat Penguasaan Lahan
No. Jenis Lahan Luas (Ha) Status Jenis
Komoditi
Pola Tanam
(Semusim)
1 Sawah
2 pengembalaan
3 Sayuran
4 dll
Status : Milik Sendiri, Gadai, Garap, Sewa.
D. Usaha tani pertahun
Berapa luas lahan usaha tani milik Bapak/Ibu?
Jenis lahan : Pekarangan/kebun/kawasan hutan/ sawah
Yang digarap sendiri …........... ha
Yang digarap orang lain …...........ha
Status lahan : Hak milik/Sewa/Bagi hasil
Berapa luas lahan milik orang lain yang Bapak/Ibu garap? …........ ha
Komoditas dan varietas apa yang di tanam di lahan milik Bapak/Ibu?
No Komuditas Varietas Masa Tanam
48
E. Penerimaan responden
No. Sumber
Pendapatan
Produksi dan nilai produksi
Produksi (Kg/Ha) Harga
(Rp/kg)
Nilai produksi
Area
agroforestri
Luar
agroforestri
Area
agroforestri
Luar
agroforestri
1. Pertanian
- Padi
- Jagung
- Ubi Kayu
- …….
2. Kehutanan
- Kayu
- Non Kayu
3. Non pertanian
- Jual-jualan
- Buruh
- ……
1. Apakah Bapak/Ibu mengenal cara-cara konservasi tanah dan air di usaha tani
?
(1) Tidak (2) Ya
Jika jawaban YA, sebutkan cara-cara konservasi tanah dan air yang Bapak/Ibu
ketahui
…................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.........................
2. Apa kegunaan konservasi tanah dan air yang anda lakukan ?
3. Apa hambatan yang anda alami dalam menerapkan teknik konservasi tanah
dan air
4. Apa alasan anda menerapkan teknik konservasi tersebut?
49
Lampiran 4. Tabel Tipologi Masyarakat Berdasarkan Tipologi Sosial Ekonomi
No. Nama Umur Penghasilan/bulan Pendidikan Luas
lahan AK Jenis Tanaman Tekmik KTA
1 Dg Rowa 42 1.450.000 Tidak Tamat SD 0, 55 4
Rumput – Padi –
Jati,gamal,bambu,jambu
monyet,jagung
Tanaman Penutup Tanah, teras
bangku, Saluran air, Kebun Campuran
2 Nassa 34 1.160.000 SD 0, 42 3 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
3 Darman 46 1.175.000 SD 0, 30 2 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
4 Ansar 38 985.000 Tidak Tamat SD 0, 30 3 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
5 Tarrin 32 1.250.000 Tidak Tamat SD 0, 40 2 Jagung,jambu,Jati, gamal,pisang Kebun Campuran
6 Marzuki 32 850.000 Tidak Tamat SD 0, 25 4 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
7 Dg Ati 40 900.000 Tidak Tamat SD 0, 30 5 Jagung,pisang,sukun,ubi
kayu,pepaya,jati Kebun Campuran
8 Dg Nai 52 985.000 Tidak Tamat SD 0, 28 2 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
9 Abbas 43 1.350.000 Tidak Tamat SD 0, 40 3 Rumput, padi, Jati,pisang,jambu
biji,mangga
Tanaman penutup tanah, teras
bangku, saluran air, Kebun Campuran
10 Dg Masso 35 1.125.000 Tidak Tamat SD 0, 3 5 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
11 Raju 55 1.560.000 Tidak Tamat SD 0, 6 4 Pisang, ubi Kayu,sukun, jagung,
nangka, gamal Kebun campuran
12 Dg Japa 49 1.450.000 Tidak Tamat SD 0, 40 3 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
13 Firman 34 1.300.000 Tidak Tamat SD 0, 50 3 Jagung Pengolahan tanah menurut kontur
14 Dg Usman 47 1.200.000 SD 0, 2 4 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
15 Mulawarman 39 2.550.000 PT 0,80 3 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
16 Jupri 56 1.700.000 Tidak Tamat SD 0, 75 3 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
50
17 Rudy 37 720.000 Tidak Tamat SD 0, 26 3 Jagung Pengolahan tanah menurut kontur
18 Sapri 34 1.500.000 Tidak Tamat SD 0, 55 2 Pisang,gamal,jati,jambu biji Kebun campuran
19 Lukman 38 1.900.000 Tidak Tamat SD 0, 60 3 Rumput- Padi, Pisang, ubi kayu,
coklat, pepaya
Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku, Pekarangan
20 Minna 40 1.150.000 Tidak Tamat SD 0, 40 5 Rumput, padi, Pisang, ubi kayu,
mangga, jati
Tanaman penutup tanah, teras
bangku, saluran air, Pekarangan
21 Massa 37 900.000 Tidak Tamat SD 0, 25 3 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
22 Jahu 51 1.850.000 Tidak Tamat SD 0, 39 4 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
23 Rusli 39 950.000 Tidak Tamat SD 0, 4 3 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
24 Rannu 30 850.000 Tidak Tamat SD 0, 25 5 Jambu biji,jagung,pisang,ubi
kayu Pekarangan
25 Rahman 46 1.350.000 Tidak Tamat SD 0, 30 4 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
26 Mardin 39 920.000 Tidak Tamat SD 0, 23 4 Rumput – Padi Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku
27 Ina 20 985.000 Tidak Tamat SD 0, 20 3 Rumput – Padi , jagung, ubi
kayu, pisang, sukun
Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku, Pekarangan
28 Arman 29 1.250.000 Tidak Tamat SD 0, 20 2 Rumput – Padi, pisang, ubi
kayu, sukun, nangka, jagung
Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku, pekarangan
29 Dg Nassa 33 1.165.000 Tidak Tamat SD 0, 50 2 Pisang, ubi kayu, coklat, pepaya Pekarangan
30 Supardi 50 2.650.000 Tidak Tamat SD 1,5 4 Rumput – Padi, jabon, coklat,ubi
kayu,pisang, jagung
Tanaman Penutup tanah, saluran air,
teras bangku, kebun campuran
51
Lampiran 5. Perhitungan Uji Chi Square (X2)
X2
= ∑
Penentuan Nilai Frekuensi observasi dan nilai frekuensi ekspektasi
Uji chi square antara Penerapan Teknik KTA dengan umur petani
Fo1 = 4, Fe1 = = 1,8 Fo4 = 2, Fe4 = = 4,2
Fo2 = 3, Fe2 = = 5,1 Fo5 = 14, Fe5 = = 11,9
Fo3 = 2, Fe1 = = 2,1 Fo6 = 5, Fe6 = = 4,9
X2 = + + + +
+
= 2,69 + 0,864 + 0,005 + 1,152 + 0,370 + 0,002
= 5,083
Uji Chi Square antara Penerapan Teknik KTA dengan Pendapatan
Fo1 = 4, Fe1 = = 4,6 Fo4 = 2, Fe4 = = 1,4
Fo2 = 14, Fe2 = = 13 Fo5 = 3, Fe5 = = 3,96
Fo3 = 5, Fe3 = = 5,3 Fo6 = 2, Fe6 = = 1,63
X2 = + + + +
+
= 0,078 + 0,076 + 0,016 + 0,257 + 0,232 + 0,083
=0,742
52
Uji Chi Square antara Penerapan Teknik KTA dengan Luas Lahan Garapan
Fo1 = 3, Fe1 = = 4,2 Fo4 = 3, Fe4 = = 1,8
Fo2 = 14, Fe2 = = 11,9 Fo5 = 3, Fe5 = = 5,1
Fo3 = 4, Fe3 = = 4,9 Fo6 = 2, Fe6 = = 2,1
X2 = + + + +
+
= 0,342 + 0,370 + 0,165 + 0,8 + 0,864 + 0,385
= 2,926
Uji Chi Square antara Penerapan Teknik KTA dengan Jumlah Tanggungan
Keluarga
Fo1 = 3, Fe1 = = 1,2 Fo4 = 3, Fe4 = = 4,8
Fo2 = 2, Fe2 = = 3,4 Fo5 = 15, Fe5 = = 13,6
Fo3 = 1, Fe3 = = 1,4 Fo6 = 6, Fe6 = = 5,6
X2 = + + + +
+
= 2,7 + 0,576 + 0,114 + 0,675 + 0,144 + 0,028
= 4,237
54
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian
Mengidentifikasi jenis tanaman yang ada di pekarangan
Wawancara bersama petani