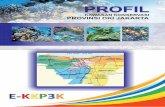Konservasi tanaman matoa (Pometia pinnata Forst) menurut ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Konservasi tanaman matoa (Pometia pinnata Forst) menurut ...
Prosiding Seminar Nasional V 2019 Peran Pendidikan dalam Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
ISBN 978-602-5699-83-2; PUBLIKASI ONLINE 5 MARET 2020
76
Konservasi tanaman matoa (Pometia pinnata Forst) menurut tradisi Suku Kurudu Di Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen-Papua Moses Gotlief Rumperiai Universitas Muhammadiyah Malang
Penulis koresponden Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang Email: [email protected]
ABSTRAK
Salah satu keanekaragaman hayati flora Papua adalah tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.). Saat ini muncul keprihatinan tentang berkurangnya bahkan musnahnya plasma nutfah tanaman matoa di Papua. Salah satu penyebab kelangkaan tanaman matoa adalah pola pengambilan buah matoa atau panen buah matoa dengan cara memotong cabang-cabangnya bahkan menebang pohonnya. Untuk mencegah kepunahan tanaman matoa, diperlukan upaya konservasi tanaman matoa. Jauh sebelum konservasi sumber daya alam hayati (KSDAH) dipelajari atau diaplikasikan sebagai ilmu pengetahuan moderen, leluhur suku Kurudu di Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua telah memberlakukan tradisi spesifik tentang perlindungan dan pelestarian tanaman matoa. Tradisi ini menjadi faktor utama yang membedakan kualitas buah matoa kurudu dengan buah matoa lainnya di seluruh kawasan Papua maupun di luar Papua. Bagaimana tradisi suku Kurudu tersebut ? Tulisan ini mengulas tentang konservasi tanaman matoa menurut tradisi suku Kurudu, termasuk ancaman budaya asing terhadap pergeseran nilai-nilai luhur dalam tradisi ini. Diharapkan melalui tulisan ini setiap pihak yang berkompeten dapat memelihara tradisi suku Kurudu demi konservasi tanaman matoa di Pulau Kurudu.
Kata kunci: Matoa Punah Kurudu Tradisi konservasi
Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Malang
PENDAHULUAN Belakangan ini, Keanekaragaman
Hayati (Kehati) di dunia menjadi hal yang sangat menarik. Kehati di dunia mencakup jumlah spesies yang sangat banyak dan berada dalam komunitas biologi yang kompleks, tiap spesies menampilkan variasi genetik yang sangat kaya. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kehati, menempati urutan ketiga sesudah Brazil dan Zaire. Salah satu kekayaan alam adalah tumbuh-tumbuhan (flora). Diperkirakan sekitar 30.000 spesies tumbuhan berbunga berada di hutan tropis Indonesia (Zurriyati dan Dahono, 2016: 12). Dari 30.000 spesies tumbuhan Indonesia, 6.201 spesies dicatat pada tahun 2001 oleh Rukmana dan Oesman sebagai tanaman buah-buahan unggulan. Jumlah ini membawa Indonesia
menjadi salah satu negara yang kaya akan plasma nutfah (germ plasm) tanaman buah. Sayang sekali sebagian buah-buahan tersebut kini mulai langka. Gejala itu disebabkan antara lain oleh makin meluasnya pembangunan, kurangnya perawatan dan pengembangan maupun gangguan alami. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai usaha untuk melestarikan kekayaan tanaman buah nusantara.
Konservasi merupakan upaya pelestarian atau perlindungan terhadap sesuatu. Berkaitan dengan gangguan dan kerusakan kehati, konservasi diterjemahkan sebagai the wise use of nature resource (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana). Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (KSDAH) adalah pengelolaan sumberdaya
77
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Tujuan KSDAH adalah terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta kesinambungan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.) merupakan tanaman buah asli Papua. Pernyataan “matoa tanaman asli papua” telah ditulis 41 tahun lalu dalam literatur ilmiah tahun 1978 karya seorang botanis bernama Womersley, dan dikutip dalam artikel berjudul “Upaya Perbanyakan Vegetatif Tanaman Matoa (Pometia pinnata, Forst.) melalui Diferensiasi Kalus Kultur Jaringan Daun”, hasil penelitian tiga orang dosen biologi Universitas Cenderawasih (Linus Yhani Chrystomo, Verena Agustini dan Puguh Sujarta) tahun 1998. Tanaman matoa mempunyai buah dengan rasa dan aroma yang khas sehingga banyak digemari oleh masyarakat setempat serta laris terjual di pasaran lokal. Namun di alam tidak mudah untuk mendapatkan buah matoa matang yang siap dikonsumsi atau dijual, karena selain musim buah yang berlangsung hanya dua kali dalam setahun, pohonnya pun tinggi (sekitar 10m - 20m) sulit dan beresiko jika dipanjat, batangnya besar dengan diameter antara 60cm-100cm, bahkan letak buah di terminal ranting jauh dari jangkauan sekitar 6m - 10m sebagaimana ilustrasi di Gambar 1.
Letak buah yang sulit dijangkau ditambah pula dengan harga jual yang sangat baik di pasaran menjadi penyebab adanya praktek panen buah matoa dengan cara menebang pohon atau memangkas cabang (bukan ranting). Panen tradisional ala nomaden ini dilakukan langsung pada pohon matoa yang tumbuh liar di alam, karena masyarakat Papua tidak punya tradisi budidaya tanaman matoa. Praktek ini berlaku universal di Papua sejak leluhur hingga generasi saat ini. Tidak terhitung jumlah pohon matoa yang telah mati
ditebang. Selain penebangan untuk panen buah, penebangan juga dilakukan untuk memperoleh bahan bangunan, meubel, kayu gergajian dan kayu bakar. Praktek ini pun sudah lama berlangsung, dan belum ada praktek budidaya tanaman matoa untuk produksi kayu di kalangan masyarakat Papua. Tanaman matoa yang sering dipangkas tidak banyak menghasilkan buah. Hal ini menghambat perkembangbiakan generatif alamiah matoa. Penebangan tumbuhan matoa di alam untuk mendapatkan buah maupun untuk untuk mendapatkan kayunya, serta pemangkasan yang kontinyu menjadi faktor pendorong penurunan jumlah populasi dan ancaman kepunahan tanaman matoa di daerah asalnya (Papua).
Gambar 1. Ilustrasi pohon matoa
Bertambahnya kebutuhan manusia
yang diiringi dengan bertambahnya jumlah penduduk, mengakibatkan ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam umumnya dan kekayaan flora khususnya berkembang semakin cepat, bahkan ada kecenderungan dimanfaatkan dalam jumlah yang semakin banyak. Dampaknya, terjadi alih fungsi lahan habitat tanaman matoa secara besar-esaran dan masif menjadi lokasi pemukiman dan pembangunan infrastruktur umum.
Dewasa ini sudah timbul keprihatinan tentang berkurangnya bahkan musnahnya plasma nutfah tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.), sehingga ada gerakan ke arah untuk melakukan konservasi. Matoa (Pometia pinnata Forst.) merupakan salah satu kekayaan keanekaragaman hayati flora Nusantara
78
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
dari Papua yang perlu dijaga kelestariannya dengan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.
Suku kurudu adalah orang-orang asli yang mendiami Pulau Kurudu (Hidayah, 2015: 196), yaitu salah satu pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Yapen. Akses satu-satunya untuk datang dan pergi ke dan dari pulau Kurudu adalah melalui transportasi laut menggunakan perahu motor. Sampai saat ini belum ada penelitian ekologis terhadap kehati pulau Kurudu sehingga informasi tentang potensi flora dan fauna secara kuantitatif tidak tersedia. Menurut informasi dari Direktur WWF Region Papua, Drs. Benja Victor Mambai, M.Sc., tanggal 02 Juli 2011 bahwa sampai saat ini WWF belum memiliki data hasil penelitian spesifik tentang kehati pulau Kurudu. Informasi ini menunjukan bahwa riset kehati Pulau Kurudu belum dilakukan. Walaupun demikian Pulau Kurudu menyimpan potensi keanekaragaman hayati flora dan fauna yang melimpah tersebar di kawasan perairan lautnya sampai ke kawasan hutannya. Salah satu kekayaan hayati flora Pulau Kurudu yang sangat terkenal dan menjadi kekayaan budaya orang Kurudu adalah buah matoa (Pometia pinnata Forst.) dengan rasa khas yang selalu menjadi incaran para penggemar buah matoa di tingkat lokal, daerah, nasional, maupun internasional. Beberapa fakta empirik yang menunjukkan kualitas unggul buah matoa kurudu sehingga menjadi incaran para penggemar buah matoa di tingkat lokal, daerah, nasional, maupun internasional antara lain sebagai berikut. 1. Menurut pengakuan masyarakat kota
Serui asal Maluku, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Jawa, Kalimantan,
Sumatera, Cina, Korea, Malaysia,
bahkan orang Belanda di jaman
kolonial; bahwa buah matoa asal pulau
Kurudu memiliki rasa yang lebih baik,
lebih nikmat dan secara estetis
memuaskan jiwa lebih dari atau
berbeda rasa dengan buah matoa di
Pulau Yapen, bahkan di seluruh
kawasan Papua dan di luar Papua.
Mereka mengatakan telah berkeliling
pelosok Papua dan merasakan buah
matoa tetapi rasanya tidak sama
dengan rasa matoa Kurudu. Oleh
sebab itu bila musim buah matoa tiba
walaupun di pasar kota serui tersedia
banyak buah matoa yang dijual tetapi
mereka sangat selektif dalam membeli
buah matoa, biasanya mereka bertanya
sebelum membeli: apakah ini matoa
kurudu? Jika penjual mengatakan
‘tidak’ maka mereka tidak membeli
tetapi akan terus berkeliling sampai
menemukan matoa kurudu barulah
dibeli. Biasanya para penggemar matoa
kurudu berjaga-jaga di tempat parkir
perahu motor di mana orang Kurudu
membongkar muatan hasil panen buah
matoa yang dibawa dari Pulau Kurudu
melalui transportasi laut ke kota Serui,
sehingga buah matoa yang hendak
dijual di pasar kota terlanjur habis
diborong penggemar dan penikmatnya
sebelum tiba di pasar kota. Matoa
Kurudu yang telah dibeli biasanya
untuk konsumsi rumah tangga dan
sebagian dikirim kepada kaum
keluarga di daerah asal masing-masing
ke seantero Nusantara sebagai oleh-
oleh dari Papua, sehingga secara tidak
langsung matoa kurudu ikut
mengharumkan nama Papua di
seantero Nusantara. Tingginya minat
penggemar buah matoa kurudu
mengakibatkan munculnya fenomena
baru di kalangan pedagang buah matoa
di kota Serui, yakni untuk pelaris
biasanya para penjual
mempromosikan buah matoa
jualannya dengan nama matoa Kurudu
walaupun buah matoa yang dijual itu
bukan matoa asal Kurudu.
2. Orang-orang Korea, Cina, dan Malaysia
yang bekerja pada pabrik plywood and
sawn timber PT. Kodeco Mamberamo
dan PT. Sinar Wijaya Plywood
Industrie yang berkedudukan di ujung
79
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
timur Pulau Yapen tepatnya di Dawai
dengan jarak tempuh ke Pulau Kurudu
45 menit menggunakan speedboat;
jika musim buah matoa tiba, para WNA
ini selalu datang ke pulau Kurudu
untuk menikmati buah matoa.
Kedatangan mereka ke pulau Kurudu
bukan karena di sekitar lokasi
perusahaan tidak tersedia matoa,
faktanya masyarakat di sekitar
perusahaan juga menyediakan banyak
buah matoa di pasar perusahaan tetapi
para WNA ini telah terpikat selera
jiwanya dengan kenikmatan buah
matoa Kurudu sehingga mereka
terlanjur memuja, mencintai dan
gelisah hatinya lebih memilih datang
ke Pulau Kurudu walaupun harus
mengeluarkan biaya yang lebih untuk
transportasi tetapi bagi mereka
kepuasan batin yang disuguhkan oleh
nikmatnya daging buah matoa Kurudu
lebih berharga dari rupiah yang
dikeluarkan. Kepuasan yang mereka
nikmati dari matoa kurudu dibagikan
pula kepada kaum keluarga, istri,
suami, anak-anak, orang tua, teman
dan sahabat mereka di negara asalnya
masing-masing. Sehingga paket
kiriman buah matoa kurudu ke negara
Korea, Cina, dan Malaysia selalu
dilakukan setiap tahun seiring musim
buah matoa. Tradisi kiriman paket
buah matoa kurudu oleh para WNA ini
secara tidak langsung ikut
memperkenalkan buah Indonesia asal
Papua (buah matoa) di mancanegara,
sehingga mengharumkan nama
Indonesia di tingkat regional dan
internasional khususnya di kalangan
para penikmat dan penggemar buah.
3. Kaum PERANCIS (Peranakan Cina
Serui) di kota Serui-Papua, telah
mengirim bibit dari varietas terbaik
matoa kurudu kepada kaum
keluarganya di Singapura untuk
dibudidayakan. Alasan mereka
memilih varietas matoa Kurudu karena
lebih unggul dari matoa lainnya di
kawasan Papua maupun di luar Papua.
Budidaya matoa kurudu di Singapura
secara tidak langsung ikut
memperkenalkan kekayaan flora buah-
buahan Indonesia di Singapura.
Benarkah buah matoa Kurudu lebih unggul dari seluruh matoa di Papua dan di luar Papua? Sampai saat ini belum ada penelitian komparatif ilmiah tentang hal itu, sehingga perlu dilakukan kajian ilmiah oleh para saintis untuk pengembangan lebih lanjut potensi buah matoa kurudu sebagai komoditas unggulan Papua bagi kesejahteraan masyarakat.
Mengapa kualitas buah matoa (Pometia pinnata Forst.) di Pulau Kurudu lebih baik dari daerah lain ? Kita bisa berhipotesa bahwa hal itu ada hubungannya dengan struktur dan kandungan tanah di Pulau Kurudu. Fakta empirik menunjukkan bahwa beberapa daerah di Pulau Yapen bagian timur seperti Waindu, Paparu, Saweri, Woda, dan Wansma juga memiliki bentuk tanah yang sama dengan bentuk tanah di Pulau Kurudu dan tentunya struktur dan kandungannya juga sama, tetapi kenyataannya buah matoa yang berasal dari daerah-daerah tersebut bila dipasarkan bersama-sama dengan buah matoa asal pulau kurudu di tempat yang sama dan waktu yang sama, pembelinya lebih memilih buah matoa kurudu karena rasa dan kenikmatannya tidak sama. Fakta ini sebenarnya suatu aktualisasi suara alam yang tak terdengar sedang berkata bahwa buah matoa asal pulau kurudu memiliki kualitas lebih dari daerah lain meskipun bentuk, struktur, dan kandungan tanahnya sama. Fakta lain yang lebih ekstrim adalah ratusan bahkan ribuan biji matoa asal pulau Kurudu yang telah ditanam di daerah-daerah tersebut dan telah mencapai masa produktif tetapi rasa khas buah matoa kurudu tidak diwariskan di sana. Jadi apa sesungguhnya faktor penyebab yang membedakan kualitas rasa dan kenikmatan buah matoa (Pometia pinnata Forst.) asal pulau kurudu dengan buah matoa (Pometia pinnata Forst.) dari
80
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
daerah lain ? Hanya orang Kurudu (suku Kurudu) yang tahu jawabannya, dan jawaban itu adalah jati diri suku Kurudu karena berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar tradisi atau budaya suku Kurudu. Suku Kurudu punya tradisi sakral bagi tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.). Dalam tradisi tersebut, terkandung relasi mencintai dan dicintai, menghargai-dihargai, memberi-diberi yang terbaik, antara tanaman matoa dan suku Kurudu. Cinta kasih, penghargaan, pemberian yang terbaik dari suku Kurudu terhadap tanaman matoa mendapat respon sebaliknya yang sama dari tanaman matoa kepada suku Kurudu. Jadi rasa buah matoa Kurudu yang unggul sebagaimana ungkapan para penggemar dan penikmatnya seperti diuraikan di atas merupakan hasil terbaik dalam diri tanaman matoa yang dipersembahkan kepada suku Kurudu sebagai penghormatan atas cinta kasih yang diberikan oleh suku Kurudu terhadap tanaman matoa. Tradisi ini menjadi protektor bagi populasi matoa (Pometia pinnata Forst.) di Pulau Kurudu sehingga jauh sebelum munculnya gerakan moderen tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (KSDAH), bukan hanya Raja Asoka (252 SM) di Asia Timur dan Raja William I (1804 M) di Inggris yang dianggap sebagai pemimpin dunia yang pertama kali memberlakukan kebijakan KSDAH, tetapi leluhur suku Kurudu juga dalam kearifan primitifnya telah memberlakukan tradisi KSDAH terhadap tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.), dan tradisi itu tetap terpelihara hingga kini. Sehingga kalau Papua, Indonesia, dan dunia memprediksikan suatu saat di masa depan akan terjadi kepunahan tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.), maka suku Kurudu sebaliknya tidak digelisahkan oleh prediksi tersebut karena memiliki kearifan dalam tradisi melestraikan tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.).
Bagaimana atau seperti apa tradisi suku Kurudu melindungi dan melestarikan tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.) ? Artikelini akan menguraikan bagaimana tradisi konservasi tanaman matoa (Pometia pinnata Forst) oleh suku Kurudu
di Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen-Papua.
Mengenal Pulau Kurudu Dan Suku Kurudu
Pulau Kurudu merupakan salah satu pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Yapen yang terletak paling timur dari gugusan pulau-pulau yang berbaris satu dengan lainnya menghubungkan kepala burung dan punggung burung peta Pulau Papua seolah-olah menjadi dinding batas antara Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data pulau-pulau kecil di Provinsi Papua oleh Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi bersama-sama dengan Panitia Pembakuan Nama Rupa Bumi Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang memiliki pulau, termasuk di danau maka Gubernur Provinsi Papua melalui Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 menetapkan Pulau Kurudu sebagai salah satu pulau kecil di Provinsi Papua yang terletak di dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Yapen. Keputusan Gubernur ini menjadi dasar hukum tentang nama pulau ini, yakni Pulau Kurudu. Pulau ini menjadi titik batas alam dari tiga wilayah administratif pemerintahan Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Akses satu-satunya untuk datang ke atau pergi dari pulau ini melalui transportasi laut. Jarak dari ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen (kota Serui) ke Pulau Kurudu cukup jauh, dapat ditempuh dalam waktu lima sampai enam jam perjalanan menyusuri laut pesisir dan menyeberang selat dengan perahu motor, jika cuaca baik dan laut bersahabat. Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Pulau Kurudu ditetapkan menjadi satu wilayah pemerintahan setingkat Kecamatan dengan nama Distrik Pulau Kurudu yang membawahi delapan kampung, yaitu Kampung Kurudu, Kampung Kirimbri, Kampung Andesarya,Kampung Mnusndu, Kampung Mnukwar, Kampung Kaipuri, Kampung Dorei Amini, dan Kampung Mansiesi. Secara geografis Pulau Kurudu
81
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
terletak di ujung timur Pulau Yapen pada koordinat 136059’17,212” hingga 13703’11,038” Bujur Timur dan 1050’15,267” hingga 1052’1,574” Lintang Selatan. Luas pulau Kurudu 21,49 km2
(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen, 2018).
Gambar 2. Peta Pulau Kurudu
Pulau Kurudu memiliki beberapa
julukan antara lain: pulau melinjo,pulau sagu merah, pulau tenggiri, pulau matoa. Julukan-julukan itu diberikan oleh kaum kerabat orang kurudu yang berasal dari daerah-daerah dan atau pulau-pulau sekitarnya antara lain daerah Waropen, Pulau Yapen, dan Pulau Biak. Julukan-julukan itu diberikan atas dasar potensi keanekaragaman hayati flora dan fauna yang melimpah di kawasan Pulau Kurudu.
Dijuluki pulau melinjo karena hampir setiap jengkal tanahnya ditumbuhi melinjo. Selain tumbuh liar secara alami, penduduk setempat juga memelihara (budidaya tradisional) melinjo di pekarangan rumahnya untuk sayuran dengan usia pohon lebih dari 100 tahun, sehingga pulau ini merupakan satu-satunya pulau di dunia yang menyimpan pohon melinjo budidaya tradisional dengan diameter batang terbesar. Pulau ini merupakan penghasil emping melinjo di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pulau Kurudu dijuluki pulau sagu merah, karena pulau ini memiliki kekayaan populasi sagu (Metroxylon spp) yang melimpah. Menurut Limbongan J. et al. (2004), di Pulau Papua terdapat 60 spesies sagu (Metroxylon spp) terdiri dari 43 spesies sagu berduri dan 17 spesies sagu tidak berduri. Di Pulau Kurudu, suku Kurudu mengenal 16 spesies sagu. Semua kaum wanita di pulau ini terampil
mengolah tepung sagu menjadi produk sagu kering dari varietas sagu dengan pati kering merah cerah atau pink. Ada pula varietas dengan pati kering putih keabu-abuan. Sagu kering dari pulau Kurudu lebih populer disebut sagu bambu karena pengolahannya menggunakan bambu alam sebagai wadah cetakan. Produk sagu keringnya merupakan produk terbaik dari semua produk sagu bambu di Tanah Papua.
Dijuluki pula pulau tenggiri, karena lautnya yang berbatasan langsung dengan samudera pasifik menjadi habitat ikan tenggiri yang melimpah. Menurut pengakuan penyelam tradisional penduduk setempat, di dalam lautnya ditemukan populasi ikan tenggiri yang melimpah dengan pola susunan (formasi) tujuh lapis dari ukuran terbesar sampai terkecil, lapisan pertama paling bawah adalah tenggiri dengan ukuran tubuh besar dan panjang, sedangkan lapisan ketujuh yaitu lapisan paling atas merupakan anakan tenggiri yang masih kecil-kecil. Daging ikan tenggiri segar menjadi sumber protein utama keluarga penduduk di pulau ini setiap hari sejak leluhur hingga kini. Satu-satunya kelompok penduduk bumi yang memancing ikan tenggiri dengan umpan bunga (bait flower) adalah penduduk pulau tenggiri alias pulau Kurudu.
Sebagai pulau di Samudera pasifik, Pulau Kurudu memiliki komunitas terumbu karang dan biota laut lainnya yang tersedia melimpah, serta panorama pantai berpasir yang asri, juga ombak pantai yang sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari. Selain itu juga bagi para penikmat fenomena alam sun rise (matahari terbit) dan sunset (matahari terbenam) dapat dengan leluasa dan gratis menyaksikannya di pulau ini sepuas-puasnya. Menurut penuturan Marinus Imbiri kepada ANTARA dalam Berita Daerah.com edisi Jumat, 07 November 2008 bahwa Pulau Kurudu adalah Pulau Surga karena menyimpan beragam potensi alam yang indah dan unik. Setiap orang yang datang ke pulau ini pasti mendapat suguhan sayur melinjo dengan teknik pengolahan tradisional yang alami dan cita rasa yang
82
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
khas dilengkapi sajian sagu kering asli kurudu dan daging tenggiri segar dan lezat.
Julukan terakhir adalah Pulau matoa (the matoas island), karena sebagaimana melinjo, hampir setiap jengkal tanah pulau ini ditumbuhi matoa (Pometia pinnata Forst). Penduduk setempat mengenal 2(dua) spesies tanaman matoa (Pometia pinnata Forst) yaitu Matoa Kelapa(bhs.kurudu: Antaun Anggadi/Antaun tu) dan Matoa Papeda (bhs.kurudu: Antaun Anin/ Antaun Pambre), dengan 288 varietas matoa kelapa, belum terhitung varietas matoa papeda. Banyaknya varieatas matoa di Pulau Kurudu disebabkan karena secara kultur penduduk pulau ini menganggap buah matoa sebagai buah sorga (heaven fruit) yang menjelma dari manusia menjadi pohon buah-buahan sehingga dilestarikan, tumbuh secara alami, walaupun ada juga yang sengaja menanam (budidaya tradisional) untuk maksud memperbanyak jumlah kepemilikan pohon matoa. Keberadaannya di alam tanpa gangguan menjadikan penyerbukan alami berlangsung dengan baik dan menghasilkan varietas-varietas baru dalam pergiliran keturunan matoa di pulau Kurudu. Menurut Arisoy (2009), berdasarkan asal-usulnya, orang Kurudu membagi tanaman matoa menjadi dua, yaitu Antaun mnat (pohon matoa yang dari leluhur, pohon matoa yang sudah lama) dan Antaun sitarm weworu (pohon matoa yang baru ditanam).
Suku Kurudu
Suku kurudu adalah orang-orang asli yang mendiami Pulau Kurudu. Menurut Arisoy (2008), orang Kurudu tinggal di Pulau Kurudu dan membentuk sebuah komunitas yang terdiri dari beberapa kampung. Komunitas kampung Mansior, kampung Mnusndu, kampung Mnukwar, kampung Orpambo, kampung Mnuba-Krimbri dan kampung Mnupui. Menurut Rumbiak M.D.E, et. al., dalam Isir R (2009) dan www.ethnologue.com, Suku Kurudu merupakan suku yang ke 110 dari 264 suku bangsa di Tanah Papua yang mana dalam peta penyebaran suku-suku bangsa Papua, suku Kurudu mendiami Pulau Kurudu. Pada literatur yang lain Dr.
Kamma mencatat dalam bukunya “Ajaib di Mata Kita, Jilid 3 halaman 387” bahwa pada tahun 1912 Van Hasselt melakukan perjalanan yang lama ke timur (dari 16 Juli sampai 2 September 1912). Ia menumpang kapal uap kecil yang berjalan lewat Biak dan Yapen, dan dari Pom (Yapen) ia melanjutkan perjalanan naik perahu ke jurusan Teluk Yos Sudarso. Dalam perjalanan itu, Van Hasselt singgah di hampir semua kampung, di sana-sini dengan menggantikan perahu, lewat Kurudu menyusuri muara-muara sungai Mamberamo menuju Sarmi. Para pendayungnya berasal dari Kurudu”. Menurut catatan ada dua puluh orang pendayung dari Kurudu, pakai perahu totanggo mengantar Pendeta Van Hasselt (Arisoy, 2008).
Sejarah Suku Kurudu Mengenal Tanaman Matoa
Sejak dahulu kala leluhur Kurudu telah mengenal pohon buah-buahan alam pulau Kurudu yang dikonsumsi sebagai bahan pangan, sebagaimana tertera dalam Tabel 1.
Tabel 1. Jenis-jenis pohon buah-buahan endemik pulau Kurudu.
No Nama Lokal Bahasa Kurudu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mangga hutan besar Mangga hutan kecil Jambu air Jambu hutan asam Jambu hutan manis Gayang Kelapa Sukun Sukun gomo Kenari hutan Matoa
Karson Anirm Kerndau Karsan Bosu Amte Anggadi Anggoin Ambatr Anaweri Antaun
Dari sebelas buah di Tabel 1, matoa
merupakan buah terbaik karena memiliki rasa dan aroma yang sangat spesial sehingga leluhur Kurudu menyebutnya sebagai buah surga (heaven fruit) dan diberi perlakuan khusus dalam kebudayaan suku Kurudu.
Leluhur Kurudu memiliki struktur sosial dalam sistem kekerabatan yang dikenal dengan nama “keret”. Setiap keret terdiri dari beberapa marga. Adanya
83
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
perang suku dan penangkapan budak yang mewarnai kehidupan suku-suku di jaman dahulu ikut mempengaruhi pola hidup bersama leluhur Kurudu. Mereka tidak hidup di goa-goa seperti moyangnya tetapi mereka membangun rumah dan bernaung di dalamnya. Jumlah rumah tidak banyak hanya beberapa saja sesuai jumlah keret.
Pola hidup bersama ini berpengaruh pada hak-hak dasar seperti hak atas tanah, hak atas dusun sagu, hak atas tempat pencaharian. Tiap-tiap keret memiliki satu atau lebih hak-hak tersebut di atas. Adanya hak-hak tersebut mempengaruhi perlakuan leluhur Kurudu terhadap tanaman matoa sebagai buah yang dikagumi. Mereka belum mengenal istilah budidaya tanaman sehingga setiap tanaman matoa yang tumbuh liar di atas hak tanah, hak dusun, atau hak tempat pencaharian keret tertentu menjadi milik keret tersebut. Saat itu tanaman matoa yang ada merupakan tanaman liar yang tersebar di kawasan hutan pulau Kurudu.
Buah matoa Kurudu ternyata menjadi makanan kesukaan kelelawar dan beberapa jenis burung di pulau Kurudu seperti kakatua putih, kakatua hijau, kakatua biru, kakatua merah, murai, dan gagak. Jika daging buah matoa sudah mulai manis, ribuan kelelawar dari hutan di dataran Waropen terbang melintasi selat Saireri dan selat Saipai menuju pulau Kurudu untuk menikmati daging buah matoa Kurudu. Perilaku migrasi populasi kelelawar ini menjadi fenomena alam yang indah setiap sore hari ketika musim buah di pulau Kurudu. Fenomena tersebut indah dipandang oleh leluhur Kurudu saat itu tetapi menjadi masalah besar bagi mereka karena kelelawar-kelelawar tersebut tidak mengenal batas-batas keret. Tidak ada aturan yang melarang kelelawar-kelelawar itu untuk tidak memakan buah matoa keret tertentu, kehidupannya bebas di alam dan mencari makan mengikuti irama alam. Kelelawar menjadi hama utama bagi buah matoa di pulau Kurudu. Berikutnya adalah burung-burung pemakan buah matoa yang hidup di pulau Kurudu. Kelelawar menjadi hama di malam hari sedangkan burung-burung menjadi hama di siang hari. Hama-hama buah matoa ini memberi inspirasi bagi
leluhur Kurudu untuk berbuat sesuatu jika ingin menikmati buah surga (buah matoa). Mereka mulai membuat api di bawah pohon matoa, karena secara naluriah mereka tahu bahwa kelelawar dan burung-burung takut terhadap asap api. Sifat api adalah menyala dan membakar, sehingga membutuhkan kayu sebagai bahan bakar dan tenaga manusia sebagai penjaga api supaya tetap menyala. Sementara populasi tanaman matoa saat itu tumbuh dengan pola tersebar (tidak berkelompok) sehingga satu keret harus membuat sejumlah api sesuai dengan jumlah pohon matoa yang hendak diselamatkan dari hama, sedangkan jarak antara pohon-pohon matoa berjauhan sehingga merepotkan dalam penjagaan. Upaya ini tidak efisien sebab membutuhkan banyak waktu, tenaga, kayu bakar, dan resiko jaga malam yang rawan terhadap keselamatan dan kesehatan diri, sedangkan hasil buah yang dipanen tidak optimal karena hama buah matoa (kelelawar dan burung) dapat masuk sewaktu-waktu ketika api kekurangan kayu bakar atau padam akibat hujan.
Tantangan hama buah matoa (kelelawar dan burung) ini terus memberi inspirasi bagi leluhur Kurudu untuk lebih arif. Mereka berpikir untuk tidak merepotkan diri dengan menjaga banyak pohon matoa yang sangat berjauhan jaraknya, lebih baik menjaga beberapa pohon matoa yang tumbuh berdekatan(mengelompok) karena lebih hemat waktu, tenaga, dan kayu bakar. Pohon matoa yang lain dibiarkan saja untuk mengalihkan perhatian hama agar tidak mengganggu buah matoa pada pohon yang dijaga, dengan demikian diharapkan hasil panen buah lebih optimal. Akhirnya pada musim buah berikutnya pohon-pohon matoa yang lain dibiarkan menjadi makanan kelelawar dan burung. Mereka hanya menjaga beberapa pohon saja, dan hasil panennya memuaskan. Tetapi berjaga-jaga seorang diri atau beberapa orang secara bergantian di bawah naungan pohon matoa bersama api masih sangat beresiko bagi keselamatan dan kesehatan diri karena bahaya perang suku, penangkapan budak, adanya roh jahat suanggi, serta udara dingin dan kehujanan;
84
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
bahkan tidak dijamin hama tidak masuk ke pohon matoa memakan buahnya. Persoalan lain adalah saat jaga malam ketika pertukaran jaga, tidak ada tempat tidur yang baik atau layak untuk bergantian tidur.
Kendala-kendala ini menjadi natural education yang membentuk leluhur Kurudu semakin arif. Mereka terus berbenah diri dalam kearifan budayanya menjaga dan menyelamatkan buah matoa (buah surga) dari hama. Timbul ide untuk membuat rumah kecil (pondok) di sekitar pohon-pohon matoa yang dijaga, maka pada musim buah berikutnya dibuatlah rumah jaga matoa. Rumah itu berguna sebagai tempat berlindung dari hujan dan dingin, tempat menyimpan kayu bakar untuk api, tempat tidur (istirahat). Di rumah itu mereka lebih aman dari bahaya perang suku, penangkapan budak, roh suanggi. Manfaat lain ialah dengan adanya rumah memungkinkan untuk menambah orang jaga termasuk anak-anak pun bisa ikut. Bertambahnya orang jaga ini merubah suasana hutan yang sepi menjadi tidak sepi lagi karena diramaikan oleh suara-suara manusia (bercakap-cakap, tertawa dan beteriak) ditambah kepulan asap api yang menyesakkan napas, sehingga kelelawar dan burung pemakan buah matoa tidak berani mendekat ke pohon matoa yang sedang dijaga. Penjagaan dengan rumah ini memberikan hasil panen yang sangat optimal, sehingga mereka mulai berpikir untuk menanam bibit-bibit matoa dalam jumlah banyak di sekitar rumah jaga agar ketika tanaman-tanaman itu produktif (berbuah), mudah dijaga walaupun banyak. Sejak itulah bermunculan dusun-dusun matoa milik masing-masing keret dan budaya jaga matoa menggunakan rumah jaga dilakukan hingga kini.
Adaptasi adalah kemampuan mahkluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kelelawar dan burung-burung pemakan buah matoa secara perlahan-lahan beradaptasi dengan asap api dan suara-suara manusia sehingga di waktu tertentu pada jaman dahulu leluhur Kurudu terkejut menyaksikan hama-hama buah matoa ini merajalela
menghabiskan buah matoa. Masalah datang lagi ! Hasil panen buah matoa berkurang drastis, walaupun ada api, rumah jaga, dan suara-suara manusia. Alam terus menantang dan memberikan pembelajaran kepada leluhur Kurudu untuk menemukan pola penjagaan buah matoa yang lebih baik agar hasil panennya optimal. Mereka terinspirasi untuk menciptakan suatu alat bunyi yang dapat mengeluarkan suara mengusir kelelawar dan burung. Ide dasar dari inspirasi tersebut ialah, jika alat bersuara itu ditempatkan langsung pada pohon matoa maka kerjanya lebih efektif mengusir hama. Dibuatlah songge (bhs. Kurudu), yaitu sejenis kentongan dari bambu air yang besar dengan panjang kurang lebih 3 meter. Bambu tersebut dibelah pada salah satu ujungnya agar ketika membentur cabang matoa akan menghasilkan bunyi. Songge digantungkan pada cabang pohon matoa dan dihubungkan ke pondok jaga dengan seutas tali. Pada bagian dekat salah satu ujung songge diberi lubang tegak lurus panjang bambu (jarak ujung songge ke lubang kurang lebih 3 – 4 ruas) dan melalui lubang tersebut dimasukkan batangan bambu kecil (tidak lebih kecil dari lubang songge dan tidak sampai menyempit) digunakan diameter yang sesuai agar bambu melintang tersebut penjadi poros yang baik untuk gerakan songge (gerak bolak-balik seperti ayunan bandul sederhana) menjauhi garis normal dan kembali ke garis normal. Panjang bambu kecil melintang lebih kurang 3 meter. Fungsi bambu kecil melintang ini selain sebagai poros melintang, juga menjadi tempat menggantungnya (titik tumpuan) songge pada cabang matoa.
Ujung songge yang berada di atas poros tengah diberi simpul berbentuk gelang dan kepada simpul itu diikatkan ujung tali penghubung dari pondok jaga agar songge terhubung dengan orang di pondok jaga. Jika orang di pondok jaga menarik tali penghubung maka ujung songge yang berada di atas poros tengah akan bergerak ke arah yang sama dengan arah gaya tarik dan gerakan tersebut akan memberi gaya tuas/pengungkit kepada poros tengah sehingga mengungkit ujung songge yang menggantung ke bawah
85
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
terangkat (berayun) ke arah yang berlawanan menjauhi cabang matoa (garis normal) membentuk sudut 900 - 1200, dan apabila tarikan tali dilepas kembali ke keadaan semula maka songge akan berayun kembali ke posisi semula (garis normal) dan membentur cabang matoa, akibat benturan itu terjadilah bunyi keras mengejutkan kelelawar atau burung sehingga terbang meninggalkan pohon matoa. Teknik pembuatan songge oleh leluhur Kurudu menjelaskan bahwa leluhur Kurudu di jaman dahulu telah menerapkan teori fisika tentang gerak elastik dan prinsip kerja tuas.
Gambar 3. Ilustrasi songge
Sampai saat ini suku Kurudu tetap
memelihara tradisi leluhurnya menyelamatkan buah matoa dari kelelawar dan burung (hama buah matoa), yakni dengan cara: membuat api, bersuara (berteriak), membuat rumah jaga (pondok), dan menggunakan songge.
Rumperyai (2010), menjelaskan bahwa orang Kurudu mempunyai beberapa cara mengusir burung-burung pemakan buah matoa yang dilakukan turun-temurun. Pertama, menyalakan api di bawah pohon matoa siang-malam. Asap api dapat mengusir burung-burung tersebut. Kedua, membunyikan “songge” yaitu alat pengusir burung yang terbuat dari bambu, dirancang seperti kentongan, digantungkan pada cabang pohon matoa dan diberi tali dari rotan yang telah disayat, panjang tali disesuaikan dengan jarak songge dan rumah jaga. Ketiga, menempati rumah jaga siang-malam mulai dari tahap mitta (daging buah mulai matang) sampai tahap tampo (daging buah telah matang) dan dipanen.
Tradisi Konservasi Tanaman Matoa oleh Suku Kurudu
Suku Kurudu membagi proses pertumbuhan dan perkembangan buah matoa menjadi lima tahap, yaitu sebagai berikut. - Pu (bunga) - Ansyou-Ndokmi (buah muda kecil
seukuran mata udang) - Mitta (buah telah berukuran besar dan
masih terus bertambah ukurannya; daging buah setengah matang, tidak manis, dan masih melekat pada biji)
- Tampo (buah dewasa dan tidak bertambah ukuran lagi, daging buah telah matang, sangat manis, dan tidak melekat pada biji). Jika pertumbuhan dan perkembangan
buah matoa telah mencapai tahap keempat (tampo) maka siap dipanen. Dalam tradisi suku Kurudu, panen matoa dianggap sebagai hari kematian buah matoa dan kematian (ajal) itu merupakan tahap kelima atau tahap akhir dalam seluruh proses atau tahapan pertumbuhan dan perkembangan buah matoa. Tahap kelima ini dinamakan sesuai aktifitas panen matoa yaitu sikar.
Menurut suku Kurudu, kelima tahap pertumbuhan dan perkembangan buah matoa identik dengan lima tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Filosofi ini disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Lima kesamaan tahapan pertumbuhan dan perkembangan antara buah matoa dan manusia.
Subjek Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Manusia Bayi Anak-anak
Pemuda Dewasa meninggal
Buah matoa
Pu Ansyou-ndokmi
Mitta Tampo sikar
Rumperyai (2010), meringkas lima
tahap ini menjadi empat dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Pu (berbunga)
Orang Kurudu menamakan tahap ini “pu” karena setiap kuncupnya mengeluarkan bunga. Tahap ini merupakan tahap paling awal dari perkembangan buah matoa.Pada tahap ini pemilik pohon matoa akan selalu mengamati perubahan yang terjadi pada bunga.
86
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
2. Ansyou-Ndokmi (mata udang) Orang Kurudu menyebutnya “Ansyou-
Ndokmi” karena ukuran buahnya sebesar mata udang kali. Arisoi (2008), menjelaskan bahwa pada tahap ini orang Kurudu mengatakan : “Antaun niye pu ne wiyer a” (bunga matoa mulai beralih ),“We Ansyou-ndokmi ”(nampak buah matoa sebesar biji mata udang kali).
Pada tahap ini, pemiliknya melakukan pembersihan di sekitar pohon matoa. 3. Mitta (daging masih melekat pada biji)
Orang Kurudu menyebutnya “mitta” karena pada tahap ini buah matoa telah memiliki daging tetapi masih melekat pada biji dan rasanya kurang manis. Pada tahap mitta, buah matoa sudah harus dijaga karena banyak burung dan kelelawar akan memakan habis buah-buah matoa. Untuk mencegah hal ini, burung-burung tersebut harus diusir. 4. Tampo (daging sudah terlepas dari biji)
Orang Kurudu menyebutnya “tampo” karena daging buahnya sudah terlepas dari biji bersama selaput yang melindunginya. Pada tahap perkembangan ini daging buahnya terasa sangat manis dan siap dipanen.
Atas dasar kesamaan antara buah matoa dan manusia sebagaimana disajikan pada tabel 2 di atas, maka dalam tradisinya leluhur Kurudu mengajarkan dua hal penting kepada keturunannya dan menjadi kewajiban setiap orang Kurudu untuk mewariskan ajaran ini kepada keturunan selanjutnya. Dua hal itu adalah sebagai berikut. 1. Buah matoa adalah manusia (buah
matoa sama dengan manusia). 2. Buah matoa adalah buah surga yang
menjelma dari manusia menjadi tanaman matoa agar tetap menghasilkan buah di bumi bagi manusia.
Dengan dua hal ini maka suku Kurudu dilarang dan diwajibkan melakukan hal-hal berikut. 1. Dilarang membawa parang ke atas
pohon matoa; dilarang memotong batang, cabang, dan ranting pohon matoa; dilarang menebang pohon matoa.
2. Diwajibkan menghormati, menghargai, merawat pohon matoa seperti layaknya seorang manusia.
3. Diwajibkan menjaga buah matoa dengan baik sejak tahap pu sampai tahap tampo dan sikar.
4. Diwajibkan meratapi kematian buah matoa (panen buah matoa = tahap sikar) seperti halnya meratapi seorang manusia yang meninggal. Perbedaannya adalah buah matoa diratapi/ditangisi sebelum dipanen (sebelum mengakhiri hidupnya), sedangkan manusia diratapi/ditangisi setelah meninggal. Mengapa demikian ? Karena kematian manusia merupakan misteri (tidak diketahui waktunya), sedangkan panen buah matoa (sikar= akhir hidup buah matoa) waktunya ditentukan oleh pemiliknya jika telah memasuki tahap tampo.
5. Dilarang memanen buah matoa dengan cara memotong cabang-cabangnya atau menebang pohonnya. Panen buah matoa dilakukan dengan satu set peralatan panen tradisional yang terdiri dari : tongkat/galah pematah, wadah pemetikan buah, dan tali. Fungsi masing-masing alat antara lain: tongkat/galah pematah untuk mematahkan tangkai induk buah matoa; wadah pemetikan buah untuk menampung buah di atas pohon; tali untuk menurunkan wadah pemetikan buah yang telah penuh terisi buah matoa.
Tongkat/galah Pematah (Doikam)
Gambar 4. Ilustrasi galah pematah
87
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
Tongkat (galah) pematah dinamakan
doikam, terbuat dari bambu berdiameter 2-3 cm dengan panjang kurang lebih 7 meter, pada salah satu ujung doikam diikatkan sepotong kayu sedemikian rupa sehingga membentuk kait-kait. Fungsi kait-kait adalah untuk disangkutkan atau dikaitkan pada dahan atau ranting matoa yang pada pucuknya terdapat rangkai buah matoa lalu ditarik hingga dahan atau ranting tersebut patah.
Dilarang menjatuhkan buah matoa bersama dahan atau ranting yang dipatah ke tanah. Dahan atau ranting yang sudah dipatahkan akan terjepit pada kait-kait doikam sehingga dengan mudah didekatkan ke pemegang doikam kemudian tangkai utama buah matoa dipatahkan dari dahan atau ranting barulah dahan atau ranting tersebut dijatuhkan ke tanah karena tidak mengandung buah. Selanjutnya buah matoa dipetik dari tangkai utamanya dan dimasukkan ke dalam wadah penampung, sehabis memetik buah matoa, tangkai utama tersebut dapat dijatuhkan ke tanah. Semua proses ini berlangsung di atas pohon matoa.
Wadah Pemetikan Buah (Namete)
Gambar 5. Ilustrasi namate
Wadah pemetik buah adalah noken
yaitu sejenis kantung besar yang terbuat dari anyaman serat kulit pohon hutan, dalam bahasa kurudu disebut namete. Namete biasanya diikatkan pada tali (wainsni) dan dinaikkan ke atas pohon matoa kepada orang yang sedang memanen matoa. Selanjutnya sang pemanen buah matoa akan menggantungkan namete pada posisi yang baik agar mudah untuk diisi dengan buah matoa yang telah dipetik dari rangkainya. Jika namete telah penuh dengan buah matoa maka diturunkan dengan menggunakan tali. Di bawah pohon matoa ada orang yang siap menjemput namete yang sedang diturunkan dengan tali (wainsni). Bila namete sudah tiba di atas tanah maka orang tersebut akan melepaskan simpul tali dari namete dan membawa namete tersebut ke tempat penampungan akhir buah matoa yang telah disiapkan di pondok jaga. Kemudian namete yang telah kosong diikatkan kembali pada tali lalu di tarik ke atas pohon untuk diisi lagi dengan buah matoa. Begitulah seterusnya hingga buah matoa habis dipanen dari pohonnya. Tali (Wainsni)
Tali dalam bahasa Kurudu dinamakan wainsni. Wainsni dipakai sebagai alat bantu untuk menaikan dan menurunkan namete ke atas pohon dan ke bawah pohon.
Beberapa Kebiasaan Pada Saat Panen Buah Matoa Oleh Suku Kurudu Persiapan
Sebelum panen, beberapa hal yang dipersiapkan antara lain:
Bahan makanan (bhs. Kurudu : anan).
Peralatan panen buah matoa : doikam, wainsni, namete
Menetapkan waktu pelaksanaan panen buah matoa dan menghubungi (mengundang secara adat) orang yang akan meratapi buah matoa pada upacara adat dalam rangka panen buah matoa, serta orang yang akan memanen buah matoa.
Prosesi undangan adat sebagai berikut:
88
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
“Pemilik pohon matoa yang akan dipanen menyiapkan sejumlah makanan, diantarkan ke rumah orang yang hendak diundang sebagai peratap dan pemanen, di rumah pihak yang diundang, makanan diserahkan dan pengundang menyampaikan maksudnya mengundang mereka untuk meratapi atau memanen buah matoa pada hari sesuai yang telah ditetapkan, pengundang juga memberitahukan tempat pelaksanaan (nama dusun matoa miliknya).
Rumperyai (2010), menjelaskan bahwa apabila buah matoa telah matang (tampo) siap dipanen maka pemiliknya akan menyiapkan bahan makanan dan mengundang peratap dan pemanen buah matoa. Biasanya pemanen yang diundang adalah saudara laki-laki dari isteri (om/paman), sedangkan peratap adalah orang-orang khusus yang telah belajar di RUMRA (sekolah adat suku Kurudu). Pelaksanaan
Pelaksanaan panen buah matoa mencakup upacara adat meratapi buah matoa (Sai Antaun), panen buah matoa (sikar), dan pembagian hasil panen kepada kaum keluarga (siwow). Meratapi buah matoa (Sai Antaun)
Meratapi buah matoa merupakan tradisi sakral (upacara adat) suku Kurudu yang dilakukan selama 12 jam (satu malam) menjelang panen buah matoa. Upacara ini dinamakan ”Sai Antaun = meratapi buah matoa”, karena dilaksanakan dengan melantunkan nyanyian-nyanyian ratapan terhadap buah matoa yang akan dipanen. Bila telah tiba waktu panen buah matoa sebagaimana disampaikan dalam undangan adat, maka peratap akan mendatangi pengundang di rumah jaga matoa pada waktu menjelang malam, dan sepanjang malam itu upacara/ritual ratapan dilakukan, semua orang di pondok jaga hening dan peratap menuju pohon matoa sambil memegang tali songge. Di bawah pohon matoa peratap mulai melantunkan syair-syair nyanyian ratapannya meratapi buah matoa sambil membunyikan songge sepanjang malam. Orang di pondok jaga ikut membunyikan
songge-songge lainnya seperti biasanya mengusir kelelawar. Jika fajar telah menyingsing maka peratap menghentikan nyanyian-nyanyian ratapannya pertanda berakhirnya upacara/ritual Sai Antaun dan telah mendapat restu alam untuk panen buah matoa.
Menurut Rumperyai (2010), peratap buah matoa berdiri sepanjang malam sambil memegang tali “songge” dan meratap. Salah satu nyanyian ratapan yang sangat terkenal adalah “BUISO” dengan syair-syair sebagai berikut.
Buiso......Buiso......Buiso...... Buiso songge Songge ryo na antaun syen dun o ...... Makna yang terkandung dalam
nyanyian (Sai Antaun) ini adalah : “oh..., anakku sayang, besok ketika mentari pagi terbit memancarkan sinarnya memberi kehidupan kepada semua makhluk, engkau akan tiada dalam hidup itu, waktumu akan berakhir. Hanya malam ini saja engkau ada bersama kami yang mencintaimu, memilikimu, menghargaimu, menghormatimu, mengagumimu. Hidupmu sebatas fajar menyingsing di ufuk timur. Oh...., anakku sayang.....”
Lirik nyanyian ratapan Sai Antaun ini telah ditransfer sebagai nyanyian umat kristen oleh Henky Arisoi (seniman dan budayawan Papua) dengan judul lagu : “Tuhan Raja Kami”. Menurutnya, konteks teologi nyanyian ratapan Sai Antaun adalah : “buah matoa menemui ajalnya (mati) agar memberi manfaat bagi kehidupan suku Kurudu (dimakan). Ibarat Yesus Anak Allah harus mati agar memberi hidup kekal bagi manusia”. Nyanyian ini termuat dalam buku : SEGALA YANG BERNAFAS (buku nyanyian umat kristiani), dan telah menjadi salah satu nyanyian utama dalam tata ibadah umat kristen di Negeri Belanda. Berikut ini sedikit informasi tentang penggunaan lirik Sai Antaun dalam nyanyian jemaat pada ibadah umat Kristen di Negeri Belanda, dikutip dari surat yang dikirim dari Negeri Belanda tahun 1989 kepada Bapak Henky Arisoi di Jayapura.
Prosiding Seminar Nasional V 2019 Peran Pendidikan dalam Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
ISBN 978-602-5699-83-2; PUBLIKASI ONLINE 5 MARET 2020
89
Gambar 6 Lirik lagu
Panen buah matoa (Sikar) Setelah buah matoa diratapi sepanjang
malam, dan ketika mentari pagi terbit maka pemilik matoa telah menyiapkan jamuan makan yang dikhususkan bagi peratap yang telah menyelesaikan tugasnya dan para pemanen buah yang telah berkumpul di rumah jaga untuk melaksanakan tugasnya sesuai undangan. Setelah jamuan makan, peratap boleh pulang beristirahat sedangkan para pemanen mulai melaksanakan tugasnya membawa peralatan dan memanjat pohon matoa untuk memanen buah matoa. Suku kurudu menyebut peristiwa panen buah matoa dengan istilah “patah matoa” (sikar) karena panen buah matoa dilakukan
dengan cara mematahkan dahan atau ranting matoa dengan doikam untuk mengambil buahnya.
Gambar 7 Ilustrasi buah matoa
90
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
Dalam tradisi panen buah matoa, jika
wadah pemetikan buah matoa (namete) pertama telah penuh dan diturunkan dengan tali, maka setelah isi namete dituang ke tempat penampungan buah matoa di pondok jaga, sebelum namete tersebut diikat pada tali penarik untuk dinaikkan kembali ke pohon, di dasar namete harus diletakkan dua pasangan buah matoa mansoperu, yaitu buah matoa ganda (kembar) berbentuk angka delapan. Biasanya diambil dua buah matoa mansoperu dirangkai menjadi satu menggunakan seutas tali kemudian diletakkan di dasar namete.
Rangkaian mansoperu yang telah diletakkan pada dasar namete pertama tadi digunakan untuk namete selanjutnya hingga seluruh buah matoa habis dipanen dari pohonnya.
Menurut suku Kurudu, buah matoa mansoperu merupakan simbol keberuntungan atau kelimpahan rejeki buah matoa. Tradisi meletakan buah matoa mansoperu ke dasar namete merupakan simbol permohonan adat kepada penguasa agar hasil panen melimpah ruah serta berharap agar pada musim berikutnya hasil panen tetap melimpah.
Selain tradisi mansoperu, orang kurudu juga menganggap tabu menjatuhkan buah matoa dari pohon ke tanah saat melakukan panen. Pelanggaran terhadap hal ini berbahaya terhadap keselamatan orang yang sedang memanen buah matoa di pohon; bisa terjadi kecelakaan jatuh dari pohon. Pelanggaran terhadap hal ini juga berpengaruh pada kelebatan buah matoa di musim berikutnya. Ada tiga hal tersirat dalam ketabuhan ini, yakni: pertama, suku Kurudu memandang buah matoa seperti layaknya seorang manusia. Jangan menjatuhkan seorang manusia dari pohon yang tinggi ke tanah sebab hal itu hanya dilakukan oleh orang jahat. Orang jahat akan menerima akibat dari perbuatannya. Kedua, suku Kurudu sangat mengenal karakteristik buah matoa bahwa kulit buahnya sangat tipis, tidak tahan benturan serta kandungan gula dalam daging buahnya yang sangat tinggi menjadi
kesukaan semut dan mikroba. Jika buah matoa dijatuhkan ke tanah maka kulit buahnya akan pecah akibat benturan, dan kandungan gula dengan aroma khas dalam daging buahnya akan keluar, banyak semut berdatangan serta terjadi invasi mikroba sehingga buah tidak nyaman dikonsumsi dan tidak aman bagi kesehatan. Selain itu, tanah menjadi habitat berbagai mikroorganisme patogen sehingga buah matoa tidak boleh kontak fisik dengan tanah (harus dijaga sanitasi buah) agar sehat dikonsumsi. Kualitas buah matoa pasca panen diperhatikan secara arif dan bijak oleh suku Kurudu. Ketiga, kuantitas buah matoa yang dijatuhkan ke tanah sangat minim karena sebagian buah hancur terbentur, sebagian lagi hancur terinjak kaki orang yang mengumpul, sebagian dimakan anjing (beberapa anjing di Kurudu suka makan buah matoa), dan sebagian tidak terkumpul karena terselip di balik serasah, rerumputan, semak, perdu, dan rumpun-rumpun bambu. Pembagian hasil panen buah matoa kepada kaum keluarga (Siwow)
Setelah panen, hasil panen buah matoa dibagikan kepada semua kaum keluarga. Terlebih dahulu memisahkan bagian yang dikhususkan kepada peratap dan para pemanen. Landasan filosofi suku Kurudu melakukan tradisi pembagian hasil panen buah matoa adalah: “semakin banyak dibagikan, semakin subur pohonnya dan semakin lebat buahnya”. Atas dasar filosofi ini, pembagian dilakukan sedemikian rupa sehingga semua kaum keluarga yang terikat dalam sistem kekerabatan marga dan memiliki hak bersama atas dusun matoa yang dipanen mendapat bagiannya masing-masing, termasuk calon bayi yang dikandung ibu pun mendapat pembagian yang sama. Bagiannya akan dikonsumsi oleh sang ibu dan sang janin menikmati buah matoa miliknya melalui plasenta ibunya. Tradisi pembagian hasil panen buah matoa ini menjadi barometer suku Kurudu tentang kejujuran dan keadilan dalam memberi apa yang menjadi hak orang lain, secara khusus hak kepemilikan bersama atas dusun matoa. Tradisi ini menjadi dasar budaya untuk menjelaskan tentang faktor penyebab kelebatan buah matoa. Jika
91
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
berbuah lebat, pertanda bahwa pemiliknya berlaku jujur dan adil dalam pembagian hasil panen; sebaliknya jika buah tidak lebat, pertanda ketidakjujuran dan ketidakadilan. Tradisi ini dilakukan dengan benar (jujur dan adil) oleh suku Kurudu sehingga meskipun tanaman matoa tidak dikebunkan dengan teknologi budidaya tanaman tetapi hasil buahnya sangat lebat dan mampu memberi makan seluruh kaum keluarga sejak leluhur hingga anak cucu saat ini serta masa mendatang. 1. Dilarang mengambil buah matoa yang
telah dipanen untuk diri sendiri atau keluarga sendiri tanpa membagikannya kepada kaum keluarga lainnya dalam satu keret atau marga yang memiliki hak bersama atas pohon matoa yang dipanen.
2. Dilarang membuat api dekat pohon matoa karena akan menyebabkan rusaknya kulit batang matoa dan mengakibatkan kematian pohon matoa.
Tujuh larangan dan kewajiban di atas merupakan aturan adat tidak tertulis (konvensi) yang berlaku turun-temurun dalam kehidupan suku Kurudu sebagai wujud mencintai, menghormati, merawat, memelihara, melindungi tanaman matoa seperti layaknya seorang manusia. Aplikasi ketujuh aturan adat di atas oleh suku Kurudu menjadi sarana komunikasi dalam irama alam antara suku Kurudu dan tanaman matoa yang sulit dipahami oleh para ilmuan. Didalamnya tersirat rasa saling memiliki, saling memberi, saling menghargai, kekerabatan, antara suku Kurudu dan tanaman matoa. Menurut falsafah suku Kurudu: “jika kita ingin diperlakukan dengan baik maka kita harus berlaku baik kepada sesama manusia yang lain”. Bagi orang Kurudu, tanaman matoa sama dengan manusia sehingga ketika diperlakukan dengan baik maka sebaliknya tanaman matoa akan mempersembahkan hasil buah terbaik untuk dinikmati oleh suku Kurudu. Inilah faktor utama yang membuat rasa dan aroma buah matoa Kurudu berbeda (lebih nikmat) dari buah matoa pada daerah lain di Papua dan luar Papua.
Rumperyai (2010), menjelaskan bahwa: “Kurudu people also see the symbol. So, in way of their thinking, they saw matoa fruit was not a fruit only. Matoa fruit was considered as human being who experience life cycle that started from baby, small child, adolescent, adult, and experience the end its life. It is different with human being. The human being could go through a period of their life cycle to the end of their life. But according to Kurudu people, matoa fruit ended its life not base on its wishful thinking, but because it was forced. In bewail matoa fruit, Kurudu people have certainly persons. Not all persons can bewail the matoa fruit. People who have authority to bewail matoa fruit are people who had entered and taught in Rumra (traditional education house)”. Artinya: “Dalam alam pemikiran orang Kurudu, buah matoa tidak hanya dipandang sebagai buah semata. Buah matoa dianggap seperti layaknya manusia yang mengalami siklus hidup mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan mengalami akhir dari hidupnya. Perbedaannya adalah kematian manusia terjadi secara alami, sedangkan buah matoa menemukan ajalnya karena dipaksa (keinginan manusia). Hal inilah yang menyebabkan orang Kurudu harus meratapi buah matoa, dan untuk meratapi buah matoa tidak semua orang Kurudu bisa. Hanya orang-orang yang masuk belajar di RUMRA (rumah pendidikan tradisional orang Kurudu), merekalah yang layak meratapi buah matoa.” Ancaman Terhadap Tradisi Konservasi Tanaman Matoa Suku Kurudu
Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Penetrasi budaya asing ke dalam budaya suku Kurudu dapat merubah tradisi suku Kurudu dalam hal menjaga, melindungi, dan melestarikan tanaman matoa. Hal ini tidak dapat dicegah karena perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat, dan perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar
92
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan.
Beberapa penetrasi budaya asing yang telah, sedang, dan akan masuk mempengaruhi kehidupan sosiokultur orang Kurudu antara lain:
Budaya uang sebagai nilai tukar benda.
Kedatangan pencinta dan penggemar matoa kurudu ke pulau Kurudu untuk membeli buah matoa pada musim buah dengan sejumlah uang, dan adanya pasaran buah matoa kurudu di kota Serui yang sangat menjanjikan, membuktikan bahwa budaya uang telah mempengaruhi tradisi konservasi matoa suku Kurudu. Dengan adanya uang, orang Kurudu akan lebih melihat uang dari pada kaum keluarga yang selayaknya mendapat pembagian hasil panen sebagaimana tradisi yang terpelihara sejak leluhur. Cara pandang orang Kurudu terhadap pohon matoa yang menghasilkan buah tidak seperti biasanya, melihat buah matoa yang lebat tidak lagi sebagai pengikat hubungan kekerabatan tetapi sebagai penghasil jutaan rupiah. Uang menyebabkan adik tidak mengenal kakak dan sebaliknya. Nilai kekerabatan keret dan marga yang terpelihara dalam tradisi pembagian buah matoa akan hilang. Jika hal itu terjadi maka akibat adatnya adalah buah matoa tidak lebat seperti biasanya. Budaya instan/praktis sebagai cara termudah (hemat materi, hemat biaya, hemat tenaga, hemat waktu) untuk memperoleh sesuatu.
Tradisi panen buah matoa oleh suku Kurudu membutuhkan banyak biaya, materi, tenaga, dan waktu; dimulai sejak pemilik pohon matoa mempersiapkan bahan makanan dan mengolahnya untuk mengundang peratap dan pemanen, sampai pada menyiapkan makan saat berakhirnya upacara Sai Antaun dan memberi makan para pemanen. Selain itu, proses panen buah matoa dengan doikam, wainsni, dan namete juga sangat menyita banyak tenaga dan waktu. Sementara itu kita ketahui bahwa kemajuan dan kesulitan hidup jaman ini telah memberikan pembelajaran kepada manusia untuk
bekerja secara cepat dan tepat (mudah, hemat waktu, biaya, dan tenaga) untuk mencapai hasil yang maksimal. Sebagai contoh, orang Kurudu dahulu membawa hasil panen matoanya ke kota Serui dengan mendayung perahu selama 3 hari, dengan adanya kemajuan dunia menyediakan teknologi yang instan atau memudahkan melalui tenaga motor tempel orang Kurudu ke Serui dengan berpangku tangan dalam waktu 5 – 6 jam. Sadar atau tidak, orang Kurudu akan terbiasa dengan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi, dan kebiasaan tersebut akan terbawa ke tradisi panen buah matoa. Orang Kurudu tidak suka merepotkan diri dengan mengundang peratap dan pemanen buah matoa, juga tidak perlu bersusah payah menggunakan pemanen buah dengan alat doikam, wainsni, dan namete yang merepotkan serta menghabiskan banyak waktu. Lebih baik pemilik pohon matoa memanen sendiri dengan cara memangkas cabang-cabang matoa atau menebang pohon matoa, karena cara ini lebih hemat tenaga, waktu, dan biaya atau lebih instan. Tanaman matoa tidak diperlakukan sebagai manusia lagi dalam budaya suku Kurudu karena tidak mengawali panen matoa dengan upacara/ritual Sain Antaun, membawa parang ke atas pohon matoa dan memotong cabang matoa atau menebang pohon matoa, menjatuhkan buah matoa dari pohon ke tanah. Jika hal ini terjadi maka merupakan bukti bahwa budaya instan telah mempengaruhi tradisi konservasi matoa suku Kurudu. Budaya percepatan pembangunan oleh pemerintah
Berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua termasuk pulau Kurudu, merupakan budaya asing yang disambut baik oleh suku Kurudu. Saat ini di Pulau Kurudu setiap kampung kucuran dana yang cukup besar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah-rumah layak huni kepada masing-masing Kepala Keluaraga. Pembangunan perumahan masyarakat pulau Kurudu membutuhkan kayu sebagai bahan bangunan. Daya dukung hutan pulau
93
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
Kurudu terbatas dalam menyediakan kayu bangunan non matoa, sehingga peluang untuk eksploitasi pohon matoa sebagai bahan bangunan oleh masyarakat pulau kurudu sangat besar, dan tidak dapat dicegah. Selain itu, dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menetapkan Pulau Kurudu menjadi sebuah Distrik definitif. Status sebagai Distrik definitif ini memberi peluang bagi kemajuan pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau Kurudu. Hal itu tercapai melalui penataan infrastruktur yang membutuhkan lahan sebagai areal atau kawasan pembangunan. Konsekuensinya adalah konversi hutan matoa menjadi lahan pembangunan. Budaya suku kurudu yang melarang orang Kurudu menebang pohon matoa terpaksa dilanggar. Tradisi konservasi tanaman matoa oleh suku Kurudu akan mengalami tekanan besar karena eksploitasi pohon matoa dan kenversi hutan matoa menjadi lahan pembangunan. Budaya pertambangan dan industri
Menurut analisa Atmawinata dan Ratman dari P3R/BMR, dan sesuai penjelasan Dr. John Karubaba (Dinas Pertambangan Provinsi Papua) tahun 1983, bahwa berdasarkan hasil foto udara di kawasan Pulau Kurudu sampai ke muara Mamberamo dan Selat Saireri terdapat Gas Alam Cair dengan kapasitas yang sangat besar.
Gambar 8 Keberadaan gas alam cair
Jika eksploitasi Gas Alam Cair di kawasan ini dilakukan maka ekosistem pulau Kurudu akan mengalami kerusakan termasuk di dalamnya populasi tanaman matoa. KESIMPULAN
Pengakuan serta sikap masyarakat pencinta dan penggemar buah di kota Serui terhadap rasa dan aroma khas buah matoa Kurudu, merupakan fakta empirik yang menunjukkan bahwa kualitas buah matoa Kurudu lebih baik dari buah matoa lainnya di Papua maupun di luar Papua. Kualitas buah matoa Kurudu disebabkan oleh tradisi khusus dalam budaya suku Kurudu terhadap tanaman matoa, yaitu menghormati, menghargai, mencintai, mengagumi dan memperlakukan tanaman matoa seperti layaknya manusia. Tradisi khusus suku Kurudu terhadap tanaman matoa merupakan tindakan KSDAH tanaman matoa (Pometia pinnata Forst.) atau dapat diterjemahkan sebagai the wise use of nature resource (pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana).
Konservasi tanaman matoa(Pometia pinnata Forst.) menurut tradisi suku Kurudu secara konvensional diatur dalam 7 (tujuh) tatanan adat, yaitu sebagai berikut. Dilarang membawa parang ke atas pohon matoa; dilarang memotong batang, cabang, dan ranting pohon matoa; dilarang menebang pohon matoa. Diwajibkan menghormati, menghargai, merawat pohon matoa seperti layaknya seorang manusia. Diwajibkan menjaga buah matoa dengan baik sejak tahap pu sampai tahap tampo dan sikar. Diwajibkan meratapi kematian buah matoa seperti halnya meratapi seorang manusia yang meninggal. Dilarang memanen buah matoa dengan cara memotong cabang-cabangnya atau menebang pohonnya. Dilarang mengambil buah matoa yang telah dipanen untuk diri sendiri atau keluarga sendiri tanpa membagikannya kepada kaum keluarga lainnya dalam satu keret atau marga yang memiliki hak bersama atas pohon matoa yang dipanen. Dilarang membuat api dekat pohon matoa karena akan menyebabkan rusaknya kulit batang matoa dan mengakibatkan
94
Rumperiari / Seminar Nasional V 2019 Hal. 76-94
kematian pohon matoa. Ancaman terhadap tradisi konservasi tanaman matoa suku Kurudu tidak dapat dicegah karena perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing.
Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang disampaikan adalah sebagai berikut. Perlu adanya kajian ilmiah tentang potensi kehati pulau Kurudu yang diprakarsai oleh Pemerintah Distrik Pulau Kurudu bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Pemerintah Provinsi Papua serta WWF Region Papua, Universitas Cenderawasih Jayapura, dan Universitas Negeri Papua Manokwari. Riset perbandingan kualitas buah matoa di seluruh kawasan Papua maupun di luar Papua harus dilakukan untuk mengukur kualitas buah matoa Kurudu yang mana secara empiris dianggap lebih unggul oleh pencinta dan penggemar buah matoa di kota Serui.
Suku Kurudu hendaknya memelihara dan melestarikan tradisi konservasi matoa dalam kearifan budayanya, meskipun disadari bahwa penetrasi budaya asing ke dalam budaya suku Kurudu dapat merubah tradisi suku Kurudu dalam hal menjaga, melindungi, dan melestarikan tanaman matoa. Kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan Distrik Pulau Kurudu demi peningkatan kesejahteraan masyarakat hendaknya memperhatikan pelestarian dan perlindungan populasi tanaman matoa dan kehati lainnya di pulau ini.
DAFTAR PUSTAKA Arisoy Henky. 2009. Pengajaran Bahasa
Kurudu untuk pemula. Buku 2. Jayapura.
Arisoy Henky. 2008. Tokopi dan Mampuri Tonggak-Tonggak Perjalanan Orang Kurudu. Jayapura.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen. 2018. Distrik Pulau Kurudu dalam angka 2018. BPS Kabupaten Kepulauan Yapen.
Hidayah, Z. 2015. Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Isir Robert. 2009. syukur bagimu tuhan kau b’rikan Tanahku Papua (makna hari raya pondok daun kristen sion dan hari raya syukuran bumi papua untuk membangun papua emas) aktualisasi visi pastor i.s kijne tentang kota emas. Jayapura : Komite Jaringan Doa Sahabat Papua.
Limbongan J, Hayati Lakui dan Louw J. 2004. Program penelitian dan pengkajian sagu berwawasan agribisnis dan ketahanan pangan di Papua. Prosiding Lokakarya Nasional Pendayagunaan Pangan Spesifik Lokal Papua. Kerjasama UNIPA dan Pemprov Papua, Jayapura, 2-4 Desember 2003.
Pemerintah Provinsi Papua. 2008. Nama dan Koordinat pulau-pulau kecil di Propinsi Papua. Jayapura : Biro Tata Pemerintahan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
Rumperyai Z. 2010. Sai antaun ritual on kurudu people. Jayapura: Universitas Cenderawasih.
Zurriyati, Y. dan Dahono. 2016. Keragaman sumber daya genetik tanaman buah-buahan eksotik di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.Buletin Plasma Nutfah. Volume 22 No. 1. Juni 2019.