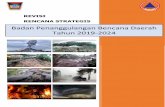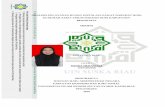PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KAWASAN RAWAN BENCANA DI INDONESIA (PRA BENCANA, TANGGAP DARURAT DAN...
Transcript of PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KAWASAN RAWAN BENCANA DI INDONESIA (PRA BENCANA, TANGGAP DARURAT DAN...
TTEEOORRII PPEERREENNCCAANNAAAANN LLAANNJJUUTT
PPLL 55220011
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KAWASAN
RAWAN BENCANA DI INDONESIA
(PRA BENCANA, TANGGAP DARURAT DAN
PASCA BENCANA)
Disusun Oleh :
Irma Yusfida NIM. 25413037
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPPK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2014
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KAWASAN RAWAN
BENCANA DI INDONESIA (PRA BENCANA, TANGGAP
DARURAT DAN PASCA BENCANA)
I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah sebuah negara yang rawan bencana hal ini dikarenakan letak geografis
Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menyebabkan negara ini rentan terhadap gunung
meletus. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di
dunia Posisi geografis yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia: Eurasia, Indo-
Australia dan Pasifik, Indonesia menyebabkan Indonesia rentan pula terhadap resiko
ancaman gempa dan tsunami.
Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Indonesia juga
tidak lepas dari bencana besar yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian
tidak sedikit. Banjir yang hampir setiap tahun menimpa Jakarta dan wilayah sekitarnya, kota-
kota di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo dan beberapa daerah lain di Indonesia
menimbulkan kerugian material dan non-material senilai triliunan rupiah. Demikian pula
kekeringan yang semakin sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, selain mengancam
produksi tanaman pangan juga kian mempermiskin penduduk yang mata pencahariannya
tergantung pada pertanian, perkebunan dan peternakan.
Berdasarkan Kementerian PU, korban terbesar dari bencana adalah masyarakat yang tinggal
di kawasan rawan bencana. Masyarakat pula yang secara langsung menghadapi bencana.
Menurut Zamroni (2011), Lemahnya kapasitas warga menjadikan kerentanan (vulnerability)
semakin tinggi sehingga jika terjadi bencana sekecil apapun maka warga akan lebih mudah
terperosok dalam ketidakberdayaan (exposure).
Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana
(PP 21 Tahun 2008). Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran
dan kapasitas masyarakat dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
Masyarakat yang siap dan waspada terhadap bencana dapat mengurangi, mencegah bahkan
menghilangkan resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut di atas maka disusunlah paper
tentang “Partisipasi Masyarakat Pada Kawasan Rawan Bencana Di Indonesia (Pra Bencana,
Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana”. Tujuan dari penulisan paper ini adalah mengetahui
praktek partisipasi masyarakat di Indonesia pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan
pasca bencana.
II. TINJAUAN KONSEP DAN KEBIJAKAN
2.1 Definisi Rawan Bencana
Rawan Bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah
kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial,
budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pasa satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemapuan untuk mengagapi dampak buruk bahaya tertentu.
2.2 Konsep Pengurangan Resiko Bencana
Paradigma penanggulangan bencana sudah beralih dari paradigma bantuan darurat menuju
paradigma mitigasi/preventif dan sekaligus juga paradigma pembangunan. Karena setiap
upaya pencegahan dan mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksinya telah diintegrasikan
dalam program-program pemabngunan di berbagai sektor.
Menurut BNPB (2008) Paradigma Pengurangan Resiko Bencana yang merupakan rencana
terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi dan
lingkungan. Dalam implementasinya kegiatan pengurangan resiko bencana nasional akan
disesuaikan dengan rencana pengurangan risiko bencana pada tingkat regional dan
internasional. Dalam paradigma pengurangan resiko ini diperkenalkan bagaimana cara
mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta
meningkatkan kemampuan (capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman. Secara
skematis, hubungan antara ancaman, kerentanan, risiko dan kejadian bencana yang dapat
digambarkan sebagai berikut .
Gambar 1 Bahaya, Kerentanan, Resiko dan Bencana
a. Bahaya (Hazards)
Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi
mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan United Nations-International Strategy for Disaster Reduction (UN-
ISDR), bahaya ini dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu :
1) Bahaya beraspek geologi : gempa bumi, tsunami, gunungapi. longsor.
2) Bahaya beraspek hidrometerologi : banjir, kekeringan, angin topan, gelombang
pasang.
3) Bahaya beraspek biolog : wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman.
4) Bahaya beraspek teknologi : kecelakaan transportasi, kecelakaan industri,
kegagalan teknologi.
5) Bahaya beraspek lingkungan : kebakaran hutan, kerusakan lingkungan,
pencemaran limbah.
b. Kerentanan (Vulnerability)
Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang
mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya.
Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sabagai salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi bila
"bahaya" terjadi pada "kondisi yang rentan". seperti yang dikemukakan Awotona
(1997:1-2) dalam Bappenas : " .... Natural disaster are the interaction between
natural hazard and vulnerable condition". Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari
kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi.
Kerentanan fisik (infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur)
yang rawan terhadap faktor bahaya (hazard) tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat
dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut : persentase kawasan terbangun;
kepadatan bangunan; persentase bangunan konstruksi darurat; jaringan listrik; rasio
panjang jalan; jaringan telekomunikasi; jaringan PDAM; dan jalan KA. Wilayah
permukiman di Indonesia dapat dikatakan berada pada kondisi yang sangat rentan
karena persentasi kawasan terbangun, kepadatan bangunan dan bangunan konstruksi
darurat di perkotaan sangat tinggi sedangkan persentase, jaringan listrik, rasio panjang
jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan PDAM, jalan KA sangat rendah.
c. Resiko Bencana (Disaster Risk)
Resiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman
bahaya (hazard) yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat tetap
karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan atau pembentukan roman
muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan
daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut
semakin meningkat.
Jika ketiga variabel tersebut digambarkan adalah sebagai berikut :
Gambar 2 Hubungan Variabel Bahaya, Kerntanan dan Ketidamampuan
Sumber : BNPB, 2008
Hubungan antara ancaman bahaya, kerentanan dan kemampuan dapat dituliskan dengan
persamaan berikut:
Risiko = f (Bahaya x Kerentanan/Kemampuan)
Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut
terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masayarakat atau
penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi
tingkat kemampuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Dalam
kaitannya dengan pengurangan resiko bencana maka upaya yang dapat dilakukan adalah
melalui pengurangan tingkat kerentanan, karena hal tersebut relatif lebih mudah
dibandingkan dengan mengurangi/memperkecil bahaya/hazard.
2.3 Penyelenggaraan Bencana
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana
adalah sebagai berikut :
Gambar 3 Siklus Penanggulangan Bencana
Sumber : BNPB
Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni :
1. Pra bencana yang meliputi:
- situasi tidak terjadi bencana
- situasi terdapat potensi bencana
2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana
3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana
2.4 Definisi Partisipatif
Berdasarkan Purnamasari, 2008 secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris
“participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa
Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan,
keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam
pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut
membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di
dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat
yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.
Adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat
membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil
pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo 2005 :26) mengemukakan bahwa pada
dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana.
Keterlibatan masyarakatdapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif
dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan
usulan kepada pemerintah.
Adapun bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Robert
(dalam Soemarmo, 2005) bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal
dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif menurut Robert dibagi atas
perencanaan sebagai aktivitas perencana dan aktivitas Masyarakat, digambarkan sebagai
berikut:
Gambar 4 Peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Alternatif Kebijakan dan Program
Berdasarkan gambar di atas, partisipasi masyarakat berada pada tahap pemilihan alternatif
kebijakan dan program sementara penetapan tujuan, dan sasaran kebijakan dilakukan secara
bersama dengan perencana. Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran
dan kebijakan secara bersama antara asyarakat dan perencana menurut Mc Connel (dalam
Soemarmo, 2005) merupakan input sekaligus sebagai ekspresi dan aspirasi masyarakat.
Alexander Abe (2002:81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai
berikut: “perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan
kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung
maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan
untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan
sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.”
Adapun menurut Adimiharja (2004), Perencanaan partisipatif dapat dilakukan jika praktisi
pembangunan tidak berperan sebagai perencana untuk masyarakat tetapi sebagai pendamping
dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat.
2.5 Langkah-langkah Perencanaan Partisipatif
Menurut Abe dalam Purnamasari, 2009 dikemukakan bahwa langkah-langkah dalam
perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga
perencanaan sebagai berikut:
Gambar 5 Langkah-langkah Perencanaan Partisipatif
Sumber : Abe dalam Purnamasari, 2009
Langkah-langkah di atas, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:
a. Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan
persoalan-persoalan bersifat local yang berkembang di masyarakat.
b. Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan.
c. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga
diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
d. Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit
(uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah
ditetapkan.
e. Rumusan Tujuan. Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang
diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk
mencapainya.
f. Langkah rinci. Penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang
akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh,
perencanaan dalam sebuah rencana tindak.
g. Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha
untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.
Perencanaan partisipatif dapat dilakukan di pembangunan wilayah, pembangunan desa,
pembangunan sosial melalui pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan pasca bencana
karena pembangunan lebih secara langsung bersinggungan dengan masyarakat sehingga
masyarakat dapat berperan lebih banyak dalam perencanaan.
2.6 Partisipasi Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana
Menurut Mercer (2009), perencana harus melibatkan kearifan lokal dan ilmu pengetahuan
untuk mengurangi resiko bencana. Dalam hal ini peran masyarakat sangatlah vital karena
masyarakat pribumi yang harus aktif berpartisipasi untuk mengurangi kerentanan komunitas
dan bahaya lingkungan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Zamroni (2011) bahwa
gaya hidup masyarakat Jawa mengutamakan sikap nrimo, sabar, waspada –eling andhap asor
dan Prasaja (Molder, 1983 dalam Zamroni). Sikap ini tercermin dari masa tanggap darurat
Merapi pada tahun 2010 dimana solidaritas sosial orang jawa tersebut dapat diamati secara
jelas dan nyata. Rakyat bergerak lebih cepat daripada pemerintah yang menunjukkan
komunitas lokal memiliki kecerdasan lokal sehingga lebih tanggap terhadap bencana.
Menurut Ganapati (2009), masyarakat harus aktif dilibatkan dalam perencanaan pasca
bencana sehingga masyarakat tidak dianggap sebagai penerima manfaat saja. Selain itu
Pemda dan Organisasi Berbasis Masyarakat hendaknya dilibatkan dalam proses perencanaan
melalui diskusi dan konsultasi. Pendekatan yang dilakukan dalam rekonstruksi sebaiknya
tidak berbasis proyek sehingga lemahnya kapasitas lokal. Masyarakat sebaiknya dilibatkan
sebelum rencana ditetapkan sehingga aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam rencana.
Selain itu berdasarkan Lutfiana (2013), pemerintah lebih fokus dalam pemulihan fisik pasca
bencana seperti rekonstruksi perumahan dan infrastruktur sehingga pemulihan kondisi sosial
ekonomi terkadang terabaikan. Sedangkan menurut Wimbardana (2009) pembangunan fisik
lebih diutamakn karena bentuknya jelas dan dapat berdampak luas terhadap komunitas dalam
jangka waktu pendek. Pemulihan sosial ekonomi dapat dilakukan melalui pemantapan sosial
ekonomi komunitas seperti yang terjadi di Gunung Merapi.
Partisipasi masyarakat pasca bencana juga melibatkan masyarakat luas tidak hanya di lokasi
bencana seperti yang dituliskan oleh Andayani (2011) dimana dana masyarakat yang
dikumpulkan oleh media massa cetak maupun elektronik melalui pembukaan rekening amal.
Keterlibatan masyarakat di daerah bencana juga diaktifkan dalam pemulihan dini dalam
bentuk program padat karya dan gotong royong sehingga masyarakat mendapatkan ruang
berpartisipasi dan mendapatkan kesempatan bangkit kembali dari kehidupannya.
Adapun berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
c. Pengembangan budaya sadar bencana;
d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
e. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
III. PEMBAHASAN
Ancaman bencana merupakan hal yang harus dihadapi secara bersama. Seluruh pihak ikut
bertanggung jawab dalam mempersiapkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang peka dan
waspada terhadap bencana. Dalam melaksanakan penanggulangan becana di daerah akan
memerlukan koordinasi antar sektor (perencanaan kolaboratif). Secara garis besar dapat
diuraikan peran dan potensi masyarakat menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun
2008 adalah sebagai berikut :
1) Masyarakat
Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana
harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana
tidak berkembang ke skala yang lebih besar.
2) Swasta
Peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada
saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas
dari sektor swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam
menghadapi bencana.
3) Lembaga Non-Pemerintah
Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan
yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik
lembaga Non Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya
penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana.
4) Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian
Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan
ilmupengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu diperlukan kontribusi pemikiran
dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.
5) Media
Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu peran
media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana
melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa
peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan
kebencanaan kepada masyarakat.
6) Lembaga Internasional
Pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada
saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Namun demikian harus
mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan pada tahap tahap prabencana, saat tanggap darurat,
dan pascabencana karena masyarakat yang berhadapan langsung dengan bencana. Dalam
kaitannya dengan pengurangan resiko bencana maka upaya yang dapat dilakukan adalah
melalui pengurangan tingkat kerentanan, karena hal tersebut relatif lebih mudah
dibandingkan dengan mengurangi/memperkecil bahaya/hazard.
Gambar 6 Konsepsi Pengurangan Resiko Bencana
Selanjutnya partisipasi masyarakat di kawasan rawan bencana berdasarkan jenis kegiatan
menurut Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Partisipasi masyarakat dibagi
berdasarkan tahapan yaitu pra bencana berupa kegiatan pencegahan dan mitigasi, Pra bencana
saat terdapat Potensi bencana berupa kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana
(rehabilitasi dan rekonstruksi).
Tabel 1 Analisis Partisipasi Masyarakat
Tahap
Kegiatan (Peraturan
Kepala BNPB No.4
Tahun 2008)
Tinjauan Literatur
(Jurnal) Bentuk Partisipasi Masyarakat Analisis
Contoh
Lokasi
Pra Bencana Pencegahan dan
Mitigasi
Mitigasi Pasif
Penyusunan peraturan,
Pembuatan Peta Rawan
Bencana, Analisis
Resiko dan Bahaya,
Litbang, Pembentukan
forum masyarakat
Mitigasi Aktif
Penempatan tanda
peringatan, Penyuluhan,
Pelatihan dasar
kebencanaan,
Pengembangan SDM.
Pratiwi (2013) menyebutkan
Perencanaan di kawasan pasca
bencana dapat menciptakan
lingkungan permukiman yang
antisipatif terhadap
kemungkinan bencana.
Mercer (2009), perencana harus
melibatkan kearifan lokal dan
ilmu pengetahuan untuk
mengurangi resiko bencana.
a. Masyarakat penyuluhan
dalam mempersiapkan diri
dan lingkungannya
menghadapi bencana
b. Masyarakat ikut serta dalam
memberikan informasi sesuai
dengan kearifan lokal daerah
masing-masing guna
mewujudkan lingkungan yang
antisipatif terhadap bencana
meliputi desain bangunan,
bahan bangunan dll.
c. Akademisi dan Peneliti
melakukan penelitian terkait
lingkungan permukiman yang
antisipatif terhadap
kemungkinan bencana
Pemerintah mengamanatkan pelaksanaan persiapan
masyarakat pada pra bencana pada daerah-daerah
yang rawan bencana. Hal ini diharpkan dapat
meningkatkan kapasitas masyarakat yang tanggap
terhadap bencana sehingga dapat mengurangi
besarnya resiko bahaya. Jalur evakuasi, bangunan
dan bukit evakuasi beserta penunjuk arahnya sudah
disediakan tetapi ternyata pada prakteknya di Aceh
masih ditemui permasalahan misalnya sempitnya
jalur evakuasi. Semakin bertambah waktu Indonesia
menjadi semakin lebih baik persiapannya pada pra
bencana. Bahkan saat ini telah disusun Rencana
Pengurangan Resiko Bencana di kawasan-kawasan
Rawan Bencana oleh KemenPU. Tetapi idak kalah
penting yaitu perlunya arahan dan kontrol supaya
pelasanaan rencana tersebut berjalan optimal.
Selain itu dalam merencanakan lingkungan juga
harus memperhatikan kearifan dan budaya lokal
karena pada umumnya masyarakat pribumi
memiliki pengetahuan tidak tertulis terkait
pengurangan resiko bencana.
Aceh, DIY,
Kep.
Mentawai
Pra bencana
saat terdapat
Potensi
bencana
Kesiapsiagaan
Pembentukan POSKO,
pelatihan siaga/
simulasi, peringatan,
rencana kontingensi,
mobilisasi sumber daya
dll.
a. Masyarakat membentuk posko
peringatan bencana dan
melakukan pembagian job desk
terhadap anggota posko dan
menyusun rencana kontingensi
b. Masyarakat mengikuti pelatihan
bencana secara berkala seperti
yang telah dilakukan di Aceh
dengan mengikuti petunjuk
yang telah ditentukan.
Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi
kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari
jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan
berubahnya tata kehidupan masyarakat. Masyarakat
secara rutin telah mengikuti pelatihan
siaga/simulasi sehingga diharapkan masyarakat
lebih tanggap terhadap bencana dan mengetahui
langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika
terjadi bencana.
Kawasan
Rawan
Bencana :
Aceh, Nias,
DIY, Jateng
Tanggap
Darurat
Pernyataan Bencana,
Bantuan Darurat
Rakyat bergerak lebih cepat
daripada pemerintah yang
menunjukkan komunitas lokal
a. Pemberian bantuan darurat
oleh sektor swasta, NGO
b. Solidaritas sosial warga dalam
Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap
penindakan atau pengerahan pertolongan untuk
membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna
Solidaritas
Sosial di
DIY, Jawa
Tahap
Kegiatan (Peraturan
Kepala BNPB No.4
Tahun 2008)
Tinjauan Literatur
(Jurnal) Bentuk Partisipasi Masyarakat Analisis
Contoh
Lokasi
memiliki kecerdasan lokal
sehingga lebih tanggap terhadap
bencana (Zamroni, 2011)
Dana masyarakat yang
dikumpulkan oleh media massa
cetak maupun elektronik melalui
pembukaan rekening amal
menolong sesama pada masa
tanggap darurat
menghindari bertambahnya korban jiwa.
Masyarakat saling menolong setelah terjadinya
bencana seperti yang terjadi di DIY dimana rakyat
bergerak cepat menolong sesama yang
menunjukkan budaya gotong royong. Selain itu
kepedulian masyarakat di wilayah lain juga
ditunjukkan melalui aksi bantuan melalui media
massa baik cetak maupun elektronik, bantuan dari
swasta serta NGO.
Tengah
Pasca
Bencana
Kaji Bencana,
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Ganapati dan Ganapati
(2009), masyarakat harus
aktif dilibatkan dalam
perencanaan. Selain itu
Pemda dan Organisasi
Berbasis Masyarakat
hendaknya dilibatkan dalam
proses perencanaan melalui
diskusi dan konsultasi.
Pendekatan yang dilakukan
dalam rekonstruksi sebaiknya
tidak berbasis proyek
sehingga lemahnya kapasitas
lokal.
a. Masyarakat sudah dilibatkan
melalaui program
REKOMPAK JRF yang
dikelola oleh Kementerian
PU. Program ini melibatkan
partisipasi total masyarakat
dalam rekonstruksi dan
rehabilitasi perumahan pasca
bencana.
b. Selain itu masyarakat juga
diberdayakan untuk lebih
peduli terhadap
lingkungannya, dan
berinovasi untuk
pengembangan
lingkungannya.
Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan
rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap
rehabilitasi adalah untuk mengembalikan
kondisi daerah yang terkena bencana yang serba
tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik,
agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat
berjalan kembali. Sedangkan tahap rekonstruksi
merupakan tahap untuk membangun kembali sarana
dan prasarana yang rusak akibat bencana secara
lebih baik dan sempurna. Oleh sebab itu
pembangunannya harus dilakukan melalui suatu
perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari
berbagai ahli dan sektor terkait. Masyarakat sudah
berperan aktif dalam program rekonstruksi dan
rehabilitasi pasca bencana. Adapun pendekatan
yang dilakukan tidak berbasis proyek tetapi
pemberdayaan. Anggaran REKOMPAK JRF ini
dalam bentuk bantuan sosial bukan belanja modal
(berbasis proyek). Metode yang digunakan pada
umumnya menggunakan Participatory Research
Appraisal (PRA) dimana masyarakat yang
menentukan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi
potensi masalah dan daya dukung, menyusun
rencana dan strategi serta menyusun prioritas.
Aceh, DIY,
Jateng,
Pangandaran
(Jabar)
Sumber : Hasil Analisis, 2014
Berdasarkan tabel di atas maka sudah terlihat adanya tanda partisipasi (Arnstein,1969 dalam
Ganapati, 2009). Proses partisipasi sudah diupayakan untuk dilaksanakan pada tahapan pra
bencana, saat terjadi potensi bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Tanda partisipasi
ditunjukkan melalui peran serta masyarakat pada pra bencana berupa keikutsertaan
masyarakat dalam memberikan informasi dan aspirasi dalam perencanaan kawasan rawan
bencana berdasarkan kearifan lokal. Selain itu dalam tahap pasca bencana juga terdapat tanda
partisipasi berupa keikutsertaan warga dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana
dimana masyarakat aktif dalam penyusunan rencana permukiman, pembangunan dan
pengelolaan lingkungan seperti yang terjadi DIY dan Jawa Tengah. Tetapi intensitas
partisipasi warga juga tergantung pada kearifan lokal di wilayah rawan bencana dan
pengalaman serta pengetahuan masyarakat terkait bencana (kesiapsiagaan). Terkadang
partisipasi masyarakat tidak optimal di beberapa wilayah karena budaya masyarakat yang
berbeda dan faktor kesiapsiagaan.
IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penulisan paper dengan judul “Partisipasi Masyarakat Pada Kawasan Rawan
Bencana Di Indonesia (Pra Bencana, Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana” anatara lain
sebagai berikut :
a. Masyarakat sudah aktif dilibatkan dalam tahapan pra bencana, saat terjadi potensi
bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di kawasan rawan bencana. Tanda
partisipasi ditunjukkan melalui peran serta masyarakat pada pra bencana berupa
keikutsertaan masyarakat dalam memberikan informasi dan aspirasi dalam perencanaan
kawasan rawan bencana berdasarkan kearifan lokal, kepedulian saling menolong
sesama melalui bantuan sosial, gotong royong dll.
b. Masyarakat yang berperan aktif tersebut meliputi masyarakat di daerah rawan bencana
(korban bencana), media massa, akademisi (perguruan tinggi), swasta dan NGO.
c. Perlunya koordinasi yang efektif dan kerjasama antar pihak (Kementerian/Lembaga dan
OPD) di semua tingkatan dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan
mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
d. Bencana merupakan permasalahan bersama maka diperlukan koordinasi yang efektif
dan efisien = perencanaan kolaboratif yang melibatkan seluruh stakeholder baik
pemerintah dan swasta di kawasan rawan bencana.
DAFTAR PUSTAKA
Adimihardja, Kusnaka. 2004. Participatory Research Appraisal dalam Pengabdian Kepada
Masyarakat. Bandung : Humaniora
Bappenas. 2006. Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana
Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah
Ganapati, Sukumar & Ganapati. 2009. Enabling Participatory Planning After Disasters : A
Case Study of The World Bank’s Housing Reconstruction in Turkey. Journal of The
American Planning Association, Winter 2009, Vol. 75 No.1
Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. Pedoman Pendampingan Penanganan Kawasan Rawan
Bencana Longsor. http://www.rekompakjrf.org/download/Pedoman%20Pendampingan
%20Penanganan%20Kawasan%20Rawan%20Bencana%20Longsor%20Rekompak%20
JRF.pdf diakses 12 Mei 2014
Lutfiana, Dian. 2013. Exploring Social Capital Role To Restore Community Resilience After
West Java Earthquake: Case Study Pangalengan Sub-District, Bandung Region, West
Java. Disampaikan dalam Planocosmo 2013, SAPPK ITB
Mercer, Jessica, Ilan Kelman, Lorin Taranis and Sandie Suchet-Pearson. 2006. Framework
for integrating indigenous and scientific knowledge for disaster risk
reduction.http://web.mit.edu/.../Mercer-DRR-CC-Reiven..Diakses 12 Mei 2014
Purnamasari, Irma. 2008. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di
Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Thesis. Magister Ilmu Administrasi,
Universitas Diponegoro, Semarang. http://eprints.undip.ac.id/17845/1/
IRMA_PURNAMASARI.pdf diakses 12 Mei 2014
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Pratiwi, Wiwik. D. 2012. Perencanaan perumahan dan permukiman untuk antisipasi bencana.
Disampaikan dalam Planocosmo 2012, SAPPK ITB
Soemarmo, 2005, Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan
Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi
Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik), Tesis, Magister Administrasi Publik,
Universitas Diponegoro, Semarang.