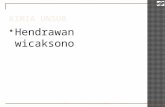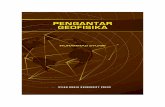OSEANOGRAFI GEOFISIKA KIMIA
-
Upload
universitasjenderalsoedirman -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of OSEANOGRAFI GEOFISIKA KIMIA
LAPORAN PRAKTIKUM
OSEANOGRAFI GEOFISIKA KIMIA
Oleh :
Adad Furqon Al Hadad
NIM. H1K012034
Asisten: Antares Bagas Saputra
JURUSAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Oseanografi Geofisika Kimia.
Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dr. Agung Dhamar Syakti, DEA selaku dosen pengampu mata kuliah Oseanografi
Geofisika Kimia yang telah memberikan petunjuk dalam setiap kegiatan praktikum.
2. Seluruh asisiten praktikum Oseanografi Geofisika Kimia yang telah memeberikan
arahan dan petunjuk selama berlangsungnya kegiatan praktikum.
3. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu kritik
dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.
Purwokerto, 11 Desember 2014
Penulis
DAFTAR ISI
hal
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI.................................................................................................................................. 3
DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... 5
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................... 6
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................. 7
I. PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 8
1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 8
1.2. Tujuan................................................................................................................................... 9
II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................................................... 10
2.1. Parameter Geologi .............................................................................................................. 10
2.1.1. Sediment ......................................................................................................................... 10
2.2. Parameter Fisika ................................................................................................................. 10
2.2.1. Suhu ............................................................................................................................. 10
2.2.2. Kecepatan Arus ............................................................................................................ 11
2.2.3. Kecerahan .................................................................................................................... 12
2.2.4. Pasang Surut ................................................................................................................ 13
2.3. Parameter Kimia ................................................................................................................. 15
2.3.1. Nitrat ............................................................................................................................ 15
2.3.2 Klorofil-a ...................................................................................................................... 16
III. MATERI METODE ............................................................................................................. 18
3.1. Materi ................................................................................................................................. 18
3.1.1. Alat .............................................................................................................................. 18
3.1.2. Bahan ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2. Metode ................................................................................................................................ 19
3.2.1 Sedimen ........................................................................................................................ 19
3.2.1.1. Pengambilan Sedimen .............................................................................................. 19
3.2.1.2. Analisa Sampel Sedimen .......................................................................................... 19
3.2.2. Nitrat................................................................................................................................ 19
3.2.2.1. Pembuatan larutan induk nitrat ................................................................................. 19
3.2.2.2. Pembuatan larutan baku nitrat, NO3 N ..................................................................... 20
3.2.2.3. Cara Uji..................................................................................................................... 20
3.2.1.2. Perhitungan ............................................................................................................... 20
3.2.3. Kecerahan .................................................................................................................... 20
3.2.4. Kecepatan Arus ............................................................................................................ 21
3.2.5. Pasang Surut ................................................................................................................ 21
3.2.6. Klorofil-a ..................................................................................................................... 21
3.3. Waktu Dan Tempat ............................................................................................................ 22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................................................. 23
4.1. Pembahasan ........................................................................................................................ 23
4.1.1 Deskripsi Lokasi ............................................................................................................... 23
4.1.2. Parameter geologi ........................................................................................................... 23
4.1.2.1. Sedimen ........................................................................................................................ 23
4.1.3. Parameter Fisika ............................................................................................................. 25
4.1.3.1. Suhu ......................................................................................................................... 25
4.1.3.2. Kecepatan Arus ........................................................................................................ 25
4.1.3.3. Kecerahan ................................................................................................................ 26
4.1.3.4. Pasang Surut ............................................................................................................ 27
4.1.4. Parameter Kimia .............................................................................................................. 29
4.1.4.1. Klorofil-a .................................................................................................................. 29
4.1.4.2 Nitrat .......................................................................................................................... 29
4.1.4.3. Salinitas .................................................................................................................... 30
V. KESIMPULAN....................................................................................................................... 31
5.1. Kesimpulan......................................................................................................................... 31
5.2. Saran ................................................................................................................................... 31
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. 32
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................... 34
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Alat Praktikum ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. Bahan Praktikum.............................................................. Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Grafik Kecepatan Arus................................................................................................ 26
Gambar 2. Grafik Kecerahan ........................................................................................................ 27
Gambar 3. Grafik Pasang Surut .................................................................................................... 28
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Hasil Perhitungan ............................................................................................. 34
Lampiran 2. Foto-foto Kegiatan Praktikum .................................................................................. 37
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Oseanografi adalah kombinasi dari dua kata yunani: oceanus (samudera) dan graphos
(uraian/deskripsi) sehingga oseanografi mempunyai arti deskripsi tentang samudera. Tetapi
lingkup oseanografi pada kenyataan lebih dari sekedar deskripsi tentang samudera, karena
samudera sendiri akan melibatkan berbagai disiplin ilmu jika ingin diungkapkan. Oseanografi
dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari lautan. (Supangat dan
Susanna, 2008).
Planet Bumi merupakan anggota tata surya yang unik di mana samudera melingkupi ±
140 juta mil persegi dari total ± 200 juta mil persegi luas permukaannya. Ini berarti
samudera meliputi sekitar 70 persen permukaan bumi dengan volume air yang dikandungnya
± 350 juta mil kubik. Di dalamnya juga terkandung 3,5 persen garam terlarut disamping
zat-zat terlarut lainnya yang sebanding dengan 160 juta ton garam per mil kubik (Bhatt,
1978).
Oseanografi sendiri seringkali diungkapkan berdasarkan empat kategori keilmuan yaitu
fisika, biologi, kimia, dan geologi (Stowe,1983). Oseanografi fisis khusus mempelajari segala
sifat dan karakter fisik yang membangun sistem fluidanya. Oseanografi biologi mempelajari
sisi hayati samudera guna mengungkap berbagai siklus kehidupan organisme yang hidup di
atau dari samudera. Oseanografi kimia melihat berbagai proses aksi dan reaksi antar unsur,
molekul, atau campuran dalam sistem samudera yang menyebabkan perubahan zat secara
reversibel atau ireversibel. Dan oseanografi geologi memfokuskan pada bangunan dasar
samudera yang berkaitan dengan struktur dan evolusi cekungan samudera.
Karimun Jawa adalah nama kepulauan di sebelah utara pulau jawa, letaknya kurang lebih
83 km dari kota Jepara Jawa Tengah dan telah ditetapkan menjadi Taman Nasional sejak tahun
2001. Kepulauan Karimun Jawa memiliki tipe ekosistem beraneka ragam, seperti hutan pantai,
mangrove forest, ikan hias dan terumbu karang. Sebutan 'karimun jawa the virginal tropical
paradise' memang sangat tepat, sebab Karimun jawa memiliki pulau yang berjumlah 27 buah
namun baru 4 saja yang berpenghuni. Kepulauan Karimun jawa merupakan kawasan konservasi
laut yang memiliki kandungan potensi keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistem laut yang
khas. Karena kandungan potensi tersebut serta letaknya yang berada pada lintasan wisata bahari
antara Indonesia Bagian Barat dan Timur menjadikan wilayah ini sebagai obyek wisata bahari
yang strategis (Gita, 2002).
1.2. Tujuan
1. Mahasiswa dapat melakukan pengamatan dan pengukuran : parameter geologi, fisika dan
kimia laut.
2. Mahasiswa dapat menganalisa parameter geologi, fisika dan kimia laut.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Parameter Geologi
2.1.1. Sediment
Sedimen air laut adalah partikel-partikel yang berasal dari hasil pembongkaran batuan-
batuan dan potongan-potongan kulit (shell) serta sisa-sisa rangka-rangka organisme laut (Siaka,
2009). Tidaklah mengherankan jikalau ukuran partikel-partikel ini sangat ditentukan oleh sifat-
sifat fisik mereka dan akibatnya sedimen yang terdapat pada berbagai tempat di dunia
mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda satu sama lain. Misalnya sebagian besar dasar laut
yang dalam ditutupi oleh jenis partikel yang berukuran kecil yang terdiri dari sedimen halus.
Sedangkan hampir semua pantai ditutupi oleh partikel berukuran besar yang terdiri dari sedimen
kasar (Ronowicz, 2012).
Berdasarkan asalnya sedimen dapat dibagi menjadi tiga bagian:
1. Sedimen lithugeneus, jenis sedimen ini berasal dari sisa pengikisan batu-batuan di daratan,
yang diangkut ke laut oleh sungai-sungai.
2. Sedimen biogenus, jenis sedimen ini berasal dari sisa-sisa rangka dari organisme hidup yang
membentuk endapan partikel-partikel halus yang dinamakan ooze yang biasanya diendapkan
pada daerah yang jauh dari pantai. Sedimen ini digolongkan ke dalam dua tipe yaitu calcareous
dan siliceous.
3. Sedimen hidrogeneus. Jenis partikel dari sedimen golongan ini dibentuk sebagai hasil reaksi
kimia dalam air laut. (Hutabarat dan Evans, 1984)
2.2. Parameter Fisika
2.2.1. Suhu
Temperatur adalah ukuran energi gerakan molekul. Di samudra temperatur bervariasi
secara horizoltal sesuai dengan garis lintang, dan juga secara vertical sesuai dengan kedalaman.
Temperature merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan
dan penyebaran organisme (Nyabakken,1988). Air mempunyai daya muat panas yang lebih
tinggi daripada daratan. Akibatnya untuk menaikan suhu sebesar 1 C, air akan membutuhkan
energi yang lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh daratan dalam jumlah massa yang sama.
Dengan kata lain dengan jumlah pemanasan yang sama, daratan akan lebih cepat menjadi panas
dari pada lautan. Demikian juga kebalikannya, lautan lebih efektif untuk menyimpan panas yang
diterima daripada daratan, sehingga pada waktu tidak ada pemanasan (malam hari) lautan akan
memerlukan waktu yang lebih lama untuk menjadi dingin daripada daratan (Hutabarat dan
Evans, 1986). Sidjabat (1978) dalam hafidz 2003, suhu air laut, terutama lapisan permukaan,
ditentukan oleh pemanasan matahari yang intensitasnya senantiasa berubah terhadap waktu,
sehingga suhu air laut akan konsonan dengan perubahan intensitas penyinaran matahari tersebut.
Perubahan suhu ini dapat terjadi secara : (1) harian, (2) musiman, (3) tahunan, dan (4) jangka
panjang.
Selanjatnya dikatakan bahwa jika suatu perairan yang homogen dan tenang dipanasi oleh
matahari, distribusi suhu secara vertikal akan menurun eksponensial ke bawah. Apalagi jika tidak
ada gangguan pada perairan ini, keadaan perairan akan selalu stabil karena lapisan yang paling
atas yang lebih panas akan lebih rendah densitasnya dari pada lapisan bawah (Sidjabat, 1978
dalam hafidz 2003).
2.2.2. Kecepatan Arus
Arus merupakan salah satu faktor terpenting dalam mempengaruhi kesuburan air laut.
Arus dapat membawa nutrisi dari suatu perairan ke perairan lainnya. Sverdrup dkk (1972) dalam
Arinardi (1979) membagi arus laut ke dalam tiga golongan besar, yaitu :
1). Arus yang disebabkan oleh perbedaan sebaran densitas di laut. Arus ini disebabkan oleh air
yang berdensitas lebih berat akan mengalir ke tempat air yang berdensitas kecil atau lebih ringan.
Arus jenis ini biasanya membawa sejumlah besar air dari suatu tempat ke tempat lain;
2). Arus yang ditimbulkan oleh angin yang berhembus di permukaan laut. Arus jenis ini biasanya
membawa air kesatu jurusan dengan arah yang sama selama satu musim tertentu ;
3). Arus yang disebabkan oleh air pasang. Arus jenis ini mengalirnya bolak-balik dari dan ke
pantai, atau berputar. Arus air pasang dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari terhadap
bumi dan datangnya secara periodic sehingga dapat di ramalkan.
2.2.3. Kecerahan
Kecerahan perairan adalah suatu kondisi yang menunjukan kemampuan cahaya untuk
menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada perairan alami kecerahan sangat penting
karena erat kaitannya dengan aktifitas fotosistesa. Kecerahan air laut dipengaruhi oleh substensi
material organik dan anorganik yang larut didalamnya, dan organisme renik seperti plankton. Air
yang terkontaminasi oleh berbagai jenis material akan berubah warna sehingga menjadi keruh.
Klasifikasi sedimen juga dapat dilakukan berdasarkan kecepatan pengendapanya
(Koesoemadinata, 1980).
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerahan adalah kandungan lumpur, padatan
tersuspensi, plankton dan bahan-bahan terlarut lainnya. Perairan yang memiliki kecerahan yang
rendah pada cuaca normal memberikan suatu indikasi banyaknya partikel yang terlarut dan
tersuspensi ke dalam perairan. Keadaan tersebut dapat mengurangi laju fotosintesis sehingga
dapat mengganggu laju pernapasan hewan akuatik. Kecerahan menunjukkan kemampuan
penetrasi cahaya kedalam perairan. Tingkat penetrasi cahaya sangat dipengaruhi oleh partikel
yang tersuspensi dan terlarut dalam air sehingga mengurangi laju fotosintesis (Junaidi, 2011).
Faktor lain yang menentukan masuknya cahaya adalah antara lain absorbsi cahaya oleh partikel-
partikel air, kecerahan, pemantulan cahaya oleh permukaan air laut, musim dan lintang geografis
(Ifa et all, 2011).
2.2.4. Pasang Surut
Pasang surut dikenal sebagai gerakan osilasi permukaan air laut secara berkala dan turun
naik pada interval yang berbeda-beda (Mahlan, 1984). Perbedaan pasang-surut dipengaruhi oleh
gaya gravitasi bulan dan matahari, pada saat bulan purnama air pasang akan lebih tinggi bila
dibandingkan saat air pasang ketika matahari bersinar tegak di siang hari. Hal tersebut
disebabkan oleh gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada gravitasi matahari dikarenakan jarak
bulan ke bumi lebih dekat bila dibandingkan dengan jarak matahari ke bumi. Faktor lain yang
dapat menyebabkan perberdaan ketinggian pasang surut air laut yaitu gaya sentrifugal dari proses
rotasi bumi dan beberapa faktor lokal, seperti adanya rensonasi lokal akibat morfologi teluk,
pantai dan estuari.
Pasang surut dikenal sebagai gerakan osilasi permukaan air laut secara berkala dan turun
naik pada interval yang berbeda-beda (Mahlan, 1984). Perbedaan pasang-surut dipengaruhi oleh
gaya gravitasi bulan dan matahari, pada saat bulan purnama air pasang akan lebih tinggi bila
dibandingkan saat air pasang ketika matahari bersinar tegak di siang hari. Hal tersebut
disebabkan oleh gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada gravitasi matahari dikarenakan jarak
bulan ke bumi lebih dekat bila dibandingkan dengan jarak matahari ke bumi. Faktor lain yang
dapat menyebabkan perberdaan ketinggian pasang surut air laut yaitu gaya sentrifugal dari proses
rotasi bumi dan beberapa faktor lokal, seperti adanya rensonasi lokal akibat morfologi teluk,
pantai dan estuari.
Perairan laut memberikan respon yang berbeda terhadap gaya pembangkit pasang surut,
sehingga terjadi tipe pasut yang berlainan di sepanjang pesisir. Menurut Dronkers (1964), ada
tiga tipe pasut yang dapat diketahui, yaitu :
1. Pasang surut diurnal. Yaitu bila dalam sehari terjadi satu satu kali pasang dan satu kali
surut. Biasanya terjadi di laut sekitar katulistiwa.
2. Pasang surut semi diurnal. Yaitu bila dalam sehari terjadi dua kali pasang dan dua kali
surut yang hampir sama tingginya.
3. pasang surut campuran. Yaitu gabungan dari tipe 1 dan tipe 2, bila bulan melintasi
khatulistiwa (deklinasi kecil), pasutnya bertipe semi diurnal, dan jika deklinasi bulan mendekati
maksimum, terbentuk pasut diurnal.
Menurut Wyrtki (1961), pasang surut di Indonesia dibagi menjadi 4 yaitu :
1. Pasang surut harian tunggal (Diurnal Tide) Merupakan pasut yang hanya terjadi satu kali
pasang dan satu kali surut dalam satu hari, ini terdapat di Selat Karimata
2. Pasang surut harian ganda (Semi Diurnal Tide) Merupakan pasut yang terjadi dua kali
pasang dan dua kali surut yang tingginya hampir sama dalam satu hari, ini terdapat di Selat
Malaka hingga Laut Andaman.
3. Pasang surut campuran condong harian tunggal (Mixed Tide, Prevailing Diurnal)
Merupakan pasut yang tiap harinya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut tetapi terkadang
dengan dua kali pasang dan dua kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu, ini
terdapat di Pantai Selatan Kalimantan dan Pantai Utara Jawa Barat.
4. Pasang surut campuran condong harian ganda (Mixed Tide, Prevailing Semi Diurnal)
Merupakan pasut yang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari tetapi terkadang
terjadi satu kali pasang dan satu kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda, ini
terdapat di Pantai Selatan Jawa dan Indonesia Bagian Timur.
nitrosomonas
nitrobakter
2.3. Parameter Kimia
2.3.1. Nitrat
Nitrat (NO3) adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrient
utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrat sangat mudah larut dalam air dan bersifat
stabil. Senyawa ini dihasilkan dari proses oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan.
Nitrifikasi yang merupakan proses oksidasi ammonia menjadi nitrit dan nitrat adalah proses yang
penting dalam siklus nitrogen dan berlangsung pada kondisi aerob. Oksidasi ammonia menjadi
nitrit dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas,sedangkan oksidasi nitrit menjadi nitrat dilakukan
oleh bakteri Nitrobacter. Kedua jenis bakteri tersebut merupakan bakteri kemotrofik, yaitu
bakteri yang yang mendapatkan energi dari proses kimiawi. Oksidasi nitrit menjadi ammonia
ditunjukan dalam persamaan berikut (a). Sedangkan oksidasi nitrit menjadi nitrat ditujukan
dalam persamaan (b).
2NH3 + 3O2 2NO2
+ 2H+
+ 2H2O (a)
2NO3 + O2 2NO3 (b)
Nitrat menyebabkan kualitas air menurun, menurunkan oksigen terlarut, penurunan
populasi ikan, bau busuk, rasa tidak enak. Nitrat adalah ancaman bagi kesehatan manusia
terutama untuk bayi, menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai methemoglobinemia, yang juga
disebut "sindrom bayi biru". Air tanah yang digunakan untuk membuat susu bayi yang
mengandung nitrat, saat nitrat masuk kedalam tubuh bayi nitrat dikonversikan dalam usus
menjadi nitrit, yang kemudian berikatan dengan hemoglobin dan membentuk methemoglobin,
sehingga mengurangi daya angkut oksigen oleh darah (Tresna, 2000).
Pengambilan sampel untuk analisis kadar nitrat biasanya dilakukan dengan cara
memasukannya ke dalam botol plastik atau botol kaca gelap untuk mencegah masukknya sinar
matahari kedalam botol karena dapat mengurangi kadar nitrat. Sampel yang di dalam botol
letakan pada suhu 4oC atau lebih rendah dan di analisa dalam jangka waktu 24-28 jam, hal ini
dilakukan untuk menghidari terjadinya nitrifikasi yang terjadi pada suhu optimum 20oC – 25oC.
Nilai pH obtimum bagi nitrifikasi adalah 8-9. Pada pH< 6 proses nitrifikasi akan terhenti, bakteri
yang melakukan nitrifikasi cenderung menempel pada sedimen dan bahan padatan lain
(Effendi.2003).
2.3.2 Klorofil-a
Klorofil merupakan parameter yang sangat menentukan produktivitas primer lautan.
Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil berkaitan langsung dengan kondisi
oseanografi perairan itu sendiri. Beberapa parameter fisika-kimia yang mengontrol serta
mempengaruhi sebaran klorofil adalah intensitas cahaya dan nutrien (terutama nitrat, fosfat dan
silikat) (Sverdrup et al., 1961).
Hatta (2002), menyatakan bahwa umumnya sebaran konsentrasi klorofil tinggi di
perairan pantai sebagai akibat dari tingginya suplai nutrien yang berasal dari daratan melalui
limpasan air sungai. Namun sebaliknya cenderung rendah di daerah lepas pantai karena pada
daerah lepas pantai ini tidak mendapat suplai nutrien dari daratan. Walaupun demikian pada
beberapa tempat yang jauh dari daratan masih ditemukan konsentrasi klorofil yang tinggi.
Keadaan ini terjadi akibat adanya proses sirkulasi massa air yang memungkinkan terangkutnya
sejumlah nutrien dari daerah lain,seperti yang terjadi pada daerah upwelling. Ketersediaan
nutrien dan intensitas cahaya matahari sangat mempengaruhi konsentrasi klorofil-a suatu
perairan. Apabila nutrien dan intensitas cahaya matahari tersedia cukup, maka konsentrasi
klorofil akan tinggi begitu pula sebaliknya. Perairan di daerah tropis umumnya memiliki
konsentrasi klorofil yang rendah karena keterbatasan nutrien dan kuatnya stratifikasi kolom
perairan sebagai akibat pemanasan permukaan perairan yang terjadi sepanjang tahun.
Salah satu organisme yang hidup di ekosistem perairan pesisir adalah fitoplankton.
Fitoplankton di dalam ekosistem perairan berperan sebagai pengubah zat - zat anorganik menjadi
zat - zat organik melalui proses fotosintesis, yang kemudian dapat menentukan produktivitas
perairan. Proses fotosintesis memerlukan klorofil, sehingga kandungan klorofil – a pada
fitoplankton itu sendiri dapat dijadikan indikator tinggi rendahnya produktivitas suatu perairan
(Alkatiri dan Sardjana, 1998 dalam Roshisati, 2002).
Kandungan pigmen fotosintesis (terutama klorofil - a) dalam air sampel menggambarkan
biomassa fitoplankton dalam suatu perairan. Klorofil - a merupakan pigmen yang selalu
ditemukan dalam fitoplankton serta semua organisme autotrof dan merupakan pigmen yang
terlibat langsung (pigmen aktif) dalam proses fotosintesis. Jumlah klorofil – a pada setiap
individu fitoplankton tergantung pada jenis fitopl ankton, oleh karena itu komposisi jenis
fitoplankton sangat berpengaruh terhadap kandungan klorofil – a di perairan (Arifin, 2009)
III. MATERI METODE
3.1. Materi
3.1.1. Alat
Tabel 1. Alat Praktikum
No Nama Alat
Fungsi
1 Tiang Pasut Pengukuran Pasut
2 Thermometer Pengukuran Temperatur
3 Sechii Disc Pengukuran Kecerahan dan Kedalaman
4 Stop Watch Pengukuran Arus
5 Botol Air Mineral Pengukuran Arus, sampel air
6 Plastik zip Tempat Sampel
7 Shiev Sacker Memisahkan Butir Sedimen
8 Core Sampler & Ekman Grab Mengambil Sampel Sedimen
9 Botol Polietilen Sampel Nitrat
10 Ice Box Tempat Penyimpanan Semua Sampel
3.1.2. Bahan
Tabel 2. Bahan Praktikum
No Nama Bahan Fungsi
1 Aquades Pembersih Alat
2 Sampel Air Laut Pengukuran Ph dan Salinitas
3 HgCl2 Pengawetan Sampel Air
4 K NO3 Pembuatan Larutan Nitrat
5 NaCl Menguji Kadar Nitrat
6 HCl Analisis Klorofil-a
3.2. Metode
3.2.1 Sedimen
3.2.1.1. Pengambilan Sedimen
1. Menggunakan Sedimen Core
Menentukan tempat pengambilan sampel yang diperkirakan dapat mewakili kondisi
lapangan secara purposive method. Alat berupa pipa paralon (AW) denganpanjang 1 m dan
diameter 2 – 4 inch. Pipa paralon di benamkan ke dasar perairan sampai sedalam 50 cm,
masukkan plat besi / seng ke bagian dasar paralon sehingga sampel tidak jatuh padasaat pipa di
cabut / ditarik. Sampel dimasukkan kedalam wadah sampel dan dibawa di laboratorium.
2. Menggunakan Sedimen Grab
Mengikatkan ujung tali pada shackle grab, tekan jari grab kebawah sampai rahang grab
terbuka, pasang safety pen pada lubang safety pen, angkat grab kemudian turunkan sampai dasar
air, Angkat grab dan letakkan ke atas baki, miringkan grab untuk membuang air melalui jendela,
buka jendela grab pada bagian atas dan gunakan spatula dari plastik, ambil sedimen pada bagian
permukaan sampai kedalaman 5 cm.
3.2.1.2. Analisa Sampel Sedimen
1. Pengayakan ( Shieving )
Sampel di timbang, kemudian di saring dengan menggunakan shiev shaker bertingkat
berdiameter 2mm, 500µm, 300µm, 125µm, 63µm dan wadan untuk menampung sedimen yang
berdiameter < 63µm, kemudian masing masing sample ditimbang.
3.2.2. Nitrat
3.2.2.1. Pembuatan larutan induk nitrat
Kalium nitrat sebanyak 721, 8 mg, KNO3 dengan 100 mL air suling di dalam labu ukur
1000 mL dilarutkan. Air suling di tambahkan sampai tepat pada tanda tera.
3.2.2.2. Pembuatan larutan baku nitrat, NO3 N
Larutan induk Nitrat pada pipet 0,0 mL, 0,25 mL, 0,50 mL, 1,00 mL, 2,00 mL
dimasukkan masing-masing kedalam labu ukur 100 mL. Kemudan air suling ditambahkan
sampai tepat pada tanda tera sehingga diperoleh kadar Nitrat 0,00 ; 0,25 ; 0,50 ; 1,00 ; 2,00 mg/L
3.2.2.3. Cara Uji
Benda uji dalam pipet 10 mL dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer 50 mL. Larutan
NaCl 2 mL dan larutan asam sulfat 10 mL ditambahkan di aduk perlahan-lahan dan tunggu
sampai dingin. Larutan campuran brusin-asam sulfanilat ditambahkan di aduk perlahan-lahan
dan dipanaskan diatas penangas air pada suhu tidak melebihi 95º C selama 20 menit dan
didinginkan. Kemudian dimasukkan kedalam kuvet pada alat spektrofotometer, dibaca dan
dicatat serapan masuknya.
3.2.1.2. Perhitungan
Kadar nitrat-N dihitung dalam benda uji dengan menggunakan kurva kalibrasi atau
tentukan persamaan garis lurusnya. Selisih kadar maksimum yang diperbolehkan antara dua
pengukuran duplo adalah 2% kemudian rata-ratakan hasinlnya. Apabila hasil perhitungan kadar
nitrat-N lebih besar dari 2,00 mg/L, pengujian diulangi dengan cara mengencerkan benda uji.
3.2.3. Kecerahan
Sechii disc dimasukkan ke dalam air sampai warna hitam dan putih tidak terlihat, dicatat
panjang tongkat yang masuk sampai batas keping sechii (a cm), kemudian diangkat sedikit
sampai warnanya terlihat jelas, dicatat panjang tongkat yang masuk sampai batas keeping sechii
(b cm), Hitung dengan rumus perhitungan kecerahan adalah
3.2.4. Kecepatan Arus
Salah satu ujung Tali rafia 10 m diikatkan pada botol mineral 600 mL berisi air 80%,
kemudian botol dilepaskan mengikuti arus laut dengan posisi tali rafia lurus, waktu yang
ditempuh diukur dengan stopwatch, kemudian lakukan langkah tersebut smapai 3 kali ulangan.
Hitung kecepatan arus menggunakan rumus : V = S/t.
3.2.5. Pasang Surut
Tiang pancang dipasang pada titik yang ditentukan kemudian selama praktikum
berlangsug, periode kenaikan dan penurunan massa air di catat pada alat tersebut dengan selang
waktu dua jam selama 24 jam, bersaman dengan temperature dan salinitas.
3.2.6. Klorofil-a
Metode untuk pengukuran kandungan klorofil fitoplankton mengikuti cara yang
dilakukan oleh Strickland & Parsons (1969), yakni dengan menyaring contoh air laut lalu
diekstrak dengan menggunakan larutan aseton 90 % untuk selanjutnya disentrifuge pada putaran
4000 rpm selama kurang lebih 30 menit untuk memisahkan antara filtrat dengan cairan yang
bening. Kemudian cairan yang bening tersebut dibaca fluororecencenya dengan menggunakan
fluorometer turner model 450 pada besaran 10 kali. Setelah diberi HCL 8 % sampel tersebut
kemudian dibaca kembali pada panjang gelombang yang sama, 750 dan 665 nm. Tujuan
penambahan asam tersebut adalah untuk memisahkan atau merubah klorofil-a menjadi
phaeopitin. Konsentrasi klorofil-a diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :
Klorofil-a = Fx
(RB - RA)
µg Ɩ
-1 (mg m
-3)
Fx = Faktor sensitivitas fluorometer
r = RB/RA
RB = fluororesensi dari ekstraksi sampel sebelum penambahan asam
RA = fluororesensi dari ekstraksi sampel setelah penambahan asam
Ve = volume ekstrak (ml)
Vs = volume sampel (L)
3.3. Waktu Dan Tempat
Praktikum Lapang dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 November 2014 di Pulau
Menjangan Besar dan Pulau Cemara Kecil Kepulauan Karimun Jawa sedangkan Praktikum
Laboratorium dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 November 2014 di Laboratorium
Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pembahasan
4.1.1 Deskripsi Lokasi
Karimun Jawa adalah nama kepulauan di sebelah utara pulau jawa, letaknya kurang lebih
83 km dari kota Jepara Jawa Tengah dan telah ditetapkan menjadi Taman Nasional sejak tahun
2001. Kepulauan Karimun Jawa memiliki tipe ekosistem beraneka ragam, seperti hutan pantai,
mangrove forest, ikan hias dan terumbu karang. Sebutan 'karimun jawa the virginal tropical
paradise' memang sangat tepat, sebab Karimun jawa memiliki pulau yang berjumlah 27 buah
namun baru 4 saja yang berpenghuni. Kepulauan Karimun jawa merupakan kawasan konservasi
laut yang memiliki kandungan potensi keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistem laut yang
khas. Karena kandungan potensi tersebut serta letaknya yang berada pada lintasan wisata bahari
antara Indonesia Bagian Barat dan Timur menjadikan wilayah ini sebagai obyek wisata bahari
yang strategis (Gita, 2002).
4.1.2. Parameter geologi
4.1.2.1. Sedimen
Analisa granulometri merupakan suatu metoda analisa yang menggunakan ukuran butir
sebagai materi analisa. Analisa ini umum digunakan dalam bidang keilmuan yang berhubungan
dengan tanah atau sedimen. Dalam analisa ini tercakup beberapa hal yang biasa dilakukan seperti
pengukuran rata-rata, pengukuran sorting atau standar deviasi, pengukuran skewness dan
kurtosis. Pilihan atau Sortasi dapat menunjukkan batas ukuran butir atau keanekaragaman ukuran
butir, tipe dan karakteristik serta lamanya waktu sedimentasi dari suatu populasi sedimen (Folk,
1968). Menurut Friedman dan Sanders (1978), sortasi atau pemilahan adalah penyebaran ukuran
butir terhadap ukuran butir rata-rata. Sortasi dikatakan baik jika batuan sedimen mempunyai
penyebaran ukuran butir terhadap ukuran butir rata-rata pendek. Sebaliknya apabila sedimen
mempunyai penyebaran ukuran butir terhadap rata-rata ukuran butir panjang disebut sortasi
jelek.
Berdasarkan hasil yang sudah di dapat menunjukkan bahwa sedimen yang berada di
lokasi pulau menjangan besar dan cemara kecil merupakan sedimen dengan jenis pasir. Hal ini
menunjukkan pengaruh lautan sangat dominan pada perairan di pulau menjangan besar dan
cemara kecil. Nybakken (1992) menyatakan bahwa perairan yang berarus kuat umumnya tekstur
sedimen berpasir. Transport sedimen pada kawasan hilir dapat disebabkan oleh arus sejajar
pantai atau diistilahkan dengan transport sedimen sepanjang pantai (longshore sediment
transport). Koesoemadinata (1980) menyebutkan bahwa transport sedimen sepanjang pantai
terjadi apabila pasir terangkat oleh turbulensi yang disebabkan oleh gelombang pecah sehingga
menyebabkan terjadinya erosi dan akresi di daerah pantai.
Bahan organik dan detritus yang terdapat pada kawasan hulu dapat disebabkan oleh input
yang dibawa oleh air sungai yang berasal dari kawasan mangrove yang terdapat di sekitar Kuala
Gigieng. Dean dan Dalrymple (2004) mengatakan Pada umummya sedimen berpasir bersifat
terrigenous yang komposisinya dipengaruhi lokasi asli dimana ia berada. Lebih lanjut Nybakken
(1992) menyatakan bahwa jenis sedimen dan ukurannya merupakan salah satu faktor ekologi dan
mempengaruhi kandungan bahan organik dimana semakin halus tekstur subtrat semakin besar
kemampuannya menjebak bahan organik.
Ada hubungan antara ukuran butir dan sortasi dalam batuan sedimen. Hubungan ini
terutama terjadi pada batuan sedimen berupa pasir kasar sampai pasir sangat halus. Pasir dari
berbagai macam lingkungan air menunjuk bahwa pasir halus mempunyai sortasi yang lebih baik
daripada pasir sangat halus. Sedangkan pasir yang diendapkan oleh angin sortasi terbaik terjadi
pada ukuran pasir sangat halus ( Blatt,dkk dalam Kusumadinata, 1980).
4.1.3. Parameter Fisika
4.1.3.1. Suhu
Dari hasil praktikum menunjukan nilai suhu pada kedua lokasi yaitu 30º C, Untuk
temperatur perairan, khususnya perairan Indonesia, temperatur air dipengaruhi oleh siklus
perubahan musim. Selain oleh musim, temperatur air di suatu perairan juga dipengaruhi oleh
intensitas matahari, kedalaman dan daratan di sekelilingnya (Dewi,2009). Hutabarat (1985)
menambahkan beberapa hal yang mempengaruhi suhu di laut antara lain, posisi matahari,
lintang, besarnya sudut datang sinar matahari, waktu atau lamanya penyinaran
matahari,penutupan awan dan kedalaman air.
4.1.3.2. Kecepatan Arus
Berdasarkan data pengukuran kecepatan arus yang diperoleh dari dua lokasi yaitu pulau
menjangan besar dan cemara kecil di dapat hasil pada pulau cemara besar yaitu 0.055556 m/s,
sedangkan pada pulau cemara kecil yaitu 0.031447 m/s. Proses pembelokan arah aliran arus ini
dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, jika angin bertiup cukup seragam dari arah
barat, maka akan menggerakan arah yang menuju ke arah timur. Akan tetapi karena pengaruh
karakteristik dari gesekan angin (wind stress), maka angin tersebut pada lapisan permukaan
dapat membangkitkan arus yang membentuk sudut 450
dengan arah angin. Dengan demikian,
angin yang dominasi dari arah barat akan terbelokan, sehingga membangkitkan pola pergerakan
arus yang dominan menuju arah ke barat daya. Faktor berikutnya, pola pergerakan arus juga
dipengaruhi oleh batimetri atau topografi perairan yang dapat menyebabkan berubahnya arah
arus dan kekuatan arus (steers,1971).
Gambar 1. Grafik Kecepatan Arus
Pengaruh pasut akan menyebabkan aliran arus menjadi kearah teluk pada waktu pasang.
Atau sebaliknya, aliran arus menjadi kea rah laut lepas pada waktu surut. Pada saat yang sama
bila angin yang cukup kuat dnegan arah yang cukup seragam, dapat juga mengakibatkan
kenaikan peras muka laut pada tepi pantai (Csanady,1982).
4.1.3.3. Kecerahan
Nilai kecerahan dari kedua lokasi yang telah diukur berbeda, di lokasi menjangan besar
menunjukkan kecerahan 170 cm sedangkan pada lokasi cemara kecil yaitu 55 cm. Nilai
kecerahan yang berbeda pada perairan disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya bahan-
bahan yang melayang-layang dan massa air mulai surut (Hutabarat, 1985). Selain itu beberapa
peristiwa meteorologik bahkan mempengaruhi cahaya sebelum sampai ke permukaan air.
Adanya awan dan debu di udara dapat mengurangi jumlah dan intensitas cahaya yang sampai di
permukaan air setelah menjelajahi atmosfer. Keadan seperti ini mengurangi intensitas cahaya
yang menembus permukaan laut tanpa campur tangan kondisi air (Nyabakken, 1988).
0,055
0,056
0,057
0,058
0,059
0,06
0,061
0,062
0,063
0,064
0,065
P. Menjangan Besar P. Cemara Kecil
m/s
Kecepatan Arus
Kecepatan Arus (m/s)
Gambar 2. Grafik Kecerahan
Penetrasi cahaya seringkali dihalangi oleh zat yang terlarut dalam air, membatasi zona
fotosintesis dimana habitat akuatik dibatasi oleh kedalaman. Kekeruhan, terutama disebabkan
oleh lumpur dan partikel yang mengendap, seringkali penting sebagai faktor pembatas.
Kekeruhan dan kedalaman air pempunyai pengaruh terhadap jumlah dan jenis hewan bentos (
Yuyun,2005).
4.1.3.4. Pasang Surut
Salah satu fenomena fisik dan dinamis yang selalu dijumpai di lautan adalah naik
turunnya permukaan air yang bersifat periodik selama satu interval waktu tertentu yang disebut
pasang surut (Nybakken, 1992).
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
P. Menjangan Besar P. Cemara Kecil
cm
Kecerahan
Kecerahan (cm)
Gambar 3. Grafik Pasang Surut
Pasang surut terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara gaya sentrifugal dan gaya
grafitasi yang berasal dari bulan dan matahari terhadap bumi. Gaya sentrifugal adalah suatu
tenaga yang didesak ke arah luar pusat bumi, besarnya kurang lebih sama dengan tenaga yang
ditarik ke permukaan bumi. Gaya gravitasi bulan terhadap bumi dua kali lipat dibandingkan
dengan gaya gravitasi matahari terhadap bumi. Hal ini terjadi karena jarak antara bumi dan bulan
lebih dekat daripada jarak antara bumi dan matahari. Pada bagian bumi yang menghadap bulan,
gaya gravitasinya lebih kuat daripada gaya sentrifugal, sehingga air tertarik keatas, disebut
pasang naik. Adapun pada bagian bumi yang berjauhan dengan bulan juga akan mengalami
penarikan air menjauhi bumi, tetapi besarnya air yang tertarik keluar tidak sebesar dengan
penarikan air pada bagian bumi yang langsung berhadapan dengan bulan, disebut pasang turun.
Gaya grafitasi yang ada dibagian ini lemah dan gaya sentifugalnya kuat. Pada sisi dari bagian
bumi yang tidak mengalami penarikan air, disebut surut. Dengan demikian terdapat dua pasang
dan dua surut. Pasang surut akan bergerak dipermukaan bumi. Perputarannya memerlukan waktu
selama kurang lebih 24 jam 50 menit dalam satu putaran (Hutabarat dan Evans, 1986).
0
20
40
60
80
100
120
cm
Waktu
Pasang Surut
Pasang Surut
4.1.4. Parameter Kimia
4.1.4.1. Klorofil-a
Hasil Uji Klorofil a menunjukkkan hsil yang berbeda pada setiap jam yang diukur. Pada
jam 6.00 WIB menunjukkan nilai 3,4752 mg/cm3
dan pada jam 12.00 WIB menunjukkan nilai
0,5822 mg/cm3. Pengukuran kandungan klorofil-a fitoplankton dilakukan pada saat surut, hal ini
dilakukan karena pada saat air surut, air sungai secara besar-besaran akan masuk ke laut,
sehingga muara didominasi oleh air sungai yang relatif lebih keruh dan kaya akan nutrien.
Kandungan nutrien yang tinggi di perairan muara akan dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk
tumbuh dan berkembang (Wenno, 2007 dalam Rina, 2013). Secara horizontal kandungan
klorofil-a banyak ditemukan pada lapisan permukaan yang berada dekat dengan daratan dimana
semakin menuju laut maka kandungan klorofil-a semakin rendah karena daratan banyak
memberi masukan nutien kedalam perairan. Hal ini menyebabkan suburnya perairan yang
akhirnya akan bermanfaat bagi fitoplankton untuk melakukan aktivitas fotosintesis. Hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Riley dan Skirrow (1975) dalam Wenno (2007) bahwa
proses geofisik sangat mempengaruhi masuknya nutrien dari darat melalui aliran sungai yang
menyebabkan bervariasinya kandungan nutrien (fosfat, nitrat dan silikat) di laut.
Kandungan klorofil-a pada fitoplankton di suatu perairan dapat digunakan sebagai salah
satu ukuran biomassa fitoplankton dan dijadikan petunjuk dalam melihat kesuburan perairan.
Kualitas perairan yang baik merupakan tempat hidup yang baik bagi fitoplankton, karena
kandungan klorofil-a fitoplankton itu sendiri dapat dijadikan indikator tinggi rendahnya
produktivitas suatu perairan (Ardiwijaya, 2002 dalam ).
4.1.4.2 Nitrat
Hasil Uji Nitrat menunjukkan nilai yang berbeda-beda pada setia kelompoknya.pada
kelompok 1 menunjukkan nilai 0,5550 mg/l, pada kelompok 2 menunjukkan nilai 0,5546 mg/l,
pada kelompok 3 menunjukkan nilai 0,5753 mg/l, dan pada kelompok 4 menunjukkan nilai
0,5619 mg/l. Hutagalung dan Rozak (1997) yang menyatakan bahwa peningkatan kadar nitrat di
perairan disebabkan oleh masuknya limbah domestik atau pertanian (pemupukan) yang
umumnya banyak mengandung nitrat. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam hal
ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan pupuk
dan dampak yang dapat jika pemberian pupuk tersebut berlebihan.
4.1.4.3. Salinitas
Nilai salinitas pada kedua lokasi praktikum menunjukkan hasil yang sama yaitu sebesar
32 ppt. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai salinitas diantaranya, hilangnya air karena
penguapan (evaporasi) dan masuknya air baru melalui presipitasi baik oleh hujan atau salju atau
masuknya air yang mengalir dari sungai (laili, 1997). Variasi nilai salinitis air laut yang fluktuasi
juga dipengaruhi oleh kondisi tempat. Praktikum yang dilakukan dilaksanakan di teluk awur,
pada umumnya daerah teluk adalah daerah yang jarak lautnya tidak jauh dari daratan sehingga
kandungan air tawar akan terlepas keluatan pada saat air laut surut.
V. KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang di dapat pada hasil praktikum Oseanografi Geofisika Kimia adalah
sebagai berikut :
Faktor arus dalam keadaan pasang dan surut sangat mempengaruhi terbentuknya substrat.
Semakin banyak partikel atau bahan organik terlarut maka kekeruhan akan meningkat.
Kekeruhan atau konsentrasi bahan tersuspensi dalam perairan akan menurunkan efisiensi
makan dari organisme
Pasut dihasilkan oleh gaya tarik bulan, matahari dan benda langit lainnya yang disebut
faktor astronomis.
Angin adalah faktor yang paling bervariasi dalam mengakibatkan arus pada suatu daerah.
Pengaruh pasut akan menyebabkan aliran arus menjadi kearah teluk pada waktu pasang.
5.2. Saran
Diharapkan praktikum selanjutnya lebih baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Ardiwijaya, R.R. 2002. Distribusi Horizontal Klorofil-a dan Hubungannya Dengan Kandungan
Unsur Hara Serta Kelimpahan Fitoplankton di Teluk Semangka, Lampung. Program Studi
Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).
Institut Pertanian Bogor (IPB).
Arifin, R. 2009. Distribusi Spasial dan Temporal Biomassa Fitoplankton (Klorofil-a) dan
Keterkaitannya dengan Kesuburan Perairan Estuari Sungai Brantas, Jawa Timur.
Program Studi MSP. FPIK. IPB. Bogor.
Csanady, G.T.1982. circulation in the coastal ocean. Reidel. Dardrecht : 279 pp.
Dean, R.G., R.A. Dalrymple. 2004. Coastal Processes with Engineering Application. Cambridge
University. UK.
Dewi, L. 2009. Kondisi oseanografi fisika perairan barat sumatera (pulau simeulue dan
sekitarnya) pada bulan agustus 2007 pasca tsunami desember 2004. Makara Sains Vol 13
No 1 : 17-22.
Dronkers, J. J. 1964. Tidal Computations in rivers and coastal waters. North-Holland Publishing
Company: Amsterdam.
Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan.
Cetakan Kelima. Yogjakarta : Kanisius.
Folk RL, (1974), Petrology of Sedimentary Rocks, Austin Texas: Hemphill Publishing Co
Friedman GM, dan JE Sanders, (1978), Principle of Sedimentology, New York: John Wyley & Sons Ltd
Hatta, M. 2002. Hubungan Antara Klorofil-a dan Ikan Pelagis dengan Kondisi Oseanografi di
Perairan Utara Irian Jaya. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
Hutabarat, S. dan S.M. Evans. 1984. Pengantar Oseanografi. Jakarta: Universitas Indonesia
Hutabarat, S. dan S.M. Evans. 1985. Pengantar Oseanografi. Jakarta: Universitas Indonesia
Hutabarat, S. dan S.M. Evans. 1986. Pengantar Oseanografi. Djambatan. Jakarta.158 hal
Hutagalung, Horas dan Abdul Rozak.1997. Metode Analisis Air Laut, Sedimen dan Biota. Buku
Kedua. Puslitbang Oseanologi-LIPI. Jakarta.
Ifa Nur Rasyidah, Akhmad Farid dan Wahyu Andy Nugraha. 2011. Efektivitas Alat Tangkap
Mini Pure Sein Menggunakan Sumber Cahaya Bebeda Terhadap Hasil Tangkap Ikan
Kembung (Rastrelliger sp). Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan. Vol 3(1).
Junaidi M. Affan. 2012. Identifikasi lokasi untuk pengembangan budidaya keramba jaring apung
KJA) berdasarkan faktor lingkungan dan kualitas air di perairan pantai timur Bangka
Tengah. Depik.. Vol. 1(1):78-85.
Koesoemadinata, R.P. 1980. Prinsip-Prinsip Sedimentasi. Departemen Teknik ITB. Bandung.
Koesoemadinata, R.P. 1980. Prinsip-Prinsip Sedimentasi. ITB. Bandung
Lalli, C. m & T. R. parsons. 1997. Biological oceanographi : An Introduction. Pergamon Press,
New York.
Mahlan, Musrefinah. 1984. “Sumberdaya Pasang Surut sebagai Enerji Pembangkit Tenaga
Listrik”. Oseana, Volume IX, Nomor 2 : 49-55.
Nybakken, J.W. 1992. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. Jakarta: PT. Gramedia.
Rina Febriyanti et al. 2013. Kandungan Klorofil-a Fitoplankton di Sekitar Perairan Desa
Sungsang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Program Studi Ilmu Kelautan
FMIPA Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Indonesia. Maspari Journal, 2013, 5 (1), 34-39
Ronowicz Marta, Maria Wlodarska-Kowalczuk& Piotr Kuklinski, 2012. Depth- and substrate-
related patterns of species richness and distribution of hydroids (Cnidaria, Hydrozoa) in
Arctic coastal waters (Svalbard). Marine Ecology 34 (Suppl. 1) (2013) 165–176
Roshisati, I. 2002. Distribusi Spasial Biomassa Fitoplankton (Klorofil-a) di Perairan Teluk
Lampung pada Bulan Mei, Juli, dan September 2001. Program Studi MSP. FPIK. IPB.
Bogor. 71 hal. Skripsi (tidak diplublikasikan).
Sastrawijaya, Tresna. 2000. Pencemaran Lingkungan. Surabaya : Rineke Cipta
Siaka I M. 2009, KORELASI ANTARA KEDALAMAN SEDIMEN DI PELABUHAN BENOA
DAN KONSENTRASI LOGAM BERAT Pb DAN Cu. JURNAL KIMIA 2 (2), JULI
2009: 61-70
Steers, J.A. 1971. Introduction to coastine Development. The massachussells institute of
technology press. Cambridge. Massachussets : 365 pp.
Sverdrup, H. U. 1961. The Ocean, The Phisics, Chemistry, and General Biology. Plentice Hall.
New Jersey.
Wenno LF. 2007. Biodiversitas Organisme Planktonik dalam Kaitannya dengan Kualitas
Perairan dan Sirkulasi Massa Air di Selat Makassar. Pusat Penelitian Oseanografi (LIPI).
Jakarta
Wyrtki, K. 1961. Phyical Oceanography of the South East Asian Waters. Naga Report Vol.
2 Scripps, Institute Oceanography, California.
Yuyun. D. 2005. Keanekaragaman jenis makrozoobenthos di ekosistem perairan Rawapening
Kabupaten Semarang. Universitas negeri semarang.
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Hasil Perhitungan
Data praktikum lablatorium oseanografi geofisika dan kimia
Kelompok 2
Tabel 1. Berat Awal Sampel Sedimen (sebelum diayak)
Sampel Sedimen Berat Awal (gram)
A 281, 202
B 252, 019
Tabel 2. Berat Akhir Tiap Sampel Sedimen (setelah diayak)
Sampel Sedimen Berat Akhir
425 mm 150 mm <125 mm
A 26,40 gram 99,03 gram 46,14gram
B 0,89 gram 144,01gram 12,13 gram
Tabel 3. Prosentase Hasil Perhitungan Sedimen
Ukuran Sampel sedimen
A B
450 mm 9, 39 % 0,35 %
150 mm 35,22 % 57, 14 %
>125 mm 16,41 % 4, 81 %
Perhitungan :
X
Sedimen A :
450 mm
X =
150 mm
X =
> 125 mm
X =
Sedimen B :
450 mm
X =
150 mm
X =
>125 mm
X =
Data Praktikum Lapang Oseanografi GeoFisik dan Kimia
I. Kecepatan
Arus
II. Pasang Surut
Pasang surut pada tanggal 1 November 2014
Waktu (Pukul)
Kedalaman
(cm)
22:00 50
23:00 52
12:00 76
Pasang surut pada tanggal 2 November 2014
Waktu (Pukul)
Kedalaman
(cm)
1:00 89
2:00 103
3:00 91
4:00 85
5:00 76
Stasiun S (m) t (s) v (m/s)
Menjangan Kecil 10 180 0.055556
Cemara Besar 10 318 0.031447
6:00 60
22:00 42
Pasang surut pada tanggal 3 November 2014
Waktu (Pukul)
Kedalaman
(cm)
5:00 75
6:00 67
Pasang surut pada
tanggal 4 November
2014
Waktu (Pukul)
Kedalaman
(cm)
5:00 75
III. Data Lokasi
Stasiun Titik Koordinat
Menjangan
Besar
5°52’59,51” S
110°25’46,71”
E
Cemara Kecil
- 5° 49’ 57,7” S
110° 22’ 49,1”
E
IV. Salinitas, Suhu dan pH Tiap
Stasiun
Stasiun Salinitas (ppt) Suhu (°C) pH
Menjangan Besar 32 30 8.5
Cemara Kecil 32 30 8.5