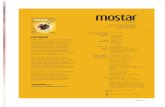Menegakkan Martabat Melalui Demokrasi
-
Upload
pustral-ugm -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Menegakkan Martabat Melalui Demokrasi
Purwo Santoso2
Lagi-lagi kita harus menelan kenyataan pahit, bahwa perpolitikan di negeri ini begitu jauh dari ideal. Reformoasi yang kita gadhag-gadhang ternyata jauh dari yang kita angankan karena memang tidak ada kesepakatan apa yang harus dilakukan, dan apa ukuran keberhasilannya. Tidak jelas juga siapa yang harus bertanggung jawab, ketika reformasi—sebuah jargon yang begitu menjanjikan—pada akhirnya dianggap tidak terwujud. Oleh karena itu, perlu kiranya kita cermati proses-proses yang niscaya terjadi.
1. Duduk Soal.
Terlepas dari perdebatan berhasil/gagalnya agenda reformasi, dimana demokratisasi menjadi komponen utamanya, tidak bisa dipungkiri bahwa realisasinya menyisakan sederetan ironi. Kebebasan berbicara dan kebebasan dari represi pemerintah—yang bagi sebagian kita adalah wujud dari demokrasi kita—justru dirasakan sebagai hal yang memuakkan. Dalam keleluasaan itu, kini semakin banyak orang mengeluhkan gejala yang sama, lalu muncullah sebutan kegaduhan politik. Kita menemukan ironi sejenis. Dalam rangka berdemokrasi, kita pemilih pemimpin melalui skema ‘pilpres’, ‘pilkada’, ‘pilleg’. Bersamaan dengan hal itu, semakin terbiasa kita menggolok-olok pemimpin. Di sini kita menyaksikan bahwa, pemilihan umum—yang selama ini diromantisir sebagai aktualisasi nyata ajaran demokrasi—justru berbalik menjadi ajang transaksi curang antara pemilih dengan dengan kandidat yang hendak dipilih. Yang menjadi persoalan di sini adalah, kita merasakan kotornya money politics, namun tidak bisa keluar darinya. Ironi terbesar yang tersirat di sini adalah, demokrasi di-claim sebagai ekspresi kekuasaan rakyat, namun nyatanya, rakyat itu sendiri tidak punya kontrol terhadap proses yang berlangsung.
1 Disampaikan dalam Seminar Nasional “Strategi Pembangunan Budaya Demokrasi yang
Bermartabat” yang diselenggarakan dalam perayaan Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jendral Soedirman ke-28, pada hari Senin 25 November 2013.
2 Guru besar Ilmu Pemerintahan, dan ketua Department Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
2
Ada persoalan di bawah permukaan yang perlu kita temukenali, dan apapun solusi yang kita tawarkan haruslah menjangkau tataran itu. Telaah yang ini dimaksudkan untuk itu.
Menggejalanya berbagai ironi tersebut di atas mengantarkan kita pada kesadaan bahwa, Indonesia saat ini terjebak dalam silang sengkarutnya praktek-praktek politik yang tak bermartabat. Demokratisasi, justru tadinya kita dambakan sebagai mantra untuk mengatasi masalah, justru menjebak kita dalam sederetan ironi kemerosotan martabat. Sungguhpun begitu, tulisan ini mencoba untuk tidak buru-buru mengutuk para pelakunya. Tanpa bermaksud untuk mengingkari adanya motif-motif bejat dari para politisi yang terlibat dalam proses demokratisasi, tulisan memperlajukan kebejatan yang terjadi sebagai situasi yang tak terelakkan. Dalam istilah Bourdieu, habitus yang melekat dibalik proses demokrasi, dimana set-up struktural tertentu menstruktur kebejatan3. Oleh karenanya, kalaulah yang bejat itu kita katakan [baca: kutuk] bejat, kutukan itu tidaklah terlalu membantu proses demokratisasi itu sendiri.
Telaah ini lebih didedikasikan untuk memetakan langkah-langkah dalam penuntasan agenda demokratisiasi itu sendiri. Untuk itu, tulisan ini mengajak kita untuk mundur selangkah, yakni melakukan refleksi kritis atas apa yang telah dan akan berlangsung, sebelum mengidentifikasi sejumlah langkah penting untuk memenuntaskan proses demokratisasi. Dari refleksi kritis ini kita menemukan sejumlah kepincangan dalam memikirkannya. Refleksi sederhana ini segera meyadarkan kita bahwa yang menjadi tantangan utama bukanlah memformulasikan demokrasi yang bermartabat4, melainkan mencari asal-usulnya mengapa persoalan martabat sempat terkelupas dalam proses demokratisasi. Perlu telaah seksama, mengapa dimensi etis luput dari agenda demokratisasi
3 Bourdieau,
4 Dalam membahas demokratisasi kita sering terjebak pada perdebatan akurasi corak yang harus kita wujudkan, namun abai dalam memetakan lapis-lapis atau rangkaian perubahan yang niscaya kita hadapi untuk corak manapun. Kominitas akademik, yang selama ini membingkai pewacanaan tentang demokrasi dan demokratisasi di negeri ini begitu asyik berdebat tentang corak demokrasi yang tepat. Kita habiskan cukup banyak energi untuk memperdebatkan unik-ataukah-universalnya demokrasi, mempertentangkan demokrasi prosedural vs. demokrasi substantif, mengusulkan demokrasi yang berkeadilan dan seterusnya. Dalam perayaan Dies Natalis Universitas Jendral Soedirman ini kita mencanangkan agenda ‘demokrasi yang bermartabat’.
Agar tidak terjebak pada perdebatan tentang akurasi corak, tulisan ini mengajak untuk membidik persoalan penegakan martabat kita dalam berdemokrasi. Demokrasi, dalam tulisan ini justru kita perlakukan sebagai endapan pengalaman dalam menegakkan martabat. Karena ide dasar dari demokrasi adalah penghormatan akan nilai-nilai kemanusiaan, maka aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku yang bermartabat niscaya meninggalkan tapak-tapak martabat kita sendiri. Di sini kita sadar bahwa, pokok persoalan kita selama ini adalah, alpha dalam menegakkan martabat sebagai bangsa dan warga negara Indonesia.
3
sedemikian sehingga ketika proses demokratisasi berlangsung justru “menormalkan” tindakan-tindakan yang tidak bermartabat.
2. Nyaman dalam Pemikiran Cengeng: Terdampar dalam Simplifikasi.
Sadar atau tidak, tindakan kita adalah aktualisasi dari apa yang kita fikirkan. Apa yang secara moralis (patologis) dipandang sebagai kebejatan-kebejatan dalam berdemokrasi—seperti tidakan menang-menangan, saling mencurangi rival politik, mengejar kemenangan dengan menyuap hakim, money politics (vote buying) dan sejenisnya—sangat mungkin merupakan ekspresi cara kita membayangkan (memaknai) realita yang kita hadapi. Para pelakunya, yang saya kita tidak mengadopsi cara pandang patologis, punya justifikasi mengapa hal-hal seperti itu dilakukan. Di sinilah problematika demokratisasi bermula. Para analisis demokratisasi di negeri ini memandang persoalan dengan pendekatan ethic (bukannya cara pandang emic) dan atas dasar kriteria normatif tentang demokrasi, dilakukanlah telaah tentang demokrasi. Di sini, para pengkaji demokrasi asyik dengan teori-teorinya sendiri, sementara para pelaku sesuai dengan kalkulasi dan rasionalitasnya sendiri. Sementara wal para politisi, tokoh-tokoh yang berkiprah di domain publik dihadapkan pada serangkaian norma baru yang harus dipatuhi, sementara itu para analis merasa ikut mengusung demokrasi dengana cara khas: asyik dengan idealitas-idealitanya sendiri. Dalam situasi seperti inilah gejolak ‘perasaan tidak berkutik’ berlangsung. Demokrasi bergulir dalam imajinasi kolektif para pelakunya, dan sepanjang teorisasi demokrasi tidak dibangun melalui intersubyektifitas dengan mereka, maka pembacaan tentang masalah serta kemajuan/kemunduran demokrasi justru menjadi sumber permasalahan baru.
Demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, diakui ataupun tidak, bergulir dalam bingkai pemikiran liberal. Demokrasi yang dimaksudkan orang kebanyakan adalah demokrasi liberal. Lebih dari itu, proses demokratisasi yang dibayangkan sudah/akan berlangsung disebut sebagai proses transisi menuju demokrasi. Dalam kerangka dikir ini, demokratisasi dibayangkan sebagai proses liberalisasi, dan liberalisasi memang telah berlangsung secara besar-besaran di negeri ini. Dengan liberalisasi itu lalu dilangsungkan pergantian pemimpin, dan kita telah berulang kali mengganti pemimpin pemerintahan. Masing-masing meminpin proses reformulasi aturan untuk berpemerintahan. Reformulasi atau bongkar pasang aturan pun sudah berlangsung. Tantangan terbesar dalam proses demokratisasi, menurut para pengusung gagasan transisi menuju demokrasi, adalah proses pembisaan untuk hidup aturan-aturan baru yang disebut demokrasi. Kalau kita baca dengan lensa analisis seperti ini, maka problema terbesar yang dihadapi Indonesia adalah melakukan
4
pembiasaan-pembiasaan sedemikian sehingga semua orang patuh pada norma dan aturan baru yang disebut demokrasi.
Kalau lihat demokratisasi di Indonesia ini kita telaah melalui lensa transisi menuju demokrasi, maka kontroversi tentang apa yang kurang dan apa yang harus dilakukan dalam proses demokratisasi adalah keniscayaan. Jelasnya, ratapan bahwa demokratisasi di Indonesia telah kebablasan bisa kita letakkan kebagai bagian dari kontroversi yang niscaya berlangsung. Sejalan dengan hal itu, ajakan untuk mencari alternatif model demokrasi, juga tidak harus ditanggapi terlalu serius. Persoalan esensialnya adalah penciptaan kepakatan semu fihak tentang wujud nyata dari demokrasi, dan bagaimana perbedaan-perbedaan pandangan tersebut harus dilerai. Sebagai contoh, pengamatan sporadis yang saya lakukan mengisyaratan bahwa khalayak ramai menyamaatikan demokrasi dengan ‘perpolitikan secara bebas.’ Mereka lalu kecewa ketika menyaksikan bahwa kebebasan yang dinikmatinya ternyata bermuara pada kekacauan atau kegaduhan. Di sisi lain, ada kalangan yang membayangkan bahwa demokrasi adalah persoalan penegakan hukum, dan ketika menyaksikan kegaduhan tersebut ikut menimpali keluhan bahwa demokratisasi yang berlangsung justru menciptakan masalah.5
Demokratisasi di negeri seluas Indonesia ini, mau tidak mau, melibatkan perubahan perilaku dan jalan fikiran dari ratusan juta orang yang masing-masing memiliki tata nilai dan terikat pada tradisi yang berbeda-beda. Dalam kompleksitas proses seperti ini, semua orang medapati ruang-ruang untuk mengekspresikan kebebasan, namun kita tidak sempat atau belum tuntas dalam mencermati adanya paradoks yang melekat dalam praktek-praktek berkebebasan itu.6
Jelasnya, agar sistem politik berbasis kebebasan dapat ditegakkan, maka ada paradoks yang harus dijadikan pegangan. Paradoknya begini. Setiap pelaku harus membayar kebebasan dengan mengekang kebebasan sendiri demi optimalnya kebebasan itu sendiri. Setiap aktor yang ingin bebas pada akhirnya memilih untuk mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan bersama.7 Tanpa kesediaan untuk ikut berinvestasi dalam
5 Sehubungan dengan hal ini, maka demokratisasi ada baiknya difahami sebagai
proses lesson drawing: menarik pelajaran dari keterlibatan-keterlibatan dalam mengelola persoalan publik.
6 Dalam konteks ini, peta teori berlabel transisi-menuju-demokrasi tadi tidak terlalu membantu karena di sana tidak diinformasikan, akan adanya situasi paradoksal ketika kesepakatan tentang berdemokrasi hendak/harus dilakukan.
7 Untuk mensimulasikan penggunaan kebebasan ini, mari kita ibaratkan penggunaan kebebasan dengan pemanfaatkan hak untuk melaju di jalan. Bayangkan apa yang tesrjadi di perempatan jalan yang mengalami kemacetan karena traffic light di situ tidak berfungsi. Tatkala semua pengendara ingin terus berjalan, maka semua kendaraan menjadi penghalang bagi kendaraan lain. Di sini moral hazard sulit dikenang, kecuali semua berkepakat untuk mematuhi seseorang menjadi pengatur lalu lintas, dan pengatur lalu lintas tersebut didihormati dengan mengekang kebebasan. Kesediaan seseorang untuk menjadi pengatur lalu lintas, dan kesediaan semua orang untuk menghormati otoritas pengatur lalu lintas, adalah bentuk pengekangan
5
pengembangan dan pemeliharaan kelembagaan yang ada, maka setiap pelaku justru harus memikul biaya mahal karena dicurangi atau dirugikan oleh fihak lain. Inilah sekelumit kerumitan dalam pelembagaan demokrasi.
Dalam konteks ini, apa yang ditengarai sebagai ‘kebejatan dalam berpolitik’ sejatinya adalah karena kealphaan kita dalam mengajak semua partisipan dalam sistem politik demokratis untuk mengembangkan institusi yang menjamin kebebasan itu sendiri. Perlu ditegaskan di sini bahwa demokratisasi adalah proses co-creation: proses menciptakan realita baru secara bersamaan, melibatkan warga negara dari berbagai kalangan dan sudut pandang. Dalam konteks ini:
• Para politisi bisa kita bayangkan sebagai ujung tombak demokratisasi. Hanya saja, perlu diingat pilihan politik mereka juga ditentukan juga oleh pilihan-pilihan orang kebanyakan. Ketika orang kebanyakan memperlakukan dirinya sebagai ‘sapi perah’ maka mereka dihadapkan pada keharusan untuk memikul beban yang kita kenal dengan istilah ‘politik berbiaya tinggi’. “Kecerdasan” para pemilih untuk memojokkan dirinya pada saat sedang membutuhkan dukungan, harus dipikul dengan keberanian menanggung resiko ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam menyikapi gejala seperti ini, lalu berkembangkan pemikiran yang muaranya menjadikan demokratisasi sebagai beban. Pada saat yangs ama, publik memposisikan diri sekedar sebagai sebagai penerima manfaat, bukan bukan pioneer, dalam proses pelembagaan kebebasan berpolitik [demokratisasi] itu sendiri.
• Universitas, berikut pada akademisi didalamnya ikut membiarkan terjadinya kebingunan-kebingunan dalam mengarungi rumitnya pelembagaan demokrasi. Ironis juga bahwa tidak sedikit dari para pengamat dan ilmuwan dari kampus yang tidak justru mereproduksi kekeruhan melalui pemikiran-pemikirannya. Kalaulah ada kedangkalan makna demokrasi yang difahami khalayak, maka universitas dengan kompetensi keilmuan yang ada, perlu ikut ambil bagian dengan menemukan solusi. Syaratnya, solusi tersebut dibangun melalui kesefahaman cara membaca realita yang kita hadapi. Melalui simpatinya (bukannya melalui cercaan-cercaan di media sebagaimana kita saksikan di media massa selama ini) ikut menjebakkan diri dalam norma-norma baru yang kita sebut demokrasi.
Simplifikasi yang berlebihan tentang makna dan demokratisasi yang kita canangkan ini harus dipertanggungjawabkan ke hadapan publik manakala rute demokratisasi yang dibimbingnya sarat dengan kebejatan.8
kebebasan. Dengan pengekangan kebebasan itulah kebebasan melaju di jalan berjalan paralel dengan kelancaran berlalu lintas.
8 Secara keilmuan kita tahu bahwa demokratisasi adalah persoalan yang sangat kompleks, dan dalam kompleksitas itu selalu mengedepan tuntutan-tuntutan praktis yang harus dijawab. Point-nya di sini bukannya kita terbiasa meremehkan kompleksitas yang ada, melainkan gagap dalam menjembatani praktikalitas dan koherensi teoritik dalam mengawal proses demokratisasi.
6
Dengan kata lain, ada cacat epistemologis dalam kita memaknai dan mengawal proses demokratisasi. Di sini, persoalan kita lebih dari sekedar mereduksi demokratisasi sebagai pemberlakuan tatanan prosedural, misalnya pemberlakukan pemilihan umum, pencabutan aturan yang represif dan sejenisnya. Secara epistemologis kita membiarkan demokrasi sebagai “produk” yang di-deliver oleh pemerintah, bukan proses kolektif untuk mengubah sosok dan cara berpemerintahan. Partisipasi yang kita perjuangkan selama ini bukanlah partisipasi dalam tataran mereformat dan mentransformasikan cara berpemerintahan melainkan partisipasi pada tataran menjalani prosedur-prosedur baru yang dibuat. Di sini kita menyaksikan bajwa pelibatan rakyat dalam proses demokratisasi ada pada tataran yang dangkal.
Untuk menjelaskan point di atas, mari kita cermati bagaimana kita menyikapi pemilihan umum. Partisipasi yang kita wacanakan adalah mencalonkan diri (dalam rangka menggunakan hak untuk dipilih) dan hadir ke bilik suara. Dari kedua bentuk partisipasi ini lalu kita mambayangkan akan hadirnya pemimpin, yang pada gilirannya nanti mebuat kebijakan yang menjawab kebutuhan para pemilih. Selanjutnya, rakyat kita persilahkan menunggu hasil dari “demokratisasi” karena rakyat sudah memilih pemimpin. Karena terbiasanya kita mengusung alur pewacanaan seperti ini, kita tidak sempat menyadari adanya kesalahan fatal, bahwa kalaulah menggunakan hak pilih dan hak dipilih ini penting, tantangan pokoknya bukanlah sekedar ‘menemukan siapa’ pemimpin yang terpilih melainkan mengembangkan instalasi pemerintahan agar rakyat—melalui kelembagaan yang ada/diperlukan—memiliki kontrol terhadap keputusan-keputusan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Dalam kealphaan ini, partai politik merasa bersalah tidak ikut berinvestasi melalui pendidikan politik (kewarganegaraan). Partai politik juga tidak merasa bersalah ketika terobsesi dengan mengembangkan tim pemenagan, dan tidak sempat menyeriusi pengembangan konsep dan infrastruktur kebijakan yang menjawab kebutuhan rakyat.
Karena kealphaan seperti itulah demokratisasi yang kita usung kandas dalam kedangkalan yang kita buat sendiri. Demokratisasi dibayangkan sekedar sebagai buah dari pohon pemilu. Kita sebetulnya ditegur dengan ironi-ironi yang mengedepan. Electoral reform yang diselenggarakan demi demokratisasi, misalnya, justru menyisakan detachment rakyat dari proses yang harusnya dikenalikannya. Dalam detacthment berselimut pemilu ini, kita lalu mudah merengek. Kita merengek: mengapa kondisi tidak kunjung membaik. Menurut hemat saya, setiap ratapan yang kita luapkan ketika mencermati praktek berdemokrasi di negeri ini sebetulnya adalah konfirmasi atas kecengengan di dalam menyikapi dan ambil bagian dalam proses demokratisasi. Dalam konteks ini perlu ditegaskan bahwa, demokrasi adalah persoaan ke-kita-an dalam mengelola urusan publik, dan kalau ada yang tidak beres dalam berdemokrasi, pastilah kita sendiri biang keladinya. Menegur pemimpin yang salah dalam demokrasi adalah keniscayaan, namun proses demokratisasi tidak akan segera tuntas kalau kita berhenti dengan mencaci-maki para pemimpin.
7
Aktualisasi hasrat berdemokrasi dalam artikulasi cengeng ini, proses demokratisasi berwatak empossing. Tiba-tiba saya ada norma-norma yang dirancang dari luar dan diberlakukan untuk kita. Berbagai hasil kajian electoral reform menghasilkan serangkaian kaidah electoral engineering yang harus kita patuhi, seakan tidak ada pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pemilu bisa dilakukan lebih baik dan lebih murah. Sebagai contoh, untuk memilih kepala daerah/negata atau anggota dewan perwakilan, kita begitu obsess dengan kepastian aturan main, dan pada gilirannya kita harus menggantungkan diri pada ada dan berhasilnya sosialisasi dari exponen dari laur masyarakat setempat. Sistem noken dalam pemilihan kepala suku di Papua sempat dianggap tidak sah karena tidak konsisten dengan kaidah electoral engineering yang ditekuni para ahli. Pada gilirannya, kita lalu menormalkan pandangan bahwa demokratisasi adalah proses yang berwatak top-down, bukan sebaliknya, proses bottom-up. Tidak cukup ruang untuk aktualisasi tradisi, kearifan dan kebiasaan masyarakat.
Observasi tersebut di atas memberi cukup dasar untuk mengatakan bahwa demokratisasi di Indonesia selama ini terkelupas dari proses kebudayaan. Yang jelas, demokrasi adalah arena baru yang harus disiasati. Dalam suasana seperti ini, berbagai moral hazard mencuat dari proses demokratisasi tidak terantisipasi. Lalu, tiba-tiba kita terkaget-kaget oleh kenyataan bahwa para aktor yang diharapkan menjadi pengusung ide demokrasi justru terjebak dalam berbagai bentuk kebejatan.
Dengan corak kontruksi wacana demokratisasi yang digambarkan di atas, terlihat bahwa demokratisasi sebetulnya bukanlah hajat yang ditekuni sepenuh hati. Hanya saja, tidak bisa dipungkiri, keterbukaan yang disediakan atas nama demokratisasi telah menyediakan landscape baru untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Demokrasi, dalam konteks ini lebih menyerupai, (maaf) tempat ‘buang hajat’. Karena elit politik adalah kalangan yang well-equipped dan memiliki cukup sumberdaya, maka merekah yang paling berkesempatan untuk mengeksploitasi kesempatan. Dalam konteks ini, tidak terlalu relevan kita meratapi kenyataan bahwa demokratisasi telah dibajak elite.9 Yang harus dilakukan adalah reintalasi demokrasi agar masyarakat punya kendali terhadap elitnya, sedemikian sehingga kalaulah elit menikmati previllages hal itu dikarenakan dedikasinya melayani publik.
Demokrasi, sebagaimana tersurat dari salah satu akar-katanya ‘demos’ adalah persoalan kerakyatan. Cara kita mewacanakan demokrasi selama ini lebih kondusif untuk dibajak elit. Kalangan yang lebih kritis bahkan bisa menuding dangkalnya pewacanaan demokrasi tersebut mengisyaratkan studi dan pewacanaan sudah berada dalam nyamannya zona yang dikehedaki elite politik. Proses demokratisasi tidak bergayut dengan gerakan-gerakan kerakayatan yang tidak menggunakan nomenklatuur demokrasi.
9 http://www.demosindonesia.org/diskursus/3078-transisi-demokrasi-telah-dibajak.html.
8
Muara dari narasi di atas adalah bahwa demokratisasi di Indonesia berlangsung setengah hati.10 Hanya saja, kalaulah ungkapan ‘setengah hati ini berisi keluhan, yang kita keluhkan tentulah bukan hanya pemerintah ataupun politisi. Keluhan ini harus kita alamatkan pada diri sendiri. Kealphaan kita dalam merefleksikan apa yang tengah berlangsung, pada gilirannya menjadikan proyek raksasa yang kita usung, yakni demokratisasi, terjebak dalam berbagai inkonsistensi. Tidak ada kesungguhan sejak awal untuk memaknai demokratisasi adalah proses transformasi, dan dalam transformasi tersebut tantangan utamanya adalah melerai kontroversi dan menyediakan ruang manuver untuk keluar dari berbagai kontradiksi. Inkonsistensi bukanlah untuk diratami melainkan sebagai situasi yang harus secara inovatif disikapi. Maka, tidaklah mengejutkan kalau hal ini mengerem laju demokratisasi di negeri ini. Marcus Mitzner, bahkan menunjukkan bahwa Indonesia belakangan ini mengalami stagnasi dalam demokratisasinya.11
3. Menegakkan Martabat.
Sebagaimana tersirat dari paparan di atas, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan resep baru dalam demokratisasi, dan resep itu berjudul ‘demokrasi yang bermartabat’. Sungguhpun demikian, tulisan ini sepakat dengan pemahaman bahwa proses demokratisasi harus menjunjung tinggi martabat kita sebagai manusia. Keperluan untuk membuat proses demokratisasi segera bergulir dan berbuah telah membuat kita alpha untuk menegakkan martabat.
Sebagai jargon politik, istilah ‘menegakan martabat’ memiliki sensasi tersendiri. Pertanyaannya adalah: bagaimana hal itu mengobsesi kita semua. Pertanyaan ini penting untuk diajukan karena berbagai hal. Pertama, persoalan martabat adalah persoalan nilai-nilai dasar kemanusiaan.12 Kalau wacana ‘demokrasi yang bermartabat digulirkan,
10 Riswandha Imawan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
11 Marcus Mitzner; “Indonesia’s Democratic Stagnation: Anti-Reformis Elites and Resilent Civil Society”, Democratization, 2011, iFirst, 1-21.
12 Dalam konteks Indonesia, nilai kemanusiaan yang diajarkan adalah yang adil dan beradab. Dalam Richard C. Snyder, Charles F. Hermann and Harold D. Lasswell; “A Global Monitoring System: Appraising the Effects of Government on Human Dignity”, International Studies Quarterly, Vol. 20, No. 2 (Jun., 1976), pp. 221-260 disebutkan bahwa nilai dasar kemanusiaan tersebut aktualisasinya mencakup hal-hal berikut ini.
• Power: participationin decision-making • Respect: honor, status, prestige, recognition • Rectitude: virtueg, oodness, righteousness • Affection: love, friendship, loyalty • Wealth: income, goods, services • Well-being: health, safety, confort • Skills: proficiency in any practice
9
niscaya akan ada perdebatan tentang bagaimana penjabaran hal itu ke dalam praktek. Yang perlu dikedepankan disini sebetulnya bukanlah apa penjabaran yang paling akurat, melainkan kesiapan untuk mengelola kontroversi yang niscaya berlangsung, dan mengupayaka agar kontroversi tersebut segera mengendapkan kearifan kolektif.
Kedua, sejalan pemberlakukan resep liberal dalam proses liberalisasi yang selama ini berlangsung, maka konsep yang selama ini membingkai demokratisasi adalah hak dan otonomi. Dalam konteks ini, perlu kejelasan apakah penegakan martabat kita perlakukan sebagai alternatif dan penegakan hak azasi manusia dan penjaminan otonomi ? Dalam konteks ini kita perlu sadari bahwa hak azasi manusia pada dasarnya adalah instalasi atau instrumen untuk mengawal penegakan martabat. 13 Di sini, kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa pewacanaan demokrasi sudah terhegemoni oleh wacana dominan, dan dominasinya berada pada tataran global. Kealphaan kita untuk mendudukkan wacana HAM sekedar sebagai instrumen untuk membuka ruang bagi aktualisasi martabat, menjadikan ruang manuver dan ruang refleksi kritis kita menjadi sempit. Sehubungan dengan hal itu, kesungguhan untuk mengedepankan martabat manusia dalam demokrasi harus ditunjukkan dengan kemampuan kita dalam membingkai dan menjerat wacana HAM dalam pemaknaan kita akan martabat. Jelasnya, jangan sampai kita meneruskan kealphaan kita selama ini bahwa pemaknaan HAM di negeri kita sudah given dan oleh karena kemajuan Indonesia dalam demokratisasi haruslah ditunjukkan dengan kepatuhan kita pada standar yang tidak kita mengerti duduk-soalnya.
Dalam paparan di atas terkesan bahwa persoalan martabat berada diluar zona atau domain demokrasi. Oleh karenanya lalu, seolah-olah, demokratisasi tidak terbebani kewajiban untuk menegakkan martabat. Persoalan martabat lalu jatuh sebagai persoalan pribadi, persoalan keluarga ataupun persoalan komunitas masing-masing. Cara pandang semacam ini sebetulnya konsisten dengan iklim demokrasi yang kita kembangkan; yakni iklim penjaminan hak untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Sebetulnya tidak ada yang iherent salah ketika kewajiban-kewajiban tersebut didudukkan pada masing ‘masing-masing’ fihak. Hanya saja, pelembagaan demokrasi dalam corak liberal yang berlangsung di negeri ini mengharuskan masing-masing untuk survive melalui kompetisi. Sebagai contoh, agar ‘jawara’ di Banten survive dan tokoh-tokoh adat di daerah-daerah di era demokrasi ini, harus ikut berkompetisi untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Maka tokoh informal yang dikenal dengan sebutan jawara dan tokoh-tokoh adat di daerah lain dapat menduduki kursi jabatan strategis dengan memobilisasi kejawaraan dan basis adat istiadat setempat.
• Enlightenment: knowledge, insight, information
13 Jack Donnelly; “Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Rights”, The American Political Science Review, Vol. 76, No. 2 (Jun., 1982), pp. 303-316.
10
Yang perlu digarisbawahi dari pengamatan ini adalah bahwa:
• Demokrasi dan demokratisasi tidak menjangkau wilayah kejawaraan ataupun wilayah adat. ‘Kejawaraan’ dan ‘institusi adat’ tetap teguh seperti sediakala, dan pada saat yang sama partisipasi tokoh-tokoh dari keluarga jawara ataupun keluarga tokoh-tokoh adat tetap terpancang dalam norma yang berlaku di masyarakat.
• Dalam konteks ini, pelembagaan demokratisasi yang berlangsung dalam domain formal terkesan dipatuhi, namun sebetulnya ditelikung dalam perpolitikan di domain informal. Praktek ‘pemberian uang’, yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dikategorikan ‘gratifikasi’, dengan enaknya dibahasakan, bahkan direlakan sebagai, ekspresi ‘kepedulian pemimpin kepada para pengikutnya’.
• Perpolitikan yang berlangsung dalam domain informal ini dengan baik dimenengerti pada peneliti, namun pemahaman ini tidak bermuara pada reteorisasi dan reframing proses demokratisasi di negeri ini.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, proses demokratisasi perlu didukkan sebagai proses keseharian masyarakat. Sehubungan dengan perbedaan makna dari tindakan-tindakan yang diambil, maka pertarungan pada tataran discursive adalah keniscayaan. Terlepas dari apapun hasil yang diraih dari pertarungan itu, lokus demokratisasi adalah keseharian masyarakat itu sendiri. Ini artinya, demokrasi harus menjadi daily life politics. Lebih dari itu, sasaran dari daily life politics ini reproduksi makna baru dan transformasi makna-makna yang bisa dijustifikasi sebagai aktualisasi demokrasi. Melalui proses inilah sense kewarganegaraan berkembang sebagai penyangga dimokratisasi.
4. Penutup
Kealphaan akademis untuk mengawal demokratisasi dengan perangkat analisis berbasis nilai dan nalar para pelaku dalam perpolitikan, telah menghasilkan kecengengan akademis. Hal ini harus diakhiri, bukan hanya karena kepentingan akademis itu sendiri, melainkan juga karena telah mengantarkan kita pada kebingungan dan stagnasi. Yang jelas, cara pandang yang bersifat patologis tidaklah memadai. Sugguhpun demikian, tawaran untuk mengembangkan demokrasi yang bermartabat tidaklah terlalu menjanjikan jika tidak disertai dengan cara baru untuk memahami dan mengelola proses demokratisasi itu sendiri.
Demokratisasi, perlu didudukkan sebagai proses dan praktek kebudayaan. Dalam kerangka ini, demokratisasi adalah hajat bersama, dan pewacanaan tentang demokratisasi akan senantiasa sarat dengan kontroversi. Untuk itu, tradisi pemikiran yang cenderung menyalah-nyalahkan pelaku perlu ditransformasikan menjadi tradisi mengambil pelajaran bersama pelaku. Di sini, universitas menghadapi tantangan
11
metodologis karena terbiasa mengembangkan ilmu secara “berjarak” dengan realita: terobsesi menjaga obyektifitas. Lebih dari itu, universitas perlu mengembangkan teori-teori demokrasi berbasis pengalaman sehari-hari, berbasis konteks yang beragam. Dengan demikian, proses demokratisasi berjalan secara simultas dengan proses teorisasi demokratisasi itu sendiri.
Proses belajar dalam bentuk pengembangan teori di universitas maupun proses refleksi kolektif di kalangan praktisi demokrasi ini melibatkan kontroversi yang tiada henti. Namun semakin jauh universitas berkontribusi melalui pengendapan teori-teori yang dihasilkan, maka semakin jauh dalam keterlibatan tersebut. Dengan kata lain, kalaulah kerangka transisi-menuju-demokrasi Indonesia memang sudah dalam fase deepening democracy, universitas [termasuk Universitas Jendral Soedirman yang secang merayakan dies natalis ini] dituntut untuk melakukan deepening the making of theory on democracy; dan pendalaman teorisasi itu adalah pendalam budaya Indonesia.