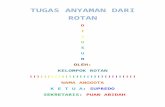Manuskrip Islam dan Mushaf Kuno dari Bali
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Manuskrip Islam dan Mushaf Kuno dari Bali
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
53
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah Keagamaan Islam di Bali: Sebuah Penelusuran Awal*)
Asep Saefullah dan M. Adib Misbachul Islam Puslitbang Lektur Keagamaan dan UIN Syahid, Jakarta
Pengantar
Keberadaan naskah tulisan tangan (manuskrip) di suatu wilayah, dari satu sisi dapat dianggap sebagai salah satu representasi dari lokalitas dan kekhasan wilayah bersangkutan. Dari sisi lain, ia dapat juga menjadi bukti adanya hubungan dengan wilayah lain jika ditemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan ke arah itu. Hal ini
*) Tulisan ini semula merupakan Makalah disajikan dalam “Seminar Hasil Penelitian
Naskah Klasik Keagamaan” Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Dep. Agama, Hotel Permata Alam, Cisarua-Bogor, 22-24 Desember 2008.
This paper is a result of our research of Islamic literature in Bali in 2008. We have discovered thirty-eight manuscripts that we can classify into three categories. The fitst category refers to tweleve manuscripts made of paper. The second category is tweleve manuscripts made of palm leaf: nine of them deal with Islam, two of them about Hinduism, and one of them is difficult to read. The third category is about fourteen Qur’anic manuscripts. In regard to Islamic literature in Bali, this category is unfortunately not taken care well. Most of this category of manuscript was torn away. In terms of codicology, we can write four important things as follows. First, this Islamic manuscript uses diverse tools, like dluang, European paper, modern lined paper, and palm leaf. Second, this Islamic manuscript adopts Arabic, Malay (Jawi), Bugese, and Balinese. Third, this Islamic manuscrip was written between the seventeenth and nineteenth century, and the oldest manuscript was written in 1625 AD (1035 AH). Fourth, this manuscript includes jurisprudence, mysticism, divinity, prayer, remembrance of God, medicines, Arabic grammar, Qur’an, and story.
Kata kunci: kodikologi, kertas Eropa, dluang, lontar, Bali
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
54
dapat ditelusuri dari berbagai informasi yang terkandung di dalam naskah itu atau dari fisik naskah.
Dalam konteks kajian keislaman di Indonesia, keberadaan naskah tersebut dapat dikaitkan dengan proses islamisasi atau perkembangan Islam yang banyak melibatkan para ulama produktif di zamannya. Dalam proses ini telah terjadi transmisi keilmuan, yang menurut Oman Fathurahman (2003: 1-2) membentuk pola dua kelompok bahasa naskah: Pertama, naskah-naskah yang ditulis da-lam bahasa Arab; dan yang kedua naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa-bahasa daerah. Dengan demikian, tidaklah menghe-rankan jika di Indonesia banyak ditemukan naskah-naskah berba-hasa Arab dan juga bahasa daerah seperti Melayu, Sunda, Jawa, Aceh, Bugis-Makassar, Bali, Batak, dan lain-lain. Sebagian naskah-naskah tersebut sudah tersimpan dengan baik di berbagai perpus-takaan dan museum, baik di dalam maupun di luar negeri, tetapi sebagian besar lagi diduga masih tersebar di tangan masyarakat. Sebagian besar naskah di luar negeri yang sudah terinventarisasi antara lain tersimpan di Malaysia, Afrika Selatan, Srilangka, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dan di berbagai negeri yang lain. (Chambert-Loir dan Fathurahman: 1999).
Persoalannya, dengan demikian, adalah bagaimana kondisi nas-kah-naskah yang masih di tangan masyarakat tersebut. Masalah ini tergolong serius karena umumnya naskah-naskah tersebut kurang terawat dan sangat tua, diperkirakan ditulis pada sekitar abad ke-17-19 M dan umumnya terbuat dari kertas yang secara fisik tidak akan tahan lama. Dengan demikian, upaya penelusuran naskah-naskah di masyarakat mutlak diperlukan sebagai upaya konservasi untuk kemudian dilestarikan dan dimanfaatkan, khususnya bagi penelitian lebih lanjut atau dalam rangka mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk merajut budaya bangsa menuju kerukunan umat beragama. Pentingnya upaya konservasi ini setidaknya disebabkan oleh dua hal: Pertama, banyaknya data penting berkaitan dengan fenomena keagamaan yang terdapat dalam naskah-naskah tersebut, dan kedua, sudah semakin rapuhnya kondisi fisik naskah-naskah tersebut seiring dengan berjalannya waktu (Bafadal dan Saefullah [Eds.], 2005: vii). Jika hal ini terus berlarut, dikhawatirkan naskah-naskah tersebut akan punah atau pindah tangan, yang pada akhirnya
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
55
hilang juga informasi dan sumber penting tentang khazanah kebu-dayaan Indonesia.
Berdasarkan permasalahan di atas, Puslitbang Lektur Keaga-maan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI melaku-kan upaya penelusuran naskah klasik keagamaan khusus milik perorangan. Hasil temuan naskah tersebut terutama dideskripsikan dan dikaji beberapa aspek kodikologinya (istilah “kodikologi” akan dijelaskan di bawah). Buku tentang kodikologi Nusantara, terlebih naskah keagamaan, tergolong masih sedikit.1
Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini merupakan bagian dari grand design—jika dapat dikatakan demikian—prog-ram konservasi naskah klasik keagamaan Indonesia yang sedang digalakkan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan. Penelitian dilaku-kan di Provinsi Bali dan sasarannya adalah naskah-naskah keaga-maan Islam.2 Dalam makalah ini akan dibahas dua masalah berikut: 1. Seberapa banyak naskah keagamaan Islam di Provinsi Bali yang
masih berada di tangan masyarakat atau milik perorangan? 2. Dari aspek kodikologi, bagaimana kondisi naskah-naskah terse-
but dan hal-hal apa saja yang dapat diungkapkan dari temuan naskah-naskah tersebut? Adapun tujuannya, pertama, untuk mengetahui jumlah naskah
keagamaan Islam di Provinsi Bali yang masih berada di tangan masyarakat, khususnya milik perorangan, dan kedua, membuat deskripsi naskah-naskah tersebut dan mengungkapkan beberapa aspek kodikologinya serta sedapat mungkin mengungkapkan hal-hal menarik dari temuan naskah tersebut. Dari segi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penye-lamatan naskah keagamaan di masyarakat dan selanjutnya dapat
1 Beberapa yang dapat disebut antara lain Kodokologi Melayu di Indonesia,
karya Sri Wulan Rujiati Mulyadi (1994), Penelusuran penyalinan naskah-naskah Riau abad XIX: Sebuah Kajian kodikologi, karya Mu'jizah dan Maria Indra Rukmi (1998), Penyalinan Naskah Melayu di Jakarta pada Abad XIX: Naskah Algemeene Secretarie Kajian dari Segi Kodikologi, karya Maria Indra Rukmi (1997), atau beberapa tulisan berupa artikel atau tesis, seperti “Penyalinan Naskah Melayu di Palembang”, karya Maria Indra Rukmi, makalah dalam Seminar Tradisi Naskah, Lisan dan Sejarah di FIB UI (2005).
2 Pilihan ini dilakukan karena naskah-naskah lontar dipandang relatif terpelihara dengan baik.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
56
menjadi bahan penelitian lebih lanjut, terutama kajian terhadap isi teks dan kontekstualisasinya.
Secara metodologis, penelitian ini sebagian besar bersifat pene-litian lapangan, yakni berupa penelusuran atas naskah-naskah ke-agamaan Islam di Provinsi Bali. Data primer dalam penelitian ini berupa naskah-naskah kuno yang disimpan perorangan dan lemba-ga-lembaga sosial keagamaan Adapun naskah-naskah koleksi per-pustakaan, museum, maupun pusat dokumentasi dalam penelitian ini tidak menjadi sasaran penelusuran karena naskah-naskahnya dipandang relatif aman dan terpelihara. Penelusuran dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan naskah-naskah yang belum diinventarisasi.
Dalam menyajikan data digunakan pendekatan kodikologi.3 Secara sederhana, kodikologi dapat dikatakan sebagai ilmu kodeks (bahan tulisan tangan), yaitu ilmu yang mempelajari seluk beluk semua aspek naskah, antara lain bahan, umur, tempat penulisan, dan perki-raan penulis naskah (Mulyadi, 1994:2).
Dalam wilayah kajian kodikologi dikenal istilah deskripsi. Secara ringkas, deskripsi adalah upaya menjelaskan seluk-beluk naskah secara fisik. Dalam makalah ini akan disajikan pengklasifi-kasian naskah-naskah yang ditemukan di lapangan, misalnya dari segi pemilik dan tempat penyimpanan, bidang kajian (isi naskah), bahan, usia naskah, kolofon, ilustrasi dan iluminasi, dan beberapa ciri khusus yang dapat diidentifikasi. Dengan kata lain, makalah ini hanya menyajikan beberapa aspek kodikologi dari naskah-naskah keagamaan Islam yang ditemukan di Provinsi Bali.
Pernaskahan di Bali Henri Chambert-Loir dan Fathurahman (1999:51) mengatakan,
“Pulau Bali terkenal sebagai gudang sastra Jawa Kuna karena sastra Jawa yang ditulis di berbagai kerajaan beragama Hindu-Buddha di
3 Tentang kodikologi di Indonesia dapat dibaca antara lain dalam Sri Wulan
Rujiati Mulyadi, Kodikologi Melayu di Indonesia, (Depok: Fakultas Sastra UI, 1994). Ada juga buku yang sangat menarik dan relatif baru tentang kodikologi Islam, yaitu Francois Deroche, Islamic Codicology, An Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script, (London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006), dan ada juga dalam edisi Arabnya yang terbit tahun 2005.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
57
Jawa Tengah dan Jawa Timur antara abad ke-10 dan ke-15, dan yang hampir punah setelah kedatangan agama Islam, masih berlanjut di Bali, bahkan hidup sampai kini.” Pernyataan ini terbukti dengan adanya sejumlah lembaga seperti museum dan perguruan tinggi di wilayah ini yang memiliki ribuan koleksi naskah. Lembaga-lem-baga tersebut antara lain Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, Denpasar mengoleksi sekitar 1.416 naskah, Museum Negeri Provinsi Bali, Denpasar menyimpan 266 naskah, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar memiliki 148 naskah, Kirtiya Liefrinck-van der Tuuk (Gedong Kirtiya), Singaraja memiliki tidak kurang dari 3000 nas-kah, Fakultas Sastra Universitas Udayana mempunyai 740 naskah, dan Balai Penelitian Bahasa, Denpasar mempunyai 156 naskah, serta Balai Arkeologi Denpasar juga menyimpan tiga naskah (Chambert-Loir dan Fathurahman, 1999:54-60; terutama berdasarkan Katalog Lontar yang Tersimpan pada Instansi Pemerintah dan Swasta yang diterbitkan oleh Kantor Dokumentasi Budaya Bali Provinsi Bali, tahun 1998). Jumlah ini belum termasuk naskah yang tersimpan pada koleksi pribadi yang diduga masih ribuan jumlahnya, terutama di puri (kediaman keluarga keturunan raja), griya (kediaman kelu-arga brahmana), dan kalangan ‘profesional’ (pemangku, dalang, balian usada atau orang-orang terdidik) (Chambert-Loir dan Fathurahman, 1999:56). Hampir seluruh naskah tersebut ditulis di atas bahan lontar sehingga sering pula disebut naskah lontar.
Di tengah “samudra koleksi naskah lontar” tersebut, di daerah-daerah tertentu di Bali ditemukan sejumlah naskah keagamaan Islam dan Mushaf Al-Qur’an kuno. Beberapa di antaranya ditulis di atas bahan dluang (kertas dari kulis kayu). Pada bulan Oktober 2008 yang lalu kami melakukan penelusuran ke pelosok-polosok pulau dewata ini. Kami menemukan 24 naskah keagamaan Islam yang terdiri atas 12 naskah ditulis di atas dluang, kertas Eropa, maupun kertas bergaris modern, dan 12 naskah lontar (naskah lontar berben-tuk geguritan; 9 naskah berisi cerita tentang tokoh Islam dan ajaran moral Islam, 2 cerita Hindu, dan 1 tidak terbaca). Di samping itu, ditemukan pula 14 Mushaf Al-Qur’an kuno, termasuk satu Mushaf ditulis di atas dluang. Naskah-naskah tersebut tersebar di beberapa kabupaten di Bali, antara lain Denpasar, Buleleng, Jembrana, dan
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
58
Karang Asem. Dengan demikian, jumlah naskah yang kami temukan sebanyak 38 naskah.
Perlu disebutkan bahwa dalam penelusuran naskah keagamaan Islam di Bali, kami melakukan kontak dengan pihak yang dipan-dang otoritatif dalam bidang keagamaan, yaitu Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali. Kami mendapatkan informasi awal, baik dari pejabat maupun pegawai Departemen Agama Provinsi Bali tentang lokasi-lokasi dan orang-orang yang diduga menyimpan dan atau mempunyai naskah keagamaan Islam.4
Lokasi-lokasi yang selanjutnya didatangi adalah: Kampung Bugis Kepaon Denpasar dengan Masjid Al-Muhajirin; Masjid Agung Jami’ Singaraja Buleleng; Pesantren Al-Hidayah Bedugul; Pegayaman Singaraja Buleleng; Masjid Asy-Syuhada Kampung Bugis Serangan Denpasar; Kampung Islam Buitan Sidemen Karang Asem; Kampung Islam Gelgel; dan Masjid Baitul Qadim, Loloan Timur, Negara, Jembrana. Temuan Naskah dan Tempat Penyimpanannya
Naskah keagamaan Islam di Bali yang berhasil ditelusuri terdiri atas naskah pelajaran agama, seperti fikih, tasawuf, wirid dan doa, dan juga obat-obatan yang disertai doa-doa, serta hikayat yang terutama ditulis di atas bahan lontar yang disebut geguritan. Di samping itu ditemukan juga naskah-naskah Al-Qur’an kuno yang sejauh ini belum pernah didata.
Sebagaimana disebutkan, hasil penelusuran di lapangan ditemu-kan 38 naskah, termasuk 14 naskah Al-Qur’an. Berikut temuan naskah berdasarkan lokasi atau tempat ditemukannya naskah.
4 Beberapa informan awal yang kami datangi di Kanwil Departemen Agama
Provinsi Bali adalah Ketut Ariawan, SH, Kasubag Umum, Drs. Ida Bagus Nyana, Staf Urusan Agama Hindu. Mereka menyarankan kami mendatangi Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, Gedong Kirtya-Singaraja-Buleleng, Karang Asem-Tradisi Tulis Lontar, Budakeling, Gianyar, dan Bangli. Informan lain Drs. H. Musta’in, Kabid Bimas Islam & P. Haji, Drs. H. M. Soleh, Kabid. Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Masjid. Selanjutnya kami mendapat banyak informasi dari Drs. H. Ghufron, Kasi. Penamas. Wawancara, 28 Oktober 2008. Selanjutnya penelusuran dilakukan sampai dengan 2 Nopember 2008.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
59
1. Denpasar Di Kampung Bugis Serangan, Denpasar ditemukan 3 (tiga)
naskah milik H. Burhanuddin, dekat Masjid Asy-Syuhada, dua di antaranya beraksara dan berbahasa Bugis, dan 1 (satu) Al-Qur’an Kuno milik Bapak Marjui.5 Di Kampung Bugis Kepaon, Denpasar ditemukan 6 (enam) naskah milik H. Musthafa Amin, dan 1 (satu) naskah Al-Qur’an kuno di Masjid Al-Muhajirin.6 Di Masjid Al-Mu’awanatul Khairiyah Kampung Bugis Suwung, Denpasar, masing-masing satu naskah Al-Qur’an. 7
Di samping itu, di Yayasan An-Nur, Denpasar, ditemukan 12 naskah lontar. Menurut informasi salah seorang ustadz di PP al-Hidayah, Bedugul,8 naskah lontar yang tersimpan di Yayasan An-Nur, pada awalnya merupakan koleksi Prof. Dr. Shaleh Saidi, salah seorang Guru Besar di Universitas Udayana, Bali. Meski sudah tersimpan di Perpustakaan Yayasan, naskah-naskah lontar tersebut belum dikaji secara kodikologis9. Oleh karena itu, dalam laporan penelitian ini naskah-naskah lontar koleksi Yayasan Masjid An-Nur penting untuk didata dan disampaikan. 2. Buleleng
Wilayah yang didatangi di Buleleng meliputi Pegayaman, Singaraja, dan Kampung Jawa. Di Pegayaman, Kampung Islam di pedalaman dekat Singaraja ditemukan 3 (tiga) naskah milik Drs. Suharto. Di sini ditemukan pula 1 (satu) Al-Qur’an kuno milik I
5 Naskah ini telah diteliti oleh E. Badri Yunardi, “Beberapa Mushaf Kuno
dari Provinsi Bali”, Jurnal Lektur Kegamaan, Vol. 5, No. 1, 2007. h. 1-18. 6 Mushaf ini sangat tidak terawat. Kondisinya tidak lengkap lagi, dan
ditumpuk dengan Al-Qur’an lain cetakan zaman sekarang. Tetapi, mushaf ini sangat menarik terutama dari segi iluminasinya yang indah dan, merujuk identifikasi Annabel Teh Gallop (2004) termasuk tipe Pantai Timur Melayu, Pattani atau Trengganu.
7 Kedua naskah ini juga sudah diteliti oleh E. Badri Yunardi, “Beberapa Mushaf Kuno dari Provinsi Bali”, Jurnal Lektur Kegamaan, Vol. 5, No. 1, 2007. h. 1-18. Sebelumnya, naskah ini disimpan di rumah H. Husen Abdul Jabbar. Wawancara dengan beliau pada 2 November 2008 di Loloan Timur.
8 Hadiman, Wawancara, 29 Oktober 2008, di Bedugul. 9 Semua naskah lontar koleksi Yayasan an-Nur hanya disebutkan judulnya,
dan beberapa di antaranya dijelaskan juga ukuran lontarnya.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
60
Wayan Ma’ruf.10 Di Singaraja, ditemukan banyak naskah Al-Qur’an kuno, yaitu di Masjid Agung Jami’. Di masjid ini ditemukan 8 (delapan) Al-Qur’an kuno (satu satu di antaranya merupakan litograf yang iluminasinya diberi pewarnaan). Di Kampung Jawa, tidak jauh dari Masjid Agung Singaraja, ditemukan 1 (satu) Al-Qur’an Kuno milik Bapak M. Zen Usman. Mushaf ini sangat menarik, karena selain ditulis pada bahan dluang, Al-Qur’an kuno ini masih lengkap, ditulis dengan khat Naskhi yang indah, dan yang terpenting mempunyai kolofon yang sangat tua, yaitu tahun 1035 H, sekitar 1625 M. 11 Sementara di Bedugul, antara Denpasar-Singaraja, menurut Hadiman, Gunawan, Syarifuddin, dan Agus, 12 konon ada naskah semacam Barzanji, tapi tidak berhasil ditemukan karena pemiliknya tidak ada di tempat dan tidak berhasil dijumpai. 3. Jembrana
Di Masjid Bait al-Qadim, Loloan Timur, Negara, Jembrana, ditemukan satu buah naskah Al-Qur’an. Naskah Al-Qur’an ini konon merupakan wakaf dari Encik Ya’qub dari Trengganu.13
10 Menurut Bapak Drs. H. Muchlis Sanusi, Lurah Kampung Bugis dan juga
Ketua Ta’mir Masjid Agung Singaraja, dan beberapa Pengurus Masjid, antara lain H. Abdurrahman Alawi, H. Abdurrahman Said, H. Hasyim Zaki, dan H. Hidayat, bahwa masjid ini sering didatangi wartawan dari berbagai media massa dan meliput salah satu Al-Qur’an kuno di sana, yang dipandang mushaf tertua di Buleleng. Akan tetapi, sejauh ini koleksi lain yang tersimpan di dalam lemari kaca belum pernah dilihat, yang ternyata seluruhnya Al-Qur’an kuno sebanyak tujuh mushaf, sehingga seluruhnya ada delapan Al-Qur’an kuno. Wawancara, 30 Oktober 2008 di Masjid Agung Singaraja.
11 Bunyi kolofon tersebut: “tamma al-qur’±n f³ yaum al-kh±mis min syahr al-mu¥arram f³ hil±li i¥d± wa ‘isyr³na ba‘da alfi sanah khamsin wa £al±£µna al-hijrah an-nabawiyyah “ (Al-Qur’an ini selesai [ditulis] pada hari Kamis dari bulan Muharram pada malam dua puluh satu pada tahun seribu tiga puluh lima [21 Muharram 1035] Hijrah Nabi).
12 Para ustadz di Pesantren Al-Hidayah, Bedugul, Wawancara, 29 Oktober 2008.
13 Naskah ini juga sudah diteliti oleh E. Badri Yunardi, “Beberapa Mushaf Kuno dari Provinsi Bali”, Jurnal Lektur Kegamaan, Vol. 5, No. 1, 2007. h. 1-18. Sebelumnya, naskah ini disimpan di rumah H. Husen Abdul Jabbar. Wawancara dengan beliau pada 2 November 2008 di Loloan Timur.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
61
4. Karang Asem Di Karang Asem, peneliti hanya mendatangi Kampung Islam
Buitan—sebuah kampung kecil yang hanya berpenduduk 25 kelu-arga. Konon di sini pernah ada naskah beraksara Bugis, tetapi karena sudah hancur, naskah-naskah tersebut dibuang. Naskah yang tersisa adalah kitab-kitab cetakan sekitar tahun 1300-an Hijriah, antara lain:
1) Kitab Sabil al-Muhtadin karya Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, jilid 1 dan 2, dan di tepinya ada Kitab Sirat al-Mustaqim, tentang ilmu fikih karangan Nuruddin Al-Raniri (diterbitkan di Mekah, al-Matba’ah al-Miriyah al-Ka’inah, 1321 H/1903 M);
2) Kumpulan kitab dalam satu bundel terdiri dari empat kitab, a) Kitab Miftah al-Jannah tentang Usuluddin karangan Muhammad Tayyib bin Mas’ud al-Banjari, b) Kitab Usul al-Tahqiq juga tentang Usuluddin, c) Kitab Mau’i§ah li al-N±s tentang tata cara sembahyang, dan f) Kitab Tajwid al-Qur’an, pengarang ketiga kitab ini tidak disebutkan; dan pada pias halaman ada Hamisy Kitab Asrar al-Dini, (diterbitkan di Mesir, Maktabah al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, t.t.);
3) Kitab Siraj al-Huda karangan Muhammad Zain al-Din bin Muhammad Badawi al-Sumbawa’i, Syarah atas Matan Umm al-Barahin karya Sanusi; dan di piasnya ada Hamisy Risalah Diya al-Murid, terjemahan Dawud bin Abdullah Fatani, Cet. Ke-6 (diterbitkan di Mekah, al-Matba’ah al-Miriyah al-Ka’inah, 1320 H/1902 M).
Ada yang menarik dari kitab-kitab ini, yaitu catatan pemiliknya, antara lain pada sampul dalam Kitab Siraj al-Huda terdapat tulisan, “Haza al-Kitab ini yang empunya Bapak Abd al-Rahman negeri Bali, Karangsem,14 Kampung Biutan As-Salam15 adanya”. Teks ini juga terdapat pada Kitab Sabil al-Muhtadin Juz I. Catatan kedua pada Daftar Isi Kitab Miftah al-Jannah, h. 44, berbunyi, “Tanda keterangan haza al-haq 16 Pak Muhammad Sa’id bin Mukhammad Ali Kusamba, Kampung Islam Pasuruan, dan membeli pada bulan Ramadan tanggal 15 hari Ahad pada tahun Zai Hijrah Nabi
14 Teks aslinya: kaf-ra-ng-syin-mim, bisa jadi maksudnya Karang Asem? 15 Sebagian orang Bali menyebut “Kampung Islam” dengan bunyi ucapan
yang terdengar adalah “Kampung Selam”. Teks dalam kitab ini juga bertuliskan “al-salam” (السالم), tapi bisa jadi dibaca “Selam”, yang maksudnya “Islam” seba-gaimana kebiasaan sebagian orang Bali, atau bias juga tetap dibaca “as-Salam” sebagaimana bahasa Arab.
16 Kata “¥aq” kadang diartikan “kepunyaan”, jadi “ha©a al-¥aq..” bisa diartikan “ini kepunyaan…”
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
62
Sallallahu ‘alaihi wa sallam 1334 H”. Tahun 1334 H adalah sekitar tahun 1915 M.
Nama-nama di atas, menurut Abdullah, 17 salah seorang yang dituakan di Buitan, adalah para leluhurnya, dan sebagian keluarga di sana, selain berasal dari Bugis, juga berasal dari Madura. Jika demikian, bisa jadi Kitab Miftah al-Jannah khususnya dibeli di Pasuruan.
Bidang Kajian (Isi Naskah)
Dilihat dari segi bidang kajiannya, kandungan isi naskah-naskah keislaman di Bali setidaknya meliputi: Fikih, Tasawuf, Tauhid, doa, wirid, obat-obatan, tata bahasa Arab (nashwu-saraf), Al-Qur’an, dan geguritan (cerita). 1. Fikih: Dalam bidang fikih hanya ditemukan satu naskah, yaitu
“Kitab Nikah” milik H. Musthafa Amin (MA 01), dan ini pun bagian pertama dari kumpulan teks lain yang berisi tentang obat-obatan disertai doa dan wirid.
2. Tasawuf/Akhlak: Naskah dalam bidang ini ada empat, yaitu Khazinah al-Asrar serta satu naskah beraksara dan berbahasa Bugis milik H. Burhanuddin. Dua naskah lainnya milik H. Musthafa Amin, no. MA 03 dan MA 04 yang dalam teksnya tidak disebutkan judulnya. Naskah MA 04 ditulis dalam buku Letjes.
3. Tauhid/Teologi: Dalam bidang ini ada empat naskah, satu naskah milik H. Musthafa Amin, antara lain berisi tanya jawab tentang Uluhiyah (ketuhanan), satu naskah beraksara dan berbahasa Bugis milik H. Burhanuddin, dan dua naskah lainnya milik Drs. Suharto di Pegayaman, yang berisi tentang sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, dan jaiz (satu dari dua naskah milik Drs. Suharto juga berisi teks lain yang berisi masalah fikih, milsanya tentang taharah [bersuci], tetapi naskah ini sudah bercerai berai dan tidak berjilid).
4. Wirid, Doa, dan Obat-obatan: Naskah yang berisi doa, wirid, dan obat-obatan, juga berisi wifiq, terdapat dua naskah, yaitu milik H. Musthafa Amin, nomor MA 05 dan MA 06. Dalam
17 Wawancara, Kampung Islam Buitan, Karang Asem, 2 November 2008.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
63
naskah MA 01 juga terdapat naskah jenis ini, yang terletak setelah “Kitab al-Nikah”.
5. Bahasa: Dalam bidang bahasa ditemukan satu buah naskah tanpa judul, milik Drs. Suharto, Pegayaman, ditulis di atas dluang, berisi tentang morfologi bahasa Arab atau ilmu sharaf.
6. Al-Qur’an: Meskipun naskah Al-Qur’an tidak sepenuhnya menjadi sasaran dalam penelitian ini, tetapi temuan ini penting karena banyak naskah baru yang ditemukan. Dari 14 naskah Al-Qur’an yang ditemukan, 11 di antaranya belum pernah diin-ventarisasi. Ke-14 naskah tersebut adalah delapan naskah Al-Qur’an di Masjid Agung Jami’ Singaraja, satu naskah di Kampung Jawa Singaraja, satu naskah di Pegayaman, dan satu naskah di Masjid Muhajirin Kapaon Denpasar, satu naskah di Masjid Al-Mu’awanatul Khairiyah Kampung Bugis Suwung, Denpasar, satu naskah milik Bapak Marjui, Kampung Serangan Denpasar, dan satu naskah di Masjid Bait al-Qodim Loloan Timur.
7. Geguritan: Sebagaimana yang dikenal secara luas oleh masya-rakat, Bali memang identik dengan Hindu, dan karenanya tradisi pernaskahan di sana pun dengan sendirinya juga tidak dapat dilepaskan dari Hindu. Meskipun demikian, hasil pene-litian lapangan terhadap naskah-naskah lontar di Bali berhasil memberikan informasi lain terkait dengan tradisi pernaskahan di Pulau Dewata tersebut. Ini dapat dilihat dari beberapa naskah lontar yang ditemukan di lapangan. Dari 12 naskah lontar yang berhasil ditemukan, dan semuanya dalam bentuk geguritan,18 sembilan di antaranya menunjukkan adanya pengaruh Islam dalam tradisi kesusastraan Bali. Berikut ini gambaran mengenai isi 1119 naskah lontar yang berhasil ditemukan:
18 Geguritan adalah karya sastra Bali yang dibangun di atas pupuh.
Sementara itu, pupuh diikat oleh beberapa kaidah yang mencakup: banyaknya baris dalam tiap bait, banyaknya suku kata dalam tiap baris, dan bunyi akhir tiap-tiap baris (Agastia, t.t.: 155).
19 Dari 12 naskah lontar, ada satu naskah yang tidak dapat dibaca. Pembacaan naskah lontar oleh Made Suparta, dosen pada Program Studi Jawa, FIB Universitas Indonesia.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
64
a. Cerita Islam
1). Pepalihan Gama Selam Bali. Teks ini menceritakan proses islamisasi di Bali.
2). Geguritan Semaun. Teks ini berisi cerita mengenai tokoh heroik yang bernama Sema’un pada masa-masa awal islamisasi
3). Geguritan Bagendhali. Teks ini menceritakan tokoh Bagendhali yang sangat sakti, beserta dua saudaranya: Bagenda Sulaiman dan Bagendha Alah.
4). Kidung Tuwan Semeru. Teks ini berisi cerita tentang kehidupan Nabi. 5). Geguritan Krama Selam. Tidak banyak berbeda dengan teks
Pepalihan Gama Selam, teks ini juga berisi cerita tentang proses islamisasi di Bali.
6). Geguritan Siti Badariyah. Teks ini tentang kehidupan keluarga kerajaan di negeri Arab.
7). Geguritan Amir Hamzah. Teks ini berisi cerita tentang peran Amir Hamzah dalam proses islamisasi di Nusantara.
8). Geguritan Jayengrana. Teks ini menceritakan sosok pahlawan muslim dalam melawan raja kafir. Di samping itu, teks ini juga banyak mengandung ajaran moral dan etika Islam.
9). Geguritan Jimat Teks ini berisi mistik Islam.
b. Cerita Hindu
1). Geguritan Sebun Bangkung. Teks ini berisi filsafat moral Hindu yang disampaikan secara naratif.
2). Geguritan Pan Bongkling. Teks ini berisi konsep dharma dalam agama Hindu.
Gambaran isi naskah lontar di atas secara jelas memperli-hatkan adanya pengaruh Islam dalam tradisi kesusastraan Bali, meskipun kapan dan dari mana awal mula masuknya pengaruh Islam tersebut masih perlu diteliti lebih jauh lagi, sebab deskripsi kodikologis terhadap naskah-naskah lontar di atas menunjukkan bahwa naskah-naskah lontar tersebut memang masih muda. Yang menarik, semua kolofon20 yang terdapat dalam naskah lontar itu menginformasikan adanya tahun penyalinan yang sama, yakni 1923 isaka atau 2001.
20 Dari 12 naskah lontar di atas, empat di antaranya tidak bertanggal, yaitu:
Geguritan Siti Badariyah, Geguritan Amir Hamzah, geguritan Jayengrana, dan satu naskah yang tidak dapat diidentifikasi baik judul maupun isinya karena kondisi fisiknya yang sudah lapuk.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
65
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah Islam di Bali
1. Kondisi Naskah Naskah keagamaan Islam di Bali kurang mendapat perhatian,
tidak seperti naskah lontar yang, di samping telah banyak dikaji, juga terdokumentasi dengan baik sebagaimana dijelaskan di atas. Naskah-naskah keagamaan Islam yang ditemukan pada masyarakat umumnya tidak terpelihara dan bahkan tak terperhatikan sama sekali, seperti Al-Qur’an kuno di Masjid Al-Muhajirin Kepaon. Kondisi naskah lontar di Yayasan An-Nur memang mendapatkan perawatan, tetapi naskah-naskah lontar itu termasuk baru, karena sebagian di antaranya disalin ulang pada tahun 2000-an.
Naskah-naskah yang ditemukan di rumah H. Musthafa Amin, di Kepaon Denpasar, dari enam naskah yang dimilikinya, ada empat naskah yang relatif terbaca, tetapi hampir semuanya tidak ada yang lengkap. Satu buah naskah berlubang dimakan rayap dan satu lagi tinggal setengahnya. Demikian juga di Kampung Bugis Serangan, dari empat naskah yang ditemukan, satu naskah di antaranya dari bahan kertas modern bergaris, tetapi tidak utuh. Di Pegayaman pun demikian, empat naskah yang ditemukan sudah lapuk semua; satu naskah tercerai berai, satu naskah Al-Qur’an tidak lengkap lagi dan tengahnya berlubang dimakan serangga, dan dua naskah lainnya yang ditulis di atas dluang telah robek, terutama pada halaman belakang.
Kondisi naskah di Masjid Singaraja dan milik M. Zen Usman relatif baik. Meskipun telah disimpan dalam kotak kayu khusus, seperti mushaf kuno milik M. Zen Usman, dan di dalam lemari kaca, seperti mushaf koleksi Masjid Singaraja, di dalam tempat penyimpanan naskah itu tidak terlihat ada bahan penangkal serang-ga, seperti cengkih atau kapur barus. Sebagian besar mushaf itu juga tidak lengkap dan banyak lembarannya yang sudah terlepas, kecuali mushaf yang diduga ditulis oleh Gusti Ngurah Ketut Jelantik Selagi, salah seorang keturunan Raja Buleleng yang masuk Islam (MAJS/NQ/01), 21 dan mushaf milik M. Zen Usman yang lengkap dan kondisinya bagus.
21 Wawancara dengan Drs. Muhlis Sanusi, Lurah Kampung Islam, Singaraja,
Buleleng, 30 Oktober 2008. Hadir pula beberapa pengurus Ta’mir Masjid Agung yang lain, yaitu H. Abdurrahman Alawi, H. Hasyim Zaki, dan H. Hidayat.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
66
2. Bahan Bahan yang digunakan untuk menulis naskah-naskah keagama-
an Islam di Bali dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis: a) Dluang, b) Kertas Eropa, c) Kertas modern bergaris, dan d) lontar. Dari 38 naskah, terdapat tiga naskah yang ditulis di atas dluang, yaitu: dua naskah milik Drs. Suharto di Pegayaman dan satu mushaf Al-Qur’an, lengkap 30 juz, milik M. Zen Usman di Kampung Jawa Singaraja. Sebagian besar naskah lainnya ditulis di atas kertas Eropa. Beberapa cap kertas (watermark) dan cap tandingan (countermark) yang berhasil diidentifikasi antara lain kelompok Crescent, Pro Patria, Britania, dan Horn (tertera angka tahun 1825 pada mushaf di Masjid al-Muhajirin, Kepaon). Naskah yang ditulis di atas kertas Eropa berjumlah tujuh naskah.
Naskah ditulis di atas kertas modern bergaris (Letjes) ada dua, yaitu milik H. Musthafa Amin di Kepaon (MA 04) dan H. Burha-nuddin di Serangan, keduanya di Denpasar, serta satu naskah lain ditulis di atas kertas bergaris bukan Letjes milik H. Musthafa Amin. Bahan lontar digunakan untuk menyalin 12 naskah geguritan; 11 naskah menggunakan bahasa dan aksara Bali, dan satu naskah menggunakan bahasa Melayu dengan aksara Bali. Semua naskah lontar tersebut milik Yayasan An-Nur, Denpasar. 3. Usia Naskah
Dilihat berdasarkan usia naskah, naskah Al-Qur’an dari Kam-pung Jawa, milik M. Zen Usman termasuk naskah yang paling tua, bahkan ia merupakan naskah Al-Qur’an tertua ketiga di Asia Tenggara. Berdasarkan kolofonnya, mushaf ini selesai ditulis pada malam Ahad, 21 Muharram 1035 H atau sekitar tahun 1625 M. 22 Naskah-naskah lain pada umumnya ditulis pada abad ke-13 H atau sekitar abad ke-18-19 M. Misalnya naskah Kitab Al-Nikah dan Obat-obatan (MA 01) milik H. Musthafa Amin menyebutkan angka
22 Mushaf tertua konon mushaf nomor MS 12716 koleksi William Marsden
di Perpustakaan School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, berangka tahun Jumadil Awwal 993/1585 dan kedua adalah mushaf dari Ternate, Maluku Utara, yang ditulis oleh Al-Faqih al- Salih Afifuddin Abdul Baqi bin Abdullah Al-Adni, pada 7 Zulqa’dah 1005 H/1597 M. (Bafadal dan Anwar, 2005: vii-viii)
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
67
tahun 1287 H/1870 M dan 1288 H/1871 M. Kolofon yang agak tua terdapat pada naskah Al-Qur’an MAJS/NQ/03 koleksi Masjid Agung Jami’ Singaraja, yaitu bulan Zulqa’dah 1265 H/1848 M. Demikian juga dilihat dari kertas Eropa yang digunakan. Kertas Eropa yang memiliki cap kertas pada kelompok Pro Patria, Britania, Horn, atau Crescent, pada umumnya diproduksi antara pertengahan abad ke-17 M sampai abad ke-19 M. Misalnya, dari daftar cap kertas yang disusun Heawood diketahui bahwa kertas dengan cap kertas kelom-pok Pro Patria diproduksi pertengahan abad ke-17 M (Heawood, 1986: 145-146). Cap kertas yang terlihat pada naskah MA 03 yang termasuk kelompok Names dengan cap kertas berupa: tulisan nama I Pigoizard, menurut Heawood (1986:140), diproduksi sekitar tahun 1737 atau sesudahnya. 4. Bahasa dan Aksara
Naskah-naskah keagamaan Islam di Bali setidaknya mengguna-kan empat aksara dan empat bahasa. Aksara yang digunakan adalah Arab, Jawi, Bugis, dan Bali, sedangkan bahasanya adalah Arab, Melayu, Bugis, dan Bali. Selain Al-Qur’an yang berjumlah 14 naskah, naskah berbahasa Arab hanya dua, yaitu naskah tentang morfologi Arab (saraf) dan sifat-sifat Allah dari Pegayaman. Nas-kah yang menggunakan aksara dan bahasa Bugis ada dua, yaitu milik H. Burhanuddin, Serangan Denpasar. Sementara aksara dan bahasa Bali hanya digunakan pada 12 naskah lontar koleksi Yaya-san An-Nur. Selebihnya, atau sekitar delapan naskah lainnya meng-gunakan bahasa Melayu dengan aksara Jawi. Tentang istilah Jawi, dalam naskah MA 02 disebut “bahasa Jawi”, misalnya ketika mengartikan kata “uluhiyah” dan “ilah” pada h. 10r-10v disebutkan demikian, “… dan arti uluhiyah pada bahasa Jawi ketuhanan dan arti Ilah pada bahasa Jawi Tuhan…” 5. Kolofon
Dari 38 naskah yang diinventarisasi, tidak banyak ditemukan naskah yang mempunyai kolofon. Setidaknya ada enam naskah yang berkolofon, dan dalam naskah MA 01 milik H. Musthafa Amin terdapat dua kolofon.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
68
Pada naskah MA 01, yang terdiri dari beberapa teks, h. 33v bagian akhir teks pertama terdapat nama kitab, yakni “Kitab Nikah” dan waktu penyalinannya. Bunyi kolofon tersebut sebagai berikut:
Haza [al-]Kitab al-Nikah [ter] Hijrah al-Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam seribu dua ratus delapan puluh tujuh (1287) pada tahun Ba alif(?) pada malam ahad waktu jim(?) pada pukul delapan pada delapan hari bulan Rabi’ al-Awwal pada ketika itulah hamba Pa Abdul A’raf sudah selesai menyuruh ini kitab di dalam negeri Badung Bali Badung adanya Kampung Kepaon 1287
Tamma wa sallallahu ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallam
Pada teks kedua h. 41v, kolofonnya berbunyi:
Telah mengambil ijazah faqir a-haqir ila Allah Ta’ala Haji Hasan ibn al-Marhum al-Haj Muhammad Amin al-Din Palimbangi akan mengamalkan laqad ja’akum serta doa yang kemudian kepada Syaikhuna wa ustazuna wa wasilatuna ila Allah Ta’ala al-Arif bi Allah sayyidi al-Syaikh Muhammad Azhari ibn al-Mukarram al-Marhum Kemas Muhammad Haji Abdullah Palimbangi Nafa’ana Allah bi barakatihi wa barakat ‘ulumihi. Amin 1288 H di Ampenan Syahr [al-]Shafar.
Agak sulit menghubungkan kedua kolofon yang terdapat dalam
satu naskah ini. Kolofon pertama menyebutkan tempat penulisan di negeri Badung, Kampung Kepaon, Bali, sedangkan kolofon kedua menyebutkan Ampenan, yang bisa dipastikan di Palembang sebab yang mengambil ijazah untuk amalan dalam teks ini adalah Haji Hasan Palimbangi, orang Palembang. Satu hal yang dapat diduga adalah telah terjadi hubungan antara Palembang dan Bali sekitar tahun 1287-1288 H/1870-1871 M.
Nama Kepaon juga disebut dalam naskah MA 02. Naskah ini tergolong masih baik karena tulisannya dapat dibaca, walaupun jilidnya sudah lepas. Dalam kolofonnya disebutkan bahwa teks ditulis oleh Haji Dawud, Badung, Kepaon, di Pabeyan. Berikut bunyi kutipan kolofon pada h. 10v:
“…tammat, namanya orang menyurat ini Haji Dawud dari negeri Badung Kepaon tatkala menyurat ini di negeri Pabeyan rumah bapak Tayid23 tamat al-kalam”
23 Ba-pa-alif ta-alif-ya-dal (بفأ تايد)
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
69
Kolofon lain ditemukan dalam mushaf Kuno nomor MAJS/NQ/03 koleksi Masjid Agung Jami’ Singaraja. Letak kolofon ini di pias halaman bagian akhir mushaf setelah Surah al-Nas dan sebelum doa khatm Al-Qur’an. Dalam kolofonnya, mushaf ini disebutkan selesai ditulis oleh Haji Muhammad Ja’far pada waktu duha hari Rabu bulan Zulqa’dah 1265 H/1848 M. Kolofon ini ditulis dalam bahasa Arab. Berikut ini kutipan kolofon:
“kana al-farag al-kha¯¯ ¥ajj Mu¥ammad Ja‘far yauma arba‘ wa f³ waqti a«-«u¥± f³ syahri ©i al-qa‘dah f³ sanah alfi taqw³m £al±£24 hijrah an-nab³ 1265 “
Penting dicatat, bahwa di Bali ditemukan juga kolofon yang menyebutkan angka yang sangat tua, 1035 H/1625 M, yakni pada Mushaf milik Zain Usman, Kampung Jawa Singaraja. Pada kolo-fonnya disebutkan, mushaf ini ditulis oleh Abd Shafiyyuddin pada hari Kamis tanggal 21 Muharram 1035 H. Kolofon ini juga ditulis dalam bahasa Arab, bunyinya demikian:
“tamma al-qur’±n f³ yaum al-kh±mis min syahr al-mu¥arram f³ hil±li i¥d± wa ‘isyr³na ba‘da alfi sanah khamsin wa £al±£µna al-hijrah an-nabawiyyah “
Pada naskah Litrograf beraksara Bugis milik H. Burhanuddin, Serangan, ditemukan angka tahun 1373 H/1885 M pada halaman sampul. Angka tahun ini menerangkan selesainya pencetakan naskah. Selain itu disebutkan pula nama dan tempat percetakan serta pemilik percetakannya; percetakan at-Taufiq milik Haji Muhammad Abduh, Pare-pare, dalam bahasa Arab yang berbunyi sebagai berikut:
“tubi‘a bima¯ba‘ah al-Tauf³q li ¡±¥ibih± al-¥±jj Mu¥ammad ‘Abduh pepajah bi Pare-pare 1373”
6. Penjilidan
Aspek lain dalam kodikologi adalah bagian penjilidan. Dari segi penjilidan, kondisi naskah-naskah Bali beragam; ada yang masih baik, ada yang sudah lapuk, dan ada juga yang sudah terlepas dari
24 sanah alfi taqw³m £al±£, bisa jadi berarti tahun seribu masuk ratusan
ketiga, artinya 1200-an lebih, dan angka tahun yang tertulis adalah 1265 H, sama dengan 1848 M.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
70
ikatan kuras naskah.25 Bahkan sebagian di antaranya lepas jilidan-nya, seperti yang terlihat pada satu mushaf di Masjid asy-Syuhada, Loloan Timur, dan satu mushaf di masjid al-Muhajirin, Kepaon. Pada dua mushaf ini, jilidan aslinya sudah tidak ada, namun untuk mushaf koleksi masjid asy-Syuhada sudah diganti dengan sampul dari kertas karton.
Dari segi bahan sampul, naskah-naskah Bali cukup bervariasi; ada yang bahan sampulnya terbuat dari kulit, dan ada juga yang terbuat dari karton. Selain naskah mushaf, kebanyakan bahan sampul naskahnya adalah kertas karton tipis. Adapun untuk naskah mushaf, hampir semua bahan sampulnya terbuat dari kulit tebal dengan motif floral serta menggunakan amplop. 26 Naskah lain adalah yang ditulis di atas kertas bergaris dalam buku Letjes dengan sampul kertas berwarna biru khas Letjes. 7. Kaligrafi
Selain naskah lontar, seluruh naskah ditulis dalam aksara Arab dan Jawi. Oleh karena itu, menarik juga untuk dilihat model-model tulisannya atau yang lazim disebut kaligrafi. Naskah-naskah Al-Qur’an umumnya menggunakan jenis kaligrafi atau khat Naskhi, walaupun masih sangat sederhana dan belum dapat dikatakan stan-dar. 27 Berbeda dengan yang lainnya, Mushaf dari Kampung Jawa Singaraja sudah menggunakan khat Naskhi yang indah dan mende-kati standar apalagi jika dilihat masa penulisannya—walaupun belum menggunakan pena khat untuk membentuk tipis-tebalnya huruf—, yaitu tahun 1035 H/1625 M (Gambar 01). Pada masa ini, khususnya di Nusantara, belum banyak ditemukan naskah yang
25 Kuras adalah istilah yang mengacu pada sejumlah lembar kertas/perkamen
yang dilipat dan dijahit untuk kepentingan penjilidan (Francois Deroche, 2005: 122).
26 Sampul seperti ini banyak ditemukan di Nusantara, misalnya beberapa naskah di Bayt al-Qur’an dan Museum Istiqlal TMII Jakarta (Saefullah, 2007: 47).
27 Kaligrafi Arab standar dalam bahasa Arab disebut Al-Kha¯¯ al-Mansµb mempunyai tiga alat ukur, yaitu: Alif, titik belah ketupat, dan lingkaran. Pena yang digunakan biasanya dimiringkan mata penanya sehingga ketika ditarik menyamping miring kanan ke bawah akan membentuk titik belah ketupat ( ). Tinggi alif pada jenis Naskhi standar, misalnya, lima titik belah ketupat. Rumusan ini diciptakan oleh Ibnu Muqlah (Sirojuddin, 1992:86-99)
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
71
disalin dengan khat Naskhi yang indah, bahkan untuk naskah keagamaan lainnya digunakan Khat Farisi atau Riq’ah, baik yang cenderung ke Naskhi maupun Farisi.
Jika dikelompokkan ke dalam jenis-jenis khat, maka naskah-naskah yang ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis khat, yaitu Naskhi, Farisi, dan Riq’ah. Jenis Naskhi yang ditemukan memang sangat sederhana, misalnya naskah dari Pegayaman, tipis tebal goresan aksaranya sudah nampak dan memperlihatkan bentuk Naskhi yang cukup indah (Gambar 02). Sementara jenis Khat Riq’ah yang biasanya tipis-tipis dan condong ke kiri ditemukan dalam banyak naskah. Namun demikian, sapuan pada beberapa huruf, khususnya sin dan kaf memperlihatkan gaya Farisi. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan Riq’ah, khususnya naskah MA 06 (Gambar 03). Jenis Farisi misalnya ditemukan pada Naskah MA 03 dari Kepaon. Karakter tulisannya condong ke kanan dan sapuan-sapuan pada sin dan gigi ba, ta, £a, atau ya, yang agak meliuk-liuk dan memanjang, walaupun masih sederhana dan ada kesan Riq’ah karena sebagian hurufnya condong ke kanan (Gambar 04). 8. Ilustrasi dan Iluminasi
Ilustrasi adalah sebuah gambar atau hiasan yang ada hubungan-nya dengan teks, dan biasanya digunakan untuk memberikan penje-lasan lebih lengkap dari teks bersangkutan. Sedangkan iluminasi, yang berasal dari kata illumination, yang berarti menerangi, biasa-nya lebih berfungsi sebagai hiasan, dan tidak berkaitan langsung dengan teks. Dalam naskah-naskah keagamaan Islam di Bali tidak ditemukan iluminasi, kecuali dalam naskah Al-Qur’an. Ilustrasi yang ditemukan pun hanya sedikit. a. Ilustrasi
Ilustrasi terdapat pada naskah tasawuf dan masalah doa, wirid, dan wifiq. Dalam naskah MA 03, h. 11r, terdapat ilustrasi tentang sifat-sifat Allah berdasarkan kalimat L± Il±ha Ill± All±h yang dibagi ke dalam empat kategori “L±”, “Il±ha”, “Ill±”, dan “All±h” (Gambar 05). Pada naskah MA 04, h. 17v, kata “Il±h” diletakkan dalam kotak belah ketupat dan segi empat, dan di sekelilingnya terdapat penje-lasan sehingga membentuk semacam concept map (peta konsep),
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
72
terkait dengan ilmu ma’rifah, dan disebut juga nama-nama malaikat, sahabat, dan lain-lain (Gambar 06).
Pada naskah Serangan 01 yang berbahasa dan beraksara Bugis, tentang tasawuf, terdapat ilustrasi lafa§ al-jal±lah, kata “All±h”, yang diletakkan dalam blok hitam. Ada dua blok yang semuanya berisi kata “All±h”, dan di atas-bawahnya terdapat penjelasan yang diduga terkait dengan zikir (Gambar 07).
Contoh ilustrasi terakhir adalah tentang wifiq. 28 Dalam naskah wirid dan doa MA 05, h. 12v-13r, terdapat simbol-simbol yang diletakkan dalam bingkai garis, misalnya kata “Allah” dan “Muhammad” dalam satu kotak, kata “Muhammad” dan “Ilah”, kalimat L± Il±ha ill± All±h Mu¥ammad Rasµl Allah”, masing-masing dalam satu kotak, dan simbol-simbol huruf hijaiah yang dirangkai sedemikian rupa dan diletakkan dalam satu kotak (Gambar 08). b. Iluminasi
Iluminasi hanya ditemukan dalam naskah-naskah Al-Qur’an. Meskipun naskah Al-Qur’an terkadang dikhususkan dalam klasi-fikasi kajian naskah klasik, tetapi karena pentingnya temuan ini, dan juga dapat dikaji secara kodikologis, hasilnya disajikan di sini. Iluminasi dalam mushaf-mushaf kuno yang ditemukan di Bali sangat luar biasa. Desain hiasan yang menurut identifikasi Annabel Teh Gallop (2004) sebagai tipe Aceh, Sulawesi, Pantai Timur Semenanjung Melayu atau Pattani dan Trengganu, dan Jawa, ditemukan di Bali. Bahkan satu mushaf di Masjid Agung Singaraja (MAJS/NQ/01) sangat khas, unik, dan menarik, yakni iluminasi dalam bentuk arabesk (pola geometris yang disalin bersilangan) dari kalimat L± Il±ha ill± All±h Mu¥ammad Rasµl Allah sebagai bingkai hiasan yang mengelilingi bidang teks ayat-ayat Al-Qur’an, yang terdapat pada bagian tengah mushaf.
Karakter kedaerahan iluminasi dapat juga dilihat dari penem-patan halaman berhias pada awal, tengah, atau akhir; ada perbedaan kedaerahan yang konsisten dan mencolok. Dalam hal penempatan
28 Wifiq: suatu formula yang terdiri atas susunan bilangan atau angka Arab
tertentu yang mengandung rahasia-rahasia spiritual. Bagi yang mempercayainya, pengetahuan mengenai formula tersebut merupakan hikmah ilahiyah.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
73
iluminasi tengah: Aceh selalu bagian tengah Al-Qur’an, yaitu awal juz 16 atau bagian tengah Surah al-Kahf; Pantai Timur Melayu biasanya pada permulaan juz 15 atau awal Surah al-Isra’; dan di Jawa hampir selalu ditemukan pada permulaan surah al-Kahf (Gallop, 2004: 132). Penempatan ini dapat ditemukan pula pada mushaf-mushaf Bali. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat keempat tipe atau desain hiasan tersebut.
1). Tipe Aceh dan Istimewa: Iluminasi Kalimat L± Il±ha Ill±
All±h Mu¥ammad Rasµl All±h Di Masjid Jami’ Agung Singaraja terdapat mushaf, kode
MAJS/NQ/0129 yang sejauh pengetahuan kami memiliki keistime-waan yang luar biasa, yakni iluminasi bagian tengah. Rangkaian dari kalimat L± Il±ha Ill± All±h Mu¥ammad Rasµl All±h yang didekor sedemikian rupa sehingga menciptakan bingkai hiasan berbentuk arabesq yang mengelilingi teks ayat Al-Qur’an. Belum lagi desain hiasannya dan motif pewarnaannya yang memiliki unsur-unsur daerah lain, yaitu Sulawesi dan Aceh. Demikian juga dengan bahannya, meskipun berupa kertas Eropa tetapi berdasarkan cap kertas (water mark)-nya yang termasuk kelompok Cressent, adalah kertas yang umumnya digunakan di Afrika, “paper used by Denham in Africa” (Heawood, 1986: 85). 30
29 Tebal naskah 682 halaman, setiap halaman terdiri atas 14 baris, kecuali
halaman awal yang terdiri atas 7 baris. Naskah berukuran 27 X 21 cm, sementara ukuran teksnya adalah 18 X 14, 5 cm. Pada naskah ini terdapat bingkai teks berupa tiga buah garis tipis berwarna hitam dan merah. Sampul naskah berukuran 33,5 X22 cm yang terbuat dari kulit berwarna merah maron dengan motif floral. Bagian dalam sampul naskah dilapisi kain saten. Sampul naskah memakai tutup (plop). Teks ditulis dengan menggunakan khat naskhi. Tinta yang digunakan berwarna hitam. Pada bagian tertentu, seperti kepala surah, awal juz, atau tanda baca, digunakan tinta berwarna merah. Pada halaman pelindung terdapat catatan yang tertulis: “h±©a al-waqf mu¡¥af masjid jam³‘”. Menurut keterangan pengurus takmir masjid, naskah mushaf ini ditulis oleh Gusti Ngurah Ketut Jelantik Selagi, salah seorang keturunan Raja Buleleng yang masuk Islam.
30 Tentang bahan kertas yang biasanya digunakan di Afrika, mengapa dapat sampai ke Bali, dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa orang-orang Bugis pada masa lalu telah banyak bermukim di Bali. Bahkan, desa di mana Masjid Agung Singaraja berada pun bernama Kampung Bugis. Wawancara dengan H. Hasan (penduduk setempat), H. Hasyim Zaki, dan H. Abdurrahman Alawi (Pengurus Ta’mir Masjid), 30 Oktober 2008.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
74
Merujuk pada identifikasi yang pernah dibuat Annabel Teh Gallop (2004) tentang ragam hias mushaf, salah satu mushaf Al-Qur’an di Masjid Jami’ Agung Singaraja memiliki unsur-unsur yang umumnya terdapat di Aceh dan Sulawesi. Ciri kedaerahan pada umumnya dapat dilihat pada pola, pewarnaan dan detail hiasan bingkai (Gallop, 2004: 129). Iluminasi mushaf Aceh mudah dike-nali dengan “garis bingkai vertikal, yang mengapit bidang teks pada masing-masing halaman, memanjang ke atas dan ke bawah, dan miring ke dalam pada ujung atas dan bawah. Di ketiga sisi luar bidang teks, ada garis melengkung sampai ke tepi, sementara lengkungan pada sisi vertikal diapit oleh dua ‘sayap’ kecil, yang dapat berbentuk sulur lembut yang tipis ataupun berukuran lebih besar. Segi empat berhias di sekitar bidang teks sering diisi dengan sulur ikal warna putih, dan di bagian-bagian tertentu sering terdapat motif jalinan. Sepasang bingkai berhias dari Aceh ini dicirikan dengan pewarnaan yang kuat, namun terbatas, terutama merah, kuning dan hitam. Warna dasar keempat dalam naskah beriluminasi dari Aceh adalah warna putih, namun menampilkan latar belakang kertas itu sendiri, yang memang berwarna putih.
Desain seperti diuraikan di atas jelas sekali terlihat pada ilumi-nasi bagian awal mushaf ini (MAJS/NQ/01).31 Sedangkan iluminasi yang istimewa terdapat pada bagian tengah mushaf, di satu sisi memperlihatkan pola Aceh dengan “sepasang garis tegak kiri-kanan”, tetapi di bagian kiri dan kanan garis tegak tersebut terdapat bentuk segitiga, yang dekat ke Sulawesi, walaupun tidak terlalu jelas sebab salah satu ciri kedaerahan iluminasi Sulawesi adalah garis lurus. Dari segi teks ayat pada bagian tengah yang berilu-minasi, mushaf ini sama dengan mushaf-mushaf dari Aceh yang selalu menempatkan awal juz 16 atau bagian tengah Surah al-Kahf, dan mushaf ini menempatkan awal juz 16. Segi empat berhias di sekitar bidang teks pada pola Aceh yang sering diisi dengan sulur
31 Bagaimana pola Aceh terdapat dalam mushaf ini? Berdasarkan keterangan pengurus Ta’mir masjid dan penduduk setempat, bahwa di wilayah ini pernah kedatangan orang-orang dari Aceh, hanya saja tidak diketahui siapa dan kapan hal itu terjadi. Akan tetapi, jejaknya bisa ditemukan bahwa salah seorang pengurus ta’mir masjid sendiri, Bapak H. Hasyim Zaki, adalah seorang Muslim Bali yang memiliki darah Aceh. Menurut kakaknya, H. Hasan, leluhur mereka ada yang berasal dari Aceh. Wawancara dengan H. Hasan (penduduk setempat), H. Hasyim Zaki, dan H. Abdurrahman Alawi (Pengurus Ta’mir Masjid), 30 Oktober 2008.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
75
ikal warna putih, dan di bagian-bagian tertentu sering terdapat motif jalinan, dalam mushaf MAJS/NQ/01, berupa jalinan kalimat L± Il±ha Ill± All±h Mu¥ammad Rasµl All±h yang membentuk pola arabesq dan sedikit motif floral. Warna yang dominan adalah merah dan hitam (Gambar 09 dan 10; bandingkan dengan Gambar 10a).
2). Tipe Sulawesi Tipe Sulawesi ditemukan pada mushaf dari Pegayaman, milik
Bapak I Wayan Ma’ruf. Mushaf ini sudah tidak lengkap lagi dan sebagian besar sudah dimakan serangga. Akan tetapi, dari iluminasi yang masih bisa dilihat pada bagian awal dan bagian tengah, desain-nya sama dengan desain yang umumnya ditemukan di Sulawesi, yakni dua bingkai yang diletakkan secara berhadapan dengan ciri khas garis-garis tegak. Iluminasi hiasan mushaf dari Sulawesi yang menurut Gallop (2005) “Sulawesi Diaspora”, bercirikan bentuk-bentuk geometris yang kuat, yakni garis-garis vertikal, horizontal dan diagonal, dan tidak memiliki garis-garis lengkung bergelom-bang. Dua buah garis vertikal di kiri-kanan paling luar, dua bidang empat persegi panjang yang mengapit teks ayat, dua bidang persegi panjang di atas membingkai kepala surah dan di bawah mem-bingkai keterangan surah, dan keduanya mengapit teks ayat di atas dan di bawah, segitiga di tengah bagian pinggir menghadap keluar, dan beberapa bentuk setengah lingkaran di atas, bawah, dan pinggir luar bingkai. Sedikit berbeda, bahwa di bagian luar bingkai pada mushaf Pegayaman ini, bukan segi tiga tetapi lengkungan-lengkungan yang membentuk semi segitiga yang di dalamnya dihiasai desain floral dengan pewarnaan merah, hitam, dan kuning, di samping putih yang merupakan warna dasar kertas. Di bagian akhir mushaf, masih terdapat surah Al-Fatihah yang diletakkan dalam bingkai berhias melengkapi sepasang hiasan akhir mushaf (Gambar 11; Gambar 12, bandingkan dengan Gambar 12a).
3). Tipe Pantai Timur Semenanjung Malaya Ciri khas iluminasi mushaf dari Pantai Timur Semenanjung
Malaya adalah “Lengkungan luar bingkai berhias sering ditutup dengan rangkaian ‘ombak-ombak’ atau ‘dedaunan’ kecil”, misalnya dari Pattani dan Trengganu (Gallop, 2004:130). Iluminasi mushaf dari Pattani bercirikan, “lengkungan pada bingkai berhias kadang-
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
76
kadang terdiri dari dua ombak yang saling berpautan yang ditutup dengan semacam kubah”. Sementara Trengganu lebih bercirikan pembatas beriluminasi yang memenuhi tepi luar kertas. “Dari pem-batas luar ini banyak garis atau sulur kecil mengarah ke dalam seakan-akan bertemu dengan ‘ombak-ombak’ yang muncul dari lengkungan, menimbulkan efek ‘stalagnit-stalaktit’. Ketika garis-garis dan ombak disepuh, secara keseluruhan efeknya adalah pancaran emas yang cemerlang. Pewarnaan hiasan bingkai Pantai Timur lebih luas daripada yang ditemukan di Aceh, meliputi warna-warna muda seperti biru dan hijau maupun warna-warna tua yang lebih menggetarkan, dan emas sering digunakan” (Gallop, 2004:130).
Pola hiasan pada Al-Qur’an kuno dari Masjid Al-Muhajirin Kepaon Denpasar32 memperlihatkan tipe Pantai Timur Semenanjung Malaya. Dua buah bingkai diletakkan secara berhadapan di halaman kiri-kanan, dan bingkai kedua halaman tersebut disatukan dalam bingkai luar. Lengkungan-lengkungan dan riak-riak gelombang ter-gambar dengan jelas dalam mushaf ini, yakni di atas-bawah dan pinggir bingkai teks ayat. Bingkai teks ayat berupa empat persegi panjang agak lebar mengelilingi bidang teks dan diisi dengan hiasan bermotif daun dan dipadukan dengan lengkungan setengah ling-karan. Pewarnaannya terdiri atas merah, merah muda, hijau, hitam, dan kuning emas, di samping warna putih yang merupakan warna dasar kertas (Gambar 13, bandingkan dengan Gambar 13a).
4). Tipe Jawa dan Mushaf Tertua Ketiga di Nusantara: Tahun
1035 H/1625 M Mushaf lain yang menarik, unik, dan luar biasa adalah mushaf
yang ditemukan di Kampung Jawa Singaraja milik M. Zen
32 Naskah ini berukuran 30 X 19 cm, ukuran teksnya 19, 5 X 11, 5 cm. Bingkai
teks berupa tiga buah garis tipis berwarna hitam dan merah. Penomoran halaman tidak ada. Di beberapa halaman verso terdapat kata alihan. Sampul naskah sudah tidak ada. Alas naskah yang digunakan adalah kertas Eropa. Dalam kertas ini terlihat adanya garis bayang tebal dan garis tipis. Jarak garis tebal pertama sampai ke-6 13 cm. Jumlah garis tipis dalam 1 cm 9 buah. Selain itu, dalam kertas terdapat angka 1825. Teks ditulis dengan menggunakan khat Naskhi. Tinta yang digunakan berwarna hitam. Teks ditulis dengan menggunakan garis panduan yang ditekan. Secara umum, naskah sudah lapuk dan tidak lengkap. Teks yang masih ada dimulai bagian tengah surat al-Baqarah dan berakhir pada surah al-Naba, awal Juz ke-30 (juz ‘amma)
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
77
Usman. 33 Dikatakan demikian karena beberapa alasan: Pertama, mushaf ini ditulis di atas dluang. Alas tulis dari bahan dasar kulit kayu ini pada umumnya tergolong tua karena kertas ini umumnya telah ada sebelum kertas Eropa masuk ke Nusantara. Kedua, naskah ini memiliki kolofon yang menunjukkan waktu penyalinannya pada Kamis, 21 Muharram 1035 H (23 Oktober 1625 M), sebuah masa yang tua, oleh Abd al-Sufi al-Din, dan kolofonnya dalam bahasa Arab, yang berbunyi: “tamma al-qur’±n f³ yaum al-kh±mis min syahr al-mu¥arram f³ hil±li i¥d± wa ‘isyr³na ba‘da alfi sanah khamsin wa £al±£µna al-hijrah an-nabawiyyah “. Ketiga, dari segi kaligrafinya, mushaf ini memperlihatkan goresan seorang khattat (ahli kaligrafi) Arab dengan khat Naskhi yang indah walaupun tidak dengan kalam khat yang tipis-tebal, dan untuk kepala surah masih berupa Sulus sederhana. Keempat, iluminasinya memperli-hatkan unsur Jawa, jika merujuk identifikasi Gallop (2004), tetapi lengkungan-lengkungan yang mengelilingi teks ayat lazim ditemukan di Turki Usmani.
Iluminasi pada mushaf ini terdapat pada bagian awal yang membingkai Surah al-Fatihah dan awal Surah al-Baqarah. Desain hiasan ini menunjukkan salah satu karakter khas Jawa, yakni pada pewarnaan yang cenderung menggunakan warna biru (Gallop, 2004: 130). Bidang teks ayat diapit di kiri-kanan oleh blok empat persegi panjang yang dihiasi dengan pola arabesq, dan di atas-bawahnya diapit juga oleh blok empat persegi panjang; blok atas membingkai nama surah Al-Fatihah, dan blok bawah mengbingkai keterangan surah. Sementara itu, di tiga sisinya, atas-bawah dan pinggir, terdapat segi tiga yang juga berhiaskan bentuk arabesq. Selanjutnya, kedua bingkai yang berhadapan pada dua halaman kiri-kanan ini disatukan oleh bingkai garis yang memotong setiap ujung segitiga pada setiap sisinya. Bagian dalam bingkai ini pun
33 Secara umum, mushaf ini masih baik; hanya beberapa halaman yang tampak
lapuk. Mushaf ini berukuran 24 X 16 cm, dan ukuran teksnya adalah 16 X 11 cm. bingkai teks berupa tiga buah garis berwarna hitam. Tebal naskah 769 halaman yang terdiri atas 754 halaman isi. Sampulnya terbuat dari kulit berwarna coklat motif floral. Tulisan rapi dan jelas. Teks ditulis dengan menggunakan khat Naskhi. Jumlah baris setiap halaman 13, kecuali halaman awal yang terdiri atas 7 baris dan halaman akhir yang terdiri atas 10 baris. Tinta yang digunakan berwarna hitam. Untuk bagian yang berisi keterangan awal surah tinta dan awal juz digunakan berwarna merah.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
78
diberi hiasan berbentuk arabesq yang dipadukan dengan pola dedaunan (Gambar 14, bandingkan dengan Gambar 14a).
Pemiliknya tidak mengetahui secara pasti asal usul mushaf ini kecuali bahwa ia mendapatkannya dari orang tuanya dan konon telah dimilikinya secara turun temurun. Namun demikian, kebera-daan mushaf ini di sebuah tempat yang disebut Kampung Jawa, bisa diduga bahwa asal-usulnya berkaitan dengan Pulau Jawa, terutama dari beberapa unsur yang terdapat pada pola hiasannya. Lebih dari itu, mushaf ini menambah koleksi dan informasi mushaf tertua di Nusantara, yakni ditulis pada Kamis, 21 Muharram 1035 H/1625 M (Gambar 15). Setidaknya mushaf ini menjadi mushaf tertua ketiga setelah Mushaf kode MS 12716 di University of London yang ditulis Jumadil Awwal 993/1585 dan mushaf dari Ternate yang ditulis pada 7 Zulqa’dah 1005 H/1597 M (Bafadal dan Anwar, 2005: vii-viii).
Penutup 1. Kesimpulan
a. Penelusuran awal naskah-naskah keagamaan Islam di Bali berhasil menemukan 38 naskah yang tersebar di berbagai daerah di pulau Dewata ini. Dari 38 naskah tersebut, 35 di antaranya merupakan naskah keagamaan Islam. Walaupun jumlahnya tidak begitu signifikan dibandingkan dengan nas-kah non keislaman yang biasanya ditulis di atas lontar, keber-adaan 35 naskah keislaman itu dapat menunjukkan mata rantai Islamisasi di Indonesia dan jaringan keilmuan dan keulamaan Islam Nusantara, misalnya tentang nama tokoh al-Haj Muhammad Amin al-Din Palimbangi dan Muhammad Sa’id bin Muhammad Ali Kusamba, atau tempat, seperti Palembang dan Pasuruan, serta iluminasi mushaf yang memperlihatkan empat tipe Aceh, Sulawesi, Pantai Timur Malaya, dan Jawa.
b. 1) Kondisi naskah keagamaan Islam di Bali pada umumnya sangat memprihatinkan, tidak terawat dan kurang men-dapat perhatian. Sebagian besar naskah sudah rusak, dan bahkan tidak utuh lagi.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
79
2. Dari aspek kodikologi, dapat dicatat beberapa hal: a) bahan yang digunakan beragam, yaitu dluang, kertas Eropa, kertas bergaris modern, dan lontar; b) Bahasa dan aksara yang digunakan meliputi Arab, Melayu (Jawi), Bugis, dan Bali; c) Waktu penyalinan antara abad ke-17–19 M, dan yang tertua tahun 1035 H/1625 M; 4) Isi naskah antara lain mencakup fikih, tasawuf, tauhid, doa, wirid, dan obat-obatan, bahasa (nahwu-saraf), Al-Qur’an, dan geguritan (cerita).
2. Rekomendasi
a. Kondisi naskah keagamaan Islam di Bali yang mempriha-tikan perlu mendapatkan perhatian serius dan perlu segera dilakukan upaya konservasi lebih lanjut, antara lain dengan penelusuran naskah dan digitalisasi.
b. Keberadaan naskah keagamaan Islam di Bali yang tersebar di berbagai kabupaten memungkinkan masih ada naskah-naskah lain yang belum tersentuh sehingga penelusuran lebih lanjut perlu segera dilakukan.
c. Analisis terhadap isi teks dan penjelasannya secara konteks-tual perlu diteliti lebih lanjut, setidaknya untuk melihat bagaimana hubungan Islam-Hindu di Bali, dan bagaimana posisi Bali dalam proses Islamisasi maupun dalam jaringan transmisi keilmuan dalam Dunia Islam.Lebih dari itu, adanya naskah lontar yang mengandung unsur keislaman membuktikan bahwa hubungan antarumat beragama, khu-susnya Islam-Hindu di Bali terjalin dengan baik, dan untuk itu perlu pembuktian melalui penelitian secara lebih mendalam. Wa All±h a‘lam…[]
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
80
Daftar Pustaka
Agastia, Ada Bagus Gede. tanpa tahun. “Jenis-jenis ‘Naskah Bali’” dalam Soedarsono (Ed), Keadaan dan Perkembangan Bahasa, Sastra, Etika, Tatakrama, dan Seni Pertunjukan Jawa, Bali, dan Sunda. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Bafadal, Fadhal AR, dan Anwar, Rosehan. 2005. Mushaf-Mushaf Kuno di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.
Bafadal, Fadhal AR, dan Saefullah, Asep (Eds.). 2005. Naskah Klasik Keagamaan Nusantara 1. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan.
Chambert-Loir, Henri & Fathurahman, Oman. 1999. Khazanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Sedunia. Jakarta: Ecole francaise d’Extreme-Orient-Yayasan Obor Indonesia
Deroche, Francois. 2006. Islamic Codicology, An Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script. London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation. Edisi bahasa Arab diteritkan tahun 2005 oleh penerbit yang sama dengan judul al-Madkhal ila ‘Ilm al-Kitab al-Makhtut bi al-Harf al-‘Arabi, diterjemahkan ke Bahasa Arab oleh Ayman Fuad Sayyid.
Fathurahman, Oman. 2003. “Pentingnya Memelihara, Melestarikan, dan Memanfaatkan Khazanah Naskah Islam: Sebuah Refleksi”, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 1, No. 1. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan. h. 1-10.
Gallop, Annabel Teh. 2004. “Seni Mushaf di Asia Tenggara”, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 2, No. 2. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan. h. 121-143.
Gallop, Annabel Teh. 2005. “Islamic Manuscript art of Southeast Asia”, dalam James Bennett (Ed.), Crescent Moon: Islamic Art & Civilisation in Southeast Asia, Adelaide: Art Gallery of South Australia. h. 156-183.
Heawood, Edward. 1986. Watermarks: Mainly of the 17th and 18th Centuries. Hilversum: The Paper Publications Society. Cet. V.
Mulyadi, Sri Wulan Rujiati. 1994. Kodikologi Melayu di Indonesia. Depok: Fakultas Sastra UI.
Kumar, Ann dan McGlynn, John H. 1996. Illuminations, The Writing Traditions of Indonesia. The Lontar Foundation, Jakarta, Weatherhill Inc., New York dan Tokyo.
Rukmi, Maria Indra. 1997. Penyalinan Naskah Melayu di Jakarta pada Abad XIX: Naskah Algemeene Secretarie Kajian dari Segi Kodikologi, Depok: Fakultas Sastra UI.
Rukmi, Maria Indra. 2005. “Penyalinan Naskah Melayu di Palembang”, makalah dalam Seminar Tradisi Naskah, Lisan dan Sejarah di FIB UI , Depok.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
81
Saefullah, Asep. 2007. “Ragam Hiasan Mushaf Kuno Koleksi Bayt al-Qur’an dan Museum Istiqlal Jakarta”, dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 5, No. 1. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan. h. 39-62.
Sirojuddin AR. 1992. Seni Kaligrafi Islam. Jakarta: Multi Kreasi Singgasana.
Yunardi, E. Badri. 2007. “Beberapa Mushaf Kuno dari Provinsi Bali”, Jurnal Lektur Kegamaan, Vol. 5, No. 1. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan. h. 1-18.
Informan:
1. Ketut Ariawan, SH, Kasubag Umum, Kanwil Dep. Agama Prov. Bali 2. Drs. Ida Bagus Nyana, Staf Urusan Agama Hindu, Kanwil Dep. Agama
Prov. Bali 3. Drs. H. Musta’in, Kabid Bimas Islam & P. Haji, Kanwil Dep. Agama Prov.
Bali 4. Drs. H. M. Soleh, Kabid. Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Masjid,
Kanwil Dep. Agama Prov. Bali 5. Drs. H. Ghufron, Kasi. Penamas, Kanwil Dep. Agama Prov. Bali (No. 1-5) Wawancara di ruang kerja masing-masing pada 28 Oktober 2008. 6. H. Husen Abdul Jabbar, Wawancara pada 2 Nopember 2008 di Loloan
Timur. 7. Drs. H. Muchlis Sanusi, Lurah Kampung Bugis dan juga Ketua Ta’mir
Masjid Agung Singaraja, 8. H. Abdurrahman Alawi, Ketua Dewan Penasehat MUI Singaraja. 9. H. Abdurrahman Said, Ketua MUI Singaraja 10. H. Hasyim Zaki, Pengurus Harian Masjid Agung Jami’ Singaraja 11. H. Hidayat, Sekretaris MUI Sngaraja (No. 7-11) Wawancara, secara terpisah pada 29-30 Desember 2008 di
Masjid Agung Singaraja maupun di kantor MUI Singaraja. 12. Hadiman, Syafruddin, Gunawan, dan Agus, para ustadz di Pesantren Al-
Hidayah, Bedugul, Wawancara, 29 Oktober 2008. 13. Abdullah, yang dituakan di Kampung Islam Buitan, Karang Asem,
Wawancara, 2 Nopember 2008. 14. H. Hasan, penduduk Singaraja yang bekerja di Denpasar, Wawancara, 30
Oktober 2008.
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
82
Lampiran:
1. Contoh Deskripsi Naskah Milik Musthafa al-Amin, Denpasar
Fk/Bali Kitab Nikah, Obat-obatan, Wirid dan Doa
MA 01 Bhs. Arab dan Melayu Aks. Arab dan Jawi Prosa 98 hlm. 19 baris/hlm. 24x16 cm Kertas Eropa
Naskah ini merupakan kumpulan teks yang terdiri atas beberapa bidang
kajian. Tebal naskah 98 halaman (49 lembar) dengan jumlah baris 19 per halaman. Jarak antarbaris di setiap halaman 7 mm. Naskah berukuran 24 X 16 cm, sementara ukuran teksnya adalah 19 X 11 cm. Naskah sudah tidak bersampul dan bagian awal teks yang berisi Kitab Nikah sudah tidak lengkap. Sepertinya bagian awal teks dimulai dari “Had al-Qa©af”, yakni pembahasan tentang tuduhan suami bahwa istrinya berzina. Adapun bunyi kalimat pertama (1r) adalah sebagai berikut:
Terpelihara dirinya daripada had ta-waw-kaf-sin karena jikalau ia tia(da) mau bersumpah maka dipukul ia delapan puluh kali demikian lagi disuruh bersumpah istrinya di atas mimbar lima kali supaya terpelihara ia daripada had zina maka apabila sudah bersumpah keduanya jatuhlah talaknya itu talak bain kubra …
Alas naskah yang digunakan adalah kertas Eropa. Akan tetapi cap kertas hanya terlihat sebagian. Setelah dicocokkan dengan daftar cap kertas yang disusun oleh Heawood (1986), tampaknya cap kertas ini mirip dengan contoh no. 860, yang termasuk kelompok Crescent. Menurut Heawood (1986: 84), kertas dengan cap kertas nomor tersebut tidak bertanggal, namun dimungkinkan diproduksi pada masa modern.
Teks ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu dan aksara Jawi dengan menggunakan garis panduan yang ditekan. Tinta yang digunakan berwarna hitam, sementara rubrikasi berwarna merah.
Sebagaimana disebutkan, naskah ini merupakan kumpulan teks, yang terdiri atas: 1. Halaman 1r-33v: Teks kitab nikah; dalam kolofon teks ini disebutkan “Kitab
Nikah”. Bunyi kolofon tersebut sebagai berikut: Haza [al-]Kitab al-Nikah [ter] Hijrah al-Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam seribu
dua ratus delapan puluh tujuh (1287) pada tahun Ba alif(?) pada malam ahad waktu jim(?) pada pukul delapan pada delapan hari bulan Rabi’ al-Awwal pada ketika itulah hamba Pa Abdul A’raf sudah selesai menyuruh ini kitab di dalam negeri Badung Bali Badung adanya Kampung Kepaon 1287.
Tamma wa sallallahu ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2. Halaman 33v-41v: Teks obat-obatan, tetapi tidak disebutkan judulnya. Kalimat pertama teks ini berbunyi:
Sebagai lagi (obat) supaya bincar(?) buang air seni ambil limau nipis tiga biji ditaruh gula batu maka embunkan pagi2 minum insya Allah ‘afiyah berturut-turut tiga pagi.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
83
Kalimat terakhir berbunyi: Telah mengambil ijazah faqir a-haqir ila Allah Ta’ala Haji Hasan ibn al-Marhum
al-Haj Muhammad Amin al-Din Palembangi akan mengamalkan laqad ja’akum serta doa yang kemudian kepada Syaikhuna wa ustazuna wa wasilatuna ila Allah Ta’ala al-Arif bi Allah sayyidi al-Syaikh Muhammad Azhari ibn al-Mukarram al-Marhum Kemas Muhammad Haji Abdullah Palimbangi Nafa’ana Allah bi barakatihi wa barakat ‘ulumihi. Amin 1288 H di Ampenan Syahr [al-]Shafar.
3. Halaman 41v-47r: Teks berisi berbagai macam masalah, antara lain kitab waris, wirid dan doa, penanggalan, dan teks khutbah nikah.
4. Halaman 47v-48v: Teks Li °³bat Aqli al-Ins±n.
Pemilik Naskah: H. Musthofa Amin, Kampung Bugis, Kepaon, Denpasar, Bali. 2. Contoh Deskripsi Naskah Lontar Milik Yayasan An-Nur, Denpasar
Gg/Bali Pepalihan Gama Selam Bali
YN 02 Bhs. Bali Aks. Bali Puisi 9 lempir 4 baris/lempir 40,5 x 3,5 cm Lontar
Berdasarkan informasi di luar teks, naskah ini berjudul Pepalihan Gama
Selam Bali. Tebal naskah 9 lempir dengan jumlah baris 4 per lempir. Jarak antarbaris tiap lempir adalah 0,5 cm. Naskah berukuran 40,5 X 3,5 cm, sedangkan ukuran teksnya adalah 34 X 2, 5 cm. Pias kanan berukuran 3 cm, pias kiri berukuran 3 cm. Naskah di tempatkan dalam kotak yang terbuat dari kayu jati berwarna coklat. Ukuran kotak tempat menyimpan naskah ini adalah 46 X 8,5 cm.
Teks ditulis di atas lontar dengan menggunakan bahasa dan aksara Bali. Tinta yang digunakan berwarna hitam. Di bawah setiap baris teks terdapat garis panduan tipis berwarna hitam. Teks dibagi dalam dua kolom. Kondisi lontar masih baik. Tulisan tampak rapi dan jelas. Teks ini berisi cerita proses islamisasi di Bali.
Pemilik naskah: Yayasan An-Nur, Denpasar
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
84
Lampiran II: Gambar-Gambar A. Beberapa Jenis Kaligrafi B. Ilustrasi
Gambar 01: Khat Naskhi pada Mushaf kuno dari Kampung Jawa, Singaraja
Gambar 02: Khat Naskhi pada naskah tauhid dari Pegayaman Singaraja, milik Drs. Suharto
Gambar 03: Khat Riq’ah pada MS MA 06, milik H. Musthafa Amin, Kepaon,
Denpasar
Gambar 04: Khat Farisi MS MA 01, koleksi H. Musthafa Amin, Kepaon,
Denpasar
Gambar 05: MS MA 03, h. 11r. naskah koleksi H. Musthafa Amin,
Kepaon, Denpasar
Gambar 06: MS MA 04, h. 17v. naskah koleksi H. Musthafa Amin,
Kepaon, Denpasar
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
85
C. Iluminasi pada Mushaf
Gambar 07: MS Serangan 01, h. 56, milik H. Baharuddin,
Kp. Serangan, Denpasar.
Gambar 08: MS MA 03, h. 12v-13r. naskah milik
H. Musthafa Amin, Kepaon, Denpasar
Gambar 09: MS MAJS/NQ/01. Iluminasi halaman awal pada Mushaf Kuno
koleksi Masjid Jami’ Agung Singaraja
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
86
Gambar 10: MS MAJS/NQ/01. Iluminasi halaman tengah pada Mushaf Kuno
koleksi Masjid Jami’ Agung Singaraja
Gambar 10a: Tipe Iluminasi mushaf halaman tengah dari Aceh., koleksi Perpustakaan Nasional
Jakarta, dalam Ann Kumar dan John H. McGlynn, Illuminations, 1996, h 46 dan 87.
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
87
Gambar 11: Iluminasi bagian akhir pada mushaf kuno dari
Pegayaman, milik I Wayan Ma’ruf; pada di halaman kiri terdapat surah Al-Fatihah.
Gambar 12: Iluminasi bagian awal pada
mushaf kuno dari Pegayaman, milik I Wayan Ma’ruf.
Tampak tidak utuh lagi kerena dimakan serangga.
Gambar 12a:
Tipe Iluminasi halaman tengah tipe Sulawesi juga terdapat pada Tafsir Al-Qur’an, sepertinya Tafsir Jalalain. Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta,
dalam Ann Kumar dan John H. McGlynn, Illuminations, 1996, h. 59
Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7, No. 1, 2009: 53 - 90
88
Gambar 13: Iluminasi bagian tengah pada mushaf kuno dari Masjid Al-Muhajirin, Kepaon, Denpasar.
Gambar 13a:
Tipe Iluminasi mushaf seperti ini umum ditemukan di Pantai Timur Semenanjung Malaya, tetapi Al-Qur’an ini berasal dari Cirebon; Iluminasi ini terdapat pada again awal surah al-
Fatihah dan awal al-Baqarah. Al-Qur’an kuno koleksi Museum Sri Baduga, Bandung, Jawa Barat, dalam Ann Kumar dan John H. McGlynn, Illuminations, 1996, h. 114
Beberapa Aspek Kodikologi Naskah ... — Asep Saefullah dan Adib M. Islam
89
Gambar 14: Iluminasi bagian awal pada mushaf kuno dari Kp. Jawa Singaraja, milik H. Zen Usman.
Gambar 14a: Tipe Iluminasi mushaf halaman tengah dari Jawa. Mushaf disalin di Surakarta pada
1797-1798 M oleh Ki Atmaparwita, koleksi Widya Budaya, Kraton Yogyakarta, dalam Ann Kumar dan John H. McGlynn, Illuminations, 1996, h. 35