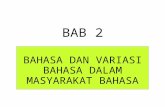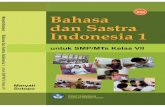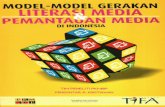LITERASI MEDIA DALAM BAHASA DAN SASTRA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LITERASI MEDIA DALAM BAHASA DAN SASTRA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA Lingkup Hak Cipta
Pasal 1 Ayat 1 :1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembat-asan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pidana:Pasal 113
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cip-ta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 114Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dip-idana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
LITERASI MEDIA DALAM BAHASA DAN SASTRA
Penulis : Dr. Nurmalina, M.Pd.Penyelaras Aksara : NurrahmawatiTata Letak : Ridwan Nur MDesain Cover : Bintang W Putra
Penerbit: Bintang Pustaka Madani (CV. Bintang Surya Madani) Jl. Wonosari Km 8.5, Dukuh Gandu Rt. 05, Rw. 08 Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773 Telp: 4358369. Hp: 085865342317 Email: [email protected] Facebook: Penerbit Bintang Madani Instagram: @bintangpustaka Website: www.bintangpustaka.com www.pustakabintangmadani.com
Cetakan Pertama, November 2020Bintang Pustaka Madani Yogyakarta ix + 86 hal : 15.5 x 23 cm ISBN :
Dicetak Oleh: Percetakan Bintang 085865342319
Hak cipta dilindungi undang-undang All right reserved Isi di luar tanggung jawab percetakan
v
KATA PENGANTAR
Literasi mempunyai posisi strategis di sekolah. Membaca-berpikir-menulis yang merupakan inti literasi sangat diperlukan peserta didik untuk menyelesaikan studi, melanjutkan studi, mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan, dan belajar sepanjang hayat di tengah masyarakat. Melalui pembelajaran berbasis literasi media diharapkan seseorang dapat menguasai ber bagai teknologi informasi, mendorong kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan kreatif, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomuni kasikan pesan dalam berbagai bentuk medium, terutama dalam meningkatkan kemampuan berbahasa dan bersastra .
Dengan dijadikannya literasi sebagai basis pengembangan kegiatan pembelajaran, berarti bahan ajar yang dirancang guru bertumpu pada konten-konten informasi yang telah diakses. Peran guru dalam menggunakan bahan ajar yang tepat akan menentukan tercapainya kompetensi dasar dan hasil belajar siswa dalam semua jenis pembelajaran khusunya pembelajaran Bahasa Indonesia.
Buku Menulis Buku Ajar dari Literasi Media dimaksudkan sebagai bahan panduan dalam penulisan buku mata pelajaran Bahasa
vi Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Indonesia di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan andil dan menjadi bagian dari Gerakan Literasi Media di Indonesia.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang turut membantu dalam penyelesaian buku ini. Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya.
Riau, November 202
Penulis
viiLiterasi Media dalam Bahasa dan Sastra
KATA PENGANTAR ....................................................................... vDAFTAR ISI ....................................................................................... viiBAB ILITERASI DALAM PEMBELAJARAN ........................................ 1
A. Pentingnya Literasi ................................................................... 1B. Literasi dalam Dunia Pendidikan .......................................... 3C. Peningkatan Keterampilan Bahasa Indonesia
di Sekolah Melalui Literasi ..................................................... 5BAB IIDASAR PENGEMBANGAN BAHAN AJAR .............................. 9
A. Pengertian Bahan Ajar ............................................................. 9B. Jenis-jenis Bahan Ajar .............................................................. 11C. Tujuan dan Manfaat Bahan Ajar ............................................ 16D. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar ....................................... 19E. Prosedur Pengembangan Bahan Ajar.................................... 23
1. Analisis Kurikulum ........................................................... 262. Identifikasi Materi ............................................................. 273. Memilih Sumber Bahan Ajar............................................ 28
BAB IIILITERASI MEDIA ............................................................................ 31
A. Konsep Literasi ....................................................................... 31B. Literasi Media ........................................................................... 33
DAFTAR ISI
viii Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
BAB IVTEORI PROSES PEMBELAJARAN ............................................. 39
A. Teori Belajar ............................................................................... 39B. Teori Mengajar .......................................................................... 41C. Proses Pembelajaran ................................................................. 42
BAB VPELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS LITERASI . 45
A. Pelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 13 ............... 45B. Konsep dan Manfaat Buku Ajar ............................................ 47C. Buku Ajar Berbasis Cetak ........................................................ 48D. Variabel Pemeriksaan dan Penyempurnaan Buku E. Ajar Bahasa Indonesia .............................................................. 51
BAB VITAHAPAN PENGEMBANGAN BUKU AJAR BAHASA INDONESIA ........................................... 53
A. Desain Pengembangan ............................................................. 53B. Uji Coba Produk ........................................................................ 58C. Subjek Uji Coba ......................................................................... 59D. Jenis Data ................................................................................... 60E. Instrumen Pengumpulan Data ............................................... 62F. Teknik Analisis Data ............................................................... 63
BAB VIIIMPLEMENTASI PRODUK R&D ................................................ 67
A. Bahan Ajar Teks Cerpen Berbasis Literasi Media ................ 67B. Pemanfaatan Media Sosial untuk Bahan Ajar ...................... 70C. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2o13 ... 74
DAFTAR RUJUKAN ........................................................................ 77BLURB ................................................................................................. 85Biodata Penulis .................................................................................. 86
1
LITERASI DALAM PEMBELAJARAN
A. Pentingnya Literasi
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menentukan posisi suatu negara dalam bidang pendidikan, peringkat literasi negara Indonesia sangat memprihatinkan. Peringkat tersebut menentukan negara yang terbaik dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2015, Indonesia berada pada urutan ke 57 dari total 65 negara. Dengan hasil survei PISA ini menegaskan bahwa dengan peringkat pendidikan yang berada pada papan bawah, tentunya mendukung rendahnya kemampuan literasi masyarakat Indonesia, karena literasi salah satunya berhubungan dengan kemampuan membaca.
BAB I
2 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Berkaitan dengan literasi, konsep pendidikan harus mempersiapkan masyarakat untuk bisa hidup dalam dunia sesak-media. Literasi merupakan upaya pembelajaran bagi khalayak media sehingga menjadi khalayak yang berdaya hidup di tengah dunia yang disebut dunia sesak-media (media-saturated) (Iriantara, 2006: 59). Kemudahan mengakses informasi tak akan banyak artinya bila kemudian tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Persiapan itu diperlukan karena media komunikasi dan informasi bukan hanya melaporkan apa yang terjadi melainkan juga mempengaruhi khalayaknya.
Akibat dari perkembangan media komunikasi, masyarakat Indonesia mesti berhadapan dengan kondisi-kondisi baru, sejalan dengan kebebasan berkomunikasi yang dijalankan saat ini. Cayari (2011) menyatakan bahwa beragamnya media sosial yang muncul dan menjadi tren terbaru bagi masyarakat menghendaki penggunanya untuk memiliki kontrol diri dalam pemakaiannya. Banyak orang yang khawatir akan informasi yang disampaikan melalui media komunikasi, sehingga banyak muncul keluhan dari berbagai pihak, yang diperlukan kini adalah penguatan pada orang-orang yang mengkonsumsi informasi tersebut melalui sebuah upaya memahami informasi yang lebih baik yaitu melalui literasi.
Literasi yang rendah mengakibatkan rendahnya pemahaman (Geske & Ozola, 2008), sebaliknya kemampuan literasi yang tinggi menyebabkan tingginya kemampuan pemahaman seseorang (Iswari, 2015). Hal ini sesuai dalam ajaran agama Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran. Dalam Qs. Al-Isra’ ayat 36, Allah SWT berfirman:
“Wa laa taqfu maa laisa laka bihi ‘ilmun innassam’a walbashoro walfuaada kullu uulaaaika kaana ‘anhu masulaa”.
3Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”
B. Literasi dalam Dunia Pendidikan
Kebutuhan literasi di era global ini menuntut pemerintah untuk memfasilitasi sistem dan pelayanan pendidikan. Program literasi mencakup upaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang meliputi kecerdasan intelektual, emosi, bahasa, estetika, sosial,spiritual, dengan daya adaptasi terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi (Kemendikbud, 2016a). Untuk mendukung kemajuan literasi masyarakat Indonesia, Kemdikbud mencanangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang pelaksanaannya meliputi tiga tahapan, yakni pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015). Tahap pembelajaran dilakukan dengan strategi meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran diantaranya menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Gerakan ini didukung dengan pencanangan kurikulum 2013 revisi tahun 2016 yang salah satu kerangka pengembangannya menekankan pada kompetensi literasi dan kemampuan belajar serta berinovasi (Kemendikbud, 2016b).
Kurikulum 2013 mendukung kegiatan literasi yang tidak hanya berfokus pada peserta didik, melainkan mengakomodasi kemampuan dan peran guru dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengoptimalkan proses dan kompetensi literasinya. Beers mengungkapkan dalam buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (Kemendikbud, 2016a:11) bahwa salah satu prinsip literasi di sekolah adalah terintegrasinya program literasi dengan kurikulum.
Alwasilah (2004) menemukan bahwa dalam budaya Indonesia literasi belum diartikan sebagai “kemampuan untuk membaca dan menulis” tapi masih diartikan sebatas “kemampuan untuk membaca”.
4 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Selain itu, guru lebih banyak menghabiskan waktu yang telah mereka alokasikan untuk menerangkan grammar daripada mengajarkan keterampilan menulis itu sendiri. Alasan lain yang dia temukan adalah guru sering mengeluh dengan kelas besar yang mereka ajar. Hal ini menjadikan guru tak mungkin mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik secara efektif.
Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa literasi mempunyai posisi strategis di sekolah. Membaca-berpikir-menulis yang merupakan inti literasi sangat diperlukan peserta didik untuk menyelesaikan studi, melanjutkan studi, mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan, dan belajar sepanjang hayat di tengah masyarakat.
Menurut data dari hasil penelitian Weber Shandwick (2015),perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa komunikasi,untuk wilayah Indonesia ada sekitar65 juta pengguna facebook aktif. Sebanyak 33 juta pengguna aktif perharinya, 55 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan, dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile perharinya. Di Indonesia dinyatakan bahwa 61.1% pengguna internet khususnya facebook didominasi oleh para remaja usia 14-24 tahun. Oleh karena itu, sangat beralasan apabila konten-konten yang ada di media-media komunikasi dan informasi dijadikan basis dalam pengembangan pembelajaran setelah melewati proses literasi oleh guru.
Semisal ketika guru sedang memberikan materi pembelajaran siswa malah asyik bermain handphone, baik itu bermain game, berselancar di media sosialtanpa peduli apa yang disampaikan gurunya. Hal ini bisa ditepis apabila siswa benar-benar memanfaatkan handphonedalam hal positif terutama dalam pembelajaran maka akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar bisa memuaskan dari pihak siswa, guru, maupun sekolah itu sendiri.
5Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Dengan dijadikannya literasi sebagai basis pengembangan kegiatan pembelajaran, berarti bahan ajar yang dirancang guru bertumpu pada konten-konten informasi yang telah diakses, dianalisis, dievaluasi, dan dikomunikasikan yang biasanya disertai berbagai kegiatan lain, seperti berdiskusi, memecahkan masalah, mengembangkan proposal kegiatan, meneliti, dan melaporkannya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa bagi peserta didik.
C. Peningkatan Keterampilan Bahasa Indonesia di Sekolah Melalui Literasi
Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia dipelajari untuk menjadikan peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Selain itu, penguasaan berbahasa dengan baik dan benar akan membantu peserta didik dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan kurikulum 2013. Jadi, pemerintah berharap menjadikan bahasa sebagai wahana untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran secara estetis dan logis pada peserta didik.
Pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemampuan berbahasa dituntut mampu menjadi pembelajaran berkelanjutan karena bahasa Indonesia menjadi ujung tombak mata pelajaran lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia dimulai dengan meningkatkan pengetahuan tentang jenis, kaidah dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan keterampilan menyajikan suatu teks tulis dan lisan.
6 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Tidak hanya dari aspek pengajar, ketidaktercapaian kompetensi menulis cerpen dan teks cerita ulang dalam pelajaran bahasa Indonesia di SMA juga disebabkan pula dari aspek peserta didiknya. Peserta didik di SMA kurang tertarik untuk berhasil atau untuk bisa menulis cerpen dan cerita ulang. Padahal keterampilan-keterampilan ini bermanfaat untuk perkembangan sosial peserta didik. Hal ini ditekankan oleh Mahsun (2014: 24), bahwa teks cerita ulang memiliki tujuan sosial menceritakan kembali tentang peristiwa pada masa lalu agar tercipta semacam hiburan atau pembelajaran dari pengalaman pada masa lalu bagi pembaca atau pendengar.
Cerpen menjadi salah satu materi dalam pengembangan model pembelajaran ini. Teguh, dkk (2014: 2) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran menulis teks cerita pendek menjadi sangat penting sebab dapat merangsang siswa menjadi gemar menulis dan tentunya akan meningkatkan kemampuan siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Selain itu, kegiatan menulis cerita pendek akan dapat menumbuhkembangkan kecintaan siswa pada sastra sehingga apresiasi siswa terhadap sastra akan meningkat.
“Since it is short, and aims at giving a ‘single effect’, there is usually one plot, a few characters; there is no detailed description of setting. So, it is easy for the students to follow the story line of the work. Therefore, it seems to be the most suitable one to help students enhance the four skills—listening, speaking, reading and writing” (Ceylan, 2016).
“Karena singkat, dan bertujuan memberi ‘efek tunggal’, biasanya ada satu plot, beberapa karakter; Tidak ada deskripsi pengaturan yang rinci. Jadi, mudah bagi para siswa untuk mengikuti alur ceritanya. Oleh karena itu, tampaknya yang paling sesuai untuk membantu siswa meningkatkan empat keterampilan-mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis” (Ceylan, 2016).
7Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Peran guru dalam menggunakan bahan ajar yang tepat akan menentukan tercapainya kompetensi dasar dan hasil belajar siswa dalam semua jenis pembelajaran khusunya pembelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahan ajar yang tepat akan memotivasi siswa untuk menciptakan pembelajaran Bahasa Indonesia yang menarik dan menyenangkan. Untuk itu, usaha mengembangkan bahan ajar yang layak untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas belajar siswa dipandang sebagai salah satu langkah awal yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya kebermaknaan.
9
Di dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa pendidik diharapkan mengembangkan materi pembelajaran. Pengaturan ini dipertegas melalui Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan pendidik untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu komponen RPP adalah materi ajar. Dengan demikian, pendidik harus mengembangkan materi ajar atau bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar.
A. Pengertian Bahan Ajar
Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian dalam pengembangan bahan ajar. Beberapa pakar telah memaparkan konsep-konsep mengenai bahan ajar tersebut. Salah satu pengertian
DASAR PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
BAB II
10 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
bahan ajar adalah menuru Tomlinson. bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan guru atau siswa untuk memudahkan belajar bahasa, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman berbahasa Tomlinson (1998:2).
Pendapat senada dipaparkan pula oleh Belawati (2003:13), yang menjelaskan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Secara resmi, Depdiknas (2006:4) mendefenisikan bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
Widodo dan Jasmadi (2008:40), menjelaskan kembali mengenai konsep bahan ajar. Menurut mereka bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam mencapai tujuan yang diharapkan, mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pada tahun yang sama, National Centre for Vicational Education Research Ltd/National Centre for Competency Based Training (dalam Majid, 2008:174) memaparkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis”.
Dengan konsep yang lebih rinci Prastowo (2012:173) memaparkan bahwa bahan ajar pada dasarnya merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Lebih lanjut Majid memaparkan konsep bahan ajar secara sederhana.
11Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Menurutnya bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. kemudian materi pembelajaran atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa pengetahuan, ketrampilan maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran agar dapat menjadi kompeten (Nasar, 2006:19).
Paparan lain menuliskan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran (Andi, 2011:16). Lebih lanjut, Ahmad (2012: 102) menjelaskan bahwa bahan ajar adalah materi yang akan diajarkan kepada peserta didik yang telah dipilih (diseleksi), atau bahan ajar adalah materi (pesan) yang harus dipelajari dan dipahami oleh peserta didik.
Dengan demikian bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Simpulan ini senada dengan beberapa pendapat pakar yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun, yang lebih sesuai adalah pendapat yang dikemukakan oleh Andi (2011:16).
B. Jenis-jenis Bahan Ajar
Berbagai pendapat pakar pun dipaparkan mengenai jenis-jenis bahan ajar ini. Salah satunya adalah jenis-jenis bahan ajar menurut Koesnandar. Jenis bahan ajar berdasarkan subjeknya terdiri dari dua jenis antara lain: (a) bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar, seperti buku, handouts, LKS dan modul; (b) bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya kliping, koran, film, iklan atau berita. Koesnandar juga menyatakan bahwa jika ditinjau dari fungsinya, maka bahan ajar yang dirancang terdiri atas tiga kelompok yaitu bahan presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri (Koesnandar, 2008: 81).
12 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Jika Koesnandar jenis bahan ajar berdasarkan dua hal, maka berdasarkan teknologi yang digunakan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (2008: 11) mengelompokkan bahan ajar menjadi empat kategori, yaitu bahan ajar cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan model/maket. Bahan ajar dengar (audio) antara lain kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, dan film. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web (web based learning material).
Pendapat berbeda dijelaskan oleh Mudlofir (2011: 149) bahwa bentuk bahan ajar paling tidak dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:
a. Bahan cetak, seperti; hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leafleft.
b. Audio visual seperti; video/film, VCD.c. Audio seperti; radio, kaset, CD audio, PH.d. Visual seperti; gambar, model/makete. Multimedia seperti; CD Interaktif, computer based, internet.
Selain pendapat-pendapat di atas, Majid (2012: 174) memaparkan pula bahwa ada beberapa jenis bahan ajar, yaitu: 1) Bahan cetak, seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, dan brosur; 2) Bahan ajar dengar, seperti kaset dan radion; 3) Bahan ajar pandang dengar, seperti video dan film; 4) Bahan ajar interaktif seperti CD Interaktif. Secara umum Lestari (2013: 7) membedakan empat jenis, bahan ajar, yaitu sebagai berikut.
1. Buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap.
2. Buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk
13Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya.
3. Buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran.
4. Buku bahan ajar, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan dijabarkan.
Berbeda lagi jenis bahan ajar menurut Prastowo (2013: 306-309) yang memaparkan bahwa bahan ajar dibagi berdasarkan bentuk, cara kerja, sifat, dan substansi (isi materi).
a. Menurut bentuk bahan ajar
Dari segi bentuknya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
1) Bahan ajar cetak (printed), yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contoh: handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto/gambar, model, atau market.
2) Bahan ajar dengar (audio) atau program audio, yaitu: semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh: kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio.
3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual), yaitu: segala sesuatu yang memungkinan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contoh: video, compact disk, dan film.
4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching materialsi), yaitu: kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan
14 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
suatu perintah dan atau perilaku alami dari presentasi. Contoh: compact disk interaktif.
b. Menurut Cara Kerja Bahan Ajar
Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:
1) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar ini adalah bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya. Sehingga, siswa bisa langsung memergunakan (membaca, melihat, mengamati bahan ajar tersebut). Contoh: foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya.
2) Bahan ajar yang diproyeksikan. Bahan ajar yang diproyeksikan adalah bahan ajar yang memerlukan proyektor agar bisa dimanfaatkan dan atau dipelajari siswa. Contoh: slide, filmstrips, overhead transparancies (OHP), dan proyeksi computer.
3) Bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam. Untuk menggunakannya, kita mesti memerlukan alat pemain (player) media perekam tersebut, seperti tape compo, CD, VCD, multimedia player, dan sebagainya. Contoh: kaset, CD, flash disk, dan sebagainya.
4) Bahan ajar video. Bahan ajar ini memerlukan alat pemutar yang biasanya berbentuk video tape player, VCD, DVD, dan sebagainya. Karena bahan ajar ini hampir dengan bahan ajar audio, jadi memerlukan media rekam. Namun, perbedaannya bahan ajar ini ada pada gambarnya. Jadi, secara bersamaan, dalam tampilan dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara. Contoh: video, film, dan lain sebagainya.
5) Bahan (media) Komputer. Bahan ajar computer adalah
15Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
berbagai jenis bahan ajar noncetak yang membutuhkan computer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Contoh: computer mediated instruction (CMI) dan computer based multimedia atau hypermedia.
c. Menurut Sifat Bahan Ajar
Jika dilihat dari sifatnya, maka bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:
1) Bahan ajar berbasiskan cetak. Yang termasuk dalam kategori bahan ajar ini adalah buku, pamphlet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah atau Koran, dan lain sebagainya.
2) Bahan ajar berbasiskan teknologi. Yang termasuk dalam kategori bahan ajar ini adalah audioassete, siaran radio, slide, filmstrips, film, video, siaran televisi, video interaktif, computer based tutorial, dan multimedia.
3) Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Contoh: kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya.
4) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia (terutama untuk keperluan pendidik jarak jauh). Contoh: telepon, handphone, video conferencing, dan lain sebagainya.
d. Menurut Substansi Materi Bahan Ajar
Secara garis besar, bahan ajar (instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Atau, dengan kata lain, materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi tiga jenis materi, yaitu materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
16 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Jenis-jenis bahan ajar menurut Daryanto dan Dwicahyono (2014: 173) seperti berikut ini.
1. Bahan ajar pandang (visual) terdiri atas bahan cetak (printed) seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, non cetak (non printed), seperti model/maket.
2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio.
3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film.
4. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI (computer assisted instruction), CD (compact disk) multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials).
Setelah paparan pendapat para pakar mengenai jenis-jenis bahan ajar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis bahan ajar sesuai dengan yang dijelaskan oleh Prastowo (2013: 306-309). Prastowo menjelaskan bahwa bahan ajar dibedakan atas beberapa klasifikasi, yaitu: menurut bentuk bahan ajar, menurut kerja bahan ajar, menurut sifat bahan ajar, dan menurut substansi bahan ajar. Dalam penelitian ini, bahan ajar yang akan dikembangkan adalah bahan ajar berdasarkan sifat bahan ajar tersebut. Salah satu jenis bahan ajar berdasarkan sifat bahan ajar adalah bahan ajar berbasis cetak.
C. Tujuan dan Manfaat Bahan Ajar
Bahan ajar tentunya memiliki tujuan-tujuan dan manfaat-manfaatnya. Tujuan dan manfaat tersebut pun dipaparkan dalam subjudul ini menurut beberapa pendapat ahli. Salah satu tujuan bahan ajar dikutip dari buku yang diterbitkan oleh Depdiknas (2008:10), bahwa tujuan penyusunan bahan ajar, yakni: (1) menyediakan bahan ajar
17Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah; (2) membantu siswa dalam memperoleh elternatif bahan ajar; dan (3) memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran”.
Pendapat lain mengenai tujuan bahan ajar adalah menurut Daryanto dan Dwicahyono (2014: 171-172) yang memaparkan bahwa tujuan bahan ajar adalah sebagai berikut ini.
1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yaitu bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik.
2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh.
3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Mulyasa (2006: 46-47) juga memaparkan bahwa ada beberapa keunggulan bahan ajar, sebagai berikut ini.
1. Berfokus pada kemampuan individual siswa, karena pada hakekatnya siswa memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.
2. Adanya kontrol terhadap hasil belajar mengenai penggunaan standar kompetensi dalam setiap bahan ajar yang harus dicapai oleh siswa.
3. Relenvasi kurikulum ditunjukan dengan adanya pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya.
Selain manfaat bagi guru ada juga manfaat bagi siswa, yaitu: (1) kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik; (2) siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru, dan (3) siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai.
18 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Secara garis besar bagi guru bahan ajar berfungsi untuk mengarahkan semua aktifitasnya dan siswa dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi yang seharusnya dijabarkan kepada siswa. Sedangkan bagi siswa adalah menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok.
1. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, sebagai berikut. a) Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas
dan pengendalian proses pembelajaran (dalam hal ini, siswa bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar).
b) Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan.
2. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, sebagai berikut. a) Sebagai media utama dalam proses pembelajaran. b) Sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan
mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi.
c) Sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya.
3. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, sebagai berikut. a) Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses
belajar kelompok, dengan cara memberikan informasi tentanglatar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya
19Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
sendiri. b) Sebagaibahan pendukung bahan ajar utama, dan apabila
dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa (Prastowo, 2011: 25-26).
Dengan demikian dapat dimunculkan postulat mengenai tujuan dan manfaat bahan ajar. Tujuan dan manfaat bahan ajar adalah bagi guru bahan ajar berfungsi untuk mengarahkan semua aktifitasnya dan siswa dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi yang seharusnya dijabarkan kepada siswa. Sedangkan bagi siswa adalah menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Prastowo.
D. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar
Untuk mengembangkan bahan ajar, tentunya harus diperhatikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Mulyasa (2006: 154) menjelaskan mengenai kriteria-kriteria dalam mengembangkan materi standar adalah :
a) Kesesuaian (Validity), berkaitan dengan tingkat kesesuaian dan keterujian materi dengan kompetensi.
b) Tingkat kepentingan (significance), berkaitan dengan tingkat kepentingan, dan kebermaknaan, serta sumbangan materi terhadap pencapaian suatu kompetensi, sehingga materi tersebut benar-benar penting untuk dipelajari, dan berhubungan langsung dengan pembentukan kompetensi
c) Kegunaan (utility), berkaitan dengan kegunaan, manfaat, atau faedah materi pembelajaran bagi peserta didik, baik secara akademis maupun non akademis.
20 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
d) Kemungkinannya untuk dipelajari (learnability), berkaitan dengan kemungkinan materi tersebut untuk dipelajari, baik berkaitan dengan ketersediaan maupun kelayakan materi untuk dipelajari dan kemudahan untuk memperolehnya.
e) Kemenarikan (interest), berkaitan dengan kemenarikan tingkat materi, sehingga dapat mendorong dan membangkitkan anfsu belajar peserta didik untuk mengadakan berbagai pengakajian lebih lanjut
Prinsip pengembangan bahan ajar juga dipaparkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (2008: 8-9), yaitu sebagai berikut.
1. Ketersedian bahan ajar sesuai tuntutan, artinya bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum.
2. Karakteristik sasaran, artinya bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa sebagai sasaran, karakteristik tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, geografis maupun tahapan perkembangan siswa.
3. Pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar.
Harjanto (2008: 222-224) juga menjelaskan sebagai contoh dalam pengembangan bahan ajar dalam sistem instruksional, sebagai berikut.
a. Kriteria tujuan instruksional. b. Bahan ajar supaya terjabar. c. Relevan dengan kebutuhan siswa. d. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat. e. Bahan ajar mengandung segi-segi etik. f. Bahan ajar tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang
sistematik dan logis. g. Bahan ajar bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi
guru yang ahli, dan masyarakat. Menurut Widodo dan Jasmadi (2008: 50), terdapat berbagai hal
yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar yang mampu
21Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
membuat siswa untuk belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam proses pembelajaran sebagai berikut.
1. Memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka mendukung pemaparan materi pembelajaran.
2. Memberikan kemungkinan bagi siwa untuk memberikan umpan balik atau mengukur penguasaannya terhadap materi yang diberikan dengan memberikan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya.
3. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan siswa.
4. Bahasa yang digunakan cukup sederhana karena siswa hanya berhadapan dengan bahan ajar ketika belajar dengan mandiri.
Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan materi pembelajaran menurut Muchith (2011: 31), adalah:
1) Prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi.
2) Prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa satu macam, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan juga harus meliputi satu macam. Artinya, materi pembelajaran yang diberikan pada waktu tertentu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Lebih pada pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran harus sebanding dengan banyaknya kompetensi dasar yang ditetapkan.
3) Prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa mengusai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi pembelajaran hendaknya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.
22 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Lebih jelas, Prastowo (2013: 317) memaparkan bahwa ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Ketiga penerapan prinsip-prinsip tersebut dipaparkan sebagai berikut:
1. Prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian SK dan KD. Cara termudah ialah dengan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan prinsip dasar ini, guru akan mengetahui apakah materi yang hendak diajarkan tersebut materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap atau aspek psikomotorik sehingga pada gilirannya guru terhindar dari kesalahan pemilihan jenis materi yang tidak relevan dengan pencapaian SK dan KD.
2. Prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus dikerjakan juga harus meliputi empat macam.
3. Prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa mengusaai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.
Secara runtut, Daryanto dan Dwicahyono (2014: 172-173), memaparkan prinsip pengembangan bahan ajar seperti berikut ini.
1. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongret untuk memahami yang abstrak.
2. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 3. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap
pemahaman peserta didik.
23Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
4. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar.
5. Mencapai tujuan, ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu.
6. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan.
Berbagai prinsip pengembangan bahan ajar tersebut perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Namun, agar lebih jelas, perlu disimpulkan bahwa prinsip pengembangan bahan ajar adalah: (1) memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka mendukung pemaparan materi pembelajaran, (2) memberikan kemungkinan bagi siwa untuk memberikan umpan balik atau mengukur penguasaannya terhadap materi yang diberikan dengan memberikan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya, (3) kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan siswa, dan (4) bahasa yang digunakan cukup sederhana karena siswa hanya berhadapan dengan bahan ajar ketika belajar dengan mandiri. Prinsip ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Widodo dan Jasmadi (2008: 50).
E. Prosedur Pengembangan Bahan Ajar
Setelah memaparkan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, maka diperlukan pula prosedur pengembangan bahan ajar. Salah satu pendapat mengenai prosedur pengembangan bahan ajar ini adalah prosedur yang dipaparkan oleh Jolly dan Bolitho. Menurut Jolly dan Bolitho (dalam Thomlinson, 1998:98) tahap-tahap pengembangan bahan ajar, yakni: (1) identifikasi kebutuhan guru dan siswa; (2) penentuan kegiatan eksplorasi kebutuhan materi; (3) realisasi kontekstual dengan mengajukan gagasan yang sesuai dengan pemilihan teks dan konteks bahan ajar; (4) realisasi pedagogis melalui tugas dan latihan; (5) produksi bahan ajar; (6) penggunaan bahan ajar oleh siswa; dan (7) evaluasi bahan ajar.
24 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Pendapat lain yang dipaparkan mengenai prosedur pengembangan bahan ajar ini adalah pendapat Richard. Richard (Tirto, 2005: 10) menjelaskan bahwa rancangan pengembangan bahan ajar, meliputi: (1) pengembangan tujuan; (2) pengembangan silabus; (3) pengorganisasian bahan ajar ke dalam unit-unit pembelajaran; (4) pengembangan struktur perunit; dan (5) pengurutan perunit. Dengan rinci Departemen Pendidikan Nasional (2008: 19), menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pendidik dalam menulis sebuah buku, yaitu:
a. Mempelajari kurikulum dengan cara menganalisisnyab. Menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan SK
yang akan disediakan bukunyac. Merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup
seluruh aspek yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi.
d. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan, upayakan untuk menggunakan referensi terkini dan relevan dengan bahan kajiannya.
e. Menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Untuk siswa SMA diupayakan untuk membuat kalimat yang tidak terlalu panjang, maksimal 25 kata per kalimat dan dalam satu paragraph 3-7 kalimat.
f. Mengevaluasi/mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Jika ada kekurangan segera dilakukan penambahan
g. Memperbaiki tulisanh. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya
materi misalnya buku, majalah, internet, jurnal hasil penelitian. Prastowo (2011: 50) kemudian memaparkan langkah-langkah
pokok dalam pembuatan bahan ajar meliputi beberapa aspek, yaitu:
25Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
a. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar1) Analisis kurikulum2) Menganalisis sumber belajar3) Memilih dan menentukan bahan ajar
b. Memahami Kriteria Pemilihan Sumber Belajarc. Menyusun Peta Bahan Ajard. Memahami Struktur Bahan Ajar
Lebih lanjut dalam buku terbaru, Depdiknas menggambarkan alur analisis penyusunan bahan ajar adalah sebagai berikut ini.
Gambar 1. Alur Analisis Penyusunan Bahan Ajar
(Nobonnizar, 2013: )
Berdasarkan beberapa pendapat mengenai prosedur pengembangan bahan ajar di atas, maka secara garis besar langkah-langkah pengembangan bahan ajar meliputi: (1) analisis kurikulum, (2) identifikasi materi, dan (3) memilih sumber bahan ajar. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa pakar sebelumnya. Namun, pendapat yang paling dipertimbangkan adalah prosedur pengembangan bahan ajar yang dikemukakan oleh Prastowo (2011: 50).
Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator
Materi Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Bahan Ajar
26 Moderasi Dakwah Hasan al-Banna
1. Analisis Kurikulum
Sebelumnya telah dipaparkan mengenai prosedur pengembangan bahan ajar. Agar lebih jelas, prosedur pengembangan bahan ajar tersebut dipaparkan satu persatu. Prosedur pertama yang harus diperhatikan adalah menganalisis kurikulum dari pelajaran yang akan dikembangkan. Nunan (1997:158) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan dasar prosedur untuk perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan, program pendidikan. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Pengembangan bahan ajar merupakan salah satu dari pengembangan kurikulum. Oleh sebab itu, untuk melakukan pengembangan bahan ajar di sekolah harus memperhatikan kurikulum yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang sedang berlaku sekarang ini adalah Kurikulum 2013 revisi 2016. Kurikulum ini dipahami sebagai serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang sudah dirintis sejak tahun 2004 yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi kemudian dilanjutkan dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh (dalam Kurniasih, 2014:7), mempertegas bahwa Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penjelasan lain mengenai Kurikulum 2013 dijelaskan oleh Fadillah (2014: 16), bahwa:
“Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang dikembangkan dari kurikulum sebelumnya yaitu KBK dan KTSP, dengan menggunakan pembelajaran yang bersifat tematik integrative dalam semua mata pelajaran guna untuk meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan”.
27Moderasi Dakwah Hasan al-Banna
2. Identifikasi Materi
Sebelum menentukan materi pembelajaran yang akan dikembangkan, Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 219), menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah: (1) materi pelajaran hendaknya sesuai dengan kurikulum sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional, (2) materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan peserta didik pada umumnya, (3) materi pelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan, dan (4) materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual.
Materi pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dapat dibedakan menjadi: pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) (Sanjaya, 2010:142). Aspek pengetahuan memberikan informasi yang disimpan dalam pikiran siswa, hal ini berarti pengetahuan adalah segala hal yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa, sehingga ketika dibutuhkan siswa dapat mengungkapkan kembali hal-hal yang telah dikuasai tersebut. Aspek Keterampilan menunjuk pada tindakan-tindakan baik fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh siswa dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan aspek sikap menunjuk pada kecendrungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan norma maupun nilai yang diyakini oleh siswa.
Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan materi pembelajaran adalah :
1) Prinsip relevansi, artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi.
2) Prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa satu macam, maka materi
28 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
pembelajaran yang harus diajarkan juga harus meliputi satu macam. Artinya, materi pembelajaran yang diberikan pada waktu tertentu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Lebih pada pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran harus sebanding dengan banyaknya kompetensi dasar yang ditetapkan.
3) Prinsip kecukupan, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa mengusai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi pembelajaran hendaknya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit (Rahman dan Sofan Amri, 2013: 78-79).
Lebih lanjut Rahman dan Sofan Amri (2013:80), menjelaskan bahwa dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu :
a) Aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur) b) Aspek afektif; dan c) Aspek psikomotorik
Tidak hanya memperhatikan jenis materi pembelajaran saja, prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran juga harus diperhatikan. Hal tersebut menyangkut:
a) Keluasan materi, adalah menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan kedalam suatu materi pemebelajaran
b) Kedalaman materi, adalah seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari/dikuasai oleh siswa
3. Memilih Sumber Bahan Ajar
Tahapan memilih sumber bahan ajar dimaksudkan untuk menganalisis ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan sumber belajar yang akan menjadi bahan dalam penyusunan bahan ajar.
29Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Sumber belajar adalah informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Lebih lanjut Sanjaya (2010: 60), yang menyatakan bahwa ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai sumber materi pembelajaran, yakni tempat atau leingkungan, orang atau narasumber, objek, serta bahan cetak dan non-cetak.
Sudjana (dalam Prastowo, 2013: 358), menjelaskan bahwa untuk memudahkan proses pemilihan sumber belajar tersebut, menunjukkan dua kriteria yang bisa digunakan dalam pemilihan sumber belajar, yaitu kriteria umum dan khusus.
a. Kriteria umumSecara umum, ketika memilih sumber belajar, hendaknya kita memperhatikan empat kriteria, yaitu: (1) segi ekonomis, maksudnya harga sumber belajar harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; (2) segi praktis dan sederhana maksudnya dalam penggunaanya tidak diperlukan pelayanan atau pengadaan sampingan yang sulit dan langka; (3) segi kemudahan memperoleh maksudnya sumber belajar hendaknya dipilih yang dekat dan mudah dicari; (4) bersifat fleksibel maksdunya bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran atau dengan istilah kompatibel.
b. Kriteria khusus
Ada sejumlah kriteria khusus untuk pemilihan sumber belajar. Kriteria khusus tersebut antara lain:
1) Sumber belajar dapat memotivasi siswa;2) Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, maksudnya sumber
belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan;
3) Sumber belajar untuk penelitian, maksudnya sumber belajar yang digunakan hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya;
30 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
4) Sumber belajar untuk memecahkan masalah, sumber belajar hendaknya mampu mengatasi problem belajar siswa yang dihadapi saat kegiatan belajar mengajar; dan
5) Sumber belajar dapat untuk presentasi, sumber belajar yang dipilih di sini hendaknya bisa sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan.
Pengembangan bahan ajar yang akan dilakukan berhubungan dengan istilah basis. Basis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Alwi, et. all. 2002:111) bermakna dasar atau asas. Kata dasar diartikan alas atau fondasi; pokok atau pangkal suatu pendapat, aturan, atau ajaran (Alwi, et. all. 2002:238). kemudian kata asas bermakna dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (Alwi, et. all. 2002:70). Oleh karena itu, berdasarkan arti kata basis, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis Literasi Media Sosial adalah pembelajaran yang menjadikan kegiatan literasi media sosial sebagai dasar, asas, pangkal, atau tumpuan.
Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Literasi di SMK, maka sumber yang dijadikan dalam penyusunan bahan ajar Bahasa Indonesia ini adalah materi-materi yang dihasilkan dari proses literasi informasi, yaitu mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dari media-media komunikasi dan informasi yang digunakan oleh masyarakat.
31
A. Konsep Literasi
Pada awalnya, literasi memiliki makna kemampuan membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan dunia kerja dan kehidupan di luar sekolah (Tompkins, 1991). Kemudian Literasi memiliki makna melek teknologi, informasi, politik, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kirsch dan Jungeblut dalam buku Literacy: Profile of Americs’s Young Adult memaparkan makna literasi kontemporer adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pendapat Kirsch dan Jungeblut ini senada dengan yang dikemukakan oleh Baran (2004) yang menuliskan bahwa literasi diartikan adalah kemampuan memahami simbol-simbol tertulis secara efisien dan efektif serta komprehensif.
LITERASI MEDIA
BAB III
32 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
UNESCO (dalam Iriantara, 2006:79) mendefinisikan literasi dengan menyatakan: berdasarkan definisi UNESCO tahun 1958, literasi adalah kemampuan seorang individu untuk membaca dan menulis dengan memahami pernyataan singkat yang terkait dengan kehidupannya. Kemudian definisi ini berkembang sehingga meliputi ranah-ranah keterampilan jamak yang masing-masing dipandang memiliki taraf penguasaan yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda pula. Perkembangan sosial itulah yang membuat Lamb (dalam Iriantara, 2006) menyatakan bahwa literasi tidak hanya didefiniskan sebagai kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga “kemampuan menempatkan, mengevaluasi, menggunakan dan mengkomunikasikan melalui berbagai sumber daya termasuk sumber daya teks, visual, suara, dan video.
Pendapat lain mengenai konsep literasi adalah pendapat dari Harras. Menurut Harras (2011), literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis atau kadang disebut dengan istilah atau “melek aksara” atau keberaksaraan. Kemudian Kirsch dan Jungeblut memaparkan bahwa literasi kontemporer diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas (Takdir, 2012).
Secara sederhana Subadriyah, dkk. (2013) menjelaskan bahwa literasi merupakan salah satu model pengembangan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Selanjutnya Subadriyah, dkk juga mengungkapkan bahwa model pembelajaran literasi adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan di kelas atau pembelajaran tutorial untuk meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan berpikir, berbicara, membaca, dan menulis untuk membangun suatu kemampuan pada operasi kognitif tertentu dengan tulisan, perkataan, kalimat, dan teks agar mampu berkomunikasi untuk melayani tuntutan masyarakat modern.
33Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Konsep literasi sekarang ini memang sudah banyak mengalami perkembangan. Dari beberapa konsep literasi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipaparkan lagi pendapat lain mengenai literasi. Pendapat lain memaparkan bahwa literasi merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan makna melalui membaca dan menulis (Sandra & Donna, 2015:202)
Dari beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai literasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan menempatkan, mengevaluasi, menggunakan dan mengkomunikasikan melalui berbagai sumber daya termasuk sumber daya teks, visual, suara, dan video. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lamb (dalam Iriantara, 2006). Lamb menjelaskan bahwa literasi tidak hanya didefiniskan sebagai kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga “kemampuan menempatkan, mengevaluasi, menggunakan dan mengkomunikasikan melalui berbagai sumber daya termasuk sumber daya teks, visual, suara, dan video.
B. Literasi Media
Dengan adanya perkembangan media elektronik yang tidak terbatas lagi, maka kemampuan itu tidak lagi bernama literasi, tetapi menjadi literasi media atau lebih dikenal dengan kecerdesan bermedia. Literasi media diharapkan mampu menjadi ‘obat’ dari adanya dampak negatif media. Selain itu, literasi media diharapkan juga mampu mengurangi ketimpangan informasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.
Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang media menjadi salah satu rintangan atau kendala bagi masyarakat dalam memahami realitas dibalik media yang sebenarnya. Dengan pemahaman yang seadanya maka masyarakat akan mudah terpengaruh pada kenyataan atau realitas yang dipaparkan oleh media tanpa berfikir menganai kebenaran informasi yang mereka
34 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
peroleh. Oleh sebab itu, kegiatan literasi media lahir dalam rangka mengentaskan “kebodohan” dalam media atau sering dikenal dengan sebutan melek media.
Terdapat lima elemen literasi media yang dikemukakan oleh Silverblat (1995:2-3), yaitu:
1. Kesadaran akan dampak media pada individu dan masyarakat.
2. Pemahaman atas proses komunikasi massa. 3. Pengembangan strategi untuk menganalisis dan
mendiskusikan pesan media. 4. Kesadaran atas konten media sebagai sebuah teks yang
memberikan pemahaman kepada budaya kita dan diri kita sendiri.
5. Pemahaman kesenangan, pemahaman dan apresiasi yang ditingkatkan terhadap konten media.
Senada dengan beberapa pendapat sebelumnya, literasi media dapat dikatakan sebagai suatu proses mengakses, menganalisis secara kritis pesan media, dan menciptakan pesan menggunakan alat media. Pernyataan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Hobbs (1996). Tidak hanya Hobbs, Rubin (1998) memaparkan bahwa literasi media diartikan sebagai pemahaman sumber, teknologi komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi, interpretasi, dan dampak dari pesan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa dengan Internet atau media baru ini mengubah pola komunikasi manusia. Seseorang tidak hanya menjadi konsumen sebagai penikmat media tetapi juga bisa sebagai produsen dalam media tersebut.
Pendapat lain mengenai literasi media adalah menurut Brown (1998), yang memaparkan bahwa literasi media merupakan kemampuan untuk menganalisis dan menghargai karya-karya sastra dan untuk berkomunikasi efektif melalui tulisan yang baik.
35Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Setelah beberapa lama, literasi mendapatkan perubahan makna, dari sebelumnya bermakna keterampilan membaca dan menulis, sekarang menjadi lebih berkembang. Pemahaman literasi media sebelumnya menjadi diperluas mencakup kemampuan untuk membaca teks film, televisi, dan media visual karena studi tentang pendidikan media dimulai dengan mengikuti pengembangan area media (Ferrington, 2006)
Menurut Potter (2004: 124), ada tujuh kemampuan atau kecakapan yang diusahakan muncul dari kegiatan literasi media, yaitu:
1. Analyze/ MenganalisaKompetensi berikutnya adalah kemampuan menganalisa struktur pesan, yang dikemas dalam media, mendayagunakan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan untuk memahami konteks dalam pesan pada media tertentu. Misalnya, mampu mendayagunakan informasi di media massa untuk membandingkan pernyataan-pernyataan pejabat publik, dengan dasar teori sesuai ranah keilmuannya. Kompetensi lainnya bisa diperiksa dengan kata kerja seperti, membedakan, mengenali kesalahan, menginterpretasi, dan sebagainya.
2. Evaluate/Menilai.Setelah mampu menganalisa, maka kompetensi berikutnya yang diperlukan adalah membuat penilaian (evaluasi). Seseorang yang mampu menilai, artinya ia mampu menghubungkan informasi yang ada di media massa itu dengan kondisi dirinya, dan membuat penilaian mengenai keakuratan, dan kualitas relevansi informasi itu dengan dirinya; apakah informasi itu sangat penting, biasa, atau basi. Tentu saja kemampuan dalam menilai sebuah informasi itu dikemas dengan baik atau tidak, juga adalah bagian dari kompetensinya. Di sini, terjadi membandingkan norma dan nilai sosial terhadap isi yang dihadapi dari media.
36 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
3. Grouping/PengelompokanMenentukan setiap unsur yang sama dalam beberapa cara: menentukan setiap unsur yang berbeda dalam beberapa cara.
4. Induction/InduksiMenyimpulkan suatu pola di set kecil elemen, maka pola generalisasi untuk semua elemen dalam himpunan tersebut.
5. Deduction/deduksiMenggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan khusus.
6. Synthesis/sintesisMerakit unsur-unsur ke dalam struktur baru.
7. Abstracting/ abstrakMenciptakan singkat, jelas, dan gambaran tepat menangkap esensi dari pesan dalam sejumlah kecil kata-kata dari pada pesan itu sendiri.
Lebih lanjut James W. Potter mendefinisikan literasi media adalah:A set of perspectives that we actively use to expose ourselves to the media to interpret the meaning of the messages we encounter (Literasi media sebagai satu perangkat perspektif dimana kita secara aktif memberdayakan diri kita sendiri dalam menafsirkan pesan-pesan yang kita terima dan bagaimana cara mengantisipasinya) (Potter, 2005: 22).
Menurut Center of Media Literacy (Kellner & Sahre, 2005: ), terdapat lima konsep tentang literasi media, yaitu: semua pesan media ‘dikonstruksikan’, pesan media dikonstruksikan dengan bahasa yang kreatif sesuai dengan aturan mereka, individu memaknai pesan tergantung dari pemahamannya atas pesan yang ditangkapnya dari media, media mempunyai sudut pandang dan mengandung nilai tersendiri, hampir semua pesan media memiliki kepentingan keuntungan ataupun kekuasaan. Kemudian secara tradisional pemahaman mengenai literasi media diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan menciptakan
37Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
(Silverblatt, 2007: 136). Sedangkan McLuhan berpendapat bahwa masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuannya untuk menghadapi teknologi tersebut. Media secara umum bertindak secara langsung untuk membentuk dan mengorganisasikan sebuah budaya (Turner, 2008: 139). Simpulan dari pendapat McLuhan adalah bahwa teknologi media memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan bermasyarakat.
National Leadership Conference on Media Education menyatakan bahwa literasi media sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam pelbagai bentuknya. Dalam pasal 52 Undang-undang No.32/2003 tentang penyiaran memaknai literasi media sebagai kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat (Iriantara, 2009:25). Dengan kata lain pendidikan media merupakan bentuk pemberdayaan khalayak media. Oleh karena itu, salah satu dari prinsip pendidikan media atau literasi media adalah memberdayakan khalayak. Memberdayakan dimaksudkan karena dalam pandangan Brow (Iriantara 2009:13), “literasi media menjadi kompas baru dalam mengarungi dunia media.” Karena, menurut pandangan Brow, “bila orang tidak diberdayakan, maka orang akan menjadi korban media.”
Literasi media yang terdiri atas dua kata, yaitu kata ‘literasi’ dan ‘media’’, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan media sebagai sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk atau sesuatu yang terletak diantara dua pihak (Tim KPI, 2011: 34). Menurut Konferensi Kepemimpinan Nasional dalam Literasi Media (National Leadership Conference of Media Literacy) di Amerika Serikat tahun 1992, definisi literasi media menjadi “kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan” (Tim KPI, 2011: 34).
38 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Kemampuan literasi media wajib dimiliki para guru dan peserta didik. Hal ini dikarenakan agar guru dan peserta didik tidak tertinggal dan menjadi asing di antara lingkungan yang sudah terjangkit arus informasi digital. Diharapkan, literasi media peserta didik akan penggunaan media sosial dapat menghambat dampak buruk dari penggunaan media tersebut. Selain itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa informasi tersebut juga menyebar pada hal-hal negatif, seperti: konsumerisme, budaya kekerasan, budaya ngintip pribadi orang, bahkan kematangan seksual lebih cepat terjadi pada usia anak-anak (Rahmi, 2013: 56). Oleh karena itu, peserta didik diharapkan dengan baik dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperbanyak serta memperluas wawasannya, bukan sekadar media hiburan untuk mengakses online game dan hal lainnya.
Blake (dalam Potter, 2005) menyebutkan literasi media dibutuhkan pelajar karena: (1) hidup di lingkungan bermedia; (2) literasi media menekankan pada pemikiran kritis; (3) menjadi literat terhadap media merupakan bagian dari pembelajaran terhadap warga negara, membuat dapat berperan aktif dalam lingkungan yang dipenuhi dengan media; dan (5) pendidikan media membantu dalam memahami teknologi komunikasi.
Pendapat terbaru dipaparkan oleh Tamburaka (2013:7) yang menjelaskan bahwa literasi media berasal dari bahasa Inggris yaitu media literacy, terdiri dari dua suku kata Media berarti media tempat pertukaran pesan dan literacy berarti melek, kemudian dikenal dalam istilah literasi media. Dalam hal ini literasi media merujuk pada kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi media massa. Padanan kata istilah literasi media juga dikenal dengan istilah melek media pada dasarnya memilik maksud yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan.
39
A. Teori Belajar
Dalam proses pembelajaran di sekolah setidaknya terdapat dua kegiatan yang berlangsung. Kegiatan tersebut adalah kegiatan belajar dan mengajar. Sardiman (2007: 21), mengemukakan bahwa konsep belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Di awal Sardiman menggunakan kata perkembangan, sedangkan Fathurrohman dan Sutikno lebih menggunakan kata perubahan. Menurut Fathurrohman dan Sutikno (2007: 6), belajar merupakan perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun tidak semua perubahan termasuk
TEORI PROSES PEMBELAJARAN
BAB IV
40 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
kategori belajar, misalnya: perubahan fisik, mabuk, gila, dan sebagainya. Namun, dalam belajar yang terpenting adalah proses bukan hasil yang diperolehnya.
Senada dengan konsep belajar sebelumnya, Baharuddin dan Wahyuni memaparkan pula tentang pengertian belajar. Menurut Baharuddin dan Wahyuni (2007: 11) belajar adalah proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Kemampuan manusia dalam belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Selain itu, belajar juga akan memberikan kontribusi dalam setiap kehidupan individu dan masyarakatnya.
Konsep pembelajaran lainnya dikemukakan oleh Hergenhahn dan Olson (2008: 8), yang mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku atau potensi perilaku yang relatif permanen yang berasal dari pengalaman dan tidak bisa dinisbahkan ke temporary body states (keadaan tubuh temporer) seperti keadaan yang disebabkan oleh sakit, keletihan, atau obat-obatan. Kesamaan pendapat mereka adalah sama-sama menyatakan bahwa di dalam belajar, terjadinya perubahan tingkah laku. Namun terdapat sedikit perbedaannya yaitu pada pendapat Hergenhahn dan Olson yang menyatakan bahwa di dalam belajar terdapat perubahan perilaku yang permanen.
Gredler (2011: 119) dalam bukunya menyatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku secara fungsional berkaitan dengan perubahan dalam lingkungan atau kondisi. Hampir senada dengan Gredler, Slavin (2011: 177) memaparkan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang berasal dari pengalaman. Kesamaan pendapat Gredler dan Slavin adalah sama-sama berpendapat bahwa di dalam belajar terjadi perubahan perilaku.
Setelah memaparkan pendapat-pendapat mengenai konsep belajar sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu tahap yang mengakibatkan perubahan pada diri seseorang
41Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
baik dari segi kompetensi, keterampilan, dan sikap. Keberhasilan Belajar bisa ditandai dengan perubahan tingkah laku dan perilaku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, serta dari tidak terampil menjadi terampil. bahkan dapat dijelaskan pula bahwa proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang sedang belajar. Proses belajar tersebut bisa diamati dari ada atau tidak adanya perubahan perilaku seseorang yang belajar dari pada sebelumnya.
B. Teori Mengajar
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam pembelajaran terdapat dua kegiatan penting, yaitu belajar dan mengajar. Oleh karena itu, selain konsep belajar, konsep mengajar juga akan dipaparkan dalam bab ini. Fathurrahman dan Sutikno (2007: 7), memaparkan bahwa mengajar adalah suatu proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling memengaruhi, yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan siswa yang memainkan peranan serta dalam hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang tersedia.
Jihad dan Haris (2009: 8), menjelaskan bahwa mengajar dapat dipandang dalam dua aspek. Pertama, pengertian mengajar secara tradisional. Kedua, pengertian mengajar dalam dunia modern. Menurut pengertian tradisional, mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa atau murid di sekolah. Kemudian mengajar dalam dunia modern adalah membantu siswa memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara-cara belajar.
42 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
C. Proses Pembelajaran
Proses belajar dan mengajar merupakan suatu aktivitas yang disebut dengan istilah proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat berlangsung di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, dan oleh siapa saja. Salah satu proses pembelajaran yang dilakukan adalah proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, baik sekolah formal, informal, maupun nonformal. Sekolah tersebut dimulai dari tingkat dasar hingga ke tingkat yang tinggi. Setiap manusia pastinya pernah mengalami dan melakukan proses pembelajaran yang berakibat pada perubahan sikap, mental, kompetensi, dan keterampilan manusia masing-masing. Pembelajaran merupakan suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan oleh guru guna membelajarkan siswa (Djamarah, 2002: 43).
Pendapat lain dipaparkan oleh Suherman. Menurut Suherman dkk. (2003: 8) pembelajaran sebagai upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 (Susetyo, 2005: 167) pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Menurut Uno (2006: 184-185), dalam proses pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang musti dipertimbangkan. Terdapat lima prinsip dalam belajar yang dipaparkan oleh Uno , yaitu:
1. Mengenali betul apa yang menarik untuk kita. Jika kita mengetahui betul apa sesungguhnya yang menarik bagi kita, tentu akan lebih mudah mencari ragam informasi penting yang akan kita pelajari.
2. Kenalilah kepribadian diri sendiri. Jika kita tahu betul siapa kita dan apa yang kita inginkan, mempelajari sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kepribadian kita menjadi lebih mudah dilakukan.
43Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
3. Rekam semua informasi dalam kata. Langkah yang paling mudah dan bijaksana adalah apabila kita terbiasa merekam semua informasi itu dengan cara menuliskannya kembali dalam bentuk apa saja.
4. Belajar bersama orang lain. Cara termudah untuk belajar sesungguhnya adalah apabila kita melakukannya secara bersama-sama.
5. Hargai diri sendiri. Belajar memahami dan menyerap informasi akan menjadi lebih terasa bermanfaat dan berarti apabila kita menghargainya.
Tidak hanya prinsip, komponen dalam proses pembelajaran pun harus ditimbangkan. Hamalik (2003: 54), menjelaskan bahwa komponen proses pembelajaran terdiri dari: (1) tujuan pembelajaran; (2) siswa yang belajar; (3) guru yang mengajar; (4) metode pembelajaran; (5) media pembelajaran; (6) situasi pembelajaran; dan (7) evaluasi pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran tersebut tidak berdiri sendiri namun saling terkait. Pandangan pembelajaran sebagai komponen-komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut merupakan pendekatan sistem. Proses pembelajaran dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi interaksi komunikasi belajar mengajar antara guru, siswa, dan komponen pembelajaran lainnya sehingga tercapai tujuan pembelajaran (Rusman, 2011: 15).
45
A. Pelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 13
Pelajaran Bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 dikategorikan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks. Hal ini berdasarkan pengertian teks dalam Kurikulum 2013 yang telah berkembang. Pemahaman teks dalam kurikulum 2013 berbeda dengan pemahaman teks selama ini. Badan Bahasa (2008: 142), menjelaskan bahwa teks selama ini diartikan sebagai wacana tertulis. Dalam Kurikulum 2013, teks tidak hanya diartikan sebagai bentuk bahasa tulis, tetapi teks itu adalah ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya ada situasi dan konteksnya. Teks dibentuk oleh konteks situasi penggunaan bahasa yang di dalamnya ada register atau ragam bahasa yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut (Mahsun, 2014: 121). Dari penjelasan tersebut, teks dalam
PELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS LITERASI
BAB V
46 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
pelajaran bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 dapat berbentuk lisan dan tulisan.
Berdasarkan pendapat di atas, berarti menguatkan bahwa teks dapat berbentuk lisan dan tulisan. Teks sebagai urutan teratur sejumlah kalimat yang dihasilkan dan memiliki makna. Hartoko dan Rahmanto (1986: 141), berpendapat bahwa teks yang ditulis oleh siswa harus memiliki makna. Dengan adanya makna dalam teks tersebut, akan lebih bermanfaat bagi orang yang membacanya.
Derewianka (2003: 135), menjelaskan bahwa penekanan pembelajaran berbasis teks adalah pada penciptaan makna pada seluruh tingkat teks. Kemudian makna tersebut harus dipahami oleh siswa agar pembelajaran berbasis teks menjadi efektif. Berdasarkan pendapat Derewianka, pendidik yang akan membuat suatu teks untuk pembelajaran berbasis teks, terlebih dahulu harus berusaha menentukan makna di dalam teks yang dibuatnya. pendidik harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik sehingga peserta didik mampu menemukan makna yang terkandung di dalam teks. Apabila pesera didik telah mampu menentukan makna yang terkandung dalam suatu teks, pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik akan berjalan dengan baik dan lancar.
Teks memiliki beberapa fitur yaitu komunikatif, memiliki tujuan, terstruktur, dan berorientasi akademis. Fitur-fitur tersebut harus diikuti oleh penulisnya, namun penulisnya juga boleh berkreativitas dalam menulis suatu teks. Berdasarkan pendapat Linli, kalau seseorang membuat suatu teks, di dalam teks yang dibuatnya harus komunikatif, memiliki tujuan, terstruktur, dan berorientasi akademis. Penulis teks juga harus mengikuti aturan teks yang dibuatnya (Lin dan Meitzener, 2005: 23).
Yu dan Dong (2009: 77), memaparkan bahwa pembelajaran berbasis teks telah diadopsi secara luas dalam pembelajaran bahasa di dunia. Kemudian Shuhua (2009: 99) menyatakan bahwa pembelajaran
47Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
berbasis teks menekankan bagaimana untuk mewujudkan tujuan komunikasi nyata dalam teks. Oleh karena itu, dalam penelitian pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia berbasis literasi media sosial ini merupakan pengembangan bahan ajar berbasis teks.
B. Konsep dan Manfaat Buku Ajar
Akbar dan Sriwiyana (2010: 189), menjelaskan bahwa buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Farida (2008: 85), memaparkan bahwa pada umumnya buku menawarkan berbagai gambaran spesifik yang membantu pembaca menemukan informasi yang dibutuhkan. buku yang dikemas menjadi suatu paket yang terdiri atas buku pelajaran yang diajarkan di kelas. Kemudian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Buku, Pasal 1, ayat (3). Buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Pendapat lain mengenai buku ajar adalah pendapat Majid. Menurut Majid (2008: 176), buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Oleh pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara mislanya: hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi.
Dengan demikian, dapat dimunculkan postulat mengenai konsep buku ajar. Buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Pendapat ini senada dengan pendapat Akbar dan Hadi Sriwiyana (2010: 189).
48 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Adapun manfaat buku ajar menurut Nasirudin (2011: 102-103) adalah sebagai berikut:
a. Buku ajar dapat membantu guru melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku.
b. Buku ajar merupakan pegangan dalam menentukan metode pengajaran.
c. Buku ajar memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru.
d. Buku ajar memberikan kontinuitas pelajaran di kelas yang berurutan, sekalipun guru bergantian.
e. Buku ajar dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan bila direvisi dapat bertahan dalam waktu yang lama menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.
f. Buku ajar memberi pengetahuan dan metode pengajaran yang lebih.
C. Buku Ajar Berbasis Cetak
Buku ajar yang digunakan oleh guru di sekolah lebih banyak buku ajar cetak. Oleh karena itu, dalam penyusunan buku ajar cetak tersebut harus memperhatikan bahan ajar atau materi pembelajaran cetak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam buku ajar berbasis cetak menurut Arsyad (2011: 87-90), antara lain adalah:
a. Konsistensib. Dalam penyusunannya harus menggunakan konsistensi
format dari halaman ke halaman. Jarak spasi antar judul dan baris pertama serta garis samping harus sama, begitu pula dengan jarak spasi antara judul dan teks utama. Perbedaan spasi akan membuat hasil cetakan menjadi tidak rapi.
c. b. Formatd. Terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan, pertama,
jika lebih banyak menggunakan paragrap panjan, akan lebih sesuai dibuat satu kolom. Kedua, isi yang berbeda
49Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
harus dipisahkan dan dilabel secara visual. Ketiga, strategi pembelajaran yang berbeda sebaiknya dipisahkan dan diberi label secara visual.
e. c. Organisasif. Upayakan untuk menginformasikan kepada siswa, sejauh
mana teks yang sedang dibacanya. Siswa harus mampu melihat secara sepintas berada di bab mana atau bagian apa yang sedang dibacanya. Teks harus disusun sedemikian rupa sehingga informasi mudah diperoleh. Selain itu, dapat pula digunakan kotak untuk memisahkan bagian-bagian teks.
g. d. Daya tarikh. Perkenalan setiap bab atau bagian baru harus dengan cara
yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat termotivasi untuk terus membaca.
i. e. Ukuran hurufj. Ukuran huruf harus dipilih sesuai dengan siswa, pesan,
dan lingkungannya. Ukuran guruf yang baik untuk buku teks biasanya adalah 12 poin. Selain itu harus dihindari penggunaan huruf capital untuk seluruh teks. Hal ini akan membuat proses membaca menjadi sulit.
k. f. Ruang (spasi) kosongl. Gunakan ruang kosong tak berisi teks atau gambar untuk
menambang kontras. Hal ini penting untuk membuat siswa beristirahat pada titik tertentu pada saat matanya bergerak menyusuri teks. Ruang kosong dapat berbentuk ruang kosong sekitar judul, batas tepi (margin), spasi antar kolom, permulaan paragraph diidentasi, serta penyesuaian spasi antar barus antar paragraph. Spasi antar baris atau antar paragraph dapat membantu meningkatkan tingkat keterbacaan.
50 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Dalam penyusunan bahan ajar cetak, harus memperhatikan beberapa hal seperti yang paparkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2008: 18) berikut ini.
a. Susunan tampilan, yang menyangkut: urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, rangkuman, dan tugas pembaca.
b. Bahasa yang mudah, menyangkut: mengalirnya kosa ksata, jelasnya kalimat, jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang tidak terlalu penjang.
c. Menguji pemahaman, yang menyangkut: menilai melalui orangnya, check list untuk pemahaman.
d. Stimulan, yang menyangkut: enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong pembaca untuk berfikir, menguji stimulan.
e. Kemudahan dibaca, yang menyangkut: keramahan terhadap mata (huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks terstruktur, mudah dibaca.
f. Materi instruksional, yang menyangkut: pemilihan teks, bahan kajian, lembar kerja (work sheet).
Semua pendapat yang dipaparkan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan buku ajar berbasis cetak tersebut harus dipertimbangkan. Namun, agar dalam penyusunan buku ajar dalam penelitian dan pengembangan ini lebih terarah dan lebih mudah dinilai, maka hal-hal prinsip yang harus diperhatikan adalah seseuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tarigan dan H.G. Tarigan (2009: 22). Kriteria yang harus dipenuhi dalam penyusunan buku ajar tersebut adalah: (a) mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu yang melandasi konsep-konsep yang digunakan dalam buku teks harus jelas, (b) relevan dengan kurikulum, (c) menarik minat pembaca yang menggunakannya., (d) mampu memberi motivasi kepada para pemakainya, (e) dapat menstimulasi aktivitas peserta didik, (f) membuat ilustrasi yang mampu menarik penggunaannya, (g) pemahaman harus didahului komunikasi yang tepat, (h) isi
51Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
menunjang mata pelajaran lain, (i) menghargai perbedaan individu, (j) berusaha memantapkan nilai yang berlaku dalam masyarakat., (k) mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan kemampuan peserta didik yang memakai, (l) menggunakan konsep yang jelas sehingga tidak membingungkan peserta didik, (m) mempunyai sudut pandang (point of view) yang jelas.
D. Variabel Pemeriksaan dan Penyempurnaan Buku Ajar Bahasa Indonesia
Setelah selesai menulis bahan ajar, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah evaluasi terhadap bahan ajar tersebut. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahan ajar telah baik ataukah masih ada hal yang perlu diperbaiki. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008:28), teknik evaluasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya evaluasi kepada validator ataupun uji coba kepada peserta didik secara terbatas. Komponen evaluasi mencakup kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan kegrafikan.
Komponen kelayakan isi mencakup, antara lain:
1) Kesesuaian dengan SK, KD2) Kesesuaian dengan perkembangan anak3) Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar4) Kebenaran substansi materi pelajaran5) Manfaat untuk penambah wawasan6) Kesesuaian dengan nilai moral, dan nila-nilai social
Komponen kebahasaan antara lain mencakup:
1) Keterbacaan2) Kejelasan informasi3) Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik
dan benar4) Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan
singkat)
52 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Komponen penyajian antara lain mencakup:
1) Kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai2) Urutan sajian 3) Pemberian motivasi, daya tarik4) Interaksi (pemberian stimulus dan respond)5) Kelengkapan informasi6) Komponen kegrafikan antara lain mencakup:7) Penggunaan font; jenis dan ukuran8) Lay out atau tata letak9) Ilustrasi, gambar, foto10) Desain tampilan
53
A. Desain Pengembangan
Desain pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia bisa diadaptasi dari berbagai model. Dalam buku ini desain pengembangan buku ajar berpedoman pada model pengembangan ADDIE. Pengembangan ADDIE terdiri atas lima tahap pengembangan yaitu Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Menurut Hasyim (2016:97-98) model rancangan pembelajaran ADDIE merupakan model prosedural yang sederhana dan mudah untuk memproduk bahan ajar, untuk pelatihan jangka pendek atau berkesinambungan. Langkah ADDIE dapat disesuaikan dengan langkah R&D.
Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti mengikuti prosedur pengembangan model ADDIE (Pribadi, 2009:127) yang disajikan dalam diagram di bawah ini:
TAHAPAN PENGEMBANGAN BUKU AJAR BAHASA INDONESIA
BAB VI
54 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Gambar Prosedur R&D
Buku Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Literasi
Analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa
Menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran
Memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran
Melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi pembelajaran
ANALYSIS
DESIGN
DEVELOPMEN
IMPLEMENTATION
Melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar
EVALUATION
55Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Penjelasan lebih rinci mengenai desain pengembangan diuraikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1. Tahap Pengembangan Buku Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Literasi
No. Langkah Pengem-bangan
Kegiatan Peneliti
Deskripsi Kegiatan
1 Analysis
Need Analysis
- Menganalisis kebutu-han guru dan siswa da-lam mata pelajaran ba-hasa Indonesia khusus-nya materi teks Cerpen
- Melakukan pretest ter-hadap kemampuan ba-hasa Indonesia siswa
Contextual Anal-ysis
Menganalisis tempat atau objek yang akan dijadikan tempat penelitian pengembangan
Theory Analysis
Menganalisis peranan dan pentingnya literasi dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia
D Design Merancang proses
pembelajaran
Mengembangkan bahan ajar, media presentasi, silabus, dan RPP
56 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
D DevelopMenghasilkan
kontenMenghasilkan buku ajar bahasa Indonesia berbasis literasi
Menghasilkan dan
memvalidasi instrumen
Memvalidasi instrumen:- Instrumen validasi pro-
duk- Instrumen praktikalitas- Instrumen efektivitas,
dan Melakukan
revisi formatif- Memvalidasi buku ajar
Bahasa Indonesia ber-basis literasi
- Pengisian instrumen oleh pakar yang mem-validasi buku ajar Ba-hasa Indonesia berbasis literasi
- Melakukan Focus group Discussion
Uji coba terbatas
- Melakukan uji coba ter-batas terhadap produk pengembangan bahan ajar dengan 4 orang siswa
- Melakukan wawancara dengan peserta uji coba terbatas.
57Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
I Implementasi Mempersiapkan tenaga pengajar
Persiapan pembelajaran selama empat pertemuan oleh guru
Mempersiapkan peserta didik
Persiapan pembelajaran oleh peserta didik
Implementasi Mengimplementasikan silabus, RPP, buku ajar, dan media presentasi
Uji Praktis Kelompok besar
a. Menyebarkan angket praktikalitas kepada seluruh peserta didik di kelas yang telah menggunakan buku ajar Bahasa Indonesia berbasis literasi dan media presentasi
b. Menyebarkan angket praktikalitas kepada seluruh guru bahasa Indonesia yang ber-jumlah 3 orang
E Evaluation 1. Menilai kual-itas proses
pengemban-gan
Melakukan observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung
2. Menilai kual-itas produk pengemban-
gan
Melakukan tes kemampuan peserta didik setelah menggunakan buku ajar Bahasa Indonesia berbasis literasi
58 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
3. Revisi bahan ajar
Memperbaiki buku ajar Bahasa Indonesia berbasis literasi dan media pembelajaran berdasarkan evaluasi dari uji praktis, efektif, serta melakukan FGD
B. Uji Coba Produk
Uji coba produk penelitian pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia berbasis literasi dilakukan dalam model ADDIE menurut Branch (2009:123) disebut formative evaluation. Menurut Branch formative evaluation terdiri dari one to one trial, small group trial, dan field trial. Untuk menentukan jumlah masing-masing percobaan dalam penelitian ini merujuk kepada rekomendasi Dick and Carey bahwa tahap uji coba dilakukan kepada kelompok kecil atau one to one trial (3 orang), kelompok sedang atau small group trial (6 orang), dan kelompok besar atau field trial (15-30 orang) (Punaji, 2013:233).
59Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Gambar 3. Desain Uji Coba Produk Bahan Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Literasi Media
C. Subjek Uji Coba
Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik. Validator dalam pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi ini adalah ahli bahan/materi ajar, ahli bahasa, dan ahli teknologi pendidikan. Untuk uji coba terbatas praktikalitas diberikan kepada 4 peserta didik. Uji coba terbatas ini merupakan bagian dari evaluasi formatif dalam pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi. Selain itu, uji coba luas praktikalitas dan efektifitas
DESAIN UJI COBA PRODUK BAHAN AJAR BI BERBASIS LITERASI
LANGKAH INSTRUMEN SUBJEK UJI
Draf 1 Pengembangan Bahan Ajar
1. Panduan wawancara 2. Angket
bidang kurikulum, pendidik, dan peserta didik
Analisis Revisi
Draf 2 Pengembangan Bahan Ajar
Analisis
Revisi Pengembangan Bahan Ajar,
Media presentasi, silabus dan RPP
Analisis
Revisi
Implementasi
Analisis
Revisi Buku ajar, Media presentasi,
silabus dan RPP
Analisis
Revisi
Produk Akhir
1. Draft Ahli Bahan /materi Ajar,
Ahli bahasa, dan Ahli teknologi pendidikan
1. Draft 2. Silabus 3. RPP 4.
Ahli bahan/materi Ajar, Ahli bahasa dan Ahli teknologi
pendidikan
1. Angket 2. Panduan observasi
1. Observasi 2. Soal Ujian
peneliti, pendidik, dan peserta didik
Uji Coba Terbatas (4-6 org)
Observasi
Uji Coba Kelompok Besar
60 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
diberikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar di kelas.
D. Jenis Data
Jenis data pada penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif terdiri dari hasil diskusi, observasi/pengamatan, dan wawancara, sedangkan data kuantitatif dari instrumen validasi, instrumen praktikalitas, dan instrumen efektivitas. Oleh sebab itu, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 2. Jenis Data Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Berbasis Literasi di SMK
No. Tahapan Jenis Data Subjek1 Analisis Jenis data pada
tahap analisis ada-lah data mengenai pelaksanaan pem-belajaran bahasa Indonesia sebelum menerapkan pro-duk pengemban-ganKebutuhan guru dan peserta didik terhadap pembela-jaran bahasa Indo-nesia yang inovatif
Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan peserta didik
61Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
2 Desain Data silabus dan RPP yang akan digunakan dalam penelitian pengem-banganData analisis metode, bahan ajar, dan strategi pem-belajaran
Guru mata pelajaran
3 Pengem-bangan
Validasi oleh ahli terhadap buku ajar, silabus, dan RPP melalui angket validasiWawancara den-gan ahli mengenai buku ajar, silabus, dan RPP melalui prosedur wawan-cara
Ahli materi/bahan ajar, ahli bahasa, dan ahli teknologi pendi-dikan
4 Imple-mentasi
Data praktikalitas kelompok kecil ter-hadap 3-6 orangData praktikalitas kelompok besar terhadap > 15 orangAngket kepuasan, reaksi, dan respon peserta didik men-genai keterpakaian buku ajar
Guru dan Peserta didik
5 Evaluasi Evaluasi formatif dari observasi Hasil belajar peser-ta didik (posttest)
Peneliti, Guru, dan Pe-serta didik
62 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
E. Instrumen Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner yang terdiri dari instrumen pre-research, validasi, praktis, dan efektif. Instrumen pre-research, validasi, dan praktis dihitung validitasnya sebelum digunakan. Instrumen efektivitas berupa soal tes dinilai oleh pakar dan kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat validitas butir soal, daya pembeda, tingkat kesukaan, kriteria penerimaan soal dan reliabilitas tes. Selain itu terdapat beberapa angket untuk menemukan praktikalitas produk pengembangan. Berikut instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Instrumen Pre-researchPre-research dilakukan untuk mengumpulkan data bagaimana bentuk bahan ajar bahasa Indonesia di sekolah yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik berdasarkan pertimbangan beberapa pihak. Pertama, mengembangkan instrumen pre-research dikembangkan berdasarkan indikator prinsip bahan ajar di sekolah dan pelaksanaan pembelajaran. Kedua, dilakukan judgement validity instrumen pre-research oleh tiga pakar. Instrumen yang telah dinilai oleh ketiga pakar tersebut disebarkan kepada peserta didik. Kemudian instrumen tersebut diberikan kepada peserta didik.
2. Lembar Validasi Instrumen Validitas Produka. Lembar validasi instrumen buku ajar bahasa Indonesia
berbasis literasi mediab. Lembar validasi perangkat pembelajaran1) Validasi instrumen perencanaan pembelajaran
(Silabus dan RPP)2) Validasi instrumen buku ajar bahasa Indonesia
berbasis literasi3) Expert judgement instrumen efektivitas bahan ajar
bahasa Indonesia berbasis literasi
63Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
3. Instrumen Praktikalitasa. Lembar angket praktikalitas bahan ajar bahasa
Indonesia berbasis literasi media terdiri dari lembar praktikalitas terhadap perangkat pembelajaran (perencanaan pembelajaran, bahan ajar, dan lembar penilaian) yang sudah dikembangkan berdasarkan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi.
b. Lembar validitas instrumen silabus dan RPP. c. Panduan observasi aktivitas guru dan siswa dalam
proses pembelajaran di sekolah.5. Instrumen efektivitas
Lembar efektivitas berupa tes kemampuan peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Expert judgement dilakukan terhadap lembar tes tersebut kepada lima orang pakar.
Semua instrumen tersebut akan divalidasi dan dihitung reliabilitasnya. Berikut dijelaskan langkah-langkah yang akan digunakan untuk melakukan analisis validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan.
a. validitas angket bertujuan untuk mengetahui apakah item instrumen sudah valid atau shahih digunakan rumus deskriptif.
b. Uji reliabilitas instrumen (angket) menunjukkan bahwa instrumen yang akan digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus ICC.
F. Teknik Analisis Data
Data penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk mendeskripsikan kevalidan dan kepraktisan. Analisis validitas dan praktikalitas menggunakan skala likert
64 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
berdasarkan lembar validasi dan praktikalitas dalam langkah-langkah:
1. Analisis Data Uji ValiditasData uji validitas bahan ajar bahasa Indonesia berbasis
literasi yang diperoleh dari validator ditabulasi dan hasilnya dipersentasekan mengikuti langkah berikut:
a. Penskoran untuk masing-masing indikator dengan skala 1-5. Dengan 1) Nilai 1 = tidak valid, 2) nilai 2 = kurang valid, 3) nilai 3 = cukup valid, 4) nilai 4 = valid, dan 5) nilai 5 = sangat valid.
b. Menjumlahkan skor dari setiap indikatorc. Pemberian nilai validitas dhitung menggunakan
P =Skor yang diperoleh x 100 % Skor maksimum
Kemudian direfleksikan pada kategori validitas pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Kategori Validitas
No. Persentase Kategori12345
0 –2020 –4040 –6060 –8080 – 100
Tidak validKurang validCukup Valid Valid Sangat valid
Sumber: Riduwan (2005)
Untuk menentukan toleransi perbedaan hasil validasi dari validator digunakan teknik pengetesan reliabilitas pengamatan (Arikunto, 2006). Validator bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi ini lebih dari dua orang, maka reliabilitas dinilai dengan menggunakan reliabilitas antar rater dengan menghitung koofisien
65Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
korelasi antar kelas (Interclass Correlation Coeffisient, ICC). Nilai korelasi (ICC) diperoleh dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Widhiarso (2005).
r = Mspeople- Msresidual .
Mspeople + (dfpeople x dfresdual)
Penghitungan nilai ICC dalam mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi menggunakan program SPSS. Interpretasi ICC dapat direfeksikan berdasarkan tabel berikut.
Tabel 4. Interpretasi Indeks ICC
Indeks Keterangan<0, 40 Lemah0,40 – 0,75 Baik > 0,75 Baik sekali
Data tersebut kemudian ditrianggulasi menggunakan data-data kualitataif hasil pengamatan dan wawancara. Data ini digunakan untuk mengetahui tanggapan, kesan, saran, dan masukan yang bisa diperoleh dari responden dan observer setelah proses validasi bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi.
1. Analisis data uji praktikalitasData uji praktikalitas bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi dan perangkat pembelajaran yang diperoleh dari pengguna, ditabulasi, dan hasilnya dipresentasekan mengikuti langkah berikut:
a. Penskoran untuk masing-masing indikator dengan skala 1-5. Dengan: 1) nilai 1 = sangat tidak setuju, 2) nilai 2 = tidak setuju, 3) nilai 3 = netral, 4) nilai 4 = setuju, dan 5) nilai 5 = sangat setuju.
66 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
b. Menjumlahkan skor setiap indikator.Pemberian nilai validitas dihitung menggunakan:
c. P = Skor yang diperoleh x 100 % Skor maksimum
Kemudian direfleksikan pada kategori praktis pada tabel berikut.
Tabel 5. Kategori Praktis
No. Persentase Kategori12345
0 –2020 –4040 –6060 –8080 – 100
Tidak praktisKurang praktisCukup praktis Praktis Sangat prakis
Sumber : Riduwan (2005)
Data tersebut kemudian ditrianggulasi menggunakan data-data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara. Data ini digunakan untuk mengetahui respon, kepuasan, reaksi, dan masukan yang bisa diperoleh dari responden dan observer setelah menggunakan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi dan perangkat pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.
3. Analisis Uji EfektifitasData uji hasil efektivitas berupa hasil belajar peserta didik
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi. Nilai tersebut dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik yang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis literasi. Kedua data tersebut dibandingkan dengan menggunakan SPSS 20 dengan melakukan . uji t-test.
67
A. Bahan Ajar Teks Cerpen Berbasis Literasi Media
“Effective teaching begins with effective planning of instruction”, (Jones & Davis, 2011: 101). Pendapat ini menegaskan pentingnya rancangan dalam pembelajaran termasuk merancang bahan ajar. Bahan ajar betujuan memudahkan siswa untuk mempelajari materi-materi atau informasi yang disampaikan agar dapat dipelajari secara efektif, efisien, dan produktif sehingga mencapai tujuan instruksional secara optimal (Suyono, 2009). Dalam hal ini, yang menjadi penanggungjawab utama adalah guru. Guru hendaknya berupaya secara terus-menerus meningkatkan kemampuannya untuk menjadi guru hebat yang mampu menginspirasi siswa agar mereka terlibat secara aktif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran (Suwandi, 2013). Dengan demikian, siswa
IMPLEMENTASI PRODUK R&D
BAB VII
68 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
akan termotivasi sehingga menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (Muslich, 2010: 160).
Bahan ajar teks cerpen yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini sudah dapat dikatakan memenuhi ciri bahan ajar yang baik, yaitu memenuhi prinsip relevansi (keterkaitan materi dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar), prinsip konsistensi, prinsip kecukupan (materi yang diajarkan cukup memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi yang diajarkan) (Mudlofir, 2011:130). Bahan ajar teks cerpen yang disusun berbasis literasi media dibentuk melalui proses literasi dari cerpen-cerpen yang ada di media dalam pengembangannya. Cerpen-cerpen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar apresiasi cerita pendek tentu saja melalui seleksi kelayakan bahan ajar (Sufanti, 2018). Oleh karena itu, sangat beralasan apabila konten-konten yang ada di media-media komunikasi dan informasi dijadikan basis dalam pengembangan pembelajaran setelah melewati proses literasi. Dengan dijadikannya literasi sebagai basis pengembangan kegiatan pembelajaran, berarti bahan ajar yang dirancang bertumpu pada konten-konten informasi yang telah diakses, dianalisis, dan dievaluasi dalam upaya peningkatan kemampuan berbahasa bagi peserta didik.
Sebagai bahan pengajaran, cerita pendek dapat digunakan untuk berlatih bahasa, memahami bacaan keterampilan, meningkatkan apresiasi estetika dalam pengajaran bahasa (Tarakçioglu & Hatice (2014), pengembangan pribadi dan refleksi, serta pemahaman budaya dan toleransi (Zahra & Mohammed, 2016). Melalui cerpen juga dapat memancing emosi dalam diri, memberitahu berperilaku orang, mereka mengajarkan psikologi manusia (Sufanti, 2018). Bahkan, dengan menganalisis cerita pendek, siswa akan belajar berpikir kritis (Saka, 2014).
69Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Bahan ajar teks cerpen yang disusun berbasis literasi media sosial ini memiliki prinsip yang sama dengan model pembelajaran berbasis teks. Teks memiliki beberapa fitur yaitu komunikatif, memiliki tujuan, terstruktur, dan berorientasi akademis. Fitur-fitur tersebut harus diikuti oleh penulisnya, namun penulisnya juga boleh berkreativitas dalam menulis suatu teks. Dalam membuat suatu teks harus komunikatif, memiliki tujuan, terstruktur, dan berorientasi akademis. Penulis teks juga harus mengikuti aturan teks yang dibuatnya (Lin, 2005).
Pembelajaran berbasis teks telah diadopsi secara luas dalam pembelajaran bahasa di dunia (Yu & Dong, 2009. Pembelajaran berbasis teks menekankan bagaimana untuk mewujudkan tujuan komunikasi nyata dalam teks (Shuhua, 2009). Demikian pula penelitian pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia berbasis literasi, khususnya literasi media sosial seperti facebook sesuai untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Yunus & Salehi (2012) di Malaysia dan Iran yang menyimpulkan bahwa grup di Facebook dapat menguntungkan guru untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Hasil penelitian Schein, Wilson & Keelan (2010) di Kanada juga menunjukkan bahwa banyak hal yang bermanfaat yang disediakan oleh media sosial yang ada.
Penelitian pengembangan ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang telah ada, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Schilder, E., Lockee, B., Saxon, D. P., & Houston, S. (2016) dan Melki, J. (2011). Dua penelitian ini mengupas tentang peran media sosial di kalangan pemuda di negara mereka dan juga meneliti tentang prosedur penilaian untuk mengukur kemampuan literasi di sekolah. Sementara itu, penelitian yang telah dilakukan ini diarahkan kepemanfaatan media informasi yang terhubung dengan internet untuk peningkatan kemampuan literasi peserta didik.
70 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
B. Pemanfaatan Media Sosial untuk Bahan Ajar
Pemanfaatan media sosial yang terhubung langsung dengan internet sangat bermanfaat dan mampu membantu ketercapaian dan mempermudah proses pembelajaran. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Wallace (2004) di Amerika Serikat, Wallaace mengembangkan framework untuk guru dengan menggunakan internet dalam mengajar karena menurut beliau “sebenarnya guru mampu mengefektifkan penggunaan internet untuk proses pembelajaran”.
Kebaruan penelitian ini yaitu literasi dijadikan sarana untuk memperoleh materi ajar yang akan dibahas oleh peserta didik di sekolah. Selain itu, dalam bahan ajar ini dilengkapi dengan QR Code. Dengan QR Code ini siswa bisa langsung mengakses teks cerpen atau teks lainnya yang dicantumkan dalam buku “Cerpen Berbasis Literasi Media”. Siswa dipersilakan membaca cerpen melalui smartphone mereka masing-masing. Dengan demikian minat baca siswa akan lebih meningkat dengan membaca di smartphone dibandingkan membaca di buku ajar.
Saat ini penggunaan QR Code mulai digunakan di beberapa institusi meskipun masih terus berkembang seperti Hongkong Institute of Education (Ramsden, 2008), Bath University (Ramsden, 2008). Tidak hanya dalam pembelajaran, aplikasi QR Code juga telah dimanfaatkan juga baik secara personal ataupun secara administrasi seperti sistem pengamanan (Ridwan et.al., 2010) dan lainnya. Sebab, menambahkan bahwa QR Code memberikan banyak solusi dalam setiap aspek yang ingin dikaji (Narayanan, 2012).
Penggunaan smarthphone dalam proses pembelajaran untuk zaman sekarang ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Smarthphone sudah menjadi suatu kebutuhan dan kesenangan bagi setiap individu, terutama remaja. Badan Pengamat Teknologi Indonesia mengemukakan bahwa 40% remaja mengakses media sosial, seperti
71Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
facebook, saat pelajaran berlangsung (Suwarno, 2009). Ini menandakan bahwa mereka lebih sering online daripada mendengarkan pelajaran yang diterangkan guru mereka. Meskipun penggunaan teknologi tingkat tinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka, sangat sedikit siswa teknologi penggunaan asli digital untuk tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru tidak bisa membendung kenyataan ini. Salah satu solusinya adalah menggiring siswa memanfaatkan smarthphone mereka untuk hal-hal yang bermanfaat. smarthphone juga bisa berfungsi dalam bidang pendidikan terutama dalam proses pembelajaran, baik dalam proses perencanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran serta penilaian pembelajaran dan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar melalui fitur internet (Nikmah, 2013).
Di sisi lain, hasil penelitian Uswatun (2011), menemukan dampak negatif penggunaan smarthphone, yang meliputi: membuat siswa malas belajar, mengganggu konsentrasi belajar siswa, melupakan tugas dan kewajiban, mengganggu perkembangan anak, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku, dan pemborosan. Bahkan, Rahma (2015) banyak menemukan pengaruh negatifnya dari pada pengaruh positifnya dalam penggunaan smarthphone, salah satunya adalah perkembangan bahasa yang buruk.
Media sosial banyak memberi ruang dan mengakomodir bahasa pergaulan anak-anak sekolah, remaja dalam bermedia sosial. Sayangnya, cukup banyak dari kalangan pelajar yang terjebak dalam penggunaan bahasa yang dapat mengakibatkan ‘banalitas intelektual’ dalam aspek kebahasaan. Ini karena budaya literasi mereka belum tumbuh, namun sudah disodori dengan kemudahan akses informasi melalui media sosial (Aminah, 2013).
Tanpa disadari, muncul kreativitas bahasa yang dimiliki oleh remaja dan dapat mempengaruhi kebiasaan berbahasa resmi. Gaya bahasa yang mereka gunakan tidak lagi memperhatikan kesopanan tersebut lambat laun dapat mengubah gaya hidup generasi muda.
72 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Rendrasari (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya penggunaan bahasa prokem pada siswa adalah karena para pengguna ingin dianggap gaul dan tidak ketinggalan zaman. Dalam penelitiannya ditemukan tiga penyebab terjadinya pemakaian bahasa prokem pada siswa, yaitu: (1) faktor pergaulan, (2) faktor gengsi, dan (3) faktor iklan. Kini, banyak kalangan remaja Indonesia yang tampak seolah tidak mengenal etika kesantunan yang semestinya ia tunjukan sebagai hasil dari pendidikan di keluarga, sekolah dan masyarakat (Mislikhah, 2014). Kondisi demikian menjadikan terkikisnya karakter bangsa Indonesia yang sejatinya dikenal dengan bangsa berkarakter santun.
Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia dipelajari untuk menjadikan peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Selain itu, penguasaan berbahasa dengan baik dan benar akan membantu peserta didik dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan kurikulum 2013. Jadi, pemerintah berharap menjadikan bahasa sebagai wahana untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran secara estetis dan logis pada peserta didik.
Dalam need analysis disimpulkan bahwa responden membutuhkan bahan ajar ini. Harapan guru masing-masing siswa memiliki buku sebagai bahan ajar mereka. Selama ini guru masih menggunakan buku paket dari kementerian dan buku dari penerbit. Riyanto dalam penelitiannya yang juga menemukan bahwa guru masih tergantung pada bahan ajar yang menjadi pegangan guru dan cenderung tidak mengubah bahan ajar yang ada. Guru masih cenderung takut dan tidak mau berimprovisasi dengan kesiapan materi bahan ajar dan pembelajaran hasil rancangannya. Guru dalam melakukan pembelajaran di kelas masih sangat bergantung dengan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran (2013:28).
73Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Menurut guru, semakin banyak buku yang dijadikan bahan ajar akan semakin membantu proses pembelajaran. Sebab, banyak terdapat siswa rendah minat membacanya. Padahal, dengan membaca dapat diperoleh berbagai informasi, gagasan, pendapat, pesan dan lain-lain yang disampaikan penulis melalui lambang-lambang grafis yang sudah dikenal (Riyanto (2013:28). Bahkan, diketahui bahwa minat membaca siswa berpengaruh 33% terhadap prestasi belajar siswa (Widyasmoro, 2014). Namun, kemampuan membaca siswa Indonesia di dunia internasional menggambarkan kondisi yang memprihatinkan (Suryaman, 2012). Hasil tes yang dilakukan oleh PIRLS tahun 2011 untuk mengukur hasil membaca teks sastra dan teks informasi hampir pada semua butir belum dapat dijawab dengan sempurna oleh siswa Indonesia. Di dalam PIRLS 2011 ini teks sastra berisi cerita pendek atau episode yang disertai dengan ilustrasi pendukung. Untuk itu, kompetensi akademik peserta didik perlu secara terus-menerus diasah dan dikembangkan. Kunci kompetensi akademik untuk menghasilkan pengetahuan bagi masyarakat informasi saat ini adalah literasi membaca (Delgadova, 2015).
Kesulitan pada materi pelajaran merupakan kesulitan yang paling berpengaruh pada mutu hasil belajar (Basuki et.al., 2017). Ketidakmampuan siswa menguasai materi pelajaran merupakan masalah yang perlu dicari penyelesaiannya, sehingga program pembelajaran bahan ajarnya harus sesuai dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Materi ajar atau bahan ajar bahasa Indonesia secara umum harus disesuaikan pada setiap jenjang pendidikan. Tujuannya agar bahan ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, serta kurikulum yang telah ditentukan (Febriani, 2012). Disamping itu, sebuah bahan ajar yang baik harus mencakup: (1) petunjuk belajar (petunjuk guru dan siswa); (2) kompetensi yang akan dicapai; (3) informasi pendukung; (4) latihan-latihan; (5) petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja (LK); dan (6) evaluasi (Lestari, 2013:3),.
74 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
C. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2o13
Dalam contextual analysis penelitian dan pengembangan ini, bahan ajar diterapkan di sekolah dirancang berdasarkan kurikulum dan silabus serta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar. Kurikulum 2013 menekankan kompetensi anak dalam membaca dan menulis melalui pembelajaran berbasis teks, kurikulum ini tidak mematok target minimal buku yang harus dibaca siswa. Dilihat dari sisi ini, tampak kegamangan Kurikulum 2013. Secara berpikir sederhana pun tentu dapat dipahami bahwa jika para siswa dituntut mampu memproduksi tulisan, maka tentu mereka harus banyak membaca. Melalui aktivitas banyak membaca para siswa akan mendapat banyak inspirasi, memiliki gagasan dan wawasan yang kaya, dan sekaligus memperoleh banyak model tulisan yang baik.
Kurikulum 2013 lebih menekankan pada kata kerja operasional, seperti memahami, membandingkan, mengevaluasi, menyunting, dan mengonversi. Adapun yang dikenai kata kerja operasional tersebut adalah cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan film/drama. Kondisi tersebut akan menuntut guru untuk melakukan pembelajaran dalam bentuk memahami, membandingkan, mengevaluasi, menyunting, dan mengonversi cerita pendek; memahami, membandingkan, mengevaluasi, menyunting, dan mengonversi pantun; memahami, membandingkan, mengevaluasi, menyunting, dan mengonversi drama; dan lain sebagainya. Akan tetapi, struktur tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa guru dituntut untuk melakukan pembelajaran berupa memahami, membandingkan, mengevaluasi, menyunting, dan mengonversi cerpen, drama, atau puisi.
Struktur tersebut tidak sejalan dengan prinsip apresiasi sastra. Prinsip pembelajaran apresiasi sastra menitik beratkan bahwa siswa harus mampu mengapresiasi karya sastra. Akan tetapi, struktur
75Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
materi pada Kurikulum 2013 kurang memberikan peluang kepada siswa untuk melakukan sebuah apresiasi. Pembelajaran cerpen pada hakikatnya harus sejalan dengan konsep apresiasi sastra karena pembelajaran merupakan jembatan bagi siswa agar mampu mengapresiasi sebuah karya sastra (Svarcova, 2010). Apabila konsep pembelajaran tidak sejalan dengan konsep inti, bisa dipastikan tujuan akhir dari sebuah pembelajaran tersebut akan bias.
Pada kurikulum 2013, pelajaran bahasa Indonesia dinobatkan sebagai penghela dan pembawa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan konsep keilmuan dan seperangkat kompetensi yang seharusnya dimiliki dan dikembangkan dalam pembelajaran. Bahasa Indonesia digunakan untuk memahami tahapan yang harus dilakukan peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya.
Cerpen menjadi materi dalam pengembangan model pembelajaran ini. Teguh, dkk (2014: 2) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran menulis teks cerita pendek menjadi sangat penting sebab dapat merangsang siswa menjadi gemar menulis dan tentunya akan meningkatkan kemampuan siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Selain itu, kegiatan menulis cerita pendek akan dapat menumbuhkembangkan kecintaan siswa pada sastra sehingga apresiasi siswa terhadap sastra akan meningkat.
“Since it is short, and aims at giving a ‘single effect’, there is usually one plot, a few characters; there is no detailed description of setting. So, it is easy for the students to follow the story line of the work. Therefore, it seems to be the most suitable one to help students enhance the four skills—listening, speaking, reading and writing” (Ceylan, 2016).
“Karena singkat, dan bertujuan memberi ‘efek tunggal’, biasanya ada satu plot, beberapa karakter; Tidak ada deskripsi pengaturan yang rinci. Jadi, mudah bagi para siswa untuk mengikuti alur ceritanya. Oleh karena itu, tampaknya yang paling sesuai untuk membantu siswa meningkatkan empat keterampilan-mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis” (Ceylan, 2016).
76 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Siswa yang kesulitan dalam mengisahkan suatu kejadian dalam rangkaian paragraf akan membentuk alur cerita yang tidak menarik. Siswa sulit menemukan ide-ide, gagasan, perasaan, dan pikiran tentang apa yang akan ditulisnya. Hal itu disebabkan oleh kurangnya siswa dalam membaca (Tivana, 2015). Siswa dalam menulis masih banyak kesalahan EYD, pemakaian konjungsi, dan kalimat serta pemilihan diksi yang tepat dalam menulis cerpen.
Keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan sangat diperlukan karena bahan ajar merupakan sarana komunikasi siswa dalam pembelajaran. Sebagai sarana komunikasi, materi dan redaksi sajian yang terdapat dalam bahan ajar harus bisa dipahami siswa. Indikator yang mendukung aspek keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan dalam bahan ajar adalah komunikatif, dialogis dan interaktif, lugas, keruntutan alur pikir, koherensi, kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar, dan penggunaan istilah dan simbol atau lambang yang sesuai dengan perkembangan siswa (Muslich, 2010: 168). Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya (Daryanto, 2013: 11).
Bahan ajar telah dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan prosedur-prosedur penelitian dan pengembangan. Berdasarkan tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar dalam bentuk buku ajar ini sudah valid, praktis, dan efektif untuk diimplementasikan di kelas. Perhitungan kevalidan, kepraktisan, dan keefektivan buku ajar sesuai dengan prosedur perhitungan baik berdasarkan angket, instrumen, maupun secara statistik seperti yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya.
77Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
DAFTAR RUJUKANAhmad, Z.A. (2012). Perencanaan Pembelajaran. Yogyakarta: Pedagogia.Akbar, S. dan Hadi S. (2010). Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran:
Ilmu Pengetahuan Sosial. Yogyakarta: Cipta Media.Alwasilah, A. Chaedar. (2004). Pendidikan Berpikir Kritis. Makalah
pada KONASPI VI, Surabaya 5-9 Oktober.Alwi, H.. et. all. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas
dan Balai Pustaka.Andi, P. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: A-Ruzz Media.Arikunto, 2006). Arsyad, A. (2011). Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafundo
Persada.Badan Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.Baran, S.J. (2004). Introduction to Mass Communication: Media Literacy
and Culture. Third Edition. McGraw and Hill Inc. USA.Belawati, T. (2003). Pengembangan Bahan Ajar. Jakarta: Universitas
Terbuka.Branch, R.M. (2009). Instructional Design. The ADDIE Approach.
Departmen od Educational Psychology and Instructional Technology University of Ggeorgia. USA : Spinger.
Brown, J.A. (1998). Media Literacy Perspectives. Journal of Communication, 48 (1) 44-57.
Cayari, C. (2011). The Youtube Effect: How YouTube Has Provided New Ways to Consume. Create, and Share Music. 12/6, 1-30.
Ceylan, N.O. (2016). Using Short Stories in Reading Skills Class. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 232, 14 October 2016, Pages 311-315. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.027.
Daryanto dan Aris Dwicahyono. (2014). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Silabus, RPP. PHB. Bahan Ajar. Yogyakarta: Gava
78 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Media.Delgadova, E. (2015). Reading literacy as one of the most significant
academic competencies for the university students, ProcediaSocial and Behavioral Sciences 178 ( 2015 ) 48 – 53.
Derewianka, B. (2003). Trends and Issues in Genre Based Approaches. RELC Journal, (Online), Vol. 34, No. II, (http://agusdepe.staff.uns.ac.id/files/2011/09/trendsnissuesingenrebasedapproach.pdf, diakses tanggal 28 April 2018).
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2008. Seri Bahan Bimbingan Teknis Implementasi KTSP SMK (Teknik Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Silabus Sekolah Menengah Kejuruan). Dekdiknas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMK
Djamarah, S.B. (2002). Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta.Fadillah. (2014). Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta: Ar—Ruzz
Media.Farida, R. (2008). Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi
Aksara.Fathurrohman, P. dan M. Sobry S. (2007). Strategi Belajar Mengajar
Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami. Bandung: Refika Aditama.
Ferrington, G. (2006). What is Media Literacy? International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, I (4), 10-15.
Gredler, M.E. (2011). Learning and Instruction: Teori dan Aplikas, 6th. Ed. Jakarta: Kencana.
Hamalik, O. (2003). Perencanaa Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta: Bumi Aksara.
Harijanto, M. (2007). Pengembangan Bahan Ajar untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Program Pendidikan Pembelajaran Sekolah Dasar. Dalam Didaktika. [online], Vo;l. 2 (1), 11 Halaman. Tersedian: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%
79Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
2Futsurabaya.files.wordpress.com%F2010%2F08%2Fharijanto1-pengembangan-bahan-ajar-
Harras, K. A. (2011). “Mengembangkan Potensi Anak melalui Program Literasi Keluarga”, Jurnal Artikulati Vol. 10 No. 1.
Hartoko, D. dan Rahmanto. (1986). Pemandu di Dunia Sastra. Yogyakarta: Kanisius.
Hasyim, A.N. (2016). “Pengertian Layanan” (Online), (www.damandiri.or.id/file/nurhasyimadunairbab2. Pdf. Di akses 20 Desember 2016.
Hergenhahn, B.R. dan Matthew H. O. (2008). Theories of Learning. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hobbs, R. (1996). Media Literacy, Media Activism. Telemedium, the journal of Media Literacy 42 (3).
Iriantara, Y. (2006). Media Relations Konsep, Pendekatan dan Praktik. Cetakan Pertama. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Kurniasih, I. (2014). Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013. Surabaya: Kata Pena.
Iriantara, Y. (2006). Media Relations Konsep, Pendekatan dan Praktik. Cetakan Pertama. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Iskandarwassid dan Sunendar, D. (2009). Strategi Pembelajaran Bahasa. 2009. Bandung: Remaja Rosdakarya dan Universitas Negeri Padang.
Jihad, A. dan Abdul H. (2009). Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi Pressindo.
Kellner, D., & Sahre, J. (2005). Toward Critical Media Literacy: Core Concepts, Debates, Organizations, and Polcy. Discourse: Studies in the Culture Politics of Education, 26 (3), 369-386.
Koesnandar. (2008). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web. Tersedia: http://www/teknologipendidikan.net/2008/02/12/pengembangan-bahan-belajar-berbasis-web/[6 November 2012]
Lestari, I. (2013). Pembelajaran Bahan Ajar Berbasis Kompetensi; Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Padang” Akademia Permata.
80 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Lin, L.W. dan Meitzener, S. (2005). Would Yuy do it Again? Relationship Skills Gained in a Long-Distance Relationship. College Student Journal. Lincoln: Vol. 39, Iss,1: pg 192, 9 pgs.
Mahsun, MS. (2014). Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Majid, A. (2012). Perencanaan Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
____________. (2007). Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
____________. (2008). Perencanaan Pembelajaran (mengembangkan Standar Kompetensi Guru). Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Mislikhah, ST. (2014). Kesantunan Berbahasa. AR-RANIRY: INTERNATIONAL Journal of Islamic Studies 1(2), 285 -296.
Muchith, S. (2011). Pengembangan Kurikulum. Kudus: Nora Media Interprise.
Mudlofir, A. (2011). Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rahagrafindo Persada.
Mulyasa, E. (2006). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Muslich, M. (2010). Text Book Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian Buku Teks. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Narayanan, A. S. (2012). QR code and security solution. International Journal of Computer Science and Telecommunications, 3(7), 69–71.
Nasar. (2006). Merancang Pembelajaran Aktif dan Kontekstual Berdasarkan “SISKO” 2006. Jakarta: Grammedia Widiasarana Indonesia.
Nasirudin, S. (2011). Teknologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.Nikmah, Astin. (2013). “Dampak Penggunaan Handphone Terhadap
Prestasi Siswa”, E- Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya, (Vol V,No. 5), hlm. 2.
Nunan, D. (1997). Language Teaching Methodology A Textbook for
81Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Teachers. Cambridge : Cambridge University Press.Paula Jones dan Rita Davis. (2011). Instructional Design Methods
Integrating Instructional Technology, New York, Hershey: Information Science Reference, 2011
Potter, J.W. (2004). Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach. London: Sage.
Prastowo, A. (2013). Pengembangan Bahan Ajar Tematik-Panduan Lengkap Aplikatif. Yogyakrta: Diva Press.
____________. (2011). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Jogjakarta: DIVA Press.
____________. (2012). Pengembangan Sumber Ajar. Jogjakarta: Pedagogia.Pribadi, B.A. (2010). Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian
Rakyat.Punaji, S. (2013). Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan.
Jakarta: Kencana.Rahman, M. dan Sofan A. (2013). Strategi dan Desain Pengembangan
Sistem Pembelajaran. Jakarta: Prestasi Pustaka.Rahmi. A. (2013). Pengenalan Literasi Media pada Anak Usia Sekolah
Dasar. SAWWA, 8 (2), 261-275.Ramsden, A. (2008). The use of or codesin education: A getting started
guide for academics. University of Bath. Bath-United Kingdom.Riduwan. (2012a). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.
Bandung: Alfabeta.Ridwan, F. Z., Santoso, H., & Agung, W.P. (2010). Mengamankan
single identity number (SIN) menggunakan QR code dan sidik jari. Nternet Working Indonesia Journal, 2(2), 17–20.
Riyanto, A. (2013). “Pengembangan Buku Pengayaan Keterampilan Membaca Bahasa Indonesia yang Bermuatan Nilai Kewirausahaan”. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Rubin, A. (1998). Media Literacy: Editor’s Note. Journal of Communication, 48 (1), 3-4.
Saka, F. Özlem. (2014). Short stories in English language teaching.
82 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 1 (4), 278-288.
Sandra & Donna. (2015). Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta : Kencana.
Sanjaya, W. (2010). Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana.
Sardiman, A.M. (2007). Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Schilder, E., Lockee, B., Saxon, D. P., & Houston, S. (2016) dan Melki, J. (2011)
Shuhua, T. (2009). Integrating Cooperative Learning into Genre Based Teaching of EFL Writing. CELEA Journal Bimonthly, (Online), Vol. 32, No. I, (http://www.celea.org.cn/teic/83/83-99.pdf, diakses tanggal 22 Juni 2016).
Silverblat. (1995). Media Literacy, keys to Interpretting Media Massages. Westport: Praeger.
Slavin, R.E. (2011). Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik, Edisi Kesembilan, Jilid 1. Alih Bahasa Marianto Samosir. Jakarta: PT Indeks.
Subadriyah, dkk. (2013). Penerapan Model Pembelajaran Literasi Dalam Peningkatan Membaca Kalimat Dengan Aksara Jawa Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kenoyojayan Tahun Ajaran 2012/2013. FKIP: PGSD Universitas Sebelas Maret.Takdir, 2012: ).
Sufanti, M. (2018). Pemilihan Cerita Pendek Sebagai Materi Ajar Pembelajaran Sastra oleh Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sma di Surakarta. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 19, No. 1, 10-19.
Suherman, H. E. dkk. (2003). Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Suryaman, M. (2012). “Analisis Hasil Belajar Peserta Didik dalam Literasi Membaca melalui Studi Internasional (PIRLS) 2011”. Laporan Penelitian. Jakarta: Puspendik Balitbang Kemdikbud.
83Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Susetyo, B. (2005). Politik Pendidikan Penguasa. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
Suwandi, S. (2013d). “Peran Guru Bahasa Indonesia yang Inspirarif untuk Mewujudkan Peserta Didik Berkarakter” Proceeding Seminar Internasional Pengembangan Peran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Mewujudkan Generasi Berkarakter. Surakarta: PBSI FKIP UNS.
Suyono. (2005). Pembinaan Perilaku Berliterasi Berbasis Kegiatan Ilmiah: Pengembangan Program, Strategi, dan perangkat Pendukungnya untuk SMA. Disertasi. Tidak Diterbitkan. Malang: PPs Universitas Negeri Malang.
Tamburaka, A. (2013). Literasi Media. “Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tarakçioglu, Özlem and Hatice Kübra Tunçarslan. (2014). The Effect of Short Stories on Teaching Vocabulary to Very Young Learners (aged 3-4-year): A Suggested Common Syllabus. Journal of Language and Linguistic Studies, 10 (2), 67-84.
Tarigan. D dan H. G. Tarigan. (2009). Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia. Bandung: Angkasa,
Teguh, dkk. (2014). Pembelajaran Menulis Cerita Cerpen Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Tumijajar. Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya); Mei 2014 FKIP Universitas Lampung.
Tivana, Engla. (2015). Pengaruh Metode Sugestopedia dan Motivasi Belajar Terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2015. STKIP Siliwangi Bandung, 25 November 2015.
Tomlinson, B. (1998). Materials Development in Language Teaching. Cambridge: CUP.
Tompkins, R.S. (1991). The USA of a Spatial Learning Strategy to Enhance Reading Comprehension of Secondary Subject Area Text.
84 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Paper Presented at The Annual Indiana Reading Conference (ERIC DocumentnNo. ED.337752).
Uno, H. B. (2006). Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Uswatun. 2011. Dampak Positif dan Negatif Handphone bagi Pelajar. 1 (1). (Online). (diakses 27 Agustus 2018).
Wallace, J dan Charles Temple. (1994). Un-derstanding Reading Problems: Assessment and Instruction. Fourth Edition. New York: Harper Collins College Publishers.
Widodo, C. S., dan Jasmadi. (2008). Panduan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT. Elex Media Komputhindo.
Widyasmoro, A. (2014). “Pengaruh Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas V SD Di Desa Pagergunung Kabupaten Pemalang Tahun Ajaran 2013/2014”. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
Yu W. and Hailin D. (2009). Applying SF-based Genre Approaches to English Writing Class. International Education Studies Journal, (Online), Vol. 2, No. III, (http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/viewFile/33 26/2992, diakses tanggal 22 Juni 2014).
Yu W. and Hailin D. (2009). Applying SF-based Genre Approaches to English Writing Class. International Education Studies Journal, (Online), Vol. 2, No. III, (http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/viewFile/33 26/2992, diakses tanggal 22 Juni 2014).
Zahra, Nimer A. Abu and Mohammed A. Farrah. (2016). Using Short Stories in the EFL Classroom. IUG Journal of Humanities Research Peer-reviewed Journal of Islamic University-Gaza.Vol 24, No1, 2016, pp 11-42.
85Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
BLURBMenulis tidaklah serumit “mencari jarum di jerami”. Buku ini bisa
diandalkan untuk membantu kamu-kamu yang ingin menulis tapi bingung memulainya dari mana? Tidak hanya untuk Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia saja, buku ini juga bisa diaplikasikan untuk menulis buku ajar mata pelajaran lainnya.
Konsep literasi dan literasi media dipaparkan secara lugas dengan teori-teori yang jelas dan lengkap. Konsep literasi media menjadi dasar dalam pengembangan dalam pembelajaran terutama dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun, untuk pengembangan buku ajar pembelajaran lainnya pun konsep ini bisa diterapkan.
Dalam buku ini, dipaparkan pula tentang landasan untuk menulis buku ajar. Teori-teori pengembangan bahan ajar pun dipaparkan dengan jelas. Tidak hanya itu, metodologi pengembangan ajar dan tahapan-tahapan menyusun hingga memvalidasi bahan ajar pun diuraikan dengan jelas. Di akhir buku juga dipaparkan tentang implikasi buku ajar dalam dunia pendidikan dengan teori-teori yang jelas.
86 Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra
Biodata Penulis
Nurmalina, berprofesi sebagai dosen di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Kuliah Strata 1 di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia pada tahun 2006 dan melanjutkan Strata 2 di bidang yang sama pada tahun 2010. Sempat mengabdi dulu sebagai dosen S2 dan akhirnya memutuskan untuk berburu beasiswa BPPDN pada tahun 2015 dan akhirnya menyelesaikan Strata 3 di Universitas Negeri Padang pada tahun 2020.
Sebagai ibu rumah tangga dengan dua orang putri yang masih balita, masih menyempatkan diri untuk berkarya dalam bentuk tulisan sederhana. Dari awal selalu merasa bahwa menulis merupakan hobi dan wadah untuk berbagi ilmu pengetahuan. Namun, keberanian dan ketekunan menjadi modal untuk keberhasilan dalam menulis. Di tahun 2020 ini buku pertama berhasil ditulis berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.