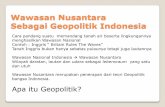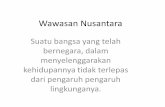SASTRA NUSANTARA
Transcript of SASTRA NUSANTARA
SASTRA NUSANTARAKEANEKARAGAMAN SASTRA BUDAYA INDONESIA
MAKALAH Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Diskusi
pada Mata Kuliah Sastra Nusantara Semester Duayang Diampu oleh Drs. H. M. Nur Fauzan Ahmad, M. A.
Oleh :
Siti Eka Soniawati(13010112130129)
PRODI BAHASA DAN SASTRA INDONESIAFAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGOROSEMARANG2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat
menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan baik.
Makalah ini saya persembahkan kepada :
1. Drs. H. M. Nur Fauzan Ahmad,M.A. selaku dosen
pembimbing mata kuliah Sastra Nusantara.
2. Kedua orangtua saya, bapak dan ibu yang selama ini
telah memberikan biaya kuliah.
3. Teman-teman seperjuangan Sastra Indonesia angakatan
2012.
4. Pembaca yang budiman.
Secara garis besar makalah ini mencakup tentang ragam suku
budaya yang ada di Indonesia. Betapa banyak dan corak suku-suku
budaya di Indonesia. Artinya, ini mencerminkan Indonesia adalah
negeri yang kaya akan warisan budaya. Dilihat dari banyak suku
yang ada, seperti suku Dayak, suku Jawa dengan tembang Macapat,
suku Batak, suku Toraja, suku Bali, suku Minang, dll. Masing-
masing mempunyai ciri khas yang berbeda-beda.
Demikianlah makalah saya. Ibarat pepatah tiada gading yang tak
retak, saya menyadari masih banyak kesalahan baik dalam
penulisan, sistematika, tata bahasa. Oleh karena itu, mohon
kritik dan saran yang membangun guna revisi makalah
selanjutnya. Sedikit atau banyak, mudah-mudahan makalah ini
bermanfaat.
Semarang, 29 Juni 2013
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………………….….
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………...
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah…………………………………………………..
1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………..…….
1.3 Tujuan Masalah ……………………………………………………….…..
Bab II PEMBAHASAN
I. Sastra Melayu ……………………………………………………………..
1.1 Pengertian ………………………………………………………….…..
1.2 Sejarah …………………………………………………………………
1.3 Ciri sastra Melayu ………………………………………………..……
1.4 Pembagian sastra Melayu …………………………………………..…
II. Keanekaragam suku di Indonesia
2.1 Sastra Jawa……………………………………………………………..
2.1.1. Pengertian………………………………………………………..
2.1.2. Sejarah ………………………………………………………..…
2.1.3. Periodisasi………………………………………………………..
2.2 Sastra Minangkabau
2.2.1 Pengertian………………………………………………………
2.2.2 Sejarah …………………………………………………………
2.2.3 Ciri Khas sastra Minangkabau………………………………….
2.2.4 Karya sastra Minangkabau……………………………………...
2.3 Sastra Dayak
2.3.1 Pengertian …………………………………………………..….
2.3.2 Karya sastra Dayak…………………………………………….
2.3.3 Sejarah …………………………………………………………
2.4 Sastra Sunda
2.4.1 Pengertian ……………………………………………………...
2.4.2 Sejarah …………………………………………………………
2.4.3 Karya sastra …………………………………………………....
2.5 Sastra Bugis
2.5.1Pengertian ……………………………………………………...
2.5.2 Sejarah ………………………………………………………...
2.5.3 Karya sastra ………………………………………….……..…
2.6 Sastra Bali
2.6.1Pengertian …………………………………………………..….
2.6.2 Pembagian …………………………………………….………
2.6.3 Periodisasi……………………………………………….…….
2.6.4 Tokoh sastra Bali ………………………………………..…….
2.7 Sastra Batak
2.7.1 Pengertian
…......................................................
........................
2.7.2 Karya
Sastra.................................................
..............................
Bab III PENUTUP
3.1 Kesimpulan ……………………………………………………….…………
3.2 Saran ………………………………………………………………..……….
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berkaitan dengan Sastra Nusantara sebagai salah satu mata
kuliah yang khususnya mempelajari seluk beluk kesusastraan
tidak akan lepas dari budaya sekitar. Kebudayaan adalah salah
satu yang dijadikan objek penelitian yang nanti akan
dikembangkan kemudian dipelajari secara mendalam. Lepas dari
masalah tersebut, Sastra Nusantra yang berarti adalah semua
hasil sastra/kebudayaan yang berada di Indonesia baik dari
Sabang sampai Merauke merupakan salah satu hal yang wajib kita
ketahui dan pelajari. Sebenarnya, Indonesia adalah negeri yang
kaya. Kaya akan tradisi dan budaya. 33 Provinsi di Indonesia
mempunyai corak dan cirri khas yang berbeda-beda, itu
menunjukkan betapa kaya Indonesia akan budaya. Corak dan budaya
dari masing-masing daerah pun berbeda, itu menunjukkan bahwa
negeri kita berhias dengan warisan budaya. Hal yang mudah saja,
ada banyak suku di Indonesia serta budaya-budaya yang menjadi
cirri khas masing-masing daerah.
Sehubungan dengan itu, keanekaragaman sastra di Indonesia
seperti ada sastra Jawa, sastra Batak, sastra Dayak, sastra
Bali, , sastra Bugis, dll. Hal itu merupakan sebagian kecil
kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun perlu diketahui, dengan
adanya berbagai macam suku di Indonesia tidak akan memecahkan
ras atau membedakan antara suku satu dengan suku yang lain.
Bahkan, dengan banyaknya suku di Indonesia sikap dan toleransi
masing-masing daerah semakin harmonis.
Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, seberapa
luas cakupan tentang suku-suku yang diketahui di Indonesia,
saya sebagai penyusun mengkaji dan member judul makalah dengan
“SASTRA NUSANTARA KEANEKARAGAMAN SASTRA DI INDONESIA”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana hakikat Sastra Melayu dengan kebudayaan yang ada
khususnya suku-suku di Indonesia?
2. Apa saja ragam sastra yang ada di Indonesia?
3. Apa kesimpulan/ manfaat dari pembelajaran sastra Nusantara
berkaitan dengan keanekaragaman sastra di Indonesia?
C. Tujuan
1. Menjelaskan hakikat sastra Nusantara dengan kebudayaan
yang ada khususnya suku-suku di Indonesia.
2. Menjelaskan ragam sastra yang ada di Indonesia.
3. Menjelaskan kesimpulan/manfaat dari pembelajaran sastra
Nusantara berkaitan dengan keanekaragaman suku di
Indonesia.
BAB IIPEMBAHASAN
I. SASTRA MELAYU
I.1 PENGERTIAN
Sastra Melayu Klasik lama adalah sastra yang
berbentuk lisan atau sastra melayu yang tercipta dari
suatu ujaran atau ucapansastra yang hidup dan berkembang
di daerah Melayu pada masa sebelum dan sesudah Islam
hingga mendekati tahun 1920-an di masa balai pustaka. Masa
sesudah Islam merupakan zaman dimana sastra Melayu
berkembang begitu pesat karena pada masa itu banyak tokoh
Islam yang mengembangkan sastra Melayu.(Agepe. 2013.
“Sastra Melayu Klasik”. Dalam alamat website http://agepe-
lesson.blogspot.com)
I.2 Sejarah
Sastra melayu lama masuk ke Indonesia bersamaan dengan
masuknya agama Islam pada abad ke-13. Peninggalan sastra
Melayu lama terlihat pada batu nisan seorang muslim di
Minye Tujuh, Aceh. Sastra Melayu berkembang di lingkungan
masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau
dan daerah Sumatera lainnya. Karya sastra pertama yang
tebit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair. Catatan
tertulis pertama dalam bahasa Melayu kuna berasal dari
abad ke-7 Masehi, dan tercantum pada beberapa prasasti
peninggalan Kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera
dan wangsa Syailendra di beberapa tempat di Jawa Tengah.
Tulisan ini menggunakan aksara Pallawa. Selanjutnya,
bukti-bukti tertulis bermunculan di berbagai tempat,
meskipun dokumen terbanyak kebanyakan mulai berasal dari
abad ke-18.(Agepe. 2013.”Sastra Melayu Klasik”. Dalam almat
website http://agepe-lesson.blogspot.com)
I.3 Ciri-ciri sastra Melayu
1)Timbul karena adat dan kepercayaan masyarakat.2)Merupakan milik bersama masyarakat.3)Bersifat istana sentris, maksudnya ceritanya berkisarpada lingkungan istana.4)Disebarkan secara lisan.5)Banyak bahasa klise, yaitu bahasa yang bentuknyatetap.6)Bentuk: puisi terikat: Pantun, syair, mantra, bidal,seloka, gurindam.7)Menggunakan Bahasa: arab Melayu, Melayu tradisional,daerah.8)Dipengaruhi: Kehidupan tradisi, kesetiaan terhadapadat istiadat.9)Sifat masyarakat: statis, perubahan sangat lambat.
(Jayanti :2012).
I.4 Pembagian sastra Melayu
Beberapa pembagian Sastra Indonesia Lama adalah sebagai
berikut :
A. Berdasarkan bentuknya, sastra lama dibagi menjadi dua,
yaitu :
1. Prosa lama
Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat
pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Karya sastra
prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan,
disebabkan karena belum dikenalnya bentuk tulisan. Setelah
agama dan kebudayaan Islam masuk ke indonesia, masyarakat
menjadi akrab dengan tulisan.
(agsuyoto.files.wordpress.com/2008/03/sastra-melayu-
klasik.doc).
2. Puisi Lama
Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-
aturan. Aturan- aturan itu antara lain jumlah kata dalam 1
baris, jumlah baris dalam 1 bait, persajakan, banyak suku
kata tiap baris, irama.
(agsuyoto.files.wordpress.com/2008/03/sastra-melayu-
klasik.doc).
B. berdasarkan isinya, sastra lama dibedakan menjadi tiga,
yaitu :
1. Sastra Sejarah
Sastra yang berkaitan tentang sejarah/mengkaji
sejarah. Hasil sastra berisi sejarah seperti Hikayat
Aceh, Hikayat Banjar, Hikayat Raja Pasai.
(http://myindoliterature.blogspot.com/2011/sastra-
sejarah,html).
2. Sastra Undang-Undang
Yang dimaksud dengan undang-undang dalam sastraundang-undang bukan seperti dalam bahasa Inggris yangdisebut law, tapi adat kebiasaan yang dipakai sejakzaman dahulu secara turun-temurun yang biasadisebut customary law. (Djamaris, dkk. 1981:3).
3. Sastra petunjuk Bagi Raja atau Penguasa
C. Berdasarkan pengaruh asing, Sastra Indonesia Lama
dibedakan menjadi tiga
1. Sastra Indonesia Asli
Karya sastra yang hidup dan berkembang secara turun-
temurun dari generasi-kegerasi berikutnya.Karya
sastra yang hidup di kalangan manyarakat menjadi
milik bersama, bikan milik perorangan.Yang Termasuk
Sastra Melayu Asli: kepercayaan, pandangan hidup,
adat istiadat, peribahasa, teka-teki, pantun..
(http://myindoliterature.blogspot.com/2011/10/sastra-
lama.html).
2. Sastra Indonesia Lama Pengaruh Hindu
Sastra yang diengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Seperti
Kitab Ramayana, Bharatayudha dan Pancatantra.
(http://myindoliterature.blogspot.com/2011/10/sastra-
lama-pengaruh-hindu.html).
3. Sastra Indonesia Lama Pengaruh Islam
Sastra yang dipengaruhi oleh pengaruh agama Islam.
Jenis Karya Sastra dengan Pengarh Islam seperti kisah
tentang para Nabi, hikayat tentang Nabi, dongeng dan
legenda Islam.
(agsuyoto.files.wordpress.com/2008/03/sastra-melayu-
klasik.doc)
II. KEANEKARAGAMAN SASTRA NUSANTARA DI INDONESIA
1. SASTRA JAWA
1.1 Pengertian
Sastra yang banyak kaitan degan masyarakat Jawa.
1.2 Sejarah
Wikipedia
Abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi, dimulai
dengan Prasasti Sukabumi. Karya sastra ini ditulis
baik dalam bentuk prosa (gancaran)
maupun puisi (kakawin). Karya-karya ini mencakup
genre seperti sajak wiracarita, undang-undang
hukum, kronik (babad), dan kitab-kitab keagamaan.
Sastra Jawa Kuno diwariskan dalam
bentuk manuskrip dan prasasti. Manuskrip-manuskrip
yang memuat teks Jawa Kuno jumlahnya sampai ribuan
sementara prasasti-prasasti ada puluhan dan bahkan
ratusan jumlahnya. Meski di sini harus diberi
catatan bahwa tidak semua prasasti memuat teks
kesusastraan.Penelitian ilmiah mengenai sastra
Jawa Kuno mulai berkembang pada abad ke-19 awal
dan mulanya dirintis oleh Stamford Raffles,
Gubernur-Jenderal dari Britania Raya yang
memerintah di pulau Jawa. Selain sebagai seorang
negarawan beliau juga tertarik dengan kebudayaan
setempat. Bersama asistennya, Kolonel Colin
Mackenzie beliau mengumpulkan dan meneliti naskah-
naskah Jawa Kuno.
1.3 Periodisasi
1. Sastra Jawa kuno
sastra dalam bahasa Jawa sebelum masuknya pengaruh
Islamatau pembagian yang lebih halus lagi adalah
sastra Jawa yang terlama. Jadi merupakan sastra Jawa
sebelum masa sastra Jawa Pertengahan.
Daftar sastra Jawa kuno dalam bentuk prosa :
a. Candakarana
b. Sang Hayng Kamahayanikan
c. Adiparwa
d. Sabhaparwa
e. Uttarakanda
(R. Ng. Poerbatjaraka dan Tardjan Hadidjaja.
1952. Kepustakaan Djawa. Djakarta/Amsterdam:
Djambatan.Asmawasanaparwa).
Daftar sastra Jawa juno dalam bentuk puisi
(kakawin) :
a. Kakawin tertua Jawa
b. Kakawin Ramayan
c. Kakawin Aarjunawiwaha
d. Kakawin Kresnayana
e. Kakawin Sumanasantaka
f. Kakawin Smaradahana
g. Kakawin Bhomakawya
h. Kakawin Gatotkacasraya
(R. Ng. Poerbatjaraka dan Tardjan Hadidjaja.
1952. Kepustakaan Djawa. Djakarta/Amsterdam:
Djambatan.Asmawasanaparwa).
2. Sastra Jawa Pertengahan
Sastra Jawa Pertengahan muncul
di Kerajaan Majapahit, mulai dari abad ke-13 sampai
kira-kira abad ke-16. Setelah ini, sastra Jawa
Tengahan diteruskan di Bali menjadi Sastra Jawa-
Bali.Pada masa ini muncul karya-karya puisi yang
berdasarkan metrum Jawa atau Indonesia asli.
Daftar karya sastra Jawa Tengahan yaitu :
a. Tantu Panggelaran
b. Pararato
c. Calon Arang
d. Tantri Kamandaka
e. Korawasrama
Daftar karya sastra Jawa Tengahan puisi yaitu :
a. Kakawin Dewaruci
b. Kidung Sudamala
c. Kidung Subrata
d. Kidung Sunda
e. Kidung Panji Angreni
f. Kidung Sri Tanjung
(R. Ng. Poerbatjaraka dan Tardjan Hadidjaja.
1952. Kepustakaan Djawa. Djakarta/Amsterdam:
Djambatan.Asmawasanaparwa).
3. Sastra Jawa Baru
Sastra Jawa baru kuranglebih muncul setelah
masyarakat agama Islam di pulau Jawa dan Demak antara
abad kelimabelas dan keenambelas Masehi. Dengan
masuknya agama Islam, orang Jawa mendapatkan ilham
baru dalam menulis karya mereka. Maka, pada masa-masa
awal, zaman Sastra Jawa Baru, banyak pula digubah
karya-karya sastra mengenai agama Islam. Suluk Malang
Sumirang adalah salah satu yang terpenting.
Daftar Karya Sastra Jawa Baru masa Islam :
a. Suluk Wujil
b. Suluk Malang Sumirang
c. Serat Nitisruti
d. Serat Nitipraja
e. Serat Sewaka
f. Serat Menak
g. Serat Yusup
h. Serat Rengganis
i. Serat Manik Maya
j. Serat Ambiya
k. Serat Kandha
4. Sastra Jawa Modern
Sastra Jawa Modern muncul setelah pengaruh
penjajah Belanda dan semakin terasa di
Pulau Jawa sejak abad kesembilan belas Masehi.
Para cendekiawan Belanda
memberi saran para pujangga Jawa untuk menulis
cerita atau kisah mirip orang Barat dan tidak
selalu berdasarkan mitologi, ceritawayang, dan
sebagainya. Maka, lalu
muncullah karya sastra seperti di Dunia
Barat; esai, roman, novel, dan
sebagainya. Genre yang cukup populer adalah
tentangperjalanan. Gaya bahasa pada masa ini masih
mirip dengan Bahasa Jawa Baru. Perbedaan utamanya
ialah semakin banyak digunakannya kata-
kata Melayu, dan juga kata-kata Belanda.Pada masa
ini (tahun 1839, oleh Taco Roorda) juga
diciptakan huruf cetak berdasarkan aksara
Jawa gaya Surakarta untuk Bahasa Jawa, yang
kemudian menjadi standar di pulau Jawa.
Daftar karya sastra :
a. Lelampahaning Purwalelana , Raden Mas
Purwalelana (jeneng sesinglon) 1875-1880
b. Rangsang Tuban , Padmasoesastra, 1913
c. Ratu , Krishna Mihardja, 1995
d. Tunggak-Tunggak Jati , Esmiet
e. Lelakone Si lan Man , Suparto Brata, 2004
f. Pagelaran , J. F. X. Hoery
g. Banjire Wis Surut , J. F. X. Hoery
2. 2 SASTRA MINANGKABAU
2.2.1 Pengertian
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas :
Sastra Minangkabau adalah sastra yang hidup dan
dipelihara dalam masyarakat Minagkabau, baik lisan
maupun tulisan, adapun sastra lisan yang masih hidup
dalam masyarakat Minangkabau adalah jenis kaba dan
dendang.
2.2.2 Sejarah
Karya sastra Minangkabu dihasilkan antara 1870-1972
yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera
seperti Langkat, Tapnuli, Minagkabau dan daerah
Sumatera lainnya. Orang Tionghoa dan masyarakat
Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 1870.
(http://www.scribd.com/doc/53959412/Karya-sastra-
Minangkabau).
2.2.3 Ciri khas sastra Minangkabau
a. Menggunakan bahasa Minagkabau
b. Berlatarbelakang budaya Minangkabau
c. Berbicara tentang manusia dan kemanusiaan
Miangkabau
d. Diwarnai oleh kesenian Minangkabau
(http://www.minangforum.com/Thread-Karya-Sastra-
Minangkabau).
2.2.4 Karya sastra Minangkabau
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia
bebas
a. Kaba
Kaba adalah cerita yang disampaikan oleh tukang
kaba dengan iringan gesekan rebab. Kekuatan
sastra kaba ini sangat ditentukan kemampuan
tukang kaba. Jenis sastra kaba tersebut
misalnyaKaba Cindua Mato, Kaba Anggun Nan
Tongga, Kaba Lareh Simawang, Kaba Rancak
Dilabuah, Kaba Gadih Basanai, Kaba Malin
Deman, Kaba Rambun Pamenan. di dalam kaba
(cerita) tukang kaba tidak hanya menyampaikan
bahan berbentuk prosa ssaja seperti contoh di
atas, namun tukang kaba juga menyampaikan bahan
cerita yang bukan cerita dengan bentuk seperti
petuah adat dan nasihat seperti halnya gurindam.
b. Dendang
Dendang adalah seni suara yang diiringi oleh
alat musik saluang.
2.3 SASTRA DAYAK
2.3.1 Pengertian
Sastra dayak adalah salah satu kesusatraan pada
ruang lingkup daerah Kalimantan. Salah satu hasil
sastra adalah Karungut.
2.3.2 Karya sastra Dayak
a. Karungut
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Seni ini berupa sastra lisan atau juga bisa
disebut pantun yang dilagukan.Karungut merupakan
karya yang dijunjung masyarakat Dayak sebagai sastra
besar klasik dan merupakan semacam pantun
ataugurindam. Pelantun karungut mengisahkan syair-
syair kebajikan dengan meramu bermacam legenda,
nasihat, teguran, dan peringatan mengenai kehidupan
sehari-hari. Karungut sering dilantunkan pada acara
penyambutan tamu yang dihormati. Salah satu ekspresi
kegembiraan dan kebahagiaan diungkapkan dalam bentuk
Karungut.
Karungut adalah salah satu kesenian tradisional
yang sangat komunikatif, karena pesan-pesan yang
disampaikan berbentuk pantun dalam bahasa daerah
Dayak dan mudah dimengerti penontonnya. Karungut
diiringi alat musik kecapi, bisa pakai band
atau organ. Karungut semacam sastra lisan nusantara
untuk Kalimantan Tengah sama dengan Madihin jika di
Kalimantan Selatan. Sedangkan di Jawa Tengah
disebut Macapat. Dengan kata lain karungut dapat
dikatakan suatu irama lagu daerah Kalimantan Tengah
untuk melagukan syair-syair atau naskah yang bukan
berbentuk syair. Karungut dikenal di sepanjang
jalur sungai Kahayan, Kapuas, Katingan, Rungan
Manuhing dan sebagian jalur sungai Barito.
Karungut merupakan seni khas Kalimantan Tengah
yang mempunyai arti dan makna yang sangat dalam untuk
ritual dan untuk menyampaikan segala sesuatu sesuai
dengan keperluannya. Dahulu karangut dinyanyikan para
ibu untuk menidurkan putra-putrinya. Dewasa ini
karungut dapat ditemui di tempat hajatan perkawinan
maupun khitanan, untuk menyambut tamu penting, untuk
kampanye pilkada dan lain-lain.
2.3.3 Karya sastra Dayak
Beberapan sastra lisan yang ada di daerah ini antara
lain:
a. Bekana merupakan cerita orang tua masa lalu yang
menceritakan dunia khayangan atau Orang Menua
Pangau (dewa-dewi) dalam mitologi Dayak Ibanik:
Iban , Mualang, Kantuk, Desa dan lain-lain.
b. Bejandeh merupakan sejenis bekana tapi objek
ceritanya beda.
c. Nyangahatn, yaitu doa tua pada masyarakat Dayak
Kanayatn.
Pada suku Dayak Uut Danum, sastra lisannya terdiri
dari Kollimoi (jaman kedua), Tahtum (jaman ketiga),
Parung, Kandan dan Kendau. Pada jaman tertua atau
pertama adalah kejadian alam semesta dan umat manusia.
Pada sastra lisan jaman kedua ini adalah tentang
kehidupan manusia Uut Danum di langit. Pada jaman
ketiga adalah tentang cerita kepahlawanan dan
pengayauan suku dayak Uut Danum ketika sudah berada di
bumi, misalnya bagaimana mereka mengayau sepanjang
sungai Kapuas sampai penduduknya tidak tersisa sehingga
dinamakan Kopuas Buhang (Kapuas yang kosong atau
penghuninya habis) lalu mereka mencari sasaran ke
bagian lain pulau Kalimantan yaitu ke arah kalimantan
Tengah dan Timur dan membawa nama-nama daerah di
Kalimantan Barat, sehingga itulah mengapa di Kalimantan
Tengah juga ada sungai bernama sungai Kapuas dan Sungai
Melawi. Tahtum ini jika dilantunkan sesuai aslinya bisa
mencapai belasan malam untuk satu episode, sementara
Tahtum ini terdiri dari ratusan episode. Parung
adalahsastra lisan sewaktu ada pesta adat atau
perkawinan. Kandan adalah bahasa bersastra paling
tinggi dikalangan kelompok suku Uut Danum (Dohoi,
Soravai, Pangin, Siang, Murung dan lain-lain)yang biasa
digunakan untuk menceritakan Kolimoi, Parung, Mohpash
dan lain-lain. Orang yang mempelajari bahasa Kandan ini
harus membayar kepada gurunya. Sekarang bahasa ini
sudah hampir punah dan hanya dikuasai oleh orang-orang
tua.
( http://palingindonesia.com/suku-dayak-kalimantan/).
2.3.4 Sejarah
kepercayaan suku Dayak di Kalimantan Tengah, pada
zaman dahulu manusia diturunkan dari langit
bersamaan palangka bulau (tetek tatum). Pada waktu berada
di bumi, palangka bulau adalah alat untuk menurunkan
manusia dari langit ke bumi oleh Ranying Hatalla langit
atau dewa para petinggi suku Dayak. Maka dari itulah
mulai adanya alunan suara atau tembang-tembang dan
sejak itulah Karungut muncul. Bahasa yang digunakan
dalam Karungut adalah bahasa Sangiang atau
sejenis bahasa Ngaju yang sangat tinggi sastranya
digunakan dalam upacara adat dan berkomunikasi dengan
roh halus. Dalam kehidupan masyarakat Dayak yang
melaksanakan upacara, khususnya upacara adat,
keagamaan, perkawinan, dan syukuran selalu di warnai
dengan kegiatan kesenian seperti tari Manasai
Karungut, Karunya, Tandak Mandau, dan Deder.
2.4 SASTRA SUNDA
2.4.1 Pengertian
Dari wikipedia ensiklopedi bebas
Adalah karya sastra yang mencakup wilayah Jawa
Barat.
2.4.2 Sejarah
Nama Sunda mulai digunakan oleh
raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut
ibukota Kerajaan Tarumanagara yang didirikannya.
Untuk mengembalikan pamor Tarumanagara yang
semakin menurun, pada tahun 670, Tarusbawa,
penguasa Tarumanagara yang ke-13, mengganti nama
Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian
peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh
untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan
Tarusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin
menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima
tuntutan raja Galuh. Akhirnya kawasan Tarumanagara
dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan
Sunda dan Kerajaan Galuh denganSungai
Citarum sebagai batasnya.
2.4.3 Karya sastra Sunda
a. Lutung kasarung
Lutung Kasarung adalah cerita pantun yang
dianggap paling sakral diantara pantun Sunda
yang lain, sehingga jarang sekali ada juru
pantun yang berani menceritakannya.
Cerita pantun Lutung Kasarung bukan hanya
merupakan karya sastra lisan yang luhur dari
masyarakat Sunda. Pantun tersebut mengandung
bagian-bagian yang menyangkut peristiwa sejarah
Sunda, maka pantun Lutung Kasarung memiliki
nilai sejarah. Karena itu, cerita pantun Lutung
Kasarung dianggap sebagai artefak budaya
masyarakat Sunda sekaligus bentuk kebudayaan
Sunda yang paling besar.
(http://mangfirman.wordpress.com/2012/09/06/
puisi-tradisional-sunda/).
b. Sawér
yaitu bentuk karya sastra tradisional Sunda
buhun yang sering digunakan dalam upacara
nyawér. Dalam pelaksanaan sawér atau nyawér
biasanya naskah sawér ditembangkan, dikawihkeun
(dinyanyikan) ataudideklamasikan.
(http://mangfirman.wordpress.com/2012/09/06/
puisi-tradisional-sunda/).
2.5 SASTRA BUGIS
2.5.1 Pengertian
Sastra yang berkembang di wilayah Makasar. Sastra
bugis pada umumnya adalah hasil cipata masyarakat
Bugis.
2.5.2 Sejarah
Dilihat dari tradisi perkemabngan satra Bugis
menempuh dua cara, yaitu tradisi lisan dan tradisi
tulis.
a. Periode awal yang ditandai dengan munculnya
karya sastra bugis yang kemudian disebut karya
sastra galigo. Masa perkembangannya diperkirakan
oleh beberapa pakar secara berbeda. Mattulada,
misalnya memperkirakan antara abad ke-7 hingga
abad ke-10 sezaman dengan perkembangan kerajaan-
kerajaan Hindu di nusantara seperti Sriwijaya dan
Syailendra. Berbeda halnya dengan pendapat
Fakhruddin Ambo Enre yang memperkirakan sekitar
abad ke-14 atau masa perkembangan sastra galigo
diduga sezaman dengan sezaman dengan kerajaan
Malaka dan kerajaan Majapahit yang sebagaimana
yang disebutkan dalam naskah galigo. Dalam periode
ini muncul atau berkembang dua bentuk pustaka
bugis, ada yang tergolong karya sastra yang
disebut tolok dan yang bukan karya sastra yang
disebut lontarak.
b. Periode kedua para pakar menyebutnya zaman
tomanurung atau periode yang ditandai dengan
munculnya sebuah bentuk pustaka bugis yang berbeda
dengan pustaka galgo (sastra). Dalam periode ini
muncul atau berkembang dua bentuk pustaka bugis,
ada yang tergolong karya sastra yang disebut tolok
dan yang bukan karya sastra yang disebut lontarak.
C. Ketika periode lontarak berkembang beberapa
lama, muncul pula bentuk pustaka bugis yang lain
dari kedua bentuk karya sastra yang berkembang
sebelumnya (galigo dan tolok), yakni pau-pau atau
pau-pau rikadong serta pustaka lontarak yang
berbau islmi. Selain itu ada perkembanga baru
sastra bugis dalam bentuk prosa. Pada umumnya,
sastra prosa ini merupakan saduran dari sastra
Melayu kuno atau sastra pars
2.5.3 Bentuk karya Sastra Bugis
Karya sastra Bugis yang berbentuk puisi, yaitu:
a. Elong, dalam pengertian secara harfiah, elong
berarti nyanyian dalam bahasa Bugis. Elong
merupakan puisi yang berupa syair yang
menggambarkan falsafah, petuah serta suasana
pikiran. Elong dalam masyarakat Bugis betul-betul
dinyanyikan atau dilagukan secara lisan. Fungsi
elong sebagi hiburan sangat menonjol
Bentuk-bentuk elongmpugi yaitu:
a) Berdasarkan jumlah larik setiap bait: bait
yang terdiri atas dua larik dan tiga larik.
b) Berdasarkan posisi dan suku katanya:
1) Elong sikai-kai
2) Elong yang berangkai ana sure
3) Elong yang berangkai nama-nama hari
c) Berdasarkan cara penuturannya:
Elong sibali (dinyanyikan secara berbalasan)
d) Berdasrkan isi dan bentuknya:
1) Elong sipaqdio-rio
2) Elong assimiliereng
3) Elong silebbai
4) Elong osong dan aruq
e) Berdasarkan usia:
1) Elong ana-ana
2) Elong to malolo (elong mappadicawa
dan elong sicanring)
3) Elong to matoa (elong pangngajak dan
elong masigala)
4) Elong toto/ nasib (elong peddi dan
elong maruddani)
f) Berdasrkan gaya bahasanya:
1) Elong maliung
2) Elong bawang
b. Cenningrara (mantra) adalah salah satu jenis
puisi lama. Mengandung makna permohonan, permintaan,
atau harapan. Jumlah barisnya tidak tetap, ada yang
berjumlah tiga baris, empat baris, dan bahkan ada yang
lebih dari sepuluh baris. Cenningrara bersifat magis,
memiliki kekuatan gaib dan kesaktian bila diyakini oleh
pemiliknya.
c. Warekkada (ungkapan) adalah suasana yang
indah untuk mengungkapakan sesuatu secara halus.
Warekkda dapat berupa sindiran dan nasihat.
d. Paddennuang (pribahasa) adalah kata atu
seelompok kata yang susunannya tetap yang merupakan
perumpamaan yang bersifat halus.
e. Pappaseng adalah perintah, nasihat, amanat,
dan permintaan yang disampaikan oleh orang lain, atau
merupakan wasiat yang diturunkan secara turun temurun
oleh masyarakat, yang berisikan ajaran moral yang patut
untuk dituruti.
2. Karya sastra Bugis yang berbentuk prosa yaitu:
a. Sastra Lagaligo, merupakan epic terpanjang di
dunia. Isinya sebagian trbesar berbentuk puisi yang
ditulis dalam Bahasa Bugis kuno.
b. Pau-pau rikadong atau merupakan cerita rakayat
masyarakat Bugis. Contohnya: Dewatae, olo-kolo, dan
towaranie.
c. Sastra Tolo, merupakan cerita tentang
kepahlawanan.
(http://lifeiseducation09.blogspot.com/2012/12/sejarah-
sastra-bugis.html).
2.6 SASTRA BALI
2.6.1 Pengertian
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sastra Bali merupakan salah satu khazanah kesusastraan
Nusantara.Seperti kesusastraan umumnya, sastra Bali ada
yang diaktualisasikan dalam bentuk lisan (orality) dan
bentuk tertulis (literary). Menurut katagori
periodisasinya kesusastraan Bali ada yang disebut
Sastra Bali Purwa dan Sastra Bali Anyar. Sastra Bali
Purwa maksudnya adalah Sastra Bali yang diwarisi secara
tradisional dalam bentuk naskah-naskah lama. Sastra
Bali Anyar yaitu karya sastra yang diciptakan pada masa
masyarakat Bali telah mengalami modernisasi. Ada juga
yang menyebut dengan sebutan Sastra Bali Modern.
Bali sebelum dikenal adanya kertas di Bali, umumnya
ditulis di atas daun lontar. Karena ditulis di atas
daun lontar, "buku sastra" ini disebut dengan "lontar".
Memang ada bentuk tertulis lainnya, seperti prasasti,
dengan menggunakan berbagai media seperti batu dan
lempengan tembaga, namun tidak terdapat karya Sastra
Bali ditulis di atas bilah bambu, kulit binatang, kayu,
kulit kayu. Belakangan setelah dikenal kertas, penulis
karya sastra Bali menuliskan karyanya di atas kertas,
bahkan sudah banyak diketik.
Bahasa yang digunakan untuk menulis Sastra Bali ada
tiga jenis yaitu Bahasa Jawa Kuna (Kawi Bali), Bahasa
Jawa Tengahan, Bahasa Bali.
2.6.2 Pembagian sastra Bali
a. Sastra Bali menurut bentuknya
1) Tembang
Di Bali terdapat berbagai jenis tembang
yang mempunyai struktur dan fungsi yang
berbeda-beda. Masyarakat Bali membedakan
seni tembang ini menjadi empat (4)
kelompok yaitu gegendingan, macapat,
palawikia, kakawin.
2) Gancaran
3) Palawikia
b. Sastra Bali menurut jamannya
c. Sastra Bali menurut cara penuturunyaa
d. Sastra Bali menurut bahasanya
2.6.3 Periodisasi sastra Bali
1) periode runtuhnya Kerajaan Gelgel, 1686, hingga
ekspedisi Belanda ke Buleleng, 1849, selama periode ini
bahasa Bali untuk pertama kalinya digunakan pada karya
sastra lokal baru;
(2) periode 1849 sampai dengan 1908: untuk periode
ini, koleksi-koleksi dan publikasi oleh Van Eck dan
Van der Tuuk menunjukkan bukti yang subtantif untuk
perkembangan aksara Bali sampai dengan akhir abad ke-
19 M;
(3) periode 1908 sampai dengan Indonesia merdeka pada
1945, ketika ibukota di Singaraja, di mana pendidikan
berkembang dan terakhir Gedong Kirtya yang memengaruhi
kesusasteraan Bali: selama periode ini penulis-penulis
asal Bali awal menggunakan bahasa Indonesia sudah mulai
aktif sejak 1930-an;
(4) periode 1945 dan seterusnya, ketika ibukota
dipindahkan ke Den Pasar, Universitas Udayana dibangun,
jurnalisme dan penyiaran menyediakan media saluran baru
bagi para penulis, dan penggunaan bahasa Indonesia menjadi
resmi dan menyebar ke seantero Bali.
(http://wacananusantara.org/periodisasi-sastra-bali/)
2.6.4 Tokoh sastra Bali
1. Tokoh dalam mitologi Hindu
Nama: Pratipa
Aksara Dewanagari
Ejaan Sanskerta: Pratīpa
Muncul dalam kitab: Mahabharata; Purana
Gelar: Raja Hastinapura
Asal: Hastinapura, Kerajaan Kuru
Kediaman: Hastinapura
Kasta: Ksatriya
Profesi: Raja
Dinasti: Kuru, keturunan Candra
Pasangan: Sunanda
Anak: Dewapi, Bahlika, Santanu
Dalam mitologi Hindu, Pratipa (Sanskerta:Pratīpa)
adalah nama seorang Raja India dari trah Candrawangsa atau
Dinasti Candra. Ia merupakan seorang keturunan Maharaja
Bharata, dan memerintah Kerajaan Kuru dengan pusat
pemerintahan di Hastinapura. Ia menikah dengan Sunanda,
putri dari Kerajaan Sibi dan memiliki tiga orang putra,
yaitu Dewapi, Santanu, dan Bahlika. Di antara ketiga
putranya tersebut, Santanu yang dinobatkan sebagai raja,
sebab Dewapi memilih untuk menjadi pertapa. Sementara itu,
Bahlika memilih untuk mengembara ke wilayah India Barat.
(http://sastrabali.com/category/sastra-2/mahabharata/
tokoh-mahabharata/page/9).
2.7 Sastra Batak
2.7.1 Pengertian
Sastra Batak adalah sastra masyarakat batak toba yang
memiliki makna yang berkaitan erat dengan kehidupan
yang dialami setiap hari, misalnya: falsafah
pengetahuan (Batak: Habisuhon), kesusilaan (Batak:
Hahormaton), tata aturan hidup (Batak: Adat Dohotuhum)
dan kemasyarakatan (Batak: Parngoluon siganup ari).
Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak
Mandailing, Batak Dairi-Pakpak. Tetapi pendapat ini
sangatlah lemah karena bukti untuk itu tidak kuat.
(http://togapardede.wordpress.com/2012/02/04/sastra-budaya-batak-toba/)
2.7.2 Karya Sastra
1. Pantun (Batak: umpasa): adalah ungkapan yang
berisi permintaan berkat, keturunan yang banyak,
penyertaan dan semua hal yang baik, pemberian dari
Allah.
Umpasa batak toba ini adalah karya sastra dalam
bentuk syair/puisi yang berisi pernyataan restu,
nasehat dan doa bagi orang yang mendengarnya. Umpasa
adat batak toba diperdengarkan dalam upacara adat dan
ditujukan kepada muda-mudi, pasangan pengantin,
upacara menyambut tamu atau berbagai acara lainnya,
serta Kadang kala umpasa ini juga diperdengarkan
dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh: Bintang na rumiris,ombun na sumorop.Sai tubu di hamu anak na riris,boru pe antong torop.
2. Kiasan/persamaan (Batak: tudosan): adalah pepatahyang berisi persamaan dengan ciptaan (alam) dansemua yang ada di sekitar kita, misalnya: pematangsawah yang licin.
3. Nyanyian (Batak: endeende): adalah pepatah yangsering dinyanyikan, diungkapkan oleh orang yangsedang rindu, yang bergembira dan yang sedangsedih.
4. Pepatah (Batak: Umpama). Terdapat beberapa macampepatah yang ada dalam Sastra Batak.
5. Batak Toba
Masyarakat Batak Toba pada umumnya hidup tersebar
atau tinggal di sekitar daerah Sumatera Utara,
khususnya di daerah pulau Samosir dan daerah
Tapanuli.
Namun demikian orang Batak telah tersebar ke
berbagai penjuru dunia ini. Suku Batak Toba menjadi
suku bangsa yang besar. Nenek moyang suku bangsa
Batak diduga berasal dari Hindia Belakang, walau
menurut mitos orang Batak yang beredar di kalangan
masyarakat ini, nenek moyang Orang Batak berasal dari
titisan dewa Si Raja Deang Parujar. Raja Batak
sebagai manusia pertama dikirim oleh dewa ke bumi ini
di gunung Pusuk Buhit, di pulau Samosir. Suku ini
memiliki beberapa persamaan dengan salah satu suku di
daerah Fhilipina. Karena itu diperkirakan bahwa
sebenarnya keturunan Batak Toba berasa dari daerah
Asia bagian Hindia Belakang. Banyak teori dan
pendapat yang berbicara tentang keberadaan suku Batak
Toba.
(http://togapardede.wordpress.com/2012/02/04/sastra-budaya-batak-toba/ )
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Setelah mengetahui hakikat sastra Melayu serta ragam corak
sastra di Indonesia dapat diketahui betapa kaya Indonesia
akan budaya. Maka dari itu, kita harus mempunyai rasa bangga
terhadap sastra-sastra yang ada di Indonesia. Manfaat dari
pembelajaran ini adalah kita sadar akan adanya sastra di
tengah-tengah kita, dengan begitu karya sastra tersebut
tetap utuh.
3.2 Saran
Adanya pembelajaran tentang sastra Nusantara, Melayu, dan
sastra-sastra di daerah lain dapat menambah wawasan serta
manfaat bagi yang membaca. Semoga bermanfaat di kemudian
hari.
DAFTAR PUSTAKA
Agepe. 2013.”Sastra Melayu Klasik”. Dalam almat website http://agepe-lesson.blogspot.com.
Agsuyoto.files.wordpress.com/2008/03/sastra-melayu-
klasik.doc.
http://myindoliterature.blogspot.com/2011/sastra-sejarah,html.
http://myindoliterature.blogspot.com/2011/10/sastra-lama-pengaruh-hindu.html.
http://www.scribd.com/doc/53959412/Karya-sastra-Minangkabau
http://www.minangforum.com/Thread-Karya-Sastra-Minangkabau
http://palingindonesia.com/suku-dayak-kalimantan
http://mangfirman.wordpress.com/2012/09/06/puisi-tradisional-sunda
http://lifeiseducation09.blogspot.com/2012/12/sejarah-sastra-bugis.html
http://sastrabali.com/category/sastra-2/mahabharata/tokoh-mahabharata/page/9
(http://togapardede.wordpress.com/2012/02/04/sastra-budaya-batak-toba/ )
R. Ng. Poerbatjaraka dan Tardjan Hadidjaja.
1952. Kepustakaan Djawa. Djakarta/Amsterdam:
Djambatan.Asmawasanaparwa.