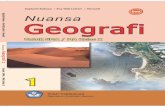perancangan tata letak fasilitas bengkel center of automotive ...
letak geografi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of letak geografi
BAB IPENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Permasalahan sampah merupakan isu yang terus
menjadi perhatian utama, karena keberadaan sampah
termasuk jenis-jenis pencemaran yang dapat digolongkan
dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial
(Bintarto, 1984). Sampah (solid waste) secara umum dapat
diartikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari
aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau
digunakan lagi, baik berbentuk padat atau setengah padat
(Tchobanoglous, 1993).
Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau
dibuang; yang merupakan hasil aktivitas manusia maupun
alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah
diambil unsure atau fungsi utamanya (KuncoroSejati dalam
Ruslinda, 2009). Setiap aktivitas yang dilakukan oleh
manusia selalu menghasilkan sampah dan hamper setiap
hari manusia menghasilkan sampah. Jika sampah tersebut
tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan
berbagai masalah seperti masalah estetika karena bau
yang ditimbulkannya, menjadi vector penyakit dan dapat
menganggu kualitas tanah dan air tanah sekitarnya.
Sampah berasal dari setiap aktivitas manusia yang
terbuang, sehingga potensi penambahan volume sampah
sangat rentan, volume sampah berbanding lurus dengan
kegiatan atau tingkat konsumsi yang kita gunakan setiap
1
harinya, peningkatan jumlah penduduk serta teknologi
yang digunakan. Adanya penambahan jumlah atau volume
sampah tentunya berpengaruh pada penyediaan lahan serta
perlu difikirkan bagaimana mengelolanya, agar tidak
terjadi pencemaran yang diakibatkan sampah.
Realita setiap pengelola kebersihan mengalami
kendala dan masalah dalam member pelayanan yang sesuai
dengan teknis yang diharapkan masyarakat, masih banyak
pecemaran yang diakibatkan pengelolaan yang tidak baik
sehingga terjadi berbagai pencemaran pada saat
pengelolaan sampah ; pewadahan, pengumpulan, pemindahan,
pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir, potensi
dampak yang dihasilkan seperti : (a) perkembangan vector
penyakit, (b) pencemaran udara, (c) pencemaran air, (d)
pencemaran tanah, (e) gangguan estetika, (f) dampak
social, (g) resiko lingkungan. Untuk mencegah terjadinya
gangguan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia maka
perlu dirancang suatu system pengelolaan persampahan
yang baik mulai dari sumber, pengumpulan, transportasi
hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Rouf,2014).
Dalam perancangan system pengelolaan persampahan
suatu daerah diperlukan data mengenai timbulan sampah,
komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan di
daerah yang direncanakan. Karakteristik sampah yang
dianalisis biasanya meliputi karakteristik fisik, kimia
dan biologi. Karakteristik fisik berupa factor pemadatan
dan berat jenis sampah diperlukan untuk menghitung beban
2
massa dan volume total sampah yang harus dikelola, baik
untuk system transportasi maupun di TPA. Karakteristik
kimia berupa analisis perkiraan yang terdiri dari kadar
air (kelembapan), kadar volatile dan kadar abu
diperlukan untuk perencanaan pengolahan sampah.
Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir
pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), hal ini
menjadi beban berat bagi pengelola, yang harus
menyediakan lahan luas, penyediaan fasilitas untuk
meminimalisasi pencemaran. Berdasarkan ketentuan
Peraturan pemerintah (PP) 16/2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum yang berkaitan dengan
perlindungan air baku, mensyaratkan beberapa ketentuan,
antara lain: (a)ketentuan penerapan standard pelayanan
minimal, (b)ketentuan metode pembuangan akhir Sanitary
landfill (Kota besar/Metropolitan) dan Controlled
landfill (kota kecil/sedang), (c)ketentuan zona
penyangga di sekitar TPA, (d)ketentuan melakukan
monitoring leachet, (e)melarang dilaksanakannya open
dumping sampai tahun 2008 (Rouf, 2014).
Persyaratan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah
yang baik sebagai berikut; (a)Lahan terpilih hendaknya
memberikan nilai tertinggi ditinjau dari berbagai aspek,
yaitu aspek kesehatan masyarakat, lingkungan hidup,
biaya, dan sosial–ekonomi, (b)Pemilihan yang dibuat
hendaknya dapat di pertanggung jawabkan, artinya harus
dapat ditunjukkan secara jelas bagaimana dan mengapa
3
suatu lokasi dipilih di antara yang lain (Damanhuri,
1995).
Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
merupakan satu program Nasional di daerah yang berkaitan
dengan penyediaan tempat penampungan akhir sampah. UU No
18 menyatakan pada BAB XVI ketentuan Peralihan pasal 44
bahwa “Pemerintah daerah harus membuat perencanaan
penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang
menggunakan system pembuangan terbuka paling lama 1
tahun terhitung sejak berlakunya Undang– undang ini”.
Hal ini mengakibatkan masing–masing kota atau kabupaten
wajib untuk merencanakan TPA yang berbasis sanitary
landfill atau controlled landfill terhitung 1 tahun
sejak undang-undang ini diberlakukan.
TPA merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk
tempat pengolahan akhir sampah. Pada TPA system sanitary
landfill, sampah yang diolah akan ditimbun merata secara
berlapis, kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah
atau material lain pada setiap akhir hari operasi
(Tchobanolousdkk dalam Mzwar, 1993). Sampah yang
ditimbun di TPA akan mengalami reaksi fisik, kimia dan
biologi secara bersama-sama serta saling berhubungan
melalui proses dekomposisi sampah yang kemudian akan
menghasilkan gas landfill (CO2, CH4, dan H2S) dan cairan
lindi sampah (leachate). Leachate menjadi hal yang
penting diperhatikan dalam pengoperasian dan pengelolaan
TPA karena memiliki sifat mudah bereaksi dengan air,
4
tanah maupun udara sehingga dapat mengakibatkan
pencemaran lingkungan. Sedangkan gas landfill yang
terbentuk akan meningkatkan tekanan internal TPA yang
dapat menyebabkan terjadinya self combustion, keretakan
dan bocornya tanah penutup. Untuk meminimalkan resiko
lingkungan tersebut, maka penentuan lokasi TPA harus
memenuhi syarat-syarat kelayakan lingkungan.
Menurut Rahman dkk. (2008), penentuan lokasi TPA
harus memperhatikan karakteristik lokasi, kondisi social
ekonomi masyarakat, ekologi dan factor penggunaan lahan.
Rahmatiyah (2002) menjelaskan lebih rinci bahwa proses
pemilihan lokasi TPA perlu mempertimbangkan tiga hal
penting, yaitu : (a)pertimbangan operasional; secara
operasional TPA memerlukan lahan yang cukup untuk
menampung segala jenis sampah dan zonesi ketersediaan
lahan harus memperhatikan rencana regional serta aspek
aksesibilitas (keterjangkauan); (b)pertimbangan ekologi;
yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan lokasi TPA
setelah tidak dipergunakan lagi; (c)pertimbangan
topografi, geologi dan hidrologi; lebih mengarah pada
aspek persyaratan fisik lahan, misalnya berdasarkan
relief atau topografi dapat dipilih lokasi-lokasi yang
bebas dari bahayab anjir ataupun erosi dan berdasarkan
aspek hidrologi, lokasi TPA harus berada di wilayah
dengan muka air tanah yang dalam, sehingga lindi sampah
tidak mencemari air tanah.
5
Di Indonesia, penentuan lokasi TPA dilakukan
berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3241-
1994 yang membagi criteria pemilihan lokasi TPA menjadi
tiga, yaitu : (a)kelayakan regional untuk menentukan
zone layak atau zone tidak layak, (b)kelayakan penyisih
untuk menentukan tingkat kesesuaian dari beberapa
alternative lokasi yang telah diperoleh pada penilaian
tahap pertama, dan (c)kelayakan rekomendasi untuk
menetapkan lokasi terbaik dari beberapa alternative
lokasi yang telah diperoleh pada penilaian sebelumnya.
Analisis penentuan lokasi TPA dapat dilakukan
dengan menggunakan SIG dan telah banyak diaplikasikan
(Azizi, 2008). Lunkapis (2004), mendefinisikan SIG
sebagai sistem informasi berbasis komputer yang
digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengintegrasikan,
memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data
bereferensi geografis, sebagai alat bantu pengambilan
keputusan dalam perencanaan dan pengolahan penggunaan
lahan, sumberdaya alam, lingkungan, transportasi,
fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Setiawan
(2010), menjelaskan bahwa aplikasi SIG untuk penentuan
lokasi TPA dilakukan dengan memanfaatkan beberapa
fasilitas yang dimiliki oleh SIG, yaitu perhitungan
(calculating), pengharkatan (scorring), tumpang susun
(overlay), distance modelling (buffer), transformasi,
penyederhanaan (dissolve) dan generalisasi.
6
Kota Makassar merupakan salah satu kota yang
mengalami permasalahan kompleks di bidang persampahan.
Berdasarkan data yang didapatkan di Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, terlihat
adanya peningkatan yang cukup signifikan. Terkait
sistim penanganan sampah di Kota Makassar. Pada
tahun 2010 jumlah timbulan sampah Kota Makassar
mencapai 3.781,23 m³/hari, sedangkan yang
tertangani adalah sebesar: 3.373,42 m³/hari, yakni
hanya 89,21 persen terhadap timbulan. Pada tahun 2011
jumlah timbulan sampah mencapai 3.923,52 m³/hari,
sedangkan jumlah sampah tertangani mencapai 3.520,07
m³/hari, yakni hanya 89,72 persen terhadap timbulan.
Jumlah timbulan sampah per hari dari tahun 1997/1998
hingga tahun 2009 bertambah lebih dari 37%. (Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, 2011). Hingga
saat ini, satu-satunya TPA yang beroprasi di kota
Makassar adalah TPA Amangapa Antang yang telah digunakan
sejak than 1993. Berdasarkan hal di atas maka masalah
persampahan dewasa ini merupakan masalah yang harus di
tangani secara serius dan mendorong peneliti untuk
mengetahui kondisi kelayakan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Sampah Tamangapa, Antang di Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kesesuaian lahan potensial untuk Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Makassar ?
7
2. Bagaimana kelayakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sampah Tamangapa, Antang di Kota Makassar?
C. Tujuan
Tujuan penelitian kesesuaian lahan potensial Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Makassar adalah:
1. Memetakan lokasi potensial Tempat Pengolahan Akhir
(TPA) Sampah di Kota Makassar menggunakan Sistem
Informasi Geografis (SIG).
2. Menganalisis kelayakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sampah Tamangapa, Antang di Kota Makassar.
D. Manfaat
Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan
manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
a. Diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan.
b. Diharapkan penelitian dapat menjadi inspirasi
untuk pengembanga penanganan permasalahan sampah
di kota Makassar.
c. Diharapkan karya tulis ini menjadi pedoman bagi
peneliti dalam penulisan selanjutnya.
2. Manfaat praktis
a. Bagi pemerintah, penerapan penelitian ini dapat
menjadi solusi menentuan lokasi potensial Tempat
Pengolahan Akhir (TPA) Sampah di Kota Makassar
menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).
8
b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini
dapat memberi perhatian lebih pada penanganan
permasalahan sampah di kota Makassar.
c. Bagi penulis, penelitian ini menjadi kegiatan
pembelajaran dalam pembuatan karya tulis ilmiah.
9
BAB IIFAKTOR-FAKTOR YANG TERKAIT
A. Faktor –Faktor Kongkrit (Fisik) Pembangunan
Menurut Damanhuri E., (1995) beberapa alasan
mengapa sebuah parameter serta kriterianya penting untuk
dipertimbangkan dalam pemilihan sebuah calon lokasi yang
diuraikan di bawah ini. Parameter penyaring yang sering
digunakan adalah:
1. Geologi
Fasilitas pembuangan sampah tidak dibenarkan
berlokasi di atas daerah yang mempunyai sifat geologi
yang dapat merusak keutuhan sarana tersebut
nanti.Daerah yang dianggap tidak layak adalah daerah
dengan formasi batuan berupa batu pasir, batu gamping
atau dolomite berongga dan batuan berkekar lainnya.
Hal ini disebabkan batuan yang berpori akan dengan
mudah meloloskan air, sehingga larutan yang terbentuk
dari penguraian sampah organic akan memasuki zona air
tanah bebas (Azikin S., 1980).
Biasanya batu lempung dan batuan kompak yang
bersifat kedap terhadap air (impermeable) lainnya
dinilai layak untuk lokasi lahan urug atau lokasi TPA
sampah. Daerah geologi lainnya yang perlu dievaluasi
adalah daerah yang mempunyai potensi gempa, misalnya
zona volkanik yang aktif akan dapat menimbulkan bahaya
pada penduduk di sekitar lokasi serta daerah longsoran
(Alzwar M., 1998).
10
2. Hidrogeologi
Dalam tinjauan geohidrologi akan diuraikan
tentang air, pengaruh topografi, dan pengaruh batuan
penyusun kerak bumi. Kandungan air dalam tanah berasal
dari resapan sebagian air hujan ke dalam celah dan
rongga batuan dan selanjutnya beredar di dalamnya,
sehingga menjadi jenuh atau mengisi penuh seluruh
rongga dan celah-celah batuan (Allen J.R.L. dalam
Miswar 1984).
Air yang berada di dalam tanah ada yang diserap
oleh mineral menjadi air Kristal atau tetap tinggal di
dalam tanah sebagai air tanah. Sebagian lagi akan
muncul dari dalam tanah atau batuan yang mempunyai
kemungkinan sebagai suatu sumber dan selanjutnya akan
beredar bersama air permukaan lainnya.
Topografi merupakan bentuk-bentuk roman muka
bumi, dimana kebanyakan bentuk topografi suatu daerah
akan berpengaruh terhadap keadaan air tanah yang
terdapat di dalamnya. Resapan air hujan yang masuk,
banyak dipengaruhi oleh sudut lereng dan faktor
vegetasi yang menutup lahan tersebut (Chay A., 1995).
Secara sektoral maupun regional kenampakan
topografi suatu daerah akan memberikan gambaran
tentang letak garis pemisah air (water devide), serta
cekungan hidrografi ke arah mana akumulasi air
tanahnya. Jika topografi menunjukkan ketidak-aturan,
11
maka muka air tanah akan terpengaruh (Verhoef, P.N.W,
1989).
Resapan air hujan kedalam air tanah akan
dipengaruhi oleh jenis batuan penyusun lapisan tanah
tersebut. Sifat atau kemampuan porositas dan
permeabilitas tanah dikendalikan oleh granulometrik
batuan penyusunnya.Makin kasar butiran makin besar
pula kemungkinan untuk bersifat permeable. Daya serap
antara batuan satu dengan lainnya juga akan berbeda,
hal ini tergantung dari jenis tekstur dan struktur
dari masing-masing batuan tersebut. Struktur batuan
yang berpengaruh terhadap resapan air serta akuifer
adalah pada struktur batuan sedimen. Dengan adanya
struktur batuan akan mempengaruhi pola aliran muka air
tanah di samping topografi (Irham, 2006).
Keberadaan air tanah dalam akuifer dapat
dibedakan menjadi dua macam yakni : air tanah bebas
dan air tanah tertekan. Ait tanah bebas terdapat pada
akuifer yang tidak dibatasi oleh lapisan yang akuiklud
sehingga air tanah masih berhubungan dengan udara yang
mempunyai tekanan 1 atmosfer.Air tanah tertekan
menempati akuifer yang tertutup oleh lapisan yang
kedap air, tidak berhubungan dengan udara sehingga
tekanan lebih besar dari 1 atmosfer (Srikandi F.,
1992).
3. Topografi
12
Tempat pengurungan sampah tidak boleh terletak
pada suatu bukit dengan lereng yang tidak stabil.Suatu
daerah dinilai lebih baik terletak di daerah landai.
Sebaliknya suatu daerah tifak layak bila terletak pada
daerah depresi yang berair, lembah-lembah yang rendah
dan tempat-tempat lain yang berdekatan dengan air
permukaan dan kemiringan alami lebih besar dari 20%.
Topografi dapat menunjang secara positif maupun
negative pada pembangunan sarana ini.Lokasi yang
tersembunyi di belakang bukit atau lembah mempunyai
dampak visual yang kurang, disbanding tempat yang
berlokasi di lapangan datar tanpa penghalang
pandangan. Di sisi lain, suatu lokasi di tempat
berbukit mungkin lebih sulit untuk dicapai karena
adanya lereng-lereng yang curam dan mahalnya
pembangunan jalan pada daerah berbukit. Pada lokasi
dengan relief yang cukup untuk mengisolir atau
menghalangi pemandangan dan member perlindungan
terhadap angin dan sekaligus mempunyai jalur yang
mudah untuk aktivitas operasional dianggap lebih bagus
dari daerah-daerah yang diurai sebelumnya (Hidartan
dan Hadayana 1982).
Topografi dapat juga mempengaruhi biaya bila
dikaitkan dengan kapasitas tamping. Suatu lahan yang
cekung dapat dimanfaatkan secara langsung akan sangat
disukai, disebabkan volume lahan untuk pengurungan
sampah sudah tersedia tanpa harus mengeluarkan biaya
13
operasi untuk penggalian yang mahal. Pada dasarnya,
dalam masa layan 5 – 10 tahun akan dapat bertahan.
4. Tanah
Tanah dibutuhkan baik dalam tahap pembangunan
maupun dalam tahap operasi sebagai lapisan dasar
(liner), lapisan atas, penutup antara dan harian atas
untuk tanggul-tanggul dan jalan-jalan dengan jenis
tanah yang berbeda. Beberapa kegiatan memerlukan tanah
berdeb atau tanah liat, misalnya utuk liner dan tanah
penutup final, sedangkan aktifitas lainnya memerlukan
tanah permiabel seperti pasir dan kerikil, misalnya
untuk ventilasi gas dan sistem pengumpulan lindi.
Selanjutnya menurut Surya T. D., (1992), kriteria
negara industri, lahan untuk landfill sampah kota
termasuk kategori kelas 2, yaitu lahan semi-permiabel
dengan nilai kelulusan air antara 10-5 – 10-7 cm/dt.
Untuk landfill sampah kota di Indonesia perlu
dipertimbangkan hal-hal seperti :
a. Lahan biasanya terletak di luar kota, dimana
kadangkala berdekatan dengan perumahan yang belum
terjangkau oleh sistem PDAM yang baik, sehingga
masalah pencemaran lindi perlu dipertimbangkan.
b. Intensitas hujan di Indonesia yang cukup tinggi.
Pada dasarnya tanah mempunyai kemampuan untuk
mengadsorpsi dan mendegradasi pencemar, namun adanya
lapisan liner tambahan akan lebih menjamin hal
tersebut di atas, (Chow, V.T., 1988). Walaupun tanah
14
dasar TPA sampah relatif baik jika dilihat dari sudut
kelulusan, maka tetap dibutuhkan penyiapan dasar TPA
yang baik. Disarankan bahwa dasar TPA sampah di
Indonesia di lapisi 2 x 0,25 meter tanah yang relatif
kedap. Dan dipadatkan sampai densitas proctor 95%.
Disarankan pula bahwa kemiringan dasar TPA mengarah ke
titik tertentu yaitu tempat lindi terkumpul untuk
ditangani lebih lanjut. Guna memperlancar aliran serta
menjaga agar liner tersebut tidak rusak, maka
diperlukan “karpet kerikil” setebal 20 – 40 cm. Lindi
akan terkumpul dengan baik bila dasar TPA tersebut
dilengkapi dengan pipa pengumpul lindi.
5. Tata Guna Tanah
Tempat pegurugan sampah yang menerima sampah
organik dapat menarik kehadiran burung, sehingga tidak
boleh diletakkan dalam jarak 300 meter dari landasan
lapangan terbang yang digunakan oleh penerbangan jenis
piston.
Disamping itu lokasi yang tidak boleh terletak
pada kawasan hutan lindung atau taman nasional, jenis
penggunaan tanah lainnya yang biasanya dipertimbangkan
kurang cocok untuk lokasi lahan urug adalah wilayah
konservasi lokal. Sedangkan daerah yang dianggap lebih
baik adalah pada daerah yang diperuntukkan untuk
pertanian jika dibandingkan dengan tanah untuk
perumahan, (Soemarwoto O., 1996).
15
6. Lindi
Air tanah atau air permukaan yang berinfiltrasi
kedalam timbunan sampah akan menghasilkan lindi,
larutan yang mengandung suspended solid halus yang
terlarut dan hasil buangan mikroba. Lindi dapat
mengalir keluar dari timbunan ke permukaan tanah
sebagai mata air atau perlokasi melalui tanah dan batu
dibawah timbunan (Fred L., 1986).
Dalam keadaan normal lindi ditemukan pada dasar
TPA, dimana dari dasar TPA lindi dapat bergerak pada
arah horizontal atau vertikal tergantung dari
krakteristik meterial penyusun tanah atau batuan
sekitarnya.Permiabilitas tanah dipengaruhi oleh :
ukuran partikel, perbandingan ruang, derajat kejenuhan
dan temperatur. Selama pengaliran lindi di dalam air
tanah, nilai Keofisien permieabilitas tanah akan
menurun sesuai dengan waktu, karena reaksi yang
memperkecil ukuran pori tergantung dari waktu, Secara
umum mekanisme-mekanisme yang terjadi dalam
pembentukan lindi adalah : oksidasi biologi aerobik,
dekomposisi anaerobik, pelarutan, oksidasi dan
reduksi, dan perombakan mineral tanah.
7. Daerah Banjir
Sarana yang terletak didaerah banjir harus tidak
membatasi aliran bnjir serta tidak mengurangi
kapasitas penyimpanan air sementara dari daerah
16
banjir, atau menyebabkan terbilasnya sampah tersebut,
sehingga menimbulkan bahaya terhadap kehidupan
manusia, satwa liar tanah atau sumber air yang
terletak berbatasan dengan lokasi tersebut. Unutk
memenuhi kebutuhan ini, suatu serana yang berlokasi
pada daerah banjir memerlukan perlindungan yang lebih
kuat dan lebih baik. Diperlukan pemilihan periode
ulang banjir yang sesuai dengan jenis sampah yang akan
datang.
B. Faktor-Faktor Abstrak (non fisik) Pembangunan
Persyaratan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
yang baik sebagai berikut; a. Lahan terpilih hendaknya
memberikan nilai tertinggi ditinjau dari berbagai
aspek,yaitu aspek kesehatan masyarakat, lingkungan
hidup, biaya, dan sosial–ekonomi b. Pemilihan yang
dibuat hendaknya dapat dapat dipertanggungjawabkan,
artinya harus dapat ditunjukkan secara jelas bagaimana
dan mengapa suatu lokasi dipilih di antara yang lain
(Damanhuri, 1995).
Pada dasarnya pertimbangan utama dalam pemilihan
lokasi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
didasarkan atas berbagai aspek yaitu:
1. Aspek kesehatan masyarakat berkaitan langsung dengan
manusia, terutama kenaikan mortalitas (kematian),
mordibilitas, serta kecelakaan karena operasi tersebut
(Juli, 1996).
17
2. Aspek lingkungan hidup terutama berkaitan dengan
pengaruhnya terhadap ekosistem akibat pengoperasian
sarana tersebut, termasuk akibat transportasi dan
sebagainya (Juli, 1996).
3. Aspek biaya berhubungan biaya spesifik antara satu
lokasi dengan lokasi lain, terutama dengan adanya
biaya ekstra pembangunan, pengoperasian, dan terhadap
penduduk sekitar lokasi yang dipilih.
4. Aspek sosio–ekonomi berhubungan dengan dampak sosial
ekonomi penduduk sekitar lahan yang dipilih. Termasuk
disini adalah keuntungan dab kerugian akibat nilai
tambah yang dapat dinikmati penduduk, ataupun
penurunan nilai hak milik karena berdekatan dengan
sarana tersebut.
5. Aspek biologi berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan
oleh pencemaran pada system air tanah oleh air lindi.
Pada umumnya air lindi banyak mengandung bakteri yang
dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Kandungan
bakteri dalam air lindi dapat berupa Coliform maupun
Coli tinja, yang jumlahnya bias melebihi ambang batas
dari nilai air yang dapat dikonsumsi sebagai air
minum, (Larona, 1982).
Secara operasional terdapat peraturan yang
juga perlu dijadikan acuan terkait keberadaan
TPA sampah yaitu Keputusan Dirjen Pemberantasan
Penyakit Menular dan Penyehatan Pemukiman Departemen
kesehatan No. 281tahun1989 tentang Persyaratan Kesehatan
18
Pengelolaan Sampah.Dalam lampiran Keputusan Dirjen
tersebut dijelaskan persyaratan kesehatan pengelolaan
sampah untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang
dinyatakan antara lain :
1. Lokasi untuk TPA harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut: (a) Tidak merupakan sumber
bau, asap, debu, bising, lalat, binatang
pengerat bagi pemukiman terdekat (minimal 3 KM), (b)
Tidak merupakan pencemar bagi sumber air baku
untuk minum dan jarak sedikitnya 200 meter
dan perlu memperhatikan struktur geologi setempat,
(c) Tidak terletak pada daerah banjir, (d)
Tidak terletak pada lokasi yang permukaan
airnya tinggi, (e) Tidak merupakan sumber
bau, kecelakaan serta memperhatikan aspek
estetika, (f ) Jarak dari bandara tidak kurang dari 5
KM
2. Pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut: (a) Diupayakan agar lalat,
nyamuk, tikus, kecoa tidak berkembang biak
dan tidak menimbulkan bau, (b) Memiliki drainase yang
baik dan, (c) Leachate harus diamankan sehingga tidak
menimbulkan masalah pencemaran, (d) TPA yang digunakan
untuk membuang bahan beracun dan berbahaya, lokasinya
harus diberi tanda khusus dan tercatat di
Kantor Pemda, (e) Dalam hal tertentu, jika
populasi lalat melebihi 20 ekor per blok gril atau
19
tikus terlihat pada siang hari atau nyamuk
Aedes, maka harus dilakukan pemberantasan dan
perbaikan cara-cara pengelolaan sampah.
C. Analisis Deskripsi Keterkaitan antara Faktor-Faktor
Pembangunan
Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kelurahan Tamangapa,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan. Penelitian ini diawali dengan penentuan
kriteria pemilihan lokasi TPA berdasarkan SNI 03-3241-
1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat
Pembuangan Akhir Sampah. Pada penelitian ini ditetapkan
15 kriteria pemilihan lokasi TPA, yang dikelompokkan
dalam dua kategori kelayakan, yaitu ; (a) kelayakan
regional dan (b) kelayakan penyisih.
Penentuan lokasi TPA dilakukan melalui 2 tahap
penilaian. Penilaian tahap pertama dilakukan dengan
metode binary untuk menentukan zone layak atau tidak
layak sebagai lokasi TPA berdasarkan delapan kriteria
penilaian kelayakan regional. Pada lahan yang memenuhi
kriteria penilaian diberi nilai 1 dan lahan yang tidak
memenuhi kriteria penilaian diberi nilai 0. Sehingga
zone layak TPA ditetapkan apabila nilai lahan mencapai
jumlah maksimal (delapan). Penilaian tahap kedua
dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan
Weighted Linear Combination (WLC) untuk menentukan tingkat
kesesuaian lahan dari beberapa alternatif lokasi yang
20
telah diperoleh pada penilaian tahap pertama berdasarkan
tujuh kriteria penilaian kelayakan penyisih. AHP
digunakan untuk menentukan bobot dan nilai dari masing-
masing kriteria penilaian, sedangkan WLC digunakan untuk
operasi perhitungan nilai kesesuaian sebagai lokasi TPA.
Pada penelitian ini, tingkat kesesuaian lahan untuk
lokasi TPA ditentukan dengan persamaan berikut :
Si=∑j
nWj.Xj
Keterangan :
S : Tingkat kesesuaian lahan lokasi I untuk TPA
Wj : Bobot penilaian parameter j
Xj : Nilai parameter j
n.j : Jumlah parameter penilaian
Hasil penilaian tingkat kesesuaian lahan
dikelompokan dalam 5 tingkat kesesuaian, yaitu : sangat
rendah (30-41), rendah (42-53), sedang (54-65), tinggi
(66-77) dan sangat tinggi (78-90) (Mswar, 2012)
1. Potensi penempatan TPA dengan pemilihan lokasi TPA
berdasarkan SNI 03- 3241-1994 tentang Tata Cara
Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Pada
penelitian ini ditetapkan 15 kriteria pemilihan lokasi
TPA, yang dikelompokkan dalam dua kategori kelayakan,
yaitu ;
a. kelayakan regional, meliputi ; kemiringan lereng,
kondisi geologi, jarak terhadap badan air, jarak
21
terhadap permukiman penduduk, jarak terhadap
kawasan budidaya pertanian, jarak terhadap kawasan
lindung, jarak terhadap lapangan terbang, dan jarak
terhadap perbatasan daerah.
Tabel 1. Kriteria Kelayakan Regional
22
b.
23
No. Parameter Nilai
1.Kemiringan lereng
a. 0 – 15 %
b. >15%
1
0
2.Kondisi geologi
a. Tidak berada di zona sesar aktif
b. Berada di zona sesar aktif
1
0
3.Jarak terhadap badan air
a. > 300 m
b. < 300 m
1
0
4.Jarak terhadap permukiman
a. > 1500 m
b. < 1500 m
1
0
5.Kawasan budidaya pertanian
a. > 150 m dari kawasan budidaya
b. < 150 m dari kawasan budidaya
1
0
6.Kawasan lindung
a. Di luar kawasan lindung
b. Di dalam kawasan lindung
1
0
7.Jarak terhadap lapangan terbang
a. > 3000 m
b. < 300 m
1
0
8.Jarak terhadap perbatasan daerah
a. > 100 m
b. < 100 m
1
0
kelayakan penyisih, meliputi ; luas lahan, zona penyangga,
permeabilitas tanah, kedalaman muka air tanah,
intensitas hujan, bahaya banjir dan transportasi sampah.
Tabel 2. Kriteria Kelayakan Penyisih
No. Parameter Bobot Nila
i
1.
Luas lahana. Untuk operasional > 10 tahunb. Untuk operasional 5-10 tahunc. Untuk operasional < 5 tahun
5321
2.
Kebisingan dan baua. Ada zona penyanggab. Ada zona penyangga terbatasc. Tidak ada zona penyangga
2321
3.
Permeabilitas tanaha. < 10-9 cm/dtb. 10-9 – 10-6 cm/dtc. > 10-6 cm/dt
5321
4.
Kedalaman muka air tanaha. ≥ 10m, permeabilitas < 10-
9cm/dtb. < 10m, permeabilitas < 10-
9cm/dt atau ≥ 10m, permeabilitas 10-9 – 10-6 cm/dt
c. < 10m, permeabilitas 10-9 – 10-6
cm/dt
5
32
1
5.
Intensitas hujana. < 500 mm/tahunb. 500-1000 mm/tahunc. > 1000 mm/tahun
3321
6. Bahaya banjira. Tidak ada bahaya banjirb. Kemungkinan banjir > 25
tahunan
5321
24
c. Kemungkinan banjir < 25 tahunan
7.
Transport sampaha. < 15 menit dari pusat sumber
sampahb. 16-60 menit dari pusat sumber
sampahc. > 60 menit dari pusat sumber
sampah
5
32
1
BAB IIIPEMBAHASAN
Potensi penempatan TPA dengan pemilihan lokasi TPA
berdasarkan SNI 03- 3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan
Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Pada penelitian ini
ditetapkan 15 kriteria pemilihan lokasi TPA. Penentuan
lokasi TPA dilakukan melalui 2 tahap penilaian. Penilaian
tahap pertama dilakukan dengan metode binary untuk
menentukan zone layak atau tidak layak sebagai lokasi TPA
berdasarkan delapan kriteria penilaian kelayakan regional.
Sesuai kriteria kelayakan regional, zona yang dapat
digunakan sebagai lokasi TPA adalah zona yang memiliki
nilai total 8 dalam arti lain zona tersebut memiliki
kemiringan lereng dibawah 15%, tidak berada pada zona sesar
aktif, tidak berada pada radius 300 meter dari badan air,
jarak terhadap permukiman lebih dari 1500 meter, tidak
25
berada pada zona budidaya dan kawasan lindung, tidak berada
pada radius 3000 meter dari lapangan terbang, dan 1000
meter dari perbatasan daerah.
Pada penilaian tahap pertama (kelayakan regional)
dengan memasukkan kriteria tersebut dan mengolah data
menggunakan ArcMap didapatkan 5 zona layak TPA yaitu ID 1,
ID 2, ID 3, ID 4, dan ID 5. TPA dengan luas total 121,
693 ha. Antang adalah salah satu dari zona layak secara
regional dengan luas 7,3 ha. Namun pada kenyataannya,
lokasi TPA sampah Tamangapa Antang memiliki luas 14,3 Ha
yang telah digunakan sejak 1993. Selain dari pada itu TPA
Sampah Tamangapa yang sedianya dirancang untuk kebutuhan
selama 10 tahun, namun kenyataannya bahwa hingga saat ini
TPA tersebut masih digunakan, yang berarti telah berumur
hampir 22 tahun. Daerah TPA Sampah Tamangapa Antang Kota
Makassar telah terjadi pencemaran lingkungan yang dapat
menimbulkan efek terhadap lingkungan di daerah ini.
26
Analisis tahapan penyisih merupakan kelanjutan dari
analisis tahapan regional. Analisis tahapan penyisih ini
dilakukan berdasarkan 7 (tujuh) parameter yang meliputi ;
luas lahan, zona penyangga, permeabilitas tanah, kedalaman
muka air tanah, intensitas hujan, bahaya banjir dan
transportasi sampah. Kemudian dilakukan analisis secara
menyeluruh yaitu dengan menggunakan metode scoring
berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan dengan
menggunakan data wawancara, observasi maupun data sekunder
yang didapat.
Tabel 3. Hasil penelitian kriteria kelayakan penyisih
29
Sumber: Analisis data sekunder, 2014
Berikut penjelasan tiap-tiap parameter kelayakan
penyisih:
1. Luas lahan
luas lahan TPA sampah Tamangapa Antang 14,3 Ha yang
telah digunakan sejak 1993. Selain dari pada itu TPA
30
No. ParameterBobo
tNilai Hasil
1
Luas lahan,
Untuk operasional > 10
tahun
5 3 15
2
Kebisingan dan bau,
Ada zona penyangga yang
terbatas
3 2 6
3Permeabiltas tanah,
< 10-9 cm/dt5 3 15
4
Kedalaman muka air tanah,
≥ 10 m, permeabiltas < 10-9
cm/dt
5 3 15
5Intensitas hujan,
500-1000 mm/tahun3 2 6
6Bahaya banjir.
Tidak ada bahaya banjir5 3 15
7
Transpor sampah,
> 60 menit dari pusat
sumber sampah
5 1 5
Jumlah 77
Sampah Tamangapa yang sedianya dirancang untuk kebutuhan
selama 10 tahun, namun kenyataannya telah beroperasi
selama lebih dari 10 tahun atau hampir 22 tahun. Dengan
melihat kenyataan ini dapat diasumsikan bahwa di daerah
TPA Sampah Tamangapa Antang Kota Makassar telah terjadi
pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan efek
terhadap sanitasi lingkungan di daerah ini.
Dampak yang dapat ditimbulkan oleh TPA Sampah
Tamangapa Antang adalah terutama terhadap kualitas
airtanah dangkal. Pencemaran terhadap airtanah dangkal
yang diakibatkan oleh perembesan limbah cair dari TPA
sampah, dan dapat pula mencemari sumur penduduk di
sekitarnya.Pencemaran ini telah dirasakan oleh penduduk
sekitar TPA tersebut terutama bagi yang memanfaatkan
airtanah bebas sebagai sumber air bersih. Disamping
pencemaran airtanah juga polusi udara dengan bau yang
menyengat, (Fauzi, 2001).
2. Kebisingan dan bau
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada
salah satu petugas UPTD TPA Tamangapa yaitu Bapak Saiful
Ihsan, bahwa dalam upaya menghindari kebisingan dan bau
yang berasal dari TPA sehingga tidak berdampak kepada
masyarakat setempat yaitu dengan menempatkan lokasi TPA
yang berjarak lebih dari 1500m dari pemukiman penduduk.
Namun kenyataannya masih banyak dari masyarakat
disekitar TPA yang mengeluh akan pencemaran udara (bau)
yang berasal dari TPA tersebut. Dari hasil wawancara
31
bahwa suatu kewajaran bila masyarakat setempat terkena
dampak dari bau sampah dikarenakan mereka membangun
pemukiman yang mendekati TPA.
3. Permeabilitas tanah
Peresapan di lokasi ini mempunyai nilai
permeabilitas (k) 10-3 sampai 10-4 (Fauzi Arifin, 2014).
Data selengkapnya mengenai litologi daerah TPA Tamangapa
Antang, selengkapnya diperlihatkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Uraian Batuan dan Permeabilitas Lapangan
Kedalaman LitologiPermeabilitas
cm/s
0 – 0,3Tanah
penutup-
0,3 – 7,5 Lempung 9,5 x 10-4
8,5 – 22
Breksi
vulkanik
dan bongkah
andesit
5,81 x 10-4 s/d
3,2 x 10-4
22 – 27,5
Batupasir
dan sisipan
lempung
2,4 x 10-5
27,5 – 30Breksi
vulkanik1,6 x 10-5
Sumber: Kanwil Pertambangan dan Energi Sul-Sel, 2008.
32
4. Kedalaman muka air tanah
Kondisi hidrologi daerah TPA Antang termasuk dalam
sistem akuifer bebas atau akuifer tidak tertekan.
Akuifer tidak tertekan terdapat pada kedalaman ± 30
meter dan terdiri dari satuan breksi vulkanik beserta
pelapukannya yang mempunyai permeabilitas (K) 9,5 x 10-4
sampai 1,6 x 10-4 cm/s (Fauzi Arifin, 2014).
5. Intensitas hujan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) Wilayah Makassar memperkirakan intensitas hujan
pada Januari 2014 tinggi, yakni 700- 800 milimeter (mm).
Sama dengan intensitas hujan pada Januari 2013 yang juga
700 mm (Redaksi, 2013).
6. Bahaya banjir
Dari hasil wawancara kepada salah satu petugas UPTD
TPA Tamangapa yaitu Bapak Saiful Ihsan, bahwa di lokasi
TPA Sampah Tamangapa Antang tidak pernah terjadi banjir.
Sehingga pada lokasi TPA tidak ada bahaya banjir bagi
lingkungan sekitar.
7. Transport sampah
Berdasarkan hasil observasi, transport sampah
sampai di lokasi TPA Sampah Tamangapa membutuhkan waktu
lebih dari 60 menit dari pusat sumber sampah (TPS), hal
tersebut disebabkan karena kemacetan.
33
Berdasarkan hasil penilaian menggunakan kriteria
kelayakan penyisih, nilai tingkat kesesuaian lokasi TPA
Antang adalah 77 (tinggi). Hal ini berarti Penentapan TPA
Sampah di Antang telah sesuai dengan kriteria pemilihan
lokasi TPA berdasarkan SNI 03-3241-1994.
TPA Sampah Tamangapa yang sedianya dirancang untuk
kebutuhan selama 10 tahun dan telah beroprasi sejak 1993
tersebut hingga saat ini masih beroprasi. Beradasarkan
hasil penilaian tahap pertama lahan yang layak hanyalah 7,3
ha namun TPA Antang telah menggunakan 14,3 ha. Dengan beban
sampah sebesar 800 ton atau sekitar 4000 m3 tiap harinya
maka diperkirakan TPA Antang akan Over Capasity pada 2016
sehngga perlu adanya pembebasan lahan baru untuk
menampunya.
34
BAB IVKESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penlaian penentuan pemilihan lokasi TPA
berdasarkan SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan
Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Pada penilaian
tahap pertama (kelayakan regional) dengan memasukkan
kriteria tersebut dan mengolah data menggunakan ArcMap
didapatkan 5 zona layak TPA yaitu ID 1, ID 2, ID 3, ID
4, dan ID 5. TPA dengan luas total 121, 693 ha. TPA
Sampah Antang adalah salah satu dari zona layak secara
regional dengan luas 7,3 ha. Dan berdasarkan hasil
penilaian menggunakan kriteria kelayakan penyisih, nilai
tingkat kesesuaian lokasi TPA Antang adalah 77 (tinggi).
TPA Sampah Tamangapa yang sedianya dirancang untuk
kebutuhan selama 10 tahun dan telah beroprasi sejak 1993
tersebut hingga saat ini masih beroprasi. Beradasarkan
hasil penilaian tahap pertama lahan yang layak hanyalah
7,3 ha namun TPA Antang telah menggunakan 14,3 ha.
Dengan beban sampah sebesar 800 ton atau sekitar 4000 m3
tiap harinya maka diperkirakan TPA Antang akan Over
Capasity pada 2016 sehngga perlu adanya pembebasan lahan
baru untuk menampunya.
B. Saran
Melihat kondisi TPA Sampah Antang yang melebihi
kapasitas sesuai zona yang layak digunakan maka harus
35
segera dilakukan pencarian lokasi alternatif. Besarnya
kapasitas sampah yang datang setiap harinya
menggambarkan betapa kurangnya usaha pengolahan dan
pemanfaatan sampah di kota Makassar. Sehingga perlu
kiraya upaya penggalakan sistem 3R (Reuse, Reduce, dan
Recycle)
DAFTAR PUSTAKA
Alzwar. M., 1988, Pengantar Ilmu Gunungapi. Nova, Bandung.
Azikin, S., 1980, Dasar-Dasar Geologi Struktur. Departemen TeknikGeologi, Institut Teknologi Bandung. Bandung.
Chay A. C., 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Damanhuri E, Padmi T, 2004, Pengelolaan Sampah, ITB Bandung
Fauzi, Arifin, M., 2001. Tinjauan Geohidrologi sebagai Salah SatuPertimbangan dalam Pemilihan Lokasi TPA Sampah. Makassar :Universitas Hasanuddin.
Fauzi Arifin, M., dkk. 2014. Tinjauan Geohidrologi Lokasi TPASampah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus TPASampah Tamangapa Antang). Prosiding Seminar NasionalGeofisika 2014
36
Irham. M, 2006., Pemetaan Sebaran Air Tanah Asin Pada Akuifer Dalamdi Wilayah SemarangBawah.http://eprints.undip.ac.id/2139/1/.pdf
Mizwar, Andi. 2012. Penentuan Lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA)Sampah Kota Banjarbaru Menggunakan Sistem Informasi Geografis(SIG). Jurnal EnviroScienteae ISSN 1978-8096, vol.8(1), 16-22.
Rahman, M., Sultan, and K. R., Hoque, A. dkk., 2008, Suitablefor Urban Solid Waste Disposal Using GIS Approach in Khulna CityBangladesh, Proc. Pakistan Acadd.
Rahmatiyah, 2002, Evaluasi Kelayakan Lahan untuk TempatPembuangan Akhir Sampah di Kota Samarinda, Tesis ProgramStudi Ilmu Lingkungan UGM, Yogyakarta.
Redaksi MT, 2013. 19 Kawasan Pemukiman Terancam Banjir. www.makassarterkini.com. Diakses pada tanggal 2 Mei 2015.
Rouf,Ahmad dkk., 2014, Analisis Kesesuaian Lokasi Tempat PembuanganAkhir (Tpa) Sampah Di Wilayah Penilaian Adipura Kabupaten Jepara, Geo Image ISSN 2252-6285, , vol 2(2)
Ruslinda, Yenni dkk.2002.Studi Timbulan, Komposisi Dan KarakteristikSampah Domestik Kota Bukittinggi, Jurnal Teknik LingkunganUNAND ISSN 1829-6084, Vol.9 (1) : 1-12.
Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah.Bandung: PT Bumi Aksara
Soemarwoto, O., 1996. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Srikandi, F., 1992. Polusi Air dan Udara. IPB, Bogor.
37