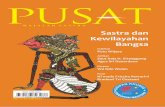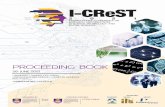Laporan Sistem Saraf Pusat I dan Sistem Saraf Pusat II
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Laporan Sistem Saraf Pusat I dan Sistem Saraf Pusat II
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar belakang
Farmasi merupakan profesi yang berhubungan
dengan seni dan ilmu penyediaan (pengolahan) bahan
sumber alam dan bahan sintesis yang cocok dan
menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan
dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit
(Anif, 1993). Dalam bidang farmasi mempelajari
berbagai disiplin ilmu salah satunya adalah
farmakologi dan toksikologi. Farmakologi dan
toksikologi adalah ilmu yang mempelajari
pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik
sifat kimiawi maupun fisiknya, reabsorpsi, dan
nasibnya dalam organisme hidup. Menyelidiki semua
interaksi antara obat dan tubuh manusia khususnya,
serta penggunaanya pada pengobatan penyakit.
Salah satu yang dipelajari dalam farmakologi
dan toksikologi yaitu Sistem Saraf Pusat. Sistem
saraf pusat (SSP) merupakan sistem saraf yang dapat
mengendalikan sistem saraf lainnya didalam tubuh
dimana bekerja dibawah kesadaran atau kemauan. SSP
biasa juga disebut sistem saraf sentral karena
merupakan sentral atau pusat dari saraf lainnya.
Sistem saraf pusat ini dibagi menjadi dua yaitu
1
otak (ensevalon) dan sumsum tulang belakang (medula
spinalis).
Sistem saraf pusat dapat ditekan seluruhnya
oleh penekan saraf pusat yang tidak spesifik
misalnya hipnotik sedatif. Obat yang bekerja pada
sistem saraf pusat terbagi menjadi obat depresan
saraf pusat yaitu anastetik umum, hipnotik sedatif,
psikotropik, antikonvulsi, analgetik, antipiretik,
inflamasi, perangsang susunan saraf pusat.
Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan
Sistem Saraf Pusat I dan Sistem Saraf Pusat II.
Dimana Sistem Saraf Pusat I menggunakan alkohol 70%
dan etil asetat untuk melihat efek anastetik umum,
sedangkan Sistem Saraf Pusat II menggunakan
antalgin untuk melihat efek analgetik dengan
menggunakan hewan coba mencit (Mus musculus).
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud percobaan.
Untuk mempelajari efek farmakologi yang
ditimbulkan oleh obat yang bekerja pada Sistem
Saraf Pusat I dan Sistem Saraf Pusat II pada hewan
coba mencit (Mus musculus).
1.2.2 Tujuan Percobaan
Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari
pemberian obat anestesi umum yaitu etil asetat dan
2
alkohol 70% serta obat analgetik yaitu antalgin
pada hewan coba mencit (Mus musculus).
BAB II
TINJAUAN TEORI
3
II.1 Teori Umum
Sistem saraf pusat manusia adalah suatu jalinan
jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan
saling berhubungan satu sama lain. Sistem saraf
mengkoordinasi, menafsirkan dan mengontrol
interaksi antara individu dengan lingkungan
sekitarnya. Susunan saraf pusat terdiri atas otak
besar, batang otak, otak kecil dan sum-sum tulang
belakang dan diliputi oleh selaput otak (metix)
yang terdiri atas pachmenix dan leptomenix obat
yang bekerja pada sistem saraf pusat terbagi
menjadi obat antikonvulsi, psikotropik, anestetik
umum hipnotik-sedatif, antiperkinson,
analgesik – anti piretik serta anti inflamasi. Obat
hipnotik-sedatif dan penenang sering dicampurkan
karena bebas tumpang – tindihnya
(Ganiswarna,1995).
1. Analgetik (Gunawan, Sulistia Gan, 2007)
Analgetik adalah obat yang mengurangi atau
melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan
kesadaran.
2. Anastesi
Anastesi adalah obat-obat yang diberikan
untuk menghilangkan rasa nyeri (rasa sakit)
dengan atau tidak disertai hilangnya kesadaran.
Hilangnya suatu kesadaran biasanya digunakan
4
untuk anastesi umum. Sedangkan tidak hilangnya
kesadaran digunakan untuk anastesi lokal.
Anastesi terbagi menjadi (Gunawan, Sulistia Gan,
2007) :
a) Anastesi Umum (Inhalasi dan Intravena)
Anastesi Umum anastesi umum merupakan cara
anastesi, dimana rasa sakit hilang disertai
dengan hilangnya kesadaran. Anastesi umum
sering digunakan pada proses operasi
(pembedahan), agar pasien tidak merasakan
sakit.
b) Anastesi Lokal.
Anastesi Lokal anastesi lokal merupakan
cara anastesi, dimana rasa sakit hilang tanpa
disertai dengan hilangnya kesadaran.
Anastesi lokal digunakan pada saat
pencabutan gigi. Anastesi tersebut merintangi
penghantaran implus saraf ke sistem saraf
pusat. Hal ini dilakukan agar si pasien tetap
dalam keadaan sadar. Mekanisme kerja anastesi
umum, secara umum dibagi 2 yaitu (Mycek, 2001)
:
a. Anatesi umum (inhalasi)
Anastesi ini terdiri atas gas, semakin
banyak gas yang disemprotkan kedalam tubuh,
maka semakin banyak pula gas yang berdifusi
5
atau mengalir didalam aliran darah.
Sehingga efek anastesi yang ditimbulkan
semakin lama. Contoh obatnya : Enfluran,
Isofluran, Sevofluran dan Metoksifluran.
b. Anastesi umum (intravena)
Anastesi ini terdiri atas injeksi,
dimana obat yang disuntikan (diinjeksikan)
kedalam tubuh dan masuk kedalam peredaran
darah yang menyebabkan terjadinya
peningkatan pembuluh darah, sehingga obat
tersebut menghambat masuknya ion Na+ dan
menghambat keluarnya ion K+. Contoh obatnya
: Diazepam, morfin, dll.
Adapun Tahap-tahap Anastesi (Mycek, 2001) :
- Stadium 1 (Analgesia) yaitu untuk
menghilangkan rasa nyeri, dimana pada
stadium ini pasien masih dalam keadaan
sadar dan masih dapat diajak berbicara,
tetapi rasa sakitnya sudah berkurang.
- Stadium 2 (Gelisah/eksitasi)) yaitu
setelah rasa sakitnya berkurang pada
stadium 1, pasien akan merasa gelisah
dan khawatir tentang apa yang akan
terjadi selanjutnya.
- Stadium 3 (Pembedahan) Pada stadium ini
kesadaran secara lokal atau keseluruhan
6
menghilang. Dan proses pembedahan pun
dilakukan pada stadium ini.
- Stadium 4 (Paralisis Modula) pada
stadium ini, kemungkinan besar
II.2 Uraian Bahan
a. Alkohol (Dirjen POM, 1979)
Nama Resmi : Aethanolum
Nama Lain : Alkohol, etanol
RM/BM : C2H5OH/46,07
Rumus Struktur :
Pemerian : Cairan tak
berwarna, jernih, mudah dan
mudah bergerak, bau khas, rasa
panas, mudah
terbakar dengan memberikan
nyala biru yang
tidak berasap.
Kelarutan : Sangat mudah
larut dalam air, dalam
kloroform P, dan dalam eter P.
Penyimpanan : Dalam wadah tertutup
rapat, terlindung dari cahaya,
7
ditempat sejuk, jauh dari
nyala api.
Kegunaan : Sebagai
antiseptik
b. Aquades (Dirjen POM, 1979)
Nama Resmi : Aqua Destillata
Nama Lain : Air murni, air
suling, air batering.
RM/BM : H2O/18,02
Rumus Struktur : O
H H
Pemerian : Cairan jernih,
tidak berwarna tidak berbau,
tidak berasa.
Penyimpanan : Dalam wadah tertutup
baik
Kegunaan : Sebagai zat tambahan
c. Antalgin (Depkes RI, 1979; Tjay, HT 2006)
Nama Resmi : Metampyronum
Nama Lain : Metampiron, antalgin
RM/BM : C13H16N3N4O4SH5H2O/351,17
Rumus Struktur :
8
Pemerian : Serbuk hablur, putih atau
putih kekuningan
Penyimpanan : Dalam wadah tertutup baik
Farmakologi : Obat ini sering dikombinasikan
dengan obat-obat lain. Obat
ini dapat secara mendadak dan
tak terduga menimbulkan
kelainan darah yang adakalanya
fatal karena bahaya
agronologositosis
Indikasi : Meringankan rasa sakit,
terutama nyeri kolik dan sakit
setelah operasi.
Kontra indikasi : Hipersensitif hamil dan
menyusui, penderita dengan
tekanan darah sistolik <100
mmHg
Efek samping : Hipersensitif,
agronologositosis.
d. Etil Asetat (Dirjen POM, 1979)
Nama resmi : Etil etanoat, Etil asetat
Nama Lain : Etil ester, Ester asetat,
Ester etanol
RM/BM : C2H4O2/60,05
9
Rumus Struktur :
Pemerian : Cairan jernih, tidak
berwarna, bau menusuk, rasa
asam, tajam
Kelarutan : Dapat campur dengan air,
dengan etanol
(95%), dan dengan gliserol.
Penyimpanan : Dalam wadah tertutup
rapat
Khasiat : Sebagai obat
anastesi
e. Na. CMC (Dirjen POM, 1979)
Nama Resmi : Natrii Carboximethyl
Cellulosum
Nama Lain : Natrium Karboksimethil
Selulosa
Pemerian : Serbuk atau butiran, putih
atau putih kekuningan, tidak
berbau atau hampir tidak
berbau.
Kelarutan : Mudah mendispersi dalam air
membentuk suspensi koloid,
tidak larut dalam etanol
(95%)P dalam eter P
10
Khasiat : Zat tambahan
Penyimpan : Dalam wadah tertutup rapat
II.3 Uraian Hewan Coba
a.Karakteristik Hewan Coba (Mycek, 2001)
Mencit (Mus musculus)
Lama hidup : 1-2 tahun bisa sampai 3 tahun
Lama bunting : 19-21 hari
Umur dewasa : 35 hari
Siklus eksterus : 4-5 hari
Lama ekstrus : 12-24 jam
Berat dewasa : 20-40
Berat lahir : 0,5-1 gram
Jumlah anak : 6-15
Suhu tubuh : 35-39 C
Volume darah : 6% BB
b.Klasifikasi Hewan Coba (Mycek, 2001)
Mencit (Mus musculus)
Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Subphylum : Vertebrata
Class : Mamalia
Ordo : Rodentia
11
Gambar II.3.1Mencit(Mus musculus)
III.1 Alat Dan Bahan
III.1.1 Alat yang digunakan
1. Alu
2. Batang pengaduk
3. Dispo 1 ml
4. Gelas ukur (Pyrex)
5. Gelas kimia (Pyrex)
6. Lumpang
7. Lap halus
8. Lap kasar
9. Neraca analitik
10. Selang NGT
III.1.2 Bahan yang digunakan
1. Aquadest
2. Alkohol 70 %
3. Antalgin 500 mg
4. Kapas
5. Kertas perkamen
6. Na-CMC 5 gram
7. Paracetamol 500 mg
8. Tissu
III.2 Cara kerja
III.2.1 Pembuatan Na-CMC (Larutan stok)
1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. Dibersihkan alat dengan menggunakan alkohol 70
%.
13
3. Ditimbang Na CMC sebanyak 5 gram.
4. Diukur aquadest sebanyak 100 mL.
5. Dipanaskan aquadest tersebut dengan menggunakan
penangas air sampai hangat.
6. Dimasukkan Na CMC kedalam lumpang.
7. Dimasukan air hangat sedikit demi sedikit dalam
lumpang.
8. Digerus hingga terbentuk musilago.
9. Dimasukkan musilago yang telah terbentuk
kedalam gelas kimia.
10. Ditutup menggunakan aluminium foil.
III.2.2 Perlakuan anastesi pada hewan coba
(Etil asetat)
1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. Diambil kapas secukupnya.
3. Dibasahi kapas menggunakan etil asetat.
4. Dimasukkan kapas tersebut kedalam toples.
5. Didiamkan sebentar.
6. Dimasukkan mencit kedalam toples dan ditutup.
7. Diamati dan dicatat onset dan durasi pada
mencit.
III.2.3 Perlakuan anastesi pada hewan coba
(Alkohol 70 %)
1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. Diambil kapas secukupnya.
3. Dibasahi kapas menggunakan alcohol 70 %.
14
4. Dimasukkan kapas tersebut kedalam toples.
5. Didiamkan sebentar.
6. Dimasukkan mencit kedalam toples dan ditutup.
7. Diamati dan dicatat onset dan durasi pada
mencit.
III.2.4 Pemberian antalgin pada hewan coba
1. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
2. Dibersihkan alat menggunakan alkohol 70%.
3. Ditimbang berat badan mencit dan dihitung dosis
serta volume pemberiannya.
4. Ditimbang antalgin sebanyak 2 tablet.
5. Dimasukkan tablet antalgin kedalam lumpang,
kemudian digerus hingga halus.
6. Ditimbang antalgin sebanyak 97,5 mg, dan
diletakkan pada kertas perkamen.
7. Disuspensikan antalgin kedalam musilago Na CMC
sebanyak 50 mL hingga homogen
8. Diambil suspensi tersebut dengan menggunakan
dispo sebanyak 0,5 mL dan diberikan pada mencit
yang berat badannya 18,21 gram secara oral.
9. Setelah perlakuan, diamati perilaku mencit
tersebut dan dicatat berapa kali mencit
mengangkat kaki.
15
V.1.2 Tabel Percobaan Sistem Saraf Pusat II
Obat BB hewan
Pengangkatan
kaki mencit
(Menit)
Antalgin18,21
gram97 kali
IV.2 Pembahasan
IV.2.1 Sistem Saraf Pusat I
Anestesi menurut arti kata adalah
hilangnya kesadaran rasa sakit, namun obat
anestasi umum tidak hanya menghilangkan rasa
sakit akan tetapi juga menghilangkan
kesadaran. Pada operasi-operasi daerah
tertentu seperti perut, maka selain hilangnya
rasa sakit dan kesadaran, dibutuhkan juga
relaksasi otot yang optimal agar operasi
17
dapat berjalan dengan lancar (Staff Pengajar,
2004).
Pada percobaan ini diamati dan dihitung
onset serta durasi dari zat-zat anestesi.
Onset adalah mula kerja obat, dihitung mulai
waktu mencit diberi zat sampai mencit
teranestesi, sedang durasi adalah lama
bekerja obat, dihitung mulai mencit
teranestesi sampai mencit sadar. Efek
anastetik pada mencit dapat dideteksi dengan
touch respon, yaitu dengan menyentuh leher
mencit dengan suatu benda misalnya pensil.
Jika mencit tidak bereaksi maka mencit
terpengaruh oleh anastetik (Olson, 2002).
Pada percobaan anestesi ini, mencit yang
digunakan sebanyak 2 ekor dengan perlakuan
dimasukkan kedalam wadah atau toples yang
ditambahkan kapas dengan pembasahan etil
asetat dan alkohol. Mekanisme kerja dari etil
asetat yaitu melakukan kontraksi pada otot
jantung, terapi in vivo ini dilawan oleh
meningginya aktivitas simpati sehingga curah
jantung tidak berubah, etil asetat
menyebabkan dilatasi pembuluh darah kulit.
Etil asetat diabsorpsi dan diekskresi melalui
paru-paru, sebagian kecil diekskresi urin,
18
air susu, dan keringat. Efek sampingnya yaitu
iritasi saluran pernafasan, depresi nafas,
mual, muntah, salivasi (Ganiswarna, 1995).
Pada percobaan pertama dimasukkan kapas
yang telah dibasahi etil asetat kedalam
toples, kemudian dinyalakan stopwatch sampai
terjadi penguapan. Hasil yang diperoleh waktu
onset 3 menit 12 detik dan durasi 1 menit 56
detik dengan berat mencit 29,6 gram. Nilai
onset dan durasi yang ditimbulkan beragam
adanya yang lambat dan ada pula yang cepat
bahkan ada mencit yang mengalami kematian.
Hal tersebut dapat terjadi karena
vasodilatasi yang sangat kuat akibat kecilnya
tempat yang digunakan untuk meletakkan mencit
yang diamati, sehingga uap zat teranastesi
yang terhirup lebih pekat dari yang
seharusnya (Ganiswarna, 1995).
Pada percobaan kedua dimasukkan kapas
yang telah dibasahi alkohol 70 % kedalam
toples, kemudian nyalakan stopwatch sampai
terjadi penguapan. Hasil anastesi tidak
diperoleh karena menurut FK UI (2012) yang
menyatakan bahwa obat-obatan seperti etil
asetat, memang pernah digunakan sebagai
anestetik inhalasi, sedangkan alkohol 70 %
19
kurang efektif digunakan sebagai anestetik
inhalasi dan itu terbukti dipercobaan dimana
tidak memberikan efek anastesi. Namun
dikatakan bahwa alkohol sebagai Antiseptik
yang dapat menghambat pertumbuhan dan merusak
sel-sel bakteri, spora bakteri jamur, virus
dan protozoa, tanpa merusak jaringan tubuh
(Pediatri, 2005).
IV.2.2 Sistem Saraf Pusat II
Pada percobaan kedua yaitu percobaan
sistem saraf pusat II yakni percobaan untuk
melihat adanya efek dari pemberian obat
antalgin yang merupakan obat analgetik atau
obat pereda nyeri pada hewan coba mencit.
Mekanisme karja untuk obat antalgin yaitu
dangan cara merintangi terbentuknya
rangsangan pada reseptor nyeri perifer. Baik
analgetik maupun antipiretik pada dasarnya
melakukan fungsi yang sama yaitu menghalangi
terbentuknya rangsangan pada reseptor. Hanya
saja, analgetik menghalangi terbentuknya
rangsangan nyeri, sedangkan antipiretik
menghalangi terbentuknya rangsangan pada
panas. Namun, kedua rangsangan itu diatur
oleh hipotalamus (Marjono, 2004).
20
Metode yang dilakukan pada percobaan obat
analgetik ini yaitu metode rangsangan panas.
Prinsip kerja dari metode ini yakni dengan
melihat perilaku mencit yang mengangkat kaki
akibat dipanaskan. Perilaku ini diakibatkan
adanya nyeri yang diterima oleh hipotalamus
akibat panas. Metode ini membandingkan jumlah
pengangkatan kaki mencit tanpa diinduksikan
antalgin dengan mencit yang diinduksikan obat
antalgin.
Dalam percobaan ini, hal pertama yang
dilakukan adalah mempersiapkan alat-alat dan
bahan yang akan digunakan seperti selang NGT
dan hot plate yang dipakai untuk memanaskan
mencit. Selanjutnya dibuat suspensi antalgin
sebanyak 97,5 mg kedalam 50 mL larutan Na-CMC
yang kemudian di induksikan sebanyak 0,60 mL
ke mencit. Jumlah antalgin yang di induksikan
ke mencit telah dikonversikan dari dari dosis
manusia ke mencit sehingga tidak akan
bersifat toksik bagi mencit. Setelah
diinduksikan, dibiarkan mencit selama 15
menit agar efek analgetik dari antalgin
bereaksi seluruhnya dengan mencit serta untuk
menunggu hot plate panas (Malole, 1989).
Setelah 15 menit, kemudian mencit diletakkan
21
diatas hot plate selama 10 menit dan dihitung
berapa kali mencit mengangkat kaki. Mencit
mengangkat kakinya sebanyak 97 kali untuk
penggunaan antalgin, hal ini jauh lebih
sedikit dari pada tanpa diinduksikan
antalgin. Jumlah pengangkatan kaki untuk
penggunaan antalgin lebih sedikit karena
senyawa aktif antalgin menghalangi
terbentuknya rangsangan nyeri pada
hipotalamus, hal ini sesuai dengan mekanisme
kerja obat analgetik. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa antalgin dapat bersifat
analgetik atau pereda nyeri (Marjono, 2004).
22
BAB V
PENUTUP
V.1 Kesimpulan
Efek farmakologi dari obat-obat yang bekerja
pada sistem saraf pusat I adalah bersifat
memberikan efek anastesi, dan efek farmakologi dari
obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf pusat II
adalah bersifat memberikan efek analgetik atau
pereda nyeri, contohnya seperti antalgin secara
peroral
V.1 Saran
Disarankan kepada pengelolah laboratorium agar
melengkapi alat dan bahan yang akan digunakan untuk
menunjang jalannya praktikum dengan lebih baik
lagi.
23
DAFTAR PUSTAKA
Dirjen POM. 1979. Farmakope Indonesia Edisi ketiga.Jakarta: Depkes RI.
Ganiswarna. G Sulistia. 1995. Farmakologi dan Terapi
Edisi 4. Jakarta: Gaya baru.
Malole. 1989. Penggunaan Hewan-Hewan Percobaan diLaboratorium. Bandung: ITB
Marjono, Mahar. 2004. Farmakologi dan Terapi Edisi 5.Jakarta :UI Press.
Mycek, Mary J. 2001. Farmakologi Ulasan Bargambar.Jakarta : Widya Medika.
Olson, James, M D. 2002. Belajar Mudah Farmakologi.Jakarta: ECG
24
Pediatri, S. 2005. Journal peran Alkohol 70%, Povidon-Iodine10% dan Kasa Kering Steril dalam Pencegahan Infeksi padaPerawatan Tali Pusat. Yogyakarta.
Staff Pengajar Bagian Anestesiologi dan TerapiIntensif FKUI. 2004. Anestesiologi. Jakarta :Bagian Anestesiologi dan Terapi IntensifFakultas Kedokteran Universitas Indonesia
25