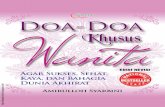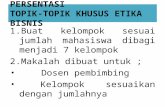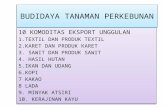LAPORAN PRAKTEK LAPANG MANAJEMEN PERKEBUNAN KHUSUS
-
Upload
caripeluangusaha -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of LAPORAN PRAKTEK LAPANG MANAJEMEN PERKEBUNAN KHUSUS
LAPORAN PRAKTEK LAPANG MANAJEMEN PERKEBUNAN KHUSUSDI PTPN VI KAYU ARO KERINCI
DI SUSUN OLEH:FRENGKI SIREGAR (D0B012036)
DOSEN PENGAMPUH:Ir. Hanibal, MP
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIANUNIVERSITAS JAMBI
2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan LAPORAN PRAKTIKUM MANAJEMEN TANAMAN
PERKEBUNAN KHUSUS di PTPN VI KAYU ARO KERINCI yang merupakan
salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian Mata Kuliah
MANAJEMEN TANAMAN PERKEBUNAN KHUSUS.
Seiring dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih
kepada yang terhormat Bapak Ir. Hanibal, MP yang memberikan
Mata Kuliah ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan
kesehatan serta rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.
Dalam pembahasan ini ada beberapa pembahasan yakni
mengenai budidaya tanaman teh yang dimulai dari persiapan
lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, panen, proses
produksi, serta pemasaran teh.
Penulis menyadari betul bahwa baik isi maupun penyajian
makalah ini masih jauh sempurna, untuk itu penulis sangat
mengharapkan adanya kritik dan saran sebagai penyempurnaan
laporan ini, sehingga dikemudian hari laporan ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Jambi, 24 Juni
2014
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkebunan teh merupakan salah satu aspek dari sektor
pertanian yang menguntungkan di Indonesia. Kebutuhan dunia
akan komoditas perkebunan sangat besar khususnya teh. Teh
merupakan minuman penyegar yang disenangi hampir seluruh
penduduk di dunia. Bahkan minuman teh sudah banyak sekali
dijadikan minuman sehari-hari. Selain sebagai minuman yang
menyegarkan, teh telah lama diyakini memiliki khasiat bagi
kesehatan tubuh. Teh hitam dibuat dari pucuk daun muda tanaman
teh (Camellia sinensis L) yang berupa bubuk. Secara
tradisional teh dibagi menjadi tiga jenis yaitu teh hijau, teh
olong, dan teh hitam.
Produk teh di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu teh
hitam dan teh hijau. Perbedaan kedua macam teh tersebut
disebabkan oleh perbedaan cara pengolahan. Dalam proses
pengolahan teh hitam memerlukan proses oksidasi enzimatis
sedangkan teh hijau tidak memerlukan proses oksidasi
enzimatis. Untuk mengikuti perkembangan pasar/konsumen, yang
beberapa tahun terakhir lebih menghendaki teh dengan ukuran
partikel yang lebih kecil (broken tea) dan cepat seduh (quick
brewing). Maka proses pengolahan teh hitam pada tahap
penggilingan yang semula menggunakan sistem orthodox murni
sekarang berkembang menjadi orthodox rotorvane. Penambahan
alat rotorvane bertujuan agar proses penghancuran lebih
intensif teh yang dihasilkan memiliki ukuran partikel kecil
yang lebih banyak.
PTPN VI merupakan salah satu perusahaan pengolahan teh
yang berkualitas. Teh yang diproduksi sudah bertaraf ekspor ke
luar negeri. Ini membuktikan kualitas teh PTPN VI tidak kalah
kualitasnya dengan teh yang lain, hal ini juga dapat ditinjau
dari segi teknologi yang digunakan dan mutu produk yang
dihasilkan. Seiring dengan proses globalisasi yang menuntut
produsen untuk menghasilkan produk berkualitas, maka pemberian
jaminan mutu yang pasti dari perusahaan terhadap produk
berkualitas sangat berpengaruh dalam menentukan pasar dan daya
saing, sehingga mendorong penulis untuk mengetahui proses
pengolahan dan pemasaran teh secara rinci. Dalam mata kuliah
kewirausahaan kami melakukan survey beberapa tempat yang
khusus nya pada kelompok 4 untuk mengujungi dan mencari
informasai tentang perkebunan teh PTPN VI di Propinsi Sumatra
Barat.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah PTPN VI ?
2. Bagaimana pengolahan the PTPN VI ?
3. Bagaimana pemasaran produk olahan teh PTPN VI ?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui dan memahami sejarah PTPN VI
2. Mengetahui cara pengolahan teh PTPN VI
3. Mengetahui pemasaran produk olahan teh PTPN VI
1.4 Manfaat Praktikum
- Melalui penelitian dan analisis hasil penelitian dapat
meningkatkan pemahaman tentang produksi bersih.
- Masukan data bagi industri dalam meningkatkan keuntungan
secara ekonomi dan memperkecil resiko lingkungan.
- Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi guna
menambah khasanah pengetahuan terkait dengan penerapan
produksi bersih di pabrik teh.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Tanaman Teh
Teh adalah tumbuhan yang daunnya dapat dijadikan sebagai
minuman. Teh mengandung kafein atau sebuah infuse yang dibuat
dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang
dikeringkan dari tanaman Camellia Sinensis dengan air panas.
Istilah teh juga digunakan untuk minuman yang dibuat dari
buah, rempah-rempah atau tanaman obat lain yang diseduh
misalnya teh rosehip, teh comomile, krisan, jiaogulan.
Teh diperoleh dari pengolahan daun tanaman teh Camellia
sinensis) dari familia Theaceae. Tanaman ini diperkirakan
berasal dari daerah pegunungan Himalaya dan pegunungan yang
berbatasan dengan RRC, India, dan Burma. Tanaman ini dapat
tumbuh subur di daerah tanaman tropik dan subtropik dengan
menuntut cukup sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun
(Siswoputranto, 1978).
Secara sistematika tanaman teh dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
1. Divisio : Spermatophyta (tumbuhan biji)
2. Subdivisio : Angiospermae (tumbuhan biji terbuka)
3. Clas : Dialypatalea
4. Famili : Guttiferales (Elusiale)
5. Subfamili : Cammelliaceae (Tehaceae)
6. Genus : Cammellia
7. Spesies : Cammellia Sinensis
2.2 Morfologi Teh
1. Morfologi Tanaman Teh
Tanaman teh berbentuk pohon. Tingginya bisa mencapai
belasan meter. Namun tanaman teh di perkebunan selalu
dipangkas untuk memudahkan pemetikan, sehingga tingginya
mencapai 90-120 cm. Mahkota tanaman teh terbentuk kerucut.
Daunnya berbentuk jorong atau agak bulat telur berbalik, tapi
daun berigi. Daun tunggal dan letaknya hampir berseling.
Tulang daun menyirip. Permukaan atas daun muda, berbuulu
halus, sedangkan permukaan bawahnya bulunya hanya sedikit
permukaan daun tua halus dan tidak berbulu lagi.
2. Morfologi Pucuk Tanaman Teh
Bunga tunggal dan ada yang tersusun dalam rangkaian
kecil. Bunga muncul dari ketiak daun. Warnanya putih bersih
dan berbau wangi lembut. Namun ada bunga yang berwarna semu
merah jambu. Mahkota bunga berjumlah 5-6 helai, putik dengan
tangkai yang panjang atau pendek dan pada kepalanya terdapat 3
buah sirip. Jumlah benang sari 100-200. Buah teh berupa buah
kotak berwarna hijau kecoklatan. Buah yang masak dan kering
akan pecah dengan sendirinya serta bijinya ikut keluar.
Bijinya berbentuk bulat atau gepeng pada satu sisinya,
berwarna putih sewaktu masih muda dan berubah menjadi coklat
setelah tua. Akar teh berupa akar tunggang dan mempunyai
banyak akar cabang. Apabila akar tunggangnya putus, akar-akar
cabang akan menggantikan fungsinya dengan arah tumbuh yang
semula melintang (horizontal) menjadi ke bawah (vertikal).
Akar bisa tumbuh besar dan cukup dalam, tanaman teh mengalami
pertumbuhan tunas yang silih berganti. Tunas tumbuh pada
ketiak / bekas ketiak daun. Tunas yang tumbuh kemudian diikuti
dengan pembentukan daun. Tunas baru pada teh memiliki daun
kuncup yang menutupi titik tumbuh serba daunnya.
2.3 Pemetikan
Pemetikan adalah pemungutan hasil pucuk tanaman teh yang
memenuhi syarat-syarat pengolahan. Pemetikan berfungsi pula
sebagai usaha membentuk kondisi tanaman agar mampu berproduksi
tinggi secara berkesinambungan. (Arifin, 1992). Menurut
Siswoputranto (1978), teh dihasilkan dari pucuk-pucuk tanaman
teh yang dipetik dengan siklus 7 sampai 14 hari sekali. Hal
ini bergantung dari keadaan tanaman masing-masing daerah,
karena dapat mempengaruhi jumlah hasil yang diperoleh. Cara
pemetikan daun selain mempengaruhi jumlah hasil teh, juga
sangat mempengaruhi mutu teh yang dihasilkan. Cara pemetikan
daun teh dibedakan menjadi dua yaitu pemetikan halus (fine
plucking) dan cara pemetikan kasar (coarse plucking).
Kegiatan pemetikan yang memerlukan karyawan yang
jumlahnya paling besar masih banyak ditemui hasil pemetikan
yang hanya mengejar target tanpa memperhatikan tata cara
pemetikan yang benar. Apalagi menghadapi musim hujan yang
produksinya lebih banyak dari pada musim kemarau maka akan
dibutuhkan lebih banyak lagi karyawan. Hal ini menyebabkan
perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif dalam
pelaksanaannya (Maulana, 2000).
2.4 Produk Olahan Teh
Teh adalah bahan minuman yang sangat bermanfaat, terbuat
dari pucuk tanaman teh (Camellia sinensis) melalui proses
pengolahan tertentu. Manfaat minuman teh ternyata dapat
menimbulkan rasa segar, dapat memulihkan kesehatan badan dan
terbukti tidak menimbulkan dampak negatif. Teh yang bermutu
tinggi sangat diminati oleh konsumen. Teh semacam ini hanya
dapat dibuat dari bahan baku (pucuk teh) yang benar serta
penggunaan mesin-mesin peralatan pengolahan yang memadai
(lengkap) (Arifin, 1994).
Menurut Hartoyo (2003), teh dapat dikelompokan berdasarkan
cara pengolahan. Pengelompokkan teh berdasarkan tingkat
oksidasi adalah sebagai berikut :
1. Teh Hijau
Daun teh yang dijadikan teh hijau biasanya langsung diproses
setelah dipetik. Setelah daun mengalami oksidasi dalam jumlah
minimal, proses oksidasi dihentikan dengan pemanasan. Teh yang
sudah dikeringkan bisa dijual dalam bentuk lembaran daun teh
atau digulung rapat berbentuk seperti bola-bola kecil.
2. Teh Hitam atau Teh Merah
Daun teh dibiarkan teroksidasi secara penuh. Teh hitam masih
dibagi menjadi 2 jenis: Orthodoks (teh diolah dengan metode
pengolahan tradisional) dan CTC (metode produksi teh Crush,
Tear, Curl yang berkembang sejak tahun 1932). Menurut Arifin
(1994), teh wangi dibuat dari teh hijau yang dicampur dengan
bahan pewangi dari bunga melati, melalui proses pengolahan
tertentu untuk mendapatkan cita rasa yang khas, disamping rasa
tehnya masih tetap ada. Seduhan teh wangi mempunyai aroma
bunga yang berkombinasi dengan rasa tehnya sendiri.
BAB III
METODE PELAKSANAAN
3.1. Rancangan Praktikum
Praktikum ini merupakan penelitian tindakan yang
dimaksudkan untuk memperoleh peluang-peluang produksi bersih
pada salah satu produksi pertanian yaitu proses produksi teh
yang dimaksudkan untuk pembuatan laporan.
3.2. Ruang lingkup penelitian
Pengupayaaan Produksi Bersih yang dilakukan oleh PTPN VI
KAYU ARO KERINCI difokuskan pada peluang produksi bersih.
3.3. Lokasi penelitian
Penelitian dilakukan di PTPN VI KATU ARO Kerinci Jambi.
3.4. Jenis dan sumber data
Jenis dan data yang digunakan adalah data primer yang
terkait dalam pemilihan peluang produksi bersih dan data
sekunder dari pustaka, internet, catatan-catatan dari
perusahaan dan wawancara langsung dengan karyawan.
3.5. Instrumen penelitian
Kunjungan Kebun dan Pabrik
Wawancara
Studu Pustaka dan Literatur
3.6. Teknik pengumpulan data
Pengamatan lapangan
Wawancara
3.7. Analisa data
Peluang produksi bersih yang dapat diterapkan di
perusahaan teh yang diteliti dievaluasi dari kemungkinan
pengurangan limbah langsung pada sumber dan kemungkinan
pemanfaatan. Dan sebagai tolak ukur evaluasi pengelolaan
lingkungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan adalah
dengan menggunakan Baku Mutu Limbah.
3.8. Waktu penelitian
Kegiatan Penelitian ini dilakukan pada Sabtu 21 Juni 2014
pukul 09:00 WIB sampai selesai. Penelitian dilakukan oleh 40
mahasisiwa Universitas Jambi fakultas pertanian program D3
agribisnis yang mengontrak mata kuliah yang bersangkutan.
BAB IV
GAMBARAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) KEBUN
KAYU ARO
4.1 Sejarah singkat Perusahaan
a. Kebun kayu aro dibuka pada tahun 1925 sampai dengan 1928
oleh perusahaan Belanda yaitu NV. HVA (Namlodse Venotchaaf
Handle Veriningging Amsterdam). Penanaman pertama dimulai pada
tahun 1929 dan pabrik teh didirikan tahun 1932. Sejak mulai di
buka, the yang dihasilkan adalah jenis teh hitam (Ortodox).
Pada tahun 1959, melalui PP No. 19 Tahun 1959 tentang
“Penentuan Perusahaan Petani/Perkebunan Milik Belanda yang
dikenakan Nasionalisasi’, dimbil alih Pemerintah Republik
Indonesia.
Sejak itu berturut-turut kebun Kayu Aro mengalami
perubahan status/organisasi dan manajemen sesuai dengan
keadaan yang berlaku, yaitu :
- Tahun 1959 s/d. 1962 Unit Produksi dari PN Aneka Tanaman
VI.
- Tahun 1963 s/d. 1973 bagian dari PNP Wiayah I Sumatera
Utara.
- Mulai tanggal 01 Agustus 1974 menjadi salah satu kebun
dari PT. Perkebunan VIII yang berkedudukan di JL. Kartini
No. 23 Medan.
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11/1996 tanggal 14
Pebruari 1996 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.
165/KMK.016/1996. Tanggal 11 Maret 1996. Seluruh PTP yang
adadi Indonesia diadakan kosolidasi Ex. PTP VIII dan PTP
lainnya yang ada di Sumbar/Jambi menjadi PTP Nusantara VI
(Persero).
Maka terhitung mulai tanggal 11 Maret 1996, Kebun Kayu
Aro telah merupakan menjadi salah satu Unit Kebun dari PTP.
Nusantara VI yang berkantor pusat di JL. Khatib Sulaiman No.
54 PO. BOX 349 padang dan JLn. Zanir Haviz No. 1 Kota Baru
Jambi.
4.2 Letak/Tempat Perusahaan
Kebun Kayu Aro terletak di desa bedeng VIII Kecamatan
Kayu Aro Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, dengan jarak :
- Dari Ibukota Kabupaten (Sungai Penuh) ± 37 km- Dari Ibukota Propinsi (Jambi) ± 452 km- Dari Pelabuhan terekat, Teluk Bayur Padang
Via Pesisir Selatan ±325 km Via MUara Labuh ± 237 km
4.3 Data Geografis
a. Elevasi/Tinggi dari Permukaan Laut
- Posisi/Letak Kebun 1°46.978° LS s/d 101° 16.856° BT- Elevasi Pabrik 1.430 m
- Elevasi Kebun terendah 1.401 m
- Elevasi Kebun tertinggi 1.715 m
b. Iklim Cuaca
- Curah Huajn setahun rata-rata 2.000 mm
- Hari Hujan setahun rata-rata 200 Hari
- Sian Matahari setahun rata-rata 6 Jam/hari
- Suhu Udara Antara 17° - 23° C suhu minimum 5° C
- Kelembaban Nisibi/RH antara 70 – 95 %
c. Jenis Tanah
- Jenis tanah dominan Jenis Andonsol
4.4 Areal Hak Guna Usaha (HGU)
Sertifikat HGU No. 2 tanggal 08 mei 2002
a. Luas lahan yang ditanami.
- Tanaman menghasilkan (RKAP 2005) : 2.552,69 Ha
- Tanaman belum menghasilkan 2006 : 72 Ha
- Rencana Tanaman Ulang Tahun 2006 : - Ha
Jumlah areal teh 2.624,69 Ha
b. Luas lahan belum/tidak ditanami
- Emplasment/bangunan : 105,77 Ha
- Jurang/kuburan/Hutan : 227,21 Ha
- Jalan/Jembatan : 56,93 Ha
JUMLAH : 389,91 Ha
c. Luas HGU ( a + b ) : 3.014,60 Ha
4.5 Statistik Produksi
a. Perkembangan Produksi Selama Dasawarsa terakhir sbb :
Tahun Daun Basah Teh Kering1990 22.270.848 kg 4.567.073 kg1991 23.610.479 kg 4.873148 kg1992 24.118.861 kg 5.025.380 kg1993 26.049.594 kg 5.455.686 kg1994 23.334.770 kg 4.914.334 kg1995 25.374.508 kg 5.081.388 kg1996 24.762.283 kg 5.378.745 kg1997 24.445.865 kg 5.495.195 kg
1998 26266.105 kg 5.776.052 kg1999 24.919.610 kg 5.480.285 kg2000 24.811.260 kg 5.458.376 kg2001 27.268.403 kg 6.087.940 kg2002 26.853.130 kg 5.966.234 kg2003 26.998.470 kg 5.902.567 kg2004 25.595.735 kg 5.360.250 kg2005 26.641.249 kg 5.867.514 kg2006 26.447.905 kg 5.817.228 kg
RKAP’2007 28.329.072 KG 6.481.725 kg
Produksi sampai dengan Bulan Desember 2006 :
Daun Basah : 26.447.905 Kg Timb. Kebun
: 26.317.230 Kg Timb. Pabrik
Teh Kering/Jadi : 5.817.228 Kg
b. Pelabuhan Export
1. Pelabuhan Export via pelabuhan Belawan sedang pelabuhan
Teluk Bayur adalah sebagai
Gudang Transit.
2. Pelabuhan Export via Tanjung Priok.
3. Penjualan Export dan Lokal langsung ditangani oleh Kantor
Direksi PTP. Nusantara VI Jambi melalui Kantor Pemasaran
Bersama (kPB) Jakarta dengan menggunakan Sistem Lelang Contoh
(Auction).
c. Pemasaran Teh Export
- Negara Eropa Barat dan Eropa Timur
- Negara Rusia dan Negara-negara bekas pecahan Rusia
- Negara Timur Tengah
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Data Umum Perkebunan Teh dan Pabrik PTPN VI KAYU ARO
Kerinci
5.1.1 Sejarah Perusahaan
Kebun Kayu Aro dibuka pada tahun 1925 sampai dengan 1928
oleh Perusahaan Belanda yaitu NV. HVA (Namlodse Venotchaaf
Handle Veriniging Amsterdam). Penanaman pertama dimulai pada
tahun 1929 dan Pabrik Teh didirikan tahun 1932. Sejak mulainya
dibuka Teh yang dihasilkan adalah Jenis Teh Hitam (Ortodox).
Pada tahun 1959, melalui PP No. 19 Tahun 1959 tentang “
Penentuan Perusahan Pertanian/Perkebunan milik Belanda yang
dikenakan Nasionalisasi “, diambil alih Pemerintah Republik
Indonesia. Sejak itu berturut-turut Kebun Katu Aro mengalami
perubahan Status/Organisasi dan manajemen sesuai dengan
keadaan yang berlaku, yaitu:
- Tahun 1959 s/d. 1962 Unit Produksi dari PN Aneka Tanaman
VI
- Tahun 1963 s/d. 1973 bagian dari PNP Wilayah I
SumateraUtara
- Mulai tanggal 01 Agustus 1974 menjadi salah satu Kebun
dari PT. Perkebunan VIII yang berkedudukan di JL. Kartini
No. 23 Medan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11/1996 Tanggal 14
Pebruari 1996 dan Surat Keputusan Mentri keuangan RI No.
165/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996, PTP VIII Termasuk
Danau kembar dan PTP Lainnya yang ada di Sumbar/Jambi
dikonsilidasi menjadi menjadi PTP Nusantara VI (Persero). Maka
terhitung tanggal 11 Maret 1996, Danau kembar telah menjadi
salah satu Unit Kebun dari PTP Nusantara VI (Persero) yang
berkantor pusat di Jalan Zainir Havis No. 1 Kota Baru Jambi.
4.1.2 Letak/Tempat Perusahaan Dan Geografis
Danau kembar terletak di Desa Bedeng VIII Kecamatan Danau
kembar Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, dengan jarak :
Dari Ibu Kota Kabupaten (Sungai Penuh) ± 37 km.
Dari Ibu Kota Propinsi (Jambi) ± 452 km.
Dari Pelabuan terdekat, Teluk Bayur Padang :
- Via Pesisir Selatan ± 325 km.
- Via Muara Labuh ± 237 km.
Secara geogarfis, Danau kembar terletak pada elevasi/tinggi
dari permukaan laut antara lain :
1. Posisi/letak kebun : 1046, 9780 LS s/d. 1010 16, 8560 BT
2. Elevasi Pabrik : 1.430 m. Dpl
3. Elevasi Kebun Terendah : 1.401 m. Dpl
4. Elevasi Kebun Tertinggi : 1.715 m. Dpl
Di daerah Danau kembar, kondisi iklim/cuaca yang terjadi dalam
1 tahun sebagai berikut:
· Curah hujan setahun rata-rata : 2.000 mm
· Hari hujan setahun rata-rata : 200 Hari
· Sinar Matahari setahun rata-rata : 6 Jam/Hari
· Suhu Udara antara 170 – 230 dan suhu minimum 50 C
· Kelembaban Nisbi/RH antara 70 – 95%
Jenis tanah yang dominan di daerah Danau Kembar adalah
memiliki jenis tanah Andosol.
4.1.3 Areal Hak Guna Usaha (HGU)
Berdasarkan Sertifikat HGU No. 2 tanggal 08 Mei 2002,
Kebun Danau kembar memiliki Areal/lahan yang telah ditanami
dan belum/tidak ditanami antara lain :
1. Areal/Lahan yang ditanami
· Tanaman menghasilkan (RKAP 2009) : 2.338,65 Ha
· Tanaman Non Produktif : 94,04 Ha
· Rencana Tanaman Ulang/Compacting : 114,00 Ha
· Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) : 78,00 Ha
2. Jumlah Areal/Lahan Teh : 2.624,69 Ha
Areal/Lahan Teh tersebut terbagi dalam beberapa bagian
Afdeling :
· Areal/Lahan Afd. A : 274,87 Ha
· Areal/Lahan Afd. B : 280,12 Ha
· Areal/Lahan Afd. C : 308,72 Ha
· Areal/Lahan Afd. D : 390,40 Ha
· Areal/Lahan Afd. E : 330,59 Ha
· Areal/Lahan Afd. F : 356,83 Ha
· Areal/Lahan Afd. G : 369,80 H
· Areal/Lahan Afd. H : 313,36 Ha
3. Jumlah (Afd. A s.d H) : 2.624, 69 Ha
Areal/Lahan belum/tidak ditanami.
· Emplasment/Bangunan : 105,77 Ha
· Jurang/Kuburan/Hutan : 227,21 Ha
· Jalan/Jembatan : 56,93 Ha
Jumlah : 389,91 Ha
Maka jumlah areal/lahan Danau kembar adalah 3.014,60 Ha
4.2 Manajemen Tanaman Teh PTPN VI Kayu Aro Kerinci
4.2.1 Budi Daya Tanaman Teh
1. SYARAT TUMBUH TANAMAN TEH
Iklim untuk budidaya teh yang tepat yaitu dengan curah
hujan tidak kurang dari 2.000 mm/tahun, dengan bulan penanaman
curah hujan kurang dari 60 mm tidak lebih 2 bulan. Tanaman
memerlukan matahari yang cerah. Suhu udara harian tanaman teh
adalah 13-25o C.Kelembaban kurang dari 70%. Dari segi
penyinaran sinar matahari sangat mempengaruhi pertanaman teh.
Makin banyak sinar matahari makin tinggi suhu, bila suhu
mencapai 30o C pertumbuhan tanaman teh akan terlambat.Pada
ketinggian 400 – 800 m kebun-kebun teh memerlukan pohon
pelindung tetap atau sementara. Disamping itu perlu mulsa
sekitar 20 ton/ha untuk menurunkan suhu tanah. Suhu tanah
tinggi dapat merusak perakaran tanaman, terutama akar dibagian
atas.
Faktor iklim lain yang harus diperhatikan adalah tiupan
angin yang terus menerus dapat menyebabkan daun rontok. Angin
dapat mempengaruhi kelembaban udara serta berpengaruh pada
penyebaran hama dan penyakit. Untuk media tanamnya jenis tanah
yang cocok untuk teh adalah Andasol, Regosol, dan Latosol.
Namun teh juga dapat dibudidayakan di tanah podsolik
(Ultisol), Gley Humik, Litosol, dan Aluvia. Teh menyukai tanah
dengan lapisan atas yang tebal, struktur remah, berlempung
sampai berdebu, dan gembur. Derajat kesamaan tanah (pH)
berkisar antara 4,5 sampai 6,0. Berdasarkan ketinggian tempat,
kebun teh di Indonesia dibagi menjadi tiga daerah yaitu
dataran rendah sampai 800 m dpl, da-taran sedang 800-1.200 m
dpl, dan dataran tinggi lebih dari 1.200 m dpl. Perbedaan
ketinggian tempat menyebabkan perbedaan pertumbuhan dan
kualitas teh. Ketinggian tempat tergantung dari klon, teh
dapat tumbuh di dataran rendah pada 100 m dpl sampai
ketinggian lebih dari 1000 m dpl.
2. PERSIAPAN LAHAN
Persiapan lahan dimulai dengan pembongkaran
tunggul-tunggul dan pohon sampai ke akar agar tidak menjadi
sumber penyakit akar. Lahan yang digunakan untuk penanaman
baru dapat berupa hutan belantara, semak belukar atau lahan
pertanian lain, yang telah diubah dan dipersiapkan bagi
tanaman teh. Secara umum urutan kerja persiapan lahan bagi
penanaman baru adalah sebagai berikut.
1. Survey dan pemetaan tanah
Survey dan pemetaan tanah perlu dilakukan karena berguna dalam
me-nentukan sarana dan prasarana yang akan dibangun seperti
jalan-jalan kebun untuk transportasi dan kontrol, pembuatan
fasilitas air, serta pembuatan peta kebun dan peta kemampuan
lahan.
2. Pembongkaran pohon dan tunggul
Pelaksanaan Pembongkaran pohon dan tunggul dapat dilakukan
dengan tiga cara berikut.
a. Pohon dan tunggul dibongkar langsung secara tuntas sampai
keakar-akarnya, agar tidak menjadi sumber penyakit akar
bagi tanaman teh.
b. Pohon dapat dimatikan terlebih dahulu sebelum dibongkar
dengan cara pengulitan pohon (ring barking), mulai dari
batas permukaan tanah sampai setinggi 1m. setelah 6-12
bulan, pohon akan kering dan mati.
c. Pohon dimatikan dengan penggunaan racun kimia atau
aborosida seperti Natrium arsenat atau Garlon 480 P.Pada
cara ini kulit batang dikupas berkeliling selebar 10-
20cm, pada ketinggian 50-60 cm dari atas tanah, kemudian
diberikan racun dengan dosis 1,5 g/cm lingkaran batang.
Pohon akan mati setelah 6-12 bulan, yaitu setelah
cadangan pati dalam akar habis. Batang ditebang pada
batang leher akar dan tunggul ditimbun sedalam 10 cm
dengan tanah.
3. Pembersihan semak belukar dan gulma
Setelah dilaksanakan pembongkaran dan pembuangan
pohon, semak belukar dibabat, kemudian digulung kemudian
dibuang ke jurang yang tidak ditanami teh, atau ditumpuk di
pinggir lahan yang akan ditanami. Sampah tersebut tidak boleh
dibakar karena pembakaran akan merusak keadaan teh, membunuh
mikroorganisme tanah yang berguna, dan akan membakar humus
tanah, sehingga akan menyebabkan tanah menjadi tandus.
Pembersihan gulma dapat juga menggunakan bahan kimia yaitu
herbisida dengan dosis yang telah tercantum dalam merk dagang.
4. Pengolahan tanah
Maksud pengolahan tanah adalah mengusahakan tanah
menjadi subur, gembur dan bersih dari sisa-sisa akar dan
tunggul, serta mematikan gulma yang masih tumbuh. Areal yang
akan ditanami dicangkul sebanyak dua kali. Pencangkulan
pertama dilakukan sedalam 60 cm untuk menggemburkan tanah,
membersihkan sisa-sisa akar dan gulma. Sedangkan pencangkulan
kedua dilakukan setelah 2-3 minggu pencangkulan pertama,
dilakukan sedalam 40 cm untuk maratakan lahan.
5. Pembuatan jalan dan saluran drainase
Setelah pengolahan selesai selanjutnya dilakukan
pengukuran dan pematokkan. Ajir/patok dipasang setiap jarak 20
m, baik kearah panjang maupun kearah lebar. Dengan demikian
akan terbentuk petakan-petakan yang berukuran 20m x 20m atau
seluas 400 m2.
Selesai membuat petakan selanjutnya pembuatan
jalan kebun. Dalam pembuatan jalan kebun ini hendaknya
dipertimbangkan faktor kemiringan lahan serta faktor pekerjaan
pemeliharaan dan pengangkutan pucuk. Dengan demikian jalan
kebun dibuat secukupnya, tidak terlalu banyak yang menyebabkan
tanah terbuang dan tidak terlalu sedikit sehingga menyulitkan
pelaksanaan pekerjaan di kebun.
3. PEMBIBITAN
Tanaman teh dapat diperbanyak secara generative
maupun secara vegetative. Pada perbanyakan secara generative
digunakan bahan tanam asal biji, sedangkan perbanyakan secara
vegetative digunakan bahan tanaman asal setek berupa klon.
Biji yang baik ditandai dengan beberapa ciri, antara lain:
a. Kulit biji berwarna hitam dan mengkilap.
b. Berisi penuh, dengan isi biji berwarna putih.
c. Mempunyai berat jenis yang lebih besar dari pada air,
sehingga apabila dimasukkan kedalam air akan
tenggelam.
d. Mempunyai bentuk dan ukuran yang normal.
e. Tidak terserang penyakit, cendawan ataupun kepik biji.
Biji yang dipungut untuk dijadikan benih adalah biji yang
telah jatuh ke tanah, dikumpulkan secara teratur setiap hari,
benih yang digunakan adalah benih yang baik. Sebaiknya biji
segera disemai karena daya kecambah biji teh cepat menurun dan
biji teh mudah menjadi busuk.
1. Penyemaian biji
Persiapan lahan untuk persemaian harus dilaksanakan 6 bulan
sebelum penyemaian benih. Tanah dibersihkan dan dicangkul
sedalam 30 cm, ke-mudian dibuat bedengan. Diantara bedengan
dibuat saluran drainase untuk membuang kelebihan air. Bedengan
diberi atap naungan miring timur-barat dengan sudut kemiringan
300. Pengecambahan biji dimaksudkan untuk memperoleh biji yang
tumbuh seragam dan serempak sehingga memudahkan pemindahannya
ke persemaian bibit atau kekantong plastik.
2. Pemeliharaan dipersemaian bibit asal biji
Untuk memperoleh bibit yang baik, yang tumbuh subur dan sehat
serta terhindar dari gangguan hama dan penyakit, bibit
dipersemaian harus dijaga dengan baik.
Pemeliharaan bibit terdiri atas:
- Penyiraman
- Penyulaman
- Penyiangan
- Pemupukan
- Pengendalian hama dan penyakit
- Pengaturan naungan
3. Pemindahan bibit ke lapangan
Setelah bibit berumur dua tahun, benih yang mempunyai ukuran
lebih besar dari pensil, dapat dibongkar untuk dipindahkan ke
kebun.
Cara pembongkaran bibit adalah sebagai berikut:
a. Dua minggu sebelum bibit dibongkar, batang dipotong
setinggi 15-20 cm dari permukaan tanah.
b. Bibit dibongkar dengan cara mencangkul tanah disekitar
bibit sedalam 60 cm, selanjutnya dicabut dengan hati-
hati, akar tunggang dan akar se-rabut yang terlalu
panjang bisa dipotong.
c. Bibit ini disebut bibit stump, yang sebaiknya ditanam
segera pada hari itu juga di kebun yang telah
dipersiapkan.
d. Bibit yang ukuran batangnya lebih kecil dari pensil
sebaiknya tidak di-gunakan.
Pertanaman teh diarahkan pada cara memperoleh produksi
yang tinggi dan mantap, sehingga perusahaan perkebunan teh
menjadi lebih efisien. Hal ini sulit dicapai apabila digunakan
bahan tanam asal biji. Karena biji merupakan hasil per-
silangan yang dapat menimbulkan perubahan sifat pada
keturunannya.
Pembibitan menggunakan stek merupakan cara yang paling cepat
untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam jumlah yang banyak, dan
jenis klon yang di-tentukan dapat dipastikan sifat
keunggulannya sama dengan induknya. Untuk memperoleh hasil
pembibitan setek berupa setek bibit yang baik, diperlukan
adanya perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang baik dan
tepat waktu.
Adapun lokasi untuk pembibitan, diantaranya:
1. Lokasi terbuka, drainase tanah baik dan tidak becek.
2. Dekat dengan sumber air, untuk keperluan penyiraman.
3. Dekat dengan sumber tanah, untuk mengisi polibag.
4. Lebih baik bila lahan melandai kearah timur, agar
mendapat sinar matahari pagi.
5. Dekat dengan jalan agar memudahkan dalam pengawasan dan
peng-angkutan ke lokasi yang akan ditanami.
Media tanah untuk setek terdiri dari tanah lapisan atas
(topsoil) dan lapisan bawah (subsoil). Syarat-syarat subsoil
yang baik adalah mengandung liat yang relatif tinggi sehingga
dapat menahan ataupun menyerap air lebih lama, kan-dungan
pasir tidak boleh lebih dari 30%, dan bahan organik maksimal
10%. Serta pH ta-nah 4,5 – 5,6. Mengingat pentingnya
penggunaan media yang steril untuk persemaian guna untuk
membantu terciptanya bibit yang sehat dan layak untuk dikem-
bangkan. Karena suatu kondisi media persemaian merupakan salah
satu faktor dalam menentukan keberberhasilan ataupun kegagalan
bibit yang dihasilkan.
Tanah disimpan selama 4-6 minggu dalam bangunan
penyimpanan, dan tanah harus tetap dalam keadaan lembab.
Setelah disimpan, ayaklah tanah menggunakan ayakan kawat yang
berdiameter ± 1 cm. sebelum media tanah di-masukkan kedalam
kantong plastik, terlebih dahulu dicampur dulu dengan pupuk,
fungisida dan tawas. Adapun pengambilan ranting stek atau
stekres mulai dapat diambil 4 bulan setelah pemangkasan. Tanda
bahwa setekres matang ialah apabila pangkal stekres sepanjang
± 10 cm sudah menunjukkan warna coklat. ranting dipotong
dengan pisau tajam. Satu stek terdiri dari satu lembar daun
dengan ruas sepanjang0.5 cm diatas dan 3-4 cm dibawah buku.
Setek ditampung dalam satu tempat yang berisi air bersih. Stek
tidak boleh direndam lebih dari 30 menit. Dari satu ranting
stek hanya digunakan bagian tengahnya saja dan rata-rata
diperoleh 3-4 stek yang baik untuk dijadikan bibit.
Penanaman setek :
1. Satu hari sebelum setek ditanam, kantong plastik/polibag
yang sudah berisi tanah disiram dengan air bersih sampai
cukup basah.
2. Setek dicelupkan dalam larutan Dithane M 45 0,2% selama 1
menit dan Atonik 0,025% selama 2 menit.
3. Setek ditanam dengan mengarah daun ke tangan si penanam.
Arah daun miring ke atas dan tidak boleh saling menutupi
satu sama lain.
4. Setelah itu disiram kembali dengan air bersih secara
hati-hati agar setekan tidak goyah.
5. Bedengan ditutup dengan sungkup plastik
6. Sungkup plastik ditutup selama 3-4 bulan tergantung
pertumbuhan bibit, dan hanya dibuka untuk keperluan
pemeliharaan saja setelah itu segera ditutup kembali
(setelah pemeliharaan selesai)
Langkah-langkah penanaman setek sebagai berikut:
1. Siapkan polibag berukuran 12cm x 25cm yang sudah
berlubang agar memudahkan untuk membuang kelebihan air.
2. Isi kantong plastik dengan media tanah yang sudah dibuat
lebih awal dan telah matang. 1/3 bagian diisi dengan
tanah bawah dan 2/3 bagian diisi dengan tanah bagian
atas.
3. Ambil setek teh yang sudah dipersiapkan dan memenuhi
syarat selanjutnya ditanam dalam polibag tersebut
(Chasandoerjat, 1969).
4. PENANAMAN
Dalam penanaman, hal-hal yang harus diperhatikan adalah
penentuan jarak tanam yang tepat, pengajiran, pembuatan lubang
tanam, teknik penanaman dan penanaman tanaman pelindung yang
diperlukan. Pembuatan lubang tanam dilakukan 1-2 minggu
sebelum dilakukan penanaman. Lubang tanam yang dibuat tepat di
tengah-tengah diantara dua ajir. Ukuran lubang tanamnya
adalah:
1. Untuk bibit asal stump biji: 30 cm x 30 cm x 40 cm.
2. Untuk bibit stek dalam kantong plastik: 20 cm x 20 cm x
40 cm.
Ada dua kegiatan dalam proses penanaman, yaitu:
1. Pemberian pupuk dasar
Pupuk dasar yang dianjurkan terdiri atas Urea 12,5 g + TSP 5 g
+ KCl 5 g per lubang. Apabila pH tanah diatas 6, maka lubang
tanam diberikan belerang murni (belerang cirrus) sebanyak 10-
15 g per lubang.
2. Cara penanaman
a. Menanam bibit stump
Bibit stump biasanya ditanam pada umur 2 tahun. Bibit ditanam
dengan cara dimasukkan ke dalam lubang tanam, persis di
tengah-tengah lubang, dengan leher akar tepat dipermukaan
tanah. Selanjutnya lubang tanam ditimbun dan dipadatkan dengan
diinjak. Bibit tidak boleh miring dan tanah di sekitar lubang
tanam diratakan.
b. Menanam bibit asal stek
Mula-mula kantong plastik disobek pada bagian bawah dan
sampingnya untuk memudahkan melepaskan bibit dari plastik.
Ujung kantong plastik bagian bawah yang telah sobek ditarik
keatas sehingga bagian bawah kantong plastik terbuka .
selanjutnya bibit dipegang dengan tangan kiri, disanggga
dengan belahan bambu, kemudian dimasukkan ke dalam lubang,
sementara tangan kanan menimbun lubang dengan tanah yang
berada di sekitar lubang dengan menggunakan kored.
Adapun untuk penanaman pohon pelindung atau pohon naungan
pertanaman teh terdiri atas pohon pelindung sementara dan
pohon pelindung tetap. Untuk dataran rendah dan sedang, pohon
pelindung sangat diperlukan oleh tanaman teh agar
pertumbuhannya baik. Jenis – jenis pohon pelindung, yaitu :
1. Pohon pelindung sementara
Pohon pelindung sementara adalah pupuk hijau seperti Theprosia
sp. atau Crotalaria sp. Penanaman pohon pelindung sementara
dilakukan setelah penanaman teh selesai. Kebutuhan benih pupuk
hijau tersebut adalah 10 kg-12 kg/ha.
2. Pohon pelindung tetap
Penanaman pohon pelindung tetap diutamakan untuk daerah dengan
ketinggian kurang dari 1.000 m dpl. Penggunaan pohon pelindung
tetap bukan jenis Leguminoceae, ini tidak dianjurkan. Jenis
pelindung yang akan ditanam harus dipilih yang memenuhi
persyaratan sebagai pelindung, yaitu memilki mahkota yang
baik, perakarannya dalam dan kuat, dan resistensinya terhadap
serangan hama atau penyakit baik.
Agar pohon pelindung tetap berfungsi baik pada tanaman teh,
pohon pelindung harus sudah dapat melindungi tanaman teh pada
saat tanaman teh berumur 2-3 tahun. Untuk itu, pohon pelindung
sebaiknya ditanam satu tahun sebelum dilakukan penanaman teh.
5. PEMELIHARAAN
1. Pemeliharaan dan pemangkasan
Tanaman teh yang belum menghasilkan mendapat
naungan sementara dari tanaman pupuk hijau seperti Crotalaria
sp. atau Theprosia sp. Namun sementara ini biasa ditanam
selang dua baris dari tanaman teh, dan pada umur sekitar enam
bulan tingginya telah mencapai lebih dari satu meter. Agar
tanaman pupuk hijau ini tidak mengganggu pertumbuhan tanaman
teh, perlu dilakukan pemangkasan.
Pemangkasan dilakukan pada tinggi 50 cm dan sisa
pangkasan dihamparkan sebagai mulsa disekitar tanaman.
Pemangkasan tanaman pupuk hijau dilakukan setiap enam bulan
sekali yaitu pada waktu musim hujan. Jangan melakukan
pemangkasan pada musim kemarau karena pada saat itu tanaman
teh muda membutuhkan naungan.
2. Pengendalian gulma
Pengendalian gulma di perkebunan teh merupakan salah satu
kegiatan rutin yang sangat penting dalam pemeliharaan tanaman
teh. Populasi gulma yang tumbuh tidak terkendali, akan
merugikan tanaman teh karena terjadinya persaingan di dalam
memperoleh unsur hara, air, cahaya matahari, dan ruang tumbuh.
Jenis-jenis gulma tertentu diduga pula mengeluarkan senyawa
racun (allelopati) yang membahayakan tanaman teh.
Gulma akan menimbulkan masalah besar terutama pada
areal tanaman teh muda atau pada areal tanaman teh produktif
yang baru dipangkas. Hal ini sebabkan sebagian besar permukaan
tanah terbuka dan secara langsung mendapatkan sinar matahari,
sehingga perkecambahan maupun laju per-tumbuhan berbagai jenis
gulma berlangsung sangat cepat. Pengendalian gulma pada
pertanaman teh bertujuan untuk menekan serendah mungkin
kerugian yang ditimbulkan akibat gulma, sehingga diperoleh
laju pertumbuhan tanaman teh dan produksi pucuk yang maksimal.
3. Pengendalian Hama dan Penyakit
Produksi dan kualitas tanaman teh dipengaruhi oleh
adanya tidaknya gangguan yang disebabkan oleh penyakit
tanaman. Penyakit yang sering menyerang tanaman teh dan cara
pengendaliannya sebagai berikut :
a. Penyakit Cacar Teh (Blister blight)
Gejala yang nampak, daun teh yang terserang terlihat bercak
berwarna putih campur hijau. Bercak terlihat seperti benjolan
kecil, terlihat berwarna hitam dan kadang berlubang. Tanaman
yang terserang daunnya mengering dan akhirnya mati.
Cara pengendalian sebagai berikut :
- Mengurangi pohon pelindung atau mengganti pohon pelindung
yang besar dengan pohon pelindung yang kecil
- Mengatur periode pemangkasan
- Pemetikan dilakukan dengan daur yang pendek (kurang dari
9 hari)
- Menanam klon yang tahan terhadap cacar antara lain : PS1,
RB 1, GMB1, GMB 2, GMB 3, GMB 4 dan GMB 5.
- Tanaman yang terserang disemprot dengan Coper oxychloride
50% WP 0,2% atau Perenox 0,2% dengan interval 1 minggu.
Penyakit cacar juga dapat disebabkan oleh jamur
Exobasidium vexans Massae berasal dari Assam, India. Untuk
pertama kalinya penyakit ini ditemukan di Indonesia pada tahun
1949, yaitu di perkebunan Bah Butong, Sumatera Utara. Sejak
saat ini penyakit cacar meluas ke hampur seluruh perkebunan
teh di Indonesia, dan menjadi penyakit yang paling merugikan,
terutama untuk kebun-kebun teh di dataran tinggi. Penyakit
cacar dapat mengakibatkan kehilangan hasil sampai dengan 40%
dan penurunan kuallitas teh jadi, yang ditandai berkurangnya
kandungan theaflavin, thearubigin, kafein, substansi polimer
tinggi, dan fenol total pucuk.
b. Penyakit Cendawan Akar Merah Bata (Poria hypolatertia)
Gejala yang nampak, pada permukaan akar terdapat benang-
benang berwarna putih. Benang ini selanjutnya mengeras dan
liat, warnanya menjadi merah sampai merah tua. Pada serangan
yang sudah lanjut benang ini dapat mengikat butir-butir pasir
dan tanah sehingga terlihat seperti kerak-kerak yang menjalar
diatas tanah. Bila serangan sudah parah, tanaman akan mati dan
benang tersebut berubah warnanya menjadi hitam.
Cara pengendalian :
- Membongkar dan membakar tanaman-tanaman yang terserang,
termasuk pohon pelindung yang terseang sampai ke akar-
akarnya.
- Membuat saluran draenasi secukupnya dan tidak menanam
pohon pelindung yang peka terhadap jamur akar.
- Melakukan fumigasi dengan Methyl Bromida dengan cara
sebagai berikut :
Methyl Bromida dialirkan melalui pipa plastik dengan
dosis 227 gram/10 m2 tanah disungkap selama 14 hari, dan
kemudian satu bulan setelah sungkup dibuka tanah dapat
ditanami teh,
- Melakukan fumigasi dengan Vapam dengan cara, menyuntikkan
8 ml Vapam pada lubang dengan kedalaman 30 cm dan jarak
antar lubang satu sama lain juga 30 cm. Satu bulan
setelah fumigasi tanah dapat ditanami teh kembali.
c. Penyakit Leher Akar (Ustulina máxima)
Gejala yang nampak, leher akar terjadi infeksi dan bagian
bawahnya terdapat noda-noda hitam. Diantara kayu dan kulit
terlihat benang-benang yang khas berbentuk seperti kipas
berwarna putih. Kayu menjadi kering dan terasa lembek serta
ada garis-garis hitam.
Cara pengendalian :
1. Bila penyakit baru menyerang, kulit dan kayu yang
terserang dipotong dan ditutup dengan obat penutup luka.
Bila penyakit sudah parah, tanaman dibongkar dan dibakar.
2. Melakukan fumigasi dengan Methyl Bromida dengan cara
sebagai berikut :
Methyl Bromida dialirkan melalui pipa plastik dengan
dosis 227 gram/10 m2 tanah disungkap selama 14 hari, dan
kemudian satu bulan setelah sungkup dibuka tanah dapat
ditanami teh,
3. Melakukan fumigasi dengan Vapam dengan cara, menyuntikkan
8 ml Vapam pada lubang dengan kedalaman 30 cm dan jarak
antar lubang satu sama lain juga 30 cm. Satu bulan
setelah fumigasi tanah dapat ditanami teh kembali.
d. Penyakit akar hitam
Cara pengendalian :
- Membongkar dan membakar tanaman-tanaman yang terserang,
termasuk pohon pelindung yang terseang sampai ke akar-
akarnya serta membersihkan sampah-sampah yang ada pada
tempat yang diserang kemudian dibakar.
- Membuat saluran draenasi secukupnya dan tidak menanam
pohon pelindung yang peka terhadap jamur akar.
- Melakukan fumigasi dengan Methyl Bromida dengan cara
sebagai berikut :
Methyl Bromida dialirkan melalui pipa plastik dengan
dosis 227 gram/10 m2 tanah disungkap selama 14 hari, dan
kemudian satu bulan setelah sungkup dibuka tanah dapat
ditanami teh,
- Melakukan fumigasi dengan Vapam dengan cara, menyuntikkan
8 ml Vapam pada lubang dengan kedalaman 30 cm dan jarak
antar lubang satu sama lain juga 30 cm. Satu bulan
setelah fumigasi tanah dapat ditanami teh kembali.
e. Penyakit Busuk Daun
Penyakit busuk daun biasanya menyerang pada bibit tanaman
melalui stek. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan
Fungisida Benomyl dengan konsentrasi 0,2% yang disemprotkan
kedalam tanah persemaian setelah stek ditanam. Cara lain
adalah dengan melakukan mencelupkan stek yang akan ditanam
kedalam larutan Fungisida Carbamat dengan konsenrasi 0,2%
formulasi.
6. PEMETIKAN
Pemetikan adalah pemungutan hasil pucuk tanaman
teh yang memenuhi syarat-syarat pengolahan. pemetikan
berfungsi pula sebagi usaha membentuk kondisi tanaman agar
mampu berproduksi tinggi secara berkesinambungan. Panjang
pendeknya periode pemetikan ditentukan oleh umur dan kecepatan
pembentukan tunas, ketinggian tempat, iklim dan kesehatan
tanaman. Pucuk teh di petik dengan periode antara 6-12 bulan.
Teh hijau Jepang dipanen dengan frekuensi yang lebih lama
yaitu 55 hari sekali. Disamping faktor luar dan dalam,
kecepatan pertumbuhan tunas baru dipengaruhi oleh daun-daun
yang tertinggal pada perdu yang biasa disebut daun
pemeliharaan.
Tebal lapisan daun pemeliharaan yang optimal adalah 15-20
cm, lebih tebal atau lebih tipis dari ukuran tersebut
pertumbuhan akan terhambat. kecepatan pertumbuhan tunas akan
mempengaruhi beberapa aspek pemetikan, yaitu: jenis pemetikan,
jenis petikan, daur petik, pengaturan areal petikan,
pengaturan tenaga petik, dan pelaksanaan pemetikan.
Beberapa istilah perlu diketahui baik dalam pemetikan maupun
dalam menentukan rumus-rumus pemetikan. Istilah-istilah
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peko adalah kuncup tunas aktif berbentuk runcing yang
terletak pada ujung pucuk, dalam rumus petikan tertulis
dengan huruf p.
2. Burung adalah tunas tidak aktif berbentuk titik yang
terletak pada ujung pucuk dalam rumus petik tertulis
dengan huruf b.
3. Kepel adalah dua daun awal yang keluar dari tunas yang
sebelahnya tertutup sisik. Sisik ini segera berguguran
apabila daun kepel mulai tumbuh. Mula-mula tumbuh daun
kecil berbentuk lonjong, licin, tidak bergerigi, biasa
disebut kepel ceuli. Selanjutnya kepel ceuli diikuti oleh
pertumbuhan sehelai daun kepel yang lebih besar yang
disebut kepel licin. Setelah daun-daun ini terbentuk,
baru diikuti oleh pertumbuhan daun yang bergerigi atau
normal. Daun kepel ini dalam rumus petikan ditulis dengan
huruf k.
4. Daun biasa/normal adalah daun yang tumbuh setelah
terbentuk daun-daun kepel, berbentuk dan berukuran normal
serta sisinya bergerigi. Dalam rumus petik ditulis dengan
angka 1,2,3,4 dan seterusnya tergantung beberapa helai
daun yang terdapat pada pucuk tersebut.
5. Daun muda adalah daun yang baru terbentuk tetapi belum
terbuka seluruhnya, dan dalam rumus pemetikan ditulis
dengan huruf m mengikuti angka (1m, 2m, 3m).
6. Daun tua adalah daun yang berwarna hijau gelap, terasa
keras, dan bila dipatahkan berserat. Dalam rumus
pemetikan ditulis dengan huruf t mengikuti angka (1t, 2t,
3t).
7. Manjing adalah pucuk yang telah memenuhi syarat sesuai
dengan sistem pemetikan yang telah ditentukan.
Macam dan rumus petikan adalah sebagai berikut:
1. Petikan imperial: bila yang dipetik hanya kuncup peko (p
+ 0).
2. Petikan pucuk pentil: bila yang dipetik peko dan satu
lembar daun dibawahnya (p + 1m).
3. Petikan halus: bila yang dipetik peko dengan satu lembar
atau dua lembar daun burung dengan satu lembar daun muda
(p + 1m, b + 1m).
4. Petikan medium: bila yang dipetik peko dengan dua lembar
atau tiga lembar daun muda dan pucuk burung dengan satu,
dua atau tiga lembar daun muda ( p + 2m, p + 3m, b + 1m,
b + 2m, b + 3m).
5. Petikan kasar: bila yang dipetik dengan tiga lembar daun
tua atau lebih daun burung dengan satu, dua, tiga lembar
daun tua (p + 3, p + 4, b + 1t, b + 2t, b + 3t).
6. Petikan kepel: bila daun yang ditinggalkan pada perdu
hanya kepel (p + n/k, b + n/k).
Jenis pemetikan yang dilakukan selama satu daun pangkas
terdiri dari:
1. Pemetikan jendangan
Pemetikan jendangan ialah pemetikan yang dilakukan pada tahap
awal setelah tanaman dipangkas, untuk membentuk bidang petik
yang lebar dan rata dengan ketebalan lapisan daun pemeliharaan
yang cukup, agar tanaman mempunyai potensi produksi yang
tinggi.
2. Pemetikan produksi
Pemetikan produksi dilakukan terus menerus dengan
daur petik tertentu dan jenis petikan tertentu sampai tanaman
dipangkas kembali. Pemetikan produksi yang dilakukan menjelang
tanaman dipangkas disebut “petikan gendesan”, yaitu memetik
semua pucuk yang memenuhi syarat untuk diolah tanpa
memperhatikan daun yang ditinggalkan.
4.2.2 Proses Produksi
Proses produksi yang dilaksanakan di Kebun Kayu Aro
terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama kegiatan
penyediaan bahan baku, kegiatan ini meliputi pemetikan,
pengangkutan dan penerimaan pucuk.
1. Pemetikan
Pemetikan adalah pekerjaan mengambil sebagian dari tunas-
tunas teh beserta daunnya yang masih muda, untuk kemudian
diolah menjadi produk teh kering yang merupakan komoditi
perdagangan. Pemetikan harus dilakukan berdasarkan ketentuan-
ketentuan sistem petikan daun dan syarat-syarat pengolahan
yang berlaku. Pemetikan berfungsi pula sebagai usaha membentuk
kondisi tanaman agar mampu berproduksi tinggi secara
berkesinambungan. Ada dua macam ranting daun yang dipetik dan
digunakan dalam pengolahan teh, yaitu ranting peko dan ranting
burung. Jika dianalisa maka ranting peko akan menghasilkan teh
hijau dengan kualitas lebih baik daripada rantai burung.
Rantai peko adalah ranting yang masih kuncup, masih tergulung
dan tumbuh aktif. Sedangkan ranting burung adalah ranting yang
tidak memiliki kuncup dan merupakan ranting yang tidak aktif
atau dorman. Periode pemetikan dilaksanakan setiap tujuh hari
sekali, dengan system rotasi. Dari area satu bergilir ke are
yang lain. Masa petik produksi yang diterapkan adalah selama
empat tahun. Setelah empat tahun, akan dilakukan pemangkasan
yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas tanaman teh.
Dalam sekali panen bisa mencapai 5 ton daun teh basah per hari
pada musim kemarau dan 20 ton daun the basah per hari pada
musim penghujan.
2. Pengangkutan Pucuk
Pengangkutan pucuk merupakan kegiatan mengangkut pucuk dari
kebun ke pabrik. Sebelum melaksanakanproses pengolahan, pucuk
teh harus dalam keadaan baik, artinya keadaannya tidak
mengalami perubahan selamapemetikan sampai ke lokasi
pengolahan. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan teh yang
bermutu tinggi. Olehkarena itu, proses pengangkutan memiliki
peranan yang sangat penting.Hal yang dilakukan untuk mencegah
kerusakan daun untuk antara lain:
a. Jangan terlalu menekan daun agar daun tidak terperas.
b. Dalam membongkar daun, jangan menggunakan barang-barang
dari besi atau yang tajam agar daun tidak robekatau
patah.
c. Hindari terjadinyan penyinaran terik matahari dalam
waktu lama, lebih dari 3 jam.
d. Jangan menumpuk daun sebelum dilayukan dalam waktu yang
lama (daun segera dilayukan).
3. Penerimaan Pucuk
Pucuk yang sudah sampai di pabrik harus segera diturunkan dari
truk untuk menghindari kerusakan pucuk, selanjutnyapucuk akan
segera ditimbang dan diangkut ke whitering through untuk
dilayukan.
4.2.3 Proses Pembuatan Teh
1. Pemanenan
Dipetik daun teh dari kebun teh. Diusahakan daun teh yang
dipetik adalah pucuk daun (peko), hal ini bertujuan agar mutu
teh yang dihasilkan pada akhir proses memiliki kualitas yang
bagus.
2. Pelayuan
Menggunakan kotak untuk melayukan daun, merupakan kotak yang
diberikan kipas untuk menghembuskan angin ke dalam kotak atau
daun teh disebar secara merata di atas rak dan diangin-
anginkan secara alami selama 24 jam.Proses pelayuan merupakan
langkah pertama pada pengolahan teh hitam. Proses ini
bertujuan memekatkan cairan sel sampai kondisi optimum untuk
berlangsungnya proses oksidasi enzimatis polifenol teh. Selain
itu pelayuan akan menghasilkan kondisi fisik daun yang
optimum untuk digulung. Pengurangan air secara drastis pada
pelayuan dapat menyebabkan perubahan struktur enzirn yang
berperan dalam oksidasi polifenol, oleh sebab itu tingkat
layu dan laju pelayuan selalu menuntut pengendalian yang
serius.
3. Pembalikan 2 – 3 kali
Bertujuan untuk meratakan proses pelayuan.
4. Penggilingan
Bertujuan untuk memecah sel-sel daun, sehingga cairan dalam
sel serta enzim dapat keluar dan proses fermentasi dapat
berlangsung secara merata.
Penggilingan bertujuan mempertemukan polifenol teh dengan
enzirn oksidase dengan jalan merusak membran dan dinding sel
sehingga cairan sel keluar kepermukaan pucuk dan bertemu
dengan oksigen dari udara. Peristiwa ini merupakan awal
oksidasi senyawa polifenol secara enzimatis yang akan
membentuk mutu dalam “inner quality” teh jadi ”made tea”. Hasil
penggilingan dipengaruhi oleh tekanan pada bahan olah,
kecepatan putar silinder penggiling dan lamanya waktu
penggilingan. Dengan mengendalikan faktor-faktor yang
berpengaruh tersebut mutu bubuk hasil penggilingan dapat
terkendali.
5. Fermentasi
Proses fermentasi dimulai sejak proses penggulungan dimulai
dan berakhir pada saat proses pengeringan dilakukan. Proses
ini merupakan reaksi oksidasi yang sekaligus bertanggung jawab
atas pembentukan flavor, aroma dan warna dari teh hitam yang
dihasilkan. Selama proses oksidasi ini, warna daun teh berubah
menjadi gelap dan mulai terbentuk rasa pahit. Proses oksidasi
harus dihentikan pada saat aroma dan flavor dari teh hitam telah
muncul atau terbentuk. Pengendalian oksidasi polifenol
(fermentasi) teh bertujuan untuk mengatur komposisi substansi
tanin/katekin dan hasil oksidasinya berupa tehaflavin dan
teharubigin. Jumlah substansi tehaflavin dan teharubigin yang
dihasilkan selama proses oksidasi akan menentukan sifat air
seduhan yang sering digambarkan oleh “tea taster” sebagai colour,
strength, quality dan briskness. Komposisi terbaik antara tehaflavin
dengan teharubigin teh hasil olahan orthodox adalah 1/10
sampai 1/12. Teh akan kehilangan briskness dan strength pada
komposisi ratio tehaflavin dengan teharubigin lebih besar atau
sama dengan 1/20. Selama proses ini berlangsung terjadi
perubahan warna dari hijau ke coklat dan kemudian menjadi
hitam. Perubahan warna ini dapat dimanfaatkan untuk
mendapatkan tingkat oksidasi polifenol yang optimum.
6. Pengeringan
Proses pengeringan ini akan menghentikan proses fermentasi
yang terjadi dengan menghentikan aktifitas enzim yang berperan
dalam proses fermentasi tersebut. Selama proses ini
berlangsung yang perlu diperhatikan adalah suhu dan lama
pengeringan. Hal ini untuk memastikan bahwa produk telah
kering secara merata. Jika proses pengeringan dilakukan
terlalu cepat maka produk akhir yang dihasilkan nanti akan
memiliki kualitas yang rendah.
7. Sortasi
Teh yang berasal dari pengeringan ternyata masih heterogen
atau masih bercampur baur, baik bentuk maupun ukurannya.
Selain iu teh juga masih mengandung debu, tangkai daun, dan
kotoran lain yang akan sangat berpengaruh pada mutu teh
nantinya. Untuk itu sangat dibutuhkan proses penyortiran atau
pemisahan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu bentuk dan
ukuran teh yang seragam sehingga cocok untuk dipasarkan dengan
mutu terjamin. Setiap jenis teh mempunyai standar ukuran
berdasarkan besar kecilnya partikel yang dipisah-pisahkan oleh
ayakan dengan ukuran mesh nomor yang berbeda-beda sesuai
dengan standar yang telah ditentukan. Didalam mesin sortasi
terdapat beberapa jenis ayakan yang kasar sampai yang halus,
sehingga teh kering yang keluar dari mesin sortir akan terbagi
menjadi tiga golongan besar yaitu:
1. Teh Daun (Leafy grades)
a. Orange pecco (OP)
b. Pecco (P)
c. Pecco Souchon (PS)
d. Souchon (S)
2. Teh Remuk (Broken grades)
a. Broken Orange Pecco(BOP)
b. Broken Pecco (BP)
c. Broken Tea (BT)
3. Teh Halus
a. Fanning (F)
b. Dust (D)
Proses sortasi kering di Perkebunan Teh Kayu Aro bertujuan
untuk mendapatkan bentuk, ukuran partikel teh yang seragam dan
bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.
Selain tujuan diatas sortasi di Kebun Kayu Aro juga bertujuan
untuk :
a. Memisahkan teh kering menjadi beberapa grade sesuai dengan
ukuran partikel.
b. Membersihkan teh dari serat, tangkai dan bahan-bahan lain
misalnya debu.
Adapun nama-nama produk Teh Kebun Kayu Aro antara lain yaitu
1. Teh Celup 25T :Rp. 3.100
2. Teh Seduh 250 Gram :Rp. 5.500
3. Teh Seduh 50 Gram :Rp. 1.200
4. Teh Seduh 50 Gram Special Blend :Rp. 1.000
5. Teh Seduh 500 Gram Resto :Rp.7.000
BAB V
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Kebun ini dibangun oleh NV. HVA ( Holand Vereniging
Amasterdam tahun 1925, setahun kemudian hamparan lahan yang
berbukit-bukit mulai ditanam teh, sampai saat ini luas kebun
teh Danau Kembar mencapai 3000 hektar. “ Keistimewaan Teh Kayu
Aro ini. Tanaman yang ada sekarang merupakan tanaman varitas
yang ditanam sejak tahun 1926. Setiap tahun produksi kebun
Danau Kembar ini mencapai 5.500 ton dalam jenis teh hitam
orthodox. Diolah dipabriknya di Bedeng Delapan, Danau kembar,
yang merupakan pabrik teh terbesar di dunia, dengan pengolahan
teknologi tradisional. Pabrik ini dibangun tahun 1970 lalu.
Produksi teh hitam ini di ekspor ke manca negara, seperti
Eropah Barat, Eropah Timur, Rusia, Timur Tengah, India,
Srilangka, Amerika dan Australia. Sekitar delapan puluh lima
persen. Produksi teh Danau Kembar diekspor, sisa nya untuk
dalam negeri.
Keunikan teh Danau Kembar adalah dari aroma dan cita rasa yang
spesifik, banyak digunakan produsen sebagai bahan utama
pencampur untuk memperoleh citarasa teh yang berkualitas. Teh
Danau Kembar dalam proses produksinya tanpa dicampur bahan
kimia ( bahan pengawet, pewarna dan perasa) sehingga sangat
bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung zat antara lain
Riboflavin zat yang membantu pertumbuhan pencernaan dan
vitalitas serta zat polifenol yang merupakan anti oksidan
jenis biovanoid yang 100 kali lebih efektiv dari vitamin C dan
25 kali lebih efentif dari vitamin E.
5.2 Saran
Bagi perusahaan seharusnya tidak menjual semua produk teh yang
berkualitas tinggi ke luar negeri.
LAMPIRAN