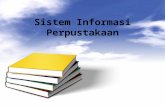korelasi high sensitivity c-reactive protein - perpustakaan ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of korelasi high sensitivity c-reactive protein - perpustakaan ...
i
KORELASI HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN(hs-CRP) DAN KOLESTEROL LOW DENSITY LIPOPROTEIN
(LDL) PADA PASIEN HIPERTENSI NON OBES
Correlation of High Sensitivity C – Reactive Protein (Hs-CRP) and Cholesterol Low Density Lipoprotein (LDL) in
Non Obese Hypertensive Patients
SUHARTINI
PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR2018
ii
KORELASI HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN(hs-CRP) DAN KOLESTEROL LOW DENSITY LIPOPROTEIN
(LDL) PADA PASIEN HIPERTENSI NON OBES
Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi
Biomedik
Disusun dan diajukan oleh
SUHARTINI
Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2018
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : SUHARTINI
Nomor mahasiswa : P1505216005
Program studi : BIOMEDIK
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini
benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan
pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian
hari terbukti atau tidak dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan
tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas
perbuatan tersebut.
Makassar, Nopember 2018
Yang menyatakan
SUHARTINI
v
PRAKATA
Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji hanya milik Allah Azza wa
Jalla, Rabb semesta alam. Penulis panjatkan kehadirat-Nya yang telah
memberikan limpahan rahmat, karunia dan kekuatan sehingga tesis ini
dapat selesai dengan baik. Salam dan salawat senantiasa penulis
haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallalahu ‘Alaihi Wassallam
sebagai satu-satunya uswa dan qudwah dalam menjalankan aktivitas
keseharian di atas permukaan bumi ini, juga kepada keluarga beliau, para
sahabatnya, dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah meniti
jalan hidup ini, hingga akhir zaman dengan Islam sebagai satu-satunya
agama yang diridhai Allah Azza wa jalla. Penulis menyadari bahwa tesis
ini, terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan
hatinya oleh Sang Khalik untuk memberikan dukungan, bantuan dan
bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima
kasih yang tak terhingga, atas segala bantuan moril dan materil yang
diberikan kepada penulis.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya,
penulis sampaikan kepada:
1. dr.Uleng Bahrun, Ph.D., Sp.PK. (K)., selaku Ketua Konsentrasi
Kimia Klinik Prodi Biomedik Sekolah Pasca Sarjana UNHAS dan
pembimbing I atas segala perhatian dan keikhlasan dalam
vi
meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran-saran
pemikiran kepada Penulis.
2. Prof. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK (K) selaku pembimbing II atas
segala perhatian dan keikhlasan dalam meluangkan waktu
membimbing dan memberikan saran-saran pemikiran kepada
Penulis.
3. Dr. dr. Ilhamjaya Patellongi, M.Kes, Dr. dr. Sitti Rafiah, M.Si, Dr. dr.
Nurahmi, M.Kes, Sp.PK, selaku penguji I, penguji II dan Penguji III.
4. Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada
pemerintah Kab. Sinjai, Puskesmas Lappae, dan Puskesmas
Samaenre atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Kepala Laboratorium Kesehatan Parahita Makassar yang telah
membantu dalam pemeriksaan sampel penelitian penulis.
6. H. Hasanuddin Thaha dan Hj. Nurhayati orang tua tersayang yang
tiada hentinya mendoakan, memotivasi penulis dalam penelitian
ini.dan saudariku yang paling mengertiku Sulastri, SE dan
Haerunisa,S.Pd yang selalu membantu dalam proses penulisan ini.
7. Teman seperjuangan Halima Hatapayo, dr.rasfayanah, M.Kes,
Supriati wila djami, Edi Sukarman, A. Yuli Rohma.
8. Suamiku tersanyang Azhar Pasahi yang memberiku kesempatan
dan selalu mendukungan dalam melaksanakan pendidikan di
Pasca Sarjana UNHAS dan anak-anakku tersayang Faika Inayah
dan Diyaulhaq Azani yang selalu mengerti kesibukanku.
vii
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis
menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak
demi kesempurnaan tesis ini.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon ridha dan
magfirahnya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak
mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Semoga karya ini
dapat bermanfaat kepada para pembaca. Aamiin.
Makassar, November 2018
SUHARTINI
viii
ABSTRAK
SUHARTINI, Korelasi High Sensitivity C - Reaktif Protein (Hs-CRP) danKolestrol Low Density Lipoprotein (LDL) pada Pasien Hipertensi Non Obes(dibimbing oleh Uleng Bahrun dan Mansyur Arif).
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) perbedaan kadar Hs-CRPpada subyek hipertensi nonobes pada kelompok jenis kelamin dan umur,(2) perbedaan kadar kolesterol LDL pada subyek hipertensi nonobes padakelompok jenis kelamin dan kelompok umur, (3) korelasi kadar hs-CRPdan kolesterol LDL pada subyek hipertensi non obes.
Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Lappae dan Samaenre diKabupaten Sinjai. Metode yang digunakan potong lintang dengan jumlahsampel 64 subyek hipertensi nonobes yang memenuhi kriteria inklusi daneksklusi. Pemeriksaan Hs-CRP menggunakan metode immunoturbidimetridan kolesterol LDL dengan metode Hom ogeneus. Data dianalis denganmenggunakan analisis statisti dengan uji-T, Mann-Whitney dan korelasiSpearman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata kadar kolesterol padasubyek hipertensi non obes pada kelompok laki-laki lebih tinggi darikelompok perempuan tetapi secara statistik tidak bermakna. Rerata kadarkolesterol pada kelompok umur ≥ 60 tahun lebih tinggi dari kelompok umur38-59 tahun, tetapi perbedaannya secara statistik tidak bermakna. KadarHs-CRP pada subyek hipertensi non obes pada kelompok jenis kelaminsecara statistik tidak bermakna, pada kadar Hs-CRP dengan kelompokumur ≥ 60 tahun dan kelompok umur 38-59 tahun, secara statistik tidakbermakna. Tidak terdapat korelasi antara kadar Hs-CRP dengan kadarkolesterol LDL (p=0.148 r = 0.133).
Kata kunci: high sensitivity C-Reaktif Protein (hs-CRP), kolesterol LDL, Hipertensi nonobes
ix
ABSTRACT
SUHARTINI, Correlation of High Sensitivity C – Reactive Protein (Hs-CRP) and Cholesterol Low Density Lipoprotein (LDL) in Non ObeseHypertensive Patients (Supervised by Uleng Bahrun and Mansyur Arif).
This aims of this research were to find out (1) differences in hs-CRP levels in non-obese hypertensive subjects in the sex and age groups,(2) differences in LDL cholesterol levels in non-obese hypertensivesubjects in the sex and age group, (3) hs level correlation-CRP and LDLcholesterol in non-obese hypertensive subjects.
This research was conducted at Lappae and Samaenre LocalGovernment Clinic in Sinjai Regency. The method used was crosssectional with a sample of sixty-four non-obese hypertensive subjects whomeet the inclusion and exclusion criteria. The hs-CRP examination usedthe immunoturbidimetry and LDL cholesterol method with theHomogeneus method. The data were analyzed by means of statisticalanalysis with t-test, Mann-Whitney and Spearman correlation.
The result shows that the mean cholesterol level in non-obesehypertensive subjects in the male group was higher than the female groupbut statistically not significant. The mean cholesterol level in the age group≥ 60 years was higher than the age group 38-59 years, but the differencewas not statistically significant. The hs-CRP level in non-obesehypertensive subjects in the sex group was not statistically significant, atthe hs-CRP level with the age group ≥ 60 years and the age group 38-59years, statistically not significant. There is no correlation between hs-CRPlevels and LDL cholesterol levels (p = 0.148 r = 0.133).
Keyword: high sensitivity c-reative (hs-CRP), low density lipoprotein (LDL), non-obese
hypertension
x
DAFTAR ISI
PRAKATA v
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
DAFTAR SINGKATAN xvii
BAB I 1
Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah 4
C. Tujuan penelitian 4
1. Tujuan umum 4
2. Tujuan Khusus 4
D. Manfaat penelititan 5
BAB II
Tinjauan pustaka 6
A. Hipertensi 6
1. Pengertian 6
2. Klasifikasi 8
3. Faktor-Faktor Risiko Hipertensi 8
xi
a. Faktor Genetik 8
b. Faktor Lingkungan 9
4. Patofisiologi Hipertensi 10
a. Retensi Sodium oleh Ginjal 12
b. System Renin Angiotensin Aldosteron (RAA) 13
c. Sistem Saraf Otonom 14
d. Disfungsi Endotel 15
B. Arterosklerosis 18
1. Pengertian 18
2. Perkembangan Arteriosklerosis 20
3. Faktor Penentu Kebutuhan dan Penyediaan Oksigen
Miokardium 23
4. Patologi 24
5. Faktor Risiko 31
a. Hiperlipidemia 32
b. Faktor lain yang dapat diubah 33
6. Patogenesis Aterosklerosis 34
C. CRP 57
D. LDL Kolestrol 61
E. Hipertensi pada penyakit jantung koroner 63
F. Kerangka Teori 65
G. Kerangka Konsep 66
H. Variabel penelitian 66
xii
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Rancangan penelitian 67
B. Lokasi dan waktu penelitian 67
C. Populasi dan sampel 67
a. Populasi 67
b. Sampel 67
D. Kriteria sampel 68
1. Kriteria inklusi 68
2. Kriteria eksklusi 68
E. Defenisi Operasional 69
F. Persiapan Alat dan Bahan 70
G. Cara Kerja 70
H. Analisis data 71
I. Alur penelitian 72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 73
B. Pembahasan 78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 81
B. Saran 81
Daftar Pustaka 82
Lampiran Data Penelitian 85
xiii
DAFTAR TABEL
Lampiran Halaman
Tabel 1 Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC VII ....................................... 8
Tabel 2 Data primer subyek penelitian 73
Tabel 3 Kadar kolesterol LDL subyek hipertensi non laki-laki dan
perempuan 74
Tabel 4 Kadar kolesterol LDL pada subyek hipertensi non obes
berdasarkan kelompok umur 75
Tabel 5 Kadar hs-CRP subyek hipertensi non obes laki-laki dan
perempuan 76
Tabel 6 Kadar hs-CRP pada subyek hipertensi non obes dengan
kelompok umur 76
Tabel 7 Korelasi kolesterol LDL dan hs-CRP pada subyek hipertensi
Non obes 77
xiv
DAFTAR GAMBAR
Lampiran Halaman
Gambar 1 Beberapa faktor resiko yang terkait dengan pengendalian
tekanan darah 11
Gambar 2 Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron 14
Gambar 3 Aterosklerosis : riwayat, gambaran morfologi, pathogenesis,
dan komplikasi-komplikasi klinis 21
Gambar 4 Perubahan patologis progresif pada penyakit aterosklerosis
koroner 25
Gambar 5 Perubahan-perubahan dinding arteri pada “hipotesis respon
terhadap cedera” 38
Gambar 6 Gambar Skematik rangkaian interaksi seluler dari hipotesis
respon terhadap cedera pada arterosklerosis 39
Gambar 7 disfungsi endotel pada arterosklerosis 43
Gambar 8 Efek filtrasi LDL menginisiasi proses radang pada dinding
Arteri 46
Gambar 9 Efek aktivasi sel T pada plak yang terinflamasi 47
Gambar 10 Gambaran skematik efek LDL dan LDL teroksidasi dalam
patogenesis aterosklerosis 53
Gambar 11 jalur inflamasi selama arterosklerosis yang dapat
meningkatkan konsentrasi penenda inflamasi pada darah 56
xvii
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN
Lambang/Singkatan Arti dan keterangan
AHA American Heart Association
Apo B Apolipoprotein B
AT1 Angiotensin II tipe I
BMI Body mass index
CDC Center for Disease Control
CRP C-Reaktive protein
CVD Cardio Vaskuler Disease
HDL High density lipoprotein
hs-CRP High sensitivity C-reactive protein
IHD Ischemic heart disease
JNC The Joint National Commision
LDL Low density lipoprotein
NaCL Natrium Clorida
NO Nitrit Oksida
NTS Nucleus traletus solitarzus
ox-LDL LDL teroksidasi
PAI-1 Plasminogen activator inhibitor-1
PGI2 Prostaglandin Inhibitor 2
PJK Penyakit Jantung Koroner
RAA Sistem Renin Angiotensin Aldosteron
RBP Retinol binding protein
xviii
Lambang/Singkatan Arti dan keterangan
ROS Reactive oxygen species
RVTL Rostral ventrolateral medulla
SKA Sindrom koroner akut
TNFα Tumor necrosis factor
UPR Unfolded protein respon
VLDL Very low density lipoprotein
WHO World Health Organization
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hipertensi berdasarkan kriteria The Joint National Commision (JNC
VII), didefenisikan sebagai kondisi dimana tekanan darah sistolik lebih dari
atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari atau
sama dengan 90 mmHg. Hipertensi mengakibatkan setengah dari
penyakit jantung koroner dan sekitar 2/3 penyakit serebrovaskuler. (Pikir,
B.S. dkk, 2015)
Menurut data World Health Organization (WHO), diseluruh dunia
sekitar 972 juta orang atau 26,4% orang diseluruh dunia mengidap
hipertensi, angka ini mungkin meningkat menjadi 29,2% ditahuin 2025.
Dari 972 juta pengidap hipertensi, 333 juta berada di negara maju dan
sisanya 639 juta berada di negara berkembang, Termasuk Indonesia
(Yonata, 2016).
Di Indonesia, sampai saat ini hipertensi masih merupakan
tantangan besar, merupakan kondisi yang sering ditemukan pada
pelayanan kesehatan primer. Hal ini merupakan masalah kesehatan
dengan prevalensi yang tinggi, yaitu sebesar 25,8% sesuai dengan data
Riskesda 2013 (Pusdatin Kemenkes, 2014). Berdasarkan kelompok umur
penderitanya, prevalensi hipertensi pada umur >75 tahun adalah 63,8%;
umur 65-74 tahun adalah 57,6%; umur 55-64 tahun adalah 45,9%; umur
2
45-54 tahun adalah 35,6%; umur 35-44 tahun adalah 24,8%; umur 25-34
tahun adalah 14,7%; dan umur 15-24 tahun adalah 8,7%, (Depkes, 2016)
Low density lipoprotein (LDL) mengganggu fungsi endotel dengan
meningkatkan produksi radikaI bebas oksigen. Radikal ini menonaktifkan
Nitrit Oksida (NO), yaitu faktor endothelial-relaxing utama. Kolesterol LDL
tertimbun dalam lapisan intima di tempat meningkatnya permeabilitas
endotel. Pemajanan terhadap radikal bebas dalam sel endotel dinding
arteri menyebabkan terjadinya oksidasi kolesterol LDL, yang berperan dan
mempercepat timbulnya plak ateromatosa. Oksidasi kolesterol LDL
diperkuat oleh kadar kolesterol High density lipoprotein (HDL) yang
rendah, diabetes mellitus, defisiensi estrogen, hipertensi, dan merokok.
(Price, S.A. dkk. 2013). Kolesterol LDL dapat juga berperan terhadap
tejadinya inflamasi yang dapat diukur dengan pemeriksaan hs-CRP.
Sejumlah penelitian, baik pengamatan (nested case control dan
kohor prospektif) dan uji coba terkontrol secara acak telah menunjukkan
hubungan biomarker pro-inflamasi dengan hipertensi, sindrom metabolik,
penyakit arteri koroner, sindrom koroner akut, penyakit arteri perifer, strok
dan kejadian koroner berulang dan serebrovaskular. Sekitar 25 penelitian
observasional besar yang diterbitkan sejak tahun 1990-an merujuk protein
C-reaktif sensitivitas tinggi (high sensitivity C-reactive protein/hs-CRP),
biomarker peradangan, sebagai penanda independen untuk Penyakit
Jantung Koroner. Sebuah analisis dari penelitian observasional ini
menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kadar hs-CRP tinggi
3
memiliki kemungkinan lebih besar 1,5 kali menderita penyakit jantung
koroner dibandingkan dengan mereka yang memiliki kadar rendah,
setelah disesuaikan dengan faktor risiko yang sudah ada (Kamath, D.Y. et
all. 2015). Data Framingham Heart study mendukung adanya hubungan
antara hipertensi dan displedemia.(Budi s.P, 2015)
Obesitas terjadi pada 64% pasien hipertensi. Lemak tubuh
mempengaruhi kenaikan tekanan darah dan hipertensi. Penurunan berat
badan menurunkan tekanan darah pada pasien obesitas. Individu obesitas
mempunyai resiko lebih tinggi signifikan terjadinya hipertensi. Body mass
index (BMI) >24,9 Kg/m dihubungkan dengan peningkatan penyakit
kardiovaskuler. Peningkatan yang sama juga telah diidentifikasi untuk
hipertensi. (Pikir,S.P, 2015)
Dalam penelitian studi Framingham, didapatkan 70% hipertensi pada
laki-laki dan 61% pada wanita memiliki kelebihan lemak atau berat badan
yang berlebih. Terdapat beberapa mekanisme yang menjelaskan bahwa
obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi yang didukung
oleh data-data dari penelitian pada manusia dan hewan coba, yaitu
melalui overaktivitas simpatis, resistensi leptin selektif, peran adipokin,
overaktivitas sistem renin angiotensin aldosteron, reactive oxygen Species
(ROS), defisiensi NO dan beberapa teori lain. Jaringan lemak viseral
merupakan penghubung antara obesitas dengan hipertensi dan
aterosklerosis (Pikir, B.S., dkk, 2015). Surentu,J. H et al tahun 2014
tentang “Hubungan kadar kolestrol High density lipoprotein darah dengan
4
kadar high sensitivity C-Reactive protein (hs-CRP) pada remaja obes”,
hasilnya tidak terdapat hubungan antara kadar kolestrol HDL darah
dengan kadar hs-CRP pada remaja obes.
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui korelasi kadar hs-CRP dan LDL kolestrol pada pasien
hipertensi yang non obes.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dirumuskan
masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana perbedaan kadar kolesterol LDL dengan jenis kelamin
dan kelompok umur pada pasien hipertensi non obes?
b. Bagaimana kadar hs-CRP dengan jenis kelamin dan kelompok
umur pada pasien hipertensi non obes?
c. Bagaimana korelasi kadar hs-CRP dan kolesterol LDL pasien
hipertensi non obes?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Mengetahui korelasi kadar hs-CRP dan kolesterol LDL pasien
hipertensi non obes.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui hubungan kadar kolesterol LDL dengan jenis
kelamin dan kelompok umur pada pasien hipertensi non obes.
5
b. Mengetahui hubungan kadar hs-CRP dengan jenis kelamin
dan kelompok umur pada pasien hipertensi non obes.
c. Mengetahui korelasi kadar hs-CRP dan kolesterol LDL pada
pasien hipertensi non obes.
D. Manfaat penelitian
1. Mengetahui korelasi inflamasi melalui penanda hs-CRP dan
kolesterol LDL pada hipertensi non obes.
2. Dapat memberikan gambaran tentang kadar hs-CRP pada pasien
hipertensi non obes.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. HIPERTENSI
1. Pengertian
Hipertensi secara umum didefinisikan sebagai kondisi di mana
tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg atau
tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Tekanan
darah yang tinggi merupakan faktor risiko yang kuat dan penting untuk
penyakit-penyakit kardiovaskular dan penyakit ginjal, seperti penyakit
jantung koroner, gagal jantung dan gagal ginjal. Tekanan darah yang
tinggi dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan dan
interaksi antara kedua faktor tersebut. Berdasarkan penyebabnya
hipertensi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hipertensi
esensial atau hipertensi primer, yaitu hipertensi dengan penyebab yang
belum diketahui dengan jelas dan hipertensi sekunder, di mana hipertensi
terjadi sebagai akibat dari penyakit lain. (Pikir,S.B, dkk, 2015)
Hipertensi akan menyebabkan kerusakan sejumlah organ penting
(target organ demage), yaitu jantung, otak, ginjal dan retina mata.
Kelangsungan hidup (survival) dalam beberapa tahun akan menurun
drastis setelah terdeteksi adanya kerusakan organ seperti hipertrofi bilik
kiri jantung, payah jantung, payah ginjal, gangguan iskemik otak maupun
stroke. Setiap kenaikan tekanan darah 20/10 mmHg akan meningkatkan
risiko mortalitas kardiovaskuler dua kali lipat. (Rilantono L.I, 2012)
7
Perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan. Penderita
hipertensi mungkin tak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Masa
laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan
organ yang bermakna. Bila terdapat gejala maka biasanya bersifat non-
spesifik, misalnya sakit kepala atau pusing. Apabila hipertensi tetap tidak
diketahui dan tidak dirawat, mengakibatkan kematian karena payah
jantung, infark miokardium, stroke, atau gagal ginjal. Namun deteksi dini
dan perawatan hipertensi 1 yang efektif dapat menurunkan jumlah
morbiditas dan mortalitas. Dengan demikian, pemeriksaan tekanan darah
secara teratur mempunyai arti penting dalam perawatan hipertensi (Price
S.A. et al, 2013).
2. Klasifikasi
Tabel 1. Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC VII (Sumber: Pikir,B.A. dkk.,
2015)
Tingkat Tekanan Darah Sistolik (mmHg) Diastolik (mmHg)
Normal < 120 < 80
Prahipertensi 120-139 80-89
Tingkat I 140-159 90-99
Tingkat 2 >160 >100
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi
8
Tekanan darah yang tinggi dapat dipengaruhi oleh faktor genetik,
faktor lingkungan dan interaksi antara kedua faktor tersebut. Berikut
beberapa faktor risiko yang berkaitan dengan kondisi hipertensi.
a. Faktor Genetik
Bukti-bukti adanya pengaruh genetik terhadap tekanan darah
sudah banyak ditunjukkan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Pada
penelitian terhadap saudara kembar, konkordansi atau
kecenderungan kemiripan kondisi tekanan darah ternyata lebih
banyak ditemukan pada saudara kembar monozigotik dibandingkan
pada kembar dizigotik. Studi-studi populasi juga menunjukkan bahwa
terdapat kecenderungan kemiripan atau konkordansi kondisi tekanan
darah yang lebih besar dalam satu keluarga dibandingkan kondisi
tekanan darah antar keluarga yang berbeda. Selain itu, pada studi-
studi tentang tekanan darah pada saudara adopsi, juga menunjukkan
bahwa kecenderungan kemiripan tingkat tekanan darah lebih besar
terdapat antar saudara kandung dari pada terhadap saudara adopsi
meskipun dibesarkan pada lingkungan rumah tangga yang sama.
(Pikir, B.S. dkk. 2015)
b. Faktor Lingkungan
1) Diet Tinggi Garam
Pada studi Intersalt dengan populasi penelitian yang cukup
luas mencakup 10.079 subjek laki-laki dan perempuan usia 20 hingga
59 tahun dari 52 pusat penelitian yang tersebar di seluruh dunia,
9
didapatkan hasil bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara
konsumsi garam dengan perkembangan terjadinya hipertensi, dengan
pengukuran ekskresi sodium lewat urine selama 24 jam dihubungkan
dengan tekanan darah sistolik dan diastolik. (Pikir, B.S. dkk. 2015)
2) Stress
Kejadian-kejadian dalam kehidupan yang menimbulkan emosi
negatif seperti kemarahan, ketakutan dan kesedihan, sudah sejak
lama diketahui dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah
secara temporer. Karena metode eksperimental yang terstandardisasi
di laboratorium untuk mengukur respons kardiovaskular dan respons
neuroendokrin terhadap stress psikologis maupun lingkungan sudah
dapat diaplikasikan, maka kini dapat dibuktikan bahwa stress
psikologis dan lingkungan dapat meningkatkan respons-respons
tersebut dalam jangka pendek. (Pikir, B.S. dkk. 2015)
Peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis terutama melalui
aktivasi terhadap reseptor beta adrenergik merupakan mediator utama
efek stress terhadap kenaikan tekanan darah, meskipun terdapat juga
faktor-faktor lain yang terlibat. Pola kepribadian dan kebiasaan
tertentu juga berhubungan dengan respons stres yang tinggi dan risiko
hipertensi yang lebih besar (Pikir, B.S. dkk. 2015).
3) Obesitas
Jaringan lemak viseral merupakan penghubung antara obesitas
dengan hipertensi dan aterosklerosis. Sel-sel lemak menghasilkan
10
beberapa substansi biologis aktif yang disebut adipokin. Beberapa
adipokin bersifat sebagai prohipertensi seperti leptin,
angiotensinogen, resistin, retinol binding protein (RBP4), plasminogen
activator inhibitor-1 (PAL-1), tumor necrosis factor (TNFα), asam
lemak, hormon steroid, dan faktor-faktor pertumbuhan. Sedangkan
beberapa adipokin bersifat sebagai antihipertensi, contohnya adalah
adiponektin. (Pikir, B.S. dkk., 2015)
Penyebab hipertensi tidak diketahui pada sekitar 95% kasus.
Bentuk hipertensi idiopatik disebut hipertensi primer atau esensial.
Patogenesis pasti tampaknya sangat kompleks dengan interaksi dari
berbagai variabel. Mungkin pula ada predisposisi genetik. Mekanisme lain
yang dikemukakan mencakup perubahan-perubahan berikut: (1) Ekskresi
natrium dan air oleh ginjal, (2) Kepekaan baroreseptor, (3) Respons
vaskular, dan (4) Sekresi renin. Lima persen penyakit hipertensi terjadi
sekunder akibat proses penyakit lain seperti penyakit parenkim ginjal atau
aldosteronisme primer (Sylvia A. Price, 2013).
4. Patofisiologi Hipertensi
Faktor-faktor yang berperan dalam pengendalian tekanan darah,
pada dasarnya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi rumus dasar:
tekanan darah = curah jantung x resistensi perifer. Tekanan darah
dibutuhkan untuk mengalirkan darah melalui sistern sirkulasi yang
merupakan hasil dari aksi pompa jantung atau yang sering disebut curah
jantung (cardiac output) dan tekanan dari arteri perifer atau sering disebut
11
resistensi perifer (Budi, S.P,2015). Pada hipertensi primer (esensial) ada
sejumlah faktor yang berperan, yaitu faktor hormonal pada system renin-
angiotensin aldosterone, system saraf otonom, tahanan perifer, asupan
garam Natrium Clorida (NaCL) dan lain-lain, seperti yang ditunjukkan di
gambar 1.
Gambar 1. Beberapa faktor resiko yang terkait dengan pengendalian tekanan darahyang berdasarkan rumus dasar: tekanan darah = curah jantung x resistensiperifer. (Pikir, B.S. dkk. 2015)
Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka peningkatan tekanan
darah secara logis dapat terjadi karena peningkatan curah jantung dan
12
atau peningkatan resistensi perifer. Peningkatan curah jantung dapat
melalui dua mekanisme yaitu melalui peningkatan volume cairan (preload)
atau melalui peningkatan kontraktilitas karena rangsangan neural jantung.
Meskipun faktor peningkatan curah jantung terlibat dalam permulaan
timbulnya hipertensi, namun temuan-temuan pada penderita hipertensi
kronis menunjukkan adanya hemodinamik yang khas yaitu adanya
peningkatan resistensi perifer dengan curah jantung yang normal (Pikir,
B.S. dkk., 2015).
Proses autoregulasi, yaitu proses di mana dengan adanya
peningkatan curah jantung maka jumlah darah yang mengalir menuju
jaringan akan meningkat pula, dan peningkatan aliran darah ini
meningkatkan pula aliran nutrisi yang berlebihan melebihi kebutuhan
jaringan dan juga meningkatkan pembersihan produk-produk metabolik
tambahan yang dihasilkan, maka sebagai respons terhadap perubahan
tersebut, pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi untuk
menurunkan aliran darah dan mengembalikan keseimbangan antara
suplai dan kebutuhan nutrisi kembali ke normal, namun resistensi perifer
akan tetap tinggi yang dipicu dengan adanya penebalan struktur dari sel-
sel pembuluh darah (Pikir S.A. dkk., 2015).
Berikut adalah beberapa faktor yang berkaitan dengan mekanisme
patofisiologi yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah.
a. Retensi Sodium oleh Ginjal
13
Ginjal dapat berperan baik sebagai pemicu maupun sebagai
sasaran dari hipertensi. Defek fundamental dari penyebab hipertensi oleh
faktor ginjal adalah karena ketidakmampuan ginjal untuk mengekskresi
sodium yang dikonsumsi berlebihan yang disebabkan oleh diet tinggi
garam. (Pikir B.S. dkk., 2015)
Pada mekanisme terkait volume autoregulasi di mana otot polos
pembuluh darah dapat mengalami vasokonstriksi dengan properti
intrinsiknya tanpa adanya pengaruh neural maupun hormonal, yang
disebabkan oleh karena peningkatan volume. Volume cairan yang
berlebihan menyebabkan peningkatan preload sehingga curah jantung
meningkat, peningkatan curah jantung menyebabkan suplai cairan ke
jaringan melebihi kebutuhan sehingga arteri merespons dengan
vasokonstriksi untuk menghentikan suplai yang berlebihan, sehingga
menyebabkan peningkatan resistensi perifer dan meningkatkan tekanan
darah (Pikir B.S. dkk., 2015).
b. Sistem Renin Angiotensin Aldosteron (RAA)
Sistem RAA merupakan sebuah sistem yang memegang peranan
penting dalam kontrol homeostatik tekanan arterial, perfusi jaringan dan
homeostatik volume ekstraseluler. Sistem ini berfungsi sebagai suatu
kelenjar endokrin yang unik di mana hormon aktifnya yaitu angiotensin II
dibentuk di ruang ekstraseluler melalui proses pembelahan proteolitik
sekuensial dari prekursomya, dan mampu meningkatkan tekanan darah
melalui berbagai mekanisme (Pikir B.S. dkk., 2015).
14
Interaksi antara angiotensin II dengan protein G reseptor
Angotensin II tipe I (AT1) akan mengaktifkan beberapa proses seluler
yang berkontribusi terhadap hipertensi dan mempercepat kerusakan
target organ akibat hipertensi. Proses-proses tersebut mencakup
vasokonstriksi, produksi Reactive Oxygen Species (ROS), inflamasi
vaskuler, remodelling vaskuler dan jantung dan produksi aldosteron. (Pikir
B.S. dkk., 2015)
Gambar 2. Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron. (Pikir, B.S. dkk. 2015)
c. Sistem Saraf Otonom
Sistem saraf otonom terdiri dari sistem saraf simpatis dan sistem
saraf parasimpatis. Pada sistem saraf simpatis, input sinaps eksitasi dan
15
inhibisi berasal dan nuklus traletus solitarzus (NTS), menuju ke saraf-saraf
di nukleus rostral ventrolateral medulla (RVLM), sebagai pusat aliran
simpatetik di batang otak. Dari RVLM di batang otak tersebut serabut
simpatis preganglionik bersinaps di medulla adrenal dan di rangkaian
ganglia simpatis para vertebral untuk melepaskan epinefrin. Serabut-
serabut postganglionik yang melepaskan norepinefrin akan menginervasi
jantung, pembuluh darah dan ginjal (Pikir, B.S. dkk. 2015).
Stimulasi Reseptor drenergik β dapat meningkatkan kontraktilitas
dan denyut jantung sehingga meningkatkan curah jantung. Sedangkan
stimulasi reseptor α pada pembuluh darah perifer dapat menyebabkan
vasokonstriksi, dan dalam jangka panjang menyebabkan remodeling
vaskuler dan hipertrofi (Pikir, B.S. dkk. 2015).
d. Disfungsi Endotel
Salah satu faktor penting dari patogenesis hipertensi adalah
disfungsi endotel. Lapisan endotel pada pembuluh darah berperan sangat
vital dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, karena merupakan suatu
pertahanan utama terhadap arteriosclerosis dan hipertensi. Disfungsi
endotel, suatu penanda adanya suatu hipertensi dan faktor resiko
kardiovaskuler yang lain, ditandai dengan adanya gangguan pengeluaran
faktor-faktor relaksasi dari endotel (endhothelial derived relaxing factors)
seperti NO dan peningkatan pengeluaran faktor endotel yang bersifat
proinflamasi, protrombotik, faktor pertumbuhan dan vasokontriksi, yang
mencakup endhotelin, tromboksan dan TGF β. Adanya faktor-faktor yang
16
disebut terakhir tersebut menunjukkan bahwa pembuluh darah terinflamasi
oleh kondisi hipertensi dan inflamasi vaskuler sendiri juga berperan dalam
pembentukan dan komplikasi munculnya tekanan darah tinggi (Pikir, B.S.
dkk. 2015).
Nitrit Oksida adalah vasodilator yang cukup poten, dan berperan
sebagai penghambat adhesi dan agregasi platelet serta penekan migrasi
dan proliferasi sel otot polos vaskuler. NO dihasilkan oleh sel endotel
normal sebagai respon terhadap berbagai rangsangan termasuk salah
satunya karena perubahan tekanan darah, adanya shear stress dan
regangan pulsatile (Pikir, B.S. dkk. 2015).
Nitrit oksida juga berperan penting dalam pengaturan tekanan
darah, thrombosis dan proses arterioklerosis. Sistem kardiovaskuler pada
individu sehat akan terpapar dengan regangan vasodilator yang terkait
dengan NO, secara terus menerus, namun relaksasi vaskuler yang terkait
dengan NO ini ternyata hilang pada individu dengan hipertensi. Suatu
percobaan dengan memberikan superoksida menjadi hydrogen peroksida
secara invivo menunjukkan adanya penurunan tekanan darah dan
mengembalikan biokativitas NO dan hal ini menunjukkan bahwa stress
oksidan yang ditunjukkan dengan adanya spesies oksidan reaktif (ROS),
berkontribusi terhadap inaktivasi NO dan perkembangan disfungsi endotel
pada hipertensi. Adanya peningkatan stres oksidan yaitu ROS dan adanya
disfungsi endotel inilah yang mungkin menjadi juga penyebab timbulnya
hipertensi (Pikir,S.B dkk., 2015).
17
Trombus adalah bekuan darah yang terdiri atas trombosit, fibrin dan
sel darah merah serta sel darah putih yang bias terbentuk di mana saja
dalam system vaskuler seperti arteri, vena, ruang jantung, atau katup
jantung (Kowalak. et al., 2017).
Tiga keadaan yang dikenal sebagai trias Virchow memudahkan
pembentukan thrombus. Ketiga keadaan tersebut adalah : cedera endotel,
aliran darah yang lamban, dan peningkatan koagulabilitas. Kalau dinding
pembuluh darah mengalami cedera, lapisan endotelnya akan menarik
trombosit dan mediator inflamasi lainnya yang dapat menstimulasi
pembentukan bekuan darah. Aliran darah yang lamban atau abnormal
juga akan memudahkan pembentukan trombus dengan memungkinkan
trombosit serta faktor-faktor pembekuan berkumpul dan melekat pada
dinding pembuluh darah. Keadaan ini meningkatkan koagulabilitas
(kemungkinan darah untuk membeku) juga menggalakkan pembentukan
trombus (Kowalak. et al., 2017).
Separuh kematian akibat hipertensi disebabkan oleh infark
miokardium atau gagal jantung. Kerusakan pembuluh darah akibat
hipertensi terlihat jelas di seluruh pembuluh darah perifer. Perubahan
pembuluh darah retina yang mudah diketahui melalui pemeriksaan
oftalmoskopik, sangat berguna untuk menilai perkembangan penyakit dan
respons terhadap terapi yang dilakukan. Perubahan struktur dalam arteri-
arteri kecil dan arteriola menyebabkan penyumbatan pembuluh darah
progresif. Bila pembuluh darah menyempit maka aliran arteri terganggu
18
dan dapat menyebabkan mikroinfark jaringan. Akibat perubahan
pembuluh darah ini paling nyata terjadi pada otak dan ginjal. Obstruksi
atau ruptura pembuluh darah otak merupakan penyebab sekitar sepertiga
kematian akibat hipertensi. Sklerosis progresif pembuluh darah ginjal
mengakibatkan disfungsi dan gagal ginjal yang juga dapat menimbulkan
kematian. Hipertensi kronis merupakan penyebab kedua terjadinya gagal
ginjal stadium akhir dan 21% kasus membutuhkan terapi penggantian
ginjal (Price,S.A.et al., 2015).
B. ATEROSKLEROSIS
1. Pengertian
Istilah aterosklerosis berasal dari bahasa yunani yang berarti
penebalan tunika intima arteri (sclerosis = penebalan) dan penimbunan
lipid (athere = pasta) yang mencirikan lesi yang khas. Secara morfologi,
aterosklerosis terdiri atas lesi-lesi fokal yang terbatas pada arteri-arteri otot
dan jaringan eIastis berukuran besar dan sedang, seperti aorta (yang
dapat menyebabkan penyakit aneurisma), arteria popliteal dan femoralis
(menyebabkan penyakit pembuluh darah perifer), arteria karotis
(menyebabkan stroke), arteria renalis (menyebabkan penyakit jantung
iskemik , atau infark miokardium) (Price S.A. et al., 2013).
Aterosklerosis merupakan penyebab utama kematian dan
kecacatan di negara maju. Namun demikian, penyakit aterosklerotik yang
19
memengaruhi arteria koronaria merupakan penyebab terpenting
morbiditas dan mortalitas (Price S.A. et al., 2013).
Patogenesis aterosklerosis saat ini didasarkan pada teori hipotesis
respons terhadap cedera, yang menjelaskan bahwa aterosklerosis
merupakan suatu respons radang kronik dinding arteri yang dicetuskan
oleh adanya cedera endotel (disfungsi endotel) (Kumar 2007).
Cedera endotel merupakan dasar pertama dari hipotesis respons
terhadap cedera. Penyebab dari cedera atau disfungsi endotel adalah
peningkatan kadar LDL dan radikal bebas yang disebabkan oleh merokok
sigaret, hipertensi, diabetes melitus, faktor genetik, peningkatan
konsentrasi plasma homosistein, infeksi mikroorganisme seperti virus
herpes atau chlamydia pneumoniae, dan kombinasi dari faktor-faktor ini.
Hal-hal penting yang terutama menyebabkan cedera endotel adalah
gangguan hemodinamik dan hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia
kronik akan menyebabkan penimbunan kolesterol LDL dalam intima pada
tempat dimana permeabilitas endotel meningkat. Dengan dilepaskannya
radikal bebas maka LDL akan teroksidasi dan dicerna oleh makrofag
untuk membentuk sel-sel busa, hal ini yang merupakan precursor
terhadap pembentukan bercak ateroma (Kumar 2007).
Mekanisme radang berperan penting dalam memacu proses
aterogenesis dengan menginisiasi, meningkatkan secara progresif,
bahkan sampai menimbulkan komplikasi dari lesi-lesi aterosklerosis. Saat
ini beberapa kepustakaan telah menyebutkan bahwa proses radang
20
berperan penting pada perjalanan penyakit arteri koroner serta
manifestasi aterosklerosis lainnya (Ross R. 1999).
Sel otot polos pembuluh darah juga berperan dalam aterogenesis.
Sel otot polos bermigrasi dari tunika media ke tunika intima, kemudian
berproliferasi dan menimbun komponen matriks ekstrasel, yang akan
mengubah fatty streak menjadi suatu ateroma fibrofatty yang matang dan
menyokong pertumbuhan lesi aterosklerotik menjadi progresif (Foppy M,
2009).
Patogenesis aterosklerosis mencakup peran cedera endotel,
radang, lemak, sel-sel otot polos, dan faktor lain seperti oligoklonal dan
infeksi. Pembahasan diawali dengan menampilkan penjelasan tentang
perkembangan aterosklerosis dari lesi awal sampai lesi komplikasi dan
korelasi klinikopatologiknya (Foppy M, 2009)..
2. PERKEMBANGAN ATEROSKLEROSIS
Perkembangan aterosklerosis telah dimulai sejak usia dini, yaitu
mulai dekade pertama dengan pembentukan fatty streak yang kemudian
pada dekade ketiga berubah menjadi bercak ateroma (fase praklinik).
Umumnya bercak ateroma secara progresif terus menerus ber- ubah,
menjadi lebih besar dan dapat menimbulkan komplikasi bercak yang
kemu- dian menimbulkan manifestasi klinik pada usia pertengahan dan
usia lanjut (fase klinik) (Kumar 2007). Lihat gambar 3.
21
Gambar 3. Aterosklerosis: riwayat, gambaran morfologi, patogenesis, dankomplikasi-komplikasi klinisnya
Arteriosklerosis yang berarti pengerasan dinding arteri adalah istilah
umum bagi penebalan dan hilangnya elastisitas dinding arteri.
Aterosklerosis merupakan bentuk arteriosklerosis yang paling sering, dan
secara karakteristik ditandai oleh adanya lesi pada intima yang disebut
bercak ateroma. Bercak ini dapat menonjol ke dalam dan menutupi lumen
pembuluh darah, serta dapat melemahkan tunika media dibawahnya.
(Kumar 2007). Dalam perkembangan aterosklerosis maka pembentukan
bercak ateroma sepanjang dinding pembuluh darah arteri akan
menyebabkan pembuluh darah itu menyempit dan mengeras (Poppy,
2009).
22
Pembentukan bercak ateroma diawali oleh adanya fatty streak,
yang merupakan lesi terawal dari aterosklerosis. Fatty streak ini tidak
menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah dan tidak
menyebabkan gangguan aliran darah. Biasanya fatty streak muncul
sebagai bintik pipih berwarna kuning, multipel, dengan diameter < 1 mm,
yang menyatu dalam larikan panjang sekitar 1 cm atau lebih. Fatty streak
terdiri dari sel makrofag dan sel otot polos dengan sito- plasma distensi
karena mengandung lemak dan membentuk sel busa. Fatty streak
merupakan prekursor bercak ateroma, yang sudah dibentuk sejak usia
dini, tersering pada dekade pertama, namun tidak semuanya akan
berkembang menjadi bercak ateroma atau lesi-lesi lanjut (Kumar 2007).
Pembentukan bercak ateroma atau disebut juga ateromatosa, atau
bercak fibrolipid (fibrous atau fibrofatty) merupakan proses utama pada
aterosklerosis dan secara morfologik ditandai oleh penebalan tunika
intima dan penimbunan lemak. Bercak ateroma berupa suatu lesi fokal
yang meninggi pada tunika intima, lembut, warna kekuningan dengan
bagian pusat mengandung lemak (terutama terdiri dari kolesterol dan
ester kolesterol), ditutupi oleh suatu penutup warna putih yang keras
disebut fibrous cap. Ukuran bercak ateroma bervariasi 0,3-1,5 cm,
kadang-kadang menyatu sehingga membentuk massa yang lebih besar
(Kumar 2007). Umumnya bercak ateroma secara progresif terus menerus
berubah, menjadi lebih besar, terdapat kematian sel dan degenerasi,
sintesis dan degradasi matriks ekstrasel (remodeling) dan organisasi
23
trombus. Manifestasi klinik akibat aterosklerosis terutama disebabkan
oleh karena penyempitan arteri, dan bila penyempitan >70% maka dapat
terjadi iskemik pada organ yang dipasoknya (Poppy, 2009).
Pada stadium lanjut bercak-bercak ateroma dapat mengalami
komplikasi yang secara klinis sangat berarti. Komplikasi dapat berupa
ruptur fokal, ulserasi, atau erosi fokal dari permukaan lumen bercak
ateroma, perdarahan ke dalam bercak serta trombosis yang merupakan
komplikasi yang penting dan paling ditakuti karena dapat menyebabkan
penutupan arteri sebagian atau secara total, kalsifikasi, dan dilatasi
aneurisma (Poppy, 2009).
3. Faktor penentu kebutuhan dan penyediaan oksigen miokardium
Terdapat suatu keseimbangan kritis antara penyediaan dan
kebutuhan oksigen miokardium; penyediaan oksigen harus sesuai dengan
kebutuhan. Berkurangnya penyediaan oksigen atau meningkatnya
kebutuhan oksigen dapat mengganggu keseimbangan ini dan
membahayakan fungsi miokardium. Terdapat empat faktor utama yang
menentukan besarnya kebutuhan oksigen miokardium: frekuensi denyut
jantung, daya kontraksi, massa otot, dan tegangan dinding ventrikel.
Tegangan dinding atau beban akhir merupakan fungsi variabel-variabel
dalam persamaan Laplace tekanan intraventrikel, radius ventrikel, dan
tebal ventrikel. Oleh karena itu, kerja jantung dan kebutuhan oksigen akan
meningkat pada takikardia (denyut jantung cepat) dan peningkatan daya
24
kontraksi, hipertensi, hipertrofi, dan dilatasi ventrikel (Price, S.A. et al.,
2013).
Bila kebutuhan oksigen miokardium meningkat, maka penyediaan
oksigen juga harus meningkat. Untuk meningkatkan penyediaan oksigen
dalam jumlah memadai, aliran pembuluh koroner harus ditingkatkan,
karena ekstraksi oksigen miokardium dari darah arteri hampir maksimal
pada keadaan istirahat. Rangsangan yang paling kuat untuk mendilatasi
arteria koronaria dan meningkatkan aliran pembuluh koroner adalah
hipoksia jaringan lokal. Pembuluh koroner normal dapat melebar dan
meningkatkan aliran darah sekitar lima sampai enam kali di atas tingkat
istirahat. Namun, pembuluh darah yang mengalami stenosis atau
gangguan tidak dapat melebar, sehingga terjadi kekurangan oksigen
apabila kebutuhan oksigen meningkat melebihi kapasitas pembuluh untuk
meningkatkan aliran. Iskemia adalah kekurangan oksigen yang bersifat
sementara dan reversibel. Iskemia yang lama akan menyebabkan
kematian otot atau nekrosis. Secara klinis, nekrosis miokardium dikenal
dengan nama infark miokardium (Price, S.A. et al., 2013).
4. PATOLOGI
Aterosklerosis pembuluh koroner merupakan penyebab penyakit
arteri koronaria yang paling sering ditemukan. Aterosklerosis
menyebabkan penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri koronari,
sehingga secara progresif mempersempit lumen pembuluh darah. Bila
lumen menyempit maka resistensi terhadap aliran darah akan meningkat
25
dan membahayakan aliran darah miokardium. Bila penyakit ini semakin
lanjut, maka penyempitan lumen akan diikuti perubahan pembuluh darah
yang mengurangl kemampuan pembuluh untuk melebar. Dengan
demikian keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan oksigen
menjadi tidak stabil sehingga mémbahayakan miokardium yang terletak di
sebelah bawah dari daerah lesi (Price, S.A. et al., 2013).
Gambar 4. Perubahan patologis progresif pada penyakit ateroskerosis koroner. (Pikir,B.S. dkk. 2015)
Lesi biasanya diklasifikasikan sebagai endapan lemak, plak
fibrosa, dan lesi komplikata (Gambar. 3), sebagai berikut:
26
1. Endapan lemak, yang terbentuk sebagai tanda awal aterosklerosis,
dicirikan dengan penimbunan makrofag dan sel-sel otot polos terisi
lemak (terutama kolesterol oleat) pada daerah fokal tunika intima
(lapisan terdalam arteri). Endapan lemak mendatar dan bersifat
non-obstruktif dan mungkin terlihat oleh mata telanjang sebagai
bercak kekuningan pada permukaan endotel pembuluh darah.
Endapan lemak biasanya dijumpai dalam aorta pada usia 10 tahun
dan dalam arteria koronaria pada usia 15 tahun. Sebagian endapan
lemak berkurang, tetapi yang lain berkembang menjadi plak fibrosa.
2. Plak fibrosa (atau plak ateromatosa) merupakan daerah penebalan
tunika intima yang meninggi dan dapat diraba yang mencerminkan
lesi paling khas aterosklerosis lanjut dan biasanya tidak timbul
hingga usia dekade ketiga. Biasanya plak fibrosa berbentuk kubah
dengan permukaan opak dan mengilat yang menyembul ke arah
lumen sehingga menyebabkan obstruksi. Plak fibrosa terdiri atas
inti pusat lipid dan debris sel nekrotik yang ditutupi oleh jaringan
fibromuskular mengandung banyaksel-sel otot polos dan kolagen.
Plak fibrosa biasanya terjadi di tempat percabangan, lekukan, atau
penyempitan arteri. Sejalan dengan semakin matangnya lesi, terjadi
pembatasan aliran darah koroner dari ekspansi abluminal,
remodeling vaskular, dan stenosis luminal. Setelah itu terjadi
perbaikan plak dan disrupsi berulang yang menyebabkan rentan
27
timbulnya fenomena yang disebut ”ruptur plak” dan akhirnya
trombosis vena.
3. Lesi lanjut atau komplikata terjadi bila suatu plak fibrosa rentan
mengalami gangguan akibat kalsifikasi, nekrosis sel, perdarahan,
trombosis, atau ulserasi dan dapat menyebabkan infark miokardium
(Price, S.A. et al., 2013).
Meskipun penyempitan lumen berlangsung progresif dan
kemampuan pembuluh darah untuk berespons juga berkurang,
manifestasi klinis penyakit belum tampak sampai proses aterogenik
mencapai tingkat lanjut. Fase praklinis dapat berlangsung 20-40
tahun. Lesi bermakna secara klinis yang mengakibatkan iskemia dan
disfungsi miokardium biasanya menyumbat lebih dari 75% lumen
pembuluh darah. Langkah terakhir proses patologis yang
menimbulkan gangguan klinis dapat tejad melalui: (1) Penyempitan
Iumen progresif akibat pembesaran plak; (2) Perdarahan pada plak
ateroma; (3) pembentukan trombus yang diawali agregasi trombosit;
(4) Embolisasi trombus atau fragmen plak; atau (5) Spasme arteria
koronaria. Meskipun terdapat berbagai penyebab yang dapat
menimbulkan penyumbatan pembuluh koroner akut, tetapi dalam
pemeriksaan otopsi terbukti bahwa trombosis intralumen merupakan
penyebab utama, yaitu menumpuk pada lesi aterosklerotik yang sudah
ada sebelumnya. Apakah oklusi trombotik merupakan peristiwa primer
atau sekunder, belum dapat ditentukan. Beberapa penyelidik percaya
28
bahwa spasme arteria koronaria dengan plak aterosklerotik akan
meningkatkan tekanan di dalam plak, mengakibatkan pecahnya plak
dan terjadi trombosis. Tetapi sebagian lagi percaya bahwa gabungan
mekanisme-mekanisme yang telah disebutkan di atas yang akhirnya
menimbulkan proses oklusi (Price, S.A. et al., 2013).
Penting diketahui bahwa lesi-lesi aterosklerotik biasanya
berkembang pada segmen epikardial di sebelah proksimal dari arteria
koronaria, yaitu pada tempat lengkungan tajam, percabangan, atau
perlekatan. Lesi-lesi ini cenderung terlokalisasi dan fokal dalam
penyebarannya; tetapi, pada tahap lanjut, lesi-lesi yang tersebar difus
menjadi menonjol (Price, S.A. et al., 2013).
Lesi awal dapat terjadi pada usia dewasa muda yaitu kurang
dari 30 tahun dan bersifat asimtomatik. Perkembangan fatty streak
menjadi bentuk yang lebih lanjut dan timbulnya plak tergantung
proses inflamasi selanjutnya termasuk infiltrasi monosit pada lesi,
yang kemudian akan berdeferensiasi menjadi makrofag dan
berkembang menjadi sel busa. Migrasi dari sel otot polos dari tunika
media membentuk kolagen untuk mengeliminasi sel busa dengan
fibrous cap. Bagian luar akan fibrous cap terus berkembang
bertambah besar sedangkan bagian sentral akan mengalami nekrosis
dan plak akan mengarah ke dalam lumen dan akan mengurangi aliran
darah menyebabkan iskemia. plak dengan selubung lipid yang besar
terdiri dari sel nekrotik, sel apoptotik dan sel debris memiliki fibrous
29
cap yang tipis akan mudah ruptur. Tempat terjadinya ruptur pada
lokasi dimana banyak terdapat makrofag akan mengakibatkan kontak
dari lipid core dan faktor pembekuan darah sehingga timbul trombus.
Trombus akan mengikuti aliran darah dan dapat menyumbat vaskuler
di tempat terjadinya stroke (Wibowo J, 2010).
Manifestasi klinis utama aterosklerosis adalah penyakit
kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner , stroke dan
penyakit vaskular perifer. (Muis M, Murtala B, 2011)
Aterosklerosis merupakan penyakit inflamasi. Faktor yang
memicu terjadinya inflamasi sangat banyak baik yang berasal dari
lingkungan internal maupun eksternal termasuk konsumsi yang
berlebih minyak yang terhidrogenasi, kadar insulin yang tinggi,
obesitas, radikal bebas oksidasi partikel LDL, infeksi bakterial, infeksi
viral, sphirokheta, infeksi Borrelia, infeksi penyakit periodontal,
helicobacter, homosistein, sitokin dalam sirkulasi termasuk IL-6 dan
TNF-α yang berperan sebagai mediator proses inflamasi. TNF-α
juga dikenαal dapat menginduksi resistensi insulin pada otot skelet
dan disfungsi endotel. IL-6 merangsang hepar untuk memproduksi
fibrinogen yang merupakan faktor prokoagulan. CRP yang
merupakan marker inflamasi berhubungan dengan resistensi insulin
obesitas dan produksi NO oleh endotel (Wibowo JW, 2010).
Proses terbentuknya aterosklerosis berlanjut sampai dewasa.
Abnormalitas metabolik ditemukan pada penderita obesitas, seperti
30
hiperglikemia, hipertensi dan aterogenik lipoprotein, yang dapat
menyebabkan kerusakan vaskuler. Bukti keterlibatan proses inflamasi
terhadap pembentukan plak aterosklerosis adalah dengan
ditemukannya peningkatan penanda inflamasi yaitu CRP (C-
Reactive Protein), interleukin-6, dan tumor necrosis factor pada
penderita obesitas dan pada penderita yang mengidap penyakit
kardiovaskuler (Anam MS, 2010).
Makrofag merupakan sel yang berperan penting pada proses
terjadinya lesi aterosklerosis dan sebagian dari sel ini akan mengalami
apoptosis, khususnya pada fase akhir dari lesi. Salah satu pemicu
apoptosis adalah akumulasi dari sejumlah besar kolesterol yang tidak
teresterifikasi atau kolesterol bebas. Sebagian dari akumulasi
kolesterol bebas pada membran retikulum endoplasma, yang pada
keadaan normal mengandung sedikit kolesterol, dan lebih banyak
cairan. Keadaan ini mungkin disebabkan karena perubahan fungsi dari
protein integral membran retikulum endoplasma, menyebabkan stress
pada retikulum endoplasma melalui jalur unfolded protein respon
(UPR). UPR meningkat pada proses apoptosis makrofag. Apoptosis
yang terjadi melalui jalur Fas dan mitokondria. Penelitian in vivo
mendukung pendapat bahwa UPR merupakan pemicu destabilisasi
dari plaque aterosklerosis pada lesi aterosklerosis tingkat lanjut, yang
akan menyebabkan aterotrombotik akut dan sumbatan pada vaskuler
yang lebih lanjut akan terjadi kematian jaringan (Wibowo JW, 2010).
31
5. FAKTOR RISIKO
Sekarang aterosklerosis tidak lagi dianggap timbul akibat
proses penuaan saja. Timbulnya “bercak-bercak lemak” pada dinding
arteria koronaria bahkan sejak masa kanak-kanak sudah merupakan
fenomena alamiah dan tidak selalu harus menjadi lesi aterosklerotik.
Sekarang dianggap terdapat banyék faktor yang saling berkaitan
dalam mempercepat proses aterogenik (Price S.A. et al., 2013).
Tiga faktor risiko biologis yang tidak dapat diubah, yaitu:usia,
jenis kelamin laki-laki, dan riwayat keluarga. Kerentanan terhadap
aterosklerosis koroner meningkat seiring bertambahnya usia; Namun
demikian jarang timbul penyakit serius sebelum usia 40 tahun,
sedangkan dari usia 40 hingga 60 tahun, insiden MI meningkat lima
kali lipat. Secara keseluruhan, risiko aterosklerosis koroner lebih besar
pada laki-laki daripada perempuan. Perempuan agaknya relatif kebal
terhadap penyakit ini sampai usia setelah menopause, dan kemudian
menjadi sama rentannya seperti pada laki-laki. Efek perlindungan
estrogen dianggap menjelaskan adanya imunitas wanita pada usia
sebelum menopause, tetapi pada kedua jenis kelamin dalam usia 60
hingga 70-an, frekuensi MI menjadi setara (Price S.A. et al., 2013).
Faktor risiko tambahan lain masih dapat diubah sehingga
berpotensi memperlambat proses aterogenik. Faktor risiko utama
yang dapat diubah adalalah peningkatan kadar lipid serum; hipertensi;
merokok sigaret; diabetes melitus; gaya hidup yang tidak aktif,
32
obesitas (terutama tipe abdominal), dan peningkatan kadar
homosistein (Price S.A. et al., 2013) .
a. Hiperlipidemia
Lipid plasma yaitu-kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam
lemak bebas-berasal dari makanan (eksogen) dan dari sintesis lemak
(endogen). Kolesterol dan trigliserida adalah dua jenis lipid yang relatif
mempunyai makna klinis penting sehubungan dengan aterogenesis.
Lipid tidak larut dalam plasma, sehingga lipid terikat pada protein
sebagai mekanisme transport dalam serum. Ikatan ini menghasilkan
empat kelas utama lipoprotein: (1) Kilomikron, (2) Lipoprotein densitas
sangat rendah (3) Lipoprotein densitas rendah, dan (4) Lipoprotein
densitas tinggi. Kadar relatif lipid dan protein berbeda-beda pada
setiap kelas tersebut. Dari keempat kelas lipoprotein yang ada, LDL
yang paling tinggi kadar kolesterolnya, sedangkan kilomikron dan
VLDL paling tinggi kadar trigliseridanya. Kadar protein tertinggi
terdapat pada HDL (Price S.A. et al., 2013).
Istilah hiperlipidemia menyatakan peningkatan kolesterol
dan/atau trigliserida serum di atas batas normal. Kasus dengan kadar
tinggi yang disebabkan oleh gangguan sistemik disebut sebagai
hiperlipidemia sekunder. Penyebab utama hiperlipidemia adalah
obesitas, asupan alkohol yang berlebihan, diabetes melitus,
hipotiroidisme, dan sindrom nefrotik. Hiperlipidemia akibat predisposisi
33
genetik terhadap kelainan metabolisme lipid disebut sebagai
hiperlipidemia primer (Price S.A. et al., 2013).
Faktor risiko gaya hidup mencakup obesitas, ketidakaktifan
fisik, dan diet aterogenik. Faktor risiko kedaruratan mencakup
gangguan glukosa puasa, homosistein, lipoprotein, faktor proinflamasi
dan protrombik, serta bukti penyakit aterosklerotik subklinis. Sindrom
metabolik mencakup faktor berikut: obesitas abdominal, dislipidemia
(peningkatan trigliserida, partikel LDL kecil atau VLDL terdegradasi),
peningkatan tekanan darah, resistensi insulin (dengan atau tanpa
intoleransi glukosa), dan keadaan proinflamasi serta protrombik. (Price
S.A. et al., 2013)
b. Faktor Lain yang Dapat Diubah
Risiko merokok berkaitan dengan jumlah rokok yang dihisap
per hari, dan bukan pada lama merokok. Seseorang yang merokok
lebih dari satu pak rokok sehari menjadi dua kali lebih rentan terhadap
penyakit aterosklerotik koroner daripada mereka yang tidak merokok.
Yang diduga menjadi penyebab adalah pengaruh nikotin terhadap
pelepasan katekolamin oleh sistem saraf otonom. Namun efek nikotin
tidak bersifati kumulatif, mantan perokok tampaknya berisiko rendah
seperti pada bukan perokok. Aterosklerosis merupakan suatu penyakit
multifaktorial, dan bukti yang ada menunjukkan bahwa beberapa
faktor risiko tertentu dapat mempercepat aterogenesis (Price S.A. et
al., 2013).
34
6. PATOGENESIS ATEROSKLEROSIS
Patogenesis aterosklerosis merupakan suatu proses interaksi yang
kompleks, dan hingga saat ini masih belum dimengerti sepenuhnya.
Interaksi dan respons komponen dinding pembuluh darah dengan
pengaruh unik berbagai stresor (sebagian diketahui sebagai faktor risiko)
yang terutama dipertimbangkan. Teori patogenesis yang mencakup
konsep, ini adalah hipotesis respons terhadap cedera, dengan beberapa
bentuk cedera tunika intima yang mengawali inflamasi kronis dinding arteri
dan menyébabkan timbulnya ateroma (Price S.A. et al., 2013).
Teori-teori lama menekankan bahwa terdapat dua hipotesis yang
dapat menerangkan terjadinya aterosklerosis yaitu yang pertama
proliferasi sel di dalam intima dan kedua organisasi serta pembentukan
trombi yang berulang-ulang. Namun saat ini konsep patogenesis dari
aterosklerosis yang dianut adalah menggabungkan kedua hipotesis lama
tersebut yang dikenal dengan istilah hipotesis respons terhadap cedera
(Response toinjury hypothesis) (foppy, 2009).
Hipotesis respons terhadap cedera menunjukkan bahwa
aterosklerosis adalah suatu respons radang kronik dinding arteri yang
dicetuskan oleh cedera endotel yang kemudian menjadi lesi yang
progresif karena interaksi antara lipoprotein termodifikasi, makrofag,
limfosit T dan kandungan seluler normal dinding arteri (Kumar, 2007).
Sejumlah pengamatan pada manusia dan hewan coba mendukung
teori hipotesis respons terhadap cedera. Pada awalnya diusulkan bahwa
35
denudasi endotel adalah langkah pertama pada proses aterosklerosis, dan
hipotesis ini lebih menekankan istilah disfungsi endotel daripada denudasi
endotel. Dalam proses aterosklerosis penyebab-penyebab disfungsi
endotel mencakup peningkatan kadar LDL termodifikasi, radikal bebas
yang disebabkan oleh merokok sigaret, hipertensi, diabetes melitus, faktor
genetik, peningkatan konsentrasi plasma homosistein, infeksi
mikroorganisme seperti virus herpes atau chlamydia pneumoniae, dan
kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Dengan kata lain penyebab dari
disfungsi endotel telah tercakup semua pada faktor-faktor resiko
aterosklerosis (Foppy M, 2010).
Hal-hal utama pada hipotesis respons terhadap cedera dapat dijelaskan
berikut ini (Kumar, 2007) : (gambar 4 dan 5)
- Perubahan paling awal yang mendahului lesi aterosklerosis
berada pada sel endotel. Umumnya cedera endotel kronik
mengakibatkan disfungsi endotel yang tidak memberikan gejala.
Cedera endotel akan menurunkan produksi nitrik oksida (NO),
meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan adhesi lekosit, serta
berpotensi trombotik. Cedera endotel mengakibatkan terjadinya
disfungsi sel endotel dan menjurus pada respons kompensatorik yang
mengubah homeostasis normal sel endotel dan meningkatkan adhesi
leukosit atau trombosit terhadap endotel.
36
- Akumulasi lipoprotein pada dinding pembuluh darah terutama
LDL dengan kandungan kolesterol tinggi, diikuti oleh modifikasi
lipoprotein pada lesi melalui proses oksidasi. Pada awal proses
aterogenesis ekspresi sel endotel melalui ICAM-I (inter- cellular
adhesion molekul-I) berikatan dengan macam-macam leukosit.
Vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-I) mengikat monosit dan
limfosit T. Setelah monosit melekat pada sel endotel, monosit akan
bermigrasi melewati taut antar sel endotel masuk ke dalam tunika
intima dan mengalami trasformasi menjadi makrofag setelah
dirangsang oleh kemo- kin. Makrofag mencerna lipoprotein LDL yang
teroksidasi membentuk sel- sel busa. Makrofag memproduksi
interleukin-1 (IL-1) dan tumor necrosis factor (TNF) yang
meningkatkan adhesi lekosit. Makrofag juga menggerakkan beberapa
kemokin termasuk monocyte chemotactic protein-1 (MCP-I) yang
merekrut lebih banyak lekosit ke dalam berca ateroma. Oksigen
toksik yang dihasil- kan oleh makrofag menyebabkan oksidasi LDL.
Partikel LDL yang tertangkap pada dinding pembuluh da- rah akan
mengalami oksidasi progresif dan masuk ke dalam makrofag me- lalui
reseptor scavenger pada permu- kaan sel membentuk peroksidase
lemak dan memudahkan penimbunan ester kolesterol kemudian
membentuk sel busa. Selanjutnya terjadi pemben- tukan fatty streak
yang terdiri dari monosit lipid laden dan makrofag yang
mencerna LDL yang teroksidasi bersama-sama dengan limfosit T.
37
- Cedera endotel juga menginduksi sel endotel yang bersifat
prokoagulan dan membentuk substansi vasoaktif seperti sitokin dan
faktor-faktor pertumbuh- an. Proses radang merangsang migrasi dan
proliferasi sel otot polos pembu- luh darah membentuk bercak
ateroma. Bilamana proses radang tidak efektif untuk melawan agen
penyerang maka respon radang akan berlangsung terus sehingga
akan direkrut lebih banyak sel-sel makrofag, limfosit, dan trombosit,
yang beremigrasi dari pembuluh darah masuk kedalam lesi
aterosklerosis. Adhesi trombosit dan pelepasan faktor-faktor activated
platelets, makrofag, atau sel-sel pembuluh darah, menyebabkan
migrasi sel-sel otot polos dari tunika media masuk ke dalam tunika
intima. Proliferasi sel-sel otot pada tunika intima dan matriks ekstrasel
mengakibatkan akumulasi kolagen dan proteoglikan, mengubah fatty
streak menjadi suatu ateroma fibrofatty yang matang dan menyokong
pertumbuhan lesi aterosklerotik yang progresif.
Fatty streaks yang progresif berkembang menjadi lesi sedang
dan lanjut, kemudian akan membentuk fibrous cap yang berbatasan
dengan lumen pembuluh darah. Fibrous cap menutupi campuran dari
lekosit, lemak dan debris seluler yang membentuk suatu pusat
nekrotik. Pusat nekrotik terbentuk sebagai akibat pening-katan aktifitas
platelet derived growth factor (PDGF), transforming growth fac-tor–ß (TGF-
ß), IL-1, TNF-α, osteopontin dan penurunan degradasi jaringan ikat
(Poppy, 2009).
38
Selanjutnya bproses aterogenesi dijelaskan secara terperinci meliputi
beberapa aspek dari peranan cedera endotel, radang, lemak, sel-sel
otot polos, dan faktor lain seperti oligoklonal dan infeksi.
Gambar 5. Perubahan-perubahan dinding arteri pada ‘hipotesis responsterhadap cedera’.1.normal, 2.cedera endotel dengan adhesi monosit dantrombosit, 3.migrasi monosit dari lumen pembuluh darah dan otot polos tunikamedia ke tunika intima, 4.proliferasi sel otot polos dalam tunika intima
39
5.terbentuknya bercak ateroma (Kumar, Abbas, Fausto, Mitcheel. Robbins BasicPathology. 2007.
Gambar 6. Gambar skematik rangkaian interaksi seluler dari hipotesis respons terhadapcedera pada aterosklerosis. Hiperlipidemia dan faktor-faktor risiko lainmenyebabkan cedera endotel, adhesi trombosit dan monosit, pelepasan faktor-faktorpertumbuhan PDGF serta memacu migrasi dan proliferasi sel otot polos. Sel-sel busapada bercak ateroma berasal dari sel-sel makrofag dan otot polos – dari makrofagmelalui reseptor very LDL dan modifikasi LDL dikenal oleh scavenger receptors (LDLteroksidasi) dan otot polos. Lemak ekstrasel berasal dari lumen pembuluh darah terutamapada hiperkolesterolemia dan degenerasi sel-sel busa.
a. Peranan cedera endotel
Cedera endotel kronik merupakan dasar pertama dari hipotesis
respons terhadap cedera. Cedera endotel diinduksi pada hewan coba
melalui denudasi mekanik, adanya faktor-faktor hemodinamik, deposisi
40
kompleks imun, radiasi, dan bahan-bahan kimia, semuanya ini
menyebabkan penebalan tunika intima; dan ditambah lagi dengan diet
kolesterol yang tinggi maka terbentuk ateroma tipikal.
Pada manusia lesi awal dimulai pada tempat-tempat yang
endotelnya utuh. Pada lesi awal belum terjadi denudasi endotel yang
disfungsional. Perubahan pada lesi awal mencakup: permeabilitas
pembuluh darah meningkat terhadap lipo- protein dan bahan lain yang
diperantarai nitrik oksida, prostasiklin, platelet derived growth factor,
angiotensin II dan endotelin, adhesi lekosit oleh aktivasi en- dotel melalui
selektin E, integrin, dan platelet endothelial cell adhesion mole- cule I
(PECAM-1) dan VCAM-1. Hal-hal ini akan menyebabkan migrasi
leukosit masuk ke dalam dinding arteri yang dapat dicetuskan oleh LDL
teroksidasi, monocyte chemotactic protein-1, interleukin-8,
PDGF,macrophage colonystimulating factor, dan osteopontin. Gangguan
umum yang sering dikaitkan dengan disfungsi endotel adalah hipertensi,
hiper- kolesterolemia, diabetes melitus dan merokok (Poppy, 2009).
Penyebab disfungsi endotel pada awal aterosklerosis belum
diketahui, namun terdapat faktor-faktor di dalam sirkulasi darah yang
berpotensi meng- ganggu seperti pada perokok, homosistein, dan
mungkin virus serta agen infeksi lainnya. Sitokin radang seperti TNF
(tumor necrosis factor), merangsang ekspresi dari gen-gen endotel yang
dapat memicu aterosklerosis. Faktor yang juga sangat penting dalam
41
menimbulkan perubahan pada endotel adalah gangguan hemodinamik
dan hiperkolesterolemia (Kumar, 2007).
Gangguan hemodinamik menyokong terjadinya aterosklerosis.
Shear stress atau turbulensi yang tinggi atau rendah adalah penting
untuk menentukan dimana tempat lesi pembuluh darah itu terjadi.
Perubahan aliran darah akan mengubah ekspresi gen untuk memberi
respons terhadap shear stress. Sebagai contoh gen-gen untuk
intercellular adhesion molecule 1, PDGF rantai B, dan faktor jaringan
pada sel endotel, ekspresinya meningkat oleh penurunan shear stress
(Ross R, 1999). Hal ini dapat dilihat terutama pada bercak-bercak
ateroma yang terjadi pada ostium pembuluh darah pada titik-titik cabang
aorta abdominal dimana terdapat gangguan pola aliran darah. Daerah-
daerah yang terganggu menunjuk- kan aliran darah turbulen dan shear
stress yang rendah, dan hal ini menyokong terjadinya aterosklerosis,
sedangkan aliran darah laminer yang lancar mencegah terjadinya
aterosklerosis. Aliran darah laminer normal tipikal dijumpai pada daerah-
daerah pembuluh darah arterial yang disebut ‘lesi yang terproteksi’ di
mana dapat menghambat mekanisme-mekanisme radang yang
dicetuskan oleh disfungsi endotel, apoptosis sel endotel, dan hal penting
dalam hubungan dengan erosi bercak ateroma. Keadaan dengan aliran
darah laminer yang lancar juga menginduksi gen-gen endotel
menghasilkan antioksidan superoksida dismutase yang melindungi
perkembangan aterosklerosis. Jadi aliran darah laminer yang tetap
42
lancar mencegah perkembangan lesi aterosklerosis dan hal ini disebut
sebagai gen-gen ateroprotektif (Kumar, 2007).
Hiperkolesterolemia menyebabkan relaksasi vaskuler yang
tergantung endotel menjadi terganggu. Banyak penelitian telah
membuktikan bahwa disfungsi endotel dapat dicetuskan oleh kadar LDL
yang tinggi. Hipertensi dapat menyebabkan penurunan vasodilator nitrik
oksida (NO). Merokok menyebabkan gangguan dilatasi pembuluh darah.
Penelitian akhir-akhir ini menyebutkan bahwa efek merokok disertai
bertambahnya LDL yang teroksidasi berhubungan dengan perubahan
keadaan redoks dinding pembuluh darah terutama pada endotel.
Bertambahnya reaktivasi spesies oksigen menghambat vasodilatasi
yang diperantarai nitrat oksida. Disfungsi endotel koroner berkembang
cepat pada perokok dibandingkan dengan yang tidak merokok. Pada
hewan coba diabetes diperlihatkan bahwa gangguan dilatasi pembuluh
darah yang tergantung endotel dihubungkan dengan nitrik oksida yang
tidak normal, dan pelepasan endotelin dari prostanoid konstriktor yang
menghambat efek nitrik oksida.
43
Gambar 7 . Disfungsi endotel pada atero- sklerosis. (Ross Russell.N.Engl.J.Med. 199 340:115-126).
b. Peranan radang
Mekanisme-mekanisme radang dapat memacu proses aterogenesis
dalam hal menginisiasi, progresi, bahkan sampai menimbulkan komplikasi
dari lesi-lesi aterosklerosis. Dalam proses awal aterogenesis, sel-sel
endotel pembuluh darah yang diaktivasi akan mengekspresi berbagai
macam leukosit pada permukaan molekul-molekul adhesi selektif sehingga
menyebabkan sel-sel leukosit tersebut menggelinding sepanjang
permukaan pembuluh darah. Molekul-molekul adhesi VCAM-1 (Vascular
cell adhesion molecule-1) mengikat secara tepat jenis-jenis leukosit
monosit, dan limfosit T yang ditemukan pada awal ateroma pada
manusia dan hewan coba. Pada saat leukosit melekat pada endotel maka
kemokin yang diproduksi pada lapisan intima akan merangsang monosit
44
untuk keluar dai pembuluh darah. Bila monosit telah melekat pada endotel
maka (Hasson, 2005):
1. monosit bermigrasi lewat celah sel endotel dan kemudian menuju
ke lapisan intima dimana hal ini paling banyak dirangsang oleh
kemokin.
2. monosit mengalami transformasi menjadi sel makrofag kemudian
menelan lipoprotein, dan secara luas mengoksidasi LDL.
Makrofag menghasilkan IL-1 (inter- leukin-1) dan TNF (tumor
necrosis factor) yang meningkatkan adhesi lekosit. Beberapa ensim yang
digerakkan oleh makrofag seperti MCP-1 (monocyte- chemotactic protein-
1) dapat merekrut lebih banyak leukosit ke dalam bercak ateroma
(Schoen, 2007). Kemokin memberi repons terhadap kemotaksis dan
akumulasi makrofag di dalam fatty streaks (Ross R, 1999). Makrofag-
makrofag juga menghasilkan spesies oksigen toksik yang menyebabkan
oksidasi LDL dalam lesi dan melepaskan growth factor yang turut
menyokong proliferasi sel-sel otot polos. Limfosit T (keduanya CD4+ dan
CD8+) juga direkrut ke dalam bercak ateroma oleh adanya kemoatraktan.
Reaksi silang sel-sel T dan makrofag mengakibatkan aktivasi imun seluler
dan humoral yang karakteristik sebagai suatu radang kronik. Sebagai
contoh sel-sel T mengalami sinyal-sinyal sehingga melepaskan sitokin-
sitokin ra- dang, seperti IFN-γ dan limfotoksin, dimana pada gilirannya
dapat merangsang sel-sel makrofag bersamaan dengan merangsang sel-
45
sel endotel dan otot polos pembuluh darah. Makrofag yang diaktifkan dan
sel-sel pembuluh darah intrinsik dapat melepaskan mediator-mediator
fibrogenik yang mencakup bermacam-macam bahan growth factor
peptide, yang dapat memacu penggandaan sel-sel otot polos dan
pelepasan matriks ekstrasel yang khas pada lesi aterosklerotik
(Rudijanto A, 2007). Gambar 5.
c. Peranan lemak
Berbagai macam lemak dalam sirkulasi darah ditranspor sebagai
lipoprotein yang kompleks menjadi apoprotein spesifik. Dislipoproteinemia
yang terjadi karena mutasi atau beberapa gangguan lain yang
mendasarinya seperti sindrom nefrotik, alkoholisme, hipotiroidisme, atau
diabetes melitus menyebabkan kerusa- kan apoliprotein. Contoh dari
lipoprotein tidak normal dapat ditemukan pada populasi dengan
(Kumar, 2007):
1. peningkatan kadar kolesterol LDL
2. penurunan kadar kolesterol HDL
3. peningkatan kadar lipoprotein abnormal Lp(a)
Studi-studi pada hewan coba dan manusia menunjukkan bahwa
hiperkolesterolemia menyebabkan akivasi endotel fokal arteri berukuran
sedang dan besar. Infiltrasi dan retensi LDL pada tunika intima arteri
menginisiasi respons radang dinding arteri. Modifikasi LDL melalui
46
oksidasi atau ensimatik yang menyerang intima, menyebabkan pelepasan
fosfolipid, yang dapat mengaktifkan sel endotel, terutama pada tempat-
tempat dimana aliran hemodinamik dengan shear stress rendah. Hal ini
akan meningkatkan ekspresi molekul-molekul adhesi dan gen-gen
radang pada sel sel endotel. Dengan demikian pola hemodinamik dan
akumulasi lemak pada intima dapat menginisiasi suatu proses radang
pada arteri (Gambar 7) (Hansson, 2005).
Gambar 8. Efek infiltrasi LDL menginisiasi proses radang pada dinding arteri.(Hansson, 2005)
47
Gambar 9. Efek aktivasi sel T pada plak yang terinflamasi (Hansson,2005). Antigen yang dipresentasikan oleh makrofag dan sel dendritik akanmerangsang aktivasi sel T pada arteri. Kebanyakan sel T yang teraktivasi akanmemproduksi sitokin Th1 (interferon γ), yang mengaktivasi sel makrofag danvaskuler, menyebabkan inflamasi. Sel T akan memodulasi proses denganmensekresi sitokin antiinflamasi (seperti interleukin-10 dan transforming growthfactor B).
Mekanisme-mekanisme aterogenesis yang disebabkan hiperlipidemia
mencakup:
- hiperlipidemia kronik, terutama hiperkolesterolemia dapat secara
langsung merusak sel-sel endotel melalui penambahan produksi
radikal bebas oksigen yang tidak mengaktifkan NO (vasodilator)
sebagai faktor yang membuat sel-sel endotel berelaksasi dan
menyebabkan bertambahnya shear stress lokal.
48
- hiperlipidemia kronik, menyebabkan penimbunan lipoprotein dalam
intima pada tempat dengan permeabilitas endotel yang meningkat.
- perubahan kimia lemak diinduksi oleh radikal-radikal bebas yang
dilepaskan oleh makrofag atau sel endotel pada dinding pembuluh
darah arteri dengan LDL teroksidasi (modifikasi). LDL yang teroksidasi
akan:
1. Dicerna oleh makrofag melalui scavenger receptor yang berbeda
dengan reseptor LDL, dan selanjutnya membentuk sel-sel busa.
2. Meningkatkan penimbunan monosit pada lesi aterosklerosis.
3. Bersifat kemotaktik terhadap monosit dan mengatur ekspresi gen
untuk macrophage colony stimulating, merangsang pelepasan
faktor-faktor pertumbuhan, sitokin-sitokin dan kemokin.
4. Akhirnya LDL yang teroksidasi bersifat sitotoksik terhadap sel
endotel dan sel otot polos pembuluh darah sehingga
menginduksi disfungsi sel endotel.
Oksidasi LDL berperan penting dalam proses aterogenesis, juga
disokong oleh akumulasinya dalam makrofag pada semua stadium
pembentukan bercak ateroma. Terapi antioksidan seperti β- carotene
and vitamin E diasumsikan dapat bersifat proteksi terhadap
perkembangan aterosklerosis (pada hewan coba) namun tidak efektif
untuk mencegah penyakit jantung iskemik (Schoen, 2005). Pada
penelitian akhir-akhir ini
49
diusulkan bahwa efek anti radang antioksidan mungkin dengan
mencegah molekul adhesi terhadap monosit. Ex vivo antioksidan juga
meningkatkan resistensi LDL manusia untuk teroksidasi, sesuai dengan
proporsi kandungan vitamin E didalam plasma. Konsumsi vitamin E
mempunyai korelasi terbalik dengan insiden infark jantung, dan pada
percobaan klinis suplemen vitamin E mengurangi penyakit arteri koroner
(Ross R,1999).
d. Peranan sel otot polos pembuluh darah
Sel-sel otot polos pada tunika media arteri dikelilingi oleh jenis
jaringan ikat tertentu. Pada tunika media arteri matriks terdiri dari jaringan
fibriler kolagen tipe I dan III, sedangkan pada lesi aterosklerosis terdiri dari
proteoglikan bercampur dengan fibril kolagen yang tersebar. Molekul
matriks penting dalam memper- tahankan struktur jaringan ikat dan
berperan penting dalam memandu fungsi sel. Sel-sel yang berikatan
dengan matriks ekstrasel melalui reseptor integrin spesifik. Matriks
metalloproteinase diproduksi oleh bermacam-macam sel yang
berlokasi pada permukaan sel dan dicatat mendegradasi bermacam-
macam matrikas ekstrasel. Matriks metalloproteinase dapat berpartisipasi
dalam migrasi sel-sel otot polos (Foppy, 2009).
Sel-sel otot polos bermigrasi dari tunika media ke tunika intima,
kemudian berproliferasi dan menyimpan komponen matriks ekstrasel,
mengubah fatty streak menjadi suatu ateroma fibrofatty yang matang dan
50
menyokong pertumbuhan lesi aterosklerotik menjadi progresif. Faktor–
faktor pertumbuhan yang diimplikasikan pada proliferasi sel-sel otot polos
adalah PDGF/platelet derived growth factor (di- lepaskan oleh platelet
adherent pada suatu fokus cedera endotel, dan oleh makrofag, sel-sel
endotel dan sel-sel otot polos), FGF (fibroblast growth factor) dan TGF-
α. Sel-sel otot polos juga dapat mengambil lemak yang sudah dimodifkasi
dan hal ini menyokong pembentukan sel-sel busa. Sel-sel otot polos dapat
menyintesis molekul-molekul matriks ekstrasel (kolagen) yang
menstabilkan bercak aterosklerotik. Namun radang yang diaktifkan
dan sel-sel imun pada bercak ataeroma dapat memicu apoptosis sel-sel
otot polos pada tunika intima (Kumar, 2007).
Perkembangan ateroma terdiri dari reaksi radang kronik dan semua
kom- ponen makrofag, limfosit, sel-sel endotel, dan sel-sel otot polos yang
menyokong berbagai faktor yang mempengaruhi fungsi sel. Pada
stadium awal bercak ateroma pada intima merupakan kum- pulan sel-sel
busa yang berasal dari makrofag dan sel-sel otot polos. Beberapa
daripadanya akan mati dan melepaskan lemak dan debris seluler. Pada
lesi yang progresif, ateroma dimodifikasi oleh sel otot polos yang
menyintesis kolagen dan proteoglikan. Jaringan ikat terutama
membentuk fibrous cap tetapi beberapa lesi tetap mempunyai pusat
sentral yang mengandung debris seluler dan sel-sel ‘lipid laden’.
Pecahnya fibrous cap dengan komplikasi terjadinya trombus sering
dihubungkan dengan bukti-bukti klinis yang berakibat buruk. Trombosit
51
yang melekat pada dinding pembuluh darah pada tempat dimana
terdapat aktivasi sel endotel menyokong perkembangan lesi aterosklerotik.
Ruptur atau erosi dari bercak pada lesi akan merangsang aktivasi
trombosit dan agregasi pada permukaan bercak yang ruptur, dan hal ini
memicu serangan akut dari trombosis arterial. Aktivasi platelet dapat juga
mempengaruhui pembentukan bercak oleh pelepasan ligan adhesif,
seperti selectin-P yang diekspresikan pada membran trombosit dan
memediasi interaksi trombosit-endotel. Sinyal dari selectin-P merangsang
monosit dan makrofag untuk memproduksi kemoatraktan atau faktor
pertumbuhan (PDGF)(Poppy, 2009).
e. Faktor-faktor aterogenik yang lain:
1. Lesi-lesi oligoklonal
Hipotesis monoklonal aterosklerosis sejak tahun 1977 sudah
menyebutkan bahwa berdasarkan pengamatan ber- cak-bercak
ateroma pada manusia adalah monoklonal atau oligoklonal yang
serupa dengan pertumbuhan neoplastik jinak. Hal ini mungkin
diinduksi oleh bahan-bahan kimia eksogen seperti kolesterol atau
beberapa produknya yang teroksidasi, atau oleh suatu virus
onkogenik. Namun studi- studi terakhir menunjukkan bahwa bercak
klonal tetap ada, dan yang ukurannya > 4mm tidak hanya pada yang
mengalami aterosklerosis tetapi juga pada arteri-arteri normal, sejalan
52
dengan kemungkinan bahwa bercak- bercak aterosklerotik tidak
timbul pada bercak-bercak klonal yang telah ada sebelumnya.
2. Infeksi
Infeksi dapat menyokong terjadinya aterosklerosis. Telah
diimplikasikan bahwa bakteri dan virus seperti chlamydia pneumoniae
dan cytomega lovirus, keduanya dapat menginfeksi dinding pembuluh
darah dan mengakibatkan infeksi yang persisten, latensi, dan rekuren.
Mekanisme spesifik aterogenesis oleh bakteri dan virus masih sukar
untuk dipahami. Infeksi sekunder lesi aterosklerotik dapat berpotensi
efek lokal dari faktor-faktor resiko yang sudah diketahui seperti
hiperkolesterolemia, melalui aselerasi radang kronik atau dengan
mengubah respons sel-sel dinding pembuluh darah terhadap cedera.
Infeksi ekstravaskuler dapat juga mempengaruhi perkembangan lesi-
lesi ateromatosa dan komplikasinya dengan jalan menguba lalui
mediator-mediator radang sirkulasi. Endotoksin atau sitokin proradang
seperti IL-1 dihasilkan sebagai respons terhadap infeksi yang
mengaktivasi sel-sel dinding pembuluh darah dan leukosit-leukosit
pada lesi- lesi sebelumnya. Dalam hal ini, organisme yang infeksius
dapat berpotensi menimbulkan komplikasi dari lesi-lesi yang
sebelumya sudah terbentuk. Contoh protein c.pneumoniae pada suhu
panas dapat mengaktifkan makrofag untuk menghasilkan matriks pro
53
teinase degradasi yang dapat melemahkan bercak aterosklerotik
sehingga peka untuk mengalami ruptur, dapat menyebabkan terjadinya
trombosis dan mencetuskan implikasi trombotik dengan mengubah
keseimbangan antara koagulasi dan fibrinolisis (Kumar, 2007).
Dinding pembuluh darah terpajan berbagai iritan yang terdapat
dalam hidup keseharian. Diantaranya adalah faktor-faktor hemodinamik,
hipertensi, hiperlipidemia, serta derivat merokok dan toksin (misal,
homosistein atau kolesterol LDL teroksidasi). Gambar 8 memfokuskan
peranan kolesterol LDL dalam patogenesis aterosklerosis. (Price S.A. et
al., 2013)
Gambar 10. Gambaran skematik efek LDL dan LDL teroksidasi dalam patogenesisaterosklerosis. Faktor risiko Lainnya, kadar HDL rendah, merokok,
LDL
LDL teroksidasi
Disfungsi endotel InflamasiBercak lemak
Plak Halus
Ruptur plak
Trombosis dan sindromkoroner akut
54
hipertensi, diabetes militus, dan defisiensi estrogen juga memperkuatoksidasi LDL. (Price, S.A. et al., 2013)
Dari kesemua agen ini, efek sinergis gangguan hemodinamika yang
menyertai fungsi sirkulasi normal yang digabungkan dengan efek
merugikan hiperkolesterolemia dianggap merupakan faktor terpenting
dalam patogenesis aterosklerosis. Kepentingan teori patogenesis respons
terhadap cedera adalah cedera endotel kronis yang menyebabkan
respons inflamasi kronis dinding arteri dan timbulnya aterosklerosis.
Berbagai kadar stres yang berkaitan dengan turbulensi sirkulasi normal
dan menguatnya hipertensi diyakini menyebabkan daerah fokal disfungsi
endotel. Misalnya, ostia pembuluh darah, titik percabangan, dan dinding
posterior aorta abdominalis dan aorta desendens telah diketahui sebagai
tempat utama berkembangnya plak aterosklerosa (Price S.A. et al., 2013).
e. Inflamasi pada Aterosklerosis
Hiperkolesterolemia menyebabkan aktivasi endotelium pada arteri
sedang dan besar. Infiltrasi dan retensi LDL pada intima menginisiasi
respon inflamasi pada dinding arteri. Trombosit adalah sel darah pertama
yang tiba pada lokasi endotelium yang teraktivasi. Glikoprotein Ib dan
IIb/IIIa akan berikatan dengan permukaan molekul sel endotelium, yang
berkontribusi pada aktivasi endotel. Sel endotel yang teraktivasi
mengekpresikan berbagai tipe molekul adhesif leukosit, yang
menyebabkan sel darah akan berikatan pada tempat aktivasi (Libby,
2006).
55
Sitokin yang diproduksi pada intima yang mengalami inflamasi
yaitu macrophage colony-stimulating factor, menginduksi monosit yang
masuk ke dalam plak dan berdiferensiasi menjadi makrofag. Hal ini
penting dalam perkembangan aterosklerosis dan berhubungan dengan
regulasi reseptor untuk imunitas bawaan, termasuk reseptor scavenger
dan reseptor toll-like (Libby, 2006).
Reseptor scavenger menangkap dan menghancurkan sejumlah
molekul dan partikel yang memiliki pola seperti patogen meliputi
endotoxin bakteri, fragmen sel apoptosis, dan LDL yang teroksidasi.
Reseptor toll-like juga berikatan dengan molekul dengan pola molekul
seperti patogen, tetapi berbeda dengan reseptor scavenger, reseptor
ini menginisiasi kaskade sinyal yang menyebabkan aktivasi sel (Libby,
2006).
Sel imun (termasuk sel T, sel dendritik yang mempresentasikan
antigen, monosit, makrofag, dan sel mast) dan patrol tissue (termasuk
arteri yang mengalami aterosklerosis) akan mencari antigen. Infiltrasi sel
T selalu dijumpai pada lesi aterosklerosis. Ketika reseptor antigen sel T
berikatan dengan antigen, aktivasi kaskade menghasilkan ekspresi
sejumlah sitokin, cell-surface molecule, dan enzim. Respon T-helper tipe
1 (Th1) mengaktivasi makrofag, menginisiasi respon inflamasi yang mirip
dengan hipersensitivitas dan berfungsi melawan patogen intraseluler,
sedangkan respon T-helper tipe 2 (Th2) berupa inflamasi alergi. Lesi
aterosklerosis mengandung sitokin yang merangsang respon Th1. Sel T
56
yang teraktivasi kemudian berdiferensiasi menjadi sel efektor Th1 dan
mulai menghasilkan sitokin interferon γ oleh makrofag. Interferon γ
meningkatkan efisiensi presentasi antigen dan sintesis sitokin inflamasi
berupa tumor necrosis factor dan interleukin 1 (Libby, 2006).
Sitokin sel T menyebabkan produksi sejumlah besar molekul pada
kaskade sitokin. Peningkatan jumlah interleukin-6 dan C-reactive protein
dapat terdeteksi di sirkulasi perifer (Pikir B.S. dkk., 2015).
Gambar 11. Jalur inflamasi selama aterosklerosis yang dapatmeningkatkan konsentrasi penanda inflamasi pada darah(Libby, 2006)
Hiperkolesteromia sendiri diyakini mengganggu fungsi endotel dengan
meningkatkan produksi radikaI bebas oksigen. Radikal ini menonaktifkan
oksida nitrat,yaitu faktor endothelial-relaxing utama. Apabila terjadi
hiperlipidemia kronis, lipoprotein tertimbun dalam lapisan intima di tempat
57
meningkatnya permeabilitas endotel. Pemajanan terhadap radikal bebas
dalam sel endotel dinding arteri menyebabkan terjadinya oksidasi
kolesterol LDL, yang berperan dan mempercepat timbulnya plak
ateromatosa. Oksidasi kolesterol LDL diperkuat oleh kadar kolesterol HDL
yang rendah, diabetes melitus, defisiensi estrogen, hipertensi, dan adanya
derivat merokok. Sebaliknya, kadar kolesterol HDL yang tinggi bersifat
protektif terhadap timbulnya penyakit jantung koroner bila terdiri atas
sedikitnya 25% kolesterol total. Hiperkolesterolemia memicu adhesi
monosit, migrasi sel otot polos subendotel, dan penimbunan lipid dalam
makrofag dan sel-sel otot polos. Apabila terpajan dengan kolesterol LDL
yang teroksidasi, makrofag menjadi sel busa, yang beragregasi dalam
lapisan intima, yang terlihat secara makroskopis sebagai bercak lemak.
Akhirnya, deposisi lipid dan jaringan ikat mengubah bercak lemak ini
menjadi ateroma lemak fibrosa matur. Ruptur menyebabkan inti bagian
dalam plak terpajan dengan kolesterol LDL yang teroksidasi dan
meningkatnya perlekatan elemen sel, termasuk trombosit. Akhirnya,
deposisi. lemak dan jaringan ikat mengubah plak fibrosa menjadi ateroma,
yang dapat mengalami perdarahan, ulserasi, kalsifikasi, atau trombosis,
dan menyebabkan infark miokardium (Price S.A. et al., 2013).
C. CRP (C-Reaktif Protein)
CRP adalah protein yang sangat stabil dan telah diukur di berbagai
laboratorium selama beberapa dekade terakhir untuk menilai proses infeksi
58
aktif atau inflamasi. Metode yang sedang berkembang adalah high-
sensitivity CRP (hs-CRP) karena dapat mengukur nilai CRP pada
konsentrasi ≤0,3 mg/L.
CRP tersusun dari 5 subunit identik dan nonkovalen, masing-
masing terdiri dari 206 residu asam amino dengan berat molekul 23,017
kDa, sehingga total berat molekul CRP sekitar 118,000 kDa dan
merupakan mekanisme pertahanan nonspesifik. CRP merupakan protein
yang meningkat secara konsisten dan protein fase akut yang paling cepat
bereaksi (waktu paruh 19 jam), menunjukkan CRP bagian dari respon
imunitas bawaan. Konsentrasi CRP akan meningkat sampai 1000 kali atau
lebih dalam waktu 24-48 jam setelah cedera jaringan. Menurut
AHA/CDC, interpretasi klinis nilai CRP terhadap risiko kardiovaskular
adalah: < 1mg/L dianggap risiko rendah, 1-3 mg/L risiko sedang, >3
mg/L risiko tinggi. Usia dan etnik tidak mempengaruhi nilai CRP,
tetapi kondisi fisik dan kebiasaan hidup seperti aktivitas fisik, obesitas,
merokok dan konsumsi alkohol mempengaruhi konsentrasi CRP.
hs-CRP adalah penanda inflamasi yang dapat memprediksi
insidensi infark miokardium, stroke, penyakit arteri perifer, dan kematian
jantung mendadak diantara orang normal tanpa riwayat penyakit jantung,
CRP juga memprediksi insidensi serupa pada penderita sindroma koroner
akut ataupun penyakit koroner stabil. CRP tidak hanya disintesis oleh hati
akibat respon terhadap interleukin-6 tetapi juga dihasilkan oleh sel otot
polos dalam arteri koroner. Penelitian menunjukkan CRP dapat
59
mempengaruhi kerentanan vaskuler secara langsung melalui banyak
mekanisme, termasuk peningkatan ekspresi molekul adhesif pada
permukaan sel endotel, MCP-1, endotelin-1, dan PAI-1; menurunkan
bioaktivitas nitrit oksida (NO); peningkatan induksi faktor jaringan pada
monosit; peningkatan serapan LDL oleh makrofag; dan kolonisasi dengan
kompleks membran komplemen dalam lesi aterosklerosis (Kumar, 2007).
Gambar 12. Mekanisme terkait CRP terhadap perkembangan dan progresiaterotrombosis (Kumar, 2007)
Dalam dekade terakhir, pemeriksaan hs-CRP untuk pengukuran
telah tersedia. Teknik assay sensitivitas tinggi seperti
immunonephelometri, immunoturbidimetri, tes ELISA dapat mendeteksi
CRP dengan kisaran sensitivitas 0,01 sampai 10 mg. Tes sensitivitas
tinggi ini membantu mengukur tingkat rendah peradangan sistemik,
dengan tidak adanya gangguan inflamasi atau imunologi sistemik yang
jelas. Tes hs-CRP adalah pemeriksaan high sensitivity CRP yang dapat
60
digunakan untuk mendeteksi konsentrasi CRP yang sangat kecil, telah
distandarisasi di platform komersial dan dapat diukur secara akurat dari
plasma segar atau beku. hs-CRP adalah biomarker yang paling banyak
dievaluasi dalam pencarian biomarker ideal untuk prediksor risiko penyakit
jantung koroner secara global (Kamath D.Y. et al. 2015).
Ada beberapa keterbatasan intrepretasi pemeriksaan hs-CRP, yaitu
non-spesifik, bisa meningkat konsentrasinya dalam keadaan infeksi akut
dan trauma. Supaya akurat, pemeriksaan hs-CRP jangan dilakukan pada
kedua kondisi tersebut (Rilantono L.I, 2012).
Kontroversi diperdebatkan apakah hs-CRP berkontribusi pada
proses arterosklerosis atau hanya sebagai penanda peradangan. hs-CRP
telah diketahui memiliki sifat opsonisasi, meningkatkan perekrutan monosit
ke dalam plak atheromatous dan juga menginduksi disfungsi endotel
dengan menekan pelepasan oksida nitrat basal dan induksi. hs-CRP juga
telah ditemukan dapat meningkatakan ekspresi vascular endotel PAI-1
dan molekul adhesi lainnya dan dapat mengubah pengambilan LDL oleh
makrofag (Kamath, D.Y. et al. 2015).
Peradangan dan CRP dimana Efek pro aterogenik CRP melampaui
endotelium ke otot polos vaskular. CRP memainkan peran penting dalam
banyak aspek atherogenesis, CRP meningkatkan serapan LDL ke
makrofag dan meningkatkan kemampuan makrofag untuk membentuk sel-
sel busa. Ini juga mengikat phosphocholine dari LDL teroksidasi. CRP
menghambat ekspresi NO sintase endotel dalam EC. NO memiliki efek
61
anti-aterogenik yang penting, termasuk penurunan agregasi trombosit,
vasokonstriksi, dan proliferasi sel otot polos. CRP meregulasi ekspresi
molekul adhesi pada ECs yang dapat menarik monosit ke tempat cedera
(Nakkeeran M, 2017).
Dalam kasus CRP peradangan intensitas rendah kronis merusak
glikokaliks endotelium vaskular, menyebabkan disfungsi dan membuatnya
lebih rentan terhadap faktor proatherogenic (Nakkeeran M, 2017).
D. LDL Kolesterol
Low density lipoprotein mengandung paling banyak kolesterol dari
semua lipoprotein, dan merupakan pengirim kolesterol utama dalam
darah. Sel hati memproduksi kolesterol dalam tubuh, kemudian
disebarkan oleh kolesterol LDL dalam darah ke jaringan-jaringan tubuh
yang membutuhkan. Kadar kolesterol LDL yang tinggi dan pekat di dalam
darah akan menyebabkan kolestrol lebih banyak melekat pada dinding-
dinding pembuluh darah pada saat trasportasi dilakukan. Kolesterol LDL
yang melekat perlahan-lahan akan mudah melakukan tumpukan-
tumpukan lalu mengendap, membentuk plak pada dinding-dinding
pembuluh darah. Tumpukan kolesterol LDL yang mengendap pada
dinding-dinding pembuluh darah dapat menyebabkan lumen pembuluh
darah menyempit. Akibatnya, suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh
terhambat. Jika dibiarkan, dapat mengakibatkan gangguan jantung, strok,
dan gangguan lain (Suharto,I. 2001).
62
Hipertensi yang terjadi pada tubuh akan memompa jantung untuk
bekerja lebih keras, aliran darah akan lebih cepat dari yang normal.
Akibatnya aliran darah semakin kuat menekan pembuluh darah. Tekanan
yang kuat ini dapat merusak jaringan pembuluh darah itu sendiri.
Pembuluh darah yang rusak sangat mudah sebagai tempat melekatnya
kolesterol LDL, sehingga kolesterol LDL dalam saluran darah pun melekat
dengan kuat dan mudah menumpuk (Suharto,I. 2001).
Brown dan Goldstein (1994) mengatakan bahwa LDL tersusun
oleh inti berupa 1500 molekul kolesterol yang dibungkus oleh lapisan
fosfolipid dan molekul kolesterol tidak teresterifikasi. Bagian hidrofilik
molekul terletak di sebelah luar, sehingga memungkinkan LDL larut dalam
darah atau cairan extraseluller. Protein berukuran besar yang disebut
apoprotein B-100 mengenal dan mengikat reseptor LDL yang mempunyai
peran penting dalam pengaturan metabolisme kolesterol. Protein utama
pembentuk LDL adalah apolipoprotein (Apo B). Kandungan lemak jenuh
tinggi membuat LDL mengambang di dalam darah. LDL dapat
menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah. LDL
berfungsi membawa kolestrol dari hati menuju jaringan (Murray, 2009).
E. HIPERTENSI PADA PENYAKIT JANTUNG KORONER
Studi hipertensi epidemiologi menunjukkkan adanya asosiasi kuat
antara hipertensi dan penyakit jantung koroner (PJK). Hipertensi kronis
arterial menjadi salah satu faktor risiko kardiovaskuler yang berkontribusi
63
terhadap kejadian arteriosklerosis dan meningkatkan kejadian penyakit
vaskular perifer, penyakit serebrovaskuler, penyakit ginjal kronis, dan
penyakit arteri koroner. Di samping itu hipertensi kronis juga merupakan
faktor risiko penting dalam patogenesis PJK, dikarenakan pasien
hipertensi lebih sering mengalami silent ischemia dan IM painless
dibanding dengan pasien normotensi. Selain itu sering kali hipertensi yang
sudah ada sebelumnya dapat tidak dikenali pada pasien first seen post-IM
(Pikir. B.S. dkk., 2015)
Patofisiologi penyakit jantung koroner
Aterosklerosis adalah gangguan vaskuler progresif dan sistemik,
yang secara klinis bermanifestasi sebagai PJK. Kejadian awal molekuler
dan seluler pada aterogenesis dipicu oleh adanya disfungsi endotel yang
berakibat penurunan produksi NO, peningkatan aktivitas cyclooxygenesis
dan inflamasi. Respon inflamasi awal biasanya menguntungkan namun
bila progresif akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Factor-
faktor proinflamasi seperti LDL teroksidasi dan agen infeksius merangsang
pelepasan sitokin dari vaskuler dan perifer lainnya. Proses ini
mengakibatkan akumulasi sel monoklear, migrasi dan proliferasi sel otot
polos, dan pembentukan jaringan fibrosa, dan berakhir pada pembentukan
plak aterosklerotik (Pikir B.S.dkk., 2015).
Perjalanan PJK tidak hanya meliputi perkembangan plak saja,
tetapi juga terjadi rupture plak, vasokontriksi dan thrombosis lokal yang
berakibat obstruksi arteri. Rupture plak tidak selalu terkait dengan ukuran
64
dan derajat stenosisplak. Pada kebanyakan kasus infark mioakard terjadi
karena adanya penipisan pada fibrous cap pada region bahu, dimana
makrofag terakumulasi dan terjadi apoptosis berlebih. Sitokin meningkat
pada plak yang peka di mana terjadi rekrutmen dan aktivasi makrofag.
Makrofag yang teraktivasi ini mengeluarkan enzimproteolitik yang
mengoperasikan cap yang kaya protein, sehingga bahan-bahan
trombogenik terpapar yang mengakibatkan sindrom koroner akut (SKA).
Dinding arteri merupakan struktur yang dinamis dan mengalami
remodeling untuk mengakomodasi perkembangan plak tanpa mengubah
dimensi lumen. Disfungsi endotel penting terhadap perkembangan plak,
oleh karena itu penting untuk indentifiksi dan menerapi secara agresif
factor-faktor risiko yang ada seperti hipertensi, displedemia, diabetes (Pikir
B.S. dkk., 2015).
Iskemik selalu berasal dari peningkatan tonus vaskular atau
hilangnya reaktivitas terhadap stres fisiologi normal. Vosokonstriksi dan
vasospasme yang berlebihan dapat berakibat langsung terjadinya rupture
plak dan onklusi pembuluh darah pada pasien PJK. Untuk mengatasi
keadaan tersebut endotel melepas NO yang berperan pada vasodinamik
vaskuler. Pelepasan NO dirangsang oleh berbagai faktor, salah satunya
shear stress. Proses ini terganggu pada keadaan aterogenik (Pikir, B.S.
dkk. 2015).
65
F. Kerangka Teori
Resiko Genetik
ACE
Angiotensinogen
Angiotensin Reseptor
Hipertensi
Mekanisme StressDisfungsi Endotel Permeabilitas Intima
LDL - kolestrol
Perkembangan PlakRupture Plak
Inflamasi
Aterosklerosis
hs-CRP
66
G. KERANGKA KONSEP
Keterangan :
= Variabel bebas
= Variabel terikat
= Variabel kendali
G. VARIABEL PENELITIAN
1. Variabel bebas : Hipertensi Non Obes dan kolesterol LDL
2. Variabel tergantung : Kadar hs-CRP
3. Variabel kendali : Strok, penyakit jantung, diabetes mellitus
Hipertensi Non Obes
Kadar Kolestrol LDL
Kadar hs-CRP
StrokePenyakit JantungDiabetes Melitus
67
BAB III
METODE PENELITIAN
A. RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan penelitian ini merupakan penelitian cross sectional
dengan populasi sampel subyek yang mengalami hipertensi non obes.
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Pengumpulan spesimen dilakukan di Puskesmas Lappae dan
Samaenre Kabupaten Sinjai pada bulan Agustus–Oktober 2018.
Pemeriksaan laboratorium dilakukan di laboratorium Klinik Parahita
Makassar.
C. POPULASI DAN SAMPEL
a. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah pasien hipertensi yang menjalani
rawat jalan di Puskesmas Lappae dan Samaenre di Kabupaten Sinjai.
b. Sampel
Sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan
eksklusi.
Besaran sampel dihitung sesuai dengan rumus untuk uji korelasi.
68
Sampel dengan koefisien korelasi sebesar (R) = 0,378.
Kesalahan tipe I ditetapkan sebesar 5%, hipotesis satu arah, sehingga:
Zα = 1,64. Kesalahan tipe II diteatapkan 10%, maka Nilai Zβ = 1,28
(Sopiyudin.M., 2010)
Perhitungan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini
menggunakan rumus :
n =
=
=
= 63,08
Sehingga didapatkan perkiraan besar sampel minimal yang dibutuhkan
adalah 63,08 sampel yang dibulatkan menjadi 64 sampel.
Keterangan :
Zα = deviat baku alfa, (untuk α =0.05 Zα = 1,64
Zβ = deviat baku beta, (untuk = 0,10 Z = 1,28
r = korelasi minimal yang dianggap bermakna
D. Kriteria sampel
1. Kriteria inklusi
a. Menderita hipertensi dengan berat badan normal (non obes).
b. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan
menandatangani surat persetujuan atas dasar kesukarelaan
69
(informed consent).
2. Kriteria eksklusi
a. Pasien dengan riwayat stroke
b. Pasien penderita penyakit jantung
c. Pasien penderita diabetes melitus
E. Defenisi Operasional
1. Penderita hipertensi adalah orang yang mempunyai tekanan darah
sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah
diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg yang berobat jalan
di Puskesmas di wilayah Kabupaten Sinjai, dan telah dinyatakan
oleh petugas kesehatan atau klinisi menderita hipertensi.
2. Non Obes adalah kondisi dengan Body mass index (BMI) < 24,9
kg/m. BMI dihitung dengan cara membagi besaran berat badan
dalam kilogram (kg) dengan kuadrat tinggi badan dalam meter (m).
3. hs-CRP adalah C-Reaktif protein merupakan suatu alfa-globulin yang
diproduksi di hepar, merupakan biomarker yang dapat mencerminkan
inflamasi yang rendah dalam tubuh, telah diidentifakasi sebagai faktor
70
resiko jantung koroner. Dideteksi dengan metode immunoturbidimetri
menggunakan kit Nanopia CRP (Sekisui Medical CO.,LTD, Japan).
Kriteria objektif, hs-CRP <0,1 mg/dl risiko rendah PJK, 0,1-0,3 mg/dl
risiko sedang PJK, dan >0,3 mg/dl risiko tinggi PJK.
4. Kolesterol LDL adalah kolesterol yang mengandung paling banyak
kolesterol dari semua lipoprotein, dan merupakan pengirim kolesterol
utama dalam darah ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan.
Dideteksi dengan metode Homogeneus menggunakan kit LDL-
Cholestrol Gen.3 (Roche Diagnostics, Germany) dengan nilai optimal
<100 mg/dl, batas tinggi 100-159 mg/dl, tinggi 160-189 mg/dl, dan
sangat tinggi ≥ 190 mg/dl.
F. Persiapan Alat dan Bahan
1. Alat Penelitian
Alat-alat yang digunakan adalah alat COBAS C 501, mikropipet
100-1000µl dan alat TMS 24i Premium.
2. Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan adalah serum, Reagen kit LDL-
Cholestrol Gen.3, reagen control Biorad, Reagen hsCRP kit siap
pakai dan reagen kalibrator CRP siap pakai.
G. Cara Kerja
1. Subjek Penelitian
71
Subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi,
yang diketahui melalui beberapa tahap: wawancara/anamnesis
untuk memperoleh informasi tentang karakteristik dan keadaan
umum subjek misal umur, riwayat penyakit, dan seterusnya sesuai
dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Pengukuran IMT,
Pemeriksaan laboratorium kadar kolesterol LDL dengan metode
Homogeneus dan hs-CRP menggunakan metode
imunoturbidimetrik.
2. Pengumpulan spesimen
Darah pasien diambil sebanyak 3 ml melalui vena mediana
cubiti. Darah yang diambil dimasukkan kedalam tabung pemisah
serum (tube separating serum) dan didiamkan membeku ±30 menit.
Sentifugasi selama 15 menit pada 1000 rpm. Serum dipisahkan
untuk pemeriksaan kolesterol LDL dan hs-CRP.
H. ANALISIS DATA
Data yang terkumpul diolah melalui analisis statistik, Dilakukan analisis
univariat, bivariate, hasilnya dinarasikan dan diperjelas oleh tabel. Untuk
uji statistik, tingkat kemaknaan (signifikansi) yang digunakan adalah 5%,
Dimana analisis yang digunakan adalah :
1. Analisis data secara deskriptif umum, dengan metode analisis
univariat untuk perhitungan minimum, maksimum, rerata, median
dan standar deviasi.
72
2. Analisis hubungan antara variabel bebas dan tergantung yaitu
analisis korelasi bivariate dan parsial. Parameter yang berdistribusi
normal menggunakan korelasi uji t dan yang tidak berdistribusi
normal dengan uji Mann-Whitney. Untuk uji korelasi digunakan uji
spearman.
I. ALUR PENELITIAN
hs-CRP Kolesterol LDL
KESIMPULANDAN SARAN
KRITERIA INKLUSI
HASIL
SAMPELPENELITIAN
KRITERIA EKSKLUSI
PENDERITA HIPERTENSI
Analisis
SPESIMEN DARAHVENA
73
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran umum subyek penelitian
Penelitian ini dilaksanan pada bulan Agustus – Oktober 2018
melibatkan 64 subyek hipertensi non obes terdiri dari 18 laki-laki (28,1 %)
dan 46 wanita (71,9%) dengan kisaran umur antara 38 tahun sampai 79
tahun, dilakukan pengukuran kadar kolesterol LDL dan hs-CRP.
Karasteristik umum subyek penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Karasteristik subyek penelitian
Karasteristik Jumlah(n = 64)
Persentase(%)
Jenis Kelamin Laki-laki
Perempuan
18
46
28,1
71,9
Klasifikasi Umur
(Tahun)
47-59
60-79
26
38
40,6
59,4
Kadar hs-CRP
(mg/dl)
Risiko rendah PJK
Risiko sedang PJK
Risiko tinggi PJK
23
26
15
35,9
40,6
23,4
Kadar Kolesterol
LDL (mg/dl)
Optimal
Batas Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
11
32
7
16
14,1
50,0
10,9
25,0
74
2. Kadar Kolesterol LDL pada subyek hipertensi non obes
Untuk mengetahui perbandingan kadar kolesterol LDL pada laki-laki
dan perempuan dilakukan analisis statistik. Sebelumnya dilakukan uji
normalitas sampel dengan uji Kolmogorov-Smirnov, hasilnya semua
kelompok berdistribusi normal. Sehingga dilakukan uji t dimana hasil dapat
dilihat pada Tabel 3.
Tabel. 3 Kadar Kolesterol LDL subyek hipertensi non obes laki-laki dan
perempuan
Jenis Kelamin NKolesterol LDL (mg/dl)
*pMean SD Range
Laki-laki
Perempuan
18
46
154,228
148,609
42,626
56,547
79-215
55-365
0,758
*p : Uji t
Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji t
didapatkan rerata kadar kolesterol LDL yang berjenis kelamin laki-laki
adalah 154,228 mg/dl sedangkan rerarata pada jenis kelamin perempuan
adalah 148,609 mg/dl, nilai p = 0,758. Hal ini menunjukkan bahwa pada
pasien berjenis kelamin laki-laki rerata kadarnya lebih tinggi dibanding
rerata kadar pada perempuan perbedaan tersebut tidak menunjukkan
perbedaan yang bermakna.
75
Tabel 4. Kadar kolesterol LDL pada subyek hipertensi non obes
berdasarkan kelompok umur.
Umur Tahun NKolesterol LDL (mg/dl)
*pMean SD Range
38-59
≥ 60
26
38
129,538
164,665
38,825
56,665
55-208
72-365
0,09
*p : Uji t
Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji t
didapatkan rerata kadar kolesterol LDL pada kelompok umur 38-59 tahun
adalah 129,538 mg/dl sedangkan rerata pada kelompok umur ≥ 60 tahun
adalah 164,665 mg/dl (p = 0,09). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun
pada subyek kelompok umur ≥ 60 tahun rerata kadarnya lebih tinggi
dibanding kelompok umur 38-59 tahun, tetapi perbedaan tersebut secara
statistik tidak bermakna.
3. Kadar hs-CRP pada subyek hipertensi non obes
Untuk mengetahui perbandingan kadar hs-CRP pada laki-laki dan
perempuan dilakukan analisis statistik. Sebelumnya dilakukan uji
normalitas sampel dengan uji Kolmogorov-Smirnov, hasilnya semua
kelompok tidak berdistribusi normal, dilakukan uji non parametrik dengan
Uji Mann-Whitney.
76
Table. 5 Kadar hs-CRP subyek hipertensi non obes laki-laki dan
perempuan
Jenis Kelamin Nhs-CRP (mg/dl)
*pMedian SD Range
Laki-laki
Perempuan
18
46
0,32
0,145
1,756
0,159
0,01-7,49
0,02-0,92
0,12
*p : uji Mann-whitney
Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai median kadar hs-CRP pada
kelompok laki-laki adalah 0,32 mg/dl, sedangkan rerata pada jenis kelamin
perempuan adalah 0,145 mg/dl dengan menggunakan uji Mann-Whitney
(p = 0,12). Hal ini menunjukkan bahwa pada pasien berjenis kelamin laki-
laki nilai median lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan, tetapi
perbedaan tersebut secara statistik tidak bermakna.
Tabel 6. Kadar hs-CRP pada subyek hipertensi non obes kelompok umur.
Kelompok
Umur (tahun)N
hs-CRP (mg/dl)*p
Median SD Range
38-59
≥ 60
26
38
0,18
0,165
0,477
1,214
0,01– 0,38
0,02-7,49
0,816
*p : Uji Mann-Whitney
Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Mann-Whitney
didapatkan median kadar hs-CRP kelompok umur 38-59 tahun adalah
0,18 mg/dl sedangkan median pada kelompok umur ≥ 60 tahun adalah
77
0,165 mg/dl (p = 0,861). Hal ini menunjukkan bahwa pada subyek
kelompok umur secara statistik tidak ada perbedaan bermakna.
4. Analisis Korelasi Kolesterol LDL dan hs-CRP pada subyek hipertensi
non obes.
Dari uji korelasi spearman diperoleh p = 0,148 yang menunjukkan
korelasi kadar kolesterol LDL dan kadar hs-CRP tidak bermakna. Nilai
koefisien korelasi sebesar r= 0,133 menunjukkan korelasi arah positif
artinya terdapat hubungan antara kadar kolesterol LDL dan hs-CRP sama-
sama meningkat dengan kekuatan korelasi yang lemah Tabel 7.
Tabel 7. Korelasi kolesterol LDL dan hs-CRP pada subyek hipertensi non
obes.
Kadar hs-CRP
Kadar Kolesterol LDL r = 0.133
p = 0.148
n = 64
*p = Uji korelasi Spearman
78
B. PEMBAHASAN
Penelitian ini mengamati korelasi kadar kolesterol LDL dan hs-CRP
pada subyek hipertensi non obes, dimana hs-CRP sebagai penanda
inflamasi tingkat rendah pada pembuluh darah. Pada penelitian ini diambil
subyek hipertensi non obes karena BMI > 24,9 kg/m3 dihubungkan
dengan peningkatan penyakit kardiovaskular. Peningkatan risiko yang
sama juga diidentifikasi untuk hipertensi, hyperlipidemia.
Berdasarkan hasil uji t (p = 0,758) tidak terdapat hubungan yang
bermakna antara jenis kelamin dengan status kolesterol LDL subyek
hipertensi non obes.
Untuk kelompok umur dengan status kolesterol LDL, uji t p = 0,09
(p> 0,05), secara statistik tidak bermakna. Pada penelitian ini, hubungan
yang tidak bermakna karena umur memang bukan termasuk faktor resiko
hiperkolesterol LDL.
Berdasarkan hasil uji Mann-whitney diketahui bahwa tidak terdapat
hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan konsentrasii hs-
CRP pada subyek hipertensi non obes (p= 0,12), hal ini karena jenis
kelamin memang bukan termasuk faktor resiko inflamasi tingkat rendah
pada pembuluh darah. The prospective Studies Collaboration
menemukan hubungan spesifik usia dari mortalitas ischemic heart
disease (IHD) dan tekanan darah sedikit lebih besar pada perempuan
dibandingkan laiki-laki dan menyimpulkan bahwa untuk mortalitas
vaskular secara keseluruhan, jenis kelamin kurang relevan (Lewington
79
dkk, 2002). Efek perlindungan estrogen dianggap menjelaskan adanya
imunitas wanita pada usia sebelum menoupouse, tetapi pada kedua jenis
kelamin dalam usia 60 hingga 70-an, frekuensi MI menjadi setara
(Price,S.A. dkk.2013).
Hasil penelitian ini menunjukkan pula tidak ada perbedaan yang
bermakna antara kadar hs-CRP dengan kelompok umur berdasarkan uji
statistik dengan uji Mann-Whitney (p = 0,816). Tekanan darah sistolik
meningkat progresif sesuai usia dan orang lanjut usia dengan hipertensi
merupakan risiko besar untuk penyakit kardiovaskular (Pikir S.B, 2015).
Berdasarkan tabel 7 hasil uji korelasi dengan uji Spearman
didapatkan nilai p= 0.148 (p> 0,05) korelasi antara kolesterol LDL dan
hs-CRP tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik.
Nilai koefisien korelasi sebesar r= 0,133 yang berarti arah positif artinya
terdapat hubungan antara kolesterol LDL dan hs-CRP sama-sama
meningkat dengan kekuatan korelasi yang sangat lemah, mungkin
disebabkan karena yang diukur kolesterol LDL bebas bukan LDL
teroksidasi (ox-LDL) yang menyebabkan inflamasi tingkat rendah pada
pembuluh darah. Oksidasi kolesterol LDL diperkuat oleh kadar kolesterol
HDL yang rendah, diabetes mellitus, defisiensi estrogen, hipertensi dan
adanya derivate merokok. Sebaliknya, kadar kolesterol HDL yang tinggi
bersifat protektif terhadap timbulnya penyakit jantung koroner bila terdiri
atas sedikitnya 25% kolesterol total (Pikir B.S., 2015). Dapat juga
80
disebabkan masih ada faktor perancu yang tidak dikendalikan seperti
merokok dan defisiensi estrogen.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada subyek
hipertensi non obes dari semua jenis kolesterol yang diperiksa dan
mengalami peningkatan yang sangat signifikan sama dengan kadar hs-
CRP adalah kolesterol LDL (Nakkeeran M, et al,2017). Hiperkolestromia
diyakini mengganggu fungsi endotel dengan meningkatkan produksi
radikal bebas, pemajanan terhadap radikal bebas dalam sel endotel
arteri menyebabkan terjadinya oksidasi kolesterol LDL yang merupakan
salah satu penyebab inflamasi tingkat rendah pada pembuluh darah
(Price,S.A.dkk.2013). Keterbatasan penelitian ini adalah pemeriksaan
yang dilakukan adalah kolesterol LDL bukan LDL teroksidasi (ox LDL),
masih ada faktor perancu yang tidak dikendalikan, tidak dilakukannya
pemeriksaan kolesterol HDL dan umur subyek hipertensi non obes tidak
terdistribusi dengan baik, tidak dibandingkannya antara pasien hipertensi
non obes dengan orang normal sebagi kontrol .
81
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Rerata kadar kolesterol pada subyek hipertensi non obes pada
kelompok laki-laki lebih tinggi dari kelompok perempuan tetapi tidak
bermakna.
2. Rerata kadar kolesterol pada kelompok umur ≥ 60 tahun lebih tinggi
dari kelompok umur 38-59 tahun, tetapi perbedaannya tidak
bermakna.
3. Tidak ada perbedaan yang bermakna kadar hs-CRP antara laki-laki
dan perempuan pada subyek HT non obes.
4. Hubungan kadar hs-CRP dengan kelompok umur ≥ 60 tahun dan
kelompok umur 38-59 tahun tidak ada perbedaan.
5. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman korelasi kadar hs-CRP
dan kolesterol LDL tidak bermakna.
B. Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan pengaruh
yang lebih jelas antara kadar LDL teroksidasi (ox-LDL) terhadap
kadar hs-CRP.
2. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan kontrol
subyek normal.
82
DAFTAR PUSTAKA
Arshad, A, dkk. (2016). To Determine the Frequency of Hypertensionwith Raised Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) inPatients of Chronic Renal Failure. Diunduh 6 Juni 2018. Availablefrom: di www.pjmhsonline.com
Corwin,E,J, (2001) Buku saku Patofisiologi EGC. Jakarta2001
Ding, et al. (2015). Body Mass Index, High-Sensitivity C-Reactive Proteinand Mortality in Chinese with Coronary Artery Disease. Diunduh 15June 2018. Available from: http://journals.plos.
Filla, Putu J.F. (2015). hs-CRP as Biomarker of Coronary Heart Disease.Diunduh 3 Juni 2018. Available from: http://juke.kedokteran.unila.ac.id
Hansson G. K. (2005). Inflammation, Atherosclerosis, and CoronaryArtery Disease. N.Engl.J.Med. Number 16.352:1685-1695.
Kamath, D.Y. et al. (2015). High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)and Cardiovascular Disease: An Indian Perspective. Indian Journalof Medical Research, 142(3): 261–268.
Kowalak P, et al. (2017). Buku Ajar Patofisiologi. Penerbit bukukedokteran. EGC.
Kemenkes RI. (2016). Sebagian besar penderita hipertensi belumterdiagnosa apalagi berobat. Jakarta: Sumber Biro komunikasi danpelayanan masyarakat.
Kumar, Abbas, Fausto, Mitcheel, 2007. Robbins Basic Pathology.8th edition. Elsevier . p343-353.
Libby P. (2006). Current consepts of the pathogenesis of the acutecoronary syndrome. Cirlulation 104:365.
Marques, P, dkk, (2018). LDL Cholesterol Control in Patients from aHypertension Clinic. Journal of Hypertension. 36():e246
Montezano, A.C. (2015). Redox signaling, Nox5 and vascular remodelingin hypertension. Diunduh 6 Juni 2018. Available from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4727501
Mouridsen MR, et. al. 2014. High Sensitivity Creative Protein and ExerciseInduced Changes in Subjects Suspected of Coronary ArteryDisease. Jurnal Inflamm Research; (7): P. 45-55.
83
Muis M Murtala B,. (2011) Peranan Ultrasonografi dalam menilai
KompleksIntima Media Arteri Karotis untuk Diagnosa dini
Aterosklerosis. Bagian Radiologi, Fakultas Kedokteran UNHAS.
Murray, R.K., Granner D.K., Mayes P.A. Rodwell, V.W. (1996). BiokimiaHarper, EGC. Jakarta.
Nakkeeran M, Periasamy S, Inmozhi SR, Santha K dan Sethupathy.(2017). Increased Level of Inflammatory Marker hs-CRP, MDA andLipid Profile in Non-obese Hypertension Subject. Diunduh 20 Juni2018. Available from: https://www.omicsonline.
Nisa H. (2016). C-Reactive Protein untuk Menimbulkan Risiko Penyakit.Diunduh 5 maret 2018. Available from:http://www.repository.uinjkt.ac.id
Paulman, P M dkk., (2013). Taylor Manual Diagnostik Dalam 10 menit.Binarupa Aksara Publisher.
Pikir, B.S. dkk. (2015). Hipertensi Manajemen Komperhensip. AirlanggaUniversity Press.
Price, S.A. dkk. (2013). Patofisiologi Konsep Klinis Proses-ProsesPenyakit. Jakarta: Penerbit Buku kedokteran EGC, 576-586
Pusdatin Kemenkes RI, (2014). Mencegah dan mengontrol hipertensi agarterhidar dari kerusakan organ jantung, otak dan ginjal. DepartemenKesehatan Republik Indonesia.
Poppy M, (2009). Perkembangan Konsep Pathogenesis Aterosklerosis.Jurnal Biomedik. Vol. 1, 1. 12-22.
Rilantono, L.I. (2012). Penyakit Kardiovaskular (PKV). Badan PenerbitFakultas Kedokteran Universitas Indonesia.235
Ross Russell (1999). Atherosclerosis – An Inflammatory Disease.N.Engl.J.Med. 340:115-126.
Rudijanto Achmad (2007). The Role of vascular Smooth Muscle Cells onthe Pathogenesis of Atherosclerosis. Acta Medica Indonesiana.Vol.XXXIX, 4: 86-91.
Schoen J Frederick (2005). Blood Vessels. In: Kumar, Abbas, Fausto.Robbins and Cotran Pathologic Basis of disease. 7th ed. ElsevierSaunders. p.516-524.
84
Sopiyudin, D.M, (2010). Besaran Sampel dan Cara Pengambilan Sampeldalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan. Edisi 3. Jakarta:Salemba Medika.
Soeharto,I. (2004). Penyakit Jantung Koroner dan Serangan Jantung.Edisi ke-2. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Surentu, J. H., dkk. (2014). Hubungan Kolestrol High Density LipoproteinDarah dengan Kadar High Sensitivity C. Reactive Protein padaRemaja Obes. Diunduh 10 April 2018. Available from:https://media.neliti.com.
Tutuncu, Y. et al. (2016). A Comparison of hs-CRP Levels in NewDiabetes Groups Diagnosed Based on FPG, 2-hPG, or HbA1cCriteria. Journal of Diabetes Research. Vol. 6
Wibowo JW., (2011), Berat badan lahir rendah sebagai faktor resiko
penyakit jantung koroner, FK UNISSULA, Sains medika,Vol 3 no 2
Yousuf, Oumair. et al. (2013). High-Sensitivity C-Reactive Protein andCardiovascular Disease. Journal of the American College ofCardiology. Vol. 62 No. 5 P. 397-408.
Yonata, A., Satria, A.2016. Hipertensi sebagai Faktor pencetus TerjadinyaStroke. Majority Vol. 5. No. 3.
Kolesterol LDL hs-CRP Lama hipertensi Klasifikasi
mg/dl mg/dl (tahun) Hipertensi
1 JE 2 57 106 0.24 5 2
2 HA 2 49 147 0.09 1 1
3 US 1 43 117 0.01 1 1
4 SA 2 59 97 0.07 2 1
5 AP 1 46 134 1.12 3 1
6 FA 1 54 144 0.2 10 2
7 EN 1 60 113 0.04 1 1
8 SA 2 50 161 0.15 5 1
9 PA 1 75 197 1.64 10 2
10 CO 1 64 185 2.38 10 2
11 BA 2 53 55 0.05 1 1
12 TA 2 60 72 0.21 10 2
13 TI 2 48 176 0.3 1 1
14 JO 2 75 177 0.19 10 2
15 SA 2 73 205 0.52 5 2
16 HA 2 80 128 0.17 12 2
17 BU 2 47 104 0.28 2 2
18 NU 2 38 105 0.17 3 2
19 CA 1 65 95 0.09 5 1
20 NA 2 50 121 0.14 2 2
21 US 1 75 193 0.39 8 2
22 SI 2 73 143 0.06 5 2
23 DI 2 48 95 0.11 2 1
24 SI 2 57 76 0.29 6 1
25 PE 2 68 156 0.02 2 1
26 TA 1 76 215 0.65 10 2
27 IK 1 67 133 0.28 3 2
28 NA 1 66 224 0.59 5 2
29 HA 2 65 78 0.17 3 2
30 AB 2 78 156 0.22 7 2
31 PI 2 75 142 0.09 12 2
32 AT 2 67 149 0.14 10 1
33 BA 1 59 208 0.52 5 1
34 JA 2 72 168 0.04 5 1
35 HA 2 70 174 0.12 7 2
36 APE 2 47 86 0.15 10 1
37 SA 2 50 148 0.08 1 1
38 RU 2 52 76 0.35 3 1
39 SU 1 66 205 0.05 1 1
40 IB 1 79 161 7.49 14 2
41 RA 2 60 213 0.08 6 2
42 SI 2 60 196 0.05 1 1
43 NUR 2 51 141 0.03 4 2
44 KA 2 71 137 0.04 2 1
45 MA 2 47 204 0.04 5 1
46 GA 1 72 126 0.32 6 2
47 HA 2 64 256 0.09 3 2
48 MU 2 57 148 0.2 5 2
49 PA 1 60 105 0.04 1 1
50 SA 1 70 124 0.2 3 2
51 HA 2 67 223 0.47 6 2
NO NAMA Jenis Kelamin UMUR
DATA SUBYEK HIPERTENSI NON OBES
52 KA 2 51 159 0.19 3 1
53 CM 2 68 138 0.92 11 2
54 MI 2 59 127 0.05 2 2
55 CD 2 52 125 0.22 3 2
56 CA 2 50 123 0.32 6 2
57 GAP 1 70 108 0.32 12 2
58 KA 2 76 110 0.29 11 2
59 MI 2 75 196 0.09 3 2
60 HA 2 69 209 0.16 2 1
61 RE 2 65 365 0.14 5 2
62 RO 2 71 139 0.04 20 2
63 HA 2 65 226 0.18 5 2
64 TI 2 62 100 0.03 1 1
Jenis Kelamin ; 1 = laki- laki, 2 = perempuan
Kalsifikasi Hipertensi ; 1 = Tingkat 1, 2 = Tingkat 2