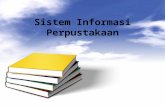tesis - perpustakaan universitas hasanuddin
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of tesis - perpustakaan universitas hasanuddin
TESIS
PENGARUH PEMBERIAN BISKUIT MAKANAN TAMBAHAN (MT)TERHADAP STATUS GIZI DAN KADAR 8-HYDROXY-2’
DEOXYGUANOSIN (8-OHdG) PADA IBU HAMILKURANG ENERGI KRONIS YANG DIBERIKAN
TABLET TAMBAH DARAH (IFA)
THE EFFECT OF FEEDING SUPPLEMENTARY BISCUITSON NUTRITIONAL STATUS AND 8-HYDROXY-2’
DEOXYGUANOSIN (8-OHDG) IN PREGNANTWOMEN KEK WHO WERE GIVEN TABLET
ADDED BLOOD
RAEHAN
(P4400215007)
PROGRAM STUDI MEGISTER KEBIDANANUNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR2017
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Raehan
Nim : P4400215007
Program studi : Ilmu Kebidanan
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-
benar merupakan hasil karya saya sendri, bukan merupakan pengambil
alihkan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti
atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesisi ini hasil
karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.
Makassar , Agustus 2017
Yang menyatakan,
RAEHAN
ABSTRAK
Raehan, Pengaruh Pemberian biskuit Makanan Tambahan dan TabletTambah darah IFA Terhadap Status Gizi dan Kadar 8-Hidroxy-2-DeoxyGuanosin Pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Dibimbing OlehVeni Hadju dan Andi Wardihan Sinrang).
Pencapaian kesehatan ibu yang optimal selama masa selamamasa kehamilan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; akses terhadappelayanan kesehatan, status gizi ibu selama hamil, keberhasilan programKIA/KB, lingkungan, sosial budaya klien yang berhubungan dengankesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan dan persalinan sertakemampuan ekonomi keluarga.
Jenis penelitian ini quasi ekperiment dengan rancanagn pre test-post test dengan kelompok kontrol. Sampel dalam penelitian ini ibu hamilKEK sebanyak 40 orang dibagi mnjadi 2 kelompok, ibu yang mendapatkanbiskuit makanan tambahan dan tablet tambah darah (Kelompok Intervesi),ibu yang mendapatkan tablet IFA (Kelompok Kontrol). Perlakuan dilakukanselama 12 minggu, analisi data menggunakan uji Wilcoxon dan uji Tindependent.
Hasil penelitian penelitian menunjukkan ada pengaruh biskuitmakanan tambahan terhadap status gizi dan kadar 8-OHdG setelahimplementasi dengan p< 0,05 (0,001). Setelah perlakuan diperoleh rata-rata pada status gizi meningkat dan terjadi penurunan pada kadar 8-OHdG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang diberikanbiskuit makanan tambahan+tablet IFA lebih aktif meningkatkan status gizidan menurunkan kadar 8-OHdG dibandingkan dengan yang hanyadiberikan tablet tambah darah (IFA).
Pemberian biskuit makanan tambahan dapat meningkatkan statusgizi pada ibu hamil KEK terutama makanan yang banyak mengandungVitamin dan asam folat untuk mencegah kerusakan DNA.
Kata kunci: Biskuit makanan tambahan, ibu hamil KEK, Status gizi, 8-Hydroxy-2’DeoxyGuanosin.
ABSTRACK
Raehan, The Effect of Feeding Supplementary Biscuits on NutritionalStatus and 8-OHdG In Pregnant Women KEK who were given TabletAdded Blood (IFA) (di bimbing Oleh Veni Hadju dan Andi wardihanSinrang)
Chieving optimal maternal health during the period duringpregnancy is influenced by several factors: Access to health services,maternal nutritional status during pregnancy, success of KIA / KB program,environmental, social and cultural clients related to maternal and infanthealth during pregnancy and childbirth and family economic capacity.
This research type is quasi experiment with pre test post-test withcontrol group. Sample in this research 40 KEK pregnant women dividedinto 2 groups, mothers who get extra food biscuit and tablets added blood(Group Intervesi), mother who get tablet IFA (Group Control). Thetreatment was carried out for 12 weeks, the data analysis using theWilcoxon test and the independent T test.
The results of the research showed that there was an effect ofadditional food biscuits on nutritional status and 8-OHdG levels after theimplementation with p <0.05 (0.001). After the treatment obtained theaverage on nutritional status increased and decreased at 8-OHdG. Theresults showed that the group of supplementary food biscuits + IFA tabletswere more active in improving nutritional status and decreasing the levelsof 8-OHdG compared to those given only blood-added tablets (IFA).
Provision of extra food biscuits can improve nutritional status inpregnant women KEK especially foods that contain lots of vitamins andfolic acid to prevent DNA damage.
Keywords: Supplementary food biscuits, KEK pregnant women, Nutritionalstatus, 8-Hydroxy-2'deoxyGuanosin.
Kata Pengantar
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat,
rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan tesis ini dapat
selesai tepat waktunya. Penulisan tesis yang berjudul “Pengaruh
pemberian biskuit makanan tambahan terhadap status gizi dan 8-hydroxy-
2’-deoxyguanosin (8-OHdG) pada ibu hamil KEK yang diberikan tablet
tambah darah”, ini merupakan bagian dari rangkaian persyaratan dalam
rangka penyelesaian program pendidikan Megister Kebidanan Program
Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
Pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan banyak
terima kasih kepada bapak Prof.dr. Veni Hadju, Ph.D.,M.Sc sebagai
pembimbing I dan bapak Prof.Dr.dr. Andi Wardihan Sinrang, M.S sebagai
pembimbing II atas bantuan, bimbingan dan petunjuk serta arahan yang
diberikan selama penulisan tesis ini.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan
kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor
Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,MS, selaku Direktur Program Pasca
Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. dr. Suryani As’ad, M.Sc, selaku Plt. Ketua Program Studi
Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Prof.dr. Nasrum Massi, PhD, bapak DR.dr. Ilham Jaya Patellongi,
M.Kes dan Ibu DR.Werna Nontji, S.Kp, M.Kes selaku penguji yang
menyempatkan diri untuk hadir dalam seminar proposal ini.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pare Pare beserta jajarannya yang
telah memberikan izin dalam pengambilan data awal.
6. Para Dosen dan Staf pengelola Program Studi Megister Kebidanan
yang telah tulus memberikan ilmu dan membantu penulis selama
mengikuti proses pendidikan.
7. Teristimewa untuk ibu dan semua saudaraku tercinta atas motivasi
dan doanya demi keberhasilan penulis.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
yang telah membantu selama penyusunan proposal ini.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan
sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat
membangun. Semoga apapun yang kita lakukan senantiasa mendapat
ridho Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.
Makassar, Agustus 2017
Penulis
Raehan
Daftar IsiTESIS .................................................................................................................................. i
ABSTRAK........................................................................................................................viii
ABSTRACK .......................................................................................................................ix
Kata Pengantar................................................................................................................. x
Daftar Isi ............................................................................................................................xi
Daftar Tabel......................................................................................................................xii
Daftar Istilah ....................................................................................................................xiii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
A. Rumusan Masalah ................................................................................................. 5
B. Tujuan Penelitian ................................................................................................... 5
C. Manfaat penelitian ................................................................................................ 6
D. Batasan Penelitian ................................................................................................. 7
E. Sistematika penelitian ........................................................................................... 7
BAB II Tinjauan Pustaka ................................................................................................. 8
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan .................................................................. 8
B. Tinjauan Tentang Ibu Hamil Dengan Kurang Energi Kronis ......................... 16
C. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi ................................................................ 23
D. Tinjauan Tentang 8-OHdG (Radikal Bebas, Stress Oksidatif dan KerusakanDNA) ...................................................................................................................... 32
E. Tinjauan Tentang Antioksidan ........................................................................... 50
F. Tinjauan Tentang Biskuit Makanan Tambahan (MT) .................................... 61
G. Tinjauan Tentang Tablet Tambah Darah (Fe) ................................................. 64
H. Studi Intervensi Pemberian Mikro Nutrien Pada Ibu Hamil ........................... 78
I. Kerangka Teori ..................................................................................................... 81
J. Kerangka Konsep ................................................................................................ 82
K. Hipotesis................................................................................................................ 82
L. Definisi operasional ............................................................................................. 82
BAB III METODE PENELITIAN.................................................................................... 85
A. Rancangan Penelitian ......................................................................................... 85
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................................................. 85
C. Populasi dan Sampel........................................................................................... 85
D. Tehnik Pengambilan Sampel ............................................................................. 86
E. Instrumen Pengumpulan Data ........................................................................... 88
1. Alat.................................................................................................................... 88
2. Bahan ............................................................................................................... 88
3. Instrumen......................................................................................................... 88
4. Prosedur Pengumpulan Data ....................................................................... 89
5. Prosedur Kerja ................................................................................................ 90
F. Alur penelitian ....................................................................................................... 93
G. Analisa Data.......................................................................................................... 94
H. Etika Penelitian..................................................................................................... 95
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.......................................................................... 98
A. Hasil Penelitian..................................................................................................... 98
B. Pembahasan Penelitian .................................................................................... 102
C. Keterbatasan Peneliti ........................................................................................ 113
BAB V PENUTUP......................................................................................................... 114
A. Kesimpulan ......................................................................................................... 114
B. Saran.................................................................................................................... 115
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................... 116
Daftar Tabel
Nomor Halaman
Tabel 2.1. Enzim-enzim antioksidan dan Fungsinya 61
Tabel 2.2. Kandungan Gizi Biskuit Makanan Tambahan 67
Tabel 2.3. Senyawa Yang Mempengaruhi Absorpsi Besi 76
Table 2.4. Penelitian intervensi yang pernah dilakukan 98
Table 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 98
Table 4.2 Hasil analisis perubahan frekuensi Status Gizi 99
Table 4.2 Hasil analisis perubahan frekuensi Kadar 8-OHdG 100
Daftar Istilah
8-OHdG : 8-hidroxy-2’-deoxyguanosin
COCs : Cumulus Oophorus Cells
DNA : Deoxyribonucleic Acid
ELISA : Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
G:C : Guanine:Cytocine
IFA : Tablet tambah darah + ferosus sulfate & folic acid
RNA : Ribonucleic Acid
ROS : Reactive Oxygen Species
T:A : Tymin:Adenine
UV : Ultra Violet
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat
kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Ketiga hal ini
dipengaruhi oleh keadaan gizi, (Depkes, 2014)
Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Masalah gizi terjadi
di setiap siklus kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan (janin), bayi,
anak, dewasa dan usia lanjut. Gambaran status gizi balita diawali dengan
banyaknya bayi berat lahir rendah (BBLR) sebagai cerminan tingginya
masalah gizi dan kesehatan ibu hamil. Sekitar 30 juta wanita usia subur
menderita kurang energi kronis (KEK), yang bila hamil dapat
meningkatkan risiko melahirkan BBLR.
Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta
perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh
kelompok umur. Gizi yang baik membuat berat badan normal atau sehat,
tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat
serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini. (Depkes, 2014)
Umumnya proses kehamilan akan berlangsung normal sejak
terjadi pembuahan atau konsepsi, sampai hasil konsepsi ini siap untuk
2
dilahirkan. Tetapi pada perjalanannya hasil konsepsi itu sampai siap untuk
dilahirkan sering disertai komplikasi-komplikasi yang bila tidak diatasi
dapat membahayakan kehidupan baik bagi wanita hamil maupun janin
yang dikandungnya (Wiknkjosatro, 2007). Ternyata komplikasi-komplikasi
yang terjadi dalam kehamilan banyak dihubungkan dengan adanya
peningkatan oxidative stress pada wanita hamil (Wagey, 2011).
Pada kehamilan metabolisme akan meningkat sehingga meme
rlukan oksigen lebih banyak, maka semakin meningkat pula radikal bebas
yang ditimbulkan. Selain itu kadar oksidatif juga meningkat dan oksidan
menurun pada saat hamil. Apabila antioksidan tidak dapat mengibangi
radikal bebas tersebut maka dapat terjadi stress oksidatif. Dengan adanya
stress oksidatif akan memicu terjadinya kerusakan DNA, (Anang S, 2014)
Penyebab kerusakan DNA pada ibu hamil dipengaruhi oleh
rendahnya antioksidan dalam tubuh, kurangnya kadar zat gizi mikro (besi,
asam folat dan seng ) dan dipengaruhi dari perubahan kondisi patologi
tubuh ibu hamil itu sendiri, sehingga terjadi peningkatan radikal bebas
yang ditandai dengan peningkatan kadar 8-hydroxy-2’-deoxyguanosin (8-
OHdG), (Hasan Syah, 2012).
Dalam proses pembentukan DNA berkaitan dengan kadar asam
folat. Asam folat adalah salah satu vitamin, termasuk dalam kelompok
vitamin B, merupakan salah satu unsur penting dalam sintesis DNA
(Tangkilisan, 2002). Proses terjadinya kerusakan DNA tidak terlepas dari
peran asam folat dalam sintesi DNA. Jika asam folat berkurang sintesis
3
DNA terganggu dan kemungkinan menyebabkan terjadinya kerusakan
DNA, sehingga perlu dilakukan pemberian gizi makro yang mengandung
antioksidan seperti vit. A, C, E asam folat serta mineral besi, seng,
selenium dan tembaga yang diharapkan dapat meningkatkan antioksidan
serta mencegah kerusakan DNA oksidatif.
Ketika kehamilan rentan terhadap stres oksidatif maka diperlukan
antioksidan tambahan, sehingga diperlukan suplemen yang mengandung
antioksidan, terutama bagi golongan yang rentan, seperti anak,ibu hamil
atau menyusui dan lanjut usia (Nadimin, 2016).
Program pemberian Biskuit makanan tambahan (PMT) kepada ibu
hamil diharapkan dapat meningkatkan antioksidan sekaligus untuk
membantu memperbaiki status gizi ibu hamil dan anak yang dilahirkan,
(arfiyanti, 2013). Adapun kandungan Biskuit makanan tambahan (MT) ibu
hamil diperkaya dengan vitamin dan mineral yaitu, protein, Vitamin A,
B1, B2, B3, B6, B12, D, E, karbohidrat, natrium, asam folat, asam
pantoteat, selenium, flour, yodium, seng, zat besi, fosfor, kalsium,
(Menkes, 2009).
Penelitian yang dilakukan oleh Anang, pada tahun 2012-214
dengan memberikan gizi mikro pada periode prakonsepsi terhadap
pencegahan kerusakan DNA ibu, terdapat penurunan kadar 8-OHdG lebih
rendah pada kelmpok yang mendapatkan kapsul zat besi (60 mg)+asam
folat (400 µg) dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan Vitamin
4
A, C, mineral besi, tembaga dan seng. Hasil penelitian tersebut sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan Syah pada tahun 2012
tentang status zat gizi mikro (Besi, asam folat dan seng) dan kerusakan
DNA pada ibu hamil anemia, terdapat hubungan yang bermakna antara
status asam folat dan kerusakan DNA pada ibu hamil trimester pertama,
sedangkan pada status besi dang seng tidak terdapat hubungan yang
bermakna.
Survei yang dilakukan oleh Southeast Asian Food and Agricultural
Science Technology (Seafest) pada tahun 2011 menemukan sekitar
57,6% ibu hamil di Indonesia mengalami defisiensi protein dan zat gizi
mikro (mikronutrien). Dari segi asupan energi, rata-rata hanya 1400 kkal
dari 1800-1900 kk per hari yang dianjurkan ditambah 300 kkal bagi ibu
hamil. Mikronutrien kendati dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit,
mikronutrien memiliki peran yang sangat penting sama halnya dengan
makronutrien.
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas)
sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Hasil Riskesdas 2013
mendapatkan proporsi ibu hamil umur 15-49 tahun dengan lila <23,5 cm
atau berisiko KEK di Indonesia sebesar 24,2%. Angka ini masih cukup
tinggi jika dibandingkan dengan negara–negara tetangga di Kawasan
ASEAN. (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI, 2015).
5
Berdasarkan data dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013 jumlah kematian ibu yang dilaporkan menjadi 115 orang
atau 78.38 per 100.000 kelahiran hidup.
Data jumlah kematian ibu di Kota Pare-pare sebanyak 7 orang dari
1165 jumlah kelahiran hidup tahun 2013 sedangkan laporan ibu hamil
dengan risiko kurang energi kronis sebanyak 177 dari total ibu hamill 1559
tahun 2015. (Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare, 2015)
Berdasarkan uraian dan data yang ada diatas sehingga peneliti
tertarik melakukan penelitian untuk melihat pengaruh pemberian Biskuit
makanan tambahan (MT) dan tablet tambah darah (IFA) terhadap status
gizi dan kadar 8-hydroxy-2’-deoxyguanosin (8-OHdG), pada ibu hamil
KEK”
A. Rumusan Masalah
Rumusan Masakah dalam penelitian ini adalah “apakah ada
pengaruh pemberian biskuit makanan tambahan terhadap status gizi dan
kadar 8-hydroxy-2’-deoxyguanosin (8-OHdG) pada ibu hamil KEK yang
diberikan tablet tambah darah (IFA)”
B. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Diketahuinya pengaruh pemberian biskuit makanan tambahan
terhadap status gizi dan kadar 8-hydroxy-2’-deoxyguanosin (8-OHdG)
pada ibu hamil KEK yang diberikan tablet tambah darah (IFA).
6
2. Tujuan Khusus
a. Diketahuinya perubahan status gizi pada ibu hamil KEK setelah
pemberian biskuit makanan tambahan selama 12 minggu.
b. Diketahuinya perubahan status gizi pada ibu hamil KEK yang tidak
diberikan biskuit makanan tambahan selama 12 minggu.
c. Diketahuinya besar perubahan status gizi antara 2 kelompok yang
diberikan biscuit makanan tambahan dan yang tidak diberikan
biskuit makanan tambahan selama 12 minggu.
d. Diketahuinya perubahan kadar 8-OHdG pada ibu hamil KEK
setelah pemberian biskuit makanan tambahan selama 12 minggu.
e. Diketahuinya perubahan kadar 8-OHdG pada ibu hamil KEK yang
tidak diberikan biskuit makanan tambahan selama 12 minggu.
f. Diketahuinya besar perubahan kadar 8-OHdG antara 2 kelompok
yang diberikan biscuit makanan tambahan dan yang tidak
diberikan biskuit makanan tambahan selama 12 minggu.
C. Manfaat penelitian
1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
masukan ataupun referensi dalam perbaikan status gizi dan
kesehatan pada ibu hamil untuk pencegahan terhadap kerusakan
DNA.
2. Sebagai bahan Informasi untuk Instansi terkait dan masyarakat umum
terhadap pencegahan kerusakan DNA khususnya pada ibu hamil
7
3. Dapat menjadi salah satu alternatif sumber pengobatan untuk
perbaikan status kesehatan pada ibu hamil dalam hal ini perbaikan
terhadap kerusakan DNA.
D. Batasan Penelitian
Lingkup pembahasan penelitian ini dititik beratkan pada
pengukuran status gizi dan kadar 8-hydroxy-2’-deoxyguanosin (8-OHdG)
sebelum dan sesudah diberikan biskuit makanan tambahan (MT) dan
tablet tambah darah pada ibu hamil KEK.
E. Sistematika penelitian
Secara garis besar pembahasan pada proposal penelitian ini
terbagi dalam beberapa bagian, antara lain:
Bab I: Pendahuluan, menguraikan latar belakang; rumusan masalah;
tujuan penelitian; manfaat penelitian; lingkup penelitian dan
sistematika penelitian.
Bab II: Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan tentang kehamilan,
tinjauan tentang kehamilan dengan keurangan energy kronis,
tinjauan tentang status gizi, tinjauan tentang kadar 8-hydroxy-2’-
deoxyguanosin (8-OHdG), dan tinjauan tentang Biskuit makanan
tambahan (MT), tinjauan tentang tablet tambha darah
Bab III: Metode Penelitian, dikemukakan mengenai jenis penelitian; lokasi
dan waktu penelitian; populasi dan sampel; jenis dan sumber
data; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data
8
BAB II
Tinjauan Pustaka
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan
1. Perubahan Fisiologi pada ibu hamil
Pada masa kehamilan ada beberapa perubahan pada hampir
semua sistem organ pada maternal. Perubahan ini diawali dengan
adanya sekresi hormon dari korpus luteum dan plasenta.
Perubahan yang relevan meliputi perubahan fungsi hematologi,
kardiovaskular, ventilasi, metabolik, dan gastrointestinal
(Santos,et.al., 2006).
a. Perubahan Metabolik
Sebagai akibat dari peningkatan sekresi dari berbagai
macam hormon selama masa kehamilan, termasuk tiroksin,
adrenokortikal dan hormon seks, maka laju metabolisme basal
pada wanita hamil meningkat sekitar 15 % selama mendekati
masa akhir dari kehamilan. Sebagai hasil dari peningkatan laju
metabolisme basal tersebut, maka wanita hamil sering
mengalami sensasi rasa panas yang berlebihan. Selain itu,
karena adanya beban tambahan, maka pengeluaran energi
untuk aktivitas otot lebih besar daripada normal (Guyton, 2006).
9
b. Perubahan Kardiovaskular
Sistem kardiovaskular beradaptasi selama masa kehamilan
terhadapa beberapa perubahan yang terjadi. Meskipun
perubahan sistem kardiovaskular terlihat pada awal trimester
pertama, perubahan pada sistem kardiovaskular berlanjut ke
trimester kedua dan ketiga, ketika cardiac output meningkat
kurang lebih sebanyak 40 % daripada pada wanita yang tidak
hamil. Cardiac output meningkat dari minggu kelima kehamilan
dan mencapai tingkat maksimum sekitar minggu ke-32
kehamilan, setelah itu hanya mengalami sedikit peningkatan
sampai masa persalinan, kelahiran, dan masa post partum.
c. Perubahan Hematologi.
Volume darah maternal mulai meningkat pada awal masa
kehamilan sebagai akibat dari perubahan osmoregulasi dan
sistem renin-angiotensin, menyebabkan terjadinya retensi
sodium dan peningkatan dari total body water menjadi 8,5 L.
Bagaimanapun, transpor oksigen tidak terganggu oleh anemia
relatif ini, karena tubuh sang ibu memberikan kompensasi
dengan cara meningkatkan curah jantung, peningkatan PaO2,
dan pergeseran ke kanan dari kurva disosiasi oxyhemoglobin
(Birnbach,et.al., 2009).
10
d. Perubahan Sistem Respirasi
Adaptasi respirasi selama kehamilan dirancang untuk
mengoptimalkan oksigenasi ibu dan janin, serta memfasilitasi
perpindahan produk sisa CO2 dari janin ke ibu (Norwitz,et.al.,
2008). Konsumsi oksigen dan ventilasi semenit meningkat
secara progresif selam masa kehamilan. Volume tidal dan
dalam angka yang lebih kecil, laju pernafasan meningkat.
e. Perubahan Sistem Renal
Vasodilatasi renal mengakibatkan peningkatan aliran darah
renal pada awal masa kehamilan tetapi autoregulasi tetap
terjaga. Ginjal umumnya membesar. Peningkatan dari renin dan
aldosterone mengakibatkan terjadinya retensi sodium. Aliran
plasma renal dan laju filtrasi glomerulus meningkat sebanyak
50% selama trimester pertama dan laju filtrasi glomerulus
menurun menuju ke batas normal pada trimester ketiga.
f. Perubahan pada Sistem Gastrointestinal
Peningkatan kadar progestron menurunkan tonus dari
sfingter gastroesofagus, dimana sekresi gastrin dari plasenta
menyebabkan hipersekresi asam lambung.
g. Perubahan Sistem Saraf Pusat dan Perifer
Konsentrasi alveolar minimum menurun secara progresif
selama masa kehamilan. Pada masa aterm menurun sekitar
11
40% untuk semua anestesi general. Namun, konsentrasi
alveolar minimum kembali normal pada hari ketiga pasca
kelahiran.
h. Perubahan Sistem Muskoloskeletal
Kenaikan kadar relaksin selama masa kehamilan membantu
persiapan kelahiran dengan melemaskan serviks, menghambat
kontraksi uterus, dan relaksasi dari simfisis pubis dan sendi
pelvik.
i. Sirkulasi Uteroplasental
Aliran darah uterin meningkat secara progresif selama
kehamilan dan mencapai nilai rata rata antara 500ml sampai
700ml di masa aterm. Aliran darah melalui pembuluh darah
uterus sangat tinggi dan memiliki resistensi rendah.
2. Perubahan Biokimia tubuh pada Ibu hamil
a. Keseimbangan cairan dan elektrolit
Kondisi cairan dan elektrolit pada kehamilan mengalami
perubahan yang cukup bermakna. Perubahan fisiologi ditandai
dengan : Penambahan berat badan, Hemodilution, Penurunan
osmolalitas plasma, Penurunan konsentrasi sodium.
Adapun penyebab perubahan keseimbangan cairan dan
elektrolit : Peningkatan volume cairan , Redistribusi cairan
antara ICF dan ECF, Retensi sodium oleh ginjal (~900 mmol),
12
Peningkatan Total Body Water (TBW) hingga 8.5 L,
Peningkatan volume plasma hingga 1.2 L
b. Keseimbangan asam basa
1) Hiperventilasi menyebabkan penurunan penurunan PaCO2
(dari ~ 39 mm Hg 31 mm Hg)
2) pH meningkat sedikit antara 7.42 – 7.44
3) HCO 3 menurun sekitar ~ ³ mmol/L
4) Alkalosis Respiratorik dengan kompesasi metabolik,
(Saryono, 2007)
c. Hormon
Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar
endokrin, yang masuk ke dalam peredaran darah untuk
mempengaruhi jaringan secara spesifik. Begitu dikeluakan,
hormon akan dialirkan oleh darah menuju berbagai jaringan sel
dan menimbulkan efek tertentu sesuai dengan fungsinya
masing-masing.
Hormon biokimia dalam kehamilan :
1) Hormon kehamilan HCG (Human Chorionic Gonadotrophin)
Hormon kehamilan ini dibuat oleh embrio segera
setelah pembuahan dan karena pertumbuhan jaringan
plasenta dan oleh villi choriales yang berdampak pada
13
meningkatnya produksi progesteron oleh indung telur
sehingga menekan menstruasi dan menjaga kehamilan.
2) Hormon Kehamilan HPL (Human Placental Lactogen)
Adalah hormon yang dihasilkan oleh plasenta,
merupakan hormon protein yang merangsang pertumbuhan
dan menyebabkan perubahan dalam metabolisme
karbohidrat dan lemak.
3) Hormon Kehamilan Relaxin
Hormon kehamilan yang dihasilkan oleh korpus
luteum dan plasenta..
4) Hormon Kehamilan Estrogen
Dihasilkan oleh ovarium dan mempengaruhi
pertumbuhan endometrium rahim, perubahan-perubahan
histologi pada vagina.
5) Hormon Kehamilan Progesteron
Hormon ini berfungsi untuk membangun lapisan di
dinding rahim untuk menyangga plasenta di dalam rahim.
Dampak hormon ini dapat "mengembangkan" pembuluh
darah sehingga menurunkan tekanan darah, itulah penyebab
sering pusing saat hamil. Hormon ini juga membuat sistem
pencernaan jadi lambat, perut menjadi kembung atau
sembelit. Hormon ini juga mempengaruhi perasaan dan
suasana hati ibu, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan
14
pernafasan, mual, dan menurunnya gairah berhubungan
intim selama hamil.
6) Hormon Kehamilan MSH (Melanocyte Stimulating Hormone)
Hormon kehamilan ini merangsang terjadinya
pigmentasi pada kulit..
d. Urine
Urine atau air kencing merupakan salah satu sisa
metabolisme tubuh yang dapat memberikan gambaran
keadaan kesehatan tubuh kita. Kandungan urin yang dapat
diketahui dengan pemeriksaan kimia antara lain:
1) Kepekatan : Kepekatan urin (disebut juga osmolalitas atau
specific gravity) dapat dihitung dengan berat jenisnya.
2) Keasaman : Urin bersifat asam jika pH-nya kurang dari 7,
bersifat basa jika pH-nya lebih dari 7. Urin yang bersifat
asam berkaitan dengan risiko penyakit asam urat dan batu
ginjal.
3) Protein : biasanya tidak ditemukan dalam urin. Demam,
olahraga keras, kehamilan, dan beberapa penyakit dapat
menyebabkan protein berada dalam urin.
4) Glukosa : adalah jenis gula yang ditemukan dalam darah.
Biasanya glukosa sangat sedikit atau tidak ada dalam urin..
Keberadaan glukosa dalam urin, yang disebut glukosuria,
15
juga dapat disebabkan oleh gangguan hormonal, penyakit
hati, obat-obatan, dan kehamilan.
5) Keton : Sejumlah besar keton dalam urin dapat menunjukkan
kondisi sangat serius yang disebut ketoasidosis diabetik.
6) Nitrit. : Bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih
(ISK) membuat enzim yang mengubah nitrat menjadi nitrit.
Nitrit dalam urin menunjukkan adanya infeksi saluran kemih
(ISK).
7) Esterase leukosit : adalah enzim yang ditemukan dalam sel-
sel darah putih. Kehadiran esterase leukosit di urin
merupakan pertanda peradangan, yang umumnya
disebabkan oleh infeksi saluran kemih.
e. Darah
Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk
hidup (kecuali tumbuhan) tingkat tinggi yang berfungsi
mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan
tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan
juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri.
Macam-macam sel darah ada 3, yaitu:
1) Sel darah merah : Sel darah merah (eritrosit) atau Red Blood
Cell adalah sel darah yang paling banyak dan fungsinya
untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh lewat darah.
16
2) Sel darah Putih : Sel darah putih (leukosit) atau White Blood
Cell adlah sel yang membentuk komponen darah. Leukosit
ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai
penyakit infeksi sebagai bagian dari system kekebalan
tubuh.
3) Keping darah : Keping darah adalah sel yang tidak
mempunyai nucleus pada DNA-nya dengan bentuk tidak
beraturan dan ukuran diameter 2-3 µm yang merupakan
fragmentasi dari megakariosit. Keping darah (trombosit)
tersirkulasi dalam darah dan terlibat dalam mekanisme
hemostatis tingkat sel dalam proses pembekuan
darah dengan membentuk darah beku..
B. Tinjauan Tentang Ibu Hamil Dengan Kurang Energi Kronis
1. Pengertian ibu hamil kurang energi kronis adalah ibu hamil
dengan hasil pemeriksaan antropometri, Lingkar Lengan Atas
(LILA) < 23,5 cm .
2. Penyebab
Secara umum, kurang gizi pada ibu hamil dikaitkan dengan
kemiskinan, ketidakadilan gender serta hambatan terhadap
akses terhadap berbagai kesempatan dan pendidikan. Kurang
gizi juga banyak dikaitkan dengan kurangnya akses terhadap
pelayanan kesehatan yang adekuat, tingginya fertilisasi dan
beban kerja yang tinggi.
17
Secara spesifik, penyebab kurang energi kronis (KEK)
adalah akibat dari ketidakseimbangan antara asupan untuk
pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Yang sering
terjadi adalah adanya ketidaktersediaan pangan secara
musiman atau secara kronis ditingkat rumah tangga yang tidak
proporsional (biasanya seorang ibu “mengorbankan” dirinya)
dan beratnya beban kerja ibu hamil. Selain itu beberapa hal
penting yang terkait dengan status gizi seorang ibu adalah
kehamilan pada usia muda (kurang dari 20 tahun), kehamilan
dengan jarak yang pendek dengan kehamilan sebelumnya
(kurang dari 2 tahun), kehamilan yang terlalu sering, serta
kehamilan pada usia terlalu tua (lebih dari 35 tahun).
3. Dampak masalah Kurang Energi Kronis
Konsekuensi Kurang Gizi pada Ibu terhadap kesehatan
Reproduksi. Status gizi wanita, terutama pada masa usia subur,
merupakan elemen pokok dari kesehatan reproduksi karena
keterkaitan ibu hamil dengan pertumbuhan dan perkembangan
janin yang dikandungnya, yang pada akhirnya berdampak
terhadap masa dewasanya. Memperbaiki status gizi ibu yang
sedang hamil dengan demikian merupakan suatu bagian yang
sangat penting walaupun bukan merupakan satu-satunya
intervensi yang harus dilakukan karena KEK dan stunting pada
wanita di negara berkembang merupakan hasil kumulatif dari
18
keadaan kurang gizi sejak janin, bayi dan kanak-kanak dan
yang berlanjut hingga masa dewasa.
Peran mikronutrien juga sangat penting terhadap kesehatan
reproduksi ibu, antara lain karena fungsinya di dalam system
imunitas yang berakibat terhadap mudahnya mengalami
berbagai penyakit infeksi.
a. Dampak terhadap kesehatan ibu
1) Kematian ibu usia reproduktif
2) Anemia
3) Komplikasi kehamilan, persalinan dan masa Nifas
b. Dampak terhadap kesehatan bayi, balita dan anak-anak
1) Asfiksia (kesulitan bernafas sebagai akibat kekurangan
oksigen O2 atau terlalu banyak karbondioksida CO2 di
dalam darah)
2) Bayi berat lahir rendah (BBLR) dan akan menyebabkan
anak tersebut dikemudian hari akan terkena malnutrisi
atau stunting sehingga menyebabkan meningkatnya risiko
gangguan kesehatan anak. Akibat dari kapasitas mental
anak menurun dan tampilan fisik yang buruk adalah
meningkatnya prevalensi infeksi pada dewasa yang
terinfeksi akan berdampak pada kehamilannya bahkan
risiko kematian ibu atau janin yang dilahirkan akan cacat.
(Nurmadinisia, 2012)
19
4. Kebutuhan nutrisi ibu hamil
a. Nutrisi
Kehamilan menyebabkan banyak perubahan pada tubuh
ibu. Perubahan-perubahan itu untuk menyesuaikan tubuh ibu
pada keadaan kehamilannya. Penggunaan zat-zat makanan
oleh tubuh menurun pada 4 bulan pertama kehamilan
sehingga kebutuhan tubuh akan makanan juga berkurang
pada beberapa bulan pertama kehamilan. Di samping itu,
perasaan malas dan kurang enak badan biasanya juga
menyebabkan ibu lebih banyak istrahat sehingga keperluan
akan makanan juga berkurang (Salmah, et al. 2006)
Status gizi ibu yang kurang baik sebelum dan selama
kehamilan merupakan penyebab utama dari berbagai
masalah kesehatan pada ibu dan bayi, yang berakibat
terjadinya bayi lahir dengan berat badan rendah, kelahiran
prematur serta kematian neonatal dan perinatal. Padahal,
usaha perbaikan status gizi ibu hamil telah banyak dilakukan
di berbagai negara (Sulistyawati, 2009).
Tabel 1. Asupan makanan harian yang dianjurkan National
Research Counsil Wanita Sebelum dan Selama Hamil dan
Menyusui (Cunningham, et al., 2006)
20
Berikut ini daftar asupan gizi yang harus dipenuhi oleh ibu
hamil.
1) Kalori
Kebutuhan kalori pada masa kehamilan memerlukan
tambahan 80.000 kkal, yang terakumulasi pada 20 minggu
terakhir. Kalori diperlukan untuk energi yang apabila asupan
kalori tidak adekuat, maka protein akan dimetabolisasi untuk
menghasilkan energi dan tidak digunakan untuk
pertumbuhan dan perkembangan janin (Cunningham, et al.,
2006).
21
2) Asam folat
Asam folat merupakan satu-satunya vitamin yang
kebutuhannya meningkat 2 kali lipat selama hamil. Asam
folat sangat berperan dalam metabolisme sel darah merah,
sistesis DNA, pertumbuhan sel dan pembentukan heme. Jika
kekurangan asam folat maka ibu dapat menderita anemia
megaloblastik dengan gejala diare, depresi, lelah berat, dan
selalu mengantuk. Jika kondisi ini terus berlanjut, dan tidak
segera ditangani maka pada ibu hamil akan terjadi BBLR,
ablosio plasenta, dan kelainan bentuk tulang belakang (spina
bifida) (Sulistyawati, 2009).
3) Protein
Asupan protein diperlukan untuk zat pembangun,
pembentukan darah, dan sel. Kebutuhan ibu hamil akan
protein sebanyak 68% atau menambah asupan proteinnya
menjadi 12% per hari atau 75-100 gram setiap harinya
(Sulistyawati, 2009).
4) Mineral
Hampir semua makanan yang menghasilkan cukup
kalori untuk menghasilkan pertambahan berat yang memadai
mengandung cukup mineral untuk mencegah defisiensi
apabila yang digunakan adalah garam yang beryodium.
22
5) Kalsium
Zat ini berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi..
Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya
susu, dan produk olahan lain seperti vitamin A, D, B2, B3, dan
C. Vitamin A sangat bermanfaat bagi mata, pertumbuhan
tulang, dan kulit.
6) Zat besi
Berfungsi dalam pembentukan darah, terutama untuk
membentuk sel darah merah hemoglobin, serta mengurangi
resiko ibu hamil terkena anemia. Kandungan zat besi sangat
dibutuhkan pada masa kehamilan memasuki usia 20 minggu
(Sulistyawati, 2009).
7) Selenium
Ini adalah komponen esensial pada enzim glutation
peroksidase, yang mengkatalisasi perubahan hidrogen
peroksida menjadi air. Selenium adalah komponen
pertahanan yang penting terhadap kerusakan akibat radikal
bebas (Cunningham, et al., 2006).
8) Vitamin A
Asupan harian vitamin A tampaknya memadai untuk
memenuhi kebutuhan sebagian besar wanita hamil. Karena
itu, suplementasi rutin selama kehamilan tidak dianjurkan.
Beberapa laporan kasus mengisyaratkan adanya keterkaitan
23
antara cacat lahir dan asupan vitamin A dosis tinggi (10.000-
50.000 IU) setiap hari selama kehamilan. Bet-carotene
prekursor vitamin A yang terdapat dalam buah dan sayuran
belum terbukti menimbulkan toksisitas vitamin A
(Cunningham, et al., 2006).
C. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi
1. Pengertian Status Gizi
Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh
seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan
penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh, (Almatsier, 2005).
Status gizi normal merupakan suatu ukuran status gizi dimana
terdapat keseimbangan antara jumlah energi yang masuk ke dalam
tubuh dan energi yang dikeluarkan dari luar tubuh sesuai dengan
kebutuhan individu. Energi yang masuk ke dalam tubuh dapat
berasal dari karbohidrat, protein, lemak dan zat gizi lainnya (Nix,
2005). Status gizi normal merupakan keadaan yang sangat
diinginkan oleh semua orang (Apriadji, 1986).
Status gizi kurang atauyang lebih sering disebut under nutrition
merupakan keadaan gizi seseorang dimana jumlah energi yang
masuk lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Hal ini dapat
terjadi karena jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari anjuran
kebutuhan individu (Khairina, 2009)
24
2. Penilaian Status Gizi
Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari
data yang diperoleh dengan menggunakan berbagaimacam cara
untuk menemukan suatu populasi atau individu yang memiliki risiko
status gizi kurang maupun gizi lebih (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).
Penilaian status gizi terdiri dari dua jenis, yaitu :
a. Penilaian Langsung
1) Antropometri
Antropometri merupakan salah satucara penilaian status gizi
yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan
dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya
antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh
seseorang (Supariasa, 2001). Metode antropometri sangat
berguna untuk melihat ketidakseimbangan energi dan
protein. Akan tetapi, antropometri tidak dapat digunakan
untuk mengidentifikasi zat-zat gizi yang spesifik (Gibson,
2005).
2) Klinis
Pemeriksaan klinis merupakan cara penilaian status gizi
berdasarkan perubahan yang terjadi yang berhubungan erat
dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi.
Pemeriksaan klinis dapat dilihat pada jaringan epitel yang
25
terdapat di mata, kulit, rambut, mukosa mulut, dan organ
yang dekat dengan permukaan tubuh (kelenjar tiroid)
(Hartriyanti dan Triyanti, 2007).
3) Biokimia
Pemeriksaan biokimia disebut juga cara laboratorium.
Pemeriksaan biokimia pemeriksaan yang digunakan untuk
mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih
parah lagi, dimana dilakukan pemeriksaan dalam suatu
bahan biopsi sehingga dapat diketahui kadar zat gizi atau
adanya simpanan di jaringan yang paling sensitif terhadap
deplesi, uji ini disebut uji biokimia statis. Cara lain adalah
dengan menggunakan uji gangguan fungsional yang
berfungsi untuk mengukur besarnya konsekuensi fungsional
dari suatu zat gizi yang spesifik Untuk pemeriksaan biokimia
sebaiknya digunakan perpaduan antara uji biokimiastatis dan
uji gangguan fungsional (Baliwati, 2004).
4) Biofisik
Pemeriksaan biofisik merupakan salah satu penilaian status
gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat
perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam
keadaan tertentu, seperti kejadian buta senja (Supariasa,
2001).
26
3. Indeks Antropometri
Indeks antropometri adalah pengukuran dari beberapa
parameter. Indeks antropometri bisa merupakan rasio dari satu
pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang
dihubungkan dengan umur dan tingkat gizi. Salah satu contoh dari
indeks antropometri adalah Indeks Massa Tubuh (IMT) atau yang
disebut dengan Body Mass Index (Supariasa, 2001). IMT
merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi orang
dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan
kelebihan berat badan, maka mempertahankan berat badan normal
memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup
yang lebih panjang. IMT hanya dapat digunakan untuk orang
dewasa yang berumur diatas 18 tahun. Dua parameter yang
berkaitan dengan pengukuran Indeks Massa Tubuh, terdiri dari :
a. Berat Badan
Berat badan merupakan salah satu parameter massa tubuh yang
paling sering digunakan yang dapat mencerminkan jumlah dari
beberapa zat gizi seperti protein, lemak, air dan mineral. Untuk
mengukur Indeks Massa Tubuh, berat badan dihubungkan
dengan tinggi badan (Gibson, 2005).
27
b. Tinggi Badan
Tinggi badan merupakan parameter ukuran panjang dan dapat
merefleksikan pertumbuhan skeletal (tulang) (Hartriyanti dan
Triyanti, 2007).
c. Cara Mengukur Indeks Massa Tubuh
Indeks Massa Tubuh diukur dengan cara membagi berat badan
dalam satuan kilogram dengan tinggi badan dalam satuan meter
kuadrat (Gibson, 2005).
4. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi
a. Umur
Kebutuhan energi individu disesuaikan dengan umur, jenis
kelamin, dan tingkat aktivitas. Jika kebutuhan energi (zat
tenaga) terpenuhi dengan baik maka dapat meningkatkan
produktivitas kerja, sehingga membuat seseorang lebih
semangat dalam melakukan pekerjaan. Semakin bertambahnya
umur akan semakin meningkat pula kebutuhan zat tenaga bagi
tubuh. Zat tenaga dibutuhkan untuk mendukung meningkatnya
dan semakin beragamnya kegiatan fisik (Apriadji, 1986).
Berat Badan (Kg)IMT =
Tinggi Badan (m) X Tinggi Badan (m)
28
b. Frekuensi Makan
Frekuensi konsumsi makanan dapat menggambarkan berapa
banyak makanan yang dikonsumsi seseorang. Menurut Hui
(1985).
c. Asupan Energi
Energi merupakan asupan utama yang sangant diperlukan oleh
tubuh. Kebutuhan energi yang tidak tercukupi dapat
menyebabkan protein, vitamin, dan mineral tidak dapat
digunakan secara efektif. Untuk beberapa fungsi metabolisme
tubuh, kebutuhan energi dipengaruhi oleh BMR (Basal
Metabolic Rate), kecepatan pertumbuhan, komposisi tubuh dan
aktivitas fisik (Krummel & Etherton, 1996).
d. Asupan Protein
Protein merupakan zat gizi yang paling banyak terdapat dalam
tubuh. Fungsi utama protein adalah membangun serta
memelihara sel-sel dan jaringan tubuh (Almatsier, 2001).
Fungsi lain dari protein adalah menyediakan asam amino yang
diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan
metabolisme, mengatur keseimbangan air, dan
mempertahankan kenetralan asam basa tubuh.
29
e. Asupan Karbohidrat
Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi kehidupan
manusia yang dapat diperoleh dari alam, sehingga harganya
pun relatif murah (Djunaedi, 2001).
f. Asupan Lemak
Lemak merupakan cadangan energi didalam tubuh. Lemak
terdiri dari trigliserida, fosfolipid, dan sterol, dimanaketiga jenis
ini memiliki fungsi terhadap kesehataan tubuh manusia
(WKNPG, 2004).
g. Tingkat Pendidikan
Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan pengetahuan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka sangat
diharapkan semakin tinggi pula pengetahuan orang tersebut
mengenai gizi dan kesehatan. Adanya pola makan yang baik
dapat mengurangi bahkan mencegah dari timbulnya masalah
yang tidak diinginkan mengenai gizi dan kesehatan (Apriadji,
1986).
h. Pendapatan
Pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi
status gizi. Apabila makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi
jumlah zat-zat gizi dibutuhkan oleh tubuh, maka dapat
mengakibatkan perubahan pada status gizi seseorang (Apriadji,
1986).
30
i. Pengetahuan
Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi tingkat
pengetahuannya akan gizi. Zat gizi yang cukup dapat dipenuhi
oleh seseorang sesuai dengan makanan yang dikonsumsi yang
diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan. Pengetahuan gizi
dapat memberikan perbaikan gizi pada individu maupun
masyarakat (Suhardjo, 1986).
5. Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan
Angka kecukupan gizi yang dianjurkan merupakan suatu
ukuran keckupan rata-rata zat gizi setiap hari untuk semua orang
yang disesuiakan dengan golongan umur, jenis kelamin, ukuran
tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai tingkat kesehatan yang
optimal dan mencegah terjadinyadefisiensi zat gizi (Depkes, 2005).
6. Masalah Gizi Kurang
Gizi kurang merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat
tidak terpenuhinya asupan makanan (Sampoerno, 1992). Gizi
kurang dapat terjadi karena seseorang mengalami kekurangan
salah satuzat gizi atau lebih di dalam tubuh (Almatsier, 2001).
7. Metode Pengukuran Konsumsi Makanan
Metode pengukuran konsumsi makanan digunakan untuk
mendapatkan data konsumsi makanan tingkat individu. Ada
beberapa metode pengukuran konsumsi makanan, yaitu sebagai
berikut :
31
a. Recall24 jam (24 Hour Recall) : Metode ini dilakukan dengan
mencatat jenis dan jumlah makanan serta minuman yang telah
dikonsumsi dalam 24 jam yang lalu. Recall dilakukan pada saat
wawancara dilakukan dan mundur ke belakang sampai 24 jam
penuh. Wawancara menggunakan formulir recall harus
dilakukan oleh petugas yang telah terlatih. Data yang
didapatkan dari hasil recall lebih bersifat kualitatif. (Supariasa,
2001).
b. Food Record : Merupakan catatan responden mengenai jenis
dan jumlah makanan dan minuman dalam satu periodewaktu,
biasanya 1 sampai 7 hari dan dapat dikuantifikasikan
denganestimasi menggunakan ukuran rumah tangga
(estimated food record) atau menimbang (weighed food record),
(Hartriyanti dan Triyanti, 2007).
c. Food Frequency Questionnaire (FFQ) : Merupakan metode
pengukuran konsumsi makanan dengan menggunakan
kuesioner untuk memperoleh data mengenai frekuensi
seseorang dalam mengonsumi makanan dan minuman.
Frekuensi konsumsi dapat dilakukan selama periode tertentu,
misalnya harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.
Kuesioner terdiri dari daftar jenis makanan dan minuman
(Supariasa, 2001).
32
D. Tinjauan Tentang 8-OHdG (Radikal Bebas, Stress Oksidatif dan
Kerusakan DNA)
1. Radikal Bebas
Radikal bebas adalah atom/ gugusan atom yang kulit
luarnya memiliki electron yang tidak berpasangan, sedangkan
oksidan adalah suatu senyawa yang dapat menerima ekeltron.
Pada keadaan normal reduksi O2 menjadi H2O dalam
rantai pernafasan yang dikatalisasi oleh sitokrom oksidase
membutuhkan empat buah electron namun pada konsumsi
oksigen tersebut juga bisa terjadi proses lain, yaitu hanya
sebuah eletron yang diambil sehingga terbentuk spesies
oksigen reaktif (ROS) yang toksis dimana penerimaan electron
pertama akan terbentuk redikal superoksida (O2), selanjutnya
dengan penerimaan electron kedua terbentuk hidroksi
peroksida (H2O2), dan selanjutnya pada penerimaan electron
yang ketiga terbentuk radikal hidroksil (OH). (Winarsi, 2007).
Secara fisiologis tubuh memang menghasilkan ROS
(radikal bebas atau oksidan), adapun sumber penghasil ROS
antara lain mitokondria, fagosit, Xantin oxidase, peroksisome,
iskemi/reper fusi, jalur pada pembetukan asam arakhidonat,
dan sebagainya. Bahan tersebut dihasilkan oleh tubuh untuk
membunuh bakteri yang masuk dalam tubuh. tubuh mempunyai
33
kemampuan untuk menjaga kadar ROS. (Tremelle K, 2008;
Agarwal, 2005; Lopes S, 1998). (Keman, 2014)
Namun bila radikal bebas atau oksidan dihasilkan oleh
tubuh secara berlebihan, maka bahan tersebut akan
dinetralisasi oleh anti radikal bebas atau antioksidan. Yang
dikenal dengan Scavenger enzyme, seperti superoksida
dismutase (SOD), katalese atau glutation peroksida. Apabila
rasio antara radikal bebas atau oksidan lebih besar dari pada
antiradikal bebas atau antioksidan, maka keadaan ini dikenal
sebagai stress oksidatif. (Winarsi, 2007)
Ada 2 jenis utama spesies radikal bebas (Agarwal, et al.,
2005) :
a. Reactive Nitrogen Species (RNS)
Nitric Oxide (NO) disinteisis selama konversi enzim L-
arginin ke L-Citrulline oleh nitric oxide synthase (NOS).
Dengan elektron tidak berpasangan, NO yang sangat
reaktif terhadap radikal bebas, kerusakan protein,
karbohidrat, nukleotida, lipid dan bersama-sama dengan
mediator inflamasi lainnya mengakibatkan kerusakan sel
dan jaringan, kurang kuat, menghambat agregasi platelet
dan adhesi (Agrawal, et al., 2005)
b. Reactive Oxygen Species (ROS)
Pada dasarnya dikenal 3 tipe utama ROS, yaitu
34
superoksida (O2•-), hidrogen peroksida (H2O2), hidroksil
(OH•). Radikal superoksida terbentuk bila terjadi
kehilangan elektron saat proses rantai transpor
elektron. Dismutasi superoksida menghasilkan pembentukan
hidrogen peroksida. Ion hidroksil bersifat sangat reaktif
bereaksi dan dapat memodifikasi purin dan pirimidin
menyebabkan penghancuran untaian rantai DNA putus dan
berakhir dengan kerusakan DNA. Beberapa enzim oksidase
dapat langsung menghasilkan hidrogen peroksidasi radikal
(Agarwal, et al., 2005; Wagey, 2011).
ROS dapat memicu lebih dari 100 macam penyakit
dan berpengaruh dalam patofisiologi reproduksi wanita,
mencakup ovari, tuba falopi, dan embrio. ROS juga
berpengaruh terhadap modulasi lanjut fungsi fisiologi
reproduksi seperti maturasi oosit, steroidogenesis ovari,
fungsi luteal corpus, dan luteolisis. ROS dapat terjadi
melalui beberapa mekanisme yang berbeda, seperti:
reperfusi-iskemia, aktivasi neutrofil dan makrofag, kimia
Fenton, endothelial cell xanthine oxidase metabolisme asam
lemak bebas dan prostaglandin, dan hipoksia seperti
ditunjukkan dalam Gambar 1. (Hiromichi, et al. 2008 cit
Wagey, F., 2011).
35
Gambar 2.2. Mekanisme terjadinya ROS
Pada kondisi tubuh sehat, ROS (reactive oxygen
species) dan antioksidan berada dalam keseimbangan.
Apabila keseimbangan ini terganggu dan bergeser dengan
peningkatan ROS maka terjadi stress oksidatif (SO). SO
berpengaruh dalam semua tahapan reproduksi seorang
ibu bahkan setelah menopouse. SO terjadi akibat
ketidakseimbangan antara prooksidan (free radical
species) dan kemampuan skavanger tubuh (body's
scavenging ability) atau antioksidan. ROS ibarat pisau
bermata dua berperan sebagai molekul pemberi sinyal
pada proses fisiologi, disamping itu juga dapat berperan
dalam proses patologi termasuk proses reproduksi wanita.
ROS mempengaruhi multi proses fisiologi dari maturasi
oosit sampai fertilisasi, pertumbuhan embrio dan
kehamilan (Agarwal, et al., 2005). SO berperan dalam
36
memodulasi penurunan fertilitas yang juga berhubungan
dengan usia. SO juga sangat berpengaruh selama
kehamilan, persalinan normal, dan inisiasi preterm
persalinan. Kanker ovari terjadi pada permukaan epitel dan
sebagai pemicunya adalah ovulasi yang berulang-ulang.
Ovulasi menginduksi kerusakan DNA epitel ovari. Hal ini
dapat dicegah dengan cara pemberian antioksidan (Wagey,
2011).
Radikal hidroksil merupakan salah satu ROS yang
sangat agresif. Diproduksi di mitokondria dan bertanggung
jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada mitokondria
bukan terhadap nukleus. Mitokondria DNA merupakan
target utama radikal oksigen oleh karena lokasinya yang
dekat dengan mitokondria membran inti tempat oksidan
terbentuk dan aktifitas perbaikan DNA berkurang
(Darmayasa, 2013).
Radikal hidroksil sangatlah reaktif dan inilah yang
menyebabkan mereka mempunyai jangka waktu hidup
sangat pendek sehingga tidak bisa dinilai secara langsung,
tetapi oksidasi produk DNA atau turunannya dapat
dideteksi di urin, serum, saliva (Helbock, et al., 1998 cit
Darmayasa, 2013).
37
Gambar 2.3. Hubungan metabolit ROS
Walaupun DNA stabil, suatu molekul yang terlindungi
dengan sangat baik, ROS dapat berinteraksi dan menimbulkan
beberapa macam kerusakan : modifikasi basa DNA, putusnya
salah satu atau kedua utas DNA, hilangnya purin (apurinic
sites), kerusakan pada gula deoksiribose, ikatan silang antara
DNA dengan protein, dan kerusakan pada sistem perbaikan
(usaha memperbaiki diri), radikal hidroksil adalah salah satu
ROS yang paling berperan menyebabkan kerusakan ini.
(Khuzaimah, 2015)
2. Stress Oksidatif Dengan Kerusakan DNA
Stres oksidatif adalah suatu keadaan ketidakseimbangan
jumlah prooksidan (radikal bebas) dengan jumlah antioksidan
38
yang ada. Terjadinya peningkatan stress oksidatif dapat
menyebabkan radikal bebas menyerang molekul-molekul yang
secara fisiologis sangat penting seperti lipid, protein termasuk
enzim dan DNA. Sebagai akibat lanjutan dari kerusakan
terhadap purin dan pirimidin akan terjadi modifikasi DNA yang
teroksidasi. (Suciani, 2014)
Stress oksidatif terjadi bila produksi radikal bebas melebihi
antioksidan alami dalam tubuh. Radikal bebas bersifat tidak
stabil dan sangat reaktif, tetapi akan menjadi stabil bila
berkaitan dengan elektron asam nukleat, lemak, protein,
karbohidrat atau molekul. Spesies oksigen reaktif berfungsi
untuk fungsi fisiologis seperti pengiriman signal sel, apoptosis,
dan pertahanan mokroorganisme, tetapi bila terjadi
ketidakseimbangan, akan terjadi efek yang merusak (Otulawa,
2015).
Stress oksidatif diketahui meningkat pada kehamilan
normal. Masa kehamilan dan pertumbuhan janin sangat rentan
terhadap stress oksidatif karena mereka sering mengalami
hiperoksia, peradangan / infeksi yang dapat berkontribusi pada
peningkatan radikal bebas (Knuppel, 2012). Selama kehamilan
dan bayi lahir prematur, mempunyai faktor antioksidan yang
lebih rendah sehingga memicu ketidakseimbangan antara
39
antioksidan dan radikal bebas yang memicu kerusakan
jaringan.
Di dalam Halliwel dan Whiteman (2004) cit Utami (2012),
disebutkan bahwa stress oksidatif dapat dihasilkan akibat :
a. Penurunan level antioksidan. Sebagai contoh, mutasi
mempengaruhi aktivitas enzim antioksidan seperti CuZnSOD
atau glutation peroksida atau racun yang dimetabolisme
melalui konjugasi dengan GSH; dosis tinggi dapat
menghabiskan GSH menyebabkan stress oksidatif.
Defisiensi terhadap mineral (Zn2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, Se) juga
dapat menyebabkan stress oksidatif.
b. Peningkatan produksi spesies reaktif. Sebagai contoh,
melalui paparan atau organisme pada level O2 yang tinggi
atau pada senyawa toksin lain yang merupakan spesies
reaktif (misal NO2*) atau yang dimetabolisme menjadi
spesies reaktif (misal paraquat), atau kelebihan aktivitas dari
dari sistem alami yang memproduksi beberapa spesies
reaktif.
Organisme harus menghadapi dan mengontrol adanya
prooksidan dan antioksidan secara terus menerus.
Keseimbangan kedua faktor ini yang dikenal dengan nama
redoks potensial, bersifat spesifik untuk tiap organel dan
lokasi biologis. Hal-hal yang mempengaruhi kesimbangan ke
40
arah manapun menimbulkan efek buruk terhadap sel dan
organisme. Perubahan keseimbangan ke arah peningkatan
prooksidan yang disebut stres oksidatif akan menyebabkan
kerusakan oksidatif. Perubahan keseimbangan ke arah
peningkatan kekuatan reduksi atau antioksidan juga akan
menimbulkan kerusakan yang disebut stres reduktif.
Gambar 2.4. Keseimbangan Oksidan dan Reduktan
Sementara itu, oxidative damage ialah kerusakan yang
dapat disebabkan oleh serangan langsung spesies reaktif
selama masa stress oksidatif. Spesies reaktif ini dapat
menyerang DNA, baik pada molekul gula fosfat ataupun
basa purin dan pirimidin (Adly, 2010 cit Utami, 2012)
Stress oksidatif memiliki beberapa konsekuensi, yaitu :
1) Adaptasi sel atau organisme terhafap pengaturan baru
sistem pertahanan tubuh, yang dapat (1) melindungi dari
kerusakan secara keseluruhan; (2) melindungi dari
kerusakan dalam beberapa tingkat tetapi tidak secara
41
keseluruhan; atau (c) overprotect (sel tersebut kemudian
akan menjadi resisten terhadap stress oksidatif dengan level
tinggi).
2) Cell injury : ini mencakup kerusakan (oxidative damage)
pada beberapa atau semua target molekul : lipid, DNA,
protein, karbohidrat dan lain-lain. Oxidative damage juga
dapat terjadi selama masa adaptasi. Tidak semua kerusakan
yang disebabkan oleh stress oksidatif adalah oxidative
damage. Sebagai contoh, kerusakan biomolekul dapat
dihasilkan dari stress oksidatif yang berkaitan dengan
perubahan level ion (misal, Ca2+) atau aktivasi protease.
3) Kematian sel : sel dapat (a) disembuhkan dengan oxidative
damage dengan memperbaiki atau mengganti molekul yang
rusak, atau (b) bertahan hidup dengan oxidative damage
yang persisten, atau (c) mengalami kematian melaui
apoptosis atau nekrosis (Halliwell dan Whiteman, 2004 cit
Utami, 2012)
42
Gambar 2.5. Mekanisme kerusakan Sel akibat stress oksidatif
DNA terdapat di dalam mitokondria dan inti sel. DNA
mitokondria mudah mengalami kerusakan oksidatif karena
tidak adanya protein protektif (histon) serta lokasinya
berdekatan dengan yang memproduksi ROS. Radikal
hidroksil mengoksidasi Guanosin atau tymin, masing-masing
menjadi 8-Hydroxy-2’-deoksiguanosine (8-OHdG) atau glikol
tamin, sehingga mengubah DNA dan mengakibatkan
terjadinya mutagenesis atau karsinogenesis. 8-OHdG telah
menjadi biomarker biologis untuk stress oksidatif.
8-OHdG adalah basa nukloetida termodifikasi, yang
sangat sering dipelajari dan dideteksi sebagai produk
43
kerusakan DNA yang diekskresi melalui urine saat terjadi
perbaikan DNA. Meskipun lebih dari 20 modifikasi basa telah
terindentifikasi, namun produk utama dari kerusakan DNA
oksidatif adaldah 8-OHdG. Hubungan antara kerusakan DNA
dan penggunakan 8-OHdG sebagai biomarker telah diteliti
pada kehamilan. Kerusakan DNA yang ditandai dengan
meningkatnya kadar 8-OHdG juga telah ditunjukan
meningkat pada komplikasi kehamilan (Kim, 2005; Furness,
2011).
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Otoluwa,
A., 2014) menunjukkan bahwa kerusakan DNA secara
bermakna dikaitkan dengan kehamilan berkembang menjadi
PE dan IUGR. Kerusakan DNA dapat disebabkan oleh
defisiensi mikronutrien. Mikronutrien memiliki peran penting
dalam melindungi kerusakan DNA dengan menyediakan co-
faktor yang diperlukan untuk berfungsinya enzim yang
berperan dalam perbaikan DNA. Fenech (2005)
mengidentifikasi bahwa asupan kalsium yang rendah, folat,
asam nicotinamide, vitamin E, retinol, beta-karoten dan
secara signifikan terkait dengan ketidakstabilan genomik.
Zinc juga telah ditunjukkan untuk memainkan peran penting
dalam perbaikan kerusakan DNA.
44
Kerusakan DNA pada wanita hamil, yang diukur
dengan konsentrasi 8-OHdG telah terbukti berhubungan
dengan PE dan IUGR. Mekanisme ini masih belum jelas
tetapi diperkirakan karena iskemia atau hipoksia plasenta.
Cedera akibat iskemia dapat berkontribusi pada stres
oksidatif dan menyebabkan pelepasan stres oksidatif ke
sirkulasi ibu dan plasenta mungkin mengakibatkan
kerusakan DNA dan bisa menjadi dasar gangguan
pertumbuhan janin dan development (Otuluwa, et al., 2014)
Antioksidan seperti vitamin A dan E dapat mencegah
produksi 8-OHdG karena aktivitas anti-oksidan dalam
menghambat radikal bebas. Suplementasi dengan vitamin
antioksidan dan vitamin B dapat mengurangi frekuensi
mikronuklei (penanda kerusa kan DNA) (Otuluwa, et al.,
2014)
Kerusakan oksidatif pada dasar DNA dianggap
sumber signifikan terjadinya mutasi dan berbagai penyakit
degeneratif seperti penuaan dan kanker. Kerusakan DNA
secara terus-menerus akan diperbaiki dan dasar kerusakan
akan diekskresikan melalui urin. Salah satu biomarker yang
paling sering digunakan untuk mendeteksi kerusakan DNA
adalah 8-hidroksi-2’-deoksiguanosin (8-OHdG) yang
merupakan modifikasi dasar nukleosida. Hubungan antara
45
reaktif oksigen spesies (ROS) dengan penggunaan 8-OHdG
sebagai biomarker terjadinya stres oksidatif telah banyak
diselidiki pada berbagai macam penyakit (Cooke, et
al.,2003)
3. Delapan-Hydroxy-2’-Deoxyguanosyn (8-OHdG)
Penemuan 8-OHdG dilaporkan pertama kali oleh Kasai da
Nishimaru pada tahun1984 di dalam usaha mereka untuk
mempelajari dan mengisolasi mutagens pada glukosa yang
dipanaskan (seperti model makanan yang dimasak). Karena
kesulitan mengisolasi mutagens yang sangat tidak stabil, metode
dikembangkan dengan memeriksa mutagen reaktif yang
merupakan derivatif guanine dari kenyataan yang ada jika
karsinogen dan reaksi mutagen dengan basa asam nukleat,
dalam hal ini guanine. Peneliti yang sama menemukan radikal
bebas oksigen berkembang pada reaksi C-8 oksidasi. Beberapa
tahun kemudian bentuk 8-OHdG dapat dikonfirmasi dalam reaksi
yang melibatkan radikal bebas oksigen seperti serat asbes dan
H2O2. Beberapa tahun kemudian kadar 8-OHdG dapat dideteksi
dan dianalisis dengan sensitifitas yang tinggi dengan
menggunakan high-performance liquid chromatography (HPLC),
gas-chromatography-mass spectrometry(GC-MS) dan liquid
chromatograpy-mass spectrometry-mass spectrometry (LC-MS-
46
MS) dan metode imunohistokimia dan eletroforesis pada sel
tunggal. Pemeriksaan dan analisis 8-OHdG dapat menggunakan
organ hewan dan sampel pada manusia seperti urin, leukosit DNA,
serum, cairan cerebrospinal, organ manusia) dapat dipakai sebagai
biomarker stress oksidatif, proses penuaan dan karsinogenesis
(Darmayasa, 2013).
Radikal hidroksil adalah salah satu ROS yang dapat
merusak DNA. Senyawa 8-hidroxy-2’-Deoxyguanosin (8-OHdG)
yang merupakan salah satu ekspresi utama kerusakan DNA.
Kadar 8-OHdG yang tinggi berhubungan dengan tingginya agresi
radikal hidroxil dan rendahnya kecukupan antioksidan (Lobo, et al.,
2010 cit Suciani, 2015).
Peningkatan stress oksidatif dapat menyebabkan radikal
bebas menyerang molekul-molekul yang secara fisiologis sangat
penting seperti lipid, protein termasuk enzim dan DNA.
Sebagai akibat lanjutan dari kerusakan terhadap purin dan pirimidin
akan terjadi modifikasi DNA yang teroksidasi. Guanin dapat
diserang oleh OH-. pada posisi C-8 menghasilkan 8-hidroxy-2’-
deoksiguanosin (8-OHdG) sebagai produk oksidasinya. Posisi lain
juga dapat diserang dan produk-produk lainnya mungkin saja
terbentuk. Di antara basa-basa yang teroksidasi itu 8-hidroksi-2’-
deoksiguanosin yang terbanyak jumlahnya (Darmayasa, 2013).
Produk lesi dari oksidasi oleh radikal hidroksil adalah 8-
47
hidroksiguanin, bersama dengan equivalennya 8-hidroksi-2’
deoksiguanosin (8-OHdG) sangat mutagenik. Komponen ini
menyebabkan mutasi (transversi) A:T m enjadi C:C atau G:C
menjadi T:A oleh karena pasangan basanya dengan adenin sebaik
sitosin (Kohen dan Nyska, 2002 cit Darmayasa, 2013).
Radikal hidroksil juga dapat menyerang basa yang lain
seperti adenin untuk membentuk 8 (atau 4-,5-) hidroksiadenin.
Produk-produk lain hasil interaksi antara pirimidin dengan radikal
hidroksil yaitu tiamin perokside, tiamin glikol, 5 (hidroksimetil) urasil
dan produk-produk lainnya. Interaksi langsung lain antara ROS
yang kurang reaktif seperti O.2- dan H2O2 tidak menimbulkan
kerusakan pada jumlah fisiologi, tapi bagaimanapun produk ini
adalah sumber-sumber intermediat reaktif yang mudah diserang
dan menyebabkan kerusakan (Darmayasa, 2013).
Delapan-hidroksi-2’-deoksiguanosin (8-OHdG) adalah suatu
basa nuklotida yang menjadi salah satu biomarker penting yang
sering digunakan sebagai penanda / indikator kerusakan DNA yang
sensitif sebagai akibat stress oksidatif. Disebutkan bahwa
komponen yang dihasilkan melalui DNA yang rusak diakibatkan
oleh radiasi, radikal hidroksil, superoksid atau peroksinitrit.
Delapan-hidroksi-2’deoksiguanosin itu sendiri mempunyai peran
biologi yang mampu menginduksi konversi G:C ke T:A selama
replikasi DNA. Adanya assay yang sensitif untuk 8-hidroksi-
48
2’deoksiguanosin menyebabkan 8-hidroksi-2’deoksiguanosin ini
dipakai di banyak laboratorium sebagai biomarker kerusakan
oksidasi DNA (Valavanidis, et al. 2009).
Faktor-faktor lain yang mendukung adalah :
a. Formasinya di DNA oleh beberapa spesies reaktif seperti
singlet oksigen dan radikal hidroksil.
b. Kemampuan mutagenisitinya dalam menginduksi transversi
GCTA.
c. Mekanisme multipel yang terlibat dalam pemindahan 8-OHdG
dari DNA atau dalam mencegah penyatuan 8-OHdG ke dalam
sel DNA, dengan asumsi bahwa sel “menganggap” 8-OHdG
adalah sebuah ancaman yang segera harus dimusnahkan.
d. Karena prevalensi dan kemudahan dalam mendeteksi
senyawa ini pada sampel-sampel biologik (Darmayasa, 2015)
Beberapa penelitian telah menguji pengaruh stress
oksidatif terhadap kualitas oosit in vitro. Persentase oosit matur
(tahap meiosis II oosit dengan polar body pertama) secara
signifikan menurun dengan pemberian radikal H2O2 dosis
tertentu tetapi dengan menginkubasi oosit dengan antioksidan
(melatonin) dosis tertentu maka pengaruh radikal terhadap
pematangan oosit dihambat (Umekawa, 2008 cit Darmayasa,
2013). Mungkin sangat besar juga pengaruhnya terhadap
kejadian ovum patologis/besarnya oosit berkualitas rendah
49
yang dipicu kronisnya paparan oleh radikal hidroksil.
Kelainan kromosom sangat menonjol dalam penilaian
dampak penyakit genetik yaitu sekitar 50% kematian mudigah,
5-7% kematian janin, 6-11 % lahir mati dan kematian neonatus
dan 0,9% dari bayi lahir hidup. Gamet-gamet abnormal kecil
kemungkinannya menghasilkan konsepsi dibandingkan dengan
gamet normal. Apabila tetap terjadi pembuahan maka seleksi
menyebabkan sebagian besar hasil konsepsi aneuploidi
(kelainan kromosom) akan lenyap sebelum implantasi
(Cunningham, et al., 2006). Dari beberapa penelitian tentang
kualitas oosit, didapatkan konsentrasi 8-hidroksi-2’-
deoksiguanosin pada cairan intrafolikel wanita yang menjalani
IVF-ET diperoleh dengan tingkat degenerasi oosit yang tinggi
(Umekawa, 2008 cit Darmayasa, 2013).
Fertilisasi dan perkembangan embrio in vivo terjadi
dalam lingkungan rendah tekanan oksigen. Tekanan oksigen
yang rendah lebih efektif untuk implantasi dibandingkan
dengan yang tinggi tekanan oksigen. Vaskularisasi folikel
menentukan kandungan oksigen intrafolikuler serta
kemampuan berkembangnya oosit. Hipoksia intrafolikuler
menyebabkan kelainan agregasi kromosom dan gangguan
mosaik embrio. Hal tersebut menjelaskan kembali bagaimana
ROS dapat merusak oosit (Agrawal, et al. 2006).
50
Pada kehamilan sendiri metabolisme akan meningkat
sehingga memerlukan oksigen lebih banyak, maka semakin
meningkat pula radikal bebas yang ditimbulkan. Stress oksidatif
yang terjadi dapat mengganggu kehamilan jika antioksidan
tidak dapat mengimbanginya.(Griebel, et al.2005; Cunningham,
et al. 2006).
E. Tinjauan Tentang Antioksidan
1. Pengertian antioksidan
Antioksidan merupakan senyawa pemberi elekron atau reduktan,
sehingga mempunyai kemampuan untuk menetralkan efek radikal
bebas. Sistem antioksidan tubuh melindungi jaringan dari efek negatif
radikal bebas.
Di dalam tubuh terdapat dua kelompok antioksidan, yaitu
antioksidan enzimatik dan nonenzimatik yang secara rinci diberikan
(Argawal, 2015) :
a. Antioksidan Enzimatik
Antioksidan enzimatik juga dikenal sebagai antioksidan alami,
mereka menetralisir berlebihan ROS dan mencegah dari kerusakan
struktur selular. Antioksidan enzimatik terdiri dari superoksida
dismutase, katalase, glutathione peroksidase dan glutation
reduktase, yang juga menyebabkan pengurangan hidrogen
peroksida untuk air dan alkohol.
51
b. Antioksidan nonenzimatik
Antioksidan non-enzimatik juga dikenal sebagai sintetis
antioksidan atau suplemen diet. Kompleks tubuh sistem antioksidan
dipengaruhi oleh asupan makanan vitamin antioksidan dan mineral
seperti vitamin C, vitamin E, selenium, zinc, taurine, hypotaurine,
glutathione, β-karoten, dan karoten. Vitamin C adalah sebuah rantai
melanggar antioksidan yang berhenti propagasi dari Proses
peroxidative. Vitamin C juga membantu recycle oksidatif dized
vitamin E dan glutation, taurin, hypotaurine dan transferin terutama
ditemukan dalam tuba dan cairan folikel di mana mereka
melindungi embrio dari stress oksidatif. Glutathione hadir dalam
oosit dan cairan tuba dan memiliki peran dalam meningkatkan
pengembangan zigot di luar blok 2-cell ke tahap morula atau
blastosis.
Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, Terdapat 3
kelompok antioksidan (Sayuti, 2015):
a. Antioksidan primer ( endogenus)
Bekerja dengan cara mencegah pembentukan radikal bebas
yang baru serta mengubah radikal bebas menjadi molekul yang
berkurang dampak negatifnya sebelum senyawa radikal bebas
bereaksi. Antioksidan primer adalah antiokisdan yang sifatnya
sebagai pemutus rekasi berantai (chain-breaking antioxidant)
yang bisa berekasi dengfan radikal-radikal lipid dengan
52
mengubahnya menjadi produk-produk yang lebih stabil.
Termasuk didalamnya adalah superoxide dismutase (SOD),
glutatin peroksidase ( GPx), dan katalase. Sering juga disebut
antioksidant enzimatis yaitu antioksidan endogenus yang
melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif yang disebabkan
oleh radikal bebas oksigen seperti anion superoksida (O2*-),
radikal hidroksil (OH*), dan hidrogen peroksida (H2O2).
Antioksidan enzimatik berperan sebagai sistem pertahanan dari
serangan stress oksidatif. Enzim-enzim tersebut merupakan
metaloenzim yang aktivitasnya sangat tergantung adanya ion
logam. Aktivitas SOD tergantung adanya Cu, Zn, dan Mn,
sedangkan katalase bergantung pada Fe (besi), dan glutation
peroksidase bergantung pada selenium. Katalase dan GPx
menunjukkan potensinya dengan mengubah H2O2 menjadi H2O,
sedangkan SOD mengkatalisis reaksi dismutasi radikal anion
superoksida. Katalase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi
dekomposisi hydrogen peroksida menjadi oksigen dan H2O.
Peranan katalase sebagai ˝peroksidase khusus˝, adalah
mengoksidasi 1 molekul hidrogen peroksida menjadi oksigen dan
secara simultan mereduksi molekul hidrogen peroksida kedua
menjadi air.
53
b. Antioksidan sekunder ( eksogenus)
Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengkelat logam
yang bertindak sebagai pro-oksidan, menangkap radikal dan
mencegah terjadinya reaksi berantai. Termasuk didalamnya
adalah vitamin E (α-tokoferol), β karoten, asam urat, bilirubin dan
albumin.
c. Antioksidan tersier
Berguna untuk memperbaiki kerusakan biomolekul yang
disebabkan oleh radikal bebas. Contoh antiokisdan tersier
adalah enzim yang memperbaik kerusakan DNA dan metionin
sulfoksida reduktase (Sayuti, 2015).
Kerusakan oksidatif atau kerusakan akibat radikal bebas dalam
tubuh pada dasarnya bisa diatasi oleh antioksidan endogen
seperti enzim catalase, glutathione peroxidase, superoxide
dismutase, dan glutathione S-transferase. Tetapi jika senyawa
radikal bebas terdapat berlebih dalam tubuh atau melebihi batas
kemampuan proteksi antioksidan seluler, maka dibutuhkan
antioksidan tambahan dari luar atau antioksidan eksogen untuk
menetralkan radikal yang terbentuk (Reynertson, 2007 cit Sayuti
K.,dan Rina Y. 2015). Antioksidan mempunyai kemampuan
mendonorkan elektron dan bisa berfungsi sebagai agen
pereduksi sehingga dapat mengkhelat ion metal dan mengurangi
potensi radikal dalam tubuh (Vaya dan Aviram, 2001 cit Sayuti
54
K., dan Rina Y., 2015). Mengkonsumsi lebih banyak antioksidan
membantu tubuh untuk menetralisir radikal bebas berbahaya.
Antioksidan berperan menetralisir radikal bebas dengan
“menyumbangkan” elektron sehingga membuatnya stabil
kembali. Diperkirakan ada lebih dari 4.000 senyawa dalam
makanan yang berfungsi sebagai antioksidan. Yang paling
banyak dipelajari adalah beta karoten (pro vitamin A), vitamin C,
vitamin E, asam fenolik, selenium, klorofil, karotenoid,
flavonoid, glutasion, koenzim Q10, melatonin dan likopen.
Perlu dicatat bahwa vitamin A sendiri bukan antioksidan
(Krisnadi, 2015).
2. Mekanisme kerja antioksidan
Menurut Lobo, et al (2010) menjelaskan ada 3 mekanisme
sistem pertahanan antioksidan dalam organisme aerobik terhadap
stress oksidatif yang diinduksi oleh radikal bebas dan senyawa oksigen
reaktif, sebagai berikut :
a. Sistem pertahanan pertama adalah preventive antioxidant, yang
menekan pembentukan radikal bebas. Penekanan radikal bebas
dengan dekomposisi senyawa non radikal hidroperoksida dan
hidrogen peroksida diantaranya adalah katalase, Glutation
peroksidase, glutathione-s-transferase, fosfolipid hidroperoksida
glutathione peroxidase (PHGPX), dan peroksidase yang diketahui
membusuk lipid hidroperoksida jika diberikan alkohol yang sesuai.
55
Glutation peroksidase dan katalase mengurangi hidrogen peroksida
air.
b. Sistem pertahanan kedua adalah radical scavenging antioxidant,
bekerja dengan cara menangkap radikal untuk menghambat rantai
inisiasi dan / atau memutus rantai reaksi propagasi pada proses
oksidasi. Berbagai endogen pada antioksidan ini adalah beberapa
hidrofilik dan lain lipofilik. Vitamin C, asam urat, bilirubin, albumin,
dan tiol yang hidrofilik, antioksidan radikal- scavenging, sementara
vitamin E dan ubiquinol yang lipofilik diterima sebagai antioksidan
lipofilik yang paling ampuh radical scavenging antioxidant.
c. Pada sistem pertahanan ketiga, bekerja dengan cara memperbaiki
kerusakan dan membangun membran yang telah rusak.
Antioksidan yag masuk dalam kelompok ini adalah lipase, protease,
DNA repair enzyme dan transferase.
d. Pada sistem pertahanan terakhir berupa proses adaptasi, dimana
tubuh memproduksi enzim antioksidan yang sesuai untuk ditransfer
ke sisi tertentu pada waktu dan konsentrasi yang tepat.
3. Sistem pertahanan melalui pemutusan reaksi radikal
Antioksidan yang berpeeran sebagai pemutus rekasi radikal
dikenal dengan antioksidan non-enzimatik. Antioksidan jenis non-
emzimatis ini diantaranya vitamin E (alfa-tokoferol), vitamin C (asam
askorbat), vitamin A dan karetonoid, riboflavin (vitamin B2).
56
a. Vitamin A
Beta-karoten dapat menangkap singlet oxygen (1O2) karena
adanya 9 ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Energi untuk
reaksi ini dibebaskan dalam betnuk panas sedemikian rupa
sehingga sistem regenerasi tidak diperlukan. Beta-karoten juga
bereaksi dengan senyawa-senyawa radikal peroksi, pertama-tama
membentuk radikal karotenoid peroksil dan kemudian membentuk
kerotenoid peroksida (Lobo, et al., 2010).
b. Tokoferol dan tokotrienol (Vitamin E)
Vitamin E adalah nama kolektif untuk satu set delapan
tokoferol terkait dan tocotrienol, yang adalah vitamin yang larut
dalam lemak dengan sifat antioksidan. Dari jumlah tersebut, α-
tokoferol telah paling banyak dipelajari karena memiliki
bioavailabilitas tertinggi, dengan tubuh istimewa menyerap dan
metabolisme formulir ini. Telah diklaim bahwa bentuk α-tokoferol
adalah antioksidan larut lemak yang paling penting, dan yang
melindungi membran dari oksidasi dengan bereaksi dengan radikal
lipid yang dihasilkan dalam reaksi berantai peroksidasi lipid. Hal ini
menghilangkan intermediet radikal bebas dan mencegah reaksi
propagasi dari melanjutkan. Reaksi ini menghasilkan teroksidasi
radikal α-tocopheroxyl yang dapat didaur ulang kembali ke bentuk
tereduksi aktif melalui pengurangan oleh antioksidan lainnya,
seperti askorbat, retinol, atau ubiquinol (Khuzaimah, 2015).
57
Vitamin E dalam dari bahan pangan sebagai antioksidan
yang paling aktif adalah deltatokoferol, sedangkan dalam tubuh
manusia yang paling berfungsi adalah alfa-tokoferol. Vitamin E
bereaksi dengan radikal bebas lipida membran sel membentuk
vitamin E radikal sedikit reaktif yang memutus propagasi dari rekasi
rantai radikal. Vitamin E radikal mengalami regenerasi dengan
adanya glutation dan vitamin C (Muchtadi, 2008; Khuzaimah,
2015)
c. Vitamin C (asam askorbat)
Asam askorbat atau "vitamin C" adalah monosakarida
antioxidantfound di kedua hewan dan tumbuhan. Karena tidak
dapat disintesis pada manusia dan harus diperoleh dari makanan,
itu adalah vitamin. Sebagian besar hewan lain yang mampu
menghasilkan senyawa ini dalam tubuh mereka dan tidak
memerlukan dalam diet mereka. Dalam sel, itu dipertahankan
dalam bentuk penurunan sebesar reaksi dengan glutathione, yang
dapat dikatalisis oleh protein disulfida isomerase dan
glutaredoxins. Asam askorbat adalah reduktor dan dapat
mengurangi dan dengan demikian menetralkan ROS seperti
hidrogen peroksida. Selain efek antioksidan langsung, asam
askorbat juga merupakan substrat untuk antioksidan peroksidase
enzim askorbat, fungsi yang sangat penting dalam ketahanan stres
pada tanaman.
58
Asam askorbat vitamin larut air utama sebagai sumber
antioksidan. Antioksidan ini menjadi bagian yang penting dalam
sistem pertahan tubuh, merupakan bagian dari pertahanan
pertama ROS dalam plasma, dan juga berperan dalam sel. Asam
askorbat dapat menangkap secara efektif sekaligus 02* dan 1O2.
Asam askorbat dapat memutuskan reaksi radikal yang dihasilkan
melalui lopoperoksidasi. Asam askorbat bereaksi secara langsung
pada air dengan radikal LOO*, lalu berubah menjadi askorbil
sedikit rekatif. Asam askorbat mempunyai peran penting dalam
perlindungan DNA. Vitamin C dapat meregenerasi vitamin E
(Muchtadi, 2008 cit Khuzaimah, 2015).
Heaton (2002) telah meneliti peranan diet antioksidan
terhadap kerusakan DNA pada anjing dewasa. Anjing yang
diberikan makanan dengan campuran bahan sumber antioksidan
(vitamin C, vitamin E, taurin, lutein, lycopene dan beta-karoten)
mengalami peningkatan kadar antioksidan setelah 4 minggu
intervensi dimana keadaan yang sama tidak terjadi pada kelompok
kontrol. Setelah 8 minggu suplementasi terjadi penurunan
kerusakan DNA pada kelompok intervensi. Penurunan kerusakan
DNA tersebutt mengindikasikan peningkatan perlindungan DNA
terhadap radikal bebas dan peningkatan perbaikan DNA yang
rusak oleh antioksidan.
59
Penelitian terhadap sopir bus dan polisi kota (bukan
perokok) di Praha menunjukan bahwa pemberian suplementasi
vitamin C dapat menurunkan kerusakan DNA total. Vitamin C
dapat cenderung melindungi integritas DNA (Novotna, 2007;
Bagryanseva, 2010). Hasil penelitian pada subyek perokok juga
daapt memberikan hasil yang sama. Melalui pemberian suplemen
vitamin C sebesar 500 mg/hari selama 6 minggu menurunkan
kadar 8-OHdG (Moller, 2002; Cooke, 1998 cit Khuzaimah, 2015).
Penelitian secara in vitro menunjukan bahwa kekurangan vitamin
C telah terbukti meningkatkan kerusakan DNA dan pada dosis
yang lebih tinggi rneningkatkan stotoksitas hidrogen peroksida
pada limfosit manusia. Kemampuan vitamin C menetralkan radikal
bebas secara in vitro bisa menurunkan kerusakan pada gen-gen
penekan tumor sehingga bisa menurunkan risiko kanker (Thomas,
2011 cit Khuzaimah, 2015).
4. Sistem pertahanan antioksidan
Sistem pertahanan preventif menghambat pertahanan
pembentukan senyaw-senyawa ROS atau merusak pembentukannya.
Dalam cairan ekstraseluler, yang terutama berfungi sistem kelasi
metal, sebaliknya dalam sel, senyawa-senyawa ROS tersebut
dirusak oleh sistem enzim (Nadimin, 2015).
Jenis antioksidan yang berfungsi sebagai sistem pertahanan
dalam cairan ekstraseluler, diantaranya protein plasma yang
60
mempunyai kemampuan mengkelat metal seperti Cu2+ dan Fe3+ dan
sekaligus menghambat rekasi feton dan pembentukan radikal yang
sangat toksik seperti *OH, LOO* atau LO*. Selain itu, dalam cairan
ekstraseluler terdapat beberapa senyawa antioksidan dapat
menangkap senyawa-senyawa ROS pada saat pembentukannya.
Diantaranya adalah asan urat, glukosa, taurin, bilirubin, estrogen,
betakorotene, sistein, melatonin, retinoid dan flafonoid (Nadimin,
2015).
Antioksidan yang berfungsi sebagai sistem pertahanan di
dalam cairan intraseluler, adalah berupa berbagai macam enzim
yang berperan dalam proses degradasi senyawa-senyawa ROS
intraseluler, jenis antioksidan ini biasa disebut antioksidan enzimatik
yaitu Superoksida dismutase (SOD), Katalase (CAT) dan Glutation
peroksidase (GPx). Enzim-enzim tersebut dapat mengkonversi
spesies oksigen reaktif (ROS) menjai molekul non reaktif (Nadimin,
2015).
Tabel 2.1. Enzim-enzim antioksidan dan Fungsinya
Enzim Fungsi
Superoksida Dismutase Menghilangkan superoksida
Katalase Menghilangkan hydrogen peroksida
Glutation Peroksidase Menghilangkan hydrogen peroksida
Glutation disulfide reduktase Mereduksi glutation teroksidasi
Glutation-S-transferase Menghilangkan hidroperoksida lipid
61
Metionin Sulfoksida reduktase Memperbaiki residu metionon teroksidasi
Peroksidase
Dekompesisi hydrogen peroksida dan
hidroperoksida lipid
Sumber : Lee, et al., 2004 cit Nadimin, 2015
F. Tinjauan Tentang Biskuit Makanan Tambahan (MT)
1. Definisi
Makanan tambahan adalah makanan yang tersedia dalam
bentuk Biskuit lapis (SandWich), bergizi sebagai tambahan
makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi
kebutuhan gizi dan diperuntukan bagi ibu hamil. Biskuit lapis
(SandWich) terbuat dari bahan pangan terigu, lemak nabati tanpa
hidrogenasi,gula, susu, telur, kacang-kacangan, buah kering
diperkaya dengan vitamin dan mineral, (Kemenkes, 2011).
2. Komponen / Kandungan Biskuit Makanan Tambahan
a. Kandungan Gizi
Tabel 2.2. Kandungan Gizi Biskuit Makanan Tambahan
INFORMASINILAI GIZI
Takaran saji 100 grJumlah sajian perkemasan:
Energi total 260 kkal
Energi dari lemak120 kkal
Jumlah per sajian %AKG* Jumlah per sajian %AKG*
Lemak total 13 gr 21 %Protein 8 gr 9%
Karbohidrat total 28 gr 9%Natrium 240 mg 16 %
Vitamin A 50% Asam foat 50%
Vitamin D 60% Asam Pantotenat 55%
Vitamin E 55% Selenium 55%
Vitamin B1 (Thimamin) 60% Flour 60%
Vitamin B2 (Riboflavin) 55% Yodium 25%
62
Vitamin B6 (Piridoksin) 60% Seng 25%
Vitamin B12 (Sianokobalamin) 60% Zat besi 25%
Vitamin C 50% Fosfor 15%
Vitamin B3 (Niasin) 55% Kalsium 15%*persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2160 kkal.
b. Cemaran
Biskuit lapis (Sandwich) harus memenuhi persyaratan batas
maksimum cemaran mikroba dan cemaran logam.
1) Cemaran mikroba
- Total Plate count (TPC) atau Angka Lompong Total
tidak lebih dari 5,0 x 10 koloni per gram (ml)
- Most Prolable Number (MPN) koliform tidak lebih dad i,0
x 102 koloni pergram (ml)
- Escherichia coli negatif per gram
- Salmonella negatif dalam 25 gr?m contoh (sampel)
- Staphylococcus aureus 1,0 x 10'koloni per gram
2) Cemaran logam
- Arsen (As) tidak lebih'dari 0,1 mg/kg
- Timbal (Pb) tidak lebih dari 0,3 mg/kg
- Timah (Sn) tidak lebih dari 40,0 mg/kg
- Raksa (Hg) tidak lebih dari 0,03 mg/kg
- Kadmium (Cd) tidak lebih dari 0,05 mg/kg
63
3. Manfaat makanan tambahan
a. Pemberian makanan tambahan (PMT) dengan energy 300- 800
kkal/hari dengan energy yang berasal dari protein < 25 % dapat
meningkatkan tambahan berat badan ibu hamil yang menderita
KEK, meningkatkan pertumbuhan janin dan ukuran bayi yang
dilahirkan.
b. Untuk melengkapi dan mencukupi kebutuhan gizi pada ibu hamil
agar berat badan sesuai usia.
c. Memenuhi kebutuhan ibu dan bayinya
d. Membantu pertumbuhan dan perkembangan janin
e. Mengurangi komplikasi dan resiko (perdarahan post partum)
f. Mencegah terjadinya BBLR dan BBLSR pada janin
g. Menghindari dan mencegah terjadinya infeksi pada persalinan
h. Sebagai sumber tenaga ibu dan janin, (Ratih, 2015)
4. Efek Biskuit Makanan Tambahan
Adapun efek samping yang dapat ditimbulkan dari Biskuit makanan
tambahan tersebut yaitu :
a. Apabila dikomsumsi melebihi dosis atau aturan yang berlaku
yaitu hanya dikomsusmi 1 bngkus biskut makanan tambahan
dalam sehari. Karena Biskuit makanan tambahan tersebut
mengandung cemaran mikroba dan cemaran logam yang
terkontrol dalam kemasan (Per Saji) sehingga akan dapat
mengakibatkan efek negative dalam tubuh.
64
b. Selain itu Biskuit tersebut mengandung Vitamin A bila
dikombinasikan dengan zat besi dan tembaga akan
meningkatkan oksidasi guanosin. Interkasi antar zat gizi dapat
membuat vitamin atau mineral yang tadinya antioksidan menjadi
prooksidan. Sehingga akan mempengaruhi fungsi utama Biskuit
makanan tambahan tersebut.
c. Demikian pula kombinasi vitamin C dengan besi, tembaga dan
seng dapat meningkatkan oksidasiguonosin. Kombinasi vitamin
C dan tembaga dapat meningkatkan oksidasi guanosin,
kerusakan DNA oksidatif serta DNA stand breaks.
G. Tinjauan Tentang Tablet Tambah Darah (Fe)
1. Defenisi
Zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh. Zat ini
terutama diperlukan dalam hemopoboesis (pembentukan darah) yaitu
sintesis hemoglobin (Hb). Hemoglobin (Hb) yaitu suatu oksigen yang
mengantarkan eritrosit berfungsi penting bagi tubuh. Hemoglobin
terdiri dari Fe (zat besi), protoporfirin, dan globin (1/3 berat Hb terdiri
dari Fe). Besi bebas terdapat dalam dua bentuk yaitu ferro (Fe2+) dan
ferri (Fe3+).
Konversi kedua bentuk tersebut relatif mudah. Pada konsentrasi
oksigen tinggi, umumnya besi dalam bentuk ferri karena terikat
hemoglobin sedangkan pada proses transport transmembran, deposisi
65
dalam bentuk feritin dan sintesis heme, besi dalam bentuk ferro.
Dalam tubuh, besi diperlukan untuk pembentukkan kompleks besi
sulfur dan heme. Kompleks besi sulfur diperlukan dalam kompleks
enzim yang berperan dalam metabolisme energi. Heme tersusun atas
cincin porfirin dengan atom besi di sentral cincin yang berperan
mengangkut oksigen pada hemoglobin dalam eritrosit dan mioglobin
dalam otot.
2. Fungsi Zat Besi
Besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh :
sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai
alat angkut elektron di dalam sel, dan sebagai bagian terpadu
berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh.
Rata-rata kadar besi dalam tubuh sebesar 3-4 gram. Sebagian
besar (± 2 gram) terdapat dalam bentuk hemoglobin dan sebagian
kecil (± 130 mg) dalam bentuk mioglobin. Simpanan besi dalam tubuh
terutama terdapat dalam hati dalam bentuk feritin dan hemosiderin.
Dalam plasma, transferin mengangkut 3 mg besi untuk dibawa ke
sumsum tulang untuk eritropoesis dan mencapai 24 mg per hari.
Sistem retikuloendoplasma akan mendegradasi besi dari eritrosit
untuk dibawa kembali ke sumsum tulang untuk eritropoesis.
Zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel
darah merah (hemoglobin). Selain itu, mineral ini juga berperan
sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang
66
membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat di tulang,
tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim. Zat besi juga
berfungsi dalam sistim pertahanan tubuh
3. Sumber Zat Besi
Sumber zat besi adalah makan hewani, seperti daging, ayam dan
ikan. Sumber baik lainnya adalah telur, serealia tumbuk, kacang-
kacangan, sayuran hijau dan beberapa jenis buah. Disamping jumlah
besi, perlu diperhatikan kualitas besi di dalam makanan, dinamakan
juga ketersediaan biologic (bioavability). Pada umumnya besi di dalam
daging, ayam, dan ikan mempunyai ketersediaan biologik tinggi, besi
di dalam serealia dan kacang-kacangan mempunyai mempunyai
ketersediaan biologik sedang, dan besi dalam sebagian besar
sayuran, terutama yang mengandung asam oksalat tinggi, seperti
bayam mempunyai ketersediaan biologik rendah. Sebaiknya
diperhatikan kombinasi makanan sehari-hari, yang terdiri atas
campuran sumber besi berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan
serta sumber gizi lain yang dapat membantu sumber absorbsi. Menu
makanan di Indonesia sebaiknya terdiri atas nasi, daging/ayam/ikan,
kacang-kacangan, serta sayuran dan buah-buahan yang kaya akan
vitamin C.
67
Berikut bahan makanan sumber besi
Bahan Makanan Kandungan Besi (mg)
Daging 23.8
Sereal 18.0
Kedelai 8.8
Kacang 8.3
Beras 8.0
Bayam 6.4
Hamburger 5.9
Hati sapi 5.2
Susu formula 1.2
Bahan makanan sumber besi didapatkan dari produk hewani dan
nabati. Besi yang bersumber dari bahan makanan terdiri atas besi
heme dan besi non heme. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat
bahwa walaupun kandungan besi dalam sereal dan kacang-kacangan
relatif tinggi, namum oleh karena bahan makanan tersebut
mengandung bahan yang dapat menghambat absorpsi dalam usus,
maka sebagian besar besi tidak akan diabsorpsi dan dibuang bersama
feses.
4. Kebutuhan Fe/Zat Besi dan Suplementasi Zat Besi Pada Masa
Kehamilan
Kebutuhan zat besi selama hamil yaitu rata-rata 800 mg – 1040
mg. Kebutuhan ini diperlukan untuk :
68
- ± 300 mg diperlukan untuk pertumbuhan janin.
- ± 50-75 mg untuk pembentukan plasenta.
- ± 500 mg digunakan untuk meningkatkan massa haemoglobin
maternal/ sel darah merah.
- ± 200 mg lebih akan dieksresikan lewat usus, urin dan kulit.
- ± 200 mg lenyap ketika melahirkan
Perhitungan makan 3 x sehari atau 1000-2500 kalori akan
menghasilkan sekitar 10–15 mg zat besi perhari, namun hanya 1-
2 mg yang di absorpsi. jika ibu mengkonsumsi 60 mg zat besi,
maka diharapkan 6-8 mg zat besi dapat diabsropsi, jika
dikonsumsi selama 90 hari maka total zat besi yang diabsropsi
adalah sebesar 720 mg dan 180 mg dari konsumsi harian ibu.
Besarnya angka kejadian anemia ibu hamil pada trimester I
kehamilan adalah 20%, trimester II sebesar 70%, dan trimester III
sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena pada trimester pertama
kehamilan, zat besi yang dibutuhkan sedikit karena tidak terjadi
menstruasi dan pertumbuhan janin masih lambat. Menginjak
trimester kedua hingga ketiga, volume darah dalam tubuh wanita
akan meningkat sampai 35%, ini ekuivalen dengan 450 mg zat
besi untuk memproduksi sel-sel darah merah. Sel darah merah
harus mengangkut oksigen lebih banyak untuk janin. Sedangkan
saat melahirkan, perlu tambahan besi 300 – 350 mg akibat
kehilangan darah. Sampai saat melahirkan, wanita hamil butuh zat
69
besi sekitar 40 mg per hari atau dua kali lipat kebutuhan kondisi
tidak hamil.
Masukan zat besi setiap hari diperlukan untuk mengganti zat
besi yang hilang melalui tinja, air kencing dan kulit. Kehilangan
basal ini kira-kira 14 ug per Kg berat badan per hari atau hampir
sarna dengan 0,9 mg zat besi pada laki-laki dewasa dan 0,8 mg
bagi wanita dewasa. Kebutuhan zat besi ibu hamil berbeda pada
setiap umur kehamilannya, pada trimester I naik dari 0,8 mg/hari,
menjadi 6,3 mg/hari pada trimester III. Kebutuhan akan zat besi
sangat menyolok kenaikannya. Dengan demikian kebutuhan zat
besi pada trimester II dan III tidak dapat dipenuhi dari makanan
saja, walaupun makanan yang dimakan cukup baik kualitasnya
dan bioavailabilitas zat besi tinggi, namun zat besi juga harus
disuplai dari sumber lain agar supaya cukup. Penambahan zat
besi selama kehamilan kira-kira 1000 mg, karena mutlak
dibutuhkan untuk janin, plasenta dan penambahan volume darah
ibu. Sebagian dari peningkatan ini dapat dipenuhi oleh simpanan
zat besi dan peningkatan adaptif persentase zat besi yang
diserap. Tetapi bila simpanan zat besi rendah atau tidak ada sama
sekali dan zat besi yang diserap dari makanan sangat sedikit
maka, diperlukan suplemen preparat besi.
70
Untuk itu pemberian suplemen Fe disesuaikan dengan usia
kehamilan atau kebutuhan zat besi tiap semester, yaitu sebagai
berikut :
a. Trimester I : kebutuhan zat besi ±1 mg/hari, (kehilangan basal
0,8 mg/hari) ditambah 30-40 mg untuk kebutuhan janin dan sel
darah merah.
b. Trimester II : kebutuhan zat besi ±5 mg/hari, (kehilangan basal
0,8 mg/hari) ditambah kebutuhan sel darah merah 300 mg dan
conceptus 115 mg.
c. Trimester III : kebutuhan zat besi 5 mg/hari,) ditambah
kebutuhan sel darah merah 150 mg dan conceptus 223 mg
Angka Kecukupan Besi
Umur (tahun) AKG Besi (mg)
10-12 20
13-49 26
50-65 12
Hamil (+ an)
Trimester 1 + 0
Trimester 2 + 9
Trimester 3 + 13
Besi dalam bentuk fero lebih mudah diabsorbsi maka
preparat besi untuk pemberian oral tersedia dalam berbagai
bentuk berbagai garam fero seperti fero sulfat, fero glukonat,
71
dan fero fumarat. Ketiga preparat ini umumnya efektif dan tidak
mahal. Di Indonesia, pil besi yang umum digunakan dalam
suplementasi zat besi adalah ferrosus sulfat, senyawa ini
tergolong murah dan dapat diabsorbsi sampai 20%.
Memberikan preparat besi yaitu fero sulfat, fero glukonat
atau Na-fero bisirat. Pemberian preparat 60 mg/hari dapat
menaikan kadar Hb sebanyak 1 gr%/ bulan. Saat ini program
nasional menganjurkan kombinasi 60 mg besi dan 50 nanogram
asam folat untuk profilaksis anemia.
Dosis zat besi yang paling tepat untuk mencegah anemia ibu
masih belum jelas, tetapi untuk menentukan dosis terendah dari
zat besi untuk pencegahan defisiensi besi dan anemia defisiensi
besi pada kehamilan telah dilakukan penelitian Pada wanita
Denmark, suplemen 40 mg zat besi ferrous / hari dari 18 minggu
kehamilan tampaknya cukup untuk mencegah defisiensi zat
besi pada 90% perempuan dan anemia kekurangan zat besi
pada setidaknya 95% dari perempuan selama kehamilan dan
postpartum.
Prevalensi anemia defisiensi besi pada 39 minggu kehamilan
secara signifikan lebih tinggi pada kelompok 20 mg (10%)
dibanding kelompok 40 mg (4,5%), kelompok 60 mg (0%), dan
kelompok 80 mg (1,5%) (p = 0,02). Pada 32 minggu kehamilan,
72
berarti Hb pada kelompok 20 mg lebih rendah dibanding
kelompok 80 mg (p = 0,06). Tidak ada perbedaan yang
signifikan dalam status besi (feritin, sTfR, dan Hb) antara
kelompok 40, 60, dan 80 mg. Postpartum, kelompok 20 mg
memiliki feritin serum rata-rata secara signifikan lebih rendah
dibanding kelompok 40, 60 dan 80 mg (p <0,01).
5. Efek Samping Pemberian Suplementasi Zat Besi
Pemberian zat besi secara oral dapat menimbulkan efek
samping pada gastrointestinal pada sebagian orang, seperti rasa
tidak enak di ulu hati, mual, muntah dan diare. Frekuensi efek
samping ini berkaitan langsung dengan dosis zat besi. Tidak
tergantung senyawa zat besi yang digunakan, tak satupun senyawa
yang ditolelir lebih baik daripada senyawa yang lain. Zat besi yang
dimakan bersama dengan makanan akan ditolelir lebih baik
meskipun jumlah zat besi yang diserap berkurang. Pemberian
suplementasi Preparat Fe, pada sebagian wanita, menyebabkan
sembelit. Penyulit Ini dapat diredakan dengan cara memperbanyak
minum, menambah konsumsi makanan yang kaya akan serat
seperti roti, serealia, dan agar-agar.
Mual pada masa kehamilan adalah proses fisiologi sebagai
dampak dari terjadinya adaptasi hormonal. Selain itu mual dapat
terjadi pada ibu hamil sebagai efek samping dari minum tablet besi.
Ibu hamil yang mengalami mual sebagai dampak kehamilannya
73
dapat merasakan mual yang lebih parah dibandingkan dengan ibu
hamil yang tidak mengalami keluhan mual sebelumnya. Ada
beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi mual akibat
minum tablet besi. Salah satu cara yang dianjurkan untuk
mengurangi mual sebagai efek samping dari mengkonsumsi tablet
besi adalah dengan mengurangi dosis tablet besi dari 1 x 1 tablet
sehari menjadi 2 x ½ tablet sehari. Akan tetapi hal ini tidak sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Milman, Bergholt, dan
Erikson (2006) yang menyatakan tidak ada hubungan antara efek
samping atau gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, nyeri
epigastrik, kolik, konstipasi, dan diare dengan empat dosis yang
diuji cobakan yaitu : 20 mg, 40 mg, 60 mg, dan 80 mg.
Konsumsi tablet besi pada malam hari juga dilakukan para
partisipan dalam upaya mencegah mual setelah minum tablet besi.
Dalam penelitian ini tablet besi diminum pada malam hari agar tidak
mengalami mual. Hal itu dilakukan atas anjuran petugas kesehatan.
6. Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Zat Besi
Diperkirakan hanya 5-15 % besi makanan diabsorbsi oleh
orang dewasa yang berada dalam status besi baik. Dalam keadaan
defisiensi besi absorbsi dapat mencapai 50%. Banyak faktor
berpengaruh terhadap absorbsi besi. Bentuk besi di dalam
makanan berpengaruh terhadap penyerapannya. Besi-hem, yang
merupakan bagian dari hemoglobin dan mioglobin yang terdapat
74
didalam daging hewan dapat diserap dua kali lipat daripada besi-
nonhem. Kurang lebih 40% dari besi didalam daging , ayam dan
ikan terdapat besi-hem dan selebihnya sebagai non-hem. Besi-
nonnhem juga terdapat di dalam telur, serealia, kacang-kacangan,
sayuran hijau dan beberapa jenis buah-buahan. Makan besi-hem
dan non-hem secara bersama dapat meningkatkan penyerapan
besi-nonhem. Daging, ayam dan ikan mengandung suatu faktor
yang membantu penyerapan besi. Faktor ini terdiri atas asam
amino yang mengikat besi dan membantu penyerapannya. Susu
sapi, keju, telur tidak mengandung faktor ini hingga tidak dapat
membantu penyerapan besi. Asam organik, seperti vitamin C
sangat membantu penyerapan besi-nonhem dengan merubah
bentuk feri menjadi bentuk fero. Seperti telah dijelaskan, bentuk
fero lebih mudah diserap. Vitamin C disamping itu membentuk
gugus besi-askorbat yang tetap larut pada pH tinggi dalam
duodenum. Oleh karena itu sangat dianjurkan memakan makanan
sumber vitamin C tiap kali makan. Asam organik lain adalah asam
sitrat. Asam fitat dan faktor lain di dalam serat serelia dan asam
oksalat di dalam sayuran menghambat penyerapan besi. Faktor-
faktor ini mengikat besi, sehingga mempersulit penyerapannya.
Protein kedelai menurunkan absorbsi besi yang mungkin
disebabkan oleh nilai fitatnya yang tinggi. Karena kedelai dan hasil
olahnya mempunyai kandungan besi yang tinggi, pengaruh akhir
75
terhadap absorbsi besi biasanya positif. Vitamin C dalam jumlah
cukup dapat melawan sebagian pengaruh faktor-faktor yang
menghambat penyerapan besi ini. Tanin yang merupakan polifenol
dan terdapat di dalam teh, kopi dan beberapa jenis sayuran dan
buah juga menghambat absorbsi besi dengan cara mengikatnya.
Bila besi tubuh tidak terlalu tinggi, sebaiknya tidak minum teh atau
kopi waktu makan. Kalsium dosis tinggi berupa suplemen
menghambat absorbsi besi, namun mekanismenya belum diketahui
dengan pasti.
Tingkat keasaman lambung meningkatkan daya larut besi.
Kekurangan asam klorida di dalam lambung atau penggunaan
obat-obatan yang bersifat basa seperti antasid menghalangi
absorbsi besi. Faktor intrinsik di dalam lambung membantu
penyerapan besi, diduga karena hem mempunyai struktur yang
sama dengan vitamin B12. Kebutuhan tubuh akan besi
berpengaruh terhadap absorbsi besi. Bila tubuh kekurangan besi
atau kebutuhan meningkat pada kondisi tertentu, absobsi besi-
nonhem dapat meningkat sampai sepuluh kali, sedangkan besi-
hem dua kali.
76
Tabel 2.3. Senyawa Yang Mempengaruhi Absorpsi Besi
Aktivasi Inhibitor
Asam askorbat
Daging
Alkohol
Polifenol (grup galoil)PitatKalsiumMirisetin
Asam klorogenik (kopi)
7. Tablet besi berguna untuk kesehatan ibu dan bayi
Proses haemodilusi yang terjadi pada masa hamil dan
meningkatnya kebutuhan ibu dan janin, serta kurangnya asupan zat
besi lewat makanan mengakibatkan kadar Hb ibu hamil menurun.
Untuk mencegah kejadian tersebut maka kebutuhan ibu dan janin
akan tablet besi harus dipenuhi.
Anemia defisiensi besi sebagai dampak dari kurangnya asupan
zat besi pada kehamilan tidak hanya berdampak buruk pada ibu,
tetapi juga berdampak buruk pada kesejahteraan janin. Hal
tersebut dipertegas dengan penelitian yang dilakukan yang
menyatakan anemia defisiensi besi dapat menyebabkan gangguan
pertumbuhan janin dan kelahiran prematur. Lebih lanjut dalam
penelitiannya tentang mekanisme biologi dampak pemberian zat
besi pada pertumbuhan janin dan kejadian kelahiran premature
melaporkan anemia dan defisiensi besi dapat menyebabkan ibu
dan janin menjadi stres sebagai akibat diproduksinya corticotropin-
releasing hormone (CRH). Peningkatan konsentrasi CRH
77
merupakan faktor resiko terjadinya kelahiran prematur, pregnancy-
induced hypertension. Disamping itu juga berdampak pertumbuhan
janin. Temuan lain pada penelitian yang dilakukan adalah
pemberian tablet besi sebelum hamil dapat meningkatkan berat
badan lahir bayi. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian
Cristian (2003) dan Palma (2007) yang menyatakan suplemen zat
besi berhubungan dengan resiko BBLR pada ibu yang mengalami
anemia.
Gangguan pertumbuhan janin yang ditimbulkan tergantung
pada periode pertumbuhan apa ibu mengalami anemia. Penelitian
yang dilakukan Georgieftt (2008) menyatakan kejadian defisiensi
besi pada awal kehidupan janin berdampak pada gangguan neural,
metabolisme monoamine dan proses myelinasi.
Janin untuk pertumbuhan dan perkembangan intra uterin
diperoleh janin dari nutrisi yang ada di tubuh ibunya. Kebutuhan
janin ditransfer dari tubuh ibu melaluilasenta. Kebutuhan janin yang
tidak terpenuhi dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan
dan perkembangan janin. Metabolisme tubuh membutuhkan
oksigen agar dapat menghasilkan energi dan komponen lain yang
dibutuhkan tubuh. Ketersediaan oksigen besi dalam tubuh ibu
dapat dilihat dari adanya tanda dan gejala: letih, lemah, lesu,
pusing dan mudah lupa sebagai akibat tidak terbentuknya energi
secara optimal.
78
H. Studi Intervensi Pemberian Mikro Nutrien Pada Ibu Hamil
Beberapa penellitian telah melakukan studi intervensi pemberian mikro nutrient pada ibu hamil. Diantaranya :
Table 2.4. Penelitian intervensi yang pernah dilakukan
Namapeneliti/tahun
Judul penelitian Jenispenelitian
Subjek Penelitian Hasil/kesimpulan penelitian
Hermansyah, VeniHadju,BurhanuddinBahar/ 20
Pengaruh ekstrak daunkelor terhadap asupandan berat badan ibuhamil pekerja sektoralinformal
Randomizedcontrolleddouble blind
Ibu hamil Pemberian ekstrak daun kelorberpengaruh terhadappeningkatan berat badan danlingkar lengan atas tetapi tidakberpengaruh terhadappeningkatan asupan
Anang otuluwa,etal/2014
Effect of moringa oleiferaleaft extractssupplementation inpreventing maternal DNAdamage
Doubleblind,randomized, control trial
Ibu hamil trimester I tidak ada perbedaan yangsignifikan dalam tingkat 8-OHdG antara kelompokintervensi dan kelompokkontrol
Masyita Muis,VeniHadju, SyamsiarRusseng, danM.FurqanNaiem/2014
Effect of moringa leaveextract on occupationalstress and nutritionalstatus of pregnantwomen informal sectorworkers
Randomizedcontrollrdintervensionwith doubleblind
Ibu hamil pekerja Pemberian ekstrak moringaleaft pada ibu hamil pekerjadapat menurnkan MuddleUpper Arm Circumference(MUAC) tapi tidak pada kadarHb
79
Nadimin/2016 The influence provision ofmoringa leaftextracy(moringa oliefera)againt the level of Mda(Malondialdehyde) inpregnant women
Randomizeddouble blind
Ibu hamil Pemberian ekstrak daun kelormenghambat peningkatanMDA pada wanitahamil(7.82±1;22 vs 8.34±1.70nmol/g
M.IshaqIskandar/2015
Efek pemberian ekstrakdaun kelor terhadappeningkatan berat badandan kejadian anemiapada ibu hamil dikabupaten gowa
Double blind,randomizedtrial, pre-postcontrolled
Ibu hamil Pemberian ekstrak daun kelormenunjukkan pertambahanberat badan, LILA signifikanpada kelompok intervensi daripada kontrol. Namun tidaksignifikan pada peningkatankadar Hb.
Nadimin/2015 Pengaruh pemberianekstak daun kelor(moringa oliefera)terhadap pencegahananemia, kerusakan DNAoksidatif pada ibu hamildan berat badan lahirbayi
Double blind,randomizedtrial, pre-postcontrolled
Ibu hamil Pemberian ekstrak daun kelordapat mencegah anemia dankerusakanDNA akibat stressoksidatif pada ibu hamil, sertamencegah BBLR
AnnaKhuzaimaha/2016
Pengaruh Madu danMoringa oleifera DaunEkstrak Suplementasiuntuk MencegahKerusakan DNA di PasifKehamilan Merokok
Randomizedtrial, Pra-posttest
Ibu hamil trimester III Ada pengaruh madu danekstrak daun kelor padapencegahan kerusakan DNApada wanita hamil perokokpasif
Shalini Effect of supplementation Randomized Wanita menopause Penelitian menunjukkan bahwa
80
Kushwaha,Paramjit Chawla, AnitaKochhar/2014
of drumstick ((Moringaoleifera) and amaranth(Amaranthus tricolor)leaves powder onantioxidant profile andoxidative status amongpostmenopausal women
trial tanaman ini memiliki sifatantioksidan dan memilikipotensi terapi untukpencegahan komplikasiselama postmenopause
81
I. Kerangka Teori
q
,
Gambar 2.8.Kerangka Teori
Normal DNA, Damagerepair
8-OHdG
Metabolisme Kebutuhan gizi
Oksigen
Radikal Bebas
Stress oksidatif
Kerusakan DNA
Biskuit MakananTambahan (Lemak,Protein, Karbohidrat,
Natrium, Zat Besivitamin C, E, selenium,
zinc, taurine,hypotaurine, glutathione,β-karoten, Vitamin B1,B2, B3, B6, B12 dan
Asam folat,
Antioksidan EnzimatisSOD,katalase,glutation
oksidase
Antioksidan Non-enzimatisVitamin,A,C,E,β-karoten,flavonoid
Ion superoksida(O2.-)Hidrogen peroksida
(H2O2)
Transisi metal Fe++,Cu+
Radikal hidrosil (.OH)
Air(H2O),O2
Reaktif oksidasi spesies ROS ( O2.-,H2O2, .OH)
Mn-SOD,Cu,Zn-SOD
CAT. GPX
Kehamilan Normal
Kadar 8-OHdG
82
J. Kerangka Konsep
Keterangan:
: Variabel Independent
: Variabel Dependent
Gambar 2.9.Kerangka Konsep
K. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah “ada pengaruh pemberian biscuit
Makanan tambahan (MT) dan Tablet tambah darah terhadap status gizi
dan kadar 8-hydroxy-2’-deoxyguanosin (8-OHdG) pada ibu hamil KEK”
L. Definisi operasional
a. Biskuit makanan tambahan (MT) (Variabel Independent)
Biskuit lapis (SandWich) terbuat dari bahan pangan terigu, lemak
nabati tanpa hidrogenasi,gula, susu, telur, kacang-kacangan, buah
Biskuit makanan tambahan
(MT) dan tablet tambah darah
(IFA)
Delapan-hidroxy-2’deoxyguanosin
(8-OHdG)
Status Gizi
83
kering diperkaya dengan vitamin dan mineral, mengandung multi
mikronutrien, Adapun kandungan makanan tambahan tersebut
yaitu: Lemak total 13 gr, Protein 8 gr, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin
D, Vitamin B2 (Riboflavin), Yodium, Karbohidrat total 28 gr, Natrium
240 mg , Asam foat, Asam Pantotenat, Selenium, Vitamin B6
(Piridoksin), Seng, Vitamin B12 (Sianokobalamin), Zat besi, Vitamin
C, Vitamin B3 (Niasin), Fosfor, Kalsium. Membagikan biskuit pada
ibu hamil KEK yang menjadi responden setiap 4 minggu. Biskuit
dikomsumsi 50 gram/hari dipantau dengan menggunakan lembar
ceklis setiap hari selama selama 12 minggu. Dengan metode
pemeriksaan lembar kontrol dengan skala nominal.
b. Tablet tambah darah (IFA) (Variabel Independent)
Tablet tambah darah yang mengandung ferosus sulfate & folic acid
Membagikan Tablet tambah darah pada ibu hamil KEK yang
menjadi responden setiap 4 minggu. Biskuit dikomsumsi 50
gram/hari dipantau dengan menggunakan lembar ceklis setiap hari
selama selama 12 minggu. Dengan metode pemeriksaan lembar
kontrol dengan skala nominal
c. Kadar 8-hidroxy-2’deoxyguanosin (8-OHdG) (Variabel dependent)
Konsentrasi yang digunakan untuk mengukur kerusakan DNA
dengan menggunakan Metode tes Enzim-Linked Immunosorbent
Assay (ELISA). Dengan tes TBA skala rasio.