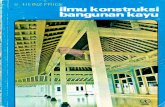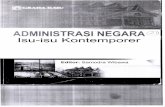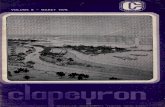KONSTRUKSI ISU DISABILITAS DI MEDIA ONLINE TEMPO.CO
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of KONSTRUKSI ISU DISABILITAS DI MEDIA ONLINE TEMPO.CO
KONSTRUKSI ISU DISABILITAS DI MEDIA ONLINE
TEMPO.CO
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk
Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Qusyairi Sazali Kuba
NIM : 11150510000018
PROGRAM STUDI JURNALISTIK
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA
1442 H/ 2021 M
KONSTRUKSI ISU DISABILITAS DI MEDIA ONLINE TEMPO.CO
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.)
Oleh
Qusyairi Sazali Kuba NIM : 1150510000018
PROGRAM STUDI JURNALISTIK
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1442 H/ 2021 M
ii
LEMBAR PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Qusyairi Sazali Kuba
NIM : 11150510000018
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul KONSTRUKSI ISU
DISABILITAS DI MEDIA ONLINE TEMPO.CO adalah benar merupakan
karya saya sendiri yang belum pernah diajukan sebagai skripsi atau karya
ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga lain dan tidak melakukan tindakan
plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan
karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya
bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan
merupakan plagiat dari karya orang lain.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Jakarta, 26 Desember 2020
Qusyairi Sazali Kuba
NIM 11150510000018
KONSTRUKSI ISU DISABILITAS DI MEDIA ONLINE
TEMPO.CO
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos)
Oleh:
Qusyairi Sazali Kuba
NIM 11150510000018
Pembimbing:
Bintan Humeira, S.Sos. M.Si
NIP 19771105 200112 2 002
PROGRAM STUDI JURNALISTIK
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1442 H / 2021
i
ABSTRAK
Qusyairi Sazali Kuba
11150510000018
Konstruksi Isu Disabilitas Di Media Online Tempo.Co
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan disabilitas sangat berhubungan dengan stigma dan diskriminasi. Selama bertahun-tahun media di Indonesia melihat disabilitas sebagai orang lemah, tak berdaya dan menjadi masalah sosial, cara pandang medis (Medical Model) yang menggambarkan bahwa disabilitas adalah bencana bagi mereka yang mendapatkannya, tepatnya disabilitas dianggap tragedi yang menimpa seseorang, tak heran pemberitaan yang muncul selalu menempatkan disabilitas sebagai orang yang harus dikasihani dan selalu dijadikan sebagai objek inspirasi dimana penyandang disabilitas melakukan sesuatu yang biasa saja dibingkai menjadi objek inspirasi.
Tempo.co muncul dengan gaya baru dalam pemberitaan disabilitas dengan cara menjadikan isu disabilitas menjadi sebuah kanal khusus pada laman web tempo.co. Hal ini tentu merupakan sebuah kemajuan besar bagi dunia jurnalisme di Indonesia untuk mengurai konstruksi disabilitas yang telah terbentuk di masyarakat sebagai objek kasihan dan kehebatan. Berdasarkan konteks di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konstruksi isu disabilitas serta proses produksi isu disabilitas pada media online Tempo.co dalam rubrik Difabel. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Strukturasi Anthony Giddens. Dalam teori ini disebutkan bahwa struktur dapat diproduksi dan direproduksi baik oleh tindakan-tindakan manusia maupun melalui medium tindakan sosial.
Penelitian ini menggunakan metode campur kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Hasil temuan data penelitian menunjukkan isu disabilitas dikonstruksi berdasarkan 3 kategori, yaitu isu aksesibilitas, inklusifitas dan rehabilitas dan isu yang paling dominan pada pemberitaan media Tempo.co dalam rubrik Difabel adalah isu inklusifitas dan isu aksesibilitas. Proses produksi isu disabilitas yaitu Cheta Nilawati dan Rini Kustiani sebagai pencetus lahirnya rubrik Difabel berperan sebagai agensi dan aktor daam membentuk struktur sosial yang aware terhadap disabilitas yang masih dimarginalkan. Kata Kunci: Konstruksi, Disabilitas, Tempo.co
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa
Ta’ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat
diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
pada Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis telah
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Konstruksi Isu Disabilitas Di
Media Online Tempo.co.
Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad
SAW. yang melalui beliau kita dapat merasakan cahaya kehidupan dan nikmat
ilmu pengetahuan seperti yang sedang kita rasakan saat ini.
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada
pihak-pihak yang sudah turut membantu dan mendukung penulisan skripsi ini:
1. Prof. Dr. Amany Lubis selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Suparto, M. Ed sebagai Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Dr. Siti Napsiyah, S.Ag, BSW, MSW sebagai Wakil
Dekan I Bidang Akademik dan Wakil Dekan II Bidang Administrasi
Umum.
iii
3. Kholis Ridho, M.Si dan Drs. Hj. Musfirah Nurlaily, MA sebagai Ketua
Jurusan Jurnalistik dan Sekretaris Jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Bintan Humeira, M.Si, selaku pembimbing yang telah meluangkan
waktu serta sabar dalam memberikan ilmu, arahan, bimbingan, saran,
serta nasihat yang bermanfaat selama penelitian hingga selesai
penulisan.
5. Segenap dosen Program Studi Jurnalistik yang telah mendidik penulis
selama menuntut ilmu di Program Studi Jurnalistik Fakultas Dakwah
dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah
banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Cheta Nilawati dan Rini Kustiani sebagai narasumber yang telah
mengizinkan penulis untuk melangsungkan interview agar
memperoleh informasi data penelitian.
7. Keluarga penulis, Ayahanda (Alm) Zaini Dahlan dan Ibunda Maneh,
Adinda Raudhatun Nisa dan Abangda Afdhalul Rahman Kuba dan
Ariful Muharis. Terima kasih atas doa dan usahanya sudah menempa
penulis menjadi anak yang kuat dan mandiri.
8. Teman-teman jurusan Jurnalistik angkatan 2015.
iv
9. Segenap Keluarga Besar Forum Ruhul Islam Anak Bangsa (FARIS
JAKARTA), Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA) Jakarta,
sebagai rumah di perantauan.
10. Putri Andira yang telah menemani penulis sepanjang 2018-2020 dalam
proses pengerjaan skripsi ini.
Penulis sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak
yang telah membantu semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan
balasan kebaikan atas bantuan semua pihak.
Jakarta, 26 November 2020
Penulis,
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... ii DAFTAR ISI.................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ........................................................... 7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ........................................... 7
D. Metodologi Penelitian .......................................................................... 9
E. Tinjauan Kajian Terdahulu ................................................................ 16
F. Sistematika Penulisan ........................................................................ 20
BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 22
A. Media dan Kelompok Marjinal .......................................................... 22
B. Media dan Disabilitas ........................................................................ 24
C. Difabel dan Disabilitas ....................................................................... 28
D. Perubahan Paradigma Disabilitas ...................................................... 33
E. Isu Disabilitas di Media ..................................................................... 40
F. Produksi Isu Disabilitas dalam Teori Strukturasi .............................. 50
G. Kerangka Teori .................................................................................. 56
BAB III GAMBARAN UMUM MEDIA ONLINE TEMPO.CO ........... 57
A. Sejarah dan Perkembangan Tempo.co ............................................... 57
B. Rubrik difabel di Tempo.co ............................................................... 60
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN ...................................... 62
A. Isu Disabilitas Pada Media Online Tempo.co.................................... 62
B. Produksi Isu Disabilitas Rubrik Difabel Pada Media Tempo.Co ...... 88
BAB V TEMPO DAN ISU DISABILITAS ............................................... 94
A. Analisis Teori Strukturasi Pemberitaan Tempo Terhadap Isu Disabilitas .................................................................................................. 94
B. Relasi Struktur Dan Aktor Terhadap Isu Disabilitas ....................... 100
vi
C. Konstruksi Isu Disabilitas Pada Media Online Tempo.co ............... 103
BAB VISIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ................................ 106
A. KESIMPULAN ................................................................................ 106
B. IMPLIKASI ..................................................................................... 107
C. SARAN ............................................................................................ 108
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 109
LAMPIRAN............................................................................................... 113
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejak adanya media yang menemani keseharian kita, media
memiliki peran yang sangat penting dalam setiap lini kehidupan, terlebih
lagi media massa. Kita dapat memperoleh informasi terkait suatu realitas
atau peristiwa yang terjadi di tempat lain dari media. Di era digitalisasi
seperti saat ini, tentu saja media massa online dipandang sebagai media
yang cukup interaktif dan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat terkait segala informasi dan berita yang terliput oleh media
sebagai salah satu sebagai hasil dari karya jurnalistik. Keberadaan media
massa online di tengah masyarakat saat ini bahkan telah membuat
perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan karena bukan hanya
menyuguhkan kemampuannya dengan daya jangkau yang luas namun
juga memfasilitasi masyarakat akan berita dengan kecepatan yang cukup
mengejutkan.
Dengan semakin pesatnya perkembangan media online dalam
menyajikan berita, terlihat beberapa isu yang mengalami penyimpangan
dalam pemberitaannya; di antaranya isu disabilitas. Dampak diskriminasi
dan representasi terhadap penyandang disabilitas dalam media online
membuat kaum disabilitas ini seolah termarjinalkan dan lama kelamaan
menjadi terlupakan secara total. Sebagai akibatnya, wawasan, informasi,
2
dan pengetahuan masyarakat menjadi sangat terbatas terhadap segala
persoalan dan isu tentang disabilitas serta akan menjadi suatu masalah
yang sangat terabaikan.
Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
mencatat bahwa dari kurun waktu 2011-2016 hanya ada 89 berita yang
menyuarakan berita terkait penyandang disabilitas Tahun 2011 ada enam
berita, 2012 empat berita, 2013 tujuh berita, 2014 sedikit ada peningkatan
menjadi 11 berita. Kemudian 2015 ada 40 berita, dan 2016 sampai dengan
bulan April ada 20 berita.1 Untuk sebuah angka jumlah berita yang
memberitakan kaum difabel tersebut, 89 tentulah merupakan angka
sangat sedikit padahal Tim Riset LPEM FEB Universitas Indonesia
menjelaskan estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar
12,15 persen dengan dua kategori. Yang masuk kategori sedang sebanyak
10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Artinya, dengan
jumlah populasi lebih kurang sebanyak 11 juta penduduk di Indonesia
menjadi termarjinal dengan sedikitnya isu tentang mereka yang diangkat
oleh media. Media sebagai corong informasi dengan jangkauan yang luas
juga yang dapat menembus setiap lapisan masyarakat dinilai memiliki
1Dani Prabowo, “Komnas Ham Nilai Isu Disabilitas Kurang Mendapatkan Perhatian
media,” artikel diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 dari https://nasional.kompas.com/read/2017/02/17/17232611/komnas.ham.nilai.isu.disabilitas.kurang.mendapatkan.perhatian.media.
3
peran yang sangat krusial dalam mendorong isu disabilitas ini. Pasalnya
dengan jumlah 12,15 dari populasi di Indonesia namun diberitakan hanya
sebanyak 89 kali dalam kurun waktu 5 tahun itu adalah sesuatu yang tidak
masuk akal dan perlu ditindak dengan serius.
Tempo.co merupakan satu-satunya media online yang
memberikan ruang luas bagi pemberitaan disabilitas. Hal tersebut
didukung oleh peluncuran kanal difabel di laman Tempo.co pada 21
Februari 2019. Apa yang dilakukan oleh tempo sangat bermanfaat bagi
perjuangan kelompok disabilitas yang saat ini merasa di diskriminatif dan
dianggap menjadi warga kelas dua.
Permasalahan disabilitas sangat berhubungan dengan stigma dan
diskriminasi. Selama bertahun-tahun media di Indonesia melihat
disabilitas sebagai orang lemah, tak berdaya dan menjadi masalah sosial.
Cara pandang medis (Medical Model) yang menggambarkan bahwa
disabilitas adalah bencana bagi mereka yang mendapatkannya, tepatnya
disabilitas dianggap tragedi yang menimpa seseorang, tak heran
pemberitaan yang muncul selalu bersubjek kasihan ataupun berlebihan,
dimana penyandang disabilitas melakukan sesuatu yang biasa saja
dibingkai menjadi objek inspirasi.
Tempo.co muncul dengan gaya baru dalam pemberitaan
disabilitas dengan cara menjadikan isu disabilitas menjadi sebuah kanal
4
khusus pada laman web tempo.co. Hal ini tentu merupakan sebuah
kemajuan besar bagi dunia jurnalisme di Indonesia. Apa yang dilakukan
oleh Tempo sangatlah baik untuk mengurai konstruksi disabilitas yang
telah terbentuk di masyarakat sebagai objek kasihan dan kehebatan.
Tempo mencoba mengulas isu disabilitas dengan konsisten dan menarik
lewat topik yang lebih beragam, aktivitas, tips bagaimana bersosialisasi
dengan difabel, gaya hidup, pendidikan dan lainnya.
Dalam “Mengenal Gejala Anak Disabilitas Psikososial dan
Penanganannya”, misalnya, berita ini merupakan bentuk pendidikan
literasi ke masyarakat soal disabilitas, yang memang masih sangat minim
di Indonesia. Berita berunsur literasi seperti itu kerap muncul
di Tempo.co, seperti terlihat dalam “Buka Identitas Anak Difabel Bisa
Cegah Anak Alami Bullying” dan “Seperti Apa Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Inklusif Bagi Difabel”. Selain itu, aspek literasi disabilitas
di Tempo.co juga ditampilkan dalam hal-hal kecil dan menarik, seperti
kursi roda, main kartu bagi disabilitas netra, dan lainnya. Berita bercorak
literasi seperti itu membantu isu disabilitas hadir lebih sering dalam
perbincangan dan pengetahuan masyarakat sehari-hari.
Corak lain yang kerap muncul dari berita-berita disabilitas
di Tempo.co adalah berita tentang penyandang disabilitas yang mampu
melakukan hal-hal biasa yang selama ini dilakukan oleh abled-body. Ini
5
penting karena selama ini penyandang disabilitas kerap dianggap tidak
mampu melakukan hal-hal tertentu. Tengoklah berita “Latte Art Karya
Barista Satu Tangan di Sunyi Coffee House And Art” dan “Kisah Presti
Murni, Tunanetra yang Menjadi Guru Fiqih di Madrasah”.
Biasanya, berita seperti ini tergoda untuk membingkai
penyandang disabilitas secara inspirasional, “orang hebat”, dan
sebagainya. Namun, kedua berita tadi ditulis dengan biasa, tanpa melebih-
lebihkan, dan tanpa nada yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai
sumber inspirasi. Hanya membuka mata bahwa penyandang disabilitas
sama seperti yang lainnya: bisa mengajar, bisa menjadi barista, bisa
mengaji, dan seterusnya.
Demikian pula dengan sudut pandang dan judul berita, tak ada
kata superscript atau menghereoisasi. Difabel dianggap sebagai entitas
biasa sebagaimana manusia pada umumnya. Kejadian dan peristiwa yang
melingkupi difabel dibungkus dengan apa adanya, tanpa menggiring dan
mengarahkan pada ideologi “kenormalan”. Ini berbeda dengan banyak
berita atau talkshow yang menghadirkan penyandang disabilitas sebagai
objek atraksi atau inspirasi.
Usaha melepas superscript dan excessive charity atas pemberitaan
disabilitas yang dilakukan Tempo.co sangatlah baik untuk mengurai
“konstruksi” yang selama ini telah melingkupi masyarakat: disabilitas
6
dianggap sebagai objek kasihan dan kehebatan. Dibandingkan dengan
media-media mainstream yang lain, Tempo.co lebih punya kesadaran
menggunakan paradigma yang sejalan dengan tujuan pengarusutamaan
difabel di kalangan aktivis difabel.
Ini tentu merupakan kerja jurnalistik yang tidak mudah mengingat
konstruksi mengenai disabilitas yang sudah hegemonik, tertanam dalam
alam bawah sadar kita. Artinya, wartawannya harus selalu bersikap kritis
dan mempertanyakan segala asumsinya yang sudah mapan mengenai
disabilitas.2 Karena media massa memiliki tanggung jawab untuk
mengakomodasi rujukan dan melindungi kelompok minoritas ditengah-
tengah dominasi suatu kelompok dalam masyarakat plural. Maka dari itu,
penelitian ini mengambil bagian dari “KONSTRUKSI ISU
DISABILITAS DI MEDIA ONLINE TEMPO.CO”.
2 Slamet Thohari, “Mendengar Difabel Melalui Tempo,” diakses pada tanggal 17
Oktober 2019 dari http://www.remotivi.or.id/amatan/536/Mendengar-Difabel-Melalui-Tempo.co
7
B. Batasan dan Rumusan Masalah a. Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian adalah pembatasan terhadap
kategori isu disabilitas yang diterbitkan Tempo.co dalam 3 aspek, yaitu
isu aksesibilitas, isu inklusifitas dan rehabilitasi dalam kurun waktu 3
bulan yaitu periode Agustus, September dan Oktober 2019 pada
pemberitaan isu-isu disabilitas di media online Tempo.co.
b. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul yang sudah dipaparkan, maka rumusan
masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:
1. Apa saja isu disabilitas yang terdapat pada pemberitaan media online
Tempo.co ?
2. Manakah isu yang paling dominan dalam pemberitaan media online
Tempo.co pada periode Agustus hingga Oktober 2019 ?
3. Bagaimana proses konstruksi dan produksi isu disabilitas dalam rubrik
difabel Tempo.co ?
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, secara khusus
penelitian ini bertujuan untuk:
8
a. Mengetahui isu disabilitas yang diberitakan pada media
online Tempo.co.
b. Mengetahui isu yang paling dominan pada pemberitaan
media online Tempo.co pada periode Agustus hingga
Oktober 2019.
c. Menjelaskan bagaimana proses konstruksi produksi isu
disabilitas di media Tempo.co dilihat dalam relasi agen dan
struktur.
2. Manfaat Penelitian
a. Signifikansi Manfaat Akademis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah
satu referensi dalam pengembangan ilmu komunikasi bagi
akademisi, baik dosen maupun mahasiswa. Khususnya dalam
kajian konstruksi sosial untuk mengetahui bagaimana isu disabilitas
dikonstruksikan oleh media massa.
b. Signifikansi Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi para
jurnalis, khususnya media online Tempo.co itu sendiri dan sebagai
pertimbangan atau masukan kepada media-media online dalam
mendorong isu disabilitas, serta dapat memberikan masukan kepada
pengambil kebijakan terkait isu disabilitas yang berkembang. Juga
9
memberi acuan kepada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana
isu disabilitas ini dapat dikonstruksikan oleh media massa.
D. Metodologi Penelitian 1. Metodologi Penelitian
a. Paradigma Penelitian
Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah
paradigma konstruktivis. Menurut paradigma konstruktivis, realitas
sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan, hal
ini dapat diartikan bahwa realitas sosial tidak dapat disamaratakan.
Menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari berbagai
realitas yang terkonstruksi oleh individu dan dampak dari konstruksi
tersebut bagi kehidupan mereka dengan cara yang nyata dalam
memandang realitas tersebut. Paradigma konstruktivis juga sering
disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Dengan
konsentrasi analisis yaitu menemukan bagaimana peristiwa realitas
tersebut dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi dibentuk.
Paradigma konstruktivis yang memandang bahwa untuk
mengetahui “dunia arti” (world of meaning) mereka harus
menginterpretasikannya. Mereka juga harus menyelidiki proses
pembentukan arti yang muncul dalam bahasa atau aksi-aksi sosial para
aktor.
10
Paradigma ini menilai aspek-aspek etika, moral, dan nilai-nilai
tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Etika dan
moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok
atau nilai tertentu umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu adalah
bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan
mengkonstruksi realitas.
b. Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk
menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data
sedalam-dalamnya.3 Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai
pelaku observasi dari kehidupan sekitar. Penelitian jenis ini terdiri dari
sekumpulan interpretasi praktis yang menggambarkan kondisi aktual
dengan jelas. Interpretasi tersebut direpresentasikan dalam catatan
lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo. Pada
tahap ini, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan naturalistik
interpretatif. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari hal-hal
dalam kondisi yang natural, mencoba untuk memahami, atau untuk
menafsirkan fenomena yang mereka temukan.
3 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta:Prenada Media
Group, 2009) hlm. 56
11
2. Desain Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan mixed
method. Mixed methods research design (metode penelitian
campuran) ialah sesuatu prosedur dalam mengumpulkan,
menganalisis, dan “menggabungkan” metode kuantitatifserta kualitatif
dalam sebuah penelitian atau serangkaian riset yang dibuat guna
memahami permasalahan penelitian. Pendekatan ini mencoba
menggabungkan dua metode dengan tujuan buat membagikan uraian
yang lebih baik tentang permasalahan penelitian serta persoalan
penelitian dari pada dilakukan sendiri-sendiri. Berikutnya Sugiyono
(2014, hlm. 404) menyatakan bahwa metode campuran (mixed
methods) ialah sebuah metode penelitian yang mencampurkan ataupun
mengombinasikan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitafi
secara bersama-sama dalam sebuah penelitian sehingga informasi
yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel, serta obyektif.
Creswell (2009) menyatakan “A Mixed methods design is useful when either the quantitative or qualitative approach by itself is inadequate to best understand a research problem or the strengths of both quantitative and qualitative research can provide the best understanding”.
Metode penelitian kombinasi akan berguna bila metode
kuantitatif atau metode kualitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup
akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian, atau
dengan menggunakan metode kuatitatif dan kualitatif secara
12
kombinasi akan dapat memperoleh pemahaman yang paling baik (bila
dibandingkan dengan satu metode). Desain ini memungkinkan penulis
untuk mengambil data penelitian kuantiatif dan kualitatif secara
bersamaan guna memahami masalah penelitian.
Data kuantitatif berasal dari berita yang di ambil dari rubrik
Difabel Tempo.co, data tersebut kemudian diolah untuk memudahkan
penulis dalam melihat perkembangan rubrik difabel Tempo.co. data
kuanitiatif yang dimaksud adalah 82 berita periode bulan Agustus-
Oktober 2019 yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu aksesibilitas,
Inklusifitas dan Rehabilitasi. Dalam waktu bersamaan penulis juga
melakukan metedo penelitian kualitatif untuk melihat arah
pembingkaian
Kualitatif
Kuantitatif
Perbandingan /Hubungan
Interpretasi
13
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah tim redaksi penanggung jawab
rubrik di difabel Tempo.co, sementara objek penelitiannya adalah
pemberitaan pada rubrik Difabel Tempo.co periode terbit Agustus
hingga Oktober 2019 sebanyak 86 berita.
4. Metode Pengumpulan Data
Adapun tahapan-tahapan dalam pengumpulan data, peneliti
menggunakan dua metode, yaitu :
a. Wawancara.
Peneliti melakukan wawancara face to face interview
(wawancara langsung) dan indepth interview (wawancara
mendalam) dengan Cheta Nilawati (Reporter) Rini Kustiani
(Editor) dan rubrik difabel Tempo.co.
1) Cheta Nilawati
Cheta Nilawati telah bekerja di Tempo.co selama 14 tahun.
Jabatannya adalah seorang reporter. Mulanya, Cheta
bukanlah orang dengan disabilitas. Karena penyakit
diabetes yang dialaminya, ia kehilangan penglihatan pada
tahun 2016 atau di tahun ke-10 ia menjadi wartawan
Tempo. Cheta menjadi agensi pencetus rubrik difabel di
tempo.co. Tujuan mewawancarai Cheta Nilawati adalah
14
untuk mengetahui bagaimana proses produksi dan
konstruksi isu disabilitas dalam rubrik difabel tempo.co.
2) Rini Kustiani
Rini Kustiani merupakan wartawan Tempo sejak tahun
2005 yang menjabat sebagai editor pada rubrik Tempo.co.
Tujuan mewawancarai Rini Kustiani adalah mengetahui
hubungan relasi agen dan struktur dalam proses produksi
isu di media Tempo.co.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu berupa penelusuran berita pada rubrik
Difabel laman online tempo.co periode Agustus hingga Oktober
2019. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan
membaca buku-buku yang berkaitan dengan jurnalistik, analisis
konten, komunikasi, media massa serta hasil-hasil dari penelitian
sebelumnya yang relevan.
5. Teknik Analisis Data
a. Reduksi Data (Reduction)
Reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan berita
menjadi 3 kategori, yaitu isu disabilitas aksesibilitas, inklusifitas dan
rehabilitasi yang terdapat di rubrik kanal difabel Tempo.co selama
15
kurun waktu 3 bulan periode Agustus hingga Oktober 2019.
Kemudian, dilihat data yang paling dominan dari kategori isu
disabilitas tersebut.
b. Penyajian Data (Data Display)
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan
sejenisnya. Lebih dari itu data juga dapat disajikan dengan bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan
sejenisnya.
c. Conclusion Drawing / Verification
Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat dan
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
16
E. Tinjauan Kajian Terdahulu
Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu
tentang topik penyandang disabilitas dan media massa. Penelitian
mengenai penyandang disabilitas itu sendiri bermacam-macam, ada
yang melakukan penelitian dari sisi kesehatan, psikologis, aksesibilitas
dan lain-lain. Kemudian berikut ini adalah beberapa referensi bacaan
yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:
Pertama, “Identitas Kelompok Disabilitas Dalam Media
Komunitas Online: Studi Mengenai Pembentukan Pesan Identitas
Disabilitas Dalam Kartunet.com” Oleh Auliani Dwi Nasiti dalam
Jurnal Komunikasi Indonesia Vol. II, No.1, April 2013.
Penelitian ini bertujuan mengangkat pembentukan identitas
yang terjadi dalam media komunitas online Kartunet sebagai subjek
studi. Situs yang merupakan akronim dari karya tunanetra ini
merupakan media komunitas bagi kelompok penyandang disabilitas
yang dikelola oleh kelompok tunanetra, namun isinya ditujukan
kepada masyarakat umum. Kartunet menyadari posisi kelompok
penyandang disabilitas sebagai kelompok yang termarjinalkan dalam
lingkungan sosial dan cenderung ditempatkan sebagai kelompok
minoritas yang dikenakan stereotip tertentu. Stereotip ini dipandang
negatif oleh individu di dalam kelompok tersebut, seperti misalnya
17
stereotip tunanetra sebagai tukang pijat atau manusia kelas dua. Dalam
komunitas kartunet, terlihat bahwa anggota komunitas memahami
stigma ini merupakan hasil konstruksi dari lingkungan sosial
masyarakat. Oleh karena itu, melalui Kartunet.com mereka
membentuk identitas yang melawan stereotip tersebut dengan
menyuarakan pesan lewat media dan membentuk suatu komunitas agar
lingkup pergerakannya lebih luas dan terarah.
Kedua, “Kemunculan Diri Dan Peran Pemilik Industri
Media di Indonesia dalam Kerangka Teori Strukturasi Anthony
Giddens” Oleh Ignatius Haryanto dalam Jurnal Lembaga Studi Pers
dan Pembangunan (LSPP) Vol. VI, No.2, Desember 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana dan apa
yang membuat pemilik media (media owner) menjadi sesuatu yang
penting untuk dilihat dalam kerangka teori tarik menarik struktur dan
agen, dan dimana persisnya letak owner media ini, apakah ia adalah
seorang penguasa struktur atau ia adalah seorang agen. Gejala tentang
pengaruh dari pemilik media boleh dikatakan bukan merupakan suatu
telaah yang baru, dalam hal ini penelitian yang dilakukan adalah
tentang bagaimana menjelaskan posisi sosial dari para pemilik media
dan peran yang dibawakannya. Apakah media owner semata-mata
18
tunduk pada kepentingan modal, ataukah ia juga merupakan seorang
penerobos dari kebekuan sistem sosial yang ada.
Ketiga, “Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat
Dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada
Masyarakat di Stain Kudus” Karya Ekawati Rahayu Ningsih,
STAIN Kudus Jawa Tengah dalam Jurnal Penelitian Vol.8, No.1,
Februari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
memahami kebutuhan pelayanan mahasiswa difabel. Hal ini
dikarenakan sebagai sesama manusia, kaum difabel memiliki potensi
yang sama bahkan mungkin lebih dari manusia normal. Yang
membedakan hanya tampilan fisik saja yang akhirnya terkesan tidak
normal. Tetapi tidak normalnya fisik mereka bukan berarti tidak bisa
melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang
lain. Sehingga dalam penelitian ini dapat membantu dan mendukung
upaya memfasilitasi dan memberikan pelayanan bagi kaum difabel
agar lebih memiliki peran yang sama dengan manusia non difabel,
yaitu dengan cara mengintegrasikan disabilitas ke dalam tema-tema
penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
Keempat, Agensi Penyandang Disabilitas Dalam
Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus Tunanetra
di Yayasan Mitra Netra). Karya Luthfi Auliani Jurusan Sosiologi
19
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah, tahun 2017.
Kondisi disabilitas yang masih diliputi stigma tertentu dalam
masyarakat menyebabkan munculnya kesenjangan atau
ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan pada penyandang disabilitas berupa
distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata, pola relasi yang
tidak setara, dan kesempatan untuk berpartisipas dalam kehidupan
sehari-hari yang tidak sama dibandingkan dengan mereka yang non
difabel. Sehingga dalam penelitian ini lebih lanjut dikaji tentang
bagaimana peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk
memperjuangkan hak-hak bagi penyandang disabilitas di samping
kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Lalu sejauh mana
lembaga tersebut dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk
mendapatkan pekerjaan, dan apa saja yang menjadi rintangan selama
proses itu berlangsung.
20
F. Sistematika Penulisan
Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini sistematis, untuk
itu penulis membaginya menjadi enam bab, yaitu tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub sebagai berikut;
BAB I PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang masalah,
batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI yang terdiri dari pembahasan tentang
teori media massa, teori Strukturasi Anthony Giddens, dan
identitas disabilitas.
BAB III GAMBARAN UMUM MEDIA ONLINE TEMPO.CO
memuat tentang latar belakang berdirinya, visi, misi dan tujuan
berdirinya, dan struktur organisasi pada rubrik difabel.
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN pada bab ini berisi
tentang uraian penyajian data (coding) dari temuan penelitian
sesuai dengan analisis penerapan teori strukturasi terhadap isu
disabilitas pada media online tempo.co.
BAB V PEMBAHASAN pada bab ini berisi tentang uraian dari
temuan penelitian (penerjemahan coding) sesuai dengan
21
analisis penerapan teori strukturasi terhadap isu disabilitas pada
media online tempo.co.
BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN terdiri dari
kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban terhadap
semua bab-bab tersebut. Skripsi ini juga dilengkapi dengan
daftar pustaka dan lampiran.
22
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Media dan Kelompok Marjinal
Kaum marginal menurut indikatornya terpisah menjadi beberapa
kriteria yaitu sosiologis, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, politik,
ekonomi, ekologis, indeks pembangunan. Contohnya adalah seperti buruh
anak, gizi buruk, buta huruf dan lain-lain. Namun Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan UNESCO mengatakan bahwa difabel
adalah termasuk kaum yang termarjinal.4
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “marginal”
diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan batas (tepi). Sedang kata
“marginalisasi” diartikan sebagai pembatas. Jadi, kata marginal dapat
didefinisikan sebagai yang berkaitan dengan batas atau pembatasan.5
Sedangkan dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, Istilah
“marginal” memiliki dua makna, yaitu, pertama, suatu kelompok yang
terasimilasi tidak sempurna. Kedua, suatu kelompok yang terdiri dari
orang-orang yang memiliki kedudukan rendah.6
4 http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-dan-unesco-perhatikan-kaum-marjinal/19033 5 Depdikbud, Marginal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 14 6 Kartasapoetra dan Hartini, Kamus Sosiologi dan Kependudukan, (Jakarta:
Bumi Aksara,1992), hal. 244
23
Menurut istilah, marginal berarti adalah mereka yang tidak dapat
menyesuaikan dan melibatkan diri dalam proses pembangunan. Mereka
masih berjuang melawan penderitaan, kelaparan, ketidakadilan,
keterasingan dan diskriminasi.7 Pernyataan tersebut dengan kata lain
dapat dirumuskan, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai yang
memiliki budaya pinggiran yang ditempatkan di luar sistem, apabila
dikaitkan dan didasarkan pada perspektif pembangunan modern atau
budaya modern.
David Berry mengartikan marginal sebagai suatu situasi dimana
orang bercita- cita atau keinginan pindah dari kelompok sosial yang satu
ke kelompok sosial yang lain, akan tetapi ditolak keduanya. 8Secara
singkat, definisi ini menggambarkan permasalahan relasi sosial-budaya
yang ditanggung oleh kaum marginal. Sedangkan, Menurut Wini
Septriani, pengertian marginalisasi menunjukan kepada status seseorang
atau sekelompok orang yang berbeda kebudayaan.9
7 Y. Argo Trikromo, Pemulung Jalanan Yogyakarta: Konstruksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Budaya-Budaya Dominan (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999 ), hal.7 8 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995 ), h. 14
9 S. Wisni septiarti, Masyarakat kelompok Marginal dan Pendidikannya, dalam Cakrawala Pendidikan ,(Mei,1994), h. 11-12)
24
Media memiliki kontribusi penting dalam membantu pemenuhan
hak-hak kelompok marjinal maupun dalam melegitimasi bahkan memicu
tindakan diskriminasi terhadap mereka (Briant et al, 2011; Troshanovski,
2016; Gillespie et al, 2013). Peran media tersebut terwujud dalam bentuk
representasi.
Representasi menurut Hall dkk (1997) adalah penggunaan bahasa,
tanda, dan citra untuk mengkomunikasikan atau merepresentasikan
pemahaman seseorang atas dunia kepada orang lain. Dengan cara inilah
dunia disederhanakan dan dikaitkan dengan konsep, sehingga dapat
dimengerti. Makna yang dihasilkan dari proses inilah yang membentuk
berbagai pedoman praktik sosial. Melalui representasi media, isu dan
kelompok marginal dapat dipelajari secara sosial.
B. Media dan Disabilitas
Representasi penyandang disabilitas di media kerap berhadapan
dengan dua masalah yaitu; underrepresentation dan misrepresentation.
Representasi kehadiran disabilitas di media sangat sedikit
(underrepresented). Namun kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja
namun juga terjadi di negara-negara lain, sehingga menjauhkan kita dari
25
realitas kehidupan penyandang disabilitas. Misalnya dalam drama TV di
Jepang, karakter difabel hanya berjumlah 1,7%.10
Selain masalah representasi yang sedikit, representasi disabilitas
yang muncul di media-media pun kerap keliru (misrepresented). Ada
penggambaran yang tidak tepat atau bahkan tidak adil pada penyandang
disabilitas yang berdampak pada posisi sosial mereka dan kebijakan
publik terkait pemenuhan hak mereka.
Isu disabilitas menurut Paul Hant diidentifikasikan dengan 10
jenis stereotype yang digambarkan oleh media: the disabled person as
pitiable or pathetic, an object of curiosity or violence, sinister or evil, the
super cripple, as atmosphere, laughable, his/her own worst enemy, as a
burden, as non-sexual, being unable to participate in daily life.11 Sama
juga halnya dengan penggambaran umum penyandang disabilitas juga
terdapat dalam laporan Disabling Imagery and the Media oleh The British
Council of Organisations of Disabled People yang mengidentifikasi
karakteristik umum stereotip media di Inggris terhadap kelompok
disabilitas. Karakteristik tersebut antara lain: 12
10 http://www.remotivi.or.id/amatan/503/Bolehkah-Saya-Menjumpai-Difabel-di-Media-dengan-Layak
11 Danica Pirls and Solzica Popovska, International Journal of Scientific Engineering and Research Media Mediated Disability: How to Avoid Stereotypes, University of Nis and University of Skopje, 2013
12 Colin Barnes, Disabling Imagery and The Media, The British Council of Organisations of Disabled People, 1992
26
1. Orang yang hidupnya menyedihkan dan patut dikasihani
2. Objek kekerasan
3. Orang yang kejam dan mengerikan
4. Orang yang misterius dan mengancam
5. Orang yang memiliki kekuatan super dan kekuatan ajaib
dibandingkan orang ‘normal’
6. Objek lelucon dan kekonyolan
7. Satu-satunya musuh dan musuh terburuk dari orang ‘norma’
8. Beban sosial bagi orang lain
9. Orang dengan kelainan seksual
10. Orang yang terasing dari masyarakat
Stereotype tersebut dapat ditemukan dalam berbagai program
siaran media Indonesia. Misalnya karakter pelawak Bolot yang menjadi
objek tertawaan (laughable) atau beban sosial (burden). Atau karakter
Cecep (diperankan Anjasmara) dalam “Wah Cantiknya” (SCTV, 2001)
yang selain menjadi objek tertawaan (laughable), dikasihani (pitiable),
dan dipandang aseksual. Dalam talkshow, selain kerap menjadi objek
rasa penasaran (misalnya dalam “Hitam Putih”, Trans 7), penggambaran
27
disabilitas paling dominan adalah sebagai objek inspirasi (misalnya
dalam “Kick Andy”, Metro TV).13
Pada contoh yang terakhir yang telah disebutkan diatas, ramai
yang menyetujui bahwa media sejauh ini sudah memberikan
penggambaran yang terbaik akan isu disabilitas dengan memunculkan
sosok penyandang disabilitas adalah sosok yang inspiratif. Padahal lebih
jauh daripada itu, dalam tayangan yang memunculkan para disabilitas
tersebut, mereka semata-mata hanya menjadi objek yaitu objek inspirasi.
Mereka hanya menjadi objek yang dikonstruksi seolah “mereka
mempunyai kekurangan namun kelebihannya adalah mereka tidak
menyerah”.
Stella Young yang merupakan seorang aktivis difabel dan
pelawak tunggal, menyebut hal itu sebagai inspiration
porn. Menurutnya, menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek
inspirasi secara terus menerus telah mendehumanisasi karena dimensi
hidupnya ditinggalkan. Sebab, mereka tidak hidup semata ditugaskan
untuk menginspirasi orang14.
13 http://www.remotivi.or.id/amatan/503/Bolehkah-Saya-Menjumpai-Difabel-di-
Media-dengan-Layak 14 Young, S. 2014. “I’m Not Your Inspiration, Thank You Very Much.” TED. Diakses 10 February 2015.
28
C. Difabel dan Disabilitas
Pengertian difabel yang dikemukakan oleh John C. Maxwell
adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang
sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk
melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal. Sedangkan
World Health Organization (WHO) mendefinisikan difabel adalah suatu
kehilangan dan ketidaknormalan baik itu yang bersifat fisiologis,
psikologis, maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis15.
Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan
fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat
menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan
efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu different ability
yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat
beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas,
Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat,
15 Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, ‘Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance‟ (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 20, 21
29
Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan
khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita
cacat.
Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas dari
beberapa sumber:
● Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006,
penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu
menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan
individu normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari
kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam
hal kemampuan fisik atau mentalnya.
● Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok
masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
● Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan
sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang
tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah
sosial.
30
● Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu
atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan
secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik;
penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
● Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau
sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak.16
Menurut Rahayu, terdapat empat asas yang dapat menjamin
kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus
dipenuhi, yaitu sebagai berikut:
1. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua
tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan.
16 Reefani, Nur Kholis, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, Yogyakarta:
Imperium, 2103, hal. 20
31
2. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan
semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu
lingkungan.
3. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu
lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi
semua orang termasuk disabilitas.
4. Asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan
masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan
dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan
orang lain.17
Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang
cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-
anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas
penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya,
kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam
ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud rehabilitasi meliputi
17 Rahayu, Sugi. Dewi, Utami dan Ahdiyana, Marita. 2013. Pelayanan Publik Bidang
Transportasi Bagi Difabel di Daerah Jogjakarta. hal. 13
32
rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan
rehabilitasi sosial.
Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang
cacat/disabilitas berhak memperoleh:
1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan
derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan
menikmati hasil-hasilnya
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan
sosial.
6. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan,
dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak
dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Berdasarkan hak-hak yang harus didapatkan oleh kaum difabel
sebagai kaum yang termarjinalkan, media menjadi corong utama dalam
mengkonstruksi isu supaya hak-hak mereka sebagai warga negara dapat
terpenuhi. Namun pemberitaan pada media kerap mengalami
underrepresentation dan misrepresentation atau dengan kata lain,
33
pemberitaan terkait isu difabel di Indonesia masih mengalami
diskriminasi dan stereotip baik dari segi jumlah media yang meliput
jumlah artikel tentang difabel maupun konten berita yang
menggambarkan mereka dengan label tertentu sehingga membuat mereka
menjadi kelompok yang termarjinalkan. Padahal mengingat angka jumlah
penyandang disabilitas di Indonesia kian banyak, seyogyanya mereka
juga mendapatkan porsi yang besar dalam pemberitaan di media
manapun.
D. Perubahan Paradigma Disabilitas
Pergeseran paradigma dalam memaknai disabilitas perlu terus
digulirkan seiring dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang
bertumpu pada penguatan dasar hak asasi manusia. Dengan bergulirnya
semangat reformasi dan demokratisasi pada dasar hak asasi manusia
(HAM) ini, penyandang disabilitas pada hakikatnya adalah makhluk
sosial yang memiliki potensi, sehingga berpeluang untuk berkontribusi
dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat. Pernyataan tersebut terungkap dalam
Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Penyandang Disabilitas
yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI, 2015). Hal ini menunjukkan adanya perhatian dan good will
34
terhadap penyandang disabilitas untuk melibatkan mereka dalam berbagai
sektor dan bidang kehidupan.
Sejalan dengan hal tersebut, istilah yang digunakan untuk
menyebut orang dengan disabilitas pun mengalami perubahan dan
pergeseran dari masa ke masa seiring perkembangan kesadaran dan
pemahaman masyarakat terhadap isu persamaan dalam hak asasi manusia
(HAM) bagi orang dengan disabilitas. Istilah cacat menjadi dirasa kurang
pantas sehingga mengalami pergeseran menjadi “ketunaan”. Orang
dengan ketunaan pun kemudian menjadi kurang sopan sehingga muncul
istilah “disabilitas”.
Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948),
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), dan
Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), tidak
satu pun klausul kesetaraan yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas
sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas yang dirujuk
sebagai isu HAM dalam berbagai dokumen, hanya berkaitan dengan
jaminan sosial dan kebijakan kesehatan preventif. Baru pada tahun 1970-
an, dengan diundangkannya Deklarasi Orang dengan Keterbelakangan
Mental (1971) dan Deklarasi Hak-hak Penyandang Disabilitas (1975),
membuat penyandang disabilitas menjadi subyek dari deklarasi HAM.
Namun begitu, instrumen awal itu masih mencerminkan gagasan
35
disabilitas sebagai model medis. Model tersebut memandang penyandang
disabilitas sebagai orang dengan masalah medis, yang penanganannya
bergantung pada jaminan sosial dan kesejahteraan yang disediakan pada
setiap negara (Degener, 2000).
Dalam perkembangannya, pada tahun 2011, pandangan The
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
(WHO, 2011) mengenai disabilitas meliputi impairment, keterbatasan
aktivitas (activity limitations), dan hambatan partisipasi (participation
restriction). Dalam konteks ini, impairment meliputi masalah pada fungsi
atau struktur tubuh; keterbatasan aktivitas ditujukan pada kesulitan dalam
melaksanakan tugas atau melakukan aksi; dan hambatan partisipasi yaitu
bahwa orang dengan disabilitas mengalami masalah dalam keterlibatan di
masyarakat atau situasi kehidupannya. Dengan demikian, orang dengan
disabilitas tidak lagi dipandang sebagai orang yang bermasalah, akan
tetapi lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan
akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakatnya (Rioux &
Carbert, 2003).
Rioux & Carbert (2003) menyebutkan seiring dengan semakin
banyaknya perhatian dunia internasional bagi para penyandang disabilitas
ini, semakin banyak pula komitmen yang dicurahkan oleh berbagai pihak
internasional berkaitan dengan hak asasi manusia para penyandang
36
disabilitas. Komitmen-komitmen tersebut didorong oleh perubahan
paradigma di dunia internasional. Salah satunya adalah dengan secara
formal disebutkan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(ECOSOC) (1994), mengingat International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR) menyebutkan:
“… since the Covenant's provisions apply fully to all members of society, persons with disabilities are clearly entitled to the full range of rights recognized in the Covenant. In addition, insofar as special treatment is necessary, States parties are required to take appropriate measures, to the maximum extent of their available resources, to enable such persons to seek to overcome any disadvantages, in terms of the enjoyment of the rights specified in the Covenant, flowing from their disability. Moreover, the requirement contained in article 2 of the Covenant that the rights 'enunciated ¼ will be exercised without discrimination of any kind' based on certain specified grounds 'or other status' clearly applies to discrimination on the grounds of disability”.
Komitmen-komitmen lain yang telah dilakukan negara-negara di
dunia dalam penelitian Quinn & Degener (2002) menemukan ada 39
negara yang telah melembagakan dan menelurkan kebijakan non
diskriminatif atau kesamaan kesempatan dalam konteks disabilitas. Rioux
& Carbert (2003) menyebutkan dalam penelitiannya rangkuman berbagai
gerakan di dunia internasional yang mendorong terwujudnya kesamaan
akses bagi para penyandang disabilitas, seperti World Programme of
Action Concerning Disabled Persons, 1982; The UN Standard Rules on
the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, 1994;
37
Resolutions of the United Nations Commission on Human Rights;
Regional Agreements and Declarations; Disabled Persons International
(DPI) Sapporo Declaration, 2002; International Norms and Standards
Relating to Disability.
Pemerintah Indonesia sendiri mengatur dan melindungi
penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non-fisik untuk penyandang
disabilitas relatif sangat terbatas, sehingga menyulitkan mereka untuk
bisa melakukan kegiatannya secara mandiri (PPUA Penca, 2015). Sejalan
dengan hal tersebut, berbagai macam hambatan dialami oleh penyandang
disabilitas, antara lain adalah hambatan-hambatan sebagai berikut:
1. Inadequate policies & standards: Kebijakan/aturan yang dibuat
sering tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas,
misal kebijakan pendidikan, pekerjaan.
38
2. Negative attitudes: Sikap negatif dan prejudice menghambat bidang
pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan dan partisipasi sosial.
3. Lack of provision of services: Terutama pada pelayanan kesehatan,
rehabilitasi, dan support & assistance.
4. Problems with service delivery: Karena kurangnya koordinasi, staf
tidak mencukupi, kompetensi kurang.
5. Inadequate funding: Sumber-sumber dana yang dialokasikan untuk
mengimplementasikan kebijakan tidak mencukupi.
6. Lack of accessibility: Bangunan publik, sistem transportasi dan
informasi tidak aksesibel.
7. Lack of consultation & involvement: Penyandang disabilitas sering
tidak ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8. Lack of data & evidence: Kurangnya data tentang disabilitas dan
bukti efektivitas program mempengaruhi program aksi selanjutnya.
Dengan berbagai macam hambatan yang diterima dan dihadapi
oleh penyandang disabilitas, maka keberadaan mereka seringkali
terpinggirkan dan berada pada posisi tidak beruntung, sehingga kondisi
mereka semakin terpinggirkan dari interaksi sosial dan penerimaan
dalam masyarakat.
Berdasarkan situasi tersebut, maka permasalahan yang dihadapi
penyandang disabilitas pun mulai bergeser. Semula disabilitas
39
dipandang sebagai permasalahan dalam konteks individu kemudian
bergeser menjadi isu sosial sehingga terjadi pergeseran paradigma
disabilitas, dimana semula berupaya untuk menghilangkan atau
meminimalisir malfunction yang dialami oleh individu, kemudian
menjadi upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir hambatan
dalam masyarakat18.
Berbagai bentuk pergeseran dan berbagai perubahan perspektif
masyarakat dalam hal memandang disabilitas dapat dirangkum dalam
tabel di bawah ini:
Tabel 1. Pergeseran Paradigma Dalam Memandang Disabilitas
18 Santoso, Meilanny dan Nurliana C. 2017. “Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas”, Jurnal Of International Studies, edisi 1(2), hal. 166-176
Paradigma Lama Paradigma baru
Isu Disabilitas Isu individual
Malfunction
Isu sosial
Hambatan dalam masyarakat
Pendekatan Layanan langsung
Kuratif
Mengubah disabled
Perubahan sosial
Promotif dan preventif Mengubah
masyarakat
Pelayanan Spesialistik Umum dan spesifik
40
Sumber: Dewi, 2017 dari berbagai sumber
E. Isu Disabilitas di Media
Media memiliki peran untuk membentuk makna tentang
disabilitas di mata masyarakat. Sejak berkembangnya jurnalisme online,
media di Indonesia merumuskan kembali dan mencari model baru dalam
menyampaikan berita. Selain lahirnya banyak situs-situs berita internet,
kini surat kabar, majalah, radio, bahkan televisi juga melakukan
konvergensi dengan membuat media versi online. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri bagi industri media massa dalam menjalankan
fungsinya sebagai pers tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Isu disabilitas pada media massa memang sangat terlihat minim,
hal ini menyebabkan pengetahuan masyarakat atau bahkan penyandang
disabilitas itu sendiri jadi minim informasi dan pengetahuan. Di
Indonesia, tugas, fungsi, dan tanggung jawab pers diatur dalam UU No.
40 Tahun 1999 Tentang Pers. Fungsi media massa menurut UU No. 40
/1999 adalah: (1) memberikan informasi (to inform), (2) mendidik (to
educate), (3) menghibur (to entertain), dan (4) pengawasan social (social
control).
Oleh professional Oleh masyarakat dan professional
Rehabilitasi Perbaikan fungsi Pemecahan hambatan sosial
41
Media-media yang di Indonesia tentu tak lepas dari fungsi ini,
dengan catatan memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan
melakukan kontrol sosial. Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, perlu
memiliki kesadaran (Awareness) dan pengetahuan (Knowledge)
mengenai dunia disabilitas agar dapat mendukung, memberikan informasi
yang lebih proporsional, dalam rangka menciptakan kemanusiaan inklusif
dan setara.
Kesadaran dan pengetahuan itu menyangkut pemahaman tentang
jenis-jenis disabilitas (tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan
tunarungu/wicara) serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan
keterbatasan dan pelayanan (hak) yang mereka butuhkan. Termasuk
pengetahuan tentang peraturan perundangan dan kondisi-kondisi
perbandingan, baik di dalam maupun luar negeri.
Setidaknya, terdapat tiga hal yang patut diperhatikan dalam
mengawal isu disabilitas pada media massa, yaitu:
1. Aksesibilitas
Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Disabilitas Pasal 1 ayat 4 menyatakan “Aksesibilitas‟ adalah
kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupan. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 10 ayat 2
42
dimana penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan
keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas
dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
Undang undang tersebut dimaksudkan dengan tujuan berusaha
mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan
dan penghidupan penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya
hidup bermasyarakat. Tujuannya dengan adanya Undang-Undang ini
memberikan kemudahan kemudahan aksesibilitas yang menjamin
para penyandang disabilitas, diantaranya dengan adanya fasilitas
ramah difabel berupa alat transportasi, sarana pendidikan, lapangan
kerja, maupun tempat rekreasi ataupun ruang terbuka publik yang
dapat mereka manfaatkan dengan nyaman.
2. Inklusivitas
Kesadaran para aktivis disabilitas mengenai berbagai fakta
diskriminasi terhadap difabel membuat mereka berpikir bahwa
masalah ini sebagai persoalan sosial yang menyangkut sistem
ekonomi, kebijakan, prioritas distribusi sumber daya, kemiskinan,
pengangguran, sistem pelayanan medis.19 Semua diaktori oleh kaum
difabel sendiri, para pembuat kebijakan, pengacara, politikus, pelaku
19Bahrul Fuad Masduqi, “Kecacatan: Dari Tragedi Personal menuju Gerakan Sosial”, Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel, edisi 65, hal. 26.
43
ekonomi, masyarakat umum, jurnalis, aktor film, dan elemen
masyarakat lain. Oleh karena itu, fakta ini didekati para aktivis
difabilitas dengan mempertimbangan pendekatan sosial. Sebab,
pendekatan sosial lebih menekankan advokasi marginal menuju arus
utama. Artinya, difabel dan “orang normal” berada pada kondisi
setara.
Namun bila dikaji lebih jauh dan tidak bermaksud
menyederhanakan isu, masalah mendasar yang dihadapi kaum
difabel sebenarnya menunjuk pada rendahnya pengakuan atau
penerimaan masyarakat terhadap keberadaan difabel sebagai bagian
kehidupan masyarakat secara setara. Oleh karena itu, para aktivis
difabel meletakkan tujuan gerakannya pada terciptanya masyarakat
inklusif.
Masyarakat inklusif merupakan sebuah tatanan di mana semua
elemen masyarakatnya memiliki kesempatan setara untuk
berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan
suku, ras, agama, dan perbedaan bentuk fisik. Maka dengan
terwujudnya tatanan tersebut, para difabel bisa memberikan
sumbangsih dengan berbagai karya yang dapat dilakukan, baik hal
kecil maupun besar. Bahkan, mereka bisa memperoleh penghargaan
44
yang tinggi atas apa yang dilakukannya, contohnya Rainy M.P.
Hutabarat, difabel pendengaran.20
Helen Lok memposisikan masyarakat inklusif sebagai
masyarakat yang bertumpu sekaligus bergantung pada adanya
kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan hak dan
kewajiban mereka dengan seimbang.21 Lok mendasarkan
argumentasi pemikiran pada adanya masyarakat yang melindungi
hak-hak individual. Hal ini dinyatakan dalam bentuk munculnya
akses pertanggungjawaban dari para pemimpinnya yang dapat
meningkatkan ketahanan sosial, politik, ekonomi seluruh warga
negara serta memperbolehkan berkepentingan dalam dialog terbuka
bagi kestabilan pembangunan dalam hal prioritas dan nilai-nilai
pembangunan.
Sebenarnya, masyarakat inklusif tidak hanya mensyaratkan
keterbukaan dengan menerima perbedaan saja melainkan ada empat
nilai yang harus dipenuhi dan operasionalisasi secara simultan dan
seimbang dalam masyarakat. Empat nilai tersebut menunjuk pada
pluralisme atau keberagaman, kesetaraan, martabat, dan partisipasi
20 Donny Anggoro. Rainy MP. Hutabarat: Kita harus Dua Kali Lebih Dari Yang
Lain. Jurnal Perempuan edisi 69, hal. 147 21Helen Lok, “Individu Pembaharu dan Masyarakat Terbuka” dalam Muhammad Hidayat Rahz (eds.), Menuju Masyarakat Terbuka, (Yogyakarta: Ashoka Indonesia-Insist, 1999), hal. 4.
45
aktif.22 Kesetaraan membuat orang mampu menyadari bahwa tidak
seorangpun individu boleh diperlakukan lebih tinggi atau rendah
secara hukum dan sosial dalam masyarakat dengan demikian semua
orang memiliki kesempatan yang sama dalam banyak hal. Martabat
seseorang harus dihargai dalam relasi yang dibangun. Partisipasi
aktif mensyaratkan adanya kesetaraan keterlibatan dan berkontribusi
dalam aktivitas sosial dalam masyarakat guna tercapainya harapan
dan cita-cita yang dibangun bersama.
3. Rehabilitasi
Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang
cacat pasal 1 menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan proses
refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan
penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar dalam kehidupan masyarakat. Pengertian tersebut
menekankan pada pemulihan fungsi sosial dan pengembangnnya
agar seseorang yang mengalami kecacatan dapat menjalani
kehidupannya di masyarakat secara mandiri.
Penjelasan lain menurut Sunaryo (1995:108), rehabilitasi
adalah suatu proses, produk, atau program yang sengaja disusun
22 Bahrul Fuad Masduqi, “Kecacatan: Dari Tragedi Personal menuju Gerakan
Sosial”, Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel, edisi 65, hal. 28.
46
agar orang- orang yang cacat dapat mengembangkan dan
memfungsikan potensinya seoptimal mungkin. Sejalan dengan
pendapat tersebut, Agung Yuwono (dalam Yusuf, 1996:136) yang
menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan rangkaian usaha
berproses yang mencakup berbagai bidang yang dilakukan oleh
suatu tim dari berbagai keahlian. Penjelasan tersebut menunjukkan
bahwa rehabilitasi merupakan sesuatu yang diupayakan dan
direncanakan melalui program-program yang tepat untuk
mengembangkan potensi seorang penyandang disabilitas.
Rehabilitasi mencakup berbagai bidang layanan sehingga
memerlukan kolaborasi dari berbagai bidang keahlian. Oleh karena
itu, melaksanakan rehabilitasi memerlukan perencanaan dan proses
berkelanjutan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Tujuan rehabilitasi diantaranya memperbaiki dan
memungkinkan individu yang mengalami kecacatan dapat
mencukupi kehidupannya sendiri sebisa mungkin. Bitter
mengemukakan (dalam Higgins, 1985:26) “... the goal of
rehabilitation is to restore or to enable individuals who have
become impaired in some way to become as self-sufficient as
possible. Konsep ini berkaitan dengan kemandirian yang sebisa
mungkin dicapai setelah seseorang menjalani proses rehabilitasi.
47
Pendapat lebih luas dikemukakan oleh Sunaryo (1995:111) bahwa
program rehabilitasi memiliki tujuan agar individu atau penyandang
cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial.
Kemandirian yang dimaksud berupa kemampuan mengurangi
ketergantungan terhadap orang lain dan keseimbangan sikap antara
apa yang masih dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat
dilakukannya.
Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Nomor 4
tahun 1997 tentang Penyandang cacat pasal 18 ayat 2, rehabilitasi
meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.
Keempat jenis rehabilitasi tersebut saling berkaitan satu sama lain.
Munawir Yusuf (1996,136-137) menjabarkan ruang lingkup
keempat jenis rehabilitasi tersebut.
1) Rehabilitasi medic
Lingkup layanan rehabilitasi medik antara lain:
a. mencegah terjadinya kecacatan permanen
b. memberikan bantuan bagi yang masih dalam kesakitan
(perawatan pasca operasi, dan sebagainya)
c. bantuan alat bantu fungsi fisik, seperti kruk, kacamata, alat
bantu lengan, dan sebagainya).
48
2) Rehabilitasi sosial
Lingkup layanan rehabilitasi sosial meliputi. usaha
pengembalian fungsi dan peran sosial yang hilang atau tidak
dimiliki sebelumnya;
a. pemberian bimbingan sosial untuk mencapai kesejahteraan
sosial
b. memberikan penyuluhan sosial kepada keluarga dan
masyarakat sekitar tempat tinggal klien
3) Rehabilitasi Pendidikan
Lingkup layanan rehabilitasi sosial meliputi:
a. pemberian layanan pendidikan formal di sekolah maupun
panti
b. pendidikan di masyarakat, misalnya pendidikan
keterampilan dan kebutuhan praktis masyarakat
c. Pendidikan keluarga dan pemberian beasiswa
4) Rehabilitasi Karya/Vokasional
Lingkup layanan rehabilitasi karya meliputi pelatihan-
pelatihan dan penempatan kerja. Hal ini dapat dilakukan
melalui sistem magang, atau dipersiapkan melalui latihan
formal di lembaga pelatihan kerja. Purwaka Hadi (2005:252),
rehabilitasi vokasional bertujuan melatih individu agar
49
memiliki keahlian yang memadai sebagai bekal bekerja dan
bermata pencaharian sehingga dapat hidup mandiri.
Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu rehabilitasi
perlu dibuat program-program rehabilitasi yang sesuai dengan
potensi dan memungkinkan tercapainya kemandirian dan
kesejahteraan klien. Sunaryo (1995:121) menjabarkan program
rehabilitasi sebagai suatu proses dalam kegiatan rehabilitasi
yang saling berkaitan mulai dari kegiatan administrasi,
ketenagaan, proses rehabilitasi dan penyaluran. Program-
program tersebut diantaranya:
a. Program terapi fisik, bertujuan mengembangkan kekuatan,
koordinasi, keseimbangan, dan belajar menggunakan alat
bantu
b. Program vokasional, bertujuan mempersiapkan klien
menjadi individu yang produktif dan mampu bekerja.
c. Program psikologis, bertujuan meningkatkan kemampuan
dan kebutuhan individual serta memberikan layanan
konseling dan psikoterapi.
d. Program pelayanan sosial, bertujuan mendorong
partisipasi keluarga dan membantu mengatasi problem
pribadi maupun problem sosial.
50
e. Program pendidikan dan latihan, bertujuan
mengembangkan keterampilan intelektual, sosial, dan
mengurus diri sendiri serta program remedial bagi yang
mengalami kesulitan belajar.
f. Program orientasi dan mobilitas, bertujuan
mengembangkan keterampilan orientasi dan mobilitas
agar dapat bepergian, berjalan dengan aman dan lancar,
serta mengadakan hubungan sosial dengan baik.
F. Produksi Isu Disabilitas dalam Teori Strukturasi
Teori strukturasi merupakan hubungan antara pelaku (tindakan)
dan struktur berupa relasi dualitas. Dualitas terjadi dalam “praktik sosial”
yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Priyono,
2002:22).
Teori ini yang mengintegrasikan antara agen dan struktur.
Giddens mengatakan bahwa setiap riset dalam ilmu sosial atau sejarah
selalu menyangkut penghubungan tindakan (seringkali disinonimkan
dengan agen) dengan struktur. Namun dalam hal ini tak berarti bahwa
struktur menentukan tindakan atau sebaliknya (Ritzer dan Douglas,
2004:507).
51
Anthony Giddens merupakan sosiolog kontemporer asal Britania
Raya yang lahir pada 18 Januari 1939. Giddens mempunyai pengaruh
yang besar pada pertumbuhan teori sosiologi sepanjang lebih dari 2
dekade yang secara teoritis memberi pengaruh besar di Amerika dan
seluruh dunia. Dia menimba ilmu di Universitas Hull, di the London
School Economics, serta di Universitas London. Tahun 1961 ia menjadi
dosen di universitas Leicester. Karya-karya awal mulanya bersifat empiris
serta memusatkan perhatian pada permasalahan bunuh diri. Tahun 1969,
dia pindah jabatan jadi dosen sosiologi di Universitas Cambridge serta
menjadi anggota King’ s College. Salah satu teori yang sangat terkemuka
yang dipelopori oleh Anthony Giddens ialah teori strukturasi dengan
pemikirannya yang menyeluruh tentang kehidupan masyarakat modern.
Dalam teori strukturasi, terdapat dua kata kunci yang menjadi
fokus ulasan dalam teori ini ialah“ struktur” serta“ agensi”. Dia
membangun teorinya sendiri dengan proses panjang lewat kritik serta
sintesis. Giddens memusatkan perhatiannya pada upaya untuk
merekonstruksi secara radikal teori sosial, sebab teori yang yang
berkembang pada saat itu dipandang tidak mampu untuk memahami
masyarakat modern serta segala praktik sosial didalamnya. Dia
mengkritik teori sosial klasik, mengambil hal- hal yang bermanfaat
52
darinya untuk membangun teori baru serta membuang yang dianggapnya
tidak relevan23.
Di samping merevisi uraian terhadap sosiologi yang semula sama
modelnya seperti ilmu alam, Giddens pula memperbaharui pendekatan
dalam Mengulas perkara‘ struktur’ serta ‘agensi’. Giddens melihat hal
yang semulanya sebagai hubungan dualisme dengan pendekatan dualitas
, keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama. Pemikiran Giddens
menjadi jalan tengah bagi pertentangan teori sosial klasik, Giddens juga
menawarkan jalur tengah dalam melihat kehidupan sosial modern.
Gidens memahami “ struktur” merupakan“ rules and resources”
yang dipakai pada produksi serta reproduksi sistem. Sebaliknya“ agensi”
merupakan orang. Seluruh suatu tidak bisa jadi terjalin melalui intervensi
orang. Giddens adalah orang pertama yang berhasil menciptakan teori
yang dapat menghubungkan struktur dan agensi dalam melihat praktik
sosial masyarakat modern. Teori tersebut dikenal sebagai “Teori
Strukturasi”.
Dalam teori ini, struktur serta agensi tidak dilihat sebagai dua hal
yang terpisah, sebab bila demikian timbul dualisme struktur- agensi. Bagi
Giddens, harus dilihat sebagai (duality), dua sisi mata uang yang sama.
23 Firman, Abdul. 2006. “Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Gidden Sebagai Alternatif”, Jurnal Sosiohumaniora, edisi 8, hal.205-218
53
hubungan antara keduanya adalah hubungan dialektik, dengan kata lain
struktur dan agensi saling memberikan pengaruh antara keduanya yang
berlangsung secara berkelanjutan tanpa henti. Teori Strukturasi Giddens
didasarkan pada premis;
“[….] the constitution of agents and structures are not two independently given sets of phenomena, a dualism, but represent a duality…the structural properties of social systems are both medium and outcome of the practices they recursively organize…the moment of the production of action is also one of reproduction in the contexts of the day-to-day enactment of social life”.
Struktur memberi pengaruh pada agensi dalam 2 makna:
memampukan (enabling) serta membatasi (constraining).
Terbentuknya pertentangan dalam penafsiran struktur ini dikarenakan
Giddens memandang struktur ialah hasil (out come) sekaligus fasilitas
(medium) dari praktik sosial. Serta tidaklah keseluruhan indikasi,
bukan kode tersembunyi seperti yang terdapat dalam strukturalisme,
serta bukan pula kerangka keterkaitan bagian-bagian dari sesuatu
keseluruhan seperti yang dipahami para fungsionalis. Dalam
penafsiran Giddens, agensi bisa meninggalkan struktur, dia tidak
senantiasa tunduk pada struktur. Dia bisa mencari peluang ataupun
keluar dari peraturan serta berbagai ketetapan yang ada (dialectic of
control). Agensi bisa melawan struktur yang berbentuk kontrol.
54
“The more tightly- knit and inflexible the resmi relations of authority within an organization, in fact, the more the possible openings for circumventing them”.
Dengan demikian dalam teori strukturasi yang jadi pusat atensi
bukanlah struktur, juga bukan pula agensi, melainkan apa yang oleh
Giddens disebut “social practices” Memang kita tidak boleh
melupakan struktur serta agensi, sepatutnya kita harus mampu
memahami lebih rinci tentang agen dan struktur. Tetapi fokus utama
wajib diletakkan pada social practice, bagaimana manusia- manusia
menempuh hidup setiap hari, baik dalam hubungannya dengan anak-
istri/ suami, teman, ataupun dengan birokrat, pelayan bank, serta lain-
lain24.
Menurut Giddens, ambisi utama yang ia ingin lakukan adalah
mengajukan teori strukturasi dalam ilmu-ilmu sosial ialah bukan pada
praktek sosial yang dilakukan pada kaitan dalam ruang dan waktu.
Lebih lanjut Giddens mengatakan: “Human social activities, like some self- reproducing items in nature, are recursive. That is to say, they are not brought into being by social actors but continually recreated them by them via the very means whereby they express themselves as actors. In and through their activities agents reproduce the conditions that make these activities possible”.
Anthony Giddens merombak pemikiran ilmu sosial dengan
memperhatikan masalah ruang dan waktu bukan sebagai “arena dimana
24 Ibid
55
manusia bertindak’, tetapi dalam suatu unsur konstitutif dari tindakan
dan pengorganisasian masyarakat. Dan untuk itu maka unsur waktu dan
ruang menjadi unsur konstitutif dari tindakan dan pengorganisasian
masyarakat25.
Menurut Barker (2011) Strukturasi mengandung tiga dimensi,
yaitu sebagai berikut: Pertama, pemahaman (interpretation /
understanding), yaitu menyatakan cara agen memahami
sesuatu. Kedua, moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara
bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. Ketiga, Kekuasaan dalam
bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan
Kasus yang mendukung konsepsi subjek sebagai agen aktif dan
mengetahui banyak hal secara konsisten telah dikemukakan Gidden.
Giddens mengambil pandangan Garfinkel (1967), berpendapat bahwa
tatanan sosial dibangun di dalam dan melalui aktivitas sehari-hari dan
memberikan penjelasan tentang aktor atau anggota masyarakat yang ahli
dan berpengalaman. Sumber daya yang diambil oleh sang aktor, dan
dibangun olehnya adalah karakter sosial, struktur sosial (atau pola
aktivitas teratur)26.
25 Haryanto, Ignatius. 2014. “Kemunculan Diri Dan Peran Pemilik Industri Media Di Indonesia Dalam Kerangka Teori Strukturasi Anthony Giddens”, Jurnal Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), edisi 6(2), hal. 60-71 26 https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/
56
G. Kerangka Teori
Media (Tempo.co) Konstruksi Isu disabilitas yang cenderng hegemonik
Dikemas dengan gaya yang lebih menarik dan muncul topik baru seperti:
Pendidikan
Tips dan trik
Gaya hidup
Kesehatan
Aktivitas
Dan lain-lain
Bagaimana Tempo.co melakukan konstruksi pada Rubrik Disabilitas? Seperti apa hasilnya?
57
BAB III
GAMBARAN UMUM MEDIA ONLINE TEMPO.CO
A. Sejarah dan Perkembangan Tempo.co
Tempo adalah majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya
meliput berita dan politik. Tempo merupakan majalah pertama yang tidak
memiliki afiliasi dengan pemerintah. Edisi pertama Tempo diterbitkan
pada 6 Maret 1971 dengan Goenawan Mohamad sebagai Pemimpin
Redaksi. Terbitnya Tempo tersebut tidak bisa lepas dari peran Harjoko
Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, dan Bur Rasuanto yang kemudian
dianggap sebagai pendiri.
Majalah ini pernah dilarang oleh pemerintah pada tahun 1982 dan
21 Juni 1994 dan kembali beredar pada 6 Oktober 1998. Tempo juga
menerbitkan majalah edisi bahasa Inggris sejak 12 September 2000 yang
bernama Tempo English Edition dan pada 2 April 2001 Tempo juga
menerbitkan Koran Tempo.
Pelarangan terbit Majalah Tempo pada 1994 (bersama dengan
Majalah Editor dan Tabloid Detik, tidak pernah jelas penyebabnya. Tapi
banyak orang yakin bahwa Menteri Penerangan saat itu, Harmoko,
mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Tempo karena
laporan majalah ini tentang impor kapal perang dari Jerman. Laporan ini
dianggap membahayakan "stabilitas Negara". Laporan utama membahas
58
keberatan pihak militer terhadap impor oleh Menristek BJ Habibie.
Sekelompok wartawan yang kecewa pada sikap Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) yang menyetujui pembredelan Tempo, Editor, dan
Detik, kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).27
Awalnya portal berita Tempo.Co ini lahir dengan nama Tempo
Interaktif (www.tempointeraktif.com). Portal merupakan pionir portal
berita, sejak 1995 hadir menjawab kebutuhan itu yang mampu
menyajikan informasi yang “enak dibaca dan bisa dipercaya”.
Dalam perjalanannya, portal Tempo Interaktif, banyak mengalami
pembenahan. Pada 2008, Tempo Interaktif tampil dengan wajah baru dan
sajian berita yang berkualitas. Sepanjang 2009 dan 2010, Tempo
Interaktif telah berkembang lebih jauh. Dari sisi jumlah berita yang
ditampilkan, misalnya, kini rata-rata jumlahnya sehari telah mencapai 300
berita. Jumlah pengunjung pun meningkat pesat.
Catatan Google Analytics menyebutkan bahwa sepanjang 2010
terjadi peningkatan jumlah pengunjung Tempo Interaktif sebesar 190
persen, yaitu dari rata-rata 1 juta pengunjung naik menjadi 3,5 juta
pengunjung per bulan. Sementara itu, jumlah halaman yang dibuka oleh
satu pengunjung juga mengalami peningkatan menjadi 11 juta halaman
27 Dokumentasi resmi Tempo.co
59
per bulan. Yang menarik pendapatan iklan Tempo Interaktif pada 2010
ikut mengalami peningkatan sebesar 26%.
Seiring dengan meningkatnya tren akses mobile, Tempo Interaktif
kini juga telah mengembangkan aplikasi yang bisa diakses via telepon
seluler, BlackBerry, iPhone, iPad, dan tablet Android. Jumlah pengakses
Tempo Interaktif via mobile meningkat lebih dari 500 persen. Tempo
Interaktif juga mengembangkan aplikasi iPad dan Android untuk majalah-
majalah Grup Tempo, seperti Tempo, Tempo Edisi Bahasa Inggris, dan
produk Tempo lainnya.
Di kuartal akhir 2011, manajemen Tempo setuju untuk mengubah
nama portal TEMPO Interaktif menjadi Tempo.Co. Langkah perubahan
ini merupakan bagian dari upaya Tempo meningkatkan kualitas dan
menyempurnakan sajian produk. Lebih dari itu, pengubahan ini juga
mengindikasikan langkah serius Tempo untuk mengembangkan sebuah
produk media yang mampu mencerdaskan pembacanya. Pengubahan
nama portal menjadi Tempo.Co ini, sekaligus menandai bahwa Tempo
Media memulai langkah untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai
konvergensi media. Memadukan semua bentuk media. Semua
peningkatan itu adalah hasil kerja keras semua lini. Namun perjuangan
untuk mencapai penyempurnaan tak pernah berhenti.
60
Tempo.co menjadi trendsetter berita online sejak diluncurkan 23
November 2011 menggantikan situs berita Tempo Interaktif. Setiap bulan
jumlah pengunjungnya terus meningkat. Rata-rata setiap bulan situs ini
dikunjungi oleh 11 juta orang. Begitu pula dengan peningkatan jumlah
halaman yang rata-rata dikunjungi sekitar 55 juta per bulan. Peningkatan
itu terjadi berkat inovasi konten yang terus dilakukan, diantaranya dengan
menambahkan tampilan audio dan video dan disajikan infografik yang
memikat.28
B. Rubrik difabel di Tempo.co
Tempo merupakan media online pertama yang meluncurkan
rubrik difabel di kanal pemberitaannya. Sejarah awal terbentuknya rubrik
difabel ini adalah bermula adanya salah satu wartawan tempo yang
bernama Cheta Nilawati yang mengalami disabilitas. Cheta Nilawati telah
bekerja di tempo selama 14 tahun. Mulanya, Cheta bukanlah orang
dengan disabilitas. Karena penyakit diabetes yang dialaminya, ia
kehilangan penglihatan pada tahun 2016 atau di tahun ke-10 ia menjadi
wartawan Tempo dan kemudian menjadi tunanetra. Setelah Cheta
menjadi tunanetra, ia kemudian banyak menulis menulis tentang apa
yang ia alami di media Indonesiana. Tempo.co kemudian menyadari jika
28 Koorporat Tempo.co
61
Cheta adalah aset yang berharga sehingga kemudian membuat channel
khusus rubrik difabel pada Senin tanggal 18 Juli 2018 dan secara resmi
dilaunching pada 21 Februari 2019.29.
Tujuan dibentuk rubrik difabel ini adalah untuk menampung,
menyampaikan aspirasi para penyandang disabilitas, serta untuk
mengingatkan lingkungan umum tentang keberadaan kelompok
disabilitas yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat
umumnya.
Setelah rubrik difabel terbentuk, secara struktural yang menjadi
reporter adalah Cheta nilawati dan kemudian editornya adalah Rini
Kustiani. Kehadiran Tempo.co dengan rubrik difabel ini diharapkan
dapat memberi ruang kepada penyandang disabilitas dan dapat
memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.
29 Wawancara dengan Rini Kustiani, Editor Rubrik Difabel Tempo.co pada Kamis,
20 Februari 2020.
62
BAB IV
DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Isu Disabilitas Pada Media Online Tempo.co
Isu disabilitas pada media online tempo.co dikategorikan kedalam
3 kategori isu, yaitu Aksesibilitas, Inklusifitas, dan Rehabilitas. Kategori
isu-isu tersebut pada rubrik difabel tempo.co dari bulan Agustus - Oktober
2019 terdapat 82 berita dapat dilihat pada gambar 4.1.
Gambar 4.1 Jumlah berita rubrik Difabel pada Tempo.co
Dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa berita tentang Inklusifitas
memiliki jumlah yang dominan selama bulan Agustus dan Oktober 2019
yaitu dengan 13 berita, namun pada bulan September memiliki penurunan
secara kuantitas menjadi 10 berita. Selanjutnya pemberitaan tentang
63
Aksesibilitas pada bulan Agustus dan September 2019 memiliki jumlah
yang sama yakni 12 berita, namun pada bulan Oktober mengalami
penurunan menjadi 11 berita. Sebaliknya, pemberitaan terkait
Rehabilitasi mengalami kenaikan setiap bulannya. Pada bulan Agustus,
rubrik difabel menerbitkan 1 berita tentang Rehabilitasi, selanjutnya pada
bulan September menjadi 4 berita dan bulan Oktober 2019 menjadi 6
berita. Dari gambar 4.1 menunjukkan persentase jumlah berita secara
keseluruhan yaitu dengan aspek Aksesibilitas sebanyak 35 berita atau
42%, Inklusivitas sebanyak 36 berita atau 43%, dan Rehabilitas sebanyak
11 berita atau 13%.
Penyajian isu disabilitas berdasarkan tiga aspek tersebut pada
rubrik Difabel memiliki jumlah yang berbeda-beda dalam pemberitaan.
Hal ini sangat dipengaruhi oleh isu atau kejadian yang berkaitan
disabilitas di lapangan. Dalam hal ini, Tempo.co mengkonfirmasi bahwa
setiap harinya berusaha menerbitkan satu berita pada rubrik Difabel ini.
1. Isu Aksesibilitas Periode Agustus – Oktober 2019
Isu aksesibilitas periode Agustus- Oktober 2019 pada rubrik
difabel tempo.co memuat sebanyak 35 berita. Isu Aksesibilitas ini tidak
hanya membicarakan satu aspek saja terkait pemenuhan akses bagi
disabilitas. Dalam hal ini, peneliti membagi menjadi lima aspek
pembahasan terhadap berita isu Aksesibilitas pada rubrik Difabel, yaitu;
64
1) Aksesibilitas Pekerjaan,
2) Aksesibilitas Ruang Publik,
3) Aksesibilitas Literasi dan Pendidikan,
4) Aksesibilitas Moda Transportasi, dan
5) Aksesibilitas Penunjang Teknologi.
Gambar 4.2. Aspek Isu Aksesibilitas Pada Rubrik Difabel
Berdasarkan Isu Aksesibilitas menurut 5 aspek tersebut terdapat
3 berita Aksesibilitas terkait pekerjaan, 14 berita terkait ruang publik, 3
berita Aksesibilitas literasi dan pendidikan, 10 berita Aksesibilitas moda
transportasi, dan 5 berita terkait teknologi penunjang (Lampiran 3).
a) Bingkai Pemberitaan Aksesibilitas Pekerjaan
3
14
3
10
5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
AksesibilitasPekerjaan
AksesibilitasRuang Publik
AksesibilitasLiterasi danPendidikan
AksesibilitasModa
Transportasi
AksesibilitasPenunjangTeknologi
65
Pada pemberitaan tentang aksesibilitas pekerjaan, tampak
bahwa framing pemberitaan Tempo menekankan pada keadilan kaum
Disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini terlihat pada
pemberitaan terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa
terjadinya diskriminasi serta pelanggaran hak-hak terhadap kaum
disabilitas dalam mengakses pekerjaan. Hal tersebut tampak dari
kutipan teks berikut :
“Dalam kasus dokter gigi Romi, dia mengikuti seleksi CPNS 2018. Pada Desember 2018, dia dinyatakan lulus dan menempati urutan pertama formasi dokter gigi di Puskesmas Talunan, Solok Selatan, Sumatera Barat. Namun, pada 18 Maret 2019, kelulusan dokter gigi Romi dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Badan Kepegawaian Negara. Alasannya, dokter gigi Romi dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, lantaran menggunakan kursi roda”(dikutip pada laman rubrik difabel Tempo.co tanggal 30 September 2019).
Makna yang dibangun tempo dalam teks kutipan diatas adalah
adanya tindakan diskriminasi yang dialami oleh para penyandang
disabilitas dalam mengakses pekerjaan sebagai contoh dokter gigi
Romi yang seharusnya lulus PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun
karena ia disabilitas, maka kelulusan tersebut dibatalkan.
Secara hukum, Indonesia telah mengatur UUD tentang hak
pekerjaan bagi kaum disabilitas. Namun, UUD tersebut kerap
66
dilanggar dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut.
Hal ini tercermin pada teks:
”Tiga pasal itu adalah Pasal 11, Pasal 53, dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. "Pembatalan kelulusan dokter gigi Romi termasuk tindakan penghalangan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak kerja yang layak," kata Maulani (dikutip pada laman rubrik difabel Tempo.co tanggal 30 September 2019).
Dari uraian teks diatas tampak bahwa tempo.co ingin
mengarahkan pembaca pada frame tentang aksesibilitas pekerjaan
dalam makna tertentu yaitu, aksesibilitas pekerjaan adalah salah satu
akses yang penting bagi disabilitas dalam memperoleh pekerjaan
karena pekerjaan adalah hak bagi semua masyarakat tak terkecuali
disabilitas yang seharusnya telah mendapatkan akses pekerjaan dalam
UUD nomor 8 tahun 2016, namun kerap terjadi pelanggaran UUD
pekerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut.
b) Bingkai Pemberitaan Aksesibilitas Ruang Publik
Mengenai framing pemberitaan aksesibilitas ruang publik,
tampak bahwa Tempo.co menekankan pada kesetaraan dalam
aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas lebih besar. Hal ini dapat
dilihat dari jumlah berita berdasarkan lima aspek aksesibilitas tersebut,
aksesibilitas ruang publik memiliki jumlah terbanyak dalam periode tiga
67
bulan dengan 14 berita atau sebanyak 40% dari keseluruhan berita.
Kesetaraan yang ingin dibangun Tempo.co dalam aksesibilitas ruang
publik tampak dalam pemberitaan tempo yang memberitakan peristiwa-
peristiwa aksesibilitas ruang publik yang sulit dan kurang ramah
terhadap disabilitas, bahkan kerap terjadi diskriminasi. Hal ini terlihat
dalam kutipan teks berikut :
“Seorang calon pengantin dari Massachusetts, Amerika Serikat, Alaina Leary misalnya, terpaksa melepaskan mimpi mengadakan pesta pernikahan di kastil karena tempatnya sulit diakses. "Terlalu banyak anak tangga, jalur yang berkelok-kelok, dan pengelola kastil tidak menerima permintaan fasilitas tambahan untuk tamu undangan," kata Alaina Leary, (dikutip dalam laman rubrik difabel Tempo.co Selasa,28 Agustus 2019) .
Makna yang dibangun Tempo.co dalam kutipan teks diatas
adalah terjadinya akses ruang publik yang kurang ramah terhadap
disabilitas, dimana Alaina Leary merupakan seorang penyandang
disabilitas. Tubuh bagian kanannya lunglai sehingga harus disangga
tongkat. Karena itu Leary memikirkan bagaimana aksesibilitas dia dan
para tamu di tempat resepsi pernikahannya. Namun pengelola kastil
tidak menerima permintaan fasilitas akses bagi disabilitas.
Diskriminasi lainnya terhadap aksesibilitas ruang publik bagi
disabilitas yang ditampilkan Tempo.co dalam hal ini dapat dilihat pada
kutipan teks berikut:
68
“Kuhu Das yang merupakan penyandang polio sejak lahir diminta mencopot rok yang menutupi penyangga kakinya ketika harus melewati alat pendeteksi metal. "Saya sudah menyampaikan kondisi saya kepada petugas bandara dan saya memang menggunakan alat bantu yang terbuat dari logam, Alat bantu yang dipasang di kaki Kuhu Das berfungsi membantunya berjalan. "Tapi petugas perempuan itu malah memanggil petugas yang lain dan mengancam saya," ujar Kuhu Das (dikutip pada rubrik difabel Tempo.co tanggal 25 Oktober 2019).
Tak hanya Kuhu Das yang mengalami diskriminasi, Jeeja Ghosh
juga mengalami hal yang sama. Seperti yang dikutip pada teks berikut :
“Aktivis penyandang disabilitas yang juga mengalami diskriminasi di Bandara Kalkutta, India, adalah Jeeja Ghosh. Penyandang disabilitas Celebral Palsy ini ditolak ketika meminta pendamping dan kursi roda selama penerbangan. Jeeja meminta pendamping karena keterbatasan mobilitas akibat Celebral Palsy”.
Makna yang dibangun Tempo.co dalam kutipan teks diatas adalah
para penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dalam
aksesibilitas ruang publik. Dimana tidak tersedianya akses dan
pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas.
Dari uraian diatas tampak bahwa Tempo.co ingin mengarahkan
pembaca pada frame tentang aksesibilitas ruang publik dalam makna
kesetaraan dan pemerataan aksesibilitas ruang publik bagi disabilitas.
Kesetaraan ini dimaksudkan agar tersedianya aksesibilitas dan
69
pelayanan yang baik bagi disabilitas dalam ruang publik. Karena
aksesibilitas terhadap ruang publik merupakan hak dan kebutuhan
semua kalangan masyarakat dalam kehidupan bersosial tak terkecuali
penyandang disabilitas.
c) Bingkai Pemberitaan Aksesibilitas Literasi dan Pendidikan
Untuk frame aksesibilitas literasi dan pendidikan, tampak
bahwa Tempo.co menekankan pada pemerataan akses literasi dan
pendidikan bagi disabilitas secara menyeluruh. Hal ini tampaknya
karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap
warga Negara. Tempo dalam hal ini membingkai isu disabilitas dengan
menyajikan pemberitaan pemenuhan aksesibilitas yang masih sangat
minim dan terbatas terhadap literasi dan pendidikan bagi penyandang
Disabilitas. Hal ini dapat terlihat dalam pemberitaan kutipan teks
berikut :
“Kendati akses literasi bagi difabel sudah tersedia, anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, Furqon Hidayat mengatakan ketersediaan bacaan edisi Braille atau audiobook masih terbatas. Bahan bacaan yang bisa mereka dapatnya cuma-cuma secara daring pun, menurut dia, terkadang formatnya tidak memungkinkan untuk dibaca menggunakan aplikasi pembaca layar ” Ujar Furqon (dikutip pada laman rubrik difabel Tempo.co tanggal 19 September 2019).
70
Makna yang dibangun Tempo.co berdasarkan kutipan teks
diatas adalah Tempo ingin memberikan kesadaran kepada pembaca
bahwasanya Aksesibilitas literasi dan pendidikan masih sangat minim
dan terbatas para penyandang disabilitas, dimana buku-buku bacaan
yang tersedia dalam bentuk Braile masih terbatas dan akses bagi
penyandang disabilitas masih sulit.
Dari uraian diatas tampak bahwa Tempo.co ingin mengarahkan
pembaca pada frame tentang aksesibilitas literasi dan pendidikan
dalam makna yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat penting
bagi setiap manusia, oleh karena itu pemenuhan literasi dan pendidikan
bagi disabilitas adalah menjadi wajib dilakukan.
d) Bingkai Pemberitaan Aksesibilitas Moda Transportasi
Untuk frame aksesibilitas moda transportasi, tampak bahwa
Tempo.co menekankan pada kesejahteraan dan kesetaraan dalam akses
transportasi bagi penyandang disabilitas lebih besar. Hal ini dapat dilihat
dari jumlah berita yang disajikan Tempo pada isu ini yaitu tercatat
sebanyak 10 berita atau 30% dari keseluruhan berita dari isu
aksesibilitas moda transportasi ini, artinya isu ini tak kalah penting
dalam pemenuhan hak dalam mengakses moda transportasi bagi
penyandang disabilitas sebagai masyarakat.
71
Hal ini tampaknya Tempo melihat bahwa transportasi
merupakan salah satu pendukung aktivitas masyarakat yang seharusnya
memberikan akses yang sama bagi semua warga tak terkecuali
penyandang disabilitas. Pada satu sisi, Tempo dalam hal ini
memperlihatkan bahwa moda transportasi yang tersedia bagi disabilitas
masih sangat minim dan kurang ramah terhadap disabilitas, dan juga
terlihat adanya pemberitaan Tempo terhadap peristiwa diskriminatif
yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam mengakses
transportasi. Seperti yang dialami oleh seorang penumpang disabilitas
pengguna kursi roda bernama Shinta Utami yang gagal terbang karena
menolak untuk menandatangani surat pernyataan sakit. Seperti yang
dikutip dalam teks pemberitaan sebagai berikut :
"Di situ, saya lagi-lagi disuruh menandatangani surat pernyataan sakit. Tapi saya tidak mau, Berkali-kali saya tegaskan kepada mereka bahwa saya adalah penyandang disabilitas, bukan penumpang yang sakit," kata Shinta kepada Tempo, Jumat 23 Agustus 2019.
“Atas penolakan tersebut, Shinta mengatakan petugas memintanya dan mendorong keluar pesawat. Tiga temannya juga turut keluar pesawat. "Sesampainya di bandara, tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak ada manager on duty, tidak ada pernyataan maaf, meskipun ada tawaran melakukan refund pengembalian uang tiket," kata Shinta”.
72
Makna yang dibangun oleh Tempo pada teks diatas adalah kurang
ramahnya pelayanan moda transportasi bagi penyandang disabilitas.
Dimana seorang penyandang disabilitas yang ingin menggunakan
transportasi seperti pesawat maka ia harus menandatangani surat
keterangan sakit. Hal ini merupakan tindakan pembeda atau kurangnya
kesetaraan bagi disabilitas dalam mengakses transportasi.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Tempo.co ingin
mengarahkan pembaca pada frame aksesibilitas moda transportasi pada
makna bahwa transportasi adalah hak semua warga, dimana akses untuk
pemenuhan dan kesetaraan bagi disabilitas harus disadari oleh
masyarakat dan penyedia moda transportasi, guna membentuk
masyarakat yang lebih sejahtera.
e) Bingkai Pemberitaan Aksesibilitas Penunjang Teknologi
Frame isu aksesibilitas penunjang teknologi, Tempo.co dalam
hal ini tampak menekankan pada penemuan penunjang teknologi yang
telah diciptakan bagi penyandang disabilitas. Hal ini tampaknya
karena Tempo melihat perhatian masyarakat maupun disabilitas itu
sendiri masih minim terhadap penemuan teknologi penunjang yang
dapat memudahkan aktivitas disabilitas.
73
Tempo.co membingkai isu disabilitas penunjang teknologi
dengan menyajikan berita-berita penemuan teknologi baru bagi
disabilitas. Hal ini dapat dilihat pada kutipan teks berikut :
“Sebuah tongkat tunanetra dengan sensor dibuat dan mulai digunakan di Turki. Selain dapat menunjukkan jalan berdasarkan peta digital, tongkat bernama We Walk ini dapat mendeteksi berbagai halangan di depan tunanetra yang menggunakannya (dikutip dari laman rubrik difabel Tempo.co, tanggal 20 September 2019).
Selain tongkat we walk, teknologi penunjang lainnya yaitu
jaket pengantar suara bagi disabilitas tunarungu. Hal ini dapat dilihat
pada kutipan teks berikut :
"Kami bisa merasakan musik dan berdansa karena kami dapat merasakan gelombang suara dari musik itu tanpa perlu pendengaran, melainkan dari sensasi di organ tubuh lain," ujar Hermon Berhane, seorang tuli yang menggunakan jaket CuteCircuit saat menikmati musik di London Club (dikutip dari laman rubrik difabel Tempo.co, tanggal 16 Oktober 2019).
Makna yang dibangun oleh Tempo.co berdasarkan teks diatas
adalah telah terdapat penemuan-penemuan dalam hal teknologi
penunjang bagi disabilitas. Dalam hal ini Tempo ingin mengarahkan
pembaca dalam melihat penemuan teknologi bagi disabilitas agar
tumbuhnya kesadaran bagi masyarakat sehingga dapat terciptanya
penemuan-penemuan baru lainnya dalam hal teknologi guna
74
memberikan akses penunjang teknologi yang lebih sempurna bagi
disabilitas.
2. Isu Inklusifitas Periode Agustus – Oktober 2019
Inklusif adalah istilah yang digunakan oleh penyandang disabilitas
dan para pegiat hak-hak penyandang disabilitas yang menegaskan
sebuah gagasan bahwa setiap orang harus secara bebas, terbuka dan
tanpa rasa kasihan memberikan kemudahan atau akomodasi kepada
penyandang disabilitas, tanpa penolakan dan atau hambatan apapun
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Tempo.co melalui rubrik difabel dalam periode Agustus – Oktober
2019 telah memberitakan terkait isu inklusifitas ini sebanyak 36 berita.
Dalam hal ini, peneliti membagi menjadi lima aspek pembahasan
terhadap berita isu inklusifitas pada rubrik Difabel, yaitu;
1) Inklusifitas Kesetaraan,
2) Inklusifitas Hukum,
3) Inklusifitas Ruang publik,
4) Inklusifitas Kisah sukses difabel, dan
5) Inklusifitas yang menghadirkan isu disabilitas yang lebih
beragam.
75
Gambar 4.3. Aspek Isu Inklusifitas Pada Rubrik Difabel
Berdasarkan 5 aspek pembahasan diatas, isu inklusifitas dengan
aspek kesetaraan tercatat sebanyak 15 berita, 7 berita dengan aspek
hukum, 3 berita ruang publik, 6 berita aspek kisah sukses difabel, dan 7
berita terkait aspek yang menghadirkan isu disabilitas yang lebih
beragam (Lampiran 4).
a) Bingkai Pemberitaan Inklusifitas Kesetaraan
Frame inklusifitas kesetaraan, tampak bahwa Tempo.co
menekankan pada kesetaraan akan hak dan kehadiran disabilitas dimuka
publik. Tempo mencoba membangun isu ini dengan menghadirkan
ragam kegiatan yang dilakukan disabilitas di tengah masyarakat. Hal ini
terlihat jelas bahwa tempo ingin memberikan pandangan bahwa
penyandang disabilitas adalah warga negara yang harus mendapatkan
15
7
36 7
02468
10121416
InklusifitasKesetaraan
InklusifitasHukum
InklusifitasRuang publik
InklusifitasKisah sukses
difabel
Inklusifitasisu disabilitas
yang lebihberagam
Inklusifitas
76
hak yang sama dengan warga lainnya. Hal ini tampak pada kutipan teks
berikut:
"Ziadah Ziad yang juga Koordinator Regional Komunitas Duta Damai NTB mengatakan, setiap orang memiliki hak berwisata yang sama. Sebab itu, tempat wisata juga harus bisa dinikmati oleh siapapun, tidak terkecuali difabel.
"DiveAble ingin mengkampanyekan kesetaraan berwisata khususnya di bawah air," katanya. Kendati terbilang ekstrem, menurut dia, kegiatan menyelam tetap dipilih karena olahraga ini tetap bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk difabel”.
Makna yang dibangun Tempo dalam teks diatas Tempo
tampaknya ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa
penyandang disabilitas juga mempunyai kemampuan yang sama dalam
menikmati pariwisata tentunya dengan cara yang berbeda.
Kesetaraan dalam hak serta peran dalam masyarakat
mendorong difabel hadir dengan semestinya, negara hadir
memberikan hak yang sama untuk mereka, misalnya dalam hal
mendapatkan penyuluhan bunuh diri, penyandang disabilitas adalah
orang yang dekat dengan isu dan topik bunuh diri dikarenakan mereka
kerap dilanda perasaan menjadi tidak berguna karena status mereka
sebagai penyandang disabilitas. Misalnya insan tuli, penyandang
disabilitas yang mengalami masalah pada indra pendengaran
bagaimana mereka bisa mengakses pengetahuan tentang pencegahan
77
bunuh diri jika kita tidak menciptakan pendidikan inklusi. Hal ini
terlihat pada kutipan teks berikut:
“Pencegahan bunuh diri adalah tugas semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai kelompok minoritas, penyandang disabilitas juga harus memiliki akses terhadap upaya pencegahan bunuh diri. Salah satunya cara berkomunikasi. "Teman - teman difabel, termasuk Disabilitas tuli juga ingin menjadi penyintas terhadap pencegahan bunuh diri, karena itu penyediaan akses bahasa isyarat sangat diperlukan," ujar Silvia Adriana, Person In Charge Lokakarya bahasa isyarat dalam Festival Into The Light, di Sunyi Coffee House and Hope, Ahad 1 September 2019”.
Menurut Tempo, penyandang Disabilitas juga harus
mempunyai akses yang sama untuk menjadi pelopor dalam upaya
pencegahan bunuh diri, hal ini tampak pada teks diatas bahwa
Tempo menekankan pada pentingnya mengajak insan tulis untuk
bisa berpartisipasi dalam upaya pencegahan bunuh diri dengan
menghadirkan akses bahasa isyarat. Dengan menghadirkan akses
bahasa isyarat dan mengajak para penyandang Disabilitas hadir serta
mengambil peran dalam upaya kampanye pencegahan bunuh diri
kita telah selangkah lebih maju untuk memberikan akses yang sama
bagi seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas.
Tindakan diskriminasi yang kerap diterima para penyandang
disabilitas juga terjadi pada pemberitaan, media kerap
78
menggambarkan difabel dengan tidak semestinya, hal ini berdampak
pada terciptanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.
Bahwa kehadiran difabel di media juga masih kurang dan tidak
sebanyak isu-isu lain. Ketua dewan pers mendorong bahwa isu
disabilitas juga harus menjadi prioritas dalam pemberitaan media,
sehingga isu ini setara dengan lainnya nya, misalnya dalam teks:
“Hendry Ch. Bangun berharap pemimpin media massa dapat membuat agenda berita bagi penyandang disabilitas, sehingga minimal setara dengan pemberitaan anak, minoritas, dan berperspektif gender. Perihal ini, Tempo.co telah melakukan langkah nyata dengan membuat kanal khusus untuk konten difabel di melalui difabel.tempo.co” (dikutip pada laman rubrik difabel Tempo.co tanggal 28 Oktober 2019).
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tempo ingin
mengarahkan pembaca pada frame bahwa inklusifitas kesetaraan
merupakan hak yang sama bagi disabilitas dalam memperoleh peran
di masyarakat dan media massa juga harus menjadi pelopor dalam
pemberitaan disabilitas yang setara.
b) Bingkai Pemberitaan Inklusifitas Hukum
Frame pada inklusifitas hukum tampaknya Tempo
menekankan pada keadilan hukum yang sama bagi Disabilitas.
Dalam hal ini, Tempo melihat bahwa penyandang Disabilitas kerap
79
mendapatkan perlakuan diskriminasi dimata hukum. Hal ini tampak
pada kutipan teks berikut :
“Kasus di Sukoharjo menimpa anak perempuan yang mempunyai disabilitas ganda, yaitu difabel wicara dan difabel intelektual atau tunagrahita. Dia mengalami kekerasan seksual oleh gurunya. Alih-alih mendapat respons cepat, polisi menolak menangani kasus itu. "Mereka beralasan ada hambatan komunikasi dengan kendala daya ingat korban," kata Syafi'i yang merupakan Peneliti Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau Sigab. (dikutip dari laman rubrik difabel Tempo.co, tanggal 9 Agustus 2019).
Selain tindakan diskriminatif, Tempo dalam hal ini
melihat sistem hukum peradilan masih sangat diskriminatif,
hal ini tampak pada kutipan teks berikut :
“Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII, Bambang Sutiyoso mengatakan meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai hukum reformatif, namun sistem peradilan untuk difabel masih diskriminatif. Contohnya, syarat saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah yang mendengar, melihat, atau mengalami. "Bagaimana dengan difabel netra atau tuli? Produk hukum belum membahas soal keterbatasan," kata Bambang” (dikutip dari laman rubrik difabel Tempo.co, tanggal 9 Agustus 2019).
Dari urain diatas, tampak Tempo.co mengarahkan
pembaca pada pembingkaian isu inklusifitas hukum pada
80
framing peristiwa diskriminasi yang dialami penyandang
Disabilitas saat berhadapan dengan hukum serta proses
peradilan yang masih tidak ramah bagi disabilitas.
c) Pemberitaan Inklusifitas Ruang Publik
Frame pada inklusifitas ruang publik tampaknya Tempo
menekankan pada ketersediaan fasilitas publik yang ramah terhadap
disabilitas, seperti fasilitas di stasiun kereta api dan Bandara.
Menurut tempo perlu mengajak difabel secara untuk merasakan serta
memberikan masukan pada fasilitas ruang publik. Hal ini terlihat
pada kutipan teks :
“Pelaksana Tugas General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Agus Pandu Purnama mengatakan kedatangan dan masukan dari teman difabel dengan ragam disabilitas diharapkan dapat membantu pengelola bandara dalam memperbaiki fasilitas di sana. "Kami mengucapkan terima kasih karena ada banyak masukan dari teman penyandang disabilitas untuk kenyamanan pelayanan mereka di Yogyakarta International Airport," kata Agus Pandu.“
Selain di Bandara, fasilitas publik yang lain seperti stasiun kereta
juga harus ramah bagi disabilitas.
“Saudara kita penyandang disabilitas tidak perlu khawatir menggunakan moda transportasi kereta api karena fasilitas di stasiun sudah aman nyaman bagi siapapun, termasuk difabel," kata Eko Budiyanto. Beberapa kondisi yang ramah difabel di dalam stasiun misalnya beberapa ruas jalan di
81
dalam stasiun dibuat langsam supaya dapat diakses pengguna kursi roda.”
Dari uraian teks diatas tampak bahwa tempo.co ingin
mengarahkan pembaca pada frame tentang inklusifitas ruang publik
pada ketersedian fasilitas publik yang ramah terhadap disabilitas
serta mengajak difabel merasakan langsung dan memberikan
masukan terhadap fasilitas publik.
d) Bingkai Pemberitaan Inklusifitas Dalam Keberagaman Isu
Dalam hal isu inklusifitas yang lebih beragam, frame Tempo
menekankan pada isu disabilitas beragam misalnya, fashion, permainan,
atau cara-cara yang bisa dilakukan oleh disabilitas untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan orang biasa. Tempo berhasil membuat pemberitaan
ini apa adanya, terlepas dari pola penulisan berita yang terkesan
supercrip atau heroisme tanpa melebih-lebihkan dan tanpa ada nada
menjadikan disabilitas sebagai objek inspirasi.
Contohnya pemberitaan tentang ‘Laninka Siamiyono, Beauty
Vlogger yang gagas 2.000 lipstik untuk disabilitas’, dalam
pemberitaannya, Tempo.co hanya menggambarkan sebagaimana
kejadian aslinya berlangsung, tanpa melebih-lebihkan dan menjadikan
Lalinka sebagai objek inspirasi.
82
“Selama sepuluh tahun masa terpuruknya, seorang teman membawakan Laninka Siamiyono sebuah eyeliner. Dia kemudian iseng memakai alat penegas garis mata itu. Dan hasilnya, mata Laninka terlihat berbinar”.
Kutipan di laman difabel Tempo.co ini sama sekali tidak
mengandung supercrip atau heroisme objek inspirasi, sebenarnya
Tempo mempunyai peluang untuk mendramatisir cerita dengan
menambahkan emosi yang menjadikan narasumber sebagai objek
inspirasi, namun Tempo tidak melakukan hal tersebut. Berita dikemas
apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan
teks berikut:
"Setelah dipakai, saya merasa lebih cantik. Kemudian saya berpikir, walau tidak bisa mengubah keadaan, berdandan dapat menggugah semangat saya untuk berbuat sesuatu," ujar Laninka.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Tempo ingin
mengarahkan pembaca pada isu disabilitas tanpa melebih-
lebihkan atau menjadikan disabilitas sebagai ojek inspirasi atau
heroisme. Hal tampak untuk mneghindari stigma negatif pada
penyandang disabilitas.
83
e) Bingkai Pemberitaan Inklusifitas Kisah Sukses Difabel
Frame pemberitaan tentang kisah sukses para disabilitas
selanjutnya juga dikemas apa adanya, tanpa mengandung sedikitpun
unsur supercrip atau heroisme yang menjadikan disabilitas sebagai
objek inspirasi. Seperti kisah Marita Ariani yang menjadi kapten tim
nasional sepak bola penyandang disabilitas intelektual putri. Sebelum
dipilih masuk tim sepak bola, Marita Ariana mengaku lebih fokus pada
olahraga lari. Dia lantas mengikuti tim kelimaan nasional, hingga
memperkuat tim nasional dalam berbagai pertandingan internasional, di
antaranya di Abu Dhabi, Malaysia, Filipina, dan India. Dalam hal ini,
tempo memberitakan kisah ini seperti apa adanya tanpa dilebih lebihkan.
"Posisi saya sebagai penyerang dan kapten," kata Marita yang berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu dari sejumlah pertandingan internasional tersebut. Dalam pertandingan di India pada 2019, tim yang dikomandoi Marita Ariani menyabet medali emas serta menjadi runner up di Abu Dhabi 2018.”
“Bagi Marita Ariani, pengalaman bertanding di berbagai negara dirasa sudah cukup. Sekarang yang dia butuhkan adalah memiliki pekerjaan tetap. "Saya tidak menyesal, saya bangga bisa sampai ke mana-mana berkat sepak bola. Sekarang saya butuh pekerjaan tetap," kata Marita seraya berharap dapat bertemu Bupati Temanggung, Muhammad Al Khadziq, untuk menyampaikan keinginannya itu.
84
Dari uraian teks diatas tampaknya tempo ingin mengarahkan
pembaca pada frame bahwa cerita sukses difabel harus ditempatkan
sama dengan hal lain, tidak dilebih-lebihkan bahkan pada tahap mengais
iba pembaca. Narasi framing supercrip biasanya digunakan media untuk
pemberitaan tentang isu disabilitas di media.
3. Isu Rehabilitasi Periode Agustus – Oktober 2019
Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas adalah suatu proses
untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara
optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang
disabilitas di masyarakat. Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang
disabilitas dirancang untuk menghasilkan upaya yang terarah,
terpadu dan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga/organisasi rehabilitasi, dan/atau oleh
masyarakat yang dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas
yang mengalami masalah sosial, sehingga mereka dapat setara
berada dalam lingkungan yang kondusif.
Pemberitaan Tempo.co dalam menyajikan isu rehabilitas
terhadap penyandang disabilitas ini, ada dua aspek yang ditelaah
oleh peneliti dari isu ini, yaitu:
85
1) Rehabilitasi Tips dan Trik
2) Rehabilitasi Terapi
Gambar 4.3. Aspek Isu Rehabilitasi Pada Rubrik Difabel
Dalam periode tiga bulan tersebut, Tempo.co melalui rubrik
Difabel telah menerbitkan 11 berita dengan aspek Tips dan Trik
sebanyak 8 berita atau menduduki 73% dari keseluruhan jumlah berita
pada isu ini. Dan 3 berita dengan aspek Terapi terhadap kaum difabel
(Lampiran 5).
a) Bingkai Pemberitaan Rehabilitasi Tips dan Trik
Frame Rehabilitasi tips dan trik tampak bahwa tempo.com
menekankan pada pentingnya pengetahuan dalam berhadapan dengan
disabilitas. Hal ini tampaknya karena Tempo melihat bahwa
pengetahuan tentang bagaimana dan hal apa saja yang harus dilakukan
ketika berhadapan dengan disabilitas sangat penting, memahami hal
8
3
0
2
4
6
8
10
Tips dan Trik Terapi
Rehabilitasi
86
tersebut dapat menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan jika
dihadapkan pada berbagai masalah. Seperti bagaimana berhadapan
dengan anak Disabilitas intelektual harus menggunakan pola
komunikasi khusus yang berbeda dengan anak non-disabilitas. Seperti
yang terlihat dalam teks berikut:
"Kuncinya komunikasi yang sederhana dan berulang," kata Adi dalam acara bedah buku Panduan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Intelektual di Sekolah Inklusi, di Aula Juwono Sudharsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kamis 15 Agustus 2019. Dia mencontohkan, ketika mengenalkan diri, gunakan bahasa yang simpel dan mudah diingat.
“Saya tidak mungkin memperkenalkan diri dengan nama lengkap beserta titel pendidikan yang saya punya kepada anak penyandang disabilitas intelektual. Saya akan membahasakan nama saya 'Adi' saja," ujarnya. Setelah dibuat lebih sederhana, para pendamping anak disabilitas intelektual tak boleh bosan mengulang segala sesuatu yang perlu diketahui oleh anak.”
Disabilitas dewasa tentunya berbeda dengan disabilitas sejak
lahir, beban mental yang dihadapi jauh lebih besar dan kerap terpuruk
pada perasaan yang tak berguna karena merasa ada hal yang hilang dari
kehidupannya, butuh waktu serta dorongan untuk bisa berada pada
tahap menerima. Seperti teks berikut ini:
87
“Dokter Spesialis Kejiwaan lainnya, Agung Kusumawardhani, menyebutkan, salah satu tahap yang harus dilalui penyandang disabilitas dalam menghindari emosi yang meledak adalah dengan penerimaan atau tahap acceptance. Setiap individu memiliki periode yang berbeda pada tahapan ini”.
“Untuk mencapai tahapan penerimaan, seorang penyandang disabilitas dewasa harus mau merawat dirinya, baik merawat secara fisik maupun kejiwaannya. Harus bisa membahagiakan diri sendiri," kata Agung. Menurut dia, terdapat delapan tahap kehidupan yang terkait dengan perkembangan psikologi manusia“.
Dari uraian teks diatas tampak bahwa tempo.co ingin
mengarahkan pembaca pada frame tentang rehabilitasi tips dan trik
pada pentingnya pengetahuan dalam berhadapan dengan penyandang
disabilitas, pengetahuan ini berguna untuk menentukan langkah yang
tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada.
b) Bingkai Pemberitaan Rehabilitasi Terapi
Frame Rehabilitasi terapi tampak bahwa Tempo.co
menekankan pada berbagai informasi penting yang berguna bagi
disabilitas dan pendamping disabilitas. Makna-makna yang dibangun
tempo pada pemberitaan rehabilitasi terapi ini berhubungan dengan
berbagai terapi yang dapat dilakukan bagi disabilitas. Misalnya
kegiatan menunggang kuda seperti teks berikut:
“Tammera Pollman menjelaskan Equine Assisted Therapy berasal dari budaya Yunani kuno. Pada abad ke-17, terapi
88
menunggang kuda ini diterapkan oleh masyarakat di negara-negara Skandinavia untuk menangani polio. Jurnal kesehatan mental dan ilmu saraf juga memuat bukti klinis bahwa menunggang kuda dapat membantu meningkatkan kepercayan diri difabel mental dan intelektual.
“Terapi ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat berinteraksi," kata Pollman. Dan salah satu binatang yang mampu merasakan mood orang yang berkomunikasi dengannya, menurut dia, adalah kuda dan tentunya sudah dilatih.”
Dari uraian teks diatas tampak bahwa tempo.co ingin
mengarahkan pembaca pada frame tentang rehabilitasi terapi pada
informasi-informasi seputar terapi yang diperuntukkan untuk difabel,
isu ini menjadi bahan rujukan bagi pendamping difabel untuk mencoba
berbagai terapi untuk difabel sesuai dengan kebutuhan yang mereka
inginkan.
B. Produksi Isu Disabilitas Rubrik Difabel Pada Media Tempo.Co
Isu disabilitas ini lahir dari kesadaran subjektif si penulis yaitu
wartawan tempo yang bernama Cheta Nilawati yang karena penyakit
diabetes yang dialaminya, menyebabkan ia kehilangan penglihatan pada
tahun 2016 atau di tahun ke-10 ia menjadi wartawan di media online
Tempo.co. Pada satu kesempatan, Cheta menulis pengalamannya tentang
penyakit diabetes yang membuat kebutaan di laman Indosiana, Tempo.co
pada tahun 2017. Melihat hal itu, Tempo memberikan ruang khusus
89
kepada Cheta untuk bisa menyuarakan isu disabilitas dengan membentuk
kanal rubrik difabel. Hal tersebut bukan tanpa alasan, tentu saja atas
usulan Cheta-lah rubrik itu dibentuk. Sebagai seorang wartawan yang
telah terbiasa dengan liputan dan menulis berita harian, tentunya membuat
Cheta merasa teramputasi sebagai jurnalis jika hanya ditempatkan sebagai
wartawan citizen jurnalisme. Kejadian dan segala pengalaman Cheta
menjadi seorang difabel membuatnya menulis banyak hal tentang
disabilitas. Karena itu Cheta merasa perlu menyuarakan banyak hal lagi
tentang disabilitas yang disajikan pada kanal rubrik difabel Tempo.co.
Dalam proses produksi isu, kanal rubrik difabel ini dikendalikan
oleh 3 orang yaitu Cheta Nilawati sebagai reporter, Rini Kustiani sebagai
editor, dan Dito sebagai kontributor. Tema pemberitaan tentang
disabilitas pada rubrik difabel ini disusun berdasarkan 3 kategori isu, yaitu
isu Aksesibilitas, isu Inklusifitas dan isu Rehabilitas. Pada proses
pemilihan berita, dilakukan blowing terlebih dahulu oleh Cheta terhadap
isu difabel pada rapat perencanaan. Dalam hal ini, Cheta lah yang menjadi
frontlinernya. Kemudian isu tersebut di kritisi dan diduskusikan oleh
Tempo.co secara berlayer, dengan tujuan tidak terjadinya konflik of
interest, dan tidak ada keberpihakan yang berlebihan. Tempo.co dalam
hal ini memakai metode saringan, namun sebelum diajukan ke dalam
90
rapat perencanaan pemberitaan, Cheta dan Rini terlebih dahulu telah
menyepakati dan mendiskusikan pemberitaan isu tersebut30.
“Saya frontlinernya seperti ujung jarum, ketika saya blowing di rapat perencanaan, ini begini loh ada isu ini, mereka akan kritis dulu, tanya dulu otomatiskan, ini gimana, itu gimana, akhirnya ketemu semua lah, kan di tempo itu berlayer, gak hanya sendiri, biar gak ada konflik of interest, biar tidak ada keberpihakan yang berlebihan gitu, kita tetap pakai metode saringan, kalau yang terdekat antara saya dan mbak rini dulu tentunya.” Kata Cheta.
Dalam hal kebijakan redaksional Tempo.co dalam menerbitkan
berita terhadap isu disabilitas di rubrik Difabel ini sudah sejalan
dengan kode etik jurnalistik dimana tidak mengandung unsur
diskriminatif, tidak menyudutkan, dan cover both side yang sudah
sesuai dengan kode etik jurnalistik.31 Dalam segi penerbitan berita,
rubrik difabel memproduksi minimal 1 berita sehari namun bisa juga
dua atau tiga berita. Hal ini dikarenakan rubrik difabel Tempo.co
belum dijadikan rubrik prioritas.
30 Wawancara dengan Cheta Nilawati, Reporter Rubrik Difabel Tempo.co pada
Sabtu, 14 Maret 2020.
31 Wawancara dengan Rini Kustiani, Editor Rubrik Difabel Tempo.co pada Rabu, 5
Februari 2020.
91
“Nah difabel ini belum dijadikan prioritas, jadi belum dikejar target. Minimal sehari 1 berita, tapi kadang dua atau tiga berita sih, tergantung”. Kata Rini.
Dalam produksi isu, tampak bahwa Tempo lebih menekankan
pada pemenuhan isu Aksesibilitas dan isu Inklusifitas. Hal ini tampaknya
Tempo melihat bahwa aksesibilitas dan inklusifitas merupakan faktor
yang sangat penting disuarakan dalam memperjuangkan hak-hak
disabilitas yang telah hilang. Hal ini dapat dilihat pada hasil temuan data
pada produksi isu disabilitas 3 kategori ini menunjukkan bahwa isu yang
paling dominan muncul pada tempo selama 3 bulan yaitu Agustus -
Oktober 2019 yaitu isu dengan kategori aksesibilitas dan inklusifitas,
sedangkan isu rehabilitas merupakan isu yang paling sedikit muncul
dalam rubrik difabel Tempo.co.
Kebijakan Tempo.co tentang pegawai disabilitas saat ini belum
ada kebijakan khusus yang mengaturnya. Karena hingga saat ini hanya
Cheta lah satu-satunya pegawai disabilitas di Tempo.co. Namun, dalam
hal karier, golongan dan jabatan misalnya, pegawai di Tempo.co
golongannya bisa naik, namun jabatannya tetap sama.
“Nah dalam hal karir misalnya, golongan dan jabatan. Disini golongan mereka bisa naik, tapi kan mungkin kinerja pekerjaannya jabatannya sama, jadi dalam hal ini golongan mereka bisa naik namun jabatannya tetap, karena itu kan berpengaruh ke penghasilan” Ujar Rini.
92
Sebagai pegawai disabilitas, Cheta Nilawati dalam proses
produksi isu disabilitas dalam hal ini Tempo memfasilitasi Cheta untuk
kinerja penunjang sebagai jurnalis. Fasilitas yang diberikan Tempo adalah
berupa pendamping untuk liputan dan dana tambahan. Fasilitas
pendamping tidak diberikan secara langsung oleh Tempo, namun Tempo
memberikan kewenangan dan dana kepada Cheta. Support dananya yaitu
untuk membayar pendamping dalam liputan. Biasanya Cheta
menggunakan pendamping dari organisasi Bravo (Barisan Relawan dan
Volunteer) dari UNJ. Bravo dalam hal ini menangani tunanetra dan
tunarungu yang menggunakan bahasa isyarat.
Sebagai pelaku produksi isu di rubrik difabel Tempo.co, Cheta
kerap mengalami diskriminasi stigma negatif dari seorang disabilitas,
dimana ia awalnya kerap diremehkan oleh teman-teman liputan lainnya
bahkan disangka tukang pijat oleh “gojek” atau orang yang
mengantarkannya ke lokasi tempat ia bekerja atau liputan.
“Nah kalau di liputan itu ya saya otomatisnya banyak yang belum tau, tapi begitu tahu saya buta. Kamu buta? gitu. Awalnya pertama otomatis adalah diskriminasi atau meremehkan apa itu pasti ada. Gak usah teman-teman di liputan ya, tukang gojek aja itu masih gak percaya saya bekerja sebagai wartawan, mereka mengira saya tukang pijat”. Ujar Cheta.
Meskipun kerap mengalami diskriminasi dan diremehkan sebagai
jurnalis tunanetra, namun Cheta mampu bekerja secara profesional.
93
Dimana kanal rubrik difabel dapat terisi dan menghadirkan isu-isu
penting bagi disabilitas sebagai wujud menyuarakan hak-hak disabilitas
yang kerap termaginalkan.
94
BAB V
TEMPO DAN ISU DISABILITAS
A. Analisis Teori Strukturasi Pemberitaan Tempo Terhadap Isu
Disabilitas
Tempo.co melalui rubrik difabel telah menghadirkan isu-isu
tentang disabilitas kepada masyarakat melalui pemberitaan pada media
online sebagai akses bagi masyarakat untuk mengetahui isu-isu yang
berkembang terhadap disabilitas. Hasil riset ini menunjukkan bahwa
Tempo.co sebagai media massa online ingin mengangkat isu-isu
disabilitas dalam ruang publik dengan penekanan pada aspek tertentu,
yaitu aspek aksesibilitas, inklusifitas dan rehabilitas. Penekanan 3 aspek
ini tampak dari pilihan Tempo dalam menyajikan pemberitaan di laman
media online rubrik difabel yang menempatkan posisi berita dalam 3
kategori ini. Dari 3 kategori tersebut, riset ini menunjukkan bahwa Tempo
memberikan perhatian paling besar pada aspek Aksesibilitas dan
Inklusifitas.
Hal ini tampaknya Tempo melihat bahwa aksesibilitas dan
inklusifitas bagi kelompok penyandang disabilitas sering kali
dikesampingkan dan masih menjadi PR di masyarakat dalam pemenuhan
hak-hak disabilitas tersebut. Dalam teori Giddens disebutkan bahwa
struktur sangat memiliki peran dalam membangun sebuah isu menjadi
95
pengaruh dalam setiap pengambil kebijakan, baik itu secara internal
struktur itu sendiri maupun secara eksternal. Dalam hal ini, Tempo
bertindak sebagai struktur yang membangun sebuah isu disabilitas
sehingga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat dalam melihat
disabilitas. Artinya, Tempo mempunyai andil dalam menggeser stigma
negatif disabilitas yang telah tercipta di masyarakat.
Dari temuan riset ini tampak bahwa Tempo.co mem frame
kelompok disabilitas sebagai kelompok marginal yang harus
mendapatkan perhatian khusus dalam segi pemenuhan hak-hak sebagai
warga negara bagi disabilitas. Dalam hal ini tampak dalam pilihan Tempo
untuk membingkai isu disabilitas pada frame kesetaraan, keadilan,
pemerataan, dan kesejahteraan bagi disabilitas yang masih kerap terjadi
diskriminasi. Hal ini dilandasi oleh prinsip Tempo sebagai media online
yang berpihak pada kelompok marginal. Praktik sosial yang berlangsung
dalam ruang media Tempo.co tidak bisa dilepaskan dari struktur media
itu sendiri yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian dari
kepentingan kelompok marginal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh
Gidden bahwa seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh
struktur memerlukan tindakan sosial. Sifat struktur adalah mengatasi
waktu dan ruang (times and spaceless), maya (virtual) serta bisa
diterapkan pada berbagai situasi dan kondisi. Selain itu, struktur juga
96
bersifat memberdayakan (enabling) yang memungkinkan terjadinya
praktik sosial. Titik tolak analisis Giddens adalah tindakan manusia.
Hasil temuan data dalam hal aksesibilitas, pemenuhan
aksesibilitas penyandang disabilitas masih sangat kurang dan bisa
dikatakan didiskriminasi. Dalam aksesibilitas pekerjaan, adanya
diskriminasi terhadap disabilitas yang tidak bisa menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS), dan dalam hal pendidikan, kurangnya aksesibilitas terhadap
pemenuhan hak untuk melanjutkan pendidikan bagi disabilitas serta
kurangnya literasi baca terhadap disabilitas. Selanjutnya di ruang publik,
kurangnya aksesibilitas disabilitas di ruang publik bahkan sering terjadi
diskriminasi seperti di bandara, stasiun kereta api, dan fasilitas umum
lainnya. Jurnalis pada media Tempo.co disini berperan sebagai agen
dalam menyuarakan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Sebagaimana dijelaskan dalam teori Giddens, ia memberikan penekanan
terhadap agen. Menurutnya agen mempunyai kemampuan untuk
menciptakan pertentangan dalam kehidupan sosial.
Dalam hal ini, Tempo.co mempunyai kekuatan untuk merubah
diskriminasi yang kerap terjadi pada disabilitas dengan menghadirkan
pertentangan isu disabilitas dalam kehidupan sosial. Agen merupakan
individu atau sekelompok orang yang melakukan perilaku secara
berulang-ulang yang mana kemudian perilaku ini menciptakan praktik
97
sosial, kepribadian dan tindakan sosial. Tindakan sosial yang diharapkan
adalah terciptanya pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok penyandang
disabilitas.
Dalam hal isu inklusifitas, kesetaraan dan kebebasan masyarakat
dalam menghadirkan masyarakat yang inklusif harus diperhatikan.
Berdasarkan hasil temuan data terhadap isu inklusifitas menunjukkan
bahwa disabilitas telah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan sosial
dalam hal mengapresiasikan diri, namun hal ini perlu kesadaran
masyarakat yang lebih lanjut dalam kesetaraan sosial bagi disabilitas.
Kesetaraan sosial bagi disabilitas terlihat penting. Menurut Giddens,
dalam menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor, orang terlibat dalam
praktik sosial dan melalui praktik sosial itulah baik kesadaran maupun
struktur diciptakan. Giddens memusatkan pada kesadaran atau
refleksivitas. Dalam merenung (reflexive) manusia tak hanya merenungi
diri sendiri, tetapi juga terlibat dalam memonitor aliran terus-menerus dari
aktivitas dan kondisi struktural.
Isu inklusifitas pada pemberitaan tempo juga menghadirkan isu
disabilitas lebih beragam misalnya, fashion, permainan, atau cara-cara
yang bisa dilakukan oleh disabilitas untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan seperti orang normal biasanya. Tempo juga menghadirkan
kisah-kisah kemandiriian disabilitas, dimana dalam hal ini tempo tidak
98
menjadikan disabilitas sebagai objek inspirasi. Tindakan agen sebagai
jurnalis dalam hal ini sebagaimana menurut teori Gidden yang
menyebutkan bahwa tindakan agen yang dilakukan secara terus menerus
akan menghadirkan praktik sosial baru yang mana hal ini tentunya dengan
tujuan untuk menggeser stigma negatif terhadap disabilitas yang kerap
dianggap sebagai objek inspirasi.
Fenomena-fenomena yang masih berlawanan dengan perspektif
disabilitas secara social board atau empowering board masih sangat
banyak. Setidaknya ada empat hal yang mempengaruhi pemberitaan
tentang disabilitas. Yang pertama, porno Inspirasi, artinya keadaan yang
bersyukur karena keadaan orang lain dianggap lebih menyedihkan. Yang
kedua karakter plot, artinya melihat kemalangan orang lain dengan sangat
menyedihkan. Yang ketiga, kecenderungan yaitu dari kedua hal itu tadi,
media cenderung memberikan penyandang disabilitas kalau tidak karena
inspirasinya maka sebab kemalangannya. Bahkan isu disabilitas di media
massa bisa di-hold sampai satu tahun masa tunggu terbitnya. Misalnya
ada satu disabilitas yang mau diberitakan, maka benar-benar ditunggu
sampai sekarat baru-lah dianggap sebuah berita yang bagus dari sisi
kemanusiaannya. Yang keempat adalah hyperheroism, sesuatu yang
sebenarnya biasa saja tetapi dilebih-lebihkan sehingga jadi hebat. Ini
adalah keadaan yang menganggap disabilitas itu luar biasa dengan
99
karyanya, padahal semua orang yang punya karya itu memang luar biasa.
Tapi dalam konteks ini, terlalu melebihkan nilai untuk disabilitas.
Misalnya ada disabilitas yang menulis buku, padahal isi bukunya hanya
diary tentang dirinya, atau sebenarnya isinya tidak terlalu bagus dan
terkesan biasa saja tetapi hal itu menjadi luar biasa karena penulisnya
adalah penyandang disabilitas.
Temuan data terhadap isu rehabilitasi yang merupakan isu
pemulihan atau pemberdayaan disabilitas dalam hal ini mengacu pada
bentuk literasi terhadap masyarakat bagaimana berhadapan dengan
panyandang disabilitas dan tips dan trik seputar cara-cara berinteraksi
dengan disabilitas serta terapi yang bisa dilakukan disabilitas dalam
proses pemberdayaan atau penyembuhan diri. Dalam hal ini, jurnalis
Tempo.co sebagai agen yang memberikan ruang agar aktivitas
berlangsung, namun dalam hal ini aktor juga mempunyai kesadaran untuk
menciptakan suatu kejadian. Hal ini sejalan dengan teori Gidden yang
menyebutkan bahwa kesadaran yang dibahas oleh Giddens mencakup
motivasi tak sadar, kesadaran diskursif, serta kesadaran praktis. Dimana
kesadaran praktis menimbulkan praktik sosial yang terus menerus
dilakukan tanpa jarang mempertanyakannya kembali.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran isu
disabilitas pada rubrik difabel media online Tempo merupakan suatu
100
kemajuan dalam pemberitaaan disabilitas di Indonesia. Tempo.co sebagai
struktur yang dimana struktur dan Jurnalis sebagai agen (Cheta Nilawati)
ini dapat membentuk suatu praktik sosial yang bertujuan agar mengubah
paradigma disabilitas.
B. Relasi Struktur Dan Aktor Terhadap Isu Disabilitas
Dalam membangun isu disabilitas tentunya tidak hanya struktur,
seperti yang disebutkan dalam teori Giddens bahwa membangun sebuah
isu merupakan bentuk dari praktik sosial secara menyeluruh. Artinya ada
keterlibatan antara struktur, agency, dan aktor. Struktur disini dapat
dimaksud sebagai pemberi kebijakan, agency sebagai pemilik/penyedia
ruang, dan aktor yang menjalankannya (bisa keduanya; sebagai
pengambil kebijakan dan sebagai pemilik/penyedia ruang atau salah
satunya saja).
Keterlibatan aktor sebagai pemberi ruang kepada isu yang
dibangun merupakan suatu hal yang harus ada. Dalam membangun isu
disabilitas, keterlibatan aktor secara langsung menjadi langkah awal
terbentuknya konstruksi yang ingin dicapai. Baik oleh Rini Kustiani
maupun Cheta Nilawati yang menjadi aktor dalam konstruksi isu
disabilitas ini menunjukkan adanya kesepahaman yang mereka bangun
melalui rubrik difabel di kanal Tempo.co.
101
Aktor bisa dilihat dari dua sisi. Yaitu, aktor sebagai agen dalam
struktur yang memiliki wewenang memberi perintah dan/atau mengambil
kebijakan dalam struktur itu sendiri. Kedua, aktor yang memiliki
pengaruh dalam struktur yang menjadi sumber atau rujukan kepada
kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap isu disabilitas.
Cheta Nilawati yang menjadi pengawas rubrik difabel pada kanal
Tempo.co tentu saja memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan-
kebijakan dalam melakukan konstruksi isu disabilitas lewat kanal yang
dikelolanya. Sebagai Frontliner atau orang paling depan dalam
menangani isu ini, Cheta membawa isu-isu disabilitas yang akan
diberitakan pada rapat perencanaan dengan para redaksi agar tidak adanya
conflict of interest, dan tidak ada keberpihakan yang berlebihan atas berita
yang akan diterbitkan. Sehingga berita yang dihasilkan benar-benar telah
melewati proses saringan yang ketat oleh tim redaksi.
Peran Cheta sebagai pengambil kebijakan tampaknya baru sebatas
dalam struktur atau pada tahap pemberitaannya. Sama halnya dengan Rini
Kustiani yang juga memiliki wewenang yang sama pada kanal ini. Namun
kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan hanya pada taraf menggiring
pembaca atau publik untuk lebih aware dalam menyikapi atau
memandang disabilitas. Karena posisinya, Tempo.co sebagai media harus
tetap mengkritisi, apakah itu baik atau buruk tentang kebijakan-kebijakan.
102
Minimal apa yang selama ini menjadi pemberitaan tentang
disabilitas sudah mulai dinilai dan diperhitungkan pemerintah. Misalnya
seperti yang dilakukan program hitam putih di TransTV. Saat mereka
mengundang tuna netra dengan keahlian memahatnya. Akhirnya dilirik
pemerintah lalu hasil karya tuna netra itu dijadikan cenderamata pada saat
Asian Paragames. Lalu saat isu pemilu juga, ada penyandangan disabilitas
intelektual dan disabilitas mental yang tidak boleh memilih, padahal
mereka punya hak pilih yang sama. Ketika hal itu diangkat di media,
akhirnya bisa menjadi bahan perundingan baru di pemerintahan sampai
bisa jadi sebuah kebijakan baru. Dan sekitar 400-an penyandang
disabilitas akhirnya bisa menggunakan hak pilih mereka.
Tempo.co melalui rubrik difabel yang terus memberikan berita-
berita tentang disabilitas, hal ini bukan tanpa tujuan. Dalam hal ini
Giddens mengungkapkan mengenai menjadi manusia berarti menjadi
agen yang memiliki tujuan. Manusia sebagai agen memperhitungkan
ekspetasi-reaksi dari lingkungan di sekitarnya dan perubahan kebutuhan
atau keinginan saat melakukan suatu tindakan. Dengan demikian suatu
tindakan yang dilakukan oleh agen pasti memiliki tujuan yang mampu
dipahami dan dijelaskan oleh pelakunya. Dalam hal ini Tempo tampaknya
berusaha agar dapat dilirik oleh pemerintah dalam mengatur kebijakan
terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas yang telah terabaikan.
103
C. Konstruksi Isu Disabilitas Pada Media Online Tempo.co
Data angka yang menunjukkan jumlah kaum difabel dari dulu
hingga sekarang tidak pernah ada hitungan pasti (underrepresentative).
Referensi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health
Organization (WHO) mengatakan ada 15 persen dari total penduduk
dunia adalah penyandang disabilitas. Sedangkan di Indonesia, terdapat
informasi terbaru Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 yang
menyatakan ada 14,2 persen penyandang disabilitas atau 30.38 Juta Jiwa
dari total penduduk di Indonesia.32 Sekalipun Indonesia sudah
mempunyai Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 1997 yang mengusung
enam isu utama, diantaranya kesamaan kesempatan, pendidikan, tenaga
kerja, aksesibilitas, dan kesehatan, tetapi untuk pemenuhannya kurang
terimplementasikan dengan baik. Pengelolaannya pun masih terkesan
karitatif. Maksud karikatif disini adalah ketika membuat kebijakan-
kebijakan terkait penyandang disabilitas tidak benar-benar di konsep
untuk membangun si kaum disabilitas sepenuhnya, tetapi cenderung
hanya diberikan beberapa manfaat saja.
Sebagai industri media online, yang mengharuskan mendapat klik
atau viewers sebagai pengembangan bisnis menjadi tantangan tersediri
32 Ekawati Rahayu Ningsih, Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam
Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat Di Stain Kudus, (Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Februari 2014), hal. 87
104
bagi rubrik difabel yang terbilang usianya masih begitu muda. Sehingga
dapat dikatakan masih sangat jauh dari nilai bisnis. Meskipun begitu,
tampaknya rubrik Difabel memiliki value dari sisi isi pemberitaan.
Apalagi media landscape sekarang ini banyak yang sudah berubah jadi
Jurnalisme Presisi, artinya bisa menjadi informasi yang mendidik dengan
mempresisi sebuah isu. Minimal sebagai hubungan masyarakat Tempo ke
publik, ini menjadi media yang reliable, yang masih mengusung isu yang
tidak hanya memandang profit semata, tetapi juga punya value.
Maka setelah melihat relasi antara struktur dan aktor dalam
membangun isu disabilitas, dalam fenomena ini dapat dilihat bahwa
struktur sebagai sebuah pemikiran pada isu disabilitas dalam konteks
media dan agen adalah orang-orang yang tidak hanya masyarakat yang
punya kesadaran tentang disabilitas. Tetapi dua hal ini (struktur dan agen)
dalam konteksnya, Tempo.co tidak terpisah karena memiliki jurnalis
dengan kondisi disabilitas.
Jurnalis tersebut dianggap perlu untuk bersuara dan menyuarakan
kelompok disabilitasnya yang kebetulan ia berada dalam media sebagai
sebuah struktur yang punya resource atau sumber daya, punya ruang
untuk bersuara, dan punya jurnalis atau reporter yang membuat berita
dengan isu disabilitas. Sehingga Tempo.co dianggap menjadi alat
perjuangan sebagai media yang membela kelompok marjinal yaitu
105
kelompok disabilitas yang kebetulan pada media itu sendiri ada jurnalis
dengan kondisi disabilitas.
Hasil konten pada kanal difabel Tempo.co merupakan hasil
dualitas relasi yang saling tarik menarik antara struktur dengan agen
(aktor). Pelaku tidak hanya menulis sebagai perspektif orang ketiga tapi
dia juga sebagai pelaku yang menulis mewakili difabel. Karena akan
berbeda jika yang menulisnya bukan seorang difabel, tidak merasakan
bagaimana menjadi seorang disabilitas. Sehingga berita yang ditulis
Cheta sebagai reporter dengan kondisinya yang disabilitas, menjadi lebih
dekat konteksnya. Maka ketika dia menjadi bagian dari munculnya rubrik
difabel, dia tidak hanya sebagai agen yang bertugas sebagai reporter dan
menulis tentang disabilitas tapi dia juga sebagai agensi yaitu membangun
rubrik tersebut untuk diisi dengan isu difabel yang harus disuarakan
tentang kelompoknya sendiri. Dalam hal ini, Cheta sebagai jurnalis
difabel yang membangun isu disabilitas pada rubrik difabel merupakan
hasil dari fasilitas oleh struktur (owner/pemilik media).
106
BAB VI
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian penulis mengenai konstruksi isu
disabilitas pada media online Tempo.co, penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Isu disabilitas dikontruksi dalam rubrik difabel Tempo.co
berdasarkan teori strukturasi Anthony Giddens dimana
terdapat 3 kategori isu, yaitu isu Aksesibilitas, Inklusifitas dan
isu Rehabilitas.
2. Hasil temuan data penelitian menunjukkan isu Inklusifitas
(dalam aspek kesetaraan) dan isu Aksesibilitas (aspek ruang
publik) merupakan isu yang paling dominan diberitakan pada
rubrik Difabel Tempo.co selama periode Agustus - Oktober
2019. Hal ini menunjukkan bahwa Tempo.co memusatkan
perhatian pada isu tersebut agar masyarakat maupun
pemerintah aware terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas
dalam hal Inklusifitas yaitu kebebasan dan kesetaraan
disabilitas dan juga Aksesibilitas yaitu pemenuhan hak untuk
mengakses berbagai fasilitas dengan tujuan mewujudkan
kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.
107
3. Proses produksi isu disabilitas dalam rubrik difabel Tempo.co
adalah Cheta Nilawati dan Rini Kustiani yang berperan sebagai
aktor sekaligus agensi dalam membentuk struktur sosial
masyarakat agar sadar dan peduli terhadap penyandang
disabilitas yang masih dimarjinalkan dalam kehidupan sosial
dan masyarakat. Selanjutnya yang menjadi objektif tempo.co
adalah penyandang disabilitas itu sendiri.
B. IMPLIKASI
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa
implikasi dari penelitian adalah dorongan melakukan konstruksi isu
disabilitas secara meluas kepada publik dengan membangun relasi positif
tentang penyandang disabilitas. Sehingga dapat menjadi edukasi dan
pemenuhan informasi kepada publik maupun kepada penyandang
disabilitas itu sendiri.
Rubrik difabel ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan
kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait
penyandang disabilitas. Namun tetap tidak melupakan tugasnya sebagai
media yang menjadi kritik kepada pemerintah.
108
C. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa
saran terkait fakta dan hasil data dari pemberitaan terkait isu disabilitas
yang dibangun pada rubrik difabel ini, antara lain:
1. Rubrik Difabel pada media Tempo.co agar dapat dijadikan rubrik
prioritas sebagaimana rubrik yang lainnya. Mengingat isu disabilitas
sepertinya memang masih jarang diberitakan secara menyeluruh
oleh media lain.
2. Pemberitaan disabilitas pada media Tempo.co dalam rubrik Difabel
dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam mengambil
kebijakan terkait penyandang disabilitas.
109
DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Barnes, Colin. 1992. Disabling Imagery and The Media, The British Counsil
of Organisations of Disabled People.
Berry, David. 1995. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Creswell, John W.2009. Research Design Pendekatan Kualitatif.
Depdikbud. Marginal, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Giddens, A. 2010. Teori Strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur
sosial di masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Given, Lisa M. 2008. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Method.
Singapore; Sage Publication.
Kartasapoetra dan Hartini. 1992. Kamus Sosiologi dan Kependudukan.
Jakarta: Bumi Aksara.
Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta:
Prenada Media Group.
110
Lok, Helen. 1999. “Individu Pembahalaru dan Masyarakat Terbuka” dalam
Muhalammad Halidayat Rahalz (eds.), Menuju Masyarakat
Terbuka. Yogyakarta: Ashaloka Indonesia-Insist.
Pirls, Danica and Popovska, Solzica. 2013. International Journal of Scientific
Engineering and Research Media Mediated Disability: How to
Avoid Stereotypes, University of Nis and University of Skopje.
Rahayu, Sugi. Dewi, Utami dan Ahdiyana, Marita. 2013. Pelayanan Publik
Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerag. Yogjakarta.
Reefani, Nur Kholis. 2013. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus.
Yogyakarta: Imperium.
Sugiono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
JURNAL:
Donny Anggoro, Rainy MP. HALutabarat: Kita halarus Dua Kali Lebihal
Dari Yang Lain, Jurnal Perempuan edisi 69.
Ekawati, Ningsih. Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam
Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat Di
Stain Kudus, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Februari 2014.
Firman, Abdul. Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori
Strukturasi Anthony Gidden Sebagai Alternatif, Jurnal
Sosiohumaniora, Vol 8, No.2, Juli 2006.
111
Haryanto, Ignatius. Kemunculan Diri Dan Peran Pemilik Industri Media Di
Indonesia Dalam Kerangka Teori Strukturasi Anthony Giddens,
dalam Jurnal Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
Volume VI, No. 2, Desember 2014.
Masduqi, Bahrul Fuad. Kecacatan: Dari Tragedi Personal menuju Gerakan
Sosial dalam Jurnal Perempuan: Mencari Ruang untuk Difabel,
edisi 65.
Nastiti, Aulia Dwi. Identitas Kelompok Disabilitas dalam Media Komunitas
Online: Studi Mengenai Pembentukan Pesan Identitas Disabilitas
dalam Kartunet.com, dalam Jurnal Komunikasi Indonesia. Volume
II Nomor 1 April 2013. ISSN 2301-9816.
Pratiwi, Ardhina. 2018. Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika
dan BBC News Model Robert N. Entman, dalam Jurnal Konstruksi
Realitas dan Media Massa. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta.
Santoso, Meilanny dan Nurliana C. 2017. Pergeseran Paradigma Dalam
Disabilitas, Jurnal Of International Studies, edisi 1 No. 2.
WEBSITE:
Dani Prabowo, “Komnas Ham Nilai Isu Disabilitas Kurang Mendapatkan
Perhatian media,” artikel diakses pada tanggal 17 Oktober 2019
dari
112
https://nasional.kompas.com/read/2017/02/17/17232611/komnas.h
am.nilai.isu.disabilitas.kurang.mendapatkan.perhatian.media.
Roh Thaniago, “Bolehkah Saya Menjumpai Dilabel di Media Dengan Layak,”
artikel diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 dari
http://www.remotivi.or.id/amatan/503/Bolehkah-Saya-
Menjumpai-Difabel-di-Media-dengan-Layak
Slamet Thohari, “Mendengar Difabel Melalui Tempo,” diakses pada tanggal
17 Oktober 2019 dari
http://www.remotivi.or.id/amatan/536/Mendengar-Difabel-
Melalui-Tempo.co
http://www.remotivi.or.id/amatan/503/Bolehkah-Saya-Menjumpai-Difabel-
di-Media-dengan-Layak
http://lipi.go.id/lipimedia/lipi-dan-unesco-perhatikan-kaum-marjinal/19033
Young, S. 2014. “I’m Not Your Inspiration, Thank You Very Much.” TED. Diakses 10 February 2015.
114
No Pertanyaan Jawaban
1. Boleh dijelaskan
bagaimana Latar
Belakang munculnya
rubrik Difabel
Tempo.co? Sejarah
kemunculan serta
siapa yang
menginginkan rubrik
ini hadir.
Iya jujur aja ya, website ini tu dibuat tahun 2017 waktu
itu sebenarnya uncounted antara saya, mas Komang, mas
Elik. Waktu itu saya bilang saya habis dari Mitra Netra
itu, saya belajar di mitra netra 4 bulan. 2017 sudah
launching lagi di kantor (tempo), saya gak mungkin kan
langsung liputan, saya ditaruh di Indonesiana, saya bilang
ke mas komang, mas Komang kok kayaknya kalo saya
cuma di taro di citizen journalism, saya sebagai jurnalis
seperti teramputasi gitu, saya merasa turun derajatnya
hehe, sorry ya turun gengsinya maksudnya. Bukan apa-
apa ya saya masih bisa menulis, saya masih bisa mengejar
target seperti dulu ketika saya reporter, 1 hari 3 berita.
Saya bisa gitu kan bahkan ketika saya di citizen
journalism saya masuk ke dunia disabilitas, saya sangat
produktif mau menulis apapun yang pengen saya tulis
gituloh. Tapi gak bisa sembarangan, citizen journalism
itu nunggu giliran kan. Beda kalau misalnya saya punya
website sendiri saya bilang, saya pengen numpahin
semua segala macam, apapun tentang disabilitas. Oke
boleh kata mas Komang gitu akhirnya saya bilang gimana
kalau kita buat rubrik disabilitas aja mas khusus. Mas
Komang juga menawarkan iya kita buat rubrik disabilitas
aja? Iya, kata saya. Kamu berani menerima tantangan ?
ya berani. Kamu presentasi di depan retmit semua?
Berani. Yaudah dipanggil lah semua retmit, semua kanal
di panggil waktu itu, seni, gaya hidup, ekonomi, bisnis,
nasional, semua kumpul waktu itu ada sekitar 15-an
orang kalo gak salah ya, saya presentasi disitu, saya
bilang saya ingin membuka kanal namanya difabel, trus
115
tadinya ada 5 hal atau 7 hal gitu yang saya ajukan. Jadi
kayak kanal habis itu kanalnya lagi gitu, saya ngajuin ada
rehabilitasi, ada inklusivitas, ada aksesibilitas, waktu itu
ada paragames, trus ada kaya kesehatan, tapi yang
kaitannya dengan difabel, kayak misalnya kesehatan
mata, amputi, para pregi sama 2 lagi saya lupa
ilansiarpidi sama undang-undang, pokoknya rubrik
nasional tapi kaitannya sama difabel. Tadinya 7 yang
saya ajuin, tapi yang disetujuin 3, yaitu Aksesibilitas,
Inklusivitas, Rehabilitasi.
2. Tujuan Tempo
menerbitkan rubrik ini
Otomatis pasti untuk menampung aspirasi temen-temen
penyandang disabilitas, menampung aspirasi,
menyampaikan aspirasi mereka, mengingatkan juga
kepada lingkungan umum tentang keberadaan mereka.
Karna gini ya kalau dari saya pantau ni kuba dan temen-
temen ya isu disabilitas itu pasti berpotongan dengan isu
kesehatan, kesra (kesejahteraan rakyat) dan olahraga ya
kan tapi ketika isu disabilitas masuk ke tiga kanal ini, itu
gak pernah menjadi main isu, gak pernah menjadi isu
utama yang diperhatikan ngertikan jadi cuma sekedar
objek inspirasi kalau di olahraga ya kan, kalau di kesra
cuma kayak ya bagian-bagian cs nya saja jadi kayak ini
mah bisa digeser, bisa ditunda sampai 7 bulan berikutnya
apa gimana gitu misalnya. Tapi kalau kita punya isu
sendiri, kita punya kanal sendiri jadi kayak semacam juga
mengembalikan fungsi jurnalisme sebagai sarana edukasi
bagi masyarakat.
116
3. Pandangan Tempo.co
tentang kebijakan
pemerintah terhadap
penyandang
Disabilitas?
Kalau menurut saya, tempo tetap mendukung tapi tetap
kritis. Jadi mereka gak selamanya ohh mentang-mentang
ini kita punya kanal khusus difabel, semua kebijakan dari
pemerintah itu kita ia kan karna demi mendukung difabel,
enggak tetap kita kritisi. Seperti kemaren panti berubah
jadi balai rehabilitasi ya di kemensos yang kasus Surya
Tambunan itu tetap kita liput. Waktu itu sengaja gak
disitu, saya gak diliput karena saya tuna netra nanti
takutnya konflik internal kan jadi teman lain yang
meliput kesitu. Tapi ketika ada temen-temen tuna daksa
diusir dari panti gara-gara mau berubah jadi balai
rehabilitasi padahal itu punya dinas, kewenangannya aja
udah salah, kalau dinas tetap dinas kan, bukan pusat dong
bukan kemensos berarti kan, itu tetap saya kritisi dan
diberitakan juga. Atau tetap misalnya ada disabilitas yang
jadi tersangka waktu itu di tangerang karena kasus
penganiayaan atau pembunuhan saya lupa tapi pelakunya
penyandang disabilitas coba, itu tetap kita beritakan,
walaupun ya, walaupun masih banyak keterbatasan di
kanal ini, karena sumber daya nya kurang. Orang yang
mengerjakan kanal ini itu secara total Cuma tiga orang,
saya, Dito, mbak Rini, mbak Rini itu editornya, saya itu
reporter sekaligus pengawas kanalnya ya kan. Jadi saya
ngisi terus. Kalau Dito kontributor di Jogja, karena jogja
udah lumayan inklusif ya jadi bagus juga itu
pergerakannya. Ya tapi dia juga gak bisa diandalkan
karena dia mencari berita yang lain juga, kontributor kan
kalo Dito. Kemarin itu sempat Bram ngasih berita ya
117
gitulah kita kolektif akhirnya. Karena yang terpenting
adalah follow up issue nya gitu. Kalau saya sendiri
mengcover seluruh isi juga gak bisa, saya akui jujur aja
ya apalagi sifatnya yang hard news yang sifatnya harus di
follow up, kejar-kejaran, mobilitas saya sangat terbatas
saya akui sebagai disabilitas tapi saya gak mau itu jadi
permakluman buat saya, kalau mau dianggap setara ya
kita bekerja seperti orang umum gitu. Cuma tetap harus
dilihat ya saya mengakui saya ada keterbatasan tapi
jangan mentang- mentang saya disabilitas lalu saya di
istimewakan.
4. Mohon dijelaskan
mengapa Tempo
mengambil tema
Aksesibilitas,
Inklusivitas dan
Rehabilitasi dalam
rubrik Difabel.
Bagaimana pandangan
Tempo tentang
masing-masing aspek
tersebut.?
Kenapa saya memilih 3 ini, karena 3 ini adalah aspek
yang selalu berkaitan dengan penyandang disabilitas.
Aksesibilitas itu kan sebenarnya adalah cara bagaimana
penyandang disabilitas itu berperan di masyarakat,
semacam fasilitas tapi bukan sekedar fasilitas, tapi
fasilitas yang bisa di akses sama penyandang disabilitas.
Kalau akses misalnya ni ke satu ruangan ada tangga ya
kan, mungkin orang pada umumnya bisa mengakses
ruangan dengan tangga tapi kan penyandang disabilitas
kursi roda gak bisa, mereka harus pake ram. Dengan
adanya ram bisa diakses sama penyandang disabilitas
pengguna kursi roda, bisa diakses sama orang pada
umumnya. Orang umumnya bisa kan lewat ram, kayak
nenek-nenek, kakek-kakek, orang hamil jadi ini kan
prinsip aksesibilitas, dimana pun itu harus bisa kita
review sebagai penyandang disabilitas. Nah menurut
118
saya tempo harus mengakomodasi itu, karena ini aspirasi,
artinya setiap penyandang disabilitas memerlukan itu,
menyampaikan aspirasinya, karena tanpa aksesibilitas
mereka gak bisa mengakses. Ini isu yang paling penting
menurut saya antara ketiga ini. Yang kedua itu
inklusivitas. Inklusifitas itu adalah kaitannya sama kiprah
penyandang disabilitas yang berkecimpung sama
masyarakat pada umumnya. Jadi disabilitas itu gak
selamanya eksklusif, mengurung diri, gak selamanya
apa-apa dikhususkan, enggak, penyandang disabilitas
bisa berkiprah di lingkungan. Inklusivitas ini sebenarnya
bagian dari 2 metode atau 2 mode stigma tentang
penyandang disabilitas. Jaman dulu sebelum seluruh
negara di dunia ini meratifikasi yang namanya
Konferensi United Nation Convention Of Rat People
With Disability tahun 2011 itu menganggap bahwa
penyandang disabilitas itu adalah bagian dari penyakit
kesalahan medis. Jadi sudut pandang diambil
perspektifnya medis. Kalo kita perspektifnya medis, ya
pasti saya cacat, cacat aja. Saya gak bisa kemana-mana.
Sekali lagi ya, namanya cacat bukan disabilitas. Jadi saya
cacat itu artinya ada terminasi organ saya hilang, gak
kepake, gak berfungsi, itu mode jaman dulu, belum ada
Konferensi United Nation Convention Of Rat People
With Disability itu namanya mode medis ya. Nah setelah
Konferensi United Nation Convention Of Rat People
With Disability tahun 2011 itu modenya dibilang mode
sosial. Artinya seorang penyandang disabilitas menjadi
119
disabilitas karena lingkungan sekitar tidak menyediakan
akses buat dia. Artinya semua orang yang lahir walaupun
istilahnya dia cacat dari lahir itu bukan karena kerusakan
organ, tapi dia tercipta begitu, itu bagian dari
keanekaragaman yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya
saya taruh inklusivitas ini dibagian kedua karena ini
penting. Inklusifitas ini menekankan bahwa teman-teman
penyandang disabilitas banyak yang bisa berkiprah di
dunia umum, jangan jadi super heroism. Nah yang ketiga
yang gak kalah penting itu rehabilitasi. Kenapa saya
masukin rehabilitasi adalah gini semua orang cacat itu
kan gak cacat dari lahir. Disabilitas itu gak semua dari
lahir. Disabilitas itu sebabnya ada 4. Ada yang dari lahir,
ada karena disebabkan sakit, karena kecelakaan, dan ada
yang karena tua. Nah rehabilitasi itu adalah program yang
mengembalikan penyandang disabilitas dewasa ke
kondisi sebelumnya. Kayak saya gini contohnya saya
dulunya melihat dan sekarang tdk melihat, nah saya ikut
rehabilitasi di Mitra Netra. Program itu banyak, belajar
pake tongkat ngerasain gimana, itu apa, kalau buat para
plagie, cara muter kursi roda gimana, buat yang tuna
rugu, bicara bahasa isyarat gimana. Jadi rehabilitasi itu
mengembalikan kondisi orang ke kondisi sebelumnya,
itulah kira-kira.
5. Apakah Tempo
memberikan
keberpihakan dalam
Keberpihakan tentu ada tapi tentu dilihat dulu sampai
sejauh mana kapasitasnya. Kalau kita misalnya nya ada
berita nih Mbak diberitakan dong, apa tuh kami nanya
120
kebijakan organisasi
terhadap kelompok
difabel? Jika ya, dalam
bentuk apa
keberpihakan itu
dilakukan?
kan, Ini nih kita mau launching kegiatan tapi dana kita
nggak disetujui sama Pemko sama Pemda misalnya,
beritain dong di Tempo, nggak, saya memilih nggak
begitu. Keberpihakan secara umum kita kalau
mendukung iya tapi kalau yang sifatnya pribadi institusi
saya menghindari itu, editornya pun juga tahu udah lah
nggak usah ya, gitu.
6. Selain Mba sendiri
apakah ada
penyandang disabilitas
yang menjadi
wartawan di rubrik
difabel?
Tidak ada, cuma saya sendiri wartawan difabel di Tempo,
kemarin kalau nggak salah ada salah satu teman juga
yang mulai rusak matanya ya karena minus nya tinggi
tapi nggak tahu keluar Jadi kontributor atau enggak tahu
gimana tuh di gaya hidup tapi dia jauh lebih bagus
matanya masih bisa ngeliat sih.
7. Saya melihat ada
kerjasama Tempo.co
dengan Yayasan Mitra
Netra liputan rubrik
difabel saat launching.
Mengapa dan
bagaimana kerjasama
itu dibangun? Dalam
bentuk apa?
Perkembangan saat ini
seperti apa?
Karena itu berlaku hanya 1 tahun sudah habis berarti ya,
jadi sudah tidak ada kerjasama lagi tadinya tuh kita
MOUnya seperti ini teman-teman di fabel termasuk staf
Mitra yang Non difabel, pengen menulis isu tentang
difabel silakan saja, nanti Tempo yang akan memuat, tapi
tentu diedit dulu dan rencananya tadi itu mau ada
kompensasi jadi kayak confee gitu, dibayarin tapi saya
nggak mengerti ya sampai sekarang. Ya mungkin karena
saya baru ya bagian dari organisasi penyandang
disabilitas saya ikut di Mitra Netra itu, saya nggak ngerti
cara Founding kerjanya gimana, saya pikir kayaknya
mereka punya cara cari duit yang lebih bagus gitu jadi
setelah ditawari itu nggak ada satupun yang mau menulis
bahkan kayak ogah-ogahan gitu tu. Jadi di Mitra Netra
121
itu kayaknya kemarin kita salah MOU, menurut saya ya,
tapi ini off the record, jadi semacam sia-sia karena tidak
ada follow up nya, temen-temen yang suka menulis, saya
ajak menulis tidak mau nulis, kaya udah burning up lah,
kaya udah bosan atau apa, gada intens, gada tertarik-
tertariknya untuk menulis. saya kira sebaiknya dulunya
saya MOUnya sama solider, adalah satu website yang
khusus juga buat difabel, mean issue, namanya Solider.
Kalau ga Perdik yang di makassar, itu lebih awere, kalau
tahu begitu saya kerjasama sama mereka.
P: karena mereka intens dalam menulis ya ?
N: Iya, menulis betul.
Di mitra itu organisasi pergerakan ya, jadi mereka
terimanya kaya ada kegiatan apa, yuk kita ikut-ikut,
nonton bersama gitu, terus sepedaan bersama, ya begitu-
gitu. Saya baru sadar gitu loh, mereka tipe yang begitu,
bukan tipe kaya Perdik atau Solider, kalau solider itu
bahkan wartawan difabelnya keliling, oh saya bilangnya,
harusnya saya konsen ke mereka aja harusnya kemarin
kalau tau gitu.
8. Dampak apa yang
diharapkan oleh
Tempo dengan
kehadiran rubrik ini ?
Yang pertama ya tentunya kesetaraan buat teman-teman
Disabilitas di bidang apapun dibidang kesehatan,
olahraga, di bidang pendidikan, pekerjaan, semuanya. itu
kesetaraan satu, yang kedua legalitas, artinya begini ada
peran difabel yang diakui. Jadi kan kalau cuman dari
mulut ke mulut doang sia-sia lagi kan . Tapi ketika kita
122
punya bukti formal Oh ada artikel Oh ada berita yang
mengatakan ini bagus Oh ada berita yang mengatakan
profilnya bagus Oh ada produknya saya berharap itu di
legal-formal kan Oh ini ada lu hitam diatas putih nya Oh
ini ada buktinya gitu bawa itu aja bukan hanya dari mulut
ke mulut jadi semacam eksistensi kan keberadaan difabel
dan kegiatan yang positif jangan selama ini hanya jadi
objek inspirasi misalnya Cheta Nilawati seorang seorang
perempuan pedagang kerupuk hidupnya di rumah
rombeng beralaskan tikar dan makan kertas koran
misalnya itu bukan inspirasi tapi objek inspirasi menurut
saya bahwa itu stigmatisasi bahwa penyandang
disabilitas itu malang nasibnya tinggal di rumah
rombeng, tunanetra jualan kerupuk walaupun jualan
kerupuk nggak salah ya tapi dia hanya menerima duit tapi
kerupuknya tidak terjual ini salah begitu amit-amit ya
jangan sampai
P: Banyakan Charity
N: iya jangan sampai begitu
Nah itu harus diganti stigma nya sekarang bukan charity
lagi itu tapi empowering artinya nggak papa dia penjual
kerupuk asalkan dia pengusaha kerupuk berita begitu.
9. Apa yang anda pahami
tentang kelompok
disabilitas?
Pertama ya yang tadi saya bilang uncounted, artinya ada
koneksi yang terbentuk karena hal ini artinya dulu ketika
masih bisa melihat saya pernah menolong orang di
Pondok Cabe tunanetra tuh kan ada markasnya di Pondok
123
Cabe dia naik angkot terus angkotnya kencang saya di
angkot yang sama saya teriak sama supirnya Pak bapak
itu orang buta mau turun gitu akhirnya turun lah di
pondok cabe kan tapi ini udah kelewat jauh. Terus saya
anterin tu tunanetra. Nah waktu itu yang saya lakukan
adalah Saya memegang tangannya. Terus dia pindahin
tangannya ke siku. Terus yang ada di pikiran saya adalah
wah ni tunet centil nih. Terus saya nanya kan kenapa
harus di siku. Terus dia jelasin kan, oh enggak mbak
karna kalau saya berjarak, saya pegang tangannya, di
depan ada batu, di depan ada meja saya kesandung. Oh
bener juga saya bilang. Ohh maaf-maaf pak, kata saya ke
tuna netra ini kan. Bayangkan ini tidak tereduksi pada
semua orang, jadi setiap tuna netra yang pegang sikunya
dikira pelecehan ya kan, jadi yang terbentuk seperti itu.
Jadi persepsi saya banyak yang salah tentang disabilitas
tapi otomatis yang terbentuk di kepala saya adalah pasti
kasihan itu udah nggak bisa disalahin itu udah natural
gitu ya. Tapi setelah saya tahu begitu pandangan saya kok
semua negatif, saya kualat kayaknya hehe. Jadi semua
stigma itu berubah bergeser jauh banget ketika saya
menjadi disabilitas. Saya lebih bisa memposisikan diri,
lebih bisa tau, lebih tau gimana rasanya di deskriminasi
itu saya tau.
10. Mohon dijelaskan
sejauh mana
komitmen
Kalau jadi polisi atau regulasi nggak mungkin ya karena
ini hanya sekedar artikel kami berharap ini memberikan
dampak atau Impact ke semua pergerakan difabel
124
keberpihakan tempo
terhadap isu ini?
Apakah hanya
memberikan ruang di
media atau pada taraf
bisa menekan
pemerintah dalam
mengambil kebijakan
terhadap penyandang
disabilitas?
walaupun dampaknya kecil sekali entah apapun itu
bentuknya tapi kami berharap itu bisa lah
keberpihakannya di situ, tentu ya begitu tapi kalau untuk
menjadi sumber regulasi, mengubah kebijakan kalau itu
kami belum tentu bisa sampai disitu ya kalau nggak di
push up sama kanal nasional atau apa gitu tu, belum
sampai segitu tarafnya karna kan usianya baru ya kanal
ini, jadi mereka masih dalam tahap perjuangan. Tapi
waktu itu pernah ada contoh jadi pematung atau pemahat
ya saya lupa apa waktu itu dia diberitain di difabel sama
kontributor Jogja besoknya dipanggil ke Hitam Putih
akhirnya karya dia itu jadi cindera mata di Asian para
games. Nah itu juga lumayan lah ya menurut saya, terus
soal kemarin penyandang disabilitas intelektual dan
mental yang tidak boleh menjadi peserta Pemilu, padahal
mereka punya hak memilih ya kan. Nah akhirnya
kemaren ada sekitar 400 -an difabel bisa ikut pemilu dan
memberikan suaranya. Hal-hal yang seperti itulah paling,
belum sampai yang istilahnya mengubah kebijakan apa
enggak karena rata-rata kalau kebijakan terhadap difabel
itu sifatnya positif mendukung kecuali kayak kemarin ya
dari Panti berubah menjadi Balai rehabilitasi ada
konsekuensi kalau panti kan dulu bertahun-tahun
penghuninya difabelnya boleh nginap boleh
berkecimpung di situ, Tapi ketika dia sudah menjadi
Balai rehabilitasi Itu kan cuma 6 bulan kalau saya tidak
salah. Itu tidak bisa kita ubah karena menurut saya itu
positif, Jadi tidak ada yang salah. Kalau untuk jadi
125
regulasi sih belum ya Kuba tapi kami berharap ini bisa
jadi referensi untuk kayak misalnya dinas sosial mau
membuat peraturan tentang apa, mereka tidak punya
masukan tentang difabel, saya harap mereka bisa melihat
di rubrik difabel. Tapi kami mengawal soal PP teknis,
jadi kan undang-undang nomor 8 tahun 2016 disahkan,
setelah itu presiden janji ada 7 PP teknis Yang diterbitkan
itu kami mengawal banget dan akan terus-terusan.
P : Sekarang baru satu disahkan?
N: iya Baru satu
Nanti dalam waktu dekat, PP peradilan, apa apa gitu, juga
mau disahkan tapi masih dalam tanda tangan, eh, tapi
kayanya di meja, di meja staf KSP kantor staf presiden
kalau gak salah. Sama satu lagi kebijakan tentang kartu
disabilitas, kartu Disabilitas ini konsekuensinya nanti
buat sensus sekaligus tunjangan bulanan jadi modelnya
NDIS di Asutralia yaitu National Disability Insurance
System, kayaknya mau kaya gitu, tapi belum pasti deh,
saya belum tahu skemanya bagaimana, tapi katanya
dengan adanya KPD itu Kartu Penyandang Disabilitas,
disabilitas disensus berdasarkan tingkatan paling rendah,
paling rendah kelurahan ya, kayaknya kelurahan deh, di
setiap kelurahan ada disabilitas di laporkan terus di data,
nanti yang udah punya KPD itu kalo ga salah katanya
mau dapat tujuangan tapi ini isu yang terjadi adalah ini
salah juga ya difabelnya banyak yang udah pura-pura
menerbitkan KPD gitu terus bilang, ini bu kartunya bulan
126
depan jadi, ibu bayarkan ke saya aja tiap bulan sepuluh
ribu, sampe ada yang kaya gitu, petugas kelurahannya
gitu, jadi difabel dijadikan objek.
11. Secara personal bisa
dijelaskan bagaimana
proses mba cheta
menerima diri mba
sebagai seorang
difabel, bagaimana
penyesuaian nya? Dan
bagaimana mba Cheta
kembali menjalankan
tugas sebagai Jurnalis?
Yang pertama saya jawab tentang penyesuaian ya, karna
kadang-kadang perspektif saya dengan tuna netra awal-
awal itu masih beda gitu. Tapi saya masih penyesuaian,
mental saya masih up and down. Tapi alhamdulillah dari
masa saya merasa harus mengakhiri hidup saya itu gak
lama, jadi proses saya dari melihat total ke buta total itu
8 bulan. Saya merasa waktu itu masa-masa paling down
atau drop itu di bulan ke 5 atau bulan ke 4 ya. Saya
sempat berfikir yaudah ya Allah akhiri aja, saya itu udah
gak bisa makan, setiap makan saya muntahin karna saya
pusing dan saya bilang ke mamah saya ini mah gak ada
yang masuk itu selama 8 minggu itu berarti udah 2 bulan
kan. Setiap yang saya makan, masuk dikit muntahin.
Waktu itu berat badan saya turun sampai 9 kilo dalam
waktu sebulan. Saya juga sempat mimpi saya pamit ke
tetangga-tetangga gitu. Udahlah itu masa-masa terendah
saya. Sampai pada saat itu temen saya bilang ada di Mitra
Netra khusus untuk para disabilitas. Nah di Mitra Netra
saya mulai bangkit, mulai belajar laptop, kenal dengan
teman-teman tuna netra yang lain, sharing, banyak
ngobrol juga kalau saya gak sendiri lah di dunia itu. Itu
saya penyesuaiannya 4 bulan. Jadi setelah itu saya balik
lagi ke kantor itu 2017, jadi udah launching lagi Januari
2017. Tapi gak langsung di kanal ya, saya ditempatkan di
127
Jurnalistik Cityzen dulu. Saya di tempatkan di
Indonesiana. Jadi alhamdulillah mungkin itu cara Mas
Komang dan kawan-kawan menyuruh saya pemanasan
lah setelah setahun sebelumnya saya hidup enggak mati
tak mau. Nah saya waktu di Indonesiana, dan pada saat
itu saya bilang ke Mas Komang kalo begini terus saya
bosan, kenapa gak bikin isu difabel aja. Akhirnya saya
presentasi waktu itu di depan teman-teman dan akhirnya
dibuat lah itu kanal difabel, walaupun gak menjanjikan.
12. Apa yang membuat
Mba Cheta masih
teguh menjadi Jurnalis
setelah difabel?
Ini mau jawaban Normatif atau Pragmatis, haha. Oke
Normatifnya dulu ya. Kalau jawaban normatifnya adalah
karena otomatis saya bisa, mau gak mau lah ya, saya udah
punya fasilitas ini di tempo, inilah cara saya empowering
temen-temen yang seperti saya gitu. Saya punya
kemampuan disini, saya punya kesempatan, jadi ini yang
bisa saya berikan buat tempo, balas budi saya, terus
istilahnya saya melakukan sesuatu gitu buat teman-teman
saya yang difabel. Karena saya besarnya di jurnalis
sebagai profesi saya. Tapi kalau ditanya jawaban
pragmatisnya apa ya saya udah karyawan tetap di Tempo,
terus yang kedua tempo ya banyak fasilitasnya terus
walaupun gajinya tidak besar, saya juga udah 10 tahun di
Tempo.
13. Keuntungan Tempo
dengan hadirnya
rubrik ini ? Karna
rubrik ini belum
Saya melihatnya begini, otomatis sebagai industri kita
harus cari klik bait ya, klik viewers dan segala macamnya
itu, adduh, difabel mah jauh banget dari hal itu, saya akui
hal itu tetapi kami punya value, kalau saya melihat dari
128
menjadi rubrik
prioritas kan.?
media landscape sekarang banyak berubahkan
Jurnalisme presisi kalau ga salah namanya, jadi juga
mendidik, jadi jurnalisme presisi itu saya berharap ini
bisa presisi ke isunya dia ga menuai klik bait atau klik
viewers tetapi menuai sebuah value, saya berharap value
ini bisa menjadi humas buat industri media yang lain
kalau masih ada media di Indonesia yang memang
mementingkan Jurnalisme sebagai sarana edukasi, bukan
cuma cari popularitas. Kemaren waktu saya belajar PDT
di bali itu ya, jadi diluar negeri itu, saya ga ngerti deh,
mereka selalu punya perspektif yang bertentangan antara
dunia disabilitas dengan dunia pers, jadi perspektif di
media itu selalu dibilang mencari popularitas, difabel di
anggap hyper heroisme dan objek inspirasi, selalu
menjadi komersial trede, artinya kalau lu ga malang, lu
ga sedih, lu gak mampu, artinya lu ga bisa jadi objek
berita, terus selalu digambarkan sebagai sosok yang
jahat, bermasalah dan kepribadiannya bermasalah juga
karena cacat. Contoh karakter-karakternya. The
Hunchback si bongkok, Kapten Hook yang ga punya
tangan, kakinya serta matanya juga satu, haji bolot yang
budeg, semua digambarkan bodoh kan ? atau si encet
yang dulu, bidadari atau apa ya saya lupa. itu tu karakter
plot device yang artinya digunain sebagai bahan jualan
tapi menurut saya itu jaman dulu, karena setelah itu ada
beberapa teori yang bilang, terutama dari kelly Elis yang
ngomong kalau sekarang media landscape sudah
berubah, social value itu selalu digadang-gadangkan
129
sebagai nilai tambah yang sifatnya intangible artinya ga
selalu berbentuk materi. Contoh Nike produk nike kita
bicara media mainstream artinya semua ya, iklan,
sinetron, radio, media massa dan newsmedia, nike itu
selalu punya produk yang dikhususkan untuk teman-
teman Difabel, contohnya sepatu lari buat temen-temen
Cerebral Palsy, Cerebral Palsy kan ga bisa mengikat tali
sepatu, akhirnya dibuatlah sepatu yang dibelakangnya
ada resleting nya, akhirnya teman-teman Cerebral Palsy
itu bisa lari, ada yang khusus untuk temen-temen
disabilitas dari lahir yang jalannya pake dengkul, pernah
liatkan itu sepatunya dibuat menyesuaikan bentuk
dengkul terus mereka selalu membuat iklan yang ada
kursi rodanya, pemain basket kursi roda, atau yang
lainnya saya pernah melihat waktu saya masih bisa
melihat, pelari yang bisa lari dengan satu kaki, sedangkan
satu kaki lainnya yang model loncat-loncat, sebenarnya
kalau ditanya, waktu itu saya baca beritanya, sebenarnya
di nike itu gada nilai iklannya (Komersil), tapi valuenya
tinggi, orang-orang jadi tahu kalau nike itu punya produk
terakses, selama produk itu terakses berarti bukan hanya
diakses oleh para disabilitas, bisa di akses sama ibu
hamil, orang tua yang juga kesusahan kan maupun anak-
anak. Jadi misalnya anak-anak susah pakai tali sepatu,
pakai sepatu teman-teman yang cerebral palsy pasti
mereka bisa pakai, itu news value yang tidak intangible
maksudnya ga terhitung dari biaya, tapi misalnya ni
kemaren tempo digebukin soal apa, wah dia yang
130
bertentangan sama pemerintah, ada yang bilang tempo itu
nginjek, tapi di satu sisi ketika orang liat tempo punya
humas Difabel orang juga akan ngeh, wah gila ya
medianya luar biasa, tingkat kepercayaan masyarakat
kepada medianya jadi bertambah, Itu yang saya bilang
mempengaruhi leadership. Leadership secara langsung
udah besar udah pasti siapa yang tertarik dengan isu
disabilitas, pertama subjeknya, kita itu minoritas di antara
minoritas, isu perempuan Itu udah termasuk minoritas
kan, isu perempuan terkenal kemana-mana kesetaraan
gender Lgbt dan sebagainya Itu perempuan, tapi dibalik
perempuan itu ada terkandung Penyandang disabilitas
kecil tapi proporsinya dari perempuan, Isu anak-anak
tetap aja kita kalah dengan jumlah subjek, anak-anak
dengan disabilitas berapa, tapi bayangkan diantara
semuanya subjek-subjek yang minoritas ini , perempuan,
suku ras dan agama anak-anak, lgbt ,semua ada
penyandang disabilitasnya. Nggak memandang kan, tapi
kalau ditanya ini penting nggak?, ya otomatis kalau
misalkan mereka yang tidak punya kepentingan terhadap
disabilitas nggak bakal akan baca isu itu, kecuali emang
curious (penasaran), oh ternyata ini dunia baru, oh begini
oh begini atau rasa ingin tahunya tinggi ya baru baca isu
itu yakan. Tapi itu kan minimal sebagai humas buat
tempo ke masyarakat, oh ini ada media yang reliable
masih mengusung isu yang cuman bukan hanya profit
semata, tetapi punya value. Kalau kita pakai ukuran
131
materi ya rubrik ini sangat tidak kontributif, udah isunya
baru, subjeknya jarang, dan konfliknya kurang.
14. Menurut Mba sendiri,
bagaimana fasilitas
dan akses di Kantor
Tempo.co
So Far Alhamdulillah, waktu awal-awal saya tunet (Tuna
Netra) dan gedungnya memang didesain buat yang non
Disabilitas, otomatis saya merasa kurang, jauh, awalnya
ya, tapi mereka berusaha memperbaiki diri, mereka
belajar dari saya otomatis, tapi Tempo waktu itu
alhamdulillah waktu pertama sekali, saya lihat di depan
(Lobby) sudah ada RAMP. Jadi kalau ada pengguna kursi
roda yang mau datang ke kantor Tempo ga perlu naik
tangga, mereka ada RAMP. masuk ke depan ada lift,
cuma buat kami yang Tuna Netra otomatis ga bisa
mengakses lift karena gada suaranya, gada braille juga,
jadi ini lantai berapa, nanya ke sesama penunggang Lift,
saya pernah sekali dulu waktu lantai delapan belum
dibikin, masih gelap, itu saya dari lantai 4 saya mau turun
ke atas eh kebawa ke lantai 8, begitu saya buka ting, kok
hawanya, hawa panas, hawa serem-serem berdebu
kayanya lantai delapan nih, saya tutup aja terus saya
kebawah gitu, jadi pernah tuh saya sempat naik turun di
lift itu sampe 3 kali. pernah juga sekali saya sudah kebelet
pipis pas awal-awal saya buta, adduh ga ada yang bisa di
ajak nih ke bawah, karena kan sebenarnya toilet redaksi
tempo di di bawah di lantai mezanin, jadi satu lantai bagi
dua gitu jadi toiletnya di lantai tanggung di bawah saya
harus turun tangga, biasa saya bergabung sama orang, ini
gada orang, terus saya sudah kebelet pipis banget,
132
akhirnya saya berdiri tu, adduh, mba-mba, mas-mas ada
yang lagi nganggur ga, tiba-tiba mas jaka jawab, kenapa
cheta ? mau pipis mas, akhirnya di anterin. Saya dulu juga
pernah parah, saya dulu pernah wawanara komnas ham
nih, orang komnas HAMnya pertama ga tahu nih kalau
saya Tuna Netra, terus saya bilang ke dua, pak, saya tuna
netra pak, dia minta wawancara di mall, segitu ramenya
coba, saya datang sendiri, karena saya kira cuma dua
doang, saya nunggu di satu restoran kaya begini, saya
tunggu lama dia ga datang-dateng, terus dia tanya, Mba
udah di restoran mana? udah di restoran ini jawab saya,
ga bisa pindah ya mba? waduh pak, saya ini gada yang
anter pak saya sendiri, yaudah saya datang. Baik nih
narasumber saya, duduk, udah selesai wawancara bla bla
bla, terus saya mau pulang nih, tinggal sama dia doang
nih, komisioner Komnas HAM terus saya bilang, pak
saya mau pipis, boleh diantar ke restroom dulu ? akhirnya
Komisioner Komnas Ham itu anterin saya. Sampai saya
pulang saya bilang ke dia, bapak anterin saya aja ke
depan ke satpam, nanti biar saya sama satpam, iya iya iya,
terima kasih ya, baru kali ini saya diwawancara nganterin
wartawannya pipis kata dia, itu kek gitu, hal-hal, hal hal
yang kek gitu, jadi saya menurut orang pada umumnya
bisa dilakukan secara mandiri tapi difabel ga bisa kan
kalau tidak ada akses, gitu, makanya saya bilang saya
paling males, di wawancara di mall yang harus
kedalamnya itu ngelewatin orang banyak, kaya ruangan
luas, kalau beginikan enggak, ini gampangkan kan,
133
pinggir jalan, langsung masuk, kang gojek juga anterin
saya langsung, mba duduk disini ya, saya bisa di anterin
mesan, kek gitu, gitu. itu aksesibilitas yang saya bilang,
tapi ini gapapa loh jangan wah ini saya salah, gpp saya
senang wawancara, diluar gitu senang cuman kalau di
mall itu agak kesulitan, karena masuk kedalam, tukang
ojek juga ga boleh masuk ke dalam, kadang gitu
kesulitannya, selama ada restoran membolehkan tukang
ojek masuk gada masalah, saya sering banget wawancara
sendiri kok, kaya interview cuma ngobrol gitu off the
record atau apa saya masih lakukan hal itu, untuk isu-
isu yang kaya kemarin wanita yang bawa anjing ke
mesjid di bogor itu, itu kan saya wawancara kaya sama
LPSK nya, perempuan itu di taro dimana dan ternyata di
taro di rumah sakit supaya dia tidak di tangkap polisi.
P: Karena dia Disabilias ?
N: iya ternyata dia disabilitas mental
dan ceritanya di kantor polisi kan, tapi ga ini di rumah
sakit, di rumah sakit polri, karena untuk mengamankan
yang di bogor ini karena garis keras atau gimana ya atau
memang garis keras itu ada yang bilang kalau perempuan
itu gada ditaro di kantor polisi perempuan itu saya bakar,
anjingnya itu ditemui mati, sebelum perempuan itu
masuk, anjing itu udah ga tahu, udah habis tersayat-sayat,
terpotong-potong anjing nya ga salah apa-apa padahal,
namanya orang gila gitukan, iya orang-orang itu ga mau
paham, karena mereka mikir gini, kok orang gila bisa
134
nyetir gitu, orang gila kok tau itu masjid, kok tau itu,
justru itu karena gila dia main ke masjid dan dia ga tahu
norma karena saat itu di releps, saat dia ga relaps dia bisa
nyetir, bisa belajar, bisa makan dan bisa berkomunikasi,
bahkan kita ga tahu dia gila gitu. jaman dulu dibilang
Cacat mental, sekarang dikenal dengan istilah Disabilitas
Intelektual dibilangnya.
15. Pernah mendapatkan
Iklan dan kalau boleh
tau klik view perhari
berapa mba? Jika ada
kalau boleh tau siapa
saja yang pasang dan
harganya biasa berapa.
Belum pada taraf ini
16. Bagaimana berita di
rubrik Difabel
disusun, apa saja
temanya, dari mana
biasanya dapat berita,
dan dalam rubrik
tersebut yang paling
berpengaruh dalam
mengambil setiap
keputusan siapa, ada
bias atau tidak
Semua ya, saya Frontlinernya seperti ujung jarum, ketika
saya blowing di rapat perencanaan, ini begini loh ada isu
ini, mereka akan kritis dulu, tanya dulu otomatiskan, ini
gimana, itu gimana, akhirnya ketemu, semua lah, kan di
tempo itu berlayer, ga hanya sendiri, biar gada konflik of
interest, biar tidak ada keberpihakan yang berlebihan
gitu, kita tetap pakai metode saringan, kalau yang
terdekat antara saya dan mbak rini dulu tentunya.
135
17. Secara Struktural siapa
yang mengendalikan
rubrik ini, selain mba
cheat dan mbak rini?
Wartawannya seperti
apa dan proses
distribusi beritanya
gimana
Di Tempo itu cuma kita bertiga, yaitu Mba Rini, saya dan
Dito (kontributor Jogya).
18. Fasilitas apa saja yang
tempo berikan untuk
menunjang kinerja
mba cheta sebagai
Jurnalis
Ya Alhamdulillah ya di Tempo itu pertama yang paling
saya syukuri adalah saya dikasih keren untuk liputan. Jadi
ada Asyer atau pendamping yang menemani saya setiap
liputan. Tempo memang gak menyediakan orangnya
langsung, tapi Tempo memberikan kewenangan dan dana
kepada saya. Support dananya dulu buat ngebayar orang
gitu loh. Akhirnya saya dikasih uang untuk liputan per
hari termasuk ongkos dan keren, tapi keren itu biasanya
kalau makan bensin, itu saya ongkosin lagi. kan gak
masalah dengan hal itu karena dia banyak membantu
saya. Orangnya gak dari Tempo, orangnya bebas. Karena
Tempo itu gak bisa meng-hire yang itu. Di Tempo itu
kalau meng-hire itu prosesnya panjang. Harus ada proses
di HRD. Siapa aja boleh. Saya biasanya suka pake anak
Bravo yang dari UNJ. Bravo kalau gak salah organisasi.
Barisan Relawan dan Volunteer. Mereka itu gak cuma
tangani teman-teman tuna netra, tapi juga tunarungu yang
pakai bahasa isyarat. Mereka bisa ada kayak gitu. kadang
kalau saya sudah benar-benar mentok, saya kadang suka
136
menawarkan diri ke tukang gojek di jalan. Bapak saat ini
mau gak temani saya, saya bayar sekian. Nanti antarin
saya ke toko buku ya. Saya ada seminar di sini, boleh
gak saya diantarin gini gini. Oh iya mbak, paling cuma 2
jam atau 3 jam gitu. 2 jam lah paling lama. Anterin saya
ke narasumber ini saya mau wawancara. Nanti bapak ini
ya ini ini. Saya catat nomor handphonenya ya. Iya boleh.
kadang kayak gitu. Kadang juga saya punya kawan tu.
Kawan SMP yang lagi nganggur kan. Yaudah lu jadi
keren gua aja ya. Iya. Menolong orang juga kan? Iya.
Membuka lapangan juga kan difabel.
19. Bagaimana
pemahaman teman-
teman Jurnalis Mba
Cheta ketika
mengetahui ada
wartawan Difabel,
apakah mereka tau
literasi atau mereka
belum mendapatkan
pemahaman yang baik
tentang dunia
disabilitas
Nah kalau di liputan itu ya saya otomatisnya banyak yang
belum tau, tapi begitu tahu saya buta. Kamu buta? gitu.
Awalnya pertama otomatis adalah diskriminasi atau
meremehkan apa itu pasti ada. Karena mereka berpikir
Oo ini saya disabilitas lagi bisa apa itu ada banyak. Gak
usah teman-teman di liputan ya, tukang gojek aja tu
masih gak percaya saya bekerja sebagai wartawan. Saya
pernah ni dari Sawangan ke sini, ke Palmerah naek gojek
langsung. Mbak mau ke mana?. Mau kerja. Oh kerja.
Mijit di mana? haha. Disangkanya orang buta itu kerja
mijit atau jual kerupuk ya kan. Enggak pak saya kerja. Oh
kerja. iya iya. Di mana kerjanya? Saya kerja di Tempo.
Di website. Tempo namanya. Tempo.co. Oh udah lama?
Udah. Udah lama. Udah belasan tahun. Oh hebat ya.
Bertahan. Terus udah deket-deket Palmerah tu. Ini di
mana mbak kantornya? Masih nanya lagi kan padahal
137
tadi saya sudah bilang. Sesuai titik pak. Di kantor gedung
Tempo. Oh iya iya. Oh mijitnya di situ? haha. Udah
nyampe di Gedung Tempo. Depan gedung lobby. Mbak
ke atasnya bisa? Bisa. Saya diantar sama satpam. Oo
pelanggannya udah banyak ya mbak. Hahaha. Oke deh
pak. Terserah deh. Yaudahlah orang itu gak ngerti ya.
Makanya saya bilang stigma tu ya kayak gitulah stigma.
Saya pernah di Bali waktu sebelum saya ke PMPDT
kemarin. Saya ada program namanya Alpa kan. itu tiga
bulan juga di Bali. Nah saya naek Grab nih. Saya bertiga.
Tunet semua. Eh satu melihat deh. Jadi berempat. 1
melihat. 3 Tunet. Ini kan bertiga turun duluan. Baru saya
nerusin perjalanan saya sendiri kan karena saya paling
jauh. Jadi di Bali itu ada pantai, namanya Pantai Padang-
Padang. Jadi di Pantai padang-padang itu banyak tukang
pijat , di belakangnya gelar handuk. Buka handuk terus
plus-plus gitu. Buat cewek-cowok. Pokoknya sama. Itu
saya ditawarin sama tukang Grab-nya. Mbak. Mbak udah
bekerja? Udah pak. Alhamdulillah. Banyak orderannya?
Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Terus saya bilang.
Orderan apa pak? Ini mbak. Saya sarankan ya mbak.
Mbak kan tunanetra. ini keuntungannya lumayan.
Ooiya!?. Saya penasaran kan saya tanya. Keuntungan
gimana pak? Mbak gelar aja handuk di Pantai Padang-
padang. Terus? Nanti mijat mbak di sana. Kalau bisa
dapat klien, saya gak tau tadi itu klien atau enggak. Terus
klien tadi bayarnya gede mbak, apalagi mau dibawa ke
138
hotel. Terus saya bilang. emangnya bapak ngira kerja
saya apa deh? Mbak massage kan? Ya bukan pak. Buta-
buta gini saya masih kerja pak. Jadi wartawan di tempo.
Oh gitu maaf mbak maaf maaf. Tapi saya jadi tau kan
faktanya. Ternyata ada yang begitu. Saya dua kali pernah
suka begitu. Saya pernah dari Gunadarma masih nenteng
laptop padahal itu udah jam 11.00. Dari mana mbak? Ini
abis nginstall laptop di Astro. Ooh. itu laptop itu dari
klien ya? Dari Tempo pak. Baik ya kliennya. Kalau kerja
malam terus nih? Entah saya yang terlalu hipersensitif
atau gimana, tapi menurut saya itu pertanyaannya gak
mention gitu. Ya pak yang kerjanya jam 09.00 malam
selain saya juga banyak. Padahal saya udah pakai
kerudung kurang apa gitu kan. Tapi ya mereka itu udah
terlanjur terstigma. Katanya ternyata saya juga baru tau
dari teman-teman massage yang gabung di Go-Massage.
Itu kan ada beberapa teman-teman saya yang tunanetra di
situ. Itu memang banyak yang mengalami pelecehan. Jadi
saya rasa karena itu. Ini kan tunanetra gak bisa apa-apa
ya yang dulu yang kerja di Go-Massage atau vokasional.
Jadi mereka sering kayak disuruh ngebantuin. Jadi pernah
ni ada yang ngejebak teman saya namanya Mbak Kus
dari Jawa Timur. Iya mbak kemarin itu ada pelanggan. Di
namanya itu perempuan dia bilang. Terus saya datanglah
karena dia memang massage-nya memang perempuan.
Ternyata yang minta pijat itu laki-laki. Ngakunya
perempuan itu adiknya. Terus saya bilang yaudah kalau
saya pijat tolong ditungguin katanya teman saya ini kan.
139
Tapi karena kawan saya ini Tunetnya total, jadi gak bisa
ke mana-mana juga kan. Pas dia lagi mijat itu tiba-tiba
dia dikunciin dari luar. Jadi perempuan yang nemenin itu
keluar terus teman saya itu di dalam dikunciin. Teman
saya ini memang dijebak ya soalnya udah dia di dalam
terus dia bilang si yang dipijit ini. Mbak. Udahan sampai
sini aja mijitnya. Mau gak mbak bantuin saya dia bilang.
Mau bantuin apa?. Bantu keluarin dengan cara sex self
service gitu. Kata kawan saya, saya di sini cuma disuruh
mijit pak. Saya bukan bertugas buat begitu. Tapi kemarin
banyak temannya yang mau. Tolong sudah kepepet di
dalem kan. Toh mbak ini gak ngeliat. Katanya begitu.
Tolong dibantuin saya mbak. Silahkan aja deh bapak
melakukan kegiatan sendiri katanya gitu. Dan akhirnya
dia ngelakuin itu di depan teman saya walaupun teman
saya gak ngeliat, tapi dia mendengar ya. Menurut saya itu
udah pelecehan banget. Kamu harusnya lapor ke Gojek.
Itu Gojeknya gak perhatian. Yang ngadain itu juga
kemarin punyanya Angkie Yudistia disable enterprise itu
juga gak aware. Yang aware sama itu tu organisasi buruh
migran My Grand Care. Jadi My Grand Care itu
ngumpulin data-data teman-teman yang kerja di Go-
Massage yang dapat pelecehan itu baru dilaporin.
20. Berapa jumlah
disabilitas di Indonesia
? Sampai sekarang itu
kan belum ada data
Oke. Saya berpegangan pada survey atau sensus. Kalau
gak salah BPS tahun 2017. Itu Supas, saya lupa
kepanjangannya. Jadi ada Susenas dan ada Supas kan.
Ada Susenas yang memang survey besar tiap yang 5
140
jelas berapa jumlah
penyandang disabilitas
karena tiap lembaga
atau instansi itu beda-
beda. itu bagaimana
menurut tanggapan
mbak?
tahun sekali. Ada yang Supas setiap tahun. Nah Supas
itu menyatakan bahwa penyandang disabilitas di
Indonesia itu 21.800.000 orang. Jadi saya berpegangan
pada itu. Jadi 1 orang di antara 10 penduduk di Indonesia
adalah penyandang Disabilitas, tapi kan fenomenanya
kayak Ice berg. Di atas kelihatan, di bawah enggak.
Karena disabilitas di desa itu masih banyak yang
dipasung, diumpetin di rumah, gak diakui keluarganya,
gak punya KTP dan gak disensus karena dianggap orang
cacat ya kan. Itu permasalahannya. Ini yang terdata itu
juga saya gak ngerti, apa dari rumah sakit. Disabilitas
yang orang tua yang tadinya gak cacat jadi cacat. Apakah
itu terdata? Itu belum. Kalau misalnya itu kita pakai
maksudnya melihat efek gelembung ya. Itukan bisa 2
atau 3 kali lipat ya kan. Itu yang kita gak pernah sadari.
Sekarang negara maju kayak Amerika aja, 3 di antara 5
orang aja cacat. Mereka mau mengakui hal itu. 3 di antara
5 lho bayangin. Lebih dari setengah berarti kan. Mereka
mengakui hal itu. Makanya sekarang banyak yang kayak
MBIS itulah. Lembaga jaminan sosial gitu. National
Security untuk para difabel. Karena orang nanti ujungnya
ke sana. Mereka udah percaya itu. American Disability
Association itu percaya bahwa semua orang tua itu nanti
akan ke sana. Makanya mereka punya anggapan tahapan
sebelum meninggal itu cacat dulu. Karena sakit. Kalau
ada yang sakit langsung meninggal itu bersyukur
katanya. Tapi ada yang sakitnya itu cacat dulu baru
meninggal. Jadi dia anggapnya stage hidup itu tu bukan
141
cuma lahir, tumbuh, menikah punya anak, tua dan
meninggal. Bukan. Tapi di antara tua dan meninggal itu
ada dulu difabel. Nah itu mereka sudah menyadari itu
kalau di negara-negara sana ya. Jadi mereka mengakui 3
dari 5 itu adalah cacat. Mereka punya buktinya. Mereka
sensus itu. Itu dimasukin ke dalam sensus besar
pertanyaan itu. Misalnya adakah anggota keluarga yang
merupakan penyandang disabilitas. Nanti kalau ada
berapa orang. Terus disabilitasnya apa. Atau sadarkah
anda bahwa anggota keluarga anda adalah seorang
penyandang disabilitas. Karena kan kalau di sana itu
permasalahannya yang tadi saya cerita ODGJ atau
Disabilitas Intelektual. Itukan gak teraba. Sampai mereka
memeriksakan diri ya kan. Tau-tau udah relapse aja. Tau-
tau pingsan. Tau-tau Skizofrenia kan. Nah itu. Kalau di
sana lebih pada gitu terdeteksinya, tapi kalau misalnya
orang-orang buta, tunarungu, disabilitas mental itu mah
udah langsung automatically terkomputerisasi. Itu negara
maju dengan segala tingkat kesehatan, kesadaran akan
kesehatan itu udah setingkat itu. Kalau negara kita,
negara berkembang, itu 1 dari 10. Percaya gak? Nah
harusnya lebih banyak kan. Ngakunya masih 1 dari 10
orang. Padahal gak tau di rumahnya ini orang tua udah
tuli udah budeg sampai gak dengar apa yang dibilang. Oo
gak ada cacat di rumah, gitu.
142
21. Saat ini gimana sih
wajah disabilitas di
media massa kita?
Ya. Itu yang tadi saya masih bilang ya. Fenomena-
fenomena yang masih berlawanan dengan perspektif
difabel secara social board atau empowering board itu tu
masih banyak. Kemarin saya nyatet itu ada empat ya.
Yang pertama namanya Porno Inspirasi yang tadi saya
cerita. Waduh gila tu. Mbak Cheta pergi ke kantor sendiri
tapi buta. Bersyukurlah gue gak buta. Makanya itu saya
naik busway sendiri. Itu porno inspirasi. Bersyukur
karena keadaan orang lain dianggap lebih menyedihkan.
Jadi dia bersyukur dia sendiri itu porno inspirasi, jadi
inspirasinya porno. Gak bener gitu. Terus yang kedua
Karakter Plot. Jadi untuk jualan yang tadi disabilitas
kalau misalnya gak harus menyedihkan banget,
rumahnya rombeng, malang banget gitu atau yang jahat
banget itu susah. Iya gak bisa digoreng. Terus yang ketiga
cenderung pilih kan. Isu disabilitas itu bisa di-hold
bayangkan satu tahun. Kejadiannya kapan nunggu
sampai malang bangetlah pokoknya. Udah sekarat,
kejek-kejek nih. Gitu tu baru tuh. Itu ada yang kayak gitu.
Atau yang ngeselin diambil tuh duitnya. Kalian ingat gak
jalinan kasih Indosiar? Tapi ini jangan ditulis ya. Ini
contoh salah satunya. Kalau gak cacat banget gak usah.
Itu ada yang kayak gitu. Itu yang ketiga ya dipilih isunya.
Nah yang keempat Hyperheroism. Ini yang sebenarnya
terjadi di Kick Andy, tapi jangan ditulis lagi. Ini menurut
saya ya, di Kick Andy itu, ada nih tunanetra kan emang
udah dari sananya perginya pake suara kan gak mungkin
pake penglihatan. Banyak yang bekerja di bidang musik.
143
Banyak sebenarnya. Tapi ni tunanetra bikin lagu.
Lagunya apa? Jingle Indomilk atau apa gitu. Terus
diceritain. Hebat. Dapat Kick Andy Award misalnya.
Sampai dulu pernah ada satu, ini off the record lagi ya,
nama tunanetranya Ramaditya Dikara, dia mengaku yang
nyiptain jingle untuk Game Mario Bross. Bayangin coba.
Itukan fatal banget ya. Itu Kick Andy gak check re-check
lagi, itu pihak Mario Bross protes. Itu yang nyiptain ya
gamers-nya. Ramaditya ini bukan. Cuma karena dia
tuntutan dia anak pertama, keluarganya banyak yang
hebat. Dia tu kayak harus gitu. Itu tu gak dicek ulang oleh
Kick Andy. Nah itu Hyperheroism. Menurut saya
sebenarnya itu adalah hal biasa. Misalnya tunanetra
menulis buku. Biasa kan sebenarnya. Tiba-tiba dapat
Kick Andy Award gara-gara dia nulis buku. Terus saya
tanya bukunya bagus gak? Enggak sih mbak. Cuma isi
diary-nya doang sama rumah tangganya dia. Udah kayak
seleb ni dia pengen punya anak terus tiba-tiba dia nulis
mau punya anak gimana. Itu menurut saya
Hyperheroism. Nah jadi Hiperheroisme yang terlalu
berlebihan yang sebenarnya biasa aja gitu, tapi dianggap
hebat. Tunanetra bisa ngulek sambel, woah hebat.
Tunanetra bisa jalan kaki dari sini ke sana, woah hebat.
Padahal itu hal biasa.
22.
Pemberitaan tentang
Disabilitas di
Indonesia cenderung
Ya. Padahal semua di daerah itu banyak. Banyak banget.
Ada yang pelari dulu tu di Asian Para Game dapat
emasnya itu gak tanggung-tanggung ya. 5 kalau gak
144
Jakarta sentris, apa
tanggapan anda?
salah. Terus dia pulang jarang olahraga kena diabetes dan
TBC. Udah itu gak ada yang cover abis itu. Jadi
Hyperheroism nya dulu giliran kayak gini tu gak ada
yang ngangkat lagi. Elias Pikal misalnya Sakit Stroke gak
ada yang tau kan. Itu difabel juga. Untung Muhammad
Ali dulu Parkinson ada yang ngangkat kan. Parkinson itu
disabilitas juga kan. Ya karena dia Legend juga. Ya
gitulah ya. Itu yang terjadi. Itu fenomenanya di jurnalistik
ini. Jurnalismenya yang seperti ini. Jadi ada 4 yang saya
catat. Berlawanan ya, tapi ada juga kok argumentasi lagi
dari medianya. Jadi 4 argumentasi dari media itu kalau
gak salah yang pertama adalah sekarang media lebih
berorientasi pada value ya kan dibandingin cuman
readership rate tingkat keterbacaan. Karena sekarang
ternyata pembaca itu gak bisa di-drive oleh berita. Ya
gak? Sekarang pembaca itu lebih aware, lebih cerdas.
Jadi gak bisa disetir. Terus nilai sosialnya berubah.
Tingkat readership jadi gak begitu penting. Karena
ternyata media yang punya nilai social value yang lebih
tinggi itu banyak juga yang baca. Contohnya Tirto. Ya
kan? Tirto emang bikin isunya banyak yang ini? Gak
kan? Isu-isu pasti banyak sosial, in-depth, tapi banyak
yang gemari ya kan? itu yang kayak gitu. Terus yang
terakhir apa gitu saya lupa. Ya Jurnalisme Data ya.
Jurnalisme Presisi itu ya. Terus DAAI TV. Ya kan?
Walaupun gak ada yang nonton, ujung-ujungnya kita tu
punya alternatif pilihan buat ditonton dan dibaca ya kan?
Gak harus running news Corona, Corona semua. Cuma
145
jeleknya, jeleknya ni ya, jeleknya media online kita kan
sering pakai News Pack yang lagi laku nih misalnya biar
buat apa ya yang ngangkat sedikit gitulah. Kita pake
News Pack Corona gitulah. Kita cari berita yang ada
kaitan difabel dengan Corona lah. Itu gak bisa dipungkiri
lagi. Itulah industri ya. Tapi tetap core-nya Social Value.
DAAI TV juga gitu. Terus ada yang media internal yang
tadi saya cerita, Solider itu d Jogja, tapi sayangnya dia
bukan media mainstream. Jadi media untuk LSM dan
komunitas. Dia khusus lebih hardcore lagi. Isu tentang
disabilitasnya lebih dalam lagi. Mana kalau nulis itu
beritanya panjang ke mana-mana. Kadang kalau baca itu
capek ya gitu. Tapi ya itu mereka saking hardcore-nya.
Aktivisnya itu ini banget. Di Makassar itu PerDIK. Tapi
sayang banget sih media ini untuk LSM. Pustaka PerDIK
namanya. Pergerakan Difabel Untuk Kesetaraan. Nanti
kalau mau kontaknya saya punya nanti saya kasih. Kalau
mau misalnya media yang lain saya gak punya, saya
cuma punya yang tadi itu PerDIK dan Solider yang
isunya benar-benar fokus ke isu difabel. Kalau Tempo
karena inilah saya fikir tadi kan karena ada yang
uncounted juga ya. Karena tiba-tiba ada wartawannya
yang buta terus akhirnya yaudahlah jadi liputan
partisipatif.
23. Kalau misalnya gak
ada Mbak Cheta,
apakah Tempo
Saya gak bisa jawab itu. Ini kewenangannya Mas
Komang. Waktu itu Mas Komang sempat bilang
alasannya salah satu wartawan ada yang disabilitas. Itu
146
memang udah fokus ke
isu ini atau karena ada
Mbak Cheta. Menurut
mbak gimana?
mungkin saya, tapi saya rasa gak cuma itu
pertimbangannya ya. Saya rasa itu terlalu sederhana dan
terlalu istimewa buat saya kalau iya bener sampai begitu.
Hanya karena saya difabel, dibikinlah Rubrik Difabel.
Enggak. Saya yakin Tempo punya News Value lagi yang
dicari. Kalau saya liat, Tempo ini kan media untuk belajar
walaupun gaji gak gede, tapi kalau kalian belajar di
institusi ini kalian akan mendapatkan banyak ilmu. Media
untuk belajar, jadi menurut Tempo ini penting karena
pertimbangannya itu. Ini presisi isunya terus baru bisa
dijadikan pelajaran. Apa aja komponennya. Apa aja
skemanya. Mungkin ya itu yang diteliti. Sama seperti
halnya mereka pertama kali buka Rubrik Gaya Hidup
atau Kesehatan. Seperti itu. Jadi menurut saya bukan
hanya karena wartawannya difabel sih. Cuma mereka
kayak baru oh ada yang begini nih ternyata begini.
Karena ya mungkin momennya baru datang bertepatan
saat saya buta.
P : Mungkin sudah dipikirkan, tapi belum dijalankan.
N : Ya. Tapi belum tereksekusi atau apalah. Mungkin
konsepnya Tempo pas tiap ada presisi misalnya bisnis.
Tapi itu udah lama ya. Yang baru itu Cantik Cantika. Nah
itukan gaya hidup tentang perempuan dan kesehatan
perempuan. Itu kan baru. Dan pertimbangannya ini
kayaknya akan menuai klik yang banyak. Dan ternyata
benar kan. Lumayan. Kalau difabel ini saya rasa Tempo
pada pertimbangan tadi, pada value. Dengan begitu orang
147
Lampiran 1. Wawancara Narasumber Cheta Nilawati
Narasumber : Cheta Nilawati (Reporter rubrik difabel tempo.co)
Tanggal : 14 Maret 2020, 15.00 Wib
Tempat : Restoran KFC Simpang Gaplek
juga bakalan tau walaupun Tempo gak menjalankan, tapi
dia tetap ada isu tentang ini. Gak ada media yang mau
buang energi kayak gini. Ini sebenarnya buang energi
banget ya kan.
24. Sebelum di Rubrik
Difabel, Mbak Cheta
konsen di bagian
mana?
Saya termasuk jurnalis yang floating ya, yang udah
keliling. Dulu saya 6 tahun pertama di nasional. Saya
ngepos di KPK. Terus 4 tahun kemudian saya nge-pos di
Gaya Hidup. Terakhir itu saya di Kesehatan, tapi ya gitu.
Gak sehat juga, hehe.
148
Lampiran 2. Wawancara Narasumber Rini Kustiani
RINI KUSTIANI (Editor Rubrik Difabel)
Pertanyaan Penelitian:
Pertanyaan Umum
1. Latar belakang munculnya Difabel Tempo.co
Jawab: Perlu diketahui kalau di tempo itu ada wartawan difabel namanya
cheta, jadi pada satu periode dimana saya punya tim nah cheta salah satu
didalamnya kemudian dia punya diabetas pada satu ketika setelah dicek
ternyata dia punya gangguan di penglihatannya. Dan beriring waktu dia
semakin parah, sempat menjalani operasi namun gagal, sehingga menjadi
tunanetra. Kemudian dia nulis di indonesiana tentang yang ia alami kemudian
tempo mengganggap dia aset sehingga membuat channel khusus rubrik difabel
pada tanggal 18 Juli 2018. Awal mulanya saya rasa seperti itu, hingga
konsisten sampai sekarang.
2. Tujuan Tempo menerbitkan rubrik Difabel
Jawab : Kita ingin publik tau bahwa difabel itu harus diperlakukan seperti apa,
difabel juga punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, tapi caranya
aja yang berbeda. Kebetulan ditahun yang sama juga ada ASEAN Paragames
dimana ini menjadi momentum yang pas, ada pilkada, kemudian oktober ada
ASEAN Paragames, jadi ini menjadi momentum yang pas tempo menerbitkan
rubrik Difabel.
3. Pandangan Tempo.co tentang kebijakan pemerintah terhadap penyandang
Disabilitas.
Jawab : Nah kalo udah ngomongin kebijakan pemerintah ya memang salah
sebenarnya sudut pandang terhadap difabel ya, orang-orang mengganggap
149
difabel itu Charity padahal bukan itu, itu hak asasi mereka loh, mereka
misalnya dapat sumbangan kursi roda nah itu bukan suatu hal yang harus
dikasihani, bukan kemurahan hati orang, tapi itu memang hak dia untuk dapat
itu, terlepas yang ngasih misalnya itu pemerintah ya, itu memang sudah hak
dia. Nah payung hukumnya kan Undang-Undang Nomor 8 2016 ya tentang
disabilitas nah itu belum ada PP turunan kaya Komisi Disabilitas Nasional itu
ya. Ternyata membuat turunan PP Undang-Undang itu cukup rumit karena
satu, sudut pandang tadi, kedua, kewenangan antar lembaga yang harus
mensinkonkan antara kemensos, kemenkes, sama kementrian
ketenagakerjaan.
4. Mohon dijelaskan mengapa Tempo mengambil tema Aksesibilitas,
Insklusivitas dan Rehabilitasi dalam rubrik Difabel. Bagaimana pandangan
Tempo tentang masing-masing aspek tersebut.
Jawab : Itu tiga-tiga nya Cheta yang pegang, saya terus-terang tidak begitu
paham tentang itu apalagi istilah-istilahnya itu saya belajar dari dia. Tapi yang
saya pahami kalo rehabilitasi itu lebih ke penyembuhan, inklusivitas lebih ke
personal atau dia bisa healing diri dia seperti apa, kalo aksebilitas kita udah
tau ya itu lebih ke publik.
5. Bagaimana keberpihakan Tempo terkait dengan masalah disabilitas.
Jawab : Ya tentu saja ada, gini ketika kita punya reporter difabel, saya nanya
ke dia , mekanisme kerja yang nyaman dia seperti apa, agar tidak
memberatkan dia juga. Dia juga bisa kerja diluar, gak harus ke kantor, cuaca
yang tidak bersahabat kadang -kadang ya, jadi kita bisa berkoordinasi lewat
chat.
150
6. Apakah Tempo memberikan keberpihakan dalam kebijakan organisasi
terhadap kelompok difabel? Jika ya, dalam bentuk apa keberpihakan itu
dilakukan ?
Jawab : Tentu, salah satunya dalam rangka penilaian, saya sih kerap kali
ditanya , gimana kinerjanya (difabel), saya sih spesifik ya. Nah dalam hal karir
misalnya, golongan dan jabatan. Disini golongan mereka bisa naik, tapi kan
mungkin kinerja pekerjaannya jabatannya sama, jadi dalam hal ini golongan
mereka bisa naik namun jabatannya tetap, karena itu kan berpengaruh ke
penghasilan.
7. Apakah ada penyandang disabilitas yang menjadi wartawan di rubrik
difabel ?
Jawab : Ada, namanya Cheta. Untuk saat ini hanya dia doang.
8. Saya melihat ada kerjasama Tempo.co dengan Yayasan Mitra Netra
diliputan rubrik difabel saat launching. Mengapa dan bagaimana kerjasama
itu dibangun? Dalam bentuk apa ?
Jawab : Jadi begini, Yayasan Mitra itu yang jembatani kan Cheta. Sejauh yang
saya pahami tadinya kami maunya Yayasan Mitra Netra itu memasok tulisan,
karena mereka kan punya base practice nya kan mereka menyebutnya “Client”
ya, ada client tuna netra dewasa misalnya seperti cheta itu lalu treatment nya
seperti apa, tentu kan psikologisnya dulu, sebenarnya kami berharap dari
mereka itu memasok bahan-bahan tulisan, tetapi mereka sendiri kekurangan
tenaga, nah justru mereka meminta kita untuk meliput, sementara disinikan
yang meliput hanya cheta. Nah karena di tempo ini rubrik difabel belum
dijadikan prioritas, jadi belum sangat di kejar. Disini saya memangku 6 kanal
di tempo yaitu: satu situs sendiri, seleb.tempo.co, gaya.tempo.co,
151
cantik.tempo.co, travel.tempo.co, difabel.tempo.co, dan cantika.tempo.co.
Nah dari 6 ini yang jadi prioritas itu 4, Nah difabel ini belum dijadikan
prioritas, jadi belum dikejar target. Minimal sehari 1 berita, tapi kadang dua
atau tiga berita sih, tergantung.
9. Dampak apa yang diharapkan oleh Tempo dengan kehadiran rubrik ini.
Jawab : Kami berharap kami bisa mengedukasi masyarakat, terutama dalam
memandang difabel itu sendiri.
Pertanyaaan dijawab dengan perspektfi sebagai Reporter dan Editor
Rubrik Difabel (Rini Kustiani & Cheta Nilawati)
1. Apa yang anda pahami tentang kelompok disabilitas?
Jawab : Iya yang tadi, punya potensi, punya kesempatan nah gimana
memberikan ruang untuk mereka. Yang pasti sih harus ditanya dulu ya
karena pernah ada temen difabel datang kesini, cerita-cerita, lucu sih,
tapi bagi saya agak miris sih, tapi mereka menertawakan itu. Sebuah
apa ya kebesaran hati yang begitu ya gak bisa kita pungkiri kalau
melihat mereka jatuhnya kasihan, tapi ketika kita sudah tau potensinya
nah itu yang dikembangkan.
2. Menurut pemahaman anda isu disabilitas di media Tempo.co di lihat
sebagai apa?
152
Jawab : Saya berharap dewan pers menjadikan tempo.co salah satu
contoh media yang mendukung isu disabilitas.
3. Apa yang anda pahami kebijakan redaksional tempo.co terhadap isu
disabilitas di rubrik Difabel
Jawab : Setahuku memang karena kan itu menyangkut kode etik
jurnalistik juga, harusnya tidak diskriminatif, tidak mengandung sara,
dan tidak menyudutkan, terus tentang cover both side menurut saya sih
apa yang tertera di kode etik jurnalistik ya sejalan juga dengan sikap
kanal difabel ini.
4. Secara personal apakah pemahaman anda dalam mehamahi isu disabilitas
ini memberikan pengaruh terhadap diri anda, misalnya anda lebih peduli
dan menghargai terhadap disabilitas.
Jawab : Iya, tentu. Apalagi teman sendiri ya. Saya tau Cheta itu
mampu kemampuannya itu sangat besar, menulis dia bisa disetarakan
dengan wartawan pada umumnya, hanya saja mungkin ada liputan-
liputan tertentu dia perlu pendamping, toh out put nya juga ada, ya
jangan minta dia bikin foto lah kira-kira begitu.
5. Mohon dijelaskan sejauh mana komitmen keberpihakan tempo terhadap
isu ini ? Apakah hanya memberikan ruang di media atau pada taraf bisa
menekan pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap penyandang
disabilitas ?
Jawab : Oke, kalau yang sejauh ini memang penekanan terhadap
pemerintah belum terlalu ya . Apakah itu bisa dimaknai menekan
153
pemerintah, mudah-mudahan iya, mudah-mudahan , tapi yang jelas
sikap redaksi tentang isu difabel ya akan tetap sama, tidak akan
berubah. Tetap progresif beritanya, sesuai fakta, bahwa mungkin itu
akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan
yaitu kan bagian dari fungsi media.