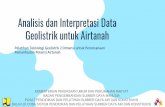Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (2008) (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
Transcript of Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (2008) (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
1
Konservasi Airtanah
”Sebuah Pemikiran”
2008
Heru Hendrayana ([email protected],id) Doni Prakasa Eka Putra ([email protected])
Jurusan Teknik Geologi – Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Airtanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah. Airtanah merupakan sumber air utama bagi makhluk hidup,
khususnya bagi manusia. Akan tetapi dari tahun ke tahun persediaan airtanah
yang ada di bumi ini kian menipis bahkan dikatakan untuk masa mendatang
pesediaan airtanah di bumi ini akan habis jika manusia terus menerus
mengeksploitasi airtanah dengan maksimal tanpa memikirkan pengelolaannya.
Pengelolaan airtanah sangat diperlukan baik secara teknis maupun non teknis,
disesuaikan dengan perilaku airtanah meliputi keterdapatan, penyebaran,
ketersediaan, dan kualitas airtanah serta lingkungan keberadaannya. Kegiatan
pengelolaan airtanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau,
dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan konservasi, pendayagunaan
airtanah dan pengendalian daya rusak airtanah. Pengelolaan airtanah perlu
diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pendayagunaan airtanah
dan upaya konservasi.
Konservasi airtanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan
keadaan, sifat, dan fungsi airtanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas
dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
2
pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi airtanah
dilakukan secara menyeluruh pada cekungan airtanah, mencakup daerah
imbuhan dan daerah lepasan airtanah. Kegiatan konservasi airtanah antara
lain mencakup:
1. perlindungan dan pelestarian airtanah;
2. pengawetan airtanah dan penghematan airtanah;
3. penentuan zona konservasi airtanah.
Kegiatan konservasi airtanah merupakan bagian dari pengelolaan sumber
daya air tepadu, telah diatur dalam UU Sumber Daya Air BAB III, yang
kemudian diperinci dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai
Airtanah Tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, kegiatan konservasi airtanah,
masih memerlukan pedoman yang lebih rinci agar kegiatan konservasi tersebut
dapat berjalan dengan optimal.
Agar kegiatan konservasi berjalan optimal dibutuhkan Peraturan Menteri
(Permen) yang berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam pengelolaan
airtanah khususnya pada kegiatan konservasi airtanah. Kegiatan penyusunan
Permen ini berupa pembuatan naskah akademik dan sosialisasi khususnya
mengenai konservasi airtanah. Permen tersebut diharapkan dapat dipahami
oleh semua stakeholder mulai dari pemerintah, instansl terkait, pihak industri
dan masyarakat, dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pengelolaan airtanah khususnya yeng berbasis konservasi.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari tulisan ini adalah menyusun rancangan peraturan menteri tentang
konservasi airtanah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan
pengelolaan airtanah khususnya yang berbasis konservasi.
Tujuan dari tulisan ini adalah tersedianya Peraturan Menteri mengenai
konservasi airtanah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi stakeholder
mulai dari pemerintah, instansi terkait, pihak industri dan masyarakat, dalarn
pelaksanaan pengelolaan airtanah khususnya yeng berbasis konservasi.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
3
I.3 SASARAN
Sasaran dari tulisan ini adalah:
1) Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebaga acuan bagi
Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan konservasi
airtanah.
2) Tersedianya acuan bagi pelaksanaan pengelolaan airtanah terutama
dalam memanfaatkan airtanah tanpa menimbulkan dampak yang
merugikan.
3) Terciptanya pelaksanaan pengelolaan airtanah terutama kegiatan
konservasi airtanah sesuai dengan amanat UU No. 7 tahun 2004
tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah tentang Airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
4
BAB II
BATASAN KONSEPTUAL KONSERVASI DAN PENGENDALIAN AIRTANAH DALAM KERANGKA
PENGELOLAAN AIRTANAH
Pengelolaan airtanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan konservasi,
pendayagunaan airtanah dan pengendalian daya rusak airtanah.
Perkembangan pemanfaatan airtanah yang berkelanjutan membutuhkan
konsep pengelolaan airtanah yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Pada
dasarnya pengelolaan airtanah bertujuan untuk menselaraskan kesetimbangan
pemanfaatan dalam kerangka kuantitas dan kualitas dengan pertumbuhan
kebutuhan akan air yang meningkat dengan tajam. Penerapan pengelolaan
airtanah sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya penurunan kuantitas dan
kualitas airtanah akibat pengambilan airtanah dan pencemaran airtanah oleh
manusia. Oleh sebab itu, pengelolaan airtanah tidak saja merupakan upaya
mengelola sumber daya airtanah (managing aquifer resources) tetapi juga
upaya mengelola manusia yang memanfaatkannya (managing people).
Pengelolaan airtanah sangat diperlukan baik secara teknis maupun non teknis
untuk menghindari degradasi airtanah yang serius (baik kuantitas maupun
kualitasnya), dimana pengelolaan ini harus disesuaikan dengan perilaku
airtanah meliputi keterdapatan, penyebaran, ketersediaan, dan kualitas
airtanah serta lingkungan keberadaannya. Pengelolaan airtanah perlu
diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pendayagunaan airtanah
dan upaya konservasi serta pengendaliannya.
Dalam kerangka pemanfaatan airtanah yang berkelanjutan pada suatu wilayah
cekuangan airtanah, terdapat empat komponen teknis pengelolaan airtanah
penting yang harus diperhatikan yaitu:
1. Resource Evaluation: Evaluasi Potensi Sumber Daya Airtanah
2. Resource Allocation: Alokasi Sumber Daya Airtanah yang tepat
3. Hazard and Risk Assessment: Kajian bahaya dan resiko pemanfaatan
airtanah dan atau pencemaran airtanah
4. Side Effect and/or Pollution Control: Pengendalian dan pengontrolan
efek negative pemanfaatan airtanah dan atau pencemaran airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
5
Menilik peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah (termasuk
didalamnya rancangan peraturan) mengenai pengelolaan airtanah, ke-empat
hal tersebut umumnya telah dipertimbangkan, walau terkemas dalam istilah
dan urutan yang berbeda.
Berdasarkan arti dari pengelolaan airtanah, konservasi airtanah merupakan
salah satu komponen pengelolaan. Arti dari konservasi airtanah adalah upaya
menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung, fungsi
airtanah serta mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan airtanah.
Disebutkan juga bahwa konservasi airtanah dilaksanakan melalui: (a)
penentuan zona konservasi airtanah, (b) perlindungan dan pelestarian
airtanah, (c) pengawetan airtanah, (d) pengelolaan kualitas dan pengendalian
pencemaran airtanah, (e) pengendalian penurunan kuantitas airtanah dan (f)
pemulihan airtanah. Penjelasan ini berarti secara konsep tindakan konservasi
airtanah meliputi juga tindakan pengendalian airtanah, sehingga batas antara
kedua istilah ini menjadi saling tumpang tindih. Beberap literatur/pustaka
menggabungkan kedua istilah ini dalam satu istilah yang disebut perlindungan
airtanah (groundwater protection). Dimana, secara umum strategi perlindungan
airtanah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu (1) perlindungan alamiah (natural
protection), (2) tindakan pencegahan (preventive actions) dan (3) tindakan
koreksi (corrective actions)
Berkaitan dengan pembuatan pedoman konservasi dan pengendalian airtanah,
batasan antara konservasi dan pengendalian airtanah perlu diperjelas agar isi
kedua pedoman ini tidak saling tumpang tindih atau hanya merupakan
perulangan. Untuk itu dengan berdasarkan ke-empat faktor teknis dalam
pengelolaan airtanah, batasan konservasi dan pengendalian harus ditetapkan.
Secara umum komponen teknis pengelolaan airtanah, dapat dibagi menjadi
dua kelompok yaitu:
1. Komponen teknis yang berkaitan dengan sumber daya airtanah, dan
2. Komponen teknis kajian bahaya/resiko pemanfaatan dan pencemaran
airtanah.
Didalam mewujudkan pemanfataan airtanah yang berkelanjutan, komponen
sumber daya airtanah adalah komponen yang wajib untuk dikonservasi demi
mempertahankan keberadaan airtanah baik kuantitas maupun kualitasnya
(lihat Gambar 1). Di sisi lain, pemanfaatan airtanah yang berkelanjutan juga
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
6
harus ditunjang dengan pengendalian terhadap aktivitas eksploitasi airtanah
dan pencemaran airtanah (lihat Gambar 2). Berdasarkan pemikiran sederhana
ini, batasan konseptual antara tindakan konservasi dan pengendalian airtanah
dapat ditetapkan seperti diperlihatkan pada gambar 3. Pada gambar ini, yang
dimaksudkan dengan konservasi airtanah adalah segala tindakan melindungi
airtanah dengan cara melestarikan mengawetkan sumber daya airtanah dan
penghematan pemanfaatan sumber daya airtanah. Tindakan pelestarian,
pengawetan dan penghematan ini harus didasarkan pada hasil evaluasi
kondisi sumber daya airtanah dan alokasi pemanfaatan sumber daya airtanah
ini. Sedangkan pengendalian airtanah adalah segala tindakan melindungi
airtanah dengan cara mengendalikan efek negatif yang dapat muncul akibat
pemanfaatan airtanah dan pencemaran airtanah.
Gambar 1. Komponen yang harus dikonservasi dalam kerangka pemanfaatan airtanah yang berkelanjutan.
Evaluasi Sumber
Daya Airtanah
Alokasi Sumber Daya Airtanah
Potensi/Tata Guna Sumber Daya
Aitranah
Pemanfaatan Airtanah yang Berkelanjutan
Harus Dikonservasi
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
7
Gambar 2. Komponen yang harus dikendalikan dalam kerangka pemanfaatan airtanah yang berkelanjutan.
Berdasarkan penjelasan diatas maka konservasi airtanah merupakan tindakan
melindungi airtanah dengan strategi perlindungan alamiah (natural protection)
dan tindakan pencegahan (preventive actions) untuk mempertahankan potensi
dan alokasi sumber daya airtanah. Sedangkan tindakan pengendalian airtanah
adalah tindakan perlindungan airtanah dengan strategi tindakan pencegahan
(preventive actions) dan tindakan koreksi (corrective actions) terhadap
pengambilan dan atau pemanfaatan airtanah serta pencemaran airtanah yang
terjadi. Perlu digarisbawahi bahwa tindakan pencegahan lebih masuk akal
karena umumnya lebih mudah dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dan
dengan biaya yang lebih rendah daripada tindakan koreksi yang umumnya
membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.
Kajian Bahaya/Resiko
Efek Samping Eksploitasi dan
Pencemaran Airtanah
Berhubungan dengan aktivitas
pengambilan airtanah dan pencemaran
airtanah
Pemanfaatan Airtanah yang
Berkelanjutan
Harus Dikendalikan
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
8
Gambar 3. Skema Konservasi dan Pengendalian Airtanah dalam Menunjang Pemanfaatan Airtanah Yang Berkelanjutan.
Evaluasi Potensi
Sumber Daya Airtanah
Kajian Bahaya dan Resiko Pemanfaatan dan Pencemaran
Airtanah
Alokasi Sumber Daya Airtanah
Pengendalian Efek Negatif Pemanfaatan dan Pencemaran
Airtanah
Konservasi Pengendalian
Tindakan Pelestarian,
Pengawetan dan Penghematan Sumber
Daya Airtanah
Tindakan Pengendalian untuk menghindari
timbulnya efek negatif pemanfaatan airtanah dan
pencemaran airtanah
GGrroouunnddwwaatteerr RReessoouurrcceess
PPootteennttiiaall GGrroouunnddwwaatteerr AAbbssttrraaccttiioonn
aanndd PPoolllluuttiioonn
KKoommppoonneenn TTeekknniiss PPeennggeelloollaaaann AAiirrttaannaahh PPaaddaa
SSuuaattuu WWiillaayyaahh CCeekkuunnggaann AAiirrttaannaahh
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
9
BAB III
KONSERVASI AIRTANAH
III.1. Etika Konservasi Airtanah
Kurang lebih 95% air tawar yang ada di bumi ditemukan tersimpan di dalam
akuifer-akuifer airtanah dan tidak berada pada danau-danau atau sungai-
sungai di permukaan tanah. Bahkan akuifer-akuifer ini memberikan suplai air
yang sangat berharga bagi sungai-sungai di permukaan. Oleh karena itu,
airtanah adalah sumber daya penting yang memerlukan konservasi, sehingga
pemanfaatannya dapat berkelanjutan bukan hanya untuk kepentingan manusia
namun juga untuk keseimbangan eko-sistem yang bergantung pada airtanah.
Di Indonesia, kontribusi airtanah sebagai sumber air baku adalah sangat
penting. Kemungkinan hingga saat ini lebih dari 150 juta penduduk Indonesia
terpenuhi kebutuhan air bersihnya dari sumber daya airtanah. Akan tetapi dari
tahun ke tahun persediaan airtanah yang ada akan kian menipis bahkan
dikatakan untuk masa mendatang persediaan airtanah di bumi ini akan habis
jika ekploitasi airtanah dilakukan secara maksimal tanpa memikirkan
pengelolaannya. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat kebutuhan air akan
meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan daerah
urban, peningkatan jumlah air yang digunakan per kapita, peningkatan
kebutuhan sanitasi, peningkatan kebutuhan industri dan pertanian, serta
tantangan lain yang sejalan dengan kemajuan peradaban kehidupan manusia.
Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan di dalam
perencanaan dan pengelolaan airtanah, jika sumber daya airtanah ingin
dipergunakan secara berkelanjutan, yaitu: (1) airtanah adalah sumber daya
yang sangat berharga dan dapat diperbaharui; airtanah pada umumnya
memiliki kualitas yang baik karena adanya proses purifikasi alamiah, adapun
jika membutuhkan pengolahan terlebih dahulu, umumnya hanya memerlukan
pengolahan yang sederhana. Oleh karena itu, airtanah adalah sumber daya air
yang dapat dikembangkan dengan biaya yang murah, yang memerlukan
teknologi sederhana dalam pengembangannya, (2) Airtanah mengalami
ancaman degradasi baik kuantitas maupun kualitasnya akibat penggunaan dan
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
10
pengelolaan yang tidak benar, (3) Airtanah harus dikelola secara hati-hati jika
diperuntukkan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk
generasi mendatang.
III.2. Strategi Konservasi Airtanah
Konservasi airtanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan
keadaan, sifat, dan fungsi airtanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas
dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik
pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Secara umum strategi
konservasi airtanah dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar; konservasi
alamiah, tindakan pemulihan dan tindakan pencegahan. Pemilihan dari ketiga
strategi konservasi tersebut memerlukan penentuan pilihan yang tepat. Perlu
diingat bahwa penentuan pilihan strategi konservasi tidak memiliki rumusan
tertentu yang dapat memberi garansi bahwa strategi konservasi terpilih akan
tepat dan berhasil bagi suatu daerah atau wilayah cekungan airtanah.
Setiap wilayah cekungan airtanah seharusnya memilih strategi yang sesuai
dengan kondisinya. Hal ini merupakan konsukuensi dari keanekaragaman
sistem airtanah, persepsi lokal tentang permasalahan pengelolaan airtanah,
tradisi sosial dan politik, serta kemampuan pengelolaan dan pembiayaan
program konservasi airtanah. Sehingga apa yang tepat dan berhasil bagi suatu
wilayah cekungan airtanah tertentu belum tentu sesuai untuk diterapkan bagi
wilayah cekungan airtanah yang lain. Tetapi secara umum, prinsip konservasi
airtanah harus berdasarkan pada pengelolaan yang memperhatikan aspek
lingkungan, dan tindakan pencegahan adalah tindakan yang lebih masuk akal
karena tindakan ini umumnya hanya membutuhkan biaya yang lebih murah
daripada tindakan pemulihan yang umumnya mahal, membutuhkan waktu
yang lama serta kadang memerlukan tindakan teknik yang tidak
memungkinkan untuk dilakukan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
11
III.3. Kegiatan Konservasi Airtanah
Konservasi airtanah adalah pengelolaan airtanah untuk menjamin
pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara serta meningkatkan mutunya. Pada
dasarnya merupakan tindakan yang perlu dilakukan dalam mengelola
sumberdaya airtanah agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan
/berkelanjutan.
Untuk dapat melaksanakan konservasi airtanah perlu pemahaman tentang
sifat-sifat, karakteristik airtanah di alam, meliputi antara lain; geometri dan
konfigurasi sistem akuifer, proses pembentukan dan pergerakan airtanah mulai
dari daerah imbuh hingga daerah pelepasan, serta sifat fisik dan kimia
sumberdaya air tersebut.
Kegiatan konservasi airtanah merupakan bagian dari pengelolaan sumber
daya air tepadu, telah diatur dalam UU Sumber Daya Air BAB III, yang
kemudian diperinci dalam Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai
Airtanah Tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, kegiatan konservasi airtanah
masih memerlukan pedoman yang lebih rinci agar kegiatan konservasi tersebut
dapat berjalan dengan optimal.
Berdasarkan batasan antara konservasi dan pengendalian airtanah, konservasi
airtanah antara lain mencakup kegiatan:
1. perlindungan dan pelestarian airtanah;
2. pengawetan dan penghematan airtanah;
3. penentuan zona konservasi airtanah.
Seperti disebutkan diatas, upaya konservasi dilakukan melalui serangkaian
kegiatan meliputi pelestarian, perlindungan, pengawetan yang ditentukan
dalam kerangka zona konservasi airtanah. Pelestarian airtanah merupakan
upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan airtanah agar tidak
mengalami perubahan. Perlindungan airtanah merupakan upaya menjaga
keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan
airtanah, dan termasuk di dalamnya upaya memelihara keberadaan airtanah
agar tersedia sesuai fungsinya. Pengawetan airtanah merupakan upaya
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
12
memelihara kondisi dan lingkungan airtanah agar selalu tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai.
Upaya konservasi airtanah dilaksanakan secara menyeluruh pada wilayah
cekungan airtanah, mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan airtanah
dan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan
pendayagunaan airtanah dan perencanaan tata ruang. Pelaksanaan
pendayagunaan airtanah dan kegiatan lain yang berpotensi mengubah dan
merusak kondisi dan lingkungan airtanah wajib disertai dengan upaya
konservasi airtanah yang dibahas pada beberapa bab terpisah. Setiap upaya
konservasi airtanah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah baik
pusat maupun daerah. Upaya perlindungan dan pelestarian airtanah harus
juga mengikut sertakan peran masyarakat.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
13
BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN AIRTANAH
IV.1. Perlindungan Airtanah
Perlindungan airtanah merupakan upaya menjaga keberadaan serta
mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan airtanah, dan termasuk
didalamnya upaya memelihara keberadaan airtanah agar tersedia sesuai
fungsinya. Cara paling efektif untuk memelihara keberadaan airtanah adalah
dengan menetapkan kawasan lindung airtanah pada satu wilayah cekungan
airtanah atau kawasan sempadan mata air (Basin Management) dan
penetapan zona perlindungan sumber air baku yang berasal dari mataair atau
airtanah (Well Management).
Penetapan kawasan lindung airtanah, terutama dikaitkan dengan perencanaan
pengembangan penggunaan lahan pada suatu wilayah cekungan airtanah.
Kawasan lindung airtanah ditetapkan menurut batas daerah imbuhan airtanah
regional suatu wilayah cekungan airtanah. Penetapan kawasan sempadan
mata air, dimana batasnya ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi
kemunculan dan sebaran mata air. Batas kawasan ini setidaknya harus
mencakup daerah imbuh mata air – mata air tersebut. Batas cekungan airtanah
dan daerah imbuhan airtanah harus ditentukan berdasarkan hasil evaluasi
kondisi dan potensi sumber daya airtanah.
Guna melindungi airtanah secara menyeluruh (kuantitas dan atau kualitas)
pada kawasan lindung airtanah, penggunaan lahan harus diarahkan sebagai
berikut:
1. Tidak ada kawasan pemukiman baru dan pusat-pusat perdagangan di
dalam kawasan lindung airtanah kecuali sistem buangan limbah yang
baik tersedia, pengadaan air bersih disarankan dari PDAM
2. Kawasan industri baru atau perluasan kawasan industri yang ada tidak
terletak di dalam kawasan lindung airtanah, kecuali sistem pengolahan
limbah telah terpasang, sebaiknya juga tidak pada daerah yang
pengambilan airtanahnya terlarang
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
14
3. Tempat pembuangan sampah akhir sebaiknya tidak berada dalam
kawasan lindung airtanah
4. Infrastruktur perhubungan (jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan
udara, dll) serta pengambilan bahan galian untuk bangunan di dalam
kawasan lindung airtanah hanya setelah ada penyelidikan rinci
5. Penggalian dalam kawasan lindung dibatasi atau dilengkapi dengan
upaya-upaya pencegahan.
6. Konservasi penggunaan lahan yang ada sekarang ini, sebaiknya juga
seluruh daerah berhutan dan pertanian.
Tabel 1. Contoh pembagian kawasan lindung airtanah dan implikasi pengelolaannya.
Penetapan zona perlindungan sumber air baku (baik yang berasal dari mata air
maupun airtanah), terutama dikaitkan dengan kesinambungan/keberlanjutan
sumber airtanah (mataair dan atau sumur produksi airtanah) sebagai sumber
air baku masyarakat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Zona
perlindungan ini umumnya dibagi menjadi tiga zona yaitu:
1. Zona 1: area yang mewakili wilayah broncaptering sumur produksi atau
broncaptering mataair.
2. Zona 2: area yang mewakili zona 50 hari waktu tempuh perjalanan
airtanah menuju sumur produksi atau mataair. Waktu tempuh
perjalanan airtanah 50 hari ditetapkan berdasarkan asumsi, bahwa
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
15
mikrobiologi umumnya akan mati setelah menempuh perjalanan 50 hari
dalam airtanah, walaupun hal ini tergantung pada faktor lingkungan
yang lain.
3. Zona 3: zona terluar yang mencakup seluruh catchment area
pemompaan airtanah atau seluruh area imbuhan mataair.
Dalam konsep perlindunganan yang menyeluruh, zona 3 wajib untuk
ditentukan dan dilindungi dalam kerangka perlindungan terhadap kuantitas dan
kualitas airtanahnya. Seperti halnya pada kawasan perlindungan airtanah
tindakan khusus guna melindungi airtanah berkaitan dengan pengaturan tata
guna lahan harus diterapkan pada zona ini. Pengaturan tata guna lahan pada
zona perlindungan sumber air baku ini meliputi:
1. Pembatasan pengembangan atau perubahan tata guna lahan sejak
penerapan zona perlindungan sumber air baku.
2. Pembatasan kegiatan/aktifitas manusia khususnya yang dapat
menurunkan kualitas airtanah, seperti contohnya penggunaan
pestisida, pupuk yang berlebihan pada areal pertanian.
3. Pelarangan pembuangan limbah baik padat atau cair secara
sembarangan; pengaturan dan pembuatan jaringan sanitasi, limbah
secara menyeluruh dan terpadu
4. Termasuk didalamnya larangan lokasi tempat pembuangan sampah
akhir di zona perlindungan sumber air baku.
5. Pembatasan/larangan lain yang dianggap perlu guna melindungi
kuantitas dan kualitas airtanah.
Zona terluar perlindungan sumber air baku ini dapat ditentukan dengan
menggunakan metoda perhitungan manual, pemetaan hidrogeologi hingga
metoda pemodelan numerik airtanah. Hingga saat ini metoda pemodelan
numerik airtanah dianggap sebagai metoda terbaik dalam penentuan batas
zona perlindungan sumber air baku. Namun seringkali pemodelan numerik
membutuhkan data evaluasi kondisi airtanah yang baik dan seringkali tidak
semua daerah di Indonesia memiliki informasi hidrogeologi yang lengkap.
Dalam pedoman ini dijabarkan dua metode yang sederhana dari penentuan
zona terluar perlindungan airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
16
Untuk kasus sumur produksi airtanah, perhitungan manual yang sering
digunakan secara luas adalah konstruksi zona lingkaran/elips dan metoda
perhitungan berdasar karakteristik akuifer yang dikembangkan oleh Todd
(1959). Zona lingkaran ini adalah luasan yang menunjukkan daerah imbuhan
yang diperlukan untuk menyeimbangkan debit pemompaan (Burgess &
Fletcher, 1998). Daerah As (m2) dari luas suatu daerah sumber tangkapan air
didalam area imbuhan tahunan U (meter/detik) dapat dihitung dari hubungan
sederhana dari keseimbangan airtanah :
As = Q / U
Dimana Q debit pemompaan dari suatu sumber (m3/detik) Radius dari zona lingkaran daerah sumber tangkapan air digambarkan sebagai:
r = √ (As/ п) Dimana r radius dari batas sumber tangkapan air dalam meter (m). Berdasarkan data karakteristik akuifer, perhitungan manual dari daerah
tangkapan sumur dapat juga dilakukan. Dalam perhitungan manual, jarak
menuju titik nol atau batas pemompaan downstream dari lubang bor pompa xu
(meter) yaitu :
Lebar maksimum dari daerah tangkapan secara orthogonal hingga arah aliran
B (meter) yaitu :
Dimana: Q debit airtanah (m3/det) T transmisivitas akuifer (m2/det) io gradient hidrolika sebelum pemompaan
Q
2 · п · T ·io
xu =
Q
T ·io
B =
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
17
Lebar maksimum (B) akan ditempatkan pada jarak yang dihitung dari titik nol
ke arah upstream Dwr (meter) yaitu :
Akhirnya, jarak menuju batas pemompaan upstream dari lubang bor
pemompaan Dwo (meter) dapat dihitung seperti :
Dwo = 3 · r50,o Dimana: t50 50 hari = 4.32 x 106 detik kf konduktivitas hidrolika dari akuifer (m/det) M ketebalan akuifer (m) ne porositas efektif ( - ) r50 batas upstream zona 2
Gambar 4. Skema penentuan batas zona 3 pada suatu sumur produksi airtanah sebagai sumber air baku.
Xu2 + (B/2)2
2 · xu
Dwr =
Q · t50
п · M · ne
r50,o = kf · io
ne
+ · t50
Arah aliran airtanah
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
18
Untuk penentuan zona perlindungan mataair, penentuan batas zona menjadi
agak kompleks dibanding dengan penentuan zona perlindungan sumur
produksi. Perhitungan manual seperti dijabarkan diatas tidak tepat
diaplikasikan pada mataair. Cara penentuan batas zona 3 pada mataair yang
paling sederhana adalah dengan mengabungkan hasil penelitian hidrogeologi
mengenai batas-batas sistem mataair dengan prakiraan luasan daerah imbuh
mata air dapat secara kasar diperkirakan menurut hubungan antara debit mata
air dan imbuhan airtanah rata-rata tahunan (Gambar 5).
Gambar 5. Hubungan antara luasan daerah imbuhan mata air, imbuhan
airtanah rata-rata tahunan dan debit mata air (Todd, 1980).
Ketentuan penggunaan lahan di kawasan perlindungan, kawasan sempadan
mataair dan zona perlindungan sumber air baku harus ditetapkan oleh
pemerintah daerah setempat dengan memperhatikan fungsi kelestarian
airtanah baik kuantitas maupun kualitasnya, dan selaras dengan rencana tata
ruang wilayah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
19
IV.2. Pelestarian Airtanah
Pelestarian airtanah merupakan upaya menjaga kelestarian kondisi dan
lingkungan airtanah agar tidak mengalami perubahan. Pelestarian airtanah
dapat dilakukan dengan cara (1) pelestarian fungsi daerah imbuhan airtanah
termasuk mata air dengan vegetasi, (2) pelestarian airtanah dengan penerapan
teknologi dan (3) Pengaturan secara ketat luasan lahan yang boleh dibangun
atau pengaturan penutupan lahan, yang bertujuan untuk memberikan peluang
peresapan air hujan ke dalam tanah.
Pelestarian fungsi daerah imbuhan airtanah dengan cara vegetasi merupakan
upaya konservasi airtanah dengan memanfaatkan peran tumbuhan secara
alami untuk dapat mempertahankan siklus dan dinamika air. Pelestarian
airtanah dengan penghijauan dapat dilakukan pada wilayah dengan beberapa
permasalahan airtanah, seperti fluktuasi tinggi, muka airtanah yang dalam,
kawasan resapan, kawasan lindung, kawasan mataair dan bentuk perairan
permukaan lainnya. Cara vegetasi ini umumnya dimaksudkan untuk
peningkatan infiltrasi air dan pengurangan evaporasi air, yang dapat dilakukan
dengan:
1. Reboisasi atau penghijauan pada lahan-lahan daerah perbukitan berlereng
curam dan pembuatan hutan (penghutanan), yang dapat diterapkan pada
zona kawasan perlindungan airtanah.
2. Pembuatan hutan kota (jantung kota), yang dapat diterapkan pada lahan-
lahan kosong di perkotaan dan kawasan padat hunian kota;
3. Pembuatan jalur hijau berupa penanaman tanaman keras pada tepian
jalan.
4. Pengaturan secara ketat luasan lahan yang boleh dibangun atau
pengaturan penutupan lahan, yang bertujuan untuk memberikan peluang
peresapan air hujan ke dalam tanah, dapat diterapkan pada wilayah atau
kawasan padat hunian.
Ketentuan pengaturan luasan lahan yang boleh dibangun atau pengaturan
penutupan lahan yang masih memberikan peluang peresapan air hujan ke
dalam tanah harus ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
20
Penerapan teknologi untuk melestarikan airtanah dapat dilakukan dengan cara
meningkatkan atau mempertahankan volume imbuhan airtanah. Terdapat
empat metoda umum untuk meningkatkan atau melestarikan imbuhan airtanah
yaitu metoda water harvesting, in-channel structure, off-channel structure dan
injection well (lihat Tabel 2).
Tabel 2. Macam-macam tipe struktur imbuhan buatan airtanah (GW-Mate, 2005).
Tipe Sub-Tipe Penerapan
Water Harvesting
Lubang/sumur gali/tangki resapan
Baik diterapkan untuk pedesaan dimana penduduknya jarang, dengan permeabiltas tanah yang cukup tinggi
terasiring/kontur ploughing/reboisasi/penghutanan
Baik diterapkan untuk daerah dengan kemiringan yang curam dan berada pada bagian atas catchment area
On-Channel Structure
check/dam
Baik diterapkan pada area dimana frekuensi runoff yang tidak tentu/rendah dan kemiringan lembah sungai yang cukup besar
recharge dam
Baik diterapkan pada lembah sungai bagian atas dengan frekuensi runoff yang mencukupi dan kedalaman muka airtanah yang dalam
riverbed baffling; menahan aliran air untuk meningkatkan infiltrasi
Baik diterapkan pada sungai besar teranyam
Subsurface cut-off; membuat parit-parit untuk menahan airtanah
Baik diterapkan pada area endapan aluvial tipis yang menumpang diatas batuan dasar impermeabel
Off-Channel
Tehniques
cekungan buatan Baik diterapkan pada endapan aluvial tebal dengan permebilitas rendah
land spreading Baik diterapkan pada area dengan endapan aluvial yang permeabel
Sumur Injeksi
sumur pemboran Baik diterapkan untuk air limbah yang telah diolah dengan sangat baik
Metoda water harvesting merupakan metoda yang paling dikenal dengan
pembuatan sumur atau lubang resapan (Gambar 6), dan baik diaplikasikan
pada daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Karena penerapan
sumur atau lubang resapan sebaiknya diperuntukkan hanya untuk air hujan,
dan bukan air limpasan permukaan daerah urban (urban runoff) apalagi air
limbah. Beberapa air yang disebutkan terakhir memerlukan perlakukan fisik,
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
21
kimia atau biologis sebelum air tersebut diimbuhkan ke dalam lubang atau
sumur resapan. Peningkatan imbuhan airtanah dengan air berkualitas buruk
akan menyebabkan degradasi kualitas airtanah dan tujuan pelestarian airtanah
tidak akan tercapai seperti yang diharapkan.
Formula penentuan dimensi sumur resapan yang sering digunakan di
Indonesia, dibahas dibawah ini:
1. Formula Sumur Resapan menurut Sunjoto (1998)
21
R
FKT
FK
QH
dengan:
H : tinggi muka air dalam sumur (m) Q : debit air masuk (m3/jam) F : faktor geometrik (m) K : koefisien permeabilitas tanah (m/j) T : durasi dominan hujan R : radius sumur
2. Formula Sumur Resapan menurut Litbang Pemukiman PU (1990)
Formula ini dibangun berdasarkan keseimbangan statik.
PKTA
KTAAITH
s
S
dengan:
H : tinggi air dalam sumur (m) I : intensitas hujan (m/j) A : Luas bidang atap (m2) As : luas tampang sumur (m2) P : keliling sumur K : koefisien permeabilitas tanah (m/j) T : durasi pengaliran (jam)
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
22
Gambar 6. Contoh tipe-tipe sumur resapan (Dep. PU, 2006)
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
23
Formula penentuan dimensi sumur resapan yang sering digunakan di
Indonesia, dibahas di bawah ini:
1. Formula Sumur Resapan menurut Sunjoto (1998)
21
R
FKT
FK
QH
dengan:
H : tinggi muka air dalam sumur (m) Q : debit air masuk (m3/jam) F : faktor geometrik (m) K : koefisien permeabilitas tanah (m/j) T : durasi dominan hujan R : radius sumur
2. Formula Sumur Resapan menurut Litbang Pemukiman PU (1990)
Formula ini dibangun berdasarkan keseimbangan statik.
PKTA
KTAAITH
s
S
dengan:
H : tinggi air dalam sumur (m) I : intensitas hujan (m/j) A : Luas bidang atap (m2) As : luas tampang sumur (m2) P : keliling sumur K : koefisien permeabilitas tanah (m/j) T : durasi pengaliran (jam)
3. Formula Sumur Resapan menurut HMTL-ITB (1990)
Dengan berdasar keseimbangan statik, dibangun suatu fromula empiris
untuk menghitung dimensi sumur resapan yang mendasarkan konsep V.
Breen bahwa hujan terkonsentrasi adalah 90 % dan konsep Horton bahwa
air yang meresap alami adalah 30 % sehingga yang harus diresapkan
adalah 70 %.
1000
6/9,07,0
24
17924
24
d
dRAH
p
j
dengan:
H : tinggi air dalam sumur (m) A : luas bidang atap (m2) d : diameter sumur (m) p : faktor perkolasi (menit/cm)
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
24
R24j : curah hujan terbesar dalam 24 jam (mm/jam) 0,7 : air hujan yang diresapkan (70 %) 0,9 : hujan terkonsentrasi ( 90 %) 1/6 : faktor konversi dari 24 jam ke 4 jam
4. Faktor Geometrik Sumur Resapan
a. Berbentuk bola, seluruh lapisan tanah porus (Samsioe, 1931; Dachler,
1936; Aravin, 1965)
F = 4πR
b. Dasar setengah bola, lapisan tanah bawah porus, atas kedap air (Samsioe,
1931; Dachler, 1936; Aravin, 1965)
F = 2 πR
c. Dasar rata, lapisan tanah bawah porus atas kedap air (Fornhheimer, 1930;
Dachler, 1936; Aravin, 1965)
F = 4R
d. Dasar setengah bola, seluruh lapisan tanah porus (Sunjoto, 1996)
F = π2R
e. Dasar rata, seluruh lapisan tanah porus
Hvorslev (1951): F = 5,5R
Sunjoto (1989) : F = 2 πR
f. Dasar setengah bola, dinding bawah sumur porus, lapisan tanah bawah
porus dan atas kedap air (Sunjoto, 1996)
1ln
2ln2
22
2
RL
RRL
RLF
g. Dasar rata, dinding bawah sumur porus pada lapisan tanah bawah porus
dan atas kedap air
Menurut Dachler (1936):
1ln
2
2
RL
RL
LF
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
25
Menurut Sunjoto (1996):
1ln
2ln2
22RL
RRL
RLF
h. Dasar setengah bola, dinding bawah sumur porus dan seluruh lapisan
tanah porus (Sunjoto, 1996)
1ln
2ln2
2
222
2
RL
RRL
RLF
i. Dasar rata, dinding bawah sumur porus dan seluruh lapisan tanah porus
Menurut Dachler (1936):
1ln
2
2
22 RL
RL
LF
Menurut Sunjoto (1996):
1ln
2ln2
2
222
RL
RRL
RLF
j. Dasar setengah bola seluruh dinding porus dan seluruh lapisan tanah porus
(Sunjoto, 1996)
1ln
2ln2
2
52
5
22
2
RH
R
RH
RHF
k. Dasar rata, seluruh dinding sumur porus dan seluruh lapisan tanah porus
(Sunjoto, 1996)
1ln
2ln2
2
52
5
22
RH
R
RH
RHF
F : Faktorgeometrik sumur resapan (m) R : Radius sumur H : Tinggi muka air dalam sumur (m)
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
26
Formula penentuan dimensi parit resapan air hujan yang sering digunakan di
Indonesia, dibahas dibawah ini :
1. Formula Luas Bidang Resapan menurut HMTL – ITB (1990)
Bidang resapan ini merupakan parit dengan kedalaman sekitar 1 m yang
diisi pasir dan kerikil. Air dari atap dialirkan melalui pipa porus sepanjang
parit dengan letak 70 cm dari dasar parit. Dengan demikian luas (
pandangan atas ) dihitung dengan formula yang didasarkan pada asas V.
Breen yang banyak digunakan untuk limpasan permukaan telah diturunkan
suatu persamaan sbb :
128
69,07,0 24 pRAA
j
br
dengan :
Abr : luas bidang resapan ( m2 ) A : luas atap ( m2 ) R24j : curah hujan rerata maksimum ( mm/hr ) p : faktor perkolasi
2. Formula Panjang Parit menurut Sunjoto (1996)
Secara analitis Sunjoto menurunkan formula ini dengan asas
kesetimbangan dinamik sbb :
Q
HKfb
TKfB
1ln
dengan :
B : panjang parit ( m ) b : lebar parit ( m ) f : faktor geometrik parit ( m ) K : koefisien permeabilitas tanah ( m / jam ) H : tinggi air dalam parit ( m ) Q : debit masuk ( m3 / detik )
3. Formula Faktor Geometrik Parit menurut Sunjoto (1996)
Menurut Sunjoto harga dari faktor geometrik parit ( f ) diturunkan dari faktor
geometrik sumur ( F ) dengan dasar bahwa keliling sumur sama dengan
keliling parit yang berbentuk bujur sangkar yang besarnya merupakan
kelipatan dari ( b + B ), yaitu jumlah panjang dan lebar parit yang tiap
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
27
keadaan harganya tergantung dari keadaan sumur serta peletakkannya
dengan lapisan tanah. Kemudian besaran ini dikoreksi oleh faktor luas yaitu
walau keliling sama besar namun bila bentuk bukan lagi bujur sangkar
maka harganya akan mengecil dengan harga koreksi sebesar ( 2 √ b B ) / (
b + B ) yang berasal dari akar panjang kali lebar parit dibagi akar dari
setengah jumlah panjang dengan lebar kuadrat.
a. Tampang lingkaran, seluruh lapisan tanah porus.
Bbf 8
b. Dasar setengah lingkaran, lapisan tanah bawah porus atas kedap air.
Bbf 4
c. Dasar rata, lapisan tanah bawah porus atas kedap air.
Bbf /8
d. Dasar setengah lingkaran, seluruh lapisan tanah porus.
Bbf 2
e. Dasar rata, seluruh lapisan tanah porus.
Bbf 4
f. Dasar setengah lingkaran, dinding bawah parit porus pada lapisan tanah
bawah porus dan atas kedap air.
12
ln
2ln24
2
Bb
L
Bb
BbL
BbLf
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
28
g. Dasar rata, dinding bawah parit porus pada lapisan tanah bawah porus dan
atas kedap air.
12
ln
2ln4
2
Bb
L
Bb
BbL
BbLf
h. Dasar setengah lingkaran, dinding bawah parit porus dan seluruh lapisan
tanah porus.
122
2ln
2ln24
2
Bb
L
Bb
BbL
BbLf
i. Dasar rata, dinding bawah parit porus dan seluruh lapisan tanah porus.
122
2ln
2ln4
2
Bb
L
Bb
BbL
BbLf
j. Dasar setengah lingkaran, seluruh dinding parit porus dan seluruh lapisan
tanah porus.
15
2
5
22ln
2ln24
2
Bb
H
Bb
BbH
BbHf
k. Dasar rata, seluruh dinding parit porus dan seluruh lapisan tanah porus.
15
2
5
22ln
2ln4
2
Bb
H
Bb
BbH
BbHf
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
29
Metoda in-channel atau off-channel structure, dilakukan dengan membuat
dam, danau, waduk atau kolam resapan buatan. Secara alami, hanya sebagian
kecil air permukaan akan mencapai airtanah, sehingga usaha konservasi
dengan membuat in-channel atau off-channel structure adalah upaya yang
logis untuk meningkatkan pengisian airtanah dari air permukaan (Gambar 7).
Gambar 7. Waduk resapan pada suatu aliran sungai.
Pada metoda in-channel structure, metoda pengisian airtanah dengan cara
memanfaatkan aliran sungai yang ada, dimana pada saluran sungai tersebut
dibangun beberapa "check dam" berukuran relatif kecil secara melebar atau
melintang memotong aliran. Dengan adanya beberapa "check dam" yang
memotong aliran tersebut, dimaksudkan untuk memperlambat jalannya aliran
sungai dan memperpanjang waktu kontak antara air dan dasar sungai,
sehingga akan memperbesar jumlah peresapan air sungai ke dalam lapisan
tanah/batuan di bawahnya.
Metoda in-channel structure baik dipergunakan pada sungai losing stream,
yaitu sungai yang mempunyai muka air yang lebih tinggi dari pada muka
airtanah di daerah tersebut. Dengan demikian sungai tersebut akan mampu
meresapkan dan menambah air ke dalam akuifer di sekitamya. Keuntungan
metoda ini adalah mempunyai daerah kontak antara air dan pemukaan tanah
yang relatif luas, waktu kontak cukup lama, dengan demikian jumlah
peresapan air ke dalam tanah/batuan sangat besar. Disamping itu kualitas
airtanah yang didapatkan cukup baik dan pada metoda ini tidak memerlukan
perawatan serta konstruksi khusus. Sedangkan kelemahan metoda ini antara
lain apabila terjadi banjir, pada dasar sungai akan terendapkan material-
material halus maupun kasar yang mengakibatkan tertutupnya pori-pori
tanah/batuan, sehingga memperkecil jumlah peresapan. Dalam
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
30
perencanaannya metoda ini memerlukan penelitian yang cukup detail dari
daerah sepanjang aliran sungai dan sekitamya, serta daerah hulu sungai,
meliputi daerah pengisian (recharge area) ataupun daerah penangkapan titik-
titik air hujan (catchment area).
Salah satu bagian dari metoda imbuhan off-channel structure disebut juga
sebagai metoda imbuhan airtanah cekungan. Pada metode ini air yang akan
dipergunakan dalam pengisian dialirkan ke dalam suatu cekungan yang dibuat
dengan cara penggalian ataupun dengan cara pembuatan tanggul dan dam
kecil. Dimensi cekungan bervariasi dari beberapa meter hingga beberapa ratus
meter. Umumnya air yang dipergunakan berasal dari pemompaan sumber air
permukaan yang berada di dekat cekungan, dimana air tersebut diharapkan
bebas lumpur dan pengotoran-pengotoran lain. Hal ini untuk menghindari
tertutupnya dasar cekungan selama pengisian, yang dapat mengakibatkan
terhalangnya peresapan air ke dalam tanah/batuan. Metode ini banyak
dipergunakan dalam pengisian airtanah, karena memerlukan perawatan yang
relatif mudah, dapat meresapkan air dalam jumlah yang besar dan merupakan
cara yang paling mungkin diterapkan di berbagai daerah. Kecepatan pengisian
airtanah dengan mempergunakan metoda ini pada setiap daerah tidak selalu
sama, hal ini tergantung pada kondisi tanah/batuan dan beberapa faktor lain
yang berpengaruh.
Cekungan-cekungan imbuhan airtanah ini umumnya dibuat sejajar dengan
aliran sungai, dimana air sungai tersebut dialirkan ke dalam cekungan (melalui
pipa-pipa saluran atau teknik lainnya). Cekungan yang pertama diisi air sungai
hingga penuh, kelebihan aimya akan disalurkan pada cekungan yang kedua.
Selanjutnya apabila cekungan kedua sudah penuh, maka kelebihan aimya
akan mengalir ke dalam cekungan ketiga, demikian seterusnya hingga pada
cekungan yang terakhir. Kelebihan air pada cekungan yang terakhir akan
disalurkan kembali pada saluran induk atau aliran sungai. Mekanisme
pengisian tersebut berjalan menerus secara berulang, sehingga akan
memperbesar jumlah peresapan air dalam cekungan ke dalam tanah batuan
dan menambah jumlah volume airtanah.
Variasi dari metoda cekungan disebut sebagai metode parit (Furrow method),
yaitu pengisian airtanah ini adalah dengan cara mendistribusikan air
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
31
permukaan pada suatu alur atau parit kecil yang relatif sejajar, dangkal, dan
mempunyai dasar yang rata serta pada suatu daerah tertutup. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mendapatkan kontak semaksimal mungkin antara air dan
permukaan tanah, sehingga peresapan yang terjadi akan mencapai titik
optimum.
Perencanaan parit-parit tersebut dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan
konfigurasi topografi daerah setempat. Saluran-saluran pengisi dan parit-parit
haruslah mempunyai gradien yang cukup besar, sehingga aliran aimya akan
mampu mengangkut material-material halus yang terlarut. Pengendapan
material berukuran halus tersebut akan mengakibatkan tertutupnya pori-pori
dasar saluran, sehingga akan memperkecil jumlah peresapan air ke dalam
tanah/batuan. Pada suatu daerah yang bertopografi tidak beraturan, relatif
terjal dan bergradien sangat besar, metoda parit ini tidak banyak
dipergunakan, sebab pada daerah tersebut mempunyai kontak air dan
permukaan tanah yang minimum, sehingga jumlah peresapannya juga sangat
kecil. Metoda ini dibandingkan dengan metoda cekungan, mempunyai
kecepatan peresapan yang lebih kecil dan memerlukan konstruksi serta
pemeliharaan yang lebih teliti.
Flooding method adalah salah satu metoda imbuhan land spreading. Pada
daerah yang bertopografi relatif datar dan luas, air permukaan yang disebarkan
untuk tujuan pengisian airtanah secara buatan ada kemungkinan akan
menyimpang dan keluar dari daerah pengisian yang telah direncanakan. Untuk
mencegah kemungkinan tersebut, di sekeliling daerah pengisian/daerah
perendaman dibuat parit-parit yang dipergunakan untuk menampung air dan
sebagai pengontrol jumlah air yang ada. Air yang masuk ke dalam parit akan
disalurkan kembali pada saluran induk dan selanjutnya disebarkan kembali
pada daerah perendaman. Dengan demikian akan didapatkan suatu
penyebaran air yang merata, kontak air dan permukaan tanah cukup lama,
kecepatan aliran minimum, sehingga jumlah peresapan mencapai titik
optimum. Kelemahan metoda ini antara lain adalah sering didapatkannya
endapan-endapan lumpur pada daerah perendaman, hal ini disebabkan oleh
kecepatan aliran air yang relatif lambat. Metoda ini dibandingkan dengan
metoda yang lain sangat jarang dipergunakan dalam pengisian airtanah secara
buatan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
32
Pada daerah irigasi sering kali air disebarkan di atas permukaan tanah
mempunyai tujuan untuk memperbesar jumlah cadangan airtanah, disamping
untuk keperluan irigasi daerah pertanian atau persawahan di sekitarnya, yaitu
dengan cara menyalurkan air secara sistematis pada tanah yang diolah melalui
beberapa saluran. Dengan adanya saluran-saluran irigasi tersebut akan
mengakibatkan terjadinya penambahan peresapan air di sepanjang saluran,
sehingga akan menambah pula besar cadangan airtanah di sekitar daerah
irigasi. Metoda pengisian airtanah dengan sistem irigasi ini banyak
dipergunakan pada daerah pertanian ataupun daerah persawahan yang luas.
Keuntungan metoda pengisian ini antara lain mempunyai daerah pengisian
yang sangat luas, tidak memerlukan perawatan yang teliti dan sangat baik
diterapkan di daerah persawahan dan pertanian yang luas.
Pada daerah yang tersusun oleh lapisan batuan bersifat kedap air
("impermeable"), pengisian airtanah dengan cara penyebaran air di atas
permukaan tanah, seperti yang telah dijelaskan di atas tidak akan efektif, dan
jumlah peresapan air ke dalam tanah/batuan relatif sedikit. Apabila lapisan
yang bersifat kedap air tersebut relatif dangkal dan tidak terlalu tebal, maka
pengisian airtanah dapat dilakukan dengan cara menggali atau mengupas
lapisan kedap air terlebih dahulu. Oleh Todd (1980) cara pengisian airtanah
tersebut dinamakan metoda pengisian airtanah melalui lubang galian. Pada
saat-saat tertentu secara periodik dasar lubang pengisian harus dibersihkan
dari endapan lumpur dan material halus yang lain, untuk mencegah tertutupnya
pori-pori tanah/batuan. Metoda ini mempunyai konstruksi yang relatif rumit,
memerlukan perawatan dan pengawasan yang lebih teliti serta mempunyai
kecepatan dan volume pengisian yang kecil dibandingkan dengan metoda
penyebaran air di atas permukaan, maka metoda ini jarang dipergunakan
dalam pengisian airtanah secara buatan.
Metoda Injection Well dalam kerangka peningkatan imbuhan airtanah
dilakukan dengan membuat sumur injeksi air ke dalam akuifer. Seperti halnya
lubang atau sumur resapan, dalam kerangka pelestarian airtanah, air yang
diinjeksi kedalam akuifer harus berkualitas baik. Beberapa air yang berkualitas
buruk seperti air limbah memerlukan perlakukan fisik, kimia atau biologis
sebelum air tersebut diinjeksikan ke dalam sumur injeksi.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
33
Pengisian airtanah melalui sumur injeksi dapat diartikan, memasukkan air
permukaan ke dalam formasi bawah permukaan dengan melalui sumur-sumur
pengisi (Jesus, 1980). Todd (1980) menyebutkan sumur injeksi adalah sumur
yang dipakai untuk memasukkan air dari permukaan ke dalam formasi bawah
permukaan, dimana sumur ini mempunyai konstruksi yang sama dengan
sumur pemompaan/sumur produksi. Sumur injeksi ini sering juga disebut
sebagai "recharge well", "inverted well", "diffusion well" ataupun "disposal well".
Sumur injeksi mempunyai arah aliran yang berlawanan dengan sumur
produksi, sehingga bentuk kerucut muka airtanahnya juga mempunyai bentuk
yang beriawanan. Dimana pada sumur produksi kerucut muka airtanah bersifat
cembung ke arah atas ("cone of depression"), sedangkan pada sumur injeksi
kerucut muka airtanah bersifat cekung ke arah atas ("cone of recharge'').
Perhitungan debit pada sumur injeksi dapat diturunkan dari asumsi Dupuit
yang menerangkan perhitungan debit pada sumur produksi (Jesus, 1980),
yaitu :
pada akuifer tertekan :
)/ln(
)(2
rwro
hohwKbQr
Dimana:
Qr debit injeksi rata-rata sumur (m3/hari) K permeabilitas akuifer (m/hari) b ketebalan akuifer (m) hw ketinggian air sumur dari atas akuifer (m) ho ketinggian bidang piezometrik semula sebelum injeksi (m) ro jari-jari pengaruh maksimum kenaikan bid. pisometrik dari sumur(m) rw jari-jari sumur (m)
pada akuifer bebas :
)/ln(
)( 22
rwro
hohwKbQr
Dimana:
Qr debit injeksi rata-rata sumur (m3/hari) K permeabilitas akuifer (m/hari) hw ketinggian muka air dari dasar sumur (m) ho ketinggian muka air sebelum injeksi (m) ro jari-jari pengaruh (m) rw jari-jari sumur (m)
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
34
KF
QP
2
Adapun daya pompa untuk menginjeksi air melalui sumur injeksi dapat
dihitung dengan (Sunjoto,1998) :
dengan :
P : daya pompa ( kg m / detik )
Q : debit air masuk ( m3 / detik )
F : faktor geometrik sumur ( m )
K : koefisien permeabilitas sumur ( m / detik )
: berat jenis air ( kg / m3 )
: rendemen pompa ( 0,6 – 0,75 )
Pada waktu pengisian sering kali lumpur yang ada pada air permukaan ikut
masuk ke dalam sumur injeksi dan menutup pori-pori di sekitamya, sehingga
mengakibatkan penyumbatan dan-memperkecil jumlah peresapan air ke dalam
akuifer. Disamping itu gas/udara, bakteri dan mikroorganisme yang terbawa ke
dalam sumur injeksi dalam jumlah yang besar juga mempengaruhi kelulusan
dan penyumbatan pada akuifer. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa
penyebab terjadinya penurunan kecepatan pengisian airtanah melalui sumur
injeksi.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
35
Gambar 8. Aliran radial dan bentuk cone of recharge pada sumur injeksi (a)
akuifer tertekan, (b) akuifer bebas.(Todd, 1980)
Metoda pengisian airtanah dengan sumur injeksi ini sangat baik dipergunakan
untuk : (1) daerah yang relatif sempit, tidak memerlukan daerah yang luas
misalnya daerah perkotaan, (2) pada akuifer tertekan yang relatif dalam (3)
apabila air yang dipergunakan untuk pengisian mempunyai kualitas cukup baik.
Disamping itu, metoda pengisian airtanah melalui sumur injeksi ini merupakan
salah satu cara yang paling praktis dan banyak dipergunakan di kota-kota
besar, untuk pengisian airtanah secara buatan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
36
BAB V
PENGAWETAN DAN PENGHEMATAN AIRTANAH
Pengawetan airtanah merupakan upaya memelihara kondisi dan lingkungan
airtanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
Selain itu, pengawetan airtanah dilakukan untuk menjaga kesinambungan
ketersediaan airtanah guna memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
Pengawetan airtanah dilaksanakan dengan cara :
a. Penetapan Basin Yield dan Aquifer Yield;
b. Penghematan pemanfaatan airtanah;
c. Memelihara kualitas airtanah;
d. Penggunaan air yang saling menunjang antara airtanah dengan air
selain airtanah (Conjunctive Use).
Basin Yield adalah debit pengambilan maksimum pada suatu sistem airtanah
yang tidak menyebabkan penurunan muka airtanah atau bidang piezometrik,
yang dapat memicu akibat yang buruk pada komponen hidrologi lain di sistem
airtanah tersebut, dalam arti lain debit pengambilan airtanah pada suatu sistem
unit hidrogeologi (cekungan airtanah) yang tidak menimbulkan efek negatif
terhadap siklus hidrologi/kesetimbangan air pada sistem tersebut.
Basin Yield sebaiknya ditentukan berdasarkan konsep Sustainable Yield (debit
maksimum pengambilan airtanah yang berkelanjutan, lihat Gambar 10), yang
harus dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang dalam
pemberian ijin dalam rangka pengambilan airtanah yang berkesinambungan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
37
Gambar 9. Skema kondisi alamiah suatu sistem airtanah, pemompaan yang
berkelanjutan dan pemompaan yang tidak berkelanjutan (GW-Mate, 2005).
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perhitungan Sustainable Yield
adalah kesetimbangan air tahunan yang meliputi bukan saja kesetimbangan
sistem airtanah tetapi juga air permukaan (Water balance), dinamika
kebutuhan pemanfaatan air (Water needs) serta fungsi dan keterbatasan pada
sistem akuifer.
Hingga saat ini, metodologi untuk penentuan Sustainable Yield masih belum
baku. Pendekatan ilmiah yang umum digunakan untuk menentukan
Sustainable Yield adalah berdasarkan hasil pemodelan airtanah. Di dalam
pemodelan airtanah, parameter-parameter hidrologi, hidrogeologi,
pengambilan dan atau pemanfaatan airtanah dapat disimulasi sehingga debit
pengambilan airtanah yang berkelanjutan pada wilayah cekungan airtanah
dapat ditentukan.
Konsep Safe Yield sebaiknya tidak digunakan dalam mengendalikan
pengambilan dan atau pemanfaatan airtanah. Safe yield ditentukan hanya
berdasarkan volume imbuhan airtanah tahunan. Konsep ini mengasumsikan
sistem airtanah yang tertutup dan tidak memperhitungkan lepasan airtanah dari
akuifer yang umumnya mensuplai mata air, sungai, rawa-rawa dan danau.
Pengambilan airtanah berdasarkan Safe Yield akan mempengaruhi
keberlangsungan ekosistem yang tergantung pada sistem aliran airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
38
Untuk menjaga fungsi airtanah sebagai suplai ekosistem, umumnya safe yield
ditetapkan sebagai prosentase dari imbuhan airtanah tahunan.
Gambar 10. Konsep sederhana untuk membedakan konsep safe yield dan
sustainable yield pada pengambilan airtanah di suatu cekungan airtanah.
Konsep Optimum Yield (Qopt) sebaiknya juga tidak diterapkan. Konsep ini
menentukan debit optimal pengambilan dengan berdasarkan skenario
penambangan airtanah (mining groundwater). Debit optimum (Qopt) dihitung
berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas jenis (Qs) dan surutan optimum
(Sopt) atau dapat ditulis Qopt = Qs x Sopt. Sementara itu, Sopt umumnya dihitung
dari pengurangan kedudukan muka airtanah kritis (MAT_cr) dengan
kedudukan muka airtanah awal (MAT_initial). Skenario penambangan
dimunculkan dengan kriteria penurunan muka airtanah (semisal 40% dari muka
airtanah awal, dan sebagainya). Dengan berjalannya waktu yang disertai
dengan dinamika kesetimbangan air, perlu disadari bahwa penerapan
Optimum Yield tidak akan menghasilkan pemanfaatan airtanah yang
berkelanjutan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
39
Gambar 11. Skema konsep Optimum Yield
Aquifer Yield adalah maksimum debit pengambilan airtanah yang dapat
diberikan oleh akuifer tanpa penurunan muka airtanah atau bidang piezometrik
yang berarti. Metoda penentuan Aquifer Yield yang paling baik dilakukan
dengan bantuan model airtanah (groundwater modeling). Prinsipnya adalah,
membuat rekaan (simulasi) kondisi hidrogeologi kemudian ditetapkan
beberapa skenario pengambilan airtanah pada suatu lapisan akuifer tertentu.
Dari skenario tersebut dapat diketahui jumlah pengambilan airtanah maksimum
dari suatu lapisan akuifer tertentu dalam area per km2 yang menimbulkan efek
penurunan muka airtanah atau bidang piezometrik tak berarti atau aman.
Dalam kerangka pengawetan airtanah, penetapan Basin Yield dan Aquifer
Yield menjadi kewajiban Pemerintah Daerah setempat. Basin Yield dan Aquifer
Yield yang telah ditetapkan harus digunakan sebagai acuan umum pemberian
rekomendasi debit sumur pengambilan airtanah (Well Yield) yang diatur lebih
lanjut di dalam pedoman pengendalian airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
40
Gambar 12. Skema konsep penentuan Aquifer Yield
Penghematan pemanfaatan airtanah ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas
pemanfaatan airtanah. Upaya penghematan pemanfaatan airtanah dilakukan
dengan cara :
a. pemanfaatan teknologi;
b. pemanfaatan air berkualitas jelek;
c. pengambilan sesuai kebutuhan;
d. pemberlakukan instrument ekonomi untuk penghematan air;
e. sosialisasian gerakan hemat air;
f. pemanfaatan airtanah untuk air minum dan rumah tangga menjadi
prioritas utama;
g. pemanfaatan airtanah sebagai alternatif terakhir.
Pemanfaatan teknologi; pemanfaatan teknologi dapat dibedakan menjadi dua
cara, yaitu penerapan teknologi hemat air (real-water savings) dan penerapan
teknologi daur ulang (recycle use).
Pengunaan teknologi hemat air telah banyak dijumpai di berbagai bidang.
Pada sektor rumah tangga, teknologi hemat air telah banyak dijumpai pada
peralatan rumah tangga, sanitasi dan sebagainya. Pada sektor pertanian,
teknologi hemat air berkaitan dengan cara distribusi air misalnya dengan
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
41
sistem pengairan perpipaan yang mengantikan sistem pengairan tradisional
(Gambar 13). Bahkan, pada sektor pertanian, penerapan teknologi hemat air
secara tidak langsung merupakan juga upaya pemeliharaan kualitas airtanah
dengan menurunkan volume infiltrasi dan perkolasi zar-zat agrokimia dari
lahan pertanian. Di bidang industri, teknologi hemat air seharusnya menjadi
persyaratan AMDAL dan atau UKL/UPL yang harus dipenuhi.
Penerapan teknologi daur ulang, tidak saja dimaksudkan dengan penerapan
teknologi pengolahan limbah air (waste water treatment) dan pemanfaatan
kembali air hasil pengolahan limbah dalam proses (umum dalam proses
industri), tetapi juga penggunaan air limbah atau air olahan limbah secara
langsung untuk pemanfaatan yang lain semisal untuk pengairan areal
pertanian. Pada beberapa contoh, air berkualitas jelek bisa digunakan pada
bidang pertanian untuk menghemat air yang berkualitas baik bagi kegunaan
lainnya. Salah satu praktek yang dapat dilakukan adalah mencampur air
kualitas jelek dan air kualitas baik untuk meningkatkan persediaan air, dengan
tetap mempertahankan kualitas air yang dapat diterima.
Gambar 13. Contoh penerapan teknologi hemat air pada sektor pertanian
(GW-Mate, 2005).
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
42
Pengambilan airtanah sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan dengan cara:
(1) Penerapan wajib adanya dokumen jumlah dan proyeksi kebutuhan air bagi
setiap kegiatan yang akan memanfaatkan airtanah sebagai sumber air
(2) Penerapan meterisasi pengambilan air bagi setiap kegiatan pengambilan
airtanah dan volume air limbah
(3) Pemantauan jumlah pengambilan airtanah, volume air limbah dan jumlah
pengambilan airtanah.
Penerapan instrument ekonomi; penerapan instrumen ekonomi untuk
penghematan air dapat dilakukan dengan penerapan harga/pajak dan insentif.
Dalam bidang airtanah, terdapat dua cara yang relevan :
(1) Penerapan biaya/harga pengambilan airtanah dengan cara;
(a) direct pricing (biaya langsung) pengambilan airtanah (Kepmen ESDM
tahun 2001 tentang Nilai Perolehan Airtanah),
(b) indirect pricing (biaya tak langsung) yang diterapkan dengan
biaya/pajak pembuangan limbah air atau dengan menaikkan biaya
listrik/energi.
(2) Penerapan insentif misalnya dengan cara pemberian subsidi bagi pihak
atau kegiatan yang menggunakan teknologi hemat air.
Sosialisasi gerakan hemat air dapat dilakukan dengan cara sosialisasi melalui
media komunikasi (Televisi, Radio, Koran, Majalah), sosialisasi langsung ke
masyarakat pengguna airtanah.
Pemanfaatan airtanah untuk air minum dan rumah tangga sebagai prioritas
utama sebaiknya menjadi syarat utama dalam pemberian ijin pengambilan
airtanah. Namun perlu diperhatikan bahwa syarat ini dapat diberlakukan jika
terdapat sumber air lain sebagai pengganti yang potensial.
Pemanfaatan airtanah sebagai alternatif terakhir dapat dilakukan semisal
terdapat sumber air permukaan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk
pemenuhan kebutuhan akan air.
Dalam kerangka pengawetan airtanah, pemeliharaan kualitas airtanah dapat
dillakukan dengan cara: (1) penerapan teknologi pengolahan air limbah;
penerapan teknologi ini sebaiknya diberlakukan untuk semua limbah yang
dihasilkan oleh aktivitas manusia baik limbah rumah tangga, komersial, industri
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
43
sebelum limbah dibuang ke lingkungan; dan (2) untuk mendukung penerapan
teknologi ini, pemberian subsidi dapat diterapkan bagi kegiatan yang
menggunakan teknologi pengolahan air limbah.
Pemanfaatan airtanah dan air permukaan secara tandem atau disebut sebagai
conjuctive use dalam kerangka pengawetan airtanah dapat dikembangkan
dengan cara: (1) penggunaan sumber air permukaan untuk pengairan
tradisional (inefficient irrigation) untuk meningkatkan imbuhan airtanah
khususnya di musim penghujan, (2) penggunaan airtanah untuk pengairan
pertanian pada musim kering untuk menggantikan suplai dari air permukaan
yang tidak mencukupi saja, dan (3) Pengembangan penggunaan sumber air
permukaan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga, komersial dan industri.
Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka menjaga keberlanjutan
pemanfaatan airtanah wajib mengupayakan pengawetan airtanah agar
senantiasa dapat selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
Selain pemerintah, upaya pengawetan airtanah terutama harus melibatkan
industri pengguna airtanah yang umumnya merupakan penyadap terbesar
airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
44
BAB VI
PENENTUAN ZONA KONSERVASI AIRTANAH
Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas upaya-upaya konservasi airtanah
yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian, pengawetan termasuk
didalamnya penghematan airtanah. Berdasarkan upaya-upaya tersebut di atas,
maka menjadi logis jika zona konservasi airtanah dibedakan berdasarkan
upaya-upaya konservasi tersebut.
Untuk dapat memetakan upaya-upaya konservasi tersebut, terdapat dua faktor
utama yang harus dipertimbangkan; (1) potensi kuantitas dan kualitas
sumberdaya airtanah dan (2) alokasi pemanfaatan sumberdaya airtanah.
Potensi airtanah suatu cekungan airtanah atau daerah ditentukan oleh faktor
alami, yang merupakan sesuatu yang diterima apa adanya sesuai kemampuan
alam itu sendiri. Sedangkan pengambilan/pemanfaatan airtanah suatu daerah
ditentukan oleh faktor non-alami yang tergantung pada kebutuhan/aktivitas
manusia, yang umumnya meningkat dengan berjalannya waktu oleh karena
peningkatan kepadatan penduduk dan urbanisasi yang meningkat secara
tajam.
VI.1. Parameter Penentuan Zona Konservasi Airtanah Untuk mengetahui potensi dan pemanfaatan sumberdaya airtanah suatu
daerah, langkah yang harus dilakukan adalah inventarisasi seluruh aspek
airtanah yang ada dengan melakukan pemetaan, penyelidikan, penelitian,
eksplorasi dan evaluasi data airtanah. Informasi penting yang perlu diketahui
adalah:
a. Batas cekungan airtanah
b. Dimensi, geometri dan parameter akuifer
c. Daerah imbuh dan daerah lepasan airtanah; daerah sempadan
mataair
d. Jumlah ketersediaan airtanah;
e. Mutu airtanah
f. Jumlah dan lokasi pengambilan airtanah, termasuk didalamnya
pemanfaatan mataair sebagai sumber air baku.
g. Penggunaan lahan
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
45
A. Batas Cekungan Airtanah
Cekungan airtanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-atas
hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan
pengaliran, pelepasan airtanah berlangsung. Pengkajian geometri cekungan
airtanah dimaksudkan untuk mengetahui geometri dan dimensi cekungan,
yang merupakan ruang (space), yakni suatu tempat di mana di dalamnya
seluruh peristiwa hidrogeologi terjadi. Artinya batas-batas cekungan airtanah
ditentukan berdasarkan pertimbangan hidraulika airtanah yang membentuk
ruang tersebut.
Pengkajian geometri cekungan airtanah meliputi (lihat Pedoman Penentuan
Batas Cekungan Airtanah):
Penentuan batas lateral cekungan airtanah berikut tipenya;
Penentuan batas vertikal cekungan airtanah yang meliputi batas
bagian atas dan bagian bawah.
Mengingat teknis pengelolaan airtanah didasarkan pada satuan wilayah
cekungan airtanah, maka penentuan batas cekungan ini menjadi penting
karena terkait dengan batas kewenangan pengelolaan oleh daerah. Dengan
tidak berimpitnya batas cekungan airtanah dengan batas administrasi, maka
konservasinya akan terdapat areal cakupan cekungan airtanah :
Cekungan tunggal dalam Kabupaten
Cekungan lintas Kabupaten
Cekungan lintas Propinsi
B. Dimensi dan Geometri Akuifer
Informasi yang diperoleh dapat dibedakan antara konfigurasi sistem akuifer
dan parameter akuifer. Pengkajian konfigurasi slstem akuifer dimaksudkan
untuk mengetahui sebaran baik lateral maupun vertikal serta dimensi sistem
akuifer dan nonakuifer yang merupakan suatu wadah atau media di mana
airtanah tersimpan dan mengalir. Pengkajian ini meliputi :
a. Penentuan sebaran lateral akuifer dan non-akuifer
Sebaran lateral akuifer dan non-akuifer dalam suatu cekungan airtanah
ditentukan berdasarkan kemampuan meluluskan air dari satuan batuan /
formasi batuan yang membentuk cekungan tersebut. Artinya,
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
46
mengkonversikan satuan batuan atau formasi batuan menjadi satuan-
satuan hidrogeologi berdasarkan kemampuan meluluskan air, apakah
termasuk akuifer atau non-akuifer (akuiklud, akuitar, akuifug). Penentuan
kemampuan meluluskan air dari suatu satuan batuan atau formasi batuan
dilakukan-dengan metode deduktif, yakni penge!ompokan satuan
hidrogeologi yang didasarkan kemampuan meluluskan air dari litologi
penyusun satuan batuan / formasi batuan yang dominan. Pengelompokan
satuan hidrogeologi secara lateral di atas disajikan dalam suatu bentuk
peta tematik, misal Peta Satuan Hidrogeologi (Map of Hydrogeological
Units).
b. Penentuan sebaran vertikal sistem akuifer dan non-akuifer
Sebaran vertikal dari unit hidrogeologi ditentukan dengan pendekatan
sistem, artinya beberapa akuifer atau non-akuifer yang mempunyai
karakteristik hidraulika yang relatif sama, misal kedudukan muka
airtanahnya, dikelompokkan menjadi satu sistem (akuifer atau non-akuifer).
Data yang digunakan meliputi data hidrogeologi bawah permukaan yang
diperoleh dari hasil analisis geofisika dan hasil kegiatan pengeboran sumur
eksplorasi, sumur eksploitasi, serta sumur pantau. Penentuan sebaran
vertikal dilakukan dengan cara :
Membuat penampang hidrogeologi;
Menentukan kedalaman bagian atas sistem akuifer;
Menentukan kedalaman bagian bawah sistem akuifer.
c. Penentuan model konseptual sistem akuifer
Hasil pengkajian pada butir a) dan b) di atas, dipakai dasar untuk
menentukan model konseptual sistem akuifer dari cekungan airtanah yang
dikaji, dengan tujuan antara lain untuk memudahkan di dalam
penghitungan neraca air pada cekungan airtanah tersebut.
C. Parameter Akuifer
Pengkajian parameter akuifer dan non-akuifer dimaksudkan untuk menentukan
koefisien kelulusan (k), koefisien keterusan (T), dan koefisien simpanan (S).
Parameter akuifer ini sangat penting artinya untuk melakukan penghitungan-
penghitungan yang berkaitan dengan hidrodinamika airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
47
1. Koefisien kelulusan (k)
Koefisien kelulusan ( K ) dari suatu akuifer atau non-akuifer ditentukan
berdasarkan hasil uji lapangan, uji laboratorium, atau penentuan
dengan metode deduktif;
Penentuan koefisien kelulusan (k) dengan uji lapangan dilakukan
melalui uji pemompaan, uji peker (packer test), atau uji perkolasi;
Penentuan koefisien kelulusan (k) dengan metode deduktif dilakukan
pada suatu titik lokasi yang diketahui urut-urutan batuannya secara
vertikal atau suatu kelompok akuifer dan kelompok non-akuifer, namun
tidak tersedia data hasil pengujian atau pengujian hanya dilakukan
pada lapisan batuan tertentu. Penentuan cara ini dilakukan dengan
memperhatikan macam, sifat-sifat fisik, dan penyusun utama batuan
serta membandingkannya dengan koefisien kelulusan yang terdapat
dalam berbagai sumber.
2. Koefisien keterusan (T)
Koefisien keterusan (T) dari suatu akuifer atau non-akuifer ditentukan
dengan uji pemompaan atau gabungan antara metode deduktif dan
analitis;
Penentuan koefisien keterusan (T) dengan uji lapangan dilakukan
melalui uji pemompaan;
Penentuan koefisien keterusan (T) dengan metode gabungan antara
deduktif dan analitis dilakukan dengan mengalikan koefisien kelulusan
(k) hasil deduksi dan ketebalan akuifer (D).
3. Koefisien simpanan (S)
Koefisien simpanan (S) dari suatu akuifer atau non-akuifer ditentukan
melalui uji pemompaan.
D. Daerah Imbuh dan Daerah Lepasan Airtanah
Penentuan daerah imbuh dan daerah lepasan sangat penting artinya dalam
rangka perencanaan pengelolaan sumber daya airtanah di suatu cekungan. Di
daerah imbuh utama, proses pembentukan airtanah berlangsung kemudian
airtanah mengalir menuju daerah lepasannya. Oleh karena itu, upaya
pengelolaan di daerah imbuh merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya
pengelolaan airtanah dalam suatu cekungan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
48
Penentuan daerah imbuh dan daerah lepasan bukanlah hal yang mudah
mengingat ketersediaan data di suatu cekungan berbeda-beda terutama
ketersediaan data muka preatik dan muka pisometrik yang dipakai dasar untuk
penentuan batas kedua daerah tersebut; (1) di suatu cekungan airtanah di
mana data muka preatik dan muka pisometrik tersedia memadai, penentuan
batas antara daerah imbuh dan daerah lepasan diperoleh dengan cara
menumpang-tindihkan (overlay) antara peta muka preatik dan peta muka
pisometrik. Garis perpotongan antara muka preatik dan muka pisometrik
adalah garis engsel (hinge line), yang merupakan batas antara daerah imbuh
dan daerah lepasan; dan (2) di suatu cekungan airtanah di mana data muka
preatik dan muka pisometrik tidak tersedia secara memadai, penentuan batas
antara daerah imbuh dan daerah lepasan dilakukan dengan cara pendekatan
yang mengacu kepada konsepsi-konsepsi hidrogeologi yang berlaku;
E. Jumlah Ketersediaan Airtanah
Pengkajian jumlah airtanah dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara
perubahan airtanah yang masuk maupun ke luar dari suatu wadah di dalam
cekungan (intra-basin) maupun antar cekungan (inter-basin) dalam batasan
waktu tertentu (neraca air). Pengkajian jumlah airtanah melalui penghitungan
parameter-parameter jumlah sebagai berikut :
a. Imbuhan Airtanah
Penghitungan imbuhan airtanah untuk mengetahui perkiraan secara
kuantitatif tentang jumlah imbuhan ke dalam suatu akuifer di suatu
cekungan. Perkiraan secara kuantitatif ini sering menemui kesulitan
sehubungan dengan faktor-faktor yang terkait seperti hidrometeorologi dan
sifat fisik tanah serta karakteristik hidraulikanya. Penilaian jumlah imbuhan
airtanah dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain perhitungan
berdasarkan neraca air (water balance), persentase curah hujan
(precipitation percentage), neraca khlorida (chloride balance), dan hidrograf
sumur (well hydrograph);
b. Aliran Airtanah
Penghitungan debit aliran airtanah meliputi aliran yang masuk ke dalam
suatu cekungan airtanah atau yang ke luar dari cekungan tersebut.
Penghitungan debit aliran airtanah dilakukan dengan jejaring aliran (flow
net) dan menerapkan persamaan Darcy;
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
49
c. Basin Yield dan Aquifer Yield
Penentuan sustainable yield dalam kerangka cekungan dan akuifer di suatu
cekungan airtanah merupakan faktor penting dalam penentuan tingkat
potensi airtanah. Metoda yang paling baik menentukan basin yield dan
aquifer yield adalah dengan bantuan model airtanah. Patut diingat, bahwa
kondisi hidrogeologi suatu daerah, sangat menentukan cadangan airtanah,
sehingga batas basin yield dan aquifer yield, sangat berbeda dari suatu
daerah ke daerah yang lain, tergantung dari kondsi hidrogeologinya.
F. Mutu Airtanah
Mutu airtanah dinyatakan menurut sifat fisik, kandungan unsur kimia, maupun
kandungan bakteriologi yang terkandung di dalamnya. Data yang digunakan
untuk menentukan mutu airtanah bersumber dari hasil pengamatan dan
pengukuran lapangan dan analisis laboratorium dari beberapa contoh air yang
mewakili. Berkaitan dengan pengkajian potensi sumber daya airtanah,
pengkajian mutu dimaksudkan untuk mengetahui karidungan kimia dan
bakteriologi di dalam airtanah, dan kelayakan penggunaannya untuk keperluan
tertentu.
a. Pengkajian Hidrokimia
Pengkajian hidrokimia dimaksudkan untuk mengetahui kandungan kimia di
dalam airtanah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang asal
usul (genesa), kecepatan dan arah pergerakan, dan imbuhan serta luahan
airtanah;
b. Pengkajian Bakteriologi
Pengkajian bakteriologi dimaksudkan untuk mengetahui kandungan bakteri
patogen dan coli di dalam airtanah dengan tujuan untuk mendeteksi polusi
biologi terhadap airtanah serta menguji kelayakan penggunaannya untuk
keperluan air minum;
c. Pengkajian Peruntukan
1. Pengkajian peruntukan dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan
penggunaan airtanah bagi berbagai keperluan seperti air minum, rumah
tangga, industri, dan pertanian, dan lain-lain;
2. Berkaitan dengan penyusunan Peta Potensi Airtanah, sebagai salah
satu produk dari pengkajian potensi sumber daya airtanah, pengkajian
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
50
peruntukan dilakukan untuk mengetahui kelayakannya bagi keperluan
air minum;
G. Penggunaan Lahan
Faktor penggunaan meliputi jenis tata guna lahan, termasuk di dalamnya
informasi mengenai sumber air yang dimanfaatkan, sistem drainasi, sanitasi,
mutu limbah, dan pembuangan air limbah. Informasi ini harus diolah menjadi
informasi resiko lahan terhadap penurunan kuantitas airtanah (gangguan
terhadap siklus air, seperti penurunan imbuhan airtanah dan bukan aspek
pengambilan/pemanfaatan airtanah) dan kualitas airtanah.
Semisal tata guna pemukiman, harus dikategorikan berdasarkan sistem
sumber air yang digunakan (piping water atau penurapan airtanah di
bawahnya), sistem sanitasi (termasuk sistem pembuangan, kuantitas dan
kualitas limbah yang dibuang), prosentase penutupan permukaan oleh
bangunan, trotoar atau jalan (sealing), sistem drainasi, dan hal lainnya yang
dapat mempengaruhi degradasi kuantitas dan/atau kualitas airtanah.
VI.2. Metodologi Penentuan Zona Konservasi Airtanah Berdasarkan Informasi-Informasi parameter yang telah disebutkan di atas,
langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat peta-peta di bawah
ini:
(1) Peta daerah imbuhan – lepasan airtanah; atau peta daerah resapan
airtanah;
(2) Peta kawasan sempadan mataair;
(3) Peta perlindungan sumber air baku;
(4) Peta karakteristik potensi akuifer (K, T atau S)
(5) Peta kualitas/mutu airtanah dan;
(6) Peta debit pemompaan/pemanfaatan airtanah sekarang dan atau
mendatang; atau peta lokasi penurapan airtanah lengkap dengan
(7) Peta klas resiko lahan terhadap degradasi kuantitas dan kualitas
airtanah.
Langkah kedua adalah evaluasi penentuan zona klas atau tingkatan
kepentingan (urgency) konservasi yang ditentukan berdasarkan peta-peta no.1
s/d no.5 tersebut di atas dengan metoda overlay sederhana, sistem rating,
hingga multi point count system (MPCS). Standar metodologi evaluasi seperti
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
51
disebutkan di atas yaitu overlay sederhana, rating atau MPCS tidak ditentukan,
mengingat keberadaan data yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang
lain. Serta perkembangan kebijakan lingkungan daerah khususnya mengenai
airtanah yang berlainan dari satu wilayah ke wilayah yang lain.
Hal mendasar yang perlu diperhatikan untuk evaluasi penentuan zona klas
atau tingkatan kepentingan (urgency) konservasi adalah pembobotan masng-
masing paramater. Pada dasarnya kawasan atau zona atau area imbuhan
airtanah, resapan airtanah, sempadan mataair, zona perlindungan sumber air
baku harus selalu memiliki bobot yang tinggi dibanding faktor yang lain. Diikuti
dengan parameter potensi akuifer serta mutu airtanah, dengan prinsip semakin
besar potensi dan semakin baik mutu airtanahnya, semakin besar nilai
kepentingan (urgency) sumberdaya airtanah ini untuk dikonservasi.
Setelah klas atau tingkatan kepentingan (urgency) konservasi terpetakan,
langkah berikutnya adalah menentukan tindakan/upaya konservasi pada setiap
zona klas atau tingkatan urgency konservasi. Hal ini dilakukan dengan
melakukan overlay peta zona klas atau tingkatan kepentingan (urgency)
konservasi dengan peta debit pemompaan/pemanfaatan airtanah eksisting
dan/atau prakiraan pemompaan/pemanfaatan mendatang, serta peta resiko
lahan terhadap degradasi kuantitas dan kualitas airtanah. Hasil overlay ini akan
menunjukkan upaya-upaya apa saja dalam kerangka kegiatan konservasi
airtanah (perlindungan, pelestarian, pengawetan dan penghematan) yang
harus dilakukan berdasarkan informasi kebutuhan/pemanfaatan airtanah.
Tindakan atau upaya konservasi pada setiap zona urgency, harus dijelaskan
pada tabel yang termuat didalam peta zona klas konservasi airtanah (Gambar
14).
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
52
Gambar 14. Skema metodologi penentuan zona klas konservasi airtanah
dan upaya konservasinya.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
53
BAB VII
KONSERVASI AIRTANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
Pengelolaan airtanah di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada aspek
hukum dan aspek teknis. Aspek hukum merupakan undang-undang dan
peraturan yang digunakan untuk melandasi upaya pengelolaan airtanah, baik
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam
era otonomi, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah sebenarnya merupakan pranata hukum yang bertindak sebagai ujung
tombak pelaksanaan upaya pengelolaan dan perlindungan airtanah, dengan
demikian peraturan daerah sangat menentukan dalam pelaksanaan konservasi
sumberdaya airtanah.
VII.1. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Pengelolaan Airtanah
Undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan airtanah pada dasarnya
menggunakan pasal dalam UUD 1945 sebagai acuan, yaitu Pasal 33 ayat 3
yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat”. Adapun beberapa peraturan perundangan yang menyangkut tentang
airtanah antara lain adalah :
a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974
Sebagai perwujudan ayat (3) pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka
pada tahun 1974 dikeluarkan Undang-Undang No. 11 tentang Pengairan.
Undang-Undang ini menitik-beratkan fungsi sosial sumberdaya air, oleh sebab
itu penguasaan atas penggunaan sumberdaya tersebut dilakukan oleh Negara
bagi kemakmuran rakyat.
Peraturan yang ada mengenai air dan atau sumber-sumber air, sebelum
Undang-Undang ini ditetapkan, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan saat itu dan tidak memenuhi cita-cita yang diharapkan seperti pada
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Algemen Waterreglement (AWR) Tahun 1936 yang dipakai dasar pengaturan
sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, tidak memberikan dasar yang
kuat untuk usaha pengembangan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
54
air guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu AWR hanya berlaku di P.
Jawa dan Madura.
Khusus tentang airtanah pasal 5 ayat (2) pada undang-undang tersebut,
ditetapkan sebagai berikut :"Pengurusan administratif atas sumber airtanah
dan mataair panas sebagai sumber mineral dan tenaga adalah di luar
wewenang dan tanggung jawab Menteri yang disebut dalam ayat (1) pasal ini"
(maksudnya Menteri yang diserahi tugas urusan pengairan).
Dengan pasal tersebut jelas, bahwa airtanah memerlukan pengaturan
tersendiri oleh Menteri yang diserahi tugas urusan airtanah.
b. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982
Untuk pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, kemudian ditetapkan
Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air. Pada
ayat (2) pasal 5 Undang-Undang No. 11 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 22, maka pengurusan administratif atas sumber airtanah,
mataair panas sebagai sumber mineral dan sumber tenaga menjadi wewenang
Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan. Selanjutnya
pasal 6 ayat (2) dan (3) peraturan pemerintah tersebut menetapkan :
Ayat (2) :
Pengambilan airtanah untuk penggunaan airnya pada batas kedalaman
tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan izin Gubernur yang bersangkutan
setelah mendapat petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
Karena kedudukan lapisan pembawa airtanah (akuifer) pada tiap daerah
berbeda-beda kedalamannya, maka pengaturan pengambilan airtanah harus
disesuaikan dengan kondisi hidrogeologi setempat. Batas-batas kedalaman ini
ditetapkan oleh Menteri yang diatur dalam suatu peraturan tersendiri.
Pengambilan airtanah memerlukan izin dari pejabat yang diberi wewenang
oleh Menteri yang berwewenang dalam bidang pertambangan yang
pelaksanaannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang
khusus mengatur hal tersebut, sedang penggunaannya tunduk pada
ketentuan-ketentuan tersebut pada Peraturan Pemerintah ini atau perundang-
undangan lain dalam bidang pengairan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
55
Ayat (3) :
Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
Dengan demikian kewenangan dalam pengaturan air merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat, sedangkan dalam batas-batas tertentu kewenangan
tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas
pembantuan.
d. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.
03/P/M/Pertamben/1983
Mengingat ketentuan pada pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 22
Tahun 1982, maka ditetapkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 03/P/M/Pertamben/1983, tentang Pengelolaan Airtanah. Pada dasarnya
peraturan Menteri tersebut menetapkan, bahwa pengurusan administratif
airtanah adalah pengelolaan airtanah dalam arti luas yang mencakup segala
usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan dan pengendalian
serta pengawasan dalam rangka konservasi airtanah.
Aspek konservasi disebutkan dalam Bab I. Ketentuan Umum, Pasal 1.
disebutkan bahwa “konservasi sumber air bawah tanah adalah pengelolaan air
bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin
kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta
meningkatkan mutunya” (dalam bab berikutnya tentang konservasi air bawah
tanah telah dibahas). Sedangkan aspek pengendalian disebutkan dalam Bab
VIII Pasal 16 disebutkan bahwa “Direktorat Geologi Tata Lingkungan
melaksanakan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah pada daerah yang
potensi air bawah tanahnya sudah menurun yang mungkin dapat
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup”.
Peraturan ini lebih lanjut mengatur wewenang dan tanggung jawab Menteri
dalam melaksanakan pengurusan administratif atas sumber airtanah yang
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, yang
dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada Direktur Geologi Tata
Lingkungan.
Pengambilan airtanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari
Gubernur, yaitu setelah mendapat saran teknik yang mengikat dari Direktur
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
56
Geologi Tata Lingkungan. Selain kewenangan dalam pemberian izin,
Pemerintah Daerah dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan airtanah
bersama-sama dengan Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kantor
Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
Dengan demikian Pemerintah Daerah melakukan tugas pembantuan pada
pengurusan administratif airtanah. Meskipun di dalam Peraturan Menteri
tersebut tidak diatur secara khusus mengenai masalah pungutan/biaya
pengelolaan, namun untuk melaksanakan tugas pembantuan tersebut,
Pemerintah Daerah menetapkan sendiri pungutan/biaya pengelolaan airtanah
di daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah di bidang airtanah.
Berdasarkan peraturan Menteri di atas, maka Dirjen Geologi dan Sumberdaya
Mineral mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Air Bawah Tanah No. 392.k/526/060000/85.
d. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral
No. 392.k/526/060000/1985
Keputusan ini membahas pedoman pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
Dalam keputusan ini disebutkan mengenai wewenang instansi yang mengurusi
pengendalian pengambilan air bawah tanah beserta tatacaranya. Hal ini
disebutkan dalam bab yang mengatur tentang pengendalian yaitu pada Bab VI,
dimana:
Pasal 1 :
Pengendalian pengambilan air bawah tanah dan mataair dilaksanakan oleh
Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan/atau Kantor Wilayah Departemen
Pertambangan dan Energi, bekerjasama dengan Instansi Pemenrintah yang
berwenang;
Pasal 2 :
Tatacara pengendalian, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini,
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pasal 4 :
Rencana pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50
(lima puluh) liter perdetik atau rencana pembuatan lebih dari 5 (lima) buah
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
57
sumur bor untuk daerah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar, wajib
dilengkapi dengan studi kelayakan dan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL),
termasuk cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan pencemaran
lingkungan hidup yang mungkin timbul;
Pasal 8 :
Untuk setiap 5 (lima) buah sumur bor yang dimiliki, atau setiap pengambilan air
bawah tanah dengan debit lebih dari 50 (limapuluh) liter perdetik, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) pasal ini, pemegang izin diwajibkan menyediakan 1
(satu) buah sumur bor khusus memonitor perubahan lingkungan sebagai
akibat pengambilan air bawah tanah di daerah sekitarnya;
e. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 08.P/03/M.PE/1991
Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 menetapkan: Penggunaan
air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha industri dan pertambangan,
termasuk kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi diatur bersama
oleh Menteri dan Menteri yang bersangkutan.
Oleh itu penggunaan air untuk masing-masing kegiatan tersebut, seperti
dinyatakan pada penjelasan pasal di atas, perlu diatur tersendiri dengan
memperhatikan aspek teknis maupun administratif bidang bersangkutan dan
tata pengaturan air secara keseluruhan. Untuk keperluan itu, pasal tersebut
menjelaskan, bahwa Menteri bersama Menteri yang bersangkutan ditugaskan
untuk menetapkan peraturan dan persyaratan penggunaan air untuk masing-
masing bidang teknis yang bersangkutan.
Atas dasar penjelasan tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi No. 08.P/03/M.PE/1991 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983 tanggal 15 Desember
1983 yang menetapkan, bahwa : “Izin pengambilan dan pemanfaatan airtanah
dan mataair untuk kegiatan usaha industri dan pertambangan diberikan oleh
Menteri yang pelaksanaannya dilakukan Direktur Jenderal (Direktur Jenderal
Geologi dan Sumberdaya Mineral), sementara izin pengambilan dan
pemanfaatan airtanah dan mataair untuk kegiatan di luar usaha industri dan
pertambangan tetap dapat diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan
Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1985”.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
58
f. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/101/M.PE/1994
Pada pelaksanaan di lapangan dari kedua peraturan di atas ditemui adanya
pemahaman yang berbeda tentang kewenangan pemberian izin pengambilan
airtanah untuk kegiatan usaha industri oleh Pemerintah Daerah, sehingga
pengelolaan airtanah di beberapa daerah kurang dapat berjalan dengan lancar.
Oleh sebab itu, di samping untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah di
bidang deregulasi dan debirokratisasi, terutama berkaitan dengan pengambilan
dan pemanfaatan airtanah, maka Menteri memandang perlu mencabut
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/83
dan Nomor 08.P/03/M.PE/1991 dan menetapkan Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/101/M.PE/1994 tanggal 26 Desember
1994 tentang Pengurusan Administratif Airtanah.
Di dalam peraturan baru tersebut yang paling mendasar adalah, bahwa izin
pengeboran dan izin pengambilan airtanah untuk kegiatan di luar kegiatan
usaha pertambangan dan energi diberikan oleh Gubernur. Sementara izin
pengeboran dan pengambilan airtanah untuk kegiatan usaha pertambangan
dan energi diatur tersendiri oleh Menteri.
g. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.
1945.K/102/M.PE/1995
Berkaitan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di beberapa
bidang kepada Daerah Tingkat II Otonomi Percontohan seperti diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, maka di bidang airtanah, Menteri
Pertambangan dan Energi menetapkan Keputusan Menteri Pertambangan dan
Energi No.1945.K/102/M.PE/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang
Pedoman Pengelolaan Airtanah untuk Daerah Tingkat II.
Urusan bidang airtanah yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II Otonomi
Percontohan meliputi:
a. penerbitan izin pengeboran dan izin pengambilan airtanah
b. penetapan tarif dan retribusi airtanah
c. pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pengelolaan airtanah
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
59
h. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.
1946.K/102/M.PE/1995
Sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 02.P/101/M.PE/1994, maka ditetapkan Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi No. 1946.K/102/M.PE/1995 tanggal 26 Desember
1995 tentang Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Airtanah untuk Kegiatan
Usaha Pertambangan dan Energi.
Dalam keputusan tersebut ditetapkan, bahwa pengeboran dan pengambilan
airtanah untuk kegiatan usaha pertambangan dan energi hanya dapat
dilaksanakan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Geologi dan
Sumberdaya Mineral.
i. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1451
K/10/MEM/2000
Sebagai lanjutan dari Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tentang
Pengelolaan Airtanah yang sudah ada, maka Menteri Energi dan Sumberdaya
Mineral sesuai dengan kewenangannya menetapkan Keputusan Menteri
Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000 tanggal 3
November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Airtanah.
Keputusan tersebut berisi berbagai pedoman dan prosedur pada pengelolaan
airtanah di daerah otonom, yang dimaksudkan sebagai acuan pada
pelaksanaan pengelolaan. Pedoman dan prosedur tersebut meliputi:
1. Pedoman Teknis Evaluasi Potensi Airtanah.
2. Pedoman Teknis Perencanaan Pendayagunaan Airtanah.
3. Pedoman Teknis Penentuan Debit Pengambilan Airtanah.
4. Prosedur Pemberian Izin Eksplorasi Airtanah.
5. Prosedur Pemberian Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Airtanah.
6. Prosedur Pemberian Izin Penurapan dan Izin Pengambilan Mata air.
7. Prosedur Pemberian Izin Perusahaan Pengeboran Airtanah.
8. Prosedur Pemberian Izin Juru Bor Airtanah.
9. Pedoman Teknis Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Sumur
Produksi Airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
60
10. Pedoman Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Pemanfaatan
Airtanah dalam Penghitungan Pajak Pemanfaatan Airtanah.
11. Pedoman Pelaporan Pengambilan Airtanah.
j. Undang-undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004
Dalam undang-undang ini terdapat bab khusus yang membahas mengenai
konservasi sumber daya air dimana dalam bab tersebut dibahas mengenai
konservasi dan pengendalian airtanah. Hal ini disebutkan dalam pasal-pasal
pada bab tersebut, yaitu :
Pasal 20 Konservasi Menjaga Kelangsungan Daya Dukung dan Tampung dan
Fungsi Sumber Daya Air (SDA) :
(1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan
keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air.
(2) Konservasi sumber daya air sbagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air,
pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air dengan mengacu pola Pengelolaan Sumber Daya Air
yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
(3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagiamana dimaksud
pada Ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.
Pasal 21 Perlindungan dan Pelestarian :
(1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan
melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap
kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk
kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah
tangkapan air;
b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan sumber air
dapat berupa:
- mengatur pemanfaatan sabagian atau seluruh sumber air
tertentu melalui perizinan; dan/atau
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
61
- pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh
sumber air tertentu.
c. pengisian air pada sumber air;
d. pengaturan prasarana dan sarana snitasi;
e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan
pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam.
(3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
(4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif
dan/atau sipil teknis melalui pendekatan social, ekonomi, dan budaya.
(5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air
sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.
Pasal 22 Pengawetan Air :
(1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan
ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaat.
(2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan
cara :
a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat
dimanfaatkan pada waktu diperlukan ;
b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif ; dan/atau
c. mengendalikan penggunaan airtanah
(3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 23 Pengelolaan Kualitas :
(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan
untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan
yang ada pada sumber-sumber air.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
62
(2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan
dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana
sumber daya air.
(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada
sumber air dan prasarana sumber daya air.
(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 25 Pelaksanaan Konservasi :
(1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk,
rawa, cekungan airtanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan
pantai.
(2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan
pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.
k. UU RI No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Dalam undang-undang ini sedikit dibahas mengenai penataan ruang terhadap
kawasan lindung, dimana kawasan lindung tersebut digunakan untuk
konservasi airtanah. Hal ini disebutkan dalam bab ketentuan umum yaitu :
Pasal 1 ayat 7
“Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan”.
l. Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Hukum Tata Lingkungan
Undang-undang tentang lingkungan hidup menyebutkan tentang usaha
konservasi sumber alam non hayati. Hal ini disebutkan pada Pasal 11 UULH
yang menyatakan : Ketentuan tentang perlindungan sumber daya alam non
hayati ditetapkan dengan undang-undang.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
63
Penjelasannya berbunyi : “Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini
meliputi tiap jenis sumber daya alam non hayati, seperti ketentuan tentang air,
tanah, udara, bahan galian, bentang alam dan formasi geologis atau
perwujudan proses alam”.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasal 11 ini
akan diuraikan di sini, sebagai contoh pengaturan perlindungan sumber daya
non hayati.
Dalam rangka perlindungan air sebagai sumber daya alam non hayati
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UULH, terdapat pengaturannya dalam
Bab III tentang Perlindungan, yaitu Pasal 13, yang menyatakan :
1. Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus
dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya,
supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal
2 Undang-undang ini, dengan jalan :
a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air
terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;
c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air,
yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-
banguan pengairan sehingga tetap berfungsi sebagaimana
mestinya.
2. Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Pengaturan
Pemerintah.
Adapun penjelasan Pasal 13 tersebut berbunyi:
Ayat (1) : Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air tersebut
pada huruf a dilaksanakan antara lain dengan melakukan pembinaan hutan
lindung dan atau jenis tumbuh-tumbuhan lainnya, pengendalian erosi dan
sebagainya.
Ayat (2) : Cukup jelas
Dalam hubungan dengan perlindungan air dan sekaligus perlindungan tanah
dapat dikemukakan pengembangan Daerah Aliran Sungai. Pada UULH yang
dimaksud dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan
yang dipisahkan dari wilayah lainnya oleh topografi dan merupakan :
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
64
a. Satu satuan wilayah tata air yang menampung dan menyimpan air
hujan yang jatuh diatasnya untuk kemudian mengalirkannya melalui
sungai utama ke laut;
b. Satu satuan ekosistem dengan unsur-unsur utamanya sumber daya
alam, flora, fauna, tanah dan air serta manusia dan segala aktivitasnya
yang berinteraksi satu sama lainnya.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dimaksudkan sebagai upaya manusia di
dalam mengendalikan hubungan timbal balik di antara sumber daya alam
dengan manusia dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian
dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam
bagi manusia.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dianggap perlu untuk memecahkan
masalah erosi dan perluasan tanah kritis yang terdapat di hulu sungai.
Peningkatan daya dukung antara lain dapat ditempuh melalui :
a. Konservasi, yaitu merubah jenis penggunaan tanah ke arah usaha yang
lebih menguntugkan, tetapi masih sesuai dengan kemampuan
wilayahnya.
b. Intensifikasi dengan penggunaan teknologi baru dalam usaha tani.
c. Konservasi atau pengawetan tanah, yaitu pencegahan kerusakan lahan
dan peningkatan kesuburannya.
Dalam rangka pengembangan lebih lanjut, telah dibentuk Proyek Perencanaan
dan Pembinaan Reboisasi dan Penghijauan Daerah Aliran Sungai, disingkat
P3RPDAS. P3RPDAS adalah proyek sektoral dengan tugas pokok
perencanaan dan pembinaan Proyek-proyek dalam rangka Program Bantuan
Penghijauan dan Reboisasi (Inpres Penghijauan dan Reboisasi).
Pertimbangan diadakannya Inpres tentang bantuan Penghijauan dan
Reboisasi adalah bahwa perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan
dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-
daerah kritis di wilayah DAS dan bahwa dalam kegiatan tersebut perlu
ditingkatkan peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat
secara luas. Untuk keperluan tersebut disediakan Bantuan Penghijauan dan
Reboisasi dalam APBN tahun anggaran yang bersangkutan dengan Instruksi
Presiden. Untuk tiap-tiap tahun anggaran dikeluarkan Inpres dengan anggaran
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
65
tertentu untuk keperluan : (1) pelaksanaan penghijauan; (2) pengadaan bibit
penghijauan; (3) pelaksanaan reboisasi; (4) pengadaan bibit reboisasi; (5)
petugas lapangan; (6) penyelenggaraan pendidikan dan latihan; dan (7)
pembinaan umum.
Yang dimaksudkan dengan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi adalah
bantuan langsung atas beban APBN tahun anggaran yang bersangkutan
kepada :
a. Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboisasi serta pengadaan bibit
reboisasi;
b. Daerah Tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan dan pengadaan
bibit penghijauan.
Bantuan diberikan untuk menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam,
tanah, hutan dan air, terutama di daerah-daerah kritis, yaitu di daerah-daerah
yang ditinjau dari segi hidrologi dapat membahayakan kelangsungan
pembangunan dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau wilayah lain.
Penghijauan meliputi penanaman tanaman tahunan atau rerumputan serta
pembuatan bangunan pencegah erosi tanah di areal yang tidak termasuk areal
hutan negara atau areal lain yang berdasarkan rencana tataguna tanah tidak
diperuntukkan untuk hutan.
Reboisasi meliputi penanaman atau pemudaan pohon-pohon serta jenis
tanaman lain, di areal hutan negara dan areal lain yang berdasarkan rencana
tataguna tanah diperuntukkan hutan.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :
a. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan
Penghijauan dan Reboisasi;
b. pelaksanaan reboisasi dan pengadaan bibit reboisasi;
c. pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi;
d. pembinaan swadaya masyarakat untuk melaksanakan penghijauan.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas :
a. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan
penghijauan dan pengadaan bibit penghijauan;
b. pengamanan hasil penghijauan dan reboisasi;
c. pemeliharaan hasil penghijauan;
d. bimbingan kepada masyarakat untuk turut memikul tanggung jawab
dalam pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi;
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
66
e. pembinaan swadaya masyarakat untuk melaksanakan penghijauan.
Pada dasarnya pengembangan DAS mempergunakan pola dan standar-
standar dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Penutupan lahan dengan menanami tanaman bawah sebagai tanaman
makanan ternak (rerumputan) atau jenis tanaman lain yang bermanfaat
dan bisa dipungut hasilnya dalam waktu yang singkat, dilakukan di atas
lahan dengan kemiringan di atas 50 %.
b. Intensifikasi pertanian tanah kering dengan memperhatikan aspek
konservasi tanah dan air, dilakukan pada lahan dengan kemiringan 10-
50 %.
c. Intensifikasi lahan pekarangan melalui usaha penanaman jenis
tanaman yang produktif dan bercocok tanam tanaman semusim dengan
memperhatikan aspek penyelamatan tanah dan air.
d. Pengembangan pengairan dengan pembangunan dam sedang dan
kecil/check dam, weir dan pembuatan saluran tersier.
e. Konservasi lahan pertanian kering sesuai kondisinya menjadi sawah
dengan membangun/menyediakan fasilitas air bagi terlaksananya
usaha tersebut.
f. Usaha untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan ketrampilan
para petani melalui latihan penyuluhan.
(Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi, 1976:6)
Dengan pengembangan DAS yang ditujukan kepada One River, One Plan,
One Management akan dapat diperoleh keterpaduan horizontal antar sektor
dan keterpaduan vertikal antara Pusat dan Daerah.
m. Kepmen Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2001
Dalam Kepmen ini dibahas mengenai jenis rencana dan kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam
Kepmen ini disebutkan bahwa pengambilan air bawah tanah (sumur tanah
dangkal, sumur tanah dalam dan mataair) dengan debit > 50 l/detik (dari 1
sumur; atau dari 5 sumur dalam area < 10 ha) wajib dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
67
n. Peraturan Daerah tentang Airtanah
Dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka beberapa daerah
Kabupaten/Kota telah menerbitkan peraturan daerah tentang airtanah, tetapi
sebagian besar masih mengandalkan peraturan daerah yang lama. Hal
tersebut antara lain disebabkan karena belum adanya undang-undang yang
baru tentang sumberdaya air setelah pemberlakukan otonomi daerah.
Kelembagaan yang berwenang melaksanakan pengelolaan airtanah beragam
dari satu daerah otonom ke daerah otonom yang lain. Beberapa contoh
peraturan daerah yang ada adalah :
1) Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995
Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1995
tentang pengawasan kualitas air ini mempunyai tujuan untuk :
1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air
dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat
2. Mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat
membahayakan kesehatan serta meningkatkan kualitas air.
Dalam peraturan tersebut dibahas, bahwa kegiatan pengawasan kualitas air
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan dibawah
koordinasi dan petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Hal ini diatur pada Bab IV ayat 4.
Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup :
a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada
proses produksi dan distribusi.
b. Pemeriksaan contoh air.
c. Analisa hasil pemeriksaan.
d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil
kegiatan tersebut huruf a, b dan c ayat ini.
e. Pemantauan upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan
penyuluhan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
68
2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 ini akan
mengatur tentang Perlindungan Sumber Air Baku (PSAB) ditetapkan dengan
dasar pasal 27 Peraturan Daerah Tingkat II Sleman Nomor 23 Tahun 1994
mengenai Penetapan dan Kebijaksanaan Kawasan Perlindungan Setempat.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 ini mempunyai
tujuan untuk :
1. Mengatur, mengawasi dan membina kegiatan di sekitar sumber air
baku
2. Melindungi terhadap sumber-sumber air baku
Rancangan peraturan ini membahas tentang pembagian zona perlindungan
sumber air baku yang dibagi menjadi zona perlindungan I, II dan III.
3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No 2 Tahun 2001
Peraturan daerah ini membahas mengenai Perlindungan Sumber Air Baku
dalam rangka menjamin kualitas dan kuantitas sumber air baku serta
tersedianya air minum yang sehat pada kawasan sumber air baku sebagai
kawasan lindung. Peraturan daerah ini membahas mengenai pembagian zona
perlindungan sumber air baku yang dibagi menjadi zona perlindungan I, II dan
III.
4) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.3 Tahun 2004
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air. Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada
dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat
dilakukan sendiri-sendiri (partial) oleh satu pemerintah daerah. Dengan
demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan
didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan
yang efisien dan efektif.
Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke
sumber air harus :
d. mempunyai izin pembuangan air limbah;
e. memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
69
f. memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) yang bersertifikat;
g. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang
ke media lingkungan;
h. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
i. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
j. melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
k. melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
l. melakukan swapantau dan melaporkan hasilnya;
m. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Pemantauan kualitas air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan
secara terkoordinasi dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2006
Peraturan daerah ini dibuat untuk mengatur pengelolaan kawasan lindung.
Perlindungan terhadap hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya
erosi, bencana banjir, sedimentasi serta menjaga fungsi hidroorologis dan
ekologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, airtanah dan air
permukaan. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan,
pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
Perlindungan terhadap kawasan resapan air dimaksudkan untuk
mempertahankan kawasan-kawasan tersebut agar tetap berfungsi sebagai
kawasan resapan, yang secara hidroorologis dapat menjamin ketersediaan
sumberdaya airtanah. Kriteria kawasan resapan air ini merupakan kriteria yang
bersifat kumulatif, sehingga suatu kawasan merupakan kawasan resapan air
apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;
b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter/hari;
d. Kedalaman muka airtanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
e. Kelerengan kurang dari 15%;
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
70
f. Kedudukan muka airtanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka
airtanah dalam.
6) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.5 Tahun 2000
Peraturan daerah ini mengatur tentang pengendalian pencemaran air di
Propinsi Jawa Timur. Pengendalian pencemaran air, dimaksudkan sebagai
upaya pencegahan pencemaran dan sumber pencemar, penanggulangan dan
atau pemulihan mutu air pada sumber-sumber air. Pengendalian pencemaran
air dilaksanakan untuk menjaga agar mutu air pada sumber-sumber air tetap
terkendali sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian pencemaran air
bertujuan untuk rnewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada
sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan
peruntukannya.
Peraturan ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Gubernur
untuk mengendalikan pencemaran yang meliputi :
a. perlindungan, penanggulangan dan pernulihan mutu air pada sumber-
sumber air;
b. pencegahan pencemaran air pada sumber pencemaran;
c. penetapan perizinan pembuangan limbah cair;
d. pengawasan.
VII.2. Permasalahan Undang-Undang dan Peraturan Mengenai Konservasi
Airtanah di Indonesia
Keberadaan peraturan perundangan tentang sumberdaya air dan airtanah
pada dasarnya menunjukkan, bahwa air mempunyai nilai ekonomi dan
lingkungan yang strategis, oleh sebab itu perlu diatur, bahkan dimasukkan
dalam konstitusi. Prinsip dasar hukum airtanah seperti diuraikan di atas,
seharusnya menjadi dasar peraturan perundangan airtanah di Indonesia.
Undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan airtanah yang sudah ada
umumnya lebih membahas mengenai pengendalian airtanah yang sebagian
besar berisi tentang pengambilan dan pengendalian pencemaran airtanah,
sedangkan pembahasan mengenai konservasi airtanah kurang dibahas secara
detail. Undang-undang dan peraturan tentang airtanah yang menyebutkan
mengenai konservasi airtanah adalah UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
71
dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983.
Dalam UU Sumber Daya Air No 7 Tahun 2004 mempunyai pembahasan yang
cukup lengkap mengenai konservasi airtanah. Dalam UU Sumber Daya Air
tersebut dibahas upaya mengenai pelestarian, perlindungan, pengawetan,
pengelolaan kualitas dan upaya pelaksanaan konservasi terhadap airtanah.
Namun salam UU tersebut belum menjelaskan batasan antara konservasi
airtanah dengan pengendalian airtanah.
Penjelasan mengenai konservasi airtanah secara umum juga disebutkan pada
undang-undang dan peraturan mengenai tata ruang dan lingkungan hidup,
misalnya pada UU RI No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-
undang Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997 Tentang Hukum Tata
Lingkungan dan Kepmen Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2001
mengenai jenis kegiatan yang wajib dilengkapi Andal. Pada undang-undang
dan peraturan tersebut dibahas mengenai upaya penataan ruang terhadap
kawasan lindung untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam non hayati, dalam pembahasan kali ini yang
dimaksud adalah sumber daya air. Pada Undang-undang Lingkungan Hidup
No 23 Tahun 1997 disebutkan upaya –upaya perlindungan terhadap sumber
daya air yang disebutkan pada Bab III tentang Perlindungan pada Pasal 13.
Selain itu juga disebutkan kewenangan dari tiap instansi pemerintahan dalam
upaya perlindungan terhadap sumber daya air tersebut.
Undang-undang dan peraturan di tingkat daerah umumnya sudah membahas
mengenai konservasi airtanah walaupun tidak dibahas secara detail. Hal ini
dapat dilihat pada contoh-contoh peraturan daerah yang ada diatas. Secara
umum Perda-perda tersebut hanya membahas mengenai pengelolaan kualitas
dan pencemaran airtanah, misalnya pada Perda di Yogyakarta, Jawa Barat
dan Jawa Timur. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No 2 Tahun 2001
membahas mengenai upaya perlindungan pada kawasan sumber air baku
sebagai kawasan lindung. Selain itu dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Barat No.2 Tahun 2006 diatur juga tentang pengelolaan kawasan lindung
disebutkan mengenai upaya perlindungan terhadap kawasan resapan air.
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa konservasi airtanah sudah
masuk dan dibahas dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Pada
undang-undang dan peraturan mengenai tata ruang dan lingkungan hidup,
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
72
konservasi airtanah merupakan bagian dari upaya upaya penataan ruang
terhadap kawasan lindung. Penjelasan yang cukup detail mengenai upaya
konservasi telah dijabarkan pada Undang-undang Sumber Daya Air No.7
Tahun 2004. Sayangnya peraturan-peraturan mengenai airtanah dibawahnya
(Kepmen, Perda, dll) umumnya lebih membahas mengenai upaya
pengendalian airtanah. Upaya konservasi biasanya hanya disebutkan sebagai
bagian dari upaya pengendalian airtanah, misalnya usaha untuk pengelolaan
kualitas dan pencemaran airtanah. Oleh karena itu perlu dibuat undang-
undang dan peraturan mengenai airtanah yang secara detail membahas
mengenai konservasi airtanah. Mengingat upaya konsevasi airtanah tersebut
sebenarnya dapat dipisahkan dengan pengendalian airtanah.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
73
BAB VII
PENUTUP
Sesuai dengan maksud dan tujuan tulisan ini adalah menyajikan bahan/materi
berupa kajian ilmiah pedoman konservasi airtanah yang meliputi tiga kegiatan
utama konservasi airtanah, yaitu:
1. Kegiatan perlindungan dan pelestarian airtanah,
2. Kegiatan pengawetan dan penghematan airtanah, dan
3. Penentuan zona konservasi airtanah.
Berdasarkan sasaran kajian ini, diharapkan pihak terkait dapat
mempergunakan penyusunan tulisan ini sebagai:
4) Pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan konservasi airtanah.
5) Pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan airtanah terutama dalam
memanfaatkan airtanah tanpa menimbulkan dampak negatif bagi
lingkungan.
6) Pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan airtanah terutama kegiatan
konservasi airtanah sesuai dengan amanat UU No. 7 tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah
yang telah ada tentang airtanah.
7) Pedoman bahan penyusunan peraturan perundangan tentang konservasi
airtanah di Indonesia.
Menilik permasalahan pengelolaan airtanah di Indonesia dan salah satu faktor
tantangan pengelolaan airtanah, yaitu mengelola masyarakat pengguna
airtanah (managing people), diharapkan pedoman hasil kajian ilmiah ini dapat
dipergunakan bagi masyarakat untuk mengenal bagaimana cara melindungi
dan melestarikan airtanah, mengawetkan dan menghemat airtanah, serta
mengetahui implementasi zona konservasi airtanah yang telah ditentukan.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
74
DAFTAR PUSTAKA
AG Boden (1996), Bodenkundliche Kartieranleting, 4.- Auflage, Hannover Aller, L. T., Bennett, J., Lehr, R., Petty, and Hackett, G. (1987), DRASTIC: A Standardized System for Evaluating Ground Water Pollution Potential using Hydrogeologic Settings. U.S Environmental Protection Agency, EPA/600/2-87/035. ARGOSS (2001), Guidelines for Assessing the Risk to Groundwater from On Site Sanitation, British Geological Survey Commisioned Report, CR/01/142, 97 pp. Bedient, P.B., Rifai, H.S., and Newell, C.J. (1999), Ground Water Contamination: Transport and Remediation, 2 nd ed., 604 p, Prentice-Hall. Burgess, D.B., and Fletcher, S.W. (1998), Methods used to delineate groundwater source protection zones in England and Wales, in: Robins, N.S. (ed.) Groundwater Pollution, Aquifer Recharge and Vulnerability, Geological Society, London, Special Publications, 130, p. 199 – 210. Chilton, J., Schmoll, O and Appleyard, S. (2006), Assessment of Groundwater Pollution Potential, In: Schmoll, O, Howard, G, Chilton, J and Chorus, I. (ed) Protecting Groundwater for Health : Managing Quality of Drinking Water Sources, WHO Drinking Water Quality Series. Conrad, J., Hughes, S., and Weaver, J. (2002), Map Production, in Zaporozec, A., (ed), 2002, Groundwater Contamination Inventory: A Methodological Guide, IHP – VI, Series on Groundwater No. 2, UNESCO. p 75 - 98. Daly D and Warren W.P. (1998), Mapping groundwater vulnerability: the Irish perspective, in: Robins N.S., (ed), Groundwater Pollution, Aquifer Recharge and Vulnerability, Geological Society, London, Special Publications, 130, p. 179 – 190. Daly, D., Dassargues, A., Drew, D., Dunne, S., Goldscheider, N., Neale, S., Popescu, I.C., Zwahlen, F. (2002), Main Concepts of the European Approach to Karst Groundwater Vulnerability Assessment and Mapping, Hydrogeology Journal, Vol. 10, p. 340 – 345, Springer-Verlag. Danaryanto, H. (2000), Perencanaan Pendayagunaan dan Konservasi Airtanah, Lokakarya Nasional Desentralisasi Airtanah yang Berwawasan Lingkungan, Direktorat Geologi Tata Lingkungan – ESDM, Puncak, Cianjur 29-31 Oktober 2000. Davis, S.H. and De Weist, R.J.M. (1966), Hydrogeology. 463 p., New York Dillon, P. (2005), Future Management of Aquifer Recharge, Hydrogeology Journal, Vol 13, No. 1, p.313 – 316, Springer – Verlag.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
75
Fetter, C.W., 1999, Contaminant Hydrogeology, 2nd edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York. Foster, S., and Hirata, R. (1988), Groundwater Pollution Risk Assessment; A Methodology Using Available Data, PAN American Center For Sanitary Engineering and Environmental Sciences (CEPIS), Lima, Peru. Foster, S., Hirata, R., Gomes, D., D’Elia M., and Paris, M. (2002), Groundwater Quality Protection: a guide for water utilities, municipal authorities, and environmental agencies, 103 p, GW-MATE, The World Bank, Washington. Foster S.S.D. (1998), Groundwater recharge and pollution vulnerability of British aquifers: a critical overview in: Robins N.S., (ed), Groundwater Pollution, Aquifer Recharge and Vulnerability, Geological Society, London, Special Publications, 130, p. 7 – 22. Freeze, R.A., and Cherry J.A. (1979), Groundwater, 604 p, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ. Gogu, R.C., Dassargues, A. (2000), Current trends and future challenges in groundwater vulnerability assessment using overlay and index methods, Environmental Geology Journal, 39 (6), p.549 – 559, Springer-Verlag. GW-MATE (2005), Groundwater Management Strategies: facets of the integrated approach, Briefing Note Series No. 3, World Bank. Hadimulyono, M.B. (2005), Kebijakan Pengunaan yang Saling Menunjang antara Air Permukaan dan Airtanah, Lokakarya Kebijakan Nasional Pengelolaan Airtanah, Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan – ESDM, Bandung, 29 Juli 2004. Hasyim, I. (2000), Peran Propinsi dalam Pengelolaan Sumberdaya Airtanah yang Berwawasan Lingkungan, Lokakarya Nasional Desentralisasi Pengelolaan Airtanah yang Berwawasan Lingkungan, Direktorat Geologi Tata Lingkungan – ESDM, Puncak, Cianjur 29-31 Oktober 2000. Helweg, O.J., 1992, Water Resources : Planning and Management, 2nd edition Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, 364 p Hendrayana, H., 2000b, Konservasi Airtanah dalam rangka Pemanfaatan Air yang Berkelanjutan, Makalah Pembinaan kepada Pemakai Air Bawah Tanah, Dinas Pertambangan DIY, Yogyakarta. Hendrayana, H., 2002a, Dampak Pemanfaatan Airtanah, Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hendrayana, H., 2002b, Konsep Dasar Manajemen Cekungan Airtanah, Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hendrayana, H., 2002c, A Concept Approach of Total Groundwater Basin Management, International Symposium on Natural Resource and Environmental Management, held in the framework of the 43rd Anniversary of
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
76
UPN “Veteran” Jogyakarta, on January 21 – 22, 2002 (Published in English Proceeding). Hendrayana, H., 2002d, Konsep Dasar Pengelolaan Cekungan Air Bawah Tanah, Pelatihan Manajemen Air Bawah Tanah di Wilayah Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, 15 – 27 September 2002, Yogyakarta. Hendrayana, H., 2002e, Program Perencanaan Pendayagunaan Sumberdaya Air Bawah Tanah, Pelatihan Manajemen Air Bawah Tanah di Wilayah Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, 15 – 27 September 2002, Yogyakarta. Hendrayana, H., 2002f, Sistem Pengelolaan Air Bawah Tanah Yang Berkelanjutan, dalam buku Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia, P3-TPSLK BPPT and HSF, Jakarta. Hendrayana, H., 2002g, Groundwater Conservation for Sustainable Groundwater Resources (Discussion on Technical Aspect), presented in Seminar on Mineral and Groundwater Resources Management, Yogyakarta. Hendrayana, H.; Putra, DPE., 2008a, Assessment of Urban Groundwater Contaminant Loading, Proceeding of Science and Technology on Groundwater Usage and Conservation, Indonesian Geological Board, Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic Indonesia, Bandung. Hendrayana, H., Putra, DPE., 2008b, Urbanization and Groundwater Resources : Interaction and Management, Proceeding of National Seminar on Strategy and Challenge in Geological Education and National Development, Yogyakarta, 15 February 2008. Hölting, B., Haertlé, Th., Hohberger, K.-H., Nachtigall, K., Villinger, E., Weinzierl, W., and Wrobel, J.-P. (1995): Konzept zur Ermittlung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung; C 63: 5-24. Hölting, B., and Coldeway, W.G. (2005), Hydrogeologie: Einfuehrung in die Allgemeine und Anngewandte Hydrogeologie, 6. Auflage, 326 S, 118 Abb, 69 Tab, Spektrum – Elsevier. Ibe K.M., Nwankwok G.I., and Onyekumu S.O. (2001), Assesment of groundwater vulnerability and its application to the development of protection strategy for the water supply aquifer in Owerri, Southeastern Nigeria, Environmental Monitoring and Assesment, p.323-360, Kluwer Academic Publishers. Johansson, P.-O, and Hirata, R. (2002), Rating of Groundwater Contaminant Sources, in Zaporosec, (ed), Groundwater Contamination Inventory: A Methodological Guide, IHP-VI, Series on Groundwater No.2, UNESCO, p.63 – 74. http://unesdoc.unesco.org /images/ 0013/001325/132503e.pdf Kovaleschy, V.S., Kruseman, G.P., and Rushton, K.R., (ed). (2004), Groundwater Studies: An International Guide for Hydrogeological Investigations, IHP-VI, Series on Groundwater No.3, UNESCO.
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
77
Lerner, D.N., Issar, A.S., and Simmers. I. (1990), Groundwater Recharge: A Guide to Understanding and Estimating Natural Recharge, International Contributions to Hydrogeology Vol. 8, IAH, Verlag Heinz Heise, Hannover, Germany. Mato, R.R.A.M. (2002), Groundwater Pollution in Urban Dar es Salaam, Tanzania: Assessing Vulnerability and Protection Priorities, Dissertation, Eindhoven University of Technology, University Press of Eindhoven University of Technology. Maxe, L. and Johansson, P-O. (1998), Assessing groundwater vulnerability using travel time and specific surface area as indicators, Hydrogeology Journal, Vol. 6, p. 441 – 449, Springer-Verlag. Morris, B.L., Lawrence, A.R., Chilton, P.J.C., Adams, B., Calow, R.C., and Klinck, B.A. (2003), Groundwater and its susceptibility to degradation: A global assesment of the problem and options for management. Early Warning and Assesment Report Series, RS.03-3. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. Palmer, R.C., and Lewis, M.A. (1998), Assessment of groundwater vulnerability in England and Wales, In: Robins, N.S. (ed) Groundwater Pollution, Aquifer Recharge and Vulnerability, Geological Society, London, Special Publications, 130, p. 191 – 198. Putra, D.P.E. (2003), Integrated Water Resources Management in Merapi-Yogyakarta, Project Seed Net No UGM 01047, Fakultas Teknik UGM (tidak dipublikasikan) Putra, D.P.E. (2007), The Impact of Urbaization on Groundwater Quality: A Case Study in Yogyakarta City – Indonesia, Mitteilungen zur Ingenieurgeologie und Hydrogeologie, Heft 96, 148 S, 72 Abb, 49 Tab, 6 Anl, Herausgegeben vom Lehrstuhl fuer Ingenieurgeologie und Hydrogeologie Univ.-Prof. Dr. Rafig Azzam, RWTH Aachen, Germany, Oktober 2007. Rachmat, H.S. (2000), Peran Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sumberdaya Airtanah pada Era Otonomi Daerah, Lokakarya Nasional Desentralisasi Pengelolaan Airtanah yang Berwawasan Lingkungan, Direktorat Geologi Tata Lingkungan – ESDM, Puncak, Cianjur, 29-31 Oktober 2000. Sembiring, S.F. (2004), kebijakan Nasional Pengelolaan Airtanah, Lokakarya Nasional Pengelolaan Airtanah, Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan, ESDM, Bandung 29 Juli 2004. Teutsch, G., Grathwohl, P., and Schiedek, T. (1997), Literaturstudie zum natürlichen Rückhalt/Abbau von Schadstoffen im Grundwasser.- Texte und Berichte zur Altlastenbearbeitung, Band 35/97, November 1997, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, 51 Seiten, Karlsruhe. Todd, D.K., 1980, Groundwater Hydrology, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York
Konservasi Airtanah-Sebuah Pemikiran (Heru Hendrayana & Doni Prakasa EP)
78
US EPA (1991), Subsurface Contamination Reference Guide, United State Environmental Protection Agency, EPA/540/2-90/011. Vbra, J., Zaporosec, A. (1994), Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability. International Association of Hydrogeologist (International Contributions to Hydrogeology 16). Verlag Heinz Heise, Hannover. Voigt, H.-J., Heinkele, T., Jahnke, C., and Wolker, R. (2004), Characterization of Groundwater Vulnerability to Fulfill Requierements of The Water Framework Directive of The European Union, Geofisica International, Vol. 43, No,. 4, p. 567 – 574. Wimmer, G., Leppig, B., and Dietz, T. (2002), Die Grundwassergefaerdungskarte ueber Locker-bzw. Festgesteinsaquiferen – Erfahrungen bei der Umsetzung des theoretischen Modells in die Praxis, Hrsg: Lehrstuhl fur Ingenieurgeologie und Hydrogeologie der RWTH Aachen Prof. Dr. K. Schetelig, Mitteilungen zur Ingineurgeologie und Hydrogeologie, Heft 80, s. 253 – 272, LIH der RWTH Aachen. Zaporozec, A., (ed). (2002), Groundwater contamination inventory: a methodological guide, IHP-VI, Series on groundwater No. 2, 160 p, UNESCO, Paris, France.