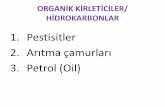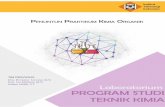KONSENTRASI BAHAN ORGANIK DALAM SEDIMEN DASAR ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of KONSENTRASI BAHAN ORGANIK DALAM SEDIMEN DASAR ...
1
KONSENTRASI BAHAN ORGANIK DALAM SEDIMEN DASAR PERAIRAN KAITANNYA DENGAN KERAPATAN
DAN PENUTUPAN JENIS MANGROVE DI PULAU PANNIKIANG KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU
SKRIPSI
AYU LESTARI
L111 13 002
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
DEPARTEMEN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
i
ABSTRAK
AYU LESTARI. L111 13 002. Konsentrasi Bahan Organik Dalam Sedimen Dasar
Perairan Kaitannya Dengan Kerapatan Dan Penutupan Jenis Mangrove Di Pulau
Pannikiang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Dibimbing oleh Prof. Dr. Amran
Saru, ST, M.Si Pembimbing Utama dan Dr. Mahatma Lanuru, ST., M.Sc Selaku
Pembimbing Anggota.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 dan bertujuan untuk
mengetahui perbedaan kandungan bahan organik disetiap jenis mangrove dan
hubungan kerapatan dan penutupan jenis mangrove dengan kandungan bahan
organik di sedimen. Pengambilan data mangrove dan sampel bahan organik
berdasarkan jenis mangrove dominan di pulau pannikiang. Pengambilan data
dengan menggunakan metode transek (Line transect) dengan luas plot 10 x 10
meter pada ke tiga stasiun jenis mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada jenis mangrove dominan dan tumbuh berkelompok antar jenis mangrove di
pulau Pannikiang tidak berbeda kandungan bahan organiknya sedangkan
stasiun jenis mangrove dengan stasiun yang tidak ditumbuhi mangrove berbeda
kandungan bahan organiknya. Hal ini dikarenakan bahwa keberadaan bahan
organik dipengaruhi oleh kerapatan dan penutupan jenis mangrove. Hasil
pengukuran kerapatan di setiap jenis mangrove tergolong dalam kategori sedang
yang berkisar antara 0,06 – 0,12 (individu/m2). Kandungan bahan organik
tertinggi pada stasiun 1 jenis mangrove Rhizophora apiculata adalah 32,83% dan
stasiun 3 Rhizophora stylosa 30,57%. Hubungan kerapatan jenis mangrove
dengan kandungan bahan organik menggunakan analisis linear diperoleh nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,353, sedangkan nilai koefisien korelasi
diperoleh sebesar 0,594 yang berarti berkorelasi positif antara kandungan bahan
organik dengan kerapatan jenis mangrove.
Kata Kunci : Jenis Mangrove, Kerapatan Jenis Mangrove, Penutupan Jenis
Mangrove, Jenis Sedimen, Kandungan Bahan Organik di Sedimen, Pulau
Pannikiang
ii
ABSTRACK
AYU LESTARI. L111 13 002. Concentrations of Organic Matter in Aquatic-Basic
Sediments are in relation to density and Closure of Mangroves in Pannikiang
Island, Balusu Subdistrick, Barru Districk. Guided by Prof.Amran Saru, ST., M.Si
as first thesis Supervisor and Dr. Mahatma Lanuru, ST., M.Sc as second thesis
Supervisor
This research implemented in August 2017 and aimed to determine the
difference of organic matter content in each species of mangroves and the
relation of density and closure of Mangrove species with the content of organic
matter in sediment. Retrieval data of mangroves and samples oof organic matter
accordingly dominant species of mangroves in Pannikiang Island. Retrieval data
by used transect method (linear transect) with a plot area of 10x10 meters at the
three stations of mangrove type. The result of this research showed that in each
dominant species of mangroves and growth in colony bbetween mangrove
species is not different about the content of organic matter in Pannikiang Island,
meanwhile the mangrove type station and stations which are not overgrown with
mangroves are different about the content of organic matter. This is caused that
existance of organic matter influenced by density and closure of mangrove type.
Measurement result of aech species mangrove density belong to medium ranged
category between 0,06-0,12 (ind/m2). The highest content of organic materials at
first station with mangrove type of Rhizophora apiculata are 32,83% and at the
third station of Rhizophora stylosa are 30,57%. The corellation of mangrove type
density with the content of organic materials used linear analysis obtained the
coefficient of determination (R2) amount 0,353. Meanwhile the coefficient of
determinaton obtained amount 0,594 which mean positively correlated between
the content of organic material with mangrove type density.
Keywords: Mangrove Type, Mangrove Density, Mangrove Closure, Sediment
Type, Organic Material Content in Sediment, Pannikiang Island.
iii
KONSENTRASI BAHAN ORGANIK DALAM SEDIMEN DASAR PERAIRAN KAITANNYA DENGAN KERAPATAN DAN PENUTUPAN JENIS MANGROVE DI PULAU PANNIKIANG KECAMATAN BALUSU
KABUPATEN BARRU
Oleh : AYU LESTARI
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Hasanuddin
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
DEPARTEMEN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
iv
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Skripsi : Konsentrasi Bahan Organik Dalam Sedimen Dasar
Perairan Kaitannya Dengan Kerapatan Dan
Penutupan Jenis Mangrove Di Pulau Pannikiang
Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.
Nama Mahasiswa : Ayu Lestari
Nomor Pokok : L111 13 002
Program Studi : Ilmu Kelautan
Departemen : Ilmu Kelautan
Skripsi telah diperiksa dan disetujui oleh :
Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,
Prof. Dr, Amran Saru, ST. M.Si Dr. Khairul Amri, ST, M.Sc.Stud NIP. 19670924 1995031001 NIP. 196907061995121002
Mengetahui,
Dekan Sekertaris Program Studi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Departemen Ilmu Kelautan,
Dr. Ir. Aisjah Farhum, M.Si Dr. Khairul Amri, ST, M.Sc.Stud NIP. 196906051993032002 NIP. 196907061995121002
Tanggal lulus : 18 Januari 2018
v
RIWAYAT HIDUP
Ayu Lestari dilahirkan pada tanggal 15 April 1995
di Mare, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari tiga bersaudara
pasangan dari Ayahanda Abd. Rasyid dan Ibunda
Baba. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di
TK Mario Pulana, Mare pada tahun 2001, setelah
itu pada tahun 2007 lulus dari SDN 10/73 Padaelo,
tahun 2010 lulus pendidikan SMPN 1 Mare, dan
tahun 2013 lulus dari SMA Negeri 1 Mare. Pada tahun 2013 penulis
diterima di Universitas Hasanuddin melalui jalur SNMPTN (Seleksi
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada Departemen Ilmu
Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada Himpunan Mahasiswa
Ilmu Kelautan (HMIK) sebagai Anggota Bidang Kesekretariatan periode
2013-2014 dan Anggota muda Marine Science Diving Club (MSDC)
periode 2014-2015 Universitas Hasanuddin. Selain itu, penulis pernah
aktif sebagai asisten mata kuliah Iktiologi dan Oseanografi Fisika.
Penulis menyelesaikan rangkaian tugas akhir, melakukan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Reguler angkatan 93 di Kabupaten Wajo Kecamatan
Tanasitolo Desa Nepo dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai
Penelitian Budidaya Air Payau Maros pada tahun 2015. Sebagai salah
satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di Departemen Ilmu
Kelautan, penulis melakukan penelitian berjudul “Konsentrasi Bahan
Organik Dalam Sedimen Dasar Perairan Kaitannya Dengan Kerapatan
dan Penutupan Jenis Mangrove di Pulau Pannikiang Kecamatan Balusu
Kabupaten Barru” dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Amran Saru, ST, M.Si
dan Bapak Dr. Mahatma Lanuru, ST, M.Sc.
vi
KATA PENGANTAR
بسم اهلل الرحمن الرحيم Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul : “Konsentrasi Bahan Organik Dalam Sedimen Dasar
Perairan Kaitannya Dengan Kerapatan Dan Penutupan Jenis Mangrove Di Pulau
Pannikiang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di
Departemen Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas
Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak
terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan
keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.
Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat
mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah
perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, tetapi alhamdulillah dapat penulis atasi
dan selesaikan dengan baik.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat
balasan dari Allah SWT.
Makassar, Januari 2018
Penulis,
Ayu lestari
vii
UCAPAN TERIMA KASIH
1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Abd. Rasyid dan Ibundaku
tercinta Baba, yang selama ini mendidik, membesarkan, menyayangi setulus
hati, mendoakan dan memberikan dorongan selama penulis menyelesaikan
studi. Demikian pula kepada saudaraku tercinta, Marlina dan Marlinda yang
senantiasa memberikan semangat, perhatian, materi dan kasih sayang.
2. Bapak Prof. Dr. Amran Saru, ST, M.Si dan Dr. Mahatma Lanuru, ST, M.Sc
selaku pembimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang telah
banyak membantu dan memberikan bimbingan, perhatian dalam
penyusunan skripsi ini.
3. Kepada para dosen penguji, Bapak Dr.Ir. Muhammad Farid Samawi, M.Si.,
bapak Dr.Ir. Abd. Rasyid J, M.Si., dan bapak Dr. Khaerul Amri, ST,
M.Sc.Stud yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan krtitik dan
saran pada penelitian dan perbaikan skripsi yang membangun sehingga
penulis mampu menyelesaikan studi ini.
4. Kepada Ibu Dr.Ir Aisjah Farhum, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan
dan Perikanan dan Bapak Dr. Mahatma Lanuru, ST, M.Sc selaku Ketua
Departemen Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin.
5. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Kelautan dan Staf pengajar FIKP
atas segala ilmu dan keakraban yang telah diberikan. Semoga ilmu yang
bapak/ibu berikan bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada sahabat-sahabatku ramsis unit 2 Wana, Mita, Lia, Risma, Indah,
Sri, Mega, Sasa, Wulan, Mala, Dian, Ira, Ariska, Cia, Ifa, Sertin, Ice.
Terimakasih atas canda tawa kalian.
viii
7. Kepada saudara-saudariku seperjuanganku KERITIS 13’ Safah, Beni, Bilal,
Permas, Andi, Ilo, Taufik, Jalil, Niar, Risma, Mega, Lia, Nisa, Mita, Indah,
Dewi, serta teman-teman yang lain, belum bisa penulis sebutkan
satupersatu. Terimakasih atas canda tawa, kebersamaan dan bantuan
selama di Ilmu Kelautan.
8. Kepada Abdilah yang rela mengorbankan waktunya untuk menemani
hingga penyelesaian tugas akhir ini. Terimakasih.
9. Team Pannikiang Andi, Abdilah, Safah, Ilo, Indah, Mega, Lia, Wiwi, Santi,
Wulan. Terimakasih atas semangat dan kerjasamanya.
10. Kepada Keluarga KEMAJIK-UH dan MSDC-UH secara tidak langsung
membentuk pribadi penulis dalam berorganisasi.
11. Kepada ibu Surya selaku pengelolah perpustakaan FIKP. Terimakasih atas
bantuan dan tampungannya selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada teman-teman pondok KHADIJAH kak caya, sari, surah, eka,
destri, melinda. Terimakasih keakraban, kekompakan dan makanannya.
13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses
penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu. Terima
Kasih.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan
dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran penulis hargai demi penyempurnaan
penulisan serupa dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga
skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang
membutuhkan.
ix
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................ i
ABSTRACK ........................................................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iv
RIWAYAT HIDUP ................................................................................................ v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
UCAPAN TERIMA KASIH................................................................................. vii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiv
I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
A. Latar Belakang .............................................................................................. 1 B. Tujuan dan Manfaat ....................................................................................... 3 C. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................ 3 II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 4
A. Pengertian mangrove .................................................................................... 4 B. Ciri-ciri ekosistem mangrove ....................................................................... 5 C. Fungsi dan manfaat mangrove ..................................................................... 6
1. Tempat pemijahan (Nursery ground) ........................................................ 6 2. Tempat berlindung fauna ......................................................................... 6 3. Habitat alami yang membentuk keseimbangan ekologis .......................... 6 4. Perlindungan pantai terhadap bahaya abrasi ........................................... 7 5. Perangkap sedimen ................................................................................. 7 6. Penahan angin laut .................................................................................. 7 7. Sumber bahan obat .................................................................................. 7
D. Jenis Mangrove di Pulau Pannikiang ........................................................... 8 E. Satwa yang ada di hutan mangrove ............................................................. 8
1. Ikan .......................................................................................................... 8 2. Kepiting .................................................................................................... 9 3. Moluska ................................................................................................... 9 4. Serangga ................................................................................................. 9 5. Reptil........................................................................................................ 9 6. Amphibia .................................................................................................. 9 7. Burung ..................................................................................................... 9 8. Mamalia ................................................................................................. 10
F. Vegetasi hutan mangrove ........................................................................... 10 1. Flora mangrove mayor (flora mangrove sebenarnya) ............................. 10 2. Flora mangrove minor ............................................................................ 11 3. Asosiasi mangrove, contohnya adalah Cerbera, Acanthus, Derris,
Hibiscus, Calamus, dan lan-lain. ............................................................ 11 G. Zonasi hutan mangrove .............................................................................. 11
1) Mangrove terbuka .................................................................................. 13
x
2) Mangrove tengah ................................................................................... 13 3) Mangrove payau .................................................................................... 13 4) Mangrove daratan .................................................................................. 14
H. Sedimen dan karakteristik sedimen ........................................................... 15 I. Bahan organik .............................................................................................. 16 J. Faktor lingkungan ....................................................................................... 18
1) Suhu ...................................................................................................... 18 2) pH (Derajat keasaman) .......................................................................... 19 3) Salinitas ................................................................................................. 19 4) Pasang surut .......................................................................................... 20 5) Arus ....................................................................................................... 21
III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN .......................................................... 23
A. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian ............................................................ 23 B. Alat dan Bahan ............................................................................................ 23
1) Alat ........................................................................................................ 23 2) Bahan .................................................................................................... 24
C. Metode dan Penelitian ................................................................................ 24 1. Persiapan ............................................................................................... 25 2. Observasi Awal ...................................................................................... 25 3. Penentuan Stasiun di Lokasi Penelitian ................................................. 25 4. Prosedur Penelitian ................................................................................ 26
a. Prosedur pengambilan data mangrove dan sampel sedimen .............. 26 1) Identifikasi jenis mangrove dominan ................................................. 26 2) Bagan transek dan ukuran plot jenis mangrove ................................ 26 3) Bahan organik sedimen dasar perairan ............................................ 27
b. Analisis besar butir sedimen ................................................................ 28 c. Pengukuran parameter lingkungan...................................................... 30
1) Salinitas ........................................................................................... 30 2) Suhu................................................................................................. 30 3) pH tanah .......................................................................................... 30 4) Pasang surut .................................................................................... 30 5) Arus.................................................................................................. 31
5. Pengolahan Data ................................................................................... 31 1) Data mangrove.................................................................................... 31 2) Analisis kandungan bahan organik total pada sedimen ....................... 33 3) Analisis besar butir sedimen ................................................................ 33
6. Analisis Data .......................................................................................... 33 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................................ 34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian........................................................... 34 B. Kondisi Lingkungan Stasiun Penelitian .................................................... 35
1. Suhu ...................................................................................................... 35 2. Salinitas ................................................................................................. 36 3. pH Sedimen ........................................................................................... 36 4. Arus ....................................................................................................... 37 5. Pasang Surut ......................................................................................... 37
C. Bahan Organik Total (BOT) di Sedimen Jenis Mangrove ......................... 38 D. Partikel Sedimen Jenis Mangrove .............................................................. 40 E. Struktur Vegetasi Mangrove ....................................................................... 41
1. Kerapatan Jenis Mangrove .................................................................... 41 2. Penutupan Jenis Mangrove .................................................................... 42
F. Hubungan Kandungan Bahan Organik Sedimen dengan Kerapatan Jenis Mangrove ..................................................................................................... 43
xi
G. Hubungan Penutupan Jenis Mangrove dengan Kandungan Bahan Organik Sedimen ......................................................................................... 44
H. Hubungan Partikel Sedimen dengan Kandungan Bahan Organik di Sedimen ....................................................................................................... 45
V. SIMPULAN DAN SARAN ............................................................................. 46
A. Simpulan ...................................................................................................... 46 B. Saran ............................................................................................................ 46 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 47
LAMPIRAN ....................................................................................................... 50
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Skala Wenworth untuk mengklasifikasikan ukuran partikel sedimen .......
(Hutabarat dan Evans, 1984) ............................................................... 15
Tabel 2. Kriteria kandungan bahan organik dalam sedimen ............................... 17
Tabel 3. Klasifikasi perairan berdasarkan derajat keasaman (pH) ..................... 19
Tabel 4. Stasiun dan Jenis Mangrove di Pulau Pannikiang ................................ 25
Tabel 5. Kriteria Kerapatan dan Penutupan mangrove (KEPMEN_LH Nomor 201
Tahun 2004) ........................................................................................ 32
Tabel 6. Data hasil pengukuran parameter lingkungan di setiap stasiun ........... 35
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Zonasi vegetasi mangrove (White et al., 1989 dalam Noor et al.,
2006) ..... …………………………………………………………………14
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian di Pulau Pannikiang Kabupaten Barru ....... 23
Gambar 3. Lembar Identifikasi Mangrove ....................................................... 26
Gambar 4. Bagan Transek dan Ukuran Plot Sampling Mangrove ................... 27
Gambar 4. Pola pasang surut duduk tengah sementara (DTS) tinggi muka air37
Gambar 5. Kandungan bahan organik sedimen .............................................. 39
Gambar 6. Ukuran partikel sedimen pada tiap stasiun .................................... 40
Gambar 7. Kerapatan jenis mangrove di tiap stasiun ...................................... 41
Gambar 8. Penutupan jenis mangrove di tiap stasiun ..................................... 42
Gambar 9. Hubungan Kerapatan Dengan Kandungan Bahan Organik Sedimen
...................................................................................................... 43
Gambar 10. Hubungan Penutupan Jenis dengan Kandungan Bahan Organik
...................................................................................................... 44
Gambar 11. Hubungan Partikel Sedimen dengan Kandungan Bahan Organik
Sedimen ................................................................. ………………..45
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Mentah Lingkar Batang Mangrove di Setiap Stasiun
Pengamatan ............................................................................... 51
Lampiran 2. Kerapatan Jenis Mangrove di Stasiun 1 ...................................... 53
Lampiran 3. Kerapatan Jenis Mangrove di Stasiun 2 ...................................... 53
Lampiran 4. Kerapatan Jenis Mangrove di Stasiun 3 ...................................... 53
Lampiran 5. Data Mentah Penutupan Jenis Mangrove di tiap Stasiun ............ 54
Lampiran 6. Data Rata-rata Penutupan Jenis Mangrove di tiap Stasiun
Pengamatan ............................................................................... 56
Lampiran 7. Data Mentah Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Setiap
Plot Pengamatan. ....................................................................... 57
Lampiran 8. Data Rata-rata Nilai Parameter Lingkungan Setiap Stasiun
Pengamatan ............................................................................... 58
Lampiran 9. Data Mentah Hasil Pengukuran Arus di Setiap Stasiun
Pengamatan ............................................................................... 59
Lampiran 10. Data Mentah Hasil Pengukuran Pasang Surut di Lokasi Penelitian
................................................................................................... 60
Lampiran 11. Data Mentah Kandungan Bahan Organik di Setiap Stasiun
Pengamatan ............................................................................... 61
Lampiran 12. Analisis Uji One Way Anova Kerapatan dan Penutupan ke Tiga
Stasiun Jenis Mangrove .............................................................. 62
Lampiran 13. Analisis Uji One Way Anova Kandungan Bahan Organik Total dan
Partikel Sedimen ke Empat Stasiun Pengamatan ....................... 63
Lampiran 14. Hasil Uji Regresi Hubungan Kerapatan Jenis Mangrove dengan
Kandungan Bahan Organik di Sedimen Menggunakan Program
SPSS 16.0 .................................................................................. 64
Lampiran 15. Hasil Uji Regresi Hubungan Penutupan Jenis Mangrove dengan
Kandungan Bahan Organik di Sedimen Menggunakan Program
SPSS 16.0 .................................................................................. 65
Lampiran 17. Hasil Uji Regresi Hubungan Partikel Sedimen Mangrove dengan
Kandungan Bahan Organik di Sedimen Menggunakan Program
SPSS 16.0 .................................................................................. 66
xv
Lampiran 18. Meminta izin melakukan pengambilan data penelitian dengan
Kepdes Pulau Pannikiang .......................................................... 67
Lampiran 19. Pengambilan data mangrove dan sampel BOT
................................................................................................... 67
Lampiran 20. Pengukuran parameter lingkungan ............................................. 67
Lampiran 21. Analisis sampel di laboratorium................................................... 68
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak diantara laut dan
daratan yang berfungsi sebagai zona penyangga alami yang harus dilestarikan.
Vegetasi mangrove terdiri dari tumbuhan yang hidup di habitat berair, lumpur
atau rawa pantai pada daerah pasang surut.
Mangrove tersebar diberbagai belahan negara di dunia dengan estimasi
luasan sekitar 19,9 juta hektar. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara
yang memiliki hutan mangrove tertinggi di dunia dan memiliki tingkat
keanekaragaman tertinggi dengan jumlah 202 jenis mangrove (Noor et al., 2006).
Tingginya tingkat keanekaragaman hayati menjadikan hutan mangrove sebagai
aset berharga yang tidak hanya dilihat dari fungsi ekologisnya tetapi juga dari
fungsi ekonomisnya.
Darmadi et al., (2012) menyatakan bahwa secara umum kondisi habitat
mangrove Indonesia dengan tipe komunitas (jenis pohon dominan) ini memiliki
perbedaan jenis mangrove dari satu tempat ke tempat lainnya, seiring dengan
variasi ketebalan dari garis pantai. Faktor utama yang menyebabkan adanya
zonasi pertumbuhan mangrove adalah jenis substrat dan kandungan bahan
organik sedimen pada jenis mangrove tersebut.
Menurut Mulya (2002), peranan bahan organik dalam ekologi laut adalah
sebagai sumber energi bagi tumbuhan maupun hewan, sebagai sumber bahan
keperluan bakteri, sebagai zat yang dapat mempercepat dan memperlambat
pertumbuhan sehingga memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan.
Buckman dan Brady (1982), menyatakan bahwa bahan organik merupakan salah
2
satu komponen penyusun substrat dasar perairan yang terdiri dari timbunan sisa-
sisa tumbuhan dan hewan.
Salah satu daerah yang dapat menjadi sumber data tentang bahan organik
sedimen dan jenis mangrove adalah pulau Pannikiang. Pulau tersebut
merupakan salah satu pulau yang ada di gugusan Kepulauan Spermonde
dengan hutan mangrove yang masih tergolong alami dan memiliki
keanekaragaman jenis mangrove. Hal inilah yang mendasari penulis dalam
memilih lokasi penelitian.
Jenis mangrove yang ditemukan di Pulau Pannikiang yaitu sebanyak 30
jenis, terdiri dari 17 jenis mangrove sejati dan 13 jenis mangrove asosiasi.
Jumlah jenis mangrove sejati yang ditemukan di pulau Pannikiang tergolong
sedang dengan cara hidup yang tumbuh dominan maupun hidup berkelompok
antar jenis mangrove, sedangkan jenis mangrove yang memiliki kerapatan jenis
tertinggi yaitu jenis Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, dan Sonneratia
alba. Kondisi ini diduga bahwa terjadi perbedaan kandungan bahan organik
sedimen pada jenis mangrove yang memungkinkan berpengaruh terhadap
pertumbuhan mangrove (Suwardi, 2013).
Jenis mangrove yang tumbuh dengan kerapatan tinggi dari satu tempat ke
tempat lainnya memiliki perbedaan nilai kandungan bahan organik. Salah
satunya adalah bahan organik dalam sedimen yang merupakan sumber
kesuburan bagi tumbuhan mangrove. Berdasarkan uraian di atas, maka
dilakukan penelitian tentang konsentrasi bahan organik sedimen kaitannya
dengan kerapatan dan penutupan jenis mangrove di Pulau Pannikiang,
Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
3
B. Tujuan dan Manfaat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kandungan bahan
organik disetiap jenis mangrove yang dominan dan mengetahui konsentrasi
bahan organik di sedimen kaitannya dengan kerapatan dan penutupan jenis
mangrove.
Manfaat hasil dari penelitian ini dapat memberi informasi tentang perbedaan
kandungan bahan organik sedimen pada jenis mangrove serta memberikan
gambaran tentang kaitan kandungan bahan organik dengan kerapatan dan
penutupan jenis mangrove di Pulau Pannikiang, Kecamatan Balusu, Kabupaten
Barru.
C. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini meliputi identifikasi jenis mangrove dominan
yang tumbuh, bahan organik pada sedimen mangrove, kerapatan jenis (Di),
penutupan jenis (Ci). Selain itu dilakukan pengukuran parameter lingkungan
seperti suhu, salinitas, pH tanah, arus, pasang surut dan analisis besar butir
sedimen.
4
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian mangrove
Ekosistem mangrove adalah ekosistem pantai yang disusun oleh berbagai
jenis vegetasi yang mempunyai bentuk adaptasi biologis dan fisiologis secara
spesifik terhadap kondisi lingkungan yang cukup bervariasi. Ekosistem mangrove
umumnya didominasi oleh beberapa spesies mangrove sejati diantaranya
Avicennia sp., Sonneratia sp., Rhizophora sp., Bruguiera sp. Spesies mangrove
tersebut dapat tumbuh dengan baik pada ekosistem perairan dangkal, karena
adanya bentuk perakaran yang dapat membantu untuk beradaptasi terhadap
lingkungan perairan, baik dari pengaruh pasang surut maupun faktor-faktor
lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap ekosistem mangrove seperti :
suhu, salinitas, sedimen, pH, arus dan pasang surut (Saru, 2013).
Menurut Nybakken (1992), hutan mangrove adalah secara umum yang
digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropik yang didominasi
oleh beberapa jenis pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang
mempunyai kemampuan untuk tumbuh pada perairan asin. Hutan mangrove
meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili, dan terdiri
atas 12 genus tumbuhan berbunga: Avicennia, Sonneratia, Rhizophora,
Bruguiera, Ceriops, Xylocarpus, Lummitzera, Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis,
Snaeda dan Conocarpus (Bengen, 2000).
Menurut Watson (1928), pembentukan mangrove dimulai dengan
pengendapan lumpur di daerah pantai yang dibawa oleh aliran sungai,
bercampur dengan pasir sebagai hasil erosi pantai. Watson juga mengatakan
bahwa jenis mangrove yang pertama tumbuh adalah jenis Avicennia, kemudian
disusul jenis Sonneratia. Penyebaran jenis Sonneratia umumnya dibantu oleh air
5
dan berkembang pada tanah yang banyak mengandung bahan organik
bercampur lumpur. Vegetasi berikutnya yang berkembang adalah jenis
Bruguiera, Rhizopora dan Casuarina.
B. Ciri-ciri ekosistem mangrove
Ekosistem hutan mangrove bersifat kompleks dan dinamis, dikatakan
kompleks karena ekosistemnya disamping dipenuhi oleh vegetasi mangrove,
juga merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Jenis tanah yang
berada di bawahnya termasuk tanah perkembangan muda (saline young soil)
yang mempunyai kandugan liat yang tinggi dengan nilai kejenuhan basa dan
kapasitas tukar kation yang tinggi. Kandungan bahan organik, total nitrogen, dan
ammonium termasuk kategori sedang pada bagian yang dekat laut dan tinggi
pada bagian arah daratan (Kusmana, 2002). Bersifat dinamis karena hutan
mangrove dapat tumbuh dan berkembang terus serta mengalami suksesi sesuai
dengan perubahan tempat tumbuh alaminya. Ciri-ciri terpenting dari
penampakan hutan mangrove, terlepas dari habitatnya yang unik menurut
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Mangrove Indonesia (2008) adalah :
1. Memiliki jenis pohon yang relatif sedikit
2. Memilki akar nafas (pneumatofora) misalnya seperti jangkar melengkung
dan menjulang pada bakau Rhizopora sp., serta akar yang mencuat vertikal
seperti pensil pada pidada Sonneratia sp., dan pada api-api Avicennia sp.
3. Memliki biji yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di pohonnya,
khususnya pada Rhizopora yang lebih di kenal sebagai propagul.
4. Memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon.
6
C. Fungsi dan manfaat mangrove
Mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting
di wilayah pesisir dan lautan. Secara lebih terperinci fungsi bio-ekologis dan
sosio-ekonomis dari hutan mangrove.
Menurut Purnobasuki (2005) dijabarkan sebagai berikut :
1. Tempat pemijahan (Nursery ground)
Ekosistem mangrove terkenal sebagai bahan organik yang merupakan mata
rantai makanan di daerah pantai. Serasah daun mangrove yang subur dan
berjatuhan di perairan sekitarnya diubah oleh mikroorganisme (terutama kepiting)
dan mikroorganisme pengurai menjadi detritus, berubah menjadi fitoplankton
yang dimakan oleh binatang-binatang laut, sehingga demikian di lingkungan
mangrove kaya akan zat nutrisi bagi ikan-ikan dan udang yang hidup di habitat
tersebut.
2. Tempat berlindung fauna
Mangrove dengan tajuknya yang rata dan rapat, serta selalu hijau dan
membentuk lapisan yang berbasis di sepanjang pantai merupakan tempat yang
disukai oleh burung-burung besar sebagai tempat membuat sarang dan bertelur.
3. Habitat alami yang membentuk keseimbangan ekologis
Dalam lingkungan hutan mangrove terdapat beranekaragam biota yang satu
dengan lainnya saling berinteraksi dalam kehidupannya. Dalam keadaan alami
keragaman biota tersebut membentuk suatu keseimbangan, terutama
keseimbangan antara prey (mangsa) dengan predator (pemangsa). Secara
ekologis keseimbangan ini harus dijaga agar kehidupan alami dapat berjalan apa
adanya. Namun dengan hilangnya salah satu komponen akan mengganggu
keseimbangan tersebut dan pada akhirnya menuju pada rusaknya ekosistem
hutan mangrove secara keseluruhan.
7
4. Perlindungan pantai terhadap bahaya abrasi
Sistem perakaran mangrove yang rapat dan terpancang sebagai jangkar,
dapat berfungsi untuk meredam gempuran gelombang laut dan ombak, serta
cengkeraman akar yang menancap pada tanah dapat menahan lepasnya patikel-
partikel tanah, dengan demikian bahaya abrasi atau erosi oleh gelombang laut
dapat dicegah.
5. Perangkap sedimen
Sistem perakaran mangrove juga efektif dalam menangkap partikel-partikel
tanah yang berasal dari hasil erosi di sebelah hulu. Perakaran mangrove
menangkap partikel-partikel tanah tersebut dan mengendapkannya, sehingga
akan terjadi suatu kondisi di mana endapan lumpur tidak hanyut oleh arus
gelombang laut.
6. Penahan angin laut
Jajaran tegakan mangrove yang tumbuh di pantai, melindungi pemukiman
nelayan di sebelahnya (kearah daratan) dari hembusan angin yang kencang.
Angin laut yang bertiup kencang kearah daratan dapat ditahan oleh lapisan hutan
mangrove dan dibelokkan kearah atas. Pemukiman di belakang hutan mangrove
tersebut akan terletak di belakang bayangan angin (leading area).
7. Sumber bahan obat
Sebagian besar dari tumbuhan mangrove bermanfaat sebagai bahan obat.
Ekstrak dan bahan mentah dari mangrove telah banyak dimanfaatkan oleh
masyarakat pesisir untuk keperluan obat-obatan alamiah. Campuran senyawa
kimia bahan alam oleh para ahli kimia dikenal sebagai pharmacopoeia.
Sejumlah tumbuhan mangrove dan tumbuhan asosianya digunakan pula sebagai
bahan tradisional insektisida dan pestisida.
8
D. Jenis Mangrove di Pulau Pannikiang
Menurut Saru (2013), ekosistem mangrove di Kecamatan Balusu terdiri dari
jenis tumbuhan mangrove sejati yaitu Sonneratia alba, Rhizophora stylosa,
Rhizophora mucronata dan Ceriops decandra dengan formasi campuran,
sedangkan jenis mangrove ikutan terdiri dari jenis mangrove Ipomoea pes-
caprae dan Acanthus ilicifolius. (Suwardi et al., 2013) menyatakan bahwa di
Pulau Pannikiang diperoleh komposisi jenis mangrove sejati yaitu Avicennia
lanata, Avicennia marina, Lumnitzera racemosa, Excoecaria agallocha, Pemphis
acidula, Xylocarpus granatum, Xylocarpus mollucensis, Aegiceras corniculatum,
Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorrhiza, Ceriops decandra, Ceriops tagal,
Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Scyphiphora
hydrophyllaceae, Sonneratia alba.
Komposisi jenis mangrove asosiasi yaitu Acanthus ilicifolius, Sesuvium
portulacastrum, Sarcolobus globosus, Terminalia catappa, Ipomoea pes-caprae,
Derris trifoliate, Pongimia pinnata, Scaevola taccada, Cassyta filiformis, Hibiscus
tilaceus, Thespesia populnea, Pandanus tectorius.
E. Satwa yang ada di hutan mangrove
Hutan mangrove menjadi habitat berbagai jenis fauna, mulai dari satwa air
hingga primata. Ekosistem mangrove menjadi tempat berkembang biak berbagai
satwa air seperti ikan, udang-udangan, kepiting dan moluska. Beberapa jenis
burung air juga memilih tempat mencari makan sejumlah satwa liar seperti reptil
dan mamalia. Berikut ini jenis-jenis satwa yang sering dijumpai di hutan
mangrove :
1. Ikan
Ikan menjadikan mangrove sebagai tempat berlindung, mencari makan dan
berkembang biak. Ikan-ikan kecil memilih berkembang biak di habitat mangrove
9
untuk menghindari predator. Mangrove menyediakan makanan bagi ikan dalam
bentuk material organik yang berupa guguran vegetasi tanaman, berbagai jenis
serangga, kepting, udang-udangan dan invertebrata.
2. Kepiting
Kepiting merupakan hewan yang paling umum dan mudah ditemukan di
areal mangrove. Menurut sejumlah penelitian rata-rata ada 10-70 ekor kepiting
disetiap meter persegi hutan mangrove
3. Moluska
Moluska banyak ditemukan di hutan mangrove indonesia. Hewan ini hidup
di dalam tanah, permukaan tanah atau menempel di batang-batang pohon.
4. Serangga
Serangga yang hidup di hutan mangrove kebanyakan berasal dari ordo
Hymenoptera, Diptera dan Psocoptera. Serangga memiliki peranan penting
dalam jaring makanan di hutan mangrove. Beberapa diantaranya menjadi pakan
bagi burung air, ikan dan reptil.
5. Reptil
Reptil yang ditemukan di hutan mangrove biasanya dapat ditemukan juga di
lingkungan air tawar atau di daratan. Beberapa diantaranya adalah buaya
muara, biawak, ular air, ular mangrove dan ular tambak.
6. Amphibia
Hewan jenis amphibia jarang ditemukan di area mangrove. Sejauh ini hanya
ada dua jenis amphibia yang sanggup hidup di lingkungan bersalinitas tinggi
seperti mangrove, yakni Rana cancrivora dan Rana limnocharis.
7. Burung
Hutan mangrove adalah surga bagi burung air dan burung migrasi lainnya.
Setidaknya ada 200 spesies burung yang bergantung pada ekosistem mangrove,
atau sekitar 13% dari seluruh burung yang ada di Indonesia. Beberapa di
10
antaranya termasuk burung-burung bangau yang punah, seperti bangau wilwo
(Mycteria cinerea), bubut hitam (Centropus nigrorufus), dan bangau tongtong
(Leptoptilos javanicus).
8. Mamalia
Mamalia menjadikan habitat mangrove sebagai tempat mencari makan.
Beberapa diantaranya adalah babi liar, kelelawar, kancil, berang-berang dan
kucing bakau, sedangkan untuk mamalia air ada lumba-lumba yang hidup
disekitar muara. Harimau sumatera juga ditemukan berkeliaran di hutan
mangrove wilayah Sungai Sembilang, Sumatera Selatan. Primata merupakan
salah satu jenis mamalia yang sering mencari makan di hutan mangrove.
Diantaranya ada lutung, monyet ekor panjang, dan bekantan, namun mamalia
tersebut tidak ada yang eksklusif hidup di hutan mangrove.
F. Vegetasi hutan mangrove
Soerianegara (1987) dalam Noor et al., (1999) memberikan batasan hutan
mangrove sebagai hutan yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan
sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut serta ciri dari hutan
ini terdiri dari tegakan poho Avicennia, Sonneratia, Aegiceras, Rhizophora,
Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria, Xylocarpus, Scyphyphora dan
Nypa. Flora mangrove terdiri atas pohon, epipit, liana, alga, bakteri dan fungi.
Telah diketahui lebih dari 20 famili flora mangrove dunia yang terdiri dari 30
genus dan lebih kurang 80 spesies. Berdasarkan jenis-jenis tumbuhan yang
ditemukan di hutan mangrove indonesia memiliki sekitar 89 jenis, yang terdiri
atas 35 jenis pohon, 5 jenis terna, 9 jenis perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit dan 2
jenis parasit.
Tomlinson (1986) membagi flora mangrove menjadi tiga kelompok, yakni :
1. Flora mangrove mayor (flora mangrove sebenarnya)
11
Flora yang menunjukkan kesetiaan terhadap habitat mangrove,
berkemampuan membentuk tegakan murni dan secara dominan mencirikan
struktur komunitas, secara morfologi mempunyai bentuk-bentuk adaptif khusus
(bentuk akar dan viviparitas) terhadap lingkungan mangrove, dan mempunyai
mekanisme fisiologis dalam mengontrol garam. Contohnya adalah Avicennia,
Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Kandelia, Sonneratia, Lumnitzera, Laguncularia
dan Nypa.
2. Flora mangrove minor
flora mangrove yang tidak mampu membentuk tegakan murni, sehingga
secara morfologis tidak berperan dominan dalam struktur komunitas, contoh :
Excoecaria, Xylocarpus, Heritiera, Aegiceras, Aegialitis, Acrostichum,
Camptostemon, Scyphiphora, Pemphis, Osbornia dan Pelliciera.
3. Asosiasi mangrove, contohnya adalah Cerbera, Acanthus, Derris, Hibiscus,
Calamus, dan lan-lain.
G. Zonasi hutan mangrove
Menurut Bengen (2001), flora mangrove umunya tumbuh membentuk zonasi
mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi di hutan mangrove
mencerminkan tanggapan ekofisiologis tumbuhan mangrove terhadap degradasi
lingkungan. Zonasi yang terbentuk bisa berupa zonasi yang sederhana (satu
zonasi, zonasi campuran) dan zonasi yang kompleks (beberapa zonasi
tergantung pada kondisi lingkungan mangrove yang bersangkutan. Beberapa
faktor lingkungan yang penting dalam mengontrol zonasi adalah :
1. Pasang surut yang secara tidak langsung mengontrol dalamnya muka air
(water table) dan salinitas air dan tanah. Secara langsung arus pasang surut
dapat menyebabkan kerusakan terhadap anakan.
12
2. Tipe tanah yang secara tidak langsung menentukan tingkat aerasi tanah,
tingginya muka air dan drainase.
3. Kadar garam tanah dan air yang berkaitan dengan toleransi spesies
terhadap kadar garam serta pasokan dan aliran air tawar.
4. Cahaya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anakan dari spesies
intoleran seperti Rhizophora, Avicennia dan Sonneratia.
5. Pasokan dan aliran air tawar
Menurut struktur ekosistem, secara garis besar dikenal tiga tipe formasi
mangrove, yaitu :
1. Mangrove pantai : tipe ini air laut dominan dipengaruhi air sungai. Struktur
horizontal formasi ini dari arah laut ke arah darat adalah mulai dari tumbuhan
pionir (Avicennia sp.), diikuti oleh komunitas campuran Sonneratia alba,
Rhizophora apiculata, selanjutnya komunitas murni Rhizophora sp. dan
akhirnya komunitas campuran Rhizophora-Bruguiera. Bila genangan
berlanjut, akan ditemui komunitas murni Nypa fruiticans di belakang
komunitas campuran yang terakhir.
2. Mangrove muara : pengaruh oleh air laut sama dengan pengaruh air sungai.
Mangrove muara dicirikan oleh mintakat tipis Rhizophora spp. Di tepian alur,
diikuti komunitas campuran Rhizophora–Bruguiera dan diakhiri komunitas
murni Nypa fruticans.
3. Mangrove sungai : pengaruh oleh air sungai lebih dominan daripada air laut,
dan berkembang pada tepian sungai yang relatif jauh dari muara. Jenis-
jenis mangrove banyak berasosiasi dengan komunitas daratan.
Secara sederhana, mangrove umumnya tumbuh dalam 4 zona, yaitu pada
daerah terbuka, daerah tengah, daerah yang memilki sungai berair payau
sampai hampir tawar, serta daerah ke arah daratan yang memiliki air tawar.
13
1) Mangrove terbuka
Mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. Samingan
(1980) menemukan bahwa di Karang Agung, Sumatera Selatan, di zona ini
didominasi oleh Sonneratia alba yang tumbuh pada areal yang betul-betul
dipengaruhi oleh air laut. Van Steenis (1958) melaporkan bahwa Sonneratia
alba dan Avicennia alba merupakan jenis-jenis ko-dominan pada areal pantai
yang sangat tergenang ini. Komiyama et al., (1988) menemukan bahwa di
Halmahera, Maluku, di zona terbuka sangat bergantung pada substratnya.
Sonneratia alba cenderung untuk mendominasi daerah berpasir, sementara
Avicennia marina dan Rhizopora mucronata cenderung untuk mendominasi
daerah yang lebih berlumpur (Van Steenis, dalam Imran, 2002).
2) Mangrove tengah
Mangrove di zona ini terletak dibelakang mangrove zona terbuka. Di zona
ini biasanya didominasi oleh jenis Rhizopora. Namun, Samingan (1980)
menemukan di Karang Agung didominasi oleh Bruguiera cylindrica. Jenis-jenis
penting lainnya yang ditemukan di Karang Agung adalah Bruguiera eriopetala,
Bruguiera gymnrrhiza, Exoecaria agallocha, Rhizophora mucronata, Xylocarpus
granatum dan Xylocarpus moluccensis.
3) Mangrove payau
Mangrove berada disepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar. Di
zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Nypa atau Sonneratia. Di Karang
Agung, komunitas Nypa fruticans terdapat pada jalur yang sempit di sepanjang
sebagian besar sungai. Di jalur-jalur tersebut sering sekali ditemukan tegakan
Nypa fruticans yang bersambung dengan vegetasi yang terdiri dari Cerbera sp,
Gluta renghas, Stenochlaena palustris dan Xylocarpus granatum. Ke arah
pantai, campuran komunitas Sonneratia-Nypa lebih sering ditemukan. Sebagian
besar daerah lainnya, seperti di Pulau Kaget dan Pulau kembang di mulut Sungai
14
Barito di kalimantan Selatan atau di mulut Sungai di Aceh, Sonneratia caseolaris
lebih dominan terutama di bagian estuari yang berair hampir tawar (Gesen dan
van Balen, 1991).
4) Mangrove daratan
Mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakag jalur
hijau mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis yang umum ditemukan pada zona
ini termasuk Ficus microcarpus (Ficus retusa), Intsia bijuga, Nypa fruticans,
Lumnitzera racemosa, Pandanus sp. dan Xylocarpus moluccensis (Kantor
Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1993). Zona ini memiliki kekayaan jenis yang
lebih tinggi dibandingkan dengan zona lainnya.
Zonasi vegetasi mangrove dapat dlihat pada gambar sebagai berikut :
Gambar 1. Zonasi vegetasi mangrove (White et al., 1989 dalam Noor et
al., 2006)
Menurut Irwanto (2006), umumnya di perbatasan daerah laut didominasi
jenis mangrove pionir Avicennia spp. dan Sonneratia spp. Di pinggiran atau
bantaran muara sungai, Rhizophora spp., Sonneratia spp., Bruguiera spp., dan
jenis pohon yang berasosiasi dengan mangrove seperti tingi (Ceriops sp.) dan
15
panggang (Excoecaria sp.). Disepanjang sungai di bagian muara biasanya
dijumpai pohon nipah (Nypah fruiticans).
H. Sedimen dan karakteristik sedimen
Substrat sangat penting untuk perkembangan habitat mangrove karena
ukuran butiran dan tipe sedimen secara langsung atau tidak langsung dapat
mempengaruhi berbagai aspek hidrologi dan kesuburan tanah.
Dahuri et al., (1996) menyatakan bahwa keseimbangan antara sedimen
yang dibawa oleh sungai dengan kecepatan pengangkutan sedimen di muara
sungai akan menentukan berkembangnya daratan pantai. Jumlah sedimen yang
dibawa ke laut segera diangkut oleh arus laut, maka pantai akan dalam keadaan
stabil. Sebaliknya jumlah sedimen melebihi kemampuan arus laut dalam
pengangkutannya, maka daratan pantai bertambah.
Sebagian besar sedimen terdiri dari partikel-partikel yang berasal dari
pembongkaran batuan dan potongan-potongan kulit (shell) serta sisa-sisa rangka
dari organisme laut. Skala klasifikasi sedimen pantai berdasarkan ukuran yang
banyak digunakan yaitu skala Wenworth (Hutabarat dan Evans, 1984).
Tabel 1. Skala Wenworth untuk mengklasifikasikan ukuran partikel sedimen (Hutabarat dan Evans, 1984)
Kelas Ukuran Sedimen Diameter butiran (mm)
Boulder (Bongkah) >256
Cobble (Kerikil kasar) 64-256
Pebble (kerikil sedang) 4-64
Granule (kerikil halus) 2-4
Very coarse sand (pasir sangat kasar) 1-2
Coarse Sand (Pasir kasar) 0,5-1
Medium Sand (pasir sedang) 0,25-0,5
Fine sand (pasir halus) 0,125-0,25
Very fine sand (pasir sangat halus) 0,062- 0,125
Silt (lanau) 0,0039-0,062
Clay (lempung) <0,0039
16
Umumnya semakin besar ukuran partikel semakin besar pula beratnya, oleh
karena itu air yang mengalir dengan kecepatan yang sangat lambat hanya dapat
mengangkut material-material yang sangat halus. Sebaliknya, sedimen yang
berukuran lebih besar seperti kerikil dipindahkan hanya oleh aliran air yang
cepat. Pasir yang cenderung mengendap lebih cepat sedangkan lanau yang
terangkut pada jarak yang cukup jauh sebelum diendapkan dan lempung yang
ukurannya sangat halus akan tersuspensi untuk jangka waktu tertentu dengan
jarak yang cukup jauh (Block, 1986 dalam Amda, 2003).
Jenis sedimen berkaitan erat pula dengan kandungan oksigen dan
ketersediaan bahan organik didalam sedimen. Pada jenis sedimen berpasir
kasar, kandungan oksigennya relatif lebih besar dibandingkan dengan tipe pasir
halus, seperti lumpur. Hal ini disebabkan karena pada tipe sedimen pasir kasar
terdapat pori yang memungkinkan berlangsungnya percampuran yang lebih
intensif degan air yang berada diatasnya. Namun kalau ditinjau dari segi bahan
organik atau zat makanan, terjadi sebaliknya. Pada sedimen pasir kasar bahan
organik yang dikandungnya relatif sedikit. Sebaliknya pada jenis sedimen pasir
halus atau lanau, oksigen yang terkandung tidak banyak karena pori yang dimiliki
tipe sedimen pasir halus tidak memungkinkan penyerapan oksigen dengan
jumlah besar, tetapi bahan organik yang dikandungnya banyak karena semakin
halus tekstur sedimen, semakin besar kemampuannya menjebak bahan organik
(Efriyeldi, 1997).
I. Bahan organik
Menurut Buckman dan Brady (1982), bahan organik merupakan salah satu
komponen penyusun substrat dasar perairan yang merupakan penimbunan sisa-
sisa tumbuhan dan hewan. Sumber penting bahan organik juga berasal dari
17
daratan melalui sungai, sehingga di daerah tersebut memiliki besar bahan
organik (Nybakken, 1988).
Hutabarat dan Evans (1995) menjelaskan bahwa didalam perairan, bahan
organik terdapat dalam bentuk detritus. Sejumlah besar bahan-bahan ini
terbentuk sisa-sisa tumbuhan atau hewan benthik yang hancur, yang hidup di
perairan pantai yang dangkal. Sumber lain bahan organik adalah sisa-sisa tubuh
organisme pelagis yang mati dan tenggelam ke dasar serta kotoran binatang
dalam perairan.
Menurut Paul dan Ladd (1981) bahwa semakin dalam (dari permukaan
tanah) maka kandungan bahan organik semakin menurun dengan kandungan
tertinggi pada lapisan atas atau top soil (0-10 cm) diikuti bagian bawah atau
subsoil (10-20 cm). Reynold (1971) mengklasifikasikan kandungan bahan
organik dalam sedimen yaitu terlihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Kriteria kandungan bahan organik dalam sedimen
No. Kandungan Bahan Organik (%) Kriteria
1 >35 Sangat Tinggi
2 17-35 Tinggi
3 7-17 Sedang
4 3,5-7 Rendah
5 <3,5 Sangat Rendah
Sumber : Reynold (1971)
Nybakken (1988) menyatakan bahwa di daerah yang bersubstrat lumpur
banyak mengandung bahan organik. Hal ini karena di daerah tersebut biasanya
gerakan air relatif kecil sehingga partikel organik yang tersuspensi dalam air
akan mengendap di dasar perairan.
Bahan organik yang terdapat dalam ekosistem mangrove dapat berupa
bahan organik yang terlarut dalam air (tersuspensi) dan bahan organik yang
18
tertinggal dalam sedimen. Bahan organik adalah nutrien yang penting bagi
mikroorganisme. Jumlah mikroorganisme di laut secara umum sangat kecil, tapi
kelimpahannya bertambah terhadap kehadiran bahan organik yang diproduksi
oleh fotosintesis plankton, seaweed atau organisme lain dan juga dari populasi
bahan organik dari aktivitas perkapalan (Gunkel, 1976). Selain itu, dijelaskan
bahwa bahan organik terdiri dari beberapa komponen yang banyak dari daratan.
Berdasarkan sumber atau asal komponen bahan organik dalam lingkungan laut,
bahan organik dapat digolongkan dua golongan :
1. Pelepasan bahan organik dari organisme laut
2. Populasi air laut dari aktivitas manusia dan proses alam (pelapukan,
bleaching dan lain-lain)
Sumber bahan organik tanah sebagian besar dari hancuran seperti akar-
akar, semak, rumput dan tanaman lain sedangkan hewan biasanya dianggap
sebagai sumber bahan organik kedua.
J. Faktor lingkungan
Faktor lingkungan perairan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove
yaitu :
1) Suhu
Suhu merupakan faktor yang sangat menentukan kehidupan dan
pertumbuhan mangrove. Suhu yang baik untuk kehidupan mangrove adalah
tidak kurang dari 20°C (Ghufran dan Kordi, 2012).
Menurut Anwar et al., (1984), pada perairan dangkal suhu dapat mencapai
34°C. Daerah mangrove sendiri suhunya lebih rendah dan variasinya hampir
sama dengan daerah pesisir lainnya yang terlindung.
19
2) pH (Derajat keasaman)
Derajat keasaman pH mempunyai pengaruh yang besar terhadap tumbuhan
dan hewan air sehingga sering digunakan sebagai petunjuk untuk menyatakan
baik buruknya suatu lahan untuk penggunaannya. Nilai pH tanah merupakan
tingkat keasaman atau kebasaan suatu tanah yang dapat menjadi patokan
menentukan tanah yang baik untuk media tumbuh tanaman. Wahyu dan
Widyastuti (1998), menyatakan bahwa tanah yang sesuai mendukung
pertumbuhan mangrove berkisar antara 6,0–8,5. Menurut Banareja, 1967 dalam
Hasbi, 2004 klasifikasi perairan berdasarkan derajat keasaman (pH) sebagai
berikut.
Tabel 3. Klasifikasi perairan berdasarkan derajat keasaman (pH)
Derajat Keasaman (pH) Keadaan Perairan
5,5 – 6,5 Kurang produktif
6,5 – 7,5 Produktif
7,5 – 8,5 Sangat produktif
>8,5 Tidak produktif
3) Salinitas
Salinitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan
perkembangan mangrove. Bengen (2002) menjelaskan bahwa mangrove dapat
tumbuh pada salinitas tertentu dengan kisaran 2–22°/∞. Perbedaan salinitas ini
menyebabkan terjadinya zonasi dari salinitas tertinggi sampai salinitas rendah,
dari salinitas tinggi ke salinitas rendah terbentuk zonasi yang umum ditemukan
yaitu Avicennia sp., Sonneratia sp., Rhizophora sp., Bruguiera sp., dan Nypa sp.
Pembentukan zonasi bukan hanya tergantung pada salinitas sehingga zonasi ini
tidak teratur sesuai besaran salinitas saja. Rhizophora mucronata dan
20
Rhizophora Stylosa mentoleril salinitas maksimum pada 55°/∞ sedangkan C.
Tagal pada salinitas 60°/∞.
Menurut Ardhana (2002), bahwa perairan laut pada umumnya mempunyai
kestabilan salinitas yang relatif tinggi dibandingkan perairan payau. Perubahan
salinitas lebih sering terjadi pada perairan dekat pantai, hal ini disebabkan
banyak air tawar yang masuk baik melalui run off terutama pada waktu musim
penghujan. Nilai salinitas 7°/∞–14°/∞ masih merupakan kisaran salinitas yang
dapat ditolerir oleh bakau untuk dapat tumbuh.
Setiap jenis mangrove umumnya memiliki toleransi yang berbeda terhadap
tingginya salinitas. Batas ambang toleransi tumbuhan bakau diperkirakan pada
salinitas sekitar 90°/∞ atau kurang lebih 2,5 kali salinitas air laut (Ciotron, 1978).
Menurut Walter (1971), Rhizophora merupakan marga yang memiliki
kemampuan toleransi terhadap kisaran salinitas yang luas dibandingkan dengan
mangrove lainnya.
4) Pasang surut
Faktor fisik yang sangat berpengaruh pada hutan mangrove salah satunya
adalah pasang-surut. Pasang surut adalah naik dan turunnya permukaan air laut
secara periodik selama interval waktu tertentu (Nybakken, 1988).
Menurut Triatmodjo (1999), dalam oseanografi pasang surut diberbagai
daerah dapat dibedakan dalam empat tipe pasang surut, yaitu :
a. Pasang surut harian ganda (semidiurnal tide), pada tipe ini dalam satu
hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi yang hampir
sama dengan pasang surut yang terjadi berurutan secara teratur.
Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit.
21
b. Pasang surut harian tunggal (diurnal tide), dalam satu hari terjadi satu
kali pasang dan satu kali surut. Periode pasang surut adalah 24 jam 50
menit.
c. Pasang surut condong keharian ganda (mixed tide preavailling diurnal),
dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut tetapi tinggi
periodenya berbeda.
d. Pasang surut condong ke harian tunggal (mixed tide preavalling diurnal),
pada tipe ini dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air
surut, tetapi kadang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan
tinggi dan periode yang berbeda-beda.
5) Arus
Arus merupakan gerakan air yang sangat luas yang terjadi pada seluruh
lautan di dunia. Terjadinya arus di laut diakibatkan oleh berbagai hal diantaranya
adalah sebagai akibat adanya perbedaan temperatur, densitas, bentuk topografi
dasar laut (relief), pengaruh arus sungai yang bermuara ke perairan, disebabkan
oleh angin permukaan dan pengaruh pasang surut.
Menurut Dahuri et.al (1996), gelombang yang menuju pantai dapat
menimbulkan arus pantai (Near shore current) yang berpengaruh terhadap
proses endapan material dan pengangkutan bahan organik di pantai. Pola arus
pantai ini ditentukan terutama oleh besarnya sudut yang dibentuk antara
gelombang yang dating dengan garis pantai jika sudut dating itu cukup besar,
maka akan terbentuk arus susur pantai yang disebabkan oleh perbedaan
tekanan hidrostatik. Jika sudut gelombang kecil atau sama dengan nol maka
terbentuk rip current dengan arah menuju pantai.
Kecepatan dan arah arus sangat penting dalam proses pengadukan dan
perpindahan dalam perairan seperti mikro nutrient dan material tersuspensi.
22
Selanjutnya dikatakan bahwa ruang, waktu dan kedalaman mempengaruhi
distribusi arah dan kecepatannya (Storm, 1989).
23
III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei – Agustus 2017 di pulau
Pannikiang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Gambar 2).
Analisis sampel bahan organik pada sedimen dasar dilakukan di Laboratorium
Oseanografi Fisika dan Geomorfologi Pantai, Departemen Ilmu Kelautan,
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian di Pulau Pannikiang Kabupaten Barru.
B. Alat dan Bahan
1) Alat
Alat yang digunakan pada saat penelitian yaitu global positioning system
(GPS) untuk menentukan koordinat titik sampling, Alat tulis menulis untuk
mencatat data, kompas untuk menentukan arah sampling, roll meter 100 meter
untuk mengukur luasan area, tali rapia untuk membuat garis transek, pH meter
24
untuk mengukur pH tanah, handrefractometer untuk mengukur salintas perairan,
termometer untuk mengukur suhu perairan, tiang skala untuk mengukur pasang
surut, skop untuk mengambil sampel sedimen, pipa paralon dengan ukuran
diameter 2 inch panjang 20 cm untuk mengambil sampel bahan organik pada
sedimen dasar.
Cool box untuk menyimpan sampel sedimen yang diambil dari lapangan,
cawan porselin untuk tempat sampel, timbangan digital untuk menimbang berat
sampel sampel sedimen, oven untuk mengeringkan sampel sedimen, desikator
untuk mendinginkan sampel sedimen, gegep besi untuk mengambil cawan
porselin di dalam tanur, sieve net untuk mengayak sampel sedimen dan
memisahkan sedimen berdasarkan ukuran butir sedimen, kertas licin
(pembungkus nasi) untuk menyimpan sedimen yang telah diayak, spidol untuk
menandai kantong sampel, kuas untuk membersihkan sisa-sisa yang telah
diayak, perahu untuk alat transportasi menuju lokasi penelitian.
2) Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar identifikasi dan
buku panduan pengenalan mangrove di Indonesia (Noor et al., 2006) untuk
mengidentifikasi jenis mangrove, kantong sampel sedimen, kertas label dan
spidol permanen untuk menandai kantong sampel, aquades untuk
membersihkan alat yang telah digunakan, tissue digunakan untuk membersihkan
alat yang telah dipakai.
C. Metode dan Penelitian
Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yang dimulai dari tahap persiapan,
observasi awal, penentuan stasiun, prosedur penelitian, pengolahan data dan
analisis data yang dijabarkan sebagai berikut ;
25
1. Persiapan
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur
terkait dengan judul penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing dan
melakukan observasi awal pada lokasi yang telah ditentukan.
2. Observasi Awal
Observasi awal dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang
lokasi penelitian. Kegiatan observasi ini meliputi pengamatan jenis mangrove
dan pengamatan jenis sedimen secara visual.
3. Penentuan Stasiun di Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi sampling berdasarkan keberadaan jenis mangrove
dominan dan tumbuh berkelompok antar jenis mangrove yang ada di lokasi
penelitian.
Tabel 4. Stasiun dan Jenis Mangrove di Pulau Pannikiang
Stasiun Titik Koordinat Jenis Mangrove Dominan
1 E 119°35’38.75”
Rhizophora apiculata S 04°21’44.48’’
2 E 119°36’17.74”
Sonneratia alba S 04°20’25.50”
3 E 119°35’38.10”
Rhizophora stylosa E 119°35’38.10”
4 E 119°36’06.42”
Tidak ada mangrove S 04°21’35.33”
Prinsip penentuan stasiun ini berdasarkan keterwakilan lokasi, dimana
terdapat 4 stasiun yang terdiri dari 1 stasiun kontrol dan 3 stasiun pengamatan
jenis mangrove dominan, untuk membandingkan kandungan bahan organik
sedimen ke 3 stasiun diambil 3 plot setiap stasiun yang ditentukan secara acak.
Pengambilan data pada stasiun kontrol dilakukan pada daerah yang tidak
26
ditumbuhi mangrove. Pengambilan data pada stasiun kontrol ini dilakukan untuk
membandingkan kandungan bahan organik sedimen pada stasiun yang
ditumbuhi jenis mangrove. Pengambilan titik koordinat stasiun pengamatan
dilakukan dengan menggunakan global positioning system (GPS).
4. Prosedur Penelitian
a. Prosedur pengambilan data mangrove dan sampel sedimen
1) Identifikasi jenis mangrove dominan
Mengidentifikasi spesies dari tiap–tiap tumbuhan mangrove yang dominan di
lokasi penelitian dengan pengamatan secara visual. Sampel mangrove
diidentifikasi dengan merujuk pada lembar identifikasi dan berdasarkan buku
Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia (Noor et al., 2006).
Gambar 3. Lembar Identifikasi Mangrove (Noor et al., 2006)
2) Bagan transek dan ukuran plot jenis mangrove
Pengambilan data mangrove menggunakan metode transek garis (line
transect). Metode transek dilakukan dengan cara membuat garis yang ditarik
secara tegak lurus dari garis pantai terhadap stasiun. Panjang transek
disesuaikan dengan luasan jenis mangrove yang tumbuh.
27
Setiap transek yang telah dibentuk pada masing-masing stasiun
pengamatan, didalamnya dibuat plot ukuran bertingkat 1x1 (m) untuk tingkat
semaian, 5x5 (m) untuk tingkat anakan, dan 10x10 (m) untuk tingkat pohon.
Gambar 4. Bagan Transek dan Ukuran Plot Sampling Mangrove
Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah pohon, anakan dan semaian
mangrove yang tumbuh dalam luasan plot tersebut (English et al., 1994 dan
Kusmana, 1997 dalam Saru, 2013). Kemudian jarak antara plot satu ke plot
berikutnya 10 meter, jarak tersebut disesuaikan dengan kondisi luasan
mangrove.
3) Bahan organik sedimen dasar perairan
Pengambilan sampel bahan organik di sedimen, diambil setiap plot
ditentukan secara acak pada jenis mangrove. Pengambilan sampel sedimen
dilakukan dengan menggunakan core yang terbuat dari pipa paralon dengan
ukuran diameter 2 inch dengan panjang 20 cm. Pengambilan sampel sedimen
dilakukan dengan menancapkan core pada sedimen hingga tenggelam lalu
mengangkat kembali core tersebut, kemudian memasukkan ke dalam kantong
sampel sesuai dengan kode sampel setiap plot yang telah dibuat, setelah itu
28
menyimpan kedalam cool box yang berisi es batu. Fungsi es batu sebagai
pendingin agar tidak terjadi penguraian oleh bakteri. Sampel dibawa
kelaboratorium untuk dianalisis. Analisis bahan organik sedimen dilakukan
dengan menggunakan metode Loss In Ignition mengikuti metode yang
digunakan oleh Fairust dan Graham (2003).
Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada analisis kandungan bahan
organik sedimen di laboratorium, sebagai berikut :
a) Memasukkan sampel sebanyak-banyaknya ke dalam beaker glass
b) Mengeringkan sampel sedimen dengan menggunakan oven selama 2x24
jam/sampel sampai benar-benar kering.
c) Mengeringkan cawan porselin yang kosong di dalam oven selama 10
menit
d) Menimbang berat cawan porselin yang kosong
e) Menimbang berat sampel sedimen yang telah di oven sebanyak kurang
lebih 5 gr dan mencatatnya sebagai berat awal (Wa)
f) Memanaskan cawan porselin yang berisi sampel sedimen sebanyak 5 gr
dengan menggunakan tanur pada suhu 650°C selama kurang lebih 3,5
jam
g) Setelah mencapai 3,5 jam sampel sedimen dikeluarkan dari tanur dan
dimasukkan ke dalam desikator agar sampel tidak kembali lembab.
h) Menimbang kembali sampel berat cawan yang sudah di tanur sebagai
berat akhir (Wt)
b. Analisis besar butir sedimen
Penentuan ukuran butiran sedimen dilakukan dengan menggunakan metode
pengayakan kering (dry sieving). Porsi sedimen yang tertahan pada setiap
ayakan ditimbang dan diklasifikasikan menurut ukuran butirannya. Analisis
29
sampel sedimen dilakukan dengan metode ayakan kering. Metode ini digunakan
untuk mengetahui ukuran butiran sedimen dan dominanasi sedimen pada stasiun
jenis mangrove.
Adapun prosedur kerja yang dilakukan untuk menganalisis besar butir
sedimen di laboratorium sebagai berikut ;
a) Pengambilan sampel sedimen untuk melihat partikel sedimen di ambil
pada jenis mangrove yang telah ditentukan
b) Pengambilan sampel sedimen sebanyak 500 gram di lapangan dilakukan
dengan menggunakan skop.
c) Sampel sedimen yang diperoleh di lapangan dikumpulkan sesuai dengan
plot.
d) Sampel dibawa ke laboratorium untuk dianalisis kemudian setelah itu
sampel tersebut dimasukkan ke dalam oven yang dilengkapi dengan
pengatur suhu dengan suhu 1050C.
e) Sedimen kering tersebut diambil dan kemudian ditimbang untuk dianalisis
± 100 gram sebagai berat awal.
f) Sampel dimasukkan ke dalam ayakan yang memiliki ukuran butir 2 mm, 1
mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,125 mm, 0,63 mm, dan <0,63 mm setiap
tingkatan. Kemudian diguncang secara merata selama minimum 10
menit untuk sempurnanya pengayakan, sehingga didapatkan pemisahan
ukuran masing-masing partikel sedimen berdasarkan ukuran ayakan.
g) Sampel dipisahkan dari ayakan untuk mengantisipasi tertinggalnya
butiran pada ayakan disikat dengan perlahan.
h) Hasilnya kembali dihitung untuk mendapatkan berapa gram hasil masing-
masing tiap ukuran ayakan.
30
c. Pengukuran parameter lingkungan
Tujuan pengukuran parameter lingkungan ini untuk menggambarkan kondisi
lingkungan mangrove di lokasi penelitian. Adapun parameter lingkungan yang
diukur pada saat di lokasi pengamatan, yaitu ;
1) Salinitas
Pengukuran salinitas perairan dilakukan langsung di lokasi menggunakan
Handrefraktometer dengan tiga kali ulangan pada setiap plot stasiun
pengamatan.
2) Suhu
Pengukuran suhu perairan dilakukan langsung di lokasi menggunakan
termometer dengan tiga kali ulangan pada setiap plot stasiun pengamatan.
3) pH tanah
Pengambilan data keasaman dilakukan langsung di lokasi menggunakan pH
meter dengan tiga kali ulangan pada setiap plot stasiun pengamatan.
4) Pasang surut
Pengukuran pasang surut dilakukan di sekitar dermaga yang selalu
tergenang oleh air laut. Pengukuran ini menggunakan metode Doodson.
Pengambilan data pasang surut dilakukan setiap 1 jam selama 39 jam dan
dimulai pada pukul 00.00 hingga 39 jam.
Untuk menghitung pasang surut suatu perairan adalah (Jalil et al., 2015)
Keterangan : DTS = Duduk tengah sementara
Hi = Tinggi muka air (cm)
Ci = Konstanta Doodson
DTS = ∑ Hi x Ci / ∑Ci
31
5) Arus
Pengukuran kecepatan arus dilakukan disetiap stasiun dengan
menggunakan layang-layang arus yang dilepaskan ke perairan, dibiarkan hanyut
terbawa oleh arus sampai tali meregang. Waktu yang tercatat di stopwatch
dicatat.
Untuk menghitung kecepatan arus suatu perairan adalah (Jalil et al., 2015)
V
Keterangan : V = Kecepatan arus (cm/detik)
s = Jarak tempuh layang–layang arus (meter)
t = Waktu tempuh layang–layang arus (detik)
5. Pengolahan Data
1) Data mangrove
Data mangrove yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis untuk
mengetahui kerapatan jenis i (Di) dan penutupan jenis i (Ci) (Bengen, 2002 dan
Kusmana, 1997) :
a. Kerapatan jenis i (Di) adalah jumlah tegakan jenis dalam suatu unit area.
Kerapatan Relatif Jenis (RDi) adalah perbandingan antara jumlah
tegakan jenis i (ni) dan jumlah total tegakan seluruh jenis (∑n), dengan
rumus :
Keterangan : Di = Kerapatan jenis i (Indiv/m2)
ni = Jumlah total tegakan jenis i
A = Luas total area pengambilan sampel (m2)
RDi = Kerapatan relatif jenis i (%)
∑n = Jumlah total tegakan seluruh jenis
Di = ni / A
RDi = (ni /∑n) x 100%
32
b. Penutupan Jenis i (Ci) adalah luas penutupan jenis i dalam suatu unit
area dihitung dengan rumus berikut di bawah ini :
Keterangan : Ci = Penutupan jenis dalam satu unit area,
A = Luas total area sampling (plot),
∑C = Jumlah tutupan dari semua jenis,
RCi = Penutupan relatif jenis i (%),
DBH = Diameter batang pohon,
π = Konstanta yang bernilai 3,1416
BA = Basal area,
CBH = Lingkar batang pohon
Kondisi mangrove didasarkan pada standar baku kerapatan dan penutupan
mangrove berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun
2004.
Tabel 5. Kriteria Kerapatan dan Penutupan mangrove (KEPMEN_LH Nomor 201 Tahun 2004)
Kriteria Penutupan (%) Kerapatan (pohon/ha)
Sangat Padat >75 > 1500
Sedang > 50 - < 75 >1000 - < 1500
Jarang < 50 < 1000
Ci = ∑BA
A
RCi = Ci
∑Cx 100
BA = 𝜋 𝐷 𝐵𝐻2
4
DBH = CBH
4
33
2) Analisis kandungan bahan organik total pada sedimen
Analisis kandungan bahan organik sedimen dilakukan dengan metode Loss
In Ignition mengikuti metode yang digunakan oleh Fairust dan Graham (2003).
Keterangan : BWa = Berat awal (gram)
BWt = Berat akhir (gram)
Bc = Berat cawan (gram)
3) Analisis besar butir sedimen
Analisis besar butir sedimen mangrove dilakukan dengan menggunakan
metode pengayakan kering.
a) Perhitungan % berat
b) Menghitung % berat komulatif
% Komulatif = %berat1 + %berat2
6. Analisis Data
Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil kandungan bahan organik
total dalam sedimen perairan antara ke empat stasiun, maka dilakukan analisis
ANOVA menggunakan software SPSS versi 16.0. Untuk mengetahui ada
tidaknya antara hubungan bahan organik total dalam sedimen dengan kerapatan,
penutupan dan jenis sedimen pada ketiga stasiun jenis mangrove menggunakan
analisis regresi dengan menggunakan software SPSS.
Berat awal = Berat Cawan Kosong + Berat Sampel (5 gr)
Kandungan bahan organik = ± (BWa–Bc) – (BWt –Bc)
OT O w b um d p j − O d p j
mp ×
34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pulau Pannikiang merupakan salah satu pulau yang secara administratif
termasuk dalam Dusun Pannikiang, Desa Madello, Kecamatan Balusu,
Kabupaten Barru. Secara geografis Pulau Pannikiang berada pada 04° 19’
45.21’’ – 04°22’19.93” LS dan 119° 34’32.45”-119°36’46.22” BT dengan luas
sekitar 97 Ha. Batas–batas administratif pulau Pannikiang adalah sebagai
berikut :
Sebelah Utara : Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batukalasi
Sebelah Timur : Daratan Kota Kecamatan Balusu
Sebelah Selatan : Pulau Puteangin
Sebelah Barat : Selat Makassar
Pulau Pannikiang dapat dicapai dengan transportasi laut dari pelabuhan
Garongkong dengan menggunakan. Jarak tempuh dari pelabuhan Garongkong
sekitar ±20 menit. Pulau Pannikiang berada di bagian Barat Kecamatan Pantai
Balusu dengan luas daratan 97 hektar.
Secara masyarakat yang ada di pulau Pannikiang berprofesi sebagai
nelayan dengan alat tangkap yang digunakan adalah pancingan dengan bantuan
perahu yang bermesin. Hasil tangkapan utama berupa kepiting, udang, kerapu,
kakap, cumi-cumi dan jenis ikan lainnya yang bukan hanya sebagai bahan
konsumsi sehari-hari.
35
B. Kondisi Lingkungan Stasiun Penelitian
Berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan yang dilakukan pada setiap
stasiun mengenai kondisi perairan, disajikan sebagai berikut :
Tabel 6. Data hasil pengukuran parameter lingkungan di setiap stasiun
Stasiun Jenis Mangrove Suhu (°C) Salinitas (‰) pH Arus
(m/detik)
1. Rhizophora apiculata 29,0 34,2 6,4 0,07
2. Sonneratia alba 29,4 34,5 6,6 0,02
3. Rhizophora stylosa 28,8 35,7 6,5 0,03
4. Tidak ada mangrove 30,0 34,0 4,0 0,04
1. Suhu
Suhu merupakan faktor yang sangat menentukan kehidupan dan
pertumbuhan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisaran nilai suhu
di lokasi penelitian yaitu 28,8°C hingga 30,0°C. Nilai suhu yang terendah berada
pada stasiun 3. Hal ini disebabkan karena kerapatan pohon yang cukup tinggi,
sehingga bisa menghambat intensitas cahaya ke dalam ekosistem mangrove,
sedangkan stasiun yang memiliki nilai suhu tertinggi adalah stasiun 4 30,0°C,
karena stasiun tersebut tidak ditumbuhi mangrove, sehingga sinar matahari
langsung menembus badan air.
Kisaran suhu bergantung pada kerapatan mangrove di stasiun
pengamatan, perbedaan suhu pada masing-masing stasiun disebabkan oleh
faktor intensitas matahari yang terpapar langsung dilingkungan mangrove,
sehingga menyebabkan suhu ke empat stasiun berubah-ubah sesuai dengan
kondisi mangrove tersebut. Kisaran suhu stasiun yang ditumbuhi jenis
mangrove, sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan mangrove,
36
seperti yang diungkapkan oleh Gufran dan Kordi (2012), bahwa suhu yang baik
untuk kehidupan mangrove adalah tidak kurang dari 20 °C.
2. Salinitas
Salinitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan
perkembangan mangrove. Kisaran nilai yang diperoleh antar stasiun
pengamatan adalah 34‰ hingga 35,7‰. Dimana nilai yang tertinggi terdapatp
ada stasiun 3 35,7‰. Hal ini dikarenakan stasiun tersebut mengalami pasang air
laut sehingga sangat mempengaruhi salinitas di habitat mangrove. Meskipun
demikian, beberapa spesies dapat tumbuh di daerah dengan salinitas sangat
tinggi, seperti yang dilaporkan oleh Arsornkoae (1993), bahwa di Australia jenis
mangrove dapat tumbuh di daerah dengan salinitas maksimum Sonneratia spp.
44‰, Rhizophora apiculata 65‰ dan Rhizophora stylosa 74‰.
Nilai salinitas terendah pada stasiun 4 34,0‰. Rendahnya salinitas pada
stasiun tersebut dikarenakan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan mangrove.
Menurut Kushartono (2009), kenaikan konsentrasi salinitas dipengaruhi oleh air
yang masuk kedalam tanah, yang berasal dari intrusi air laut yang datang pada
saat pasang surut, dimana air tersebut meresap kebawah dan sampai pada
lapisan kedap air, berkumpul sehingga salinitasnya lebih tinggi dibanding
permukaan perairan.
3. pH Sedimen
Hasil pengukuran pH sedimen antar stasiun pengamatan menunjukkan
nilai yang bervariasi, dimana nilai yang terendah pada stasiun 4 yang tidak
ditumbuhi mangrove dengan nilai 4,0, sedangkan stasiun yang ditumbuhi
mangrove menunjukkan hasil yang bervariasi yaitu 6,5 hingga 6,6. Nilai pH
sedimen antar stasiun yang ditumbuhi mangrove termasuk perairan yang
produktif. Hal ini menunjukkan bahwa ke tiga lokasi yang ditumbuhi mangrove,
sangat cocok untuk habitat pertumbuhan jenis mangrove. Widyastuti (1999)
37
mengemukakan bahwa kisaran nilai pH antara 6 hingga 8,5 sangat cocok untuk
pertumbuhan mangrove.
4. Arus
Pengukuran arus dilakukan pada setiap stasiun pengamatan. Kecepatan
arus paling tinggi didapatkan pada stasiun 1. Stasiun ini secara lansung
berhadapan dengan laut dan dipengaruhi aktivitas yang terjadi dilaut seperti
angin dengan nilai kecepatan arus 0,07 m/detik pada saat pasang. Kecepatan
arus terendah ditemukan di stasiun 2 dengan nilai 0,02 m/detik, dimana stasiun
ini sama dengan stasiun 1 berhadapan langsung dengan laut, kondisi pasang
surut pada saat pengukuran arus di stasiun 2 adalah surut.
5. Pasang Surut
Pasang surut merupakan peristiwa gerakan naik turunnya permukaan air
laut akibat gaya tarik bulan dan matahari terhadap permukaan bumi (Saru,
2013).
Gambar 4. Pola pasang surut duduk tengah sementara (DTS) tinggi muka air
Data mengenai pasang surut merupakan data primer yang diperoleh dari
hasil pengukuran di lokasi penelitian selama 39 jam (Gambar 4). Dari hasil
0
20
40
60
80
100
120
140
160
00
.00
03
.00
06
.00
09
.00
12
.00
15
.00
18
.00
21
.00
00
.00
03
.00
06
.00
09
.00
12
.00
Tin
ggi m
uka
air
(cm
)
Waktu (Jam)
Tinggi Air
DTS
38
pengukuran pasang surut selama 39 jam pada tanggal 23–24 Juli 2017,
diketahui bahwa tinggi muka air maksimum adalah 144 cm dan tinggi air
minimum 33 cm. Dengan demikian, nilai ini menunjukkan bahwa kisaran pasang
surut yang diperoleh 111 cm dan nilai rata-rata muka air adalah 77,367 cm. Pada
gambar 4 menunjukkan bahwa pasang tertinggi pada pukul 06.00 WITA,
sedangkan surut terendah berada pada pukul 21.00 WITA.
Tipe pasang surut di lokasi penelitian termasuk tipe Diurnal, yakni tipe
pasang surut yang terjadi satu kali pasang satu kali surut dalam 24 jam/satu hari.
Hutan mangrove yang tumbuh daerah pasang diurnal, memiliki struktur dan
kesuburan yang berbeda dari hutan mangrove yang tumbuh di daerah semi-
diurnal dan berbeda juga dengan hutan mangrove yang tumbuh di daerah
pasang campuran. Perkembangan daerah mangrove di lokasi penelitian sangat
baik karena pasang surut dan substrat yang mendukung. Menurut Watson
(1928), hubungan antara komposisi jenis dengan tingkat pasang surut dan tipe
tanah sangat berpengaruh, dimana tingkat pasang surut akan menentukan
substrat yang mengendap sehingga jenis mangrove dapat tumbuh dan
menyesuaikan kondisi lingkungan.
C. Bahan Organik Total (BOT) di Sedimen Jenis Mangrove
Kandungan bahan organik antar stasiun pengamatan, termasuk dalam
klasifikasi sangat rendah sampai tinggi, dimana berada pada kisaran 2,58-
32,83% seperti yang telah dijelaskan Reynold (1971), kriteria bahan organik
sedimen adalah sangat tinggi : >35, tinggi : 17–35, sedang : 7–17, rendah : 3,5–
7, sangat rendah < 3,5.
Hasil analisis uji One-way Anova, kandungan bahan organik total dalam
sedimen pada ke empat stasiun signifikan berbeda pada (p<0,05) dan uji lanjut
Tukey LSD menunjukkan bahwa kandungan bahan organik yang terkandung di
39
stasiun 1, tidak signifikan berbeda (p>0,05) dengan stasiun 2 dan 3. Stasiun 2
dan 4 tidak berbeda nyata (p<0,05) nilai kandungan bahan organiknya.
Stasiun 4 yang tidak ditumbuhi mangrove dengan ke 3 stasiun jenis
mangrove berbeda (p<0,05) nilai kandungan bahan organik dalam sedimen
(Lampiran 13).
Gambar 5. Kandungan bahan organik sedimen
Tingginya kandungan bahan organik pada stasiun 1 dan 3 jenis Rhizophora
dikarenakan memiliki ukuran daun yang tidak keras sehingga lebih cepat
terdekomposisi dan memiliki ukuran partikel sedimen yang kecil dan stasiun ini
tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Hal ini dipertegas oleh pendapat
Efriyeldi (2012), tingginya kandungan bahan organik total sedimen tidak terlepas
dari adanya aktivitas masyarakat yang ada di sekitar mangrove, sedangkan
kandungan bahan organik pada stasiun 4 tidak ada mangrove lebih rendah
dibandingkan dengan ke 3 stasiun yang ditumbuhi jenis mangrove. Hal ini
dikarenakan stasiun 4 tidak ditumbuhi mangrove dan kurang sumbangan dari
vegetasi mangrove sehingga kandungan bahan organik sangat rendah.
32,83 ± 23,45
10,85 ± 4,19
30,57 ± 4,98
2,58 ± 0,19
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
1 2 3 4
Bah
an O
rgan
ik T
ota
l (%
)
STASIUN
a
b
a
a
40
D. Partikel Sedimen Jenis Mangrove
Hasil analisis partikel sedimen menggunakan metode ayakan kering dengan
bantuan software Gradistat V8, memperlihatkan bahwa kisaran nilai yang
diperoleh ke 4 stasiun adalah 0,59–1,13 mm.
Gambar 6. Ukuran partikel sedimen pada tiap stasiun
Hasil analisis uji One-way Anova tidak signifikan berbeda (p>0,05) dengan
jenis sedimen ke empat stasiun (Lampiran 13). Stasiun yang memiliki partikel
butiran sedimen tertinggi yaitu stasiun 4 tidak ada mangrove, sedangkan stasiun
partikel butiran sedimen terendah adalah stasiun 1, 2, dan 3 yaitu berkisar 0,59-
0,96 mm. Bengen (2004), menyatakan bahwa bakau dapat tumbuh dengan baik
pada substrat yang berlumpur dan dapat mentoleransi tanah lumpur berpasir.
Selain itu partikel sedimen yang kecil dapat menjebak bahan organik. Hal ini
dipertegas oleh pendapat Efriyeldi (1997), sedimen yang memiliki partikel relatif
besar bahan organik yang dikandungnya relatif sedikit. Sebaliknya, pada
sedimen partikel kecil bahan organik yang terkandung banyak. Semakin halus
tekstur sedimen maka besar kemampuannya menjebak bahan organik.
0,59 ± 0,10
0,96
± 0,23 0,72
± 0,24
1,13 ± 0,24
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1 2 3 4
Par
tike
l Se
dim
en
(m
m)
STASIUN
a
a
a
a
41
E. Struktur Vegetasi Mangrove
1. Kerapatan Jenis Mangrove
Kerapatan mangrove pada setiap stasiun tergantung banyaknya jumlah
mangrove. Semakin banyak jumlah mangrove di setiap stasiun, maka semakin
padat mangrove di stasiun tersebut. Hasil pengamatan memperlihatkan kisaran
nilai kerapatan jenis mangrove antara 0,08 (ind/m²) hingga 0,12 (ind/m²).
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun
2004, kondisi kerapatan jenis mangrove disetiap stasiun tergolong kategori
jarang.
Gambar 7. Kerapatan jenis mangrove di tiap stasiun
Hasil analisis uji One-way Anova menunjukkan bahwa kerapatan mangrove
antar stasiun tidak berbeda nyata (p>0,05) (Lampiran 12). Kondisi kerapatan
jenis mangrove tertinggi stasiun 3 adalah 0,12 (ind/m²), sementara kerapatan
terendah stasiun 2 adalah 0,06 (ind/m²). Tingginya kerapatan jenis mangrove di
stasiun 1 dan 3, dikarenakan memiliki jumlah tegakan pohon yang banyak dan
ciri khas akar tunjang yang padat berfungsi sebagai perangkap sedimen.
Menurut Halidah (2014), bahwa akar yang padat sangat efektif untuk menangkap
0,08 ± 0,03
0,06 ± 0,02
0,12 ± 0,07
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
1 2 3
Ke
rap
atan
Je
nis
(in
div
idu
/m2
)
STASIUN
a
a
a
42
dan menahan lumpur. Sedimen yang terperangkap kaya akan kandungan bahan
organik sehingga dapat memperluas habitat mangrove serta dapat meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan mangrove (Furukawa dan Wolanski,1996).
2. Penutupan Jenis Mangrove
Penutupan jenis adalah luas penutupan jenis i dalam suatu unit area
(Bengen, 1999). Kisaran nilai penutupan jenis mangrove yang diperoleh disetiap
stasiun adalah 6,98–58,78 cm2/m2. Kondisi tutupan jenis mangrove ke 3 stasiun
yang ditumbuhi mangrove menunjukkan kategori jarang pada setiap stasiun jenis
mangrove.
Gambar 8. Penutupan jenis mangrove di tiap stasiun
Berdasarkan hasil analisis uji One-way Anova, bahwa penutupan jenis
magrove signifikan berbeda (p<0,05) antar stasiun dan uji lanjut Tukey HSD
menunjukkan bahwa stasiun 1 dan stasiun 3 tidak signifikan berbeda (p>0,05)
penutupan jenis mangrove, sedangkan stasiun 1 dan stasiun 3 signifikan
berbeda (p<0,05) dengan stasiun 2 (Lampiran 12). Hasil perhitungan tutupan
jenis mangrove diperoleh stasiun 1 dan 3 memiliki nilai penutupan lebih rendah
bila dibandingkan dengan stasiun 2 jenis Sonneratia alba. Hal ini dikarenakan
6,98 ± 4,50
58,78 ± 27,87
19,81 ± 3,67
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
1 2 3
Pe
ntu
pan
Je
nis
(cm
2/m
2)
STASIUN
a
b b
a
43
diameter batang pohon jenis di Stasiun 2 lebih besar sehingga daun yang
dihasilkan banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Dahuri dalam Day et al.,
1989), semakin besar diameter batang pohon mangrove, semakin banyak daun
yang dihasilkan. Daun yang jatuh di atas permukaan tanah akan mengalami
proses penghancuran dan berpengaruh tingginya kandungan bahan organik. Hal
ini sesuai dengan pernyataan Yusuf et al., (2016) menyatakan bahwa, daun yang
secara alami akan gugur menjadi serasah dan akan terdekomposisi menjadi
bahan organik.
F. Hubungan Kandungan Bahan Organik Sedimen dengan Kerapatan
Jenis Mangrove
Pada Gambar 9, memperlihatkan hubungan antara kerapatan jenis
mangrove dengan kandungan bahan organik sedimen.
Gambar 9. Hubungan Kerapatan dengan Kandungan Bahan Organik
Sedimen
Persamaan regresi linear, yaitu y = 199,1x+7,4934 dengan nilai koefisien
Determinasi (R2) sebesar 0,353. Ini artinya pengaruh kerapatan terhadap
kandungan bahan organik sedimen sebesar 35,3% sementara 64,7%
dipengaruhi faktor lain, sedangkan nilai koefisien korelasi (r) diperoleh sebesar
y = 199,1x + 7,4934 R² = 0,3536
r = 0,594
0
10
20
30
40
50
60
70
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Bah
an O
rgan
ik T
ota
l (%
)
Kerapatan Jenis (Indvidu/m2)
Rhizophora
apiculata
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
44
0,594. Menurut Sugiyono (2013), bahwa nilai 0,40–0,599 menunjukkan korelasi
yang sedang. Sesuai dengan pernyataan Saru et al., (2017) bahwa kerapatan
mangrove sangat mendukung tinggi rendahnya bahan organik total dalam
sedimen.
G. Hubungan Penutupan Jenis Mangrove dengan Kandungan Bahan
Organik Sedimen
Pada Gambar 10, memperlihatkan hubungan antara penutupan jenis
mangrove dengan kandungan bahan organik sedimen.
Gambar 10. Hubungan Penutupan Jenis dengan Kandungan Bahan
Organik
Persamaan regresi linear yaitu y =-0,2829x + 32,816 dengan nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,2322. Nilai ini menyatakan bahwa pengaruh
penutupan terhadap kandungan bahan organik sedimen sebesar 23,22%
sedangkan 76,78% dipengaruhi oleh faktor lain, sedangkan untuk nilai koefisien
korelasi (r) diperoleh nilai sebesar 0,481 menunjukkan bahwa korelasi antara
variabel penutupan dengan bahan organik adalah sedang.
y = -0,2829x + 32,816 R² = 0,2322
r = 0,481
0
10
20
30
40
50
60
70
0 20 40 60 80 100
Bah
an O
rgan
ik T
ota
l (%
)
Penutupan Jenis (cm2/m2)
Rhizophora
apiculata
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
45
H. Hubungan Partikel Sedimen dengan Kandungan Bahan Organik di
Sedimen
Pada Gambar 11, memperlihatkan hubungan antara partikel sedimen
dengan kandungan bahan organik di sedimen.
Gambar 11. Hubungan Partikel Sedimen dengan Kandungan Bahan
Organik Sedimen
Persamaan regresi linear yaitu y = -0,0111x + 1,0609 dengan nilai koefisien
Determinasi (R2) sebesar 0,4452. Nilai ini menunjukkan bahwa 44,52% pengaruh
partikel sedimen terhadap kandungan bahan organik dan 55,48% dipengaruhi
oleh faktor lain, sedangkan untuk nilai koefisien korelasi (r) diperoleh nilai
sebesar 0,671. Nilai ini dikategorikan memiliki hubungan yang kuat antara
kandungan bahan organik dengan partikel sedimen. Hal ini disebabkan karena
sedimen yang memiliki ukuran partikel kecil sangat berpengaruh keberadaan
kandungan bahan organik. Hasil penelitian oleh Yusuf et al., (2016) yang
menyatakan bahwa lumpur yang mempunyai porositas rendah, sehingga mampu
menahan bahan organik dengan baik dibanding substrat yang lebih besar.
y = -40,243x + 53,42 R² = 0,450 r = 0,671
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Bah
an O
rgan
ik T
ota
l (%
)
Partikel Sedimen (mm)
Rhizophora
apiculata
Rhizophora stylosa
Sonneratia alba
Kontrol
46
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan, sebagai berikut :
1. Kandungan bahan organik sedimen jenis mangrove dominan di Pulau
Pannikiang memiliki kandungan bahan organik tidak signifikan berbeda
p>0,05 antar stasiun yang ditumbuhi mangrove, sedangkan stasiun yang
ditumbuhi mangrove dengan yang tidak ada mangrove signifikan
berbeda p<0,05. Nilai kandungan bahan organik tertinggi pada stasiun 1
jenis Rhizopora apiculata (32,83%) dan kandungan bahan organik
terendah berada pada stasiun 4 tidak ada mangrove (2,58%).
2. Berdasarkan hasil uji regresi dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan (p>0,05) terhadap kandungan bahan organik sedimen dengan
kerapatan jenis mangrove dan nilai koefisien korelasi (r) diperoleh
sebesar 0,594, artinya nilai ini dikategorikan memiliki hubungan antara
kandungan bahan organik sedimen dengan kerapatan jenis mangrove.
B. Saran
Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan tentang hubungan bahan organik
dengan kerapatan dan penutupan jenis mangrove yang dominan dengan cara
pengambilan sampel sedimen pada saat pasang dan surut di Pulau Pannikiang
Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.
47
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, 1984. Bahasa Jurnalistik dan Komposisi. Jakarta: Pradaya Paramita. Ardhana, I W. 2002. Konsep Penelitian Pengembangan dalam Bidang
pendidikan dan Pembelajaran. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Angkatan II Metodologi Penelitian Pengembangan Bidang Pendidikan dan Pembelajaran. (Skripsi).
Arsornkoae, S. 1993. Ecology and management of mangrove. IUCN. Bangkok.
Thailand. Bahar, A. 2015. Pedoman Survei Laut. Makassar: Masagena Press. Makassar.
Bengen, D.G. 2000. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem dan Sumber daya
Pesisir (Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir
Terpadu, Bogor 13-18 November 2000. Pusat Kajian Sumber daya
Pesisir dan Lautan IPB).
Bengen, D.G., 2001. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
Bengen. 2002. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir. Pusat Kajian
Sumberdaya pesisir dan Lautan. Sinopsis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Buckman, H. O. dan N. C. Brady. 1982. Ilmu Tanah. Gajah Mada University
Press. Yogyakarta. Dahuri, R., Rais J, dan Ginting. S.P., M.J. 1996. Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Secara Terpadu. Pradnya Paramitha, Jakarta. Darmadi, M. W. Lewaru dan A.M.A. Khan. 2012. Struktur Komunitas Vegetasi
Mangrove Berdasarkan Karakteristik Substrat di Muara Harmin Desa Cangkring Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu. Jurnal Perikanan dan Kelautan. 3(3): 347 – 358.
Efriyeldi, 2012. Ekobiologi Kerang Sepetang di ekosistem mangrove pesisir Kota
Dumai Riau (disertasi). Bogor : Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor 172 hal.
Efriyeldi. 1997. Struktur Komunitas Makrozoobentos dan Keterkaitannya dengan
Karakteristik Sedimen di Perairan Muara Sungai Bantan Tengah, Bengkalis. Tesis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 102 hal.
English. 1994. Survey Manual for Tropical Marine Resources. Australian Institute
of Marine Science. Townsville.
48
Ghufran, M dan Kordi, K. 2012. Ekosistem Mangrove Potensi, Fungsi dan
Pengelolaan. Rineka Cipta. Jakarta.
Gunkel W. 1976. Organic Substrate. Bacteria, Fungi and Blue Green Algae. John Wiley and Sons Inc. New York.
Gunkel W. 1976. Organic Substrate. Bacteria, Fungy and Blue Green Algae.
John Wiley and Sons Inc. New York. Halidah. 2014. Penyebaran Alami Avicennia marina (Forsk) Vierh dan Sonneratia
alba Smith pada Substrat Pasir di Desa Tiwoho, Sulawesi Utara. Indonesian Rehabilitation Forest Journal, 1 (1) 51-58.
Hasbi. 2004. Studi Laju Dekomposisi Serasah Mangrove Di Pantai Larea-Rea
Kabupaten Sinjai. (Skripsi). UNHAS Makassar. Hutabarat, S dan S.M. Evans. 1995. Pengantar Oceanografi. Universtas
Indonesia Press, Jakarta. Hutabarat, S. dan Evans, S.M. 1984. Pengantar Oseanografi. UI Press. Jakarta. Irwanto, 2006. Keanekaragaman Fauna Pada Habitat Mangrove. Yogyakarta.
Jalil, A.R., M. Lanuru., W. Samad., dan M. Hatta (ed). 2015. Pedoman Survei Laut. Makassar: Masagena Press. Makassar.
Kushartono, E W. 2009. Beberapa Aspek Bio-Fisik Kimia Tanah di Daerah Mangrove Desa Banggi Kabupaten Rembang. Jurusan Ilmu Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. Semarang.
Kusmana, C. 1997. Metode Survei Vegetasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Kusmana, C. 2002. Ekologi Mangrove. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor
Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2004. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Kerusakan Mangrove. Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
Mulya, M. B. 2002. Keanekaragaman dan Kelimpahan Kepiting Bakau (Scylla spp.) di Hutan Mangrove Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur. Tesis. Program Pascasarjana IPB, Bogor.
Noor, Y., R. 2006. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Wetland
International – Indonesia Programme. Bogor.
Nybakken, J. W. 1988. Biologi Laut. Suatu Pendekatan Ekologis. Gramedia. Jakarta.
Nybakken, J.W. 1992. Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. Eidman, M.,
Koesoebiono, D.G. Begen, M. Hutomo, dan S. Sukardjo (penerjemah).
Terjemahan dari: Marine Biology: An Ecological Approach. PT Gramedia.
Jakarta.
49
Purnobasuki, H. 2005. Tinjauan Perspektif Hutan mangrove. Arlangga University Press. Surabaya.
Reynold, S. C, 1971. A Manual of Introductory Soil Science and Simple Soil
Analysis Methods. South Pasific. Nouena New Caledonia.
Samingan, M. T. 1980. Notes on the Vegetation of the Tidal Areas of South Sumatra, Indonesia, with Special Reference to Karang Agung dalam International Social Tropical Ecology, Kuala Lumpur. Hal. 1107-1112
Saru, A. 2013. Mengungkap Potensi Emas Hijau di Wilayah Pesisir. Masagena
Press. Makassar.
Saru, A., K. Amri, dan Mardi. 2017. Konektivitas Struktur Vegetasi Mangrove Dengan Keasaman dan Bahan Organik Total pada Sedimen di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal SPERMONDE, 3(1):1-6
Storm, C. 1989. Influence of River System and Coastal Hydrodinamics on Water Quality During One Moonson Periode. Departement of Physical Geography. University Netherlands.
Sugiyono. 2013. Statistika untuk penelitian. Bandung : Alfabeta.
Suwardi, Tambaru, E., Ambeng, dan Priosambodo, D. 2013. Keanekaragaman Jenis Mangrove di Pulau Pannikiang Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Jurnal. Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Hasanuddin. Makassar.
Tomlinson, PB. 1986. The Botany of Mangroves. Cambridge University Press. Massachusetts.
Triatmodjo. 1999. Teknik Pantai (Edisi Kedua), Beta Offset. Yogyakarta.
Van Steenis, C.G.G.J. 1958. Ecology of Mangroves. Introduction to account of the Rhizophoraceae by Ding Hou, Flora Malesiana, Ser. 1(5) : 431-441
Wahyu, S. L., dan Widyastuti, M. 1998. Identifikasi dan Pengukuran Parameter-Parameter Fisika Lapangan. Kerjasama Fakultas Geografi-UGM dan Bakosurtanal-BAGANDA. Proyek MREP. Sulawesi Selatan.
Watson, J.G. 1928. Malyan Forest Record. Mangrove forest of The Malay Peninsula. Published by Permision of The Federeted Malay Status Goverment. Printed by Fraser and Neane Ltd. Singapore
Yusuf, S., B. Selamat., K. Amri., A.l. Burhanuddin, dan Mashoreng. S. 2016. Kondisi Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Liukang Tuppabbiring Kabupaten Pangkep. Coremap-CTI; Jakarta.
51
Lampiran 1. Data Mentah Lingkar Batang Mangrove di Setiap Stasiun Pengamatan
Stasiun No. Plot
Pohon Tipe
substrat SP IND Lingkar Batang
(CBH) Diameter
Batang (DBH)
1
1 Rhizophora apiculata
6
27 8,60
Lumpur berpasir
43 13,69
24 7,64
29 9,24
31 9,87
16 5,10
2 Rhizophora apiculata
6
25 7,96
Lumpur berpasir
34 10,83
35 11,15
27 8,60
35 11,15
29 9,24
3 Rhizophora apiculata
12
32 10,19
Lumpur berpasir
35 11,15
43 13,69
29 9,24
28 8,92
29 9,24
29 9,24
30 9,55
34 10,83
44 14,01
45 14,33
43 13,69
2
1 Sonneratia
alba 8
22 7,01
Pasir berlumpur
88 28,03
37 11,78
98 31,21
84 26,75
130 41,40
204 64,97
149 47,45
2 Sonneratia
alba 5
20 6,37
Pasir berlumpur
18 5,73
18 5,73
134 42,68
135 42,99
3 Sonneratia
alba 5
79 25,16 Pasir berlumpur 136 43,31
52
162 51,59
130 41,40
97 30,89
3
1 Rhizophora
stylosa 20
49 15,61
Lumpur berpasir
41 13,06
39 12,42
32 10,19
46 14,65
44 14,01
43 13,69
48 15,29
39 12,42
39 12,42
21 6,69
43 13,69
40 12,74
39 12,42
47 14,97
46 14,65
32 10,19
31 9,87
24 7,64
36 11,46
2 Rhizophora
stylosa 9
30 9,55
Lumpur berpasir
80 25,48
46 14,65
47 14,97
50 15,92
34 10,83
53 16,88
45 14,33
41 13,06
3 Rhizophora
stylosa 7
50 15,92
Lumpur berpasir
44 14,01
78 24,84
55 17,52
70 22,29
47 14,97
45 14,33
53
Lampiran 2. Kerapatan Jenis Mangrove di Stasiun 1
Stasiun Jenis
Mangrove Sub
stasiun Kerapatan jenis
(Di) (ind/m) Kerapatan relatif
jenis (RDi)
1 Rhizophora apiculata
1 0,06 100
2 0,06 100
3 0,12 100
Rata-rata 0,08
Total 0,24
Lampiran 3. Kerapatan Jenis Mangrove di Stasiun 2
Stasiun Jenis
Mangrove Sub
stasiun Kerapatan Jenis
(Di) (ind/m) Kerapatan Jenis
Relatif (RDi)
2 Sonneratia
alba
1 0,08 100
2 0,05 100
3 0,05 100
Rata-rata 0,06
Total 0,18
Lampiran 4. Kerapatan Jenis Mangrove di Stasiun 3
Stasiun Jenis
Mangrove Sub
stasiun Kerapatan Jenis
(Di) (ind/m) Kerapatan Jenis
Relatif (RDi)
3 Rhizophora
stylosa
1 0,2 100
2 0,09 100
3 0,07 100
Rata-rata 0,12
Total 0,36
54
Lampiran 5. Data Mentah Penutupan Jenis Mangrove di tiap Stasiun
St. Jenis
Mangrove Plot DBH BA Ci RCi
1 Rhizophora apiculata
1
8,6 58,06
4,15 100
13,69 147,12
7,64 45,82
9,24 67,02
9,87 76,47
5,1 20,42
∑
414,91 4,15
2
7,96 49,74
4,62 100
10,83 92,07
11,15 97,59
8,6 58,06
11,15 97,59
9,24 67,02
∑
462,08 4,62
3
10,19 81,51
12,16 100
11,15 97,59
13,69 147,12
9,24 67,02
8,92 62,46
9,24 67,02
9,24 67,02
9,55 71,59
10,83 92,07
14,01 154,08
14,33 161,20
13,69 147,12
∑
1215,82 12,16
2 Sonneratia
alba
1
7,01 38,57
85,17 100
28,03 616,76
11,78 108,93
31,21 764,64
26,75 561,72
41,4 1345,46
64,97 3313,56
47,45 1767,43
∑
8517,08 85,17
2
6,37 31,85
29,64 100 5,73 25,77
5,73 25,77
42,68 1429,94
55
42,99 1450,79
∑
2964,13 29,64
3
25,16 496,93
61,53 100
43,31 1472,47
51,59 2089,30
41,4 1345,46
30,89 749,04
∑
6153,19 61,53
3
Rhizophora stylosa
1
15,61 191,28
24,02 100
13,06 133,89
12,42 121,09
10,19 81,51
14,65 168,48
14,01 154,08
13,69 147,12
15,29 183,52
12,42 121,09
12,42 121,09
6,69 35,13
13,69 147,12
12,74 127,41
12,42 121,09
14,97 175,92
14,65 168,48
10,19 81,51
9,87 76,47
7,64 45,82
11,46 103,10
∑
2402,12 24,02
2
9,55 71,59
17,35 100
25,48 509,65
14,65 168,48
14,97 175,92
15,92 198,96
10,83 92,07
16,88 223,67
14,33 161,20
13,06 133,89
∑
1735,43 17,35
Rhizophora stylosa
3
15,92 198,96
18,05 100 14,01 154,08
24,84 484,37
17,52 240,96
56
22,29 390,02
14,97 175,92
14,33 161,20
∑
1805,50 18,05
Lampiran 6. Data Rata-rata Penutupan Jenis Mangrove di tiap Stasiun
Pengamatan
Stasiun Jenis Mangrove Plot Penutupan Jenis
(Ci) Rata-rata
1 Rhizophora apiculata
1 4,15
6,98 2 4,62
3 12,16
2 Sonneratia alba
1 85,17
58,78 2 29,64
3 61,53
3 Rhizophora stylosa
1 24,02
19,81 2 17,35
3 18,05
57
Lampiran 7. Data Mentah Hasil Pengukuran Parameter Lingkungan di Setiap Plot Pengamatan.
Stasiun Plot Suhu (° C ) Salinitas ( ‰ ) pH
1
1.1 29 34 6,2
1.2 29 34 6,4
1.3 29 34 6,3
Rata-rata 29 34,0 6,3
2.1 29 34 6,2
2.2 29 35 6,4
2.3 29 35 5,9
Rata-rata 29 34,67 6,17
3.1 29 34 6,8
3.2 29 34 6,8
3.3 29 34 6,8
Rata-rata 29 34 6,8
2
1.1 30 34 6,8
1.2 30 35 6,4
1.3 30 35 6,7
Rata-rata 30 34,67 6,63
2.1 29 34 6,5
2.2 29 35 6,7
2.3 30 35 6,6
Rata-rata 29,33 34,67 6,6
3.1 29 34 6,8
3.2 29 34 6,7
3.3 29 34 6,2
Rata-rata 29 34 6,57
3
1.1 29 35 6,2
1.2 29 35 6,3
1.3 29 35 6,4
Rata-rata 29 35 6,3
2.1 29 36 6,5
2.2 29 36 6,4
2.3 29 36 6,6
Rata-rata 29 36 6,5
3.1 28 36 6,6
3.2 29 36 6,6
3.3 28 36 6,6
Rata-rata 28,33 36 6,6
4
1 30 34 4,4
2 30 34 3,9
3 30 34 3,7
58
Rata-rata 30 34,0 4,0
Lampiran 8. Data Rata-rata Nilai Parameter Lingkungan Setiap Stasiun Pengamatan
Stasiun Jenis Mangrove Plot Suhu (°C) Salinitas ‰ pH
1 Rhizophora apiculata
1 29 34 6,3
2 29 34,67 6,17
3 29 34 6,8
29,0 34,2 6,4
2 Sonneratia alba
1 30 34,67 6,63
2 29,33 34,67 6,6
3 29 34 6,57
29,4 34,4 6,6
3 Rhizophora
stylosa
1 29 35 6,3
2 29 36 6,5
3 28,33 36 6,6
28,8 35,7 6,5
4 Tidak ada mangrove
30 34 4,4
30 34 3,9
30 34 3,7
30,0 34,0 4,0
59
Lampiran 9. Data Mentah Hasil Pengukuran Arus di Setiap Stasiun Pengamatan
Jam Hari St. Jenis mangrove Waktu S Jarak Arah K. arus
(m/detik)
16'50'' Minggu 1 Rhizophora apiculata 2'30'' 150 10 40 U 0,07
13'57'' Minggu 2 Sonneratia alba 10'40'' 640 10 90 U 0,02
10'45" Senin 3 Rhizophora stylosa 05'27'' 327 10 105 U 0,03
15'29'' Minggu 4 Tidak ada mangrove 04'07'' 247 10 360 U 0,04
60
Lampiran 10. Data Mentah Hasil Pengukuran Pasang Surut di Lokasi Penelitian
No. Jam Tinggi Muka Air (H) Konstanta (C) H x C DTS (Cm)
1 00.00 58 1 58
77,367
2 01.00 71 0 0
3 02.00 90 1 90
4 03.00 110 0 0
5 04.00 129 0 0
6 05.00 140 1 140
7 06.00 142 0 0
8 07.00 139 1 139
9 08.00 125 1 125
10 09.00 114 0 0
11 10.00 102 2 204
12 11.00 89 0 0
13 12.00 78 1 78
14 13.00 68 1 68
15 14.00 60 0 0
16 15.00 53 2 106
17 16.00 48 1 48
18 17.00 46 1 46
19 18.00 41 2 82
20 19.00 37 0 0
21 20.00 34 2 68
22 21.00 33 1 33
23 22.00 34 1 34
24 23.00 37 2 74
25 00.00 46 0 0
26 01.00 60 1 60
27 02.00 88 1 88
28 03.00 100 0 0
29 04.00 122 2 244
30 05.00 139 0 0
31 06.00 144 1 144
32 07.00 143 1 143
33 08.00 134 0 0
34 09.00 122 1 122
35 10.00 108 0 0
36 11.00 91 0 0
37 12.00 74 1 74
38 13.00 60 0 0
39 14.00 53 1 53
Jumlah 30 2321
61
Lampiran 11. Data Mentah Kandungan Bahan Organik di Setiap Stasiun Pengamatan
St. Jenis
Mangrove BCK
Berat Contoh 5
gr
BC + Berat Contoh
Sebelum di Pijar
Berat BO Setelah di
Pijar
Kandungan BO
% BO Rata-rata
Kandungan BOT (%)
1
Ra.1.1 17,172 5,019 22,191 21,756 0,435 8,6671
12,59
32,83
Ra.1.2 17,058 5,015 22,073 21,654 0,419 8,3549
Ra.1.3 17,679 5,016 22,695 21,654 1,041 20,7536
Ra.2.1 22,231 5,008 27,239 25,922 1,317 26,2979
27,35 Ra.2.2 27,261 5,003 32,264 30,753 1,511 30,2019
Ra.2.3 26,683 5,018 31,701 30,419 1,282 25,5480
Ra.3.1 16,17 5,022 21,192 15,047 6,145 122,3616
58,54 Ra.3.2 11,604 5,029 16,633 15,047 1,586 31,5371
Ra.3.3 12,058 5,007 17,065 15,977 1,088 21,7296
2
Sr.1.1 23,183 5,056 28,239 27,569 0,67 13,2516
13,95
10,85
Sr.1.2 11,77 5,038 16,808 16,298 0,51 10,1231
Sr.1.3 11,103 5,031 16,134 15,204 0,93 18,4854
Sr.2.1 14,557 5,005 19,562 19,223 0,339 6,7732
12,51 Sr.2.2 15,13 5,011 20,141 19,633 0,508 10,1377
Sr.2.3 15,981 5,026 21,007 19,971 1,036 20,6128
Sr.3.1 13,244 5,078 18,322 18,02 0,302 5,9472
6,08 Sr.3.2 15,324 5,017 20,341 19,963 0,378 7,5344
Sr.3.3 17,524 5,016 22,54 22,301 0,239 4,7648
3
Rs.1.1 22,783 5,032 27,815 25,419 2,396 47,6153
34,03
30,57
Rs.1.2 26,003 5,005 31,008 29,206 1,802 36,0040
Rs.1.3 21,694 5,045 26,739 25,807 0,932 18,4737
Rs.2.1 12,483 5,033 17,516 15,421 2,095 41,6253
32,83 Rs.2.2 10,915 5,01 15,925 14,895 1,03 20,5589
Rs.2.3 12,425 5,012 17,437 15,617 1,82 36,3128
Rs.3.1 12,251 5,033 17,284 16,583 0,701 13,9281
24,86 Rs.3.2 11,843 5,048 16,891 15,668 1,223 24,2274
Rs.3.3 13,354 5,083 18,437 16,586 1,851 36,4155
4
Kontrol.1.1 13,381 5,041 18,422 18,295 0,127 2,5193
2,58 2,58 Kontrol.1.2 11,735 5,008 16,743 16,603 0,14 2,7955
Kontrol.1.3 12,109 5,057 17,166 17,043 0,123 2,4323
62
Lampiran 12. Analisis Uji One Way Anova Kerapatan dan Penutupan ke Tiga Stasiun Jenis Mangrove
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Kerapatan Between Groups .006 2 .003 1.313 .337
Within Groups .013 6 .002
Total .018 8
Penutupan Between Groups 4367.115 2 2183.557 8.085 .020
Within Groups 1620.418 6 270.070
Total 5987.533 8
Uji Lanjut Post Hoc Test
Multiple Comparisons
Penutupan
Tukey HSD
(I) Stasiun (J) Stasiun
Mean Difference
(I-J) Std. Error Sig.
95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
Rhizophora apiculata Sonneratia alba -51.80333* 13.41814 .020 -92.9739 -10.6328
Rhizophora stylosa -12.83000 13.41814 .628 -54.0005 28.3405
Sonneratia alba Rhizophora apiculata 51.80333* 13.41814 .020 10.6328 92.9739
Rhizophora stylosa 38.97333 13.41814 .061 -2.1972 80.1439
Rhizophora stylosa Rhizophora apiculata 12.83000 13.41814 .628 -28.3405 54.0005
Sonneratia alba -38.97333 13.41814 .061 -80.1439 2.1972
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
63
Lampiran 13. Analisis Uji One Way Anova Kandungan Bahan Organik Total dan Partikel Sedimen ke Empat Stasiun Pengamatan
ANOVA
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Bahan_Organik_Total Between Groups 1982.791 3 660.930 4.460 .040
Within Groups 1185.568 8 148.196
Total 3168.359 11
Besar_Butir_Sedimen Between Groups .519 3 .173 3.917 .054
Within Groups .353 8 .044
Total .872 11
Uji Lanjut Post Hoc Test
Multiple Comparisons
Bahan_Organik_Total
LSD
(I) Stasiun (J) Stasiun
Mean
Difference (I-J) Std. Error Sig.
95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
Rhizophora apiculata Sonneratia alba 21.98000 9.93969 .058 -.9410 44.9010
Rhizophora stylosa 2.25333 9.93969 .826 -20.6676 25.1743
Kontrol 30.24333* 9.93969 .016 7.3224 53.1643
Sonneratia alba Rhizophora apiculata -21.98000 9.93969 .058 -44.9010 .9410
Rhizophora stylosa -19.72667 9.93969 .082 -42.6476 3.1943
Kontrol 8.26333 9.93969 .430 -14.6576 31.1843
Rhizophora stylosa Rhizophora apiculata -2.25333 9.93969 .826 -25.1743 20.6676
Sonneratia alba 19.72667 9.93969 .082 -3.1943 42.6476
Kontrol 27.99000* 9.93969 .023 5.0690 50.9110
Kontrol Rhizophora apiculata -30.24333* 9.93969 .016 -53.1643 -7.3224
Sonneratia alba -8.26333 9.93969 .430 -31.1843 14.6576
Rhizophora stylosa -27.99000* 9.93969 .023 -50.9110 -5.0690
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
64
Lampiran 14. Hasil Uji Regresi Hubungan Kerapatan Jenis Mangrove dengan Kandungan Bahan Organik di Sedimen Menggunakan Program SPSS 16.0
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,594636123
R Square 0,353592119
Adjusted R Square 0,261248136
Standard Error 13,80181958
Observations 9
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 729,4015 729,4015 3,829076 0,091248559
Residual 7 1333,432 190,4902
Total 8 2062,833
Coefficients Standard
Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 7,493429952 9,946159 0,753399 0,475781 -16,02549925 31,01236 -16,0255 31,01235915
Kerapatan 199,1014493 101,7484 1,956802 0,091249 -41,4951995 439,6981 -41,4952 439,6980981
65
Lampiran 15. Hasil Uji Regresi Hubungan Penutupan Jenis Mangrove dengan Kandungan Bahan Organik di Sedimen Menggunakan Program SPSS 16.0
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,481896533
R Square 0,232224268
Adjusted R Square 0,122542021
Standard Error 15,04181403
Observations 9
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 479,0399 479,0399 2,117246 0,188978
Residual 7 1583,793 226,2562
Total 8 2062,833
Coefficients Standard
Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 32,81619091 7,475177 4,390022 0,003195 15,14021 50,49217 15,14021 50,49217481
Penutupan -
0,282853707 0,194391 -1,45508 0,188978 -0,74252 0,176808 -0,74252 0,176808061
66
Lampiran 16. Hasil Uji Regresi Hubungan Partikel Sedimen Mangrove dengan Kandungan Bahan Organik di Sedimen Menggunakan Program SPSS 16.0
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,6708973
R Square 0,4501032
Adjusted R Square 0,3951136
Standard Error 13,199509
Observations 12
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 1426,089 1426,089 8,185232 0,016928
Residual 10 1742,27 174,227
Total 11 3168,359
Coefficients Standard
Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 53,420453 12,55084 4,256325 0,001673 25,45544 81,38547 25,45544 81,38547 Partikel Sedimen -40,242642 14,06601 -2,86098 0,016928 -71,5837 -8,90161 -71,5837 -8,90161
67
Lampiran 17. Meminta izin melakukan pengambilan data penelitian dengan Kepdes Pulau Pannikiang
Lampiran 18. Pengambilan data mangrove dan sampel BOT
Lampiran 19. Pengukuran parameter lingkungan