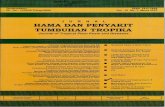Jurnal Praktikum sedimentologi 2015 ANALISIS PH DAN FOSFAT (KIMIA SEDIMEN) DALAM SEDIMEN PADA...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Jurnal Praktikum sedimentologi 2015 ANALISIS PH DAN FOSFAT (KIMIA SEDIMEN) DALAM SEDIMEN PADA...
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 1
ANALISIS PH DAN FOSFAT (KIMIA SEDIMEN) DALAM SEDIMEN PADA
PERAIRAN SUNGAI MUSI, PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
SINDY LISE SILVIA
Program Studi Ilmu Kelautan FMIPA Universitas Sriwijaya FMIPA, Universitas
Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia
ABSTRAK
Peraktikum ini dilakukan di Sungai Musi, stasiun 4 (dermaga Kertapati),
Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui nilai PH dan Fosfat yang terkandung di dalam
Sedimen dasar perairannya. Praktikum ini diuji dengan menggunakan metode Olsen
ataupun Bray setelah melihat/mengukur nilai PH yang terkandung di dalam sedimen
tersebut. Sampel yang di uji di ukur dengan metode Olsen dikarenakan pada PH yang di
kandungnya memenuhi syarat standar pemilihan metode Olsen yakni PH bernilai >5,50.
Setelah dilakukan pengujian dimana di dapatkan hasil pH yang ada pada perairan sungai
musi dibagian ini bersifat asam karena pHnya berkisar antara 6,60 – 6,51. Kemudian
dengan pengukuran Konsentrasi fosfat dalam sedimen pada perairan 0.3 – 0,4 ppm. Dan
hal ini dapat dikatakan bahwa nilai fosfat di dalam perairran tersebut cukup tinggi.
Kata Kunci : Sedimen, Fosfat, Metode Olsen, PH, Konsentrasi Fosfat.
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 2
PENDAHULUAN
Sungai merupakan perairan yang
memilik peran penting bagi makhluk hidup.
Keberdaan ekosistem sungai dapat
memberikan manfaat bagi makhluk hidup,
baik yang hidup didalam sungai maupun
yang ada disekitarnya. Kegiatan manusia
sebagai bentuk kegiatan pembangunan akan
berdampak pada perairan sungai. Adanya
kegiatan manusia dan industri
memanfaatkan sungai sebagai tempat untuk
membuang limbah. Hal tersebut akan
berdampak pada penurunan kualitas air,
yaitu dengan adanya perubahan kondisi
fisika, kimia dan biologi
(Sastrawijaya, 1991) .
Sungai akan memperoleh masukan
bahan maupun energi yang berasal dari
wilayah sepanjang aliran sungai ataupun
segala aktivitas manusia yang berkaitan
dengan produksi limbah dan kemudian
dialirkan melalui badan-badan sungai.
Pembangunan industri di daerah
permukiman sepanjang aliran sungai
memberikan masukan bahan-bahan
pencemar bagi perairan sungai yang pada
akhirnya akan dialirkan ke muara
(Santoso, 2007).
Sungai sangat penting
dalampengelolaan wilayah pesisir karena
fungsi sebagai sarana transportasi, sumber
air bagi masyarakat, perikanan dan
pemeliharaan hidrologi rawa dan lahan
basah. Sebagai alat angkut, sungai
membawa sedimen (lumpur, pasir), sampah
dan limbah serta zat hara melalui wilayah
permukiman masuk ke muara dan akhirnya
ke laut. Dampaknya adalah terciptanya
dataran berlumpur, pantai berpasir dan
bentuk pantai lainnya.
Indonesia memiliki sedikitnya 5.590
sungai utama dan 65.017 anak sungai. Dari
5,5 ribu sungai utama panjang totalnya
mencapai 94.573 km dengan luas Daerah
Aliran Sungai (DAS) mencapai 1.512.466
km2. Selain mempunyai fungsi hidrologis,
sungai juga mempunyai peran sebagai
sarana transportasi. Saat ini sebagian besar
sungai di Indonesia mengalami kerusakan,
salah satunya adalah tingginya laju
sendimentasi dan erosi. Akibatnya kondisi
kuantitas (debit) air sungai menjadi
fluktuatif antara musim penghujan dan
kemarau. Dan salah satu sungai di Indonesia
yang mengalami laju sedimentasi tinggi
adalah sungai Musi di Sumatera Selatan.
Sungai Musi dengan panjang + 510
km merupakan sungai terbesar dan
terpanjang di Provinsi Sumatra Selatan. Dari
segmen hulu dengan ekosistem hutan
lindung telah mengalami perubahan tata
guna lahan sampai di hilir yang sarat akan
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 3
pemukiman dan industri seperti pengilangan
minyak, pabrik pupuk, pengolahan karet
alam, kayu lapis dan lain-lain sehingga
berpotensi menyebabkan degradasi kualitas
lingkungan perairan sungai. Di bagian hilir
inipun perairan Musi merupakan sumber air,
tidak hanya bagi penduduk di sepanjang
sungai, tetapi juga merupakan sumber air
sekaligu tompat membuang limbah cair oleh
induslri sehingga berdampak kepada
perurunan kualitas perairan Musi.
Beragamnya kegiatan manusia di sepanjang
Sungai Musi ini berdampak terhadap
komunitas fitoplankton yang menghuni
perairan.
Perairan pesisir Banyuasin
merupakan bagian dari perairan Selat
Bangka dan merupakan kawasan strategis
dalam pengembangan kawasan pesisir.
Daerah tersebut dimanfaatkan sebagai areal
kegiatan perikanan, pemukiman, dan
direncanakan sebagai areal pelabuhan.
Peningkatan pemanfaatan areal pantai
tersebut berdampak pada terganggunya
keseimbangan dinamika pantai. Masalah
yang dapat timbul di daerah pantai yakni
abrasi dan sedimentasi.
Fosfat dan nitrat merupakan salah
satu zat hara yang dibutuhkan dan
mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan
dan perkembangan hidup organisme di
perairan. Fitoplankton merupakan salah satu
parameter biologi yang erat hubungannya
dengan fosfat dan nitrat. Tinggi rendahnya
kelimpahan fitoplankton disuatu perairan
tergantung kepada kandungan zat hara
diperairan tersebut antara lain zathara fosfat
dan nitrat, sama halnya dengan zat hara
lainnya, kandungan fosfat dan nitrat di suatu
perairan, secara alami tersedia sesuai dengan
kebutuhan organisme yang hidup di perairan
tersebut (Nybakken, 1988).
Dalam analisa, fosfat terlarut
ditentukan setelah melalui proses filtrasi dan
konsentrasi fosfat ditentukan berdasarkan
reaktifitasnya terhadap reagen molibdat.
Fosfat terfiltrasi yang reaktif terhadap
reagen molibdat disebut dengan fosfat
reaktif (filterable reactive phosphate, FRP)
yang terdiri atas ortofosfat dan polifosfat
serta fosfat organik yang mudah terhidrolisis
oleh asam. Sementara, konsentrasi fosfat
organic terfiltrasi (filterable organic
phosphate, FOP) ditentukan melalui tahapan
oksidasi sebelum direaksikan dengan reagen
molibdat. Meskipun fosfat terdapat dalam
berbagai bentuk, hanya ortofosfat dan fosfat
lain yang mudah berubah menjadi ortofosfat,
baik melalui proses fisika (desorpsi), kimia
(pelarutan) maupun biologis (proses
enzimatis), yang dapat dimanfaatkan secara
langsung oleh alga di badan air.
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 4
Unsur fosfat (P) adalah unsur
esensial kedua setelah N yang berperan
penting dalam fotosintesis dan
perkembangan akar. Ketersediaan P dalam
tanah jarang yang melebihi 0,01 % dari total
P. Sebagian besar bentuk P terikat oleh
koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi
tanaman. Tanah dengan kandungan organik
rendah seperti Oksisols dan Ultisols yang
banyak terdapat di Indonesia kandungan P
dalam organik bervariasi dari 20–80%,
bahkan bisa kurang dari 20% tergantung
tempatnya. P tersebut tidak dapat
dimanfaatkan secara efektif oleh tanaman,
karena P dalam tanah dalam bentuk P terikat
di dalam tanah, sehingga petani harus terus
melakukan pemupukan P di lahan sawah
walaupun sudah terdapat kandungan P yang
cukup memadai. Pada tanah masam, P
bersenyawa dalam bentuk-bentuk Al—P dan
Fe—P, sedangkan pada tanah alkali (basa) P
akan membentuk senyawa Ca—P dengan
kalsium membentuk senyawa kompleks
yang sukar larut
(Simanungkalit et al., 2006).
Kelebihan fosfat di perairan
menyebabkan peristiwa peledakan
pertumbuhan alga (eutrofikasi) dengan efek
samping menurunnya konsentrasi oksigen
dalam badan air sehingga menyebabkan
kematian biota air. Disamping itu, alga biru
yang tumbuh subur karena melimpahnya
fosfat mampu memproduksi senyawa racun
yang dapat meracuni badan air. Meskipun
konsentrasi fosfat di badan air dikurangi,
eutrofikasi masih dapat terjadi karena
adanya mobilisasi fosfat dari sedimen
melalui proses fisika, kimia dan biokimia
(Bostrom et al. 1988).
Peranan nitrat dan fosfat yang
terkandung didalam sedimen yang ada di
sungai atau muara sungai adalah sebagai
unsur yang penting bagi pertumbuhan dan
kelangsungan hidup bagi organisme di
dalamnya. Organisme tersebut berperan
sebagai mata rantai dari rantai makanan
yang mendukung produktivitas perairan.
Pengkayaan zat hara di lingkungan perairan
memiliki dampak positif, namun pada
tingkatan tertentu juga dapat menimbulkan
dampak negatif. Dampak positifnya adalah
terjadi peningkatan produksi fitoplankton
dan total produksi sedangkan dampak
negatifnya adalah terjadinya penurunan
kandungan oksigen di perairan, penurunan
biodiversitas dan terkadang memperbesar
potensi muncul dan berkembangnya jenis
fitoplankton berbahaya yang lebih umum
dikenal dengan istilah Harmful Algal
Blooms atau HABs (Risamasu dan Prayitno,
2011). Pemeriksaan kandungan nitrat dan
fosfat atau sering disebut sebagai zat hara
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 5
perlu dilakukan karena parameter tersebut
merupakan parameter tingkat kesuburan
suatu perairan (Wibisono, 2005).
Penetapan jumlah P tersedia dalam
tanah harus ditentukan dengan metode yang
tepat. Permasalahan P di dalam tanah cukup
kompleks, salah satunya adalah sumbernya
terbatas dan amat dipengaruhi oleh pH tanah
sehingga ketersediannya bagi tanaman
sangat kecil. Ada beberapa metode
penentuan P tersedia dalam tanah, yaitu
Truog, Bray I, Bray II, North Caroline, dan
Olsen. Setiap metode mempunyai sifat
tersendiri dalam mengekstrak P. Metode
yang paling baik adalah metode yang
ekstraktannya benar mampu mengekstrak P
– tersedia di dalam tanah ataupun paling
mendekati P yang terserap oleh tanaman
(Ilahi, 2000).
Kondisi pH tanah merupakan faktor
penting yang menentukan kelarutan unsur
yang cenderung berkesetimbangan dengan
fase padatan. Kelarutan oksida-oksida
hidrous dari Fe dan Al secara langsung
tergantung pada konsentrasi ion hidroksil
(OH--) dan menurun ketika pH meningkat.
Kation hidrogen (H+) bersaing secara
langsung dengan kation-kation asam Lewis
lainnya dan oleh karenanya kelarutan kation
kompleks seperti Cu dan Zn akan meningkat
dengan menurunnya pH (Soemarno, 2011).
Pengaruh parameter pH terhadap
ketersediaan fosfat dapat digunakan sebagai
salah satu tolak ukur untuk membandingkan
hasil uji P dari metode uji tanah yang ada.
Perbandingan hasil uji P tersedia dari dua
metode yang berbeda dalam penerapan uji
terhadap suasana pH tanah dapat
memberikan rekomendasi pemupukan.
Metode Olsen biasanya digunakan untuk
tanah ber-pH >5,5, sedangkan metode bray
biasanya digunakan untuk tanah ber-
pH<5,5. Kedua metode ini bisa dijadikan
salah satu tolak ukur pembanding
penggunaan metode berdasarkan perbedaan
penerapan dalam suasana tanah, yaitu asam
dan basa.
METODOLOGI
Lokasi
Penelitian ini dilakukan di perairan
Sungai Musi II, Palembang Sumatera
Selatan stasiun dengan posisi pada stasiun 4
(Dermaga Stasiun Kertapati). Waktu
penelitian dilakukan pada tanggal 8 Maret
2015 pukul 07.00 Wib Sampai dengan
selesai.
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 6
Gambar. 1 Peta Lokasi Sampling
Praktikum Sedimentologi
Alat dan Bahan
Alat dan Bahan yang digunakan
dalam pratikum ini adalah neraca analitik,
pH meter, Labu semprot, Ekman grab,
spektrofotometer, erlenmeyer, alumunium
foil, plastik klip dan label, tabung reaksi,
pipet tetes, pipet ball, gelas ukur, gelas
beker, Rak dan tabung reaksi, ayakan
bertingkat dan alat tulis.
Bahan yang digunakan dalam
menganalisis adalah pH dan Fosfat adalah
NH4F, Aquades, HCl, Amonium molibdate,
Potasium antymonil tantrate, H2SO4, Asam
Askorbat, Kalium dihidrogen (KH2PO4),
Larutan standar posfat, Air bebas ion, KCl.
Cara Kerja
Pengambilan Sampel di lapangan
Menentukan plot pada GPS untuk
mengetahui lokasi stasiun-stasiun penelitian
sesuai dengan koordinat yang telah
ditentukan untuk pengambilan data.
Pengambilan data dilakukan pada pagi hari
di perairan sungai musi , Palembang dengan
pengambilan data menggunakan metode
insitu . Sampel Sedimen diambil dengan
menggunakan Ekmen Grab. Setelah sedimen
diambil, masukan kedalam plastik dan beri
lebel. Dan masukan dalam Coolbox.
Pengukuran pH tanah.
Timbang sampel sebanyak 10 gr
sebanyak 2 kali lalu dimasukkan pada
erlenmeyer yang berisi 50 ml air bebas ion
dan erlenmeyer yang berisi 50 ml KCl 1M.
Kocok selama 30 menit dan hitung pH nya.
Penetapan Fosfat dengan Metode
Olsen.
Pengekstrak Olsen
Timbang 1,05 g NaHCO3 lalu
tuangkan dalam 25 ml aquades, buat pH 8,5
dengan menambahkan NaOH. Kemudian
0,69 (NH4)6 Mo7O24 4H2O Amonium
Molibate dengan 5 ml aquades + 0,014 g
k(SbO) Potasium antimonil) + Tambahkan 7
ml H2SO4 tepatkan hingga 50 ml. Larutan
ke 3 Timbang 0,106 g asam Karbonat.
Larutkan dengan 10 ml pereaksi P pekat.
Tambahkan 2,5 ml H2so4. Tepatkan hingga
100 ml dengan Aquades.
Larutan ke 4
Timbang 0,02 g Kalium Dihidrogen
Phospat + 50 ml Aquades. Larutkan Standar.
Larutkan 5 ml Larutan Stok 20 ml tepatkan
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 7
hingga 50 ml. Buat deret Standar
0,2,4,8,12,16,20 ppm. Di buat dalam 5 ml.
Timbang 1 g sampel 2<mm, tambahkan 20
ml pengekstrak Olsen. Kocok Selama 30
menit hingga bening. Ambil sampel 2 ml,
pada deret standar masing-masing
ditambahkan 10 ml larutan pewarna (larutan
3)homogenkan. Hitung nilai absorbansi
dengan λ 880 nm.
Fosfat
Timbang 0,19 gr as.ascorbik
tepatkan hingga 10 ml aquades. Timbang 0,4
amonium molibdate tambahkan 10 ml
aquades. Ambil 1,4 ml H2SO4 tepatkan
hingga 10 ml aquades. Timbang potasium
antymonil tantrate 0,14 + 40 ml aquades,
encerkan hingga 50 ml.
Larutan Campuran
10 ml H2SO4 + 1 ml potasium
antymonil + 3 ml ammonium molibdate + 6
ml asam ascorbic. Larutan standar dari 0
ppm sampai sampel 1 tambahkan 0,8 larutan
campuran. Hitung nilai absorbansi dengan
panjang gelombang 880 nm.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengukuran PH
Perlakuan PH rata2
Aquades 50 ml + 10
gr sedimen 6.60
Aquades 50 ml +
Kcl 6.51
Gambar 2. Tabel Pengukuran PH
Dari perhitungan yang telah di lakukan
dimana pada perlakuan pada sampel yang di
tambah dengan aquades maka PH yang di
dapat kan sebesar 6,60 , dan ketika
ditambahkan dengan KCL maka PH sedikit
menurun dimana PH nya dapat kita lihat
menjadi 6,51 dan dengan demikian metode
uji fospat yang kita gunakan adalah metode
Olsen dimana pada hal ini syarat
penggunaan Metode Olsen terpenuhi yakni
PH bernilai >5,50.
2. Penetapan Fosfat dengan Metode
Olsen
PPM Nilai
Absorbansi
0 0.0774
2 0.5276
4 0.8157
8 1
12 2
16 2.0212
20 2.5709
sampel 1 0.1497
sampel 2 0.1737
Gambar 3. Nilai Absorbansi
Setelah di ketahui Metode yang akan
di lakukan keudian di lakukan pengujian dan
kemudian di dapatkan hasil nilai absorbansi,
dari masing-masing larutan standar dan juga
dari sampel yang kita uji. Dari pengukuran
absorbansi yang telah di ukur dengan
spektrofotometer maka di dapatkan hasil,
semakin tinggi nilai PPM nya maka semakin
tinggi pula nilai absorbansi nya, Tinggi nya
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 8
nilai absorbansi maka dapat di pastikan
maka tinggi pula nilai fosfat yang ada, hal
ini di buktikan pada sampel yang kita uji.
Dimana pada sampel 1 nilai
absorbansi nya sebesar 0.1497 dan pada
sampel 2 nilainya 0.1737. Dapat kita ketahui
Kandungan fosfat dan nitrat di suatu daerah
estuari selain berasal dari perairan itu sendiri
juga tergantung kepada keadaan
sekelilingnya,seperti sumbangan dari
daratan melalui sungai ke perairan tersebut,
juga tergantung kepada hutan mangrove
yang serasahnya membusuk, karena adanya
bakteri berurai menjadi zat hara fosfat dan
nitrat. Zat hara seperti fosfat dan nitrat
merupakan zat yang diperlukan dan
mempunyai pengaruh terhadap proses
pertumbuhan dan perkembangan hidup
organisme di perairan.
Menurut Risamasu dan Prayitno,
(2011) Pengkayaan zat hara di lingkungan
perairan memiliki dampak positif, namun
pada tingkatan tertentu juga dapat
menimbulkan dampak negatif. Dampak
positifnya adalah terjadi peningkatan
produksi fitoplankton dan total produksi
sedangkan dampak negatifnya adalah
terjadinya penurunan kandungan oksigen di
perairan, penurunan biodiversitas dan
terkadang memperbesar potensi muncul dan
berkembangnya jenis fitoplankton
berbahaya yang lebih umum dikenal dengan
istilah Harmful Algal Blooms atau HABs.
Pemeriksaan kandungan nitrat dan fosfat
atau sering disebut sebagai zat hara perlu
dilakukan karena parameter tersebut
merupakan parameter tingkat kesuburan
suatu perairan (Wibisono, 2005).
Menurut Effendi (2003), sumber
utama unsur fosfat di laut berasal dari
endapan terestrial yang mengalami erosi dan
pupuk pertanian yang dibawa oleh aliran
sungai. Selanjutnya Metcalf dan Eddy
(1974) menyatakan, bahwa sumber bahan
organik yang berasal dari daratan masuk ke
dalam lautan melalui sungai.
Kemudian Pada kedua sample yang
digunakan, dilakukan perhitungan nilai
absorbansi dimana rumusnya :
C= A/ ε. B
A = Nilai Absorbansi
ε = nilai a dari persamaan regresi
B = tebal kuvet (= 1)
Lalu di dapatkan hasil dimana,
perhitungan
no
c=A/Ɛ*b
ppm ABS
1 sampel 1 0.1497 0.374344
2 sampel 2 0.1737 0.434359
Gambar 4. Nilai perhitungan nilai
Konsentrasi Fosfat
Tabel diatas merupakan hasil sampel dari
perhitungan nilai absorbansi sedimen
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 9
perairan sungai musi. Dimana sampel ke 2
lebih tinggi nilainya, karena pada sampel
kedua dilakukan perlakuan sampel
ditambahkan 25 ml larutan pewarna (larutan
ke 3).
Gambar 5. Grafik Regresi Absorbansi
Perairan Sungai Musi
Dapat kita bahas dimana semakin tinggi
nilai konsentrasi maka akan semkin tinggi
pula fosfat nya, dan hal ini membuat grafik
naik ke atas. Koefisien dari nilai absorbansi
itu positif yaitu 0,399. Dengan demikian,
sedimen memiliki peranan penting terhadap
proses eutrofikasi karena sedimen pada
suatu perairan bertindak sebagai sumber dan
sekaligus sebagai penampung fosfat. Oleh
karena itu, untuk memonitor dan
mengkontrol eutrofikasi di badan air perlu
dikaji interaksi antara sedimen dan badan air
dengan mengukur konsentrasi dan
mengkarakterisasi spesies senyawa fosfat
di sedimen yang berpotensi menjadi sumber
fosfat bagi alga di badan air. Akan tetapi,
analisa fosfat organik dan polifosfat dari
sampel sedimen maupun air sering tidak
menyatakan keadaan yang sebenarnya
karena sifat senyawa fosfat organik dan
polifosfat serta sifat sedimen yang mudah
berubah karena perubahan suhu, pH dan
konsentrasi oksigen. Untuk menghindari
perubahan fisik dan kimia dari sampel maka
analisa seharusnya dilakukan secara in situ.
Pada Hasil analisis data penelitian
Arizuna,dkk (2014) untuk kandungan fosfat
sebesar 0,820. Fosfat pada perairan sungai
dan muara tidak terdapat perbedaan karena
fosfat pada perairan kandungannya lebih
stabil dibanding nitrat karena fosfat
mengendap dan fosfat memerlukan waktu
yang lama untuk terurai. Nilai tersebut lebih
besar daripada 0,05 sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan
pada kandungan fosfat dalam air pori
sedimen sungai dan muara Sungai Wedung.
Kandungan fosfat yang cukup tinggi
menyebabkan perairan tersebut subur.
Organisme perairan dapat berkembang baik
di Sungai Wedung. Kandungan fosfor dalam
air merupakan karakteristik kesuburan
perairan yang bersangkutan. Pada umumnya
perairan yang mengandung ortofosfat antara
0,03 - 0,1 mg/L adalah perairan yang
oligotrofik. Kandungan antara 0,11 - 0,3
0.07740.5276
0.81571
22.0212
2.5709y = 0.399x - 0.347R² = 0.992
0
1
2
3
0 5 10
Nila
i Ab
sorb
ansi
PPM
Nilai Regresi Absorbansi
PPM
Linear (PPM)
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 10
mg/L perairan yang mesotrofik dan
kandungan antara 0,31 – 1,0 mg/L adalah
perairan eutrofik (Wetzel, 1975 dalam
Hidayat 2001).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan mengenai analisis pH dan
kandungan phospat di perairan Sungai Musi
bagian hulu Palembang maka diperoleh
kesimpulan :
1. Konsentrasi fosfat dalam sedimen pada
perairan 0.3 – 0,4 ppm
2. pH yang didapat pada perairan sungai
musi dibagian hulu ini bersifat asam karena
pHnya berkisar antara 6,60 – 6,51
3. Semakin besar kosentrasi yang diberikan
maka nilai absorbansi yang didapat akan
semakin besar juga.
DAFTAR PUSTAKA
Ilahi, W. 2000. Penetapan Metode Analisis
dan Batas Kritis P-Tersedia Tanah
Sawah Kelurahan Amplas Air Bersih
Kecamatan Medan Denai [skripsi].
Fakultas Pertanian USU, Medan.
Nybakken, W.J. 1988. Biologi Laut : Suatu
Pendekatan Ekologi. P.T. Gramedia,
Jakarta
Risamasu, F.J.L dan H.B. Prayitno. 2011.
Kajian Zat Hara Fosfat, Nitrit,
Nitrat dan Silikat di Perairan
Kepulauan Matasiri, Kalimantan
Selatan. Ilmu Kelautan.
Santoso, A. D. 2007. Kandungan Zat Hara
Fosfat pada Musim Barat dan
Musim Timur di Teluk Hurun
Lampung. Jurnal Teknologi
Lingkungan. Jakarta.
Sastrawijaya, T. 1991. “Pencemaran
Lingkungan”. PT Rineka Cipta,
Jakarta.
Simanungkalit, R.D.M., D.A. Suriadikarta.,
R. Saraswati., D. Setyorini., dan W.
Hartatik. 2006. Pupuk Organik dan
Pupuk Hayati. Balai Besar Litbang
Sumber Daya Lahan Pertanian,
Bogor.
Soemarno. 2011. Faktor-Faktor
Ketersediaan Hara dalam Tanah.
F.Pertanian, Brawijaya.
Wibisono, M. S. 2005. Pengantar Ilmu
Kelautan. PT Gramedia. Jakarta
Jurnal Praktikum Sedimentologi 2015
Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya | Sindy Lise Silvia (08121005035) 11
LAMPIRAN